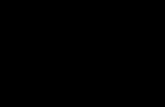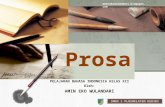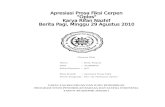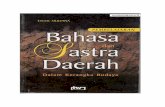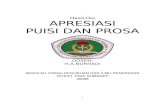Prosa 1
-
Upload
zulfikar-albar -
Category
Documents
-
view
81 -
download
5
Transcript of Prosa 1
Alua-Patuik, Anggo-Tanggo, Raso-ParesoWritten by Ekadj. Dt. Endang Pahlawan Saturday, 12 November 2005
rumah basandi batu adat basandi alua jo patuik mamakai anggo jo tanggo sarato raso jo pareso Norma adat dibentuk oleh tungku nan tigo sajarangan : alua-patuik, anggo-tanggo, dan raso-pareso. Norma ini terkristalisasi di dalam adat Minangkabau, dan digunakan dalam berbagai pertimbangan adat. Ketiga hal ini merupakan tungku bagi pemasakan adat, sedangkan apinya adalah para pemangku adat. Setiap penghulu adat hendaknya memahami dan menguasai ketiga norma tersebut, sehingga kepemimpinan adat yang dimilikinya dapat menanak rasa keadilan dan kesejahteraan terhadap kaum yang dipimpinnya. Sedangkan bagi anak Minangkabau pada umumnya, pemahaman terhadap alua-patuik, anggo-tanggo, dan raso-pareso berguna untuk menumbuhkan jatidiri dan memahami batasan-batasan hidup dalam bermasyarakat. Pasar jalan karono dilalui. a. Alua jo Patuik Pengertian alua (alur) adalah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang berlaku di dalam adat. Sedangkan pengertian patuik (patut) adalah kepantasan sesuatu terletak pada tempatnya. Dengan demikian pengertian alua jo patuik adalah kesesuaian sesuatu berdasarkan prosedur adat dan terletak pada tempatnya. Beberapa pitatah adat mengenai ketentuan alua : bajanjang naiek batanggo turun mangaji dari alif, babilang dari aso Beberapa pitatah adat mengenai ketentuan patuik : nagari aman, kampuang santoso padi masak, jaguang manjadi taronak berkembang biak bapak kayo, ibu batuah mamak dihormati urang pulo penghulu ibarek pohon di tangah padang ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang daunnyo tampek bataduah kapanasan dan balindung kahujanan pai tompek batanyo, pulang tampek babarito Dalam suatu keputusan adat, bilamana suatu keputusan akan ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu prosedur yang telah ditempuh : pandangan jauoh lah dilayangkan, pandangan dakek lah ditukikkan ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun Sehingga sampai kepada kepantasan : indak ado murai nan bakicau, indak ado rantiang nan badatak Bulek lah buliah digolongkan, picak lah buliah dilayangkan Tapi bila ada ketidaksesuaian dalam pertimbangan, pantunnya adalah : salido maso dahulu bakosiek bapantai cermin kapalo samo berbulu bapikie balain-lain
Bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka : silang pangkal cakak sangketo pangkal perang Oleh karenanya dalam timbangan adat alua jo patuik, hendaknya teliti dalam melihat permasalahan. Bisa saja masalah tersebut benar secara alua tapi tidak secara patuik, atau sebaliknya. Banyak permasalahan adat yang tumbuh belakangan ini didasarkan hanya mengikuti ketentuan alua, namun tidak menimbang kepatutan; seperti mengambil jalan pintas dalam keputusan-keputusan adat. Hal ini pada akhirnya menimbulkan silang-sengketa dan perseteruan di dalam masyarakat. Penyelesaian adatnya adalah : anggang jo kekek bari makan tabang ka pantai kaduonyo panjang jo singkek paulehkan mangkonyo sampai nan dicito b. Anggo jo Tanggo Anggo (anggaran dasar) mempunyai pengertian : ketentuan pokok, sedangkantanggo (anggaran rumah tangga) mempunyai pengertian : ketentuan pelaksanaan. Ketentuan anggo dibentuk dari pahatan norma (pitatah) yang tersusun sedemikian rupa dari ketentuan-ketentuan pokok adat (barih adat). barih baukua jo pitatah, disabuik anggo Anggo merupakan pedoman dalam perjalanan hidup kemasyarakatan, seperti halnya manfaat kompas dalam pelayaran. biduak didayuang manantang ombak layar dikambang manghadang angin nangkodo ingek di kamudi padoman usah dilupokan Sedangkan tanggo merupakan peraturan pelaksanaan adat yang menjalankan ketentuan anggo. di ateh anggo berdiri tanggo Adapun ukuran tanggo disebutkan : balabeh bajangko jo patiti, disabuik tanggo Ketentuan anggo diatur dengan tanggo disebut anggo jo tanggo. Anggo jo tanggo mendasari pemikiran dalam menjalani alua jo patuik; sehingga pedoman alua jo patuik bersandarkan pada ketentuan pokok dan ketentuan pelaksanaan dari hukum adat (anggo jo tanggo). c. Raso jo Pareso Raso adalah rasa atau perasaan manusia. Raso dapat berbentuk malu, takut, senang, atau bahagia. Walaupun pengaturan raso ini terdapat di otak kecil manusia, namun selalu diibaratkan raso itu tumbuh di dalam hati, atau raso tumbuah di dado. Ukuran raso didasarkan pada nilai budi yang dimiliki oleh setiap orang, dan karena itu raso setiap orang akan berbeda-beda. Pitatah adatnya adalah : latiek-latiek tabang ka pinang hinggok di pinang duo-duo satitiek aie dalam pinang disinan bamain ikan rajo Beberapa pantun budi-kebaikan : nan kuriek iyolah kundi nan merah iyolah sago nan baiek iyolah budi
nan indah iyolah baso pulau pandan jauah di tangah di baliek pulau si angso duo hancua badan dikanduang tanah budi baiek dikanang juo pisang ameh dibao balayar masak sabuah di dalam peti hutang ameh buliah dibayar hutang budi dibao mati Beberapa pantun tentang kehidupan tidak berbudi : anak urang koto hilalang pai ka pakan baso malu jo sopan kalau lah hilang hilanglah raso jo pareso Rarak limau dek binalu tumbuah sarumpun jo sikasek kalau hilang malu jo sopan umpamo kayu lungga pangabek dek ribuik rabahlah padi dicupak nak urang canduang hiduik kalau indak babudi duduak tagak kumari cangguang Talangkang carano kaco badarai carano kandi bareh nan samo dirandang baganggang karano dek raso bacarai karano dek budi itu nan samo kito pantangkan Pareso adalah periksa, yaitu menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti sehingga dapat diketahui keadaan yang sebenarnya. Untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya diperlukan kemampuan analisis dan pemikiran, karena itu disebutkanpareso tumbuah di kapalo. Raso-pareso merupakan suatu pandangan hidup yang didasarkan pada budi-kebaikan serta pemikiran untuk mengungkapkan kebenaran. Posisi raso-pareso adalah hati dan akal, yang perlu didudukkan secara selaras agar tercapai keseimbangan sikap. Di dalam pengembangan sikap, patiti adat mengatakan : raso dibao naiek pareso dibao turun tarimolah raso dari luar pareso bana raso ka dalam antah iyo antah indak Raso dibao naiek dimaksudkan budi-kebaikan seseorang hendaknya selalu ditingkatkan untuk diseimbangkan dengan posisi akal yang berada di atas. Cita-rasa seseorang terhadap kebaikan, keindahan, kepantasan, dan lain sebagainya hendaknya selalu meningkat seiring dengan jauhnya perjalanan yang dilalui serta bertambahnya wawasan hidup. Perhatikan kato pitatah : pandangan jauah, dilayangkan Pareso dibao turun dimaksudkan pemikiran dan penilaian tentang sesuatu hendaknya difokuskan kepada inti kebenaran dan selaras dengan posisi hati yang berada di bawah. Ketajaman pemikiran akan mengasah kemampuan analisis seseorang, sehingga dapat memilah mana yang emas dan mana yang loyang. Perhatikan kato pitatah :
pandangan dakek, ditukikkan Tarimolah raso dari luar dimaksudkan perlunya memahami pandangan dan pemikiran orang lain, sehingga dapat membentuk empati. Raso yang dimiliki seseorang perlu ditimbang dengan raso yang dimiliki oleh orang lain. Pareso bana raso ka dalam dimaksudkan perlunya upaya introspeksi terhadap raso yang dimiliki sendiri. Antah iyo antah indak, sebagai bentuk timbang rasa dalam hidup bermasyarakat. Perhatikan kato patiti : bajalan paliaro kaki bakato paliaro lidah kaki tataruang inai padahannyo lidah tataruang ameh padanannyo bajalan salangkah madok suruik kato sapatah dipikiri lamak di awak katuju di urang 28 Juli 2004
Kato Pitatah PatitiWritten by Ekadj. Dt. Endang Pahlawan Monday, 10 October 2005
latiek-latiek tabang ka pinang hinggok di pinang duo-duo satitiek aie dalam pinang disinan bamain ikan rajo Ketentuan adat sebagian besar tersimpan di dalam ajaran adat berbentuk kato-pitatah-patiti. Kondisi Minangkabau sedikit berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, terutama begitu menonjolnya budaya tutur dan hampir tiadanya aturan adat yang tertulis. Di dalam kato-pitatah-patiti tersimpan berbagai nilai dari berbagai ajaran agama dan sistem pemerintahan selama berabadabad lamanya, dan terwariskan dari generasi ke generasi sebagai wujud adat dan budaya masyarakat Minangkabau. Kato-pitatahpatiti yang sampai pada kita saat sekarang ini, merupakan nilai budaya terunggul setelah melalui berbagai seleksi dari berbagai generasi. Itulah inti adat yang kita pakai sebagai sejatinya manusia Minangkabau. Ajaran adat memiliki bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Tanpa pemahaman terhadap struktur kata-kata, agak sulit dalam memahami makna dan maksud dari berbagai ajaran adat tersebut. Penulis menemukan sebuah referensi yang cukup bagus, yang dapat menjelaskan beberapa pemahaman adat tersebut, yaitu buku Seluk-Beluk Adat Minangkabau" karya Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, penerbit N.V. Nusantara Bukittinggi-Jakarta tahun 1965. Uraian berikut adalah bersumber dari buku tersebut ditambah dengan beberapa sumber lain yang Penulis miliki. a. Kato-kato Adat Minangkabau ialah suatu susunan peraturan hidup yang diatur dengan kato-kato. Adapun kato-kato itu adalah suatu istilah adat yang artinya : serangkaian perkataan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua kalimat pendek, tetapi dalam artinya dan luas pemahamannya. Seperti contoh : hidup dikandung adat mati dikandung tanah Pernyataan di atas terdiri dari dua kato, tiap-tiap kato merupakan kalimat pendek. Kato pertama : hidup dikandung adat"; tersusun dari kata-kata pilihan : hidup dikandung adat. Maknanya adalah : segala tingkah laku dan perbuatan manusia Minangkabau di dalam lingkungan masyarakat adatnya diatur dalam peraturan-peraturan adat. b. Pitatah Pitatah atau pepatah, berasal dari kata tatah, yang maksudnya adalah pahatan atau patokan. Berbagai nilai dan ajaran adat dipahat dalam kato-kato berbentuk pitatah. Seperti kato hidup dikandung adat" merupakan kato pitatah, yang menjadi sumber peraturan yang mengatur segala hubungan dan sangkutan pergaulan hidup masyarakat Minangkabau. c. Patiti Patiti berasal dari titi, yang artinya : diatur secara seksama sehingga betul dan tepat. Sehingga patiti merupakan aturan yang mengatur pelaksanaan adat dengan seksama. Dengan demikian kalau pitatah merupakan pahatan kata yang menjadi norma hukum adat, maka patiti merupakan kaitan peraturan yang mengatur batas-batas pelaksanaan dari pitatah. Misalnya kato pitatah hidup dikandung adat", maka kato patitinya adalah : adat hidup tolong menolong adat mati janguak manjanguak karojo baiek baimbauan karojo Buruak baambauan d. Pantun Dalam memahami pitatah-patiti bagi masyarakat di masa lampau, dilakukan dengan berbagai cara di antaranya dengan menguntai kata ke dalam pantun. Hal ini dilakukan semata untuk memudahkan dalam penghapalan, seperti contoh : nan merah iyolah sago nan kuriak iyolah kundi nan indah iyolah baso
nan baiak iyolah budi Untuk pantun pitatah dapat dilihat sebagai berikut : panakiek pisau sirauik patungkek batang lintabuang salodang ambiek ka Niru satitiek jadikan lauik sakapa jadikan gunuang alam takambang menjadi guru Untuk pantun patiti dapat dilihat sebagai berikut : anak urang koto hilalang poi ka pakan baso malu jo sopan kalau lah hilang hilanglah raso jo pareso Marilah kita pelajari bagaimana nilai-nilai adat itu tersimpan di dalam kato-kato : latiek-latiek tabang ka pinang hinggok di pinang duo-duo satitiek aie dalam pinang disinan bamain ikan rajo Apakah mungkin setitik air di dalam pinang bisa menjadi tempat berenangnya ikan rajo? Perlu pemahaman yang mendalam tentang makna kato patiti tersebut. Seperti yang ditafsirkan oleh berbagai ahli adat : buah pinang berbentuk jantung, sebagai perlambang lubuk hati nurani. Setitik air di dalam buah pinang muda biasanya diambil sepemakan sirih. Setitik air ini merupakan lambang rasa peri kemanusiaan" di dalam lubuk hati manusia . Ikan rajo merupakan ibarat sesuatu yang besar, yaitu budi baik. Sehingga makna "ikan rajo bamain di satitiek aie dalam pinang" adalah : budi baik itu hidup dalam rasa peri-kemanusiaan yang terkandung dalam lubuk hati nurani manusia. Bentuk rasa yang berupa budi baik itulah yang dikatakan raso" menurut adat. raso tumbuah di dado pareso tumbuah di kapalo Marilah kita pahami beberapa pantun pitatah-patiti berikut : karakap madang di hulu baputik alah babuah balun marantau bujang dahulu di kampuang baguno balun hiu bali balanak bali ikan panjang bali dahulu induak cari dunsanak cari induak samang cari dahulu dimaa kain kabaju dijaik indaklah sadang lah takana mangko diungkai dimaalah nagari indak kamaju adat sajati tu banalah nan hilang dahan jo rantiang nan bapakai supayo jarami naknyo takerai larakkan padi ditampuaknyo supayo nagari naknyo salasai latakkan sasuatu di tampaiknyo anak urang koto hilalang pai ka pakan baso malu jo sopan kalau lah hilang
hilanglah raso jo pareso Rarak limau dek binalu tumbuah sarumpun jo sikasek kalau hilang malu jo sopan umpamo kayu lungga pangabek 28 Juli 2004
Babuhua Mati-Sintak, Barih-Balabeh Ukua-JangkoWritten by Ekadj. Dt. Endang Pahlawan Monday, 17 October 2005
kok tabik nan bak padi, digaro kok tumbuah nan bak bijo, disiang Ketentuan-ketentuan adat tersimpan dalam susunan adat yang berbentuk ikatan, pahatan, dan bangunan adat; atau yang disebut : adat nan babuhua mati jo babuhua sintak, barih-balabeh, dan ukua-jangko. Sedangkan ketentuan adat tersebut didasarkan pada norma adat yang dibentuk oleh tungku nan tigo sajarangan : alua-patuik, anggo-tanggo, dan raso-pareso. a. Babuhua Mati jo Babuhua Sintak Susunan adat memiliki sifat mutlak dan nisbi, karena asal-usul pembentukannya didasarkan pada nilai-nilai keyakinan keilahiatan hingga pengalaman hidup kemasyarakatan dari generasi ke generasi. Karena itu susunan adat ada yang bersifat tetap-abadi dan ada yang bersifat relatif-berubah. Ikatan terhadap susunan adat ini yang diibaratkan dengan buhua (buhul = simpul ikatan). Bilamana susunan adat itu bersifat tetap, maka disebut dengan babuhua mati, sedangkan sebaliknya disebut dengan babuhua sintak. Di dalam hukum nan ampek, susunan adatnya adalah batanggo turun, mulai dari babuhua mati hingga babuhua sintak, yaitu : adat nan sabana adat adat nan diadatkan adat nan teradatkan adat istiadat Keluwesan pembentukan nilai adat didasarkan pada tingkatannya. Untuk ketentuan babuhua mati, yaitu adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan, hampir tidak ada perubahan nilai terutama dalam kurun 600 tahun terakhir ini. Sebagaimana kato patiti : mamutiah cando riak danau tampak nan dari muko-muko baratuih tahun dalam lunau namun intan bakilek juo adat dipakai, baru baju dipakai, usang adat bapacik nan balaku limbago tajarang nan batuang
indak lapuak dek hujan indak lakang dek paneh Sedangkan untuk ketentuan babuhua sintak, yaitu adat nan teradatkan dan adat istiadat, telah mengalami banyak perubahan sesuai tuntutan zaman. Sebagaimana kato patiti : kok tabik nan bak padi, digaro kok tumbuah nan bak bijo, disiang baiak dipakai jo mufakek buruk dibuang jo rundingan b. Barih-Balabeh Barih (baris) mempunyai pengertian segala sesuatu yang membentuk susunan; sedangkan balabeh (belebas) mempunyai pengertian aturan yang membentuk susunan tersebut menjadi teratur. Dengan demikian pengertian barih-balabehadalah susunan yang telah diatur. Dalam pemahaman majemuk, pengertian barih-balabeh adalah ketentuan-ketentuan adat sebagai hukum adat, yang tersusun dari
kato-pitatah-patiti. Dapat dibayangkan di masa dahulu, pemahaman terhadap kato-pitatah-patiti diibaratkan sebagai baris-baris ketentuan (barih) yang tersusun sedemikian rupa (balabeh) yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Seorang penghulu disebut tantu jo barih-balabeh, ditafsirkan secara umum : paham dan menguasai hukum-hukum adat yang tersusun dari berbagai kato-kato adat. c. Ukua-Jangko Ukua (ukur) berarti ukuran terhadap suatu susunan, sedangkan jangko (jangka) adalah pembatasan terhadap suatu bentuk. Ukuajangko di dalam adat digunakan untuk mengukur dan memberikan batasan terhadap susunan dan bentuk bangunan adat. Sebagai sebuah bangunan, ketentuan adat di-ukua-jangko sehingga tercapai ketepatan bentuknya dan keserasian setiap tiang pembentuknya. Dari pemahaman di atas, maka barih diatur dengan balabeh. Susunan adat dapat dikur, sedangkan keteraturan di dalam susunan adat tersebut dapat dijangka. Barih diukua, balabeh dijangko. Aksioma pemahaman ini dapat dilanjutkan dengan ketentuan : barih baukua jo pitatah balabeh bajangko jo patiti d. Barih Baukua jo Pitatah Barih baukua jo pitatah dimaksudkan susunan adat diukur dengan pahatan kato. Bentuknya adalah : cupak nan duo undang-undang nan ampek kato nan ampek e. Balabeh Bajangko jo Patiti Balabeh bajangko jo patiti dimaksudkan keteraturan di dalam bangunan adat dibatasi secara seksama. Dengan demikian kato pitatah cupak nan duo, undang-undang nan ampek, kato nan ampek dibatasi dengan kato patiti : cupak usali cupak buatan undang-undang luhak undang-undang nagari undang-undang dalam nagari undang-undang nan 20 kato pusako kato dahulu kato mufakat kato kemudian Dalam pemahaman lebih lanjut ketentuan : - barih baukua jo pitatah, disebut anggo - balabeh bajangko jo patiti, disebut tanggo. Kuat rumah karanao sandi, Rusak sandi rumah binaso, Kuat bangso karano budi, Rusak budi hancualah bangso.
Ekonomi Manjilih di tapi aia Maradeso di paruik kanyang Hilang rupo dek pinyakik Ameh pandindiang malu Kain pandindiang miang Tak aia bambu dipancuang Tak kayu janjang dikapiang Tak ameh bungka diasah Kayu hutan bukan andaleh Elok dibuek ka lamari Tahan hujan barani ba paneh Baitu urang mancari rasaki ----- ----Semua dimamfaatkan nan buto pahambuih lasuang Nan pakak palapeh badia Nan lumpuah pahunyi rumah Nan kuat pambawo baban Nan cadiak ka dilawan barundiang Nan pandia ka disuruah suruah ----- ----Akhlak Bakato sapatah dipikiri bajalan salangkah maliyek suruik Muluik tadorong ameh timbangannyo Kaki tataruang inai padahannyo Urang pandorong kadang kanai Urang pandareh ilang aka ----- ----Diplomasi Kok tagang tajelo-jelo Kok kandua ba dantiang dantiang Pado pai surik nan labiah Samuik tapijak indak mati Alu tataruang patah tigo ----- ----Falsafah Layang Layang alang-alang dianjuang mangkonyo naik alah naiak carilah angin nan salasai Katahui raso jo raso Kok tagang dikandua-i Kok kandua tagang-tagangkan Carilah luruih batagak tali baa bana rancak lenggok di langik Pulangnyo ka tanah juo Bagisia banang di udaro
Ujuang jari marasokan Basaua banang di udaro Ka pangkanyo disalasaikan. ----- ----kapalang Tanggung alang tukang tabuang kayu Alang cadiak binaso adat Alang alim binaso agamo Alang safaham kacau nagari Dek ribuik kuncang ilalang Katayo panjalin lantai Hiduik jan mangapalang Kok nan kayo barani pakai Baburu ka padang data Dapek ruso balang kaki Baguru kapalang aja Bak bungo kambang tak jadi ----- ----Sosial Karajo baiak bahimbauan Karajo Buruak bahambuan ----- ----Kebesaran Nagari Basawah ladang Bataratak bapanyabuangan Badusun bagalanggang Ba itiak ba ayam Ba anak ba kamanakan Bakabau bakambiang Batabek taman taman Bakorok bakampuang ----- -----
Raja-raja Minang di NusantaraWritten by Afandri Adya Friday, 13 January 2012
Banyak pihak menilai, abad ke-20 merupakan masa kejayaan peradaban Minangkabau. Hal ini ditandai dengan besarnya peran mereka dalam lima lini pokok kehidupan bermasyarakat di Indonesia (dan Nusantara pada umumnya). Dari lima bidang tersebut, yakni : politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, serta sosial keagamaan, Minangkabau telah melahirkan ratusan bahkan ribuan ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Para ahli itu, yang telah go internasional dan bahkan melegenda antara lain : Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Tuanku Abdul Rahman, Yusof Ishak (politik); Hasyim Ning, Abdul Latief, Tunku Tan Sri Abdullah (ekonomi/bisnis); Chairil Anwar, Muhammad Yamin, Sutan Takdir Alisjahbana, Usmar Ismail, Soekarno M. Noer (budaya); Emil Salim, Sheikh Muszaphar Shukor, Taufik Abdullah, Azyumardi Azra (ilmu pengetahuan); serta Agus Salim, Hamka, Natsir, Tahir Jalaluddin, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syafii Maarif (sosial-keagamaan). Namun dari itu, sedikit sekali orang yang mengetahui kejayaan Minangkabau di masa lampau. Menurut hasil penelitian Mochtar Naim yang dituangkan dalam disertasinya Merantau, sejak dahulu kala orang-orang minang telah banyak berkontribusi dalam pembentukan peradaban Nusantara. Dan diantara mereka banyak pula yang menjadi raja ataupun pendiri sebuah kerajaan. Dalam tulisan kali ini, kita akan melihat sepak terjang raja-raja asal Minangkabau, yang memerintah di banyak negeri seantero Nusantara.
Dapunta Hyang Sri Jayanasa, dipercaya sebagai pendiri imperium besar Sriwijaya. Menurut Tambo alam Minangkabau, Dapunta Hyang berasal dari lereng Gunung Merapi, yang kemudian melakukan migrasi bersama sejumlah penduduk setempat. Dengan mengaliri Sungai Kampar dari pedalaman Minangkabau, Dapunta Hyang beserta rombongannya tiba di bibir pantai Selat Malaka. Mereka terus melanjutkan perjalanan ke selatan hingga bertemu muara Sungai Musi. Dari sini mereka mencoba memudiki Sungai Musi dan berjumpa lereng Gunung Dempo. Dari lereng gunung inilah kemudian Dapunta Hyang beserta rombongannya membangun sebuah kedatuan yang berpusat di tepian Sungai Musi. Kisah perjalanan Dapunta Hyang dari tanah Minang, terukir jelas dalam Prasasti Kedukan Bukit. Prasati itu bercerita tentang rombongan Dapunta Hyang yang selamat melakukan perjalanan dan penyerangan dari Minanga, bersama serombongan pasukan yang melewati darat maupun laut. Hingga saat ini, penafsiran isi prasasti tersebut masihlah simpang siur. Poerbatjaraka berpendapat bahwa Minanga (atau Minanga Tamwar) merupakan hulu pertemuan dua sungai Kampar, yang berada di luhak Lima Puluh Koto. Dan Minanga Tamwar diprediksi sebagai asal usul nama Minangkabau. Sedangkan para ahli lainnya seperti George Coedes dan Slamet Muljana, justru berteori bahwa Minanga merupakan kerajaan taklukan Dapunta Hyang yang terletak di hulu Batanghari. E.S Ito dalam novelnya Negara Kelima, juga menyinggung mengenai migrasi Dapunta Hyang dari Minangkabau ke Palembang. Dikatakannya bahwa Dapunta Hyang telah menghiliri Sungai Batanghari sampai ke muara Jambi, dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki hingga ke tepian Sungai Musi. Menurutnya Dapunta Hyang adalah salah seorang pembesar Minangkabau, yang ingin mengembalikan kejayaan imperium Atlantis. Putra Minangkabau lainnya yang duduk di tampuk kekuasaan adalah Kalagamet. Dia merupakan raja Majapahit kedua yang memerintah pada tahun 1309-1328. Kalagamet yang bergelar Sri Jayanagara, beribukan Dara Petak seorang permaisuri yang berasal dari Kerajaan Dharmasraya. Pada masa berkuasa, dia mengangkat saudara sepupunya yang juga keturunan Minangkabau, Adityawarman, sebagai duta untuk negeri Tiongkok. Adityawarman adalah putra Dara Jingga, permaisuri Dharmasraya lainnya yang bersuamikan Adwayawarman. Di masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, Adityawarman naik jabatan sebagaiwreddhamantri atau perdana menteri kerajaan. Dalam posisi strategis itu, dia membangkang kepada Tribhuwana dan melecehkan Majapahit. Pada tahun 1347, dia pulang kampung ke Sumatra dan mendirikan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini merupakan penerus wangsa Mauli yang telah berkuasa di Sumatra selama hampir satu setengah abad. Pada abad ke-14, Kerajaan Pagaruyung memiliki daerah taklukan ke hampir seluruh wilayah Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Kekuasaannya atas Nusantara barat, merupakan balance of power bagi Majapahit yang berkuasa di bagian tengah kepulauan. Selain Jayanagara dan Adityawarman, tokoh Majapahit lainnya yang dipercaya berasal dari Minangkabau adalah Gajah Mada. Namanya mengikuti genre jago silat Minang lainnya seperti Harimau Campa, Gajah Tongga, atau Anjing Mualim. Sebagian orang memperkirakan, Gajah Mada merupakan putra seorang pendekar Minangkabau yang ikut mengantarkan Dara Petak dan Dara Jingga ke Majapahit. Namun Ridjaluddin Shar dalam novelnya Maharaja Diraja Adityawarman: Matahari di Khatulistiwa, malah berpendapat sebaliknya. Menurutnya Gajah Mada adalah anak dari salah seorang pasukan Pamalayu yang menikahi gadis Minangkabau. Asal usul Gajah Mada memang penuh misteri dan tanda tanya. Hingga saat ini belum ada sejarawan yang berhasil mengungkap kelahiran dan kematian tokoh besar tersebut, kecuali hanya dugaan-dugaan awal saja. Yang jelas, Gajah Mada merupakan simbol kebesaran Majapahit dan persatuan Indonesia. Ketika ia ditunjuk sebagai perdana menteri pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dalam Sumpah Palapa ia bernazar akan menaklukkan seluruh Nusantara di bawah panji Majapahit. Namun janjinya tersebut tak sempat terwujud, sampai akhirnya kerajaan itu runtuh pada awal abad ke-16. Muhammad Yamin, seorang pakar hukum, ahli sejarah, budayawan, dan salah satu founding fathers Indonesia, merupakan pengagum berat sosok Gajah Mada. Kekagumannya mungkin juga dikarenakan pertalian darah yang sama sebagai putra
Minangkabau. Usahanya dalam merekonstruksi peran Gajah Mada dalam buku setebal 112 halaman, merupakan salah satu bentuk kegandrungannya. Jasa Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara, telah mengilhaminya untuk menggabungkan seluruh jajahan Hindia-Belanda dalam satu kesatuan wilayah politik. Pada bulan Oktober 1928, cita-citanya itu benar-benar terwujud. Dalam sebuah ikrar bersama yang kelak dikenal dengan Sumpah Pemuda, Yamin berhasil menyatukan seluruh komponen rakyat Hindia-Belanda, dalam satu bangsa, bahasa, dan tanah air. Pada tahun 1390, seorang pengelana Minangkabau yang kemudian berjuluk Raja Bagindo, mendirikan Kesultanan Sulu. Tak banyak riwayat mengenai raja yang satu ini, kecuali para keturunannya yang menjadi pelaut ulung. Kabarnya mereka sangat ditakuti oleh pedagang-pedagang Eropa yang acap melintasi perairan utara Nusantara. Mohd. Jamil al-Sufri dalam bukunya Tarsilah Brunei: The Early History of Brunei up to 1432 AD menyebutkan, bahwa dari silsilah raja-raja Brunei Darussalam, diketahui bahwa pendiri kerajaan ini : Awang Alak Betatar atau yang bergelar Sultan Muhammad Shah, berasal dari Minangkabau. Selain itu raja-raja Serawak di Kalimantan Utara, juga banyak yang berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan informasi para bangsawan Serawak, yang ditemui Hamka pada tahun 1960. Kamardi Rais Dt. Panjang Simulie dalam bukunya Mesin Ketik Tua juga memerikan berita bahwa ketika James Brook dirajakan di Serawak, yang melantiknya adalah datuk-datuk asal Minangkabau. Sultan Buyong, anak dari raja Indrapura yang bertahta di Pesisir Selatan, pernah berkuasa di Kesultanan Aceh pada tahun 1586-1596. Buyong (Buyung ?) naik menjadi raja, berkat pengaruh dan kekuatan para pedagang Minang yang berniaga di Kutaraja. Sebelum itu kakak ipar Buyong, Sultan Sri Alam, juga sempat bertahta di Kesultanan Aceh (1575-1576). Sri Alam berkuasa melalui kudeta berdarah hulubalang Minangkabau, yang disebut-sebut telah berkomplot dalam pembunuhan Sultan Muda. Untuk menyingkirkan pengaruh Minangkabau dari Kerajaan Aceh, sekaligus membalaskan dendam kematian Sultan Muda, pada tahun 1596 ulama-ulama Aceh melakukan pembunuhan berencana terhadap Buyong. Dengan terbunuhnya Buyong maka berakhirlah pengaruh Indrapura di tanah rencong. Kesultanan Indrapura yang beribu kota di Indrapura (selatan Painan), merupakan pecahan dari Kerajaan Pagaruyung. Pada paruh kedua abad ke-16, kesultanan ini memiliki pengaruh yang cukup luas di pesisir barat Sumatra. Wilayahnya menjangkau daratan Aceh di utara hingga Bengkulu di selatan. Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I atau yang dikenal dengan Raja Kecil adalah salah seorang putra Pagaruyung pendiri Kesultanan Siak Sri Indrapura. Sebelum mendirikan Kesultanan Siak pada tahun 1723, Raja Kecil sempat bertahta di Kesultanan Johor (1717-1722). Namun kekuasaannya tak bertahan lama, karena aksi kudeta yang dilancarkan Bendahara Abdul Jalil dan pasukan Bugis. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Siak melakukan perluasan teritori hingga ke wilayah Rokan, dan berhasil membangun pertahanan armada laut di Bintan. Pada tahun 1740-1745, Siak menaklukkan beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. Dan 40 tahun kemudian, wilayah kekuasaannya telah meliputi Sumatra Timur, Kedah, hingga Sambas di pantai barat Kalimantan. Di Semenanjung Malaysia, Raja Melewar yang merupakan utusan Pagaruyung, menjadi raja bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1773, konfederasi sembilan nagari di Semenanjung Melayu, membentuk sebuah kerajaan yang diberi nama Negeri Sembilan. Kerajaan ini terbentuk pasca derasnya arus migrasi Minangkabau ke wilayah tersebut. Seperti halnya masyarakat di Sumatra Barat, rakyat Negeri Sembilan juga menggunakan hukum waris matrilineal serta model adat Datuk Perpatih. Pada tahun 1957, Tuanku Abdul Rahman yang merupakan keturunan Raja Melewar, menjadi Yang Dipertuan Agung Malaysia pertama. Di Tapanuli, Sisingamangaraja yang dipercaya sebagai Raja Batak, juga berasal dari Minangkabau. Hal ini berdasarkan keterangan Thomas Stamford Raffles yang menemui para pemimpin Batak di pedalaman Tapanuli. Mereka menjelaskan bahwa Sisingamangaraja adalah seorang keturunan Minangkabau yang ditempatkan oleh Kerajaan Pagaruyung sebagai raja bawahan (vassal) mereka. Hingga awal abad ke-20, keturunan Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Minangkabau melalui perantaraan Tuanku Barus.