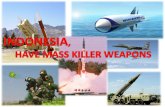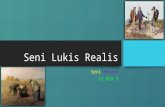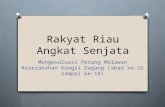Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ...
Perjanjian Pembatasan Dan Pengendalian Senjata, Perang Dalam Perspektif Realis
Click here to load reader
-
Upload
erika-angelika -
Category
Documents
-
view
1.171 -
download
3
Transcript of Perjanjian Pembatasan Dan Pengendalian Senjata, Perang Dalam Perspektif Realis

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 1
UAS Take Home Pengkajian Strategi—Dosen : Dra. Nurani Chandrawati, M.Si
Nama : Erika
NPM : 0706291243
1. Carilah satu contoh kasus perjanjian Pembatasan atau Pengendalian Senjata. Kemudian
berikan pemikiran kritis tentang isi Perjanjian berdasarkan konsep tentang Pengendalian dan
Pembatasan Senjata yang telah diberikan di Kuliah. Jelaskan pula pihak-pihak yang terlibat
dalam Perjanjian tersebut dan Tujuan Perjanjian tersebut!
Arms control/pembatasan senjata dimengerti sebagai upaya-upaya yang diambil untuk
menghambat pengembangan dan penggunaan senjata tertentu. Sementara
disarmament/perlucutan senjata dimengerti sebagai upaya untuk menghancurkan atau
memusnahkan jenis senjata tertentu. Tujuan dilakukannya pembatasan dan pengendalian
senjata adalah:
a. Mencegah mispersepsi dan salah pengertian terhadap tindakan lawan sehingga
dibutuhkan upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersaing dalam suatu
perundingan persenjataan (tujuan politis).
b. Upaya untuk membangun komunikasi secara terus-menerus.
c. Pemenuhan kebutuhan akan prestise dan kredibilitas negara dalam rangka pencegahan
perang dan pengelolaan krisis.
d. Untuk menciptakan hotline (terutama setelah Krisis Kuba), sebagai bentuk komunikasi
yang lebih efektif, serta untuk membentuk aturan main bersama dalam rangka
menghindari pertikaian yang tidak dikehendaki.
e. Membatasi proliferasi senjata secara vertikal, yaitu larangan pada negara yang berupaya
memiliki, mengembangkan, dan menggunakan berbagai senjata baru.
f. Membatasi proliferasi senjata secara horizontal, yaitu ketika penyebaran senjata dari
satu negara ke negara lain semakin banyak sehingga semakin banyak pula negara yang
memiliki dan menggunakan senjata tertentu.
Pembatasan dan pengendalian senjata ini sendiri dapat dilakukan dengan dua model, yaitu
model arms control dan model disarmament. Model arms control merupakan model yang
menganut prinsip Graduated Reciprocation in Tension-Reduction atau GRIT, dengan
memberikan batas akumulasi senjata secara kuantitas (membatasi jumlah) dan kualitas
(melarang pengembangan kualitas senjata tertentu). Sementara model disarmament
merupakan langkah pemusnahan total dan atau menghentikan penyebaran senjata ke
negara-negara lain.
Contoh kasus Perjanjian Pembatasan Senjata adalah Bangkok Treaty/Treaty on the Southeast
Asia Nuclear-Weapon-Free Zone, yang berisi tentang kesepakatan negara-negara ASEAN

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 2
untuk mewujudkan suatu kawasan bebas nuklir. Perjanjian tersebut melibatkan 10 negara
ASEAN (Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Philliphine, Kamboja,
Myanmar, Vietnam, Singapore, dan Laos). Bangkok Treaty sendiri merupakan tindak lanjut
dari Declaration on the Zone on Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) yang
ditandatangani pada 27 November 1971 di Kuala Lumpur, sebagai bukti komitmen
negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi aktif mewujudkan perdamaian dan stabilitas
regional.1 Bangkok Treaty juga bertujuan untuk turut aktif menegakkan pentingnya Treaty
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) dalam pencegahan pengembangan
senjata nuklir di kawasan ASEAN, serta untuk melindungi kawasan ASEAN dari polusi
lingkungan dan racun yang disebabkan oleh limbah dan material radioaktif yang datang dari
senjata nuklir.2 Bangkok Treaty sendiri ditanda tangani di Bangkok, Thailand, pada 15
Desember 1995 dan mulai aktif berjalan sejak 27 Maret 1997.3 Selain melibatkan 10 negara
ASEAN, Bangkok Treaty juga membuka dirinya pada 5 negara yang memiliki kepemilikan
senjata nuklir, yaitu Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat; akan tetapi kelima
negara tersebut masih belum mau meratifikasi Bangkok Treaty, dikarenakan masih ada
keberatan kelima negara ASEAN tersebut pada dimasukkannya wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif dan pantai kontinental pada wilayah larangan pemakaian nuklir.4
Tujuan
dimasukkan wilayah ZEE dan pantai kontinental pada Bangkok Treaty adalah karena negara
ASEAN ingin menciptakan suatu wilayah bebas nuklir/Nuclear-Weapon-Free Zone (NWFZ)
di Asia Tenggara, tidak hanya di wilayah daratan, namun juga pada wilayah perairan.5
Melalui Bangkok Treaty ini, negara-negara ASEAN menginginkan terciptanya kawasan
yang bebas dari segala bentuk senjata pemusnah massal.6
Sehubungan dengan konsep pengaturan dan pembatasan senjata, seperti berbagai perjanjian
pembatasan senjata lainnya, Bangkok Treaty berfungsi sebagai wadah komunikasi
negara-negara ASEAN dalam menyatukan tujuannya untuk membangun suatu wilayah Asia
Tenggara yang bebas nuklir. Bangkok Treaty, karenanya, berfungsi untuk menyamakan dan
menerapkan suatu aturan main bersama antar negara-negara ASEAN, yang kemudian harus
dipatuhi bersama demi terwujudnya stabilitas dan perdamaian kawasan. Proliferasi senjata
nuklir dalam Bangkok Treaty dilakukan dalam dua cara, secara horizontal yaitu melarang
1
Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (Bangkok Treaty). http://www.fas.org/
nuke/control/seanwfz/text/asean.htm, diakses pada 31 Mei 2009, pukul 08.56. 2 Ibid.
3Status of the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone Treaty. http://www.opanal.org/NWFZ/
Bangkok/bangkok_en.htm, diakses pada 31 Mei 2009, pukul 09.06. 4 NTI. Treaty of Bangkok. http://www.nti.org/f_wmd411/bangkok.html, diakses pada 31 Mei 2009, pukul 09.14.
5 Surya P. Subedi. Problems and Prospects of the Treaty on the Creation of Nuclear-Weapon-Free Zone in Southeast
Asia. http://www.gmu.edu/academic/ijps/vol4_1/subedi.htm, diakses pada 31 Mei 2009, pukul 09.19. 6 NTI, op.cit.

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 3
penyebaran senjata nuklir dari satu negara ke negara lain, dan secara vertikal, yaitu melarang
pengembangan kualitas senjata nuklir yang dimiliki. Dengan meratifikasi Bangkok Treaty,
kesepuluh negara ASEAN diikat oleh kesepakatan untuk tidak melakukan proliferasi senjata
nuklir baik secara horizontal, maupun secara vertikal. Penggunaan senjata nuklir dalam
wilayah yang disepakati juga dilarang. Semua ini dilakukan demi menciptakan keamanan,
stabilitas, dan perdamaian kawasan.
2. Berikan contoh kasus yang dapat menjelaskan pengertian Perang dari Perspektif Realis
kemudian berikan analisis anda mengapa perang tersebut anda anggap mewakili Perspektif
realis. Mohon contoh kasus adalah Perang yang current pada masa pasca perang dingin.
Boleh Perang antar negara maupun perang dalam negara.
Pengertian perang secara formal dipahami sebagai situasi dimana terjadi pertikaian di antara
dua pihak atau lebih yang berlawanan dengan menggunakan kekuatan militer. Dalam
memandang perang, Realis sebagai pandangan tertua dalam ilmu Hubungan Internasional
mengatakan:
a. Perang merupakan fenomena yang harus terjadi dalam situasi yang anarki, hal ini
berangkat dari asumsi dasar Realis tentang Anarkisme Internasional.
b. Perang merupakan hal yang wajar terjadi, tidak hanya dikondisikan oleh struktur yang
anarki tetapi juga dikendalikan oleh sifat dasar manusia. Pemikiran ini berangkat dari
asumsi dasar kaum Realis bahwa manusia adalah makhluk irasional dan senantiasa
memiliki sifat dan keinginan dasar untuk berkelahi (Hobbes).
c. Perang adalah fenomena wajar dan seringkali tidak dapat dihindari terutama dalam
pembentukan struktur sistem internasional.
d. Perang adalah lambang kejayaan negara.
e. Perang dianggap sebagai hal yang baik dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan dan demi
mempertahankan kepentingan nasional dan eksistensi suatu bangsa.
Realis juga menolak Doktrin Just War atau Perang yang adil, Realis menganut pandangan
Clausewitz tentang perang sebagai kelanjutan proses politik dengan menggunakan kekerasan.
Realis juga memandang tidak adanya aturan baku tentang dimulainya suatu peperangan.
Situasi dan kondisi sistem internasional yang anarki memberikan pengaruh paling minim
dari kemungkinan terjadinya perang. Realis berasumsi bahwa lawan akan selalu menyerang
terlebih dahulu dan segera, sehingga sebelum hal itu terjadi maka perlu disiapkan kekuatan
militer baik untuk kebutuhan pertama maupun untuk penangkalan. Hal inilah yang membuat
Realis memandang strategi perang sebagai bagian penting dari strategi pertahanan negara.
Oleh Realis, perang kemudian juga diartikan sebagai perlindungan terhadap kemungkinan
serangan pertama lawan. Menyinggung soal wilayah, Realis berpendapat ekskalasi perang
bersifat tidak terbatas dengan menggunakan kekuatan maksimal, sehingga pada dasarnya

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 4
perang sulit dikendalikan. Walaupun terdapat perjanjian damai atau Undang-Undang tentang
perang, namun dalam kenyataannya perjanjian tersebut seringkali dilanggar, bahkan oleh
pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan perjanjian tersebut. Akhirnya, Realis memandang
bahwa tujuan akhir perang adalah mencapai kehancuran lawan (penaklukkan). Tidak ada
upaya kompromi atau konsiliasi selama perang berlangsung, maupun setelah posisi
kemenangan perang dapat diraih. Perang, karenanya, merupakan alat untuk mencapai
kejayaan negara.
Contoh kasus Perang yang terjadi pada masa paska Perang Dingin yang dapat mewakili
pandangan kaum Realis adalah kasus invasi Amerika Serikat (AS) ke Irak yang terjadi pada
tahun 2003. Serangan itu sebenarnya berangkat dari kecurigan AS akan kepemilikan senjata
pemusnah massal (berupa senjata biologis, kimia, dan nuklir) di Irak.7 Demi menjawab
kecurigaannya, AS pun menyatakan niatnya untuk mengadakan pemeriksaan di Irak, niat
yang lantas ditolak mentah-mentah oleh Saddam Hussein.8 selaku Presiden Irak pada saat
itu. Penolakan Saddam Hussein membuat AS geram, tuduhan kepemilikan senjata pemusnah
massal pun semakin gencar dilancarkan. Tuduhan tersebut dibarengi dengan keinginan untuk
merubah rezim kepemimpinan di Irak9
yang diktator, karena rezim yang diktator
disebut-sebut semakin menyuburkan keberadaan organisasi teroris Al-Qaeda, yang
sebelumnya telah terlebih dahulu melakukan serangan pada gedung menara kembar World
Trade Center di AS pada serangan 11 September 2001. Perang terhadap Irak pun dijalankan,
tepatnya sejak 19 Maret 2003. Operasi militer AS di Irak itu dinamakan „Operation Iraqi
Freedom‟.10
Operasi militer ini didukung oleh banyak negara seperti Inggris, Australia, dan
Polandia, dengan menyediakan berbagai bantuan militer. Serangan AS ini berhasil
menghancurkan militer Irak. Invasi AS ke Irak ini diperkirakan menelan korban sebanyak
20.000 jiwa dari sisi masyarakat sipil Irak.11
Telah disebutkan sebelumnya, motif penyerangan AS ke Irak adalah karena Irak menolak
untuk dilakukan pemeriksaan di wilayahnya sehubungan dugaan kepemilikan senjata
pemusnah massal, serta untuk menumbangkan rezim diktator Saddam Hussein (dan
7 S. Rampton dan JC Stauber. Weapons of Mass Deception: The Uses of Propaganda in Bush’s War on Iraq.
(London: Constable and Robinson, 2003), hal. 37-63. 8 John Yoo. “International Law and the War in Iraq”, dalam The American Journal of International Law, Vol. 97,
No. 3, edisi Juli, 2003, hal. 565. 9 M.L. Sifry dan C. Cerf (eds). The Iraq War Reader: History, Documents, Opinions. (New York: Touchstone,
2003). 10
US Department of Defense. 21st Century Guide to Operation Iraqi Freedom: The Second Gulf War 2003.
(Progressive Management Publishers, 2003). 11
Human Rights Watch. Hearts and Minds: Post-War Civilian Deaths in Baghdad Caused by US Forces. (October
2003).

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 5
karenanya “menyelamatkan” rakyat Irak). Namun ternyata motif tersebut bukanlah motif
sebenarnya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa motif sebenarnya dari invasi AS ke Irak
adalah karena AS ingin menguasai sumber minyak untuk kepentingan nasional AS sendiri.
Irak adalah negara dengan sumber minyak terbesar kedua di Timur Tengah. Sumber minyak
yang murah dan accessible merupakan hal yang penting bagi perekonomian AS.12
Penguasaan terhadap sumber minyak di Irak berarti akan mengurangi ketergantungan AS
pada negara-negara produsen minyak (OPEC) dan pada Rusia. Selain berhubungan dengan
minyak sebagai sumber energi fundamental AS, penguasaan AS akan Irak juga dilakukan
untuk memenuhi ambisi AS memperluas hegemoninya, dimulai dari menguasai Irak sebagai
salah satu negara Timur Tengah. Proyek perluasan hegemoni ini sendiri dinamakan Project
for the New American Century, tujuan dari proyek tersebut adalah untuk mempromosikan
kepemimpinan global Amerika.13
Motif ketiga penyerangan AS ke Irak adalah, menurut
banyak sumber, untuk menyelesaikan dendam karena kekalahan Presiden Bush Sr. sebagai
ayah Presiden AS saat itu, George W. Bush di Perang Teluk pada 1991.14
Seorang seniman
Inggris pernah menyebutkan motif-motif invasi AS ke Irak pada puisinya yang berjudul
„Cause Belli‟, yaitu: elections, money, empire, oil, and Dad.15
Berbagai motif penyerangan AS ke Irak yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali unsur
dendam pribadi untuk membalas kekalahan Presiden Bush Sr., jelas menggambarkan
kepentingan nasional AS yang dapat dicapai melalui serangannya ke Irak. Hal ini sekaligus
membenarkan anggapan Realis, yang menyatakan unsur kepentingan nasional selalu
menjadi alasan di balik tingkah laku negara dalam berperang. Motif untuk memperluas
hegemoni AS juga membenarkan anggapan Realis, yang menyatakan perang seringkali
dilakukan sebagai lambang kejayaan negara; melalui serangannya ke Irak pada tahun 2003
silam, AS ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa dirinya masih merupakan
negara superpower yang berkuasa dan tidak tertandingi; bahwa AS masih merupakan negara
unggulan yang dapat menghabisi setiap lawannya yang tidak menurut padanya, dalam kasus
ini: Irak. Anggapan Realis yang menyatakan bahwa tujuan akhir perang adalah penaklukkan
kiranya juga ditemui dalam kasus Perang AS-Irak ini, di mana menurut penulis, pemenang
dari perang ini adalah AS.
Unsur kepentingan nasional sebenarnya juga dapat ditemui dari respon Irak ketika
menanggapi permintaan pemeriksaan AS atas dugaan kepemilikan senjata pemusnah massal.
Terlepas dari benar tidaknya anggapan tersebut, kekukuhan Saddam Hussein—selaku
12
Dominic McGoldrick. From ‘9-11’ to the ‘Iraq War 2003’, International Law in an Age of Complexity. (Oregon:
Oxford and Portland, 2004), hal. 19. 13
S Rampton dan J.C. Stauber. Weapons of Mass Deception: The Uses of Propaganda in Bush’s War on Iraq.
(London: Constable and Robinson, 2003), hal. 46-49. 14
Dominic McGoldrick, op.cit.., hal. 20. 15
J Simpson. The Wars against Saddam: Taking the Hard Road to Baghdad. (London : Macmillan, 2003), hal. 259.

Erika . 0706291243 . Jurusan Ilmu Hubungan Internasional . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
Universitas Indonesia
Page | 6
Presiden Irak kala itu—untuk menolak permintaan AS menunjukkan keinginan Irak untuk
menunjukkan dirinya juga adalah negara berdaulat yang masih eksis, yang harus dihormati
keberadaannya. Saddam memprediksi bahwa akan terjadi campur tangan AS yang lebih
besar dalam urusan internal Irak, bila Irak tidak mengambil sikap tegas sedini mungkin.16
Irak tidak ingin keberadaannya sebagai negara yang berdaulat diinjak-injak oleh AS, yang
dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massalnya, lantas berusaha untuk masuk ke
wilayah Irak. Keinginan untuk diakui dan tidak diperlakukan semena-mena itulah yang
mendasari penolakan Irak atas pemeriksaan AS ke wilayahnya.
Unsur ketiga selain motif kedua negara yang menunjukkan kasus Perang Irak-AS relevan
dengan anggapan kaum Realis tentang perang adalah dari segi asumsi Realis bahwa setiap
negara akan menjalankan self-help system. Dapat dilihat dari tidak akurnya hubungan
Irak-AS, dan dugaan akan adanya senjata pemusnah massal di Irak, Irak seperti sedang
mengembangkan self-help system untuk tidak bergantung pada negara lain, dengan
mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk terus eksis di dunia internasional. Amerika
Serikat, di sisi lain, juga senantiasa berupaya mengembangkan self-help system melalui
usahanya untuk menguasai sumber minyak di Irak, agar dirinya dependen secara energi dari
negara-negara penghasil minyak seperti Rusia. Upaya self-help system yang dilakukan Irak
ini ternyata membangkitkan security dilemma pada diri AS, yang merasa tersaingi oleh Irak
yang, selain memiliki sumber minyak melimpah, juga dikabarkan memiliki senjata
pemusnah massal. Dilema keamanan yang dialami AS ini lantas membuat AS melancarkan
serangan terhadap Irak, sebelum Irak menjadi semakin kuat dan akhirnya menggantikan
posisi AS sebagai negara superpower.
16
Michael R. Gordon dan General Bernard. Cobra II: The Inside Story of the Invasion and Occupation of Iraq.
(New York: Phanteon Books, 2006), hal. 4