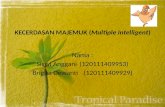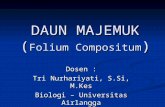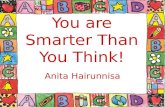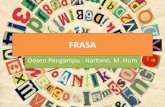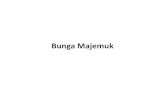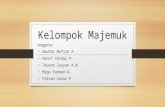PENGUKURAN INTENSITAS KONFLIK DALAM MASYARAKAT MAJEMUK
-
Upload
muhammad-rizky-firmansyah -
Category
Documents
-
view
25 -
download
1
description
Transcript of PENGUKURAN INTENSITAS KONFLIK DALAM MASYARAKAT MAJEMUK
-
v
Pendahuluan Ciri utama masyarakat majemuk (plural society) menurut Furnivall (1940) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Sebagai seorang sarjana yang untuk pertama kali menemukan istilah ini, Furnivall menunjuk masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang klasik. Masyarakat Hindia Belanda waktu itu terpisah-pisah, tidak saja antara kelompok yang memerintah dan yang diperintah dipisahkan oleh ras yang berbeda, tetapi secara fungsional masyarakatnya terbelah dalam unit-unit ekonomi, antara pedagang Cina, Arab, dan India (Foreign Asiatic) dengan kelompok petani Bumi Putera. Menurut Furnivall masyarakat dalam unit-unit ekonomi ini hidup menyendiri (exclusive) pada lokasi-lokasi pemukiman tertentu dengan sistem sosialnya masing-masing. Pemisahan kelompok-kelompok masyarakat ini dapat juga disebabkan karena perbedaan agama (seperti di Ireland), dan kasta (di India). Sebab utama dari pemisahan ini, ialah kepentingan untuk monopoli sumber-sumber ekonomi (economic resources). Dengan kata lain, kepentingan ekonomi dilanggengkan oleh ras, agama, suku, bangsa, hukum, politik, bahkan nasionalisme. Kasus kajian Furnivall mengenai masyarakat Indonesia 60 tahun yang lalu di
zaman kolonial yang melahirkan teori masyarakat majemuk ini, tentu saja akan berubah apabila ia kembali melihat bangsa Indonesia dewasa ini.
PENGUKURAN INTENSITAS KONFLIK DALAM MASYARAKAT MAJEMUK
Usman Pelly
Guru Besar Antropologi-Universitas Negeri Medan
Abstrak Masyarakat majemuk seperti Indonesia memiliki potensi konflik, baik karena faktor-faktor kemajemukan horizontal maupun faktor kemajemukan vertikal. Kondisi ke arah terjadinya konflik, potensial terjadi apabila faktor kemajemukan horizontal bersatu dengan faktor kemajemukan vertikal. Tulisan ini memberikan panduan bagaimana mengukur intensitas konflik, yang berguna bagi pengambil kebijakan dalam proses-proses penciptaan keserasian sosial dalam lingkungan masyarakat majemuk. Kata kunci: masyarakat majemuk, intensitas konflik, faktor horizontal, faktor vertikal.
Sementara itu, kajian mengenai masyarakat majemuk mendapat perhatian yang luas di kalangan ahli-ahli ilmu sosial, dengan berbagai hasil penelitian yang menarik, umpamanya, oleh Lewis (Urbanization Without Breakdown, 1952), Glazer & Moynihan (Beyond The Melting Pot, 1963), Edward Bruner (The Symbolic of Urban Migration, 1966), Barth (Ethnic Group and Boundaries, 1969), Cohen (Custom and Conflict in Urban Africa, 1971), Evers (Ethnic and Social Conflict in Urban Southeast Asia, 1980). Setidaknya, dewasa ini ada dua konsep masyarakat majemuk yang muncul dari berbagai hasil penelitian di atas: (1) konsep kancah pembauran (melting pot), dan (2) konsep pluralisme kebudayaan (cultural pluralism). Teori kancah pembauran pada dasarnya, mempunyai asumsi bahwa integrasi (kesatuan) akan terjadi dengan sendirinya pada suatu waktu apabila orang berkumpul pada suatu tempat yang berbaur, seperti di sebuah kota atau pemukimanindustri. Sebaliknya konsep pluralisme kebudayaan justru menentang konsep kancah pembauran di atas. Menurut Horace Kallen, salah seorang pelopor konsep pluralisme kebudayaan tersebut, menyatakan bahwa
-
Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISIVol. 1No.2Oktober 2005
kelompok-kelompok etnis atau ras yang berbeda tersebut malah harus di dorong untuk mengembangkan sistem mereka sendiri dalam kebersamaan, memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsep kancah pembauran hanyalah suatu mitos. Mitos yang tidak pernah menjadi kenyataan, sedang pluralisme kebudayaan menurut berbagai ahli telah mengangkat Amerika Serikat, Cina, Rusia, Kanada, dan India menjadi negara yang kuat. Urbanisasi dan industrialisasi Indonesia, seperti dibuktikan dalam sejarah, tidak dengan sendirinya mengikis unsur-unsur kemajemukan masyarakatnya, malah dalam berbagai studi menunjukkan kecenderungan penguatan aspek-aspek primordialisme (suku, agama, dan sistem simbolik lainnya) dalam kehidupan masyarakat kota. Ironisnya, kemajemukan primordialisme ini berkembang bersama proses transformasi masyarakat kota itu sendiri dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, sehingga kemajemukan dalam aspek kehidupan tersebut menjadi berganda. Masyarakat majemuk Indonesia lebih sesuai didekati dari konsep pluralisme kebudayaan, sebab integrasi nasional yang hendak diciptakan tidak berkeinginan untuk melebur identitas ratusan kelompok etnis bangsa kita, bahkan di samping hal itu dijamin oleh UUD 45, tetapi juga memerlukan pluralisme itu dalam pembangunan nasional. Masalahnya ialah bagaimana mengelola pluralisme itu dan menjauhkan dampak negatifnya dalam National Building. Kemajemukan masyarakat Indonesia dewasa ini, seperti juga pada masyarakat di belahan bumi lainnya tampak terutama di kota-kota besar sebagai wujud daripada proses urbanisasi yang tidak dapat dibendung. Dalam lima tahun terakhir ini penduduk kota di Indonesia, menurut hasil Sensus Nasional (1990) bertambah 20%. Kota-kota besar di Indonesia merupakan contoh masyarakat majemuk yang utama, sedang kota-kota kecil yang mekar di sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk Jakarta juga memperlihatkan ciri kemajemukan yang serupa. Konflik dan Persesuaian Apabila faktor-faktor kemajemukan masyarakat kota dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, horizontal dan vertikal, maka
faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Faktor Horizontal a. Etnis b. Bahasa daerah c. Adat-istiadat/perilaku d. Agama, dan e. Pakaian/makanan (budaya material)
2. Faktor Vertikal a. Penghasilan (income) b. Pendidikan c. Pemukiman d. Pekerjaan, dan e. Kedudukan Politis
Faktor kemajemukan horizontal merupakan faktor-faktor yang diterima seseorang sebagai warisan (ascribed-factors), sedang faktor-faktor kemajemukan vertikal lebih banyak diperolehnya dari usahanya sendiri (achievement-factors). Kemajemukan akan menjurus ke arah konflik yang sangat potensial apabila faktor kemajemukan horizontal bersatu dengan faktor kemajemukan vertikal. Dengan kata lain, apabila suatu kelompok etnis tertentu tidak hanya dibedakan dengan kelompok etnis lainnya karena faktor-faktor ascribed lainnya seperti bahasa daerah, agama, dan lain-lain, tetapi juga karena perbedaan faktor achievement seperti ekonomi, pemukiman dan kedudukan politis, maka intensitas konflik akan dapat menjurus kepada suasana permusuhan. Sebaliknya, apabila kemajemukan faktor-faktor horizontal tidak diperkuat oleh faktor-faktor vertikal, maka intensitas konflik sangat kecil dan mudah untuk dijuruskan kepada persesuaian atau harmoni. Intensitas konflik antarkelompok dapat digambarkan pada diagram berikut ini.
Lima faktor horizontal kemajemukan suatu kelompok dapat ditempatkan secara kumulatif pada sumbu y, sedangkan lima faktor kemajemukan vertikal ditempatkan secara kumulatif pada sumbu x. Dengan cara ini kita dapat mengukur tingkat intensitas potensi konflik, umpamanya antara kelompok etnis A, B, dan C.
Faktor-faktor horizontal dan vertikal
Angka Kumulatif
Kelompok A dan B
= 5 x 5 = 25
Kelompok A dan C
= 4 x 3 = 12
Kelompok B dan C
= 2 x 2 = 4
54
-
Usman Pelly Pengukuran Intensitas Konflik dalam Masyarakat Majemuk
55
1. Apakah perbedaan setiap kategori horizontal mencapai angka mutlak 1 (satu) atau 100% atau kurang dari 100% seperti antara kelompok suku Madura dan Jawa dalam bahasa daerah keduanya tidak berbeda benar jika dibandingkan dengan antara Ambon dan Aceh.
Kelompok A dan B hampir berbeda dalam kelima faktor, baik horizontal maupun vertikal (5x5), A dan C berbeda 4 faktor horizontal dan 3 faktor vertikal (4x3), sedang B dan C berbeda hanya dalam faktor horizontal 2 dan faktor vertikal 2 (2x2). Dari perhitungan kasar ini kita mendapat gambaran bahwa intensitas potensi konflik yang lebih tinggi adalah antara kelompok A dan B, sedang yang paling rendah adalah antara B dan C. Perhitungan di atas hanyalah merupakan langkah pertama untuk memberikan kepada kita semacam peringatan (warning) bahwa beberapa kelompok etnis tertentu memiliki potensi konflik yang lebih tinggi dari yang lain. Apabila kita ingin mengelola keserasian sosial antarkelompok-kelompok tersebut, maka perhitungan kasar tersebut, dapat diperhalus lagi sebagai berikut:
2. Apakah perbedaan setiap faktor vertikal mencapai angka mutlak satu (100%), seperti antara pemukiman elit dan kumuh, atau pemukiman semi elit dan elit.
3. Bobot perbedaan setiap faktor horizontal dan vertikal akan menghasilkan angka kumulatif tertentu pada sumbu x dan y. Dengan demikian perkalian setiap angka tersebut akan menunjukkan intensitas yang lebih ril antara individu kelompok yang satu dengan yang lain.
1 2 3 4
x 5 10 15 20 A- 5 4 3 2 1
25
20
15
10
5 y
1A-C
9
4 B-C1
Fungsi Pengukuran Intensitas Potensi Konflik Pengukuran di atas diperlukan bagi setiap pemimpin atau pengelola pembangunan yang ingin mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keserasian sosial dalam sebuah komunitas majemuk. Oleh karena itu suatu komunitas yang majemuk diperlukan suatu bentuk pengelolaan yang sering disebut sebagai management of conflict and disagreement. Seperti diutarakan sebelumnya, pengukuran ini akan memberikan gambaran atau isyarat (warning) seberapa jauh perbedaan
kemajemukan horizontal dan vertikal komunitas yang dihadapi mengandung potensi konflik. Secara praktis cara pengukuran ini setidaknya akan memudahkan kita dalam: (1) merekrut tokoh/kader lokal untuk memimpin berbagai kelompok, dan (2) membuat program dan perencanaan usaha-usaha pencegahan konflik dan pembinaan ke arah keserasian sosial. Usaha ke arah perbaikan kehidupan fisik dan nonfisik seperti: perbaikan pemukiman, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, lapangan kerja, akan sangat bermanfaat untuk mengurangi intensitas konflik faktor-faktor vertikal. Dengan kata lain, pemerataan
-
Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISIVol. 1No.2Oktober 2005
pembangunan akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk saling meningkatkan interaksi sosial dalam berbagai lembaga kehidupan ekonomi yang pada gilirannya tidak hanya akan menghilangkan sikap negatif/prasangka prejudice, tetapi juga akan memberi peluang yang lebih besar untuk saling memahami sistem makna dan simbolik budaya masing-masing kelompok dalam sebuah komunitas majemuk.
Dengan demikian, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta peningkatan kualitas kehidupan demokratisasi akan memperkecil intensitas potensi konflik dan masyarakat majemuk. Dalam keadaan itu pula usaha-usaha kerjasama akan lebih berfungsi ke arah keserasian sosial.
Daftar Pustaka Barth, Frederick. 1969. Ethnic Group and Boundaries: Social Organization of Cultural
Differences. Boston: Little Brown. Bruner, Edwar M.1982. The Symbolics of Urban Migration. Dalam The Prospects for Plural
Societies. David Maybury-Lewis (ed). Cohen, Abner. 1971. Customs and Politics in Urban Africa. London:
Routledge & Keegan. Glazer, Nathaniel dan Daniel Patrick Mcynihan 1963. Beyond The Melting Pot: The Negroes,
Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City. Boston: MIT Press.
56