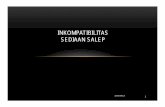PBL Blok 24 - Penyakit Hemolitik pada Bayi Baru Lahir et causa Inkompatibilitas ABO
Click here to load reader
-
Upload
samdisutanto -
Category
Documents
-
view
18 -
download
1
description
Transcript of PBL Blok 24 - Penyakit Hemolitik pada Bayi Baru Lahir et causa Inkompatibilitas ABO
Penyakit Hemolitik pada Bayi Baru Lahir et causa Inkompatibilitas ABO
Samdaniel Sutanto102013382 Kelompok B5Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida WacanaJalan Arjuna Utara No. 6 Jakarta Barat 11510Email: [email protected]
Abstrak: Penyakit hemolitik pada bayi baru lahir merupakan suatu gangguan yang dihasilkan dari destruksi sel darah merah bayi melalui perantaraan sistem imun sebagai akibat dari inkompatibilitas komponen darah ibu dengan komponen darah bayi. Inkompatibilitas ini dapat terjadi pada sistem Rhesus (Rh) maupun pada sistem ABO, namun yang paling sering menyebabkan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir adalah inkompatibilitas ABO. Kondisi ini banyak dijumpai pada ibu bergolongan darah O dan bayi bergolongan darah A atau B dikarenakan di dalam sirkulasi darah ibu bergolongan darah O terdapat antibodi terhadap faktor A dan B dalam jumlah besar. Sebagian besar kasus penyakit hemolitik yang diakibatkan oleh inkompatibilitas ABO bersifat ringan, dengan ikterus menjadi satu-satunya manifestasi klinis yang ditimbulkan. Walaupun gejalanya ringan, perlu diwaspadai mengenai hiperbilirubinemia yang ditimbulkan oleh karena kondisi tersebut akan berdampak sangat serius bila tidak ditangani segera. Terapi inkompatibilitas ABO dapat dilakukan dengan memberikan imunoglobulin intravena, porfirin timah, fototerapi dan transfusi tukar.
Kata Kunci: Inkompatibiltas ABO, hiperbilirubinemia, penyakit hemolitik.
Abstract: Hemolytic disease of the newborn is a disorder that results from destruction of the baby's red blood cells through the mediation of the immune system as a result of component incompatibility in maternal blood with baby blood components. This incompatibility can occur in the Rhesus system (Rh) and the ABO system, but the most frequent cause of hemolytic disease in newborns is ABO incompatibility. This condition is often found in the O blood group mother and in A or B blood group baby because the O blood group mother has antibodies against factor A and B in large quantities. Most cases of hemolytic disease caused by ABO incompatibility are mild, with jaundice being the only clinical manifestations caused. Although the symptoms are mild, physicians should be aware of the hyperbilirubinemia inflicted by these conditions would be very serious if not treated immediately. ABO incompatibility therapy can be done by giving intravenous immunoglobulin, tin porphyrin, phototherapy and exchange transfusion.
Key Words: ABO incompatibility, hyperbilirubinemia, hemolytic disease.
PendahuluanPenyakit hemolitik pada bayi baru lahir merupakan suatu gangguan yang dihasilkan dari destruksi sel darah merah bayi melalui perantaraan sistem imun sebagai akibat dari inkompatibilitas komponen darah ibu dengan komponen darah bayi. Inkompatibilitas ini dapat terjadi pada sistem Rhesus (Rh) maupun pada sistem ABO, namun yang paling sering menyebabkan penyakit hemolitik pada bayi baru lahir adalah inkompatibilitas ABO.Sekitar 20% bayi mengalami inkompatibilitas sistem ABO dengan darah ibunya, dan hanya sedikit kasus saja yang menunjukkan gejala klinis. Meskipun inkompatibilitas ABO sangat jarang menyebabkan hidrops fetalis pada bayi, namun penyakit ini masih berpotensi menjadi penyebab kasus anemia dan ikterus pada bayi baru lahir. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai jenis inkompatibilitas beserta gejala yang ditimbulkan perlu ditingkatkan guna untuk membantu petugas kesehatan dalam membedakan jenis inkompatibilitas yang dihadapi sehingga dapat ditentukan pengobatan yang tepat.
PembahasanInkompatibilitas ABO merupakan penyebab tersering dari penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Sekitar 15% dari bayi yang dilahirkan memiliki risiko untuk mengalami inkompatibilitas ABO, namun manifestasi klinis dari penyakit ini hanya terjadi pada sekitar 0,3-2,2%. Inkompatibilitas golongan darah mayor yang terjadi di antara ibu dan bayi umumnya akan berakhir pada kondisi yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus inkompatibilitas Rh. Biasanya inkompatibilitas ABO dapat terjadi pada ibu bergolongan darah O dan bayi yang memiliki golongan darah A atau B.1Inkompatibilitas ABO berbeda dengan inkompatibilitas Rh dikarenakan oleh beberapa alasan sebagai berikut:2 Inkompatibilitas ABO sering ditemukan pada bayi yang pertama. Hal ini terjadi oleh karena sebagian besar wanita bergolongan darah O memiliki antibodi anti-A dan anti-B sebelum masa kehamilan. Sebagian besar antibodi anti-A dan anti-B adalah imunoglobulin M (IgM), di mana antibodi ini tidak dapat melalui sawar plasenta sehingga tidak dapat mencapai eritrosit di dalam sirkulasi darah bayi. Selain itu, sel darah merah janin memiliki lebih sedikit situs antigen A dan antigen B dari sel dewasa sehingga menjadi kurang imunogenik. Penyakit yang disebabkan oleh inkompatibilitas ABO biasanya selalu lebih ringan daripada yang disebabkan oleh inkompatibilitas Rh dan jarang menghasilkan anemia yang signifikan. Bayi yang terkena biasanya jarang mengalami eritroblastosis fetalis (hidrops fetalis), melainkan hanya mengalami anemia dan ikterus yang pada umumnya dapat diobati dengan fototerapi. Inkompatibilitas ABO dapat mempengaruhi kehamilan berikutnya, namun tidak seperti inkompatibilitas Rh, penyakit inkompatibilitas ABO jarang menjadi semakin parah pada kehamilan berikutnya. Katz dan koleganya (1982) mengidentifikasi rekurensi pada 87% kasus. Dari jumlah tersebut, sekitar 62% kasus perlu dilakukan pengobatan yang pada umumnya terbatas pada fototerapi.EtiologiKasus hemolitik akibat inkompatibilitas ABO disebabkan oleh ketidakcocokan dari golongan darah ibu dengan golongan darah bayi sehingga terjadi destruksi sel-sel darah merah bayi yang diperantarai oleh sistem imun.3 Kondisi ini banyak dijumpai pada kondisi di mana ibu memiliki golongan darah O dan bayi bergolongan darah A atau B. Hal ini dikarenakan di dalam sirkulasi darah ibu bergolongan darah O terdapat antibodi terhadap faktor A dan B dalam jumlah besar.4 Walaupun antibodi terhadap faktor A dan B dapat terbentuk secara alami, umumnya antibodi ini adalah antibodi IgM yang tidak dapat melewati sawar plasenta. Namun, beberapa ibu bergolongan darah O memiliki antibodi IgG terhadap faktor A yang dapat melewati sawar plasenta sehingga menyebabkan hemolisis sel darah merah bayi bergolongan darah A. Begitu juga dengan bayi bergolongan darah B yang dipengaruhi oleh antibodi terhadap faktor B.1
EpidemiologiPenyakit hemolitik pada bayi baru lahir mempengaruhi sekitar 3 dalam 100.000 hingga 80 dalam 100.000 pasien setiap tahunnya. Inkompatibilitas ABO merupakan penyebab yang paling sering dan biasanya terjadi pada kehamilan pertama dan terjadi pada sekitar 12% kehamilan, dengan sekitar 3% kasus mengalami sensitisasi.5
PatofisiologiInkompatibilitas ABO pada umumnya terjadi pada ibu yang memiliki golongan darah O dan bayinya yang memiliki golongan darah A atau B. Sensitisasi darah ibu terhadap antigen darah bayi dapat terjadi akibat dari tranfusi sebelumnya atau akibat kondisi kehamilan yang menyebabkan eritrosit bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, seperti aborsi pada trimester pertama, kehamilan ektopik, amniosentesis, ekstraksi plasenta secara manual, previa plasenta, abruptio plasenta, dan trauma.6,7Pada ibu yang memiliki golongan darah A atau B, terdapat antibodi alami yang terbentuk berupa antibodi IgM yang tidak dapat melewati sawar plasenta, sedangkan 1% ibu bergolongan darah O memiliki titer antibodi IgG terhadap golongan darah A dan B yang tinggi. Antibodi ini kemudian akan masuk melewati sawar plasenta dan menyebabkan hemolisis dari eritrosit di dalam tubuh bayi. Hemolisis eritrosit akan menyebabkan hiperbilirubinemia sebagai manifestasi utama dari inkompatibilitas, dan pada gambaran darah tepi sering dijumpai sejumlah besar sferosit dan sedikit eritroblas. Hal ini berbeda dengan inkompatibilitas Rh, di mana pada gambaran darah tepi akan dijumpai sejumlah besar eritrosit berinti dan sedikit sferosit (lihat Gambar 1).5
Sumber: pathologystudent.comGambar 1. Sferosit yang Ditemukan pada Pemeriksaan Sediaan Apus Darah Tepi.
Manifestasi KlinisSebagian besar kasus penyakit hemolitik yang diakibatkan oleh inkompatibilitas ABO bersifat ringan, dengan ikterus menjadi satu-satunya manifestasi klinis yang ditimbulkan. Hidrops fetalis sangat jarang terjadi.1 Ikterus biasanya terjadi dalam waktu 24 jam pertama dan dapat mencapai puncak dalam waktu 12 jam.8 Walaupun gejalanya ringan, perlu diwaspadai mengenai hiperbilirubinemia yang ditimbulkan oleh karena kondisi tersebut akan berdampak sangat serius bila tidak ditangani segera. Efek yang dapat ditimbulkan oleh adanya hiperbilirubinemia meliputi kernikterus (kerusakan otak yang disebabkan oleh kadar bilirubin yang tinggi), serebral palsy, dan tuli.1,9
DiagnosisDiagnosis penyakit hemolitik akibat inkompatibilitas ABO dapat ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan fisik, tanda diagnosis yang tipikal pada bayi dengan ibu alloimunisasi ialah ikterik, kulit tampak pucat, hepatosplenomegali dapat diamati, sebagai tanda dari eritropoiesis ekstrameduler yang dihasilkan oleh tubuh bayi sebagai respon terhadap hemolisis yang signifikan. Dalam upaya untuk mengimbangi kerusakan peningkatan sel, hati dan limpa memproduksi sel-sel darah merah untuk jangka waktu lebih lama dari biasanya terlihat pada janin dan bayi baru lahir. Kendurnya sinusoid limpa oleh sel darah merah yang rusak berkontribusi untuk menyebabkan splenomegali.10Pemeriksaan laboratorium yang berguna ialah dengan melakukan pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah, dapat diperoleh nilai hemoglobin yang normal atau mungkin serendah 10 12 g/dL. Pada pemeriksaan apus darah tepi, dapat dijumpai adanya eritrosit berinti, retikulositosis, polikromasia, anisositosis, sferosit, dan fragmentasi sel. Hitung retikulosit dapat mencapai 40% pada pasien tanpa intervensi intrauterina. Eritrosit berinti yang meningkat disertai dengan peningkatan semu dari leukosit, menunjukkan keadaan eritropoiesis. Sferosit (< 40%) lebih umum ditemukan pada kasus inkompatibilitas ABO.11Pemeriksaan Coombs dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi tidak lengkap dengan menggunakan anti-human globulin. Pemeriksaan Coombs terdiri dari 2 macam jenis, yaitu: tes Coombs direk dan tes Coombs indirek.12 Tes Coombs indirek dan direk memberikan hasil positif pada ibu dan bayi yang terkena. Tidak seperti alloimunisasi Rh, hasil tes Coombs direk positif hanya sekitar 20-40% dari bayi dengan ABO inkompatibilitas. Meskipun hasil tes Coombs indirek (serum neonatus dengan dewasa A atau B sel darah merah) lebih sering positif pada neonatus dengan ABO inkompatibilitas, tes ini juga memiliki nilai prediktif yang jelek untuk mengetahui suatu hemolisis.11Hiperbilirubinemia merupakan salah satu tanda dari pemeriksaan laboratorium lainnya yang abnormal. Sekitar 10 20% bayi yang mengalami inkompatibilitas ABO, kadar bilirubin tak terkonjugasi dalam serum dapat mencapai 20 mg/dL atau lebih, kecuali bila diberikan fototerapi.1
Diagnosis BandingInkompatibilitas yang melibatkan sistem Rh merupakan penyebab kedua tersering masalah alloimunisasi pada bayi, namun komplikasi yang ditimbulkan jauh lebih parah daripada yang ditimbulkan oleh inkompatibilitas ABO. Antibodi tidak pernah dibentuk secara alami pada sistem Rh, melainkan harus melalui pemaparan antigen untuk dapat memperoleh antibodi terhadap sistem Rh. Paparan antigen diduga terjadi melalui inokulasi ibu dengan eritrosit janin melalui perdarahan plasenta atau melalui perdarahan tidak terdeteksi selama persalinan, aborsi, kehamilan ektopik, dan amniosentesis.10Inkompatibilitas Rh dapat terjadi pada bayi yang memiliki Rh positif dan ibu dengan Rh negatif yang telah tersensitisasi. Ibu dengan Rh negatif biasanya tersensitisasi dalam beberapa hari pertama setelah persalinan, yaitu ketika eritrosit dengan Rh positif dari janin akan masuk ke dalam sirkulasi darah ibu. Dikarenakan pembentukan antibodi memerlukan beberapa minggu, bayi pertama dengan Rh positif dari ibu yang memiliki Rh negatif biasanya tidak terkena dampaknya, sedangkan bayi dengan Rh negatif tidak memiliki antigen pada eritrositnya untuk bereaksi dengan antibodi ibu sehingga tidak akan terkena dampak.13Setelah ibu dengan Rh negatif mengalami sensitisasi, antibodi Rh dari darah ibu selanjutnya akan ditransfer ke dalam darah bayi pada kehamilan berikutnya melalui sirkulasi plasenta. Antibodi tersebut kemudian akan bereaksi dengan antigen eritrosit bayi yang memiliki Rh positif, menyebabkan aglutinasi dan hemolisis. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya anemia berat dengan kompensasi berupa hiperplasia dan pembesaran organ-organ pembentuk sel-sel darah, termasuk limpa dan hati, di dalam tubuh bayi. Fungsi hati mungkin dapat terganggu, disertai dengan penurunan jumlah produksi albumin yang dapat menyebabkan edema masif yang disebut sebagai hidrops fetalis (lihat Gambar 2). Jika kadar bilirubin indirek dalam darah menjadi sangat tinggi akibat hemolisis eritrosit yang berlangsung terus-menerus, bahaya terjadinya kernikterus dapat terjadi, menyebabkan kerusakan otak yang parah dan dapat berakhir dengan kematian.13 Penyakit yang disebabkan oleh inkompatibilitas Rh ini sangat mirip dengan inkompatibilitas ABO, tetapi memiliki perbedaan yang cukup signifikan (lihat Tabel 1).Tabel 1. Perbandingan Inkompatibilitas Rh dengan Inkompatibilitas ABO.
RhABO
Golongan Darah IbuNegatifO
Golongan Darah BayiPositifA atau B
Aspek Klinis yang Tampak pada Anak Pertama4%40-50%
Progresivitas pada Kelahiran BerikutnyaBiasanyaTidak
Hidrops FetalisSering Jarang
Anemia Berat++++
Hepatosplenomegali++++
Test Coomb Direk++/-
Antibodi MaternalSelalu adaTidak jelas
Sferosit -+
Insiden Late AnemiaSeringJarang
Sumber: library.med.utah.eduGambar 2. Hidrops Fetalis.
PenatalaksanaanPenatalaksanaan berupa terapi medikamentosa digunakan untuk mengelola hiperbilirubinemia dengan merangsang induksi sel-sel hati untuk mepengaruhi penghancuran heme atau untuk mengikat bilirubin dalam usus halus sehingga reabsorbsi enterohepatik menurun. Penggunaan imunoglobulin intravena (IVIG) dengan dosis 0,5 1 g/kgBB telah mampu secara efektif dalam menekan hemolisis dan mengurangi kebutuhan akan tindakan transfusi tukar. Pemberian IVIG dilakukan selama 2 jam dan bila perlu boleh diulang 12 jam kemudian jika bayi mengalami penyakit autoimun hemolitik dan kadar bilirubin total meningkat walaupun telah dilakukan fototerapi secara intensif.11Selain pemberian IVIG, pemberian porfirin timah juga berguna dalam menghambat heme oksidase, yaitu enzim yang berperan dalam proses katabolisme heme menjadi bilirubin. Pemberian porfirin timah sangat bermanfaat dalam mengurangi kebutuhan akan transfusi tukar dan durasi fototerapi pada bayi yang mengalami inkompatibilitas ABO. Efek samping pemberian porfirin timah ini meliputi fotosensitisasi kulit, defisiensi zat besi, dan kemungkinan penghambatan produksi karbon monoksida. Selain porfirin timah, tersedia juga dalam bentuk protoporfirin seng dan mesoporfirin.11Fototerapi saat ini masih menjadi modalitas terapeutik yang umum dilakukan pada bayi dengan ikterus dan merupakan terapi primer pada neonatus dengan hiperbilirubinemia tidak terkonjugasi. Fototerapi diperbolehkan untuk dilakukan pada kadar bilirubin total 2-3 mg/dL untuk bayi dengan usia 38 minggu dan sehat. Dalam melakukan fototerapi, bayi harus ditutup matanya, dalam keadaan telanjang dan dalam jarak 45 cm antara sinar dan bayi. Pemberian ASI dilakukan tiap 2 jam, suhu tubuh dilakukan tiap 4 jam, dan cek kadar bilirubin tiap 12 jam. Jika kadarnya sudah < 10 mg/dL, maka fototerapi dapat dihentikan. Beberapa efek samping fototerapi adalah perubahan suhu tubuh bayi, konsumsi oksigen, laju napas, dapat timbul kemerahan jika terlalu panas (bronze baby syndrome), dan hilangnya cairan tubuh (insensible loss).14Transfusi tukar dilakukan jika fototerapi intensif gagal dilakukan. Pada kasus-kasus yang berat di mana untuk mengoreksi tingkat anemia atau hiperbilirubinemia yang sudah berbahaya, penatalaksanaan untuk bayi adalah dengan cara melakukan transfusi tukar dengan golongan darah O yang memiliki tipe Rh sama dengan bayi. Transfusi tukar memiliki efek samping untuk bayi, di antaranya bayi bisa mengalami hipokalsemia, hipoglikemia, gangguan keseimbangan asam basa, pendarahan, infeksi, hemolysis, dan bisa menyebabkan gangguan kardiovaskular.14
Komplikasi15Ada dua komplikasi utama yang disebabkan oleh penyakit hemolitik pada bayi baru lahir meliputi ensefalopati bilirubin dan anemia. Gejala ensefalopati bilirubin meliputi letargi, tidak mau makan, dan pada akhir minggu pertama kehidupan, bayi menjadi demam dan hipertonik disertai tangisan bernada tinggi (high-pitched cry). Refleks tendon dan respirasi menjadi terdepresi. Bayi akan mengalami opistotonus disertai penonjolan dahi ke anterior.Anemia yang ditimbulkan disebabkan oleh beberapa faktor meliputi supresi eritropoiesis di dalam tubuh bayi dari transfusi Hb dewasa selama berada dalam intrauterus atau oleh transfusi tukar yang menyebabkan rendahnya kadar eritropoietin dan retikulosit. Destruksi eritrosit bayi oleh antibodi ibu yang berkelanjutan juga berperan dalam menyebabkan terjadinya anemia.
Prognosis15Secara keseluruhan, angka ketahanan hidup dapat mencapai 85-90%, namun dapat berkurang sebanyak 15% pada janin dengan hidrops fetalis. Kebanyakan janin yang bertahan hidup dari alloimunisasi gestasi, tetap memiliki fungsi neurologis yang intak. Walau begitu, abnormalitas neurologis telah dilaporkan berkaitan dengan derajat beratnya anemia dan asfiksia perinatal.
Kesimpulan Penyakit hemolitik pada bayi baru lahir merupakan suatu gangguan yang dihasilkan dari destruksi sel darah merah bayi melalui perantaraan sistem imun sebagai akibat dari inkompatibilitas komponen darah ibu dengan komponen darah bayi. Inkompatibilitas ini dapat terjadi pada sistem Rhesus (Rh) maupun pada sistem ABO. Kondisi ini perlu mendapat penanganan secara cepat dan tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi seperti bilirubin ensefalopati, anemia, dan komplikasi berat seperti hidrops fetalis.
Daftar Pustaka1. Kliegman RM, Stanton BF, St Geme III JW, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of pediatrics. 20th ed. Canada: Elsevier; 2016. p.886-7.2. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Rouse DJ, Spong CY. Williams obstetrics. 23rd ed. New York: McGraw-Hill; 2010. p.619.3. Ross MB, Alarcn PD. Hemolytic disease of the fetus and newborn. NeoReviews 2013;14(2):e83-8.4. Parveen N. Hemolytic disease of the newborn due to ABO incompatibility. Journal of Postgraduate Medical Institute 2011;4(1):117-9.5. Wagle S, Deshpande PG, Windle ML, Clark DA, Rosenkrantz T, Itani O. Hemolytic disease of newborn [cited, 2016 April 24]. Available from url:http://emedicine.medscape.com/article/974349-overview.6. Madara B, Avery CT, Pomarico-Denino V, Wagner L. Quick look nursing: obstetric and pediatric pathophysiology. Canada: Jones and Bartlett Publishers; 2008. p.108.7. Marcdante KJ, Kliegman RM. Nelson essentials of pediatrics. 7th ed. United States of America: Elsevier; 2015. p.216-7.8. Lissauer T, Clayden G. Illustrated textbook of paediatrics. 4th ed. China: Elsevier; 2012. p.169.9. Martin S, Jerome RN, Epelbaum MI, Williams AM, Walsh W. Addressing hemolysis in an infant due to mother-infant ABO blood incompatibility. J Med Libr Assoc 2008;96(3):183-8.10. Kenner C, Lott JW. Comprehensive neonatal care: an interdisciplinary approach. 4th ed. China: Elsevier; 2007. p.231.11. Ifeanyi OE. Hemolytic disease of the newborn: a review. Inter J of Pharmacotherapy 2015;5(1):58-67.12. Sudiono H, Iskandar I, Edward H, Halim SL, Kosasih R. Penuntun patologi klinik: hematologi. Jakarta: Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran UKRIDA; 2007. h.214.13. Porth CM, Matfin G. Pathophysiology: concept of altered health states. 8th ed. China: Lippincott Williams & Wilkins; 2009. p.297-8.14. Kosim MS, Yunanto A, Dewi R, Sarosa GI, Usman A. Buku ajar neonatologi. Edisi ke-1. Jakarta: IDAI, 2008. h.147-69.15. Wagle S, Deshpande PG, Windle ML, Clark DA, Rosenkrantz T, Itani O. Hemolytic disease of newborn follow-up [cited, 2016 April 25]. Available from url: http://emedicine.medscape.com/article/974349-followup.1