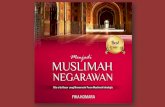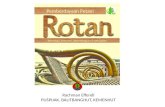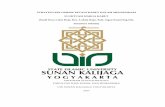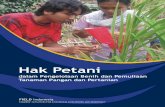Negara Agraris Tanpa Petani
-
Upload
dewa-ndaru -
Category
Documents
-
view
7 -
download
3
description
Transcript of Negara Agraris Tanpa Petani

Analisis Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Pertanian
A. Latar Belakang
Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kaya Indonesia akan sumber daya alam
dengan segala flora, fauna dan potensi hidrografis dan deposit sumber alamnya yang
melimpah. Sumber daya alam Indonesia berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan
perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi.
Sebagai negara agraris, sektor pertanian seharusnya bisa menjadi lapangan pekerjaan yang
sangat menguntungkan bagi warga negara Indonesia. Indonesia memiliki luas lahan 190,9
juta ha, lahan yang telah dimanfaatkan untuk pertanian sebesar 37,1% atau 70,8 juta ha.
Lahan Pertanian tersebut di manfaatkan bagi peruntukan sawah, lahan kering, perkebunan
dan non pertanian. Namun lahan yang belum termanfaatkan masih 62,9 % atau 120,2 juta ha.
Lahan ini masih berupa hutan (Isa, 2012). Potensi lahan yang masih luas, tidak menunjukkan
kekuatan Indonesia di sektor pertanian saat ini.
Seiring berjalannya waktu, posisi sektor pertanian sebagai basis perekonomian Indonesia
mulai tereduksi dan digantikan oleh sektor non pertanian. Sampai dengan tahun 1970an,
sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Indonesia. Namun, booming harga
minyak pada tahun 1980an menyebabkan paradigma pembangunan berubah, dari
perekonomian berbasis sektor tradisional ke modern. Proses pembangunan lebih banyak
diorientasikan ke sektor modern. Akibatnya, pembangunan sektor pertanian tersendat
sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB semakin menurun.
Kecenderungan penurunan tersebut berlangsung hingga kini.
Menurut data BPS pertumbuhan PDB tahun 2013 mencapai 5,78 persen, dimana semua
sektor ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor
Pengangkutan dan Komunikasi yang mencapai 10,19 persen, diikuti oleh Sektor Keuangan,
Real Estat, dan Jasa Perusahaan 7,56 persen, Sektor Konstruksi 6,57 persen, Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran 5,93 persen, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5,58
persen, Sektor Industri Pengolahan 5,56 persen, Sektor Jasa-jasa 5,46 persen, Sektor
Pertanian 3,54 persen, dan Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,34 persen. Pertumbuhan
PDB tanpa migas pada tahun 2013 mencapai 6,25 persen yang berarti lebih tinggi dari
pertumbuhan PDB.

Data tentang pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian tidak
begitu besar bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi non-pertanian yang mengalami
peningkatan signifikan. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap
total pertumbuhan PDB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,42 persen. Selanjutnya
diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,07 persen dan 1,03
persen, sedangkan untuk sektor pertanian sumber pertumbuhannya sebesar 0,45 persen.
Perkembangan pesat yang terjadi di perkotaan terus mengakibatkan alih fungsi lahan
pertanian menjadi non pertanian. Kondisi ini berdampak pada semakin sempitnya luas lahan
pertanian yang dimiliki oleh petani. Setidaknya terdapat dua alternatif yang ditempuh oleh
para petani yaitu membuka lahan pertanian baru atau mencari pekerjaan dalam bidang non
pertanian.
Kondisi tersebut mengakibatkan perndapatan dari sektor pertanian dipandang tidak mampu
mengimbangi peningkatan harga berbagai kebutuhan hidup petani. Pendapatan yang
diperoleh sangat rendah berakibat pada semakin tidak menariknya pekerjaan sebagai petani.
Kondisi ini pula yang mengakibatkan tenaga kerja produktif, terutama tenaga kerja muda
lebih memilih bidang pekerjaan di luar sektor pertanian. Mereka lebih baik mencari
pekerjaan di kota yang upahnya lebih baik, sehingga desa kekurangan tenaga kerja potensial
yang masih muda untuk mengembangkan sektor pertanian.
System desentralisasi pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004
memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan otonomi yang luas kepada
daerahnya. Salah satunya adalah pendidikan, yang sebelumnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat kemudian dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk
memperkuat system pendidikan maka muncul Undang-Undang No 20 Tahun 2003, yang
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.
Kewenangan desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan mampu
mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lingkungan dan dunia usaha
setempat, sehingga lulusan pendidikan benar-benar bermanfaat bagi daerah tersebut. Hal ini
sesuai dengan pengertian pendidikan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 bahwa
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
W. Arthur Lewis (1954 dalam Todaro, 2006), didalam teorinya (Lewis two-sector model)
berpendapat bahwa transformasi struktural ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern
akan diikuti oleh migrasi struktural tenaga kerja secara massive, dari sektor tradisional ke
sektor moderen. Tenaga kerja sektor tradisional bermigrasi karena tertarik akan tawaran
tingkat upah sektor modern yang lebih tinggi daripada sektor tradisional. Menurut Lewis,
perekonomian di desa merupakan representasi dari sektor tradisional, sedangkan
perekonomian di kota adalah representasi dari sektor modern. Oleh karenanya, Lewis
berpandangan bahwa migrasi tenaga dari sektor tradisional ke sektor modern terjadi dalam
bentuk migrasi penduduk dari desa ke kota.
Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif
dan sebagai unsur penunjang semata. Dewasa ini, pakar ekonomi pembangunan mulai
menyadari bahwa daerah pedesaan dan sektor pertanian ternyata tidak bersifat pasif, dan jauh
lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur
atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan sangat menentukan strategi-strategi
pembangunan secara keseluruhan.
B. Rumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi SDM pertanian di Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana program pendidikan yang mendukung pembangunan SDM pertanian ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan SDM pertanian ?
4. Bagaimana peran pendidikan dalam pembangunan SDM pertanian?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi petani di Kabupaten Karanganyar
2. Untuk mengetahui program pendidikan yang mendukung pembangunan SDM pertanian
3. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam
pembangunan SDM pertanian
4. Untuk mengetahui peran pendidikan dalam pembangunan SDM pertanian

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi pemerintah
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan di bidang
pendidikan agar dapat mendorong hasil pendidikan yang mendukung sektor pertanian,
terutama hasil pendidikan yang dapat menciptakan tenaga ahli di bidang pertanian.
2. Bagi peneliti
Memberikan wawasan tentang kebijakan pendidikan saat ini yang belum memberikan
manfaat yang besar di bidang pertanian
E. Kajian Pustaka
DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL AS A TOOL FORIMPROVING PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL SECTOR –CASE OF SERBIA
Jovan Zubovic, Ivana
Domazet, Ivan Stosic
Institute of Economics
Sciences Belgrade, Serbia
Saat ini reformasi pada sekolah-sekolah pertanian harus bersandar pada kurikulum yang menggabungkan pengajaran pelatihan praktis petani lokal. Pemecahan masalahanya harus dititik beratkan pada penyelesaian maslah pengangguran di kalangan penduduk desa, dengan reorientasi sumber daya manusia yang menawarkan program pelatihan yang membantu meningkatkan produktivitas
KAJIAN PERAN PENDIDIKANTERHADAP PEMBANGUNAN PERTANIANDI KABUPATEN DEMAK
Dwi Isnaini Saparyanti,
Universitas Diponegoro
Pembangunan pendidikan yangdilaksanakan di Kabupaten Demak baru mampu menyediakan sumber daya manusiapelaku usaha (off farm). Ketidakmampuan sektor pendidikan dalam menyediakankebutuhan sumber daya

manusia (SDM) pelaku utama (petani) dikarenakanmotivasi/animo yang rendah dari para generasi muda untuk masuk di sekolah pertanianyang disebabkan oleh beberapa alasan yaitu sektor pertanian tidak menjanjikan dari segipendapatan dan secara status sosial masih dipandang rendah. Padahal pendidikanmempunyai pengaruh terhadap perilaku bertani yaitu pada aspek sosial dan produksi
The Effects of Education in
Agriculture: Evidence from
Nepal
Som P. Pudasaini Pendidikan menunjukkan
hasil yang lebih tinggi dalam
produktivitas di lingkungan
pertanian modern dibanding
tradisional. Sementara
diantara pekerja dan efek
alokasi pendidikan memiliki
kontribusi positif terhadap
produksi pertanian.
F. Kajian Teori
1. Pengertian Pendidikan
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses
pengubahan sikap dan tata lakku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Menurut John Dewey Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan
fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.
2. Pendidikan menurut Paulo Freire
Teori pendidikan telah berkembang dari teori dengan paradigma konservativisme sampai
pada teori berparadigma ekstrem seperti liberalisme, liberasionisme sampai anarkisme.
Gagasan Freire banyak dianggap sebagai gagasan pembebasan penuh pendidikan
institusional dan mengacu pada pembebasan masyarakat dalam mengenyam pendidikan.
Gagasan ini banyak disetarakan dengan teori anarkis mengenai praktik ajar-mengajar
yang dinilai sudah cenderung menjadi komoditas kapitalistik yang tidak lepas dari usaha
pemenuhan kebutuhan semu terhadap tuntutan masyarakat semu produk sistem kapitalis.
Putar-ulang seluruh gagasan pendidikan sebagai kritik terhadap sistem dan metode
pendidikan yang sudah baku adalah gagasan para anarkis dari sini muncul
istilah 'deschooling society' yang menyatakan sikap para anarkis. Freire kemudian sangat
dekat dengan para penggagas anarkis ini terutama karena rasa antipati terhadap sistem
kapitalistik dan karena sifat praksis serta revolusioner Freire.
Beberapa konsep Freire mengenai pendidikan yang membebaskan dan memanusiakan
dapat dilihat di bawah ini:
a. Pendidikan ditujukan pada kaum tertindas dengan tidak berupaya menempatkan kaum
tertindas dan penindas pada dua kutub berseberangan. Pendidikan bukan dilaksanakan
atas kemurah-hatian palsu kaum penindas untuk mempertahankan status quo melalui
penciptaan dan legitimasi kesenjangan. Pendidikan kaum tertindas lebih diarahkan
pada pembebasan perasaan/idealisme melalui persinggungannya dengan keadaan
nyata dan praksis. Penyadaran atas kemanusiaan secara utuh bukan diperoleh dari
kaum penindas, melainkan dari diri sendiri. Dari sini sang subjek-didik
membebaskan dirinya, bukan untuk kemudian menjelma sebagai kaum penindas
baru, melainkan ikut membebaskan kaum penindas itu sendiri. Pendidikan ini bukan
bertujuan untuk menjadikan kaum tertindas menjadi lebih terpelajar, tetapi untuk
membebaskan dan mencapai kesejajaran pembagian pengetahuan.

b. Bila pembebasan sudah tercapai, pendidikan Freire adalah suatu kampanye dialogis
sebagai suatu usaha pemanusiaan secara terus-menerus. Pendidikan bukan menuntut
ilmu, tetapi bertukar pikiran dan saling mendapatkan ilmu (kemanusiaan) yang
merupakan hak bagi semua orang tanpa kecuali\
c. Kesadaran dan kebersamaan adalah kata-kata kunci dari pendidikan yang
membebaskan dan kemudian memanusiakan.
d.
G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini menggunakan
data deskripstif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati (Bogdan dan Taylor, 1975). Penelitian kualitatif daris sisi definisi lainnya
dikemukankan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka
untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau
sekelompok orang.
Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
H. Obyek Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di daerah yang mayoritas kehidupannya dari pertanian yaitu
Kabupaten Karanganyar. Obyek penelitian ini dipilih karena di Kabupaten Karanganyar
sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian besar lingkungan
di daerah tersebut adalah lahan pertanian. Selain itu Kabupaten Karanganyar juga dijadikan
sebagai salah satu lumbung padi nasional.
I. Sumber Data
1. Data Primer
Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh lansung dari lapangan
atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan
sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Dalam
penelitian ini data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada mahasiswa
dan petani.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam
sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat
perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data
sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi,
lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil
studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data
sekunder digunakan untuk memperkuat hasil data primer yang dilakukan dengan cara
wawancara, selain itu data sekunder juga digunakan untuk melengkapi data yng
dibutuhkan dalam penelitian ini.
J. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu
seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang
valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data
yang diperlukan.
1. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman,
instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang
disiarkan kepada media massa.
3. Kuesioner
Teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka
yang dibagikan kepada petani

K. Teknik Pengambilan Sampel
Mengingat terbatasnya tenaga, waktu dan dana yang dimiliki, untuk menentukan responden
yang dijadikan sampel, dipakai beberapa teknik yaitu (a) Sampel bertujuan atau purposive
sample, Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas
strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik purposive
sample digunakan untuk menentukan kecamatan yang menjadi responden dan pengambil
kebijakan (Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, dan Ketahanan Pangan, PPL); (b) Teknik
random sampling (acak) yaitu teknik pemilihan sampel tanpa memilih atau melihat sampel
yang mau diambil. Teknik random sampling (acak) digunakan untuk menentukan sampel
petani yang menjadi responden.
L. Teknik analisa
Agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, maka dalam penelitian ini akan
dilakukan beberapa analisa yaitu:
1. Analisa kondisi sosial ekonomi petani
Analisa ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani di Kabupaten
Karanganyar, sehingga diharapkan dari analisa ini dapat mengelompokkan kondisi sosial
ekonomi petani serta dapat mengetahui kebutuhan sumder daya manusia yang dibutuhkan
dalam sektor pertanian. Informasi diperoleh dari wawancara kepada petani serta Dinas
Pertanian Kabupaten Karanganyar
2. Analisis lulusan (output) pendidikan formal terhadap lapangan pekerjaan sektor pertanian
Analisa ini untuk mengetahui kompetensi apa saja yang dibutuhkan pada pendidikan
dasar guna menunjang pembangunan sumber daya manusia di sektor pertanian. Pada
analisa ini data diperoleh dari dinas pendidikan serta petugas penyuluh lapangan yang
waktu bekerjanya lebih banyak dengan petani.
3. Analisis motivasi menjadi petani
Analisis ini untuk mengetahui pandangan siswa kelas IX serta XI tentang keadaan sosial
ekonomi saat ini, serta untuk melihat seberapa besar ketertarikan kaum muda untuk
melanjutkan pekerjaan di bidang pertanian. Responden yang dipilih adalah siswa kelas IX
dan XI yang orangtuanya memiliki pekerjaan sebagai petani.

4. Analisis kebijakan
Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang pernah
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menunjang
pengembangan sumber daya manusia sektor pertanian di Kabupaten Karanganyar,
dimana Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu lumbung padi nasional. Kebijakan
yang dianalisis adalah kebijakan pendidikan serta pertanian.

DAFTAR PUSTAKA
Ancok, D. (1997). Revitalisasi Sumber Daya Manusia dalam Era Perubahan, Kelola: Gadjah Mada University Business Review, No.8, 104-117
Goleman, D.(1996), Emotional Intelligence. New York, Bantam Books
Isa Iwan. 2012. Strategi Pengendalian Alih fungsi Lahan Pertanian. Badan Pertanahan Nasional. www.balittanah.litbang.deptan.go.id. diakses 19 Januari 2013
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta : Sinar Grafika.
Ross, J. et.al. (1997), Intellectual capital: Navigating the New Business Landscape, New York, MacMillan
http://www.ipabionline.com/2012/01/2-juta-petani-indonesia-ganti-profesi.html, diakses 22
Januari 2013

Peningkatan Pendidikan dan Regenerasi Petani Masa Kini
PROPOSAL TESIS
Oleh:
BOTHY DEWANDARU
S421302009
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2014