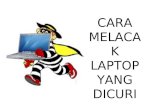Melacak Jejak Tari Di MN
-
Upload
katrinds-tuti -
Category
Documents
-
view
306 -
download
4
Transcript of Melacak Jejak Tari Di MN
SEJARAH TARI I TARI JAWA GAYA MANGKUNEGARAN MASA PEMERINTAHAN KGPAA. MANGKUNEGARA VIII - IX
Perkembangan tari Jawa khususnya di Surakarta, diawali sejak terbaginya kerajaan mataram Islam menjadi dua wilayah kerajaan yaitu Kasultanan (Jogjakarta Hadiningrat) dan wilayah Kasunanan (Surakarta Hadiningrat), dalam sebuah kesepakatan yang ditulis dalam nota perjanjian yaitu perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Di wilayah kerajaan Pembagian wilayah secara geografis tersebut Surakarta sendiri ternyata juga terbagi menjadi dua wilayah kerajaan yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. mempengaruhi pembagian wilayah budaya. Masing-masing wilayah kerajaan ingin menunjukkan jatidiri mereka melalui berbagai macam bentuk budaya, diantaranya karya seni tari. Hal tersebut mempengaruhi pula perkembangan tari Jawa, yang kemudian muncul tari gaya Mangkunegaraan yang dalam prosesnya telah melampaui perjalanan yang cukup panjang. Dalam proses tersebut tari gaya Mangkunegaran juga mendapat pengaruh dari gaya tari dari Jogjakarta khususnya dari Kasultanan. Pengaruh tersebut muncul karena adanya hubungan kerjasama, kekerabatan dan lain sebagainya. Tari gaya Mangkunegara mulai tumbuh sejak masa pemerintahan Sri Mangkunegara VII, meskipun pada masa pemerintahan Sri mangkunegaran V sudah ada pengaruh dari yogyakarta, namun secara teknis tidak berpengaruh pada gaya tarinya. Pada masa pemerintahan Sri Mangkunegara VIII dan IX, tampaknya masih tetap melestarikan gaya tersebut, meskipun semakin jauh dengan gaya Yogyakarta, karena pembinaan penarinya tidak langsung dalam gaya Yogyakarta, tetapi gaya mangkunegran (Theresia Suharti.126) Pada masa Sri mangkunegaran VIII dan IX, masih tetap melestarikan gaya tari yang hidup pada masa Sri Mangku Negara V-VII, yang terpengaruh oleh gaya Yogyakarta. Namun secara teknis tidak pengaruh pada gaya tarinya.
Tari pada masa Mangkunegara VIII IX ini sudah tampak semakin jauh dengan gaya Yogyakarta, kerana pembianaan penarinya tidak dilakukan langsung pada gerak tari Yogyakarta dan banyak penari pada masa ini telah menguasai tari gaya tari Surakarta terlebih dahulu. Dan gaya tari Mangkunegaran sendiri telah terbentuk sejak Pemerintahan MN VII. 4 Banyak karya tari yang tetap eksis dalam pergantian era kepemimpinan, dan juga terdapat beberapa tari yang baru disusun dan diciptakan pada masa pemerintahan Mangkunegara VIII IX. Penciptaaan-penciptaan tari yang tercipta pada masa pemerintahan MN VIII dan MN IX ini lebih pada upaya pelestarian dan tanggungjawab untuk senantiasa melestarikan budaya tradisi leluhur,. Tari-tari pada masa pemerintahan Mangkunegara I - VII yang masih tetap terpelihara / dilestarikan hingga masa pemerintahan MN VIII IX adalah: Bedhaya Bedhah Madiun, Srimpi Pandelori, Srimpi Muncar, Golek Lambangsari, Golek Montro, Golek Clunthang dan lain sebgainya. Mangkunegara VIII adalah putra ke 3 dari Alm. Kanjeng Pangeran Hario Suryo Kusumo Mangkunegara VII). Merupakan putra laki-laki I yang lahir dari istri selir bernama Bendara Raden Ayu Retnaningrum. Mangkunegara VIII, lahir pada hari Jumat Pahing tanggal 1 Januari 1926 , dengan nama Bendara Raden Mas Saroso. Setelah diangkat menjadi Pangeran berganti nama menjadi Kanjeng Pangeran Haryo Hamidjoyo Saroso. Menikan dengan Raden Ajeng Sunituti pada tahun 1941. kemudian berganti nama dewasa menjadi Gusti Kanjeng Pangeran Mangkunegara VIII. KGPAA Mangkunegara VIII adalah putra MN VII (Kanjeng Pangeran Hario Suryo Kusumo) yang ke 3 atau putra laki-laki I yang lahir dari istri selir yang bernama Bendara Raden Ayu Retnaningrum. Lahir pada hari Jumat Pahing tanggal satu (1) bulan Januari 1926, dengan nama Bendara Raden Mas Saroso. Setelah diangkat menjadi pangeran bernama: Kanjeng Pangeran Haryo Hamidjojo Saroso, yang pada saat dewasa bernama Gusti4
Theresia Suharti. 1990. Tari Mangkunegaran Suatu Pengaruh Bentuk dan gaya dalam Dimensi Kultural 1916-1988. Thesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal.126.
Kanjeng Pangeran Mangkunegara VIII. Beliau menikah dengan Raden Ajeng Sunituti pada tanggal 9 Oktober 1941. setelah bertahun-tahun meduduki tahta singgasana beliau wafat pada tanggal 3 September 1987. Riwayat kepemimpinana Mangkunegara berawal sejak masuknya pemerintahan Jepang, tepatnya pada tanggal 19 juli 2604 (1944). Disaat pendudukan Jepang kehidupan Kraton Mangkunegara dalam kondisi pahit dan getir, dan dalam kondisi itu mangkunegara tetap memegang otonomi dan selalu mencari jalan untuk meringankan beban rakyat dengan melindungi dari kekejaman tentara Jepang. Dalam masa pemerintahan Jepang mangkunegara menerima tambahan kekuasaan untuk mengurusi bidang pendidikan; SR, SMP, SMA, juga mengurusi pegadaian. Urusan bidang keamanan khususnya kepolisian dan ketentaraan tetap ditangani oleh pemerintahan Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, dinyatakan bahwa Mangjunegaran merupakan bagian dari NKRI dan mengaku bernaung dibawah pemerintahan Agung RI. Mangkunegara VIII mencoba membangun kekuatan wilayah dan trah keturunan Mangkunegara I dengan lebih condong pada pendekatan budaya. Hal tersebut nampak pada didirikannya organisasi yang dikenal dengan nama: Himpunan Kerabat Mangkunegaran (HKMN) Suryosumirat. MN berharap HKMN yang secara otomatis beranggotakan trah Mangkunegaran dan para punggawa baku, mampu berkembang menjadi keluarga besar dan berperan penting dalam kehidupan Pura Mangkunegaran di tengah wilayah Negara Republik Indonesia. Organisasi ini hingga kini selalau aktif dalam peran pelestarian seni khususnya seni tari gaya Mangkunegaran. Peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan tari tercatat tanggal 16-17 januari 1959 pada Dies Natalis ke IV Perguruan Tinggi Katolik Parahiangan di Bandung. Pada kesempatan itu dipersembahkan malam kesenian Mangkunegaran, sumbangan dari Sri Paduka Mangkunegara VIII beserta permaisuri. Tari tari tersebut adalah:
Tari Srimpi Tari Srimpi yang dipertunjukkan tersebut menunjukkan peperangan antara Rara Sirtupilaheli, putri Raja Karsinah dan Retna Sudarawerti adik dari Raja Kandjun (babad Menak). Dalam perkelahiannya yang seru mereka mempergunakan busur dan anak panah. Tidak ada yang kalah ataupun menang dalam perkelahian ini namun hanya merupakan adu kekuatan (perbandingan), yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sama. Gatutkaca Gandrung. Tari Gatutkaca Gandrung pada kesempatan itu ditarikan dalam 4 bagian : Bagian I, diiringi dengan Kinanti Pangukir. Mempertunjukkan saat-saat Gatutkaca yang sedang merasakan panah asmara yang sedang melanda hatinya, sehingga ia lupa bahwa ia sedang terbang berputar-putar melayang di udara, lalu jatuhlah Gatutkaca ke tanah. Bagian II, diiringi dengan Bendrongan Pada bagian ini dipertunjukkan bagaimana Gathutkaca bangun dari pingsan, tetapi dalam kondisi yang demikian masih saja dia dimabuk asmara. Diulurkanya tangannya dengan maksud hendak memeluk jantung hatinya. Namun dia segera sadar bahwa itu hanya hayalannya, dan yang ada didepannya ternyata hanya kosong bukan gadis pujaan yang dihadapinnya, dia sangat kecewa dan dibanting-bantingkannyalah kakinya ke tanah serta menggeleng-gelengkan kepala berulang-ulang. Bagian III, diiringi Pucung Rubuh Dalam adegan ini masih ditampakan perasaan cinta yang berkobar. Sehingga yang muncul, adalah gerakan gerakan berhias yang menggambarkan seseorang yang sedang dimabuk cinta, (oleh sebab itu tari ini jiga sering disebut dengan tari berhias).. gatutkaca selalu terbayang jantung hatinya yang seolah-olah ada di hadapannya, oleh sebab itu di dalam gerakan berhias seringkali berhenti sesaat.
Bagian terakhir, diiringi Srepegan. Dalam adegan ini dipertunjukkan betapa Gathutkaca tetap teguh pendiriannya dalam mencari Pergiwa sang pujaan hatinya. Lalu dia kembali terbang ke udara sambil melihat sekeliling bumi. Dan dengan kecepatan tinggi bagaikan anak panah dia turun dan mengunjungi Pergiwa.5 Pada tahun 1981, Beksa Anglir Mendhung kembali dipertunjukkan di Pringgitan Pura Mangkunegaran setelah 145 tahun menghilang, hampir satu setengah abad yang lalu. Pentas pertama kali Tari Bedhaya Anglir Mendhung di Pura Mangkunegaran, ditarikan oleh 3 orang penari. Pentas taro Bedhaya Anglir Mendhung ini terlaksana karena ada hubungan baik antara TVRI YogyakartaJakarta dan mangkunegaran. Pada awalnya dikarenakan TVRI Yogyakarta yang berniat untuk menayangkan karya tari dari Mangkunegaran, kemudian diadakan perekaman/shooting tepatnya pada tanggal 12 desember 1981 (15 Sapar 1914), antara pukul 19.00-19.30, yang ternyata itu menandai kembalinya Tarimbedhaya Anglir Mendung ke Mangkunegaran. Kembalinya Beksan Anglir Mendhung ini atas inisiatif Sri Mangkunegara VIII, untuk mengukuhkan kembali Tari Bedhaya Ketawang menjadi langenpraja Mangkunegaran, dalam menghidupkan kembali adat tradisi setiap ada peringatan kelahiran raja maupun peringatan penobatan raja. Tari Bedhaya Anglir Mendhung untuk selanjutnya menjadi pusaka mangkunegaran dan selalu dipergelarkan dalam acara kerajaan. Seperti pada Upacara khol agung P. Sambernyawa 24 windu pada tanggal 6 Maret 1982, digelar tari Bedhaya Anglir Mendhung. Begitu juga ketika memperingati Ultah Sri Mangkunegara VIII dalam genap usianya yang ke 64 tahun, tepatnya tanggal 14 maret 1982. Dalam kesempatan acara Pengukuhan Anglir Mendhung sebagai langenpraja Pura Mangkunegaran. Tari Bedhaya Anglir Mendhung beserta gendhingnya Gendhing Anglir Mendhung, telah ada pada jaman KGPAA Mangkunegara I (RM. Sahid atau5
Panitia Dies Natalis ke IV PT Katolik Parahiangan. Mempersembahkan malam Kesenian Mangkunegaran. Sumbangan dari Sri Paduka Mangkunegara VIII beserta Permaisuri. Bandung : Panti Budaja Kleijne, 16-17 Djanuari 1959. hal. 1.
Pangeran Sambernyawa) tahun 1790 Masehi sampai pada jaman pemerintahan KGPAA MN III, tahun 1835 Masehi, sebagai langenpraja yang diagungkan dan bagi komunitas mangkunegaran diyaklini membawa kemakmuran rakyat mangkunegaran. Gendhing Ketawang Alit Anglir Mendhung yang mengiringi Tari Bedaya Anglir Mendhung berwujud Gendhung Kemanak. Gendhing tersebut telah hidup sejaman dengan Gendhing Ketawang Ageng yang telah ada sejak Jaman Penembahan Senapati tahun 1575 Masehi. Oleh Empu Gendhing Kakawin (abdi dari P. Sambernyawa) yang benama Ki Secokarmo dan Ki Kidang Wulung diciptakan Tari Bedaya Anglir Mendhung untuk mengisi Gendhing Ketawang Alit Anglir Mendhung. Tarian yang diciptakan itu selesai sebelum MN II wafat. Para penari Bedhaya Anglir Mendhung menggunakan peralatan pistol yang dibawa oleh penari Pembatak (Sirah), pistol tersebut diselipkan di pinggang kiri depan penari. Pada pementasan pertama setelah TBAM menggunakan peralatan pistol. Pistol tersebut pernah digunakan oleh P. Sambernyawa. Pementasan tari Bedhaya Anglir Mendhung ini diadakan dalam acara penobatan Pangeran menjadi KGPAA tanggal 17 maret 1757. Pemenrtasan BAM harus dibarengi dengan sesaji Ketawang alit yaitu: ketan beras, enten2, jajan pasar, bekakak , sekul megana, sekul golong, sekar setaman, sekar uteran (wungun kuluk) 5 macam: kanthil , kenanga, mlathi, mawar merah dan putih. Yang bertugas menghunjukkan sesaji adalah lurah abdi dalem yang paling tinggi pangkatnya dan memakai dodot dan gelung ukel. Selanjutnya tari Bedaya Anglir Mendhung tersebut ditarikan untuk upacara Peringatan Kelahiran raja dan Peringatan Penobatan (raja) Mangkunegara. Sampai pada jaman Sri Mangkunegara III masih dilestariikan. Tetapi kemudian ketika Sri Mangku Negara III diambil putra menantu oleh Sri Paku Buwono V (tahun 1835). Tari (langen beksa) Bedhaya Anglir Mendhung dipersembahkan kepada mertuanya (PB V). Sejak saat itu Tari Bedhaya Anglir Mendhung tidak lagi menjadi tarian (langenpraja) Mangunegaran, tetapi mangkunegara I pada
berpindah ke Kraton kasunanan Surakarta. Tari Bedhaya Anglir Mendhung kemudian oleh Sri Paku Buwono V digubah dengan menambahkan jumlah penari, yang semula berjumlah 3 orang menjadi 4 orang penari (diatambah satu penari) dan dikelompokkan menjadi Tari Bedaya Srimpi. Perubahan juga terjadi pada syair untuk gerongan Gendhing Alit. Dari adanya perubahan perubahan tersebut tari Bedhaya Anglir mendhung cengkok (gaya) Sambernyawan perubah menjadi Bedhaya Srimpi Anglir Mendhung cengkok (gaya) Kraton Kasunanan Surakarta. Mengenai jumlah penari pada akhirnya diketahui berjumlah 7 orang . hal ini berdasarkan pada sumber tertulis yaitu babad mangkunegaran atau Buku Harian MN I. Pada perjalanan selanjutnya atas dasar ijin Sri Mangku Negara VIII, Tari Bedhaya Anglir Mendhung Sambernyawan dikukuhkan kembali menjadi tarian (langenpraja) Mangkunegaran. Mangkunegara VIII telah menghidupkan kembali adapt tradisi kerajaan dalam acara peringatan kelahiran dan penobatan raja. Tari Bedhaya Anglir Mendhung yang telah kembali ke Mangkunegaran itu, setahun kemudian digelar kembali dalam upacara Khol Agung Pangeran Sambernyawa ke 24 windu, tepatnya pada tanggal 6 maret 1982, dan pada peringatan kelahiran Sri mangkunegara VIII yang genap menginjak usia 64 tahun, pada tangagal 14 Maret 1982. Peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan tari tercatat pula pada tanggal 18 -28 Agustus 1994. Empat tarian Jawa - Surakarta gaya Mangkunegaran ditarikan oleh enam penari dari sanggar Suryo Sumirat Puro Mangkunegaran. Pentas diselenggarakan di Gedung Kino Centre, Moskow. Taritarian tersebut adalah: Tari Srimpi Moncar (Putri Cina), Topeng Gunungsari, Srimpi Catur Sagotro, dan Harjuna Sosro Sumantri. Pagelaran terselenggara atas permintaan KBRI di Moskow, untuk mengenalkan kesenian tradisional khusunya Jawa, pada masyarakat setempat sekaligus untuk memeriahkan HUT RI di KBRI, rombongan tersebut diketuai oleh GPH Herwasto Kusumo (Adik KGPAA. Mangkunegara IX), ketua sanggar Tari Suryo Sumirat.
Pada tanggal 30 Januari 2000, dipergelarkan Drama Tari Mintaraga,yang diciptakan oleh GPH Herwasto Koesoemo, untuk merayakan acara halal bihalal di Pendapa Ageng Pura Mangkunegaran Solo. Drama tari ini melibatkan sebanyak 100 seniman. Mintaraga adalah nama samaran dari Arjuna ketika sedang bertapa. Arjuna juga mempunyai nama lain yaitu Janaka dan Permadi. Kisah tari tersebut memetik dari Kitab Arjuna Wiwaha gubahan Empu Kanwa yang bersumberkan pada Epos Mahabarata. Dalam drama tari itu dikisahkan bahwa Arjuna dapat membasmi angkara murka setelah bertapa. Dalam drama tari dikisahkan Arjuna sedang mengalami keprihatinan yang mendalam kemudian menjalani yogalata, tekad bulat untuk berupaya mawas diri (mintaraga) dan melatih diri (witaraga) disertai pendekatan dan pemusatan pada Tuhan. Hal itiu dilakukan Arjuna untuk mencapai kepribadian yang sempurna sebagai kesatria yang tangguh terpercaya (kesatria sakti) serta waskita. Dengan kesaktian itu Arjuna Peduli ikut memayu hayuning bawana dan atas kepeduliannya itu lantas berhasil membasmi keangkaramurkaan. Akhirnya Arjuna menerima penghargaan terhormat diangkat menjadi raja di kahendran (para dewa). Menurut ketua panitia KRTH Ir. H Hartono W Kusumo MM, bahwa drama tari tersebut membawa pesan penting untuk diteladani oleh para kerabat Mangkunegaran dalam mengemban amanat Reformasi menuju Indonesia baru. Drama tari Mintaraga dalam hal ini telah menjadi indikasi cinta dan bakti serta kepedulian pihak Mangkunegaran terhadap nasib bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan oleh pendirinya yaitu RM. Said. Selain tari yang diciptakan pada masa MN VIII, tari tari yang terus hidup dan eksis pada masa pemerintahan mangkunegara VIII diantaranya, Srimpi Pandhelori. Tari Srimpi Pandhelori merupakan sebuah bentuk tari yang pertama dipelajari sesudah tari Sari Tunggal, tari dasar putrid di Kridha Beksa Wirama, Yogyakarta, pada waktu Gusti Nurul belajar. Sesudah itu kemudian menyusul Bedhaya Bedhah Madiun, Srimpi Moncar atau disebut pula Srimpi Putri Cina.
Sesudah masa akhir pemerintahan Sri mangkunegara VIII, yang kemudian diteruskan oleh Sri Mangkunegara IX, tampaknya pergeseran fungsi keberadaan tari semakin terasa mengikuti perkembangan Jaman. Kini bisa dilihat bahwa fungsi tari lebih cenderung menjadi seni tontonan. Hal ini terbukti dengan kesepakatan para kerabat Mangkunegaran yang telah dituangkan melalui Surat Keputusan, serta ajakan melalui ceramah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Surono pada tanggal 12 Desember 1987, yang ingin menjadikan Mangkunegaran sebagai Culture Center, untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pura Mangkunegaran diperlukan kesepakatan dengan seluruh kerabat , sehingga diharapkan dapat merealisasi Pura Mangkunegaran sebagai pusat kebudayaan dan objek pariwisata. Dalam pengertian ini berarti pula bahwa menggali dan membina sumbersumber potensi lahir batin dari peninggalan pra leluhur, terutama yang dapat merupakan sumber potensi cultural dan spiritual yang bersifat nasional konstruktif bagi pembangunan bangasa Indonesia (Suara Keputusan Bersama Pengageng Pura mangkunegaran dan Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryosumirat). Kepemimpinan Mangkunegara seakan mengalami kevakuman setelah surutnya MN VIII, namun kemudian pada tanggal 4 Jumadilakhir 1920 atau 24 Januari 1988 ditetapkan bahwa Gusti pangeran Haryo Sujiwo Kusumo menjadi pengganti MN VIII.
MN IX: Mangku Negara IX adalah Putra dari MN VIII. Bernama GPA Sudjiwokusumo, yang lahir pada tanggal 18 Agustus 1951 dan pada tanggal 24 Januari 1988 dikukuhkan sebagai pemimpin Pura Mangkunegaran dengan gelar KGPAA Mangku Negara IX.
Setahun kepemimpinannya (1989) telah menyelenggarakan pertunjukkanpertunjukkan yang khusus untuk kepentingan wisata. Yang dalam hal ini mengambil penari dari STSI, SMKI dan TBS serta dari masyarakata umum. Pada masa Pemerintahan MN IX ini tercipta Bedhaya Suryosumirat. Karya tari ini merupakan implikasi dari fenomena social dan politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan RI sehubungan dengan otonomi MN, sehingga MN mulai memanfaatkan asset budayanya. TARI Bedhaya SS ini ditarikan oleh 9 wanita, tari ini sama dengan tari Bedhaya di Kraton Surakarta (Kasunanan) dan Yogyakarta, namun terdaat perbedaan yaitu pada waktu pementasannya. Bedhaya SS ini dipentaskan pada saat pesta pernikahan Boyong Dalem (tanggal 7 Juli 1990), KGPAA Mangku Negara IX.6 Bedhaya Suryosumitrat ini disusun oleh Sulistyo Sukmadi Tirtokusumo (putra dari Raden Mas Ngabehi Atmosutargyo). Lahir pada tanggal 6 Juli 1953. aktiv membuat karya tari sejak masa pemerintahan Mangkunegara VIII sampai pada masa pemerintahan MN IX, karya-karya yang telah diciptakan adalah: Catur Sagotra (1973), Yudasmara (1973), Bedhaya Ratnaningprang (1974), Sunyaruri (Bedhaya laki-laki), Bedhaya Kiranaratih, Drama tari Bisma Gugur (1975) Drma Tari Arya Jipang ( 1979), Kirana Ratih (1981), Bedhaya Suryosumirat (1990), Tari Kontenporer panji Sepuh (1993), tari Harjuna Sasrabahu, tari palguna Palgunadi, tari garapan ekalaya (1986), tari Diam (1987), tari Garapan Basukarna (1987) dan Puspita ratna (1998), Tari Kontemporer Nyuri sembako (1998) dan Tari Kontemporer Krisis (1995) dan lain sebagainya. Karya-karya tari ini dipentaskan dalam Pekan Penata Tari Muda, Pekan Koreografer Indonesia, Indonesia Dance Festival, Keperluan Direktorat Kesenian, Persmian Teater, Pernikahan Putra/putrid Presiden Soekarno, dan lain sebagainya7.
6
Suharji. 2001. Bedhaya Suryosumirat Di Pura Mangkunegaran Surakarta. Thesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 1,5. 7 Suharji. 2001. Bedhaya Suryosumirat Di Pura Mangkunegaran Surakarta. Thesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal 64
Pada tahun 2005 dipergelarkan Langendriyan Mandraswara. Kesenian ini berwujid seperti wayang wong dan ketoprak hanya saja dialognya menggunakan tembang dan cerita yang dibawakannya adalah tentang sejarah Majapahit. Ide tersusunya kesenian ini dari saudagar batik kaya yang bernama Godlieb setelah sering melihat para pekerjanya ssering melantunkan tembangan ketika sedang membatik. Kemudian dari ide tersebut dinyatakan kepada Raden Mas Aryo Tondokusumo putra mantu Sri MN IV yang ahli dibidang gendhing dan tari, yang kemudian terciptalah Langendriyan Mandraswara tersebut. Setelah Godlieb mengalami kebangkrutan dan tidak dapat memelihara kesenian tersebut, olek RMA Tondokusumo Langen Mandraswara dipersembahkn kepada MN IV. Kemudian pada Jaman MN V kesenian ini dipentaskan dengan menggunakan gelar tari, yang dimainkan oleh 3 orang penari yang memarankan : Damarwulan, Menakjingga, dan Dayun, dengan lakon Menakjingga Lena. MN V yang merancang sendiri busana para penarinya seperti busana wayang orang/ketoprak. Oleh sebab itu pada masa itu kesenian ini disebut dengan Langendriyan telu (3) sesuai dengan jumlah pemainnya. Menginjak tahun 20 an Sri MN VII, menambah pemainnya menjadi 7 orang, yang kemudian disebut dengan Langendriyan pitu (7). Penambahan pemain tersebut adalah: Sabdopalon, Nayagenggong, Wahito dan Puyengan. Kesenian ini mengalami masa jaya pada tahun 1930 dan dalam masa kesempurnaan karena telah berhasil menampilkan semua babak lakon seperti: Damarwulan Ngarit sampai pada Rabine Damarwulan (Dhaupe Raden Ayu klawan Damarwulan).Klesenian yang lahir dan berkembang di wilayah Surakarta ini pada masa MN IX digelar kembali, untuk keperluan seminar perbandingan Langendriyan gaya Mangkunegaran dan gaya Yogyakarta.8
8
Penjebar Semangat. No.36, September 2005 halaman 27-44