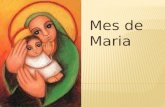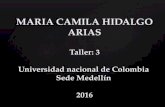maria martina nahak
Transcript of maria martina nahak

TESIS
EKSTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS (Pluchea indica. L.) DAPAT MENGHAMBAT
PERTUMBUHAN BAKTERI Streptococcus mutans
MARIA MARTINA NAHAK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
2012

TESIS
EKSTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS (Pluchea indica. L.) DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN
BAKTERI Streptococcus mutans
MARIA MARTINA NAHAK NIM 1090761025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR 2012

EKSTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS
(Pluchea indica. L.) DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI Streptococcus mutans
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister pada Program Magister, Program Studi Ilmu Biomedik,
Program Pascasarjana Universitas Udayana
MARIA MARTINA NAHAK NIM 1090761025
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK
PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
2012

Tesis ini Telah Diuji pada
Tanggal 26 Juni 2012
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK Rektor Universitas Udayana
No: 1034/UN14.4/HK/2012, Tanggal: 25 Mei 2012
Ketua : Prof. dr. I Gusti Made Aman, Sp.FK
Anggota :
1. Dr. dr. Bagus Komang Satriyasa, M.Repro
2. Prof. Dr. dr. J. Alex Pangkahila, M.Sc., Sp.And
3. Dr. dr. Ida Sri Iswari, Sp.MK., M.Kes
4. Dr. dr. Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si

UCAPAN TERIMAKASIH
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun laporan Tesis yang berjudul “Ekstrak Etanol Daun Beluntas (Pluchea indica. L.) dapat Menghambat Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans” tepat pada waktunya. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk meraih gelar Magister pada Program Pascasarjana Ilmu Biomedik dengan Kekhususan Ilmu Kedokteran Dasar Bidang Farmakologi Universitas Udayana. Tesis ini tidak mungkin diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. dr. I Gusti Made Aman, Sp.FK., selaku pembimbing I dan Dr. dr. Komang Bagus Satriyasa, M.Repro., selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan dan saran serta semangat kepada penulis sehingga laporan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
Ucapan terimakasih yang sama juga ditujukan kepada Rektor Universitas Udayana, Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Biomedik Universitas Udayana dan Direktur Politeknik Kesehatan Denpasar, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister di Universitas Udayana. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada para penguji Tesis yaitu Prof. dr. I Gusti Made Aman, Sp.FK., Dr. dr. Komang Bagus Satriyasa, M.Repro., Prof. Dr. dr. J. Alex Pangkahila, M.Sc., Sp.And., Dr. dr. Ida Sri Iswari, Sp.MK., M.Kes., Dr. dr. Wayan Putu Sutirta Yasa, M.Si., yang telah memberikan koreksi, masukan dan saran yang sangat berguna untuk penyempurnaan Tesis ini.
Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada para dosen Program Studi Ilmu Biomedik kekhususan Ilmu Kedokteran Dasar yang dengan penuh kesabaran telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan program studi ini tepat pada waktunya. Ucapan terimakasih yang sama penulis sampaikan kepada Dr. dr. I Dewa Made Sukrama, M.Si., Sp.MK(K)., selaku Kepala Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang telah mengijinkan penulis menggunakan fasilitas Laboratorium Mikrobiologi untuk penelitian Tesis. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Amy Yelly Kusmawati, SKM, MP., atas kesabaran dan ketekunannya melakukan penelitian tesis ini bersama penulis di Laboratorium Mikrobiologi FK Universitas Udayana.
Terimakasih juga penulis sampaikan kepada staf administrasi, teman-teman mahasiswa Program Magister Ilmu Biomedik kekhususan Ilmu Kedokteran Dasar, teman-teman di Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Denpasar yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. Akhirnya penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada suami tercinta, Simon Nahak, SH, MH., anak-anak tercinta, Anastasia Maria Prima Nahak, Teresita Marselina Nahak, Albertus Joseph Nahak yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk lebih berkonsentrasi dalam menyelesaikan studi di Program Magister ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan dan penyelesaian Tesis ini.
Denpasar Juni 2012
Penulis

ABSTRAK
EKTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS (Pluchea indica. L.) DAPAT MENGHAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI Streptococcus
mutans
Karies merupakan penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh demineralisasi lapisan email dan dentin akibat asam yang dihasilkan melalui proses fermentasi substarat oleh Streptococcus mutans. Bakteri ini menghasilkan asam laktat yang berperan penting untuk merubah lingkungan rongga mulut menjadi lebih asam (pH 5,2 – 5,5) sehingga email mulai mengalami proses demineralisasi dan terjadilah karies gigi. Hasil Survey Kesehatan Rumah tangga tahun 2004 menyatakan bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai 90,05% penduduk. Hasil Riset Kesehatan Dasar menunjukkan prevalensi karies aktif penduduk Indonesia mencapai 43,4%. Karies harus dirawat dengan baik dan dicegah agar gigi yang sehat tidak sampai terserang karies. Salah satu cara pencegahannya adalah menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik yang berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yaitu ekstrak etanol daun beluntas untuk mencegah pertumbuhan dan akulumasi plak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
Penelitian ini adalah eksperimen menggunakan completely randomized post test only control group design. Mula-mula disiapkan isolat bakteri Streptococcus mutans dan ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% untuk mengetahui kemampuan daya hambat ekstrak tehadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dan dilakukan uji daya hambat menggunakan metode difusi disk.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan One Way Anova, dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference dengan tingkat kepercayaan 95% dan analisis kualitatif menggunakan Chi-Square. Hasil uji One Way Anova menunjukkan terdapat perbedaan daya hambat yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menggunakan ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% dengan nilai p = 0,000. Konsentrasi ekstrak 25% mempunyai daya hambat setara dengan kontrol positif, dan kekuatan daya hambat meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Hasil analisis kualitatif menggunakan Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas dengan kualitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan nilai p = 0,000.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Konsentrasi minimal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah 25%. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan MIC dan MBC dari ekstrak etanol daun beluntas dan manfaatnya sebagai obat kumur antiseptik pada manusia. Kata kunci: Ekstrak etanol daun beluntas, Streptococcus mutans, daya hambat
ABSTRACT

ETHANOL EXTRACT OF BELUNTAS LEAVES (Pluchea indica.L.) CAN INHIBIT THE GROWTH OF Streptococcus mutans
Caries is a common disease of the teeth, caused by lactic acid produced by bacteria plaque through fermentation of substrate rich of sucrose and glucose. This bacteria plaque especially Streptococcus mutans produced acid from substrate and in a period of time change the oral cavity environment to become more acidity (pH 5.2-5.5) and at the time, demineralization process beginning and caries occurred. Indonesian Health Survey in the year 2004, found that caries prevalence in Indonesia achieved 90.05%. Basic Health Research in Indonesia in the year 2007, found that prevalence of tooth decay achieved 43,4%. According to this fact caries must be treated and prevented. Preventing caries must be done in many ways, one of this is using antiseptic mouth rinsing from plant extract that is ethanol extract of beluntas leaves to prevent plaque formation and accumulation in tooth surface. The aim of this study is to know that ethanol extract of beluntas leaves can inhibit the growth of Streptococcus mutans.
This is an experimental study with completely randomized post test only control group design. Firstly, preparation of isolate of Streptococcus mutans and then preparation of ethanol extract of beluntas leaves in difference concentration, they are: 25%, 50%, 75% and 100%. To know an inhibitory effect of this extract against the growth of Streptococcus mutans was used diffusion disk method.
Data was analyzed by One Way Anova, continuing by Least Significant Difference test. Qualitative analysis was used Chi-Square. This study found that there is a significant difference between control group and ethanol extract of beluntas leaves in varying concentration, they are 25%, 50%, 75% and 100% to inhibit the growth of Streptococcus mutans with p = 0.000. This study also found that ethanol extract with 25% of concentration shown the same inhibitory effect with chlorhexidine 0,12% as positive control and the inhibitory effect raising following the increasing of concentration of extract. Chi-Square analysis shown that there is a significant correlation between an inhibitory effect with the increasing of concentration of extract with p = 0.000.
The conclusion is Ethanol Extract of beluntas leaves in varying concentration, they are 25%, 50%, 75% and 100%, can inhibit the growth of Streptococcus mutans. Minimal inhibitory concentration in this study is 25%. An advanced study need to determine minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) of this extract and also the benefits of this extract as antiseptic mouth rinsing.
Key Words: Ethanol Extract of Beluntas Leaves, Streptococcus mutans, an Inhibitory Effect.
DAFTAR ISI

Halaman
SAMPUL DALAM………………………………………………... i
PRASYARAT GELAR …………………………………………… ii
LEMBAR PERSETUJUAN ……………… ……………………… iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI ……………………………….. iv
UCAPAN TERIMAKASIH ………………………………………. v
ABSTRAK …………………………………………………………. vii
ABSTRACT ………………………………………………………... viii
DAFTAR ISI ………………………………………………………. ix
DAFTAR TABEL …………………………………………………. xiii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………… xiv
DAFTAR SINGKATAN …………………………………………… xv
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………. xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………………… 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ………………………………. 7
1.3 Tujuan Penelitian ……………………………………………. 8
1.3.1 Tujuan umum ………………………………………. 8
1.3.2 Tujuan khusus ………………………………………. 8
1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………. 8
1.4.1 Manfaat ilmiah……………………………………… 8

1.4.2 Manfaat aplikasi ……………………………………. 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Karies ………………………………………………………. 10
2.1.1 Pengertian .. ………………………………………….. 10
2.1.2 Penyebab dan proses terjadinya karies……………….. 11
2.1.3 Akibat karies………………………………………….. 12
2.1.4 Penanggulangan karies ……………………………….. 13
2.2 Streptococcus mutans……………………………………….. 14
2.2.1 Klasifikasi ilmiah Streptococcus mutans …………….. 14
2.2.2 Efek patologis Streptococcus mutans ……………….. 16
2.3 Beluntas (Pluchea indica.L.) ……………………………….. 17
2.3.1 Deskripsi dan sistematika tumbuhan beluntas ……….. 17
2.3.2 Sifat senyawa aktif daun beluntas ……………. ……… 19
2.3.3 Farmakologi zat berkhasiat dalam ekstrak daun beluntas 27
2.3.4 Cara ekstraksi zat berkhasiat dalam daun beluntas ……. 33
2.4 Chlorhexidine ………………………………………………. 35
2.4.1 Farmakologi chlorhexidine 0,12% …………………… 36
2.4.2 Indikasi penggunaan chlorhexidine 0,12% ………….. 37
2.4.3 Efek samping chlorhexidine 0,12% ………………….. 37

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Berpikir ………………………………………….. 38
3.2 Konsep Penelitian………………………………………….. 40
3.3 Hipotesis Penelitian ………………………………………… 40
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian ……………………………………….. 42
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ……………………………….. 43
4.3 Sampel Penelitian…………………………………………… 43
4.3.1 Sampel penelitian …………………………………….. 43
4.3.2 Besar sampel penelitian ……………………………… 43
4.4 Variabel Penelitian …………………………………………. 44
4.4.1 Variabel bebas ………………………………………… 44
4.4.2 Variabel tergantung …………………………………… 44
4.4.3 Variabel kendali ……………………………………….. 44
4.5 Definisi Operasional Variabel ……………………………… 46
4.6 Bahan dan Instrumen Penelitian …………………………… 47
4.6.1 Bahan utama ………………………………………… 47
4.6.2 Bahan penunjang ……………………………………… 47
4.6.3 Instrumen penelitian …………………………………... 48
4.7 Alur Penelitian ……………………………………………… 49
4.8 Prosedur Penelitian ………………………………………… 50

4.8.1 Pembuatan ekstrak etanol daun beluntas ……………… 50
4.8.2 Pembuatan konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas … 51
4.8.3 Prosedur kerja di laboratorium ……………………….. 51
4.8.4 Penilaian kemampuan ekstrak ………………………… 56
4.9 Analisis Data ……………………………………………….. 56
4.9.1 Analisis deskriptif ……………………………………. 57
4.9.2 Uji normalitas dan homogenitas ……………………… 57
4.9.3 Uji Komparabilitas …………………………………… 57
4.9.4 Analisis kualitatif ……………………………………. 57
BAB V HASIL PENELITIAN
5.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian ………………………… 58
5.2 Hasil Uji Normalitas Data ………………………………….. 60
5.3 Hasil Uji Homogenitas Data Antar Kelompok …………….. 60
5.4 Hasil Uji Komparabilits Data Antar Kelompok ……………. 61
5.5 Hasil Uji Kualitatif Terhadap Kualitas Daya Hambat……… 64
BAB VI PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ………………… 67
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan ……………………………………………………. 73
7.2 Saran ………………………………………………………... 73
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………… 75

DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Aktivitas Biologis Alkaloid…………………………… 22
Tabel 5.1
Tabel 5.2
Tabel 5.3
Tabel 5.4
Tabel 5.5
Rerata Daya Hambat Kelompok Kontrol dan Kelompok
Esktrak Terhadap Pertumbuhan S. mutans ……………
Analisis Komparasi Daya Hambat Kelompok Esktrak
dengan Kelompok Kontrol……………………………..
Analisis Komparasi Daya Hambat Kelompok Esktrak pada
Berbagai Konsentrasi……………………………..
Hasil Tabulasi Silang Kualitas Daya Hambat Kelompok
Kontrol dan Kelompok Ekstrak Terhadap Pertumbuhan
Bakteri S. mutan…………………………………………
Tingkat Signifikansi Hubungan Antara Konsentrasi Ekstrak
dengan Kualitas Daya Hambat Terhadap Pertumbuhan
Bakteri S.mutans………………………….
61
62
64
65
66

DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1 Streptococcus mutans …………………………………. 15
Gambar 2.2
Gambar 2.3
Gambar 2.4
Tumbuhan Beluntas…………………………………….
Hasil Uji Fitokimia untuk Mengetahui Zat Aktif Fenolat..
Hasil Uji Fitokimia untuk Mengetahui Zat Aktif Steroid..
18
21
21
Gambar 2.5 Struktur Kimia Chlorhexidine…………………………… 36
Gambar 3.1 Konsep Penelitian………………………………………... 40
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Gambar 4.3
Rancangan Penelitian…………………………………….
Hubungan Antar Variabel ……………………………….
Alur Penelitian …………………………………………..
42
45
49

DAFTAR SINGKATAN
Singkatan Kepanjangannya
DMF-T Decay, Missing, Filling-Teeth
dmf-t
DepKes RI
FDI
WHO
Decay, missing, filling–teeth
Departemen Kesehatan Republik Indonesia
Federation Dental International
World Health Organization
NaCl Natrium Chlorida
ATCC American Type Culture Collection
Da Dalton
HTs Hydrosable Tannins
CTs Condensed Tannins
pH Power of Hidrogen (derajat keasaman)
HDL High Density Lipoprotein
VLDL Very Low Density Lipoprotein
DNA Deoxyribonucleic Acid
HIV Human Immunodeficiency Virus
NSAIDs
CYP 450
Non Steroid Anti Inflamation Drugs
Cytochrome P-450
Ditjen PM Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
ATPase
r
Adenosintriphosphatase
Replikasi (pengulangan)
CFU Colony Forming Unit

VP
Voges Proskauer
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Lampiran 5
Lampiran 6
Lampiran 7
Lampiran 8
Lampiran 9
Lampiran 10
Hasil uji Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Beluntas
Hasil Pengukuran Zona Hambatan
Kriteria Zona Hambatan Menurut Davis & Stout (1971)
Hasil uji Deskriptif
Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Data
Hasil Uji dengan One Way Anova
Hasil Uji Least Significant Difference
Hasil Uji Crosstab dan Chi-Square
Ethical Clearance
Foto Hasil Penelitian

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karies gigi atau dikenal dengan gigi berlubang adalah suatu penyakit pada jaringan keras
gigi yang sudah dikenal umum oleh masyarakat. Karies gigi merupakan penyakit yang paling
banyak ditemui di dalam rongga mulut, dapat mengenai semua populasi tanpa memandang umur,
jenis kelamin, ras ataupun keadaan sosial ekonomi dan merupakan penyebab utama hilangnya
gigi. Karies gigi bersifat kronis dan membutuhkan waktu yang lama dalam perkembangannya
sehingga sebagian besar penderita tidak menyadari bahwa giginya telah berlubang sampai
munculnya gejala-gejala berupa ngilu atau sakit gigi ketika memakan makanan yang manis,
dingin atau panas yang menandakan bahwa karies gigi telah mencapai fase lanjut.
Karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas jasad
renik dengan cara meragikan karbohidrat dalam mulut. Tandanya adalah adanya demineralisasi
bahan-bahan anorganik yang diikuti oleh kerusakan bahan organik dari email dan dentin.
Demineralisasi jaringan keras tersebut bersifat lokal, progresif dan terjadi pada bagian mahkota
yaitu pada email dan dentin serta bagian akar yaitu pada sementum dan dentin (Parmar et al.,
2007).
Menurut Rosenberg (2010), penyakit karies menduduki urutan kedua setelah commmon cold.
Pengalaman karies gigi sangat bervariasi antar negara, tergantung pada faktor perilaku, usia,
keadaan sosial-ekonomi dan pola hidup serta pola makan masyarakatnya (Parmar et al., 2007).
Prevalensi karies di negara-negara maju semakin menurun seiring dengan pesatnya
industrialisasi, pola hidup yang sehat dan terjangkaunya pelayanan kesehatan, sedangkan di

negara-negara berkembang cenderung terjadi peningkatan oleh karena meningkatnya konsumsi
makanan yang banyak mengandung gula olahan dan bersifat lengket serta jangkauan pelayanan
kesehatan gigi yang belum memadai. Suatu penelitian di Jepang yang dilakukan terhadap siswa
sekolah dasar dari anak-anak keturunan Brazilia-Jepang yang berumur 12 tahun diketahui bahwa
rata-rata DMFT-nya ≤ 3 yang artinya rata-rata setiap anak menderita karies pada gigi tetapnya
tidak lebih dari tiga gigi (Hashizume et al., 2006). Penelitian lain yang dilakukan di Mexico
terhadap anak-anak sekolah berusia 6-9 tahun didapatkan bahwa 52% anak-anak telah menderita
karies pada usia 6 tahun (Beltràn-Valladares et al., 2006). Suatu Survei Kesehatan Nasional yang
dilakukan secara ekstensif dan menyeluruh pada tahun 2004 di India menunjukkan bahwa 51,9%
anak-anak usia 5 tahun dan 53,8% anak-anak berusia 12 tahun telah menderita karies gigi
(Moses et al., 2011).
Data penyakit karies gigi di Indonesiapun sangat bervariasi. Suatu penelitian yang dilakukan
pada tahun 1990 di Jawa Barat terhadap anak-anak yang usianya di bawah lima tahun
menunjukkan angka yang sangat mencengangkan dengan rata-rata dmft (decay, missing dan
filling-teeth) sebesar 7,98 yang artinya rata-rata setiap anak tersebut memiliki 7-8 gigi susu yang
terkena karies (Koloway & Kailis, 1992). Berdasarkan laporan hasil Survei Kesehatan Rumah
Tangga DepKes RI tahun 2004 menyatakan bahwa prevalensi karies di Indonesia mencapai
90,05% penduduk (Anonim, 2005). Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dalam bidang
kesehatan gigi dan mulut menunjukkan prevalensi karies aktif penduduk Indonesia adalah
sebesar 43,4% belum termasuk angka pengalaman karies, sedangkan di Provinsi Bali
prevalensi karies penduduk mencapai 53% (Anonim, 2011). Angka ini masih jauh dari harapan
apabila dibandingkan dengan target FDI/WHO pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa 50%
anak berusia 6 tahun harus bebas karies (Anonim1982).

Karies disebabkan oleh empat faktor utama yaitu diet yang banyak mengandung karbohidrat
terutama sukrosa, anatomi dan morfologi gigi, bakteri yang bersifat asidogenik dan faktor waktu.
Karies terjadi akibat proses demineralisasi permukaan email yang disebabkan oleh asam yang
diproduksi oleh bakteri dalam plak utamanya yaitu Streptococcus mutans dan mungkin juga
oleh Lactobacillus. Bakteri-bakteri tersebut mengadakan fermentasi terhadap diet yang banyak
mengandung karbohidrat, menyebabkan pembentukan dan penimbunan asam yang
mengakibatkan dekalsifikasi dan destruksi jaringan gigi di bawah plak dan kondisi inilah yang
ditemui pada proses pembentukan karies gigi (Lewis & Ismail, 1993).
Streptococcus mutans adalah suatu bakteri Gram positif, bersifat facultatively anaerobic,
berbentuk coccus (bulat), tersusun seperti rantai, umumnya didapatkan di dalam rongga mulut
dan termasuk flora normal serta berperan penting dalam proses terjadinya karies. Bakteri ini
termasuk phylum dari Firmicutes dan merupakan kelompok bakteri yang menghasilkan asam
laktat dan pertama kali ditemukan pada tahun 1924 oleh J. Kilian Clarke (Clarke, 1924;
Vinogradov et al., 2004; Biswas & Biswas, 2011).
Streptococcus mutans merupakan bakteri yang memulai terjadinya pertumbuhan plak pada
permukaan gigi. Terjadinya hal itu disebabkan karena kemampuan spesifik yang dimiliki oleh
bakteri tersebut menggunakan sukrosa untuk menghasilkan suatu produk ekstraseluler yang
lengket yang disebut dextran yang berbasis polisakarida dengan perantaraan enzim
dextransucrase (hexocyltransferase) yang memungkinkan bakteri-bakteri tersebut membentuk
plak, sedangkan untuk menghasilkan asam laktat, Streptococcus mutans bersama-sama dengan
Streptococcus sabrinus dan Lactobacillus, memainkan peran yang sangat penting melalui enzim
glucansucrase yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Asam yang dihasilkan terus-
menerus melalui pemecahan substrat yang selalu tersedia, akan merubah lingkungan rongga

mulut menjadi lebih asam (pH 5,2 – 5,5), maka email mulai mengalami proses demineralisasi
sehingga terjadilah karies (Vinogradof et al., 2004; Argimȏn & Caufiled, 2011).
Berdasarkan fakta di atas, karies harus segera ditanggulangi dengan berbagai upaya
kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Upaya kuratif yang dilakukan
adalah dengan merawat dan menambal semua gigi yang belubang. Upaya promotif dilakukan
dengan cara memberikan informasi dan edukasi yang benar tentang cara memelihara kesehatan
gigi, sedangkan upaya preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara mekanis dan kimiawi
dengan tujuan untuk mengurangi akumulasi plak yang mengandung berbagai macam bakteri
terutama Streptococcus mutans yang menyebabkan karies gigi (Kustiawan, 2002; Anonim,
2011).
Upaya preventif yang dilakukan secara mekanis misalnya dengan menyikat gigi pada waktu
yang tepat dengan cara yang benar, sedangkan cara kimiawi dapat dilakukan dengan aplikasi
larutan fluor, penggunaan bahan antiseptik lain misalnya chlorhexidine atau dapat juga
menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan sebagai obat kumur yang mengandung antiseptik. Obat
kumur chlorhexidine yang biasa digunakan adalah chlorhexidine dengan konsentrasi 0,12%.
Obat kumur ini merupakan antimikroba dengan spektrum luas yang efektif terhadap bakteri
Gram positif maupun Gram negatif tetapi lebih efektif terhadap bakteri Gram positif (Kustiawan,
2002; Shahani & Reddy, 2011).
Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan keampuhan chlorhexidine
sebagai bahan antimikroba dalam rongga mulut. Menendez et al. (2005), mengatakan bahwa
obat kumur chlorhexidine 0,12% dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
dalam rongga mulut. Penelitian lain yang dilakukan oleh Joyston-Bechal & Hernaman (1993),

membuktikan bahwa chlorhexidine 0,05% yang dicampur dengan Natrium fluorida 0,05% dapat
menghambat pertumbuhan plak dan mengobati gingivitis.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Seymour dan Heasman (1995), membuktikan bahwa
penggunaan chlorhexidine 0,1% selama 6 minggu dapat menghambat pertumbuhan plak
sebanyak 54% dan dapat menghilangkan bau mulut yang berasal dari produk metabolit kuman
(plak) yang berada di dorsum lidah atau saliva. Keampuhan chlorhexidine 0,1% tidak diragukan
lagi, namun demikian obat kumur ini mempunyai beberapa efek samping yang merugikan yaitu
menimbulkan pewarnaan (staining) pada gigi, restorasi ataupun pada lidah, juga dapat
mengganggu rasa kecap setelah pemakaian meskipun tidak bersifat permanen (Peterson, 2011).
Pencegahan akumulasi plak dalam rongga mulut dapat digunakan obat-obatan kimiawi, juga
dapat digunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan atau obat-obat tradisional yang telah banyak diteliti
saat ini, salah satu diantaranya adalah daun beluntas (Pluchea indica Less).
Beluntas (Pluchea indica Less) adalah tumbuhan yang mudah dijumpai di Indonesia,
umumnya tumbuh liar di daerah kering pada tanah yang keras dan berbatu, atau ditanam sebagai
tanaman pagar. Tumbuhan ini berbau khas aromatis dan rasanya getir. Bagian yang digunakan
dari tanaman ini adalah daun dan akarnya yang berkhasiat untuk menghilangkan bau badan dan
bau mulut, meningkatkan nafsu makan, mengatasi gangguan pencernaan pada anak-anak,
menghilangkan nyeri pada rematik dan sebagainya. Senyawa aktif yang terkandung dalam daun
beluntas adalah flavonoid, triterpenoid dan fenol serta turunan minyak atsiri lainnya (Dalimartha,
1999; Nahak et al., 2007).
Flavonoid dalam daun beluntas memiliki aktivitas antibakteri, demikian juga senyawa fenol
yang terkandung di dalamnya merupakan suatu alkohol yang bersifat asam sehingga disebut juga
asam karbolat, yang mempunyai sifat antibakteri yakni menghambat pertumbuhan sel bakteri

Escherichia coli (Susanti, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyaningsih (2009),
menunjukkan bahwa ekstrak daun beluntas mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Methicillin
Resistant Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa Multi Resistant dengan
konsentrasi daya hambat minimal masing-masing adalah 20% dan 52%.
Hasil penelitian Nahak et al. (2007), menunjukkan bahwa ekstrak murni daun beluntas
dapat menurunkan 70% jumlah bakteri dalam saliva dan tidak ada perbedaan bermakna dalam
penurunan jumlah bakteri setelah ekstrak diencerkan pada konsentrasi 10%, 20% dan 30%.
Namun demikian dalam penelitian tersebut belum dapat dibuktikan jenis bakteri spesifik dalam
saliva yang dapat dihambat pertumbuhannya menggunakan ekstrak etanol daun beluntas.
Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui khasiat ekstrak etanol daun beluntas pada
berbagai tingkat konsentrasi untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
penyebab karies.
1.2 Rumusan Masalah Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah penelitian sebagai
berikut:
1. Apakah ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans?
2. Apakah ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 50% dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans?
3. Apakah ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 75% dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans?

4. Apakah ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 100% dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan umum
Tujuan umum penelitian ini adalah: untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
1.3.2. Tujuan khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
2. Untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 50% dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
3. Untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 75% dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
4. Untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 100% dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat ilmiah
1. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manfaat ekstrak etanol daun beluntas
untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.

2. Dapat mengembangkan penggunaan obat tradisional yaitu ekstrak etanol daun beluntas
sebagai bahan penghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
1.4.2 Manfaat aplikasi
1. Ekstrak daun beluntas dapat dimanfaatkan untuk menunjang program kesehatan gigi di
masyarakat, yakni sebagai salah satu alternatif upaya pencegahan terhadap pertumbuhan
dan akumulasi plak yang banyak mengandung bakteri Streptococcus mutans.
2. Dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. KARIES
2.1.1 Pengertian
Karies gigi adalah kerusakan pada jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas jasad
renik dengan cara meragikan karbohidrat dalam mulut. Tandanya adalah adanya demineralisasi
bahan-bahan anorganik yang kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organik dari email dan
dentin. Demineralisasi jaringan keras tersebut bersifat lokal, progresif dan terjadi pada bagian
mahkota yaitu pada email dan dentin serta bagian akar yaitu pada sementum dan dentin (Parmar
et al., 2007). Penyakit ini menyerang permukaan gigi-geligi yang mengakibatkan kerusakan
mahkota gigi dan apabila tidak dilakukan perawatan akan meluas ke pulpa dan dapat merusak
seluruh mahkota gigi. Hal ini kemudian akan menimbulkan rasa sakit, terganggunya fungsi
mastikasi, terjadi inflamasi jaringan gingiva dan pembentukan abses pada jaringan sekitar gigi
(Eccles & Green, 1994; Rosenberg, 2010).
Karies gigi atau dikenal dengan gigi berlubang sudah dikenal umum oleh masyarakat,
paling banyak ditemui di dalam rongga mulut dan dapat mengenai semua populasi tanpa
memandang umur, jenis kelamin, ras ataupun keadaan sosial ekonomi serta merupakan penyebab
utama hilangnya gigi. Karies gigi bersifat kronis dan membutuhkan waktu yang lama dalam
perkembangannya sehingga sebagian besar penderita tidak menyadari bahwa giginya telah
berlubang sampai munculnya gejala-gejala berupa ngilu atau sakit gigi ketika memakan makanan
yang manis, dingin atau panas yang menandakan bahwa karies gigi telah mencapai fase lanjut
(Parmar et al., 2007; Rosenberg, 2010; Moses et al., 2011).
2.1.2 Penyebab dan proses terjadinya karies

Karies disebabkan oleh empat faktor utama yaitu: substrat yang mengandung karbohidrat
jenis sukrosa, bakteri dalam rongga mulut, kondisi host dalam hal ini struktur dan morfologi gigi
serta faktor waktu. Beberapa jenis karbohidrat dalam makanan yaitu sukrosa dan glukosa yang
banyak terdapat pada makanan yang manis dan mudah melekat, dapat difermentasikan oleh
bakteri Streptococcus mutans, Streptococcus sabrinus dan Lactobacillus yang terdapat di dalam
rongga mulut dan membentuk asam sehingga dalam tempo satu sampai tiga menit pH plak akan
menurun dibawah lima. Seseorang yang mengabaikan kebersihan gigi dan mulutnya dan
mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung sukrosa secara terus-menerus, maka proses
fermentasi akan terus berlanjut sehingga pH lingkungan rongga mulut tetap dalam keadaan asam.
Lingkungan pH rongga mulut akan kembali ke tingkat yang normal, memerlukan waktu ± 30
menit. Penurunan pH yang berulang-ulang dalam waktu tertentu mengakibatkan demineralisasi
permukaan email gigi yang rentan, sehingga proses kariespun dimulai (Kidd & Joiston-Bechal,
1992; Eccles & Green, 1994).
Beberapa faktor yang lain yang turut berperan dalam terjadinya karies adalah oral hygiene
perorangan, usia, jenis kelamin, perubahan hormonal, keadaan xerostomia, pola makan, faktor
ekonomi dan sosial budaya, tingkat pendidikan serta keadaan geografis. Xerostomia adalah
suatu keadaan dimana produksi saliva sangat sedikit sehingga mulut terasa kering. Keadaan ini
dapat meningkatkan frekuensi karies karena fungsi saliva sebagai buffer dalam rongga mulut
menjadi berkurang (Kustiawan, 2002; Rosenberg, 2010).
Frekuensi karies akan meningkat seiring bertambahnya umur. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
semakin lama permukaan gigi berkontak dengan faktor-faktor risiko maka risiko untuk
terjadinya kariespun akan semakin meningkat. Perubahan hormonal misalnya pada masa
pubertas dan kehamilan dapat menyebabkan terjadinya gingivitis yang mengakibatkan sisa

makanan sukar dibersihkan sehinggga frekuensi kariespun dapat meningkat pada periode ini
(Tarigan, 1990).
2.1.3 Akibat karies
Karies pada tahap awal tidak akan menimbulkan keluhan yang berarti, namun bila tidak
dilakukan penambalan pada tahap awal, maka lubang gigi akan menjadi tempat menumpuknya
sisa makanan dan bakteri, sehingga proses karies akan berlanjut dan bertambah parah. Karies
pada tahap lanjut akan menyebabkan kematian pulpa dan menimbulkan keluhan rasa sakit yang
cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, terjadinya abses di jaringan sekitar gigi serta timbulnya
halitosis yang dapat mengganggu pergaulan. Perawatan karies tahap lanjut memerlukan waktu
yang panjang serta biaya yang besar dan apabila tidak dirawat maka gigi tidak dapat
dipertahankan lagi sehingga harus dicabut yang mengakibatkan cacatnya fungsi mastikasi dan
terganggunya fungsi estetik. Karies tahap lanjut yang tidak dirawat dapat juga menimbulkan
komplikasi terhadap organ tubuh yang lain yaitu menjadi fokal infeksi terjadinya sinusitis
maksilaris, kerusakan katup jantung dan artritis (Lewis & Ismail, 1993; Kustiawan, 2002;
Rosenberg, 2010).
2.1.4 Penanggulangan karies
Diagnosa dan rencana perawatan karies bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi
gigi serta mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut. Struktur gigi yang telah rusak tidak dapat
sembuh sempurna meskipun pada karies tahap awal masih terjadi proses remineralisasi.
Perawatan karies pada tahap awal yaitu karies yang baru mencapai email dan dentin dapat
dilakukan dengan cara membuang struktur gigi yang sudah rusak menggunakan high speed drill,
kemudian mengembalikan bentuk anatomi gigi dengan menggunakan bahan restorasi yang
sesuai. Kerusakan yang sudah mencapai pulpa akan menyebabkan terjadinya kematian pada

pulpa sehingga diperlukan perawatan saraf gigi terlebih dahulu dan selanjutnya gigi direstorasi
dengan bahan tambal yang sesuai (Ritter, 2004; Rosenberg, 2010).
Pencegahan karies dapat dilakukan dengan banyak cara diantaranya yang paling murah dan
mudah adalah menjaga personal oral hygiene dengan cara menyikat gigi secara benar dengan
waktu yang tepat yakni segera setelah makan menggunakan pasti gigi yang mengandung fluor,
penggunaan dental floss untuk menghilangkan food debris dan food impacted di antara gigi
serta mengatur pola makan. Disarankan juga untuk memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke
fasilitas pelayanan kesehatan gigi untuk deteksi dini karies, kontrol plak, penutupan fissure gigi
yang dalam (fissure sealant), topical application dengan larutan fluor serta penggunaan obat
kumur yang mengandung antiseptik baik yang kimiawi maupun yang berasal dari ekstrak
tanaman obat untuk mengurangi jumlah plak (Lewis & ismail, 1993; Rosenberg 2010).
Penelitian yang dilakukan oleh Carson et al. (2006), menunjukkan bahwa ekstrak teh hijau
dan tea tree oil apabila digunakan sebagai obat kumur dapat menghambat pertumbuhan
Streptococcus mutans dan membunuh bakteri yang lain dalam plak. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Yanti et al. (2008), menunjukkan bahwa zat Macelignan yang terdapat dalam
daging buah pala dapat mengurangi biofilm level dari Streptococcus mutans.
2.2 Streptococcus mutans
2.2.1 Klasifikasi ilmiah Streptococcus mutans
Streptococcus mutans adalah suatu bakteri yang bersifat facultatively anaerobic, Gram
positif, berbentuk coccus (bulat), tersusun seperti rantai, umumnya didapatkan di dalam rongga
mulut dan termasuk flora normal serta berperan penting dalam proses terjadinya karies. Bakteri
ini termasuk phylum dari Firmicutes dan merupakan kelompok bakteri yang menghasilkan asam

laktat dan pertama kali ditemukan pada tahun 1924 oleh J. Kilian Clarke (Clarke, 1924;
Vinogradov et al., 2004; Biswas & Biswas, 2011).
Struktur dinding sel bakteri ini terdiri atas beberapa lapisan peptidoglikan yang tebal dan
kaku (20-80µm) sehingga membedakannya dari dinding sel bakteri Gram negatif. Dinding sel
bakteri ini mengandung berbagai polisakarida juga mengandung substansi dinding sel yang
disebut dengan asam teikoat (teichoic acid) yang diperkirakan berperan dalam pertumbuhan dan
pembelahan sel. Bakteri ini juga mempunyai sifat antigen spesifik sehingga dapat dimanfaatkan
untuk mengidentifikasi spesies bakteri tersebut secara serologi (Radji, 2010).
Gambar 2.1 Strain Streptococcus mutans dalam kultur Thioglycollate broth (Clarke, 1924)
Klasifikasi ilmiah dari Streptococcus mutans adalah sebagai berikut (Clarke, 1924):
Kingdom : Bacteria
Phylum : Firmicutes
Class : Bacilli
Order : Lactobacillales

Family : Streptococcaceae
Genus : Streptococcus
Species : Streptococcus mutans
2.2.2 Efek patologis dari Streptococcus mutans
Streptococcus mutans bersama-sama dengan Streptococcus sabrinus serta Lactobacillus
memainkan peran yang sangat penting melalui enzim glucansucrase yang dihasilkan oleh
bakteri-bakteri tersebut untuk menghasilkan asam laktat. Asam yang dihasilkan terus menerus
melalui pemecahan substrat yang selalu tersedia, akan merubah lingkungan rongga mulut
menjadi lebih asam (pH 5,2 – 5,5), maka email mulai mengalami proses demineralisasi sehingga
terjadilah karies (Vinogradof et al., 2004; Argimȏn & Caufiled, 2011).
Streptococcus mutans merupakan koloni bakteri pertama yang dijumpai pada permukaan gigi
segera setelah gigi pertama erupsi dan merupakan bakteri yang memulai terjadinya pertumbuhan
plak pada permukaan gigi. Terjadinya hal tersebut disebabkan karena kemampuan spesifik yang
dimiliki oleh bakteri tersebut menggunakan sukrosa untuk menghasilkan suatu produk
ekstraseluler yang lengket yang disebut dextran yang berbasis polisakarida dengan perantaraan
enzim dextransucrase (hexocyltransferase). Produk bakteri berupa gel ekstraseluler yang lengket
tersebut memungkinkan bakteri-bakteri yang lain ikut menempel pada permukaan gigi sehingga
terbentuklah plak. Plak terdiri dari berbagai mikroorganisme yang selain menyebabkan karies
gigi dapat juga menyebabkan terjadinya gingivitis, periodontitis, abses dan halitosis.
(Vinogradof et al., 2004; Argimȏn & Caufiled, 2011).
Streptococcus mutans selain menyebabkan karies gigi juga terimplikasi sebagai patogenesis
dari penyakit cardiovaskuler tertentu. Bakteri ini merupakan spesies terbanyak yang terdeteksi

dari hasil ekstirpasi jaringan klep jantung yaitu sebanyak 68,6% dan dari atheromathous plaque
didapatkan 74,1% bakteri (Nakano et al., 2006).
Penelitian lain yang dilakukan oleh Kojima et al. (2012), menunjukkan bahwa Streptococcus
mutans strain on dextran sodium sulfate (DSS) menyebabkan ulcerative colitis pada tikus
percobaan. Sedangkan strain TW 295 akan memperparah ulcerative colitis dan dalam penelitian
yang sama strain Streptococcus mutans ini ditemukan juga pada sel-sel hati (hepatocytes) yang
mengindikasikan bahwa sel-sel hatipun menjadi target organ dari strain tersebut.
2.3 Beluntas (Pluchea indica Less)
2.3.1 Deskripsi dan sistematika tumbuhan beluntas
Beluntas merupakan tumbuhan semak yang bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu
lembut. Umumnya ditanam sebagai tanaman pagar atau bahkan tumbuh liar, tingginya bisa
mencapai dua hingga tiga meter apabila tidak dipangkas. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering
pada tanah yang keras dan berbatu, di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi pada
ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, memerlukan cukup cahaya matahari atau sedikit
naungan dan perbanyakannya dapat dilakukan dengan stek pada batang yang sudah cukup tua.
Beluntas termasuk tumbuhan berakar tunggang, akarnya bercabang dan berwarna putih kotor.
Batangnya berambut halus, berkayu, bulat, bercabang, pada tumbuhan yang masih muda
berwarna ungu dan setelah tua berwarna putih kotor (Dalimartha, 1999; Anonim, 2010).
Daun beluntas bertangkai pendek, letaknya berseling, tunggal dan berbentuk bulat telur
dengan ukuran 2,5 – 8 cm x 1-5 cm. Pangkal daun menirus, ujung daun meruncing, tepi daun
bergerigi, tangkai daun semi duduk tidak ada penumpu dengan warna hijau terang dan berbau
harum ketika dihancurkan. Bunganya terdiri dari banyak bongkol pada terminal hemisferikal

atau gundungan aksiler. Bunganya berbentuk tabung dengan panjang mahkota 3,5 – 5 mm.
Buahnya berbentuk silinder dengan panjang 1 mm dengan biji yang kecil berwarna coklat
keputih-putihan (Dalimartha, 1999; Anonim 2010).
Gambar 2.2 Tumbuhan Beluntas (Anonim, 2010)
Sistematika tumbuhan beluntas adalah sebagai berikut (Ferdian, 2010):
Kingdom : Plantae
Phylum : Magnoliaphyta
Class : Magnoliopsida
Ordo : Asterales
Family : Asteraceae
Genus : Pluchea
Species : Pluchea indica (L.)Less
2.3.2 Sifat senyawa aktif daun beluntas
Penggunaan tumbuhan sebagai obat sangat berkaitan dengan kandungan kimia yang terdapat
dalam tumbuh-tumbuhan tersebut terutama zat bioaktifnya. Senyawa bioaktif yang terdapat
dalam tumbuhan biasanya merupakan senyawa metabolit sekunder. Metabolit primer biasanya

mengandung asam amino, gugusan gula sederhana, asam nukleat dan lemak yang berguna untuk
proses-proses dalam sel misalnya pertumbuhan, fotosintesis, reproduksi dan metabolisme serta
fungsi-fungsi primer lainnya, sedangkan metabolit sekunder dalam bentuk senyawa-senyawa
aktif, berguna untuk mempertahankan diri. Tumbuhan dapat memproduksi sendiri berbagai jenis
metabolit sekunder yang sering dieksploitasi oleh manusia untuk berbagai kepentingan.
Metabolit sekunder terbagi atas tiga bagian besar yaitu: terpen dan terpenoid yang terdiri dari ±
25.000 tipe, alkaloid yang terdiri dari ± 12.000 tipe, senyawa phenolic yang terdiri dari ± 8000
tipe (Zwenger & Basu, 2008; Schultz, 2011; Hassanpour et al., 2011).
Daun beluntas berbau khas aromatik dan rasanya getir, banyak mengandung zat berkhasiat
yang sering digunakan untuk menghilangkan bau badan, bau mulut, mengatasi kurang nafsu
makan, mengatasi gangguan pencernaan pada anak, mengobati TBC kelenjar, menghilangkan
nyeri pada rematik, nyeri tulang dan sakit pinggang, menurunkan demam, mengobati keputihan
dan mengatasi haid yang tidak teratur (Dalimartha, 1999).
Kandungan kimia dalam daun beluntas adalah: Alkaloid, flavonoid, tannin, minyak atsiri,
asam chlorogenik, natrium, kalium, aluminium, kalsium, magnesium dan fosfor. Sedangkan
akar beluntas mengandung tannin dan flavonoid (Dalimartha, 2005). Daun beluntas yang akan
digunakan dalam penelitian ini diambil dari daerah Jalan Tukad Badung, Kelurahan Renon
Kecamatan Denpasar Timur. Hasil uji fitokimia yang dilakukan pada tanggal 22 November 2011
di UPT Laboratorium Pengembangan Sumber daya Genetik Kelautan dan Rekayasa Genetik
(Marine Biology) Universitas Udayana Denpasar, menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun
beluntas yang akan dipakai pada penelitian ini mengandung beberapa metabolit sekunder yaitu:
Tannin (+), Alkaloid (+), Flavonoid (++), Steroid (+++) dan Fenolat (+++). Tanda (+)
menunjukkan banyaknya kandungan zat aktif. Positif satu (+) menandakan bahwa kandungan zat

aktif dalam metabolit sekunder hanya sedikit, positif dua (++) menandakan kandungan zat aktif
yang banyak dalam metabolit sekunder, dan positif tiga (+++) menandakan kandungan zat aktif
yang sangat dalam metabolit sekunder. Wang et al. (2010), mengatakan bahwa senyawa dengan
struktur kimia yang hampir sama akan mempunyai profil farmakokinetik yang sama pula.
Gambar 2.3 Hasil Uji Fitokimia untuk Mengetahui Zat Aktif Fenolat
Gambar 2.4 Hasil Uji Fitokimia untuk Mengetahui Zat Aktif Steroid
2.3.2.1 Sifat senyawa aktif alkaloid
Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa, yang mengandung satu atau
lebih atom nitrogen, biasanya dalam cincin heterosiklik. Alkaloid merupakan senyawa organik

bahan alam yang terbesar jumlahnya mempunyai struktur yang beraneka ragam dari yang
sederhana sampai yang rumit. Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lebur
tertentu. Berdasarkan biogenetik, alkaloid diketahui berasal dari sejumlah kecil asam amino
yaitu ornitin dan lisin yang menurunkan alkaloid alisiklik dan isokuinolin, serta triptofan yang
menurunkan alkaloid indol (Putra, 2007).
Alkaloid tidak mempunyai tatanan sistematik oleh karena itu suatu alkaloid dinyatakan
dengan nama trivial, misalnya kuinin, morfin dan stiknin, Hampir semua nama trivial berakhiran
dengan –in yang mencirikan alkaloid. Berdasarkan lokasi atom nitrogen di dalam struktur
alkaloid, alkaloid dibagi menjadi lima golongan yaitu: 1) Alkaloid heterosiklis; 2) Alkaloid
dengan nitrogen eksosiklis dan amina alifatis; 3) Alkaloid putressina, spermidina dan spermina;
4) Alkaloid peptida dan 5) Alkaloid terpena (Lenny, 2006).
Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktivan biologis tertentu, ada
yang sangat beracun tetapi ada pula yang sangat berguna dalam pengobatan, misalnya kuinin,
morfin, stiknin dan nikotin adalah alkaloid yang terkenal dan mempunyai efek fisiologis serta
psikologis (Harborne dan Turner, 1984) dalam Ferdian (2010).
Berikut ini adalah aktivitas biologis dari beberapa senyawa alkaloid:
Tabel 2.1
Aktivitas Biologis Alkaloid (Putra, 2007)
Senyawa Alkaloid (Nama Trivial) Aktivitas Biologis
Nikotin Stimulan pada saraf otonom
Morfin Analgesik
Kodein Analgesik, antitusif
Kokain Analgesik
Piperin Antifeedant (bioinsektisida)

Quinin Obat malaria
Ergotamin Analgesik pada migrain
Mitraginin Analgesik dan antitusif
Saponin Antibakteri 2.3.2.2 Sifat senyawa aktif tannin
Tannin adalah suatu senyawa phenolic dengan berat molekul yang cukup besar, berkisar
antara 500–3000 Da, bersifat larut dalam air, banyak didapatkan pada daun, kulit, buah, kayu dan
akar tanaman dan umumnya didapatkan pada vakuola-vakuola dalam jaringan. Tannin
berhubungan erat dengan mekanisme pertahanan tumbuhan terhadap mammalia herbivora,
burung dan serangga. Sampai dengan saat ini definisi tentang tannin masih sukar dirumuskan
secara tepat (Hassanpour et al., 2011).
Tannin digolongkan berdasarkan kemampuannya untuk membentuk suatu kompleks dengan
ptotein, sedangkan berdasarkan struktur kimianya tannin dibagi menjadi dua kelompok besar
yaitu: hydrosable tannins (HTs) dan condensed tannins (CTs) yang dibedakan oleh berat
molekul dan struktur serta efeknya yang berbeda terhadap herbivora khususnya hewan
memamahbiak. HTs biasanya ditemukan dalam konsentrasi yang rendah pada tumbuhan
dibandingkan dengan CTs. HTs dapat membentuk senyawa pyrogallol yang bersifat toksik
terhadap mamalia. Observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa apabila senyawa toksik
yang terbentuk dalam diet melebihi 20% dapat menyebabkan nekrosis pada hati, kerusakan
ginjal disertai dengan nekrosis pada tubulus proksimalis, lesi yang dihubungkan dengan
perdarahan gastroenteritis dan dapat menimbulkna kematian pada domba dan ternak (Patra &
Saxena, 2010; Hassanpour et al., 2011).
CTs atau dikenal juga sebagai proanthocyanidines adalah jenis tannin yang umumnya
didapatkan pada berbagai macam tumbuhan. CTs mempunyai struktur kimia yang bervariasi

yang mempengaruhi aktivitas fisik dan biologiknya. CTs mengandung unit flavonoid yakni
flavan-3-ol yang dihubungkan dengan ikatan karbon-karbon. Tannin merupakan suatu substansi
polyphenolic yang mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan protein membentuk tannin-
protein complex yang bersifat mudah larut, membentuk complex tannin-poylscharides misalnya
dengan selulosa, hemiselulosa dan pectin. Tannin juga dapat membentuk kompleks dengan asam
nukleat, steroid, alkaloid dan saponin (Hassanpour et al., 2011). Penelitian-penelitian sekarang
pada hewan coba menunjukkan bahwa tannin mempunyai efek yang menguntungkan yaitu
sebagai anti mikroba, antioksidan dan anthelmintic (Patra & Saxena, 2010; Hassanpour et al.,
2011).
2.3.2.3 Sifat senyawa aktif flavonoid
Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbanyak di alam.
Senyawa-senyawa ini bertanggungjawab terhadap zat warna merah, ungu, biru dan kuning pada
mahkota bunga dengan tujuan untuk menarik serangga yang membantu penyerbukan. Flavonoid
khususnya flavanoid seperti katekin merupakan senyawa polyphenolic yang umum didapatkan
pada tumbuhan yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Flavonols terdapat dalam jumlah kecil
merupakan bioflavonoid yang asli contohnya adalah quercetin. Flavonoid tersebar luas pada
berbagai macam tanaman, toksisitasnya rendah dibandingkan dengan senyawa aktif yang lain,
membuatnya banyak dikonsumsi oleh hewan dan manusia.
Berdasarkan ikatannya dengan gula, flavonoid terdiri dari dua kelompok yaitu glikosida
yang berikatan dengan satu atau lebih molekul gula, dan yang lain yaitu aglikon adalah flavonoid
yang tidak berikatan dengan gula. Kebanyakan flavonoid yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
adalah dalam bentuk glikosida (Williamson, 2004).

Aktivitas farmakologis dari flavonoid dianggap berasal dari rutin (glikosida flavonol).
Flavonoid dapat digunakan sebagai obat karena mempunyai bermacam-macam bioaktifitas
seperti: antiinflamasi, anti bakteri, anti kanker, anti fertilitas, anti viral, anti diabetes, anti
depresan dan anti diare (Spencer & Jeremy, 2008; Cushnie & Lamb, 2011).
2.3.2.4 Sifat senyawa aktif steroid
Senyawa steroid adalah suatu senyawa organik yang terdapat dalam metabolit sekunder
yang didapatkan pada tumbuhan dan hewan. Senyawa ini berasal dari senyawa triterpen yang
merupakan derivat dari terpen dengan kerangka dasarnya adalah sistem cincin siklopentana
perhidrofenantrena. Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam
satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik, yaitu skualena.
Senyawa ini berstruktur siklik yang rumit, kebanyakan berupa alkohol, aldehid atau asam
karboksilat, berupa senyawa tanpa warna, berbentuk kristal, sering kali bertitik leleh tinggi.
Triterpenoid dapat dipilah menjadi sekurang-kurangnya empat golongan senyawa yakni:
triterpenoid sebenarnya, steroid, saponin, dan glikosida jantung. Saponin dan glikosida jantung
merupakan triterpenoid sedangkan steroid yang terutama terdapat sebagai glikosida (Rustaman et al.,
2006).
Dahulu steroid dianggap sebagai senyawa satwa berupa hormon kelamin dan asam empedu,
namun sekarang makin banyak senyawa tersebut ditemukan dalam jaringan tumbuhan. Steroid
yang terdapat dalam jaringan hewan berasal dari triterpen lanosterol sedangkan yang terdapat
dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpen sikloartenol. Tahap awal dari biosintesis steroid
adalah sama bagi steroid alam yakni pengubahan asam asetat melalui asam mevalonat dan
skualen menjadi lanosterol atau sikloartenol yang kemudian mengalami lagi beberapa tahap
perubahan sampai terbentuk senyawa steroid (Rustaman et al., 2006; Zwenger & Basu, 2008).

Steroid sebagai salah satu metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak daun beluntas,
merupakan derivat senyawa terpene yaitu triterpenoid mempunyai aktivitas antibakteri,
antiparasit, antiinflamasi, antijamur, kardiotonik dan efek anabolik (Islam et al., 2003;
Prabuseenivasan et al., 2006; Praptiwi et al., 2006; John et al., 2007). Mekanisme aktivitas
antibakteri steroid diduga berhubungan dengan kemampuan steroid menyebabkan kebocoran
pada bagian aqueous (cair) dari phosphatidylethanolamine yang kaya akan liposome (Epand et
al., 2007; Mohamed et al., 2010).
2.3.2.5 Sifat senyawa aktif fenolat
Senyawa fenol banyak didapatkan di alam, berasal dari tumbuh-tumbuhan, biasanya
terdapat di dalam vegetative foliage tumbuhan yang berguna untuk menakut-nakuti herbivora.
Umumnya, senyawa fenolat terbagi menjadi dua senyawa, yaitu fenol sederhana dan polifenol
misalnya flavonoid dan tannin, namun masih banyak senyawa-senyawa lain yang merupakan
turunan dari senyawa fenol misalnya: eugenol, estradiol, thymol dan lain-lain. Berdasarkan kimia
organic, fenol disebut juga phenolic adalah suatu klas senyawa kimia yang terdiri dari gugus
hidroksil (OH) terikat secara langsung pada suatu kelompok hidrokarbon aromatik. Senyawa
fenolat mampu menetralkan radikal bebas yang membahayakan tubuh, sehingga spektrum
aktivitas biokimia senyawa fenolat cukup luas, yaitu sebagai antioksidan, antimutagen,
antimikroba, antikarsinogenik, dan mampu memodifikasi ekspresi gen (Devi, 2011).
2.3.3 Farmakologi dari zat berkhasiat dalam ekstrak daun beluntas
2.3.3.1 Farmakologi senyawa alkaloid
Senyawa alkaloid yang terkandung dalam berbagai ekstrak tumbuhan mempunyai khasiat
yang sangat berguna bagi manusia, misalnya kuinin yang terdapat dalam ekstrak kulit tumbuhan
chincona, artemisinin yang terdapat dalam ekstrak tumbuhan Artemisia annua mempunyai

aktivitas terhadap Plasmodium falciparum. Morfin dan kodein juga adalah suatu alkaloid yang
mempunyai aktivitas biologis yang berguna yaitu sebagai analgesik yang kuat. Sintesis
senyawa-senyawa alkaloid dari tumbuhan tersebut sudah dilakukan sehingga sekarang
ditemukan obat-obatan anti malaria sintesik seperti quinine, artemisinin, obat narkotik analgesik
dan antitusif sintesik seperti opioid, yang mempunyai efek farmakodinamik, farmakokinetik
yang jelas terhadap berbagai penyebab penyakit pada manusia (Putra, 2007).
Senyawa alkaloid opioid misalnya morfin tidak dapat menembus kulit utuh, tetapi apabila
kulit mengalami luka maka akan terjadi absorbsi obat lewat kulit yang luka dan lewat mukosa
yang masih utuh. Absorbsi obat lewat usus sedikit sekali sehingga efek analgesiknya sangat
rendah dibandingkan dengan pemberian perparenteral pada dosis yang sama. Alkaloid opioid
yang diberikan secara intra vena akan berikatan dengan protein plasma yaitu α-1-acid
glycoprotein, mengalami biotransformasi di hati lewat dua fase yaitu fase oksidasi dan reduksi
yang dikatalisis oleh enzim CYP 450. Fase konyugasi akan menghasilkan D-glucoronic acid
sebagai metabolitnya yang tidak aktif selanjutnya diekskresi lewat ginjal, sistem empedu dan
juga feses. Opioid akan berinteraksi dengan reseptornya untuk menimbulkan efeknya dan potensi
analgesik tergantung pada afinitasnya terhadap reseptor opioid spesifik (Sardjono et al., 2004;
Putra, 2007).
2.3.3.2 Farmakologi senyawa tannin
Tannin yang berasal dari ekstrak tumbuhan diabsorbsi dengan cepat dari saluran cerna
kemudian mengalami distribusi dan eliminasi yang cukup cepat pula. Bioavailabilitasnya sangat
rendah setelah pemberian peroral. Konsentrasi dalam plasma adalah 213 ng/ml setelah 55 menit
pemberian peroral 0,8 g/kg BB ekstrak yang mengandung tannin. Hidrolisisnya kebanyakan

terjadi di usus besar pada pH alkalin. Senyawa tannin khususnya oligomeric proanthocianidines
dapat menembus sawar darah otak (Wang et al., 2010).
Senyawa-senyawa tannin misalnya ellagic acid dapat bereaksi dengan radikal bebas oleh
karena kemampuannya untuk berikatan dengan ion-ion metal sehingga mempunyai efek
antioksidan yang poten terhadap lipid peroksidasi di dalam mitokondria dan mikrosom. Aksinya
sebagai antioksidan ditandai oleh kemampuannya untuk menyediakan elektron sehingga
mengeliminasi radikal bebas hasil peroksidasi lipid (Wang et al., 2010). Senyawa tannin juga
berfungsi untuk menurunkan kolesterol total, VLDL dan triglicerid dan meningkatkan HDL
sehingga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi gangguan metabolisme lemak dan
obesitas (Lei et al., 2007).
Senyawa tannin juga mempunyai efek astringent. Beberapa penelitian membuktikan bahwa
senyawa tannin dapat berikatan dengan protein sehingga mempercepat penyembuhan ulcer
(Murthy et al., 2004; Ajaikumar et al., 2005). Ellagitannins adalah suatu derivat senyawa tannin
mempunyai aktivitas antibakteri dengan cara membentuk kompleks dengan proline yaitu sejenis
protein pada dinding sel bakteri, menyebabkan protein leakage, terjadi kerusakan dinding sel
bakteri sehingga menyebabkan kematian sel bakteri (Machado et al., 2003; Braga et al., 2005;
Mohamed et al., 2010). Tannin mempunyai aktivitas menghambat cara kerja enzim yang
berperan dalam replikasi RNA virus, mengendapkan protein virus yang sangat berguna untuk
siklus hidup virus sehingga menyebabkan kematian virus (Haidari et al., 2009).
Tumbuhan herbal yang mengandung banyak tannin dianjurkan untuk tidak diberikan
bersama-sama dengan herbal yang banyak mengandung alkaloid, karena campuran kedua
senyawa tersebut akan menyebabkan terjadinya presipitasi. Pemberian tannin bersama-sama
dengan ekstrak yang banyak mengandung protein kemungkinan akan terjadi reaksi presipitasi

juga oleh karena interaksi farmakologik sehingga akan mengurangi bioavailabilitas bahan aktif
dalam ekstrak (Ajaikumar et al., 2005; Haidari et al., 2009). Penelitian yang dilakukan Serafini
et al. (1996), menunjukkan bahwa pemberian susu yang dicampur dengan teh hijau dan teh
hitam akan terjadi interaksi farmakologik sehingga meniadakan efek antioksidan dari kedua jenis
teh.
2.3.3.3 Farmakologi senyawa flavonoid
Flavonoid meskipun telah dimasak, dapat mencapai usus halus dalam keadaan utuh,
diabsorbsi secara terbatas di usus halus, mengalami metabolisme dengan cepat dan terbentuk
metabolit dari hasil metilasi, glucoronidasi dan sulphatasi. Umumnya bioavailabilitas flavonoid
sangat rendah oleh karena absorbsinya yang terbatas dan eliminasinya yang cepat namun
bervariasi diantara berbagai jenis flavonoid. Isoflavon mempunyai bioavailabilitas paling baik
sedangkan flavanol mempunyai absorbsi paling rendah (Manach et al., 2005). Pemberian soy
isoflavons dan citrus flavanones peroral pada manusia menunjukkan bahwa konsentrasi puncak
dalam plasma tidak melebihi 10 micromoles/liter, sedangkan setelah mengkonsumsi
anthocyanines, flavanol dan flavonol, konsentrasi puncak dalam plasmanya kurang dari 1
micromole/liter (Manach et al., 2004).
Flavonoid mempunyai aktivitas antioksidan. Mekanisme kerjanya secara in vitro dapat
dijelaskan sebagai berikut, flavonoid mempunyai kemampuan untuk mengikat ion-ion metal
seperti besi dan tembaga yang berfungsi mengkatalisis pembentukan radikal bebas sehingga
membatasi pembentukan radikal bebas, namun belum diketahui apakah fungsinya sebagai methal
chelators agent efektif juga secara in vivo, masih diperlukan penelitian lebih lanjut (Frei &
Higdon, 2003).

Efek flavonoid yang lain yaitu mempengaruhi cell signaling pathways. Semua sel
mempunyai kemampuan untuk memberikan respon atas berbagai macam stres atau signal dengan
cara meningkatkan atau mengurangi ketersediaan protein spesifik. Reaksi cascade yang
kompleks yang menyebabkan perubahan dalam ekspresi gen spesifik disebut dengan cell
signaling pathway atau signal transduction pathways. Alur ini mengatur sejumlah proses dalam
sel misalnya pertumbuhan, proliferasi dan apoptosis (kematian sel). Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa kemampuan flavonoid untuk mempengaruhi cell signaling pathway lebih
besar dibandingkan efeknya sebagai antioksidan (Spencer et al., 2003).
Sejumlah hasil penelitian terhadap kultur sel menunjukkan bahwa flavonoid mempunyai
efek terhadap penyakit-penyakit kronis dengan cara menghambat secara selektif pembentukan
protein kinase yang berperan dalam mengkatalisis reaksi fosforilasi dari target protein (William
et al., 2004; Hou et al., 2004). Pertumbuhan dan proliferasi sel juga diatur growth factor yang
melakukan insiasi cell signaling cascade dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik dalam
membran sel. Flavonoid diduga mempengaruhi growth factor signaling dengan cara
menghambat secara kompetitif reseptor binding dalam membran sel (Lambert & Yang, 2003).
Penelitian yang lain menunjukkan bahwa flavonoid mempunyai aktivitas antimikroba
melalui beberapa mekanisme yaitu: 1) menghambat sintesa dinding sel bakteri; 2) menyebabkan
protein leakage akibatnya terjadi kebocoran dinding sel bakteri; 3) menghambat sintesis protein
bakteri; dan 4) kemungkinan mengintervensi fungsi DNA sel bakteri (Hussain et al., 2010;
Mohamed et al., 2010).
Jus anggur yang mengandung bahan aktif furanocoumarins, dihydroxybergamottin,
flavonoids naringenin dan quercetin dapat berinteraksi dengan berbagai macam obat dengan cara
menghambat secara ireversibel enzim CYP 450 3A4 in vitro (Bailey & Dresser, 2004). Beberapa

flavonoid misalnya: quercetin, naringenin, flavanol dalam teh hijau dan epigallocathechine
gallate menghambat aktivitas P-glikoprotein sehingga apabila mengkonsumsi suplemen
flavonoid dalam jumlah yang banyak maka bioavailabilitasnya akan meningkat sehingga
meningkatkan toksisitasnya. Obat-obat yang transport aktifnya menggunakan P-glikoprotein
misalnya digoxin, obat-obat antihipertensi, obat antiaritmia, obat-obat kemoterapi, obat-obat anti
jamur dan HIV protease inhibitors, apabila diberikan bersama-sama dengan flavonoid, akan
meningkatkan toksisitas obat-obat tersebut (Marzolini et al., 2004).
Penelitian ex vivo assay yang telah dilakukan membuktikan bahwa, mengkonsumsi jus
anggur ungu (500 ml/hari) dan dark chocolate (235 mg/ hari) yang banyak mengandung
flavonoid, dapat terjadi penghambatan agregasi platelet, sehingga meningkatkan risiko
perdarahan terutama pada pasien yang sedang menggunakan obat-obat antikoagulan misalnya
clopidogrel, dipyridamole, NSAIDs, aspirin dan lain-lain (Freedman et al., 2001; Murphy et al.,
2003). Flavonoid juga dapat mengurangi absorbsi nonheme iron yang terdapat dalam makanan,
demikian pula diketahui bahwa quercetin serta flavonoid yang terdapat dalam teh dapat
menghambat absorbsi vitamin C dari saluran cerna dan menghambat transport vitamin C ke
dalam sel (Song et al., 2002). Flavonoid yang berasal dari makanan nabati relatif tidak
menimbulkan efek samping. Hal ini dapat dijelaskan karena absorbsinya yang sangat sedikit dan
metabolisme serta eliminasi yang sangat cepat (Higdon et al., 2008).
2.3.4 Cara ekstraksi zat berkhasiat dalam daun beluntas
2.3.4.1 Pengertian
Ekstraksi adalah proses pengambilan/pemisahan komponen yang larut dari suatu bahan atau
campuran dengan menggunakan pelarut seperti air, alkohol, aseton dan sebagainya. Ekstraksi
dilakukan untuk mendapatkan bahan cair atau padat misalnya bahan alam yang sukar sekali

dipisahkan dengan metode pemisahan mekanis atau termis, misalnya karena komponennya
saling bercampur secara sangat erat, komponen peka terhadap panas, perbedaan sifat-sifat
fisiknya sangat kecil, atau tersedia dalam konsentrasi yang terlalu rendah (Rahayu, 2009).
Menurut Ditjen POM (1995), ekstraksi adalah kegiatan pengambilan kandungan kimia yang
dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair, sedangkan
ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia
nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai kemudian semua atau hampir
semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa
sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ginting, 2010). Prinsip ekstraksi adalah
melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam pelarut non polar.
Umumnya ekstraksi dilakukan secara berturut-turut mulai dengan pelarut non polar misalnya n-
heksana, lalu pelarut dengan kepolarannya sedang misalnya ethyl-acetate dan dichlormethane,
kemudian pelarut yang bersifat polar misalnya etanol atau metanol (Ginting, 2010).
2.3.4.2 Metode ekstraksi
Beberapa metode ekstraksi yang biasa digunakan untuk mengekstraksi metabolit sekunder
bahan alam yaitu: maserasi, perkolasi, sokletasi, refluks, digestasi dan infus (Ginting, 2010).
Metode ekstraksi metabolit sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah maserasi
menggunakan pelarut etanol.
Maserasi berasal dari kata bahasa latin macerare yang berarti perendaman, sehingga
maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan cara perendaman sampel
menggunakan pelarut organik dengan beberapa kali pengocokan dan pengadukan pada
temperatur ruangan. Teknik maserasi digunakan terutama jika senyawa organik metabolit
sekunder yang ada dalam bahan tersebut cukup banyak persentasinya dan ditemukan suatu

pelarut yang dapat melarutkan senyawa tersebut tanpa dilakukan pemanasan. Proses ini sangat
menguntungkan karena dengan proses perendaman, akan terjadi pemecahan dinding dan
membran sel akibat perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel sehingga metabolit sekunder
yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan
sempurna karena dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. Pemilihan bahan pelarut dalam
proses maserasi akan memberikan efektivitas yang tinggi dengan memperhatikan kelarutan
senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut (Harborne, 1987; Pasaribu, 2009; Dewi, 2010).
Etanol adalah senyawa dengan sifat polar dan semi polar maksudnya adalah dapat berfungsi
sebagai pelarut air dan minyak. Penambahan air pada etanol akan mengurangi daya larut minyak
di dalam etanol. Kebanyakan senyawa yang molekulnya menghasilkan rasa misalnya manis,
pahit atau asam biasanya bersifat polar sedangkan senyawa yang molekulnya menghasilkan
aroma biasanya bersifat non polar. Etanol dapat mengekstraksi senyawa-senyawa aktif dalam
jumlah kecil yang terdapat dalam sediaan bahan alam (Lersch, 2008).
2.4 Chlorhexidine
Salah satu cara untuk mengobati halitosis adalah menggunakan obat kumur yang bertujuan
untuk mengurangi dental plak dan bakteri yang hidup dalam rongga mulut. Obat kumur yang
biasa digunakan adalah Chlorhexidine gluconate 0,12% yang mengandung: 1.1’-hexamethylene
bis [5-(p-chlorophenyl) biguanide] di-D-gluconate) dalam basis yang mengandung air, alkohol
11,6%, glycerine, PEG-40 sorbitan diisostearate, flavour, sodium saccharine dan FD&C Blue
No.1. Chlorhexidine diproduksi dengan pH antara 5-7 berupa suatu garam chlorhexidine dan
gluconic acid. Struktur kimianya terlihat pada gambar dibawah ini (Kuyyakanond & Quenel,
1992):

Gambar 2.5 Struktur Kimia Chlorhexidine gluconate
2.4.1 Farmakologi chlorhexidine 0,12%
Obat kumur Chlorhexidine mempunyai aktivitas antibakteri selama penggunaannya sebagai
oral rinsing. Kemampuannya untuk mengurangi bakteri baik aerobic maupun anaerobic
mencapai 54 – 97%. Obat kumur ini efektif terhadap bakteri Gram positif dan Grram negatif
meskipun terhadap beberapa bakteri Gram negatif kurang efektif (Shahani & Reddy, 2011).
Mekanisme kerja chlorhexidine dahulu diduga bersifat bakterisid dengan cara menginaktifkan
ATPase bakteri namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa chlorhexidine bersifat
bakterisid kemudian menjadi bakteriostatik dengan cara merusak dinding sel bakteri,
menghambat sistem enzimatik bakteri, mengeluarkan lipopolisakarida bakteri sehingga
menyebabkan kematian sel bakteri (Kuyyakanond & Quenel, 1992; Mandel, 1994).
Penelitian-penelitian terhadap farmakokinetik chlorhexidine gluconate menunjukkan bahwa
30% bahan aktif obat kumur ini akan tetap berada dalam rongga mulut setelah dilakukan kumur-
kumur. Bahan aktif yang tertinggal ini selanjutnya akan dilepaskan perlahan-lahan ke dalam
cairan rongga mulut. Chlorhexidine gluconate sangat sedikit diabsorbsi dalam saluran cerna.
Setelah 30 menit seseorang menelan chlorhexidine gluconate dengan dosis 300 mg maka rata-
rata kadar puncak dalam plasma mencapai 0.206 mikrogram/L dan setelah 12 jam kadar obat
dalam plasma tidak terdeteksi lagi. Kurang lebih 90% chlorhexidine gluconate diekskresi lewat
feses dan sisanya diekskresi lewat urine (Kolahi & Soolari, 2006).
2.4.2 Indikasi penggunaan chlorhexidine 0,12%

Chlorhexidine gluconate diindikasikan sebagai obat kumur untuk mengurangi jumlah
bakteri dalam rongga mulut pada pasien yang menderita gingivitis, periodontitis, dental trauma,
kista rongga mulut dan setelah pencabutan gigi. Obat kumur ini digunakan dua kali sehari
(Kuyyakanond & Quenel, 1992; Kolahi & Soolari, 2006).
2.4.3 Efek samping chlorhexidine 0,12%
Efek samping penggunaan chlorhexidine gluconate sebagai obat kumur telah banyak
dilaporkan. Efek samping yang umum dialami oleh pasien yaitu: 1) terjadinya staining pada
permukaan gigi, restorasi, gigi tiruan dan bagian dorsum lidah. Efek staining ini akan lebih
parah pada pengguna obat kumur yang juga perokok atau punya kebiasaan mengkonsumsi teh
dan kopi; 2) gangguan rasa pengecapan yang bersifat reversibel; 3) ulcerasi dan deskuamasi pada
mukosa; 4) rasa kering dalam mulut; 5) paresthesia; 6) geographic tongue dengan angka
kejadian ± 1% (Menegon et al., 2011; Peterson, 2011) .
BAB III
KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Berpikir
Streptococcus mutans merupakan bakteri Gram positif, bersifat anaerob fakultatif,
merupakan bakteri yang memulai terjadinya pertumbuhan plak pada permukaan gigi. Terjadinya
hal tersebut disebabkan karena kemampuan spesifik dari bakteri tersebut untuk menggunakan
sukrosa untuk menghasilkan suatu produk ekstraseluler yang lengket yang disebut dextran.
Produk ekstraseluler yang lengket tersebut memungkinkan bakteri-bakteri yang lain ikut

menempel pada permukaan gigi membentuk koloni yang terdiri dari berbagai bakteri yang
disebut dengan plak. Bakteri ini juga menghasilkan asam laktat yang berperan penting untuk
merubah lingkungan rongga mulut menjadi lebih asam (pH 5,2 – 5,5) sehingga email mulai
mengalami proses demineralisasi dan terjadilah karies gigi.
Karies mempunyai dampak yang luas apabila tidak dirawat pada tahap awal. Berbagai
komplikasi dapat terjadi misalnya timbul rasa sakit yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan
terjadi abses pada mukosa sekitar gigi. Pada fase lanjut, gigi harus dicabut karena tidak dapat
dipertahankan lagi dan seseorang akan kehilangan giginya sehingga terjadi gangguan fungsi
mastikasi dan estetik. Berdasarkan fakta di atas maka karies harus dirawat dengan baik dan
dicegah agar gigi yang sehat tidak sampai terserang karies. Salah satu cara pencegahannya
adalah menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik yang berasal dari ekstrak tumbuh-
tumbuhan yaitu ekstrak etanol daun beluntas untuk mencegah pertumbuhan dan akulumasi plak.
Daun beluntas merupakan jenis obat tradisional yang banyak dijumpai di Indonesia.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun beluntas mempunyai aktivitas antibakteri
terhadap beberapa bakteri diantaranya adalah Escherichia coli, Psuedomonas aeruginosa multi
resistant dan Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Uji pendahuluan yang telah dilakukan
diketahui bahwa daun beluntas mengandung beberapa zat aktif diantaranya adalah: tannin,
flavonoid, steroid dan fenolat yang berfungsi sebagai antibakteri sehingga apabila digunakan
diharapkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans penyebab karies.

3.2 Konsep Penelitian
Gambar 3.1 Konsep Penelitian
Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%,
75% dan 100% yang mengandung: tannin, steroid,
flavonoid dan fenolat
Faktor Eksternal:
- Lingkungan rongga mulut
- Suhu - media
Faktor Internal:
- Struktur dinding sel yang kompleks
- Kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam rongga mulut
Streptococcus mutans
Pertumbuhan
(Zona hambatan)

3.3 Hipotesis Penelitian
1. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans.
2. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 50% menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans.
3. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 75% menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans.
4. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 100% menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans.

BAB IV
METODE PENELITIAN
4.1. Rancangan Penelitian
Rancangan yang dipilih pada penelitian adalah completely randomized menggunakan post-
test only control group design (Pocock, 2008).
P0 O1
P1
R O2
RA P2
P P3
S O3
O4
P4 O5
P5
O6

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian
Keterangan:
P : Populasi
S : sampel
R : Random
RA : Random Alokasi
P0 : Perlakuan dengan kontrol negatif (Aquades steril)
P1 : Perlakuan dengan kontrol positif (Chlorhexidine 0,12%)
P2 : Perlakuan dengan ekstrak etanol daun beluntas konsentrasi 25%
P3 : Perlakuan dengan ekstrak etanol daun beluntas konsentrasi 50%
P4 : Perlakuan dengan ekstrak etanol daun beluntas konsentrasi 75%
P5 : Perlakukan dengan ekstrak etanol daun beluntas konsentrasi 100%
O1 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P0
O2 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P1
O3 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P2
O4 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P3
O5 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P4
O6 : Daya hambat pertumbuhan bakteri setelah P5
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana Denpasar pada bulan Mei tahun 2012.

4.3 Sampel Penelitian
4.3.1 Sampel penelitian: Bakteri Streptococcus mutans ATCC 35668 yang dibiakkan dalam
plate agar darah
4.3.2 Besar sampel
Besar sampel ditentukan dengan menggunakan rumus besar sampel menurut Frederer
(1977), sebagai berikut: (t-1)(r-1) ≥ 15, dimana t adalah jumlah perlakuan dan r adalah jumlah
pengulangan (replikasi) tiap kelompok perlakuan. Penelitian ini terdiri dari empat kelompok
perlakuan dan dua kelompok kontrol, sehingga t = 6 dan setelah dimasukkan ke dalam rumus
menjadi:
(6-1)(r-1) ≥ 15
(r-1) ≥ 15 : 5
(r-1) ≥ 3
Besar pengulangan (r) ≥ 4
Jadi jumlah pengulangan yang dilakukan adalah sebanyak empat kali untuk tiap kelompok
sehingga jumlah sampel keseluruhan untuk empat kelompok perlakuan dan dua kelompok
kontrol adalah 24 plate, namun untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan maka jumlah sampel akan ditambahkan 25% sehingga jumlah keseluruhan menjadi
30 plate atau 5 kali pengulangan untuk setiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.
4.4 Variabel Penelitian
4.4.1 Variabel bebas: Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan
100%

4.4.2 Variabel tergantung: Diameter zona hambatan bakteri Streptococcus mutans
4.4.3 Variabel kendali:
1. Suhu pengeraman
2. Waktu pengeraman
3. Media pengeraman
4. Jumlah bakteri Streptococcus mutans
Hubungan antar variabel terlihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4.2 Hubungan Antar Variabel
Variabel Bebas
Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% yang mengandung: tannin, steroid, flavonoid dan fenolat
Variabel Tergantung
Diameter zona hambatan bakteri Streptococcus
mutans
Variabel Kendali
Suhu pengeraman Waktu pengeraman Media pengeraman Jumlah bakteri
Streptococcus mutans

4.5 Definisi Operasional Variabel
Variabel-variabel penelitian perlu didefinisikan untuk mendapatkan keseragaman
pengertian. Definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:
1. Ekstrak etanol daun beluntas adalah sediaan pekat yang didapat dengan mengekstraksi zat
aktif daun beluntas menggunakan pelarut etanol 96%. Daun beluntas yang digunakan
adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua dan dipetik saat berbunga. Konsentrasi
ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25%, 50%, 75% dan 100%
2. Diameter zona hambatan bakteri Streptococcus mutans adalah adanya zona bening yang
terbentuk pada difusi disk yang diukur dengan jangka sorong (dalam mm) untuk mengetahui
kekuatan daya hambat ekstrak etanol daun beluntas terhadap pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans. Davis dan Stout (1971), mengatakan bahwa ketentuan daya
antibakteri adalah sebagai berikut: daerah hambatan ≥ 20 mm kategorinya: sangat kuat,
daerah hambatan 10 – 20 mm kategorinya: kuat, daerah hambatan 5 – 10 mm kategorinya:
sedang dan daerah hambatan ≤ 5 mm kategorinya: lemah.
3. Suhu adalah: satuan besaran yang menyatakan derajat panas yang diperlukan untuk
pertumbuhan optimal bakteri Streptococcus mutans yang diukur menggunakan termometer
dengan skala derajat celcius yaitu 370C.

4. Waktu adalah: besaran yang menunjukkan lamanya peristiwa mulai dari masuknya media
pertumbuhan Streptococcus mutans ke dalam inkubator, selama proses inkubasi sampai
dikeluarkannya media dengan satuan jam yaitu antara 18-24 jam menggunakan timer.
5. Media pengeraman adalah: media yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri
Streptococcus mutans yaitu media padat Mueller Hinton ditambah 5% darah kambing yang
tidak mengandung fibrin pada plate agar dengan diameter 10 cm dan ketebalan 4 mm.
6. Jumlah koloni Streptococcus mutans adalah: jumlah bakteri Streptococcus mutans yang
sesuai dengan 108 CFU/ml diperoleh dengan membuat kekeruhan bakteri yang setara
dengan 0,5 Mc Farland dalam larutan NaCl 0,9% dan dilihat dengan spektrofotometer.
4.6 Bahan dan Instrumen Penelitian
4.6.1 Bahan utama
1. Daun beluntas
2. Bakteri Streptococcus mutans ATCC 35668
4.6.2 Bahan penunjang
1. Media isolasi dan numerasi: Media agar Mueller Hinton yang diperkaya dengan 5% darah
kambing yang tidak mengandung fibrin, untuk bakteri Streptococcus mutans
2. Media thioglycollate broth untuk refresh bakteri
3. Etanol 96% untuk ekstraksi daun beluntas
4. NaCl 0,9% untuk membuat kekeruhan
4.6.3 Instrumen penelitian
1. Erlenmeyer untuk pembuatan media

2. Autoclave untuk sterilisasi alat dan media
3. Mikroskop untuk melihat pertumbuhan bakteri
4. Spektrofotometer untuk melihat kekeruhan
5. Mikropipet ukuran 0,1 ml/0,01 ml untuk pembuatan konsentrasi ekstrak
6. Tabung-tabung reaksi untuk tempat media cair, media semi solid, media agar miring untuk
perlakuan
7. Difusi disk untuk melihat zona hambatan
8. Penjepit dan spatula
9. Cawan petri untuk tempat media padat datar atau agar
10. Bahan pengecatan Gram
11. Lampu spiritus
12. Jangka sorong
13. Sarbitol Broth
14. Manitol Broth
15. Voges Proskauer
4.7 Alur Penelitian
Streptococcus mutans
ATCC 35668

Gambar 4.3 Alur Penelitian
4.8 Prosedur Penelitian
4.8.1 Pembuatan ekstrak etanol daun beluntas
Mueller Hinton agar darah 5%
Pembuatan kekeruhan sebanding 108
Random difusi disk
Ekstrak 25%
Chlorhexidine 0,12 %
Ekstrak 100%
Ekstrak 75%
Ekstrak 50%
Aquades steril
Diameter zona hambatan Streptococcus mutans
Tabulasi
Analisis data

Daun beluntas yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari Jalan Tukad Badung,
Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar. Daun yang digunakan
adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua serta dipetik pada saat tumbuhan sedang
berbunga, selanjutnya ditimbang sebanyak 1000 g daun segar, dicuci bersih, diiris halus
kemudian dikering-anginkan selama 3 hari. Daun beluntas dipetik saat berbunga karena pada
masa tersebut akan terbentuk banyak metabolit sekunder yang berguna untuk mempertahankan
diri (Zwenger & Basu (2008). Selanjutnya daun beluntas kering diblender untuk mendapatkan
bubuk daun beluntas. Ekstrak etanol daun beluntas didapatkan dengan cara 100 gram bubuk
kering daun beluntas, dimaserasi (direndam) menggunakan 1 liter pelarut etanol 96% selama 48
jam sambil dilakukan pengocokan agar lebih banyak zat aktif yang terikat oleh pelarut. Pelarut
etanol dipilih karena mudah diuapkan, bersifat polar sehingga dapat melarutkan senyawa-
senyawa yang bersifat polar, dan tidak bersifat toksik (Ginting, 2010). Pelarut etanol juga dipilih
karena dapat melarutkan zat-zat aktif dalam jumlah kecil yang terkandung dalam bahan alam
(Lersch, 2008). Proses ekstraksi yang digunakan adalah proses maserasi atau perendaman
dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh pemanasan yang dapat merusak senyawa aktif, selain
itu dengan proses perendaman akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel sehingga
metabolit sekunder yang berada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan
ekstraksi senyawa aktif akan sempurna karena dapat diatur lamanya perendaman. Setelah 48 jam,
dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring Whatman 2 untuk mendapatkan filtrat.
Perendaman diulang sampai 3 kali untuk mendapatkan semua zat aktif yang terkandung pada
simplisia. Filtrat yang terkumpul selanjutnya diuapkan pelarutnya menggunakan rotary vacuum
evaporatour dan didapatkan ekstrak kasar. Ekstrak kasar yang diperoleh selanjutnya diencerkan
sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan (Pasaribu, 2009).

4.8.2 Pembuatan konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas
Konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 25%,
50%, 75% dan 100% dan untuk mendapatkan konsentrasi tersebut dilakukan dengan cara: 1) 25
g ekstrak kasar, ditambahkan pelarut aquades steril sampai didapatkan volume 100 ml sehingga
didapatkan konsentrasi ekstrak 25%; 2) untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak 50% : 50 g
ekstrak kasar, ditambahkan aquades steril sampai didapatkan volume 100 ml; 3) untuk
konsentrasi 75%: 75 g ekstrak kasar, ditambahkan aquades steril sampai didapatkan volume 100
ml; 4) untuk konsentrasi 100%: 100 g ekstrak kasar ditambahkan aquades steril sampai
didapatkan volume 100 ml (Arief, 2000).
4.8.3 Prosedur kerja di laboratorium
1. Menimbang Mueller Hinton Agar 3,4 gram dalam 100 ml aquades, dilarutkan dan
dimasukkan dalam autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit
2. Diletakkan di waterbath hingga suhu 500C selanjutnya ditambahkan 5% darah kambing
yang tidak mengandung fibrin
3. Dituang pada cawan petri dengan diameter 10 cm dengan ketebalan 4 mm
4. Kemudian 5% dari media Mueller Hinton Agar + 5% darah kambing yang tidak
mengandung fibrin di atas diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam untuk mengetahui
sterilitas media
5. Bila media dalam keadaan steril, bisa langsung digunakan sebagai media penanaman bakteri
Streptococcus mutans
6. Penanaman bakteri Streptococcus mutans pada media di atas, kemudian diinkubasi pada
suhu 370C selama 24 jam

7. Koloni yang tumbuh dilakukan pengecatan Gram dengan prosedur pengecatan sebagai
berikut:
a. Buat olesan tipis suspensi dari koloni murni bakteri pada object glass yang bersih,
dikering-anginkan. Setelah kering difiksasi dengan cara melewatkan bagian bawah object
glass di atas api bunsen 2 kali
b. Genangi olesan bakteri dengan larutan kristal violet selama 1 menit
c. Bilas dengan air keran selama beberapa detik, kering-anginkan
d. Genangi dengan larutan iodine dan biarkan selama 1 menit
e. Bilas dengan air kran selama beberapa detik dan kering-anginkan
f. Bilas dengan alkohol 95% selama 30 detik, kemudian kering-anginkan
g. Bilas dengan air keran selama 2 detik
h. Genangi dengan safranin selama 10 detik, bilas dengan air kran dan kering-anginkan
i. Amati hasil pewarnaan di bawah mikroskop kompon dengan pembesaran 1000x
menggunakan minyak emersi. Sel-sel bakteri Gram positif akan berwarna ungu hingga
biru gelap sedangkan bakteri Gram negatif akan berwarna merah (Anonim, 2008).
8. Identifikasi bakteri dengan uji Streptococcus Grouping Kit:
a. Enzim dipipet 0,4 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi
b. Koloni Streptococcus mutans diambil dengan ose steril, dimasukkan ke dalam tabung
reaksi di atas, kemudian dihomogenkan
c. Diinkubasi dalam inkubator pada suhu 370C selama 15 menit, kemudian dipipet dan
diteteskan pada lubang slide grouping kit masing-masing sebanyak 50 mikron. Satu slide
lagi berfungsi sebagai kontrol positif juga ditetesi sebanyak 50 mikron. Kemudian pada
masing-masing lubang ditetesi dengan serum grouping A (pada lubang 1), serum

grouping B ( pada lubang 2), serum Grouping C (pada lubang 3), serum grouping D
(pada lubang 4), serum Grouping E (pada lubang 5), serum grouping F (pada lubang 6),
dan pada kontrol positif (lubang ke-7).
d. Masing-masing lubang dihomogenkan dengan batang pengaduk kayu dan digoyangkan.
Dari hasil pengamatan apabila terjadi aglutinasi menunjukkan hasil positif. Bila tidak
terjadi aglutinasi berarti hasil ujinya negatif (Lehman et al., 2011).
9. Identifikasi lanjutan dengan uji biokimia yang meliputi:
a. Uji dengan Manitol broth: Ditimbang 2 gram serbuk manitol broth dilarutkan dengan
100 ml aquades kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi dengan volume masing-
masing 5 ml dan sebelumnya pada tabung tersebut sudah berisi tabung Durham dengan
posisi terbalik untuk menangkap gas yang dihasilkan oleh bakteri. Sediaan ini
dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit, selanjutnya
diletakkan di water bath hingga suhu ±500C. Untuk mengetahui sterilitias, media
diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Bila media dalam keadaan steril, bisa
digunakan sebagai media uji bakteri.
b. Uji dengan Sarbitol broth: Ditimbang 2 gram serbuk sarbitol broth dalam 100 ml
aquades, kemudian dituangkan ke dalam tabung reaksi dengan volume masing-masing 5
ml. Kemudian dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit
selanjutnya diletakkan di water bath hingga suhu ± 500C. Untuk mengetahui sterilitas,
media diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Bila media dalam keadaan steril, bisa
digunakan sebagai media uji bakteri.
c. Uji dengan VP (Voges Proskauer): Ditimbang 1,7 gram VP dalam 100 ml aquades
kemudian dituang ke dalam tabung reaksi dengan volume masing-masing 5 ml.

Selanjutnya dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit,
diletakkan di water bath hingga suhu ±500C. Untuk mengetahui sterilitas, media
diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Bila media dalam keadaan steril, bisa
digunakan sebagai media uji bakteri.
Setelah ketiga media uji siap, dilanjutkan dengan memasukkan bakteri uji ke dalam tabung
reaksi menggunakan ose steril, selanjutnya tabung reaksi dimasukkan kembali ke dalam
inkubator pada suhu 370C selama 24 jam. Hasil pengamatan menunjukkan adanya
kekeruhan dan perubahan warna menjadi kuning pada media manitol dan sarbitol sedangkan
pada media VP terjadi kekeruhan yang bila ditambah reagen Kovae berubah menjadi merah
kulit anggur. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa koloni tersebut merupakan bakteri
Streptococcus mutans (Lehman et al., 2011).
10. Pembuatan kekeruhan Streptococcus mutans sebanding dengan 108 CFU/ml: Koloni
Streptococcus mutans dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi NaCl 0,9%, dibuat
kekeruhan sebanding dengan 108 CFU/ml yang setara dengan 0,5 McFarland sehingga dapat
dibaca dengan spektrofotometer
11. Dengan menggunakan lidi kapas steril, isolat Streptococcus mutans dioleskan secara merata
pada media agar Mueller Hinton yang ditambah 5% darah kambing yang tidak mengandung
fibrin (media agar darah) pada cawan petri. Selanjutnya dilakukan uji pendahuluan
menggunakan esktrak etanol daun beluntas yang diencerkan menjadi konsentrasi 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak
yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai aktivitas anti bakteri, selain itu uji
pendahulun berguna untuk menentukan konsentrasi minimal yang dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.

12. Uji lanjutan dilakukan untuk mengetahui ekstrak etanol daun beluntas bersifat bakterisid
atau bateriostatik. Uji ini dilakukan dengan cara difusi disk yang telah mengandung ekstrak
etanol daun beluntas dengan konsentrasi berbeda dan terbukti mempunyai daya hambat
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dipindahkan ke media agar darah steril,
kemudian diinkubasi kembali pada suhu 370C selama 24 jam kemudian dilihat apakah
terdapat pertumbuhan bakteri di sekeliling difusi disk. Konsentrasi ekstrak yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat bakteriostatik apabila di sekeliling difusi disk terjadi
pertumbuhan bakteri tetapi konsentrasi ekstrak bersifat bakterisid apabila di sekeliling
difusi disk tidak terjadi pertumbuhan bakteri (Marsik, 2011).
4.8.4 Penilaian kemampuan ekstrak
Penilaian kemampuan ekstrak etanol daun beluntas terhadap pertumbuhan kultur
Streptococcus mutans dengan mengukur zona bening di sekitar difusi disk dengan menggunakan
jangka sorong secara vertikal, horizontal dan diagonal kemudian dirata-ratakan dalam milimeter
(Pratiwi, 2005).
4.9 Analisis Data
Data dianalisis secara statistik dengan uji deskriptif, uji normalitas data, uji homogenitas
data, uji komparabilitas dan analisis kualitatif. Data hasil penelitian ini diolah dengan
menggunakan program komputer yaitu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for
Windows 17.0. Analisis hasil penelitian meliputi:
4.9.1 Analisis deskriptif
4.9.2 Uji normalitas dan homogenitas

Analisis normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah sampel
≥30. Uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai p>0,05. Analisis
homogenitas data dilakukan dengan uji varians (Levene’s test of varians). Uji varians
menunjukkan bahwa data bersifat homogen dengan nilai p > 0,05.
4.9.3 Uji komparabilitas
Hasil uji normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan
bersifat homogen maka analisis komparatif data antar kelompok dilakukan dengan uji One Way
Anova dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference (LSD) pada tingkat kepercayaan 95%
untuk mengetahui kelompok mana saja yang berbeda bermakna. Berdasarkan pada taraf
kemaknaan α = 0,05 maka Ho ditolak jika nilai p<0,05 (Santoso, 2006).
4.9.4 Analisis kualitatif
Data diameter zona hambatan mula-mula dikelompokkan menjadi empat kategori menurut
(Davis & Stout (1971) yaitu: sangat kuat, kuat, sedang dan lemah. Analisis hubungan antara
konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas dengan kualitas daya hambat menggunakan tabulasi
silang dengan tingkat signifikansi hubungan diuji dengan Chi-Square.
BAB V
HASIL PENELITIAN
5.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana menggunakan ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan
100% untuk mengetahui daya hambatnya terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans

penyebab karies gigi. Mula-mula isolat bakteri dibiakkan terlebih dahulu pada media agar darah
steril (Mueller Hinton agar ditambah 5% darah kambing yang tidak mengandung fibrin) pada
suhu 370C selama 24 jam untuk mendapatkan koloni yang cukup untuk uji daya hambat,
selanjutnya dilakukan uji konfirmasi yang terdiri dari uji Gram, uji dengan Streptococcus
Grouping Kit dan uji biokimia yakni uji dengan sarbitol broth, manitol broth dan Voges
Proskauer.
Hasil uji Gram menunjukkan bahwa isolat bakteri yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bakteri Gram positif, berbentuk bulat (coccus) dan tersusun seperti rantai (foto hasil uji
terlampir). Hasil uji konfirmasi dengan Streptococcus Grouping Kit terlihat adanya aglutinasi
pada lubang ke-4 dan lubang kontrol positif yang menunjukkan bahwa isolat yang digunakan
adalah Streptococcus mutans group D (foto hasil uji terlampir). Hasil uji konfirmasi lanjutan
dengan uji biokimia yaitu uji dengan sarbitol broth, manitol broth dan Voges proskauer
menunjukkan bahwa pada media sarbitol broth dan manitol broth terjadi perubahan warna
menjadi kuning sedangkan Voges proskauer terjadi perubahan warna menjadi merah kulit anggur
setelah ditambahkan reagen Kovae, yang menunjukkan bahwa isolat bakteri yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Streptococcus mutans (foto hasil uji terlampir). Berdasarkan hasil uji
konfirmasi yang telah dilakukan maka diketahui bahwa isolat yang digunakan sebagai sampel
dalam penelitian ini adalah Streptococcus mutans group D, berbentuk bulat (coccus), tersusun
seperti rantai dan bersifat Gram positif.
Uji pendahuluan dilakukan setelah uji konfirmasi dan hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak
etanol daun beluntas dengan konsentrasi 5% - 20% tidak mempunyai daya hambat terhadap
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, sedangkan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100%
menunjukkan adanya daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans,

sehingga untuk uji daya hambat selanjutnya digunakan ekstrak etanol daun beluntas dengan
konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100%.
Uji lanjutan dilakukan untuk menentukan apakah ekstrak etanol daun beluntas bersifat
bakteriostatik ataukah bakterisidal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sekeliling difusi disk
yang mengandung ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50% dan 75% terlihat
adanya pertumbuhan bakteri yang berarti ketiga konsentrasi ekstrak tersebut bersifat
bakteriostatik (bersifat menghambat pertumbuhan bakteri), sedangkan di sekeliling difusi disk
yang mengandung 100% ekstrak tidak terlihat adanya pertumbuhan bakteri yang menunjukkan
bahwa esktrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 100% bersifat bakterisid (bersifat
membunuh bakteri) terhadap bakteri Streptococcus mutans (foto hasil penelitian terlampir).
Replikasi pada penelitian ini dilakukan sebanyak lima kali untuk setiap kelompok kontrol
dan perlakuan sehingga jumlah pengulangan seluruhnya adalah 30 kali. Hasil penelitian
kemudian dikumpulkan, ditabulasi dan dilakukan uji deskriptif dilanjutkan dengan analisis untuk
mengetahui normalitas dan homogenitas data, selanjutnya dilakukan uji komparabilitas data
antar kelompok dengan One Way Anova dilanjutkan dengan uji Least Significant Difference. Uji
kualitatif yaitu chi-square dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi antara konsentrasi
ekstrak etanol daun beluntas dengan kualitas daya hambat terhadap bakteri Streptococcus
mutans.
5.2 Hasil Uji Normalitas Data
Data hasil uji daya hambat kelompok kontrol dan ekstrak etanol daun beluntas dengan
konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% terhadap bakteri Streptococcus mutans selanjutnya

dilakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji menunjukkan bahwa
data berdistribusi normal dengan nilai p>0,05, disajikan pada lampiran 5.
5.3 Hasil Uji Homogenitas Data Antar Kelompok
Data hasil uji daya hambat kelompok kontrol dan ekstrak etanol daun beluntas dengan
konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% terhadap bakteri Streptococcus mutans selanjutnya
dilakukan uji homogenitas menggunakan Levene’s test. Hasil uji menunjukkan bahwa data antar
kelompok bersifat homogen dengan nilai p>0,05, disajikan pada lampiran 5.
5.4 Hasil Uji Komparabilitas Data Antar Kelompok
Uji komparabilitas data antar kelompok bertujuan untuk membandingkan rerata daya
hambat kelompok kontrol dan kelompok ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%,
50%, 75% dan 100% terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kelompok data berdistribusi normal dan bersifat homogen maka analisis
komparabilitas data antara kelompok dilakukan dengan uji One Way Anova dan hasilnya
disajikan pada Tabel 5.1 berikut:
Tabel 5.1 Rerata Daya Hambat Kelompok Kontrol dan Kelompok Ekstrak Etanol Daun
Beluntas dengan Konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans
Kelompok Perlakuan
r (banyaknya replikasi)
Rerata Daya Hambat
(dalam mm)
SB F p
Kontrol negatif 5 0,00 0,00
Kontrol positif 5 11,00 0,707
Kons ekst 25% 5 11,20 1,643 218,82 0,000
Kons ekst 50% 5 14,20 0,836

Kons ekst 75% 5 15,60 1,140
Kons ekst 100% 5 19,20 0,836
Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa rerata daya hambat kelompok kontrol negatif adalah
0,00 ± 0,00 mm, rerata daya hambat kelompok kontrol positif adalah 11,00 ± 0,707 mm, rerata
daya hambat kelompok konsentrasi 25% adalah 11,00 ± 1,643 mm, rerata daya hambat
kelompok konsentrasi 50% adalah 14,20 ± 0,836 mm, rerata daya hambat kelompok konsentrasi
75% adalah 15,60 ± 1,140 mm dan rerata daya hambat kelompok konsentrasi 100% adalah
19,20 ± 0,836 mm. Analisis kemaknaan dengan uji One Way Anova menunjukkan bahwa nilai F
= 218,82 dengan nilai p = 0,000 hal ini berarti bahwa rerata daya hambat antar kelompok
perlakuan berbeda secara bermakna dengan nilai p < 0,05.
Uji lanjutan dengan uji Least Significant Difference perlu dilakukan untuk mengetahui
kelompok konsentrasi ekstrak mana saja yang memiliki perbedaan daya hambat yang nyata
dengan kelompok kontrol terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Hasil uji
disajikan pada Tabel 5.2 di bawah ini:
Tabel 5.2 Analisis Komparasi Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Beluntas Berbagai
Konsentrasi dengan Kelompok Kontrol Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans
Kelompok kontrol
(I) Kelompok
Pembanding (J) Beda Rerata (dalam mm)
(I – J)
p
Kontrol negatif Kontrol positif -11,00 0,000*
Kons ekstrak 25% -11,20 0,000*
Kons ekstrak 50% -14,20 0,000*
Kons ekstrak 75% -15,60 0,000*
Kons ekst 100% -19,20 0,000*
Kontrol positif Kontrol negatif 11,00 0,000*

Kons ekstrak 25% -0,20 0,753
Kons ekstrak 50% -3,20 0,000*
Kons ekstrak 75% -4,60 0,000*
Kons ekst 100% -8,20 0,000*
*Berbeda bermakna
Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa kemampuan daya hambat ekstrak etanol daun
beluntas dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% serta kontrol positif berbeda bermakna
terhadap kontrol negatif dengan nilai p = 0,000 (p<0,05). Dibandingkan dengan kontrol positif,
hanya ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 50%, 75% dan 100% berbeda bermakna
terhadap kontrol positif dengan nilai p = 0,000 (p<0,05), sedangkan konsentrasi 25% tidak
berbeda bermakna terhadap kontrol positif dengan nilai p = 0,753 (p>0,05).
Uji lanjutan dengan Least Significant Difference juga dilakukan untuk mengetahui
perbedaan daya hambat antar kelompok konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas dengan
konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
Hasil uji terlihat pada Tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.3 Analisis Komparasi Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Beluntas pada Berbagai
Konsentrasi Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans
Konsentrasi Ekstrak (I)
Konsentrasi Ekstrak
Pembanding (J)
Beda Rerata (dalam mm)
(I – J)
p
Kons 25% Kons 50% -3,00 0,000*
Kons 75% -4,40 0,000*
Kons 100% -8,00 0,000*
Kons 50% Kons 25%
Kons 75%
3,000
-1,40
0,000*
0,035*
Kons 100% -5,00 0,000*
Kons 75% Kons 25%
Kons 50%
Kons 100%
4,40
1,40
-3,60
0,000*
0,035*
0,000*
Kons 100% Kons 25% 8,00 0,000*
Kons 50% 5,00 0,000*
Kons 75% 3,60 0,000*
*Berbeda bermakna
Berdasarkan tabel 5.3 di atas diketahui bahwa konsentrasi ekstrak 25%, 50%, 75% dan
100% berbeda bermakna antar konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans dengan nilai p<0,05.
5.5 Hasil Uji Kualitatif Terhadap Kualitas Daya Hambat
Untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas dengan
kualitas daya hambat digunakan tabulasi silang dan hasil uji disajikan pada Tabel 5.4 berikut:
Tabel 5.4

Hasil Tabulasi Silang Kualitas Daya Hambat Kelompok Kontrol dan Kelompok Ekstrak Etanol Daun Beluntas dengan Konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100% Terhadap
Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans
Kelompok Kontrol dan Ekstrak
Kriteria Daya Hambat (Menurut Davis & Stout, 1971)
Lemah Sedang Kuat Sangat Kuat
Total
Kontrol negatif 5 0 0 0 5
Kontrol positif 0 0 5 0 5
Kons ekstrak 25% 0 1 4 0 5
Kons ekstrak 50% 0 0 5 0 5
Kons ekstrak 75% 0 0 5 0 5
Kons ekstrak 100% 0 0 3 2 5
Total 5 1 22 2 30
Tabel 5.4 di atas menunjukkan bahwa daya hambat kontrol negatif terhadap pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans tergolong kriteria lemah (lima kali ulangan), daya hambat kontrol
positif, konsentrasi ekstrak 50% dan 75% terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans
tergolong kuat (masing-masing lima kali ulangan), sebagian besar daya hambat konsentrasi 25%
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans tergolong kuat (empat kali ulangan),
sebagian kecil (dua kali ulangan) konsentrasi ekstrak 100% mempunyai daya hambat yang
sangat kuat terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
Tingkat signifikansi hubungan antara kualitas daya hambat dengan kemampuan ekstrak
etanol daun beluntas pada berbagai konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans dilakukan analisis menggunakan Chi-Square dan hasilnya disajikan pada
Tabel 5.5 berikut:
Tabel 5.5 Hubungan Antara Konsentrasi Ekstrak Etanol Daun Beluntas
dengan Kualitas Daya Hambat Terhadap Pertumbuhan Bakteri Streptococcus mutans

Chi-Square hitung df p
Pearson Chi-square 45,273 15 0,000
Likelihood ratio 37,465 15 0,001
Linear-by-linear
Association
15,188 1 0,000
Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p < 0,05) antara
peningkatan konsentrasi ekstrak etanol daun beluntas dengan kualitas daya hambat terhadap
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans.
BAB VI
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil uji pendahuluan, hasil uji daya hambat dan hasil analisis data maka
dibuatlah pembahasan hasil penelitian. Hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa konsentrasi
ekstrak minimal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dalam
penelitian ini adalah 25%. Hasil penelitian pendahuluan ini sesuai dengan hasil penelitian
Susanti (2006), yang menyatakan bahwa konsentrasi daya hambat minimal ekstrak daun
beluntas yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Eschericia coli adalah 25% dan hasil
penelitian Sulistyaningsih (2009), yang menyatakan bahwa konsentrasi daya hambat minimal
ekstrak daun beluntas yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphyloccous aureus yang
resisten terhadap Methicilin adalah konsentrasi 20% sedangkan terhadap bakteri Pseudomonas
aeruginosa Multi Resistant adalah 52%.
Hasil penelitian lanjutan tentang daya bunuh ekstrak terhadap bakteri Streptococcus mutans
diketahui bahwa ekstrak etanol dengan konsentrasi 25%, 50% dan 75% bersifat bakteriostatik
sedangkan yang 100% bersifat bakterisidal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan konsentrasi
ekstrak yang besar yaitu lebih besar dari 75% untuk membunuh bakteri Streptococcus mutans.
Hal ini diduga disebabkan karena bakteri ini mempunyai dinding sel yang kompleks yang terdiri
atas beberapa lapisan peptidoglikan yang kaku dan tebal (Radji, 2010), sehingga diperlukan
konsentrasi ekstrak yang besar untuk membunuh bakteri.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun beluntas dengan konsetrasi 25%
mempunyai kualitas daya hambat setara dengan kontrol positif yaitu chlorhexidine 0,12%
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Chlorhexidine 0,12 % adalah sejenis obat
kumur yang digunakan untuk mengurangi akumulasi plak dalam rongga mulut. Obat kumur ini
mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri baik aerobic maupun
anaerobic mencapai 54-97%. Obat kumur ini efektif terhadap bakteri Gram positif maupun

negatif, meskipun untuk beberapa bakteri Gram negatif kurang efektif (Shahani & Reddy, 2011).
Mekanisme aktivitas antibakteri chlorhexidine 0,12% adalah dengan cara merusak dinding sel
bakteri, menghambat sistem enzimatik dan mengeluarkan lipopolisakarida dari dinding sel
bakteri yang mengakibatkan kematian sel bakteri (Kuyyakanond & Quenel, 1992; Mandel,
1994). Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% dalam penelitian ini mempunyai
kemampuan daya hambat setara dengan chlorhexidine 0,12% maka diharapkan mempunyai
manfaat aktivitas antibakteri yang sama pula dengan chlorhexidine 0,12%. Mengingat
chlorhexidine 0,12% mempunyai beberapa efek samping yang merugikan, maka dengan temuan
dalam hasil penelitian ini diharapkan ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% dapat
digunakan sebagai salah satu alternatif pencegahan yakni sebagai obat kumur antiseptik yang
berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan untuk menghambat pertumbuhan dan akumulasi plak
yang mengandung bakteri Streptococcus mutans. Hal ini sesuai dengan anjuran Lewis & Ismail
(1993), serta Rosenberg (2000), yang mengatakan bahwa untuk mengurangi jumlah plak pada
permukaan gigi dapat digunakan obat kumur yang mengandung antiseptik yang berasal dari
ekstrak tanaman obat. Hasil penelitian ini juga menempatkan ekstrak etanol daun beluntas
sebagai salah satu bahan obat kumur antiseptik dari ekstrak tanaman obat, yang dapat digunakan
untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans selain ekstrak teh hijau hasil
penelitian Carson et al. (2006), dan ekstrak buah pala hasil penelitian Yanti et al. (2008).
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pula, diketahui bahwa ekstrak etanol daun
beluntas dalam berbagai tingkatan konsentrasi mempunyai potensi yang cukup besar dalam
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Hal ini tidak diragukan lagi mengingat
kandungan zat berkhasiat yang terkandung dalam ekstrak etanol daun beluntas yang digunakan
dalam penelitian ini. Hasil uji fitokimia (uji pendahuluan) menunjukkan bahwa ekstrak etanol

daun beluntas yang digunakan dalam penelitian ini mengandung zat aktif fenolat (+++), steroid
(+++), flavonoid (++) dan tannin (+) yang merupakan zat anti mikroba. Hasil uji fitokimia ini
menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun beluntas yang digunakan dalam penelitian ini
mengandung zat aktif steroid dan fenolat dalam jumlah yang sangat banyak, zat aktif flavonoid
dalam jumlah yang banyak serta tannin dalam jumlah lebih sedikit.
Fenolat adalah suatu kelas senyawa hidroksil yang terikat secara langsung pada suatu
kelompok hidrokarbon aromatik. Fenolat juga bersifat asam sehingga disebut juga asam karbolat
yang mempunyai kemampuan untuk merusak dinding sel bakteri sehingga menghambat
pertumbuhan bakteri (Susanti, 2006; Devi, 2011). Steroid adalah suatu senyawa organik yang
terdapat dalam metabolit sekunder merupakan derivat senyawa terpen yaitu triterpenoid yang
mempunyai aktivitas antibakteri diduga dengan cara menyebabkan kebocoran membran sel yang
banyak mengandung lipid yakni pada bagian aqueous (cair) dari phosphatidylethanolamine yang
kaya akan liposome. Kebocoran membran sel akan menyebabkan kematian sel bakteri (Epand et
al., 2007; Mohamed et al., 2010). Flavonoid merupakan suatu substansi fenolik yang
terhidroksilasi, yang mempunyai aktivitas antibakteri yang tidak diragukan lagi terhadap
berbagai macam mikroorganisme (Mohamed et al., 2010). Flavonoid mempunyai aktivitas
antibakteri melalui beberapa mekanisme yaitu: 1) menghambat sintesa dinding sel bakteri; 2)
membentuk ikatan kompleks dengan protein, mengakibatkan kebocoran protein sehingga terjadi
kebocoran dinding sel; 3) menghambat sintesis protein bakteri; dan 4) diduga menginterfensi
fungsi DNA sel bakteri (Hussain et al., 2010; Mohamed et al., 2010). Tannin menunjukkan
aktivitas antibakterinya dengan cara berikatan dengan proline yang kaya akan protein
membentuk suatu kompleks, menyebabkan protein leakage sehingga terjadi kerusakan dinding

sel bakteri dan mengakibatkan kematian bakteri (Machado et al., 2003; Braga et al., 2005;
Mohamed et al., 2010).
Mekanisme aktivitas antibakteri sesungguhnya dari metabolit sekunder yang terkandung
dalam ekstrak etanol daun beluntas yang digunakan dalam penelitian ini tidak diketahui dengan
pasti, namun berdasarkan kandungan zat aktif di dalamnya dapat diduga bahwa fenolat, steroid,
flavonoid dan tannin bekerja secara sinergis dalam menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian para peneliti pendahulu
yang menggunakan ekstrak yang sama untuk menguji daya hambat ekstrak terhadap
pertumbuhan bakteri Eschericia coli (Susanti, 2006), selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh
Nahak, et al. (2007), yang mendapatkan bahwa ekstrak daun beluntas dapat menurunkan 70%
bakteri dalam saliva, demikian pula hasil penelitian Sulistiyaningsih (2009), yang menggunakan
ekstrak yang sama untuk menguji daya hambatnya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa
Multi Resistant dan Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, sehingga tidak diragukan lagi
kemampuan daya hambat ekstrak etanol daun beluntas terhadap berbagai bakteri patogen pada
manusia khususnya Streptococcus mutans sebagai bakteri yang bersifat kariogenik dan bakteri
pemula dalam pembentukan lapisan biofilm pada plak gigi.
Penelitian ini masih mempunyai beberapa kekurangan yaitu dalam penelitian ini belum
dapat ditentukan konsentrasi daya hambat minimal (MIC) dan Minimal Bactericidal
Concentration (MBC) sesungguhnya dari ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans, demikian juga mekanisme kerja kandungan zat-zat aktif yang terdapat di
dalam ekstrak etanol daun beluntas yang digunakan dalam penelitian inipun belum diketahui
dengan pasti, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menentukan MIC dan MBC serta
mekanisme aktivitas anti bakteri dari ekstrak etanol daun beluntas.

BAB VII
SIMPULAN DAN SARAN
7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian uji daya hambat ekstrak etanol daun beluntas terhadap
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dan pembahasan hasil penelitian didapat simpulan
sebagai berikut:
1. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25% dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans
2. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 50% dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans
3. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 75% dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans
4. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 100% dapat menghambat pertumbuhan
bakteri Streptococcus mutans
5. Konsentrasi minimal dari ekstrak etanol daun beluntas dalam penelitian ini yang dapat
menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans adalah 25%
6. Ekstrak etanol daun beluntas dengan konsentrasi 25%, 50% dan 75% bersifat
bakteriostatik sedangkan 100% bersifat bakterisid.
7.2 Saran
Sebagai saran dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan Minimal Inhibitory
Concentration (MIC) Minimal Bactericidal Concentration (MBC) dari ekstrak etanol
daun beluntas terhadap bakteri Streptococcus mutans.

2. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui mekanisme kerja
sesungguhnya dari zat-zat aktif yang terkandung dalam metabolit sekunder ekstrak
etanol daun beluntas sebagai antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans.
3. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan menggunakan ekstrak daun beluntas yang
sudah siap pakai misalnya dalam bentuk pasta gigi atau obat kumur untuk mengetahui
daya hambat esktrak etanol daun beluntas terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus
mutans secara invivo maupun secara klinis.
4. Disarankan kepada masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan kesehatan gigi untuk
memanfaatkan ekstrak daun beluntas untuk berkumur-kumur, sebagai salah satu
alternatif pencegahan terhadap pembentukan dan akumulasi plak dalam rongga mulut.
DAFTAR PUSTAKA
Ajaikumar, K.B., Asheef, M., Babu, B.H., & Padikkala, J. 2005. The Inhibition of Gastric Mucosal Injury by Punica granatum L., (Pomegranate) Methanolic Extract. Journal of Ethnopharmacology. 96: 171-176
Anonim, 1982. FDI/WHO. Global Goals for Oral Health in the Year 2000. Int Dent J. 32: 74-7 Anonim, 2005. Survei Kesehatan Nasional. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2004.
Departemen Kesehatan RI. Jakarta: Badan Litbangkes. 3:18-20

Anonim, 2008. Pedoman Diagnosis OPTK Golongan Bakteri. Departemen Pertanian. Badan Karantina Pertanian. Jakarta. p. 20-21
Anonim, 2010. Pluchea indica (Beluntas). Artikel. (Serial Online) (Citted 2011 Des 22).
Available at: http://tnalaspurwo.org/media/pdf/kea-beluntas-(pluchea-indica).pdf Anonim, 2011. Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 dalam Bidang Kesehatan Gigi dan
Mulut. Sambutan Menteri Kesehatan RI pada Pembukaan Kongres XXIV PDGI Bali, 30-31 Maret 2011. (Serial Online) (Cited 2012 Mei 1). Available at: http://www.pdgi.or.id/artikel/ detail/sambutan-menteri-kesehatan-pada-pembukaan-kongres-xxiv-pdgi-bali-30-31-maret-2011
Argimõn, S., & Caufiled, P.W. 2011. Distribution of Putative Virulence genes in Streptococcus
mutans Strain does not Correlate with Caries Experience. Journal of Clinical Microbiology. 49(3): 984-92
Arief. 2000. Ilmu Meracik Obat. Teori dan Praktek. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
p. 25 Bailey, D.G., & Dresser, G.K. 2004. Interaction Between Grapefruit Juice and Cardivasculer
Drugs. Am.J. Cardiovasc Drugs. 4(5): 281-297 Beltràn-Valladares, P.R., Cocom-Tun, H., Cassanova-Rosado, J.F., Vallejos-Sànches, A.A.,
Medina-Solis, C.E., & Maupome, G. 2006. Caries Prevalence and Some Asscotiated Factors in 6-9 Years old Schoolchildren in Campeche, Mexico. Original Article. Rev. Biomed.17:25-33
Biswas, S., & Biswas, I. 2011. Role of VitAB, an ABC Transporter Complex in Viologen
Tolerance in Streptococcus mutans. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 55(4): 1460-9
Braga, L.C., Shupp, J.W., Cummings, C., Jett, M., Takahashi, J.A., Carmo, L.S., Chartone-
Souza, E., & Nasclmento, A.M.A. 2005. Pomegranate Extract Inhibits Staphylococcus aureus Growth and Subsequent Enterotoxin Production. Journal of Ethnopharmacology. 96 : 335-339
Carson, C.F., Hammer, K.A., & Riley, T.V. 2006. Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil: A
Review of Antimicrobial and Other Medicine Properties. Clinical Microbiology Review. 19(1): 50-62
Clarke, J.K. 1924. On the Bacterial Factor in the Etiology of Dental Caries. British Journal of
Experimental Pathology. 5: 141-7 Cushnie, T.P.T., & Lamb, A.J. 2011. Recent Advances in Understanding the Antibacterial
Properties of Flavonoids. International Journal of Antimicrobial Agents. 38(2): 99-107

Dalimartha, S. 1999, Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, Jilid I. Jakarta:Trubus Agriwidya. p. 18-21
Dalimartha, S. 2005. Tanaman Obat di Lingkungan Sekitar. Jakarta: Pusoa Swara. p. 5
Davis, W.W., & Stout, T.R. 1971. Disc Plate Methods of Microbiologycal Antibiotic Assay. Microbiology. 22: 659-665
Devi, A.P. 2011. Korelasi Kadar Fenolat Daun Dendrophthoe petandra, Dendrophthoe falcata, dan Scurrula philippensis Terhadap Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH. Skripsi. Univerversitas Muhammadiyah. Surakarta. p. 1-15
Dewi, F.K. 2010. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Mengkudu (Morinda citrofolia, Linnaeus)
Terhadap Bakteri Pembusuk Daging Segar. Surakarta: Jurusan Biologi MIPA Universitas Sebelas Maret. p. 7-8
Eccles, J.D., & Green, R.M. 1994. Konservasi Gigi. Jakarta: Widya Medika. p. 1-23 Epand, R.F., Savage, P.B., & Epand, R.M. 2007. Bacterial Lipid Composition and the
Antimicrobial Efficacy of Cationoc Steroid Compounds (Ceragenins). Biochimica et Biophysica Acta. 1768(10): 2500-9
Ferdian, A. 2010. Analisa Zat Berkhasiat Beluntas. Artikel Kimia. (Serial Online) (Cited 2010 Nov 12). Available from: http://kimia.unp.ac.id/?p=1186
Frederer, W.T. 1977. Experimental Design Theory and Application. 3rd Edition. New Delhi, Bombay Calcuta. Oxford and IBH Publishing.Co. p. 544
Freedman, J.E., Parker, C., & Li, L. 2001. Select Flavonoids and Whole Juice from Purple Grapes Inhibit Plate Function and Enhance Nitric Oxide Release. Circulation. 103(23): 2792-2798
Frei, B., & Higdon, J.V. 2003. Antioxidant Activity of Tea Polyphenols in vivo: Evidence from Animal Studies. J. Nutr. 133(10): 3275S-3284S
Ginting, A.M., 2010. Pemanfaatan Matriks Nata de Coco Terhadap Ekstrak Etanol Daun Dandang Gendis. (Serial Online) (Cited 2011 August 16). Available from: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19967/4/chapter%20II.pdf
Haidari, M., Ali, M., Casscells, S.W., & Madjid, M. 2009. Pomegranate (Punica granatum) Purified Polyphenol Extract Inhibits Influenza Virus and has a Synergistic Effect with Oseltamivir. Phytomedicine. 16: 1127-1136
Harborne, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. (Padmawinata, K., Soediro, I., Pentj). Jilid II. Bandung: Institut Teknologi Bandung. p.4-5.
Hashizume, L.N., Shinada, K., & Kawaguchi, Y. 2006. Dental Caries Prevalence in Brazilian Schoolchildren Resident in Japan. Journal of Oral Science. 48(2): 51-57

Hassanpour, S., Maheri-Sis, N., Eshratkhah, B., & Mehmandar, F.B.. 2011. Plants and Secondary Metabolites (Tannins): A Review. Int. J. Forest, Soil and Erosion. 1 (1):47-53
Higdon, J., Drake, V.J., & Dashwood, R.H. 2008. Flavonoids. Reviewed Article. Linus Pauling Institute, Oregon State University. (Serial Online). (Cited 2011 July 27). Available from: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/phytochemicals/flavonoids/
Hou, Z., Lambert, J.D., Chin, K.V., & Yang, C.S., 2004. Effects of Tea Polyphenols on Signals Transduction Pathways Related to Cancer Chemoprevention. Mutat Res. 555(1-2): 3-19
Hussain, A., Wahab, S., Zarin, I., & Sarfaraj Hussain, M.D. 2010. Antibacterial Activity of the Leaves of Cocconia indica (W. and A) Wof India. Advances in Biological Research. 4(5): 241-248
Islam, A.K., Ali, M.A., Sayeed, A., Salam, S.M., Islam, A., Rahman, M., Khan, G.R., & Khatun, S. 2003. An Antimicrobial Terpenoid from Caesalpinia pulcerrima Swartz: Its Characterization, Antimcrobial and Cytotoxic Activities. Asian J Plant Sci. 2: 17-24
John, A.J., Kanurakran, V.P., & George, V. 2007. Antibacterial Activity of Neolitsea foliosa (Nees) Gamlbe var. caesia (Meisner). J.Essent.Oil. Res. 19:498-500
Joiston-Bechal, S., & Hernaman, N. 1993. The Effect of Mouthrinse Containing Chlorhexidine and Fluoride on Plaque and Gingival Bleeding. Journal of Oral Medicine and Periodontology; 20(1): 49-5
Kidd, E.A.M., & Joiston-Bechal, S. 1992. Dasar-Dasar Penyakit Karies dan Penanggulangannya. Jakarta: EGC. p. 1-18
Kojima, A., Nakano, K., Wada, K., Takahashi, H., Katayama, K., Yoneda, M., Higurashi, T., Nomura, R., Hokamura, K., Muranaka, Y., & Matshusashi, N., et al., 2012. Infection of Specific Strains os Streptococcus mutans, Oral Bacteria, Confers a Risk of Ulcerative Colitis. Scientific Report 2. Article. 332: 1-22
Kolahi, J., & Soolati, A. 2006. Rinsing with Chlorhexidine Gluconate Solution after Brushing and Flossing Teeth: a Systematic Review of Effectiveness. Quintessence Int. 37(8): 605-12
Koloway, B., & Kailis, D.G. 1992. Caries, Gingivitis and Oral Hygiene in Urban and Rural Pre-school Children in Indonesia. Community Dent Oral Epidemiol. 20: 157-158
Kustiawan, W. 2002. Lubang Gigi (Karies) dan Perawatannya. Artikel. (Serial Online) (Cited 2005 Oktober 25). Available from: http://www. pikiranrakyat.com
Kuyyakanond, T., & Quenel, L.B. 1992. The Mechanism of Action of Chlorhexidine. FEMS Microbiol Lett. 79(1-3): 211-215
Lambert, J.D., & Yang, C.S. 2003. Mechanism of Cancer Prevention by Tea Constituents. J Nutr. 133(10): 3262S-3267S

Lehman, D.C., Mahon, C.R., & Suvarna, K. 2011. Streptococcus, Enterococcus, and Other Catalase-Negative Gram-Positive Cocci. Dalam: Textbook of Diagnostic Microbiology (Edited by: Mahon, C.R., Lehman, D.C., Manuselis, G.), 4th Edition. W.B. Saunders Company. p.330-348
Lei, F., Zhang, X.N., Wang, W., Xing, D.M., Xie, W.D., Su, H., & Du, L.J. 2007. Evidence of Anti-Obesity Effects of the Pomegranate Leaf Extract in High Fat Diet Induce Obese Mice. International Journal of Obesity. 31: 1023-1029
Lenny, S. 2006. Senyawa Flavonoida, Fenilpropanoida dan Alkaloida. Karya Ilmiah. (Serial Online) (Cited 2011, Juli 27). Available from: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1842/06003489.pdf
Lersch, M. 2008. Wonders of Extractions: Ethanol. Article. (Serial Online) (Cited 2011 Des 28). Available from: http://blog.khymos.org/2008/06/08/wonders-of-extractions-ethanol/
Lewis, D.W., & Ismail, A.I. 1993. Dental Caries, Diagnosis, Risk Factors and Prevention. Can Med Assoc J. p.408-417
Machado, T.B., Pinto, A.V., Pinto, M.C.F.R., Leal, I.C.R., Silva, M.G., Amaral, A.C.F., Kuster, R.M., & Netto-dos Santoz, K.R. 2003. In vitro Activity of Brazilian Medicinal Plants, Naturally Occuring Naphtoquinones and Their Analogues Against Methicilline Resistant Staphyloccoccus aureus. International Journal of Antimicrobial Agents. 21: 279-284
Manach, C., Scalbert, A., Morand, C., Remesy, C., & Jimenez, L. 2004. Polyphenols: Food Sources and Bioavailability. Am J Clin Nutr. 79(5): 727-74
Manach, C., Williamson, G., Morand, C., Scalbert, A., & Remesy, C. 2005. Bioavailability and Bioefficacy of Polyphenols in Humans. I. Review of 97 Bioavailability Studies. Am J Clin Nutr. 81(1 Suppl): 230S-242S
Mandel, I.D. 1994. Antimicrobial Mouth Rinses: Overview & Update. J Am Dent Assoc. 125(25): 2S -10S
Marsik, F.J. 2011. Special Antimicrobial Susceptibility Tests. Dalam: Textbook of Diagnostic Microbiology (Edited by: Mahon, C.R., Lehman, D.C., Manuselis, G.), 4th Edition. W.B. Saunders Company. p.308-310
Marzolini, C., Paus, E., Buclin, T., & Kim, R.B. 2004. Polymorphisms in Human MDR1 (P-Glycoprotein): Recent Advances and Clinical Relevances. Clin Pharmacol Ther. 75(1): 13-33
Menegon, R.F., Blau, L., Janzantti, N.S., Pizzolitto, A.C., Corrêa, M.A., Monteriro, M., & Chung, M.C. 2011. A Nonstaining and Tasteless Hydrophobic Salt of Chlorhexidine. Article. (Serial Online) (Cited 2011 August 8). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21344413

Menendez, A., Li, F., Michalek, S., Kirk, K., Makhija, S.K., & Childers, N.K. 2005. Comparative Analysis of the Antibacterial Effects of Combined Mouthrinses on Streptococcus mutans. Journal of Oral Microbiology and Immunology; 20(1): 31
Mohamed, S.S.H., Hansi, P.D., & Thirumurugan, K. 2010. Antimicrobial Activity and
Phytochemical Analysis of Selected Indian Folk Medicinal Plants. International Journal of Pharma Sciences and Research (IJPSR). 1(10): 430-434
Moses, J., Rangeeth, B.N., & Gurunathan, D. 2011. Prevalence of Dental Caries, Socio-
Economic Status and Treatment Needs Among 5 to 15 Year Old School Going Children of Chidambaram. Journal of Clinic and Diagnostic Research. 5(1): 146-151
Murphy, K.J., Chronopoulos, A.K., & Singh, I. 2003. Dietary Flavanols and Procyanidine
Oligomers from Cocoa (Theobroma cacao) Inhibit Platelet Fungction. Am J Clin Nutr. 77(6): 1466-1473
Murthy, K.N.C., Reddy, K.V., Veigas, & J.M. 2004. Study on Wound Healing Activity of Punica
granatum Peel. Journal of Medicinal Food. 7: 256-259
Nahak, M.M., Tedjasulaksana, R., & Dharmawati, I.G.G.A. 2007. Khasiat Ekstrak Daun Beluntas untuk Menurunkan Jumlah Bakteri pada Saliva. Interdental Jurnal Kedokteran gigi, Denpasar. 5(3): 139-142
Nakano, K., Ianaba, H., Nomura, R., Nemoto, H., Takeda, M., Yoshioka, H., Matsue, H., & Takahashi, T. 2006. Detection of Cariogenic Streptococcus mutans in Extirpated Heart Valve and Atheromatous Plaque Specimens. Journal of Clinical Microbiology. 44(9): 3313-7
Parmar, G., Kaur, J., Varghese, C., & Rajan, K. 2007. Management of Dental Caries in Selected Rural Areas of Gujarat Through Atraumatic Restorative Technique (ART). Report. Gol-WHO Collaboration Program (2006-07). Govenrment Dental college and Hospital, Ahmedabad – 380 016, India. p.10.
Pasaribu, S.P. 2009. Uji Bioaktivitas Metabolit Sekunder dari Daun Tumbuhan Babadotan (Ageratum conyzoides L.). Jurnal Kimia Mulawarman. 6(2): 1-7
Patra, A.K., & Saxena, J. 2010. Exploitation of Dietary Tannins to Improve Rumen Metabolism and Ruminant Nutrition. J Sci Food Agric. 91: 24-37
Peterson, D. 2011. Family Gentle Dental Care. Article. (Serial Online). (cited 2011, Agustus 8). Available from: http://www.dentalgentlecare.com/periguard.htm
Pocock, S.J. 2008. Clinical Trials. A Practical Approach. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex-
England. p. 50-87 Prabuseenivasan, S., Jayakumar, M., & Ignacimuthu, S. 2006. In vitro Antibacterial Activity of
Some Plant Essential Oils. BMC Complement. Altern. Med. 6:39

Praptiwi, Chairul, & Harapini, M. 2006. Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Buah Makasar (Brucea javanica L.Merr.) terhadap Plasmodium berghei Secara in-vivo pada Mencit. Laporan Penelitian. Bidang Botani, Puslit Biologi-LIPI, Bogor. p. 1-6
Pratiwi, P. 2005. Perbedaan Daya Hambat Terhadap Streptokokus mutans dari Beberapa Pasta Gigi yang Mengandung Herbal. Majalah Kedokteran Gigi. 38(2): 64-67
Putra, S.E. 2007. Alkaloid: Senyawa Organik Terbanyak di Alam. Artikel Kimia. (Serial Online) (Cited 2011 Des 29). Available from: http://www.chem-is-try.org/artikel_kimia/biokimia/alkaloid-senyawa-organik-terbanyak-dialam
Rahayu, S.S. 2009. Ekstrasi. Artikel Kimia. (Serial Online) (Cited 2011 Agustus 16). Available from: http://www.chem-is-try.org/materikimia/kimia-industri/teknologi-proses/ekstraksi/
Radji, M. 2010. Buku Ajar Mikrobiologi. Panduan Mahasiswa Farmasi dan Kedokteran. Jakarta: EGC. p. 11-15
Ritter, A.V. 2004. Dental Caries. Talking with Patients. Article. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry. p. 76
Rosenberg, J.D. 2010. Dental Cavities. Article. (Serial Online) (Cited 2012 April 29). Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/ article/oo1055.htm
Rustaman, Abdurahman, H.M., & Al-Anshori, J. 2006. Skrining Fitokimia Tumbuhan di Kawasan Gunung Kuda Kabupaten Bandung sebagai Penelahaan Keanekaragaman Hayati. Laporan Penelitian. FMIPA. Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. p. 10-13
Sardjono, H., Santoso, O., & Dewoto, H.R. 2004. Analgesik Opioid dan Antagonis. Dalam:
Farmakologi dan Terapi. Edisi ke-4 Cetak Ulang. Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta: Gaya Baru. p. 189-206
Santoso, S. 2006. Menguasai Statistik di Era Informasi dengan SPSS 14. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. p. 214-223
Schultz, 2011. Secondary Metabolites in Plants. Article. (Serial Online). (Cited 2011 Desember 22). Available from: http://www.biologyreference.com/Re-Se/Secondary-Metabolites-in-Plants.html
Serafini, M., Ghiseli, A., & Ferro-Luzzi, A., 1996. In vivo Antioxidant Effect of Green Tea and
Black Tea in Man. Eur J Clin Nutr. 50(1): 28-32 Seymour, R.A., & Heasman, P.A. 1995. Pharmacological Control of Periodontal Disease. J.
Dent; 23(1): 5-14

Shahani, M.N., & Reddy, V.V.S. 2011. Comparison of Antimicrobial Substantivity of Root Canal Irrigants in Instrumented Root Canals up to 72 Hours: An Invitro Study. Journal of Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. 29: 28-33
Sondang, P., & Hamada, T. 2008. Menuju Gigi & Mulut Sehat: Pencegahan dan Pemeliharaan.
USU Press: 44-56 Song, J., Kwon, O., & Chen, S. 2002. Flavonoids Inhibition of Sodium-Dependent –Vitamin C
Transporter 1 (SCVT 1) and Glucose Transporter Isoform 2 (GLUT 2), Intestinal Transporters for Vitamin C and Glucose. J Biol Chem. 277 (18): 15252-15260
Spencer, & Jeremy, P.E. 2008. Flavonoids: Modulators of Brain Function. British Journal of
Nutrition. 99: ES60-77 Spencer, J.P., Rice-Evans, C., & William, R.J., 2003. Modulation of pro-Survival Akt/Protein
Kinase B and ERK ½ Signaling Cascade by Quercetin and its in vivo Metabolites Underlie Their Action on Neoronal Viability. J Biol Chem. 278(37): 34783-34793
Sulistyaningsih, Rr. 2009. Potensi Daun Beluntas (Pluchea indica Less) Sebagai Inhibitor
Terhadap Pseudomonas aeruginosa Multi Resistant dan Methicilline Resistant staphylococcus aureus. Laporan Penelitian Mandiri. Fakultas Farmasi Univ. Padjadjaran Bandung. p. 34-35
Susanti, A. 2006. Daya Anti Bakteri Ekstrak Etanol Daun Beluntas (Pluchea indica. Less)
Terhadap Escherichia coli Secara in vitro. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Surabaya. p. 1-2
Tarigan, R., 1990. Karies Gigi. Jakarta: Hipocrates. p. 17-24
Vinogradov, A.M., Winston, M., Rupp, C.J., & Stoodley, P. 2004. Rheology of Biofilms Formed from the Dental Plaque Pathogen Streptococcus mutans. Biofilm 1: 49-56
Wang, R., Ding, Y., Liu, R., Xiang, L., & Du, L. 2010. Pomegranate: Constituents, Bioactivities and Pharmacokinetics. Global Science Books. 4(2): 77-87
Williamson, G. 2004. Common Features in the Pathways of Absorbtion and Metabolism of Flavonoids. Boca Raton. CRC Press: 21-33
William, R.J., Spencer, J.P., & Rice-Evans, C. 2004. Flavonoids: Antioxidants or Signaling Molecules? Free Radic Biol Med. 36(7): 838-849
Yanti, Rukayadi, Y., Kim, K.H., & Hwang, J.K. 2008. In vitro Anti-biofilm Activity of Macelignan Isolated from Myristica fragrans Houtt Against Oral Primary Colonizer Bacteria. Phytotherapy Research. 22(3): 308-12
Zwenger, S., & Basu, C. 2008. Plant Terpenoids: Applications and Future Potentials. Biotechnology and Molecular Biology Reviews. 3(1): 1-7

Lampiran 2
HASIL PENGUKURAN ZONA HAMBATAN KELOMPOK KONTROL DAN EKSTRAK ETANOL DAUN BELUNTAS TERHADAP BAKTERI
Streptococcus mutans
REPLIKASI
HASIL PENGUKURAN ZONA HAMBATAN (dalam mm)
KONTROL NEGATIF
KONTROL POSITIF
KONS EKSTRAK
25%
KONS EKSTRAK
50%
KONS EKSTRAK
75%
KONS EKSTRAK
100%
I
0,0 10,0 12,0 15,0 14,0 20,0
II
0,0 11,0 9,0 14,0 17,0 18,0
III
0,0 12,0 12,0 14,0 16,0 20,0
IV
0,0 11,0 10,0 15,0 16,0 19,0
V
0,0 11,0 13,0 13,0 15,0 19,0

Lampiran 3
KRITERIA ZONA HAMBATAN MENURUT DAVIS DAN STOUT (1971)
REPLIKA SI
HASIL PENGUKURAN ZONA HAMBATAN (dalam mm)
K (-) Krt K(+) Krt 25% Krt 50% Krt 75% Krt 100% Krt
I 0,0 L 10,0 K 12,0 K 15,0 K 14,0 K 20,0 SK
II 0,0 L 11,0 K 9,0 SD 14,0 K 17,0 K 18,0 K
III 0,0 L 12,0 K 12,0 K 14,0 K 16,0 K 20,0 SK
IV 0,0 L 11,0 K 10,0 K 15,0 K 16,0 K 19,0 K
V 0,0 L 11,0 K 13,0 K 13,0 K 15,0 K 19,0 K
Ket:
K(-) : Kontrol negatif
K(+) : Kontrol positif
Krt : Kriteria Zona Hambatan
25% : Konsentrasi esktrak daun beluntas 25%
50% : Konsentrasi esktrak daun beluntas 50%
75% : Konsentrasi esktrak daun beluntas 75%
100% : Konsentrasi esktrak daun beluntas 100%
L : Lemah
SD : Sedang
K : Kuat
SK : Sangat Kuat

Lampiran 10
Persiapan bahan untuk uji dengan Streptococcus Grouping Kit

Hasil Uji Gram: bakteri Gram (+) berbentuk coccus tersusun seperti rantai



\
Mengulaskan biakan bakteri S. mutans pada media agar darah steril


Pengukuran zona hambatan menggunakan jangka sorong

Hasil Uji Daya Hambat Kelompok Ekstrak dan Kelompok Kontrol
2 1
3
4
5 6
Di sekeliling disk dengan Konsentrasi ekstrak 25% (1), 50% (2), 75% (3) terdapat pertumbuhan bakteri sedangkan disk 4 (kons. Ekstrak 100%) tidak terdapat pertumbuhan
bakteri