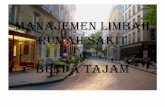makalah limbah RS
-
Upload
yanny-jasmiunnes -
Category
Documents
-
view
509 -
download
0
Transcript of makalah limbah RS
MAKALAH TUGAS BIOLOGI TERAPAN MIKROBIA SEBAGAI AGEN PENURUN FOSFAT PADA PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT
Di susun oleh :
M. Samsul Nizar ( 4401409018 ) Yusuf Anggar S ( 4401409056 )
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011
PENDAHULUAN Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang memiliki kegiatan pokok dalam pelayanan preventif, kuratif, rehabilitasi dan promosi. Kegiatan tersebut akan menimbukan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak positif rumah sakit diantaranya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya diantaranya adalah limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit. Salah satu instansi yang cukup banyak menghasilkan limbah adalah rumah sakit. Limbah yang dihasilkan rumah sakit berupa limbah padat maupun cair, mulai dari yang kurang berbahaya hingga yang berbahaya. Limbah dari rumah sakit dapat berupa limbah patologis (misalnya jaringan tubuh, darah dan organ tubuh), limbah radioaktif, limbah farmasetikal dan limbah kimiawi. Limbah tersebut dapat dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya. Sementara limbah yang berbahaya misalnya adalah limbah dari dapur, kertas, jarum, gelas dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah sakit mempunyai karakteristik limbah yang berbeda dengan limbah rumah tangga atau industri. Banyaknya rumah sakit atau lembaga medis di masyarakat, tentunya akan menimbulkan dampak banyaknya pula limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit atau lembaga medis tersebut. Pengolahan limbah rumah sakit memerlukan perlakuan tertentu, mengingat jenisnya yang bermacam-macam dan tingkat bahayanya bagi lingkungan maupun orang yang mengalami kontak dengan limbah tersebut. Diantara limbah yang memerlukan pengolahan adalah limbah cair dari rumah sakit. Limbah cair ini dapat berasal dari limbah cair dari laboratorium, dapur, pembuangan kamar mandi, limbah dari cairan untuk pembersih di rumah sakit, perawatan bangunan maupun dari disinfektan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Departemen Kesehatan DIY serta hasil survei di beberapa lokasi, diketahui bahwa beberapa rumah sakit telah mengoperasikan instalasi pengolahan limbah cair (IPAL), namun banyak juga rumah sakit atau lembaga medis yang belum memiliki IPAL. Rumah sakit yang belum memiliki IPAL akan membuang limbah cairnya ke sistem perairan umum dengan perlakuan minimal atau justru tanpa perlakuan. Sementara rumah sakit yang telah memiliki IPAL juga belum menghasilkan effluent yang memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58 Tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Parameter yang belum sesuai dengan baku mutu diantaranya adalah NH3 bebas dan PO4. Adanya pengolahan limbah yang kurang sempurna tersebut dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan dan akan membawa dampak berbahaya bagi lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan usaha untuk menurunkan kadar fosfat pada pengolahan limbah rumah sakit. Salah satu usaha yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan pengolahan limbah cair secara biologi. Menurut Wagner (2007), identifikasi mikrobia yang bertanggung jawab dalam penurunan nitrogen dan fosfor dalam instalasi pengolahan limbah dipandang penting dan perlu dilakukan. Hal tersebut berkaitan dengan pentingnya memahami hubungan antara diversitas suatu kelompok bakteri dengan fungsi tertentu yang penting, dengan stabilitas proses yang dikatalisis. Menurut Chandra (1999), limbah rumah sakit adalah bahan sisa yang tidak digunakan lebih lanjut untuk keperluan rumah sakit. Berdasarkan laporan WHO, negara dengan penghasilan tinggi mampu menghasilkan limbah berbahaya hingga 6 kg/orang/tahun. Pada kebanyakan negara dengan penghasian rendah, limbah dari perawatan kesehatan tidak dipisahkan antara yang berbahaya atau tidak berbahaya, dan total limbah yang dihasilkan antara 0,5-3 kg/orang/tahun.
Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit tentunya bukan jenis limbah yang umum ada dalam masyarakat maupun industri. Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit lebih kompleks dan dapat merupakan perpaduan antara limbah industri, rumah tangga dan limbah infeksius. Hampir 80% dari total limbah yang dihasilkan dari aktivitas perawatan kesehatan merupakan limbah umum yang mirip dengan limbah domestik. Sisanya sebanyak kurang lebih 20% merupakan bahan yang berbahaya yang kemungkinan bersifat infeksius, toksik atau radioaktif. Mayoritas limbah yang berbahaya berupa limbah infeksius dan anatomik (hingga 15% dari total limbah), limbah tajam sebanyak 1%, bahan kimia dan farmasetikal sejumlah 3% dan limbah genotoksik, radioaktif serta logam berat sekitar 1%. Sedangkan Yadav (2001) menyebutkan bahwa sekitar 85% limbah rumah sakit bersifat tidak berbahaya, 10% berupa bahan yang infektif sehingga bersifat berbahaya, dan 5% berupa bahan non infeksius tetapi berbahaya (dapat berupa bahan kimia, farmasetikal dan radioaktif). Menurut Chandra (1999), limbah rumah sakit dapat diklasifikasikan menjadi : 1. Limbah umum : tipe limbah seperti limbah domestik atau rumah tangga, tidak berbahaya bagi manusia, misalnya limbah dapur, kertas, plastik 2. Limbah patologis: berupa jaringan, organ tubuh atau darah. Limbah ini merupakan salah satu limbah yang berbahaya. 3. Limbah infeksius : limbah yang mengandung patogen dalam jumlah tertentu yang dapat menyebabkan penyakit, bersifat berbahaya, misalnya stok/kultur bahan infeksius dari laboratorium, limbah dari pembedahan, maupun limbah yang langsung berasal dari pasien infeksi. 4. Limbah yang bersifat tajam dan dapat menyebabkan luka; misalnya jarum, pecahan gelas, skalpel, pisau bedah. 5. Limbah farmasetikal : meliputi produk farmasetikal, obat-obatan dan bahan kimia yang kemungkinan tercecer, kadaluarsa atau terkontaminasi. 6. Limbah kimia : meliputi bahan padat, cair atau gas yang bersifat kimiawi, misalnya produk disinfektan ataupun bahan pembersih untuk perawatan rumah sakit. 7. Limbah radioaktif : merupakan bahan padat, cair atau gas yang mengandung bahan radioaktif hasil analisis in-vitro jaringan tubuh maupun analisis in-vivo organ tubuh. Limbah tersebut dapat berasal unit perawatan pasien, laboratorium, unit farmasi, unit gizi, unit laundry maupun unit kebersihan. Bahan kimia yang digunakan dalam rumah sakit merupakan sumber potensial bagi pencemaran air. Kebanyakan bahan kimia dan farmasetikal yang digunakan adalah berbahaya, misalnya bersifat toksik, genotoksik, korosif, mudah terbakar atau meledak. Disinfektan umumnya bersifat korosif. Beberapa substansi bersifat genotoxic dan kemungkinan dapat menyebabkan kanker (Jolibois, 2007). Salah satu problem utama adalah buangan rumah sakit dibuang ke sistem pembuangan kota tanpa melalui perlakuan awal/pendahuluan terlebih dahulu. Bahan kimia dari rumah sakit dapat mengkontaminasi sistem perairan kota dan menyebabkan penyakit kulit ataupun penyakit enterik (Gautam, et.al., 2006). Bahan kimia, farmasetikal, disinfektan, pigmen, cat pewarna, reagen dan obat-obatan merupakan bahan-bahan yang banyak digunakan di rumah sakit, baik untuk kepentingan diagnostic maupun penelitian. Disinfektan umumnya merupakan produk kompleks atau merupakan campuran berbagai bahan aktif. Setelah aplikasi, bahan diagnostik dan disinfektan akan memasuki limbah cair. Selain itu, beberapa obat yang tidak dapat dimetabolisir oleh pasien kemudian diekskresikan dan juga akan masuk ke dalam limbah cair (Gautam, et.al., 2006; Emmanuel, et.al., 2007, Kummerer, 2007).
Limbah dari rumah sakit tersebut dapat berbahaya bagi manusia maupun ekosistem alami. Manusia dapat terkena bahaya limbah rumah sakit tersebut, baik melalui kontak langsung dengan limbah, menghirup gas, serta minum atau memakan produk yang terkontaminasi limbah dari rumah sakit. Residu bahan kimia yang masuk ke dalam sistem pembuangan mungkin saja memiliki efek yang kurang menguntungkan pada perlakuan limbah secara biologi atau memiliki efek toksik bagi ekosistem alami yang menerima limbah cair. Masalah yang sama dapat disebabkan oleh residu farmasetikal, yang meliputi antibiotik obat-obatan, logam berat seperti merkuri, fenol, disinfektan dan antiseptik (www.who.int/entity, 2006; Kummerer, 2007). Limbah cair akan memasuki badan air seperti sungai, danau atau laut. Dalam kecepatan yang lebih rendah, limbah ini dapat memasuki air tanah bila konsentrasi limbah cukup tinggi atau bila terdapat retakan pada tanah. Badan-badan air umumnya dimanfaatkan sebagai sumber air oleh masyarakat, baik untuk sumber air minum, kebutuhan rumah tangga, industri, irigasi atau untuk keperluan rekreasi. Tentunya air tersebut tidak boleh menjadi media transmisi penyakit akibat kontaminasi fekal atau akibat adanya perubahan suhu, salinitas atau pH air. Oleh karena itu diperlukan suatu penanganan limbah agar badan air tidak kelebihan bahan organik atau anorganik, bahan beracun ataupun substansi yang secara estetika tidak layak (Atlas dan Bartha, 1998). Limbah cair rumah sakit yang dibuang ke sungai atau badan air akan menimbulkan dampak terhadap penduduk yang menggunakan air sungai atau badan air tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Limbah rumah sakit dapat menimbulkan perubahan pada kualitas air yang dilaluinya, yang berupa : 1. Peningkatan zat padat berupa bahan organik sehingga terjadi kenaikan limbah padatan, baik tersuspensi ataupun terlarut. 2. Peningkatan kebutuhan oksigen terlarut karena adanya aktivitas mikrobia pembusuk bahan organik, akibatnya TSS (Total Soluble Solid) dan COD (Chemical Oxygen Demand) naik serta DO (Dissolved Oxygen) rendah sehingga mengganggu kehidupan dalam perairan. 3. Peningkatan senyawa zat-zat racun dalam air yang menghasikan bau busuk yang menebar keluar dari ekosistem akuatik. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki limbah cair rumah sakit tersebut, maka dibutuhkan suatu pengelolaan khusus terhadap limbah cair rumah sakit, sebab bila tidak dikelola dengan baik maka dapat meimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu setiap rumah sakit dituntut untuk memiliki unit pengolahan limbah cair (UPLC) dengan hasil akhir pengolahan (effluent) yang memenuhi sandar baku mutu yang ditentukan, yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58/MENLH/12/1995, tanggal 21 Desember 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Menurut Karen Mancl (http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0768.html) tahap-tahap pengolahan limbah cair meliputi : 1. Preliminary Treatment, yaitu pemisahan limbah cair dari bahan padat atau sampah yang ada dalam limbah cair, misalnya sisa makanan, potongan kain, potongan kayu, mainan, kerikil, dan lain-lain. 2. Primary Treatment, yaitu pemisahan padatan terlarut/suspended solid (SS) dan lemak dari limbah cair. Pada tahap ini limbah cair didiamkan beberapa jam dalam clarifier atau
septic tank sehingga padatan akan mengendap dan lemak akan mengapung. Cara lain adalah dengan penyaringan dan penambahan bahan koagulasi. 3. Secondary Treatment, merupakan proses biologi untuk memindahkan bahan organik dari limbah cair. Mikrobia dari limbah dikultivasi dan ditambahkan dalam limbah. Mikrobia akan menggunakan bahan organik sebagai sumber makanan. Pada lagoon systems, limbah cair didiamkan beberapa bulan agar terjadi degradasi secara alami. Sistem ini memanfaatkan aerasi alami dan mikrobia dalam limbah cair untuk mendegradasi limbah. Pada tiap metode dalam secondary treatment tersebut melibatkan komunitas mikrobia yang beragam untuk mendegradasi bahan organik, melalui proses degradasi aerobik maupun anaerobik. Menurut Tsai, et.al. (1998), secara alamai beberapa mikrobia pada suspended growth dapat menghancurkan mayoritas mikrobia patogen (80-90%) melalui kompetisi biologi. Beberapa mikrobia mampu membentuk flok dan absorpsi mikrobia patogen. 4. Final Treatment, yaitu menghilangkan mikrobia penyebab penyakit dengan cara desinfeksi dengan klorin atau sinar UV. Jumlah klorin yang tinggi dapat membahayakan kehidupan aquatic dalam sungai yang menerima hasil pengolahan limbah, oleh karena itu sering ditambahkan bahan kimia penetral klorin sebelum hasil pengolahan dibuang ke sungai. Salah satu parameter yang diukur dalam penentuan kualitas hasil pengolahan limbah cair adalah kadar fosfat dalam effluent, dan kadar fosfat di beberapa rumah sakit masih melebihi baku mutu yang telah ditentukan. Fosfat dalam air limbah dapat berupa fosfat organik, orthophosphate anorganik atau sebagai fosfat kompleks/polyphosphate. Fosfat organik terdapat dalam air buangan penduduk dan sisa makanan. Fosfat organik juga dapat berasal dari bakteri atau tumbuhan penyerap fosfat. Orthophosphate berasal dari bahan pupuk. Fosfat kompleks mewakili kurang lebih separuh dari fosfat limbah perkotaan dan berasal dari penggunaan detergent sintetis. Komponen fosfat digunakan untuk membuat sabun atau detergent, yaitu berperan sebagai pembentuk buih. Detergent yang mengandung fosfat dapat menyebabkan stimulasi pertumbuhan tanaman dan surfaktan pada detergent dapat bersifat toksik Polyphosphate dalam detergent akan mengalami hidrolisis selama pengolahan biologis dan menjadi bentuk orthophosphate (PO4 3-) yang siap digunakan oleh tumbuh-tumbuhan (Connell dan Miller, 1995). Salah satu tantangan yang muncul pada pengolahan limbah cair adalah pencapaian konsentrasi total nitrogen dan total fosfor dalam effluent yang sesuai dengan standar baku mutu. Kandungan fosfat yang tinggi dalam effluent limbah cair dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu tumbuhnya lumut dan microalgae yang berlebihan dalam badan air yang menerima limbah tersebut (Ahn, et.al., 2007; Wagner, et.al., 2002). Air yang mengandung P > 0.015 mg/L dan N 0.165 mg/L yang tersedia secara biologi dapat menyebabkan eutrofikasi (Lawrence, et.al., 2002). PEMBAHASAN Menurut Lawrence,et.al. (2002), salah satu masalah yang dihadapi dalam pengolahan limbah adalah pencapaian kadar fosfat dalam effluent yang belum sesuai dengan standar baku mutu. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis effluent beberapa rumah sakit di wilayah DIY (tabel 1). Hasil analisis effluent pada beberapa rumah sakit yang telah mengoperasikan UPLC menunjukkan bahwa kadar fosfat dalam effluent masih melebihi standar baku mutu yang telah
ditentukan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58/MENLH/12/1995, tanggal 21 Desember 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. No Tabel 1. Hasil analisis effluent beberapa Rumah Sakit yang telah memiliki UPLC Parameter Kode Rumah Sakit / Baku Mutu* Golongan Mutu Limbah Cair A/I B / II C / III Fisika: Suhu (oC) 31 28 26 30oC Kimia: pH 6 6,5 7 6-9 BOD5 (mg/L) 7,1 20,1 6,6 30 mg/L COD (mg/L) 25 72 24 80 mg/L 5 TSS (mg/L) 9 25 1 30 mg/L NH3 bebas (mg/L) 0,19 0,02 0,017 0,1 mg/L PO4 (mg/L) 9,63 14,9 9,63 14,9 21,85 2 mg/L 21,85 2 mg/L Mikrobiologi : MPN-Kuman 23.104 23.104 160.1010 10.000 golongan Koli/100 ml
1 2 3 4 5 6. 7. 8.:
Keterangan : Baku Mutu* : berdasar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 58/MENLH/12/1995, tanggal 21 Desember 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit. Pada tabel 1 tampak bahwa effluent pada beberapa rumah sakit yang telah mengoperasikan UPLC masih memiliki kadar fosfat yang melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan. Pengukuran kadar fosfat effluent rumah sakit dilakukan pada 3 rumah sakit dengan golongan baku mutu limbah cari yang berbeda, yaitu golongan I, II dan III. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kadar fosfat yang melebihi standar baku mutu dapat dikatakan terjadi pada semua rumah sakit dengan berbagai tingkat golongan baku mutu limbah cair. Bila rumah sakit yang telah memiliki UPLC, bahkan yang termasuk dalam golongan baku mutu limbah cair golongan I, masih memiliki kadar fosfat yang tinggi, maka diperkirakan rumah sakit atau lembaga medis yang belum mengoperasikan UPLC juga akan memiliki kandungan fosfat yang tinggi dalam limbah cair yang dihasilkannya. Diperkirakan kandungan fosfat dalam limbah cair rumah sakit atau lembaga medis tersebut juga akan lebih tinggi daripada kandungan fosfat effluent rumah sakit yang telah memiliki UPLC. Oleh karena itu peru dipikirkan tentang upaya untuk menurunkan kadar fosfat dalam pengolahan limbah cair. Senyawa fosfor merupakan nutrient pembatas dalam lingkungan akuatik. Fosfor merupakan makronutrien yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Fosfor merupakan komponen penting untuk pembentukan ATP (adenosine triphosphate), asam nukleat (DNA dan RNA), serta fosfolipid dalam membrane sel. P dapat disimpan dalam pada granula intraseluler, baik pada prokariot maupun eukariot. P merupakan nutrient pembatas pada pertumbuhan alga dalam badan air (Bitton, 1994). Pembuangan limbah cair dengan kandungan fosfat yang tinggi ke dalam badan air dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu tumbuhnya lumut dan microalgae yang berlebihan dalam badan air yang menerima limbah tersebut. Menurut Lawrence, et.al. (2002), air yang mengandung P >
0.015 mg/L yang tersedia secara biologi dapat menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebakan beberapa masalah penting dalam air. Peningkatan populasi tumbuhan dapat menyebabkan turunnya kandungan oksigen terlarut dalam air. Hal ini disebabkan karena menurunnya kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan sehingga fotosintesis oleh tubuhan air juga menurun dan lebih lanjut terjadi penurunan kadar oksigen hasil fotosintesis. Selain itu, penurunan kandungan oksigen juga diseabkan karena pada malam hari tumbuhan menggunakan oksigen dalam badan air, serta adanya tumbuhan yang mati dan dekomposisi oleh mikrobia. Kondisi tersebut menurunkan kualitas lingkungan sebagai habitat berbagai spesies ikan dan organism lain. Pada kejadian eutrofikasi juga terjadi peningkatan turbiditas/kekeruhan dan warna pada badan air. Keadaan ini menjadikan air tidak sesuai untuk penggunaan domestik atau sulit untuk diperlakukan agar sesuai dengan standar untuk keperluan domestik. Selain itu, pertumbuhan alga juga dapat menimbulkan bau yang tidak diinginkan, sehingga menjadikan air juga tidak sesuai untuk keperluan domestik. Bila pertumbuhan tumbuhan air tersebut terus berlanjut, dan jika bersifat toksik, maka dapat menyebabkan kematian pada ikan dan organisme akuatik lainnya, serta organisme terrestrial yang menggunakan air dalam badan air tersebut. Dampak lain yang dapat ditimbulkan oleh adanya eutrofikasi adalah gangguan badan air akibat adanya makrofita yang mengapung dan sampah dari alga, yang dapat mengganggu penggunaan badan air sebagai tempat rekreasi atau kepentingan masyarakat lainnya, seperti olah raga dan transportasi perairan (Connel dan Miller, 1984). Senyawa fosfor dalam limbah cair kebanyakan berasal dari fosfat dalam deterjen. Bentuk umum senyawa fosfor dalam limbah cair adalah berupa ortofosfat (50-70% fosfor), polifosfat dan fosfor dalam senyawa organik (Bitton, 1994). Fosfor dalam limbah cair harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum limbah cair dibuang ke badan air. Kandungan fosfort dalam limbah cair dapat diturunkan secara kimia atau biologi, yaitu mealui mekanisme : 1. Presipitasi kimiawi, melalui kontrol pH dan kation, seperti Ca, Fe dan Al. 2. Akumulasi polifosfat oleh mikrobia 3. Peningkatan presipitasi kimia dengan mediasi mikrobia. Secara kimia, fosfat dapat dipresipitasi dengan menambahkan garam aluminium, kapur, ferichlorida atau ferrous sulfat sehingga selanjutnya fosfat dapat terbuang bersama lumpur yang dihasilkan. Akan tetapi, teknik ini kurang efektif karena meningkatkan jumlah lumpur yang dihasilkan dan membutuhkan biaya tambahan untuk operasional dan mengatasi measalh tersebut. Selain itu, usaha ini dapat menyebabkan kontaminasi logam berat dalam sistem pembuangan limbah cair dan meningkatkan konsentrasi garam dalam effluent. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pengendapan ini adalah : Pengendapan dengan aluminium : Al3+ + PO43- AlPO4 Pengendapan dengan garam besi : FeCl3 + PO43- FePO4 + 3 ClPengendapan dengan kapur : 5 Ca(OH)2 + 3 HPO42- Ca5(PO4)OH + 3 H2O + 6 OH(Bitton, 1994; Wagner, et.al., 2002). Proses ozonisasi merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah penurunan fosfat. Pada proses ini digunakan perangkat generator ozon yang dapat menghasilkan ozon (O3) yang mempunyai kemampuan sebagai oksidator kuat. Dengan demikian ozon dapat menguraikan berbagai senyawa organik, diantaranya fosfat yang terkandung dalam air (Fajriah, 2008). Proses ini tampaknya memberikan peluang untuk menurunkan kandungan fosfat, namun tetap perlu dipikirkan tentang biaya yang perlu dikeluarkan untuk operasional generator ozon tersebut. Strategi lain dalam penurunan jumlah fosfor adalah dengan cara biologi, yaitu dengan mekanisme mikrobiologi yang disebut enhanced biological phosphorus removal (EBPR). Dalam
teknik ini, fosfat dibuang dari limbah dalam bentuk poli(P) intraseluler (Ahn, et.al., 2007). Terdapat dua pendekatan dalam strategi EBPR ini, yaitu presipitasi kimiawi dengan bantuan mikrobia dan peningkatan pengambilan fosfor oleh mikrobia. Proses EBPR dicirikan dengan siklus lumpur aktif pada kondisi aerob dan anaerob. Presipitasi fosfat dan pembuangannya dari limbah cair terjadi karena aktivitas microbial dalam tanki aerasi dan proses lumpur aktif. Pada tahap awal tanki aerasi, aktivitas mikrobia menyebabkan pH turun, yang melarutkan komponen fosfat. Pada akhir tanki aerasi, tejadi peningkatan pH yang menyebabkan presipitasi fosfat dan penggabungan komponen fosfat ke dalam lumpur. Presipitasi fosfat dengan bantuan mikrobia ini juga terjadi dalam biofilm pada proses denitrifikasi (Bitton, 1994). Presipitasi fosfat juga dapat diinduksi oleh peningkatan konsentrasi fosfat yang dihasilkan dari pelepasan fosfor dari polifosfat pada kondisi anaerobik. Pada kondisi anaerob, bakteri memperoleh energi dari hidrolisis polifosfat dan pelepasan Pi untuk uptake asam lemak rantai pendek. Pada kondisi aerob, organisme pengakumulasi polifosfat (polyphosphate accumulating organisms/PAO) mengembalikan simpanan polifosfat melalui uptake/pengambilan fosfat dari limbah cair. Fosfat akan dibuang dalam bentuk lumpur yang mengandung polifosfat intraseluler (Wagner, et.al., 2002). PAO adalah bakteri yang memiliki kemampuan mengakumulasi fosfor yang melebihi kebutuhan sel normal, yang secara normal berkisar antara 1 3% berat kering. PAO tidak hanya mengkonsumsi fosfor untuk pembentukan komponen selulernya saja, tetapi juga mengakumulasi sejumlah besar polifosfat dalam selnya, sehingga fosfor dalam organisme ini berkisar 5-7% dari biomassa sel. PAO memiliki kemampuan mengkonsumsi komponen karbon sederhana sebagai sumber energi tanpa keberadaan aksepor electron eksternal seperti nitrat atau oksigen. PAO dapat mengasilkan energi dari polifosfat internal atau glikogen yang tersimpan di dalam selnya. Beberapa bakteri yang termasuk dalam golongan PAO adalah Acinetobacter, Pseudomonas, Aerobacter, Moraxella, E.coli, Mycobacterium dan Beggiatoa (Bitton, 1994). Pengolahan limbah cair dengan sistem EBPR sering gagal dalam menurunkan fosfat. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh adanya bakteri pengguna komponen simpanan, misalnya menggunakan glikogen. Glikogen dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan bakteri. Bakteri tersebut berkompetisi dengan PAO dalam pengambilan substrat pada kondisi anaerob. Salah satu strategi untuk meningkatkan proses dalam suatu instalasi pengolahan limbah cair adalah dengan menambahkan mikrobia tertentu atau lumpur aktif dari insatalasi lain, yang dikenal dengan proses augmentasi. Namun demikian, usaha augmentasi tersebut seringkali gagal. Beberapa kegagalan disebabkan karena penambahan mikrobia yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Mikrobia tersebut tidak mampu berkompetisi dengan mikrobia yang ada dalam instalasi pengolahan air limbah dan akhirnya akan terbuang keluar. Akan tetapi identifikasi mikrobia yang bertanggung jawab dalam penurunan nitdogen dan fosfor dalam instalasi pengolahan limbah tetap dipandang penting dan perlu dilakukan. Kita perlu memahami kaitan antara diversitas suatu kelompok bakteri yang memiliki fungsi yang penting dengan stabilitas proses yang dikatalisis (Wagner, 2007). Gammaproteobacteria dari genus Acinetobacter dipercaya sebagai satu-satunya organism pengakumulasi poli (P) /poliphosphat accumulating organism (PAO), namun selanjutnya diketahui bahwa kemelimpahan Acinetobacter dalam system EBPR tidak memiliki arti penting untuk penurunan fosfor. Microlunatus phosphorus diperkirakan merupakan PAO, karena kemampuannya mengakumulasi polifosfat dalam keadaan aerob, akan tetapi tidak ada indikasi langsung berkaitan dengan pentingnya mikrobia tersebut untuk meningkatkan penurunan fosfor.
Betaproteobacteria dan Actinobacteria menunjukkan peningkatan jumlah setelah adanya penambahan asetat pada instalasi pengolahan limbah cair. Hal tersebut menjadi dasar perkiraan bahwa kelompok bakteri tersebut memperoleh keuntungan dari peningkatan ketersediaan asam lemak rantai pendek pada keadaan anaerobik dan menjadikannya sebagai kandidat PAO (Wagner, 2002). Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Ahn, et.al. (2007), diketahui bahwa bakteri Candidatus accumulibacter phosphatis adalah organisme pengakumulasi poli (P) yang dominan dalam sistem lumpur aktif konvensional. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Wagner (2002) bahwa Betaproteobacteria dari family Rhodocyclaceae adalah PAO yang penting dalam system EBPR. Bakteri tersebut adalah Candidatus accumulibacter phosphatis. Sedangkan Seviour, et.al. (2003) memperkirakan bahwa Actinobacteria merupakan PAO. Peningkatan penurunan fosfor secara biologi juga dapat dilakukan dengan menambahkan Pseudomonas putida GM6 dari lumpur aktif. Strain P. putida GM6 ini diisolasi di laboratorium dan memiliki kemampuan akumulasi fosfat yang tinggi (Tian-Ming, et.al., 2007). Dalam Bitton (1994) disebutkan bahwa tipe bakteri pengakumulasi fosfat tergantung pada komposisi limbah cair dan proses yang digunakan untuk menghilangkan fosfor. Jika PAO diperkaya secara selektif, maka diperkirakan akan lebih banyak fosfor yang dapat dibuang dari limah cair rumah sakit, dibandingkan bila limbah cair hanya diolah dalam system lumpur aktif konvensional. KESIMPULAN Kegiatan rumah sakit merupakan kegiatan yang kompleks, yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat ataupun lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa cemaran akibat kegiatan yang dilakukan atau akibat limbah yang dibuang tanpa pengolahan yang benar. Data yang diperoleh dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Departemen Kesehatan DIY serta hasil survei di beberapa lokasi, diketahui bahwa kandungan fosfat dalam effluent hasil pengolahan limbah cari rumah sakit masih melebihi standar baku mutu. Bila limbah cair rumah sakit yang telah diolah masih memiliki kandungan fosfat yang tinggi, maka diperkirakan limbah cair rumah sakit yang tidak diolah dengan baik akan meiliki kadar fosfat yang lebih tinggi lagi. Tingginya kadar fosfat dalam badan air dapat menyebabkan munculnya eutrofikasi. Eutrofikasi dapat menyebabkan adanya penurunan kualitas air, penurunan diversitas spesies dan perubahan struktur komunitas dalam badan air. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pengolahan limbah cair yang dapat menurunkan kadar fosfat sehingga sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditetapkan. Penurunan kadar fosfat dalam limbah cair dapat dilakukan secara kimia atau biologi. Teknik secara kimia dianggap kurang efektif karena meningkatkan jumlah lumpur yang dihasilkan dan membutuhkan biaya tambahan serta dikhawatirkan menyebabkan kontaminasi logam berat dalam sistem pembuangan limbah cair dan meningkatkan konsentrasi garam dalam effluent. Alternatif lain adalah dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan aktvitas mikrobia yang mampu menurunkan kadar fosfat. Penurunan kadar fosfat dapat dilakukan melalui mekanisme enhanced biological phosphorus removal (EBPR), yang melibatkan organisme pengakumulasi polifosfat (polyphosphate accumulating organisms/PAO). PAO akan mengkonsumsi fosfor untuk pembentukan komponen selulernya dan mengakumulasi sejumlah besar polifosfat dalam selnya.
DAFTAR PUSTAKA Atlas, R.M. and Richard Bartha, 1998, Microbial Ecology, Fundamentals and Applications, Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc., California, p.66-67, 179-181, 477, 506 Chandra,H., 1999, Hospital Waste, An Environmental Hazard and Its Management, EnviroNews, Newsletter of International Society for Environmental Botanists-Indie, Vol.5 No.3, July 1999, www.geocities.com/isebidia/95_99/99-07-2.html, diakses tanggal 23 Mei 2006 Connell, D.W. and Miller G.J., 1984, Chemistry and Ecotoxicology of Pollution, John Wiley & Sons, Inc., New York Emmanuel E, Perrodin Y, Keck G, Blanchard JM, Vermande P, Ecotoxicological Risk Assesment of Hospital Wastewater: a Proposed Framework for Raw Effluents Discharging into Urban Sewer Network, www.ncbi.nlm.nih.gov, diakses 5 Maret 2007 Fajriah, S., 2008, Deradasi COD, TSS dan Fosfat pada Limbah Cair Rumah Sakit Menggunakan Teknologi Ozon, STTL YLH, Yogyakarta Gautam, A.K., Sunil Kumar and P.C. Sabumon, 2006, Preliminary Study of Physicochemical Treatment Options for Hospital Wastewater, Elsevier Ltd. Hanrahan, G., Paulo Gardoinski, Martha Gledill, and Paul Worsfold, 2002, Environmental Monitoring of Nutrients, dalam Environmental Monitoring Handbook, Frank R. Burden (editor), McGraw-Hill, New York Jolibois, B. and M. Guerbet, Hospital Wastewater Genotoxicity, Annals of Occupational Hygiene 2006, Vol. 50, No.2, p.189-196