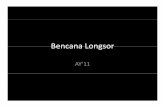Kerusakan Hutan Yang Disebabkan Oleh Ekspansi Lahan PT
-
Upload
alibaharun -
Category
Documents
-
view
59 -
download
0
Transcript of Kerusakan Hutan Yang Disebabkan Oleh Ekspansi Lahan PT
Kerusakan Hutan yang Disebabkan oleh Ekspansi Lahan PT. Sinar Mas
Sinar Mas merupakan sebuah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit terbesar diIndonesia, yang terkenal agresif dalam pembukaan lahan demi tujuan produksinya. Hinggasaat ini, grup perusahaan Sinar Mas telah memiliki 406.000 hektar lahan perkebunan kelapasawit, dan mengklaim dirinya sebagai perusahaan dengan lahan ekspansi terluas di dunia,mencapai 1,3 juta hektar. Dari beberapa operasi terakhir Sinar Mas, telah diketahui bahwalokasi penanaman kelapa sawit perusahaan ini ternyata bertempat di area hutan tropis, danekspansi lahannya melibatkan proses deforestasi terlebih dahulu. Hal inilah yang kemudianmenyebabkan rusaknya lahan gambut yang kaya karbon, serta habitat hewan endemik dihutan Indonesia
Meskipun pada segi ekonomi PT. Sinar Mas telah berkontribusi banyak terhadapperkembangan ekonomi Indonesia, tetapi kegiatan produksinya menimbulkan banyakmasalah lingkungan dan sosial. Di wilayah Sumatra dan Kalimantan, ekspansi ladang kelapasawit mengancam keberlangsungan hidup spesies yang terancam punah seperti gajah,harimau, badak, dan orangutan. Karbon dioksidan dalam jumlah yang besar pun dilepaskan diudara ketika hutan dan lahan gambut dihancurkan. Deforestasi ini menyebabkan Indonesiamenjadi salah satu negara penghasil karbon terbesar di dunia, urutan ketiga setelah AmerikaSerikat dan Cina. Deforestasi oleh PT. Sinar Mas juga menyebabkan banyak permasalahansosial dengan menggusur tempat tinggal masyarakat adat pedalaman untuk dijadikan lahanperkebunan.
Sejauh ini, PT. Sinar Mas berusaha untuk menanggulangi dampak kerusakanlingkungannya dengan bergabung dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO);sebuah organisasi pemasok minyak kelapa sawit yang beranggotakan pemasok dan konsumenminyak kelapa sawit; yang menekankan tindakan produksinya terhadap kelestarianlingkungan.
Meskipun anggota-anggota RSPO telah memberikan dana sumbangan untukperlindungan hutan dan lahan gambut, kenyataan yang terjadi di lapangan sangat berbeda.Standar yang diberikan RSPO terhadap pertanggungjawaban lingkungan tidak memadai untuk mencegah kehancuran lahan gambut dan hutan tropis Indonesia. Yang lebih buruk lagi,RSPO bahkan tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan standarnya dipatuhi oleh anggota-anggotanya. Untuk saat ini, RSPO menciptakan sebuah ilusi mengenai penanaman kelapasawit yang berkelajutan, menjunjun keadilan atas ekspansi industri mereka, kerusakan hutan,serta perubahan iklim; dan melindungi perusahaan-perusahaan yang melakukan deforestasibesar-besaran di dalamnya
.PT. Sinar Mas telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap salah satu asas yangditetapkan oleh RSPO mengenai penebangan liar serta penggusuran hutan dan lahan gambuttanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, juga perizinan dan hukum Indonesiatentang pemanfaatan hutan di bidang industri. Pada tahun 2009 silam lalu, PT. Sinar Mastelah diketahui gagal mengajukan permohonan penebangan hutan terhadap KementrianPerhutanan (IPK), di sekitar areal Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat.Tetapi ternyata PT. Sinar Mas telah memberishkan 4000 hektar hutan di wilayah itu sebelummendapat persetujuan dari pemerintah, dan pada PT. Sinar Mas tetap melakukan ekspansiperkebunan di daerah tersebut. Pada kasus yang lain, PT. Sinar Mas bahkan telah melaukanekspansi lahan dua tahun sebelum mendapatkan persetujuan pemerintah di sekitar TamanNasional Bukit Tigapuluh Sumatra
.Akibat dari pelanggaran hukum ini, pada tahun 2008, distribusi habitat orang utan diwilayah Kalimantan beririsan dengan area lahan perkebunan. Tidak hanya beririsan, tetapitiga dari empat ekspansi lahan yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas setidaknyamenghancurkan habitat asli orangutan, dan menggantinya ladang tumbuhan kelapa sawit. Diwilayah Sumatra, hal yang sama juga terjadi pada satu-satunyareintroduction habitatbagi Orangutan yang berhasil di dunia. Wilayah ini juga bahkan diketahui sebagai habitat dari 100 dari 400 harimau sumatra yang terancam punah, dan 40-60 gajah sumatra. Hal inimenunjukkan bahwa PT. Sinar Mas tidak dapat menerima standar pertanggungjawabanlingkungan, dan tidak menjunjung konsep biodiversitas di dalamnya
Selain itu, perluasan lahan kelapa sawit PT. Sinar Mas selama beberapa dekade terakhirini menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat adat, yang menggantungkankehidupannya di hutan. Kini, jutaan masyarakat adat terusir dari tempat tinggalnya, dandipaksa untuk mengubah gaya hidupnya karena hutan tempat mereka tinggal telah digusur.Salah satu contoh kasus adalah pembukaan lahan di dekat Taman Nasional Danau Sentarum,yang merupakan salah satu kawasan hulu sungai Kapuas yang menjadi sumber air danpangan bagi masyarakat sekitar. Lahan tersebut dibakar, dan masyarakar kini tidak memilikisumber air bersih serta ikan segar dari sungai lagi. Contoh lainnya adalah masyarakat adat dipapua yang menggantungkan pangan utamanya dari sagu. 20,535 hektar hutan ditebang untukmembuka lahan baru, sehingga pohon sagu kini semakin sulit dijumpai di hutan.
Kaum adat lainnya yang terancam oleh ekspansi lahan PT. Sinar Mas adalah TalangMamak dan Orang Rimba yang hidup di dalam Taman Nasional Bukit Tigapuluh
Analisis :Pada kasus ini, kegagalan pemerintah Indonesia dalam melindungi kawasan hutannyaberakar pada Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2008; tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (JPNP) yang berasal dari pemanfaatan hutan. PP ini melegalkan adanya pemanfaatkan hutan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan ekonomi di luar kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan. Peraturan ini juga mengizinkan adanya pengelolaan hutan lindung oleh pihak swasta, sehingga ada kemungkinan bahwa hutan lindung berada di bawah otoritas pihak-pihak seperti perusahaandan investor
.Keluarnya PP tentang pengelolaan hutan lindung tersebut menimbulkan kekhawatiran akan rawannya perubahan fungsi hutan lindung menjadi fungsi ekonomi. Penyebabnya antaralain adalah otoritas pihak swasta untuk mengatur dan memanfaatkan hutan lindung yangdikelolanya, sehingga seolah-olah kawasan hutan tersebut menjadi milik si pengelola tersebut. Padahal, potensi kerusakan hutan yang diterima oleh Indonesia tidak sebanding dengan harga sewa yang ditawarkan oleh pemilik modal. Peraturan ini jelas hanyamenguntungkan perusahaan besar saja.Dengan berbekal PP No. 2 Tahun 2008 ini, perubahan hutan lindung menjadi hutanproduksi dapat dilakukan hanya dengan membayar Rp 1,8 juta hungga Rp 3 juta per hektarkepada pemerintah. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak perusahaan(termasuk termasuk PT. Sinar Mas) untuk merusak dan meratakan kawasan hutan Indonesia demipelaksanaan kegiatan ekonominya.
Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menarik investor sebanyak-banyaknya, sehingga diciptakanlah suatu mekanisme yang berupa peraturan dan undang-undang yang dapat menguntungkan investor. Dengan begitu, Indonesia dapat menarikkeuntungan untuk menambah cadangan devisanya, menurunkan tingkat pengangurannya,serta pertumbuhan ekonominya
Mengesampingkan PP di atas, sesungguhnya Indonesia memiliki sepertangkat peraturanyang berisi mengenai perlindungan hutan dan lahan gambut. Tetapi kondisi birorasi Indonesiayang sarat akan korupsi membuat peraturan-peraturan tersebut menjadi sulit terealisasi.Petugas pemerintah yang dibayar rendah, dikombinasikan dengan usahawan yang tidakbertanggungjawab, serta politisi yang licik membuat peraturan tersebut diabaikan, spesiesyang terancam punah semakin bertambah, dan para pelaku perusak hutan berkeliaran bebas.
Hal ini ditambah dengan rendahnya personil polisi hutan, serta organisasi pengawaslainnya yang berfungsi untuk menjalankan peraturan-peraturan tersebut. Dengan begitu, maka dapat dilihat bahwa pemerintah di Indonesia sesungguhnyamemiliki peranan yang besar dalam kerusakan hutan di Indonesia. Peraturan yangmendukung pelaksanaan perusakan hutan; serta iklim politik yang tidak kondusif menjadipenyebab utama dari kelalaian Indonesia dalam menjaga kawasan hutannya
Tambang pasir besi picu abrasi & kerusakan ekosistem
Sindonews.com - Warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, mengeluhkan parahnya abrasi dan kerusakan ekosistem di kawasan pantai setempat. Warga menduga, abrasi yang kian meluas tersebut imbas dari praktik penambangan pasir besi di pesisir pantai utara wilayah Jepara.
Salah seorang warga Desa Bumiharjo, Dafiq mengatakan, penambangan pasir besi yang dilakukan oleh salah satu investor swasta tersebut, telah mengakibatkan abrasi di Pantai Bringin yang tiap tahun luasannya mencapai 5-10 meter. Jika tidak segera dicegah, dikhawatirkan abrasi tersebut akan mengancam keberadaan kebun, sawah, dan perkampungan penduduk yang lokasinya berdekatan dengan bibir pantai tersebut.
Makanya kami tanami lahan bekas areal penambangan pasir besi yang ada di pesisir Pantai Bringin ini. Ini ulah investor tambang pasir besi yang tidak bertanggungjawab, kata Dafiq, di Jepara, Senin (29/7/2013).
Sebelumnya, pada Maret lalu, telah melakukan penolakan terkait aktivitas penambangan pasir besi di Desa Bumiharjo yang dikelola PT Pasir Rantai Mas (PRM). Dan hingga kemarin, areal penambangan tersebut terlihat masih lengang. Sejumlah alat berat dan bangunan terkait aktivitas penambangan tersebut dibiarkan mangkrak. Warga mengancam jika sampai akhir bulan Juli ini, alat berat tersebut tidak segera diambil oleh investor, maka akan disingkirkan dari areal sekitar pantai.Dan kini, di sekitar lahan bekas penambangan yang gundul tersebut ditanami warga dengan sejumlah tanaman. Mulai dari pohon kakao, kelapa, dan pohon waru. Menurut Dafiq, aksi warga ini merupakan upaya untuk menyelamatkan ekosistem di pesisir pantai utara wilayah Jepara yang rusak akibat penambangan pasir besi Kerusakan ekosistem pantai ini, terlihat dari beberapa titik area di sepanjang pantai yang saat ini telah gundul. Bahkan dibeberapa area, bekas lahan yang digali oleh penambang telah menjadi danau kecil.
Penambangan pasir besi juga mengakibatkan daratan di sepanjang garis pantai hilang terkena abrasi. Hal ini bisa dilihat dari bekas beberapa pohon kelapa yang makin lama semakin menjorok ke tengah pantai. Selain itu, puluhan hektare tanaman kelapa di perkebunan dekat pantai juga banyak yang mati.
Jadi kerusakan ekosistem di pesisir pantai sudah sangat parah, tandasnya.
Analisis :. Pembangunan sektoral selama ini terus memperbesar eksploitasi sumber daya alam, sementara itu kebutuhan untuk melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya adalah semakin banyaknya kerusakan lingkungan, banjir, longsor, pencemaran air sungai, dan lain-lain.Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Menurut Hadi (2006), dampak lingkungan itu pada umumnya menimpa pada orang lain dan bukan pemrakarsa kegiatan yang menimbulkan dampak dimaksud. Banjir, tanah longsor, kebisingan, bau, debu, intrusi air laut, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian merupakan dampak lingkungan yang dirasakan oleh mereka yang bukan memprakarsai kegiatan.Lahan yang digunakan untuk pertambangan tidak seluruhnya digunakan untuk operasi pertambangan secara serentak, tetapi secara bertahap. Sebagian besar tanah yang terletak dalam kawasan pertambangan menjadi lahan yang tidak produktif. Sebagian dari lahan yang telah dikerjakan oleh pertambangan tetapi belum direklamasi juga merupakan lahan tidak produktif. Lahan bekas kegiatan pertambangan menunggu pelaksanaan reklamasi pada tahap akhir penutupan tambang. Kalau lahan yang telah selesai digunakan secara bertahap direklamasi, maka lahan tersebut dapat menjadi lahan produktif ( Nurdin dkk, 2000). Pertambangan dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Potensi kerusakan tergantung pada berbagai faktor kegiatan pertambangan dan faktor keadaan lingkungan. Faktor kegiatan pertambangan antara lain pada teknik pertambangan, pengolahan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor lingkungan antara lain faktor geografis dan morfologis, fauna dan flora, hidrologis dan lain-lain. Kegiatan penambangan pasir di Kabupaten jepara menimbulkan dampak terhadap fisik lingkungan yg tjdi masyarakat. Dampak terhadap fisik lingkungan yaitu adanya abrasi pantai yang mengakibatkan ekosistem pantai dan laut rusak dan berpotensi terjadinya gelombang pasang dan tsunami.
Kehadiran Freeport Ciptakan Kesenjangan Ekonomi Di Papua
Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport. Kehadiran Freeport pun tidak mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, namun berkontribusi sangat besar pada perkembangan perusahaan asing tersebut.Pada tahun 1995 Freeport baru secararesmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport mengaku hanya sebagai penambang tembaga. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Panitia Kerja Freeport dan beberapa anggota DPR RI Komisi VII pun mencurigai telah terjadi manipulasi dana atas potensi produksi emas Freeport. Mereka mencurigai jumlahnya lebih dari yang diperkirakan sebesar 2,16 hingga 2,5 miliar ton emas. DPR juga tidak percaya atas data kandungan konsentrat yang diinformasikan sepihak oleh Freeport. Anggota DPR berkesimpulan bahwa negara telah dirugikan selama lebih dari 30 tahun akibat tidak adanya pengawasan yang serius. Bahkan Departemen Keuangan melalui Dirjen Pajak dan Bea Cukai mengaku tidak tahu pasti berapa produksi Freeport berikut penerimaannya.Di sisi lain, pemiskinan juga berlangsung di wilayah Mimika, yang penghasilannya hanya sekitar $132/tahun, pada tahun 2005. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan seperti HIV/AIDS dan jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia di masa lalu dan kini. Ratusan orang telah menjadi korban pelanggaran HAM berat bahkan meninggal dunia tanpa kejelasan. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan.Pemiskinan di PapuaKegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan. Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).Para petinggi Freeport mendapatkan fasilitas, tunjangan dan keuntungan yang besarnya mencapai 1 juta kali lipat pendapatan tahunan penduduk Timika, Papua. Keuntungan Freeport tak serta merta melahirkan kesejahteraan bagi warga sekitar. Di sisi lain, negara pun mengalami kerugian karena keuntungan Freeport yang masuk ke kas negara sangatlah kecil jika dibandingkan keuntungan total yang dinikmati Freeport.Keberadaan Freeport tidak banyak berkontribusi bagi masyarakat Papua, bahkan pembangunan di Papua dinilai gagal. Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri dari 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Pada tahun 2002, BPS mencatat sekitar 41 persen penduduk Papua dalam kondisi miskin, dengan komposisi 60% penduduk asli dan sisanya pendatang. Pada tahun 2005, Kemiskinan rakyat di Provinsi Papua, yang mencapai 80,07% atau 1,5 juta penduduk.Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua. Jadi penduduk asli Papua yang miskin adalah lebih dari 66% dan umumnya tinggal di pegunungan tengah, wilayah Kontrak Karya Frepoort. Kepala Biro Pusat Statistik propinsi Papua JA Djarot Soesanto, merelease data kemiskinan tahun 2006, bahwa setengah penduduk Papua miskin (47,99 %).Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50% lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumberdaya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua.Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua Barat memang menempati peringkat ke 3 dari 30 propinsi di Indonesi pada tahun 2005. Namun Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.Selain itu, situs tambang Freeport di puncak gunung berada pada ketinggian 4.270 meter, suhu terendah mencapai 2 derajat Celcius. Kilang pemrosesan berada pada ketinggian 3.000 m, curah hujan tahuan di daerah tersebut 4.000-5.000 mm, sedangkan kaki bukit menerima curah hujan tahunan lebih tinggi, 12.100 mm dan suhu berkisar 18-30 derajat Celcius. Dengan kondisi alam seperti ini, kawasan di bawah areal pertambangan Freeport mempunyai tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Pada 9 Oktober 2003, terjadi longsor di bagian selatan area tambang terbuka Grasberg, menewaskan 13 orang karyawan Freeport. Walhi merelease longsor terjadi akibat lemahnya kepedulian Freeport terhadap lingkungan. Padahal, mereka mengetahui lokasi penambangan Grasberg adalah daerah rawan bencana akibat topografi wilayah serta tingginya curah hujan. Jebolnya dam penampungan tailing di Danau Wanagon pada tahun 2000, menyebabkan tewasnya empat pekerja sub-kontraktor Freeport. Terjadi longsor di lokasi pertambangan Grasberg pada Kamis, 9 Oktober 2003.
Analisis:pemiskinan terus berlangsung di wilayah Mimika. Kesejahteraan penduduk Papua tak secara otomatis terkerek naik dengan kehadiran Freeport yang ada di wilayah mereka tinggal. Di wilayah operasi Freeport, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Selain permasalahan kesenjangan ekonomi, aktivitas pertambangan Freeport juga merusak lingkungan secara masif serta menimbulkan pelanggaran HAM.Timika bahkan menjadi tempat berkembangnya penyakit mematikan, seperti HIV/AIDS. Tercatat, jumlah tertinggi penderita HIV/AIDS Indonesia berada di Papua. Keberadaan Freeport juga menyisakan persoalan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan aparat keamanan Indonesia pada masa lalu dan kini. Hingga kini, tidak ada satu pun pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti serius oleh pemerintah bahkan terkesan diabaikan, pemerintah terkesan buta .Kegagalan pembangunan di Papua dapat dilihat dari buruknya angka kesejahteraan manusia di Kabupaten Mimika. Penduduk Kabupaten Mimika, lokasi di mana Freeport berada, terdiri atas 35% penduduk asli dan 65% pendatang. Hampir seluruh penduduk miskin Papua adalah warga asli Papua.Di sisi lain, pendapatan pemerintah daerah Papua demikian bergantung pada sektor pertambangan. Sejak tahun 1975-2002 sebanyak 50 persen lebih PDRB Papua berasal dari pembayaran pajak, royalti dan bagi hasil sumber daya alam tidak terbarukan, termasuk perusahaan migas. Artinya ketergantungan pendapatan daerah dari sektor ekstraktif akan menciptakan ketergantungan dan kerapuhan yang kronik bagi wilayah Papua ke depan.Pada tahun 2005 terlihat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Papua menempati peringkat ke 3 dari 30 provinsi di Indonesia. Namun, Indeks Pembangunan Manusi (IPM) Papua, yang diekspresikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita karena masalah-masalah kekurangan gizi, berada di urutan ke-29. Lebih parah lagi, kantong-kantong kemiskinan tersebut berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport.Pemerintah telah kehilangan nurani, yang seharusnya saat ini harus berani mengambil langkah tegas menindak Freeport yang jelas-jelas telah melanggar hukum. Sementara dasar hukum untuk itu sudah tersedia. Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan dan Perpajakan dapat dipergunakan bila memang ada niat baik dari pemerintah untuk menghentikan ulah Freeport ini. Langkah pertama, dengan melakukan audit lingkungan dan audit keuangan terhadap Freeport.Pemerintah tidak boleh terus membiarkan ketidakadilan ini. Karena itu, langkah berikutnya adalah pemerintah harus percaya diri mengkaji ulang dan mengoreksi kebijakan serta isi KK Freeport. KK dengan Freeport harus diubah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Undang-undang ini memerintahkan agar seluruh KK yang beroperasi di Indonesia sebelum UU ini terbit, harus disesuaikan. Secara spesifik, Pasal 169 butir b pada Bab Peralihan telah mengamanatkan agar isi Kontrak Karya, tanpa terkecuali Kontrak Karya Freeport, agar disesuaikan dengan isi UU tersebut paling lambat satu tahun sejak UU disahkan. Dan ini adalah perintah UU. Karena itu, pemerintah harus percaya diri mengubah isi KK Freeport. Pemerintah yang tidak melaksanakan perintah UU tidak layak dipertahankan.
Lucu, Kita Impor Minyak dari Singapura yang Tak Punya Sumur Migas
Jakarta -Luas Singapura lebih kecil dibandingkan luas Pulau Batam. Namun negara tersebut menjadi tumpuan Indonesia sebagai pemasok sebagian besar kebutuhan BBM Indonesia. Kok bisa?
Wakil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, lucu karena Indonesia mengimpor BBM dari Singapura. Padahal negara tersebut tidak punya lapangan atau sumur minyak dan gas bumi.
"Lucu kan, kita justru malah impor dari BBM dari Singapura. Padahal mereka tidak ada eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi di negaranya," ujar Fanshurullah dihubungi detikFinance, Selasa (11/2/2014).
Fanshurullah mengungkapkan, Singapura bisa menjadi pusat perdagangan minyak dan gas bumi di Asia Tenggara, karena Singapura memiliki kilang minyak yang paling canggih di dunia.
"Dia punya kilang minyak yang diklaim paling canggih di dunia, Singapura membeli banyak minyak mentah dari mana-mana, lalu dia olah menjadi produk jadi yakni BBM, lalu diekspor ke berbagai negara salah satunya ke Indonesia," ucapnya.
Analisis:
Korupsi akan cenderung menyebabkan redistribusi sumber daya ekonomi timpang, karena penguasa akan mengoptimalkan kekuasaan dan akses yang mereka miliki untuk mengambil bagian dari redistribusi sumber daya itu, sehingga alokasi untuk masyarakat akan berkurang. Mereka juga mengambil kepentingan pribadi dari desain kebijakan publik yang mereka buat dan jalankan. Dengan begitu, mereka akan semakin kaya dan di saat yang sama masyarakat tidak mendapatkan benefit secara optimal dari alokasi sumber daya yang seharusnya mereka peroleh. Perilaku rent-seeking inilah yang menjadikan kebijakan publik berjalan buruk, tidak tepat sasaran dan menjadikan ketimpangan semakin tinggi (Johnson, 1989; Tanzi,1995).
Argumentasi utama yang menjadi landasan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tersebut adalah berinduk pada ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang pada intinya menegaskan bahwa seluruh kekayaan (sumberdaya) alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Namun dalam realitasnya ada kekayaan alam yang cukup melimpah dimasa lalu bagi daerah yang menjadi wilayah penambangan (yang memiliki potensi) ternyata masih kurang dapat menikmati hasil-hasilnya apalagi daerah-daerah yang bukan merupakan penghasil tambang. Karena itu selalu muncul pertanyaan yang mendasar kemana larinya harta kekayaan sumberdaya alam tersebut, karena ke wilayah daerah penambangan manfaat tersebut tidak mengucur dan apalagi ke wilayah daerah di luar wilayah penambangan malah lebih tidak menetes.Ada kesan dimasa lalu rakyat di wilayah pertambangan migas tetap miskin sementara para pekerja disektor pertambangan migas hidup secara eksklusif dengan segala kemewahannya, setidaknya ada dua komunitas kehidupan ekonomi yang berbeda dan bertolak belakang bahkan sampai menyangkut pola hidup dan budaya komunitas masyarakat tambang yang berbeda dengan pola hidup dan budaya masyarakat lokal. Suka atau tidak suka gambaran realitas seperti yang dikemukakan tersebut nyata keberadaannya di dunia masyarakat pertambangan khususnya untuk minyak dan gas bumi.Apabila dilihat semata-mata dari perspektif hukum memang dapat dipahami, karena pengelola pertambangan yang berbentuk badan hukum PT (Persero) atau dimasa lalu disebut Perusahaan Negara (PN) sebagai suatu entitas / badan hukum yang mengelola suatu industri migas, tentu memiliki aturan dan standar khusus dalam memberikan kesejahteraan pegawainya, apalagi beberapa standar kebutuhan hidup mereka membandingkannya dengan standar perusahaan-perusahaan asing dalam bidang industri yang sama. Karena sebagian dari mereka yang bekerja di sektor tersebut memiliki suatu kualifikasi standar keahlian tertentu dan konsekuensinya juga memiliki standar imbalan jasa yang standar dan jaminan kesejahteraan sosial yang standar pula.Jadi realitas kesenjangan kesejahteraan sosial ekonomi antara masyarakat perminyakan dengan masyarakat lokal memang merupakan suatu konsekuensi dari jenis kegiatan industri perminyakan yang high tech dan penggunaan standar keahlian khusus yang berdampak pada pendapat yang cukup tinggi. Hal ini menjadi kontras dengan realitas keberadaan sosial ekonomi masyarakat umum disekitar industri perminyakan yang nota bene bekerja pada sektor yang bersifat tradisional dengan penghasilan yang relatif rendah.Pulau Jawa Impor Air Bersih 10 Tahun Lagi?
TEMPO.CO, Madiun Direktur Bina Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Haryadi Himawan mengatakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Jawa rusak. Antara lain DAS Citarum, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas. Kondisi ini bakal berdampak pada merosotnya ketersedian air yang dibutuhkan masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di tepian sungai.
"Kalau DAS tidak ditangani secara bagus, maka akan terjadi defisit air di Jawa dalam waktu sepuluh tahun ke depan," kata dia di sela Seminar Penyelamatan Hutan Jawa yang diselenggarakan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhutani Madiun, Selasa 27 Agustus 2013.Sayangnya, menurut Haryadi, para kepala daerah kurang peduli mengurus persoalan itu. Alasannya, problematika itu tidak menjadi isu menarik untuk menggaet warga untuk memenangkan calon pimpinan daerah di dalam pemilihan umum. "Di era politik pendekatannya dapil bukan DAS. Selama ini tidak ada perubahan mendasar dan sebantar lagi kita akan impor air," kata dia.Untuk menanggulangi impor air, dia mendesak kepala daerah yang dilalui DAS agar bupati terlibat langsung mengatasinya. Upaya itu bertujuan memetakan titik-titik lahan kritis yang perlu direhabilitasi dengan cara penanaman pohon produktif. Dengan begitu, perekonomian masyarakat di daerah prioritas penanganan DAS bisa ikut ditingkatkan. "Bupatinya harus diajak duduk bareng. Pemangku kepentingan harus diajak biacara dari awal," ujarnya.Kepala daerah yang perlu diajak koordinasi oleh Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, misalnya, bupati Wonogiri, Jawa Tengah. Sebab, terang dia, daerah tersebut merupakan hulu dari DAS Bengawan Solo. "Rehabilitasi perlu seiring sejalan dengan pemberdayaan masyarakat. Penyelamatan DAS tidak hanya persoalan teknis tapi persoalan manusia," kata Haryadi.Dosen Fakultas Kehutanan UGM Yogjakarta Lis Rahayu menambahkan, kerusakan DAS itu akibat penebangan kayu di hutan secara berlebihan. "Seharusnya ada tebang juga ada tanam. Dan penanaman di hutan produksi ada rotasi," ujar dia.
Analisis:Permasalahan yang timbul yakni sering dijumpai bahwa kulaitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air minum yang sehat bahkan di beberapa tempat bahkan tidak layak untuk diminum. Air yang layak diminum, mempunyai standar persyaratan tertentu yakni persyaratan fisis, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi jika ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tesebut tidak layak untuk diminum. Pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar kualitas tersebut dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara langsung dan cepat maupun tidak langsung dan secara perlahan.Masalah air bersih yang memenuhi syarat kesehatan tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, tetapai juga sering dialami oleh masyarakat industri khususnya industri kecil dan menengah yang bergerak di dalam industri proses khususnya proses pengolahan makanan dan minuman serta proses yang berhubungan dengan senyawa kimia. Masalah air bersih yang kurang memenuhi syarat tersebut sangat berpengarauh terhadap kualitas produk. Sebagai contoh di dalam industri makanan dan minuman jika air yang digunakan kurang baik maka produk yang dihasilkan juga kurang baik, apalagi jika air yang digunakan tidak steril maka produk yang dihasilkan dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen yang mana dapat membayakan konsumen. Jika kondisi kerusakan hutan dan DAS itu dibiarkan, maka 10 tahun ke depan, Pulau Jawa impor air dari luar negerin, kata Direktur Bina Perhutani Haryadi Himawan dalam Seminar Region Jawa 'Hutan Penyelamat PulauJawa' dalam rangka Reuni 50 Tahun Emas Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta di Pusdiklat Perhutani Kota Madiun, Selasa (27/8).
Jika kerusakan DAS dan hutan tak diperbaiki, menurut Haryadi, maka Pulau Jawa diprediksi jika 10 tahun tak ada pengelolaan hutan dengan baik. Buntutnya jawa bisa terjadi impor air. Padahal, impor air bersih itu lebih bahaya dibandingkan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini hasil sebuah studi. Saya siap pertanggungjawabkan pernyataan ini, ujar Haryadi serius.
Menurut Haryadi, kondisi terparah pemicu makin menyusutnya stok air di Pulau Jawa dikarenakan buruknya sistem pengelolaan DAS. Bahkan, sampai saat ini kerusakan DAS mencapai sekitar 40%, untuk memperbaiki DAS dengan cara restorasi sulit untuk memulihkan persediaan air. Alasannya, sudah terjadi degradasi tanah di DAS memicu air terbuang begitu saja atau percuma, ujarnya lagi.Ia mengungkapkan dari 3 juta hektare hutan negara dan 1,26 juta hektare hutan rakyat di Pulau Jawa, sekitar 1,5 juta hektare dalam kondisi sangat kritis dan 30.787 hektare masih kritis.
Maka itu, penyelamatan DAS penting sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Untuk menyelamatkan DAS kondisinya rusak parah itu, ada 10 program penyelamatan, ujar Haryadi.
Ke-10 program meningkatkan kepemimpinan transformasional, meningkatkan efektivitas hutan negara, peran perencanaan DAS terpadu, peran riset dan pengembangan teknologi, meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan, meningkatkan dukungan global perubahan iklim. Lalu, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran, DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga meningkatkan peran dukungan dunia usaha, serta meningkatkan rehabilitasi lahan kritis.Hasil inventarisasi PPE Jawa menunjukkan bahwa 9 DAS Utama di pulau jawa yaitu DAS bengawansolo, brantas, ciliwung, cimanuk, cisadane, citanduy, citarum, progo dan serayu memiliki luasan sebesar 5.230.628, 74 ha, dihuni oleh 65.394.403 jiwa dan memiliki ketersediaan air 40.288.874.971 m3/tahun. Sedangkan kondisinya be rbeda-beda, antara lainDAS Cimanuk, kondisi lahannya menurut data BP DAS Cimanuk Cisanggarung menunjukkan bahwa lahan yangsangat kritis seluas 1,966.39 ha; kriitis 14,854.88 ha; agak kritis 77,250.02 ha, potensial kritis 85,114.43. Hal ini disebabkan karena tingginya erosi, longsor, banjir dan sedimentasi akibat pembukaan lahan menjadi lahan perkebunan yang sangat ekstensif di kawasan hulu.Sebagian kecil peran sederhana yang bisa dilakukan bagi yang berada di wilayah tengah atau hilir kawasan DAS adalah dengan mengelola air limbah rumahnya, atau diistilahkan mengelola grey water. Dengan peran serta inilah diharapkan krisis air pulau jawa sedikit dapat dikurangi, ketersediaan air tercukupi dan ketahanan air dapat tercipta.Apa Grey Water ...... ??Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
Hampir semua kompleks perumahan di Indonesia membuang grey water langsung ke SELOKAN tanpa diolah.black water (tinja/kotoran manusia) dari WC biasanya diolah pada tangki septic.Kenapa Ecotech Garden .... ??Karena terjadi proses dekomposisi zat organik (reaksi biokimia) yang memerlukan Oksigen Terlarut, sehingga dapat menurunkan kandungan Oksigen Terlarut dalam air limbah, ditandai dengan warna air limbah kehitaman,berbusa dan berbau busuk, reaksi yang terjadi yaitu :CxHyO2N2S2 + H2ONH4 + CO2 + CH4 + H2S + 368 kal/gr/protein ProteinBau ammoniaBau telur busukBagaimana Ecotech Garden .... ??Ecotech Garden adalah salah satu teknologi alternatif pengolahan air selokan (grey water) atau effluent tangki septik, dengan menggunakan tanaman hias air.N & P diserap tanaman untuk pertumbuhan, juga dapat menurunkan zat pencemar: BOD, COD, Detergent, bakteri patogen (effluent tangki septik), serta menghilangkan bau dan menjernihkan air.Mekanisme Penyerapan Zat PencemarMekanisme penyerapan zat pencemar pada Ecotech Garden, oleh zone akar adalah :Terjadi peningkatan lebih banyak pada rhizosphere (perakaran tanaman). Terjadi peningkatan mikro organisme 10 - 100 kali lebih banyak, karena ada penyaluran oksigen dari daun, ini membantu penyerapan bahan pencemar dari air limbah yang diolah.BOD air limbah diturunkan melalui proses oksidasi dan reduksi (fermentasi aerobic).Amonium (NH4 N), dioksidasioleh bakteri autotrop pada.Ecotech Garden di Komplek Perumahan Bumi Asri PadasukaDibuat tahun 2005,dengan memanfaatkan air selokan terbuka (grey water) yang dialirkan ke halaman rumah,dibentuk model U (luas permukaan 2,06 m2, debit 0,07 L/det). Tujuan pembuatan Ecotech Garden adalah mengolah air selokan (grey water) sekaligus membuat kesan dekoratif dalam bentuk taman hias air di halaman rumah.