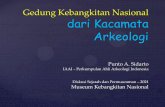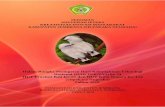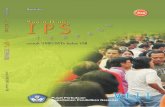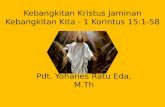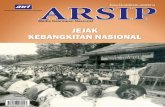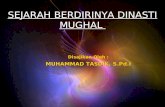KEBANGKITAN NASIONAL
-
Upload
ct-twinheart -
Category
Education
-
view
305 -
download
9
Transcript of KEBANGKITAN NASIONAL
KEBANGKITAN NASIONAL
Oleh : Siti Nurbayani, Arif, Parmadai, Mega, Dion
Disampaikan pada seminar Kebangkitan Nasional UNS
26 Mei 2011
Pengantar
Tatkala sejarah menyadarkan kita tentang perbedaan-perbedaan, ia sebetulnya telah
mengajarkan kebebasan,” ujar Francois Caaron profesor sejarah di Universitas Sorbone Paris,
karena prinsip nasionalisme mencakup unity, liberty dan equality (Persatuan, Kemerdekaan
dan persamaan).
Nasionalisme menurut Kohn dalam bukunya Nationalism : its Meaning and history
(1961:11), mengatakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu
harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Secara etimologis, kata nation berasal dari kata
bahasa Latin natio, yang berakar pada kata nascor 'saya lahir'. Pada masa Kekaisaran
Romawi, kata natio dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Kemudian, pada masa Abad
Pertengahan, kata nation digunakan sebagai nama kelompok pelajar asing di Universitas-
Universitas. Selanjutnya, pada masa Revolusi Perancis, Parlemen Revolusi Prancis menyebut
diri mereka sebagai assemblee nationale (Dewan Nasional) yang menunjuk kepada semua
kelas yang memiliki hak sama dalam berpolitik. Akhirnya, kata nation menjadi seperti
sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi
suatu negara.
Untuk lebih mengantarkan kita pada bentuk riil dari nasionalisme harusnya kita
mengacu pada konsep nasionalisme yang diungkapkan oleh Benedict Anderson dalam buku
versi terjemahan yang berjudul “Komunitas-komunitas Imajiner: renungan tentang asal-usul
dan penyebaran nasionalisme” penting pula disampaikan disini agar ada pemahaman yang
dapat disepakati bersama.
Benedict Anderson mensinyalir kurangnya kepedulian para pengkaji gerakan
kebangsaan terhadap rasa kebangsaan, rasa nasionalistis, perasaan pribadi dan kultural bahwa
seseorang dan orang lain tertentu adalah satu bangsa bahwa anda dan saya merasa sebagai
seorang indonesia, bahwa anda dan saya adalah kita. Bahwa orang-orang lain adalah mereka.
Padahal kenyataanya selama sebagai bangsa indonesia ini menurut Benedict Anderson,
hanyalah realitas imajiner. Ke-kita-an kita adalah komunitas imajiner yang kita kenal nama
Indonesia. Apa yang selama ini kita telan mentah sebagai “indonesia” seperti kata Bung
Karno, dari Sabang sampai Merauke sebagai mengejawantahkan rasa keindonesiaan kita,
adalah kesatuan wujud semata.
Istilah " Kebangkitan Nasional"
Istilah kebangkitan nasional dikemukakan oleh Perdana Menteri Hatta pada tahun
1948. Saat itu situasi politik di dalam negeri masih diwarnai perang kemerdekaan, di mana
gejolak politik begitu hebat. Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifudin pada bulan Februari
1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) dan melakukan berbagai provokasi yang
memancing reaksi dari partai lain seperti Masyumi, sehingga timbul konflik fisik. Selain itu,
akibat perjanjian Renville, tentara Siliwangi dan pemerintahan di Jawa Barat harus hijrah ke
Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia. Republik sudah berada di bawah ancaman Agresi
Militer II. Keadaan ekonomi begitu buruk, inflasi meningkat. Sementara itu, Van Mook sibuk
membentuk negara-negara federal seperti Negara Pasundan, NIT, dan lain-lain.
Melihat kondisi negara yang masih muda itu begitu mengkhawatirkan, Soewardi
Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan dr. Radjiman Wediodiningrat mengusulkan kepada
Presiden Soekarno. Perdana Menteri Hatta, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr Ali
Sastroamidjojo agar memperingati peristiwa berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei
1908, untuk mengingatkan semua orang bahwa persatuan kebangsaan itu sudah
diperjuangakan begitu lama. Usulan ini disetujui pemerintah RI. Maka dilaksanakanlah
peringatan "Kebangunan Nasional" yang ke-40 pada tahun 1948 itu. Upacara peringatan
dilangsungkan di "Presidenan", kediaman Presiden RI tahun 1946-1949, di Yogyakarta.
Hadir dalam acara yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara itu, para pimpinan partai politik
yang berseteru, dan juga tokoh tokoh-tokoh nasional lainnya. Setelah itu, diadakan iring-
iringan barisan keliling kota yang juga mengikutsertakan pasukan yang sedang hijrah. Sejak
itulah dilakukan peringatan "Hari Kebangkitan Nasional", kecuali tahun 1949 karena situasi
yang tidak memungkinkan.
Rasa nasionalisme yang dipertanyakan.
Indonesia merdeka, setidak-tidaknya dalam pengertian hukum internasional, dan kini
menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri (M.C. Ricklefs-2008). . Bangsa
Indonesia masih harus berjuang dalam perang kemerdekaan antara tahun 1945-1949, tatkala
penjajah menginginkan kembali jajahannya. Nasionalisme kita saat itu betul-betul diuji di
tengah gejolak politik dan politik devide et impera Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan
tahun 1949, nasionalisme bangsa masih terus diuji dengan munculnya gerakan separatis di
berbagai wilayah tanah air hingga akhirnya pada masa Demokrasi Terpimpin, masalah
nasionalisme diambil alih oleh negara. Nasionalisme politik pun digeser kembali ke
nasionalisme politik sekaligus kultural. Dan, berakhir pula situasi ini dengan terjadinya
tragedi nasional 30 September 1965.
Koalisi pemerintahan yang stabil susah dicapai. Peran Islam di Indonesia menjadi hal
yang rumit karena Soekarno lebih memilih negara sekuler (memisahkan antara kepentingan
agama dengan kepentingan negara) dengan berdasarkan Pancasila. Sementara beberapa
kelompok muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang mensyaratkan
umat Islam takluk kepada hukum Islam.
Pada akhir 1950 dan awal 1960, Soekarno bergerak lebih dekat dengan negara-negara
komunis di Asia dan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Komunis
adalah suatu paham yang bertolak belakang dengan Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
Sehingga pergerakan paham Komunis dalam perkembangannya di Indonesia menimbulkan
Konflik.
Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal
tersebut adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial
Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini
dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan
memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan
regional Asia. Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan
menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno
mengumumkan pengunduran diri Negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20
Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB
dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian
mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh
Inggris).
Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan
terhadap belahan barat pulau Nugini (Irian), dan mengizinkan langkah-langkah menuju
pemerintahan sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi
dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia gagal, dan
pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian
terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962
Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan
Indonesia yang menghasilkan Perjanjian New York pada Agustus 1962, dan Indonesia
mengambil alih kekuasaan terhadapa Irian Jaya pada 1 Mei 1963.
Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk
Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari
Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai
pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh
dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI.
Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta
tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil
alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian
dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah
terjadi di Jawa dan Bali.
Pada masa Orde Baru, Periode panjang pemerintahan otoriter telah berakibat pada
terjadinya proses perubahan sosial-ekonomi yang menghasilkan ketimpangan tajam antara
berbagai kelompok sosial wacana nasionalisme pun perlahan-lahan tergeser dengan
persoalan-persoalan modernisasi dan industrialisasi (pembangunan). Maka "nasionalisme
ekonomi" pun muncul ke permukaan. Nasionalisme ekonomi didorong oleh meningkatnya
rasa bangga indonesia atas prestasinya (M.C.Ricklefs,2008:610).
Sementara arus globalisasi, seakan memudarkan pula batas-batas "kebangsaan",
kecuali dalam soal batas wilayah dan kedaulatan negara. Kita pun seakan menjadi warga
dunia. Di samping itu, negara mengambil alih urusan nasionalisme, Menggunakan pancasila
sebagai alat Rezimnya atas nama "kepentingan nasional" dan "demi stabilitas nasional"
sehingga terjadilah apa yang disebut greedy state, negara betul-betul menguasai rakyat
hingga memori kolektif masyarakat pun dicampuri negara. Kemajuan banyak di jumpai pada
masa ini, baik sektor ekonomi, pendidikan, dan program yang lain misalnya keluarga
berencana. Masa ini sesungguhnya memberikan tentang kemungkinan-kemungkinan
indonesia masa depan jika saja pemerintah orde baru bukan pemerintah yang kejam, korup,
brutal dan hanya didominasai oleh satu orang. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hanya
beberapa permasalahan yang mengiringi perjalanan rezim orde baru. Masalah separatisme
yang diilhami rasa kesukuan dan agama muncul kembali. Aceh selama ini dalam keadan
tenang sejak masa kegiatan pemberontakan 1976-1982, namun pemberontakan kembali
muncul pada 1988. Pemberontakan menjadi serius pada tahun 1998, ketika pejuang GAM
menyerang pos-pos ABRI dan mengambil senjata. Timor-timur juga mulai muncul lagi
sebagai wilayah berbahaya bagi jakarta. Hingga 1989, provinsi itu tertutup bagi dunia luar
dan ABRI bebas berkeliaran disana, sebelum akhirnya provinsi itu di buka kembali. Secara
rutin dijumpai demonstrasi mahasiswa menentang soeharto dan korupsi rezimnya dalam
kampus-kampus. Pada tahun 1979, ketua dewan mahasiswa ITB berusia 25 tahun, Hery
Akhmadi, di penjara selama dua tahun karena menghina presiden, DPR dan MPR. Pada saat
vonis Hery sudah ditahan selama 1 tahun. Ketika kelas menengah indonesia mulai tidak
begitu toleran terhadap penyimpangan rezim Soeharto, dan ketika peningkatan rasa ke
islaman menuntut adanya keadilan dan moralitas yang lebih besar. Dalam kondisi penuh
tantangan ini, keluarga Soeharto dan kroni-kroninya semakin menggila dalam korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan mereka. Kemudian, krisis keuangan Asia memasukkan Indonesia
kedalam bencana ekonomi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk rakyat mendukung
pemerintahan pada tahun 1998, rezim Soeharto pun runtuh di tengah-tengah suasana yang
mirip dengan suasana kelahiranya di tahun 1965-1966, yaitu di tengah-tengah krisis ekonomi,
kerusuhan dan pertumpahan darah di jalan-jalan.
Ketika muncul upaya disintegrasi dan gerakan separatisme serta sekelumit
permasalahan yang kita hadapi sesungguhnya adalah karena persoalan pembangunan yang
tidak merata. 32 tahun dibawah kepemimpinan otoriter dan absolut, begitu besar kesenjangan
ekonomi pusat terjadi. Akibatnya warisan tersebut menjadi permasalahan yang sulit diatasi di
era reformasi.
Era reformasi yang seharusnya menawarkan demokrasi, menjanjikan kehidupan lebih
baik, karena dimungkinkannya setiap individu dan kelompok mengekspresikan aspirasinya
menjadi terkontaminasi oleh timbunan-timbunan ketidakpuasan yang terlalu dalam. Maka
kitapun menyaksikan banyaknya kerumunan-kerumunan marah yang justru dalam iklim
kebebasan ini menggunakan kesempatan untuk melampiaskan kemarahan dan tidak peduli
pada aturan yang tengah coba dibangun. Supremasi hukum yang diidamkan terasa semakin
sulit dicapai disaat hukum tak dihormati, hukum sekarang tidak lagi berpihak pada keadilan
dan kebenaran.
Ketika penegak hukum kehilangan kendali maka konflik vertikal dan horizontal
marak terjadi. Seperti halnya pada masalah pertikaian yang terjadi di berbagai daerah, tragedi
di Tual, Maluku, tragedi Sampit di Kalimantan dan aksi-aksi anarkis, banyak para elit politik
seperti tak peduli. Rakyat susah mencari keadilan di negerinya sendiri, korupsi yang
merajalela mulai dari hulu sampai hilir di segala bidang, dan pemberantasan nya yang tebang
pilih, pelanggaran HAM yang tidak bisa diselesaikan, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi,
penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap-
menyuap, dan lain-lain. Realita ini seakan menafikan cita-cita kebangsaan yang digaungkan
seabad yang lalu.
Banyak yang beranggapan bahwa nasionalisme sekarang ini semakin merosot, di
tengah isu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi yang semakin menggila. Kasus
Ambalat, beberapa waktu lalu, secara tiba-tiba menyeruakkan rasa nasionalisme kita, dengan
menyerukan slogan-slogan "Ganyang Malaysia!". Akhir-akhir ini, muncul lagi
"nasionalisme" itu, ketika lagu "Rasa Sayang-sayange" dan "Reog Ponorogo" diklaim sebagai
budaya negeri jiran itu. Kemudian ketika Tari Pendet dipakai sebagai icon dari iklan
pariwisata malaysia. Semangat "nasionalisme kultural dan politik" seakan muncul. Seluruh
elemen masyarakat bersatu menghadapi "ancaman" dari luar. Namun anehnya, perasaan atau
paham itu hanya muncul sesaat ketika peristiwa itu terjadi. Dalam kenyataannya kini, rasa
"nasionalisme kultural dan politik" itu tidak ada dalam kehidupan keseharian kita. Realita ini
seakan menafikan cita-cita kebangsaan yang digaungkan seabad yang lalu. Itulah potret
nasionalisme bangsa kita hari ini. Kini apa yang telah terjadi dengan seluruh cita-cita luhur
dan modal sosial yang telah kita miliki bersama?
Nampaknya, dalam perjalanan bangsa selama ini, terlalu banyak elemen bangsa, terutama
para elit politik, sadar atau tidak, telah banyak yang mengkhianati cita-cita luhur dan menyia-
nyiakan modal sosial yang telah dicoba dibangun dengan susah payah.
Refleksi Nasionalisme
1. BUDI UTOMO
Budi utomo merupakan suatu benih yang melahirkan gerakan nasionalis Indonesia.
Budi utomo telah sampai pada tingkat kesadaran yang fundamental (Van Niel, 1950).
Tanggal 20 mei 1908 yang merupakan kebangkitan nasional yang oleh Akira Nagazumi
disebut dengan “Fajar Nasionalisme Indonesia” (the down of Indonesian nasionalis). Konsep
kemajuan selaras untuk bangsa dan Negara cakupannya sangat luas yakni memajukan
pengajaran/pendidikan. Pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, kesenian dan
pengetahuan. Dari apa yang dilakukan Budi Utomo tampak bangkitnya kesadaran hidup
berbangsa dan bernegara (nasionalisme).
2. Sarekat Islam
Pada mulanya sarekat islam adalah perkumpulan para pedagang yang bernama
Sarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi Sarekat Islam didirikan oleh beberapa tokoh SDI
seperti H.O.S Cokroaminoto, Abdul Muis, dan H Agus Salim. Sarekat Islam berkembang
pesat karena bermotivasi agama islam yang dominan ada pada masyarakat saat itu.
Kecepatan tumbuhnya SI begaikan meteor dan meluas secara horizontal. SI
merupakan Organisasi masa pertama di Indonesia. Antara tahun 1917 sampai dengan 1920
sangat terasa pengaruhnya didalam politik Indonesia. Untuk menyebarkan propaganda
perjuangannya, Sarekat Islam menerbitkan surat kabar yang bernama Utusan Hindia.
3. Indische Partij
Tujuan Indische Partij adalah untuk membangun patriotisme semua Hindia Putra
terhadap tanah air. Konsep Hindia Putra adalah semua orang yang dilahirkan dan dibesarkan
bahkan dikebumikan di “Indonesia”, tanpa melihat suku, etnis, keturunan, agama, budaya.
4. Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik.
Pada tahun 1908 di Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische
Vereeniging. Pelopor pembentukan organisasi ini adalah Sutan Kasayangan Soripada dan
RM Noto Suroto. Para mahasiswa lain yang terlibat dalam organisasi ini adalah R.Pandji
Sosrokartono, Gondowinoto, Notodiningrat, Abdul Rivai, Radjiman Wediodipuro
(wediodiningrat) dan Brantel. Tujuan dibentuknya Indische Vereeniging adalah untuk
memajukan kepentingan berasama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia. Kedatangan
tokoh-tokoh Indische Partij seperti Cokro Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, sangat
mempengaruhi perkembangan Indische Vereeniging. Masuk kondisi “Hindia Bebas” dari
Belanda, dalam pembentukan Negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri.
Perasaan anti-kolonialisme semakin menonjol setelah ada seruan presiden Amerika Serikat
Woodrow Wilson tentang kebebasan dalam menentukan nasib sendiri pada Negara terjajah
(the right of self determination). Dalam upaya berfikir lebih jauh, organisasi ini memiliki
media komunikasi yang berupa majalah Hindia Poetra. Pada rapat umum bulan januari 1923,
Iwa Kusumasumantri sebagai ketua baru memberikan penjelasan bahwa organiasasi yang
sudah dibenahi ini mempunyai tiga asas pokok yang disebut juga Manifesto Politik.
5. Partai Nasional Indonesia
Pemberontakan PKI Pada tahun 1926 membangkitkan semangat untuk menyusun
kekuatan baru dalam menghadapi pemerintah kolonial belanda. Rapat pendirian partai ini
dihadiri Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mr Iskaq Tjokrodisuryo, Mr
Budiarto dan Mr Soenarjo. Pada awal berdirinya, PNI berkembang sangat pesat karena
didorong oleh faktor-faktor berikut:
a. Pergerakan yang ada lemah sehingga kurang bisa menggerakan masa
b. PKI sebagai partai masa telah dilarang
c. Propagandanya menarik dan mempunyai orator ulung yang bernama Ir soekarno.
Peranan PNI dalam pergerakan nasional Indonesia sangat besar. Menyadari perlunya
pernyataan segala potensi rakyat, PNI mempelopori berdirinya Pemufakatan Perhimpunan
Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI diikuti oleh PSII(Partai Sarekat Islam
Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, kaum Betawi, Indonesische Studi
Club, dan Algemenee Studi Club.
Nasionalisme dalam pemikiran kritis
Untuk dapat memahami Nasionalisme itu sendiri,sebaiknya kita mencoba melihat
nasionalisme dalam beberapa pemikiran-pemikiran kritis, yaitu :
Nasionalisme sebuah Perspektif dekonstruksi dalam postmodernisme
Gerakan dekontruksi yang mulai berkembang pada paruh abad keduapuluh
lahir sebagai penolakan terhadap doktrin-doktrin positivisme yang telah dominan
sejak Rene Descartes. Filsafat posmodernisme dan dekonstruksi telah digunakan oleh
ahli-ahli teori kritis untuk menegaskan bahwa posmodernisme dan dekontruksi adalah
suatu pemisahan dari tradisi artistik dan filosofis abad pencerahan. Mereka tandai
modernisme telah melakukan suatu sistem yang lebih besar dan universal dalam
estetika, etika dan ilmu pengetahuan. Filsafat posmodernisme dan dekontruksi
merupakan suatu revolusi terhadap rasionalitas dari modernisme. Mereka menolak
pikiran tentang kebenaran universal (universal truth) yang mencari metanarrative
atau grand theory. Mereka menolak otoritas yang secara implisit atau eksplisit
mendukung hak istimewa dari suatu teori atas teori yang lain. Mereka
menggantikannya dengan suatu titik pandang partial dan relativistik dengan
menekankan ketidak pastian dan dasar menengahi dalam pembangunan teori. Pemikir
posmodern dan dekontruksi belajar mengkontekstualisasi, mentoleransi relativismen
dan pluralisme (Helisus Sjamsudin, 2007 : 336 – 337). Secara teoritis posmodernisme
menawarkan intermediasi dari determinasi, perbedaan daripada persatuan dan
kompleksitas daripada simplifikasi (Ritzer, 2010 : 20).
Memahami Dekonstruksi menurut Prof Helius seperti melihat seorang tukang
reparasi membongkar arloji dan menyusunnya kembali. Teori Dekonstruksi
diperkenalkan oleh Jacques Derrida (1930-2004) pada tahun 1967 dan mulai
digunakan dalam seni dan sastra pada tahun 1970an (Muhadjir, 2001: 203).
Dekonstruksi merupakan gebrakan posmodernisme yang bersifat fungsionalis,
strukturalis, dan pragmatis. Dalam sudut pandang posmodernisme, karya seni tidak
dapat dilepaskan dari isu sosial dan politik serta menentang pemilahan antara seni
yang memiliki legitimasi dengan budaya populer. Dalam hal ini, maka pemaknaan
terkait erat dengan diskursus.
Dekontruksi menurut Deridda memang bukan sistem dan tidak mungkin
menyeretnya menjadi sistem namun mengingat dekonstruksi justru berlandaskan pada
hasrat untuk mengekspos kita terhadap keseluruhan yang lain, dan untuk membuka
diri terhadap berbagai kemungkinan-kemungkinan alternatif. Menurut teori
dekonstruksi yang didasarkan pada pandangan teori konflik, kajian realitas sosial
telah dijabarkan oleh Derrida dan Habermas dalam kajian dekonstruksi sosial. Kajian
dekonstruksi sosial menempatkan konstruksi sosial sebagai obyek yang
didekonstruksi. Lebih lanjut, Bungin (2007) menjelaskan pandangan Karl Heinrich
Marx (1818-1883) tentang realitas kehidupan sosial budaya masyarakat ditentukan
oleh pertentangan antara dua kelas (sesuai dengan pandangan teori konflik).
Demikian nasionalisme dalam kontek dekonstruksi dan postmodersm adalah
menghargai pluralisme atau kebinekaan dalam konteks persatuan dan kesatuan.
Menurut Oommen (2009 : 362) pluralisme bukanlah sebuah fakta, tetapi orientasi
nilai yang didasarkan pada keragaman atau heterogenitas. Di samping itu, pluralisme
sebagai nilai harus merujuk pada koeksistensi keragaman kelompok, rasial dan etnis.
Hal ini sebenarnya telah ditampilkan oleh para pejuang bangsa Indonesia sejak
dicetuskannya sumpah pemuda. Dari berbagai perkumpulan pemuda, seperti: Jong
Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks, Jong Ambon, Pemuda
Betawi, Sekar Rukun dan Pemuda Timor mereka telah berikrar mengakui berbahasa,
berbangsa dan bertumpah darah satu yaitu Indonesia. Bermula sejak Kongres Pemuda
I tahun 1926 yang dipimpin oleh Tabrani (saat itu masih berumur 24 tahun), sehingga
menjadikan momentum ini menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam
tumbuhnya identitas bangsa Indonesia. Kongres yang diikuti oleh pemuda dari
Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku dan daerah lainnya ini sudah berusah mewujudkan
tekad gerakan nasional. Sejak kongres pemuda Indonesia I, berbagai perkumpulan
pemuda yang bersifat kedaerahan mulai melebur kedalam gerakan yang bersifat
nasional. Menurut Leirissa yang dikutip oleh Tilaar (2007:173) bahwa gerakan
kedaerahan yang bersifat etnis ini berubah sebagai berikut:
1. Gerakan yang akhirnya bergabung dengan gerakan nasional;
2. Gerakan yang tetap mempertahankan identitasnya hanya mengambil simbol-
simbol gerakan nasional;
3. Gerakan yang tetap mempertahankan sifat identitas etnis saja.
Perubahan paradigma gerakan perjuangan anti kolonialisme sebenarnya sudah
jauh dimulai sebelum 1926, yaitu sejak 1908 (bangsa Indonesia memperingatinya
sebagai hari kebangkitan nasional) yaitu saat lahirnya Budi Oetomo. Paradigma
gerakan yang bersifat etnis kedaerah dan menggunakan kekerasan dalam menggapai
cita-cita kemerdekaan dirubah menjadi gerakan yang bersifat organisasi dan bersifat
nasionalis.
Melihat perubahan konsep dari etnitas menjadi nasionalitas berarti melihat
dekonstruksi dari otonomi kebudayaan kearah kesadaran diri yang lebih terorganisir
dalam kerangka perjuangan melalui jalur politik. Nasionalisme Indonesia dibangun
dan diproduksi atas dasar nasionalisme politik, yaitu adanya kebutuhan bersama
masyarakat yang kemudian dibingkai dalam kesadaran keindonesiaan, dalam rangka
melepaskan diri dari kolonialisme. Pengertian masyarakat, tentu saja pada awalnya
hanya berarti sekelompok elit terpelajar, yang dengan kemampuan dwibahasa
(Indonesia-Belanda), akses pergaulan dan informasi internasional, serta pemahaman
nasionalisme ala Eropa, kemudian mencerahkan dan membangun kesadaran
nasionalitas masyarakat secara umum. Tilaar (2007:26) menyebutnya sebagai identitas
yang terfragmentasi dan bekal identitas etnis menuju kepada kesatuan nasional yang
lebih terarah dan terintegrasi. Bangsa yang menggambarkan adanya suatu imagined
communities menemukan kembali sejarahnya yang mengikat berbagai suku bangsa di
dalam satu kesatuan, sehingga menimbulkan kebanggaan dan loyalitas nasional.
Dalam proses ini sebenarnya terjadi dekonstruksi terhadap konstruksi
pemahaman primordial dari kelompok atau etnis sehingga timbul pemikiran
nasionalis. Dekonstruksi dari karya Derrida ini menciptakan nilai penting pada
kemampuannya untuk membuat para pemuda saat itu melihat jejak dari apa yang telah
terabaikan dari konsep dan deskripsi karena kelemahan yang ada sehingga menjadi
satu entitas yang menjadi kesatuan, yang mengakibatkan mereka tidak mustahil untuk
ada dan eksis. Dekonstruksi mengajarkan seseorang untuk memikirkan dan
merenungkan lagi dasar, praktik, konsep, dan nilai yang ada/dimiliki. Apapun itu,
setelah kita menggunakan dekonstruksi, pandangan yang ada tidak akan menjadi
terlalu dogmatis atau fanatis, bahkan akan menjadi lebih murni dan jernih. Tilaar
(2007:75) menjelaskan peran besar etnis di dalam tumbuhnya rasa nasionalisme dari
bangsa Indonesia dalam menjadi empat yaitu,
1. Manusia Indonesia pertama-tama adalah milik kelompoknya atau milik etnisnya.
Nilai-nilai primordial telah mengikat kelompok itu menjadi satu kesatuan. Inilah
nilai-nilai pada tataran horizontal pada tingkat primordial yaitu rasa persatuan
yang sangat jelas kita temukan di dalam setiap kelompok etnis.
2. Dalam perkembangan rasa persatuan kita lihat peranan komunitas agama misalnya
yang terlihat pada organisasi Muahammadiyah dan NU yang telah
menyumbangkan peranan yang besar sekali dalam pengembangan demokrasai dan
melahirkan para pemimpin berwawasan Nasional.
3. Mulai berkembang identitas kelompok berupa adat-istiadat, simbol-simbol ideal
maupun yang fisik seperti pakaian adat atau pun berjnis-jenis makanan daerah,
semuanya melekat sebagai identitas etnis.
4. Berkembangnya emosi primordial yang kemudian berkembang menjadi emosi
nasionalisme terutama dalam menghadapi perubahan global.
Dengan demikian Sumpah pemuda merupakan tonggak sejarah yang
monumental. Ia mengandung ilham kepatriotan dan kepahlawanan dan sekaligus
merupakan awal babak baru dalam sejarah pergerakan dan perjuangan nasional yang
mengatasi berbagai kemajemukan dan keaneka ragaman yang ada di bumi nusantara
ini. Sumpah pemuda membangkitkan kesadaran kebangsaan yang makin meluas dan
dihayati oleh bangsa kita, terutama dikalangan generasi muda saat itu (Ridwan Tasa,
2009 : 113). Namun pada saat itu cenderung hanya menyentuh ranah politik saja.
Sementara di era globalisasi ini nasionalisme didekontruksikan tidak hanya dalam
ranah politik, tetapi menyentuh ranah sosial, budaya dan ekonomi. Karena itu
meskipun kita sangat menghargai pluralisme politik, budaya, agama, sosial namun
tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Perbedaan keyakinan, pandangan politik, klompok sosial semuanya merupakan
keunikan dan keberagaman yang patut kita syukuri bersama. Melalui keberagaman
itulah akan diperoleh hasil yang lebih nyata dan sempurna.
Pada akhirnya kita harus memutuskan rasa kebangsaan kita untuk dibangkitkan
kembali. Namun bukan nasionalisme dalam bentuk awalnya seabad yang lalu. Nasionalisme
yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi
semua permasalahan di atas, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, berani melawan
kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan lain-lain. Bila tidak bisa, artinya kita tidak
bisa lagi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran total.
Pemuda dan 4 pilar Bangsa
Dalam perspektif diatas memberikan gambaran tentang nasionalisme. Tetapi Dari
permasalahan yang kita hadapi hendaknya kita sebagai kaum intelek (pemuda) harus bisa
memberikan sebuah perubahan, kita harus sungguh-sungguh dalam mempersiapkan dan
meningkatkan kualitas diri agar mampu membangkitkan kembali nasionalisme Indonesia.
Ketika kualitas diri kita sebagai pemuda meningkat dan kajian ilmiah semakin menguat, kita
akan mampu menjadi think tank bagi pergerakan nasionalisme di Indonesia. Presiden pertama
kita, Ir.Soekarno pernah mengatakan “beri aku sepuluh pemuda maka akan kugoncangkan
dunia”. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana besarnya pengaruh pemuda dalam
menentukan masa depan bangsa. Bukan tanpa alasan, dalam sejarah perjuangan bangsa
indonesia, pemuda selalu menempati peran yang sangat strategis dari setiap peristiwa penting
yang terjadi. Bahkan dikatakan bahwa pemuda menjadi tulanmg punggung penjajahan ketika
itu. Peran tetsebut juga tetap disandang oleh pemuda hingga saat ini, selain sebagai
pengontrol independent terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan
penguasa, pemuda indonesia juga aktif melakukan kritik, hingga mengganti pemerintahan,
apabila pemerintahan tersebut tidak lagi berpihak pada masyarakat.Tentunya Nasionalisme
yang sekarang berbeda dengan Nasionalisme seabad yang lalu, serta peran pemuda saat ini
sedikit berbeda dengan peran dan tanggung jawab pemuda pada masa revolusi kemerdekaan.
Saat ini pemuda harus mampu melakukan transformasi atau perubahan dalam berbagai
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
dengan giat belajar dan mengedepankan jiwa patriotik untuk membangun masyarakat, bangsa
dan negara. Pemuda harus mampu menjawab segala tantangan zaman yang muncul di
hadapanya. Pemuda jangan sampai tergerus oleh oleh kerusakan zaman yang dibawa oleh
ideologi-ideologi yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Pemuda harus ampu
bersinergi demgan seluruh elemen lain untuk mempertahankan dan membawa INDONESIA
menuju kearah yang lebih baik. Dengan apa kita bersinergi? Ya, dengan Pancasila, sebagai
falsafah hidup bangsa Indonesia(way of life), tentunya yang di fahami secara kultural dan tak
lagi menjadikannya sebagai alat kekuasaan semata, Bhineka Tunggal Ika, sebagai pemersatu
dari keberagaman Indonesia, UUD 45, sebagai landasan dan sumber hukum bangsa
Indonesia, dan Pendikan Berkarakter, sebagai alat mengembangkan jiwa patriotisme,
kesadaran berbangsa dan bernegara serta membentuk moral bangsa yang tangguh. Selamat
Hari Kebangkitan Nasional (JANGAN TERLENA SESUNGGUHNYA KITA DALAM
BENCANA).
DAFTAR PUSTAKA
Ricklefs, M.C., 2008,Sejarah Indonesia Modern
Asvi Warman Adam, 2007, seabad kontrovesi sejarah, Ombak, Yogyakarta
www.wikipedia.com