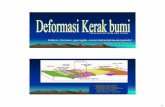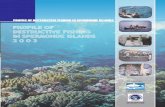KAJIAN KEPADATAN ZOOXANTHELLAE DI DALAM JARINGAN … · dengan lempengan tipis yang terbuat dari ....
Transcript of KAJIAN KEPADATAN ZOOXANTHELLAE DI DALAM JARINGAN … · dengan lempengan tipis yang terbuat dari ....

KAJIAN KEPADATAN ZOOXANTHELLAE DI DALAM JARINGAN POLIP KARANG PADA TINGKAT
EUTROFIKASI YANG BERBEDA DI KEPULAUAN SPERMONDE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN
ISMAIL
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
2010

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kajian kepadatan zooxanthellae pada tingkat eutrofikasi yang berbeda di perairan kepulauan Spermonde kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan adalah karya saya dengan arahan pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.
Bogor, September 2010
Ismail NIM C252080394

RINGKASAN ISMAIL. Kajian Kepadatan Zooxanthellae di dalam Jaringan Karang pada Tingkat Eutrofikasi yang Berbeda di Perairan Kepulauan Spermonde Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh ARIO DAMAR dan
JAMALUDDIN JOMPA.
Fluktuasi kepadatan zooxanthellae sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kondisi perairan adalah masukan nutrien, terutama nitrat dan fosfat. Masukan nutrien ke dalam perairan akan memicu pertumbuhan alga termasuk meningkatkan kepadatan zooxanthellae.
Di sisi lain zooxanthellae bersama inangnya karang (polip) tumbuh normal di kondisi perairan yang miskin nutrien (oligotrofik), dan justru pada kondisi perairan yang banyak nutrien (eutrofik) menyebabkan karang tidak berkembang baik. Sebagian besar sumber nutrien zooxanthellae disuplai dari inangnya, selebihnya diambil dari lingkungan,
Kajian kepadatan zooxanthellae di dalam jaringan karang pada kedalaman 2-3 meter di 3 lokasi berbeda yaitu pulau Laelae, pulau Barrang Lompo dan pulau Lanyukang bertujuan untuk mengkaji fluktuasi kepadatan zooxanthellae di perairan yang terkena masukan nutrien (eutrofikasi) dari daratan utama, sedangkan manfaat penelitian ini akan menambah informasi bagi pengelolaan terumbu karang di masa yang akan datang khususnya di Kepulauan spermonde.
Dalam penelitian ini, parameter yang dipakai untuk menilai tingkat eutrofikasi perairan adalah berdasarkan konsentrasi nitrat, fosfat dan total padatan tersuspensi (TSS). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menghitung kepadatan zooxanthellae yaitu dengan cara permukaan sampel karang dikerik dengan lempengan tipis yang terbuat dari stainless, dan hasil kerikan ini disimpan dalam formalin 4%, lalu digerus di dalam cawan petri sampai halus, kemudian diambil satu tetes dan dimasukkan perlahan-lahan ke haemocytometer, lalu dihitung di bawah mikroskop, sedangkan bekas kerikan sampel karang dihitung luasnya.
Berdasarkan hasil perhitungan, kisaran kepadatan zooxanthellae terendah di pulau Laelae 1,53 x 105 sel/cm2, tertinggi 2,76 x 105 sel/cm2 , di pulau Barrang Lompo terendah 2,98 x 105 sel/cm2, tertinggi 6,45 x 105 sel/cm2, dan pulau Lanyukang terendah 4,83 x105 sel/cm2, tertinggi 7,89 x 105 sel/cm2
Adanya perbedaan kepadatan zooxhantellae antar pulau pada kedalaman 2-3 meter diduga kuat disebabkan oleh faktor sumber masukan nutrien yang berbeda antar pulau dimana masukan nutrien pulau Laelae di pengaruhi dari runoff kota Makassar dan pulau Lanyukang dipengaruhi masukan nutrien dari resuspensi dan upwelling yang terjadi di Selat Makassar. sedangkan pulau Barrang Lompo relativ tidak dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, runoff dan upwelling.
. Sedangkan dengan statistik ANOVA satu faktor diperoleh Fhitung (9,34) >Ftabel (5,14) atau p<0,05, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kepadatan zooxhantellae antar pulau.
Kata kunci: Kepulauan spermonde, daratan utama, kepadatan zooxanthellae,
nutrien,runoff, upwelling.

KAJIAN KEPADATAN ZOOXANTHELLAE DI DALAM JARINGAN POLIP KARANG PADA TINGKAT EUTROFIKASI
YANG BERBEDA DI KEPULAUAN SPERMONDE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
ISMAIL
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR
2010

Judul Tesis : Kajian Kepadatan Zooxanthellae pada Tingkat Eutrofikasi
yang Berbeda di Perairan Kepulauan Spermonde Kota Makassar Provinsi Sulawesi –Selatan.
Nama Mahasiswa : Ismail
Nomor Pokok : C 252080394
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan (SPL)
Disetujui Komisi Pembimbing:
Dr. Ir. Ario Damar, M.Si Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc Ketua Anggota
Diketahui: Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB
Prof. Dr. Ir. Mennofatria Boer, DEA
Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S
Tanggal Ujian : 24 September 2010
Tanggal Lulus :

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis : Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc

PRAKATA
Puji syukur hanya kepada Allah SWT karena atas segala karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Judul dari tesis ini adalah Kajian Kepadatan Zooxanthella di dalam Jaringan Karang pada Tingkat Eutrofikasi yang Berbeda di Perairan Kepulauan Spermonde Kota Makassar Provinsi Sulawesi –Selatan. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang kepada:
1. Bapak Dr. Ir. Ario Damar, M.Si dan Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku ketua dan anggota komisi pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penulisasn tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mennofatria Boer, DEA sebagai ketua Program Studi beserta staf pengajar dan staf administrasi atas bimbingan dan bantuan selama studi penulis di SPL-IPB
3. Direktur PMO COREMAP II Ditjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya atas beasiswa yang diberikan kepada penulis
4. Ayahanda H. Abdullah Umum dan Ibunda Hj. Mantasiah Dg Baji, yang telah membesarkan dan membimbing dari kecil hingga sampai sekarang serta bapak mertua (H. Areif Makkadara) Ibu mertua (Hj.Darmawan) atas dukungan dan doanya
5. Mantan Direktur Akademi Perikanan Sorong (APSOR) yang member izin untuk melanjutkan studi Strata Dua (S2), para pembantu direktur APSOR.
6. Para dosen staf APSOR . 7. Teristimewa untuk istriku Irjayanti A. SE dan anak-anakku tersayang
Muh rizky, shafa S.Ginaya, Israini. Terimakasih atas pengertian, kasih sayang dan doa yang kalian berikan.
8. Drs. Dirham Kambe, MM sekeluarga dan bapak Jasman dan Andi Lela beserta keluarga atas dukungan moril dan material selama penulis mengukuti studi program pasca sarjana di IPB.
9. Teman-teman sandwich program 2008 seperti; Imelda, Yudha, Leri Barnabas, Heri, Iceng, Nita dan lainnya, yang tidak sempat disebutkan di sini atas dukungan dan bantuannya serta saran dan kritikannya.
Akhirnya dalam segala keterbatasan, penulis berharap kiranya tulisan ini
dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
Bogor, September 2010
Ismail

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Makassar pada tanggal 23 Januari 1973 dari Ayah
Abdullah Umum dan Ibu Mantasiah Dg. Baji. Penulis merupakan putra pertama dari empat bersaudara.
Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun 1998. Semenjak Tahun 2001 Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Akademi Perikanan Sorong, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM-KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pada tahun 2008 penulis diberi kesempatan mengikuti program magister sains (S-2) Sandwich Program kerja sama antara Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB Bogor dan The Tyukyus University, Okinawa, Jepang dengan bantuan beasiswa dari COREMAP II-World Bank.

xix
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL………………………………………………………… xxi
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………….. xxiii
DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………………….. xxv
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ……..………………………………………… 1 1.2. Tujuan Penelitian ……………………………………………… 3 1.3. Manfaat Penelitian ……………………………………………… 3 1.4. Rumusan Masalah ……………………………………………… 3
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tingkat Kerusakan Terumbu Karang …………………………… 5 2.2. Terbentuknya Endosimbiosis …….……………………………… 5 2.3. Hewan Karang2.4. Zooxanth
Sebagai Host (Inang) …………………………… 6 e
2.5. Sturuktur Karang dan Letak Zooxanthellae ……………………… 6 llae sebagai Simbion Alga ……………………………. 6
2.6. Zooxanthellae dan Bentuk Simbiosisnya dengan Karang……….. 7 2.7. Peran Zooxanthellae Dalam Polip Karang ……………………. 8 2.8. Kepadatan Zooxanthellae ………………… 10 2.9. Variasi Pola Makan Karang ……………………. 10 2.10. Faktor lingkungan dan Zooxanthellae ………………………….. 11
2.10.1. Suhu ……………………………………………………… 11 2.10.2. Salinitas ………………………………………………… 11 2.10.3. Total Suspended Solid (TSS) …………………………… 12 2.10.4. Kecerahan dan Cahaya ………………………………… 12
2.11 Fosfat …………………………………………………………… 13 2.12 Nutrien dan Kehidupan Karang ……………………………….. 13 2.13 Eutrofikasi dan Terumbu Karang 14 2.14 Kepadatan zooxanthellae dan Bioindikator …………………….. 16
3. METODE PENELITIAN
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian …………………………………… 17 3.2. Alat dan Bahan Penelitian ………………………………………. 17 3.3. Metode Pengambilan Data ………………………………………. 18
3.3.1. Data Sampel Karang ……………………………………. 18

XX
3.3.2. Data Parameter Fisika, Kimia, Biologi Perairan ………… 18 3.3.3. Data Kepadatan Zooxanthellae ………………………….. 19
3.4. Analisis Data …………………………………………………….. 19 3.4.1. Perhitungan Kelimpahan Fitolankton……………………. 19 3.4.2. Perhitungan Kepadatan Zooxanthellae………………………. 20 3.4.3. Perhitungan Kecerahan …………………………………… 20 3.4.4. Analisis Kepadatan Zooxanthellae dan Kelimpahan
Fitoplankton …………………………………………................ 21
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Kepulauan Spermonde ………………………. 23 4.1.1. Pulau Laelae …………………………………………….. 24 4.1.2. Pulau Barrang Lompo …………………………………… 25 4.1.3. Pulau Lanyukang ………………………………………… 26
4.2. Kondisi Perairan Pulau Laelae, Pulau Barang Lompo dan Pulau Lanyukang …………………………………………….. 27 4.2.1. Total Suspended Solid (TSS) ………………………….. 27 4.2.2. Nitrat …………………………………………………… 30 4.2.3. Ortofosfat ……………………………………………….. 31
4.3. Jenis dan Kelimpahan Fitoplankton ……………………………… 32 4.4. Keterkaitan Fitoplankton dengan Kondisi Perairan………………. 35 4.5. Kepadatan zooxanthellae Nutrien ………………………………… 37 4.6. Total Suspended Solid (TSS) dan Kepadatan Zooxanthellae …… 41 4.7. Keterkaitan Kepadatan zooxanthellae dan Kelimpahaan
Fitoplankton 4.8. Kepadatan Zooxanthellae dan Pengelolaan Terumbu Karang …… 43
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan ………………………………………………………. 47 5.2. Saran……………………………………………………………… 47
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………. 49
LAMPIRAN …………………………………………………………. 55

xxi
DAFTAR TABEL
Halaman
1 Klasifikasi Tingkat Pencemaran Berdasarkan Kadar TSS Menter Lingkungan Nomor 51 Tahun 2004. ……………………………………. 12
2 Baku Mutu air laut untuk biota laut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004……………………………… 14
3 Posisi dan Jarak Kepulauan Spermonde dari Daratan Utama (Mainland) Kota Makassar …..………………………………………… 21
4 Parameter kwalitas perairan Pulau Laelae Survei Tahun 2005…………… 25
5 Kondisi Parameter Oseanografi Pulau Barrang Lompo Tahun 2005 …… 26
6 Kondisi Parameter Perairan Pulau Laelae, Barrang Lompo dan Lanyukang Kota Makassar ……………………………………………… 27
7 Jenis dan Kepadatan Fitoplankton di perairan Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang …………………………. 33
8 Kriteria kesuburan berdasarkan N dan P serta nilai biomas dan produktifitas primer fitoplankton ………………………………….. 33
9 Kriteria Kesuburan Berdasarkan N dan P serta Nilai Biomas dan Produktivitas Primer Fitoplankton ……………………………………… 35
10 Kriteria Kesuburan Perairan Menurut Joshimura in Liaw 1969 …..…….. 33
11 Kepadatan zooxanthellae pada lokasi penelitian di pulau Laelae Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang …………………. 36

xxiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1 Potongan melintang Anemone dan zooxanthella dalam jaringan gastrodermis
2 Peta Lokasi Penelitian di kepulauan Spermonde ………………………. 17
…………………………………………… 7
3 Foto Pulau Laelae Kota Makassar ……………………………………… 24
4 Foto Pulau Barrang Lompo Kota Makassar……………………………… 25
5 Konsentrasi TSS (mg/l) di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan pulau Lanyukang ………………………………………………………… 28
6 Konsentras Nitrat di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang…………………………………………………………. 30
7 Konsentrasi Ortofosfat di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang ……………………………………………………. 32
9 Jenis dan Kepadatan Fitoplankton di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo, dan Pulau Lanyukang …………………………. 34
10 Jenis Karang dan Kepadatan zooxanthellae di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang ……………………. 39
11 Kepadatan zooxanthellae dan Kelimpahan Fitoplankton di Pulau Lae-lae Pulau Barrang Lompo dan Pulau Punyukang …………………. 42
12 Kepadatan zooxanthellae dan kandungan nutrien perairan. …………….. 43

xxv
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
1 Data dan perhitungan kepadatan zooxanthellae ………………………… 50
2 Data dan perhitungan kelimpahan fitoplankton ………………………… 52
3 Perhitungan analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae . Acropora appressa antar pulau ………………………………………. 53
4 Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae
pada pulau Laelae ……………………………………………………… 54
5 Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae
pada pulau Barrang Lompo …………………………………………... 55
6 Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae
pada pulau Lanyukang ………………………………………………… 56

1
1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ekosistem terumbu karang adalah sumberdaya yang mudah terserang oleh
berbagai gangguan. Hal ini disebabkan karena hewan karang hermatifik
pembangun terumbu bersifat sesil di mana tidak dapat menghindari gangguan
atau ancaman dari luar. Secara umum, sumber ancaman terumbu karang berasal
dari bencana alam seperti badai, tsunami, gempa dan berasal dari aktivitas
manusia seperti penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, polusi, dan
pembangunan wilayah pesisir yang tanpa mempertimbangkan daya dukung
sumberdaya alam.
Tingginya pembangunan wilayah pesisir di daratan tidak dapat dihindari,
memberi dampak bagi ekosistem perairan termasuk ekosistem terumbu karang.
Hampir 60% kerusakan karang dunia disebabkan oleh aktifitas manusia (Bryant at
al. 1998 in Glick 1999).
Ekosistem terumbu karang adalah suatu habitat di laut yang penting artinya
ditinjau dari berbagai hal, salah satunya diantaranya adalah segi biologi bahwa
keanekaragaman biota laut yang tinggi di perairan tropis ditemukan di dalam
ekosistem ini. Hal ini dikarenakan terumbu karang dapat berfungsi sebagai tempat
hidup dan berlindung, tempat mencari makan dan mencari mangsa, tempat
memijah dan berkembangbiak serta sebagai daerah asuhan bagi beragam biota
laut. Dengan demikian terumbu karang disebut sebagai gudang asuhan bagi
beragam biota dan rumah bagi berbagai jenis kehidupan di laut (Tomascik 1991).
Kegiatan manusia secara langsung dapat menyebabkan kematian di terumbu
melalui penggalian dan pencemaran (Nybakken 1988). Berdasarkan analisis
Burke et al. (2002) bahwa 25% kerusakan terumbu karang diakibatkan oleh
pembangunan pesisir, 7% diakibatkan oleh pencemaran, 21% diakibatkan oleh
sedimentasi, 64% akibat penangkapan yang berlebihan, 54% akibat penangkapan
ikan dengan melakukan pengrusakan, dan 18% diakibatkan oleh pemutihan
terumbu karang. Tingginya ancaman terhadap ekosistem terumbu karang baik
secara anthropogenic maupun secara alamiah dikarenakan sifat sessil dari karang
di mana mereka tidak mampu menghindar jika ada tekanan buruk dari
lingkungan.

2
Zooxanthellae adalah salah satu biota yang hidup di dalam ekosistem
terumbu karang. Sebagian besar zooxanthellae hidup bersimbiosis dengan karang
dan beberapa hewan invertebrata, sebagian lagi hidup secara bebas. Biota ini
mempunyai peranan yang sangat penting di dalam ekosistem terumbu karang
sebagai salah satu komponen pemasok energi dan nutrisi bagi hewan inangnya
(Leletkin 2000b)
Zooxanthellae tergolong dalam alga bersel satu yaitu anggota dinoflagellata,
mengandung beberapa pigmen fotosintesis dan hidup di dalam jaringan
endodermis polip, dan aktif melakukan fotosintesis memproduksi makanan bagi
hewan karang (Nybakken 1988). Selain itu zooxanthellae berperan di dalam
proses kalsifikasi dan pembentukan skeleton atau rangka karang (Goreau 1959;
Nontji 1992) dengan demikian zooxanthellae berperan dalam pembentukan
terumbu.
Bentuk simbiosis antara karang dengan zooxanthellae adalah simbiosis
mutualisme di mana zooxanthellae memperoleh perlindungan, karbon dioksida
dan beberapa senyawa anorganik dari inangnya, sedangkan karang memperoleh
oksigen dan senyawa organik dari hasil fotosintesis zooxanthellae (Benson et al.
1978). Hubungan zooxanthellae dengan karang demikian eratnya sangat
mempengaruhi metabolisme, pola warna, pertumbuhan dan sebaran vertikal
karang (Goreau 1959).
Dari kajian lain seperti dilakukan oleh Suharsono dan Kiswara (1984)
bahwa pada saat karang mengalami tekanan ditemukan adanya indikasi pelepasan
zooxanthellae. Pada kondisi dilepaskannya zooxanthellae maka akan dapat
ditemukan adanya perbedaan signifikan rasio khlorophyl a : khlorophyl c serta
adanya shock protein sebagaimana diinformasikan oleh Nganro (1992) pada biota
simbion soft coral. Di samping itu, proses relokasi zooxanthellae dalam jaringan
karang akan berbeda pembelahan mitotic indeks pada kondisi alamiah maupun
kondisi tertekan (Nganro 1992).
Eutrofikasi merupakan salah satu ancaman ekosistem terumbu karang.
Eutrofikasi adalah proses peningkatan laju input bahan organik utamanya nitrogen
dan fosfor ke sebuah perairan. Proses ini adalah penyuburan perairan secara
berlebih yang disebabkan oleh masukan bahan organik. Salah satu akibat dari

3
peningkatan bahan organik ini adalah terjadinya ledakan fitoplankton, yaitu
fenomena populasi fitoplankton tumbuh secara cepat dan dalam jumlah yang
sangat besar yang disebabkan oleh tersedianya unsur hara dalam jumlah besar.
Walaupun unsur hara (nutrien) sangat penting dalam suatu ekosistem
terutama sebagai sumber penyusunan bahan organik oleh produsen primer, tetapi
peningkatan unsur hara pada ekosistem terumbu karang justru dapat berpengaruh
negatif terhadap perkembangan ekosistem terumbu karang karena ditutupi oleh
kelimpahan alga yang menyebabkan kematian pada karang (Jompa & Cook
2002).
Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka kajian kepadatan
zooxanthellae pada tingkat eutrofikasi berbeda perlu diteliti sebagai salah satu
penilaian kondisi ekosistem terumbu karang guna mendukung pengelolaan
terumbu karang yang berkelanjutan,
1.2 Tujuan
Untuk mengkaji kepadatan zooxanthellae pada jaringan polip karang di
lokasi perairan yang berbeda tingkat eutrofikasinya di Kepulauan Spermonde.
dalam hal ini Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo, dan Pulau Lanyukang.
1.3 Manfaat
• Dapat dipertimbangkan sebagai kriteria tambahan dalam menilai kondisi
ekosistem terumbu karang di masa yang akan datang.
• Sebagai informasi penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam
menyusun indeks/tingkatan ancaman kualitas ekosistem karang.
1.4 Rumusan Masalah
Unsur hara (nutrien) sangat penting dalam suatu ekosistem terutama sebagai
sumber penyusunan bahan organik oleh produser primer, akan tetapi peningkatan
unsur hara pada ekosistem terumbu karang dinilai justru dapat berpengaruh
negatif terhadap perkembangan ekosistem ini. Hal ini bisa dilihat dari kenyataan
bahwa terumbu karang justru berkembang dengan baik pada daerah yang relatif
jauh dari sumber unsur hara dan sebaliknya tidak berkembang pada daerah yang
mendapat suplai unsur hara yang tinggi. Adanya siklus nutrien yang efektif dalam

4
ekosistem terumbu karang merupakan kunci utama tingginya produktifitas
ekosistem ini walaupun jauh dari sumber nutrien.
Pengaruh eutrofikasi tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan
kelimpahan alga makro sebagai pesaing utama hewan karang, akan tetapi juga
secara langsung berpengaruh negatif terhadap fisiologi dan perkembangan hewan
karang tersebut, misalnya terhadap perkembangan embrio dan planula karang
(Tomascik & Sander 1987 in Thamrin 2006). Dampak lain yang juga bisa timbul
adalah meningkatnya bioerosi akibat perubahan komunitas ekosistem terumbu
karang (Hallock 1988, Rose, Risk 1985, Hallock et al. 1988 in Riks, Sammarco,
Edinger 1995), sisi lain bahwa meningkatnya unsur hara akan mampu mencegah
pemutihan karang dan mempertahankan zooxanthellae di dalam inangnya
karena tersedia unsur hara di dalam inang dan di lingkungan luar (Hidaka &
Miyagi 1999).
• Apakah ada perbedaan kepadatan zooxanthellae pada polip karang
berdasarkan tingkat eutrofikasi suatu perairan?
Dari uraian tersebut di atas maka timbul pertanyaan sebagai berikut;
• Apakah tingkat kepadatan zooxanthellae merupakan indikasi laju perubahan
tingkat eutrofikasi suatu perairan?

5
2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tingkat Kerusakan Terumbu Karang
Ancaman terumbu karang saat ini diestimasi hampir mencapai 60% dari
seluruh terumbu karang dunia adalah disebabkan oleh aktifitas manusia seperti
pembangunan di wilayah pesisir, pencemaran dan praktek penangkapan ikan
yang tidak ramah lingkungan (Bryant et al. 1998). Menurut Nybakken (1988)
sumber terbesar penyebab kerusakan terumbu karang adalah badai tropik yang
hebat, contohnya topan atau angin puyuh yang kuat ketika melalui suatu wilayah
terumbu sering merusak daerah yang luas di terumbu karang. Sumber kedua
terbesar yang menyebabkan kematian terumbu karang adalah ledakan Acanthaster
plancii (bintang bulu seribu) akibat adanya kegiatan pengerukan dan beberapa
bahan kimia (pestisida) membuka ruang baru bagi Acanthaster plancii muda,
ledakan populasi juga diakibatkan oleh kegiatan manusia yang memindahkan
predator utama bulu seribu yaitu Charonia tritonis untuk diambil cangkangnya
(Nybakken 1988). Kegiatan manusia secara langsung dapat menyebabkan bencana
kematian di terumbu melalui penggalian dan pencemaran (Nybakken 1988).
Terjadinya degradasi terumbu karang seperti pemutihan karang (bleaching)
sudah disugesti sebagai respon fisiologi karang untuk menduga tekanan
lingkungan (Brown 1988 in Jones 1997). Karang mendapat keuntungan dari
zooxanthellae berupa pewarnaan dari pigmen fotosintesis. Istilah bleaching
digunakan untuk menjelaskan perubahan warna karang menjadi putih yang diikuti
oleh penurunan zooxanthellae pada jaringan karang (Yonge, Nicholls 1931 in
Jones 1997), kemudian berdampak pada penurunan suplai nutrisi dan energi ke
polip karang. Selain itu pada pemutihan karang ditemukan juga adanya perbedaan
signifikan rasio klorofil dan relokasi zooxanthellae dalam jaringan karang
sehingga akan berbeda pembelahan sel pada kondisi alamiah maupun tertekan
(Nganro 1992).
2.2 Terbentuknya Endosimbiosis
Proses terbentuknya simbiosis atau yang dikenal dengan endosimbiosis ini
mengundang perdebatan sejak awal, yakni apakah terbentuknya endosimbiosis
sejak anakan karang (planula) mulai dilepaskan oleh induknya atau melalui

6
infeksi dari lepasan planula yang keluar tanpa pembekalan (Veron 1995). Apabila
teori pertama yang terjadi maka bagaimanapun juga awal evolusinya akan
mengalami proses infeksi yang kemudian secara turun temurun mengalami proses
pembekalan sebagaimana teori pertama diterima kebenarannya. Di sini tidak
memperdebatkan keduanya, namun lebih ditekankan bahwa pada kenyataannya
terdapat endosimbiosis dengan perannya yang besar dalam mekanisme kehidupan
fungsional binatang karang.
2.3 Hewan Karang sebagai Host (Inang)
2.4 Zooxanthellae sebagai Simbion Alga
Sebagian besar inang yang bersimbiosis merupakan karnivora dan
kegagalan inang untuk mencerna atau melenyapkan infasi simbion-simbion alga
adalah tergantung sifat yang dimiliki baik hewan karang maupun alga tersebut
(Yonge 1963 in Thamrin 2004). Salah satu inang invertebrata yang bersimbiosis
yaitu hewan karang dari Ordo Scleractinia. Hewan karang dari Scleractinia
merupakan koloni dari polip-polip yang dihubungkan oleh sistem gastrovaskuler
di mana individu hewan karang atau polip menempati mangkuk kecil atau koralit
dalam kerangka yang masif. Tiap mangkuk atau koralit mempunyai beberapa seri
septa yang tajam dan berbentuk daun yang keluar dari dasar (Thamrin 2004),
Zooxanthellae adalah istilah deskriptif umum untuk semua ganggang
berwarna emas yang hidup bersimbiosis pada hewan, termasuk karang, anemon
laut, moluska, dan taksa lainnya. Walaupun istilah tidak memiliki arti taksonomi,
zooxanthellae digunakan terutama untuk merujuk kepada simbion Dinoflagellata,
sekelompok alga yang beragam. Ini adalah label generik yang berguna, mengingat
keadaan saat ini ketidakpastian dalam taksonomi simbion karang. Zooxanthellae
yang ditemukan di karang biasanya berdiameter 8-12 µM. Sel yang berada di
membran vakuola, terikat dalam sel gastrodermal. Densitas mereka umumnya
berkisar antara 1 x 106 sel/cm2 sampai 2 x 106 sel/cm2 sel permukaan karang,
walaupun ini mungkin sangat bervariasi pada skala temporal dan spasial.
Beberapa bukti menunjukkan bahwa perbedaan musiman mempengaruhi
kepadatan zooxanthellae di karang (Muller-Parker & D’Elia 1997).
2.5 Struktur karang dan letak zooxanthellae
Sebagian besar karang pembentuk terumbu termasuk dalam kelompok

7
Scleractinia. Bentuk tubuh berongga, radial simetris di mana di dalam rongga ini
terdapat binatang karang yang disebut polip. Di ujung atas rongga terdapat bukaan
yang berfungsi sebagai mulut, ke arah bawah membagi diri menjadi septa atau
sekat yang radial simetris. Pada bagian mulut tersusun tentakel yang pada karang
batu berjumlah kelipatan enam. Pada karang batu kerangka pendukung tubuh
terdapat di luar (exoskeleton). Bagian dalam tubuh tersusun dari jaringan sel,
masing-masing dari luar ke dalam ektodermis, mesoglea, dan endodermis yang
sering juga disebut gastrodermis. Di dalam lapisan endodermis atau gastrodermis
ini terdapat zooxanthellae (Muller-Parker & D’Elia 1997).
2.5 Zooxanthellae dan bentuk simbiosisnya dengan karang
Gambar 1. Potongan melintang anemone laut dan zooxanthellae dalam jaringan gastrodermis.
Hubungan antara zooxanthellae dengan karang saling menguntungkan, jenis
zooxanthellae berasal dari kelompok Dinoflagellata tidak memiliki flagella dan
dinding sel. Kehadiran zooxanthellae akan memberikan warna karena
zooxanthellae memiliki pigmen. Melalui fotosintesis, zooxanthellae mensuplai
oksigen bagi karang untuk respirasi dan karbohidrat sebagai nutrient. Sebaliknya
zooxanthellae menerima CO2
zooxanthellae juga berperan dalam memindahkan karbondioksida, sehingga
untuk fotosintesis. Sementara untuk nitrogen dan
fosfor antara zooxanthellae dan karang terjadi dengan proses di mana
zooxanthellae menerima nitrogen dalam bentuk ammonia dari karang, dan
dikembalikan ke karang dalam bentuk asam amino. Dalam proses fotosintesis
dalam kondisi optimum meningkatkan terbentuknya pengapuran pada karang
(Thamrin 2006).

8
Terapan fungsional simbiosis pertama-tama dapat ditinjau dari kaitannya
dengan transfer nutrisi diantara keduanya. Dalam memenuhi nutrisinya semua
karang dapat menggunakan tentakelnya untuk menangkap mangsa (plankton).
Proses penangkapannya mempergunakan bantuan nematocyte suatu bentuk
protein spesifik yang mampu kemampuan proteksi dan melumpuhkan biomassa
tertentu seperti zooplankton. Meskipun mempunyai kemampuan feeding
active, akan tetapi kebanyakan proporsi terbesar makanan karang berasal dari
simbiosis yang unik, yaitu zooxanthellae.
2.7 Peran zooxanthellae dalam polip karang
Zooxanthellae berperan sebagai pemasok oksigen bagi karang, di samping
juga dari oksigen terlarut. Zooplankton merupakan sumber nutrien utama bagi
karang. Dalam hubungannya dengan ketersediaan nutrien dalam air laut,
Gladfelter (1985) menyatakan bahwa tingginya tingkat ketersediaan nutrien
mempengaruhi produktivitas zooxanthellae, dan meningkatkan indeks mitosis.
Karang yang telah kehilangan zooxanthellae masih mampu hidup bila tersedia
cukup zooplankton di sekitarnya. Kebutuhan nutrien organik pada karang yang
memiliki zooxanthellae lebih kecil dari pada karang yang tidak memiliki
zooxanthellae (Gledfelter 1985).
Dalam setiap polyp ditemukan zooxanthellae dalam jumlah besar dan
memberikan warna pada polyp (Jones 1997), 90% energi dari fotosintesis di
berikan untuk kebutuhan polyp (Leletkin 2000b). Zooxanthellae menerima
nutrisi-nutrisi penting dari karang (polyp) dan memberikan sebanyak 95% hasil
fotosintesisnya (energi dan nutrisi) kepada polyp (Muscatine 1991). Assosasi
yang erat ini sangat efisien, sehingga karang dapat bertahan hidup bahkan di
perairan yang sangat miskin hara. Keberhasilan hubungan ini dapat dilihat dari
besarnya keragaman dan usia karang yang sangat tua, berevolusi pertama kali
lebih dari 200 juta tahun yang lalu (Burke et al 2002).
Berdasarkan transfer nutrisi ini maka dapat dinyatakan bahwa karang dapat
menyediakan nutrisinya baik melalui active feeding dan passive feeding. Active
feeding dilakukan dengan menembakkan nematocyte ke arah mangsa dan
mentransfernya melalui mulut yang terdapat di bagian atas; sedangkan feeding

9
passive diperoleh melalui transfer hasil fotosintesis zooxanthellae. Sejauh
diketahui hampir semua karang dapat melakukan melalui feeding passive.
Zooxanthellae memberikan pewarnaan pada terumbu karang, dari warna
terang sampai gelap kecoklatan, tergantung pada kepadatan selnya (Jones 1997).
Bilamana ada pigmen lain dalam jaringan karang, maka warna kecoklatan akan
tertutup oleh warna pigmen tadi menjadi warna biru, hijau, kuning atau warna
ungu. Bila coral kehilangan zooxanthellae, kerangka karang yang berwarna putih
dapat dilihat melalui jaringan hewan itu yang transparan, menyebabkan karang
tampak memutih. Yonge, Nicholls 1931 in Jones 1987). Pada jenis karang yang
memliki pigmen lain, karang yang putih akan nampak warna flourence, dan tidak
tampak lagi warna coklat keemasan dari zooxanthellae (Oliver 1984).
Apabila zooxanthellae keluar dari inangnya, maka zooplankton merupakan
sumber nutrient, tetapi ketersediaannya tidak cukup untuk menunjang
pertumbuhan karang (Johannes et al 1970) dan kebutuhan nutrien lebih kecil pada
karang yang memiliki zooxanthellae (Gladfelter 1985).
Hewan karang sebagai pembangun utama terumbu adalah organisme laut
yang efisien karena mampu tumbuh subur dalam lingkungan sedikit nutrien
(oligotrofik) hal ini sebagai syarat hidup dari alga simbion zooxanthellae
(Stambler 1999). Ambang batas konsentrasi nutrien yaitu dissolved inorganic
nitrogen (DIN) di bawah 1µM dan untuk soluble reactive phosphorus (SRP) 0,1
µM (Lapointe et al 1997 in Cesar et al 2002). Burke et al (2002) sebagian besar
spesies karang melakukan simbiosis dengan alga simbiotik yaitu zooxanthellae
yang hidup di dalam jaringannya. Dalam simbiosis, zooxanthellae menghasilkan
oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh
karang, sedangkan karang menghasilkan komponen anorganik berupa nitrat, fosfat
dan karbon dioksida untuk keperluan hidup zooxanthellae. Selanjutnya Sumich
(1992) menjelaskan bahwa adanya proses fotosintesa oleh alga menyebabkan
bertambahnya produksi kalsium karbonat dengan menghilangkan karbon dioksida
dan merangsang reaksi kimia sebagai berikut:
Ca (HCO3) CaCO3 + H2CO3 H2O + COFotosintesa oleh algae yang bersimbiosis membuat karang pembentuk
terumbu menghasilkan deposit cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat, kira-
2

10
kira 10 kali lebih cepat daripada karang yang tidak membentuk terumbu
(ahermatipik) dan tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Veron (1995)
mengemukakan bahwa ekosistem terumbu karang adalah unik karena umumnya
hanya terdapat di perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan
hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi dan memerlukan
kualitas perairan alami (pristine). Demikian halnya dengan perubahan suhu
lingkungan akibat pemanasan global yang melanda perairan tropis di tahun 1998
telah menyebabkan pemutihan karang (coral bleaching) yang diikuti dengan
kematian massal mencapai 90-95%.
2.8 Kepadatan zooxanthellae
Kepadatan zooxanthellae di dalam jaringan karang bervariasi sesuai dengan
jenis karangnya. Kepadatan zooxanthellae berkisar antara 1–2,5 juta sel/cm2
2.9 Variasi pola makan karang
(Drew
1972; Muscatine et al. 1985 in Jones & Yelleowlees 1997). Kepadatan
zooxanthellae juga berbeda pada masing-masing kedalaman. Drew (1972)
mengatakan bahwa kepadatan maksimum zooxanthellae ditemukan pada
kedalaman antara 10–12 m. Hal ini tergantung pada tingkat nutrisi dan ruang
yang disediakan hewan inang. Zooxanthellae berkembangbiak dengan
pembelahan mitosis sampai pada batas tertentu tergantung pada laju metabolisme
hewan inang (Taylor 1969 in Nganro 1992). Di samping itu pengurangan
kepadatan zooxanthellae yang bersimbiosis dengan karang dapat dijadikan
indikator bahwa telah terjadi stres lingkungan terhadap hewan karang.
berkurangnya konsentrasi klorofil zooxanthellae pada tubuh hewan karang juga
merupakan indikator menurunnya kesehatan hewan karang (Yakin K 2006).
Pola makan karang secara umum dapat dibagi dalam 5 kategori: (1)Sebagian
besar makanan (30-90%) berasal dari zooxanthellae hasil fotosintesis. (2)Kegiatan
pola makan lainnya adalah predasi, yang menyediakan, rata-rata, 10-40% dari
keseluruhan biomassa makanan. Hasil predasi ini, 100% habis digunakan untuk
mengganti metabolisme pada siang hari, (3) Memakan partikel atau memfiltrasi
sedimen. semua karang scleractinian mampu makan partikel ,caranya memfilter
dari air seperti bakteri, fitoplankton, sisa-sisa hewan dan tanaman, detritus, dan
bahkan beberapa suspensi netral seperti grafit atau noda, (4) Memakan zat-zat

11
organik terlarut dengan cara osmotik, (5) Memakan zooxanthellae. kondisi ini
biasa terjadi jika penentrasi cahaya rendah. Jumlah sel yang dimakan sama dengan
jumlah sel yang baru membela. Ini merupakan bentuk adaptasi. Proses ini
berlangsung di gastrodermis (
2.10 Faktor lingkungan dan kehidupan karang
Titlyanov &Titlyanova 2002).
Zooxanthellae adalah alga bersel satu golongan dinoflagellata. Sebagai alga
sumber cahaya sangat merupakan faktor pembatas. Masukan zat padat ke
perairan atau meningkatnya fitoplankton di perairan sangat mengurangi penetrasi
cahaya yang masuk. Intensitas cahaya juga mempengaruhi suhu, salinitas
lingkungan perairan.
2.10.1 Suhu
Bila hewan inang mengalami stres akibat perubahan lingkungan,
zooxanthellae akan keluar dari inang dan berenang bebas di air laut, Perubahan
suhu mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi, sehingga terjadi
ketidakseimbangan metabolisme antara zooxanthellae dengan inangnya
(Gladfelter 1985). Kenaikan suhu mempercepat laju respirasi lebih besar dari
pada laju fotosintesis. Muscatine (1985) mengatakan bahwa karang tidak dapat
memberikan nutrien yang cukup kepada simbionnya pada suhu yang tinggi.
Perubahan suhu air laut secara mendadak atau dalam waktu lama dapat
menyebabkan keluarnya zooxanthellae dari inangnya yang lama-kelamaan
mengakibatkan kematian inang. Demikian pula suhu dapat mempengaruhi laju
respirasi dan fotosintesa seperti dijelaskan di atas. Karang tumbuh dengan baik
(optimum) pada suhu antara 25 – 280
2.10.2 Salinitas
C.
Zat terlarut meliputi garam-garam organik, senyawa-senyawa organik
yang berasal dari organisme hidup dan gas-gas tertentu. Fraksi terbesar dari bahan
terlarut terdiri dari garam-garam anorganik yang berwujud ion-ion. Satu contoh,
air laut seberat 1000 gram akan berisi kurang lebih 35 gram senyawa-senyawa
terlarut yang secara kolektif disebut garam. Dengan kata lain, 96,5 % air laut
berupa air murni dan 3,5 % zat terlarut. Perbandingan ion-ion utama boleh
dikatakan tetap (Nybakken 1987) Sama halnya dengan suhu, menurun atau

12
naiknya salinitas secara mendadak dapat mengakibatkan kematian karang.
Kisaran optimum salinitas untuk pertumbuhan karang ialah antara 25 -40 0/
2.10.3 Total suspended solid (TSS)
00.
Total Padatan Tersuspensi atau sering disebut TSS adalah semua zat padat
(pasir, lumpur, dan tanah liat) atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air
berupa komponen biotik (fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi,dll), ataupun
komponen abiotik (detritus dan partikel-partikel anorganik) Lestari (2009).
Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan dan bergantung pada warna dan
kekeruhan.
Tabel 1 Klasifikasi tingkat pencemaran berdasarkan kadar TSS Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 2004.
No Total Padatan Tersuspensi (ppm) Kriteria
1 Kurang dari 20 Belum tercemar
2 20-49 Tercemar ringan
3 50-100 Tercemar sedang
4 Di atas 100 Tercemar berat
2.10.4 Kecerahan dan Cahaya.
Kecerahan berhubungan erat dengan penetrasi cahaya matahari dan partikel
tersuspensi. Naiknya konsentrasi partikel tersuspensi di air menyebabkan
kontraksi polip, meningkatnya sekresi mucus, menipisnya jaringan karang dan
keluarnya zooxanthellae. Bila keadaan ini berlangsung lama akan mengakibatkan
kematian karang (Yamazato 1986). Keadaan awan di suatu tempat mempengaruhi
pertumbuhan karang (Goreau 1959). Menurut Kanwisher dan Wainwright (1967)
titik kompensasi binatang karang terhadap cahaya adalah pada intensitas antara
200 – 700 f.c atau umumnya antara 300 -500 f.c.
2.11 Fosfat
Jumlah fosfor (P) yang diperlukan oleh blue-green algae (makhluk hidup air
penyebab algal blooming) untuk tumbuh, ternyata hanya dengan konsentrasi 10
part per billion (ppb/sepersatu miliar bagian) fosfor saja blue-green algae sudah
bisa tumbuh. Tidak heran kalau algal blooming terjadi di banyak ekosistem air.

13
Dalam tempo 24 jam saja populasi alga bisa berkembang dua kali lipat dengan
jumlah ketersediaan fosfor yang berlebihan akibat limbah fosfat di atas.
Keberadaan fosfor di perairan adalah sangat penting terutama berfungsi
dalam pembentukan protein dan metabolisme bagi organisme. Fosfor juga
berperan dalam transfer energi di dalam sel misalnya adenosine triphosfate (ATP)
dan adenosine diphosphate (ADP). Ortofosfat yang merupakan produk ionisasi
dari asam ortofosfat yang merupakan bentuk yang paling sederhana di perairan
(Boyd, 1982). Fosfor dalam perairan tawar ataupun air limbah pada umumnya
bentuk fosfat berupa ortofosfat, yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh
tumbuhan akuatik, sedangkan polifosfat harus mengalami hidrolisis membentuk
ortofosfat terlebih dahulu sebelum dapat dimanfaatkan sebagai sumber fosfor.
Menurut Perkins (1974) in Erna (2008), kandungan fosfat yang terdapat di
perairan umumnya tidak lebih dari 0,1 mg/l, kecuali pada perairan yang menerima
limbah dari rumah tangga dan industri tertentu, serta dari daerah pertanian yang
mendapat pemupukan fosfat. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup tentang baku mutu air laut tertuang dalam tabel dibawah ini.
Tabel 2 Baku Mutu Air Laut untuk biota laut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2004.
Fluktuasi asupan nutrien ke perairan pesisir di pengaruhi oleh musim,
dimana pada musim hujan asupan nutrien lebih tinggi dibandingkan pada saat
musim kemarau selain itu asupan nutrien bisa juga berasal dari perairan laut
disekitarnya (Damar 2003).
2.12 Nutrien dan kehidupan karang
Peningkatan nutrien telah diusulkan sebagai penyebab utama terumbu
karang lokal degradasi. Meskipun respon karang untuk nutrien seperti amonium
dan atau nitrat terdokumentasi baik dalam studi laboratorium. Dampak jangka
NO Parameter Satuan Baku Mutu 1 Kecerahan meter Coral <5
2 Padatan tersuspensi total mg/liter • Coral;20 • Mangrove;80 • Lamun;20
3 Ortofosfat (PO4-P) mg/liter 0.015 4 Nitrat (NO3-N) mg/liter 0.008

14
panjang dari tingginya konsentrasi nitrogen anorganik terus menerus pada
fisiologi karang susah diprediksi. Sebuah penelitian untuk melihat dampak jangka
panjang tersebut, dicobakan pada koloni karang Stylophora pistillata dan
Acropora spp yang terkena 40 µM dari NH4 + dan 30 µM NO3-
2.13 Eutrofikasi dan terumbu karang
. Kedua karang ini
dipelihara selama 12 bulan dalam aquarium. Hasilnya menunjukkan respons
berbeda terhadap peningkatan nutrien dalam kepadatan zooxanthellae. Walaupun
S. pistillata dan Acropora spp. dapat beradaptasi pada tingkat nitrogen anorganik
tinggi, tetapi dalam jangka panjang menunjukkan bahwa peningkatan nutrien
bukan hanya menyebabkan degradasi terumbu karang, tetapi dapat menghasilkan
dampak sinergis ketika karang terkena faktor tekanan lingkungan lainnya (Yuen
et al 2008).
Eutrofikasi adalah peningkatan bahan organik ke dalam sebuah ekosistem
(Nixon 1995), di mana peningkatan bahan organik ini sangat mendorong
peningkatan masukan nutrien yang diikuti oleh meningkatnya produksi primer
dan sekunder. Eutrofikasi ini juga dikenal sebagai satu dari ancaman besar
terhadap ekosistem pesisir pada skala global (Nixon 1990; Gray 1992; Pearl 1995
in Bonsdorff 1997).
Walaupun unsur hara (nutrien) sangat penting dalam suatu ekosistem
terutama sebagai sumber penyusunan bahan organik oleh produsen primer, akan
tetapi peningkatan unsur hara pada ekosistem terumbu karang dinilai justru dapat
berpengaruh negatif terhadap perkembangan ekosistem ini. Hal ini bisa dilihat
dari kenyataan bahwa terumbu karang justru berkembang dengan baik pada
daerah yang relatif jauh dari sumber unsur hara (oligotrofik) dan sebaliknya tidak
berkembang pada daerah yang mendapat suplai unsur hara yang tinggi.
Peningkatan unsur hara yang berlebihan menyebabkan berbagai dampak.
Menurut Wouthuyzen (2006) in Indrawan et al. (1998) salah satu adalah turunnya
kecerahan perairan akibat meledaknya populasi fitoplankton, kematian massal
ikan, menurunnya konsentrasi oksigen terlarut dan merugikan biota perairan pada
lapisan permukaan dan yang paling banyak adalah maraknya fitoplankton beracun
yang terdapat pada makanan laut seperti kerang-kerangan. Makanan laut yang
telah mengandung racun tersebut sangat membahayakan kesehatan manusia.

15
Bahkan makanan tersebut dapat mengakibatkan kematian dan keracunan bagi
siapa saja yang mengkonsumsinya. Hal ini karena masing-masing spesies algae
memiliki racun berbeda satu dengan yang lain.
Eutrofikasi juga meningkatkan padatan tersuspensi. Total padatan
tersuspensi atau lebih dikenal istilah TSS (Total Suspended Solid) merupakan
bahan-bahan tersuspensi (diameter >1 μm) yang tertahan pada saringan millipore
dengan diameter pori 0,45 μm. TSS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta
jasad-jasad renik terutama yang disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi yang
terbawa ke dalam badan air. Masuknya padatan tersuspensi ke dalam perairan
dapat menimbulkan kekeruhan air. Hal ini menyebabkan menurunnya laju
fotosintesis, sehingga produktivitas primer perairan menurun, yang pada
gilirannya menyebabkan terganggunya keseluruhan rantai makanan.
Entrofikasi juga berdampak pada pola rekrutmen karang. Penempelan planula
pada perairan yang eutrofik sangat rendah sehingga daerah ini miskin dengan
karang. Menurut Tomacik (1991) bahwa pola penempelan karang pada subtrat
buatan yang diletakkan sepanjang gradien eutrofikasi di Bardabos India Barat
menunjukkan tingkat persentase penempelan yang rendah, tercatat Porites
astroides 42%, Agaricia spp 23%, Porites porites 10% bahkan Jenis karang
Monstastrea annularis, Siderastrea spp dan Diplona spp hadir di terumbu karang
bagian utara, tetapi tidak hadir di daerah yang eutrofik ini. Ciri perairan yang
mengalami eutrofikasi adalah perubahan warna (hijau, coklat-kuning atau merah)
dengan viskositas tinggi. Salah satu parameter yang dapat dijadikan indikator
terjadinya eutrofikasi adalah konsentrasi klorofil-a yang merupakan ukuran dari
biomassa alga uniseluler.
2.14 Kepadatan zooxanthellae dan bioindikator
Meningkatnya aktifitas manusia mengakibatkan perubahan yang besar
terhadap suhu air laut, kimia air laut. Berbagai dampak yang terjadi seperti
hilangnya spesies, berubahnya rantai makanan yang tentunya akan mengubah
ekologi terumbu karang baik skala lokal maupun skala dunia. Perubahan dari
ekologi terumbu karang meliputi pengurangan laju kalsifikasi, pengurangan
kepadatan zooxanthellae, perubahan trofik level dari struktur komunitas terumbu
karang dimana spesies pada tropik tinggi berkurang sedangkan disisi lain spesies

16
pada tropik rendah meningkat, hal ini mengakibatkan produktivitas sekunder juga
berkurang. kesemuanya ini akan mengurangi keanekaragaman hayati dan sebaran
terumbu karang, lambat laun fungsi dari terumbu karang sebagai penghalang
abrasi akan menurun dan mengakibat perubahan garis pantai. Untuk menghindari
dampak negatif ini maka perlu upaya pengelolaan sumberdaya terumbu karang
termasuk pengaturan perdagangan sumberdaya, pengurangan laju runoff dan
limbah industri yang masuk ke badan perairan (Timothy 2002).

17
3 METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kepulauan Spermonde yaitu; Pulau Laelae,
Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang di Kota Makassar yang berlangsung
dari bulan April sampai Mei 2010, dan untuk analisa sampel dilakukan di
Laboratorium Fisika, Kimia Oceanografi Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Hasanuddin Makassar.
Sumber :Landsat ETM+Satellite Image Aquisition tahun 2002
Gambar 2. Peta lokasi penelitian di Kepulauan Spermonde.
3.2 Alat dan Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan di lapangan lokasi pengambilan sampel
adalah formalin 4%, larutan lugol, sedangkan peralatan yang digunakan yaitu:
peralatan snorkeling, alat pemotong karang, kantong plastik, DO-meter, Secchi
disc, refraktometer, spectrophotometer, mikroskop, botol sampel air, plankton net
ukuran mata jaring 25 µm, alat penggerus sampel (mortar), haemocytometer,
Pulau Lanyukang
Pulau Laelae
Pulau Barrang Lompo
Daratan Terumbu karang dangkal Pulau Lokasi Penelitian
Legenda:

18
mistar geser, alat pemotong karang, gelas ukur volume 10 ml, pipet, alat hitung
(Tally counter).
3.3 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas kegiatan
pengumpulan data di lapangan secara in situ, dan dilanjutkan dengan pengukuran
sampel di laboratorium. Data yang dibutuhkan yaitu; data sampel karang,
parameter fisika, kimia, biologi perairan (suhu, salinitas, kedalaman, partikel
terlarut, nitrat, fosfat, fitoplankton).
3.3.1 Data sampel karang.
Data sampel karang yang diteliti terdiri dari 3 spesies untuk masing masing
pulau. Sampel karang ini diambil dari koloni yang berbeda, dengan 3 kali
ulangan, dengan kedalaman yang sama yaitu 2-3 meter. Sampel karang diambil
mendekati reef slope.
Cara pengambilan sampel karang yaitu untuk karang yang bercabang,
memotong karang dengan gunting yang biasa dipakai untuk menggunting
tanaman, sedangkan untuk karang yang massif menggunakan pahat dan martil.
Ukuran karang yang dijadikan sampel disesuaikan kebutuhan penelitian,
kemudian permukaan sampel karang tersebut dikerik dengan sebuah alat yang
bentuk lempeng dari alumunium, lalu bekas kerikan tadi diukur luasnya dan
dicatat. Selanjutnya hasil kerikan sampel karang tadi dimasukkan ke wadah yang
berisi formalin 4 %, diukur dengan menggunakan gelas ukur, selanjutnya dibawa
ke laboratorium untuk dihitung kepadatan zooxanthellaenya.
3.3.2 Data Parameter Fisika, Kimia, Biologi Perairan
Untuk parameter fisika yang diukur adalah suhu, salinitas, kedalaman,
partikel tersuspensi dan kecerahan. Pengukuran suhu, salinitas menggunakan DO
meter. Untuk memastikan sampel berada pada kedalaman 2-3 meter digunakan
bambu sebagaialat bantu, sedangkan pengukuran kecerahan diperoleh berdasarkan
pengamatan langsung di kedalaman 2-3 meter. Hasil pengamatan menunjukkan
kecerahan 100%.
Pengumpulan data parameter kimia seperti; nitrat, fosfat dengan cara
mencelupkan botol ke dalam perairan, kemudian di simpan dalam coolbox suhu

19
0o
Untuk pengumpulan data kelimpahan fitoplankton menggunakan plankton
net dengan ukuran mata jaring 25 µm. Cara menggunakann plankton net yaitu air
laut dituang ke dalam jaring plankton net dengan menggunakan timba berukuran 5
liter. Kegiatan menuang air ini dilakukan berulang-ulang. Setelah itu, air yang
tertuang tersebut akan tersaring kemudian tertampung pada botol plankton net,,
lalu dipindahkan ke botol lain, dan diberikan larutan lugol 5 tetes untuk
pengawetan sampel fitoplankton, selanjutnya dimasukkan ke coolbox yang berisi
bongkahan es..
C yang berisi es yang sudah dihancurkan dan selanjutnya dibawa ke
laboratorium. Pengukuran kedua senyawa ini dimaksudkan untuk menilai tingkat
eutrofikasi di lokasi penelitian, kemudian data yang diperoleh selanjutkan akan
dikaji keterkaitannya dengan kepadatan zooxanthellae.
3.3.3 Data kepadatan zooxanthellae
Prosedur yang digunakan mengacuh pada metode yang dijelaskan
Muscatine et al. (1989) yaitu jaringan karang dikeluarkan dari setiap polip, di
mana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara karang dikerik permukaannya.
Alat pengerik terbuat dari lempeng stainless. Jarigan karang yang sudah dikerik
selanjutnya dimasukkan dalam wadah yang telah diisi formalin 4%, lalu wadah
tersebut diberi tanda disesuaikan dengan jenis karang dan nama pulau tempat
pengambilan sampel karang tersebut. Setelah itu jaringan karang yang sudah
dikeluarkan tadi, selanjutnya diaduk sampai terkumpul gumpalan, kemudian
digerus sampai halus. Setelah itu satu tetes sampel dimasukkan ke
Haemocytometer. Kemudian dihitung dibawa mikroskop, sedangkan permukaan
karang yang sudah dikerik tadi dihitung luasnya.
3.4 Analisis Data
3.4.1 Perhitungan Kelimpahan Fitoplankton
Penentuan kelimpahan fitoplakton dilakukan berdasarkan metode sapuan
di atas gelas objek. Kelimpahan fitoplankton dinyatakan secara kuantitatif dalam
jumlah sel/liter. Kelimpahan plankton dihitung berdasarkan Wibisono (2005)
dengan rumus ;

20
Dimana ;
N = Jumlah sel per liter n = Jumlah sel yang diamati (sel) Vr = Volume air yang tersaring (ml) Vo = Volume air yang diamati pada Haemocytometer (ml) Vs = Volume air yang disaring (liter)
3.4.2 Perhitungan Kepadatan Zooxanthellae
Kepadatan zooxanthellae dihitung dengan menggunakan rumus American
Public Health Asossiation (APHA ) 1992 sebagai berikut :
Di mana :
N = Jumlah zooxanthellae yang terhitung (sel),
At = Luas cover glass (mm2
Vt = Volume Total Sampel,
)
Ac = Luas Sampel yang dikerik (cm2
Vs = Volume Sampel yang digunakan (ml),
),
As = Luas Haemacytometer (mm2
3.4.3 Perhitungan Kecerahan
).
Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerahan dikenal sebagai
Secchi Disk. Bentuk alat ini adalah lingkaran (plat) dengan diameter 20 cm yang
dihubungkan dengan tali yang dikaitkan. Dan permukaan plat dibagi empat
simetris dan dicat hitam putih .Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang teliti
maka digunakan rumus seperti di bawah ini ;
A = 0,5 (B + C)
A = Tingkat kecerahan yang dicari (m)
B = Jarak dari permukaan air laut sampai secchi disk mulai hilang dari pandang
C = Jarak dari permukaan air laut sampai secchi disk ditarik ke atas lagi sampa
imulai tampak samar.

21
3.4.4 Analisis Kepadatan Zooxanthellae dan Kelimpahan Fitoplankton
Untuk melihat perbedaan kepadatan zooxanthellae dan kelimpahan
fitoplankton antar pulau digunakan analisis varians ANOVA single factor.

23
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Umum Kepulauan Spermonde
Kepulauan Spermonde (Spermonde Shelf) terdapat di bagian Selatan Selat
Makassar, tepatnya di pesisir Barat Daya Pulau Sulawesi, terbentang dari Utara ke
Selatan sejajar daratan Pulau Sulawesi. Kepulauan Spermonde terdiri atas 121
pulau, mulai dari Kabupaten Takalar di Selatan hingga Kabupaten Mamuju di
Sulawesi Barat.
Pembagian wilayah Kepulauan Spermonde menjadi empat zone, di mana
kemudian menjadi dasar pembagian zone distribusi terumbu karang dan sering
dijadikan dasar dalam penelitian yang berkaitan dengan terumbu karang (de klerk
1983; Moll 1983: Hoeksema dan Moka,1989 in Jompa et al. 2005). Zone
pertama atau zone bagian dalam, merupakan zone terdekat dari pantai daratan
utama Pulau Sulawesi mempunyai kedalaman laut rata-rata 10 m dan subtrat dasar
yang didominasi oleh pasir berlumpur. Zone kedua, berjarak kurang lebih 5 km
dari daratan Sulawesi, mempunyai kedalaman laut rata-rata 30 m dan banyak
dijumpai pulau karang. Zone ketiga dimulai pada jarak 12.5 km dari pantai
Sulawesi dengan kedalaman laut antara 20-50 m. Zone keempat atau zone terluar
merupakan zone terumbu penghalang (Barrier Reef Zone) dan berjarak 30 km dari
daratan utama Sulawesi. Di sisi timur pulau-pulau karang ini kedalaman lautnya
berkisar 40-50 m, sedangkan sisi baratnya mencapai kedalaman lebih dari 100 m.
Tabel 3 Posisi dan Jarak Kepulauan Spermonde dari Daratan Utama (Mainland) Kota Makassar.
No Pulau Posisi Jarak dari
Makassar* (km) Bujur (BT) Lintang (LS)
1 Lanyukang 119o 0404’45,3” o 40,17 58’40,8”
2 Langkai 119o 0405’46,8” o 35,80 1’52,1”
3 Lumu lumu 119o 0412’34,92” o 27,54 57’48,6”
4 Bonetambung 119o 0516’43,21” o 17,87 08’48,7”
5 Kodingareng lompo 119o 0515’53,6” o 15,05 08’48,7”
6 Kodingareng Keke 119o 0517’18,0” o 13,48 06’21,3”
7 Barrang Lompo 119o 0519’33,6” o 12,77 03’0,35”
8 Barrang Caddi 119o 0519’16,34” o 11,15 04’49,6”
9 Kayangan 119o 0524’04,9” o 2,8 06’49,5”
10 Lae lae 119o 0523’30,0” o 2,0 08’24,0”
11 Samalona 119o 0520’36,0” o 6,6 07’30,0”

24
3.1.1 Pulau Laelae
Secara administratif termasuk ke dalam wilayah di provinsi Sulawesi
Selatan Kota Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Laelae. Secara
geografis pulau terletak pada posisi 119o 23’33,1” BT dan 05o
Sumber; Foto Google Earth 2010
08’16,0” LS. Batas-
batas administrasi meliputi; sebelah barat berbatasan dengan Pulau Samalona,
sebelah Timur dengan Kota Makassar, sebelah Selatan dengan Tanjung Bunga,
dan Sebelah Utara dengan Laelae kecil. Pulau dengan luas 0.04 km² ini, dihuni
oleh 400 keluarga atau sekitar 2.000 jiwa. Jarak pulau ini dari Makassar sekitar 2
km.
Gambar 3. Foto Pulau Laelae Kota Makassar.
Di pulau Laelae ada dijumpai terumbu karang. Kondisi terumbu karang di
pulau ini termasuk jelek yang kemungkinan besar utamanya disebabkan oleh
tingginya tingkat sedimentasi dan eutrofikasi yang berasal dari massa daratan
utama atau daerah inshore. Di pulau ini juga ditemukan kelimpahan makro alga
yang paling tinggi, didominasi jenis jenis makro alga coklat yakni Sargassum spp,
Turbinaria sp, Halimeda sp, Caulerpa sp (Jompa et al. 2006). Kelimpahan
makroalga tersebut di atas sesuai dengan hasil pengamatan langsung kondisi
perairan pada kedalaman 2-3 meter, di mana dijumpai dominan makroalga,
koloni karang sangat sedikit dan ukurannya kecil, bentuk pertumbuhan karang
Pulau Laelae
Stasiun penelitian

25
pada kedalaman ini adalah tabular dan jarak antar koloni satu dengan lain cukup
jauh. Kondisi parameter nitrat dan fosfat saat penelitian ini menunjukkan kondisi
perairan yang lebih baik dibandingkan dengan kualitas perairan pulau Laelae
tahun 2005. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.
Tabel 4 Parameter kualitas perairan pulau Laelae Survei Tahun 2005
.Sumber; Survei lapangan tahun 2005 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.1.2 Pulau Barrang Lompo
Ikan Karang, ikan hias, karang, spons, lamun, alga merupakan hasil laut
yang banyak di Pulau Barrang Lompo.
sSumber; Foto Google Earth 2010.
Gambar 4. Foto Pulau Barrang Lompo kota Makassar
Kondisi masyarakat di Pulau Barrang Lompo ini sangat majemuk, dan mata
pencaharian sebagian besar penduduknya adalah pengusaha hasil laut (pedagang
pengumpul), disamping itu terdapat pula keanekaragaman nelayan mulai dari
penyelam teripang, pemancing ikan serta pemancing cumi (Jompa et al. 2006).
Parameter Utara Timur Selatan Barat Suhu ( C) 30 31 29 30 Arus (m/dt) 0.03-0,04 0,20-0,28 0,02- 0,04 0,02-0,035 Oksigen (ppt) 5,4-5,7 - 5,1 5,1 – 5,3 pH 8.05 8,08-8,39 8.04 8,13-8,18 Salinitas (o/oo 36 ) - 35 36 Nitrat (ppm) 0,49 - 0,74 - 0,84-1,04 0,06-0,74 Fosfat (ppm) 3,36 - 4,13 - 2,90-3,64 3,30-3,70
Stasiun penelitian

26
Hasil pengamatan langsung kondisi perairan pada kedalaman 2-3 meter masih
ditemukan koloni karang yang cukup baik walaupun luasan terumbu karangnya
terbatas dan terpisah pisah, ukuran koloni terumbu karangnya juga kecil. .
Tabel 5 Kondisi Parameter Oseanografi pulau Barrang Lompo tahun 2005
Parameter Utara Timur Selatan Barat
Faktor Fisika Suhu ( C) 30,5 29,5 –
30 30,5 30,5 – 31
Kecerahan (m) 15 11 13 14 Kedalaman (m) 2 – 21 16 2 - 24 2 – 21 Arus (m/dt) 0.2 0.167 0.179 0,200 Keterlindungan Barat Ya Tidak Tidak Tidak
dari musim Timur Tidak Tidak Ya Tidak Berpasir 100 - - 40 Substrat (%) Berkarang - 50 40 30 Rubble - 10 20 40 Faktor Kimia Oksigen (ppt) 6,0 5,5 –
5,7 5,4 5,3 – 5,4
pH 7.93 8.06 7.97 7.94 Salinitas o/ 34 oo 34 35 35 Nitrat (ppm) 2.45 0.32 0.17 0.11 Fosfat (ppm) 0.57 0.65 0.61 0.63
Sumber; Survei Lapangan 2005
3.1.3 Pulau Lanyukang
Terumbu Karang, ikan karang, cumi-cumi, agar-agar, kerang merupakan
hasil laut yang sering ditemui di pulau Lanyukang. Mata pencaharian penduduk
pulau Lanyukang adalah nelayan pancing dan jaring. Kondisi terumbu karang di
pulau ini walaupun jauh dari kota makasar, sudah cukup memprihatinkan.
kebanyakan daerah reef flat telah didominasi oleh karang mati, rubble, serta pasir.
namun pada daerah yang masih cukup dalam (sekitar 10 meter), kondisi
karangnya masih relatif baik 45%, jumlah dan jenis ikan-ikan karang juga masih
relatif banyak (Jompa et al. 2006).
Pulau Lanyukang didasarkan pada orientasi bentuknya, memanjang dari
Timur Laut ke Barat Daya. Luas areal dataran Pulau Lanyukang seluas ± 4,5 Ha.
Ekosistem perairan pada kedalaman 1-5 m ditandai dengan dominan hamparan

27
pasir putih mengelilingi pulau, lalu padang lamun dan rataan terumbu. Pada
bagian utara Pulau Lanyukang yang terlindung oleh pengaruh musim barat,
sebaliknya pada musim timur hanya bagian selatan yang terlindung dari pengaruh
yang ditimbulkan oleh angin musim tersebut, namun hasil pengamatan langsung
saat penelitian adalah jarang ditemukan karang pada kedalaman 2-3 meter dan
pada kedalaman ini didominasi pasir putih.
3.2 Kondisi Perairan Pulau Laelae, Pulau Barang Lompo dan Pulau Lanyukang
Kondisi Perairan saat penelitian masih berada pada musim peralihan dari
musim Timur ke Musim Barat yaitu bulan Maret – Mei 2010, namun masih
sering terjadi hujan. Lokasi pengambilan sampel hanya dibatasi pada kedalaman
2-3 meter, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pengaruh maksimum dari
kegiatan masyarakat pulau tersebut terhadap kualitas perairan.
Adapun kondisi perairan hasil perhitungan laboratorium dapat dilihat dari
Tabel 6 dibawah ini.
Tabel 6 Kondisi Perairan Pulau Laelae, Barrang Lompo dan Lanyukang Kota Makassar
No Parameter Pulau
Laelae Barrang Lompo Lanyukang
1 TSS (mg/l) 7 4 6
2 NO3 0.022 (mg/l) 0.010 0.011
3 PO4 0.91 (mg/l) 0.68 1.05
4 Jarak Dari Kota Makassar (km) 2 12.77 40.17
5 Rata-rata Kepadatan Zooxanthellae (sel/cm2 2.28 x 10) 5 x 105 6.75 x 105
6
5
Rata-rata Kepadatan Fitoplankton (sel/liter) 187.2 417.6 828
3.2.1 Total Suspended Solid (TSS)
Salah satu sumber terbesar dari pencemaran air adalah padatan tersuspensi.
Ketika partikel ini menetap di dasar badan air, mereka menjadi sedimen. Istilah
sedimen dan lumpur sering digunakan untuk merujuk pada padatan tersuspensi.

28
Padatan sedimen terdiri dari fraksi anorganik (silts, tanah liat, dan lain-lain) dan
fraksi organik (ganggang, zooplankton, bakteri, dan detritus) yang terbawa dari
runoff dari daratan. Padatan tersuspensi mempengaruhi sepanjang siklus hidup
hewan karang mulai dari saat larva seperti mortalitas larva planula, penempelan
planula, fekunditas sampai kelangsungan hidup karang. termasuk mempengaruhi
pembelahan zooxanthellae yang membutuhkan cahaya matahari untuk proses
fotosinesis (Thamrin 2004).
Adapun hasil pengukuran konsentrasi Total Suspended Solid
(TSS) dari
masing-masing pulau dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Konsentrasi TSS (mg/l) di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang.
Air laut memiliki nilai padatan terlarut yang tinggi, tetapi tidak berarti
kekeruhannya tinggi pula (Effendi 2003). Padatan tersuspensi menciptakan resiko
tinggi terhadap kehidupan dalam air pada aliran air yang menerima tailings di
kawasan dataran rendah, ini dapat dilihat bahwa padatan tersuspensi dalam jumlah
yang berlebihan (diukur sebagai total suspended solids – TSS) akan memiliki
dampak langsung yang berbahaya terhadap kehidupan dan bisa mengakibatkan
kerusakan ekologis yang signifikan melalui beberapa mekanisme seperti: 1)
Abrasi langsung terhadap insang binatang air atau jaringan tipis dari tumbuhan
air; 2) Penyumbatan insang ikan atau selaput pernapasan lainnya; 3) Menghambat
tumbuhnya/smothering telur atau kurangnya asupan oksigen karena terlapisi oleh
padatan; 4) Gangguan terhadap proses makan, termasuk proses mencari mangsa
dan menyeleksi makanan (terutama bagi predation dan filter feeding; 5) Gangguan
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Laelae Barrang lompo Lanyukang
Kons
entr
asi(m
g/l)
Pulau

29
terhadap proses fotosintesis oleh ganggang atau rumput air karena padatan
tersuspensi menghalangi cahaya matahari yang masukke perairan; 6) Terjadi
perubahan integritas habitat akibat perubahan ukuran partikel. Apabila
konsentrasi TSS yang tinggi di Pulau Laelae 7 mg/l dibiarkan terus maka akan
terjadi perubahan struktur komunitas perairan. Tingginya kadar TSS di pulau
Laelae runoff dari daratan utama (Kota Makassar), di mana jaraknya dekat dari
kota Makassar. Sumber TSS berasal dari Sungai Jeneberang yang bermuara ke
laut dekat pulau Laelae. Sedangkan kadar TSS pulau Barrang Lompo 4 mg/liter
lebih rendah dari TSS pulau Lanyukang. Tinggi konsentrasi TSS pulau
Lanyukang ini karena adanya sumber TSS dari upwelling di selat Makassar dan
resuspensi. Sementara rendahnya kadar TSS pulau Barrang Lompo dibandingkan
pulau Lanyukang diduga karena rendahnya pengaruh runoff dari daratan utama. .
Terjadinya resuspensi di Pulau Lanyukang akibat aksi gelombang yang
cukup besar, hal ini disebakan karena letaknya berada di wilayah laut terbuka
(offshore) sehingga tiupan angin juga lebih besar, dibandingkan pulau Barang
Lompo yang berada di wilayah inshore. Dampak dari adanya resuspensi sedimen
ini adalah mengangkat endapan nutrient dan sedimen di dasar perairan ke
permukaan, hal ini sesuai dengan (Cristiansen et al, (1997); Phillips et al, (2005);
Dzialowski et al, (2008) in Prasena, Hasena 2009) bahwa resuspensi sedimen
merupakan salah satu proses yang berpotensi memberikan kontribusi masukkan
nutrien penting seperti nitrat, ammonium dan fosfat dari sedimen ke kolom air
sehingga berdampak pada naiknya nilai TSS utamanya di perairan dangkal.
Resuspensi terjadi karena gelombang laut yang dibangkitkan oleh angin atau arus
pasut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecepatan angin di atas 4 m/det
mampu meningkatkan organik partikel secara nyata dari sedimen ke kolom air
yang dapat memasok kehidupan produktivitas sekunder. Arfi et al. (1994) in
Prasena, Hasena (2009) menyatakan pada kecepatan angin di atas 3 m/det mampu
menimbulkan resuspensi sedimen yang diikuti dengan peningkatan seston mineral
dan amoniak.
Hal lain yang menyebabkan tingginya nilai TSS pulau Lanyukang adalah
diduga terjadi upwelling diperairan sekitar pulau Lanyukang karena letaknya

30
dekat selat Makassar yang membawa massa air yang mengandung partikel
anonrganik dan organik.
Berdasarkan klasifikasi derajat pencemaran baku mutu air laut Menteri
Negara Lingkungan Hidup (2004) bahwa kualitas perairan ketiga pulau tersebut;
pulau Laelae, pulau Barrang Lompo dan pulau Lanyukang masih dikategorikan
belum tercemar karena nilai TSS kurang dari 20 ppm (mg/liter).
3.2.2 Nitrat
Nitrat (NO3) adalah bentuk nitrogen utama di perairan alami. Nitrat
merupakan salah satu senyawa yang penting dalam sintesa protein hewan dan
tumbuhan. Konsentrasi nitrat yang tinggi di perairan dapat menyebabkan
terjadinya blooming. Ketersediaan nutrien dapat menstimulasi pertumbuhan dan
perkembangan organisme perairan secara cepat (Alaerst & Sartika 1987).
Berdasarkan hasil pengukuran nitrat dari ketiga pulau yaitu; Pulau Laelae, Pulau
Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang maka konsentrasi nitrat tertinggi adalah
pulau Laelae, hal ini disebabkan karena masukan nutrien dari runoff sungai
Jeneberang. Selain itu, letaknya yang dekat dengan kota Makassar (2 km) di
mana kita ketahui bahwa sumbangan nitrat umumnya berasal dari kegiatan
aktivitas manusia di daratan, hal ini sesuai yang dikatakan Lahude (1998) bahwa
peningkatan hara fosfat dan nitrat di daerah pesisir lebih disebabkan pembuangan
limbah hasil aktivitas manusia termasuk industri di darat sedangkan di laut lepas
bersumber dari hasil pengangkatan massa air (upwelling) dari dasar perairan.
Perbedaan konsentrasi nitrat antar pulau lokasi penelitian dapat dilihat jelas dari
Gambar 6.
Gambar 6. Konstrasi Nitrat di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau
Lanyukang.
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
Laelae Barrang Lompo Lanyukang
Kons
entr
asi (
mg/
l)
Pulau

31
Konsentrasi nitrat ketiga pulau tersebut bila dibandingkan dengan baku
mutu air laut maka ketiga pulau tersebut berada diluar ambang batas Baku Mutu
Air Laut (BMAL) di mana konentrasi nitrat yang dibutuh untuk kehidupan
organism laut adalah 0,008 mg/liter.
3.2.3 OrtoFosfat
Ortofosfat merupakan bentuk fosfat yang dapat dimanfaatkan secara
langsung oleh tumbuhan akuatik. Berdasarkan Baku Mutu Air Laut (KLH 2004)
menunjukkan bahwa konsentrasi ortofosfat ketiga pulau ini yaitu; Pulau Laelae
0.91 mg/liter, Pulau Barrang Lompo 0.68 mg/liter dan pulau Lanyukang 1.05
mg/liter berada diluar ambang batas yang ditetapkan, kondisi perairan ini
berpotensi terjadinya eutrofikasi, Klasifikasi dikemukakan oleh Vollenweider in
Wetzel (1975) in Erna 2008. bahwa kadar ortofosfat perairan dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu; perairan oligotrofik yang memiliki
kadar ortofosfat 0.003 – 0.01 mg/liter, perairan mesotrofik yang memiliki kadar
ortofosfat 0.011 – 0.03 mg/liter, dan perairan eutrofik yang memiliki kadar
ortofosfat 0.031 – 0.1 mg/liter.
Tingginya unsur hara di perairan pesisir kebanyakan dipengaruhi oleh runoff
dari daratan, sedangkan untuk pulau yang jauh dari daratan (offshore).biasanya
tingginya unsur hara diperoleh dari resuspensi dan upwelling. Kasus ini terjadi
pada Pulau Lanyukang, merupakan pulau terjauh dari kota Makassar dan
berhadapan langsung dengan Selat Makassar.di mana angin bertiup cukup
kencang, sehingga mampu mengangkat sedimen dari dasar perairan ke
permukaan. Terkait hal tersebut di atas, tingginya konsentrasi ortofosfat di Pulau
Lanyukang diduga terjadi resuspensi pada kedalaman 2-3 meter akibat tiupan
angin cukup kuat, yang mengangkat nutrien ke permukaan, hal ini sesuai dengan
Cristianzen et al, 1979; Phillips et al, 2005; Dzialowsky et al, 2008 in Prartono
dan Hasena (2009) bahwa resuspensi sedimen merupakan salah satu proses yang
berpotensi memberikan masukan nutrien penting seperti ammonium, nitrat dan
fosfat dari sedimen ke kolom perairan dan berdampak pada pertumbuhan alga.
Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Odum (1971) bahwa perairan dasar
memiliki kandungan nitrat dan fosfat yang lebih besar dibandingkan permukaan.

32
Gambar 7. Konsentrasi ortofosfat di pulau Laelae, pulau Barrang Lompo dan pulau Lanyukang.
Selain itu, tingginya unsur hara di pulau Lanyukang juga diduga karena
akibat mendapat limpasan upwelling dari selat Makassar, hal ini sesuai dengan
berbagai penelitian tentang pengaruh upwelling terhadap kelimpahan fitoplankton
di Selat Banda (Setiadi 2004), di laut Arafura, laut Banda (Wyrtki 1961), Selat
Bali (Ilahude dan Nontji 1975), Selat Makassar (Ilahude 1971), Selatan Jawa-
Sumbawa (Wyrtki 1962), di Laut Flores dan Teluk Bone (Birowo 1975).
3.3 Jenis dan kelimpahan fitoplankton
Jenis dan kelimpahan fitoplankton merupakan salah satu indikator kualitas
perairan. Kelimpahan fitoplankton sangat dipengaruhi oleh cahaya dan unsur hara
(nitrat dan fosfat), tetapi total padatan terlarut di perairan atau TSS mengabsorbsi
cahaya sehingga mengurangi penetrasi cahaya yang sangat dibutuhkan oleh
fitoplankton.
Fitoplankton yang ditemukan selama penelitian terdiri dari 9 jenis dari
kelas Bacillariophyceae dan kelas Dinophyceae. Dari 9 jenis fitoplankton yang
ditemukan saat penelitian, 7 jenis ditemukan di pulau Lanyukang, kemudian 6
jenis di pulau Barranglompo dan 4 jenis ditemukan di pulau Laelae, lebih
jelasnya lihat Tabel 7 di bawah ini.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Laelae Barrang Lompo Lanyukang
Kons
entr
asi (
mg/
l)
Pulau

33
Tabel 7 Jenis dan Kepadatan Fitoplankton di perairan Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang.
Kedua kelas fitoplankton yang ditemukan merupakan kelas utama dan
sering ditemukan pada perairan laut, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh
Nybakken (1988) bahwa diatom (Bacillariophyceae) dan dinoflagellata
(Dinophyceae) merupakan jenis fitoplankton yang umum terdapat di laut,
berukuran besar serta biasa tertangkap oleh jaring plankton dan Diatom
berdistribusi sangat luas serta sering dominan diperairan (Basmi J 1999).
Dari tabel 7 ini terlihat bahwa total Jenis dan kelimpahan fitoplankton
terbanyak dari ketiga pulau tersebut adalah pulau Lanyukang, hal ini diduga kuat
karena letak pulau Lanyukang berada didekat selat Makassar dimana pada musim
timur sering terjadi upwelling yang membawa bukan hanya nutrien tapi juga
fitoplankton ke permukaan. Dengan adanya proses taikan air (upwelling) akan
mempengaruhi kondisi kehidupan fitoplankton, keanekaragaman dan
distribusinya, serta pengayakan nutrisi di perairan tersebut (Olivieri PB, Chapman
A, Mittchell I in Sediadi 2004). Dugaan ini diperkuat bahwa di perairan pulau
Lanyukang telah terjadi upwelling adalah pada saat pengukuran suhu secara in
situ diperoleh suhu sekitar 29oC sementara suhu perairan pengukuran secara in
situ Pulau Laelae dan Pulau Barrang Lompo sekitar 31o
Jenis Fitoplankton
C. Adapun tingginya
kelimpahan genus Chaetoceros sp di perairan Pulau Lanyukang, hal ini juga
diduga ada kaitannya dengan upwelling yang terjadi pada musim timur, hal ini
sesuai dinyatakan bahwa pada musim timur kelimpahan fitoplaknton lebih besar
dari musim peralihan dan juga pada musim timur jenis fitoplankton yang
Kepadatan Fitoplankton (Individu/liter) Laelae Barrang lompo Lanyukang
Coscinodiscus sp 57.6 72 54 Nitzschia sp 79.2 64.8 234 Diatoma sp 21.6 - - Rhizosolenia sp 28.8 108 108 Chaetoceros sp - 108 270 Ceratium sp - 14.4 36 Thalassiothrix sp - 50.4 0 Gymnodinium sp - - 72 Peridinium sp - - 54 Total 187.2 417.6 828

34
mendominasi adalah genus Chaetoceros sp dari kelompok Diatom, begitupula
perairan di Kawasan Timur Indonesia (Sediadi A 2004). Fenomena ini juga
dikuatkan oleh Damar (2003) bahwa pada musim penghujan genera utama
fitoplankton diteluk Jakarta adalah Chaetoceros sp dan Basmi (1999) bahwa
Diatoma dan Ceratoneis lebih senang hidup pada daerah temperate yang lebih
dingin, sehingga mereka berkembangbiak sangat baik pada musim dingin itu.
Untuk melihat jenis dan kelimpahan fitoplankton tersebut lebih jelasnya
dapat dilihat dari Gambar 8 dibawah ini.
Gambar 8. Jenis dan Kepadatan Fitoplankton di Pulau Laelae, Pulau Barrang
Lompo dan Pulau Lanyukang.
. Jenis fitoplankton yang tertinggi saat penelitian adalah Chaetoceros sp yaitu
270 individu/liter, yang ditemukan di pulau Lanyukang, namun jenis fitplankton
ini tidak ditemukan di pulau Laelae, selain itu tidak semua jenis fitoplakton sama
ditemukan berada di setiap lokasi penelitian. Total kelimpahan fitoplakton
tertinggi adalah di pulau Lanyukang 828 individu/liter, kemudian pulau
Barranglompo 417.6 individu/liter dan pulau Laelae 187.2 individu/liter.
Tingginya kelimpahan fitoplankton di pulau Lanyukang selain disebabkan oleh
upwelling. Selain itu, dalam penelitian juga ditemukan adanya perbedaan jenis
dan kelimpahan fitoplankton antar pulau, hal ini didasari dari perhitungan analisis
varians (anova) diperoleh hasil F-hitung (4.301) > F-tabel (3.633). Hal lain yang
diperoleh dari penelitian ini bahwa di pulau Laelae sedikit ditemukan jenis
fitoplankton yaitu; Coscinodiscus sp, Nitzschia sp, Thalassionema sp,
Rhizosolenia sp. Rendahnya jenis fitoplankton di pulau Laelae dibandingkan
dengan Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang diduga karena tingginya
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Laelae Barrang lompo Lanyukang
Kelim
paha
n (In
d/lit
er)
Coscinodiscus sp
Nitzschia sp
Diatoma sp
Rhizosolenia sp
Chaetoceros sp
Ceratium sp
Thalassiothrix sp
Gymnodinium sp
Peridinium sp

35
konsentrasi konsentrasi TSS yang mengurangi penetrasi cahaya. Faktor lain yang
menyebabkan tinggi rendahnya jenis dan kelimpahan fitoplankton adalah ratio N/
P dan P di suatu perairan. Rasio N : P disuatu badan air dapat digunakan untuk
menduga jenis alga yang mungkin terdapat pada konsentrasi nutrien berbeda
(Warsa et al. 2006 ).
4.4 Keterkaitan Fitoplankton dengan Kondisi Perairan
Jenis dan kelimpahan fitoplankton terkait erat dengan kondisi perairan
seperti tingkat kesuburan dan tingkat pencemaran perairan dimana bila unsur N
dan P melimpah akan menimbulkan blooming fitoplakton, hal ini sesuai dengan
Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8 Kriteria kesuburan berdasarkan N dan P serta nilai biomas dan produktivitas primer fitoplankton.
Parameter Tingkat kesuburan Perairan
Oligotrofik Mesotrofik Eutrofik N anorganik (pbb) 0-200 200-400 400-650 P-Total (pbb) 0-5 5.-10 .10-30
Biomassa (mg berat kering/m 20-200 3 200-600 600-10.000 Produktivitas primer(gr berat kering/m2 /thn) 15-50 50-150 150-500
Dalam kaitannya dengan pertumbuhan fitoplankton, maka konsentrasi
ortofosfat dan nitrat dari ketiga pulau tersebut berada dalam kisaran
pertumbuhan optimal bagi kehidupan fitoplankton. Hal ini sesuai dengan yang
dikemukan oleh Wardoyo (1975) in Erna bahwa untuk pertumbuhan optimal
fitoplankton memerlukan kandungan ortofosfat pada kisaran 0.09-1.80 mg/l, dan
sesuai juga dengan kriteria fosfat menurut Joshimura in Liaw (1969) in
Simanjuntak M (2003), lihat Tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9 Kriteria kesuburan perairan menurut Joshimura in Liaw 1969.
Kandungan fosfat (mg/liter) Kesuburan Perairan 0.000-0.020 Rendah
0.021-0.050 Cukup
0.051-0.100 Baik
0.101-0.200 Baik sekali

36
Sedangkan menurut Perkins (1974) in Erna (2008), kandungan ortofosfat
yang terdapat diperairan umumnya tidak lebih dari 0,1 mg/l, kecuali pada perairan
yang menerima limbah dari rumah tangga dan industri tertentu, serta dari daerah
pertanian yang mendapat pemupukan fosfat. Oleh karena itu, ketiga perairan
pulau tersebut di atas yang mengandung mengandung unsur N dan P yang cukup
tinggi melebihi kebutuhan normal organisme akuatik sehingga berpeluang
menyebabkan terjadinya blooming fitoplankton tertentu.
Selain kondisi lingkungan yang eutrofik dari ketiga pulau tersebut, juga
diduga tercemar, hal ini dibuktikan dengan kehadiran diatom Nitzschia sp di
perairan ketiga pulau tersebut, hal ini sesuai dengan Basmi (1999) bahwa sistem
saprobik yang dipakai sebagai indikator tingkat pencemaran kondisi perairan
berdasarkan organisme fitoplankton termasuk Diatom antara lain Nitzschia sp,
Hantzcschia amphioxys, Stephanodiscu hantzschii, merupakan penghuni perairan
α-mesosaprobik yang merupakan indikator biologi bahwa perairan yang dihuninya
tercemar berat.
Jenis dan kelimpahan fitoplankton di pulau Laelae ditemukan hanya 4 jenis
fitoplankton (lihat tabel 6), hal ini diduga kuat karena terjadi pencemaran perairan
di pulau Laelae sehingga mengakibatkan fitoplankton tertentu saja yang mampu
beradaptasi, hal ini sesuai dengan Ravera (1979) in Basmi (1999) bahwa
keberadaan Diatom di perairan yang terpolusi dan tidak terpolusi akan mem-
perlihatkan perbedaan baik dalam jumlah spesies maupun jumlah individu per
spesies.
4.5. Kepadatan zooxanthellae dan nutrien
Simbiosis antara karang dan zooxanthellae sangat sensitif dengan gangguan
lingkungan, ketika karang terkena gangguan maka karang akan nampak memutih
akibat kehilangan zooxanthellae. peristiwa ini disebut bleaching (Brown and
Ogden 1993 in Hidaka & Miyagi 1999). Keluarnya zooxanthellae dari inangnya
dapat disebabkan oleh kenaikan suhu, salinitas, dan runoff yang meningkatkan
nutrien perairan.
Anorganik itu merupakan sisa metabolisme karang dan hanya sebagian kecil
anorganik diambil dari perairan. Begitupula sebaliknya kehidupan karang
hermatipik sangat tergantung oleh keberadaan zooxanthellae. Tanpa zooxanthellae

37
karang akan mengalami kematian. Dari hasil penelitian ini, diperoleh bahwa nilai
rata-rata kepadatan zooxanthellae antar pulau (Pulau Laelae, Pulau Barrang
Lompo dan Pulau Lanyukang adalah berbeda.
Tingginya kepadatan zooxanthellae di Pulau Lanyukang dibandingkan dua
pulau lain karena polip karang yang berada di Pulau Lanyukang ini mendapat
sumber makanan yang melimpah berupa partikel terlarut dan zooplankton yang
berasal dari resuspensi dan upwelling. Kesemuanya ini merupakan sumber
makanan, hal ini sangat menguntungkan bagi polip karang karena sifat karang
yang heterotrofik di mana karang merupakan predator rakus bagi zooplankton
(Titlyanov et al. 2000; Grottoli 2002; Ferrier P et al. 2003; Fabricus dan Metzner
2004; Palardy et al 2005 in Haulbreque F dan Ferrier 2008).
Perubahan pola makan karang dari autotrofik ke heterotrofik merupakan
adaptasi karang yang umumnya hidup di perairan oligotrofik, namun tekanan
lingkungan dalam hal ini upwelling dan resuspensi yang terjadi di Pulau
Lanyukang di mana kedua faktor ini meningkatkan nutrien dan partikel terlarut
yang melimpah di sekitar perairan sehingga karang memakan partikel terlarut
(
Akibat tersedianya nutrien, partikel terlarut, zooplankton dan fitoplankton
yang melimpah, menjadikan polip karang active feeding, dengan demikian polip
akan tumbuh membesar karena banyaknya sumber makanan yang tersedia dan
memberi ruang bagi zooxanthellae untuk berkembangbiak, di sisi lain hasil
buangan dari polip karang akan dimanfaatkan oleh zooxanthellae untuk
membelah diri. Sifat heterotrofik dari polip karang inilah sehingga polip memiliki
kemampuan survive tinggi selain sifat autotrofik yang dimilikinya, dan sifat
hererotrofik ini menunjukkan bahwa polip karang tidak mutlak tergantung pada
produksi zooxanthellae. Sifat heterotrofik ini di gunakan karang bila perairan
melimpah partikel terlarut seperti di Pulau Lanyukang. Berbeda halnya dengan di
Pulau Laelae, kepadatan zooxanthellae terendah karena ada pengaruh sedimentasi
Anthony& Fabricius 2000).
yang terbawa runoff dari daratan utama. Hal ini dapat dilihat dari tingginya
konsentrasi TSS, dan hasil pengamatan langsung kondisi perairan Laelae yang
menunjukkan perairan warna hijau akibat pertumbuhan makroalga. Perbedaan
kepadatan zooxanthellae tersebut dapat dilihat dari Tabel 10 di bawah ini.

38
Tabel 10 Kepadatan zooxanthellae pada lokasi penelitian di Pulau Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang (n=3).
Pulau Jenis Karang Rerata Kepadatan Zooxanthellae (sel/cm2 Total
) Laelae Acropora appressa 2.54E+05
Porites lobata 2.76E+05
Acropora sp 1.53E+05
5.57E+05
Barrang Lompo Porites mayeri 5.57E+05
Porites Lobata 2.98E+05
Acropora appressa 6.45E+05
4.50E+06
Lanyukang Acropora appressa 7.89E+05
Acropora formosa 4.83E+05
Montipora sp 7.54E+05 6.08E+06
Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan ANOVA single factor
kepadatan zooxanthellae A. appressa antar pulau adalah tidak berbeda, di mana F-
hitung (9,34) > F-tabel (5,14) hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
kepadatan zooxanthellae antar pulau. Sedangkan perhitungan ANOVA single
factor kepadatan antar spesies dari ketiga pulau tersebut di atas di mana diperoleh
hasil perhitungan masing-masing pulau yaitu; Pulau Laelae dengan F-hitung
(2,57) < F-tabel (5,14 ), Pulau Barranglompo F-hitung (1,11) < F-tabel (5,14) dan
Pulau Lanyukang F-hitung (2,94) < F-tabel (5,14), dari perhitungan statistic
ANOVA ini menunjukkan bahwa ketiga pulau di atas secara keseluruhan adalah
berbeda secara signifikan artinya kepadatan zooxanthellae antar spesies pada
perairan di pulau yang sama adalah relatif berbeda, hal ini menunjukkan bahwa
antar spesies karang walaupun tinggal dilokasi yang sama tetapi respon yang
diberikan setiap spesies adalah berbeda. Hal ini disebabkan fisiologi setiap hewan
karang terhadap lingkungan sangat variasi, hal ini sesuai pernyataan Hidaka,
Miyagi 1999 bahwa dalam satu spesies perbedaan kepadatan zooxanthellae bisa
berbeda, umumnya pada bagian tip dari karang lebih besar dari pada pada bagian
basal (bottom), hal ini bisa diduga karena penetrasi cahaya lebih mudah diperoleh
pada bagian tip karang.
Adapun rerata kepadatan zooxanthellae antar spesies di masing-masing
pulau dapat dilihat dari Gambar 8 sebagai berikut:

39
Gambar 8. Jenis karang dan kepadatan zooxanthellae di Pulau Laelae, Pulau
Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang (n=3).
0,00E+00
5,00E+04
1,00E+05
1,50E+05
2,00E+05
2,50E+05
3,00E+05
3,50E+05
4,00E+05
Acropora appressa Porites lobata Acropora sp
jum
lah
zoox
anth
ella
e(se
l/cm
2)
Jenis karang
Pulau Laelae
0,00E+00
1,00E+05
2,00E+05
3,00E+05
4,00E+05
5,00E+05
6,00E+05
7,00E+05
8,00E+05
Porites mayeri Porites Lobata Acropora appressa
Jum
lah
zoox
anth
ella
e (s
el/m
2)
Jenis Karang
Pulau Barrang Lompo
0,00E+00
2,00E+05
4,00E+05
6,00E+05
8,00E+05
1,00E+06
1,20E+06
1,40E+06
Acropora appressa Acropora formosa Montipora sp
Jum
lah
zoox
anth
ella
e(se
l/cm
2)
Jenis Karang
Pulau Lanyukang

40
Active feeding polip karang pada kondisi perairan tidak normal merupakan
suatu upaya dari fisiologi polip untuk mempertahankan diri supaya kepadatan
zooxanthellae tetap stabil yaitu berkisar 1-2,5 x 106 sel/cm2
Sifat dan karakter active feeding atau hererotrofik dari karang di perairan
non-oligotrofik merupakan sebuah mekanisme adaptasi karang terhadap
gangguan, dalam hal ini polip karang menyerap partikel tersuspensi dari perairan,
selain untuk kebutuhan energinya juga untuk mengurangi endapan partikel di
tubuhnya sehingga zooxanthellae bisa optimal menerima cahaya walaupun
penetrasi cahaya di perairan non-oligotrofik adalah rendah. Kondisi adaptasi
karang ini akan berlangsung terus sampai kondisi lingkungannya normal.
(Drew 1972;
Muscatine et al. 1989 in Jones &Yellewlees 1999) di dalam jaringan polip karang,
dengan cara memanfaatkan partikel organik dan zooplankton sebanyak mungkin,
hal ini dilakukan agar suplai unsur hara tetap terjaga. Oleh karena itu polip
mampu memberi suplai anorganik yang cukup bagi zooxanthellae (Hidaka &
Miyagi 1999). Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa kepadatan
zooxanthellae di perairan tersebut berada di bawah kondisi normal (pristine).
Rendahnya kepadatan zooxanthellae di dalam penelitian ini menunjukkan adanya
gangguan dari lingkungan perairan terhadap kehidupan karang. Walaupun
gangguan atau tekanan dari lingkungan dalam hal ini adalah masukan nutrien di
perairan, yang justru meningkatkan kepadatan zooxanthellae namun peningkatan
kepadatan zooxanthellae tersebut tidak mampu mencapai kepadatan zooxanthellae
pada kondisi normal. hal ini terjadi karena perairan ketiga pulau ini adalah bukan
kondisi perairan oligotrofik sesuai yang dibutuhkan oleh karang.
Tingginya kadar nitrat dan ortofosfat pada perairan ketiga pulau tersebut
merupakan komponen penting bagi zooxanthellae untuk pertumbuhan dan
perkembangbiakannya, namun nutrien yang dibutuhkan oleh zooxanthellae hanya
sedikit saja karena sebagian besar nutrien berasal dari inangnya. Sebaliknya
tingginya kadar nitrat dan fosfat diperairan juga meningkatkan pertumbuhan
fitoplankton dan makroalga. Bila kepadatan fitoplankton dan makroalga
meningkat tajam maka penetrasi cahaya yang tembus ke dasar perairan dimana
karang berada, akan berkurang, sehingga mengurangi kapadatan zooxanthellae
pada polip karang. Menurut Glynn 1990 in Thamrin 2006 bahwa sedikit saja

41
perubahan lingkungan perairan maka secara drastis akan mempengaruhi stabilitas
kepadatan zooxanthellae di dalam karang.
4.5 Kepadatan Zooxanthellae dan Total Suspended Solid (TSS)
Konsentrasi TSS yang tinggi dapat mempengaruhi penetrasi cahaya yang
masuk ke perairan. Penetrasi cahaya rendah akan mengurangi proses fotosintesis.
yang dilakukan oleh zooxanthellae, sehingga berdampak pada penurunan
kepadatan zooxanthellae, hal ini dapat dilihat dari nilai TSS pulau Laelae
tertinggi 7 mg/liter dengan nilai kepadatan zooxhantellae terendah berkisar 1,53
x 105 hingga 2,54 x 105 atau rata 2.28 x 105 sel/cm2, sebaliknya dengan nilai
TSS yang lebih rendah, tetapi kepadatan zooxanthellae adalah tinggi seperti yang
terjadi di pulau Barrang Lompo 5.00 x 105 sel/cm2 dan pulau Lanyukang 6.75 x
105 sel/cm2. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian kepadatan zooxanthellae pada
karang A. aspera di pulau Poncan dan pulau Mursala Sibolga Sumatera Utara
menunjukkan ada pengaruh tingkat kekeruhan terhadap kepadatan zooxanthellae
(Thamrin et al. 2004). Berbeda halnya dengan nilai TSS dari Pulau Barrang
Lompo 4 mg/l lebih rendah dari nilai TSS Pulau Lanyukang 6 mg/l, akan tetapi
rata-rata kepadatan zooxanthellae Pulau Barrang Lompo juga lebih rendah dari
Pulau Lanyukang. Diduga bahwa pengaruh nilai TSS sudah berkurang,
dibandingkan dengan nilai nitrat dan ortofosfat, hal ini bisa dilihat bahwa nilai
TSS ketiga pulau tersebut masih dalam kondisi normal yaitu masih dalam kisaran
0 mg/l sampai 10 mg/l (Larcombe et al 1995; Roger 1990 in Thamrin 2006),
sementara nilai nitrat dan fosfat sudah melewati ambang batas baku mutu air laut
(KLH 2004) sehingga kepadatan zooxanthellae dari ketiga pulau tersebut adalah
di bawah kondisi perairan normal 1 - 2,5 x 106 sel/cm2
Laju partikel dan sedimen yang terbawa oleh runoff dari daratan akan
semakin berkurang dengan jauhnya jarak tempuh partikel tersebut, hal ini
disebabkan karena selama partikel dan sedimen terbawa arus terjadi absorsi dan
pencucian di kolom perairan. Namun dalam kasus ini, meningkatnya kepadatan
zooxanthellae bukan karena jarak yang semakin jauh atau rendahnya runoff dari
daratan, tetapi disebabkan oleh adanya upwelling di perairan Pulau Lanyukang
yang membawa senyawa fosfat dan nitrat yang dibutuhkan oleh zooxanthellae.
(Drew 1972; Muscatine et
al. 1989 in Jones & Yellewlees).

42
4.6 Keterkaitan kepadatan zooxanthellae dan kelimpahan fitoplankton
Secara umum kita ketahui bahwa zooxanthellae dan fitoplankton adalah
sebagai produsen primer diperairan karena memiliki klorofil sehingga mereka
dapat mensintesa makanan sendiri lewat bantuan sinar matahari atau fotosintesis,
yaitu mengubah nutrien anorganik utamanya nitrat dan fosfat menjadi organik.
Dalam penelitian ini, kepadatan zooxanthellae dan kelimpahan fitoplankton
menunjukkan peningkatan yang sama. Keduanya meningkat seiring dengan jarak
atau letak pulau yang semakin jauh dari daratan utama semakin meningkat
kepadatan dan kelimpahan mereka. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini;
Gambar 10. Kepadatan zooxanthellae dan kelimpahan fitoplankton di Pulau
Laelae, Pulau Barrang Lompo dan Pulau Lanyukang. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa keduanya fitoplankton dan
zooxanthellae merupakan alga yang memiliki peran sama dalam ekosistem
perairan sebagai produktifitas primer perairan. Pengaruh kondisi perairan tempat
di mana mereka sama-sama hadir tentunya akan berdampak relatif sama pada
mereka berdua. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pendekatan sebagai berikut;
(1) Bahwa berdasarkan definisi fitoplankton yaitu tumbuhan laut melayang layang
diperairan terbawa arus dan dapat berfotosintesis, dengan berbagai ukuran. Jenis
yang biasa tertangkap dengan plankton net umumnya adalah Diatom dan
Dinoflagellata (Nybakken 1988). (2) Peranan fitoplankton dalam ekosistem
perairan laut sangat penting sebagai penyedia energi dan beberapa jenis
diantaranya Gymnodinium mikroadriaticum (Dinoflagellata) membentuk simbion
0
5
10
15
20
25
30
Laelae Barrang Lompo Lanyukang
Kepa
data
n
Pulau
zooxanthellae (sel/cm2)
fitoplankton (sel/ml)

43
sebagai zooxanthellae yang mampu bersimbiosis dengan hewan karang (Wibisono
2005). Berdasarkan kedua pendekatan ini, menunjukkan bahwa zooxanthellae
merupakan fitoplankton juga yang berukuran lebih kecil, bahkan tidak bisa
ditangkap dengan plankton net. Oleh karena keduanya adalah termasuk kelompok
tumbuhan renik maka secara umum apa yang berlaku pada fitoplankton juga akan
berlaku pada zooxanthelllae seperti kebutuhan nutrien dan cahaya sebagai faktor
pembatas.Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa zoozanthellae adalah alga
tentunya memerlukan nutrien dan cahaya untuk pembelahan diri.
Selanjutnya kaitan antara kepadatan zooxanthellae dengan nutrien,
menunjukan pola yang tidak linear. Nutrien di Pulau Barrang lompo lebih rendah
dari nutrien perairan Pulau Laelae dan Pulau Lanyukang, sedangkan kepadatan
zooxanthellae meningkat berdasarkan jarak. ini menggambarkan kompleksnya
faktor yang mempengaruhi kepadatan zooxanthellae, tidak hanya nutrien saja
tetapi faktor lain seperti cahaya, suhu, musim dan tingkat pencemaran pollutan di
perairan. Adapun gambaran kondisi kepadatan zooxanthellae dengan nutrien dan
TSS dapat dilihat dari Gambar 11 di bawah ini.
Gambar 11. Kepadatan zooxanthellae dan kandungan nutrient perairan.
4.7 Kepadatan zooxanthellae dan pengelolaan terumbu karang
Kepadatan zooxanthellae di dalam polip di bawah kondisi normal relatif
stabil berkisar 1- 2,5 juta sel/cm2 (Drew 1972; Muscatine et al. 1989 in Jones dan
Yellewlees). Apabila ada tekanan dari lingkungan luar maka salah satu respon
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
2 12,77 40,17
Jarak (km)
zooxanthellae density(cells/cm2)TSS (mg/l)
Nitrate (mg/l)
phosfate (mg/l)

44
yang ditunjukkan oleh polip karang adalah mengeluarkan zooxanthellaenya.atau
memakan zooxanthellaenya sendiri sebagai usaha untuk mempertahankan kondisi
normal dari kepadatan zooxanthellae (Muscatine dan Pool 1979, Muscatine et al
1985 in Titlyanov at al. 1996 ), atau pada malam hari kepadatan zooxanthellae
yang berada di tentakel berkurang 6 % karena karang aktif makan pada malam
hari dibandingkan dengan siang hari. Dengan demikian dinamika kepadatan
zooxanthellae adalah penting untuk memahami fisiologi karang dalam
menghadapi ancaman-ancaman aktivitas manusia, khusus perubahan iklim dunia
(Glynn 1996;Hoegh-Guldberd 1999; Donner et al. 2005 in Thamrin 2006).
Berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa respon karang terhadap
tekanan lingkungan luar adalah hilangnya atau keluarnya zooxanthellae dari polip
karang yang merupakan bentuk adaptasi. Perbedaan kepadatan zooxanthellae
antar spesies juga menunjukkan perubahan pola musim, di mana respon karang
terhadap berbagai faktor lingkungan pada musim summer lebih rendah kepadatan
zooxanthellae daripada musim winter (e.g Stimson 1997; Fagoonee et al. 1999;
Brown et al. 1999; Fitt et al. 2000 in Pillay et al. 2005).
Peningkatan kepadatan zooxanthelae akibat ammonium dan fosfat justru
menurunkan laju pertumbuhan karang, contoh kasus ini terjadi pada Pocillopora
damicornis (Stembler et al 1995). Contoh lain, pada percobaan laboratorium 4
tahap peningkatan unsur hara (nitrat dan fosfat) pada 40 Stilophora pistilata
ternyata menurunkan kepadatan zooxanthellae 60% (Ferrier-Pages at al. 1999).
Pada saat kepadatan zooxanthellae rendah di bawah kondisi normal, maka
suplai energi ke inangnya akan berkurang sehingga kesehatan polip terganggu,
laju kalsifikasi berkurang rendahnya kepadatan zooxanthellae dan rendahnya
penetrasi cahaya sehingga pembentukan terumbu jadi lambat.
Bagi polip karang yang kurang sehat, menghasilkan planula yang tidak
berkualitas di mana planula ini memiliki kemampuan settlement yang rendah pula.
Begitupula laju kalsifikasi akan rendah ketika kepadatan zooxanthelae menurun
(Muller-Parker & D’Elia 1997). Dengan kepadatan zooxanthellae di bawah
kondisi normal berdampak pada daya tahan polip karang terhadap lingkungannya.
Pada kondisi lemah karang tidak mampu menghadapi invasi makroalga yang lama
kelamaan akan mengubah struktur komunitas terumbu karang dari awalnya

45
didominasi oleh terumbu karang berubah jadi didominasi oleh makroalga,
sehingga keanekaragaman hayati rendah, produktifitas sekunder berkurang.
Perubahan degradasi terumbu karang dalam jangka pendek (harian) dapat dilihat
dari perubahan kepadatan zooxanthellae.
Pengelolaan jangka panjang terumbu karang (sustainable) tentunya di
awali dari monitoring jangka pendek. Kesehatan terumbu karang berhubungan
dengan faktor lingkungan. Kesehatan terumbu karang dapat diduga dari pola
hubungan simbiosis karang dengan zooxanthellae sebagai elemen dasar
pembangun terumbu. Kesehatan polip karang dapat diukur dari kepadatan
zooxanthellae, dan kepadatan zooxantellae sendiri sangat respon terhadap
perubahan lingkungan baik itu cahaya, suhu, salinitas maupun unsur hara, dengan
demikian fluktuasi kepadatan zooxanthellae dapat dijadikan sebagai biondikator
dalam respon terhadap fisiologi karang dan perubahan lingkungan.

45
5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil uraian tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah
sebagai berikut;
1. kepadatan zooxanthellae Acropora appressa antar pulau tidak berbeda
nyata, begitupula kepadatan zooxanthellae antar spesies di pulau yang
sama, namun secara keseluruhan rata-rata kepadatan zooxanthellae.antar
pulau adalah berbeda nyata.
2. Kisaran kepadatan zooxanthellae yang terendah di Pulau Lae-lae berkisar
1,53 x 105 sel/cm2 sampai 2,76 x 105sel/cm2, di Pulau Barrang Lompo
berkisar 2,98 x 105 sel/cm2 sampai 6,45 x 105 sel/cm2 dan Pulau
Lanyukang berkisar 4,83 x 105 sel/cm2 sampai 7,89 x 105 sel/cm2
3. Perbedaan jenis dan kelimpahan fitoplankton maupun kepadatan
zooxanthellae antar pulau dipengaruhi oleh masukan nutrien yang berasal
dari pengaruh runoff dan upwelling.
.
4. Perbedaan konsentrasi masukan nutrien dari ketiga pulau tersebut terjadi
akibat runoff dari daratan utama dan upwelling dari Selat Makassar.
5. Kepadatan zooxanthellae dan kelimpahan fitoplankton secara berurutan
yaitu; Pulau Laelae lebih kecil dari Pulau Barrang Lompo, dan Pulau
Barrang Lompo lebih kecil dari Pulau Lanyukang.
5.2. Saran
Karena penelitian ini berlangsung pada musim peralihan sehingga perlu
penelitian lanjutan pada musim barat dan musim timur dengan lokasi yang sama.
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tahunan dari fluktuasi kepadatan
zooxanthellae terkait pola musim.
Perlu juga penelitian kemampuan daya tahan polip karang terhadap pengaruh
runoff dan upwelling dengan pendekatan kepadatan zooxanthellae dari speseis-
spesies yang ada di lokasi tersebut.

49
DAFTAR PUSTAKA
Afdal, Riyono H. 2004. Sebaran klorofil-a kaitan dengan kondisi hidrologi selat Makassar. Oceanologi dan Limnologi Indonesia 36: 69-82
Anthony K, Fabricius KE. 2000. Shifting roles of heterothropy and autotrophy in coral energetic under varying turbidity. J Exp Mar Biol and Ecol 252: 221-253.
[APHA] American Public Health Assosiation. 1992. Standard Methods for the Examination of Water.and wastewater 17th ed. [AWWA] American Water Works Association. Water Pollution Control Federation. Washington, DC: APHA.
Benson, A.A., J.S. Patton and S. Abraham. 1978. Energy exchange in coral reef ecosystems. Atoll Res .Bull 26: 35-55.
Basmi JH. 1999. Planktonologi; Chrysophyta-Diatom Penuntun Identifikasi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Bonsdorff' E, Blomqvist EM, Mattila J, Norkko A. 1997. Coastal eutrophication: causes, consequences and perspectives in the archipelago areas of the Northern Baltic Sea. Estuarine, Coastal and Shelf Science 44: 63-72.
Burke L, Selig E, Spalding M 2002. Reef at risk in South East Asia.
Brown BE, Howard LS. 1985. Assessing the Effect of Stress on reef coral. Mar Biol 22: 1-63.
www.wri.org/reefatrisk.
Cesar, Beukering, Pintz, Dierking. 2002. Economic valuation of the coral reefs of Hawaii. Final report. The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Coastal Ocean Program.
Coles SL. 1988. Limitation of reef coral development in the Arabian Gulf : temperatur or algal competition. Proc. 6th
Colha MW. 1981. Succession and Recovery of a coral reef after predation by Acanthaster planci (L). Proc. 4
Int. Coral Reef Symp. Australia.
th
Cook CB. 1990. Elevated temperature and bleaching on a high latitude coral reef the 1988 Bermuda event. Coral reefs 9 : 45-90
Int. Coral Reef Symp. Philippines.
Dahuri R, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, Sitepu MJ. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu. Hal 42, edisi ketiga. Penerbit Pradnya Paramita.
Damar A. 2003. Effects of enrichment on nutriens dynamics, phytoplankton dynamics and primary production in Indonesian tropical water ; A comparison between Jakarta Bay, Lampung Bay and Semangka Bay. [PhD Thesis], the Faculty of Mathematic and Natural Sciences, Christian-Albrechts-Universität Kiel. Germany. 1-249.

50
Drew EA. 1992. The biology and physiology of alga invertebrate symbioses. II. The density if symbiotic algal cells in a number of hermatypic hard corals and aleyonarians from various depths.J Exp Mar Biol 9: 71 – 75.
Effendi H. 2000. Telaahan kualitas air bagi pengelolaan sumberdaya dan lingkungan perairan. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.
Erna. 2008. Sebaran klorofil a hubungannya dengan parameter oseanografi di perairan Pulau Laelae Makassar.[Skripsi]. Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.
Ferrier- Pages, Gattuso jp, Dallot S, Jaubert J. 2000. Effect of nutrient enrichment on growth and photosynthesis of the zooxanthellae coral Stilophora pistilata. Coral reefs 19: 103-113. Springer-Verlag.
Glick P. 1999. Coral reef and climate change, last straw for threatened ecosystem. National Wildlife Federation’s Climate Change & Wildlife Program.
[GBRMPA] Great Barrier Reef Marine Park Authority. 2008. Water Quality Guideline for the Great Barrier Reef Marine Park. Australian Government. Townsville. GBRMPA. 1-127p.
Goreau TF. 1959. The physiology of skeleton formation in corals. I. A method
for measuring the rate of calcium carbonate deposition by corals under different conditions. Biological Bulletin 116: 59–75.
Guzman HM, Cortes J. 1992. Coral reef community structure at Cano Island, Pacific Costa Rica. J. Mar. Ecol. 10: 23-41.
Gladfelter EH. 1985. Metabolism, calcification and carbon production. Proc 5th Int Coral Reef Symp 4:527-539
Heddy, Suwasono. 1994. Prinsip-prinsip dasar ekologi suatu pembahasan kaidah ekologi dan penerapannya. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Hutagalung HP, Rozak. 1997. Metode Analisis Air Laut, Sedimen dan Biota : Buku 2. P3O-LIPI, Jakarta.
Indrawan M, Primack RB, Supriana J 1998. Biologi Konservasi. Yayasan Obor Indonesia.Edisi Revisi.345
Hidaka M, Miyagi A. 1999. Does Enrichment by Inorganic Nutriens Prevent Bleaching in The Coral Galaxea facicularis Exposed to High Temperature?. J. Japanese Coral Reef Society 1:3-7.
Jasques TG. 1983. Experimental ecology of the temperate schleractinia coral Astrangia danae. Effect of temperature, light intensity and Symbidinium sp.
Johannes R E, Wiebe WJ. 1970. Method for determination of coral tissue biomass and composition. Limnol Oceanogr 15: 822-824

51
Jones RJ, Yellowlees. 1997. Regulation and control in intracelleler algae (=zooxanthellae) in hard coral. Phil Trans R Soc Lond B 352: 457-468.
Jones RJ. 1997. Zooxanthellae loss as bioassay for assesssing stress in corals. Mar Ecol Prog Ser 149:163-171.
Jompa J, Cook M. 2002. The effects of nutrients and herbivory on competition between a hard coral (Porites cylindrica) and a brown alga (Lobophora variegata) Limnol Oceanogr 47:527–534
Jompa J, Moka W, Yanuarita D. 2005. Kondisi Ekosistem Perairan Kepulauan Spermonde: Keterkaitannya dengan Pemanfaatan Sumberdaya Laut di Kepulauan Spermonde. Makassar; Pusat Studi Terumbu Karang (PSTK). Universitas Hasanuddin (UNHAS).
Jompa J, Nurliah,.Yanuarita. 2006. Dampak Eutrofikasi Terhadap Ekosistem Terumbu Karang di Kepulauan Spermonde Sulawesi Selatan. Pros. Konferensi Nasional.
Leletkin VA. 2000a. Trophic Status and Population Density of Zooxanthellae in Hermatypic Corals. Russian Journal of Marine Biology 26:231-240 Institute of Marine Biology, Far East Division, Russian Academy of Sciences, Rusia: Vladivostok.
Leletkin VA. 2000b The Energy Budget of Coral Polyps. Russian Journal of Mar Biol 26: 389–398
Lestari IB. 2009. Pendugaan konsentrasi total suspended solid (tss) dan transparansi perairan teluk Jakarta dengan citra satelit landsat. [Skripsi]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
Loya H, Lubinevsky, Rosenfeld M, Kramarsky. 2004. Nutrien Enrichment Caused by in situ Fish Farm at Ailat Red Sea is Detrimental to coral Reproduction. Mar Pol Bull 49: 344-353. Elsevier Science Direct.
Marubini F, Davies PS. 1996. Nitrate increases zooxanthellae population density and reduces skeletogenesis in corals. Jour Mar Biol 127: 319-328. Springer Verlag.
[KLH] Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2004. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. Jakarta. KLH.
Melati 2006. Metode Sampling Bioekologi. Penerbit Bumi Aksara. Ed ke-1 Jakarta.
Muller-Parker, D’Elia CF. 1997. Interactions between corals and their symbiotic algae. Editor: C. Birkeland (Ed). Life and Death of Coral Reefs. Chapman & Hall. New York. 96-113
Muscatine L, McCloskey, Marian RE. 1981. Estimating the daily contribution of carbon from zooxanthellae to coral animal respiration. Limno. Oceanogr. 26: 601-611.

52
Muscatine L. 1990. The role of symbiotic algae in carbon and energy flux in reef coral. in: Dubinsky Z. (Ed). Coral reefs ecosystem in the world. Elsevier. Amsterdam.
Muscatine L, Valkowsky PG, Dubinsky, Cook PA, McCloskey LR. 1989. The effects of external nutriens resources on the population dynamic of zooxanthellae in coral reef. Jour Biological Sciences. Proc. R. Soc. 236: 311-324.
Nathan L, Andras JP, Harvell, Coffroth. 2009. Population structure of Symbiodinium sp. Associated with the common sea fan, Gorgonia ventalina, in the Florida Keys across distance, depth, and time. Mar Biol. Springer-Verlag 156:1609–1623.
Nixon SW. 1995 Coastal marine eutrophication: A definition, social causes, and future concerns. Ophelia 41; 199-219.
Nganro NR. 1992. Development of a tropical marine water quality bioassay using symbiotic coelenterata. [Ph.D. Thesis], the Univ. of Newcastle upon tyne, UK. 1-225.
Nybakken, J.W. 1988. Biologi Laut, Suatu Pendekatan Ekologis. Penerbit Gramedia. Jakarta. Penerjemah Eidman,Koesoebiono, Bengen DG, Hutomo M, Sukardjo. 458 hal.
Nybakken JW. 1996. Marine Biology: An ecological approach. Fourth Edition An imprint of Addition Wesley Longman, Inc.
Nontji A. 1992. Laut Nusantara. Cetakan ketiga. Penerbit PT. Djambatan. Jakarta
Oliver JK. 1984. Intra-colony variation in the growth of Acropora formosa: Extension rates and skeletal structure of white (zooxanthellae-free) and brown-tipped branches. Coral Reefs 3: 139–147.
.
Setyobudianti I,Sulistiono, Yulianda F, Kusmana C,Hariyadi S, Damar A, Sembiring A, Bahtiar. 2009. Sampling dan Analisis Data Perikanan dan Kelautan, Terapan Metode Pengambilan Contoh di wilayah Pesisir dan Laut. Makaira FPIK. Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.
Simanjuntak M. 2003. Kadar fosfat, nitrat dan silikat kaitannya dengan kesuburan di perairan delta Mahakam, Kalimantan Timur. Seminar Nasional Kimia dan Kongres Nasional Himpunan Kimia Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Setiadi A. 2004. fitoplankton di perairan laut Banda dan sekitarnya. J Makara sains. 8: 43-51
Efek upwelling terhadap kelimpahan dan distribusi
Stambler N, Popper N, Dubinsky, Stimson J. 1991. Effects of Nutrient
Enrichment and Water Motion on the Coral Pocillopora damicornis 45: 299-307. University of Hawaii Press.

53
Stambler. 1999. Coral reefs and eutrophication. Mar Biol. 360-361
Suharsono, Kiswara, Wawan. 1984. Kematian alami karang di Laut Jawa. Oseana 9 : 31-40.
Suharsono. 2008. Jenis-jenis Karang di Indonesia. COREMAP-LIPI. Jakarta.
Thamrin. 2004. Karang, Biologi Reproduksi dan Ekologi. Penerbit Minamandiri Pres. Pekanbaru-Riau.
Tarigan, Edward. 2003. Titlyanov EK, Leletkin VA, Tsukahara, Woesik, Yamazato. 1996. Degradation of
zooxanthellae and regulation of their density in hermatipic corals. Mar Ecol Prog Ser 139:167-178.
Kandungan total zat padat tersuspensi (total suspended solid) di perairan Raha Sulawesi Tenggara. J. Makara Sains 7:109-119.
Timothy R. 2002. The near future coral reef. Jour Environmental Conservation. 29:1-24.
Tomascik. 1991. Settlement patterns of Caribbean scleractinian corals on artificial substrata along a eutrophication gradient, Barbados, West Indies. Mar Ecol Prog Ser 77: 261-269.
Ubeng A. 1999. Variasi tahunan Upwelling perairan selatan Sulawesi Selatan. [Skripsi]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pillay RM, Willis B, Terashima H. 2005. Trends in the density of zooxanthellae in
Acropora millepora (Ehrenberg, 1834) at the Palm Island Group, Great Barrier Reef, Australia. Jour Symbiosis 38: 209–226.
Prartono, Hasena. 2009. Studi Kinetik Senyawa Fosfor dan Nitrogen dari Resuspensi Sedimen. E-Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan. Institut Pertanian Bogor (IPB).
Risk MJ, Sammarco PW, Edinger KN 1995. Bioerosion in Acropora across the continental shelf of Great Barrier Reef. Coral Reef 14: 79-86.
Veron. 1995. Coral in space and time. Australian Institute of Marine Science Cape Ferguson, Townsville, Quensland.
Walpole RE. 1988. Pengantar Statistik. Edisi ke-3 PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Warsa A, Astuti LP, Krismono. 2006. Hubungan Nutrien (N danP) terhadap Kelimpahan Fitoplankton di Waduk Kota Panjang. Provinsi Riau. Pros. Seminar Nasional Ikan IV. Jatiluhur.
Wibisono. 2005. Pengantar Ilmu Kelautan. PT. Gramedia Widiasaran Indonesia. Jakarta.
Yaqin K. 2006. Mengukur Kesehatan Karang dengan Biomarker. http://khusnulyaqin.blogspot.com/

54
Yonge CM. 1963. The biology of coral reefs. Adv Mar Biol 1; 209-260.
Yuen YS, Nakamura T, Yamazaki SS, Yamasaki H. (2008). Long-term effects of inorganic nitrogen enrichment on the reef-building corals Stylophora pistillata and Acropora spp. Proc the 11th International Coral Reef Symposium, Ft. Lauderdale, Florida, 7-11 July 2008. Session number

Lampiran 1 Perhitungan Kepadatan Zooxanthellae di Lokasi Penelitian
Pulau Spesies N (sel) At (mm2 Vt (ml) )
Ac (mm2
At (mm) 2 Vs (ml) ) As (mm2 Kepadatan zooxanthellae
) (sel/mm2 (sel/cm) 2)
Porites lobata 119 20 10 144 20 0.05 0.0025 1.32E+06 1.32E+05
260 20 10 144 20 0.05 0.0025 2.89E+06 2.89E+05
308 20 10 144 20 0.05 0.0025 3.42E+06 3.42E+05
Laelae Acropora appressa 444 20 30 879.2 20 0.05 0.0025 2.42E+06 2.42E+05
469 20 20 489.84 20 0.05 0.0025 3.06E+06 3.06E+05
476 20 30 816.4 20 0.05 0.0025 2.80E+06 2.80E+05
Acropora sp 468 20 10 690.8 20 0.05 0.0025 1.08E+06 1.08E+05
444 20 25 879.2 20 0.05 0.0025 2.02E+06 2.02E+05
436 20 20 942 20 0.05 0.0025 1.48E+06 1.48E+05
Porites mayeri 166 20 20 144 20 0.05 0.0025 3.69E+06 3.69E+05
153 20 10 144 20 0.05 0.0025 1.70E+06 1.70E+05
509 20 17 144 20 0.05 0.0025 9.61E+06 9.61E+05
Barrang Lompo Porites Lobata 425 20 10 285.74 20 0.05 0.0025 2.38E+06 2.38E+05
188 20 20 125.6 20 0.05 0.0025 4.79E+06 4.79E+05
157 20 10 141.3 20 0.05 0.0025 1.78E+06 1.78E+05
Acropora appressa 331 20 20 175.84 20 0.05 0.0025 6.02E+06 6.02E+05
306 20 20 150.72 20 0.05 0.0025 6.50E+06 6.50E+05
366 20 20 207.24 20 0.05 0.0025 5.65E+06 5.65E+05

Lampiran 1 Lanjutan
Pulau Spesies N (sel) At (mm2 Vt (ml) )
Ac (mm2
At (mm) 2 Vs (ml) ) As (mm2 Kepadatan zooxanthellae
) (sel/mm2 (sel/cm) 2)
Lanyukang Acropora formosa 501 20 10 508.68 20 0.05 0.0025 1.58E+06 1.58E+05
114 20 20 439.6 20 0.05 0.0025 8.30E+05 8.30E+04
873 20 10 314 20 0.05 0.0025 4.45E+06 4.45E+05
Acropora appressa 1035 20 10 314 20 0.05 0.0025 5.27E+06 5.27E+05
843 20 20 320.28 20 0.05 0.0025 8.42E+06 8.42E+05
783 20 20 251.2 20 0.05 0.0025 9.97E+06 9.97E+05
Montipora sp 843 20 20 320.28 20 0.05 0.0025 8.42E+06 8.42E+05
783 20 20 251.2 20 0.05 0.0025 9.97E+06 9.97E+05
1099 20 10 144 20 0.05 0.0025 1.22E+07 1.22E+06
Di mana : N = Jumlah zooxanthellae terhitung (sel), At = Luas cover glass (mm2), Vt = Volume Total Sampel,
Ac = Luas Sampel yang dikerik (cm2), Vs = Volume Sampel yang digunakan (ml), As = Luas Haemacytometer (mm2
).


Lampiran 2 Data dan hasil perhitungan kepadatan fitoplankton di lokasi penelitian
Pulau Fitoplankton n (sel)
Vr (ml)
Vo (ml)
Vs (liter)
N (sel/liter)
Laelae Coscinodiscus sp 8 90 0.05 250 57.6
Nitzschia sp 11 90 0.05 250 79.2
Diatomae sp 3 90 0.05 250 21.6
Rhizosolenia sp 4 90 0.05 250 28.8
Total 187.2 Barrang Lompo Coscinodiscus sp 10 90 0.05 250 72
Nitzschia sp 9 90 0.05 250 64.8
Rhizosolenia sp 15 90 0.05 250 108
Chaetoceros sp 15 90 0.05 250 108
Triceratum sp 2 90 0.05 250 14.4
Thalassiothrix sp 7 90 0.05 250 50.4
Total 417.6 Lanyukang Coscinodiscus sp 3 90 0.05 100 54
Nitzschia sp 13 90 0.05 100 234
Rhizosolenia sp 6 90 0.05 100 108
Chaetoceros sp 15 90 0.05 100 270
Triceratum sp 2 90 0.05 100 36
Gymnodinium sp 4 90 0.05 100 72
Peridinium sp 3 90 0.05 100 54
Total 828 Sumber data; Data hasil olahan 2010
Rumus kepadatan fitoplankton:
N= Kelimpahan fitoplankton (sel/liter)
n= Jumlah sel yang diamati (sel)
Vr=Volume air yang tersaring (ml)
Vo=Volume air yang diamati (ml)
Vs=Volume air yang disaring (liter)
1 tetes = 0.05 ml
1 ml = 20 tetes

Lampiran 4. Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae pada pulau Laelae.
Anova: Single Factor SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance A.appressa 3 763333.3333 254444.444 1.19E+10
P. lobata 3 828650.7548 276216.918 1.03E+09 Acropora sp 3 458508.2858 152836.095 2.21E+09
ANOVA Source of
Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 2.602E+10 2 1.3011E+10 2.575411 0.155788 5.143253
Within Groups 3.031E+10 6 5051839086
Total 5.633E+10 8
Pulau Lae-lae A.appressa P. lobata Acropora sp 1.32E+05 2.42E+05 1.08E+05 2.89E+05 3.06E+05 2.02E+05 3.42E+05 2.80E+05 1.48E+05

Lampiran 3. Perhitungan analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae Acropora appressa antar pulau.
Anova: Single Factor
SUMMARY Groups Count Sum Average Variance
Laelae 3 763333.3 254444.4 1.19E+10 Barrang
Lompo 3 1817189 605729.7 1.8E+09 Lanyukang 3 2367104 789034.6 5.74E+10
ANOVA Source of
Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 4.43E+11 2 2.21E+11 9.344824 0.014352 5.143253 Within Groups 1.42E+11 6 2.37E+10
Total 5.85E+11 8
Data kepadatan zooxanthellae Acropora appressa
PulauLaelae Pulau Barrang Lompo Pulau Lanyukang 1.32E+05 6.02E+05 5.27E+05 2.89E+05 6.50E+05 8.42E+05 3.42E+05 5.65E+05 9.97E+05

Lampiran 5. Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae pada pulau Barrang Lompo.
Anova: Single Factor SUMMARY
Groups Count Sum Average Variance P. mayeri 3 1500333.33 500111.1111 1.7E+11 P. Lobata 3 894737.251 298245.7505 2.54E+10 A. appressa 3 1817189.18 605729.7267 1.8E+09
ANOVA Source of
Variation SS df MS F P-
value F crit Between Groups 1.46451E+11 2 7322565573 1.11675 0.38699 5.143253 Within Groups 3.93421E+11 6 6557022810
Total 5.39873E+11 8
Barrang Lompo P. mayeri P. Lobata A. appressa
3.69E+05 2.38E+05 6.02E+05 1.70E+05 4.79E+05 6.50E+05 9.61E+05 1.78E+05 5.65E+05

Lampiran 6. Perhitungan Analisa sidik ragam kepadatan zooxanthellae pada pulau Lanyukang.
Anova: Single Factor
SUMMARY Groups Count Sum Average Variance
Acropora appressa 3 2367103.78 789034.5947 5.74E+10 Acropora formosa 3 685409.632 228469.8772 3.65E+10 Montipora sp 3 2261111.11 753703.7037 2.07E+11
ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 5.91352E+11 2 2.95676E+11 2.94790 0.12830 5.143253 Within Groups 6.01785E+11 6 1.00297E+11
Total 1.19314E+12 8
Lanjukang A. appressa A. formosa Montipora sp
5.27E+05 1.58E+05 3.12E+05 8.42E+05 8.30E+04 7.28E+05 9.97E+05 4.45E+05 1.22E+06

Acropora appressa Porites lobata Porites mayeri
Acropora sp Porites lobata Acropora sp
Kondisi perairan pulau Barrang Lompo Kondisi Perairan Pulau Laelae