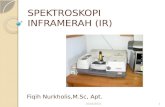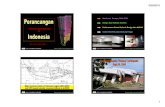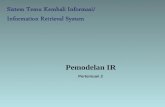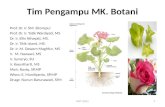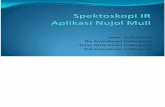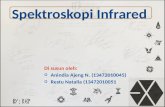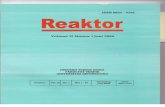Ir
description
Transcript of Ir
1. Ir. Soekarno
Ir. Soekarno yang bernama lahir Koesno Sosrodiharjo ini lahir pada 6 Juni 1901 di Blitar dari pasangan Raden Soekemi Sosrodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, diberi nama kecil, Koesno. Ir. Soekarno , 44 tahun kemudian, menguak fajar kemerdekaan Indonesia setelah lebih dari tiga setengah abad ditindas oleh penjajah-penjajah asing. Soekarno hidup jauh dari orang tuanya di Blitar sejak duduk di bangku sekolah rakyat, indekos di Surabaya sampai tamat HBS (Hoogere Burger School). Ia tinggal di rumah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Jiwa nasionalismenya membara lantaran sering menguping diskusi-diskusi politik di rumah induk semangnya yang kemudian menjadi ayah mertuanya dengan menikahi Siti Oetari (1921).Soekarno pindah ke Bandung, melanjutkan pendidikan tinggi di THS (Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian hari menjadi ITB, meraih gelar insinyur, 25 Mei 1926. Semasa kuliah di Bandung, Soekarno, menemukan jodoh yang lain, menikah dengan Inggit Ganarsih (1923).Soekarno muda, lebih akrab dipanggil Bung Karno mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia), 4 Juni 1927. Tujuannya, mendirikan negara Indonesia Merdeka. Akibatnya, Bung Karno ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman penjara oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia dijeboloskan ke penjara Sukamiskin, Bandung, 29 Desember 1949. Di dalam pidato pembelaannya yang berjudul, Indonesia Menggugat, Bung Karno berapi-api menelanjangi kebobrokan penjajah Belanda. Bebas tahun 1931, Bung Karno kemudian memimpin Partindo. Tahun 1933, Belanda menangkapnya kembali, dibuang ke Ende, Flores. Dari Ende, dibuang ke Bengkulu selama empat tahun. Di sanalah ia menikahi Fatwamati (1943) yang memberinya lima orang anak; Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rahmawati, Sukmawati dan Guruh Soekarnoputri.Soekarno adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan dengan judul Dibawah Bendera Revolusi, dua jilid. Dari buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut, tulisan pertamanya (1926), berjudul, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxism, bagian paling menarik untuk memahami gelora muda Bung Karno.Tahun 1942, tentara pendudukan Belanda di Indonesia menyerah pada Jepang. Penindasan yang dilakukan tentara pendudukan selama tiga tahun jauh lebih kejam. Di balik itu, Jepang sendiri sudah mengimingi kemerdekaan bagi Indonesia. Penyerahan diri Jepang setelah dua kota utamanya, Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom oleh tentara Sekutu, tanggal 6 Agustus 1945, membuka cakrawala baru bagi para pejuang Indonesia. Mereka, tidak perlu menunggu, tetapi merebut kemerdekaan dari Jepang.Setelah persiapan yang cukup panjang, dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs Muhammad Hatta, mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur No. 52 (sekarang Jln. Proklamasi), Jakarta.
2. Dr. Moch. Hatta
Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatra Barat. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi, dan kemudian pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang, baru kemudian pada tahun 1919 beliau pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Beliau menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik, dan pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Erasmus Universiteit). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.Saat masih di sekolah menengah di Padang, Bung Hatta telah aktif di organisasi, antara lain sebagai bendahara pada organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang.Pada tangal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yoyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul Lampau dan Datang.Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas berangkat ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di Batavia, ia juga aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat, juga sebagai Bendahara.Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Express. Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang. Di kota ini Hatta mulai menimbun pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. Aku kagum melihat cara Abdul Moeis berpidato, aku asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau, terpesona oleh ayun katanya. Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat menarik perhatian dan membakar semangat, aku Hatta dalam Memoir-nya. Itulah Abdul Moeis: pengarang roman Salah Asuhan; aktivis partai Sarekat Islam; anggota Volksraad; dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran Kaoem Moeda, Neratja, Hindia Baroe, serta Utusan Melayu dan Peroebahan. Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas ia bertolak ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera, Namaku Hindania! begitulah judulnya. Berkisah perihal janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, datanglah musafir dari Barat bernama Wolandia, yang kemudian meminangnya. Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga lebih mencintai hartaku daripada diriku dan menyia-nyiakan anak-anakku, rutuk Hatta lewat Hindania. Pemuda Hatta makin tajam pemikirannya karena diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai Bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang mukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB: Bahder Djohan. Saban Sabtu, ia dan Bahder Djohan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air. Pokok soal yang kerap pula mereka perbincangkan ialah perihal memajukan bahasa Melayu. Untuk itu, menurut Bahder Djohan perlu diadakan suatu majalah. Majalah dalam rencana Bahder Djohan itupun sudah ia beri nama Malaya. Antara mereka berdua sempat ada pembagian pekerjaan. Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya pada persiapan redaksi majalah, sedangkan Hatta pada soal organisasi dan pembiayaan penerbitan. Namun, Karena berbagai hal cita-cita kami itu tak dapat diteruskan, kenang Hatta lagi dalam Memoir-nya. Selama menjabat Bendahara JSB Pusat, Hatta menjalin kerjasama dengan percetakan surat kabar Neratja. Hubungan itu terus berlanjut meski Hatta berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden. Suatu ketika pada medio tahun 1922, terjadi peristiwa yang mengemparkan Eropa, Turki yang dipandang sebagai kerajaan yang sedang runtuh (the sick man of Europe) memukul mundur tentara Yunani yang dijagokan oleh Inggris. Rentetan peristiwa itu Hatta pantau lalu ia tulis menjadi serial tulisan untuk Neratja di Batavia. Serial tulisan Hatta itu menyedot perhatian khalayak pembaca, bahkan banyak surat kabar di tanah air yang mengutip tulisan-tulisan Hatta. Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Ia segera bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai eksterniran akibat kritik mereka lewat tulisan di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan Mamoerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya! berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda. Di Indische Vereeniging, pergerakan putra Minangkabau ini tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Lagipula, nama Indische meski masih bermasalah sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan kepulauan di Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme belanda. Dari sanalah mereka semua berasal. Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi, sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda, dan di sinilah ia bersahabat dengan nasionalis India, Jawaharlal Nehru. Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap pemerintah Belanda. Hatta akhirnya dibebaskan, setelah melakukan pidato pembelaannya yang terkenal: Indonesia Free. Pada tahun 1932 Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Belanda kembali menangkap Hatta, bersama Soetan Sjahrir, ketua Club Pendidikan Nasional Indonesia pada bulan Februari 1934. Hatta diasingkan ke Digul dan kemudian ke Banda selama 6 tahun. Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai wakil presiden pertama RI, bersama Bung Karno yang menjadi presiden RI.
3. Ki Hajar Dewantara
Pendiri Taman Siswa ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ajarannya yang terkenal ialah tut wuri handayani (di belakang memberi dorongan), ing madya mangun karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), ing ngarsa sungtulada (di depan memberi teladan). Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 28 April 1959 dan dimakamkan di sana.Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka.Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda.Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker itu antara lain berbunyi: Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun. Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk sebuah tempat tinggal yang boleh bagi seseorang untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum buang ke Pulau Bangka. Douwes Dekker dan Cipto Mangoenkoesoemo merasakan rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Mereka pun menerbitkan tulisan yang bernada membela Soewardi. Tetapi pihak Belanda menganggap tulisan itu menghasut rakyat untuk memusuhi dan memberontak pada pemerinah kolonial. Akibatnya keduanya juga terkena hukuman internering. Douwes Dekker dibuang di Kupang dan Cipto Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau Banda. Namun mereka menghendaki dibuang ke Negeri Belanda karena di sana mereka bisa memperlajari banyak hal dari pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 1913 sebagai bagian dari pelaksanaan hukuman. Kesempatan itu dipergunakan untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran, sehingga Raden Mas Soewardi Soeryaningrat berhasil memperoleh Europeesche Akte. Kemudian ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di tanah air ia mencurahkan perhatian di bidang pendidikan sebagai bagian dari alat perjuangan meraih kemerdekaan. Setelah pulang dari pengasingan, bersama rekan-rekan seperjuangannya, ia pun mendirikan sebuah perguruan yang bercorak nasional, Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3 Juli 1922. Perguruan ini sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.Tidak sedikit rintangan yang dihadapi dalam membina Taman Siswa. Pemerintah kolonial Belanda berupaya merintanginya dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan kegigihan memperjuangkan haknya, sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. Di tengah keseriusannya mencurahkan perhatian dalam dunia pendidikan di Tamansiswa, ia juga tetap rajin menulis. Namun tema tulisannya beralih dari nuansa politik ke pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Tulisannya berjumlah ratusan buah. Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, pada zaman Pendudukan Jepang, kegiatan di bidang politik dan pendidikan tetap dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai salah seorang pimpinan di samping Ir. Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. Mas Mansur. Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar Dewantara pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Nama Ki Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan sebagai seorang tokoh dan pahlawan pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional melalui surat keputusan Presiden RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Penghargaan lain yang diterimanya adalah gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa itu, ia meninggal dunia pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di sana. Kemudian oleh pihak penerus perguruan Taman Siswa, didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai semangat perjuangan Ki Hadjar Dewantara. Dalam museum ini terdapat benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar sebagai pendiri Tamansiswa dan kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. Koleksi museum yang berupa karya tulis atau konsep dan risalah-risalah penting serta data surat-menyurat semasa hidup Ki Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, budayawan dan sebagai seorang seniman telah direkam dalam mikrofilm dan dilaminasi atas bantuan Badan Arsip Nasional. Bangsa ini perlu mewarisi buah pemikirannya tentang tujuan pendidikan yaitu memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status ekonomi, status sosial, dan sebagainya, serta harus didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi.
.Penggagas Kongres Pemuda Pertama DIALAH tokoh penting di balik terselenggaranya Kongres Sumpah Pemuda Pertama 30 april-2mei 1926. Mohammad Tabrani Soerjowitjitro, wafat pada 1984, tak hanya menggagas munculnya kongres itu, tapi ia juga kemudian menjadi ketuanya.Pemuda ini bernama lengkap Mohammad Tabrani Soerjowitjitro, lahir di Pamekasan, Madura, 10 Oktober 1904. Ketika itu ia berusia 21 tahun, saat memimpin Kongres Pemuda1 Indonesia pertama yang digelar di Jakarta pada 30 April 1926 hingga 2 Mei 1926. Keputusan yang menetapkan Tabrani menjadi ketua panitia adalah hasil dari pertemuan sebelumnya yang terjadi pada tanggal 15 November 1925 dengan lima organisasi pemuda dan beberapa peserta perorangan yang bertemu di gedung Lux Orientis, Jakarta. Organisasi itu adalah Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Pelajar Minahasa, dan Sekar Roekoen. Dan Tabrani mewakili Jong Java.
hal yang menjadi pembicaraan adalah tentang usulan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Uraian singkat sebagai berikut; Pada hari terakhir Kongres Pemuda pertama ini, Muhammad Yamin (saat itu berusia 22 tahun) menyatakan hanya ada dua bahasa, Jawa dan Melayu, yang berpeluang menjadi bahasa persatuan. Namun Yamin yakin bahasa Melayu yang akan lebih berkembang sebagai bahasa persatuan. Dan peserta kongres saat itu hampir sepakat menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan.
Namun Tabrani menentang : Bukan saya tidak menyetujui pidato Yamin. Jalan pikiran saya ialah tujuan bersama, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
Menurut Tabrani, kalau nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, Maka bahasa itu harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu.Pendapat ini diterima Yamin dan Djamaludin. Keputusan menetapkan bahasa persatuan itupun ditunda dan akan dikemukakan lagi dalam Kongres Pemuda Kedua. Tujuan kongres pemuda I adalah;1. Membentuk badan sentral2. Memajukan paham persatuan kebangsaan3. Mempererat hubungan diantara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.Peserta Kongres Pemuda IISumpah Pemudamerupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan, oleh karena itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 Oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia, proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada 17 Agustus 1945.Rumusan Sumpah Pemuda ditulisMoehammad Yaminpada sebuah kertas ketikaMr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie.Pada hari ini, 28 Oktober kembali diperingati hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menggambarkan Kesatuan dan Persatuan Kebangsaan. Melalui hari Sumpah pemuda ini kita mengenal ikrar :Pertama:Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.Kedoea:Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.Ketiga:Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.Dalam peristiwa sumpah pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Soepratman pertama kali dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantudmkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial hindia belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya. Tidak kalah penting pada peristiwa ini, bendera Merah Putih dikibarkan. Sumpah Pemuda, adalah Ikrar dalam kongres pemuda ke II di Jakarta yang menyatakan bahwa Putra Putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, menjunjung bahasa persatuan dan berbangsa satu yaitu Indonesia. Hal ini bukan omong kosong dan bukan pekerjaan dalam waktu singkat, dan juga bukan hasil usaha dari beberapa gelintir orang saja. Sejak kebangkitan nasional 20 Mei 1908, para pemuda Indonesia telah membuktikan diri kepada penguasa Kolonial bahwa anggapan jelek bangsa Indonesia itu "Laksheid", yang berarti pemalas, tidak bersatu serta saling bermusuhan, adalah tidak benar.
M. Tabrani (sebelum 1928)Salah satu tokoh jurnalistik dan pergerakan nasional Indonesia. Lahir di Pamekasan, Madura 10 Oktober 1904 dan meninggal tahun 1984. Sejak masih muda ia telah berkecimpung dalam dunia pers. Ia pernah menuntut ilmu di Universitas Berlin dan Universitas Koln, Jerman dimana ia mendalami ilmu jurnalistik dan persuratkabaran. Ia juga mengikuti pendidikan stenografi bahasa Jerman yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1929 di Den Haag, Belanda.Pada tahun 1925 ia menjadi anggota redaksi dan menjadi ketua redaksi harian Hindia Baroe Jakarta. Antara tahun 1926-1930 ia membina sejumlah surat kabar dan majalah di Eropa. Di Jakarta, ia memimpin majalah mingguan Revue Politik pada tahun 1930-1932, pemimpin Sekolah Kita di Pamekasan pada tahun 1932-1936, direktur dan kepala redaksi harian Pemandangan dan mingguan Pembangoenan Jakarta. Pada tahun 1940 ia bekerja di Dinas Penerangan Pemerintah pada bagian jurnalistik Jakarta kemudian pindah ke bagian kartotek dan dokumentasi. Pada tahun 1942 ia menjadi anggota pusat redaksi harian Tjahaja.Ia juga menjadi pencetus diadakannya Kongres Pemuda Indonesia pertama tahun 1926. Pada tahun 1935 ia menjabat Ketua Partai Rakjat Indonesia (PRI) Jakarta. Kemudian ia juga memperjuangkan Petisi Sutardjo melalui harian Pemandangan. Petisi tersebut berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesiadiberi kesempatan membentuk parlemen sendiri. Melalui harian yang sama ia juga mendukung gagasan konsentrasi nasional.Soegondo Djojopoespito: Romantisme Sumpah PemudaOPINI | 15 September 2010 | 02:22 Dibaca: 2031 Komentar: 2 0 Nama Soegondo Djojopoepito dalam sejarah pergerakan nasional hanya dikaitkan dengan Sumpah Pemuda saja. Kendati dunia pergerakan dia geluti dengan berbagai resiko. Kehidupan sebagai mahasiswa telah membawa masuk Soegondo Djojopoespito dalam dunia pergerakan. Sebuah dunia yang akan di jauhi oleh sebagian besar pegawai-pegawai kolonial. Mereka selalu memperingatkan anak-anak mereka yang dalam masa sekolah agar tidak terlibat didalamnya. Tidak jarang dunia pergerakan dilingkungan kampus menjadi alasan atas gagalnya kuliah sang aktivis pergerakan. Soegondo Djojopoespito dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1905 di kota pesisir di Jawa Timur yang tersohor sejak zaman Majapahit,Tuban. Soegondo pernah kuliah di Recht Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) Jakarta walau hanya sampai tingkat candidat II.[1] Dari sini dapat ditarik kesimpulan, Soegondo jelas telah menikmati pendidikan modern di sekolah-sekolah dasar dan menengah sekuler berkualitas milik pemerintah kolonial. Sekolah Tinggi pada masa Soegondo muda, yang menjadi mahasiswa, baik kedokteran, tehnik, atau hukum hanya menerima lulusan sekolah menengah Belanda model Hogare Burgere School (HBS) maupun Algemene Middlebare School (AMS). Untuk menikmati pendidikan modern dari tingkat dasar, menengah apalagi sampai tingkat tinggi pasti membutuhkan banyak biaya. Sudah pasti Soegondo anak orang terpandang dengan penghasilan tinggi. Yang Muda Yang BergerakKaum muda adalah elemen pembaharuan. Dengan gejolaknya, kaum muda mudah terbakar. Kaum muda hampir selalu ingin bebas dari kungkungan generasi sebelumnya. Tidak jarang kaum muda melabeli generasi tua sebagai generasi kolot. Kelak jika tua nanti mereka berubah juga menjadi generasi tua kolot juga. Setiap zaman punya jiwanya sendiri. Setiap zaman juga punya pemudanya sendiri-sendiri.Pemuda bukan lagi anak-anak. Mereka mulai melihat dunia menjelang usia dewasanya. Mereka cenderung bereaksi terhadap hal-hal yang mereka anggap tidak cocok. Pemuda mulai berpikir apa yang terbai bagi dirinya, generasinya dan zamannya. Karenanya banyak pemuda bergabung dalam organisasi politik. Begitupun pemuda di tanah Hindia, khususnya pemuda pribumi terpelajar.Pemuda-pemuda Hindia yang terpelajar banyak yang terjun ke masyarakat maupun belajar lagi di sekolah tinggi. Tidak sedikit pemuda yang berstatus mahsiswa sekolah tinggi tergabung dalam sebuah organisasi politik tertentu. Syarat aktif berorganisasi politik menurut hukum kolonial pada dekade 1920an haruslah sudah menginjak usia 18 tahun. Pada umumnya mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi di Jakarta pastilah sudah lebih 18 tahun, jadi berhak menjadi anggota organisasi politik. [2]Sekelompok mahasiswa tua (tingkat atas) School tot Opleiding van Indische Artssen (Stovia: Sekolah dokter pribumi) dan Recht Hoge School (RHS) mendirikan Perhimpoenan Peladjar Peladjar Indonesia (PPPI) bulan September 1926. [3] Perhimpunan ini mendukung nasionalisme sekuler Indonesia, seperti halnya Perhimpoenan Indonesia di Negeri Belanda. Keanggotaan PPPI terdiri dari perhimpunan pelajar kesukuan yang nama depannya memakai embel-embel Jong didepan nama daerah asal mereka seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks, Jong Ambon, Jong Celebes dan Jong-jong lainnya. Tidak jarang masih aktif perhimpunan pelajar kesukuan-nya. Contohnya Muhamad Yamin dari Jong Sumatran Bond atau Amir Sjarifoedin dari Jong Bataks. Perhimpunan ini biasa berkumpul di Indonesische Clubgebouw di jalan Kramat nomor 106 di Waltevreden (Jakarta Kota sekarang). Soegondo Djojopoespito adalah ketua PPPI ini. Indonesische Clubgebouw juga menjadi tempat tinggal tempat tinggal Soegondo Djojopuspito dan kawan-kawan lainnya. Ditempat ini mereka diskusi masalah politik diatas rumput.hubungan antar anggota sangat akrab dan jauh dari kesan formal.Setelah tahun 1927 usaha membentuk badan kontak mengalami kegagalan. Jong Java yang sebelumnya menonjol kehilangan dominasinya dalam dunia gerakan pemuda. Usaha pemersatuan pemuda kemudian di ambil alih perhimpunan baru macam: PPPI dan Jong Indonesia (Pemoeda Indonesia). [4] Pada kongres pemuda tanggal 27-28 Oktober 1928, belum semua organisasi pemuda kedaerahan yang bergabung dengan perhimpunan oraganisasi pemuda semacam PPPI. Karenanya beberapa oraganisasi pemuda kemudian mengadakan perdiapan untuk melakukan fusi. Jong Java sebagai organisasi pemuda terbesar lantaran banyaknya pemuda terpelajar Jawa di Hindia. Organinsasi pemuda tertua di Hindia ini dalam Kongres ke-XI pada tanggal 25-29 Desember 1928 di Yogyakarta memyetujui ide fusi yang sedang digulirkan itu. [5]Sebelum ada organisasi fusi harus ada sebuah komisi persiapan. Sebagai tindak lanjut dari Kongres-nya Jong Java, di Semarang tahun 1929, membubarkan diri dan bergabung dengan Perkoempoelan Indonesia Moeda. Dalam persiapan fusi itu, tanggal 23 April dan 25 Mei 1929 di Gedung Indonesische Clubgebouw nomor 106, Waltevreden diadakan rapat yang dihari wakil-wakil perkumpulan yang siap melakukan fusi. [6]Hasil pertemuan antara perwakilan Jong Java, Jong Indonesia dan Pemuda Sumatra akan berganti nama dan menjadi perserikatan baru yang bedarkan kebangsaan bukan lagi kedaerahan atau kesukuan. [7]Soegondo Djojopoespito, selain di PPPI kemudian juga bergabung dengan Partai Nasional Indonesia-nya Soekarno, Pendidikan Nasional Indonesia-nya Hatta dan Syahrir. Partai Sosialis Indonesia juga menjadi tempatnya berpolitik.
TEMPO.CO, Jakarta -- Soegondo Djojopoespito, Ketua Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia dan Ketua Kongres Pemuda II, memiliki dikenal memiliki beragam profesi sepanjang perjalanan hidupnya.
Dalam wawancara dengan Sunarindrati, putri kedua Soegondo, yang saat ditemui Majalah Tempo pada 2008 telah berusia 71 tahun, melalui Majalah Tempo Edisi 36/37 tertanggal 2 November 2008 lewat tulisan yang berjudul "Peran Soegondo: Sang Pemimpin yang Redup" melukiskan kiprah Soegondo di dunia politik ini.
Sejak muda, Soegondo sudah tertarik pada politik. Namun, karena masih pelajar, ia belum dapat bergabung dengan partai politik. Meskipun demikian, ia sering menghadiri rapat-rapat umum. Jiwa kebangsaan kian kuat ketika Soegondo melanjutkan studi ke Sekolah Hakim Tinggi, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada 1925. Namun, sekolahnya tak tamat. Beasiswa dari Belanda dicabut, karena ia aktif di politik, kata Sunarindrati.
Saat kuliah, Soegondo menumpang di rumah pegawai pos di Gang Rijksman (sebuah kampung di sebelah utara Rijswik), Jalan Segara. Teman kosnya kebanyakan pegawai pos. Salah satunya pernah memberikan majalah Indonesia Merdeka terbitan Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang dilarang masuk Indonesia.
Setelah membaca majalah itu, mata Soegondo makin terbuka. Ia menyadari pentingnya meraih sebuah kemerdekaan. Ia ingin berbuat sesuatu. Soegondo lalu belajar dan berdiskusi politik dengan Haji Agus Salim. Teman-temannya dihubungi untuk membaca majalah terlarang itu dan berdiskusi di pemondokannya. Mereka antara lain Soewirjo dan Usman Sastroamidjojo, adik Ali Sastroamidjojo.
Pada 1926, Soegondo membentuk Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, terinspirasi oleh Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sigit terpilih sebagai ketua. Tugas khusus mereka adalah menghubungi mahasiswa-mahasiswa baru dan pemimpin perkumpulan pemuda untuk menularkan persatuan. Mereka membuat pamflet rahasia untuk menggulingkan Belanda.
Setahun berselang, Sigit meletakkan jabatan dan digantikan oleh Soegondo. Sebagai ketua baru, ia mengundang wakil-wakil perkumpulan, lalu membentuk panitia kongres pada Juni 1928.
Pada 1933, Soegondo masuk Partai Pendidikan Nasional Indonesia, pecahan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebelumnya, di 1928, ia adalah simpatisan PNI.
Bersama Sutan Sjahrir, Soegondo adalah satu dari delapan pendiri Partai Sosialis Indonesia pada 1948. Ia adalah anggota Politbiro Partai Sosialis Indonesia, merangkap Ketua Partai Sosialis Indonesia di Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia ideolog Partai Sosialis, kata Rosihan Anwar, tokoh pers Indonesia yang wafat tahun lalu. Menurut dia, Soegondo dan Djohan Sjahroezah termasuk perangkai ideologi partai ini.
Sampai akhir hidupnya, Soegondo (22 Februari 1905-23 April 1978) menetap di Jalan Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta. Bersama Suwarsih Djojopoespito (1912-1977), istrinya, penyuka pepes bandeng panggang ini menulis artikel di majalah dan berpolitik di dalam dan luar negeri. Karyanya tidak terkenal, tapi Suwarsih dikenal sebagai novelis. Buku Suwarsih berjudul Manusia Bebas diterbitkan dalam bahasa Belanda dan Indonesia.