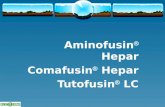hepar (1)
-
Upload
kamilla-rd -
Category
Documents
-
view
18 -
download
0
description
Transcript of hepar (1)

HEPAR
MAKALAH
UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH
Patologi Klinik
Yang dibimbing oleh drg. Mayu Winnie Rachmawati, M.Sc., dan
drg. Ivan Arie Wahyudi, M.Kes., Ph.D sebagai PJMK
Oleh
Kelompok 3
Widhi Setiyani (9953)
Elvira Purnamasari (9964)
Kamilla Rufaidah (9973)
Atma Beauty M (9983)
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2015

1.1 Definisi
Hepar (hati) merupakan kelenjar paling besar dari tubuh. Pada orang
dewasa dapat mencapai 1,5 kg atau 2-2,5% dari berat tubuh; pada anak-anak
relatif lebih berat, dapat mencapai 5% dari berat tubuh (Widjaja, 2007).
Hati adalah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, bewarna merah
kecoklatan, yang mempunyai berbagai macam fungi, termasuk perannya dalan
membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem
pencernaan (Pearce, 2002).
1.2 Anatomi
Hepar adalah organ viscera abdominalis terbesar. Terletak di cavum
abdominalis kanan, menempati regio hipokondria kanan bahkan sampai
epigastrium dan hipokondrium kiri. Holotopi: dinding anterior abdomen warnanya
coklat kemerahan saat segar. Memiliki capsula hepatis untuk mempertahankan
bentuk.
Pembagian lobus ada dua, pertama secara anatomik oleh fissura sagitalis
sinistra dibagi menjadi: lobus dextra, sinistra, quadratus, dan qaudatus. Kedua,
menurut coui-naud (dengan batas dari vesica biliaris di anterior dan vena cava di
posterior=fossa sagitalis dextra) dibagi menjadi lobus dextra dan lobus sinistra.

Terdapat beberapa ligamen:
Ligamen falciforme hepatis : memfiksasi hepar ke dinding anterior
abdomen.
Kekanan akan melanjut sebagai ligamentum coronarium.
Ke kiri melanjut sebagai ligamentum triangular sinistra.
Lanjut ke bawah terdapat : fissura ligamentum teretis, incisura ligamenti
teretis, ligamentum teres hepatis, dan ligamentum venosum.
Penggantung:
lig. falciforme, lig. teres hepatis, lig. venosum, lig. coronarium, lig. triangular dext
et sinistra, omentum minus, lig. hepato-ren, lig. hepato-gaster, lig. hepato-
duodenalis.

Hepar ditutupi peritonium kecuali pada 3 bagian: area nuda, fossa yang
ditempati vena cava superior dan vesica biliaris. Memiliki dua facies. Ada facies
visceralis yang lebih datar dan berhadapan dengan organ lain. Serta facies
diaphragmatica yang terdiri atas: pars anterior (ada lig. falciforme), pars posterior
(ada lobus caudatus), pars superior (ada area nuda, sulcus VCI), pars dextra
(bersentuhan dgn costa-costa terbawah). Memilii impresio, di sinistra ada:
impresio gastrica et esophagus. Di dextra ada impresio renalis et duodenum et
colica. Porta hepatis adalah celah transversal, berbentuk huruf H, p=5 cm, yang
merupakan tempat keluar masuknya bangunan-bangunan seperti vascular, limfe,
saraf, ductus ke hepar. ISI : a. hepatica propia, ductus hepatica, v.porta hepatis
Trias porta : terdiri atas a. hepatica propia, v. porta hepatis, ductus biliaris
1.3 Fungsi Biologi
Tiga fungsi utama hepar adalah:
o Produksi dan sekresi empedu ke dalam saluran cerna
o Berperan pada metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein
o Sebagai filter dari darah terhadap kuman maupun zat-zat toksik
(Widjaja, 2007).
Hati adalah organ metabolik terbesar dan terpenting di tubuh. Organ ini
penting bagi sistem pencernaan untuk sekresi garam empedu, tetapi hati juga
melakukan berbagai fungsi lain, mencangkup hal-hal berikut:
1. Pengolahan metabolik kategori nutrien utama (karbohidrat, lemak, protein)
setelah penyerapan mereka dari saluran pencernaan.
2. Detoksifikasi atau degradasi zat-zat sisa dan hormon serta obat dan
senyawa asing lainnya.
3. Sintesis berbagai protein plasma, mencangkup protein-protein yang
penting unutk pembekuan darah serta untuk mengangkut hormon tiroid,
steroid, dan kolesterol dalam darah.
4. Penyimpanan glikogen, lemak, besi, tembaga, dan banyak vitamin.
5. Pengaktifan vitamin D, yang dilaksanakan oleh hati bersama ginjal.

6. Pengeluaran bakteri dan sel darah merah yang usang, berkat adanya
makrofage residen.
7. Ekskresi kolesterol dan bilirubin, yang terakhir dalah produk penguraian
yang berasal dari destruksi sel darah merah yang sudah usang.
1.4 Fungsi Biokimia
o Metabolisme Glukosa
Setelah dicerna dan diserap ke dalam aliran darah, glukosa
disalurkan ke seluruh tubuh sebagi sumber energi. Ketika glukosa masuk
ke organ pencernaan (usus) lalu masuk ke pembuluh darah diperlukan
insulin agar mudah diserap di sel tubuh, apabila masih belum dipakai,
glukosa diubah sel hati menjadi glikogen dan disimpan di dalam hati
(glikogenesis). Sehingga hati berperan sebagai penyangga kadar glukosa
untuk darah. Apabila kadar gula darah turun, glikogen diubah menjadi
glukosa (glikogenolisis). Selain itu terdapat glukoneogenesis, terjadi saat
penurunan glukosa diantara waktu makan dengan mengubah asam amino
menjadi glukosa setelah deaminasi (pengeluaran gugus amino) dan
mengubah gliserol dari penguraian asam lemak menjadi glukosa.
o Metabolisme Asam Amino
Hati sebagai tempat penyimpanan protein. Setelah pencernaan
asam amino memasuki semua sel dan diubah menjadi protein untuk
digunakan untuk membentuk:
1. Enzim dan komponen struktural sel (DNA/RNA inti, basa purin dan
pirimidin, ribosom, kolagen, protein kontraktil otot).
2. Selain itu, sintesis protein digunakan dalam pembentukan protein serum
(albumin, α globulin, β globulin kecuali γ globulin)
3. Factor pembekuan darah I, II, V, VII, VIII, IX, dan X; vitamin K
digunakan sebagai kofaktor pada sintesi ini kecuali factor V)
4. Hormon (tiroksin, epinefrin, insulin)
5. Neurotransmiter, kreatin fosfat, heme pada hemoglobin dan sitokrom,
pigmen kulit melanin.

Penguraian protein terjadi ketika asam amino plasma turun
dibawah ambang batas. Ketika tidak ada lagi asam amino yang disimpan
sebagai protein, maka hati melakukan deaminasi asam amino dan
menggunakannya sebagai sumber energi atau mengubahnya menjadi
glukosa, glikogen atau asam lemak. Selama deaminasi asam amino, terjadi
pelepasan amonia yang hampir seluruhnya diubah di hati menjadi urea
yang kemudian diekskresikan lewat ginjal. Selain hati, ginjal dan mukosa
usus ikut berperan sebagai tempat penyimpanan protein.
o Biotransformasi Amonia
Amonia adalah suatu produk sampingan penguraian protein.
Sebelum rangka karbon pada asam amino dioksidasi, nitrogen terlebih
dahulu harus dikeluarkan. Nitrogen asam amino membentuk ammonia.
Amonia ditransformasikan menjadi urea (sifatnya yang larut dalam urin)
di hati dan diekskresikan dalam urin. Tanpa fungsi hati ini, terjadi
penimbunan amonia (bersifat toksik) yang bisa menyebabkan disfungi
saraf, koma, dan kematian. Walaupun urea adalah produk ekskresi
nitrogen yang utama, nitrogen juga dibentuk menjadi senyawa lain, asam
urat (produk penguraian basa purin), keratin (dari kreatin fosfat), ammonia
(dari glutamine). Semua senyawa ini, selain lewat urin, juga dikeluarkan
melalui feses dan kulit.
o Metabolisme asam lemak
Hampir semua pencernaan lemak melewati saluran limfe sebagai
kilomikron (gabungan dari trigliserida (TG), kolesterol, fosfolipid (FL)
dan lipoprotein (LP)). Kilomikron masuk ke pembuluh darah melalui
duktus torasikus. TG kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol
oleh enzim-enzim di dinding kapiler, terutama kapiler hati dan jaringan
adiposa. Dari kapiler, asam lemak dan gliserol dapat masuk ke sebagian
besar sel. Setelah itu memasuki hati dan sel lain menjadi TG kembali. TG
disimpan sampai stadium pasca-absortif. Pada saat ini, TG diubah menjadi
asam lemak bebas dan gliserol. Hormon glukagon, kortisol, hormon

pertumbuhan dan katekolamin berfungsi sebagai sinyal untuk
menguraikan TG. Gliserol dan asam lemak bebas masuk ke siklus kreb
untuk menghasilkan ATP. Sebagian tidak masuk siklus kreb tapi
digunakan hati membentuk glukosa. Hal inilah yang dapat menyebabkan
timbunan keton apabila penguraian TG secara berlebih. Otak tidak dapat
memanfaatkan TG sebagai sumber energi secara langsung kecuali melalui
glukoneogenesis.
o Metabolisme kolesterol
Hati memetabolisme sebagian kolesterol yang terdapat didalam
misel menjadi garam-garam empedu. Sisa kolesterol lainnya disalurkan ke
darah, berikatan dengan FL sebagai LP. LP mengangkut kolesterol ke
semua sel untuk membentuk membran sel, struktur intrasel, dan hormon
steroid. Tingginya kadar LDL (Low Density Lipoprotein) dan VLDL
(Very Low Density Lipoprotein) menandakan hati menangani kolesterol
dalam jumlah besar. LDL dan VLDL bisa merusak sel, terutama pada
epitel pembuluh darah dengan membebaskan radikal bebas dan elektron
berenergi tinggi selama metabolismenya. HDL (High Density Lipoprotein)
mengangkut kolesterol dari sel ke hati dan bersifat protektif terhadap
penyakit arteri. Peranan utama pada sintesis kolesterol oleh hati, sebagian
besar diekskresi dalam empedu sebagai kolesterol dan asam kolat.
1.5 Penyakit
1. HEPATITIS
o Pengertian
Hepatitis adalah inflamasi/radang dan cedera pada hepar
karena reaksi hepar terhadap berbagai kondisi terutama virus, obat-
obatan dan alkohol (Ester monika, 2002). Sedangkan menurut Brunner
dan Suddarth (2002) hepatitis adalah infeksi sistemik yang dominan
menyerang hati. Hepatitis virus adalah istilah yang digunakan untuk

infeksi hepar oleh virus disertai nekrosis dn inflamasi pada sel-sel hati
yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokomia serta seluler
yang khas.
Hepatitis merupakan suatu proses peradangan pada jaringan
hati. Hepatititis dalam bahasa awam sering disebut dengan istilah
lever atau sakit kuning. Padahal definisi lever itu sendiri sebenarnya
berasal dari bahasa Belanda yang berarti organ hati, bukan penyakit
hati. Namun banyak asumsi yang berkembang di masyarakat
mengartikan lever adalah penyakit radang hati, sedangkan istilah sakit
kuning sebenarnya dapat menimbulkan keracunan, karena tidak semua
penyakit kuning disebabkan oleh radang hati, tetapi juga karena
adanya peradangan pada kantung empedu. (M. Sholikul Huda).
Hepatitits adalah suatu proses peradangan difus pada jaringan
yang dapat di sebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik
terhadap obat – obatan serta bahan – bahan kimia.. Hepatitis virus
merupakan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan klinis,
biokimia serta seluler yang khas (Smeltzer, 2001).
o Etiologi
Menurut Price dan Wilson (2005: 485) Secara umum
hepatitis disebabkan oleh virus. Beberapa virus yang telah
ditemukan sebagai penyebabnya, berikut ini.
1) Virus hepatitis A (HAV)
2) Virus hepatitis B (HBV)
3) Virus hepatitis C (HCV)
4) Virus hepatitis D (HDV)
5) Virus hepatitis E (HEV)
6) Hepatitis F (HFV)
7) Hepatitis G (HGV)
Namun dari beberapa virus penyebab hepatitis, penyebab
yang paling dikenal adalah HAV (hepatitis A) dan HBV (hepatitis
B). Kedua istilah tersebut lebih disukai daripada istilah lama yaitu

hepatitis “infeksiosa” dan hepatitis “serum”, sebab kedua penyakit
ini dapat ditularkan secara parental dan nonparental (Price dan
Wilson, 2005). Hepatitis pula dapat disebabkan oleh racun, yaitu
suatu keadaan sebagai bentuk respons terhadap reaksi obat,
infeksi stafilokokus, penyakit sistematik dan juga
bersifat idiopatik (Sue Hincliff, 2000).
o Patofisiologi
Perubahan morfologi yang terjadi pada hati, seringkali
mirip untuk berbagai virus yang berlainan. Pada kasus yang klasik,
hati tampaknya berukuran besar dan berwarna normal, namun
kadang-kadang ada edema, membesar dan pada palpasi terasa nyeri
di tepian.
Secara histologi terjadi kekacauan susunan hepatoselular,
cedera dan nekrosis sel hati dalam berbagai derajat, dan
peradangan periportal. Perubahan ini bersifat reversibel sempurna
bila fase akut penyakit mereda. Namun pada beberapa kasus
nekrosis, nekrosis submasif atau masif dapat menyebabkan
gagalhati fulminan dan kematian (Price dan Daniel, 2005)
o Tatalaksana Gizi
Energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein,
diberikan bertahap sesuai kemampuan pasien, 40-45
kkal/Kg BB.
Lemak cukup, 20-25% dari kebutuhan energi total dalam
bentuk yang mudah dicerna atau dalam bentuk emulsi.
Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat
defisiensi.
Natrium diberikan rendah tergantung tingkat edema dan
asites.
Cairan diberikan lebih dari biasa, kecuali bila ada
kontraindikasi.

Bentuk makanan lunak bila ada keluhan mual dan muntah
atau makanan biasa sesuai kemampuan saluran cerna.
2. SIROSIS HEPATIS
o Pengertian
Sirosis adalah proses difus yang ditandai oleh fibrosis dan
perubahan struktur hepar yang normal menjadi nodula-nodula yang
abnormal. Hasil akhirnya adalah destruksi hepatosit dan digantikan oleh
jaringan fibrin serta gangguan atau kerusakan vaskular (Dipiro et al,
2006).
Progevisitas sirosis akan mengarah pada kondisi hipertensi
portal yang bertanggung jawab terhadap banyak komplikasi dari
perkembangan penyakit sirosis ini. Komplikasi ini meliputi
spontaneous bacterial peritonitis (SBP), hepatic encephalophaty dan
pecahnya varises esophagus yang mengakibatkan perdarahan
(hematemesis dan atau melena) (Sease et al, 2008).
Pada sirosis hepatis, jaringan hati yang normal digantikan oleh
jaringan parut (fibrosis) yang terbentuk melalui proses bertahap.
Jaringan parut ini mempengaruhi struktur normal dan regenerasi sel-sel
hati. Sel-sel hati menjadi rusak dan mati sehingga hati secara bertahap
kehilangan fungsinya.
Hati (liver) sebagaimana diketahui adalah organ di bagian kanan
atas perut yang memiliki banyak fungsi, di antaranya:
a. Menyimpan glikogen (bahan bakar untuk tubuh) yang terbuat dari
gula. Bila diperlukan, glikogen dipecah menjadi glukosa yang
dilepaskan ke dalam aliran darah.
b. Membantu proses pencernaan lemak dan protein.
c. Membuat protein yang penting bagi pembekuan darah.
d. Mengolah berbagai obat
e. Membantu membuang racun dari tubuh.
Sirosis merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena
mengganggu fungsi-fungsi di atas. Selain itu, sirosis juga berisiko

menjadi kanker hati (hepatocellular carcinoma). Risiko terbesar sirosis
yang disebabkan oleh infeksi hepatitis C dan B, diikuti dengan sirosis
yang disebabkan oleh hemokromatosis.
o Etiologi
Penyebab paling umum penyakit sirosis adalah kebiasaan
meminum alkohol dan infeksi virus hepatitis C. Sel-sel hati berfungsi
mengurai alkohol, tetapi terlalu banyak alkohol dapat merusak sel-sel
hati. Infeksi kronis virus hepatitis C menyebabkan peradangan jangka
panjang dalam hati yang dapat mengakibatkan sirosis. Berdasarkan
penelitian, 1 dari 5 penderita hepatitis C kronis dapat berkembang
menjadi sirosis.Penyebab lain sirosis hati meliputi:
a. Infeksi kronis virus hepatitis B.
b. Hepatitis autoimun. Hepatitis autoimun adalah sistem kekebalan
tubuh yang tidak terkendali sehingga membuat antibodi terhadap
sel-sel hati yang dapat menyebabkan kerusakan dan sirosis.
c. Penyakit yang menyebabkan penyumbatan saluran empedu
sehingga tekanan darahterhambat dan merusak sel-sel hati.
Sebagai contoh, sirosis bilier primer, primary sclerosing, dan
masalah bawaan pada saluran empedu.
d. Non-alcohol steato-hepatitis (NASH). Ini adalah kondisi di mana
lemak menumpuk di hati sehingga menciptakan jaringan parut dan
sirosis. Kelebihan berat badan (obesitas) meningkatkan risiko
Anda mengembangkan non-alcohol steato-hepatitis.
e. Reaksi parah terhadap obat dan jamu tertentu (Brandt dan
Muckadell, 2005).
f. Beberapa racun dan polusi lingkungan.
g. Infeksi tertentu yang disebabkan bakteri dan parasit.
h. Gagal jantung parah yang dapat menyebabkan tekanan balik darah
di hati.
i. Beberapa penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-
sel hati, seperti hemokromatosis (kondisi yang menyebabkan

timbunan abnormal zat besi di hati dan bagian lain tubuh) dan
penyakit Wilson (kondisi yang menyebabkan penumpukan
abnormal zat tembaga di hati dan bagian lain tubuh).
o Patofisiologi
Pada kondisi normal, hati merupakan sistem filtrasi darah yang
menerima darah yang berasal dari vena mesenterika, lambung, limfe, dan
pankreas masuk melalui arteri hepatika dan vena porta. Darah masuk ke
hati melalui triad porta yang terdiri dari cabang vena porta, arteri hepatika,
dan saluran empedu. Kemudian masuk ke dalam ruang sinusoid lobul hati.
Darah yang sudah difilter masuk ke dalam vena sentral kemudian masuk
ke vena hepatik yang lebih besar menuju ke vena cava inferior (Sease et al,
2008).
Pada sirosis, adanya jaringan fibrosis dalam sinusoid mengganggu
aliran darah normal menuju lobul hati menyebabkan hipertensi portal yang
dapat berkembang menjadi varises dan asites. Berkurangnya sel hepatosit
normal pada keadaan sirosis menyebabkan berkurangnya fungsi metabolik
dan sintetik hati. Hal tersebut dapat memicu terjadinya ensefalopati
hepatik dan koagulopati (Sease et al, 2008).
o Tatalaksana Gizi
1. Energi tinggi untuk mencegah pemecahan protein
2. Lemak cukup, yaitu 20-25% dari kebutuhan total
3. Protein agak tinggi, 1,25-1,5% g/kg BB
4. Vitamin dan mineral diberikan sesuai dengan tingkat defisiensi
5. Natrium diberikan rendah
6. Cairan diberikan lebih dari biasa
7. Bentuk makanan lunak
3. KOLELITIASIS
o Pengertian

Cholelithiasis merupakan adanya atau pembentukan batu empedu;
batu ini mungkin terdapat dalam kandung empedu (cholecystolithiasis)
atau dalam ductus choledochus (choledocholithiasis).
Kolesistitis (kalkuli/kalkulus, batu empedu) merupakan suatu
keadaan dimana terdapatnya batu empedu di dalam kandung empedu
(vesica fellea) yang memiliki ukuran,bentuk dan komposisi yang
bervariasi. Kolelitiasis lebih sering dijumpai pada individu berusia diatas
40 tahun terutama pada wanita dikarenakan memiliki faktor resiko,yaitu:
obesitas, usia lanjut, diet tinggi lemak dan genetik.
Sinonimnya adalah batu empedu,gallstones, biliary calculus. Istilah
kolelitiasis dimaksudkan untuk pembentukan batu di dalam kandung
empedu. Batu kandung empedu merupakan gabungan beberapa unsur yang
membentuk suatu material mirip batu yang terbentuk di dalam kandung
empedu.
o Etiologi
a. Obstruksi duktus sistikus dengan distensi dan iskemia
vesika bilaris. Sumbatan batu empedu pada duktus sistikus menyebabkan
distensi kandung empedu dan gangguam aliran darah dan limfe, bakteri
komensal kamudian berkembang biak
b. Cedera kimia (empedu) dan atau mekanik (batu empedu)
pada mukosa
c. Infeksi bakteri
Adanya kuman seperti E. Coli, Salmonela typhosa, cacing askaris, atau
karena pengaruh enzim – enzim pankreas.
o Patofisiologi
Stasis empedu dalam kandung empedu dapat mengakibatkan
supersaturasi progresif, perubahan susunan kimia, pengendapan. Gangguan
kontraksi sfingter odci dan kandung empedu dapat juga menyebabkan statis.
Faktor hormon (kehamilan) menyebabkan pengosongan kandung empedu.
Akibat satis, terjadilah sumbatan empedu (saluran). Adanya batu akibat statis

yang progresif tadi memungkinkan terjadi trauma dinding kandung empedu,
hal ini dapat memungkinkan infeksi bakteri lebih cepat
o Tatalaksana gizi
Syarat diet pada kandung empedu ini adalah lemak rendah untuk
mengurangi kontraksi kandung empedu, di mana lemak diberikan dalam bentuk
mudah dicerna. Kalori, protein dan karbohidrat cukup dan bila terlalu gemuk,
jumlah kalori dikurangi. Makanan ini juga mengandung vitamin tinggi, terutama
yang larut dalam lemak, mineral cukup, serta cairan tinggi untuk membantu
pengeluaran kuman atau sisa metabolisme dan mencegah dehidrasi.Makanan tidak
merangsang dan diberikan dalam porsi kecil tetapi sering untuk mengurangi rasa
kembung.
4. KOLESISTITIS
o Pengertian
Kolesistitis adalah radang kandung empedu yang merupakan
inflamasi akut dinding kandung empedu disertai nyeri perut kanan atas, nyeri
tekan dan panas badan (Brooker, 2001). Kolesistitis adalah radang kandung
empedu yang merupakan reaksi inflamasi akut dinding kandung empedu
disertai keluhan nyeri perut kanan atas, nyeri tekan dan panas badan. Dikenal
klasifikasi kolesistitis yaitu kolesistitis akut dan kronik (Suparyanto, 2009).
Kolesistitis akut adalah peradangan dari dinding kandung empedu,
biasanya merupakan akibat dari batu empedu di dalam duktus sistikus, yang
secara tiba-tiba menyebabkan serangan nyeri yang luar biasa.
Kolesistitis kronik adalah peradangan menahun dari dinding kandung
empedu, yang ditandai dengan serangan berulang dari nyeri perut yang tajam
dan hebat.
o Etiologi
a. Batu Empedu

Sifat kolesterol yang larut lemak dibuat menjadi larut air dengan cara
agregasi melalui garam empedu dan lesitin yang dikeluarkan bersama ke
dalam empedu. Jika konsentrasi kolesterol melebihi kapasitas solubilisasi
empedu (supersaturasi), kolesterol tidak lagi terdispersi sehingga menjadi
penggumpalan menjadi kristal kolesterol monohidrat padat. Sumbatan batu
empedu pada duktus sistikus menyebabkan distensi kandung empedu dan
gangguan aliran darah dan limfe, bakteri komensal kemudian berkembang
biak sehingga mengakibatkan inflamasi pada saluran kandung empedu.
b. Pembedahan (terjadi perubahan fungsi)
Dapat terjadi sebagai akibat dari jejas kimiawi oleh sumbatan batu
empedu yang menhadi predisposisi terjadinya infeksi atau dapat pula
terjadi karena adanya ketidakseimbangan komposisi empedu seperti
tingginya kadar garam empedu atau asam empedu, sehingga menginduksi
terjadinya peradangan akibat jejas kimia.
c. Infeksi
Sudah jelas jika terjadi pembentukan batu empedu akan terjadi
infeksi dengan adanya bakteri seperti E. coli, Salmonela thyposa, cacing
askaris atau karena pengaruh enzim-enzim pankreas karena sistem saliran
empedu adalah sistem drainase yang membawa empedu dari hati dan
kandung empedu ke daerah dari usus kecil yang disebut duodenum.
d. Luka Bakar
Respon umum pada luka bakar >20% adalah penurunan aktivitas
gastrointestinal. Hal ini disebabkan oleh kombinasi efek respon
hipovolemik dan neurologik serta respon endokrin terhadap adanya
perlukaan yang luas.
e. Pemasangan Infus dalam Jangka Waktu Lama
Pemasangan infus lama dapat menyebababkan radang pada
kandung empedu karena cairan infus banyak mengandung elektrolit
sehingga terpasang lama maka dapat membentuk kristal yang disebut batu
empedu selain itu juga cairan tersebut sangat peka sehingga tidak dapat
diserap oleh empedu di kandung empedu.
f. Trauma Abdomen

Trauma abdomen adalah suatu keadaan klinik akibat kegawatan di
rongga abdomen biasanya timbul secara mendadak dengan nyeri sebagai
keluhan utama yang memerlukan penanganan segera. Hal ini bisa
disebabkan karena pertama adanya inflamasi/peradangan pada kandung
empedu
o Patofisiologi
Kandung empedu memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cairan
empedu dan memekatkan cairan yang ada di dalamnya dengan cara
mengarbsobsi air dan elektrolit. Airan empedu ini adalah cairan elektrolit yang
dihasilakn oleh sel hati. Pada individu normal, cairan empedu mengalir ke
kandung empedu pada saat katup Oddi tertutup. Dalam kandung empedu,
cairan empedu dipekatkan dengan mengarbsobsi air. Derajat pemekatannya
diperlihatkan oleh peningkatan konsentrasi zat-zat padat.
Statis empedu dalam kandung empedu dapat mengakibatkan
supersaturasi progresif, perubahan susunan kimia dan pengendapan unsur
tersebut. Perubahan metabolisme disebabkan oleh perubahan susunan empedu,
statis empedu, dapat menyebabkan infeksi kandung empedu. Jika pengobatan
tertunda atau tidak tersedia, dalam beberapa kasus kandung empedu menjadi
sangat terinfeksi dan bakan gangren. Hal ini dapat mengakibatkan keracnunan
darah (septikemia), yang sangat serius dan dapat mengancam hidup. Mungkin
komplikasi lain termasuk kantong empedu dapat perforasi (pecah), atau fistula
(saluran) bisa terbentuk antara kandung empedu dan usus sebagai akibat dai
perdangan lanjutan.
o Tatalaksana Gizi1. Memberikan energy sesuai dengan kebutuhan2. Memberikan protein tinggi 20%3. Memberikan rendah lemak 15%4. Memberikan KH cukup5. Memberikan cukup vitamin dan mineral6. Cukup serat7. Hindari makanan yang bias membuat kembung

1.6 Manifestasi Klinik
1. Manifestasi penyakit hepatitis
o Pada penyakit hati terutama atresia bilier dan hepatitis neonatal dapat
terjadi diskolorisasi pada gigi sulung. Dimana pada atresia bilier gigi akan
berwarna hijau, sedangkan pada hepatitis neonatal berwarna kuning.
Keadaan ini disebabkan oleh depositnya bilirubin pada email dan dentin
yang sedang dalam tahap perkembangan.
o Menyebabkan oral hygiene buruk, dalam hal ini bau mulut tdak sedap
o Hapatitis aktif kronis dapat menyebabkan gangguan endokrin sehingga
menimbulkan penyakit multiple endokrinopati keturunan dan kandidosis
mukokutaneus
o Kegagalan hati dapat menyebabkan timbulnya foetor hepatikum. Dimana,
foetor hepatikum sering disebut bau “amine”, bau “kayu lapuk”, bau
“tikus” dan bahkan bau “bangkai segar”
o Sirosis hati dapat menyebabkan hiper pigmentasi pada mulut
o Timbul ulkus-ulkus karena berkurangnya zat-zat vitamin dan gizi dalam
rongga mulut
o Proses makan menjadi tidak benar sehingga peran saliva terganggu

DAFTAR PUSTAKA
Baron D. N, 1995. Kapita Selekta Patologi Klinik (A Short Text Book of Chemical
Pathology) Edisi 4. Jakarta : EGC
Brunner and Suddarth’s (2000). Text book of Medical Surgical Nursing. (Ninth
edition). USA. Lippincott Williams and Wilkins.
Dib, N., Oberti, F., Cales, P., 2006. Current management of the complications of
portal hypertension : Variceal bleeding and ascites. CMAJ
Mark D. B, Mark A. D, Collen M. Smith. 2000. Biokimia Kedokteran Dasar-
Sebuah Pendekatan Klinis. Jakarta : EGC
Muttaqin, Arif dan Sari, Kumala. 2011. Gangguan Gastrointestinal: Aplikasi
Asuhan Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta: Salemba Medika
Price S. A, Wilson L. M, 2005. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses
Penyakit. Jakarta : EGC
Sease, J.M., Timm, E.G., and Stragano, J.J., 2008. Portal hypertension and
cirrhosis. In: J.T. Dipiro, R.L. Talbert, G.C Yee, G.R. Matzke, B.G. Wells,
and L.M. Posey (Eds.). Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach.
Ed. 7th, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Smeltzer, Suzanne C. Dan Bare, Brenda G. 2002. Buku Ajar Keperawatan
Medikal Bedah Brunner dan Suddarth Ed. 8. Jakarta: EGC.
Widjaja, I Harjadi. 2009. Anatomi Abdomen. Jakarta: EGC