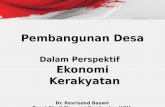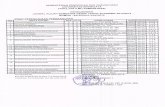Ekonomi Kerakyatan Dan Otonomi Daerah
Transcript of Ekonomi Kerakyatan Dan Otonomi Daerah

Bab III. Ekonomi Kerakyatan dan Otonomi Daerah
3.1. Tinjauan Konseptual ”Ekonomi Kerakyatan”
Konsep “ekonomi kerakyatan” atau adakalanya disebut “ekonomi rakyat” yang kini dikenal luas telah menapaki jalan panjang yang berliku. Selain Bung Hatta, beberapa pemikir yang belakangan gencar memperkenalkan dan memperjuangkan “ekonomi kerakyatan” antara lain adalah Mubyarto, Kwik Kian Gie, dan kemudian meluas dalam kalangan LSM. Meski demikian, eksistensi konsep ekonomi rakyat sebagai suatu kebijakan resmi pemerintah hingga kini timbul tenggelam karena ketidakpastian komitmen rezim yang berkuasa.
Dari sisi etimologis, menutut Mubyarto, ekonomi rakyat bukan berasal dari dua kata yang terpisah, yakni “ekonomi” dan “rakyat” tetapi muncul sebagai lawan dari “ekonomi konglomerat”. Intinya, ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 45 dan sila ke empat Pancasila (Bobo, 2003). Artinya, rakyat harus berpartisipasi penuh secara demokratis dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi kepada kekuatan atau mekanisme pasar. Ukuran apakah sistem ekonomi rakyat telah dijalankan atau tidak, terletak pada implementasinya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam ekonomi rakyat, aturan mainnya adalah keadilan ekonomi, yaitu aturan main tentang ikatan-ikatan ekonomi yang didasarkan pada etika.
Ekonomi rakyat muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat (Kartasasimita, 1996). Kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah inilah yang disebut ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat dapat dikenal dari ciri-ciri pokoknya yang bersifat tradisional, skala usaha yang kecil, dan kegiatan atau usaha ekonomi bersifat sekedar untuk bertahan hidup (survival). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi partisipatif yang memberikan akses wajar dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh input, proses produksi, distribusi, dan konsumsi tanpa ada hambatan masuk ke pasar, serta dalam pengelolaannya menjamin kelestarian sumberdaya alam pendukungnya.
Lebih jauh, pengertian “jaringan ekonomi kerakyatan” adalah sistem susunan dan hubungan antara berbagai kelembagaan ekonomi baik secara horisontal maupun secara vertikal yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, transformasi kelembagaan tradisional untuk memperkuat jaringan ekonomi kerakyatan di pedesaan menyangkut transformasi dari beberapa jenis kelembagaan yang ada serta menyangkut aspek struktur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, serta sistem tata hubungan antar kelembagaan baik secara horisontal maupun secara vertikal.
Kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sulit dihilangkan, bahkan ada kecenderungan melebar. Kesenjangan yang ada disebabkan adanya perbedaan dalam: pemilikan sumberdaya produktif (lahan

dan modal), penguasaan teknologi, akses ke pasar dan kepada sumber-sumber informasi, keterampilan manajemen, serta adanya dampak globalisasi ekonomi. Meskipun integrasi sistem ekonomi tradisional ke dalam sistem ekonomi modern sudah berlangsung, namun hasilnya menambah jurang kesenjangan yang ada. Kondisi di atas menjadikan sulitnya melakukan transformasi dari struktur masyarakat agraris menjadi struktur yang berdasarkan perkembangan industri dan pertanian secara seimbang (Tjondronegoro, 1999).
John Commons dalam Mubyarto (2002), mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (scarcity) dan asas efisiensi untuk mengatasinya, tetapi berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai “harmoni” atau “keseimbangan”. Bukan dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar melaui persaingan (competition), tetapi melalui kerjasama (cooperation) dan tindakan bersama (collective action). Diharapkan akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek di satu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang di sisi lain.
3.2. Ekonomi Kerakyatan dalam Otonomi Daerah
Kebijakan pembagunan seimbang dapat mengandung makna sebagai pembangunan yang bukan saja menitik beratkan pada pengembangan ekonomi, tetapi juga menumpahkan perhatian yang sama pentingnya pengembangan pada aspek sosial, politik dan budaya (Todaro, 1983). Dalam kerangka inilah, ketika keputusan politik-ekonomi telah diturunkan dari pusat ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten-kota dalam legalitas otonomi daerah, maka pengembangan ekonomi kerakyatan memperoleh lingkungan dan harapan baru. Dengan otonomi daerah diharapkan dapat dirumuskan suatu tata ekonomi yang khas untuk daerah tersebut, baik ideologinya, tata perilakunya, serta kelembagaanya.
Dalam tataran operasional pelaksanaan otonomi daerah haruslah mempunyai makna pemberdayaan rakyat baik yang menyangkut aspek ekonomi, politik (sistem pengambilan keputusan), dan sosial (kelembagaan yang mewadainya) hingga pada tingkat desa. Dengan mendekatkan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada rakyat di tingkat desa, maka pemerintah daerah akan lebih mampu untuk menilai potensi dan kapasitas baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang ada di wilayahnya, sehingga pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dioptimalkan. Pemberdayaan rakyat dari aspek politik juga harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengambilan keputusan pada tingkat daerah otonom. Di samping itu, pengembangan kelembagaan di tingkat lokal haruslah didasarkan atas usaha pemberdayaan kelembagaan lokal yang telah eksis dan diterima masyarakat, bukan merupakan kelembagaan yang diintroduksikan dari luar. Sehingga nilai-nilai positif yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan energi dan kohesi sosial dalam pengembangan kelembagaan. Dengan demikian pemberdayaan SDM dan kelembagaan lokal dipedesaan dapat dipandang sebagai pengembangkan budaya non-material untuk meningkatkan daya saing modal sosial (social capital) di pedesaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa.
Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, tranformasi kelembagaan perekonomian rakyat juga akan dilakukan dalam level tersebut yang cenderung

bersifat lokalitas. Dalam kontek ini, Esman dan Uphoff (1984) dan Uphoff (1992) mengklasifikasikan kelembagaan lokal ke dalam enam kategori, yaitu :
1. Administrasi lokal (local administration/LA), yang terdiri dari agen-agen lokal (local agencies) dan staff pemerintah pusat yang ada di daerah (staff of central goverment minintries), yang bertanggung jawab kepada birokrasi di pusat.
2. Pemerintah lokal (local government/LG), yang merupakan kelembagaan politik yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pembangunan dan bertugas mengeluarkan peraturan-peraturan serta bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.
3. Organisasi-organisasi yang beranggotakan komunitas masyarakat (membership organizations/MOs), yang merupakan asosiasi-asosiasi lokal yang bertujuan untuk menolong diri sendiri.
4. Kerjasama usaha (cooperative), semacam organisasi lokal yang mempunyai anggota dalam rangka pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk tujuan memperoleh keuntungan, seperti asosiasi pemasaran, gabungan kredit, masyarakat konsumen, atau kerjasama usaha diantara produsen.
5. Organisasi-organisasi pelayanan (Service Organizations/SOs), merupakan organisasi-organisasi lokal yang dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu anggota-anggota yang dapat memberikan manfaat.
6. Bisnis swasta (Private Business/PBs), yang merupakan pelaku ekonomi yang mengoperasionalkan usahanya secara independen yang dapat bergerak pada produksi primer, industri pengolahan, pedagang atau usaha jasa pelayanan.
Pengembangan ekonomi kerakyatan hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan konfigurasi dari keenam bentuk kelembagaan di atas, yang pada hakikatnya terdiri dari tiga bentuk kelembagaan pokok dalam masyarakat, yaitu: komunitas, negara, dan pasar. Salah satu jalan yang dapat digunakan untuk melakukannya adalah dengan melakukan tranformasi kelembagaan, yaitu masing-masing kelembagaan di atas secara internal, serta tranformasi tata hubungan di antara mereka, khususnya aspek struktur dan perilaku, agar pengembangan ekonomi di tingkat lokal dapat berjalan. Selain melalui jalur kelembagaan, perubahan dapat pula dilakukan dengan jalur individual. Hagen (1962) menyatakan bahwa faktor personalitas menjadi penentu kemajuan ekonomi suatu masyarakat, sejauh pada saat yang sama sistem masyarakat tidak menghambat secara serius perwujudan tatanilai maju yang dibawa oleh individu masyarakat tadi.
3.3. Pengembangan Kelembagaan untuk Mendukung Transformasi Perekonomian Rakyat
Strategi pengembangan perekonomian rakyat di pedesaan dapat di tempuh antara lain dengan pengembangan kelembagaan lokal pendukung, pengembangan pertanian rakyat berkebudayaan industrial; pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat, atau pengembangan teknologi tepat guna dan bersifat spesifik lokasi. Ada tiga pilar utama kelembagaan sebagai pendukung kehidupan masyarakat di pedesaan yaitu : kelembagaan

yang hidup dan telah diterima oleh komunitas lokal atau tradisional (voluntary sector), kelembagaan pasar (private sector), dan kelembagaan politik dalam pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector).
Kelembagaan komunitas lokal-tradisional perlu ditransformasikan ke arah kelembagaan komunitas lokal yang maju dan responsif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan tersebut dapat beruba perubahan teknologi (tradisional-modern), sektoral (pertanian-industri), maupun tatanilai yang hidup dalam masyarakat (budaya pertanian tradisional-pertanian-industrial). Kelembagaan pasar atau private, yang dapat menciptakan pelaku-pelaku ekonomi rakyat yang punya jiwa kewirausahaan tinggi, ulet-tidak mengenal lelah, dan dinamis-dalam mengikuti perubahan dinamika pasar. Sementara itu, kelembagaan pemerintah lokal atau kelembagaan politik dalam sistem pengambilan keputusan haruslah dapat di arahkan pada kelembagaan politik di tingkat lokal yang handal. Dengan demikian diharapkan masyarakat lokal dapat akses terhadap sistem pengambilan keputusan di tingkat kabupaten-kota sebagai unit otonom yang lebih tinggi. Pada gilirannya masyarakat lokal di pedesaan mempunyai akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdayadi wilayahnya sehingga pemanfaatan dan pemeliharaannya bisa lebih optimal sesuai jiwa desentralisasi pembangunan.
Pembangunan pertanian yang telah dilakukan selama ini pada hakikatnya adalah pertanian yang sebagian bersifat adaptif terhadap lingkungan yang sudah mapan. Contohnya adalah pengembangan tanaman padi dengan menggunakan input produksi seperti bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dan penggunaan alsintan dalam kondisi lingkungan sawah yang sudah siap dan menyatu dengan budaya masyarakatnya. Revolusi hijau sukses karena dilandasi penguasaan teknologi budidaya disertai dengan penyiapan kelembagaan pendukungnya, sehingga dapat berjalan cepat dan diadaptasi secara luas oleh masyarakat pedesaan. Dalam upaya pengembangan pertanian rakyat di masa depan, selain penyediaan, diseminasi, pengembangan, serta pemanfaatan teknologi budidaya; juga perlu pendalaman teknologi pada aspek pasca panen, pengolahan, serta distribusi dan pemasarannya.
Sejalan dengan proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat tradisional-subsisten ke arah masyarakat modern-komersial; maka perlu transformasi dari pertanian rakyat dengan budaya lokal-tradisional ke arah pertanian rakyat dengan budaya industrial. Beberapa ciri pertanian-industrial seperti yang dikemukakan oleh Sasmita (1996), antara lain adalah: (1) Ilmu dan pengetahuan merupakan landasan utama dalam pengambilan keputusan (bukan intuisi atau kebiasaan); (2) Kemajuan teknologi merupakan instrumen utama dalam pemanfaatan sumberdaya; (3) Mekanisme pasar merupakan media utama dalam transaksi barang dan jasa; (4) Efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumberdaya; (5) Kualitas dan mutu merupakan orientasi dan tujuan para pelaku; (6) Profesionalisme merupakan karakter yang menonjol dalam setiap kegiatan atau aktivitas yang dijalankan; dan (7) Perekayasaan harus menggantikan ketergantungan pada alam, sehingga setiap produk yang dihasilkan bersifat standar baik dalam mutu, jumlah, bentuk, rasa, dan sifat-sifat lainnya, dan dengan ketepatan waktu.

Proses transformasi budaya haruslah menjadi penggerak proses modernisasi masyarakat pertanian. Paradigma ini sedikitnya mempunyai tiga aspek: (1) pengembangan agroindustri dimulai dengan mengutamakan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan lokal; (2) menggunakan desa sebagai unit otonom terbawah sebagai wadah kegiatan; dan (3) pendekatan wilayah pedesaan itu dapat meningkatkan keterkaitan desa-kota baik keterkaitan barang (input pertanian, output pertanian, barang konsumsi), keterkaitan tenaga kerja, maupun keterkaitan modal.
Pertanian rakyat di pedesaan yang berbudaya industri akhirnya sejalan dengan industrialisasi pedesaan dengan fokus utama pada pengembangan agroindustri. Sumber peningkatan produktivitas pertanian di pedesaan adalah melalui kegiatan investasi melalui pengembangan pertanian-industrial yang didukung oleh investasi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana fisik, serta investasi modal sosial melalui pengembangan kelembagaan. Pengembangan produktivitas pertanian dan agroindustri di pedesaan melalui pembangunan pertanian-industri perlu didorong dengan menumbuhkan lembaga-lembaga pedesaan yang modern, handal, dan mengakar pada budaya masyarakatnya. Pengembangan kawasan sentra-sentra produksi pertanian di pedesaan akan menjadikan pedesaan sebagai kota-kota pertanian. Dalam operasionalnya dapat berupa pengembangan rice estate, manggo estate, tobacco estate, sugarcane estate, dan lain-lain, yang terintegrasi dengan industri hilir dan industri hulunya.
*****