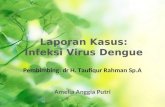DHF
-
Upload
nisau-luthfi-nur-azizah -
Category
Documents
-
view
216 -
download
2
description
Transcript of DHF

Makalah Farmasi
DENGUE HAEMORHAGE FEVER (DHF)
Oleh:
Nisa’u Luthfi Nur Azizah
G99151032
KEPANITERAAN KLINIK UPF/ LABORATORIUM FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNS / RSUD DR. MOEWARDI
SURAKARTA
2016

BAB I
PENDAHULUAN
Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang banyak
ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan subtropis, terutama asia tenggara,
Amerika tengah, Amerika dan Karibia. Host alami DBD adalah manusia,
agentnya adalah virus dengue yang termasuk ke dalam famili Flaviridae dan
genus Flavivirus, terdiri dari 4 serotipe yaitu Den-1, Den-2, Den3 dan Den-41,
ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, khususnya nyamuk
Aedes aegypti dan Ae. albopictus 2 yang terdapat hampir di seluruh pelosok
Indonesia.3
Demam dengue (DD) dan demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit
infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Sampai saat ini, infeksi virus Dengue
tetap menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Indonesia dimasukkan dalam
kategori “A” dalam stratifikasi DBD oleh World Health Organization (WHO)
2001 yang mengindikasikan tingginya angka perawatan rumah sakit dan kematian
akibat DBD, khususnya pada anak.1-3 Data Departemen Kesehatan RI
menunjukkan pada tahun 2006 (dibandingkan tahun 2005) terdapat peningkatan
jumlah penduduk, provinsi dan kecamatan yang terjangkit penyakit ini, dengan
case fatality rate sebesar 1,01% (2007).4-5 Berbagai faktor kependudukan
berpengaruh pada peningkatan dan penyebaran kasus DBD, antara lain:
pertumbuhan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak
terkendali, tidak efektifnya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis,
dan peningkatan sarana transportasi.4
Upaya pengendalian terhadap faktor kependudukan tersebut (terutama
kontrol vektor nyamuk) harus terus diupayakan, di samping pemberian terapi
yang optimal pada penderita DBD, dengan tujuan menurunkan jumlah kasus dan
kematian akibat penyakit ini. Sampai saat ini, belum ada terapi yang spesifik
untuk DBD, prinsip utama dalam terapi DBD adalah terapi suportif, yakni
pemberian cairan pengganti.6 Dengan memahami patogenesis, perjalanan
penyakit, gambaran

klinis dan pemeriksaan laboratorium, diharapkan penatalaksanaan dapat dilakukan
secara efektif dan efisien.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi
Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit demam akut yang
disebabkan oleh virus dengue serta memenuhi kriteria WHO untuk
DBD.7 DBD adalah salah satu manifestasi simptomatik dari infeksi virus
dengue.
Manifestasi simptomatik infeksi virus dengue adalah sebagai berikut 5
1. Demam tidak terdiferensiasi
2. Demam dengue (dengan atau tanpa perdarahan): demam akut selama 2-7
hari, ditandai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis (nyeri kepala, nyeri
retroorbital, mialgia/ atralgia, ruam kulit, manifestasi perdarahan [petekie
atau uji bendung positif], leukopenia) dan pemeriksaan serologi dengue
positif atau ditemukan pasien yang sudah dikonfirmasi menderita demam
dengue/ DBD pada lokasi dan waktu yang sama.
3. DBD (dengan atau tanpa renjatan)
B. Epidemiologi DBD
Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit infeksi yang
disebabkan oleh virus dengue dan mengakibatkan spektrum manifestasi klinis
yang bervariasi antara yang paling ringan, demam dengue (DD), DBD dan
demam dengue yang disertai renjatan atau dengue shock syndrome (DSS)9;
ditularkan nyamuk Aedes aegypti dan Ae. albopictus yang terinfeksi.10 Host
alami DBD adalah manusia, agentnya adalah virus dengue yang termasuk ke
dalam famili Flaviridae dan genus Flavivirus, terdiri dari 4 serotipe yaitu
Den-1, Den-2, Den3 dan Den-4.1 Dalam 50 tahun terakhir, kasus DBD
meningkat 30 kali lipat dengan peningkatan ekspansi geografis ke negara
negara baru dan, dalam dekade ini, dari kota ke lokasi pedesaan.9

Penderitanya banyak ditemukan di sebagian besar wilayah tropis dan
subtropis, terutama Asia Tenggara, Amerika Tengah, Amerika dan Karibia.1
Virus dengue dilaporkan telah menjangkiti lebih dari 100 negara,
terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat dan pemukiman di
Brazil dan bagian lain Amerika Selatan, Karibia, Asia Tenggara, dan India.
Jumlah orang yang terinfeksi diperkirakan sekitar 50 sampai 100 juta orang,
setengahnya dirawat di rumah sakit dan mengakibatkan 22.000 kematian
setiap tahun; diperkirakan 2,5 miliar orang atau hampir 40 persen populasi
dunia, tinggal di daerah endemis DBD yang memungkinkan terinfeksi virus
dengue melalui gigitan nyamuk setempat.11
Jumlah kasus DBD tidak pernah menurun di beberapa daerah tropik dan
subtropik bahkan cenderung terus meningkat12 dan banyak menimbulkan
kematian pada anak8 90% di antaranya menyerang anak di bawah 15 tahun.13
Di Indonesia, setiap tahunnya selalu terjadi KLB di beberapa provinsi, yang
terbesar terjadi tahun 1998 dan 2004 dengan jumlah penderita 79.480 orang
dengan kematian sebanyak 800 orang lebih.14 Pada tahun-tahun berikutnya
jumlah kasus terus naik tapi jumlah kematian turun secara bermakna
dibandingkan tahun 2004. Misalnya jumlah kasus tahun 2008 sebanyak
137.469 orang dengan kematian 1.187 orang atau case fatality rate (CFR)
0,86% serta kasus tahun 2009 sebanyak 154.855 orang dengan kematian
1.384 orang atau CFR 0,89%.15
Penularan virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk yang termasuk
subgenus Stegomya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Ae. albopictus sebagai
vektor primer dan Ae. polynesiensis, Ae. scutellaris serta Ae (Finlaya) niveus
sebagai vektor sekunder,9 selain itu juga terjadi penularan transexsual dari
nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui perkawinan9 serta penularan
transovarial dari induk nyamuk ke keturunannya.16-17 Ada juga penularan
virus dengue melalui transfusi darah seperti terjadi di Singapura pada tahun
2007 yang berasal dari penderita asimptomatik 18.
Dari beberapa cara penularan virus dengue, yang paling tinggi adalah
penularan melalui gigitan nyamuk Ae. aegypti.19 Masa inkubasi ekstrinsik (di

dalam tubuh nyamuk) berlangsung sekitar 8-10 hari, sedangkan inkubasi
intrinsik (dalam tubuh manusia) berkisar antara 4-6 hari dan diikuti dengan
respon imun.20
Penelitian di Jepara dan Ujungpandang menunjukkan bahwa nyamuk
Aedes spp. berhubungan dengan tinggi rendahnya infeksi virus dengue di
masyarakat; tetapi infeksi tersebut tidak selalu menyebabkan DBD pada
manusia karena masih tergantung pada faktor lain seperti vector capacity,
virulensi virus dengue, status kekebalan host dan lain-lain.21 Vector capacity
dipengaruhi oleh kepadatan nyamuk yang terpengaruh iklim mikro dan
makro, frekuensi gigitan per nyamuk per hari, lamanya siklus gonotropik,
umur nyamuk dan lamanya inkubasi ekstrinsik virus dengue serta pemilihan
Hospes.22 Frekuensi nyamuk menggigit manusia, di antaranya dipengaruhi
oleh aktivitas manusia; orang yang diam (tidak bergerak), 3,3 kali akan lebih
banyak digigit nyamuk Ae. Aegypti dibandingkan dengan orang yang lebih
aktif, dengan demikian orang yang kurang aktif akan lebih besar risikonya
untuk tertular virus dengue.
Selain itu, frekuensi nyamuk menggigit manusia juga dipengaruhi
keberadaan atau kepadatan manusia; sehingga diperkirakan nyamuk Ae.
aegypti di rumah yang padat penghuninya, akan lebih tinggi frekuensi
menggigitnya terhadap manusia dibanding yang kurang padat.22 Kekebalan
host terhadap infeksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah
usia dan status gizi, usia lanjut akan menurunkan respon imun dan
penyerapan gizi.23 Status status gizi yang salah satunya dipengaruhi oleh
keseimbangan asupan dan penyerapan gizi, khu-susnya zat gizi makro yang
berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh.24 Selain zat gizi makro, disebutkan
pula bahwa zat gizi mikro seperti besi dan seng mempengaruhi respon
kekebalan tubuh, apabila terjadi defisiensi salah satu zat gizi mikro, maka
akan merusak sistem imun.25
Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat interaksi makanan, tubuh
manusia dan lingkungan yang merupakan hasil interaksi antara zat-zat gizi
yang masuk dalam tubuh manusia dan penggunaannya. Tanda-tanda atau

penampilan status gizi dapat dilihat melalui variabel tertentu [indikator status
gizi] seperti berat badan, tinggi badan, dan lain lain.26 Sumber lain
mengatakan bahwa status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh status
keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan
[requirement] oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis: [pertumbuhan fisik,
perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lain lain].27
Status gizi sangat berpengaruh terhadap status kesehatan manusia
karena zat gizi mempengaruhi fungsi kinerja berbagai sistem dalam tubuh.
Secara umum berpengaruh pada fungsi vital yaitu kerja otak, jantung, paru,
ginjal, usus; fungsi aktivitas yaitu kerja otot bergaris; fungsi pertumbuhan
yaitu membentuk tulang, otot & organ lain, pada tahap tumbuh kembang;
fungsi immunitas yaitu melindungi tubuh agar tak mudah sakit; fungsi
perawatan jaringan yaitu mengganti sel yang rusak; serta fungsi cadangan gizi
yaitu persediaan zat gizi menghadapi keadaan darurat.28
Penderita DBD yang tercatat selama ini, tertinggi adalah pada
kelompok umur <15 tahun (95%) dan mengalami pergerseran dengan adanya
peningkatan
proporsi penderita pada kelompok umur 15 -44 tahun, sedangkan proporsi
penderita DBD pada kelompok umur >45 tahun sangat rendah seperti yang
terjadi di Jawa Timur berkisar 3,64%.29 Munculnya kejadian DBD,
dikarenakan penyebab majemuk, artinya munculnya kesakitan karena
berbagai faktor yang
saling berinteraksi, diantaranya agent (virus dengue), host yang rentan serta
lingkungan yang memungkinan tumbuh dan berkembang biaknya nyamuk
Aedes spp.30 Selain itu, juga dipengaruhi faktor predisposisi diantaranya
kepadatan dan mobilitas penduduk, kualitas perumahan, jarak antar rumah,
pendidikan, pekerjaan, sikap hidup, golongan umur, suku bangsa, kerentanan
terhadap penyakit, dan lainnya.31
C. Patogenesis DBD

Nyamuk Aedes spp yang sudah terinfesi virus dengue, akan tetap
infektif sepanjang hidupnya dan terus menularkan kepada individu yang
rentan pada saat menggigit dan menghisap darah.9 Setelah masuk ke dalam
tubuh manusia, virus dengue akan menuju organ sasaran yaitu sel kuffer
hepar, endotel pembuluh darah, nodus limpaticus, sumsum tulang serta paru-
paru. Beberapa penelitian menunjukkan, sel monosit dan makrofag
mempunyai peran pada infeksi ini, dimulai dengan menempel dan masuknya
genom virus ke dalam sel dengan bantuan organel sel dan membentuk
komponen perantara dan komponen struktur virus. Setelah komponen struktur
dirakit, virus dilepaskan dari dalam sel.7 Infeksi ini menimbulkan reaksi
immunitas protektif terhadap serotipe virus tersebut tetapi tidak ada cross
protective terhadap serotipe virus lainnya.32
Secara invitro, antobodi terhadap virus dengue mempunyai 4 fungsi
biologis yaitu netralisasi virus, sitolisis komplemen, antibody dependent cell-
mediated cytotoxity (ADCC) dan ADE.33 Berdasarkan perannya, terdiri dari
antobodi netralisasi atau neutralizing antibody yang memiliki serotipe
spesifik yang dapat mencegah infeksi virus, dan antibody non netralising
serotype yang mempunyai peran reaktif silang dan dapat meningkatkan
infeksi yang berperan dalam pathogenesis DBD dan DSS 7.
Terdapat dua teori atau hipotesis immunopatogenesis DBD dan DSS
yang masih kontroversial yaitu infeksi sekunder (secondary heterologus
infection) dan antibody dependent enhancement (ADE).7 Dalam teori atau
hipotesis infeksi sekunder disebutkan, bila seseorang mendapatkan infeksi
sekunder oleh satu serotipe virus dengue, akan terjadi proses kekebalan
terhadap infeksi serotipe virus dengue tersebut untuk jangka waktu yang
lama. Tetapi jika orang tersebut mendapatkan infeksi sekunder oleh serotipe
virus dengue lainnya, maka akan terjadi infeksi yang berat. Ini terjadi karena
antibody heterologus yang terbentuk pada infeksi primer, akan membentuk
kompleks dengan infeksi virus dengue serotipe baru yang berbeda yang tidak
dapat dinetralisasi bahkan cenderung membentuk kompleks yang infeksius
dan bersifat oponisasi internalisasi, selanjutnya akan teraktifasi dan

memproduksi IL-1, IL-6, tumor necrosis factor-alpha (TNF-A) dan platelet
activating factor (PAF); akibatnya akan terjadi peningkatan (enhancement)
infeksi virus dengue.7 TNF alpha akan menyebabkan kebocoran dinding
pembuluh darah, merembesnya cairan plasma ke jaringan tubuh yang
disebabkan kerusakan endothel pembuluh darah yang mekanismenya sampai
saat ini belum diketahui dengan jelas.34
Pendapat lain menjelaskan, kompleks imun yang terbentuk akan
merangsang komplemen yang farmakologisnya cepat dan pendek dan bersifat
vasoaktif dan prokoagulan sehingga menimbulkan kebocoran plasma (syock
hipolemik) dan perdarahan.35 Anak di bawah usia 2 tahun yang lahir dari ibu
yang terinfeksi virus dengue dan terjadi infeksi dari ibu ke anak, dalam tubuh
anak tersebut terjadi non neutralizing antibodies akaibat adanya infeksi yang
persisten. Akibatnya, bila terjadi infeksi virus dengue pada anak tersebut,
maka akan langsung terjadi proses enhancing yang akan memacu makrofag
mudah terinfeksi dan teraktifasi dan mengeluarkan IL-1, IL-6 dan TNF alpha
juga PAF.36-37 Pada teori ADE disebutkan, jika terdapat antibodi spesifik
terhadap jenis virus tertentu, maka dapat mencegah penyakit yang
diakibatkan oleh virus tersebut, tetapi sebaliknya apabila antibodinya tidak
dapat menetralisasi virus, justru akan menimbulkan penyakit yang berat.7
Kinetik immunoglobulin spesifik virus dengue di dalam serum
penderita DD, DBD dan DSS, didominasi oleh IgM, IgG1 dan IgG3.38 Selain
kedua teori tersebut, masih ada teori-teori lain tentang pathogenesis DBD, di
antaranya adalah teori virulensi virus yang mendasarkan pada perbedaan
serotipe virus dengue yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3 dan DEN 4 yang
kesemuanya dapat ditemukan pada kasus-kasus fatal tetapi berbeda antara
daerah satu dengan lainnya. Selanjutnya ada teori antigen-antibodi yang
berdasarkan pada penderita atau kejadian DBD terjadi penurunan aktivitas
sistem komplemen yang ditandai penurunan kadar C3, C4 dan C5. Disamping
itu, pada 48- 72% penderita DBD, terbentuk kompleks imun antara IgG
dengan virus dengue yang dapat menempel pada trombosit, sel B dan sel

organ tubuh lainnya dan akan mempengaruhi aktivitas komponen sistem
imun yang lain.
Selain itu ada teori moderator yang menyatakan bahwa makrofag yang
terinfeksi virus dengue akan melepas berbagai mediator seperti interferon, IL-
1, IL-6, IL-12, TNF dan lain-lain, yang bersama endotoksin
bertanggungjawab pada terjadinya sok septik, demam dan peningkatan
permeabilitas kapiler.39 Pada infeksi virus dengue, viremia terjadi sangat
cepat, hanya dalam beberapa hari dapat terjadi infeksi di beberapa tempat tapi
derajat kerusakan jaringan (tissue destruction) yang ditimbulkan tidak cukup
untuk menyebabkan kematian karena infeksi virus; kematian yang terjadi
lebih disebabkan oleh gangguan metabolic.7
D. Faktor Risiko Penularan Demam Berdarah Dengue
Salah satu faktor risiko penularan DBD adalah pertumbuhan penduduk
perkotaan yang cepat, mobilisasi penduduk karena membaiknya sarana dan
prasarana transportasi dan terganggu atau melemahnya pengendalian populasi
sehingga memungkin terjadinya KLB.40 Faktor risiko lainnya adalah
kemiskinan yang mengakibatkan orang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyediakan rumah yang layak dan sehat, pasokan air minum dan
pembuangan sampah yang benar.11
Tetapi di lain pihak, DBD juga bisa menyerang penduduk yang lebih
makmur terutama yang biasa bepergian.41 Dari penelitian di Pekanbaru
Provinsi Riau, diketahui faktor yang berpengaruh terhadap kejadian DBD
adalah pendidikan dan pekerjaan masyarakat, jarak antar rumah, keberadaan
tempat penampungan air, keberadaan tanaman hias dan pekarangan serta
mobilisai penduduk; sedangkan tata letak rumah dan keberadaan jentik tidak
menjadi faktor risiko.42 Faktor risiko yang menyebabkan munculnya antibodi
IgM anti dengue yang merupakan reaksi infesksi primer, berdasarkan hasil
penelitian di wilayah Amazon Brasil adalah jenis kelamin laki-laki,
kemiskinan, dan migrasi. Sedangkan faktor risiko terjadinya infeksi sekunder

yang menyebabkan DBD adalah jenis kelamin lakilaki, riwayat pernah
terkena DBD pada periode sebelumnya serta migrasi ke daerah perkotaan.43
E. Vektor Demam Berdarah Dengue
Demam berdarah dengue ditularkan oleh nyamuk Ae. aegypti yang
menjadi vektor utama serta Ae. albopictus yang menjadi vektor pendamping.
Kedua spesies nyamuk itu ditemukan di seluruh wilayah Indonesia, hidup
optimal pada ketinggian di atas 1000 di atas permukaan laut,10 tapi dari
beberapa laporan dapat ditemukan pada daerah dengan ketinggian sampai de-
ngan 1.500 meter,44 bahkan di India dilaporkan dapat ditemukan pada
ketinggian 2.121 meter serta di Kolombia pada ketinggian 2.200 meter.45
Nyamuk Aedes berasal dari Brazil dan Ethiopia, stadium dewasa
berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lainnya.3
Kedua spesies nyamuk tersebut termasuk ke dalam Genus Aedes dari Famili
Culicidae. Secara morfologis keduanya sangat mirip, namun dapat dibedakan
dari strip putih yang terdapat pada bagian skutumnya.46 Skutum Ae. aegypti
berwarna hitam dengan dua strip putih sejajar di bagian dorsal tengah yang
diapit oleh dua garis lengkung berwarna putih. Sedangkan skutum Ae.
albopictus yang juga berwarna hitam hanya berisi satu garis putih tebal di
bagian dorsalnya.11 Nyamuk Ae. aegypti mempunyai dua subspesies yaitu Ae.
aegypti queenslandensis dan Ae. aegypti formosus. Subspesies pertama hidup
bebas di Afrika, sedangkan subspecies kedua hidup di daerah tropis yang
dikenal efektif menularkan virus DBD. Subspesies kedua lebih berbahaya
dibandingkan subspecies pertama.11
F. Diagnosis
Penegakan diagnosis berdasarkan kriteria WHO tahun 1997(8,16,17)
1. Demam Dengue
a. Probable
Demam akut disertai dua atau lebih manifestasi klinis berikut;
nyeri kepala, nyeri belakang mata, miagia, artralgia, ruam, manifestasi

perdarahan, leukopenia, uji HI >_ 1.280 dan atau IgM anti dengue
positif, atau pasien berasal dari daerah yang pada saat yang sama
ditemukan kasus confirmed dengue infeksi.
b. Corfirmed
Kasus dengan konfirmasi laboratorium sebagai berikut deteksi
antigen dengue, peningkatan titer antibodi > 4 kali pada pasangan
serum akut dan serum konvalesens, danatau isolasi virus.
2. Demam Berdarah Dengue
Diagnosis tegak bila semua hal dipenuhi:
a. Demam akut 2-7 hari, biasanya bersifat bifasik.
b. Manifestasi perdarahan yang biasanya berupa:
1) uji tourniquet positif
2) petekie, ekimosis, atau purpura
3) perdarahan mukosa (epistaksis, perdarahan gusi), saluran cerna,
tempat bekas suntikan
4) hematemesis atau melena
c. Trombositopenia < 100.00/ul
d. Kebocoran plasma yang ditandai dengan
1) peningkatan nilai hematrokrit > 20 % dari nilai baku sesuai umur dan
jenis kelamin.
2) penurunan nilai hematokrit > 20 % setelah pemberian cairan yang
adekuat
3) efusi pleura, asites, hipoproteinemi
3. Sindrom Syok Dengue
Seluruh kriteria DBD 17 disertai dengan tanda kegagalan sirkulasi yaitu:
a. Penurunan kesadaran, gelisah
b. Nadi cepat, lemah
c. Hipotensi
d. Tekanan nadi < 20 mmHg
e. Perfusi perifer menurun
f. Kulit dingin-lembab.

G. Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan laboratorium meliputi kadar hemoglobin, kadar
hematokrit, jumlah trombosit, dan hapusan darah tepi untuk melihat adanya
limfositosis relatif disertai gambaran limfosit plasma biru (sejak hari ke 3).
Trombositopenia umumnya dijumpai pada hari ke 3-8 sejak timbulnya
demam. Hemokonsentrasi dapat mulai dijumpai mulai hari ke 3 demam.16
Diagnosis pasti dapat tegak bila didapatkan hasil isolasi virus dengue
(cell culture) atau deteksi antigen virus RNA dgn teknik Reverse
Transcriptase Polymerase Chain Reaction namun teknik ini rumit.
Pemeriksaan lain yaitu tes serologis yang mendeteksi adanya antibodi
spesifik terhadap dengue. Berupa antibodi total, IgM yang terdeteksi mulai
hari ke-3 sampai ke-5 meningkat smpai minggu 3, dan menghilang setelah
60-90 hari. IgG terbentuk pada hari ke-14 pada infeksi primer, dan terdeteksi
pada hari ke-2 pada infeksi sekunder.9
Pemeriksaan lain menunjukkan SGOT dan SGPT dapat meningkat.
Hipoproteinemi akibat kebocoran plasma biasa ditemukan. Adanya
fibrinolisis dan ganggungan koagulasi tampak pada pengurangan fibrinogen,
protrombin, faktor VIII, faktor XII, dan antitrombin III. aPTT dan PT
memanjang pada sepertiga sampai setengah kasus DBD. Asidosis metabolik
dan peningkatan BUN ditemukan pada syok berat. 9
Pemeriksaan radiologis (foto toraks PA tegak dan lateral dekubitus
kanan) dapat dilakukan untuk melihat ada tidaknya efusi pleura, terutama
pada hemitoraks kanan dan pada keadaan perembesan plasma hebat, efusi
dapat ditemukan pada kedua hemitoraks. Asites dan efusi pleura dapat pula
dideteksi denganUSG.16,5
H. Penatalaksanaan
Terdapat 5 hal yang harus dievaluasi yaitu keadaan umum, renjatan,
kebocoran plasma, perdarahan terutama perdarahan gastrointestinal dan
komplikasi. Pada dasarnya terapi DBD adalah bersifat suportif dan

simtomatis. Penatalaksanaan ditujukan untuk mengganti kehilangan cairan
akibat kebocoran plasma dan memberikan terapi substitusi komponen darah
bilamana diperlukan. Dalam pemberian terapi cairan, hal terpenting yang
perlu dilakukan adalah pemantauan baik secara klinis maupun laboratoris.
Proses kebocoran plasma dan terjadinya trombositopenia pada umumnya
terjadi antara hari ke 4 hingga 6 sejak demam berlangsung. Pada hari ke-7
proses kebocoran plasma akan berkurang dan cairan akan kembali dari ruang
interstitial ke intravaskular. Terapi cairan pada kondisi tersebut secara
bertahap dikurangi. Selain pemantauan untuk menilai apakah pemberian
cairan sudah cukup atau kurang, pemantauan terhadap kemungkinan
terjadinya kelebihan cairan serta terjadinya efusi pleura ataupun asites yang
masif perlu selalu diwaspadai.
Terapi nonfarmakologis yang diberikan meliputi tirah baring (pada
trombositopenia yang berat) dan pemberian makanan dengan kandungan gizi
yang cukup, lunak dan tidak mengandung zat atau bumbu yang mengiritasi
saluaran cerna.
Sebagai terapi simptomatis, dapat diberikan antipiretik berupa
parasetamol, serta obat simptomatis untuk mengatasi keluhan dispepsia.
Pemberian aspirin ataupun obat antiinflamasi nonsteroid sebaiknya dihindari
karena berisiko terjadinya perdarahan pada saluran cerna bagian atas
(lambung/duodenum).
Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam terapi cairan
khususnya pada penatalaksanaan demam berdarah dengue: pertama adalah
jenis cairan dan kedua adalah jumlah serta kecepatan cairan yang akan
diberikan. Karena tujuan terapi cairan adalah untuk mengganti kehilangan
cairan di ruang intravaskular, pada dasarnya baik kristaloid (ringer laktat,
ringer asetat, cairan salin) maupun koloid dapat diberikan. WHO
menganjurkan terapi kristaloid sebagai cairan standar pada terapi DBD karena
dibandingkan dengan koloid, kristaloid lebih mudah didapat dan lebih murah.
Jenis cairan yang ideal yang sebenarnya dibutuhkan dalam
penatalaksanaan antara lain memiliki sifat bertahan lama di intravaskular,

aman dan relatif mudah diekskresi, tidak mengganggu sistem koagulasi
tubuh, dan memiliki efek alergi yang minimal.47,9 Secara umum, penggunaan
kristaloid dalam tatalaksana DBD aman dan efektif. Beberapa efek samping
yang dilaporkan terkait dengan penggunaan kristaloid adalah edema, asidosis
laktat, instabilitas hemodinamik dan hemokonsentrasi.12,13 Kristaloid memiliki
waktu bertahan yang singkat di dalam pembuluh darah. Pemberian larutan RL
secara bolus (20 ml/kg BB) akan menyebabkan efek penambahan volume
vaskular hanya dalam waktu yang singkat sebelum didistribusikan ke seluruh
kompartemen interstisial (ekstravaskular) dengan perbandingan 1:3, sehingga
dari 20 ml bolus tersebut dalam waktu satu jam hanya 5 ml yang tetap berada
dalam ruang intravaskular dan 15 ml masuk ke dalam ruang interstisial.14
Namun demikian, dalam aplikasinya terdapat beberapa keuntungan
penggunaan kristaloid antara lain mudah tersedia dengan harga terjangkau,
komposisi yang menyerupai komposisi plasma, mudah disimpan dalam
temperatur ruang, dan bebas dari kemungkinan reaksi anafilaktik.15,16
Dibandingkan cairan kristaloid, cairan koloid memiliki beberapa
keunggulan yaitu: pada jumlah volume yang sama akan didapatkan ekspansi
volume plasma (intravaskular) yang lebih besar dan bertahan untuk waktu
lebih lama di ruang intravaskular. Dengan kelebihan ini, diharapkan koloid
memberikan oksigenasi jaringan lebih baik dan hemodinamik terjaga lebih
stabil. Beberapa kekurangan yang mungkin didapatkan dengan penggunaan
koloid yakni risiko anafilaksis, koagulopati, dan biaya yang lebih besar.
Namun beberapa jenis koloid terbukti memiliki efek samping koagulopati dan
alergi yang rendah (contoh: hetastarch).15,16 Penelitian cairan koloid
dibandingkan kristaloid pada sindrom renjatan dengue (DSS) pada pasien
anak dengan parameter stabilisasi hemodinamik pada 1 jam pertama renjatan,
memberikan hasil sebanding pada kedua jenis cairan.17,18

BAB III
ILUSTRASI KASUS
I. ANAMNESA
A. Identitas Penderita
Nama : Tn. MH
Umur : 20 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku : Jawa
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMA
Status : Belum menikah
Alamat : Surakarta, Jawa Tengah
No. RM : 01291784
Berat Badan : 70 kg
Tinggi Badan : 175 cm
IMT : 22.85 kg/cm2 (normoweight)
B. Data Dasar
Autoanamnesis, alloanamnesis dan pemeriksaan fisik dilakukan pada
tanggal 26 Januari 2016.

Keluhan Utama
Demam sejak 5 hari
Riwayat Penyakit Sekarang
Pasien datang dengan keluhan demam. Demam dikeluhkan sejak
5 hari SMRS, demam dirasakan mendadak naik, demam terus –
menerus sepanjang hari, demam turun dengan obat penurun demam,
tapi demam naik lagi. Demam tidak pernah hilang sama sekali.
Demam disertai dengan keringat sekujur tubuh. Demam tidak diikuti
batuk dan pilek. Demam juga tidak diikuti dengan kejang.
Pasien juga mengeluh pegal linu di seluruh persendian tubuhnya
yang dikeluhkan sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga
mengeluhkan sakit kepala berdenyut, yang dirasakan terutama nyeri di
belakang mata sejak 4 hari yang lalu, namun pandangan tidak
terganggu. Nyeri berkurang dengan istirahat dan memberat saat
aktivitas. Pasien juga mengeluh mual dan muntah 4 hari SMRS.
Muntah didahului oleh mual yang timbul terutama bila melihat
makanan dan saat makan. Muntah dalam sehari mencapai 3 – 4 kali,
yang berisi makanan dan minuman yang dikonsumsi, volume sekitar
½ - 1 gelas belimbing.
Pasien juga mengeluhkan timbul bintik – bintik merah di badan
dan tangan bagian atas 4 hari SMRS. Bintik-bintik tidak hilang
dengan penekanan dan muncul terus-menerus. Tidak dirasakan nyeri
di sekitar bagian yang berbintik-bintik. Pasien juga mengeluhkan
lemas, lemas yang dirasakan terus – menerus, terutama jika
beraktivitas. Lemas tidak berkurang dengan pemberian makanan dan
minuman, dan sedikit berkurang dengan istirahat. Pasien tidak
mengeluhkan adanya mimisan maupun gusi berdarah.
BAK dalam sehari 4 – 5 kali, masing-masing sekitar ½ - 1 gelas
belimbing, warna kuning jernih, BAK anyang-anyangen (-), BAK
nanah (-), BAK merah (-), nyeri ketika BAK (-). BAB sehari sebanyak
1 kali, konsistensi lunak, warna kuning, darah (-), lendir (-).

Penurunan berat badan (-). Pasien menyangkal berpergian keluar jawa
sebelumnya.
Riwayat Penyakit Dahulu
1. Riwayat tekanan darah tinggi : disangkal
2. Riwayat sakit gula : disangkal
3. Riwayat asma : disangkal
4. Riwayat alergi : disangkal
5. Riwayat sakit jantung : disangkal
6. Riwayat sakit ginjal : disangkal
7. Riwayat mondok : disangkal
8. Riwayat sakit liver : disangkal
9. Riwayat operasi : disangkal
Riwayat Penyakit Keluarga
Tidak diketahui
Riwayat Lingkungan Sekitar
Pasien tinggal di Surakarta dan memiliki tetangga yang mondok
dengan DBD
Riwayat Alergi
Riwayat Alergi
Tahun Bahan/Obat Gejala
- - -
- - -
Riwayat Kebiasaan
Jamu Disangkal
Merokok Disangkal
Alkohol (-)
Olahraga (-)
Riwayat Gizi
Pasien tinggal bersama keluarga. Pasien makan sebanyak 3 kali
sehari, dengan nasi, sayur, dan lauk pauk.

II. PEMERIKSAAN FISIK
Pemeriksaan fisik dilakukan tanggal 26 Januari 2016 dengan hasil
sebagai berikut:
1. Keadaan umum : Tampak lemah, kesan sakit sedang, compos
mentis, GCS E4/V5/M6, kesan gizi cukup.
2. Tanda Vital
Tensi : 120/ 80 mmHg
Nadi : 96x/ menit
Frekuensi nafas : 20x/ menit
Suhu : 38,8o C
3. VAS skor : 3 – 5
4. Status gizi
BB : 70 kg
TB : 175 cm
BMI : 22.85 kg/cm2
Kesan : Normoweight
5. Kulit : Warna coklat, turgor menurun (-), hiperpigmentasi (-),
kering (-), teleangiektasis (-), ikterik (-)
6. Kepala : Bentuk mesocephal, rambut warna hitam, mudah rontok
(-), luka (-), atrofi m. Temporalis (-).
7. Mata : Mata cekung (-/-), konjungtiva pucat (-/-), sklera ikterik
(-/-), perdarahan subkonjugtiva (-/-), pupil isokor dengan
diameter (3 mm/3 mm), reflek cahaya (+/+), edema
palpebra (-/-), strabismus (-/-), katarak DM (-/-)
8. Telinga : Sekret (-), darah (-), nyeri tekan mastoid (-), nyeri tekan
tragus (-)
9. Hidung : Nafas cuping hidung (-), sekret (-), epistaksis (-)
10. Mulut : Sianosis (-), gusi berdarah (-), papil lidah atrofi (-), gusi
berdarah (-), luka pada sudut bibir (-), oral thrush (-)
11. Leher : JVP R +2 cm, trakea di tengah, simetris, pembesaran
kelenjar tiroid (-), pembesaran kelenjar getah bening (-),

leher kaku (-), distensi vena-vena leher (-), kaku kuduk
(-)
12. Thorax : Bentuk normochest, simetris, pengembangan dada kanan
= kiri, retraksi intercostal (-), pernafasan
abdominothorakal, sela iga melebar (-), pembesaran
KGB axilla (-/-).
13. Jantung
Inspeksi : Ictus kordis tidak tampak
Palpasi : Ictus kordis tidak kuat angkat, teraba di 1 cm
sebelah medial SIC V linea medioclavicularis sinistra.
Perkusi :
- Batas jantung kanan atas: SIC II linea sternalis dextra
- Batas jantung kanan bawah: SIC IV linea parasternalis dekstra
- Batas jantung kiri atas: SIC II linea sternalis sinistra
- Batas jantung kiri bawah: SIC V 1 cm medial linea
medioklavicularis sinistra
- Pinggang jantung : SIC III lateral parasternalis sinistra
→ konfigurasi jantung kesan tidak melebar
Auskultasi : Bunyi jantung I-II murni, intensitas normal, reguler,
bising (-), gallop (-).
13. Pulmo
b. Depan
Inspeksi
- Statis : Normochest, simetris, sela iga tidak melebar, iga
tidak mendatar
- Dinamis : Pengembangan dada simetris kanan = kiri, sela iga
tidak melebar, retraksi intercostal (-)
Palpasi
- Statis : Simetris
- Dinamis : Pergerakan kanan = kiri, fremitus raba kanan = kiri
Perkusi

- Kanan : Sonor, redup pada batas relatif paru-hepar pada
SIC VI linea medioclavicularis dextra, pekak pada batas
absolut paru hepar
- Kiri : Sonor, sesuai batas paru jantung pada SIC VI linea
medioclavicularis sinistra
Auskultasi
- Kanan : Suara dasar vesikuler normal, suara tambahan
wheezing(-), ronkhi basah kasar(-), ronkhi basah halus (-),
krepitasi (-)
- Kiri : Suara dasar vesikuler normal, suara tambahan
wheezing (-), ronkhi basah kasar (-), ronkhi basah halus (-),
krepitasi (-)
c. Belakang
Inspeksi
- Statis : Normochest, simetris, sela iga tidak melebar, iga
tidak mendatar
- Dinamis : Pengembangan dada simetris kanan=kiri, sela iga
tidak melebar, retraksi intercostal (-)
Palpasi
- Statis : Simetris
- Dinamis : Pergerakan kanan = kiri, fremitus raba kanan = kiri
Perkusi
- Kanan : Sonor.
- Kiri : Sonor.
- Peranjakan diafragma 5 cm
Auskultasi
- Kanan : Suara dasar vesikuler normal, suara tambahan
wheezing(-), ronkhi basah kasar(-), ronkhi basah halus (-),
krepitasi (-)

- Kiri : Suara dasar vesikuler normal, suara tambahan
wheezing(-), ronkhi basah kasar(-), ronkhi basah halus (-),
krepitasi (-)
14. Abdomen
Inspeksi : Dinding perut sejajar dinding thorak, ascites (-),
venektasi (-), sikatrik (-), striae (-), caput medusae
(-), ikterik (-)
Auskultasi : Bising usus (+) normal, bising epigastrium (-)
Perkusi : Timpani, pekak alih (-), pekak sisi (-)
Palpasi : Supel, nyeri tekan epigastrium (-), hepar dan lien
tidak teraba
15. Tanda meningeal : Kaku kuduk (-), brudzinsky I (-), brudzinsky II (-),
brudzinsky III (-)
16. Ekstremitas
_ _
_ _
Akral dingin Oedem
+ +
_ _
Petechie Pulsasi
+ +
+ +
Sensorik Motorik
III. PEMERIKSAAN PENUNJANG
Laboratorium Darah
- Leukosit 11.700/µL
- Eritrosit 5.400/ µL
- Trombosit 100.000/µL
- Hb 11,5 g/dL
_ _
_ _
+ +
+ +
5 5
5 5

- Hct 41,5 %
IV. RENCANA PEMECAHAN MASALAH
Diagnosis Kerja : DHF Grade II
Diagnosis Banding : DHF, typhoid
Rencana Diagnostik:
1. Mondok bangsal
2. Diet lunak TKTP 1900 kkal, tidak merangsang lambung
3. Inf. RL 30 tpm
4. Paracetamol 3 x 500 mg, bila suhu > 38o
V. TATALAKSANA
Tujuan Penatalaksanaan
- mengatasi kehilangan cairan plasma akibat peningkatan permeabilitas
kapiler
- mengatasi gejala simptomatis
1. Medikamentosa
- IVFD RL 30 tpm
- Paracetamol 3 x 500 mg PO bila suhu > 38oC
Resep
RS dr. MoewardiJalan Kolonel Sutarto No. 132, Jebres, Surakarta
28 Januari 2016Dokter : dr. Nisa’u Luthfi Nur Azizah
R/ Infus Ringer Laktat flab. No III Cum infus set No. I
IV catheter no.22 No. I Three way No.I
∫ imm
R/ Paracetamol tab mg 500 No. X ∫ 3 dd tab I
Pro : Tn. MH (20 tahun)Alamat: Surakarta, Jawa Tengah

2. Non Medikamentosa
- Bedrest (tirah baring)
- Minum air yang banyak
- Mengedukasi keluarga pasien untuk melakukan kegiatan pencegahan
DBD dengan 3M, yaitu menutup, menguras, mengubur barang-
barang yang dapat menampung air.
- Menjaga asupan nutrisi yang seimbang.
VI. PROGNOSIS
- Ad vitam : bonam
- Ad functionam : bonam
- Ad sanactionam : bonam
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Ringer Laktat
a. Definisi
Ringer Laktat merupakan larutan kristaloid yang mengandung natrium laktat, natrium klorida, kalium klorida dan kalsium klorida. Osmolaritasnya sebesar 270 mOsm/l.
b. Cara kerja- Merupakan larutan isotoni Natrium Klorida, Kalium Klorida,
Kalsium Klorida, dan Natrium Laktat yang komposisinya mirip dengan cairan ekstraseluler

- Merupakan cairan pengganti pada kasus-kasus kehilangan cairan ekstraselular.
- Merupakan larutan non-koloid, mengandung ion-ion yang terdistribusi kedalam cairan intravaskuler dan interststel (ekstravaskuler)
c. Cara pemberian : intravenad. Indikasi : mengembalikan keseimbangan elektrolit pada
dehidrasi.e. Kontraindikasi : hipernatremia, kelainan ginjal,
kerusakan sel hati, asidosis laktat.f. Efek samping:
- Reaksi-reaksi yang mungkin terjadi karena larutannya atau cara
pemberiannya termasuk timbulnya panas, infeksi pada tempat
penyuntikan, trombosis vena atau flebitis yang meluas dari tempat
penyuntikan, ekstravasasi.
- Bila terjadi rekasi efek samping, pemakaian harus dihentikan dan lakukan
evaluasi terhadap penderita.
g. Cara penyimpanan: Pada suhu kamar / ruangan antara 25oC – 30oC.
h. Peringatan: - Tidak boleh dicampur dengan larutan yang mengandung
fosfat.- Penggunaan cairan ini tidak boleh terlalu bebas karena
dapat mengakibatkan asidosis metabolik akibat kandungan klor nya. Jika terjadi asidosis metabolik akan mengakibatkan penurunan aliran darah ke ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerolus. Selain itu resusitasi salin dalam volum yang besar dapat menyebabkan koagulopati.

- Laktat yang terdapat di dalam larutan RL akan dimetabolisme oleh hati menjadi bikarbonat yang berguna untuk memperbaiki keadaan seperti asidosis metabolik
i. Dosis:Pada fase awal, cairan kristaloid diguyur sebanyak 10-20 ml/kgBB dan dievaluasi setelah 15-30 menit. Bila renjatan telah teratasi (ditandai dengan tekanan darah sistolik 100 mmHg dan tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, frekuensi nadi kurang dari 100 kali per menit, dengan volume yang cukup, akral teraba hangat, dan kulit tidak pucat serta diuresis 0,5-1 ml/kgBB/jam) jumlah cairan dikurangi menjadi 7 mlkgBB/jam. Bila dalam waktu 60-120 menit keadaan tetap stabil pemberian cairan menjadi 5 ml/kgBB/jam. Bila dalam waktu 60-120 menit kemudian keadaan tetap stabil pemberian cairan menjadi 3ml/KgBB/jam. Bila 48-96 jam setelah renjatan teratasi tanda-tanda vital dan hematokrit tetap stabil serta dieresis cukup maka pemberian cairan perinfus harus dihentikan
B. Paracetamol
a. Definisi
Parasetamol (asetaminofen) merupakan obat analgetik non narkotik,
antipiretik, tidak mempunyai daya kerja anti radang dan tidak menyebabkan
iritasi serta peradangan lambung.
b. Farmakokinetik
Parasetamol cepat diabsorbsi dari saluran pencernaan, dengan kadar serum
puncak dicapai dalam 30-60 menit. Waktu paruh kira-kira 2 jam.
Metabolisme di hati, sekitar 3 % diekskresi dalam bentuk tidak berubah
melalui urin dan 80-90 % dikonjugasi dengan asam glukoronik atau asam
sulfurik kemudian diekskresi melalui urin dalam satu hari pertama; sebagian
dihidroksilasi menjadi N asetil benzokuinon yang sangat reaktif dan

berpotensi menjadi metabolit berbahaya. Pada dosis normal bereaksi dengan
gugus sulfhidril dari glutation menjadi substansi nontoksik. Pada dosis besar
akan berikatan dengan sulfhidril dari protein hati.
c. Farmakodinamik
Parasetamol menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam
arakhidonat menjadi prostaglandin terganggu. Parasetamol menghambat
siklooksigenase pusat lebih kuat dari pada aspirin, inilah yang menyebabkan
Parasetamol menjadi obat antipiretik yang kuat melalui efek pada pusat
pengaturan panas. Parasetamol hanya mempunyai efek ringan pada
siklooksigenase perifer. Inilah yang menyebabkan Parasetamol hanya
menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri ringan sampai sedang.
Parasetamol tidak mempengaruhi nyeri yang ditimbulkan efek langsung
prostaglandin, ini menunjukkan bahwa parasetamol menghambat sintesa
prostaglandin dan bukan blokade langsung prostaglandin. Obat ini menekan
efek zat pirogen endogen dengan menghambat sintesa prostaglandin, tetapi
demam yang ditimbulkan akibat pemberian prostaglandin tidak dipengaruhi,
demikian pula
peningkatan suhu oleh sebab lain, seperti latihan fisik.
d. Indikasi
Parasetamol merupakan pilihan lini pertama bagi penanganan demam dan
nyeri sebagai antipiretik dan analgetik. Parasetamol digunakan bagi nyeri
yang
ringan sampai sedang.
e. Kontraindikasi
Penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif
terhadap obat ini.
f. Sediaan dan Posologi
Parasetamol tersedi sebagai obat tunggal, berbentuk tablet 500mg atau sirup
yang mengandung 120mg/5ml. Selain itu Parasetamol terdapat sebagai
sediaan

kombinasi tetap, dalam bentuk tablet maupun cairan. Dosis Parasetamol
untuk dewasa 300mg-1g per kali, dengan maksimum 4g per hari, untuk anak
6-12 tahun: 150-300 mg/kali, dengan maksimum 1,2g/hari. Untuk anak 1-6
tahun: 60mg/kali, pada keduanya diberikan maksimum 6 kali sehari.
g. Efek samping
Reaksi alergi terhadap derivate para-aminofenol jarang terjadi.
Manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat
berupa demam dan lesi pada mukosa.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Demam berdarah dengue tetap menjadi salah satu masalah kesehatan
di Indonesia. Dengan mengikuti kriteria WHO 1997, diagnosis klinis dapat
segera ditentukan. Di samping modalitas diagnosis standar untuk menilai
infeksi virus Dengue, antigen nonstructural protein 1 (NS1) Dengue, sedang
dikembangkan dan memberikan prospek yang baik untuk diagnosis yang
lebih dini.
Terdapat 5 hal yang harus dievaluasi yaitu keadaan umum, renjatan,
kebocoran plasma, perdarahan terutama perdarahan gastrointestinal dan
komplikasi. Pada dasarnya terapi DBD adalah bersifat suportif dan
simtomatis. Terapi cairan pada DBD diberikan dengan tujuan substitusi
kehilangan cairan akibat kebocoran plasma. Dalam terapi cairan, hal
terpenting yang perlu diperhatikan adalah: jenis cairan, jumlah serta
kecepatan, dan pemantauan baik secara klinis maupun laboratoris untuk
menilai respon kecukupan cairan. Untuk terapi simptomatik dapat diberikan
analgetik dan antiperetik.

DAFTAR PUSTAKA
1. Kurane I. Dengue Hemorrhagic Fever with Spesial Emphasis on
Immunopathogenesis. Comparative Immunology, Microbiology &
Infectious Disease. 2007; Vol 30:329-40.
2. WHO. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Dengue dan
Demam Berdarah Dengue. Jakarta: WHO & Departemen Kesehatan RI;
2003.
3. Lestari K. Epidemiologi Dan Pencegahan Demam Berdarah Dengue
(DBD) Di Indonesia. Farmaka. Desember 2007; Vol. 5 No. 3: hal. 12-29.
4. Chuansumrit A, Tangnararatchakit K. Pathophysiology and Management
of Dengue Hemorrhagic Fever. Bangkok: Department of Pediatrics,
Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University; 2006.
5. Hadinegoro, Rezeki S, Soegianto S, Soeroso T, Waryadi S. Tata Laksana
Demam Berdarah Dengue di Indonesia. Jakarta: Ditjen PPM&PL
Depkes&Kesos R.I; 2001.
6. Harikushartono, Hidayah N, Darmowandowo W, Soegijanto S. Demam
Berdarah Dengue: Ilmu Penyakit Anak, Diagnosa dan Penatalaksanaan.
Jakarta: Salemba Medika; 2002.
7. Soegijanto S. Patogenesa dan Perubahan Patofisiologi Infeksi Virus
Dengue. www.pediatrikcom/buletin/20060220-8ma2gi-buletindoc; 2002
[cited 2010]; Available from: ww.pediatrik.com/buletin/20060220-8ma2gi-
buletindoc.
8. Suhendro, Nainggolan L, Chen K, Pohan HT. 2006. Demam Berdarah
Dengue. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi IV. Jilid III. Perhimpunan
Dokter Spesialis PenyakitDalam Indonesia. Jakarta: Pusat Penerbitan
Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia.

9. WHO. Dengue: Guidlines for Diagnosis, Treatment, Prevention and
Control. New Edition. Geneva: World Health Organization; 2009.
10. Supartha I, editor. Pengendalian Terpadu Vektor Virus Demam Berdarah
Dengue, Aedes aegypti (Linn.) dan Aedes albopictus (Skuse) (Diptera:
Culicidae). Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis 2008 Universitas
Udayana; 3-6 September 2008; Denpasar: Universitas Udayana Denpasar.
11. Knowlton K, Solomon G, Rotkin-Ellman M, Pitch F. Mosquito-Borne
Dengue Fever Threat Spreading in the Americas. New York: Natural
Resources Defense Council Issue Paper; 2009.
12. Weissenbock H, Hubalek Z, Bakonyi T, Noowotny K. Zoonotic Mosquito-
borne Flaviviruses: Worldwide Presence of Agent with Proven
Pathogenesis and Potential candidates of Future Emerging Diseases. Vet
Microbiol. 2010; Vol 140:271-80.
13. Malavinge G, Fernando S, Senevirante S. Dengue Viral Infection.
Postgraduate Medical Journal. 2004; Vol 80: p. 588-601.
14. Kusriastuti R. Kebijaksanaan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue
Di Indonesia. Jakarta: Depkes R.I; 2005.
15. Kusriastuti R. Data Kasus Demam Berdarah Dengue di Indonesia tahun
2009 dan Tahun 2008. Jakarta: Ditjen PP & PL Depkes RI; 2010.
16. Depkes RI. 2005. Pedoman Tatalaksana Klinis Infeksi Dengue di Sarana
Pelayanan Kesehatan. Departemen Kesehatan RI.
17. Dengue Haemorrhagic Fever: Diagnosis, Treatment, Prevention and
Control. Edition II. Geneva: World Health Organization. 1997. Available
from
htttp://www.who.int/csr/resources/publi-cations/dengue/Denguepublication
. Accessed September 2015
18. Tambyah PA, Koay ESC, Poon MLM, Lin RVTP, Ong BKC. Dengue
Hemorrhagic Fever Transmitted by Blood Transfusion. The England
Journal of Medicine. 2008; Vol. 359: p. 1526-7.

19. Gubler DJ. Epidemic Dengue Hemorrhagic Fever as a Public Health,
Sosial and Economic Problem in Tha 21st Century. Trends Microbiol.
2002; Vol. 10: p. 100-13.
20. Kristina, Ismaniah, Wulandari L. Kajian Masalah Kesehatan: Demam
Berdarah Dengue. In: Balitbangkes, editor.: Tri Djoko Wahono. 2004. p.
hal 1-9.
21. Lubis I. Peranan Nyamuk Aedes dan Babi Dalam Penyebaran DHF dan JE
di Indonesia. Cermin Dunia Kedokteran. 1990; Vol. 60.
22. Canyon D. Advances in Aedes aegypti Biodynamis and Vector Capacity:
Tropical Infectious and Parasitic Diseases Unit, School of Public Health
and Tropical Medicine, James Cook University; 2000.
23. Fatmah. Respons Imunitas Yang Rendah Pada Tubuh Manusia Usia
Lanjut. Makara Kesehatan. 2006 Juni 2006; Vol. 10 No. 1: hal. 47-53.
24. Harahap H. Masalah Gizi Mikro Utama dan Tumbuh Kembang Anak Di
Indonesia: Makalah Pribadi Falsafah Sains (PPS 702). Sekolah Pasca
Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor.; 2004.
25. Husaini MA, Siagian UL, Suharno J. Anemia Gizi: Suatu Kompilasi
Informasi dalam Menunjang Kebijaksanaan Nasional dan Pengembangan
Program. Direktorat Gizi dan Puslitbang Gizi, Depkes R.I; 2003.
26. WHO-NHD. Nutrition for Health and Development: A global agenda for
combating malnutrition. Geneva: World Health Organization; 2000.
27. Zerfas AJ, Jelliffe DB, Jelliffe PEF. Epidemiology and Nutrion in Human
Growth: A comprehensive Treatise Edisi 2, Methodology Ecological,
Genetics, and Nutritional Effects on Growth. New York.: Plenum Press. p.
475 1986.
28. Gibson RS. Anthropometric Assessment. Dalam: Principles of Nutritional.
New York: Oxford Univ.Press. Madison Av. p. 45-7; 1990.
29. Wirahjanto A, Soegijanto S. Epidemilogi Demam Berdarah Dengue, dalam
Demam Berdarah Dengue Edisi 2. Surabaya: Airlangga University Press.
Hal 1-10.; 2006.

30. Kasjono H, Kristiawan H. Intisari Epidemiologi. Jakarta: Mitra Cendikia
Press; 2008.
31. Sari CIN. Pengaruh Lingkungan Terhadap Perkembangan Penyakit
Malaria Dan Demam Berdarah Dengue. Bogor: IPB; 2005.
32. Koraka P, Suharti C, Setiati CE, Mairuhu AT, Van Gorp E, Hack CE, et al.
Kinetics of Dengue Virus-specific Immunoglobulin Classes and Subclasses
Correlate with Clinical Outcome of Infection. J Clin Microbio. 2001; Vol.
39 4332-8.
33. Darwis D. Kegawatan Demam Berdarah Dengue Pada Anak. Naskah
lengkap, pelatihan bagi dokter spesialis anak dan dokter spesialis penyakit
dalam pada tata laksana kasus DBD. Jakarta: Penerbit Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia; 1999.
34. Dewi BE, Takasaki T, Sudiro TM, Nelwan R, Kurane I. Elevated Levels of
Solube Tumour Necrosis Factor Receptor 1, Thrombomodulin and Solube
Endothelial Cell Adhesion Molecules in Patients with Dengue
Hemorrhagic Fever. Dengue Bulletin. 2007; Vol 31:103-10.
35. Gibson RV. Dengue Conundrums. International Journal of Antimicrobial
Agents. 2010; Vol 36(26-39).
36. Sowandoyo E, editor. Demam Berdarah Dengue pada Orang Dewasa,
Gejala Klinik dan Penatalaksanaannya. Seminar Demam Berdarah Dengue
di Indonesia 1998; RS Sumberwaras. Jakarta.
37. Wang S, Patarapotikul HR. Antibody Enhanced Binding of Dengue Virus
to Human Platelets. J Virology. 1995; Vol.213:1254-7.
38. Soegijanto S. Prospek Pemanfaatan Vaksin Dengue Untuk Menurunkan
Prevalensi di Masyarakat. Dipresentasikan di Peringatan 90 Tahun
Pendidikan Dokter di FK Unair; Surabaya; 2003.
39. Avirutnan P, Malasit P, Seliger B, Bhakti S, Husmann M. Dengue Virus
Infection of Human Endothelial Cells Leads to Chemokin Production,
Complement Activation, and Apoptosis. J Immunol. 1998; Vol 161:6338-
46.

40. Wilder-Smith A, Gubler D. Geographic Expansion of Dengue: the Impact
of International Travel. Med Clin NAm. 2008; Vol. 92: p. 1377-90.
41. U.S.D.T. International Travel and Transportation Trends. Washington D.
C.: Bureau of Transportation Statistics of U.S. Department of
Transportation; 2006.
42. Roose A. Hubungan Sosiodemografi dan Lingkungan dengan Kejadian
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbaru. Medan: Universitas Sumatera Utara; 2008.
43. Silva-Nunes MD, Souza V, Pannuti CS, Sperança MA, Terzian ACB,
Nogueira ML. Risk Factors for Dengue Virus Infection in Rural Amazonia:
Population-based Cross-sectional Surveys. Am J Trop Med Hyg. 2008; Vol
79 (4): p. 485–94.
44. Noor R. Nyamuk Aedes aegypti. 2009 [cited 24 Desember 2010];
Available from:
http://id.shvoong.com/medicineandhealth/epidemiologypublichealth/
2066459-nyamuk-aedes-aegypti.
45. WHO. Insect and Rodent Control Through Environmental Management.
Geneva: World Health Organization; 1992.
46. Depkes RI. Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah dengue di
Indonesia. Jakarta: Depkes RI; 2005
47. Gibbons RV, Vaughn DW. Dengue: an escalating problem. BMJ 2002;
324: 1563-6