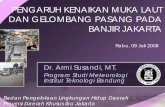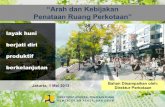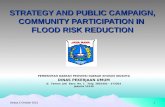Banjir Jakarta Dan Inefektifitas Tata Ruang Di Indonesia
-
Upload
larasati-eka-septari -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of Banjir Jakarta Dan Inefektifitas Tata Ruang Di Indonesia

Banjir Jakarta dan Inefektifitas Tata Ruang di IndonesiaBY JEHANSIREGAR ON FEBRUARY 3 , 2014
M. Jehansyah Siregar, Ph.D. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan (SAPPK) ITB. Email jehansiregar(at)yahoo.com.
Banjir yang setiap tahun terjadi di Jakarta salah satunya disebabkan perubahan
morfologi kota yang terakumulasi dalam kurun waktu yang lama sekali. Di banyak lokasi,
lahan-lahan basah berupa rawa, hutan bakau maupun persawahan, terutama di Jakarta
Barat dan Jakarta Utara, telah diurug dan dibangun permukiman, pabrik dan
pergudangan. Lahan-lahan basah di sepanjang bantaran sungai dan sekitar situ-situ
terus diduduki dan dibangun permukiman, baik secara formal maupun informal. Konversi
lahan basah menjadi lahan perkotaan dibiarkan terus terjadi. Selama berpuluh-puluh
tahun, lahan-lahan retensi air ketika hujan lebat ini telah banyak berkurang dan
mengakibatkan luapan air yang semakin meningkat setiap musim hujan tiba. Sudah
jelas, hal ini terjadi akibat tidak adanya pengendalian pemanfaatan ruang Jakarta.
Tata Ruang Jakarta Penuh Masalah
Dari sisi penataan ruang, kita bisa melihat bahwa semua produk rencana tata ruang di
Jakarta, mulai Rencana Induk 1965-1985 hingga RTRW 2030, adalah produk-
produk yang sangat lemah. Di dalam prakteknya, rencana-rencana tersebut selalu
”masuk angin”, baik sebelum maupun setelah ditetapkan. Hal ini dikarenakan rencana
tersebut telah dipenuhi dengan kepentingan bisnis properti dan tidak disusun
berlandaskan pada akar permasalahan dan tujuan pembangunan Jakarta secara objektif
untuk kepentingan publik.
Jakarta juga telah kehilangan keterpaduan perencanaan dengan wilayah sekitarnya
(Jabodetabek). Ketika Kota Jakarta ditingkatkan statusnya menjadi Propinsi Daerah
Khusus Ibukota, hilanglah sudah perhatian pada keterpaduan Jabodetabek.
Menghadapi masalah kebutuhan lahan yang meningkat, maka di dalam RTRW 2030
diusulkan untuk dilakukan reklamasi di perairan utara Jakarta. Karena biayanya yang
”dipandang mahal”, reklamasi akhirnya dijadikan justifikasi untuk melibatkan para
pengembang besar secara langsung. Namun dari berbagai kajian lingkungan, reklamasi
bukannya menyelesaikan masalah, justru sebaliknya berpotensi menimbulkan masalah
terganggunya keseimbangan ekosistem pantai utara Jakarta.

Selain itu, wilayah Selat Sunda hingga Laut Jawa termasuk daerah yang memiliki
sumber-sumber gempa besar sehingga lahan-lahan hasil reklamasi juga berpotensi
terancam gempa besar dan amblas seperti yang terjadi di Kobe, Jepang. Setelah
rencana Greater Jakarta tidak kunjung bisa diwujudkan, perencanaan dan manajemen
pembangunan Jakarta jadi semakin tidak berarah. Hampir semua peraturan di Jakarta
bersifat tambal sulam karena hanya diatur berdasarkan SK Gubernur semata (bukan
Perda), dengan maksud hanya menguntungkan para pengembang besar saja.
Masalah Nasional
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang di Jakarta tidaklah efektif dan
justru menjadi ajang pertarungan kepentingan dan pembenaran arah pembangunan
yang menyimpang. Mengingat penataan ruang di Jakarta adalah penataan ruang
yang tertua di tanah air, maka sudah sepantasnya dijadikan model penataan ruang bagi
kota-kota dan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka
permasalahan inefektifitas tata ruang ini adalah masalah nasional yang menjadi
tanggung-jawab pemerintah pusat.
Tata Ruang Jakarta yang tidak efektif adalah puncak gunung es dari tidak efektifnya
penataan ruang di berbagai kota-kota besar, kota-kota sedang dan wilayah Indonesia
lainnya. Oleh karena itu, inefektifitas penataan ruang ini tidak bisa tidak harus dikaji di
tataran pilihan-pilihan kebijakan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia.
Isu inefektifitas tersebut harus menjadi isu sentral di dalam praktek pembangunan
(pemanfaatan ruang) dan di dalam penyelenggaan penataan ruang itu sendiri.
Seringkali isu-isu penataan ruang yang dipandang strategis adalah soal alih fungsi
lahan, ketimpangan antar wilayah dan urbanisasi yang tinggi. Apakah benar isu-isu
tersebut yang menjadi isu strategis penataan ruang? Jawabannya, ada permasalahan
yang lebih mendasar lagi, karena alih fungsi lahan dan ketimpangan antar wilayah pada
dasarnya menyangkut penataan ruang yang tidak efektif. Inilah tanggung-jawab
pemerintah pusat yang hingga kini belum mampu diselesaikan, yaitu mewujudkan
efektifitas penataan ruang di berbagai kota-kota besar, kota-kota sedang dan wilayah
Indonesia lainnya.
Kaji Ulang Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang di Indonesia
Di dalam proses merumuskan sebuah kebijakan, pengenalan isu dan masalah yang
tepat adalah awal dari pembuatan kebijakan yang berkualitas. Ada adagium yang sudah
dikenal luas di dalam studi kebijakan publik, yaitu kebijakan yang belum terlalu tepat

namun telah disusun di atas pengenalan isu dan permasalahan yang tepat adalah jauh
lebih baik dibanding kebijakan yang tampaknya sempurna namun ternyata disusun di
atas pengenalan masalah yang kurang tepat. Oleh karena itu, penulis lebih memilih
dengan memulainya dari identifikasi akar permasalahan yang benar-benar mendasar
dalam praktek penataan ruang di tanah air.
Dari pengamatan penulis, beragam isu dan permasalahan yang paling mendasar dalam
praktek penataan ruang dapat digolongkan ke dalam permasalahan internal dan
permasalahan eksternal penataan ruang. Permasalahan internal penataan ruang yang
paling nyata adalah belum dapat diterapkannya produk-produk perencanaan ruang
secara efektif di dalam praktek pembangunan, terutama yang berkaitan dengan dimensi
fisik spasial lingkungan binaan. Permasalahan ini disebut juga dengan istilah “adanya
gap” antara rencana dan praktek pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang. Sedangkan permasalahan eksternal penataan ruang muncul dari praktek-praktek
pembangunan pada aspek-aspek lainnya yang secara langsung atau tidak langsung
semakin menjauhkan kesenjangan rencana dan implementasi, seperti isu pertanahan,
keterpaduan infrastruktur, dan sebagainya.
Penataan Ruang yang Tidak Efektif
Produk-produk rencana tata ruang wilayah (RTRW nasional, provinsi, kabupaten, kota,
dan produk rencana lainnya) yang tidak diikuti atau mengalami perubahan pada praktek
pemanfaatan ruang (baca: pembangunan), sudah menjadi isu yang dikenal luas. Di
tingkat perkotaan misalnya, wujud pembangunan kota-kota secara kumulatif dalam
kurun puluhan tahun umumnya menyimpang dari RTRW yang telah ditetapkan
sebelumnya. Bahkan secara pesimis seringkali muncul ungkapan bahwa RTRW justru
telah berubah perannya sebagai dokumen untuk memutihkan penyimpangan rencana
tata ruang pada periode sebelumnya dan sekaligus sebagai dokumen justifikasi untuk
menjalankan praktek pembangunan dari berbagai kelompok kepentingan. Rencana tata
ruang akhirnya berubah menjadi ajang pertarungan kepentingan seperti terjadi di DKI
Jakarta. Baik secara tersamar-samar maupun yang tampak nyata secara kasat mata.
Hasilnya, kepentingan publik selalu menjadi pihak yang kalah, karena hampir tidak ada
yang benar-benar memperjuangkannya.
Kegagalan mewujudkan rencana tata ruang dalam praktek pemanfaatan dan
pengendalian ruang inilah yang dimaksud sebagai penataan ruang yang tidak efektif.
Secara garis besar, ada beberapa permasalahan yang melatar-belakangi hal ini, di
antaranya:

1. Kegagalan memahami konteks pembangunan di sektor publik. Kegagalan
perencanaan ruang akan terjadi ketika proses perencanaan spasial terlepas dari
konteks pembangunan yang berada di domain publik. Pelaku-pelaku pembangunan
di sektor publik meliputi institusi pemerintah, baik pemerintah nasional maupun
pemerintah daerah, investor swasta dan individu masyarakat yang berurusan
dengan kepentingan publik, adalah pihak-pihak yang memberi pengaruh dalam
pemanfaatan ruang. Pada kenyataannya, konstelasi para pelaku ini mendudukkan
istilah “sesuai rencana” atau “tidak sesuai rencana” sebagai permasalahan yang
tidak sederhana. Di dalam konteks pembangunan di sektor publik, banyak sekali
kepentingan, penguasaan sumberdaya, dan hubungan kekuasaan yang saling
mempengaruhi satu sama lain.
2. Kegagalan membangun komunikasi dengan para pelaku pembangunan. Gagal
paham atas pembangunan yang berada di domain publik pada gilirannya menutup
upaya-upaya untuk membangun komunikasi manajemen pembangunan yang efektif
dengan para pelaku pembangunan. Permasalahan inilah yang melatar-belakangi
munculnya pihak-pihak yang ingin lebih memajukan proses perencanaan tata ruang
secara partisipatif, atau dikenal sebagai participatory planning.
3. Orientasi berlebihan pada sistem rencana tata ruang. Ini adalah cara pandang
yang beranggapan bahwa suatu rencana ruang secara otomatis diterapkan dalam
praktek pembangunan. Perspektif ini adalah buah dari kegagalan memahami
konstelasi pelaku dan kegagalan membangun komunikasi dengan berbagai aktor
pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahkan cara pandang ini
semakin menjadi-jadi dengan anggapan bahwa untuk menerapkan suatu rencana
tata ruang harus dibuat rencana tata ruang yang lebih rinci lagi. Sebagai contoh,
pelaksanaan RTRW Nasional adalah penerapannya dalam bentuk RTRW Provinsi,
RTRW Kabupaten dapat dioperasionalkan melalui RDTR, dan seterusnya.
Pandangan ini biasanya menargetkan dicantumkannya kalimat “mengacu pada
Rencana Tata Ruang yang berlaku” ataupun “pengenaan sanksi bagi yang
melanggar rencana tata ruang” di dalam pasal-pasal peraturan tertentu. Padahal
pada prakteknya, masih banyak “lubang-lubang yang menganga” dalam bentuk
istilah penyesuaian rencana, revisi rencana, dan berbagai bentuk negosiasi di antara
para pelaku yang luput dari perhatian. Semua proses inilah yang dipakai para pelaku
pembangunan sehingga tanpa disadari akhirnya menyimpangkan ketentuan
rencana, baik mereka dari pihak pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat
luas.

4. Kegagalan mengelola pembangunan berbasis prakarsa publik. Kelemahan
dalam mengenali berbagai kelompok kepentingan di dalam pembangunan sektor
publik, ditambah kelemahan membangun komunikasi yang efektif, serta diperkuat
dengan orientasi yang berlebihan pada produk-produk rencana tata ruang
sebagaimana diuraikan di atas, akhirnya bermuara pada kegagalan mengelola suatu
prakarsa pembangunan sebagai sebuah prakarsa publik. Pada dasarnya,
pembangunan memang harus menempatkan lembaga publik sebagai lokomotif
pembangunan untuk membawa prakarsa publik, karena ada begitu banyak
kepentingan publik yang dipertaruhkan di dalamnya. Kegagalan memajukan
prakarsa publik akhirnya bermuara pada bentuk-bentuk pasif dan pembiaran praktek
pembangunan oleh berbagai kelompok kepentingan. Tidak dapat dielakkan,
terciptalah iklim pembiaran yang spekulatif dan mengarah pada fragmentasi
pembangunan yang semakin parah. Sebagai contoh, di dalam perencanaan suatu
kawasan bisnis di Jakarta yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan komersial
pusat kota dengan intensitas tinggi, ternyata tanah di kawasan tersebut telah
dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu atau sudah ada konsesi tertentu yang
disepakati di balik layar. Produk rencana ruang yang seolah-olah membawa
kepentingan publik ternyata telah disusupi kepentingan golongan tertentu. Istilahnya
sekarang, “rencana yang sudah masuk angin”. Bisa diduga pula, iklim pembiaran
yang spekulatif seperti itu memang secara sengaja diciptakan oleh birokrasi yang
korup, sehingga muncul istilah di lapangan yaitu “tata ruang” berubah menjadi “tatar
uang”.
Prinsip-prinsip dasar Strategi Penataan Ruang
Dengan memahami isu-isu dan permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan
penataan ruang sebagaimana diuraikan di atas, maka strategi penataan ruang harus
bisa menjamin adanya perubahan-perubahan yang progresif dan signifikan dalam
proses penataan ruang sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Dengan kata
lain, proses penataan ruang harus memiliki landasan yang kokoh, berupa
dirumuskannya strategi-strategi penataan ruang, seperti:
1. Meningkatkan pemahaman akan karakter dan peran sektor publik di dalam
proses pembangunan yang multi dimensional,
2. Membuka eksklusifisme penataan ruang yang terlalu berorientasi pada sistem
rencana tata ruang dan mendorong inklusifisme penataan ruang sebagai bagian
pembangunan yang lebih utuh.

3. Mendorong peran pemerintah pusat untuk mengembangkan sistem dan model
pembangunan yang utuh dalam rangka memperkuat kapasitas pemerintah daerah.
Banyak sekali penyimpangan tata ruang terjadi di tingkat daerah karena lemahnya
kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola aktor-aktor pembangunan secara
terpadu. Sedangkan pemerintah pusat hadir di daerah sebatas dalam aksi sektor-
sektor yang jauh dari utuh dan terpadu. Sebagai contoh, pembangunan menara-
menara rumah susun untuk masyarakat berpendapatan rendah di perkotaan,
program pengembangan kawasan, prasarana permukiman, fasos dan fasum serta
prasarana transportasi, semuanya diprogramkan masing-masing di lokasi sasaran
yang berbeda-beda pula. Demikian pula dengan produk RTRW nya, jauh lebih tidak
terpadu lagi. Padahal semua program pembangunan fisik ini, demi mencapai tujuan
pelayanan masyarakat dan tujuan efisiensi fiskal, harus dijalankan secara terpadu,
semisal melalui penataan permukiman komprehensif dan pembangunan kota-kota
baru.
4. Membangun pemahaman yang lebih utuh akan tujuan-tujuan sebenarnya (tujuan-
tujuan publik), fungsi dan peran dari penataan ruang sebagai bagian dari
pembangunan. Pemahaman terhadap tata ruang sebagai adanya larangan
membangun ini dan itu atau larangan di sini dan di situ, tentunya bukanlah
pemahaman yang dangkal. Pemahaman atas tata ruang yang dangkal seperti ini
justru akhirnya hanya membuka ruang negosiasi untuk membuat berbagai bentuk
“penyesuaian”. Untuk itu pemerintah pusat harus terus menerus menjelaskan tujuan-
tujuan, fungsi dan peran dari penataan ruang serta pentingnya penataan ruang dari
sisi kepentingan semua sektor publik dalam praktek pembangunan di daerah.
Termasuk di dalamnya, bagaimana posisi rencana tata ruang terhadap rencana
pembangunan lainnya seperti RPJMD, RP3KP, RPIJM, KLHS, dan sebagainya,
5. Mempraktekkan pendekatan pembangunan terpadu. Peran pemerintah pusat
tidak berhenti sampai penyebarkan pemahaman yang utuh saja, namun hingga
menunjukkan model pembangunan dalam prakteknya melalui pendekatan
pembangunan yang terpadu.
Sebagai contoh, peran pemerintah pusat di bidang penataan ruang tidak cukup sampai
selesainya produk RTRW di daerah, baik provinsi, kota maupun kabupaten. Namun
pemerintah pusat harus menunjukkan bagaimana penerapan RTRW tersebut di dalam
praktek pembangunan kota, yaitu bagaimana perencanaan ruang dioperasionalkan
dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Dengan demikian, pemerintah
daerah yang kapasitasnya dinilai masih kurang memadai, dapat mecontoh bagaimana
suatu peraturan zonasi disusun dan diterapkan sesuai rencana ruang.

Target pemahaman dan praktek yang melembaga di dalam penggunaan rencana ruang
dalam pembangunan, jauh lebih penting dibanding target formal selesainya naskah
RTRW daerah tanpa diiringi kapasitas yang memadai. Ruh penataan ruang itu berada
pada praktek yang melembaga, bukan pada formalisasi dan legalisasi dokumen-
dokumen produk rencana ruang (RTRW).
Inilah strategi yang diperlukan untuk menjawab masalah inefektifitas penataan ruang
sekaligus masalah fragmentasi pembangunan, yang sepertinya tidak tampak namun
faktanya terjadi di hampir semua sektor pembangunan. Instansi penataan ruang dari
pemerintah pusat harus mampu menjelaskan pentingnya penataan ruang dari semua
sisi kepentingan sektor publik. Tujuannya tidak lain adalah efektifnya perencanaan
pembangunan di semua sektor, melalui keterpaduan pembangunan di daerah-daerah
dan di tingkat nasional.
Langkah ke Depan
Dari pemaparan sebelumnya telah dipahami bagaimana posisi penataan ruang di dalam
konteks pembangunan di sektor publik, yaitu bahwa penataan ruang adalah bagian
dalam keseluruhan pembangunan di sektor publik. Di tataran pembangunan, efektifitas
penataan ruang terwujud hanya melalui pendekatan public sector driven di dalam
praktek pembangunan. Dengan kenyataan lemahnya pembangunan di sektor publik,
maka pemerintah nasional perlu segera menyusun langkah-langkah aksi untuk
mengembangkan model pembangunan yang mendorong peran sektor publik sebagai
pemimpin pembangunan dan pemanfaatan ruang. Di tataran penataan ruang,
pemerintah nasional sudah saatnya meninggalkan pendekatan comprehensive planning
dan secara proaktif mengembangkan modelDynamic Planning dan Participatory
Planning yang lebih komunikatif dan efektif.
Semoga musibah banjir yang menimpa Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia
menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah pusat untuk segera
melakukan reformasi penataan ruang di negeri tercinta ini.