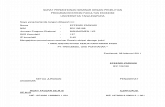bab31
-
Upload
dilla-angraina -
Category
Documents
-
view
221 -
download
2
description
Transcript of bab31
-
25Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sumatera Barat
Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang
Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi
BAB 3
-
27Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sumatera Barat
3.1 Strategi Kebijakan Provinsi Sumatera Barat untuk Mencapai Target Penurunan EmisiOleh: Dr. Ir. Ribaldi, MS
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 kota. Kondisi terakhir menunjukkan bahwa 60% wilayah Sumatera Barat merupakan kawasan hutan. Kondisi topogra sangat bervariasi, kawsan hutan bertopogra berbukit-bukit.
Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan akan bencana alam. Bencana alam yang rawan terjadi yaitu bencana longsor, gunung api, banjir dan tsunami.
Provinsi Sumatera Barat masih memerlukan kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi seperti pengembangan wilayah untuk pusat-pusat pertumbuhan (untuk jalan tol memerlukan ijin Kementerian Kehutanan). Pusat kegiatan strategis akan sangat berpengaruh di Sumatera Barat untuk mendukung pengembangan wilayah. Beberapa wilayah seperti Pasaman Barat dan Pesisir Selatan saat ini sudah ditanami sawit.
RAD GRK Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada Perpres 61 thn 2011. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RAD GRK, yaitu:1. Bagian dari strategi kebijakan daerah.2. Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.3. Terintergasi antar bidang sehingga tercipta pembangunan berkelanjutan.4. Kontribusi daerah terhadap RAN GRK.5. Melibatkan seluruh stakeholders.
Sumatera Barat pada awalnya tidak menduga saat ditugaskan untuk membuat RAD GRK, karena sosialisasinya dilaksanakan pada bulan Januari pada saat anggaran sudah teralokasikan. Hal ini mengakibatkan penyusunan RAD dilakukan tanpa ada pendanaan khusus. Baru pada bulan Agustus 2012 turun dana DAK dari Bappenas.
Di dalam penyusunan RAD GRK Sumatera Barat diidentikasi 3 (tiga) sektor penghasil emisi GRK yaitu sektor lahan dan gambut, energi dan trasnporasi, pengelolaan limbah. Emisi Sumatera Barat hasil perhitungan tim RAD GRK menunjukkan lahan dan gambut (86,08%), energi dan transportasi (12,54%) dan pengelolaan limbah (1,38%).
Bidang berbasis lahan yaitu sub sektor pertanian, sub sektor kehutanan dan alih guna lahan, dan sub sektor lahan gambut. Dengan mengunakan alat bantu perhitungan Abacus SP diperoleh nilai emisi historis 4,25 tCO2-eq/(ha/tahun), 18.019.442,96 tCO2-eq (ha/tahun).
-
28 Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi
Sumber emisi adalah adanya alih guna lahan, hutan sekunder menjadi semak belukar, hutan rawa sekunder menjadi belukar rawa, hutan sekunder menjadi perkebunan dan hutan primer menjadi semak belukar.
Nilai emisi BAU pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 229.425.945,96 tCO2-eq/tahun. Rencana aksi mitigasi atas emisi tersebut diperkirakan sebesar 168.953.423,96 tCO2-eq/tahun. Dari nilai emisi BAU dan rencana aksi mitigasi tersebut dapat diketahui besaran penurunan emisi per tahun yang dapat dihasilkan sebesar 60.472.522,00 tCO2-eq/tahun.
Strategi provinsi Sumatera Barat dalam mencapai target penurunan emisi, diantaranya:1. Mengubah semak belukar pada kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan
Tanaman (HT) dan hutan sekunder melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Hutan Nagari (Hutan Desa).
2. Mengubah tanah terbuka dan semak belukar pada zona APL melalui kegiatan KMDN dan penghijauan.
3. Pengendalian kebakaran hutan pada kawasan Hutan Sekunder dan semak belukar pada zona HP, HL dan HPT .
Permasalahan umum dalam bidang kehutanan dan lahan yaitu kerusakan hutan yang menyebabkan kemampuan daya absorbsi hutan terhadap GRK berkurang.
Sedangkan permasalahan khususnya adalah 1) adanya alih fungsi lahan/pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan, 2) luas lahan kritis yang cukup luas (50.000 Ha, pada Kabupaten Solok Selatan, Pasaman, Lima Puluh Kota dan Kep.mentawai, dan 3) kerusakan hutan dan alih fungsi kawasan hutan
Kebijakan dalam mencapai target penurunan emisi tersebut adalah melalui:1. Pemberantasan illegal logging.2. Penanggulangan kebakaran dan perambahan hutan.3. Pengaturan jatah tebang.4. Pencegahan emisi di kawasan HK, HL, HP, dan non hutan.5. Penambahan luas HKm.6. Penambahan luas hutan desa.7. Penambahan luas rehabilitasi lahan/hutan DAS.8. Penambahan luas HTI, HTR, HR dan HR Kemitraan.9. Pengelolaan Hutan Lestari melalui Teknik Silvikultur Intensif.10. Pengelolaan Hutan Lestari dengan penerapan TPTI dan RIL.
-
29Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sumatera Barat
3.2 Potensi Aplikasi INCAS Sebagai Sistim Monitoring Karbon HutanOleh: Dr. Haruni Krisnawati
INCAS (Indonesia Carbon Accounting System) adalah sebuah sistem perhitungan karbon yang disusun oleh Kementerian Kehutanan atas inisiasi dari pemerintah Australia, dimulai sejak tahun 2009. INCAS mengadopsi sistem perhitungan karbon Australia NCAS (full carbon accounting model yang dikembangkan di Australia dan sudah mendapat pengakuan internasional). Saat ini metode tersebut dikalibrasi, disesuaikan dengan kondisi hutan di Indonesia.
Untuk skala nasional yang dihasilkan dari INCAS dapat menjadi input bagi pelaporan dalam usaha pengurangan emisi dan juga dasar bagi kebijakan. Untuk skala internasional hasil dari INCAS ini dapat menjadi bahan pelaporan kepada UNFCCC.
Karakteristik INCAS yaitu: 1) desain untuk skala nasional, 2) mampu mengukur/menghitung emisi setiap tahun, 3) mencakup 5 karbon pools, 4) menghasilkan pengukuran untuk semua green house gasses (ke depan), 5) informasi bisa digunakan untuk skala internasional, nasional, sub nasional, distrik, site, dan 6) berusaha konsisten secara spasial dan temporal.
Modul INCAS terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut:1. Klasikasi biomasa, INCAS didesain untuk memonitor emisi melalui perubahan
tutupan lahan dan stok karbon. Terdapat 23 klasikasi lahan berdasarkan Kementerian Kehutanan, inilah yang diadopsi di INCAS.
2. Analisis perubahan lahan, untuk melihat perubahan tutupan lahan tahunan, dimulai tahun 2000 mencakup seluruh wilayah Indonesia.
3. Pemetaan kelas gangguan hutan, untuk melihat bagaimana hutan itu mengalami gangguan.
4. Pendugaan stok karbon, pada 5 pool karbon.
Data yang dibutuhkan dalam mendukung INCAS, yaitu:1. Data remote sensing untuk analisis perubahan lahan secara tahunan2. Ground data/data lapangan/data pengukuran berupa:
a. Data inventarisasi, yang bisa diperoleh dari Badan Planologi dan Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK)
b. Tanah/Peat, yang bisa diperoleh dari Kementerian Pertanian dan Wetlandc. Iklim, yang bisa diperoleh dari BMKG
-
30 Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi
d. Landuse and management dapat dilihat dari data pemanenan dan kejadian kebakaran
e. Data dari PSP dibutuhkan dalam kelompok data biomass and growth, sedapat mungkin data dari lapangan tetap digunakan karena lebih akurat dibandingkan data dari sumber sekunder atau dari peneliti lain.
INCAS berusaha membangun sistem dengan mengintegrasikan sistem yang sudah ada. Saat ini progress kegiatan yang telah dikerjakan oleh INCAS, diantaranya:1. Sudah diselesaikan analisis perubahan tutupan lahan di Kalimantan, Sumatera,
Sulawesi dan Papua (2000-2009).2. Ke depan akan dikerjakan analisis tutupan lahan untuk Maluku dan Jawa.3. Pilot system peta dan klasikasi biomassa di Kalimantan.4. Membangun kelas biomassa dan peta biomassa untuk Kalimantan.5. Mengintegrasikan analisis tutupan lahan tahunan dan klasikasi biomasa untuk
Kalimantan.6. Menduga gain and loss kelas biomassa tahunan di Kalimantan.7. Menduga emisi dan removal tahunan melalui kelas biomassa tahunan di
Kalimantan.8. Beberapa kali menyelenggarakan workshop mengenai penggunaan model-
model karbon dengan mengintegrasikan pengelolaan skenario untuk/dalam membangun full carbon accounting untuk perhitungan emisi.
Perhitungan karbon dan model pelaporan INCAS yaitu dengan mengintegrasikan perubahan tutupan lahan dan data perubahan stok karbon dengan menggunakan perangkat pendugaan yang eksibel. Dalam melakukan penghitungan total emisi GRK tahunan digunakan skenario-skenario tertentu. Output yang dihasilkan INCAS adalah Inventarisasi GRK nasional untuk sektor lahan.
Hasil INCAS dapat digunakan untuk:1. Komponen utama kerangka MRV untuk REDD+ yang merupakan dasar untuk
perdagangan karbon;2. Dapat mendukung pemantauan hutan nasional dengan memberikan pengambil
keputusan bagaimana mengelola emisi GRK dan mengelola lahan/hutan;3. Mengkuantikasi dampak kebijakan pengelolaan lahan pada masa lampau,
sekaranag, dan masa yang akan datang;4. Memberikan dasar scientic dan teknik bahwa Indonesia mampu menghasilkan
dasar perhitungan dengan data dan kemampuan sendiri di forum internasional;5. Dapat diangkat sebagai sistem monitoring karbon hutan nasional;
-
31Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sumatera Barat
6. Menghasilkan output yang diperlukan untuk pelaporan internasional UNFCCC, REDD+, inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional);
7. Memberikan input yang diperlukan untuk membangun skenario REL;8. Memonitor perubahan tahunan emisi dan penyerapan sektor lahan.
3.3 Peran dan Tanggung Jawab para Pihak dalam Pelaksanaan Sistem Monitoring Karbon Hutan di Sumatera BaratOleh: Ir. Rahmat Hidayat
Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) adalah semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan REDD+ adalah untuk menekan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan. Praktek-praktek pengelolaan hutan oleh masyarakat merupakan potensi yang patut dipertimbangkan dalam upaya penurunan emisi karbon dalam skema REDD+. Pola-pola pengelolaan hutan yang telah dilakukan masyarakat yang sudah berkembang di Sumatera Barat seperti Hutan Adat, Parak, Rimbo Larangan, Hutan Nagari, HKm dan bentuk lainnya dalam konteks reforestasi, rehabilitasi dan pemanfaatan berkelanjutan dapat berperan sebagai sink (penyerap/penyimpan karbon) yang dapat berkontribusi pada proses mitigasi.
Komitmen penurunan emisi nasional yang disampaikan oleh Presiden RI sebesar 26%-41% sesuai untuk diterapkan di Sumatera Barat melalui program hutan kemasyarakatan. Peluang penurunan emisi dapat diraih dengan pendekatan tradisional yang menempatkan partisipasi masyarakat.
Dalam kerangka REDD, Sumatera Barat adalah pemain baru namun mampu menyalip para pemain lama. Diawali dengan Surat usulan Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Satgas REDD+ tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat 185/III/BW-LH/Bappeda 2012 tentang Permintaan Fasilitasi REDD+, yang kemudian ditindaklanjuti dengan balasan dari Ketua Satgas REDD+ (Nomor B-135/REDDII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012) dengan memfasilitasi Sumatera Barat sebagai mitra Satgas REDD dalam penyusunan SRAP dan inisiatif strategis REDD+ untuk segera diimplementasikan di lapangan. Provinsi Sumatera Barat juga memperoleh dukungan dari Kementerian Kehutanan melalui upaya perluasan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan.
-
32 Pengembangan Sistem Monitoring PSP yang Terintegrasi dan Partisipatif di Provinsi
Pembangunan PSP menjadi hal penting karena dibutuhkan untuk sistem monitoring karbon hutan. Selain itu, PSP juga dapat dipergunakan untuk mengukur, melaporkan dan memverikasi pencapaian penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ secara berkala, sahih, akurat, menyeluruh, konsisten, transparan serta untuk mengetahui pencapaian kinerja (performance) pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK melalui REDD+. Bagian penting lainnya dari PSP ini adalah untuk pemberian insentif atas usaha pengurangan emisi.
RAD dan SRAD Sumatera Barat menempatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, sehingga RAD dan SRAD berbeda dengan 10 provinsi lainnya. Diperlukan konsultasi awal dengan masyarakat, hal ini penting untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Setelah terbangunnya kepercayaan masyarakat dilanjutkan dengan membangun kesepakatan untuk berbagi tanggungjawab.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan PSP adalah dengan melakukan pertemuan dengan komunitas disekitar hutan. Dalam pertemuan tersebut, perlu disampaikan informasi mengenai PSP secara detail. Setelah terbentuk kesamaan pemahaman terkait PUP, proses selanjutnya adalah membuat kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan PSP di wilayah Hutan Nagari dan lahan masyarakat.
Dalam mekanisme internal pelaksanaan PSP di Sumatera Barat dibuat kerjasama dengan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN).
Tugas dari LPHN adalah menentukan penanggung jawab pelaksanaan PUP di bawah koordinasi seksi jasa Lingkungan, Seksi jasa lingkungan membentuk tim untuk membantu pelaksaan PSP. Tim LPHN bersama Tim PSP Kementerian mengidentifikasi lahan untuk Plot sesuai dengan kebutuhan tipe lahan. Tim LPHN mendiskusikan hasil identikasi bersama pemilik lahan termasuk semua konsekuensinya seperti adanya kebutuhan untuk perlakuan khusus terhadap lahan dalam ukuran tertentu. Setelah ada kesepakatan dengan pemilik lahan maka lokasi tersebut ditetapkan menjadi bagian Petak Ukur Permanen (PUP/PSP).
Dalam melaksanakan monitoring PSP, diperlukan peran dan tanggungjawab berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu penurunan emisi.
Peran dan tanggungjawab pemerintah, diantaranya:1. Menyusun dokumen RAN, RAD sebagai dasar untuk implementasi penurunan
emisi GRK,2. Menyiapkan anggaran untuk penguatan kapasitas, kajian dan review,
kelembagaan, insentif,3. Menyiapkan mekanisme penghargaan dan hukuman,4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi,
-
33Prosiding Workshop Strategi Monitoring dan Pelaporan Plot Sampel Permanen
di Provinsi Sumatera Barat
5. Sinkronisasi tata ruang provinsi/kabupaten/kota dan nagari,6. Membangun sistem monitoring karbon hutan yang partisipatif, sederhana,
mudah diaplikasikan dan dimonev,7. Membangun bank data yg mudah diakses oleh public,8. Pengembangan skema-skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM),9. Penguatan instrumen kebijakan terkait monitoring karbon hutan dengan
membuat pedoman pemantauan, mekanisme complain dan keterbukaan informasi publik,
10. Penguatan/peningkatan kapasitas (dan kompetensi) dalam monitoring karbon hutan dengan menyusun kurikulum pelatihan, ToT, dan pelatihan,
11. Penguatan kelembagaan monitoring karbon hutan dengan meningkatkan jejaring kerja, etika kerja, dan panduan/standar kerja pemantauan,
12. Fasilitasi aktivitas monitoring dan penyampaian hasil pemantauan,13. Memastikan agar pelaksanaan FPIC dilakukan sebelum kegiatan dimulai,
Peran dan tanggungjawab Perguruan Tinggi, diantaranya:1. Membangun metodologi monitoring yang sederhana dengan mengakomodasi
pengetahuan lokal,2. Meningkatkan kapasitas masyarakat adat/lokal untuk dapat melakukan
pemantauan dan pelaporan secara sederhana,3. Melakukan review terhadap metodologi monitoring yang ada,4. Membantu para pihak dilevel provinsi, kabupaten dan tapak untuk memahami
metodologi monitoring karbon hutan,5. Mendesain model pelaporan.
Peran dan tanggung jawab masyarakat sipil, diantaranya:1. Mendorong penerapan FPIC,2. Membangun model-model Hutan Nagari,HKm, Hutan Adat, Parak sebagai
wilayah implementasi PSP,3. Mendorong tata ruang Mikro Desa/Nagari masuk ke dalam RTRW Kabupaten
untuk melindungi areal PSP,4. Membangun peningkatan kapasitas lembaga perwalian lokal sebagai lembaga
yang akan melakukan monitoring,5. Melakukan advokasi dan memantau pelaksanaan monitoring karbon hutan
(akses informasi, tindak lanjut hasil monitoring, mencari dukungan sumberdaya alternatif),
-
34 Kesimpulan dan Rekomendasi
6. Membangun mekanisme share learning dengan melibatkan berbagai pihak diberbagai level atas proses PSP berbasis masyarakat,
7. Mendorong pembangunan PSP baru pada kawasan PHBM diberbagai tipe ekosistem,
8. Menyiapkan skema insentif.
Peran dan tanggungjawab masyarakat di tingkat tapak:1. Melakukan pemantauan dan pelaporan secara sederhana bersama dengan para
pendukung (Pemerintah, Peguruan Tinggi dan LSM),2. Monitoring Plot terhubung langsung dengan kelembagaan hutan nagari,
khususnya untuk pengamanan,3. Mengimplementasikan tataruang mikro, RKHN dan aturan lokal.