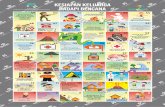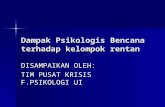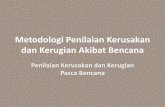BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana ...
86
28 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana Alam Terhadap Kelompok Fungsional Dampak bencana alam terhadap kelompok fungsional sanitasi memiliki beberapa perbedaan berdasarkan jenis bencananya, namun dalam hal ini akan dipaparkan beberapa dampak dari bencana alam yang terjadi terhadap kelompok fungsional sanitasi berdasarkan jenis kelompoknya: 4.1.1 Kelompok Penghubung Pengguna (User Interface) Kelompok user interface merupakan kelompok yang memiliki fungsi sebagai alat atau sarana sanitasi yang menghubungkan penguna dengan sarana sanitasi. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok user interface adalah sebagai berikut: a. WC jongkok b. WC duduk c. Wastafel Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam relatif berbeda-beda bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok user interface secara umum, yakni: a. Kerusakan Fasilitas b. Terendam genangan air c. Tertimbun reruntuhan d. Sulit diakses Rencana tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan yakni membersihkan fasilitas layanan atau sarana sanitasi jika memungkinkan untuk digunakan kembali. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan kembali maka dibuatkan layanan sanitasi darurat atau semantara untuk memenuhi kebutuhan
Transcript of BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 4.1 Dampak Bencana ...
Dampak bencana alam terhadap kelompok fungsional sanitasi
memiliki
beberapa perbedaan berdasarkan jenis bencananya, namun dalam hal ini akan
dipaparkan beberapa dampak dari bencana alam yang terjadi terhadap kelompok
fungsional sanitasi berdasarkan jenis kelompoknya:
4.1.1 Kelompok Penghubung Pengguna (User Interface)
Kelompok user interface merupakan kelompok yang memiliki fungsi
sebagai alat atau sarana sanitasi yang menghubungkan penguna dengan sarana
sanitasi. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok user interface
adalah sebagai berikut:
a. WC jongkok
b. WC duduk
bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak yang
ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok user interface
secara umum, yakni:
a. Kerusakan Fasilitas
membersihkan fasilitas layanan atau sarana sanitasi jika memungkinkan untuk
digunakan kembali. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan kembali maka
dibuatkan layanan sanitasi darurat atau semantara untuk memenuhi kebutuhan
29
Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi.
4.1.2 Pengumpulan & Penampungan dan/atau Pengolahan Awal
Pengumpulan dan penampungan merupakan tempat dimana limbah yang
dihasilkan oleh sarana sanitasi dikumpulkan atau disatukan kedalam suatu tempat
untuk meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber pencemar.
Tujuan dari dikumpulkannya limbah tersebut untuk mencegah sumber atau vektor
penyakit yang menjadi fokus sanitasi mencemari lingkungan dan manusia.
Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengumpulan &
Penampungan dan/atau Pengolahan Awal adalah sebagai berikut:
a. Cubluk
bergantung pada jenis bencannya, sebab tiap jenis bencana alam memiliki
perbedaan efek kerusakan yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan
dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengumpulan & penampungan
dan/atau pengolahan awal secara umum, ialah:
a. Kerusakan Unit/Instalasi
b. Kerusakan Perpipan
d. Unit/Instalasi tertimbun reruntuhan
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan jika masih memungkinkan, agar unit
penampungan dapat dipergunakan kembali. Namun, jika tidak mungkin
dilakukan perbaikan dapat dibuatkan penampungan sementara atau perpipaan
30
sementara untuk menghindari penyebaran vektor penyakit ke lingkungan oleh air
limbah atau limbah tinja.
pengolahan terpusat atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan/atau IPLT
(Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Pendistribusian air limbah menuju IPAL
atau IPLT dapat direncanakan mengunakan sistem perpipaan atau dengan sistem
pengangkutan mengunakan mobil tinja. Berdasarkan fungsinya yang masuk
kedalam kelompok Pengangkutan/Pengaliran adalah sebagai berikut:
a. Perpipipaan Air Limbah.
berbeda-beda bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak
yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok
pengangkutan dan pengaliran awal secara umum, ialah:
a. Kerusakan Perpipaan.
b. Kerusakan Jalan.
perpipaan atau akses jalan untuk pendistribusian air limbah jika memungkinkan
untuk dilakukan, agar tidak menghambat pendistribusian air limbah atau limbah
tinja. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka membuat jalur
atau akses jalan yang baru menuju pengolahan terpusat, menutup semua sistem
perpipaan untuk sementara waktu hingga kondisinya kembali normal dan
mengalihkan sistem perpipaan ke sistem pengangkutan menggunakan mobil tinja.
31
Pengolahan terpusat atau biasa disebut dengan IPLT atau IPAL merupakan
tempat pengolahan lumpur tinja yang didistribusikan melalui sistem perpipaan
dan pengangkutan dengan mobil tinja. Lumpur tinja perlu dilakukan pengolahan
sebab menurut Niwabaga, 2009 tinja atau limbah tinja memiliki kandungan
nutrien berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalisium, carbon yang berasal dari sumber
makanan dan minuman, selain itu tinja juga mengandung logam berat seperti
Tembaga (CU), Zinc (Zn), Nikel (Ni), Cromium (Cr), Kadmium (Cd) dan Hg.
Tinja atau limbah tinja tidak hanya mengandung nutrien dan logam berat saja
namun juga mengandung mikroorganisme seperti bakteri, virus dan protozoa yang
secara alami ada di dalam usus manusia baik itu bersifat patogen atau non patogen
(Keman, 2005). Sehingga diperlukan pengolahan agar air limbah sebelum
dibungan ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan dan manusia.
Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengolahan Terpusat
adalah sebagai berikut:
Efek kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam berbeda-beda sesuai
dengan jenis bencana alam yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan
dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengolahan terpusat secara
umum, ialah:
akibat bencana alam pada kelompok pengolahan terpusat yakni memperbaiki
unit/instalasi yang mengalami kerusakan atau kegagalan sistem akibat bencana
alam. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka yang
dapat dilakukan yakni menutup semua sistem dan memindahkan pengolahan ke
32
sementara air limbah dari daerah terdampak.
4.1.5 Daur Ulang dan/atau Pebuangan Akhir
Pembungan akhir dan daur ulang adalah tahapan akhir dari pengelolaan air
limbah tinja atau lumpur tinja secara umum pembungan akhir air olahan limbah
tinja akan dilapas kebadan air atau kelingkungan. Pembuangan akhir harus
mengikuti ambang batas baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah,
tujuannya agar beban yang diterima oleh lingkungan tidak terlalu besar, sehingga
tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan lumpur tinja dan limbah tinja biasnya
digunakan sebagai pupuk organik. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam
kelompok Pengolahan Terpusat adalah sebagai berikut:
a. Pemanfaatan sebagai pupuk organik.
b. Pembuangan air limbah ke badan air.
Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap kelompok
pembungan akhir dan daur ulang relatif berbeda-beda sesuai dengan jenis bencana
alam yang ditimbulkan. . Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana
alam berdasarkan kelompok pembungan akhir dan daur ulang, ialah:
a. Badan air meluap/banjir
c. Lokasi yang terisolir
Rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan
akibat bencana alam pada kelompok pembungan akhir dan daur ulang yakni
memperbaiki sitem pengeringan jika memungkinkan untuk dilakukan, untuk
sistem pembuangan dapat dilakukan penutupan sementara sistem hingga level
muka air di badan air menurun. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan
penutupan maka dapat dilakukan pemompaan air olahan ke badan air, untuk daur
ulang dapat membuat dinding pembatas air atau penutup sementara hingga
33
kondisi kembali normal atau mengalihkan proses pengeringan ke IPLT atau IPAL
daerah tetangga.
Peraturan atau regulasi terkait dengan bidang sanitasi di lokasi pengungsian
korban bencana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1357 Tahun 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan
Masalah Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan atau penyebaran penyakit
melalui media lingkungan, akibat terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan
lingkungan yang ada di tempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan
kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Pada PERMENKES No.
1357 Tahun 2001 dalam bidang sanitasi mengatur jumlah jamban dan akses
masyarakat, korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dengan
jarak yang tidak jauh dari lokasi pengungsian agar dapat di akses dengan mudah
dan cepat kapan saja diperlukan baik siang atau malam hari. Berikut adalah
beberapa kebijakan sanitasi yang secara khusus mengatur masalah pembuangan
kotoran manusia yang digunakan pada daerah bencana:
a. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang.
b. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut perbedaan jenis
kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki-laki dan jamban
perempuan)
c. Jarak jamban tidak lebih dari 50 m dari pemukiman (rumah atau barak
pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya
memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.
d. Jamban umum tersedia di tempat-tempat seperti pasar, titik-titik pembagian
sembako, pusat-pusat layanan kesehatan dan sebagainya.
e. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang-kurangnya berjarak 30
meter dari sumber air bawah tanah.
34
f. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.
g. Pembuangan limbah cair jamban tidak merembes ke sumber air mana pun,
baik sumur maupun mata air, sungai dan sebagainya (Keputusan Menteri
Kesehatan No. 1357, 2001).
mengatur lebih rinci mengenai teknis toilet yang akan disediakan, sehingga
penyediaan toilet di lokasi pengungsian dapat mengacu pada buku yang disusun
oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yakni Buku Standard Toilet Umum
Indonesia dimana dalam buku tersebut mengatur secar teknis penyediaan toilet
umum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan toilet di lokasi
bencana sama halnya dengan penyediaan toilet umum dimana teknis dan
persyaratannya telah diatur.
Persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standartd Toilet
Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.
Ukuran Reguler
a. Ruang untuk buang air bersar (WC).
Ukuran luas ditentukan oleh posisi buang air besar baik menggunakan kloset
duduk maupun kloset jongkok:
ukuran luas minimum menjadi:
(P x L x T) 80cm x 160cm x 220cm
Ukuran yang disarankan (recommended) adalah
(P x L x T) 90cm x 160cm x 240cm
b. Ruang untuk buang air kecil (Urinoir)
Lebar satuan untuk aktifitas buang air kecil berdiri untuk orang
dewasa minimum 70cm dengan penyekat
Ketinggian urinal minimal 40cm
35
floor standing, atau dibuat langsung diatas lantai.
c. Ruang cuci tangan dan cuci muka (wastafel)
Ukuran dan luas untuk ruang cuci tangan dan muka, minimum adalah:
Lebar 80cm.
Ukuran yang disarankan (recommended) adalah:
Lebar 80cm.
Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di lokasi pengungsian korban
bencana alam ada beberapa tipe atau jenis berikut ini merupakan jenis-jenis toilet
yang biasanya digunakan di lokasi pengungsian korban bencana alam, antara lain:
Toilet Cabin
Toilet Mobil
Toilet Bus
Toilet Portable
Dari beberapa jenis toilet diatas ada dua toilet yang menjadi pembanding
antara jenis-jenis toilet yang sudah ada dengan desain toilet yang akan
direncanakan dimana dalam perencanaan ini toilet yang akan menjadi pembanding
yakni MCK knock down dan Toilet Portable dimana kedua desain ini diambil
sebab dalam perencanaan toilet untuk lokasi pengungsian korban bencana alam
36
kedua desain atau tipe tersebut yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam segala
kondisi medan, efektif, efisien, mudah, modern, nyaman dan menjaga privasi
pengguna atau user sehingga dua jenis toliet di atas menjadi pilihan pembanding.
a. MCK Knock Down
MCK knock down merupakan toilet dengan sistem bongkar pasang yang
dapat digunakan bila ada kebutuhan amat mendesak terkait mandi, cuci, kakus
(MCK) di lokasi-lokasi pengungsian. Metode knock down atau yang lebih populer
dengan sebutana sistem bongkar pasang merupakan sistem atau metode yang
paling mudah dan banyak digunakan untuk perakitan. Sistem knock down atau
bongkar pasang ini bertujuan seperti:
Memudahkan dalam mobilitas atau transportasi.
Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen-
komponen.
Oprasional yang lebih sederhana.
Memudahkan dalam proses penyimpanan.
Struktur terbuat dari bahan atau material pipa baja dan plat baja sebagai
rangka kontruksi MCK knock down dan kain yang berfungsi sebagai dinding
penutup sementara lantainya terbuat dari bahan fiberglass. Umumnya MCK knock
down ini lengkap dengan tangki air dan kloset. Dimensi atau ukuran teknis MCK
knock down ini lebar 80cm, panjang 120cm dan tinggi 200cm. Meskipun sangat
fleksibel dengan berbagai macam kondisi di lokasi pengungsian, dan mudah
dalam proses instlasinya namun toilet dengan sistem knock down ini memiliki
beberapa kelemahan diantaranya sangat mudah mengalami kerusakan pada
dinding dan rangka, selain itu permasalahan-permasalahan seperti kebersihan,
kenyamanan dan privasi pengguna sering sekali muncul dilapangan. Berikut ini
contoh dari penggunaan MCK knock down dilokasi pengungsian.
37
b. Toilet Portabel
Definisi portable menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu
yang mudah untuk dibawa-bawa, dijinjing atau dipindahkan. Sehingga toilet
portabel dapat diartikan sebagai bilik atau ruangan khusus yang di rancang
lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan manusia untuk membuang hajat yang
mampu dipindahkan atau dibawa kemana saja tanpa mmembedakan jenis usia dan
jenis kelamin penggunanya.
Penggunaan toilet portable di pengungsian korban bencana alam terbilang
sangat baru karena penggunaan MCK knock down jauh lebih efektif dan flexibel,
namum seiring dengan kebutuhan toilet yang memiliki kontruksi yang lebih kuat
dan nyaman penggunaan toilet portable menjadi alternatif terbaik saat ini.
Kontruksi toilet portable secara umum menggunakan bahan fiberglass yang lebih
kelebihan dari toilet portabel antara lain:
Praktis dalam pengunaan
Tahan lama
Toilet portable lebih praktis jika dibandingkan dengan MCK knock doown
sebab tidak di butuhkan perakitan atau instalasi di lokasi, karena umumnya toilet
porteble telah terinstal sehingga ketika sampai dilokasi dapat langsung digunakan.
Selain itu toilet portable jauh lebih modern sebab penggunaan material fiberglass
menambah estetika yang pada akhirnya akan membuat user atau pengguna
menjadi nyaman, namun dari semua kelebihannya toilet portable ini memiliki
kelemahan dari segi mobilitas walaupun mudah untuk berpindah-pindah tetapi
proses mobilisasi harus menggunakan mobil sehingga untuk lokasi yang memliki
akses jalan atau medan yang sulit tidak dapat dijangkau.
Dimensi teknis atau ukuran toilet potabel umumnya memiliki panjang
120cm lebar 90cm dan tinggi 250cm tetapi dalam beberapa desain ukuran
menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Toilet portable
secara umum dilengkapi oleh 1 kloset jongkok atau duduk, kran air, bak air,
lampu, dan floor drain. Bahkan beberapa toilet porteble memiliki sistem
penampungan atau tanki septik dimana tanki septik tersebut memiliki beberapa
metode yakni sistem tertutup dan sistem perpipaan. Sistem tertutup adalah sistem
dimana tangki septik ditutup mengunakan dop setelah kegiatan oprasional
berlangsung tanki septik yang telah penuh oleh limbah disedot melalui saluran
drain yang ditutup oleh dop dan dipindahkan ke kendaraan penyedot limbah.
Sementara itu sistem perpipaan adalah sistem yang menghubungkan antara tanki
septik dengan IPA (Instalasi Penglahan limbah) darurat dimana umumnya tersedia
dilokasi pengungsian atau kesaluran pembuangan yang tersedia sistem ini tidak
memerlukan penyedotan atau pembuangan terpisah yang menghambat jam
oprasional toilet. Berikut ini contoh dari pengunaan toilet portable dilokasi
pengungsian.
39
4.2.3 Varian Teknologi Toilet Bencana Alam
Varian teknologi toilet ditujukan sebagai pertimbangan untuk menentukan
kriteria desain toilet yang sesuai dengan kondisi sanitasi di lokasi pengungsian
korban bencana alam, dimana varian ini merupakan pilihan yang memungkinkan
untuk diaplikasikan kedalam kriteria teknis perencanaan toilet. Beberapa varian
toilet dibawah ini sebenarnya telah direncanakan untuk kondisi bencana dan
keadaan darurat, selain itu beberapa data varian teknologi menjadi alternatif yang
akan dianalisis. Berikut ini beberapa varian teknologi toilet:
a. eSOS® – Emergency Sanitation Operation System
eSOS (Emergency Sanitastion Operation System) merupakan sebuah konsis
sistem oprasional sanitasi darurat, dimana sistem ini menerapkan solusi sanitasi
yang berkelanjutan, holistik dan terjangkau di lokasi pengungsian korban bencana
alam. Tujuan dari perencanaan ini yakni meminimalisir ancaman terhadap
kesehatan masyarakat anggota masyarakat atau pengungsi yang paling rentan.
40
for Water Education. Produk prototipe experimental dari toilet pintar tersebut
dalam proses pengembangannya juga berkerja sama dengan FLEX/ The
Innovation Lab dan SYSTECH yang seluruh kegiatannya didanai oleh Bill and
Melinda Gates foundation. Sistem dari toilet ini terdiri atas tiga komponen utama
yakni toilet cerdas modular, pemantauan dan intelejen managemen dan fasilitas
perawatan untuk aliran limbah.
Gambar 4. 3 eSOS Toilet
Toilet darurat atau eSOS ini memiliki spesifikasi bahan yang kuat dan
ringan material didominasi oleh fiberglaas dan beberapa kayu sebagai penopang
rangka. Toilet eSOS memiliki kecerdasan yang mencakup beberapa fitur-fitur
unik diataranya pemantauan penginderaan jauh, unit pasokan energi, sensor /
kartu GSM / GPS, sensor hunian, sensor akumulasi urin / faeces, tombol SOS, dan
sistem komunikasi yang memungkinkan pengumpulan data dengan penginderaan
jarak jauh dan transfernya ke atau pusat koordinasi darurat di luar lokasi. Fitur
pada toilet tersebut memiliki kemampuan untuk memisahkan limbah padat dan
cair selain itu juga dapat menentukan berat dan volume keduanya data tersebut
dapat langsung terintegrasi dengan sistem pengindraan jauh, sehingga dapat
menentukan waktu yang tepat untuk dilakukan penyedotan limbah. Selain itu
sensor pintar yang di pasang didalam toilet dapat mengurangi resiko pelecehan
seksual dan masalah-masalah privasi pengguna, sebab sensor tersebut mamapu
mengidentifikasi keberadaan lebih dari satu orang dan semua informasi yang
terkumpul dapat langsung diakses jauh dari lokasi pengungsian. Berikut ini adalah
beberapa gambar dari desain eSOS:
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Filipina pada bulan september dengan dukungan dari Bill and Melinda Gates
fondation dan Asian Development Bank, berdasarkan data yang tercatat secara
sistematik lebih dari 1000 kunjungan atau akses terhadap toilet tersebut.
sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Science and Technology
The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana
pengembangan ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah layanan sanitasi yang
berkelanjutan dan terjangkau bagi pemukiman kumuh di negara-negara
berpenghasilan rendah.
sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/nairobi-field-test.html
Toilet ini didesain sedemikian rupa sehingga mampu mengolah limbah.
Prinsip kerja treatment pada toilet ini yaitu memisahkan urin dan feses kedalam
wadah yang berbeda, air yang digunakan untuk membersihkan kloset di olah dan
digunakan kembali untuk pembersihan atau flushing setelah mengalami proses
kimiawi. Air yang dihasilkan dari proses pembilasan ditampung pada wadah yang
berbeda dengan urin dan feses, kemudian air dari proses pembilasan tersebut
melewati membran yang dirancang khusus untuk menghilangkan patogen
selanjutnya air yang sudah melewati membran akan diinjeksikan bahan kimia klor
dan dilakukan elektrosis menggunakan tenaga surya.
Toilet Blue Diversion bekerja pada prinsip inti pertama memisahkan urin
dari feses ke dalam wadah yang berbeda. Setelah itu, ditambahkan air yang dapat
digunakan untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan mangkuk toilet. Air
yang sudah kurang terkontaminasi daripada di toilet biasa, kemudian diolah secara
kimiawi dan dialirkan ulang. Proses ini menghentikan pertumbuhan kembali
bakteri yang tidak diinginkan dalam air daur ulang, yaitu kualitas minum. Toilet
membutuhkan total 11,5W energi listrik untuk berfungsi, tetapi energi ini
disediakan oleh panel surya sebesar 60Wp.
Fakta bahwa urin dan feses diambil secara terpisah membuatnya lebih
mudah untuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi pupuk dan fosfor. Di
sinilah Blue Diversion Toilet menjadi lebih dari sekedar toilet. Kotoran dan urine
yang dikumpulkan dapat diangkut ke pabrik pemulihan sumber daya di luar
lokasi, di mana mereka diubah menjadi pupuk yang dapat dijual untuk
mendapatkan keuntungaan. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar
yang menjelasakan proses treatment diatas:
45
Berikut ini dimensi atau ukuran teknis Toilet Blue Diversion :
Dimensi: tinggi 190 cm, lebar 74 cm, kedalaman 91 cm. Langkah ke toilet
pan adalah 37cm.
Bahan: tangki dan panci terbuat dari plastik LDPE; stabilisasi terbuat dari
baja
Kebutuhan energi: Energi listrik 11,5W yang disediakan oleh panel surya
60Wp
air, dan elektronik untuk kontrol dan flush
Rentang hidup: 10 tahun
Gambar dibawah ini merupakan tata cara penggunaan Toilet Blue Diversion:
sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/uploads/2/4/7/3/24735693/
Gambar 4. 10 Cara Penggunaan Blue Diversion Toilet
c. The Autarky Toilet – Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic
Science and Technology
The Autarky Toilet adalah pengembangan dari Blue Diversion Toilet oleh
Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana
toilet jenis ini memiliki kemampuan untuk memisahkan urin dan feses dan
melakukan treatment langsung ditempat.
Gambar 4. 11 The Autarky Toilet
Toilet ini menggabungkan dua jenis pengolahan urin dengan kode (2A) dan
(2B) dimana pada 2A dilakukan proses kimia biasa disebut dengan metode
stabilisasi urin dimana treatment dilakukan untuk mengurangi nutrisi yang
terkandung dalam urin, toilet yang berisi kapur yang terhidrasi cukup dilarutkan
untuk meningkatkan pH urin sampai 12. Pada pH ini, hidrolisis urea ditekan,
degasifikasi amonia dihindari dan urin distabilkan.
Produk yang dihasilkan pada pengolahan 2A adalah :
Larutan nutrisi fosfor cair, yang membutuhkan pengeringan lebih lanjut dan
menjadi produk akhir pupuk fosfor kering.
Urin stabil yang mengandung semua nutrisi lain Nitrogen (N), Kalium (K),
Sulphur (S). Cairan ini dan dipompa ke bagian atas pipa penguapan di mana
ia memasuki proses pengolahan urin kedua 2B.
Sementara 2B adalah proses pengurangan volume urin dengan metode
evaporasi. Urin yang distabilkan menetes ke sebuah pipa melalui mana udara
ambien ditarik oleh ventilator. Urin dikeringkan, dengan menjenuhkan udara
dengan air. Uap air dilepaskan melalui pipa ventilasi. Produk yang dihasilkan
pada pengolahan 2B adalah kandungan nutrisi kering pada kertas blotting di
dalam pipa dan dipanen sebagai produk akhir pupuk NKS kering.
Untuk feses pengolahan yang dilakukan adalah dengan sistem pengeringan
dan pembakaran didasarkan pada oksidasi hidrotermal (HTO, juga dikenal sebagai
oksidasi air superkritis SCWO). Produk akhirnya adalah air dan padatan yang
diendapkan. Yang terakhir mengandung semua fosfor dari kotoran. Untuk
memanaskan energi proses diperlukan sekali, dapat disediakan oleh generator atau
steker listrik 220V sederhana. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar
yang menjelasakan proses treatment tersebut:
49
d. Bio Toilet - LIPI Project
Bio-Toilet merupakan pengembangan tolet yang digagas Pusat Penelitian
Fisika LIPI, toilet ini diklaim mampu menghemat penggunaan air. Toilet ini
memiliki keunggulan dalam menghemat penggunaan air untuk oprasional, sebab
tidak digunakannya air untuk membilas (flushing) kotoran. Bio-Toilet ini
menerapkan sistem toilet kering dimana limbah yang masuk akan dimanfaatkan
sebagai kompos atau material komposit lainnya.
Toilet ini merupakan alternatif untuk mengurangi pencemaran oleh limbah
domestik yang umumnya dibuang langsung ke lingkungan tanpa mengalami
pengolahan terlebih dahulu, sehingga berpotensi mecemari tanah, air permukaan
maupun air tanah. Toilet ini diklaim mampu menghemat konsumsi air per orang
hingga 40% untuk (BAB) buang air besar dan (BAK) buang air kecil. Penggunaan
Bio-Toilet ini juga akan menekan kasus diare pada daerah dengan kepadatan
penduduk tinggi, atau sarana sanitasi yang tidak memadai.
Bio-Toilet yang dikembangakan oleh LIPI ini tidak menggunakan air untuk
membilas kotoran. Namun, kotoran akan langsung ditampung kedalam tempat
pengolah limbah biasanya mengunakan tabung bio-toilet dengan volume 0,5 m 3
dengan kapasitas 30-50 orang perhari media atau rekator tersebut dilengkapi oleh
alat pengaduk otomatis yang berkerja tiap 15 menit sekali. Setelah dikumpulkan
limbah yang masuk akan dikomposkaan bersamaan dengan serbuk gergaji atau
ligno selulosa dengan cara pengadukan proses pengomposaan ini dilakukan
sekurang-kurangnya 3-5 bulan. Limbah yang telah terurai sempurna dan matang
menjadi produk kompos dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai penyubur tanah.
Produk kompos yang dihasilkan mengandung unsur mineral seperti natrium,
kalium dan fosfor serta nitrogen, sehingga apabila diaplikasikan ketanah akan
meningkatkan nilai miniral yang terkandung didalam tanah. Setelah produk
diambil serbuk gergaji atau ligno selulosa dimasukan lagi kedalam media
tampung atau reaktor untuk proses pengomposan limbah yang baru. Berikut ini
gambar skema pengolahan Bio-Toilet :
Bio-Toilet ini didesain dan dipasarkan berupa satu unit ruang kompak
dengan dua buah lubang kloset yang akan digunakan bergantian ketika reaktor
penuh. Pembeli dapat memilih desain ruangan dalam sesuai dengan keinginannya,
termasuk juga kelengkapan aksesoris pendukung oprasional toilet. Bio-Toilet ini
didesain untuk memenuhi kebutuhan layanan sanitasi di daerah terpencil yang
tidak memiliki sistem jaringan sanitasi terpusat.
Pengembangan teknologi ini dilakukan selama lima tahun dan tiga tahun
terakhir LIPI telah melakukan uji coba sosialisasi dan pendekatan masyarakat
hingga toilet ini berhasil di uji coba di tiga lokasi di Bandung yakni Pusat
Penelitian Fisika Terapan LIPI, Pesantren Daarut Tauhid, dan di Stasiun Kiara
Condong.
The Nano Membrane Toilet dikembangkan sebagai toilet yang mampu
mengolah limbah dari kotoran manusia langsung tanpa energi eksternal dan air.
Toilet ini direncanakan untuk penggunaan satu rumah tangga (setara dengan 10
orang), toilet ini menggunakan flush dengan mekanisme berputar yang unik dan
tanpa menggunakan air untuk membilas kotoran, selain itu flush berputar tersebut
memiliki kemampuan untuk menahan bau.
menggunakan membran serat berongga-ronga dengan transisi suhu rendah.
Dinding membran berstruktur nano yang akan memfasilitasi transportasi air dalam
suasana uap hal ini jauh lebih baik ketimbang harus berada dalam suasana cair
dimana air akan berpotensi menimbulkan bau dan senyawa patogen lainnya, air
yang diolah dan dibuang langsung kelingkungan melalui saluran irigasi rumah.
sumber : https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/
Gambar 4. 14 The Nano Membrane Toilet
Sementara itu padatan yang telah terpisah dengan air akan di angkut oleh skrup
mekanis ke dalam ruang bakar yang akan mengubah padatan menjadi abu dan
energi. Energi yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk proses membran. Untuk
lebih jelasnya mengenai proses teratment yang di terapakan dalam teknologi The
Nano Membrane Toilet berikut gambarnya:
https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/
53
sumber:https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/nano-
membrane-toilet
4.3 Penentuan Kriteria Desain
atau acuan dalam merencanakan sesuatu. Penentuan kriteria pada perencanaan ini
akan menggunakan hasil penelitian terdahulu mengenai toilet, dari beberapa
penelitian yang telah dipilih akan dianalisis menggunakan metode AHP (The
Analitycal Hierarchy Process) merupakan metode yang dikembangkan oleh
Thomas Saaty sekitar tahun 1970 dimana metode ini dipergunakan untuk
pengambilan keputusan dimana metode ini akan membantu kerangka berfikir
memasukan nilai numerik sebagai pengganti presepsi manusia dalam melakukan
perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen yang
memiliki prioritas tertinggi.
matriks perbandingan berpasangan, penetapan prioritas pada masing-masing
hirarki dan pengambilan keputusan.
Penyusunan struktur hirarki ditujukan untuk memperjelas kedudukan
tujuan, berbagai kriteria-kriteria serta kemungkinan alternatif pada tingkatan
paling bawah dalam penelitian ini. Penyusunan struktur hirarki dilakukan
dengan cara melakukan studi literatur mengenai varian teknologi toilet yang
memungkinkan untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian
korban bencana alam.
Berikut ini adalah elemen serta struktur hirarki yang telah ditetapkan
berdasarkan studi literatur dan pengumpulan data skunder dan disusun kedalam
tujuan, kriteria dan alternatif.
pengungsian korban bencana.
kriteria teknis maupun non teknis yang bertujuan sebagai pembentuk
desain dimana akan menciptakan suatu tatanan perencanaan yang sesuai
dengan kebutuhan dilokasi pengungsian korban bencana alam. Dalam
perencanaan toilet dilokasi pengungsian digunakan 8 kriteria yang akan
55
kebutuhan dilokasi pengungsian.
m. Kriteria 5 = Kecepatan Waktu Pembangunan
n. Kriteria 6 = Kesesuaian Budaya Sanitasi
o. Kriteria 7 = Ketahanan Cuaca
p. Kriteria 8 = Kualitas Bahan (Kontruksi)
c. Alternatif
untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian korban
bencana alam.
g. Alternatif 2 = Blue Diversion Toilet – Eawag
h. Alternatif 3 = The Autarky Toilet – Eawag
i. Alternatif 4 = Bio Toilet - LIPI Project
j. Alternatif 5 = The Nano Membrane Toilet - Cranfield University
Berikut ini merupakan susunan struktur hirarki dalam menentukan kriteria desain
yang akan digunakan dalam perencanaan desain toilet dilokasi pengungsian
korban bencana alam pada Gambar 4.16.
56
53
yakni menetapkan perbandingan berpasangan antara kriteria-kriteria berdasarkan
tujuannya, yang berupa matriks. Nilai diagonal matriks tersebut ialah
perbandingan antara satu elemen dengan elemen itu sendiri sehingga
perbandingan tersebut di isi dengan bilangan 1. Sedangkan perbandingan satu
elemen dengan element yang lain diisi dengan bilangan 1-9 sesuai dengan Tabel
3.1 Skala Penilaian Relatif.
Bobot
Kriteria 1 1 1/2 2 3 3 5 5 7
Kriteria 2 2 1 2 3 5 5 5 5
Kriteria 3 1/2 1/2 1 3 3 3 3 5
Kriteria 4 1/3 1/3 1/3 1 2 2 2 3
Kriteria 5 1/3 1/5 1/3 ½ 1 1/2 1/2 3
Kriteria 6 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1 2 3
Kriteria 7 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1/2 1 2
Kriteria 8 1/8 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/2 1
Setelah terbentuk matriks tahapan selanjutnya matriks di atas dirubah dari bentuk
fraksi kedalam bentuk desimal (Matriks 1):
Tabel 4. 2 Matriks Perbandingan Kriteria (1)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 1,00 0,50 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 7,00
Kriteria 2 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kriteria 3 0,50 0,50 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00
Kriteria 4 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00
Kriteria 5 0,33 0,20 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 3,00
Kriteria 6 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 1,00 2,00 3,00
Kriteria 7 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 0,50 1,00 2,00
Kriteria 8 0,13 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,50 1,00
JUMLAH 4,69 3,13 6,53 11,83 18,33 17,33 19,00 29,00
54
mengkuadratkan matriks (1) dengan cara mengalika jumlah baris dengan kolom
atau iterasi 1 atau martriks (2).
A=
Kriteria 1 x Kriteria
= ((1,0 x 1,0)+(0,5 x 2,0)+(2,0 x 0,5)+(3,0 x 0,33)+(3,0 x 0,33)+(5,0 x 0,2)+ (5,0
x 0,2)+(7,0 x 0,13)
Sehingga didapatkan hasil pengkuadratan dari Matriks Perbandingan Kriteria (1)
tersebut adalah Matrik Perbandingan Kriteria (2) seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. 3 Matriks Perbandingan Kriteria (2)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 7,875 7,000 11,733 22,333 42,833 30,833 39,500 69,500
Kriteria 2 10,292 8,000 15,000 27,167 49,667 38,667 47,000 83,000
Kriteria 3 5,825 5,050 8,000 15,167 29,667 21,667 27,000 49,000
Kriteria 4 3,342 2,800 4,600 8,000 16,667 11,333 14,833 27,667
Kriteria 5 1,975 1,700 2,833 5,100 8,000 6,917 8,167 15,000
Kriteria 6 2,575 2,233 3,567 6,200 12,600 8,000 10,500 21,567
Kriteria 7 2,150 1,733 2,867 5,117 9,267 6,667 8,000 17,067
Kriteria 8 1,139 0,907 1,550 2,825 4,975 3,975 4,725 7,875
langkah berikutnya adalah pengkuadaratan bentuk matriks (2) sama dengan
matriks (1) atau iterasi II kemudian keduanya dilakukan penjumlahan dari hasil
55
perkalian silang matriks (1) dan matriks (2). Sehingga didapatkan iks
Perbandingan Kriteria (3) seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4. 4 Matriks Perbandingan Kriteria (3)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 605,1 35758,7 59344,8 107857,7 207107,0 144800,1 179356,4 333043,9
Kriteria 2 51290,0 43462,2 72143,1 131106,6 251573,7 176101,5 218125,2 405034,2
Kriteria 3 29537,6 25029,4 41546,0 75501,4 144875,9 101418,6 125625,0 233278,5
Kriteria 4 16346,2 13850,1 22990,6 41778,9 80153,9 56129,0 69527,6 129115,0
Kriteria 5 9431,8 7986,9 13262,7 24097,0 46162,2 32407,7 40142,4 74546,8
Kriteria 6 12394,3 10493,2 17426,7 31659,9 60626,1 42599,3 52772,0 98008,0
Kriteria 7 9840,2 9139,7 14341,3 26839,8 61245,1 29662,1 36747,5 68251,8
Kriteria 8 5312,1 4499,7 7470,6 13574,8 26024,8 18245,8 22600,0 41967,4
Setelah terbentuk matriks perbandingan hingga iterasi ke II maka dapat dihitung
bobot prioritas untuk perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya dengan
cara menjumlahkan hasil perkalian matriks berdasarkan baris.
Kriteria 1
= 1067873,9
dibawah ini:
Perbandingan Matriks Jumlah
Kriteria 1 1067873,85
Kriteria 2 1348836,531
Kriteria 3 776812,5133
Kriteria 4 429891,3293
Kriteria 5 248037,6124
Kriteria 6 325979,3924
Kriteria 7 256067,6217
perbandingan matriks maka tahapan berikutnya menentukan bobot prioritas dari
perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya. Perhitungan bobot prioritas
dilakuakan dengan cara membagi jumlah hasil perkalian perbandingan matriks
berdasarkan baris dengan total hasil penjumlahan.
Kriteria 1
Menentukan kriteria desain yang
didapatkan bobot prioritas dimana kriteria 2 (kemudahan mobilitas) menjadi
prioritas paling besar dengan bobot 0,294 diikuti berturut-turut kriteria 1
(kebutuhan air) dengan 0,232; kriteria 3 (kebutuhan energi) dengan 0,169; kriteria
57
4 (keamanan dan kenyamanan) dengan 0,094; kriteria 6 (kesesuaian budaya
sanitasi) dengan 0,071; kriteria 7 (ketahanan cuaca) dengan 0,056; kriteria 5
(kecepatan waktu pembangunan) dengan 0,054; dan yang paling akhir kriteria 8
(kualitas bahan) dengan bobot prioritas sebesar 0,030.
Setelah didapatkan masing-masing bobot prioritas dari tiap kriteria
selanjutnya akan dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi bertujuan untuk
mengetahui besaran penyimpangan dari konsistensi atau biasa disebut CI
(Consistency Index) selain uji konsistensi juga akan dilakukan perhitungan Rasio
Konsentrasi (CR) untuk mengetahui apakah metode AHP matriks perbandingan
dapat diterima atau tidak.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,232 x 4,69) + (0,294 x 3,13) + (0,169 x 6,53) + (0,094 x 11,83) +
(0,054 x 18,33) + (0,071 x 17,33) + (0,056 x 19,00) + (0,030 x 29,00)
= 8,34
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 8
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,41 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
58
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
pertimbangan masing-masing kriteria dalam pemilihan desain dengan cara yang
sama atau mengulangi langkah-langkah dalam menentukan bobot prioritas
kriteria.
Tabel 4. 7 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 1
Kriteria 1 Alternatif
Dari hasil perhitungan bobot prioritas alternatif desain dengan perbandingan
masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 1 (kebutuhan air)
dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency Sanitation
Operation System) dengan nilai 0,402; selanjutnya berturut-turut alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,258; alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –
Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield
University) dengan nilai 0,115; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai
0,045.
59
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,402 x 2,5) + (0,180 x 6,667) + (0,258 x 4,167) + (0,045 x 21,0) +
(0,115 x 8,5)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
60
Tabel 4. 8 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 2
Kriteria 2 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 2
(kebutuhan energi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,337; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,235;
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,136; alternatif 5 (The
Nano Membrane Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,147; dan alternatif 4
(Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,145.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,337 x 2,833) + (0,235 x 4,5) + (0,136 x 8,5) + (0,145 x 7,5) +
(0,147 x 7,5)
CI =
61
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 9 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 3
Kriteria 3 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 3
(kemudahan mobilitas) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,370; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,267;
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,200; alternatif 4 (Bio
Toilet-LIPI) dengan nilai 0,104; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -
Cranfield University) dengan nilai 0,060.
62
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,37 x 2,533) + (0,267 x 4,167) + (0,20 x 5,7) + (0,104 x 9,5) +
(0,060 x 16,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
63
Tabel 4. 10 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 4
Kriteria 4 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 4
(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut
alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,271; alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,203; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan
nilai 0,099; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,075.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,352 x 2,66) + (0,271 x 4,16) + (0,203 x 5,66) + (0,099 x 10,5) +
(0,075 x 12,0)
CI =
64
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 11 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 5
Kriteria 5 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 5
(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut
alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,303; alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan
nilai 0,091; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,075.
65
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,352 x 2,66) + (0,303 x 4,16) + (0,180 x 5,66) + (0,091 x 12,5) +
(0,071 x 16,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
66
Tabel 4. 12 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 6
Kriteria 6 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 6
(keamanan & kenyamanan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,408; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226;
alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,181; alternatif 3 (The Autarky Toilet
– Eawag) dengan nilai 0,124; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -
Cranfield University) dengan nilai 0,061.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,408 x 2,367) + (0,226 x 5,33) + (0,124 x 8,33) + (0,181 x 5,83) +
(0,061 x 15,0)
CI =
67
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 13 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 7
Kriteria 7 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 7
(kesesuaian budaya sanitasi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,401; selanjutnya
berturut-turut alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,255; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,192; alternatif 2
(Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,086; dan alternatif 3 (The Autarky
Toilet – Eawag) dengan nilai 0,065.
68
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,401 x 2,4) + (0,86 x 12,5) + (0,065 x 14,0) + (0,192 x 5,667) +
(0,255 x 4,167)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 14 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria 8 Alternatif
69
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 8
(kualitas bahan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,305; selanjutnya berturut-turut
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226; alternatif 2 (Blue
Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,210; alternatif 5 (The Nano Membrane
Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,176; dan alternatif 4 (Bio Toilet-
LIPI) dengan nilai 0,82.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,305 x 3,0) + (0,22 x 5,66) + (0,21 x 5,83) + (0,82 x 11,0) + (0,176
x 7,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
70
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
berdasarkan perbandingan dari masing-masing kriteria penilaian dalam pemilihan
desain toilet yang sesuai dengan kondisi lokasi pengungsian korban bencana alam.
Dengan cara mengalikan bobot prioritas masing-masing desain dengan bobot
prioritas kriteria. Untuk mendapatkan total bobot masing-masing alternatif desain
dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing baris seperti dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.15
Tabel 4. 15 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 1 0,23 x 0,40 0,23 x 0,18 0,23 x 0,25 0,23 x 0,04 0,23 x0,11
Kriteria 2 0,29 x 0,33 0,29 x 0,23 0,29 x 0,13 0,29 x 0,14 0,29 x 0,15
Kriteria 3 0,16 x 0,37 0,16 x 0,26 0,16 x 0,20 0,16 x 0,10 0,16 x 0,06
Kriteria 4 0,09 x 0,35 0,09 x 0,27 0,09 x 0,20 0,09 x 0,09 0,09 x 0,07
Kriteria 5 0,05 x 0,36 0,05 x 0,30 0,05 x 0,18 0,05 x 0,09 0,05 x 0,07
71
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 6 0,07 x 0,40 0,07 x 0,22 0,07 x 0,12 0,07 x 0,18 0,07 x 0,06
Kriteria 7 0,05 x 0,40 0,05 x 0,08 0,05 x 0,06 0,05 x 0,19 0,05 x 0,25
Kriteria 8 0,03 x 0,30 0,03 x 0,22 0,03 x 0,21 0,03 x 0,08 0,03 x 0,17
Tabel 4. 16 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 1 0,0935 0,0418 0,0600 0,0104 0,0268
Kriteria 2 0,0691 0,0988 0,0400 0,0426 0,0431
Kriteria 3 0,0626 0,0452 0,0338 0,0175 0,0101
Kriteria 4 0,0329 0,0254 0,0190 0,0093 0,0070
Kriteria 5 0,0192 0,0163 0,0097 0,0049 0,0038
Kriteria 6 0,0290 0,0160 0,0088 0,0128 0,0043
Kriteria 7 0,0224 0,0048 0,0036 0,0107 0,0142
Kriteria 8 0,0093 0,0069 0,0064 0,0025 0,0054
Bobot
Pada Tabel 4.15 dapat dilihat alternatif desain dengan bobot prioritas
tertinggi ada pada alternatif 1(eSOS® – Emergency Sanitation Operation System)
72
dengan nilai 0,338; selanjutnya berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –
Eawag) dengan nilai 0,2553; alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan
nilai 0,1812; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,1148; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,1108.
Sehingga dapat disimpukan bahwa alternatif desain yang paling berkesesuaian
dengan kriteria-kriteria dalam pemilihan desain toilet yang sesuai dengan kondisi
lokasi pengungsian korban bencana alam adalah alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System).
4.4 Desain Usulan
toilet bencana alam melalui analisis menggunakan metode AHP selanjutnya akan
direncanakan desain toilet portable, dimana desain ini akan dijadikan sebagai
desain usulan. Desain usulan akan menggabungkan regulasi atau peraturan terkait
dengan toilet dan kriteria desain berdasarkan alternatif terpilih.
4.4.1 Perencanaan Dimensi
Dalam perencanaan ini dimensi toilet direncanakan berdarkan regulasi
terkait dengan toilet umum. Mengingat tidak ada regulasi yang mengatur teknis
toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam, sehingga perencanaan
menggunakan regulasi yang berkaitan dengan toilet untuk menentukan dimensi
toilet portable yang akan direncanakan. Dimana dimensi yang direncakan
mengacu pada persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standard
Toilet Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana
dimensi toilet yang digunakan adalah:
Panjang = 180 cm
Lebar = 160 cm
Tinggi = 240 cm
bangunan, sehingga jika komponen strutural dihilangkan, maka bangunan akan
mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Secara
umum komponen stuktural dibagi menjadi tiga sistem, yakni : sistem pondasi,
sistem rangka, dan sistem atap.
Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam
menggunakan teknik panel struktural dimana struktural ini menggunakan sistem
knockdown atau bongkar pasang dari komponen-komponen modular yang dicetak
atau dibuat secara fabrikasi (Sabaruddin Arief, 2015). Konsep knockdown
merupakan porses pembangunan atau instalasi yang tidak membutuhkan semen
dan bata, melainkan dengan mengkombinasikan atau menggabungkan panel-panel
baja atau beton dengan baut. Panel struktural dengan konsep knockdown memiliki
keunggulan-keunggulan seperti cepat, murah, ramah lingkungan, tahan gempa,
movabel atau memiliki mobilitas yang tinggi (Sabaruddin Arief, 2015).
Modul toilet portabel yang direncanakan terdiri dari 2 panel struktural (A1
dan A2) dan 1 struktural pengunci atau pengikat. Panel struktural A1 berdimensi
22cm x 22cm x 247cm sementara panel struktur A2 memiliki dimensi 160cm x
100cm x 25 cm ,dan struktur pengunci berbentuk modular dengan dimensi 22,5
cm x 22,5cm x 50cm.
Panel struktur A1 sebagai lengan struktur yang berfungsi sebagai kolom
yang merupakan elemen struktur tekan yang memegang fungsional atau peranan
penting dari suatu struktur bangunan, sehingga kolom dapat diartikan sebagai
lokasi kritis dari suatu bangunan yang memungkinkan terjadinya collapse atau
runtuhnya seluruh struktur. Panel struktur A2 merupakan atap toilet yang juga
berfungsi sebagai balok yang merupakan bagian struktur yang memiliki peranan
pengikat kolom pada bagian atas atau bisa diartikan sebagai rangka penguat
horizontal bangunan akan beban-beban. Struktural pengikat merupakan struktur
pondasi yang memiliki fungsi pengikat kolom pada bagian bawah, meratakan
74
gaya beban dinding ke pondasi dan menahan gaya beban dinding. Berikut ini
adalah tabel spesifikasi panel struktural A1.
Tabel 4. 17 Spesifikasi Panel Struktural A1
Spesifikasi Panel
Panjang 22 cm
Lebar 22 cm
Tinggi 247 cm
Ketebalan 22 cm
Panel Jumlah lubang pada panel 8 lubang pada bagian bawah dan 4
lubang pada bagian atas
Tampilan Fisik
75
Tabel 4. 18 Spesifikasi Panel Struktural A2
Spesifikasi Panel
Panel Jumlah lubang pada panel 16 lubang pada bagian atas
Panel Masing-masing lubang berdiameter 23 mm
Tampilan Fisik Berikut ini tampilan fisik Panel Struktural A1
Berikut ini adalah tabel spesifikasi panel struktural struktural pengikat.
76
Spesifikasi Panel
Panjang 24 cm
Lebar 24 cm
Tinggi 50 cm
Ketebalan 1 cm
Panel Jumlah lubang pada panel 4 lubang pada sisi kanan dan 4
lubang pada sisi kiri
Tampilan Fisik
4.4.3 Perencanaan Material
Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam
akan menggunakan beberapa material, untuk material panel A1 dan A2 material
fiberglass yang dicetak secara fabrikasi sesuai dengan model, desain dan dimensi
yang telah direncanakan.
Material fiberglass dipilih sebab material komposit yang satu ini memiliki
kekuatan yang tidak diragukan lagi, selain itu material ini memiliki bobot yang
ringan dan sangat mudah diaplikasikan kedalam berbagai bentuk desain. Material
fiberglass juga memiliki ketahanan terhadap bahan-bahan kimia selain itu juga
didukung dengan sifatnya yang anti karat menjadikan material ini menjadi pilihan
yang paling tepat digunakan didalam perencanaan toilet portable di lokasi
pengungsian korban bencana alam. Selain pada panel struktural penggunaan
material fiberglass juga digunakan pada bagian lantai dan dinding toilet portable
(Mohan R., 2013).
dicustom sesuai dimensi dan model yang telah direncanakan. Pemilihan material
plat baja ditujukan untuk memperkokoh panel struktural, mengingat struktural
pengikat memiliki fungsi sebagai pengikat kolom pada bagian bawah yang juga
berfungsi sebagai pondasi dari toilet portable ini. Sehingga membutuhkan material
yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang besar.
Material penyusun fiberglass secara umum terdiri dari 11 jenis material
penyusun dimana 6 jenis material penyusun utama dan 5 lainnya merupakan
material yang berfungsi sebagai finishing. Material penyusun tersebut, diantaranya
: erosil, pigmen, resin, katalis, talk, mat, aseton, PVA, mirror, cobalt dan dempul
(M. Schwats, 1984).
alam perencana juga merencanakan jenis alat plambing yang akan digunakan.
Jenis-jenis alat plambing yang digunakan dalam perencanaan toilet ini meliputi
kloset, wastafel (lavatory), dan shower spray.
a. Kloset
Timur. Toilet dengan gaya jongkok pada dasarnya telah berkembang sejak
jaman kuno yang secara umum di gunakan oleh masyarakat Asia, seperti
India, Jepang, China, hingga Anatolia, sehingga masyarakat Asia bisa
menyebut kloset jongkok sebagai toilet dengan “gaya Asia” atau “gaya
Timur” (Genç 2009).
terjadinya pemborosan air dari proses pembilasan tersebut. Terlebih lagi di
lokasi-lokasi pengungsian korban bencana alam yang distribusi air
bersihnya sangat terbatas. Selain itu sistem ini juga lebih efektif dalam
membilas kotoran dan sangat praktis dalam penggunaannya.
79
b. Wastafel (lavatory)
toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam yakni lavatory
yang di customize sesuai dengan kebutuhan pada toilet tersebut.
dalam proses mobilisasi dan instalasi dilapangan, sebab jika menggunakan
wastafel yang ada dipasaran akan menyulitkan dalam proses mobilisasi
dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses isntalasinya.
Untuk itu wastafel didesain kembali untuk memenuhi unsur-unsur di atas.
Wastafel yang direncanakan menggunakan material fiberglass
yang akan difabrikasi, berikut ini adalah tabel spesifikasi dari desain
wastafel yang direncanakan.
Spesifikasi Wastafel (Lavatory)
Accessories 1 Buah kran air berputar
Tampilan Fisik
81
Shower spray digunakan untuk membersihakan atau membilas kotoran
dalam perencanaan ini digunakan shower spray untuk menggantikan
fungsi dari bak air atau ember yang bisa dijadikan tempat menampung air
untuk membilas kotoran. Penggunaan shower spray akan menghemat
tempat sebab toilet portabel ini tidak memiliki ruang yang cukup besar
selain itu penggunaan shower spray juga lebih praktis. Shower spray yang
akan digunakan adalah shower spray TOTO tipe THX20NB.
82
Selain beberapa alat plambing diatas juga direncanakan beberapa aksesoris
tambahan seperti spare paper holder yang digunakan untuk menggantungkan
tissue yang akan digunakan untuk membersihkan atau membilas. Spare paper
holder yang akan digunakan adalah spare paper holder custome.
sumber : https://www.toto.co.id/products/tx722aes
Perencanaan baik air (toren air) yang akan digunakan untuk oprasional toilet
portabel di lokasi pengungsian korban bencana alam diawali dengan menghitung
kebutuhan air bersih dahulu. Dalam perhitungan kebutuhan air akan digunakan
dua metode perhitungan yang pertama berdasarkan jumlah pengguna atau jumlah
orang dan metode kedua dilakukan berdasarkan kebutuhan jenis/alat plambing
yang akan digunakan pada perencanaan toilet portable ini.
a. Perhitungan Kebutuhan Air Berdasarkan Jumlah Pengguna
Berdasarkan PERMENKES No.1357 dalam bidang sanitasi tiap
jamban digunakan paling banyak 20 orang. Selanjutnya kembali
diasumsikan kebutuhan air perorang sebesar 140 l/hari. Sehingga
didapatkan kebutuhan air sebagai berikut.
Q = kebutuhan perorang x jumlah pengguna
= 140 l/hari x 20 orang
= 2800 l/hari
= (100% + 10%) x 2,8 m 3 /hari
= 3,08 m 3 /hari
Qh = Qd/t
Dalam perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah pemakaian
air dilakukan berdasarkan studi literatur dalam buku karangan Soufyan M.
84
Pemeliharaan Sistem Plambing. Pada tabel 3.13 pemakaian air tiap alat
plambing laju aliran airnya dan ukuran pipa cabang pipa air, halaman 49
didapatkan data perencaan sebagai berikut:
Tabel 4. 21 Pemakaian Air Tiap Alat Plambing
Jenis Alat Plumbing Pemakaian Air Untuk
Penggunaan Satu Kali (Liter)
Bak Cuci Tangan Kecil 3 12-20
Kran Air 3 12-20
Berdasarka data pada tabel 4.16 diatas, maka dapat dihitung kebutuhan air
untuk masing-masing alat plambing dengan perhitungan di bawah ini:
Diasumsikan penggunaan tiap alat plambing tiap jamnya yakni 15 kali
penggunaan, sehingga kebutuhan air perjamnya sebagai berikut:
Kloset = 15L x 15 kali/jam = 225L/jam
Bak Cuci = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam
Kran Air = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam
Total penggunaan air tiap jamnya adalah 315 L/jam atau 0,315 m 3 /jam
atau setara dengan 7,56 m 3 /hari.
Dari kedua metode perhitungan kebutuhan air didapatkan hasil
perhitungan kebutuhan air sebesar 3,08 m 3 /hari dengan menggunakan
metode perhitungan berdasarkan jumlah pengguna. Sementara itu
perhitungan kebutuhan air dengan metode perhitungan menggunakan
jumlah pemakaian air tiap alat plambing sebesar 7,56 m 3 /hari. Sehingga
perencana mengambil kesimpulan untuk kebutuhan air pada perencanaan
toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam adalah berdasar
perhitungan jumlah pemakaian air tiap alat plambing dengan besaran debit
7,56 m 3 /hari, pengambilan ini berdasarakan faktor aman.
85
menghitung dimensi bak penampung air sebagai berikut.
Diketahui:
= 0,0000875 m 3 /detik
menit atau sama dengan 3600 detik.
Jumlah Bak direncanakan 2
= 0,315 m 3
Bak direncanakan dibagi menjadi 2 bak sehingga volume tiap bak airnya
ialah:
Volume =
= 0,1575 m 3
Direncanakan panjang bak air adalah 20 cm atau 0,2 m dan lebar bak
direncanakan 70 cm atau 0,7, sehingga didapatkan tinggi bak air
didapatkan sebagai berikut:
= 0,2 x 0,7 x t
0,16 = 0,2 x 0,7 x t
t =
Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak
penampung air yakni panjang 0,2 m dengan lebar 0,7 m dan tinggi 1,2 m,
berikut ini merupakan desain dari perencanaan air bersih:
86
Gambar 4. 21 Perencanaan Air Bersih
Pada gambar diatas terdapat dua bak air bersih dimana direncanakan bak
yang satu digunkan untuk membersihkan atau memflushing pan atau kloset,
sementara bak yang satunya lagi akan digunakan untuk mengaliri air ke kran dan
wastafel dan direncakan bak yang akan diisi dengan air daur ulang yakni air
limbah pada bak untuk flushing.
4.4.6 Perencanaan Pengolahan Limbah
Perencanaan pengolahan air limbah dari oprasional toilet di lokasi korban
bencana alam bertujuan untuk meminimalisir pencemaran atau penyebaran
penyakit yang melalui media air. Selain itu pengolahan yang akan dilakukan juga
bertujuan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang air limbah yang
dihasilkan agar dapat dimanfaatkan kembali atau “re-use” untuk membilas
kotoran pada kloset atau pan. Pengolahan yang akan dilakukan merupakan
pengolahan secara fisik dan biologis dimana yang menjadi konsentrasi
pengolahan dalam perencanaan ini adalah air limbah yang dihasilkan, namun
dalam perencanaan ini perencana tidak membahas secara detail terkait pengolahan
tersebut.
87
fungsional sanitasi yang terbagagi kedalam 5 (lima) kelompok, yakni:
Penghubung Pengguna (user interface)
Pengangkutan/Pengaliran
Daur Ulang dan/atau Pemrosesan Akhir
Berikut ini merupakan diagram dari sistem pengolahan yang akan di terapkan
dalam perencanaan desain toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam.
Gambar 4. 22 Diagram Perencanaan Pengolahan Limbah
Sebelum menentukan jenis pengolahan yang akan digunakan dalam
perencanaan ini, terlebih dahuluakan dilakukan perhitungan jumlah air limbah
yang dihasilkan dari kegiatan atau oprasional toilet portable di lokasi pengungsian
korban bencana alam.
Qd = 7,56 m 3 /hari
Debit air limbah yang dihasilkan dari kegiatan oprasional yakni sebesar 7,56
m 3 /hari atau setara dengan 0,0000875 m
3 /detik. Setelah ditentukan julah debit air
limbah selanjutnya dilakuakan perhitungan desain unit pengolahan air dimana
pengolahan awal adalah pengolahan fisik dan pengolahan anaerobic filter
pengolahan tersebut direncanakan dalam satu bak penampungan atau septick tank.
Pengolahan mengunakan proses anaerobic dipilih karena kondisi geografis
Indonesia sebagai negara tropis dengan temperatur atmosfer rata-rata tinggi dan
88
stabil, sehingga mikroorganisme anarob bisa hidup secara stabil dan aktif (Tanaka
Nao, 2014).
(Anaerobic Baffled Reakto) yang membedakan AF dengan ABR adalah diisinya
media tempat mikroorganisme dapat melekat/menempel dan tumbuh pada
permukaan media tersebut atau diakomodasi di dalam ruangan yang dibentuk oleh
medianya. Karena pasokan oksigen (O2) yang terbatas menyebabkan mikroba
yang aktif pada sistem ini adalah mikroba jenis anaerobic. Air limbah yang
mengalir akan melewati media tersebut dan sewaktu aliran tersebut mengalir
mikroba akan mengurai bahan organik terlarut dan organik yang terdispersi di
dalam limbah, sehingga hasilnya pengurangan kandungan organik pada efluen
(Takana Nao, 2014).
Dibandingkan dengan ABR sistem AF kontak antara air limbah dengan
mirkoorganisme jauh lebih efisien, sehingga anaerobic filter dapat menerima
organic loading yang lebih tinggi (Takana Nao, 2014). Anaerobic filter
dioprasikan pada waktu detensi 6-24 jam, dengan konsentrasi padatan volatil 4-20
g/L dengan parameter desain utama HRT (Hydraulic Retention Time) adalah > 8
jam, kecepatan aliran 2 m/jam, beban organik 3 kgCOD/m 3 /hari, dan penyisihan
COD 65-90% dan penyisihan BOD 70-95% (Sasse, 1998). Meskipun demikian
lumpur pada kompartemen akan berbeda tergantung pada lingkungan spesifik
senyawa atau zat yang terdegradasi (Barber, 1999). Pada hasil penelitian Singh
tahun 2009 sistem anaerobic filter berfungsi sebagai pengolahan primer dengan
penyisihan BOD mencapai 78%, COD sekitar 77% dan TSS sekitar 91%.
Media yang digunakan untuk tempat melekat mikroba ada beberapa jenis,
tetapi prinsipnya lebih luas permukaannya maka mikroba yang melekat juga akan
lebih banyak, sehingga sistem pengolahan akan lebih efektif. Untuk keperluan
tersebut biasanya media dibuat khusus dari plastik cetak, tetapi juga bisa
bahan/materi lain yang awet dan tidak mudah membusuk seperti batu koral,
89
pecahan keramik, dan lain sebagainya (Takana Nao, 2014). Berikut ini contoh
media yang dapat digunakan sebagai tempat melekat dan tumbuhnya mikroba:
Media tipe “ Sarang Tawon”
limbah cair dan limbah padat, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dengan
sistem anaerobic filter mengunakan media sarang tawon sebagai tempat
melekatnya dan berkembang biak mirkroba, sehingga diharapkan mampu
mendegradasi atau meremoval BOD, COD, TSS.
Menghitung dimensi Bak
Qlimbah = 0,0000875 m 3 /detik
Waktu tinggal (HRT) direncanakan 8 jam atau sama dengan 28800 detik
Menghitung Voleme
= 2,52 m 3
Menghitung dimensi
Direncanakan ketinggian bak adalah 100 cm atau 1 m dan panjang bak adalah 180
cm atau 1,8 m sehingga didapatkan lebar bak sebesar:
Vol = P x L x T
2,52 m 3 = 1,8m x L x 1m
l =
Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak penampung air
limbah yakni panjang 1,8 m dengan lebar 1,4 m dan tinggi 1 m. Untuk
memudahkan proses pengendapan akan direncanakan 2 kompartemen dan lantai
bak akan dibuat miring sebesar 30°. berikut ini merupakan desain dari bak
penampung air limbah atau septick tank yang dikombinasikan dengan anaerobic
filter:
91
Selain perencanaan pengolahan pada bak penampung atau septick tank juga
direncanakan juga filterisasi air dengan menggunakan teknologi membran filter
RO (Reverse Osmosis) untuk menghasilkan kualitas air olahan yang baik dan
layak untuk digunakan kembali. Pemilihan membran filter dalam pengolahan
selanjutnya sebab membran filter memiliki efektifitas removal yang sangat tinggi
sehingga kualitas air yang dihasilkan memenuhi baku mutu air yang telah
ditetapkan.
Berdarkan hasil uji efisiensi penghilangan COD, BOD5, SS dan total N rata-
rata di atas 97%. Beban COD yang sangat tinggi yaitu 58.000 ppm seperti pada
limbah sweet whey berhasil diolah dengan bioreaktor membran dengan efisiensi
penghilangan kurang-lebih 98% (Stephenson, T., Judd, S.J., Jefferson, B., and
Brindle, K., 2000).
Sistem RO yang direncanakan untuk skala kecil dengan sistem low pressure
dimana tekanan yang diberikan oleh pompa kurang dari 100 psi dimana pompa
dengan tekanan kurang dari 200 watt (Said I. N., 2003). Berikut ini merupakan
skema sistem reverse osmosis:
sumber:https://airreverseosmosis.files.wordpress.com/2009/02/ro_system.jpg?w=
limbah, sistem RO harus secara berkala dilakukan pembersihan untuk mencegah
terbentuknya kerak dipermukaan membran yang dapat mengakibatkan
penyumbatan atau yang biasa disebut dengan fouling merupakan pristiwa yang
menyebabkan fluks menurun pada filter membran karena bertambahnya hambatan
membran akibat tertutupnya pori-pori membran oleh partikulat (Mallevialle,
1996). Berikut ini adalah desain dari perencanaan RO pada toilet portable di
lokasi pengungsian korban bencana alam.
Gambar 4. 26 Membrane Filter RO (Reverse Osmosis)
kebutuhan energi untuk operasional toilet. Pada perencanaan ini sumber energi
yang direncanakan yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS
merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkkan energi
matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi
photovoltaic. Photovoltaic merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk
menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik, umumnya sel photovoltaic ini
memiliki ukuran 5cm x 5cm. Sel tersebut di rangkai menjadi beberapa susunan
hingga membentuk sebuah panel, panel yang dihasilkan juga disesuaikan dengan
kebutuhana listrik yang diinginkan, panel yang terdiri dari beberapa susunan sel
photovoltaic akan menangkap energi matahari lalu mengubahnya menjadi energi
listrik DC.
d. Panel Surya
semikonduktor yang dapat menyerap photon dari sinar matahari dan
mengubahnya menjadi energi listrik DC dengan mengikuti prinsip
photovoltaic. Pada sollar cell terdapat sambungan (function) yang berada
antara dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yakni
bahan semikonduktor jenis “P” (positif) dan semikonduktor jenis “N”
(negatif). Semikonduktor jenis P merupakan lapisan permikaan yang
dibuat tipis agar cahaya matahari dapat menembus langsung mencapai
junction. Pada bagian semikonduktor P juga dilapisi oleh bahan nikel yang
berbentuk cincin, berfungsi sebagai keluaran positif. Sementara itu
dibawah semikonduktor P terdapat juga bahan semokonduktor N yang
juga dilapisi oleh bahan nikel yang berfungsi sebgai terminnal keluaran
negatif.
95
Baterai berfungsi sebagai alat untuk menyimpan muatan energi
yang di hasilkan oleh solar cell, sehingga ketika sumber energi tidak
tersedia pada malam hari energi cadangan masih tersimpan didalam
baterai. Pada perencanaan pembangkit listrik tenaga surya memilki fungsi
ganda, yaitu sebagai penyimpan energi dan berfungsi sebagai satu daya
dengan tegangan konstan untuk menyuplai beban. Baterai yang sesuai atau
cocok digunakan dalam perencanaan PLTS adalah baterai jenis deep cycle.
f. Battery Charge Controllor (BCR)
BCR merupakan alat yang mengatur pengisisan arus listrik dari
modul sollar cell ke baterai dan sebaliknya. BCR berfungsi pengaturan
kelebihan pengisian baterai dan kelebihan tegangan dari modul sollar cell.
Alat ini bermanfaat juga untuk mengindari full discharge dan overloading
serta memonitor suhu dari baterai. BCR biasanya dilengkapi olej diode
protection yang berfungsi menghidarkan arus DC dari baterai agar tidak
masuk kedalam sollar cell.
direct current (DC) menjadi alternating current (AC) sesuai dengan
kebutuhan peralatan listrik yang digunakan.
e. Kabel Instalasi
memiliki kemampuan untuk mengurangi loss (kehilangan) daya,
pemanasan pada kabel dan kerusakan pada perangkat pembangkit listrik
tenaga surya.
kebutuhan daya listrik untuk operasional toilet portable di lokasi pengungsian
korban bencana alam. Berikut ini merupakan tabel estimasi kebutuhan daya listrik
pada peralatan toilet portable.
Peralatan Jumlah Daya
Total Konsumsi Daya / Hari 1410
Total Konsumsi Daya / Hari + 20% 1692
Dalam perencanaan toilet portable peralatan yang membutuhan daya listrik
yakni : pompa air, exhaust fan dan lampu LED, setelah dilakukan perhitungan
kebutuhan daya listrik untuk ketiga peralatan tersebut didapatkan konsumsi daya
sebesar 1410 Wh. Jumlah total kebutuhan daya per-hari yang didapatkan perlu
ditambahakan 20%, dimana 20% tersebut merupakan kebutuhan daya untuk
peralatan PLTS seperti inverter dan BCR. Sehingga didapatkan kebutuhan total
daya adalah sebesar 1692 Wh.
Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya listrik yang diakibatkan oleh
kondisi cuaca yang mendung atau hujan, maka perencana akan mengalikan total
kebutuhan daya dengan 2 untuk menghindarkan kekurangan daya sehingga
didapatkan total kebutuhan daya sebesar:
Total Wh = Wh x 2
= 1692 x 2
Perhitungan Jumlah Panel Surya
Pada perencanaan ini panel surya yang akan digunakan yakni panel surya
dengan kapasitas 300Wp dengan asumsi penyinaran matahari yang normal
selama 6 jam/hari, maka jumlah panel surya yang dibutuhkan adalah:
Jumlah Panel =
BRC yang akan direncanakan adalah MPPT 20 Ampere, sebab besaran
nilai ISC atau nilai arus maksimum yang dapat dikeluarkan oleh panel
surya/short circuit current pada panel surya adalah 9,46 A. Untuk jumlah panel
surya yang terpakai sebanyak 2 buah dibutuhkan BRC 20 A.
Inverter
Dalam perencanaan toilet portable ini inverter yang akan digunakan adalah
3200 watt pure sine wave 220 V 50 Hz dengan input 48 VDC.
Baterai
Baterai yang akan direncanakan adalah baterai jenis deep cycle 12 Volt
100 Ah. Dalam perencanaan ini inverter yang beroprasi pada tegangan 48 Volt
atau tengangan input untuk jenis inverter 3200 Watt pure sine wave. Sehingga
kebutuhan tegangan input inverter adalah:
Total baterai (voltase) =
Jumlah panel solar yang digunakan adalah 2 buah dengan masing-masing
300 wp dan voltase panel surya adalah 24 volt, sehingga tiap panel surya
membutuhkan baterai:
perencanaan pembangkit listrik tenaga surya adalah:
Jumlah baterai = Jumlah berdasarkan voltase x jumlah berdasarkan kapasitas
= 4 x 1
Gambar 4. 27 Perencanaan PLTS
4.5 BOQ
BOQ (Bill of Quantity) merupakan daftar kuantitas dari semua item yang
direncanakan dalam perencanaan toilet portable di lokasi pengungisan korban
bencana alam. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang menjelaskan jumlah item-
item yang dibutuhkan dalam perencanaan:
Tabel 4. 23 BOQ Perencanaan Struktural
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Panel Struktual A1 4 Unit
2 Panel Struktual A2 1 Unit
3 Struktural Pengikat 4 Unit
4 Dinding Toilet 4 Unit
5 Pintu 1 Unit
7 Baut 7/8" x 200mm 48 Buah
8 Mur 7/8" x 30mm 48 Buah
9 Baut 7/8" x 150mm 48 Buah
10 Mur 7/8" x 20mm 48 Buah
99
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Kloset TOTO tipe Customize 1 Unit
2 Wastafel (lavatory) Customize 1 Unit
3 Shower Spray TOTO tipe THX20NB 1 Unit
4 Kran Air 1 Unit
5 Spare Paper Holder Customize 1 Unit
6 Bak Air Customize 2 Unit
7 Bak Penampung Biofilter 1 Unit
8 Filter Membran RO 1 Unit
9 Water Drain 1 Unit
10 Pipa PVC Rucika 3" 2,3 Meter
11 Pipa PVC Rucika 2" 3,2 Meter
12 Pipa PVC Rucika 3/4" 4,7 Meter
13 Fitting TEE (AW) Rucika 2" 2 Buah
14 Fitting TEE (AW) Rucika 3/4" 1 Buah
15 Fitting Elbow (AW) Rucika 3" 3 Buah
16 Fitting Elbow (AW) Rucika 2" 4 Buah
17 Fitting Elbow (AW) Rucika 3/4" 4 Buah
18 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3" 1 Buah
19 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 2" 2 Buah
20 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3/4" 2 Buah
21 Fitting Plug (AW) Rucika 3" 1 Buah
22 Fitting Plug (AW) Rucika 2" 2 Buah
Tabel 4. 25 BOQ Perencanaan PLTS dan Kelistrikan
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Panel Surya 2 Unit
2 Baterai VRLA 12V 200Ah 4 Unit
3 BCR MPPT 40 A 1 Unit
4 Inverter 3200 W pure sine wave 1 Unit
5 Kabel 25 Meter
6 Soket 1 Buah
9 Pipa PVC 1/2" 5,7 Meter
100
perencanaan toilet portable di lokasi pengungisan korban bencana alam. Berikut
ini merupakan tabel-tabel yang menjelaskan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam
perencanaan:
104
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Panel Struktual A1 4 Unit Rp 120.000 Rp 480.000
2 Panel Struktual A2 1 Unit Rp 504.000 Rp 504.000
3 Struktural Pengikat 4 Unit Rp 200.000 Rp 800.000
4 Dinding Toilet 4 Unit Rp 342.000 Rp 1.368.000
5 Pintu 1 Unit Rp 150.000 Rp 150.000
6 Ventilasi Udara 2 Unit Rp 113.000 Rp 226.000
7 Baut 7/8" x 200mm 48 Buah Rp 8.000 Rp 384.000
8 Mur 7/8" x 30mm 48 Buah Rp 8.000 Rp 384.000
9 Baut 7/8" x 150mm 48 Buah Rp 6.000 Rp 288.000
10 Mur 7/8" x 20mm 48 Buah Rp 6.000 Rp 288.000
TOTAL Rp 4.872.000
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kloset Customize 1 Unit Rp 540.000 Rp 540.000
2 Wastafel (lavatory) Customize 1 Unit Rp 330.000 Rp 330.000
3 Shower Spray TOTO tipe THX20NB 1 Unit Rp 280.000 Rp 280.000
4 Kran Air (kitchen faucet) 1 Unit Rp 120.000 Rp 120.000
5 Spare Paper Holder Customize 1 Unit Rp 75.000 Rp 75.000
6 Bak Air Customize 2 Unit Rp 167.000 Rp 334.000
7 Bak Penampung Biofilter 1 Unit Rp 200.000 Rp 200.000
8 Filter Membran RO 1 Unit Rp 883.200 Rp 883.200
105
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
9 Water Drain 1 Unit Rp 110.000 Rp 110.000
10 Pipa PVC Rucika 3" 2,3 Meter Rp 195.600 Rp 449.880
11 Pipa PVC Rucika 2" 3,2 Meter Rp 95.200 Rp 304.640
12 Pipa PVC Rucika 3/4" 4,7 Meter Rp 31.700 Rp 148.990
13 Fitting TEE (AW) Rucika 2" 2 Buah Rp 20.200 Rp 40.400
14 Fitting TEE (AW) Rucika 3/4" 1 Buah Rp 3.500 Rp 3.500
15 Fitting Elbow (AW) Rucika 3" 3 Buah Rp 37.900 Rp 113.700
16 Fitting Elbow (AW) Rucika 2" 4 Buah Rp 14.300 Rp 57.200
17 Fitting Elbow (AW) Rucika 3/4" 4 Buah Rp 2.500 Rp 10.000
18 Fitting Plug (AW) Rucika 3" 1 Buah Rp 1.300 Rp 1.300
19 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 2" 2 Buah Rp 9.500 Rp 19.000
20 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3/4" 2 Buah Rp 2.200 Rp 4.400
21 Fitting Clean Out (D) Rucika 3" 1 Buah Rp 9.400 Rp 9.400
22 Fitting Clean Out (D) Rucika 2" 2 Buah Rp -
TOTAL Rp 4.034.610
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Panel Surya 300 Wp 2 Unit Rp 440.000 Rp 880.000
2 Baterai VRLA 12V 100Ah 4 Unit Rp 1.412.000 Rp 5.648.000
3 BCR MPPT 40 A 1 Unit Rp 230.000 Rp 230.000
4 Inverter 3200 W pure sine wave 1 Unit Rp 640.000 Rp 640.000
5 Kabel 25 Meter Rp 11.000 Rp 275.000
6 Soket 1 Buah Rp 35.000 Rp 35.000
106
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
7 Lampu LED 2 Buah Rp 40.000 Rp 80.000
8 Exhause Fan 1 Unit Rp 247.900 Rp 247.900
9 Pipa PVC 1/2" 25 Meter Rp 23.300 Rp 582.500
TOTAL Rp 8.781.500
No JENIS PERENCANAAN TOTAL BIAYA
1 Perencanaan Struktural Rp 4.872.000
2 Alat Plambing dan Accessories Rp 4.034.610
3 Perencanaan PLTS dan Kelistrikan Rp 8.781.500
TOTAL Rp 17.688.110
orban bencana alam yang akan di ususlkan:
108
109
110
111
4.7 Perbandingan Desain Toilet Usulan Dengan Toilet Yang Sudah Ada
Perbandingan desain toilet usulan dengan toilet yang sudah ada dimaksudkan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari
desain usulan sehingga hasil tersebut akan menjadi bahan untuk menyempurnakan desain toilet yang akan diusulkan.
Tabel 4. 30 Perbandingan Desain
MODEL TOILET
DIMENSI DIMENSI
112
P 125cm xL 100cm x T 250cm P 100cm xL 160cm x T 247cm
STRUKTURAL STRUKTURAL
MATERIAL/BAHAN MATERIAL/BAHAN
Dinding dan Lantai Fiberglass
ALAT-ALAT PLAMBING (ACCESSORIES) ALAT-ALAT PLAMBING (ACCESSORIES)
Kloset Jongkok FPR
Wastafel
Tanki Septik Tanki Septik Biofilter
Membrane Filter RO (Reverse Osmosis)
SUMBER ENERGI ON-SITE SUMBER ENERGI ON-SITE
- PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
HARGA HARGA
beberapa perbedaan berdasarkan jenis bencananya, namun dalam hal ini akan
dipaparkan beberapa dampak dari bencana alam yang terjadi terhadap kelompok
fungsional sanitasi berdasarkan jenis kelompoknya:
4.1.1 Kelompok Penghubung Pengguna (User Interface)
Kelompok user interface merupakan kelompok yang memiliki fungsi
sebagai alat atau sarana sanitasi yang menghubungkan penguna dengan sarana
sanitasi. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok user interface
adalah sebagai berikut:
a. WC jongkok
b. WC duduk
bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak yang
ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok user interface
secara umum, yakni:
a. Kerusakan Fasilitas
membersihkan fasilitas layanan atau sarana sanitasi jika memungkinkan untuk
digunakan kembali. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan kembali maka
dibuatkan layanan sanitasi darurat atau semantara untuk memenuhi kebutuhan
29
Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi.
4.1.2 Pengumpulan & Penampungan dan/atau Pengolahan Awal
Pengumpulan dan penampungan merupakan tempat dimana limbah yang
dihasilkan oleh sarana sanitasi dikumpulkan atau disatukan kedalam suatu tempat
untuk meminimalisir pencemaran yang ditimbulkan oleh sumber pencemar.
Tujuan dari dikumpulkannya limbah tersebut untuk mencegah sumber atau vektor
penyakit yang menjadi fokus sanitasi mencemari lingkungan dan manusia.
Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengumpulan &
Penampungan dan/atau Pengolahan Awal adalah sebagai berikut:
a. Cubluk
bergantung pada jenis bencannya, sebab tiap jenis bencana alam memiliki
perbedaan efek kerusakan yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan
dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengumpulan & penampungan
dan/atau pengolahan awal secara umum, ialah:
a. Kerusakan Unit/Instalasi
b. Kerusakan Perpipan
d. Unit/Instalasi tertimbun reruntuhan
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan jika masih memungkinkan, agar unit
penampungan dapat dipergunakan kembali. Namun, jika tidak mungkin
dilakukan perbaikan dapat dibuatkan penampungan sementara atau perpipaan
30
sementara untuk menghindari penyebaran vektor penyakit ke lingkungan oleh air
limbah atau limbah tinja.
pengolahan terpusat atau IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan/atau IPLT
(Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). Pendistribusian air limbah menuju IPAL
atau IPLT dapat direncanakan mengunakan sistem perpipaan atau dengan sistem
pengangkutan mengunakan mobil tinja. Berdasarkan fungsinya yang masuk
kedalam kelompok Pengangkutan/Pengaliran adalah sebagai berikut:
a. Perpipipaan Air Limbah.
berbeda-beda bergantung pada jenis bencana alam yang timbul. Adapun dampak
yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok
pengangkutan dan pengaliran awal secara umum, ialah:
a. Kerusakan Perpipaan.
b. Kerusakan Jalan.
perpipaan atau akses jalan untuk pendistribusian air limbah jika memungkinkan
untuk dilakukan, agar tidak menghambat pendistribusian air limbah atau limbah
tinja. Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka membuat jalur
atau akses jalan yang baru menuju pengolahan terpusat, menutup semua sistem
perpipaan untuk sementara waktu hingga kondisinya kembali normal dan
mengalihkan sistem perpipaan ke sistem pengangkutan menggunakan mobil tinja.
31
Pengolahan terpusat atau biasa disebut dengan IPLT atau IPAL merupakan
tempat pengolahan lumpur tinja yang didistribusikan melalui sistem perpipaan
dan pengangkutan dengan mobil tinja. Lumpur tinja perlu dilakukan pengolahan
sebab menurut Niwabaga, 2009 tinja atau limbah tinja memiliki kandungan
nutrien berupa nitrogen, fosfor, kalium, kalisium, carbon yang berasal dari sumber
makanan dan minuman, selain itu tinja juga mengandung logam berat seperti
Tembaga (CU), Zinc (Zn), Nikel (Ni), Cromium (Cr), Kadmium (Cd) dan Hg.
Tinja atau limbah tinja tidak hanya mengandung nutrien dan logam berat saja
namun juga mengandung mikroorganisme seperti bakteri, virus dan protozoa yang
secara alami ada di dalam usus manusia baik itu bersifat patogen atau non patogen
(Keman, 2005). Sehingga diperlukan pengolahan agar air limbah sebelum
dibungan ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan dan manusia.
Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam kelompok Pengolahan Terpusat
adalah sebagai berikut:
Efek kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana alam berbeda-beda sesuai
dengan jenis bencana alam yang ditimbulkan. Adapun dampak yang ditimbulkan
dari kejadian bencana alam berdasarkan kelompok pengolahan terpusat secara
umum, ialah:
akibat bencana alam pada kelompok pengolahan terpusat yakni memperbaiki
unit/instalasi yang mengalami kerusakan atau kegagalan sistem akibat bencana
alam. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan maka yang
dapat dilakukan yakni menutup semua sistem dan memindahkan pengolahan ke
32
sementara air limbah dari daerah terdampak.
4.1.5 Daur Ulang dan/atau Pebuangan Akhir
Pembungan akhir dan daur ulang adalah tahapan akhir dari pengelolaan air
limbah tinja atau lumpur tinja secara umum pembungan akhir air olahan limbah
tinja akan dilapas kebadan air atau kelingkungan. Pembuangan akhir harus
mengikuti ambang batas baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah,
tujuannya agar beban yang diterima oleh lingkungan tidak terlalu besar, sehingga
tidak mencemari lingkungan. Pemanfaatan lumpur tinja dan limbah tinja biasnya
digunakan sebagai pupuk organik. Berdasarkan fungsinya yang masuk kedalam
kelompok Pengolahan Terpusat adalah sebagai berikut:
a. Pemanfaatan sebagai pupuk organik.
b. Pembuangan air limbah ke badan air.
Dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam terhadap kelompok
pembungan akhir dan daur ulang relatif berbeda-beda sesuai dengan jenis bencana
alam yang ditimbulkan. . Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejadian bencana
alam berdasarkan kelompok pembungan akhir dan daur ulang, ialah:
a. Badan air meluap/banjir
c. Lokasi yang terisolir
Rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan
akibat bencana alam pada kelompok pembungan akhir dan daur ulang yakni
memperbaiki sitem pengeringan jika memungkinkan untuk dilakukan, untuk
sistem pembuangan dapat dilakukan penutupan sementara sistem hingga level
muka air di badan air menurun. Namun jika tidak memungkinkan untuk dilakukan
penutupan maka dapat dilakukan pemompaan air olahan ke badan air, untuk daur
ulang dapat membuat dinding pembatas air atau penutup sementara hingga
33
kondisi kembali normal atau mengalihkan proses pengeringan ke IPLT atau IPAL
daerah tetangga.
Peraturan atau regulasi terkait dengan bidang sanitasi di lokasi pengungsian
korban bencana telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1357 Tahun 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan
Masalah Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi yang pada dasarnya
bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan atau penyebaran penyakit
melalui media lingkungan, akibat terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan
lingkungan yang ada di tempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan
kualitas kesehatan lingkungan dan kecukupan air bersih. Pada PERMENKES No.
1357 Tahun 2001 dalam bidang sanitasi mengatur jumlah jamban dan akses
masyarakat, korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dengan
jarak yang tidak jauh dari lokasi pengungsian agar dapat di akses dengan mudah
dan cepat kapan saja diperlukan baik siang atau malam hari. Berikut adalah
beberapa kebijakan sanitasi yang secara khusus mengatur masalah pembuangan
kotoran manusia yang digunakan pada daerah bencana:
a. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang.
b. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut perbedaan jenis
kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki-laki dan jamban
perempuan)
c. Jarak jamban tidak lebih dari 50 m dari pemukiman (rumah atau barak
pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya
memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.
d. Jamban umum tersedia di tempat-tempat seperti pasar, titik-titik pembagian
sembako, pusat-pusat layanan kesehatan dan sebagainya.
e. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang-kurangnya berjarak 30
meter dari sumber air bawah tanah.
34
f. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.
g. Pembuangan limbah cair jamban tidak merembes ke sumber air mana pun,
baik sumur maupun mata air, sungai dan sebagainya (Keputusan Menteri
Kesehatan No. 1357, 2001).
mengatur lebih rinci mengenai teknis toilet yang akan disediakan, sehingga
penyediaan toilet di lokasi pengungsian dapat mengacu pada buku yang disusun
oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yakni Buku Standard Toilet Umum
Indonesia dimana dalam buku tersebut mengatur secar teknis penyediaan toilet
umum. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penyediaan toilet di lokasi
bencana sama halnya dengan penyediaan toilet umum dimana teknis dan
persyaratannya telah diatur.
Persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standartd Toilet
Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut.
Ukuran Reguler
a. Ruang untuk buang air bersar (WC).
Ukuran luas ditentukan oleh posisi buang air besar baik menggunakan kloset
duduk maupun kloset jongkok:
ukuran luas minimum menjadi:
(P x L x T) 80cm x 160cm x 220cm
Ukuran yang disarankan (recommended) adalah
(P x L x T) 90cm x 160cm x 240cm
b. Ruang untuk buang air kecil (Urinoir)
Lebar satuan untuk aktifitas buang air kecil berdiri untuk orang
dewasa minimum 70cm dengan penyekat
Ketinggian urinal minimal 40cm
35
floor standing, atau dibuat langsung diatas lantai.
c. Ruang cuci tangan dan cuci muka (wastafel)
Ukuran dan luas untuk ruang cuci tangan dan muka, minimum adalah:
Lebar 80cm.
Ukuran yang disarankan (recommended) adalah:
Lebar 80cm.
Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di lokasi pengungsian korban
bencana alam ada beberapa tipe atau jenis berikut ini merupakan jenis-jenis toilet
yang biasanya digunakan di lokasi pengungsian korban bencana alam, antara lain:
Toilet Cabin
Toilet Mobil
Toilet Bus
Toilet Portable
Dari beberapa jenis toilet diatas ada dua toilet yang menjadi pembanding
antara jenis-jenis toilet yang sudah ada dengan desain toilet yang akan
direncanakan dimana dalam perencanaan ini toilet yang akan menjadi pembanding
yakni MCK knock down dan Toilet Portable dimana kedua desain ini diambil
sebab dalam perencanaan toilet untuk lokasi pengungsian korban bencana alam
36
kedua desain atau tipe tersebut yang memiliki mobilitas yang tinggi dalam segala
kondisi medan, efektif, efisien, mudah, modern, nyaman dan menjaga privasi
pengguna atau user sehingga dua jenis toliet di atas menjadi pilihan pembanding.
a. MCK Knock Down
MCK knock down merupakan toilet dengan sistem bongkar pasang yang
dapat digunakan bila ada kebutuhan amat mendesak terkait mandi, cuci, kakus
(MCK) di lokasi-lokasi pengungsian. Metode knock down atau yang lebih populer
dengan sebutana sistem bongkar pasang merupakan sistem atau metode yang
paling mudah dan banyak digunakan untuk perakitan. Sistem knock down atau
bongkar pasang ini bertujuan seperti:
Memudahkan dalam mobilitas atau transportasi.
Memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen-
komponen.
Oprasional yang lebih sederhana.
Memudahkan dalam proses penyimpanan.
Struktur terbuat dari bahan atau material pipa baja dan plat baja sebagai
rangka kontruksi MCK knock down dan kain yang berfungsi sebagai dinding
penutup sementara lantainya terbuat dari bahan fiberglass. Umumnya MCK knock
down ini lengkap dengan tangki air dan kloset. Dimensi atau ukuran teknis MCK
knock down ini lebar 80cm, panjang 120cm dan tinggi 200cm. Meskipun sangat
fleksibel dengan berbagai macam kondisi di lokasi pengungsian, dan mudah
dalam proses instlasinya namun toilet dengan sistem knock down ini memiliki
beberapa kelemahan diantaranya sangat mudah mengalami kerusakan pada
dinding dan rangka, selain itu permasalahan-permasalahan seperti kebersihan,
kenyamanan dan privasi pengguna sering sekali muncul dilapangan. Berikut ini
contoh dari penggunaan MCK knock down dilokasi pengungsian.
37
b. Toilet Portabel
Definisi portable menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu
yang mudah untuk dibawa-bawa, dijinjing atau dipindahkan. Sehingga toilet
portabel dapat diartikan sebagai bilik atau ruangan khusus yang di rancang
lengkap untuk mengakomodasi kebutuhan manusia untuk membuang hajat yang
mampu dipindahkan atau dibawa kemana saja tanpa mmembedakan jenis usia dan
jenis kelamin penggunanya.
Penggunaan toilet portable di pengungsian korban bencana alam terbilang
sangat baru karena penggunaan MCK knock down jauh lebih efektif dan flexibel,
namum seiring dengan kebutuhan toilet yang memiliki kontruksi yang lebih kuat
dan nyaman penggunaan toilet portable menjadi alternatif terbaik saat ini.
Kontruksi toilet portable secara umum menggunakan bahan fiberglass yang lebih
kelebihan dari toilet portabel antara lain:
Praktis dalam pengunaan
Tahan lama
Toilet portable lebih praktis jika dibandingkan dengan MCK knock doown
sebab tidak di butuhkan perakitan atau instalasi di lokasi, karena umumnya toilet
porteble telah terinstal sehingga ketika sampai dilokasi dapat langsung digunakan.
Selain itu toilet portable jauh lebih modern sebab penggunaan material fiberglass
menambah estetika yang pada akhirnya akan membuat user atau pengguna
menjadi nyaman, namun dari semua kelebihannya toilet portable ini memiliki
kelemahan dari segi mobilitas walaupun mudah untuk berpindah-pindah tetapi
proses mobilisasi harus menggunakan mobil sehingga untuk lokasi yang memliki
akses jalan atau medan yang sulit tidak dapat dijangkau.
Dimensi teknis atau ukuran toilet potabel umumnya memiliki panjang
120cm lebar 90cm dan tinggi 250cm tetapi dalam beberapa desain ukuran
menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan fasilitas yang dimiliki. Toilet portable
secara umum dilengkapi oleh 1 kloset jongkok atau duduk, kran air, bak air,
lampu, dan floor drain. Bahkan beberapa toilet porteble memiliki sistem
penampungan atau tanki septik dimana tanki septik tersebut memiliki beberapa
metode yakni sistem tertutup dan sistem perpipaan. Sistem tertutup adalah sistem
dimana tangki septik ditutup mengunakan dop setelah kegiatan oprasional
berlangsung tanki septik yang telah penuh oleh limbah disedot melalui saluran
drain yang ditutup oleh dop dan dipindahkan ke kendaraan penyedot limbah.
Sementara itu sistem perpipaan adalah sistem yang menghubungkan antara tanki
septik dengan IPA (Instalasi Penglahan limbah) darurat dimana umumnya tersedia
dilokasi pengungsian atau kesaluran pembuangan yang tersedia sistem ini tidak
memerlukan penyedotan atau pembuangan terpisah yang menghambat jam
oprasional toilet. Berikut ini contoh dari pengunaan toilet portable dilokasi
pengungsian.
39
4.2.3 Varian Teknologi Toilet Bencana Alam
Varian teknologi toilet ditujukan sebagai pertimbangan untuk menentukan
kriteria desain toilet yang sesuai dengan kondisi sanitasi di lokasi pengungsian
korban bencana alam, dimana varian ini merupakan pilihan yang memungkinkan
untuk diaplikasikan kedalam kriteria teknis perencanaan toilet. Beberapa varian
toilet dibawah ini sebenarnya telah direncanakan untuk kondisi bencana dan
keadaan darurat, selain itu beberapa data varian teknologi menjadi alternatif yang
akan dianalisis. Berikut ini beberapa varian teknologi toilet:
a. eSOS® – Emergency Sanitation Operation System
eSOS (Emergency Sanitastion Operation System) merupakan sebuah konsis
sistem oprasional sanitasi darurat, dimana sistem ini menerapkan solusi sanitasi
yang berkelanjutan, holistik dan terjangkau di lokasi pengungsian korban bencana
alam. Tujuan dari perencanaan ini yakni meminimalisir ancaman terhadap
kesehatan masyarakat anggota masyarakat atau pengungsi yang paling rentan.
40
for Water Education. Produk prototipe experimental dari toilet pintar tersebut
dalam proses pengembangannya juga berkerja sama dengan FLEX/ The
Innovation Lab dan SYSTECH yang seluruh kegiatannya didanai oleh Bill and
Melinda Gates foundation. Sistem dari toilet ini terdiri atas tiga komponen utama
yakni toilet cerdas modular, pemantauan dan intelejen managemen dan fasilitas
perawatan untuk aliran limbah.
Gambar 4. 3 eSOS Toilet
Toilet darurat atau eSOS ini memiliki spesifikasi bahan yang kuat dan
ringan material didominasi oleh fiberglaas dan beberapa kayu sebagai penopang
rangka. Toilet eSOS memiliki kecerdasan yang mencakup beberapa fitur-fitur
unik diataranya pemantauan penginderaan jauh, unit pasokan energi, sensor /
kartu GSM / GPS, sensor hunian, sensor akumulasi urin / faeces, tombol SOS, dan
sistem komunikasi yang memungkinkan pengumpulan data dengan penginderaan
jarak jauh dan transfernya ke atau pusat koordinasi darurat di luar lokasi. Fitur
pada toilet tersebut memiliki kemampuan untuk memisahkan limbah padat dan
cair selain itu juga dapat menentukan berat dan volume keduanya data tersebut
dapat langsung terintegrasi dengan sistem pengindraan jauh, sehingga dapat
menentukan waktu yang tepat untuk dilakukan penyedotan limbah. Selain itu
sensor pintar yang di pasang didalam toilet dapat mengurangi resiko pelecehan
seksual dan masalah-masalah privasi pengguna, sebab sensor tersebut mamapu
mengidentifikasi keberadaan lebih dari satu orang dan semua informasi yang
terkumpul dapat langsung diakses jauh dari lokasi pengungsian. Berikut ini adalah
beberapa gambar dari desain eSOS:
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Filipina pada bulan september dengan dukungan dari Bill and Melinda Gates
fondation dan Asian Development Bank, berdasarkan data yang tercatat secara
sistematik lebih dari 1000 kunjungan atau akses terhadap toilet tersebut.
sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Sumber: https://www.flex.nl/en/case/esos-smart-emergency-sanitation/
Science and Technology
The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana
pengembangan ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah layanan sanitasi yang
berkelanjutan dan terjangkau bagi pemukiman kumuh di negara-negara
berpenghasilan rendah.
sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/nairobi-field-test.html
Toilet ini didesain sedemikian rupa sehingga mampu mengolah limbah.
Prinsip kerja treatment pada toilet ini yaitu memisahkan urin dan feses kedalam
wadah yang berbeda, air yang digunakan untuk membersihkan kloset di olah dan
digunakan kembali untuk pembersihan atau flushing setelah mengalami proses
kimiawi. Air yang dihasilkan dari proses pembilasan ditampung pada wadah yang
berbeda dengan urin dan feses, kemudian air dari proses pembilasan tersebut
melewati membran yang dirancang khusus untuk menghilangkan patogen
selanjutnya air yang sudah melewati membran akan diinjeksikan bahan kimia klor
dan dilakukan elektrosis menggunakan tenaga surya.
Toilet Blue Diversion bekerja pada prinsip inti pertama memisahkan urin
dari feses ke dalam wadah yang berbeda. Setelah itu, ditambahkan air yang dapat
digunakan untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan mangkuk toilet. Air
yang sudah kurang terkontaminasi daripada di toilet biasa, kemudian diolah secara
kimiawi dan dialirkan ulang. Proses ini menghentikan pertumbuhan kembali
bakteri yang tidak diinginkan dalam air daur ulang, yaitu kualitas minum. Toilet
membutuhkan total 11,5W energi listrik untuk berfungsi, tetapi energi ini
disediakan oleh panel surya sebesar 60Wp.
Fakta bahwa urin dan feses diambil secara terpisah membuatnya lebih
mudah untuk memprosesnya dan mengubahnya menjadi pupuk dan fosfor. Di
sinilah Blue Diversion Toilet menjadi lebih dari sekedar toilet. Kotoran dan urine
yang dikumpulkan dapat diangkut ke pabrik pemulihan sumber daya di luar
lokasi, di mana mereka diubah menjadi pupuk yang dapat dijual untuk
mendapatkan keuntungaan. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar
yang menjelasakan proses treatment diatas:
45
Berikut ini dimensi atau ukuran teknis Toilet Blue Diversion :
Dimensi: tinggi 190 cm, lebar 74 cm, kedalaman 91 cm. Langkah ke toilet
pan adalah 37cm.
Bahan: tangki dan panci terbuat dari plastik LDPE; stabilisasi terbuat dari
baja
Kebutuhan energi: Energi listrik 11,5W yang disediakan oleh panel surya
60Wp
air, dan elektronik untuk kontrol dan flush
Rentang hidup: 10 tahun
Gambar dibawah ini merupakan tata cara penggunaan Toilet Blue Diversion:
sumber : http://www.bluediversiontoilet.com/uploads/2/4/7/3/24735693/
Gambar 4. 10 Cara Penggunaan Blue Diversion Toilet
c. The Autarky Toilet – Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic
Science and Technology
The Autarky Toilet adalah pengembangan dari Blue Diversion Toilet oleh
Eawag, The Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology dimana
toilet jenis ini memiliki kemampuan untuk memisahkan urin dan feses dan
melakukan treatment langsung ditempat.
Gambar 4. 11 The Autarky Toilet
Toilet ini menggabungkan dua jenis pengolahan urin dengan kode (2A) dan
(2B) dimana pada 2A dilakukan proses kimia biasa disebut dengan metode
stabilisasi urin dimana treatment dilakukan untuk mengurangi nutrisi yang
terkandung dalam urin, toilet yang berisi kapur yang terhidrasi cukup dilarutkan
untuk meningkatkan pH urin sampai 12. Pada pH ini, hidrolisis urea ditekan,
degasifikasi amonia dihindari dan urin distabilkan.
Produk yang dihasilkan pada pengolahan 2A adalah :
Larutan nutrisi fosfor cair, yang membutuhkan pengeringan lebih lanjut dan
menjadi produk akhir pupuk fosfor kering.
Urin stabil yang mengandung semua nutrisi lain Nitrogen (N), Kalium (K),
Sulphur (S). Cairan ini dan dipompa ke bagian atas pipa penguapan di mana
ia memasuki proses pengolahan urin kedua 2B.
Sementara 2B adalah proses pengurangan volume urin dengan metode
evaporasi. Urin yang distabilkan menetes ke sebuah pipa melalui mana udara
ambien ditarik oleh ventilator. Urin dikeringkan, dengan menjenuhkan udara
dengan air. Uap air dilepaskan melalui pipa ventilasi. Produk yang dihasilkan
pada pengolahan 2B adalah kandungan nutrisi kering pada kertas blotting di
dalam pipa dan dipanen sebagai produk akhir pupuk NKS kering.
Untuk feses pengolahan yang dilakukan adalah dengan sistem pengeringan
dan pembakaran didasarkan pada oksidasi hidrotermal (HTO, juga dikenal sebagai
oksidasi air superkritis SCWO). Produk akhirnya adalah air dan padatan yang
diendapkan. Yang terakhir mengandung semua fosfor dari kotoran. Untuk
memanaskan energi proses diperlukan sekali, dapat disediakan oleh generator atau
steker listrik 220V sederhana. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan gambar
yang menjelasakan proses treatment tersebut:
49
d. Bio Toilet - LIPI Project
Bio-Toilet merupakan pengembangan tolet yang digagas Pusat Penelitian
Fisika LIPI, toilet ini diklaim mampu menghemat penggunaan air. Toilet ini
memiliki keunggulan dalam menghemat penggunaan air untuk oprasional, sebab
tidak digunakannya air untuk membilas (flushing) kotoran. Bio-Toilet ini
menerapkan sistem toilet kering dimana limbah yang masuk akan dimanfaatkan
sebagai kompos atau material komposit lainnya.
Toilet ini merupakan alternatif untuk mengurangi pencemaran oleh limbah
domestik yang umumnya dibuang langsung ke lingkungan tanpa mengalami
pengolahan terlebih dahulu, sehingga berpotensi mecemari tanah, air permukaan
maupun air tanah. Toilet ini diklaim mampu menghemat konsumsi air per orang
hingga 40% untuk (BAB) buang air besar dan (BAK) buang air kecil. Penggunaan
Bio-Toilet ini juga akan menekan kasus diare pada daerah dengan kepadatan
penduduk tinggi, atau sarana sanitasi yang tidak memadai.
Bio-Toilet yang dikembangakan oleh LIPI ini tidak menggunakan air untuk
membilas kotoran. Namun, kotoran akan langsung ditampung kedalam tempat
pengolah limbah biasanya mengunakan tabung bio-toilet dengan volume 0,5 m 3
dengan kapasitas 30-50 orang perhari media atau rekator tersebut dilengkapi oleh
alat pengaduk otomatis yang berkerja tiap 15 menit sekali. Setelah dikumpulkan
limbah yang masuk akan dikomposkaan bersamaan dengan serbuk gergaji atau
ligno selulosa dengan cara pengadukan proses pengomposaan ini dilakukan
sekurang-kurangnya 3-5 bulan. Limbah yang telah terurai sempurna dan matang
menjadi produk kompos dapat diambil dan dimanfaatkan sebagai penyubur tanah.
Produk kompos yang dihasilkan mengandung unsur mineral seperti natrium,
kalium dan fosfor serta nitrogen, sehingga apabila diaplikasikan ketanah akan
meningkatkan nilai miniral yang terkandung didalam tanah. Setelah produk
diambil serbuk gergaji atau ligno selulosa dimasukan lagi kedalam media
tampung atau reaktor untuk proses pengomposan limbah yang baru. Berikut ini
gambar skema pengolahan Bio-Toilet :
Bio-Toilet ini didesain dan dipasarkan berupa satu unit ruang kompak
dengan dua buah lubang kloset yang akan digunakan bergantian ketika reaktor
penuh. Pembeli dapat memilih desain ruangan dalam sesuai dengan keinginannya,
termasuk juga kelengkapan aksesoris pendukung oprasional toilet. Bio-Toilet ini
didesain untuk memenuhi kebutuhan layanan sanitasi di daerah terpencil yang
tidak memiliki sistem jaringan sanitasi terpusat.
Pengembangan teknologi ini dilakukan selama lima tahun dan tiga tahun
terakhir LIPI telah melakukan uji coba sosialisasi dan pendekatan masyarakat
hingga toilet ini berhasil di uji coba di tiga lokasi di Bandung yakni Pusat
Penelitian Fisika Terapan LIPI, Pesantren Daarut Tauhid, dan di Stasiun Kiara
Condong.
The Nano Membrane Toilet dikembangkan sebagai toilet yang mampu
mengolah limbah dari kotoran manusia langsung tanpa energi eksternal dan air.
Toilet ini direncanakan untuk penggunaan satu rumah tangga (setara dengan 10
orang), toilet ini menggunakan flush dengan mekanisme berputar yang unik dan
tanpa menggunakan air untuk membilas kotoran, selain itu flush berputar tersebut
memiliki kemampuan untuk menahan bau.
menggunakan membran serat berongga-ronga dengan transisi suhu rendah.
Dinding membran berstruktur nano yang akan memfasilitasi transportasi air dalam
suasana uap hal ini jauh lebih baik ketimbang harus berada dalam suasana cair
dimana air akan berpotensi menimbulkan bau dan senyawa patogen lainnya, air
yang diolah dan dibuang langsung kelingkungan melalui saluran irigasi rumah.
sumber : https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/
Gambar 4. 14 The Nano Membrane Toilet
Sementara itu padatan yang telah terpisah dengan air akan di angkut oleh skrup
mekanis ke dalam ruang bakar yang akan mengubah padatan menjadi abu dan
energi. Energi yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk proses membran. Untuk
lebih jelasnya mengenai proses teratment yang di terapakan dalam teknologi The
Nano Membrane Toilet berikut gambarnya:
https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/
53
sumber:https://www.cranfield.ac.uk/case-studies/research-case-studies/nano-
membrane-toilet
4.3 Penentuan Kriteria Desain
atau acuan dalam merencanakan sesuatu. Penentuan kriteria pada perencanaan ini
akan menggunakan hasil penelitian terdahulu mengenai toilet, dari beberapa
penelitian yang telah dipilih akan dianalisis menggunakan metode AHP (The
Analitycal Hierarchy Process) merupakan metode yang dikembangkan oleh
Thomas Saaty sekitar tahun 1970 dimana metode ini dipergunakan untuk
pengambilan keputusan dimana metode ini akan membantu kerangka berfikir
memasukan nilai numerik sebagai pengganti presepsi manusia dalam melakukan
perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen yang
memiliki prioritas tertinggi.
matriks perbandingan berpasangan, penetapan prioritas pada masing-masing
hirarki dan pengambilan keputusan.
Penyusunan struktur hirarki ditujukan untuk memperjelas kedudukan
tujuan, berbagai kriteria-kriteria serta kemungkinan alternatif pada tingkatan
paling bawah dalam penelitian ini. Penyusunan struktur hirarki dilakukan
dengan cara melakukan studi literatur mengenai varian teknologi toilet yang
memungkinkan untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian
korban bencana alam.
Berikut ini adalah elemen serta struktur hirarki yang telah ditetapkan
berdasarkan studi literatur dan pengumpulan data skunder dan disusun kedalam
tujuan, kriteria dan alternatif.
pengungsian korban bencana.
kriteria teknis maupun non teknis yang bertujuan sebagai pembentuk
desain dimana akan menciptakan suatu tatanan perencanaan yang sesuai
dengan kebutuhan dilokasi pengungsian korban bencana alam. Dalam
perencanaan toilet dilokasi pengungsian digunakan 8 kriteria yang akan
55
kebutuhan dilokasi pengungsian.
m. Kriteria 5 = Kecepatan Waktu Pembangunan
n. Kriteria 6 = Kesesuaian Budaya Sanitasi
o. Kriteria 7 = Ketahanan Cuaca
p. Kriteria 8 = Kualitas Bahan (Kontruksi)
c. Alternatif
untuk diaplikasikan kedalam kondisi dilokasi pengungsian korban
bencana alam.
g. Alternatif 2 = Blue Diversion Toilet – Eawag
h. Alternatif 3 = The Autarky Toilet – Eawag
i. Alternatif 4 = Bio Toilet - LIPI Project
j. Alternatif 5 = The Nano Membrane Toilet - Cranfield University
Berikut ini merupakan susunan struktur hirarki dalam menentukan kriteria desain
yang akan digunakan dalam perencanaan desain toilet dilokasi pengungsian
korban bencana alam pada Gambar 4.16.
56
53
yakni menetapkan perbandingan berpasangan antara kriteria-kriteria berdasarkan
tujuannya, yang berupa matriks. Nilai diagonal matriks tersebut ialah
perbandingan antara satu elemen dengan elemen itu sendiri sehingga
perbandingan tersebut di isi dengan bilangan 1. Sedangkan perbandingan satu
elemen dengan element yang lain diisi dengan bilangan 1-9 sesuai dengan Tabel
3.1 Skala Penilaian Relatif.
Bobot
Kriteria 1 1 1/2 2 3 3 5 5 7
Kriteria 2 2 1 2 3 5 5 5 5
Kriteria 3 1/2 1/2 1 3 3 3 3 5
Kriteria 4 1/3 1/3 1/3 1 2 2 2 3
Kriteria 5 1/3 1/5 1/3 ½ 1 1/2 1/2 3
Kriteria 6 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1 2 3
Kriteria 7 1/5 1/5 1/3 ½ 2 1/2 1 2
Kriteria 8 1/8 1/5 1/5 1/3 1/3 1/3 1/2 1
Setelah terbentuk matriks tahapan selanjutnya matriks di atas dirubah dari bentuk
fraksi kedalam bentuk desimal (Matriks 1):
Tabel 4. 2 Matriks Perbandingan Kriteria (1)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 1,00 0,50 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 7,00
Kriteria 2 2,00 1,00 2,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Kriteria 3 0,50 0,50 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00
Kriteria 4 0,33 0,33 0,33 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00
Kriteria 5 0,33 0,20 0,33 0,50 1,00 0,50 0,50 3,00
Kriteria 6 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 1,00 2,00 3,00
Kriteria 7 0,20 0,20 0,33 0,50 2,00 0,50 1,00 2,00
Kriteria 8 0,13 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,50 1,00
JUMLAH 4,69 3,13 6,53 11,83 18,33 17,33 19,00 29,00
54
mengkuadratkan matriks (1) dengan cara mengalika jumlah baris dengan kolom
atau iterasi 1 atau martriks (2).
A=
Kriteria 1 x Kriteria
= ((1,0 x 1,0)+(0,5 x 2,0)+(2,0 x 0,5)+(3,0 x 0,33)+(3,0 x 0,33)+(5,0 x 0,2)+ (5,0
x 0,2)+(7,0 x 0,13)
Sehingga didapatkan hasil pengkuadratan dari Matriks Perbandingan Kriteria (1)
tersebut adalah Matrik Perbandingan Kriteria (2) seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. 3 Matriks Perbandingan Kriteria (2)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 7,875 7,000 11,733 22,333 42,833 30,833 39,500 69,500
Kriteria 2 10,292 8,000 15,000 27,167 49,667 38,667 47,000 83,000
Kriteria 3 5,825 5,050 8,000 15,167 29,667 21,667 27,000 49,000
Kriteria 4 3,342 2,800 4,600 8,000 16,667 11,333 14,833 27,667
Kriteria 5 1,975 1,700 2,833 5,100 8,000 6,917 8,167 15,000
Kriteria 6 2,575 2,233 3,567 6,200 12,600 8,000 10,500 21,567
Kriteria 7 2,150 1,733 2,867 5,117 9,267 6,667 8,000 17,067
Kriteria 8 1,139 0,907 1,550 2,825 4,975 3,975 4,725 7,875
langkah berikutnya adalah pengkuadaratan bentuk matriks (2) sama dengan
matriks (1) atau iterasi II kemudian keduanya dilakukan penjumlahan dari hasil
55
perkalian silang matriks (1) dan matriks (2). Sehingga didapatkan iks
Perbandingan Kriteria (3) seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 4. 4 Matriks Perbandingan Kriteria (3)
Bobot
Prioritas
Kriteria
1
Kriteria
2
Kriteria
3
Kriteria
4
Kriteria
5
Kriteria
6
Kriteria
7
Kriteria
8
Kriteria 1 605,1 35758,7 59344,8 107857,7 207107,0 144800,1 179356,4 333043,9
Kriteria 2 51290,0 43462,2 72143,1 131106,6 251573,7 176101,5 218125,2 405034,2
Kriteria 3 29537,6 25029,4 41546,0 75501,4 144875,9 101418,6 125625,0 233278,5
Kriteria 4 16346,2 13850,1 22990,6 41778,9 80153,9 56129,0 69527,6 129115,0
Kriteria 5 9431,8 7986,9 13262,7 24097,0 46162,2 32407,7 40142,4 74546,8
Kriteria 6 12394,3 10493,2 17426,7 31659,9 60626,1 42599,3 52772,0 98008,0
Kriteria 7 9840,2 9139,7 14341,3 26839,8 61245,1 29662,1 36747,5 68251,8
Kriteria 8 5312,1 4499,7 7470,6 13574,8 26024,8 18245,8 22600,0 41967,4
Setelah terbentuk matriks perbandingan hingga iterasi ke II maka dapat dihitung
bobot prioritas untuk perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya dengan
cara menjumlahkan hasil perkalian matriks berdasarkan baris.
Kriteria 1
= 1067873,9
dibawah ini:
Perbandingan Matriks Jumlah
Kriteria 1 1067873,85
Kriteria 2 1348836,531
Kriteria 3 776812,5133
Kriteria 4 429891,3293
Kriteria 5 248037,6124
Kriteria 6 325979,3924
Kriteria 7 256067,6217
perbandingan matriks maka tahapan berikutnya menentukan bobot prioritas dari
perbandingan kriteria-kriteria berdasarkan tujuannya. Perhitungan bobot prioritas
dilakuakan dengan cara membagi jumlah hasil perkalian perbandingan matriks
berdasarkan baris dengan total hasil penjumlahan.
Kriteria 1
Menentukan kriteria desain yang
didapatkan bobot prioritas dimana kriteria 2 (kemudahan mobilitas) menjadi
prioritas paling besar dengan bobot 0,294 diikuti berturut-turut kriteria 1
(kebutuhan air) dengan 0,232; kriteria 3 (kebutuhan energi) dengan 0,169; kriteria
57
4 (keamanan dan kenyamanan) dengan 0,094; kriteria 6 (kesesuaian budaya
sanitasi) dengan 0,071; kriteria 7 (ketahanan cuaca) dengan 0,056; kriteria 5
(kecepatan waktu pembangunan) dengan 0,054; dan yang paling akhir kriteria 8
(kualitas bahan) dengan bobot prioritas sebesar 0,030.
Setelah didapatkan masing-masing bobot prioritas dari tiap kriteria
selanjutnya akan dilakukan uji konsistensi. Uji konsistensi bertujuan untuk
mengetahui besaran penyimpangan dari konsistensi atau biasa disebut CI
(Consistency Index) selain uji konsistensi juga akan dilakukan perhitungan Rasio
Konsentrasi (CR) untuk mengetahui apakah metode AHP matriks perbandingan
dapat diterima atau tidak.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,232 x 4,69) + (0,294 x 3,13) + (0,169 x 6,53) + (0,094 x 11,83) +
(0,054 x 18,33) + (0,071 x 17,33) + (0,056 x 19,00) + (0,030 x 29,00)
= 8,34
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 8
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,41 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
58
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
pertimbangan masing-masing kriteria dalam pemilihan desain dengan cara yang
sama atau mengulangi langkah-langkah dalam menentukan bobot prioritas
kriteria.
Tabel 4. 7 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 1
Kriteria 1 Alternatif
Dari hasil perhitungan bobot prioritas alternatif desain dengan perbandingan
masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 1 (kebutuhan air)
dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency Sanitation
Operation System) dengan nilai 0,402; selanjutnya berturut-turut alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,258; alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –
Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield
University) dengan nilai 0,115; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai
0,045.
59
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,402 x 2,5) + (0,180 x 6,667) + (0,258 x 4,167) + (0,045 x 21,0) +
(0,115 x 8,5)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
60
Tabel 4. 8 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 2
Kriteria 2 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 2
(kebutuhan energi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,337; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,235;
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,136; alternatif 5 (The
Nano Membrane Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,147; dan alternatif 4
(Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,145.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,337 x 2,833) + (0,235 x 4,5) + (0,136 x 8,5) + (0,145 x 7,5) +
(0,147 x 7,5)
CI =
61
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 9 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 3
Kriteria 3 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 3
(kemudahan mobilitas) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,370; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,267;
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,200; alternatif 4 (Bio
Toilet-LIPI) dengan nilai 0,104; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -
Cranfield University) dengan nilai 0,060.
62
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,37 x 2,533) + (0,267 x 4,167) + (0,20 x 5,7) + (0,104 x 9,5) +
(0,060 x 16,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
63
Tabel 4. 10 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 4
Kriteria 4 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 4
(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut
alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,271; alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,203; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan
nilai 0,099; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,075.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,352 x 2,66) + (0,271 x 4,16) + (0,203 x 5,66) + (0,099 x 10,5) +
(0,075 x 12,0)
CI =
64
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 11 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 5
Kriteria 5 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 5
(ketahanan cuaca) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,352; selanjutnya berturut-turut
alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,303; alternatif 3 (The
Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,180; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan
nilai 0,091; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,075.
65
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,352 x 2,66) + (0,303 x 4,16) + (0,180 x 5,66) + (0,091 x 12,5) +
(0,071 x 16,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
66
Tabel 4. 12 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 6
Kriteria 6 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 6
(keamanan & kenyamanan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,408; selanjutnya
berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226;
alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,181; alternatif 3 (The Autarky Toilet
– Eawag) dengan nilai 0,124; dan alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet -
Cranfield University) dengan nilai 0,061.
Untuk mengetahui apakah nilai dari matriks dapat diterima atau tidak maka
dilakukan perhitungan CR dan CI atau uji konsistensi bertujuan untuk mengetahui
besaran penyimpangan dari konsistensi.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,408 x 2,367) + (0,226 x 5,33) + (0,124 x 8,33) + (0,181 x 5,83) +
(0,061 x 15,0)
CI =
67
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 13 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 7
Kriteria 7 Alternatif
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 7
(kesesuaian budaya sanitasi) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® –
Emergency Sanitation Operation System) dengan nilai 0,401; selanjutnya
berturut-turut alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,255; alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,192; alternatif 2
(Blue Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,086; dan alternatif 3 (The Autarky
Toilet – Eawag) dengan nilai 0,065.
68
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,401 x 2,4) + (0,86 x 12,5) + (0,065 x 14,0) + (0,192 x 5,667) +
(0,255 x 4,167)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
Tabel 4. 14 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria 8 Alternatif
69
perbandingan masing-masing kriteria, didapatkan bobot prioritas pada kriteria 8
(kualitas bahan) dengan bobot tertinggi yakni alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System) dengan nilai 0,305; selanjutnya berturut-turut
alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan nilai 0,226; alternatif 2 (Blue
Diversion Toilet – Eawag) dengan nilai 0,210; alternatif 5 (The Nano Membrane
Toilet - Cranfield University) dengan nilai 0,176; dan alternatif 4 (Bio Toilet-
LIPI) dengan nilai 0,82.
menjumlahkan hasil perkalian nilai eigen atau bobot prioritas dengan jumlah
perbandingan matriks 1 berdasarkan kolom.
a max = (0,305 x 3,0) + (0,22 x 5,66) + (0,21 x 5,83) + (0,82 x 11,0) + (0,176
x 7,0)
CI =
Perhitungan CR atau Consistency Ratio ditujukan untuk mengetahui apakah
metode AHP matriks dapat diterima atau tidak dalam perhitungan ini n adalah 5
70
sehingga nilai RI (random index) didapatkan 1,12 dari Tabel 3.2 Random Indeks,
sehingga didapatkan nilai CR adalah:
CR =
Hasil perhitungan CR didapatkan ≤ 0,1 artinya nilai matriks adalah bernilai
konsisten.
berdasarkan perbandingan dari masing-masing kriteria penilaian dalam pemilihan
desain toilet yang sesuai dengan kondisi lokasi pengungsian korban bencana alam.
Dengan cara mengalikan bobot prioritas masing-masing desain dengan bobot
prioritas kriteria. Untuk mendapatkan total bobot masing-masing alternatif desain
dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing baris seperti dalam
Tabel 4.14 dan Tabel 4.15
Tabel 4. 15 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 1 0,23 x 0,40 0,23 x 0,18 0,23 x 0,25 0,23 x 0,04 0,23 x0,11
Kriteria 2 0,29 x 0,33 0,29 x 0,23 0,29 x 0,13 0,29 x 0,14 0,29 x 0,15
Kriteria 3 0,16 x 0,37 0,16 x 0,26 0,16 x 0,20 0,16 x 0,10 0,16 x 0,06
Kriteria 4 0,09 x 0,35 0,09 x 0,27 0,09 x 0,20 0,09 x 0,09 0,09 x 0,07
Kriteria 5 0,05 x 0,36 0,05 x 0,30 0,05 x 0,18 0,05 x 0,09 0,05 x 0,07
71
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 6 0,07 x 0,40 0,07 x 0,22 0,07 x 0,12 0,07 x 0,18 0,07 x 0,06
Kriteria 7 0,05 x 0,40 0,05 x 0,08 0,05 x 0,06 0,05 x 0,19 0,05 x 0,25
Kriteria 8 0,03 x 0,30 0,03 x 0,22 0,03 x 0,21 0,03 x 0,08 0,03 x 0,17
Tabel 4. 16 Matriks Perbandingan Alternatif Desain Berdasarkan Kriteria 8
Kriteria
Desain
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Alternatif 4 Alternatif 5
Kriteria 1 0,0935 0,0418 0,0600 0,0104 0,0268
Kriteria 2 0,0691 0,0988 0,0400 0,0426 0,0431
Kriteria 3 0,0626 0,0452 0,0338 0,0175 0,0101
Kriteria 4 0,0329 0,0254 0,0190 0,0093 0,0070
Kriteria 5 0,0192 0,0163 0,0097 0,0049 0,0038
Kriteria 6 0,0290 0,0160 0,0088 0,0128 0,0043
Kriteria 7 0,0224 0,0048 0,0036 0,0107 0,0142
Kriteria 8 0,0093 0,0069 0,0064 0,0025 0,0054
Bobot
Pada Tabel 4.15 dapat dilihat alternatif desain dengan bobot prioritas
tertinggi ada pada alternatif 1(eSOS® – Emergency Sanitation Operation System)
72
dengan nilai 0,338; selanjutnya berturut-turut alternatif 2 (Blue Diversion Toilet –
Eawag) dengan nilai 0,2553; alternatif 3 (The Autarky Toilet – Eawag) dengan
nilai 0,1812; alternatif 5 (The Nano Membrane Toilet - Cranfield University)
dengan nilai 0,1148; dan alternatif 4 (Bio Toilet-LIPI) dengan nilai 0,1108.
Sehingga dapat disimpukan bahwa alternatif desain yang paling berkesesuaian
dengan kriteria-kriteria dalam pemilihan desain toilet yang sesuai dengan kondisi
lokasi pengungsian korban bencana alam adalah alternatif 1 (eSOS® – Emergency
Sanitation Operation System).
4.4 Desain Usulan
toilet bencana alam melalui analisis menggunakan metode AHP selanjutnya akan
direncanakan desain toilet portable, dimana desain ini akan dijadikan sebagai
desain usulan. Desain usulan akan menggabungkan regulasi atau peraturan terkait
dengan toilet dan kriteria desain berdasarkan alternatif terpilih.
4.4.1 Perencanaan Dimensi
Dalam perencanaan ini dimensi toilet direncanakan berdarkan regulasi
terkait dengan toilet umum. Mengingat tidak ada regulasi yang mengatur teknis
toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam, sehingga perencanaan
menggunakan regulasi yang berkaitan dengan toilet untuk menentukan dimensi
toilet portable yang akan direncanakan. Dimana dimensi yang direncakan
mengacu pada persyaratan ruang toilet umum yang diatur dalam Buku Standard
Toilet Umum Indonesia oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana
dimensi toilet yang digunakan adalah:
Panjang = 180 cm
Lebar = 160 cm
Tinggi = 240 cm
bangunan, sehingga jika komponen strutural dihilangkan, maka bangunan akan
mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Secara
umum komponen stuktural dibagi menjadi tiga sistem, yakni : sistem pondasi,
sistem rangka, dan sistem atap.
Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam
menggunakan teknik panel struktural dimana struktural ini menggunakan sistem
knockdown atau bongkar pasang dari komponen-komponen modular yang dicetak
atau dibuat secara fabrikasi (Sabaruddin Arief, 2015). Konsep knockdown
merupakan porses pembangunan atau instalasi yang tidak membutuhkan semen
dan bata, melainkan dengan mengkombinasikan atau menggabungkan panel-panel
baja atau beton dengan baut. Panel struktural dengan konsep knockdown memiliki
keunggulan-keunggulan seperti cepat, murah, ramah lingkungan, tahan gempa,
movabel atau memiliki mobilitas yang tinggi (Sabaruddin Arief, 2015).
Modul toilet portabel yang direncanakan terdiri dari 2 panel struktural (A1
dan A2) dan 1 struktural pengunci atau pengikat. Panel struktural A1 berdimensi
22cm x 22cm x 247cm sementara panel struktur A2 memiliki dimensi 160cm x
100cm x 25 cm ,dan struktur pengunci berbentuk modular dengan dimensi 22,5
cm x 22,5cm x 50cm.
Panel struktur A1 sebagai lengan struktur yang berfungsi sebagai kolom
yang merupakan elemen struktur tekan yang memegang fungsional atau peranan
penting dari suatu struktur bangunan, sehingga kolom dapat diartikan sebagai
lokasi kritis dari suatu bangunan yang memungkinkan terjadinya collapse atau
runtuhnya seluruh struktur. Panel struktur A2 merupakan atap toilet yang juga
berfungsi sebagai balok yang merupakan bagian struktur yang memiliki peranan
pengikat kolom pada bagian atas atau bisa diartikan sebagai rangka penguat
horizontal bangunan akan beban-beban. Struktural pengikat merupakan struktur
pondasi yang memiliki fungsi pengikat kolom pada bagian bawah, meratakan
74
gaya beban dinding ke pondasi dan menahan gaya beban dinding. Berikut ini
adalah tabel spesifikasi panel struktural A1.
Tabel 4. 17 Spesifikasi Panel Struktural A1
Spesifikasi Panel
Panjang 22 cm
Lebar 22 cm
Tinggi 247 cm
Ketebalan 22 cm
Panel Jumlah lubang pada panel 8 lubang pada bagian bawah dan 4
lubang pada bagian atas
Tampilan Fisik
75
Tabel 4. 18 Spesifikasi Panel Struktural A2
Spesifikasi Panel
Panel Jumlah lubang pada panel 16 lubang pada bagian atas
Panel Masing-masing lubang berdiameter 23 mm
Tampilan Fisik Berikut ini tampilan fisik Panel Struktural A1
Berikut ini adalah tabel spesifikasi panel struktural struktural pengikat.
76
Spesifikasi Panel
Panjang 24 cm
Lebar 24 cm
Tinggi 50 cm
Ketebalan 1 cm
Panel Jumlah lubang pada panel 4 lubang pada sisi kanan dan 4
lubang pada sisi kiri
Tampilan Fisik
4.4.3 Perencanaan Material
Perencanaan toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam
akan menggunakan beberapa material, untuk material panel A1 dan A2 material
fiberglass yang dicetak secara fabrikasi sesuai dengan model, desain dan dimensi
yang telah direncanakan.
Material fiberglass dipilih sebab material komposit yang satu ini memiliki
kekuatan yang tidak diragukan lagi, selain itu material ini memiliki bobot yang
ringan dan sangat mudah diaplikasikan kedalam berbagai bentuk desain. Material
fiberglass juga memiliki ketahanan terhadap bahan-bahan kimia selain itu juga
didukung dengan sifatnya yang anti karat menjadikan material ini menjadi pilihan
yang paling tepat digunakan didalam perencanaan toilet portable di lokasi
pengungsian korban bencana alam. Selain pada panel struktural penggunaan
material fiberglass juga digunakan pada bagian lantai dan dinding toilet portable
(Mohan R., 2013).
dicustom sesuai dimensi dan model yang telah direncanakan. Pemilihan material
plat baja ditujukan untuk memperkokoh panel struktural, mengingat struktural
pengikat memiliki fungsi sebagai pengikat kolom pada bagian bawah yang juga
berfungsi sebagai pondasi dari toilet portable ini. Sehingga membutuhkan material
yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang besar.
Material penyusun fiberglass secara umum terdiri dari 11 jenis material
penyusun dimana 6 jenis material penyusun utama dan 5 lainnya merupakan
material yang berfungsi sebagai finishing. Material penyusun tersebut, diantaranya
: erosil, pigmen, resin, katalis, talk, mat, aseton, PVA, mirror, cobalt dan dempul
(M. Schwats, 1984).
alam perencana juga merencanakan jenis alat plambing yang akan digunakan.
Jenis-jenis alat plambing yang digunakan dalam perencanaan toilet ini meliputi
kloset, wastafel (lavatory), dan shower spray.
a. Kloset
Timur. Toilet dengan gaya jongkok pada dasarnya telah berkembang sejak
jaman kuno yang secara umum di gunakan oleh masyarakat Asia, seperti
India, Jepang, China, hingga Anatolia, sehingga masyarakat Asia bisa
menyebut kloset jongkok sebagai toilet dengan “gaya Asia” atau “gaya
Timur” (Genç 2009).
terjadinya pemborosan air dari proses pembilasan tersebut. Terlebih lagi di
lokasi-lokasi pengungsian korban bencana alam yang distribusi air
bersihnya sangat terbatas. Selain itu sistem ini juga lebih efektif dalam
membilas kotoran dan sangat praktis dalam penggunaannya.
79
b. Wastafel (lavatory)
toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam yakni lavatory
yang di customize sesuai dengan kebutuhan pada toilet tersebut.
dalam proses mobilisasi dan instalasi dilapangan, sebab jika menggunakan
wastafel yang ada dipasaran akan menyulitkan dalam proses mobilisasi
dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses isntalasinya.
Untuk itu wastafel didesain kembali untuk memenuhi unsur-unsur di atas.
Wastafel yang direncanakan menggunakan material fiberglass
yang akan difabrikasi, berikut ini adalah tabel spesifikasi dari desain
wastafel yang direncanakan.
Spesifikasi Wastafel (Lavatory)
Accessories 1 Buah kran air berputar
Tampilan Fisik
81
Shower spray digunakan untuk membersihakan atau membilas kotoran
dalam perencanaan ini digunakan shower spray untuk menggantikan
fungsi dari bak air atau ember yang bisa dijadikan tempat menampung air
untuk membilas kotoran. Penggunaan shower spray akan menghemat
tempat sebab toilet portabel ini tidak memiliki ruang yang cukup besar
selain itu penggunaan shower spray juga lebih praktis. Shower spray yang
akan digunakan adalah shower spray TOTO tipe THX20NB.
82
Selain beberapa alat plambing diatas juga direncanakan beberapa aksesoris
tambahan seperti spare paper holder yang digunakan untuk menggantungkan
tissue yang akan digunakan untuk membersihkan atau membilas. Spare paper
holder yang akan digunakan adalah spare paper holder custome.
sumber : https://www.toto.co.id/products/tx722aes
Perencanaan baik air (toren air) yang akan digunakan untuk oprasional toilet
portabel di lokasi pengungsian korban bencana alam diawali dengan menghitung
kebutuhan air bersih dahulu. Dalam perhitungan kebutuhan air akan digunakan
dua metode perhitungan yang pertama berdasarkan jumlah pengguna atau jumlah
orang dan metode kedua dilakukan berdasarkan kebutuhan jenis/alat plambing
yang akan digunakan pada perencanaan toilet portable ini.
a. Perhitungan Kebutuhan Air Berdasarkan Jumlah Pengguna
Berdasarkan PERMENKES No.1357 dalam bidang sanitasi tiap
jamban digunakan paling banyak 20 orang. Selanjutnya kembali
diasumsikan kebutuhan air perorang sebesar 140 l/hari. Sehingga
didapatkan kebutuhan air sebagai berikut.
Q = kebutuhan perorang x jumlah pengguna
= 140 l/hari x 20 orang
= 2800 l/hari
= (100% + 10%) x 2,8 m 3 /hari
= 3,08 m 3 /hari
Qh = Qd/t
Dalam perhitungan kebutuhan air berdasarkan jumlah pemakaian
air dilakukan berdasarkan studi literatur dalam buku karangan Soufyan M.
84
Pemeliharaan Sistem Plambing. Pada tabel 3.13 pemakaian air tiap alat
plambing laju aliran airnya dan ukuran pipa cabang pipa air, halaman 49
didapatkan data perencaan sebagai berikut:
Tabel 4. 21 Pemakaian Air Tiap Alat Plambing
Jenis Alat Plumbing Pemakaian Air Untuk
Penggunaan Satu Kali (Liter)
Bak Cuci Tangan Kecil 3 12-20
Kran Air 3 12-20
Berdasarka data pada tabel 4.16 diatas, maka dapat dihitung kebutuhan air
untuk masing-masing alat plambing dengan perhitungan di bawah ini:
Diasumsikan penggunaan tiap alat plambing tiap jamnya yakni 15 kali
penggunaan, sehingga kebutuhan air perjamnya sebagai berikut:
Kloset = 15L x 15 kali/jam = 225L/jam
Bak Cuci = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam
Kran Air = 3L x 15 kali/jam = 45L/jam
Total penggunaan air tiap jamnya adalah 315 L/jam atau 0,315 m 3 /jam
atau setara dengan 7,56 m 3 /hari.
Dari kedua metode perhitungan kebutuhan air didapatkan hasil
perhitungan kebutuhan air sebesar 3,08 m 3 /hari dengan menggunakan
metode perhitungan berdasarkan jumlah pengguna. Sementara itu
perhitungan kebutuhan air dengan metode perhitungan menggunakan
jumlah pemakaian air tiap alat plambing sebesar 7,56 m 3 /hari. Sehingga
perencana mengambil kesimpulan untuk kebutuhan air pada perencanaan
toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana alam adalah berdasar
perhitungan jumlah pemakaian air tiap alat plambing dengan besaran debit
7,56 m 3 /hari, pengambilan ini berdasarakan faktor aman.
85
menghitung dimensi bak penampung air sebagai berikut.
Diketahui:
= 0,0000875 m 3 /detik
menit atau sama dengan 3600 detik.
Jumlah Bak direncanakan 2
= 0,315 m 3
Bak direncanakan dibagi menjadi 2 bak sehingga volume tiap bak airnya
ialah:
Volume =
= 0,1575 m 3
Direncanakan panjang bak air adalah 20 cm atau 0,2 m dan lebar bak
direncanakan 70 cm atau 0,7, sehingga didapatkan tinggi bak air
didapatkan sebagai berikut:
= 0,2 x 0,7 x t
0,16 = 0,2 x 0,7 x t
t =
Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak
penampung air yakni panjang 0,2 m dengan lebar 0,7 m dan tinggi 1,2 m,
berikut ini merupakan desain dari perencanaan air bersih:
86
Gambar 4. 21 Perencanaan Air Bersih
Pada gambar diatas terdapat dua bak air bersih dimana direncanakan bak
yang satu digunkan untuk membersihkan atau memflushing pan atau kloset,
sementara bak yang satunya lagi akan digunakan untuk mengaliri air ke kran dan
wastafel dan direncakan bak yang akan diisi dengan air daur ulang yakni air
limbah pada bak untuk flushing.
4.4.6 Perencanaan Pengolahan Limbah
Perencanaan pengolahan air limbah dari oprasional toilet di lokasi korban
bencana alam bertujuan untuk meminimalisir pencemaran atau penyebaran
penyakit yang melalui media air. Selain itu pengolahan yang akan dilakukan juga
bertujuan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang air limbah yang
dihasilkan agar dapat dimanfaatkan kembali atau “re-use” untuk membilas
kotoran pada kloset atau pan. Pengolahan yang akan dilakukan merupakan
pengolahan secara fisik dan biologis dimana yang menjadi konsentrasi
pengolahan dalam perencanaan ini adalah air limbah yang dihasilkan, namun
dalam perencanaan ini perencana tidak membahas secara detail terkait pengolahan
tersebut.
87
fungsional sanitasi yang terbagagi kedalam 5 (lima) kelompok, yakni:
Penghubung Pengguna (user interface)
Pengangkutan/Pengaliran
Daur Ulang dan/atau Pemrosesan Akhir
Berikut ini merupakan diagram dari sistem pengolahan yang akan di terapkan
dalam perencanaan desain toilet di lokasi pengungsian korban bencana alam.
Gambar 4. 22 Diagram Perencanaan Pengolahan Limbah
Sebelum menentukan jenis pengolahan yang akan digunakan dalam
perencanaan ini, terlebih dahuluakan dilakukan perhitungan jumlah air limbah
yang dihasilkan dari kegiatan atau oprasional toilet portable di lokasi pengungsian
korban bencana alam.
Qd = 7,56 m 3 /hari
Debit air limbah yang dihasilkan dari kegiatan oprasional yakni sebesar 7,56
m 3 /hari atau setara dengan 0,0000875 m
3 /detik. Setelah ditentukan julah debit air
limbah selanjutnya dilakuakan perhitungan desain unit pengolahan air dimana
pengolahan awal adalah pengolahan fisik dan pengolahan anaerobic filter
pengolahan tersebut direncanakan dalam satu bak penampungan atau septick tank.
Pengolahan mengunakan proses anaerobic dipilih karena kondisi geografis
Indonesia sebagai negara tropis dengan temperatur atmosfer rata-rata tinggi dan
88
stabil, sehingga mikroorganisme anarob bisa hidup secara stabil dan aktif (Tanaka
Nao, 2014).
(Anaerobic Baffled Reakto) yang membedakan AF dengan ABR adalah diisinya
media tempat mikroorganisme dapat melekat/menempel dan tumbuh pada
permukaan media tersebut atau diakomodasi di dalam ruangan yang dibentuk oleh
medianya. Karena pasokan oksigen (O2) yang terbatas menyebabkan mikroba
yang aktif pada sistem ini adalah mikroba jenis anaerobic. Air limbah yang
mengalir akan melewati media tersebut dan sewaktu aliran tersebut mengalir
mikroba akan mengurai bahan organik terlarut dan organik yang terdispersi di
dalam limbah, sehingga hasilnya pengurangan kandungan organik pada efluen
(Takana Nao, 2014).
Dibandingkan dengan ABR sistem AF kontak antara air limbah dengan
mirkoorganisme jauh lebih efisien, sehingga anaerobic filter dapat menerima
organic loading yang lebih tinggi (Takana Nao, 2014). Anaerobic filter
dioprasikan pada waktu detensi 6-24 jam, dengan konsentrasi padatan volatil 4-20
g/L dengan parameter desain utama HRT (Hydraulic Retention Time) adalah > 8
jam, kecepatan aliran 2 m/jam, beban organik 3 kgCOD/m 3 /hari, dan penyisihan
COD 65-90% dan penyisihan BOD 70-95% (Sasse, 1998). Meskipun demikian
lumpur pada kompartemen akan berbeda tergantung pada lingkungan spesifik
senyawa atau zat yang terdegradasi (Barber, 1999). Pada hasil penelitian Singh
tahun 2009 sistem anaerobic filter berfungsi sebagai pengolahan primer dengan
penyisihan BOD mencapai 78%, COD sekitar 77% dan TSS sekitar 91%.
Media yang digunakan untuk tempat melekat mikroba ada beberapa jenis,
tetapi prinsipnya lebih luas permukaannya maka mikroba yang melekat juga akan
lebih banyak, sehingga sistem pengolahan akan lebih efektif. Untuk keperluan
tersebut biasanya media dibuat khusus dari plastik cetak, tetapi juga bisa
bahan/materi lain yang awet dan tidak mudah membusuk seperti batu koral,
89
pecahan keramik, dan lain sebagainya (Takana Nao, 2014). Berikut ini contoh
media yang dapat digunakan sebagai tempat melekat dan tumbuhnya mikroba:
Media tipe “ Sarang Tawon”
limbah cair dan limbah padat, selanjutnya akan dilakukan pengolahan dengan
sistem anaerobic filter mengunakan media sarang tawon sebagai tempat
melekatnya dan berkembang biak mirkroba, sehingga diharapkan mampu
mendegradasi atau meremoval BOD, COD, TSS.
Menghitung dimensi Bak
Qlimbah = 0,0000875 m 3 /detik
Waktu tinggal (HRT) direncanakan 8 jam atau sama dengan 28800 detik
Menghitung Voleme
= 2,52 m 3
Menghitung dimensi
Direncanakan ketinggian bak adalah 100 cm atau 1 m dan panjang bak adalah 180
cm atau 1,8 m sehingga didapatkan lebar bak sebesar:
Vol = P x L x T
2,52 m 3 = 1,8m x L x 1m
l =
Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan dimensi bak penampung air
limbah yakni panjang 1,8 m dengan lebar 1,4 m dan tinggi 1 m. Untuk
memudahkan proses pengendapan akan direncanakan 2 kompartemen dan lantai
bak akan dibuat miring sebesar 30°. berikut ini merupakan desain dari bak
penampung air limbah atau septick tank yang dikombinasikan dengan anaerobic
filter:
91
Selain perencanaan pengolahan pada bak penampung atau septick tank juga
direncanakan juga filterisasi air dengan menggunakan teknologi membran filter
RO (Reverse Osmosis) untuk menghasilkan kualitas air olahan yang baik dan
layak untuk digunakan kembali. Pemilihan membran filter dalam pengolahan
selanjutnya sebab membran filter memiliki efektifitas removal yang sangat tinggi
sehingga kualitas air yang dihasilkan memenuhi baku mutu air yang telah
ditetapkan.
Berdarkan hasil uji efisiensi penghilangan COD, BOD5, SS dan total N rata-
rata di atas 97%. Beban COD yang sangat tinggi yaitu 58.000 ppm seperti pada
limbah sweet whey berhasil diolah dengan bioreaktor membran dengan efisiensi
penghilangan kurang-lebih 98% (Stephenson, T., Judd, S.J., Jefferson, B., and
Brindle, K., 2000).
Sistem RO yang direncanakan untuk skala kecil dengan sistem low pressure
dimana tekanan yang diberikan oleh pompa kurang dari 100 psi dimana pompa
dengan tekanan kurang dari 200 watt (Said I. N., 2003). Berikut ini merupakan
skema sistem reverse osmosis:
sumber:https://airreverseosmosis.files.wordpress.com/2009/02/ro_system.jpg?w=
limbah, sistem RO harus secara berkala dilakukan pembersihan untuk mencegah
terbentuknya kerak dipermukaan membran yang dapat mengakibatkan
penyumbatan atau yang biasa disebut dengan fouling merupakan pristiwa yang
menyebabkan fluks menurun pada filter membran karena bertambahnya hambatan
membran akibat tertutupnya pori-pori membran oleh partikulat (Mallevialle,
1996). Berikut ini adalah desain dari perencanaan RO pada toilet portable di
lokasi pengungsian korban bencana alam.
Gambar 4. 26 Membrane Filter RO (Reverse Osmosis)
kebutuhan energi untuk operasional toilet. Pada perencanaan ini sumber energi
yang direncanakan yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS
merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkkan energi
matahari yang dikonversi menjadi energi listrik dengan memanfaatkan teknologi
photovoltaic. Photovoltaic merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk
menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik, umumnya sel photovoltaic ini
memiliki ukuran 5cm x 5cm. Sel tersebut di rangkai menjadi beberapa susunan
hingga membentuk sebuah panel, panel yang dihasilkan juga disesuaikan dengan
kebutuhana listrik yang diinginkan, panel yang terdiri dari beberapa susunan sel
photovoltaic akan menangkap energi matahari lalu mengubahnya menjadi energi
listrik DC.
d. Panel Surya
semikonduktor yang dapat menyerap photon dari sinar matahari dan
mengubahnya menjadi energi listrik DC dengan mengikuti prinsip
photovoltaic. Pada sollar cell terdapat sambungan (function) yang berada
antara dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yakni
bahan semikonduktor jenis “P” (positif) dan semikonduktor jenis “N”
(negatif). Semikonduktor jenis P merupakan lapisan permikaan yang
dibuat tipis agar cahaya matahari dapat menembus langsung mencapai
junction. Pada bagian semikonduktor P juga dilapisi oleh bahan nikel yang
berbentuk cincin, berfungsi sebagai keluaran positif. Sementara itu
dibawah semikonduktor P terdapat juga bahan semokonduktor N yang
juga dilapisi oleh bahan nikel yang berfungsi sebgai terminnal keluaran
negatif.
95
Baterai berfungsi sebagai alat untuk menyimpan muatan energi
yang di hasilkan oleh solar cell, sehingga ketika sumber energi tidak
tersedia pada malam hari energi cadangan masih tersimpan didalam
baterai. Pada perencanaan pembangkit listrik tenaga surya memilki fungsi
ganda, yaitu sebagai penyimpan energi dan berfungsi sebagai satu daya
dengan tegangan konstan untuk menyuplai beban. Baterai yang sesuai atau
cocok digunakan dalam perencanaan PLTS adalah baterai jenis deep cycle.
f. Battery Charge Controllor (BCR)
BCR merupakan alat yang mengatur pengisisan arus listrik dari
modul sollar cell ke baterai dan sebaliknya. BCR berfungsi pengaturan
kelebihan pengisian baterai dan kelebihan tegangan dari modul sollar cell.
Alat ini bermanfaat juga untuk mengindari full discharge dan overloading
serta memonitor suhu dari baterai. BCR biasanya dilengkapi olej diode
protection yang berfungsi menghidarkan arus DC dari baterai agar tidak
masuk kedalam sollar cell.
direct current (DC) menjadi alternating current (AC) sesuai dengan
kebutuhan peralatan listrik yang digunakan.
e. Kabel Instalasi
memiliki kemampuan untuk mengurangi loss (kehilangan) daya,
pemanasan pada kabel dan kerusakan pada perangkat pembangkit listrik
tenaga surya.
kebutuhan daya listrik untuk operasional toilet portable di lokasi pengungsian
korban bencana alam. Berikut ini merupakan tabel estimasi kebutuhan daya listrik
pada peralatan toilet portable.
Peralatan Jumlah Daya
Total Konsumsi Daya / Hari 1410
Total Konsumsi Daya / Hari + 20% 1692
Dalam perencanaan toilet portable peralatan yang membutuhan daya listrik
yakni : pompa air, exhaust fan dan lampu LED, setelah dilakukan perhitungan
kebutuhan daya listrik untuk ketiga peralatan tersebut didapatkan konsumsi daya
sebesar 1410 Wh. Jumlah total kebutuhan daya per-hari yang didapatkan perlu
ditambahakan 20%, dimana 20% tersebut merupakan kebutuhan daya untuk
peralatan PLTS seperti inverter dan BCR. Sehingga didapatkan kebutuhan total
daya adalah sebesar 1692 Wh.
Untuk mengantisipasi kekurangan sumber daya listrik yang diakibatkan oleh
kondisi cuaca yang mendung atau hujan, maka perencana akan mengalikan total
kebutuhan daya dengan 2 untuk menghindarkan kekurangan daya sehingga
didapatkan total kebutuhan daya sebesar:
Total Wh = Wh x 2
= 1692 x 2
Perhitungan Jumlah Panel Surya
Pada perencanaan ini panel surya yang akan digunakan yakni panel surya
dengan kapasitas 300Wp dengan asumsi penyinaran matahari yang normal
selama 6 jam/hari, maka jumlah panel surya yang dibutuhkan adalah:
Jumlah Panel =
BRC yang akan direncanakan adalah MPPT 20 Ampere, sebab besaran
nilai ISC atau nilai arus maksimum yang dapat dikeluarkan oleh panel
surya/short circuit current pada panel surya adalah 9,46 A. Untuk jumlah panel
surya yang terpakai sebanyak 2 buah dibutuhkan BRC 20 A.
Inverter
Dalam perencanaan toilet portable ini inverter yang akan digunakan adalah
3200 watt pure sine wave 220 V 50 Hz dengan input 48 VDC.
Baterai
Baterai yang akan direncanakan adalah baterai jenis deep cycle 12 Volt
100 Ah. Dalam perencanaan ini inverter yang beroprasi pada tegangan 48 Volt
atau tengangan input untuk jenis inverter 3200 Watt pure sine wave. Sehingga
kebutuhan tegangan input inverter adalah:
Total baterai (voltase) =
Jumlah panel solar yang digunakan adalah 2 buah dengan masing-masing
300 wp dan voltase panel surya adalah 24 volt, sehingga tiap panel surya
membutuhkan baterai:
perencanaan pembangkit listrik tenaga surya adalah:
Jumlah baterai = Jumlah berdasarkan voltase x jumlah berdasarkan kapasitas
= 4 x 1
Gambar 4. 27 Perencanaan PLTS
4.5 BOQ
BOQ (Bill of Quantity) merupakan daftar kuantitas dari semua item yang
direncanakan dalam perencanaan toilet portable di lokasi pengungisan korban
bencana alam. Berikut ini merupakan tabel-tabel yang menjelaskan jumlah item-
item yang dibutuhkan dalam perencanaan:
Tabel 4. 23 BOQ Perencanaan Struktural
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Panel Struktual A1 4 Unit
2 Panel Struktual A2 1 Unit
3 Struktural Pengikat 4 Unit
4 Dinding Toilet 4 Unit
5 Pintu 1 Unit
7 Baut 7/8" x 200mm 48 Buah
8 Mur 7/8" x 30mm 48 Buah
9 Baut 7/8" x 150mm 48 Buah
10 Mur 7/8" x 20mm 48 Buah
99
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Kloset TOTO tipe Customize 1 Unit
2 Wastafel (lavatory) Customize 1 Unit
3 Shower Spray TOTO tipe THX20NB 1 Unit
4 Kran Air 1 Unit
5 Spare Paper Holder Customize 1 Unit
6 Bak Air Customize 2 Unit
7 Bak Penampung Biofilter 1 Unit
8 Filter Membran RO 1 Unit
9 Water Drain 1 Unit
10 Pipa PVC Rucika 3" 2,3 Meter
11 Pipa PVC Rucika 2" 3,2 Meter
12 Pipa PVC Rucika 3/4" 4,7 Meter
13 Fitting TEE (AW) Rucika 2" 2 Buah
14 Fitting TEE (AW) Rucika 3/4" 1 Buah
15 Fitting Elbow (AW) Rucika 3" 3 Buah
16 Fitting Elbow (AW) Rucika 2" 4 Buah
17 Fitting Elbow (AW) Rucika 3/4" 4 Buah
18 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3" 1 Buah
19 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 2" 2 Buah
20 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3/4" 2 Buah
21 Fitting Plug (AW) Rucika 3" 1 Buah
22 Fitting Plug (AW) Rucika 2" 2 Buah
Tabel 4. 25 BOQ Perencanaan PLTS dan Kelistrikan
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan
1 Panel Surya 2 Unit
2 Baterai VRLA 12V 200Ah 4 Unit
3 BCR MPPT 40 A 1 Unit
4 Inverter 3200 W pure sine wave 1 Unit
5 Kabel 25 Meter
6 Soket 1 Buah
9 Pipa PVC 1/2" 5,7 Meter
100
perencanaan toilet portable di lokasi pengungisan korban bencana alam. Berikut
ini merupakan tabel-tabel yang menjelaskan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam
perencanaan:
104
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Panel Struktual A1 4 Unit Rp 120.000 Rp 480.000
2 Panel Struktual A2 1 Unit Rp 504.000 Rp 504.000
3 Struktural Pengikat 4 Unit Rp 200.000 Rp 800.000
4 Dinding Toilet 4 Unit Rp 342.000 Rp 1.368.000
5 Pintu 1 Unit Rp 150.000 Rp 150.000
6 Ventilasi Udara 2 Unit Rp 113.000 Rp 226.000
7 Baut 7/8" x 200mm 48 Buah Rp 8.000 Rp 384.000
8 Mur 7/8" x 30mm 48 Buah Rp 8.000 Rp 384.000
9 Baut 7/8" x 150mm 48 Buah Rp 6.000 Rp 288.000
10 Mur 7/8" x 20mm 48 Buah Rp 6.000 Rp 288.000
TOTAL Rp 4.872.000
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Kloset Customize 1 Unit Rp 540.000 Rp 540.000
2 Wastafel (lavatory) Customize 1 Unit Rp 330.000 Rp 330.000
3 Shower Spray TOTO tipe THX20NB 1 Unit Rp 280.000 Rp 280.000
4 Kran Air (kitchen faucet) 1 Unit Rp 120.000 Rp 120.000
5 Spare Paper Holder Customize 1 Unit Rp 75.000 Rp 75.000
6 Bak Air Customize 2 Unit Rp 167.000 Rp 334.000
7 Bak Penampung Biofilter 1 Unit Rp 200.000 Rp 200.000
8 Filter Membran RO 1 Unit Rp 883.200 Rp 883.200
105
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
9 Water Drain 1 Unit Rp 110.000 Rp 110.000
10 Pipa PVC Rucika 3" 2,3 Meter Rp 195.600 Rp 449.880
11 Pipa PVC Rucika 2" 3,2 Meter Rp 95.200 Rp 304.640
12 Pipa PVC Rucika 3/4" 4,7 Meter Rp 31.700 Rp 148.990
13 Fitting TEE (AW) Rucika 2" 2 Buah Rp 20.200 Rp 40.400
14 Fitting TEE (AW) Rucika 3/4" 1 Buah Rp 3.500 Rp 3.500
15 Fitting Elbow (AW) Rucika 3" 3 Buah Rp 37.900 Rp 113.700
16 Fitting Elbow (AW) Rucika 2" 4 Buah Rp 14.300 Rp 57.200
17 Fitting Elbow (AW) Rucika 3/4" 4 Buah Rp 2.500 Rp 10.000
18 Fitting Plug (AW) Rucika 3" 1 Buah Rp 1.300 Rp 1.300
19 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 2" 2 Buah Rp 9.500 Rp 19.000
20 Fitting Valve Socket (AW) Rucika 3/4" 2 Buah Rp 2.200 Rp 4.400
21 Fitting Clean Out (D) Rucika 3" 1 Buah Rp 9.400 Rp 9.400
22 Fitting Clean Out (D) Rucika 2" 2 Buah Rp -
TOTAL Rp 4.034.610
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
1 Panel Surya 300 Wp 2 Unit Rp 440.000 Rp 880.000
2 Baterai VRLA 12V 100Ah 4 Unit Rp 1.412.000 Rp 5.648.000
3 BCR MPPT 40 A 1 Unit Rp 230.000 Rp 230.000
4 Inverter 3200 W pure sine wave 1 Unit Rp 640.000 Rp 640.000
5 Kabel 25 Meter Rp 11.000 Rp 275.000
6 Soket 1 Buah Rp 35.000 Rp 35.000
106
No Peralatan dan Spesifikasi Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga
7 Lampu LED 2 Buah Rp 40.000 Rp 80.000
8 Exhause Fan 1 Unit Rp 247.900 Rp 247.900
9 Pipa PVC 1/2" 25 Meter Rp 23.300 Rp 582.500
TOTAL Rp 8.781.500
No JENIS PERENCANAAN TOTAL BIAYA
1 Perencanaan Struktural Rp 4.872.000
2 Alat Plambing dan Accessories Rp 4.034.610
3 Perencanaan PLTS dan Kelistrikan Rp 8.781.500
TOTAL Rp 17.688.110
orban bencana alam yang akan di ususlkan:
108
109
110
111
4.7 Perbandingan Desain Toilet Usulan Dengan Toilet Yang Sudah Ada
Perbandingan desain toilet usulan dengan toilet yang sudah ada dimaksudkan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari
desain usulan sehingga hasil tersebut akan menjadi bahan untuk menyempurnakan desain toilet yang akan diusulkan.
Tabel 4. 30 Perbandingan Desain
MODEL TOILET
DIMENSI DIMENSI
112
P 125cm xL 100cm x T 250cm P 100cm xL 160cm x T 247cm
STRUKTURAL STRUKTURAL
MATERIAL/BAHAN MATERIAL/BAHAN
Dinding dan Lantai Fiberglass
ALAT-ALAT PLAMBING (ACCESSORIES) ALAT-ALAT PLAMBING (ACCESSORIES)
Kloset Jongkok FPR
Wastafel
Tanki Septik Tanki Septik Biofilter
Membrane Filter RO (Reverse Osmosis)
SUMBER ENERGI ON-SITE SUMBER ENERGI ON-SITE
- PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
HARGA HARGA