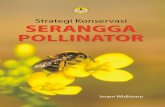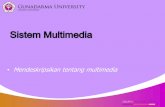BAB I.pdf
-
Upload
lia-medy-tandy -
Category
Documents
-
view
19 -
download
0
Transcript of BAB I.pdf

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Sifat dan Karakteristik Timah
Timah dalam bahasa Inggris disebut sebagai Tin dengan symbol kimia Sn dan nomor atom 50.
Kata “Tin” diambil dari nama Dewa bangsa Etruscan “Tinia”. Nama latin dari timah adalah
“Stannum” dimana kata ini berhubungan dengan kata “stagnum” yang dalam bahasa inggris
bersinonim dengan kata “dripping” yang artinya menjadi cair / basah, penggunaan kata ini
dihubungkan dengan logam timah yang mudah mencair.
Timah atau tin (Sn) adalah logam post-transisi yang berwarna putih mengkilap keperakan dengan
kekerasan yang rendah, dapat ditempa, bersifat fleksibel, memiliki berat jenis sebesar 7.365
g/cm3, serta memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Timah memiliki struktur
kristalin yaitu tetragonal dan bersifat mudah patah jika didinginkan. Timah memiliki titik cair
yang rendah, yaitu 2320C.
Timah juga bersifat tahan terhadap korosi karena tidak mudah teroksidasi dalam udara. Oleh
karena itu, timah banyak digunakan sebagai bahan pelapis pada logam lainnya untuk mencegah
karat. Timah paling banyak digunakan sebagai timah pateri serta paduan logam-logam bantalan
seperti perunggu atau ditambahkan pada paduan tembaga seng (kuningan) untuk memperoleh
ketahanan korosi.
Timah banyak dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari di berbagai industri. Kegunaan logam
timah umumnya adalah sebagai solder (52%), industri plating (16%), untuk bahan dasar kimia
(13%), kuningan dan perunggu (5,5%), industri gelas (2%), dan berbagai macam kegunaan
lainnya seperti cinderamata, pada industri farmasi, gelas, agrokimia, pelindung kayu, dan
penahan kebakaran (lihat Gambar 1.1). Timah merupakan logam ramah lingkungan, penggunaan
untuk kaleng makanan tidak berbahaya terhadap kesehatan manusia.

Gambar 1.1 Kegunaan Timah
Timah merupakan logam dasar dengan tingkat produksi yang rendah, yaitu kurang dari 300.000
ton per tahun, apabila dibandingkan dengan produksi aluminium sebesar 20 juta ton per tahun.
Timah putih merupakan unsur langka, kelimpahan rata-rata pada kerak bumi sekitar 2 ppm,
dibandingkan dengan seng yang mempunyai kadar rata-rata 94 ppm, tembaga 63 ppm dan timah
hitam 12 ppm. Sebagian besar (80%) timah putih dunia dihasilkan dari cebakan letakan (aluvial),
sekitar setengah produksi dunia berasal dari Asia Tenggara. Penggunaan timah untuk paduan
logam telah berlangsung sejak 3.500 tahun sebelum masehi, sebagai logam murni digunakan
sejak 600 tahun sebelum masehi. Kebutuhan timah putih dunia setiap tahun sekitar 360.000 ton.

1.2 Sejarah Pertambangan Timah di Indonesia
Dalam sejarah peradaban manusia, timah putih merupakan salah satu logam yang dikenal dan
digunakan paling awal. Timah digunakan sejak 3.500 tahun sebelum masehi untuk logam
paduan. Sebagai logam murni digunakan sejak 600 tahun sebelum masehi. Sekitar 35 negara
menghasilkan timah putih untuk memenuhi kebutuhan dunia (http://minerals.usgs.gov).
Kegiatan pertambangan timah putih di Indonesia telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu.
Penggunaan timah putih untuk bahan uang koin oleh Kesultanan Palembang telah berlangsung
lama, yaitu dengan diketemukannya koin uang logam timah putih dengan tertera tahun 1091 H.
Uang koin ditemukan terbuat dari timah putih, tertulis Masruf fi Balad Palembang 1091 dan koin
Sultan Fi Balad Palembang 1113. Koin ini dibuat pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman
Khalifatul Mukminin Saidul Iman. Dijumpai beberapa seri koin, ada yang tertulis tahun 13, 113,
dan 1113 dengan bentuk yang sama tapi berbeda cara penulisan tahun.
Sebagian besar uang koin Kesultanan Palembang terbuat dari timah putih. Hal ini karena bahan
baku inilah yang banyak ditemukan di wilayah Kesultanan Palembang, yaitu Bangka dan
Belitung. Koin terbuat dari timah lebih cepat rusak, mudah aus, dan patah (Muhibat, 2007).
Pulau Bangka tidak begitu besar, dekat dengan Sumatera. Nama Bangka dikenal pada abad ke-7,
ketika ditemukan prasasti Kotakapur di muara sungai Mendu, Bangka Barat. Prasasti ini adalah
peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti tertulis kata Vanca, yang berarti timah. Kata
inilah yang kemudian diyakini sebagai asal kata Bangka. Berdasarkan temuan tersebut, para ahli
pertambangan meyakini di Pulau Bangka terdapat deposit timah dalam jumlah besar. Timah
pertama kali ditemukan di Pulau Bangka pada sekitar tahun 1709 melalui penggalian di Sungai
Olin di Kecamatan Toboali oleh orang-orang Johor, Malaysia. Sejak saat itu, maka Pulau Bangka
mulai terkenal sebagai daerah penghasil timah putih (Muhibat, 2007).
Daerah cadangan timah di Indonesia merupakan suatu bentangan wilayah sejauh lebih dari 800
km, disebut sebagai "The Indonesian Tin Belt", yang merupakan bagian dari "The South East
Asia Tin Belt" yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand,
semenanjung Malaysia dan di Indonesia mencakup wilayah Pulau-pulau Karimun, Kundur,
Singkep dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu
Pulau-pulau Bangka, Belitung dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan.

Penambangan timah di Indonesia sudah berlangsung lebih dari 200 tahun, yaitu di Bangka mulai
tahun 1711, di Singkep tahun 1812 dan di Belitung sejak tahun 1852. Dengan kekayaan
cadangan yang melimpah, Indonesia merupakan salah satu negara produsen timah terbesar di
dunia. Pengerjaannya pertama kali dilakukan secara primitif oleh penduduk dengan cara
pendulangan dan mencangkul dengan sistem penggalian sumur Palembang atau sistem
kolong/parit.
Bijih timah yang dihasilkan pada waktu itu dijual kepada pedagang-pedagang yang datang dari
Portugis, Spanyol dan juga dari Belanda. Keadaan ini berubah ketika Belanda datang ke
Indonesia, pada saat mana penggalian timah mulai lebih digiatkan. Sejak tahun 1720 penggalian
timah dilakukan secara besar-besaran dibiayai oleh para pengusaha Belanda yang tergabung
dalam VOC yang kemudian memonopoli dan mengawasi seluruh tambang di Pulau Bangka.
Pada tahun 1816 Pemerintah Belanda mengambil alih tambang-tambang di pulau Bangka dan
dikelola oleh badan yang diberi nama "Bangka Tin Winning Bedrijf" (BTW). Sedangkan di Pulau
Belitung dan Pulau Singkep diserahkan kepada pengusaha swasta Belanda, masing-masing
kepada Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton (Biliton Mij) atau lebih dikenal
dengan nama GMB di Pulau Belitung, dan NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij atau
dikenal dengan nama NV SITEM di Pulau Singkep.
Secara historis penguasaan pertambangan timah di Indonesia dibedakan dalam dua masa
pengelolaan. Yang pertama sebelum tahun 1960 dikenal dengan masa pengelolaan Belanda di
mana Bangka, Belitung dan Singkep merupakan badan usaha yang terpisah dan berdiri sendiri.
Bangka dikelola oleh badan usaha milik Pemerintah Belanda sedangkan Belitung dan Singkep
oleh perusahaan swasta Belanda. Status kepemilikan usaha ini memberikan ciri manajemen dan
organisasi yang berbeda satu dengan yang lain. Ciri perbedaan itu diwujudkan dalam perilaku
organisasi dalam arti luas, baik struktur maupun budaya kerjanya.
Masa yang kedua adalah masa pengelolaan Negara Republik Indonesia. Status berdiri sendiri
dari ketiga wilayah tersebut masih terus berlangsung tetapi dalam bentuk Perusahaan Negara
(PN) berdasarkan Undang-undang No. 19 PRP tahun 1960, yaitu PN Tambang Timah Bangka,
PN Tambang Timah Belitung dan PN Tambang Timah Singkep.

Selanjutnya berdasarkan PP No. 87 tahun 1961 ketiga Perusahaan Negara tersebut
dikoordinasikan oleh Pemerintah dalam bentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang-
tambang Timah Negara (BPU Tambang Timah) dengan pembagian tugas dan wewenang seperti
bentuk "holding company".
Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1968 di mana ketiga PN dan BPU ditambah Proyek
Pabrik Peleburan Timah Mentok dilebur menjadi satu dalam bentuk PN Tambang Timah, yang
terdiri dari Unit Penambangan Timah (UPT) Bangka, Belitung, dan Singkep serta Unit Peleburan
Timah Mentok ( Unit Peltim).
Masa Kolonial
o Bangka Tin Winning Bedrijft (BTW)
o Gemeenschaappelijke Mijnbouw Maatschaappij Billiton (GMB)
o Singkep TIN Exploitatie Maatschappij (SITEM)
Tahun 1953 - 1958
Ketiga perusahaan Belanda tersebut dilebur menjadi tiga perusahaan Negara terpisah yaitu:
o BTW menjadi PN Tambang Timah Bangka
o GMB menjadi PN Tambang Timah Belitung
o SITEM menjadi PN Tambang Timah Singkep
Tahun 1961
Dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Tambang-tambang Timah (BPU PN
Tambang Timah) untuk mengkoordinasikan ketiga perusahaan tersebut.
Tahun 1968
Ketiga perusahaan Negara dan BPU tersebut dilebur menjadi Perusahaan Negara (PN)
Tambang Timah.
Tahun 1976
PN Tambang Timah diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT
Tambang Timah (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia

Tahun 1991 - 1995
PT Tambang Timah (Persero) merestrukturisasi perusahaan yang antara lain adalah relokasi
kantor pusat dari Jakarta ke Pangkalpinang, penglepasan asset yang tidak berkaitan dengan
usaha pokok perusahaan & melakukan ekspor perdana logam timah dengan kadar timbal
yang rendah dengan merek Bangka Low Lead ke Jepang.
Tahun 2003
Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Timah & PT Sarana Karya (SAKA) dalam pengolahan
aspal di Pulau Buton.
Tahun 2006
1) Anak perusahaan PT Timah Tbk, PT Timah Industri mendivestasikan 275.000
sahamnya di Plimsoll Corporation, Pte, Ltd, Singapore kepada Sky Alliance Global
Holding, Ltd.
2) Penghentian pencatatan (listing cancellation) atas Global Depositary Receipts (GDR) di
London Stock Exchange (LSE) dan sejak itu saham perseroan hanya tercatat di Bursa
Efek di Indonesia.
Tahun 2008
PT Timah (Persero) Tbk meresmikan tanur 9 & perluasan pabrik Electrolytic Refining (ER)
yang merupakan proses metamorphosis dr perkembangan industry dan perkembangan timah
dunia yang cukup drastis dari tahun 2003 – 2004.
Tahun 2009
Pada tanggal 17 Januari 2009, Peletakan batu pertama pembangunan pabrik Tin Chemical
sebagai salah satu usaha Perseroan dalam pengembangan produk hilir.
Tahun 2012
1 Februari 2012, terbentuknya INATIN dimana PT Timah dan Anak Perusahaan menjadi
anggotanya

Penambangan timah di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh suatu perusahaan yang memiliki
Izin Usaha Penambangan (IUP) dan wilayah Kuasa Pertambangan (KP). Berikut ditampilkan
perusahaan-perusahan pertambangan timah di Indonesia beserta luas KP yang dimiliki
perusahaan tersebut dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Perusahaan Pertambangan Timah di Indonesia
No Perusahaan Luas KP (Ha) Ket
1 PT Timah, Tbk. 473,800.06 Darat : 330.664,09 Ha
2 PT Koba Tin 42,680.30 Laut : 143.135,97 Ha
3 CV DS Jaya Abadi 50
4 PT Bukit Timah 50
5 PT Bangka Putra Karya 255
6 CV Duta Putra Bangka 100
7 PT Biliton Makmur Lestari 374
8 PT Tinindo Inter Nusa 539
9 CV Donas Kembara 12
10 PT Sumber Jaya Indah 75
11 PT Sari Wiguna Bina Sentosa 121
12 PT Prima Timah Utama 50
13 Yin Chinindo Mining Industry 87
14 PT Mitra Stania Prima -
1.3 Situasi Pertambangan Timah Dunia Tahun 1980-an
Perkembangan penambangan dan pasar timah dunia tidak selamanya berjalan mulus, tetapi juga
terdapat beberapa situasi yang menyebabkan bergejolaknya pasar timah. Situasi industri
pertimahan dunia decade 1980-an dijabarkan sebagai berikut.
Pada periode tahun 1980 - 1985, ketika harga timah dunia mencapai lebih dari US$ 16.000 per
metrik ton, sempat merangsang munculnya produsen-produsen baru memasuki pasaran
internasional yang mengakibatkan stok berlebih. Melambungnya harga timah yang merupakan
"artificial price", tidak lepas dari peran Dewan Timah Internasional atau International Tin
Council (ITC) sebagai "buffer stock manager" pada waktu itu.

Membanjirnya stok di pasaran dunia yang diidentifikasi berasal dari Brasil telah menyebabkan
harga turun drastis, menyusul jatuhnya ITC pada tahun 1985 yang tidak mampu lagi membeli
kelebihan stok mengambang tersebut seperti yang dilakukan sebelumnya agar harga tetap tinggi.
Untuk membandingkan harga timah, dapat ditinjau berdasarkan harga konstan dengan tahun
dasar 1990, di mana diperoleh gambaran bahwa harga berlaku (current price) yang pernah
dicapai sebesar US$ 16.000 pada tahun 1980 tersebut bila dihitung berdasarkan harga konstan
dimaksud sebenarnya bernilai US$ 26.372 pada saat itu.
Kebutuhan timah sebagai komoditi oleh industri di seluruh dunia pada tahun 1989 sebanyak
182.000 ton. Permintaan timah sejak tahun 1981 hanya tumbuh rata-rata 1-2% per tahun,
sedangkan di lain pihak pemasokannya naik rata-rata 6-8% per tahun.
Relatif stabilnya permintaan timah dikarenakan industri hilir pengguna timah seperti pelat timah
(menggunakan 45%), solder (35%), dan kimia timah (16%), tidak tumbuh lagi. Pelat timah,
misalnya, antara tahun 1984 hingga 1988 mengalami penurunan rata-rata 2% per tahun,
sedangkan solder juga tidak tumbuh seiring dengan pertumbuhan industri elektronika karena
teknologi miniaturisasi berkembang luas pada produk-produk elektronika.
Di lain pihak, produksi naik dengan pesat, terutama dalam dekade 1980-an ini karena
ditemukannya tambang-tambang yang sangat kaya dan murah di Brazil. Perkiraan kasar dan
konservatif, kekayaan Brazil adalah 10 kali kekayaan timah Indonesia. Produksi Brazil pada
tahun 1989 adalah sebesar 50.100 ton sementara pada tahun 1980 baru hanya sebesar 6.900 ton.
Perkembangan terakhir adalah masuknya Portugal sebagai negara produsen timah dalam tahun
1990, akan tetapi karena timah merupakan hasil samping dari produksi tambang tembaga maka
biaya produksinya dinilai rendah. Sampai dengan bulan Juni 1989 produksi Portugal adalah
1.500 ton, namun diperkirakan mereka menghasilkan sekitar 6.000 ton per tahunnya. Dua negara
tersebut memberi pengaruh besar pada sisi penawaran timah dunia, sedangkan produsen
tradisional seperti Malaysia, Thailand, Australia, RRC dan Bolivia tetap konstan saja.
Situasi ini mengakibatkan adanya kelebihan pasok sebesar 43.000 ton atau 22% dari kebutuhan
dunia, sehingga membuat harga timah dunia selalu dalam keadaan labil dan cenderung menurun.
Di samping itu, terdapat pula adanya 170.000 ton logam timah di tangan Pemerintah Amerika
Serikat (Defence Logistic Agency) yang setiap tahun dilepas sebanyak 7.000 ton.

Dengan keadaan yang tidak menggembirakan tersebut membuat Asosiasi Negara Produsen
Timah Dunia (Association of Tin Producing Countries, disingkat ATPC ) mencoba
mengendalikan keadaan ini sejak bulan Maret 1987 dengan menerapkan kuota produksi bagi
negara-negara anggotanya (yang dikenal dengan istilah Supply Rationalization Scheme,
disingkat SRS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat persediaan logam timah di pasar dunia
pada tingkat 20.000 ton. Namun upaya tersebut tidak menunjukkan hasil sebagaimana
diharapkan. Pada tanggal 1 Maret 1989 cadangan logam timah berada pada tingkat 31.000 ton,
namun pada tanggal 1 Maret 1990 naik menjadi 43.000 ton, dan pada akhir Juni 1990
diperkirakan 46.000 ton. ATPC sulit menjalankan fungsinya karena Brazil dan RRC tidak
menjadi anggota ATPC.
Dampak dari keseluruhan perkembangan ini adalah menurunnya harga timah secara berlanjut.
Harga timah rata-rata di pasar logam London dalam tahun 1990 adalah US$ 6.100 per ton,
bahkan pada hari Selasa 10 Juli 1990 berada pada tingkat US$ 5.955 per ton, terrendah dalam
tahun 1990 mendekati harga saat kritis timah tahun 1986 yakni US$ 5.300.
Keadaan kelebihan produksi timah ini tidak menguntungkan siapapun kecuali Brazil, RRC, dan
Portugal karena biaya produksi mereka masih cukup jauh di bawah tingkat harga tersebut. Timah
Brazil dihasilkan oleh 3 perusahaan (41%) dan penambang liar (59%). Perusahaan-perusahaan
tersebut menghasilkan timah dengan biaya produksi sekitar USD 5.500 per ton dan saat itu
sedang melakukan upaya efisiensi dan restrukturisasi untuk menekan biaya produksi menjadi
USD 4.100 dalam jangka 3 tahun, karena mereka juga terancam oleh penambang liar yang biaya
produksinya hanya sekitar USD 3.000 per ton dan RRC yang biaya produksinya sekitar USD
5.000 per ton.
Keadaan yang bersifat mendasar ini juga telah mengakibatkan tutupnya tambang-tambang timah
di Inggris, 30% tambang tutup di Thailand, 20% di Malaysia dan dengan harga serendah saat itu
setiap bulan rata-rata sekitar 10 tambang tutup.