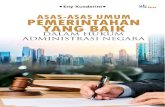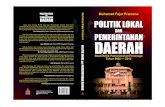BAB III Tipe Pemerintahan Lokal Dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
-
Upload
sunu-d-wibiakso -
Category
Documents
-
view
83 -
download
2
description
Transcript of BAB III Tipe Pemerintahan Lokal Dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia
BAB IIITipologi Pemerintahan Lokal dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Deskripsi Pokok Bahasan :Pemerintahan lokal di berbagai negara memiliki berbagai jenis tipologi, tergantung kepada struktur pemerintahan dan pembagian wilayah dari masing-masing negara. Namun, secara umum terdapat dua tipe pemerintahan daerah.
Tujuan instruksional umum:1. Mahasiswa dapat menjelaskan tipe-tipe pemerintahan lokal.2. Mahasiswa dapat menjelaskan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
A. Tipologi Pemerintahan DaerahPemerintahan daerah yang diselenggarakan menurut asas dekonsentrasi dan desentralisasi terdapat dua tipe, yaitu:1. Sistem Fungsional (Functional System)Menurut sistem fungsional, dalam rangka dekonsentrasi setiap departemen menempatkan kepala-kepala instansi vertikal di wilayah administrasi untuk memberikan pelayanan umum di bidangnya (sektoral) secara fungsional. Menteri/ pejabat pusat menetapkan suatu wilayah kerja pejabatnya di daerah dengan penentuan batas-batas yang didasarkan atas kriteria sesuai dengan keperluan department yang bersangkutan, seperti pembagian beban tugas, jenjang pengawasan, dan efisiensi administrasi untuk pemberian pelayanan umum. Dengan demikian, maka setiap kepala instalasi vertikal mempunyai wilayah kerja (jurisdiksi) dengan batas masing-masing.Dalam sistem fungsional keberadaan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi batas-batasnya juga tidak harus sama dengan wilayah kerja kepala-kepala instansi vertikal. Daerah otonom mempunyai batas-batas sendiri. Batas-batas daerah otonom tidak perlu mengikuti salah satu batas-batas wilayah kerja kepala-kepala instansi vertikal. Dengan demikian, batas daerah otonom tidak harus sama dengan batas wilayah kerja kepala instansi vertikal di daerahnya.Karena setiap departmen mempunyai wilayah kerja (jurisdiksi) dengan batas masing-masing di wilayah Negara, maka bisa terjadi perbedaan batas wilayah kerja (jurisdiksi) antara satu department dengan department lainnya. Misalnya, Kanwil Departemen Perhubungan wilayah kerjanya bisa tidak sama dengan Kanwil Departemen Pertanian.Dalam sistem fungsional, pada wilayah negara tidak terdapat wilayah administrasi yang dipimpin oleh seorang kepala wilayah administrasi seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan lurah. Yang ada hanyalah wilayah kerja (jurisdiksi) kepala-kepala instansi vertikal yang dipimpin oleh masing-masing kepalanya. Oleh karena itu, sistem ini seringkali menimbulkan masalah koordinasi horizontal. Untuk mengatasi masalah ini maka koordinasi di tingkat daerah dilakukan apabila dipandang perlu melalui pembentukan panitia antar departemen yang bersifat sementara.Tipe ini memperlihatkan keterpisahan antara departemen dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada wilayah kerja pejabatnya di daerah. Oleh karena itu, tipe ini dikenal dengan fragmented field administration, wilayah administrasi yang terfragmentasi. Dalam fragmented field administration wilayah jurisdiki pemerintahan daerah tidak terlalu berimpit atau mengikuti wilayah jurisdiki instansi vertikal. Karena itu, dalam model ini dimungkinkan membentuk local special purpose respresentative government seperti school district dan sanitary district. Model ini umumnya diatur negara-negara yang dipengaruhi oleh sistem fungsional, karena lebih mengutamakan fungsi pelayanan yag bersifat sektoral.
2. Sistem Prefektur (Prefectoral System)Jika dalam sistem fungsional wilayah nasional dibagi ke dalam fungsi-fungsi pelayanan department secara terfragmentasi, maka dalam sistem prefektur, teoriti nasional dibagi ke dalam wilayah administrasi dan atau daerah otonom dengan batas juridikasi yang sama dengan sebutan yang sama pula. Misalnya, Provinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kota, Daerah Tingkat II, dan Kecamatan/Kota administratif. Provinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan/Kota administratif merujuk pada pengertian wilayah administrasi (local state government) sedangkan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II menunjuk pada pengertian daerah otonom (local self government).Dalam sistem prefektur, pada wilayah administrasi yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi, ditempatkan seorang wakil pemerintah pusat yang bertaggung jawab kepada Pemerintah Pusat di bawah pembinaan Mentri Dalam Negeri. Misalnya gubernur, bupati/walikotamadya, camat/walikota administratif. Wakil pemerintah pusat tersebut menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat menyelenggarakan pemerintahan umum, mengakkan hukum dan menjaga ketertiban umum, mengawasi semua kegitan yang dilakukan oleh instansi vertikal dari setiap departemen dengan batas wilayah kerja (jurisdiksinya) sama dengan wilayah administrasi. Dengan demikian, batas wilayah kerja (jurisdiksi) kepala instansi vertikal berimpit dengan batas wilayah administrasi.Sementara itu, dalam teoriti yang sama juga dibentuk daerah otonom berdasarkan asas desentraliasi. Daerah otonom tersebut diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang penyelenggaraanya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik merupakan urusan masyarakat setempat (bersifat lokalitas) dan bertanggung jawab pada masyarakat setempat.Jika sistem prefektur dijalankan berdasarkan asas dekonsetrasi dan asas desentralisasi secara terpisah, maka ia disebut sistem prefektur tak terintegrasi (unintegrated prefectoral system). Pada sistem ini dalam teritori nasional terdapt satu prefektur yang di dalamnya terdapat lembaga yang di atur berdasarkan asas dekonsetrasi dan asas desentralisasi. Asas dekonsentrasi melahirkan wilayah administrasi sedangkan desentralisasi melahirkan daerah otonom. Menurut sistem ini, dalam satu prefektur terdapat: 1) wilayah administrasi yang dipimpin oleh pejabat sebagai wakil pemerintah pusat, 2) wilayah kerja instansi vertikal yang dipimpin oleh kepala instansi vertikal, 3) daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah otonom. Masing-masing pejabat menjalankan fungsinya sendiri-sendiri dan terpisah. Oleh karena itu, sistem ini disebut juga dualisme personal: fungsi-fungsi diberikan kepada figur yang berbeda. Dengan sistem ini dimungkinkan terbentuknya local special purpose government baik dengan perwakilan maupun tanpa perwakilan. Misal pada zaman Belanda di daerah setingkat kabupaten terdapat kepala daerah otonomi, yaitu bupati, kepala wilayah administrasi, yaitu Controluer, dan kepala-kepala instansi vertikal. Baik bupati, Controluer, maupaun kepala-kepala instansi vertikal menjalankan fungsinya secara sendiri-sendiri dan terpisah. Saat ini sistem ini dianut oleh Italia.Sebaliknya jika sistem prefektur tersebut dijalankan dalam bentuk terintegrasi antara asas desentralisasi (daerah otonom/local self government) dan dekonsentrasi (wilayah administrasi/local state government) maka ia disebut sistem prefektur terintegrasi (integrated prefectoral system). Sistem ini dianut oleh Perancis. Disebut terintegrasi karena pertama, dilihat dari elemen wilayah, batas pelayanan antara wilayah administrasi (local state government), wilayah kerja kepala- kepala instansi vertikal, dan batas geografis daerah otonom (local self government/local general purpose respresentative government) adalah berimpit, kedua dilihat dari elemen jabatan, pejabat yang mengepalai wilayah administrasi dan daerah otonom adalah sama yaitu melekat pada satu orang. Karena itu, dalam sistem prefektur terintegrasi, kepala wilayah administrasi dan kepala daerah otonom dijabat oleh satu orang denagn peran ganda (dualisme fungsional). Maksudnya pejabat tersebut merangkap dua status: sebagai wakil pemerintah pusat dan kedua sebagai kepala daerah otonom.Sistem pemerintahan di negara kita berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 jo No. 32 Tahun 2004 menganut sistem prefektur terintegrasi pada tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi, gubernur adalah kepala daerah otonom provinsi, sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi yang dipimpinnya (Rahmat Salam, 2002). Sedangkan sistem pemerintahan daerah zaman Orde Baru berdasarkan UU No.5/1974 menganut sistem prefektur terintegrasi pada tingkat kabupaten/kotamadya. Berdasarkan UU No.5/1974, wilayah administrasi berimpit dengan wilayah otonom tingkat I dan wilayah administrasi kabupaten/kotamadya berimpit dengan wilayah otonom tingkat II.
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahSentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi adalah konsep-konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi negara. Menurut M. Faltas tedapat dua kategori dalam pengambilan keputusan : 1) Keputusan politik/political authority yaitu decisions that are allocative, the commit public values, the coercive power of govermental regulation and other public values, to authoritatively chosen ends, dan 2) Keputusan administratif/administrative authority yaitu decisions of implementation about now and where resources have to be used, who would qualify for services resulting from the allocation and whether the allocated recources have been properly used.
Berkenaan dengan pengertian tersebut maka keputusan politik sering disebut juga dengan keputusan alokasi sedangkan keputusan administratif sering pula disebut dengan keputusan pelaksanaan.Dua jenis pengambilan keputusan tersebut dalam struktur organisasi dapat bervariasi :1. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan dilakukan pada puncak hirarki secara terpusat. Inilah yang disebut dengan sentralisasi penuh.2. Keputusan alokasi diambil pada puncak organisasi sedangkan keputusan pelaksanaan dilakukan pada jenjang-jenjang yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan dekonsentrasi.3. Keputusan alokasi dan keputusan pelaksanaan semuanya diserahkan sepenuhnya pada jenjang-jenjang organisasi yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan desentralisasiJHA Logemann menyebut butir 2 dan 3 sebagai desentralisasi. Logemann memasukkan dekonsentrasi dalam desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi mempunyai arti yang luas. Logemann membagi desentralisasi menjadi dua macam1. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (ambtelijke decentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya pelimpahan dari menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentrlisasi semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa.2. Desentralisasi ketatanegaraan atau staatkundige decentralisatie yang sering juga disebur sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (regelende en bestuurende bevoerheid) kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik semacsm ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing. Desentralisasi ini dibedakan menjadi dua.a. Desentralisasi teritorial (territoriale decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (autonomic), batas pengeluarannya adalah daerah. Desentralisasi territorial mengakibatkan adanya otonomi pada daerah yang menerima penyerahan.b. Desentralisasi fungsional (funcionale desentralisatie) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsiBayu Surianingrat (1980;28-29) membagi desentralisasi atas :1) Desentralisasi jabatan (ambtelijke decentralisatie), yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepat pemlimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu desentralisasi ini disebut juga dekonsentrasi2) Desentralisasi kenegaraan (statkundige decentralisatie), yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (participation) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.Ahli lain yaitu A.H Manson membagi desentralisasi menjadi dua yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif/birokrasi. Desentralisasi politik disebut juga dengan devolusi sedangkan desentralisasi administratif disebut juga dengan dekonsentrasi.James W.F menjelaskanDecentralization in French usage is a term reserved for the transfer of powers from a central government to an really or functionally specializer authority of distinct legal personality, deconcentration on the other hand, is the French equivalent for administrative decentralization (or political decentralization) involves the delegation of political authority, through which political institutions can be created with the right to make ploticies for local areas. Deconcentralization (or administrative bureaucratie authority, on the other hand, involves the delegation of bureaucratie authority, that is, the delegation of responsibility.
The local government is operated through political authority and by institutions within an area defined by community characteristics, a system of devolution (or federalism) can be said to exist on the other hand, service defined areas, bureaucratic authority, and field personnel produce only field administration or deconcentration.
Baik desentralisasi maupun dekonsentrasi merupakan instrumen dalam bidang division of power. Maksudnya dua konsep tersebut merupakan konsep administrasi, yaitu bagaimana proses-proses kegiatan untuk mencapai tujuan dilaksanakan dalam organisasi dan manajemen. Dengan demikian menjadi jelas bahwa baik dekonsentrasi maupun desentralisasi bermula dari sentralisasi dalam organisasi. Oleh karena itu, konsep sentralisasi dan desentralisasi bukanlah konsep yang dikotomis, tapi satu rangkaian kesatuan (kontinum). Dalam organisasi negara, tak ada yang sepenuhnya sentralisasi atau sepenuhnya desentralisasi. Karena implemenstasi dari dua konsep tersebut tetap dalam lingkup satu organisasi.Istilah desentralisasi dan dekonsentrasi digunakan sesuai dengan konteks kajiannya. Sebagai gambaranya perhatikan tabel berikut:Tabel :Penggunaan istilah Desentralisasi dan DekonsentrasiTerm Associated withDeconcentrationDecentralization
Organizing principleDeconcentration (French writer) Dconcentration (UN Report) Bureaucratic Decentralization Administrative DecentralizationDeconcentration (French writer) Devolution (UN Report) Democratic Decentralization Political Decentralization
Structure in which the principle dominatesField Administration Regional Administration Prefectoral AdministrationLocal GovernmentLocal Self GovernmentMunicipal Administration
PracticeDelegation of PowerDevolution of Power
Dalam konteks negara Indonesia, negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Karena itu, pada dasarnya system pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau pengahalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan dan memluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sitem administrasi negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui Undang-Undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam system administrasi pemerintahnya.Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah Penjelasan UUD 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat Staat, Negara. Dalam negara kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintah lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh R. Kranenburg sebagai pouvoir constituent, kekuasaan untuk membentuk UUD/UU dan organisasinya sendiri. Hal inilah yang membedakan negara kesatuan dengan negara federal. Negara federal adalah negara majemuk sehingga masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan membentuk UUD/UU. Sedangkan negara kesatuan adalah negara tunggal (Bhenyamin Hoessein, 2002).Pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintaha daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam negara federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah dependent dan sub-ordinat sedangkan hubungan negara bagian dengan negara federal/pusat dalam negara federal adalah independent dan koordinatif.Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintahan daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat (desentralisasi/devolusi).Berdasarkan konsepsi demikian, pada dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah hakekatnya tidak mempunyai kewenangan pemerintahan. Pemerintahan daerah baru mempunyai kewenangan pemerintahan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat (desentralisasi/devolusi).Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam system negara kesatuan ini melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan (politik dan administrasi) pada pemerintah pusat. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daeraf dan/atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi.Kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri (pemerintah pusat) tadi adalah kewenangan pemerintahan, bukan kewenangan lain (legislatif dan judikatif). Kewenangan pemerintahan terdiri atas dua jenis: kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan sedangkan kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan.Dalam sentralisasi semua kewenangan tersebut baik politik maupun administrasi berada ditangan presiden dan apata menteri (pemerintah pusat). Atau dengan kata lain berada pada puncak jenjang organisasi. Sebagai konsekuensinya dalam melaksanakan kewenangan ini anggarannya dibebankan pada APBN.Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu De yang berarti lepas dan Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan denikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat.Sebagaimana telah dijelaskan di depan, desentralisasi berkaitan dengan aspek administrasi. Perlu diingat bahwa salah satu bagian penting dari administrasi adalah organisasi. Sebuah organisasi selalu terdiri atas jenjang hirarki. Jenjang hirarki ini ada yang tingkatannya banyak dan ada yang tingkatannya sedikit. Misalnya, satuan pemerintahan yang terdiri atas Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II, dan Pemerintahan Daerah Tingkat III, adalah contoh organisasi pemerintahan dengan jenjang hirarki yang lebih panjang dari satuan pemerintahan yang terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya/Daerah Tingkat II, dan Pemerintahan Wilayah Kecamatan lebih panjang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada setiap jenjang hirarki terdapat penjabat yang bertanggung jawab atas satuan organisasi yang menjadi wewenangnya. Misal pada pemerintah provinsi terdapat gubernur, pada pemerintah kabupaten terdapat buapati dan pada pemerintah kota terdapat walikota. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah provinsi. Bupat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Dan walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan kota.Organisasi yang besar dan kompleks seperti Negara Indonesia tak akan efisien jika semua kewenangan politik dan administrasi diletakkan pada puncak.hirarji organisasi/pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat. Juga tidak cukup jika hanya dilimpahkan secara dekonsentratif kepada para pejabatnya di beberapa wilayah negara. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel, maka sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut desentralisasi. Jadi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi dari puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah daerah). Dua kewenangan tersebut (politik dan administrasi) diserahkan kepada pemerintah daerah.Karena jenjang hirarki yang lebih rendah (pemerintah daerah) tersebut diserahi wewenang penuh, baik politik maupun administrasi, maka pada jenjang organisasi yang diberi penyerahan wewenang tersebut timbul otonomi. Otonomi artinya kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat local, bukan yang bersifat nasional. Karena itu., desentralisasi menimbulkan otonomi daerah, yaitu kebebasan masyarakat yang tinggal di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya yang bersifat local. Jadi, otonomi daerah adalah konsekuensi logis penerapan asas desentralisasi pada pemerintah daerah.
a. DesentralisasiHenry Maddick (1963) menjelaskan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang/fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom. Sedangkan Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983) mengemukakan, desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan, baik keuangan maupun hukum, pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada di luar kontrol langsung pemerintah pusat.Parsons (1961) mendefinisikan desentralisasi sebagai berbagi (sharing) kekuasaan pemerintahan antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, dimana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Sementara itu, dekonsentrasi menurut Parsons adalah berbagi kekuasaan (sharing of power) di antara kelompok elite penguasa (ruling group) yang sama untuk kemudian mendapatkan otoritas dalam mengatur bidang-bidang tertentu berdasarkan wilayah pemerintahan yang ada.Dengan merajuk pada formulasi definisi seperti dikemukakan oleh Parson di atas, Mawhood (1987) kemudian dengan tegas mengatakaan desentralisasi adalah penyerahan (devolution) kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu, dekonsentrasi, yang dalam pengertian Mawhood adalah desentralisasi administrasi, merupakan pemindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Smith (1985) juga merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkatan [organisasi] lebih ke atas ke tingkatan terendah, dalam suatu hierarki teritorial, yang dapat saja berlaku pada organisasi pemerintah dalam suatu negara, maupun pada organisasi-organisasi besar lainnya [organisasi non pemerintah]. Sekali lagi, Smith terlihat dengan jelas telah memberikan tekanan khusus pada aspek penyerahan kekuasaan sebagai isu sentral dalam desentralisasi.Sedikit berbeda dengan para ilmuwan lainnya, Rondinelli dan Cheema (1983) merumuskan definisi desntralisasi dengan lebih didasarkan pada perspektif administrasi. Dalam buku mereka yang berjudul Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries, dinyatakan secara jelas bahwa desentralisasi adalah penyerahan (wewenang) perencanaan, pengambilan keputusan, dan/atau wewenang administratif (administrative authorities) dari pemerintah pusat kepada: pemerintah daerah, oragnisasi-organisasi vertikal pemerintah pusat di daerah (field organizations); unit-unit pelaksana administratif daerah; organisasi-organisasi semi otonom; dan/atau organisasi non pemerintah (1983:18)Berdasarkan definisi ini, Rondinelli dan Cheema, kemudian merumuskan sedikitnya ada empat bentuk desentralisasi, yaitu: pertama, dekonsentrasi yang berarti redistribusi tanggung jawab administratif di lingkungan pemerintah pusat, kedua, pendelegasian kepada organisasi-organisasi semi otonom atau parastatal (semi autonomous, or parastatal organistatations), yang berarti pendelegasian otoritas dalam pengambilan keputusan dan dalam pengelolaan fungsi-fungsi tertentu [spesifik] dimana tidak langsung di bawah kontrol kementrian pemerintah pusat, ketiga, devolusi, dalam arti penyerahan fungsi dan otoritas dari pemerintah pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Bentuk desentralisasi yang terakhir adalah penyerahan fungsi tertentu [urusa tertentu] dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga non pemerintah. Penyerahan fungsi yang dimaksud adalah_penyerahan beberapa tanggung jawab dalam perencanaan administratif, atau bahkan, beberapa fungsi pelayanan publik_dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi sukarela (voluntary organistations), pihak swasta (private organizations), atau dalam beberapa kasus tertentu, kepada organisasi-organisasi paralel (parallel organizations) (1983:18-25).
Tujuan DesentralisasiSecara umum, tujuan desentralisasi dapat dibedakan dalam dua kategori utama, yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Klasifikasi ini dibangun dengan merujuk pada klasifikasi yang telah dirumuskan oleh Smith. Dalam bukunya, Decentralization: The Teritorrial Demention of the State, Smith (1985) menjelaskan ada dua nilai utama desentralisasi, yaitu: nilai politik dan nilai ekonomi (political and economic values). Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah to provide training in political leadership (untuk latihan kepemimpinan). Praktik desentralisasi dan otonomi daerah dalam hal ini juga berfungsi sebagai sarana untuk training bagi para politisi dan birokrat di daerah sebelum mereka menduduki berbagai posisi penting di tingkat nasional. Oleh karena itu, melalui kebijksanaan desentralisasi, diharapakan akan mampu memotivasi dan melahirkan calon-calon pimpinan yang andal pada level nasional. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan nasional adalah to create political stability (untuk menciptakan stabilitas politik). Maksudnya adalah melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka diharapkan tidak saja akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, tetapi juga akan meningkatkan sensitivitas dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya akan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas politik.Sementara itu, dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality, yakni semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Tujuan kedua desentralisasi adalah local accountability, yaitu semkin meningkatakn tanggung jawab pemerintah daerah dalam berhadapan dengan masyarakat. Sementara itu, tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local responsiveness. Pemerintah daerah dalam hal ini dianggap lebih mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya. Maka, pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselarasi dari pembagunan sosial dan ekonomi di daerah. Dalam dimensi ekonomi, acapkali dikemukakan bahwa urgensi dari diterapkannya desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good and services (barang dan jasa untuk umum), serta untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah (Rondinelli, 1983:4). Argumentasi ini menyiratkan bahwa fungsi desentralisasi tidak lain adalah sebagai sarana (alat) untuk memeperluas ruang bagi masyarakat dalam melakukan pilihan terhadap barang dan jasa pelayanan umum, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keseimbangan antara hak individu dan kesejahteraan kolektif. Dengan kata lain, melalui penerapan suatu kebijakan desentralisasi diharapkan akan dapat mengurangi biaya pembangunan, meningkatkan capaian target (output), dan akan lebih mengefektifkan pemanfaatan sumber daya yang dimilki oleh daerah. Tujuan ekonomi lainnya desentralisasi dikemukakan oleh Jurgen Ruland (1992). Ia berpendapat bahwa desentralisasi yang selanjutnya akan melahirkan otonomi daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarkat, yang pada akhirnya akan menunjang pembangunan sosial-ekonomi (1992:3). Dengan kata lain, Ruland meyakini bahwa melalui implementasi kebijakan desentralisasi, akan terjadi peningkatan pembangunan sosio-ekonomi dan adanya perbaikan kondisi kehidupan sosial.Sementara itu, secara politis, tujuan desentralisasi, antara lain: untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, dan untuk mempertahankan integrasi nasional. Sejalan dengan dalil ini, Yluisaker kemudian mengatakan bahwa sedikitnya ada tiga aspek utama yang terkait dengan democratic decentralization (desentralisasi-demokrasi), yaitu: kebebasan (liberty), persamaan hak (equlity), dan kesejahteraan (welfare) (1959:30).Dalam formulasi yang lebih mikro, Smith (1985) membedakan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan kepentingan nasional dan daerah. Bila dilihat dari sisi kepentingan nasional, tulis Smith (1985), sedikitnya ada tiga tujuan utama dari desentralisasi.Pertama, untuk mewujudkan apa yang disebut dengan Political Education (pendidikan poltik). Di antara argumen yang sering dikemukakan untuk menjustifikasi pentingnya Political Education sebagai bagian tujuan desentralisasi adalah, pernyataan Maddick (1963) yang menyebutkan bahwa tujuan hakiki desentralisasi, atau lebih luas lagi, pembentukan pemerintah daerah adalah untuk menciptakan pemahaman politik yang sehat, (healthy political understanding) bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan negara. Melalui desentralisasi, tulis Maddick, maka masyarakat akan belajar mengenali dan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi; menghindari atau bahkan menolak untuk memilih calon legistlatif yang tidak memiliki kualifikasi kemampuan politik yang diharapkan; dan belajar mengkritisi berbagai kebijaksanaan pemerintah, termasuk di dalamnya mengkritisi masalah penerimaan dan belanja daerah (1963:50-106).
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan DesentralisasiKeberhasilan atau kegagalan kebijakan desentralisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rondineli (1983) faktor-faktor tersebut adalah:1. Derajat komitemen politik dan dukungan administrasi yang diberikan terutama oleh pemerintah pusat dan elite serta masyarakat daerah itu sendiri. Komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Departemen Dalam Negeri dan departemen teknis pusat merupakan faktor yang sangat menentukan. Wujud komitmen ini ditunjukan dalam bentuk berbagai tindakan yang didukung oleh legal frame work yang jelas sehingga pelaksanaan desentralisai dapat terlaksana dengan baik. Di samping pemerintah pusat, elite dan masyarakat daerah yang bersangkutan juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Kesiapan elite dan masyarakat daerah menjadi faktor yang sangat menentukan pelaksanaan desentralisasi. Elite dan masyarakat daerah yang tidak siap hanya menunggu perintah dan petunjuk dari pusat akan tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.2. Sikap, perilaku dan budaya masyarakat terhadap kebijakan desentralisasi. Sikap, perilaku dan budaya masyarakat terutama ditunjukkan oleh elitnya baik aparat, anggota DPRD, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang menganut pola paternalistik dan feodalistik akan menghambat pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi menuntut kreativitas, kemampuan dan kemandirian masyarakat lokal dalam mengindentifikasi, merumuskan dan mengatur dan mengurus urusan-urusan yag bersifat lokal. Tanpa adanya kemampuan ini desentralisasi tidak akan berjalan dengan baik.3. Dukungan organisasi pemerintah yang mampu menjalankan kebijakan desentralisasi secara efektif da efisien. Dukungan organisasi ini sangat penting karena kebijakan desentralisasi tidak akan dapat diimplementasikan tanpa didukung oleh organisasi pelaksananya.4. Tersedianya sumber daya yang memadai: manusia, keuangan dan infrastruktur. Kebijakan desentralisasi tidak akan berjalan jika tidak didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia, keuangan dan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penentu dalam kesuksesan desentralisasi.
Studi tentang Desentralisasi di Beberapa Negara Berkembang: Mengapa Mayoritas Negara-negara sedang Berkembang Menghendaki Desentralisasi?Smith (1985), misalnya mencatat sedikitnya ada tiga alasan utama yang dapat menjelaskan mengapa sebagian besar Negara-negara sedang berkembang menganggap penting mengaplikasikan desentralisasi, yaitu: untuk menciptakan efisiensi penyelanggaraan administratif pemerintahan; untuk memperluas otonomi daerah; dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Sementara itu, Nelson Kasfir (1987), dalam salah satu tulisannya tentang iplementasi kebijakan desentralisasi di Negara-negara Afrika tropis, mengatakan bahwa sebagian besar Negara sedang berkembang memiliki alasan serupa dalam menjustifikasi tuntutan akan kehadiran desentralisasi. Di antara alasan-alasan tersebut adalah karena desentralisasi telah dianggap sebagai salah satu resep untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk memacu percepatan proses pembangunan ekonomi daerah.Penjelasan yang relatif lebih komprehensif dikemukakan oleh Conyer (1983). Menurut Conyer, munculnya tuntutan akan desentralisasi di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an, khususnya di negara-negara Afrika mantan jajahan Inggris, sangat berkaitan erat dengan fenomena transformasi status dari negara kolonial (jajahan) menjadi negara berdaulat (merdeka). Keberadaan desentralisasi kemudian telah diartikulasi sebagai faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan dalam upaya menciptakan tatanan pemerintahan daerah yang demokratis. Lebih spesifiknya, kehadiran desentralisasi dalam hal ini tidak saja diyakini dapat difungsikan sebagai suatu strategi untuk memindahkan beban pemerintah pusat dalam penyediaan pelayanan publik kepada daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong terciptanya pendidikan politik dan partisipasi masyrakat tingkat lokal (Conyer, 1983:99).Sementara itu, dari perspektif ekonomi, acapkali dikemukakan bahwa munculnya tuntunan akan perlunya praktik desentralisasi di sebahagian besar negara-negara yang sedang berkembang tidak bisa dipisahkan dari reaksi atas kegagalan model pembangunan sentralistik yang diterapkan di negara-negara tersebut pada 1960-an. Rondinelli (1983), misalnya, dengan tegas menjelaskan bahwa kegagalan dari model perencanaan sentralistik pada tahun 1960-an telah menyebabkan mayoritas negara-negara sedang berkembang percaya betul, bahwa kebijakan desentralisasi, akan mampu untuk, antara lain: (a) mengurangi peranan dominan pemerintah pusat dalam perumusan perencanaan nasional; (b) memberi kewenangan yang lebih luas dalam bidang perencanaan pembangunan dan manajemen pemerintahan kepada para pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; (c) mengurangi masalah-masalah kompleksitas birokrasi dan korupsi di tingkat daerah; (d) meningkatkan ketrampilan serta pengetahuan para pejabat daerah, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan daya sentivitas mereka terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yag dihadapi; serta (e) akan memungkinkan para pimpinan pemerintah daerah melokalisasi pelyanan publik secara lebih efektif di lingkungan komunitasnya.
b. DekonsentrasiDekonsentrasi adalah penyerahan beban kerja dari kementerian pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah. Penyerahan ini tidak diikuti oleh kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya.
c. Delegasi (Pelimpahan Wewenang pada lembaga semi otonom)Selain dalam bentuk dekonsentrasi dan devolusi, desentralisasi juga bisa dilakukan dengan cara pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenangan administratif kepada organisasi-organisasi yang melakukan fungsi-fungsi tertentu, yang tidak di bawah pengawasan pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui dalam suatu pemerintahan terdapat organisasi-organisasi yan melakukan fungsi-fungsi tertentu dengan kewenangan yang agak independen. Organisasi ini adakalanya tidak ditempatkan dalam struktur reguler pemerintah. Misalnya BUMN seperti Telkom, Bank, jalan tol, dan lain lain. Badan perencanaan pembangunan darah, badan-badan otoritas, dan lain-lain. Terhadap organisasi semacam ini pada dasarnya diberikan kewenangan semi independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan kadang-kadang berada di luar ketentuan yang diatur oleh pemerintah, karena bersifat komersial dan mengutamakan efisiensi daripada prosedur birokratis dan politis.Pendelegasian tersebut menyebabkan pemindahan atau penciptaan kewenangan yang luas pada suatu organisasi yang secara teknis dan administratif mampu menanganinya, baik dalam merencanakan maupun melaksanakan. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut tidak mendapat supervisi langsung dari pemerintah pusat.
d. DevolusiDevolusi adalah pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintah baru yang tidak dikontrol secara langsung. Tujuan devolusi untuk memperkuat satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan. Devolusi dalam bentuknya yang paling murni, memiliki lima ciri fundamental:i. Unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri, dan secara tegas terpisah dari tingkat-tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan langsung terhadapnya.ii. Unit pemerintahan tersebut diakui memiliki batas geografi yang jelas dan legal, yang mempunyai wewenang untuk melakukan tugas-tugas umum pemerintahan.iii. Pemerintah daerah berstatus badan hukum dan memiliki kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugasnyaiv. Pemerintah daerah diakui oleh warganya sebagai suatu lembaga yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah ini mempunyai pengaruh dan kewibawaan terhadap warganya.v. Terdapat hubungan saling menguntungkan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit-unit organisasi lainnya dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah adalah bagian dari pemerintah nasional dan bukan sebagai elemen yang independen dari pemerintah pusat. Dalam devolusi tidak ada hirarki antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya, karena yang menjadi dasar adalah koordinasi dan sistem saling hubungan antara satu unit dengan unit lain secara independen dan timbal-balik.
e. PrivatisasiDesentralisasi dapat juga berbentuk penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat kepada lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Bentuk ini sering dikenal dengan privatisasi. Privatisasi adalah suatu tindakan pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat atau dapat pula merupakan peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta, misalnya BUMN dan BUMD menjadi PT. termasuk dalam pengertian ini adalah tindakan pemerintah mentransfer beberapa kegiatan kepada kamar dagang dan industri, koperasi dan asosiasi lainnya untuk mengeluarkan izin-izin, bimbingan dan pengawasan, yang semula dilakukan oleh pemerintah. Dalam bidang sosial misalnya pemerintah memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada lembaga swadaya masyarakat, pembinaan ksejehateraan keluarga, koperasi tani, dan koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kesejahteraan keluarga, petani, dan sebagainya.
Tugas dan Latihan1. Jelaskan dua tipologi pemerintahan lokal.2. Jelaskan perbedaan antara kelima bentuk asas-asas pemerintahan daerah.