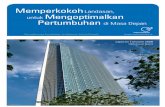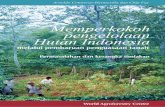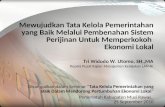Makalah 2 Peran Budaya Daerah Dalam Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa
BAB II Usaha Mikro, Kecil dan Menengah...
Transcript of BAB II Usaha Mikro, Kecil dan Menengah...
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.1.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
a. Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha mikro adalah usaha
produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
b. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi
produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini.
c. Menurut pasal 1 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah bahwa usaha menengah adalah usaha
ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
10
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2.1.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
a. Kriteria usaha mikro sesuai yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) UU
No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
adalah:
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
b. Kriteria dari usaha kecil sesuai yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2)
UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
adalah :
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
11
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
c. Kriteria usaha menengah sesuai yang tercantum dalam pasal 6 ayat
(3) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
adalah :
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.00,00 (Lima
Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00
(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
2.2. Persekutuan Komanditer (Comanditair Venootschap)
2.2.1. Pengertian Persekutuan Komanditer
Persekutuan Komanditer atau yang sering disebut CV menurut Kitab
Undang-undang Hukum Dagang Pasal 19 adalah suatu bentuk perjanjian kerja
sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin,
12
mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan
pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia
memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang
diikutsertakan dalam perusahaan itu.
(http://pengertiancv.blogspot.com/2009/04/pengertian-cv.html)
2.2.2. Prosedur Pendirian Persekutuan Komanditer
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak ada aturan tentang
pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan
komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat
para pihak saja (Pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Untuk
menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan
membuat akta kepada notaris, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut,
sebaiknya CV tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan
membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan.
(http://irmadevita.com/2007/prosedur-cara-dan-syarat-pendirian-cv)
2.2.3. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer
Berdasarkan perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah
sebagai berikut:
13
Persekutuan komanditer murni
Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam
persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan
yang lainnya adalah sekutu komanditer.
Persekutuan komanditer campuran
Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan
tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan
sekutu lain atau sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer.
Persekutuan komanditer bersaham
Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak
dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu
komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya
saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena
dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali
modal yang telah disetorkan.
2.2.4. Kelebihan dan Kekurangan Persekutuan Komanditer
Kelebihan Persekutuan Komanditer
1. Modal yang dikumpulkan lebih besar
2. Dapat lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan
usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia
14
3. Kemampuan manajemennya lebih besar
4. Pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan Perseroan
Terbatas (PT)
Kelemahan Persekutuan Komanditer
1. Sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai
tanggung jawab tidak terbatas
2. Kelangsungan hidupnya tidak menentu
3. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi
sekutu pimpinan
2.3. Akuntansi Biaya
2.3.1. Pengertian Akuntansi Biaya
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2010:7), akuntansi biaya
adalah:
“Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya
pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu,
serta penafsiran terhadapnya”.
2.3.2. Peranan Akuntansi Biaya
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yang diterjemahkan
oleh Krista adalah sebagai berikut:
15
1. “Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksikan sebelumnya. Suatu aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi orang agar berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan, untuk tujuan penetapan harga dan untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu tahun atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan nilai persedian dan harga pokok penjualan sesuai dengan aturan pelaporan eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka panjang, yang dapat mengubah pendapatan atau biaya.”
2.3.3. Manfaat Akuntansi Biaya
Penggunaan akuntansi biaya terbukti sangat penting bagi suatu
perusahaan karena memiliki banyak manfaat yang berguna bagi kelangsungan
perusahaan. Manfaat tersebut adalah sebagai salah satu informasi yang
diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, yaitu untuk
perencanaan dan pengendalian laba, penentuan harga pokok produk dan jasa,
serta bagi pengambilan keputusan oleh manajemen dalam proses produksi.
2.4. Harga Pokok Produksi
Harga pokok produksi merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang
dibebankan kedalam produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Harga pokok
produksi juga digunakan oleh perusahaan sebagai dasar dari harga jual suatu
16
produk serta dapat membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan-
kebijakan dalam pengelolaan perusahaan.
2.4.1. Pengertian Harga Pokok Produksi
Pengertian harga pokok produksi menurut Bastian Bustami dan Nurlela
(2010:49), harga pokok produksi adalah:
“Kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.”
2.4.2. Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi
Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca.
17
2.4.3. Unsur – unsur Harga Pokok Produksi
Unsur – unsur yang membentuk harga pokok produksi adalah biaya
bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Pada umumnya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung
disebut juga dengan biaya utama (Prime Cost), sedangkan yang lainnya disebut
biaya konversi (Conversion Cost). Biaya – biaya ini dikeluarkan untuk
mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Yang termasuk kedalam unsur –
unsur harga pokok produksi adalah sebagai berikut:
1. Biaya Bahan Baku Langsung (Direct Material Cost)
Berikut ini merupakan beberapa pengertian menurut para ahli
mengenai biaya bahan baku:
Menurut Mulyadi (2010:275) adalah sebagai berikut:
“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor atau dari pengolahan sendiri. Sedangkan menurut Carter (2009:40) yang diterjemahkan oleh
Krista adalah sebagai berikut:
“Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk
bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit
dalam perhitungan biaya produk.”.
18
Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa bahan baku merupakan unsur paling pokok
dalam proses produksi.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (Direct Labor Cost)
Berikut ini merupakan beberapa pengertian menurut para ahli
mengenai biaya tenaga kerja langsung:
Menurut Carter (2009:40) yang diterjemahkan oleh Krista adalah
sebagai berikut:
“Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan
konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat
dibebankan secara layak ke produk tertentu.”
Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2010:12) adalah
sebagai berikut:
“Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan
dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk
selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai”.
Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa tenaga kerja langsung merupakan faktor penting
berupa sumber daya manusia yang mempengaruhi proses
pengelolaan bahan baku menjadi barang jadi pada suatu proses
19
produksi dan biaya tenaga kerja merupakan upah yang diberikan
kepada tenaga kerja dari usaha tersebut.
3. Biaya Overhead (Overhead Cost)
Berikut ini merupakan beberapa pengertian menurut para ahli
mengenai biaya overhead:
Menurut Carter (2009:40) yang diterjemahkan oleh Krista adalah
sebaga berikut:
“Biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang
tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu. Misalnya biaya
energi bagi pabrik seperti gas, listrik, minyak dan sebagainya.”
Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela (2010:13) Biaya
Overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen:
a. “Bahan Tidak Langsung (Bahan Pembantu atau Penolong) adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contoh: amplas, pola kertas, oli dan minyak pelumas, paku, sekrup dan mur,staples, asesoris pakaian, vanili, garam, pelembut, pewarna.
b. Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung adalah biaya tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contoh: Gaji satpam pabrik, gaji pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan dokumen pabrik, gaji operator telepon pabrik, pegawai pabrik, pegawai bagian gudang pabrik, gaji resepsionis pabrik, pegawai yang menangani barang.
c. Biaya Tidak Langsung Lainnya adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contoh : Pajak bumi dan bangunan pabrik, listrik pabrik, air, dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
20
penyusutan pabrik, peralatan pabrik, pemeliharaan mesin dan pabrik, gaji akuntan pabrik, reparasi mesin dan peralatan pabrik.”
2.5. Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi
2.5.1. Metode Harga Pokok Pesanan
Menurut Mulyadi (2010:35) metode perhitungan biaya berdasarkan
pesanan adalah sebagai berikut:
“Dalam metode ini biaya – biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dalam jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan.”
2.5.1.1. Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan
Menurut Mulyadi (2010:38), karakteristik usaha perusahaan yang
produksinya berdasarkan pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap
pengumpulan biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan
metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang
produksinya berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok
produksinya secara individual.
2. Biaya produksi harus golongkan berdasarkan hubungannya dengan
produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung dan
biaya produksi tidak langsung.
21
3. Biaya produksi langsung terdiri dan biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut
dengan istilah biaya overhead pabrik.
4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi,
sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok
pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
2.5.1.2. Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi Per Pesanan
Menurut Mulyadi (2010:39), dalam perusahaan yang produksinya
berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat
bagi manajemen untuk:
1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan.
2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan.
3. Memantau realisasi biaya produksi.
4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan.
22
5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca.
2.5.2. Metode Harga Pokok Proses
Menurut Mulyadi (2010:63) metode perhitungan biaya berdasarkan
proses adalah sebagai berikut:
“Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu, selama periode tertentu, dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan.”
2.5.2.1. Karakteristik Metode Harga Pokok Proses
Menurut Mulyadi (2010:63-64), metode pengumpulan produksi
ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan
yang berproduksi massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut :
1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi
yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu
tertentu.
23
2.5.2.2. Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi
Menurut Mulyadi (2010:65), dalam perusahaan yang berproduksi massa,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk:
1. Menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan neraca.
2.5.3. Perbedaan Metode Harga Pokok Pesanan dengan Metode Harga Pokok
Proses
Menurut Mulyadi (2010:64), perbedaan diantara dua metode
pengumpulan biaya produksi tersebut terletak pada:
1. Pengumpulan biaya produksi.
2. Perhitungan harga pokok produksi per satuan.
3. Penggolongan biaya produksi.
4. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik.
2.6. Metode Penentuan Harga Pokok Produksi
Menurut Mulyadi (2010:17), metode penentuan kos produksi adalah:
24
“Cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam
memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua
pendekatan : full costing dan variable costing.”
2.6.1. Pendekatan Full Costing
Menurut Mulyadi (2010:17), metode pendekatan full costing adalah :
“Merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap.”
Dengan demikian kos produksi menurut metode full costing terdiri dari
unsur biaya produksi berikut ini :
- Biaya bahan baku xx
- Biaya tenaga kerja langsung xx
- Biaya overhead pabrik variabel xx
- Biaya overhead pabrik tetap xx
Total Harga Pokok Produksi (cost) xx
2.6.2. Pendekatan Variable Costing
Menurut Mulyadi (2010:18), metode pendekatan variable costing adalah:
“Merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.”
25
Dengan demikian kos produksi menurut metode variable costing terdiri
dari unsur biaya produksi berikut ini :
- Biaya bahan baku xx
- Biaya tenaga kerja langsung xx
- Biaya overhead pabrik variabel xx
Total Harga Pokok Produksi (cost) xx
2.7. Biaya
Biaya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses
produksi karena biaya merupakan salah satu komponen utama. Dalam hal ini
biaya (cost) berbeda dengan beban (expense). Seringkali biaya didefinisikan
sama dengan beban oleh masyarakat pada umumnya tetapi kenyataannya kedua
hal tersebut sangatlah berbeda. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis
yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan
terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan beban adalah biaya yang
telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis (Bastian Bustami dan
Nurlela, 2010 : 7-8). Keduanya jelas berbeda jika kita dapat memahami dengan
baik perbedaan antara biaya dengan beban.
2.7.1. Pengertian Biaya
Pengertian biaya menurut Mulyadi (2010:8) adalah sebagai berikut:
26
“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi, 2. Diukur dalam satuan uang, 3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi, 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah harga pokok.”
Sedangkan definisi biaya menurut Hansen dan Mowen (2009:40) adalah:
“Biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan
untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat
saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi.”
2.7.2. Klasifikasi Biaya
Penggolongan biaya merupakan salah satu hal yang dapat membantu
perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pengertian klasifikasi biaya menurut
Bastian Bustami dan Nurlela (2010:12) adalah:
“Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting”.
Menurut Mulyadi (2010:13), biaya dapat digolongkan menurut :
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek
27
pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya
benang, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya
asuransi, biaya bunga, biaya zat warna.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi
produksi, fungsi pemasaran dan fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan
menjadi tiga kelompok, yaitu :
1. Biaya Produksi
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku
menjadi produk jadi yang siap dijual.
2. Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksankan kegiatan
pemasaran produk.
3. Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan
pemasaran produk.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan
menjadi dua golongan:
28
a. Biaya langsung (Direct Cost)
adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena
adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut
tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi.
b. Biaya tidak langsung (Indirect Cost)
adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang
dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk
disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya
overhead pabrik (factory overhead cost).
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan
Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat
digolongkan menjadi :
a. Biaya variable
adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan
perubahan volume kegiatan.
b. Biaya semivariable
adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan
volume kegiatan.
c. Biaya semifixed
29
adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan
berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
d. Biaya tetap
adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan
tertentu.
5. Jangka waktu manfaatnya
Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua,
yaitu:
a. Pengeluaran modal (Capital Expenditures)
b. Pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditures)