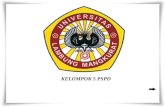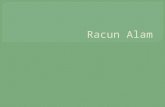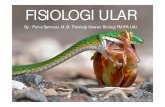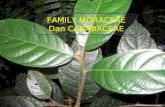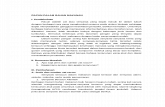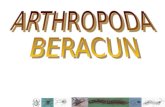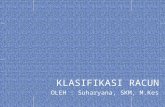BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1....
-
Upload
truongdieu -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1....
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
1. Permasalahan
Pencemaran limbah terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Industri-industri di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat,
dikarenakan masuknya era globalisasi. Pembuangan limbah terkadang kurang
menjadi perhatian oleh para pemilik industri, padahal hal tersebut adalah hal yang
paling penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang
disebabkan oleh limbah industri. Kasus pencemaran limbah cair yang marak di
Indonesia membuat sulitnya menemukan air bersih. Kualitas air harus terjaga
dengan baik agar dapat digunakan oleh manusia. Limbah industri merupakan 50
% dari beban pencemaran daerah aliran sungai yang pada akhirnya merupakan
pula beban pencemaran bagi perairan pantai (Atmakusumah, dkk. 1996: 193)
Penyakit kolera di beberapa negara berkembang dan negara industri
dilaporkan terjadi secara berkala. Selokan pada instalasi layanan rumah sakit
tempat pasien kolera dirawat, tidak selalu dihubungkan dengan instalasi
pengolahan limbah yang efisien, dan terkadang jaringan saluran perkotaan belum
terbentuk, walaupun hubungan antara penyebaran kolera dan metode pembuangan
limbah cair tidak aman belum banyak dikaji dan didokumentasikan. Pembuangan
2
limbah cair yang tidak aman diduga kuat turut berkontribusi dalam penyebaran
kolera (Pruss, 1999: 140).
Pencemaran air tidak selalu identik dengan ancaman penyakit maupun
ancaman kepunahan bagi semua spesies, seperti bahan kimia tertentu yang
terbuang ke dalam lingkungan air dapat menjadi makanan ganggang air.
Ganggang air tidak mati atau punah, akan tetapi ganggang air menjadi makanan
ikan dan ikan menjadi makanan manusia. Rantai makanan tersebut ada dua hal
yang terjadi, yaitu secara positif ganggang membersihkan air dari kontaminasi
bahan kimia beracun, akan tetapi melalui rantai makanan, racun kimia yang
terkandung dalam ganggang akhirnya sampai kepada manusia yang
membahayakan kesehatannya (Borrong, 2000. 86).
Uraian diatas menunjukan bahwa pencemaran limbah cair sangat
berbahaya bagi makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung.
Pencemaran limbah cair harus dikendalikan karena selain merugikan manusia,
juga akan berpengaruh terhadap organisme yang ada di dalam air, selain dari
bahan buangan proses sisa industri, limbah cair juga berupa feses dan urine
manusia. Pembuangan feses dan urine, apabila disalurkan ke air sungai maka air
akan terkontaminasi oleh bakteri sebagai sumber penyakit dan tentunya
menimbulkan bau yang tidak sedap. Air yang terkontaminasi oleh bakteri sangat
tidak layak apabila dikonsumsi oleh manusia. Manusia sebagai makhluk yang
mempunyai akal seharusnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.
Manusia pada dasarnya bersifat egoistis yaitu mementingkan dirinya
sendiri. Salah satu fungsi kebudayaan pada umumnya dan agama pada khususnya
3
ialah mengurangi sifat egoistis ini dan mendorong orang untuk mau berkelakuan
baik untuk kepentingan umum, karena lingkungan hidup memberi layanan kepada
masyarakat umum, berbuat baik untuk lingkungan hidup merupakan perbuatan
untuk kepentingan umum. Perbuatan pro-lingkungan bersifat juga pro-sosial,
tetapi faktanya ialah tidak ada atau sedikit sekali orang yang mau mengorbankan
kepentingan dirinya untuk kepentingan lingkungan hidup, termasuk untuk
makhluk hidup bukan manusia ataupun lingkungan sekitar yang tidak hidup atau
benda mati (Soemarwoto, 2001:87).
Teori etika lingkungan dalam hal ini diharapkan mampu menimbulkan
pemahaman baru terhadap masalah lingkungan hidup yang tidak terpisah dari
kosmologi tertentu yang dalam kenyataannya tidak menumbuhkan sikap
eksploitatif terhadap alam lingkungan. Pengembangan etika lingkungan hidup
perlu untuk mengendalikan adanya perubahan secara mendasar dari pandangan
kosmologis yang menumbuhkan sikap hormat dan bersahabat dengan alam
lingkungan, tetapi masalah krisis lingkungan tidak cukup dihadapi dengan
mengembangkan etika lingkungan hidup, apabila sudah menyangkut
kesejahteraan umum masyarakat, pemikiran etis saja tidak akan berdaya tanpa
didukung oleh aturan-aturan hukum yang dapat menjamin pelaksanaan dan
melakukan tidakan terhadap pelanggarnya (Sudriyanto dalam Santosa, 2000: 67-
68).
Bantul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang
mempunyai 17 kecamatan dan terdiri dari 75 desa. Bantul merupakan kabupaten
dengan berbagai sentra industri. Penduduk di Bantul yang semakin meningkat
4
jumlahnya, semakin meningkat pula aktivitas-aktivitas yang menghasilkan
limbah, seperti membuang limbah cair ke lingkungan tanpa melalui proses
pengolahan seperti penyaringan, atau netralisasi, sehingga dapat mengakibatklan
penurunan kualitas air. Sentra industri-industri yang marak di Bantul sebagai
upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Bantul, akan tetapi kepedulian
terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah hasil industri juga
harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu bentuk kepedulian tersebut seperti
yang dilakukan oleh kelompok tahu Ngudi Lestari di Dusun Gunung Saren
Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta dengan pembuatan instalasi pengolahan
air limbah (IPAL) biogas di beberapa lahan milik anggota kelompok tersebut
(Sumber: Program Sektor Sanitasi Kabupaten Bantul, 2011).
Pembuatan instalasi pengolahan air limbah biogas, digunakan untuk
mengolah limbah cair dari pengolahan tahu sehingga tidak terjadi pencemaran
lingkungan. Sebelum adanya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) biogas di
kelompok tahu Ngudi Lestari, pembuangan dilakukan di sungai Progo melalui
saluran irigasi ataupun secara langsung, dan di lahan rumah. Pembuangan yang
dilakukan tanpa melalui proses akan mempengaruhi kualitas air sumur dan sungai,
sehingga apabila dikonsumsi oleh warga menyebabkan sakit perut dan gatal-gatal.
Selain mengakibatkan penurunan kualitas air, juga menimbulkan bau yang tidak
sedap sehingga terjadi pencemaran udara (Wardana dalam Mardiana, 2008: 13).
Pengendalian dan pengelolaan limbah mempunyai beberapa kewajiban
yang harus dipenuhi oleh penanggungjawab kegiatan industri yaitu diatur dalam
kep. No 51/MenLH/10/1995 pasal 6. Salah satu isi peraturan tersebut adalah
5
melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair dibuang kedalam
lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang ditetapkan (Effendi,
2003: 15). IPAL biogas sebagai solusi dari masalah limbah cair tahu agar kualitas
air tetap terjaga dan terjadi keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan limbah cair
tahu melalui instalasi pengolahan air limbah biogas menghasilkan gas merupakan
suatu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya dan langkanya bahan
bakar minyak.
Penelitian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas dilakukan di
kelompok pengrajin tahu Ngudi Lestari di Dusun Gunung Saren Trimurti,
Srandakan, Bantul Yogyakarta. Kelompok tersebut merupakan kelompok yang
pertama kali mempunyai IPAL biogas yang berada di lahan milik bapak Mungin
Hadi Prayitno pada tahun 2005, kemudian seiring berjalannya waktu kelompok
tersebut mempunyai 9 IPAL biogas yang mendapatkan dana dari berbagai pihak,
seperti Universitas Gadjah Mada, kecamatan Srandakan dan juga Lembaga
Swadaya Masyarakat. Kecamatan Srandakaan yang terkenal banyak sekali
industri tahu, ada beberapa industri yang tidak membuat IPAL biogas, sehingga
limbah cair tahu dibuang di sembarang tempat dan menimbulkan pencemaran air
dan udara. Penelitian ini diharapkan bisa memberi inspirasi pada industri lainnya
untuk peduli akan pengendalian pencemaran limbah.
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) biogas sebagai solusi dalam
pengendalian pencemaran limbah cair tahu jika dikaji dari Ekosentrisme
merupakan kepeduliaan terhadap lingkungan dari masyarakat kelompok pengrajin
tahu Ngudi Lestari di Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul
6
Yogyakarta. Ekosentrisme merupakan salah satu teori etika lingkungan yang
memusatkan etika pada seluruh komunitas alam semesta, baik yang hidup maupun
tidak hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada
makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku
terhadap semua realitas alam semesta. Salah satu versi teori etika lingkungan
Ekosentrisme yakni Deep Ecology menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat
pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan
dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Deep Ecology memusatkan
perhatian pada semua spesies termasuk spesies bukan manusia, demikian pula
Deep Ecology tidak hanya memusatkan perhatian jangka pendek, tetapi jangka
panjang, maka prinsip moral yang dikembangkan Deep Ecology menyangkut
kepentingan seluruh komunitas ekosistem (Keraf, 2006: 75-76).
Kasus yang menjadi perhatian pada Kelompok Pengrajin Tahu Ngudi
Lestari Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta yaitu
kualitas air tanah, sungai dan juga udara harus bersih dan terjaga dari pencemaran
limbah cair hasil pengolahan tahu. Air tanah, sungai dan udara merupakan benda
abiotik atau benda mati, walaupun begitu benda abiotik juga perlu diperhatikan
karena termasuk dalam komunitas ekosistem yang bermanfaat bagi kehidupan
makhluk hidup. Jadi sesuai dengan pemikiran Ekosentrisme yang memandang
seluruh komunitas ekosistem. Kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab
moral kelompok pengrajin tahu “Ngudi lestari” terhadap upaya pengendalian
limbah cair dengan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas
7
perlu diapresiasi dan dicontoh bagi para pemilik industri yang belum mempunyai
IPAL.
2. Rumusan Masalah
Uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
a. Bagaimana proses pengolahan air limbah cair tahu dengan Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas pada kelompok pengrajin tahu
(Ngudi Lestari di Bantul Yogyakarta)?
b. Apa pengertian dan esensi teori etika lingkungan Ekosentrisme?
c. Apa refleksi kritis Ekosentrisme dalam pengendalian pencemaran
limbah tahu pada kelompok pengrajin Ngudi Lestari melalui Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas?
3. Keaslian Penelitian
Penelitian mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas
Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Tahu Dalam Kajian
Ekosentrisme (Studi Kasus Kelompok Pengrajin Tahu Ngudi Lestari Dusun
Gunung Saren Trimurti, Srandaan, Bantul Yogyakarta) sejauh penelusuran yang
penulis lakukan belum pernah menemukan penelitian yang sama persis. Penelitian
yang mirip dengan objek formal ataupun objek materi yaitu diantaranya sebagai
berikut:
8
a. Iwan Setiawan, 2004, Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah
Mada, dengan judul: Peran Etika Lingkungan Hidup dalam Industri
Pertambangan di Indonesia, berisi tentang peran teori etika lingkungan
hidup yang berpihak pada alam seperti (Biosentrisme, Ekosentrisme,
Hak Asasi Alam dan Ekofeminisme) dengan berbagai prinsip – prinsip
moralnya sangat diperlukan sebagai pedoman guna membatasi
tindakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, khususnya
mineral melalui industri pertambangan, sehingga industri
pertambangan di Indonesia dapat mendukung program pembangunan
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
b. Davit Oktiyadi, 2006, Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah
Mada, dengan judul: Relevansi Konsep Ecosophy dalam Etika
Ekosentrisme sebagai Alternatif Atas Krisis Ekologis di Indonesia,
berisi tentang konsep ecosophy yang mengandung nilai-nilai
keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan antara hubungan
manusia dan alam digunakan untuk perubahan mendasar dan radikal
dalam level ideologi, ekonomi, politik, dan social, sekaligus revitalisasi
dan reorientasi kearifan lokal yang telah berkembang di daerah-daerah.
c. Arif Wibowo, 2011, Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah
Mada, dengan judul: Kebijakan Pembangunan Potensi Lokal Desa
Donokerto ditinjau dari Etika Lingkungan Ekosentrisme, berisi tentang
Ekosentrisme yang diterapkan dalam pembangunan potensi lokal di
desa Donokerto agar terciptanya desa yang mandiri dengan membina
9
hubungan keselarasan antara manusia dengan masyarakat, manusia
dengan lingkungan, dan manusia dengan generasi penerus.
d. Novri Sartika Anggraeni, 2011, Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas
Gadjah Mada, dengan judul: Etika Lingkungan dalam Kehidupan
Asrama Mahasiswi Syantikara menurut Perspektif Ekosentrisme Ane
Naess, berisi tentang pengelolaan lingkungan Asrama Syantikara
dengan menggunakan teori etika ekosentrisme Naess yang didasarkan
pada Deep Ecology.
e. Agha Bukhari, 2012, Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah
Mada, dengan judul: Konservasi Hutan Suku Baduy di Banten dalam
Perspektif Teori Etika Lingkungan Ekosentrsime, berisi tentang
kehidupan suku Baduy yang pro akan Ekosentrisme yang dapat dilihat
dalam proses konservasi hutan dengan melakukan tahapan-tahapan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi,
perencanaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
f. Agus Fita Yudyanto, 2012, Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas
Gadjah Mada, dengan judul: Tanggung Jawab Sosial (Corporate
Social Responsibility) PT Sri Rejeki Isman Tekstil terhadap
Lingkungan Sekitar dari Perspektif Ekosentrisme, berisi tentang
kebijakan PT Sri Rejeki Isman Tekstil dalam pelestarian lingkungan
dengan menerapkan pemikiran Ekosentrisme sehingga dalam
pelaksanaan produksinya berupaya untuk tetap mempertahankan
10
semua yang hidup dan yang tidak hidup sebagai komponen ekosistem
yang sehat.
g. Zainal Fadri, 2014, Skripsi Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada,
dengan judul: Rawa Buatan dalam Pelestarian Sumber Daya Air
dalam Kajian Etika Lingkungan Ekosentrisme, berisi tentang
pengelolaan air dengan rawa buatan merupakan suatu bentuk
perwujudan Deep Ecology dalam mengatasi isu krisis lingkungan.
h. Mardiana, Hayya. 2008. Tesis S2 Ilmu Lingkungan, dengan judul:
Kajian Kerusakan Akibat Kegiatan Industri Tahu terhadap Penurunan
Kualitas Air Tanah (Kasus Di Kawasan Sentra Industri Tahu Desa
Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul), berisi tentang
kualitas air tanah di kawasan sentra industri tahu desa Trimurti
kecamatan srandakan kabupaten Bantul menurun yang disebabkan oleh
limbah hasil pengolahan tahu, sedangkan penelitian ini membahas
tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah biogas pada kelompok
pengrajin tahu Ngudi Lestari yang merupakan cara konvensional
sebagai pengendali pencemaran, khusus di Gunung Saren Trimurti
Srandakan Bantul.
Penelitian ini membahas tentang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Biogas sebagai upaya pengendalian pencemaran limbah cair dari hasil pengolahan
tahu dalam kajian Ekosentrisme (Studi Kasus Kelompok Pengrajin Tahu Ngudi
Lestari Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta), sehingga
kualitas air sungai, air sumur dan udara dapat terjaga kebersihannya. Jadi penulis
11
berani menjamin bahwa penelitian ini benar-benar asli yang dilakukan oleh
penulis.
4. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam
kajian lingkungan dan menjadi solusi dalam mengatasi pencemaran
limbah organik.
b. Bagi filsafat
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya studi filsafat dalam
mengkaji dan mengembangkan mata kuliah etika lingkungan.
c. Bagi bangsa dan negara
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini yang dipublikasikan
dapat menggugah masyarakat agar timbul kesadaran moral untuk peka
dan peduli terhadap lingkungan. Khususnya untuk para pemilik
industri agar memperhatikan dalam proses pembuangan limbah
industri. Salah satunya dengan membuat instalasi pengolahan air
limbah biogas seperti yang dilakukan oleh kelompok perajin Tahu
Budi Lestari di Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandaan, Bantul
Yogyakarta yang sangat peduli dengan lingkungan.
12
B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan jawaban dari permasalahan yang
telah terangkum dalam rumusan masalah, yaitu:
1. Memaparkan penjelasan secara mendalam tentang proses pengolahan limbah
cair tahu dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas pada
Kelompok Pengrajin Tahu Ngudi Lestari Dusun Gunung Saren Trimurti,
Srandakan, Bantul Yogyakarta.
2. Menjelaskan tentang teori etika lingkungan Ekosentrisme sebagai teori etika
yang menjelaskan manusia wajib menjaga dan melindungi makhluk hidup
maupun benda mati seperti sungai dan lain-lain, dan ketika lingkungan terjaga
maka kelangsungan hidup manusia akan terjamin.
3. Menganalisis penerapan pemikiran teori etika Ekosentrisme dalam
pengendalian pencemaran limbah cair tahu melalui instalansi pengolahan air
limbah (IPAL) biogas kelompok pengrajin Tahu Ngudi Lestari di Dusun
Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta.
C. Tinjauan Pustaka
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) biogas merupakan model tempat
pengolahan limbah cair organik yang akan mengalami proses anaerobik sehingga
menghasilkan gas. Tujuan utama dari IPAL biogas adalah mengendalikan
pencemaran limbah cair organik agar tidak mencemari lingkungan. Biogas yang
dihasilkan dari IPAL biogas dapat dimanfaatkan secara optimal yaitu untuk
13
kebutuhan rumah tangga seperti memasak dan untuk penerangan (Yunus, 1995:
77).
Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) biogas pada kelompok pengrajin
tahu Ngudi Lestari merupakan IPAL biogas pertama di Kecamatan Srandakan.
IPAL biogas dibangun untuk mengatasi pencemaran limbah cair tahu. DEWATS
(Decentralized Waste Water Treatmen System) yang memberi bantuan berupa
dana untuk membangun IPAL biogas (Sumber: Kecamatan Srandakan, 2008).
Komponen-komponen kimia dalam air limbah dapat diklasifikasikan
dalam tiga kelompok yang disebut zat-zat organik yang terdiri atas senyawa-
senyawa organik alam dan senyawa-senyawa organik sintesis, bahan-bahan
organik, dan gas. Zat-zat organik yang terdapat di dalam air dalam kadar rendah
dan hanya sebagian kecil dari seluruh jumlah padatan yang ada. Keberadaan
senyawa organik di dalam air akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain
masalah rasa dan bau. Keberadaan senyawa organik juga menyebabkan air
memerlukan proses pengolahan air bersih yang lebih kompleks menurunkan
kandungan oksigen, serta menyebabkan terbentuknya substansi-substansi beracun
(Siregar, 2005: 15-16). Zat-zat organik di dalam limbah cair tahu akan diolah
melalui IPAL biogas sehingga menjadi biogas.
Penanganan limbah cair meliputi berbagai proses yaitu penyaluran,
pengumpulan, pengolahan limbah cair, serta pembuangan lumpur yang dihasilkan.
Penanganan limbah cair merupakan hal yang penting karena berhubungan dengan
masalah pencemaran lingkungan, baik kontaminasi sungai, kontaminasi air
permukaan, maupun kontaminasi air tanah yang diakibatkan oleh limbah cair
14
rumah tangga, limbah cair pertanian, dan limbah cair industri. Pembuangan
limbah cair secara langsung ke badan air akan menimbulkan masalah kesehatan
sehingga perlu dibangun fasilitas pengolahan air limbah cair (Soeparman dan
Suparmin, 2001: 91). Fasilitas tersebut salah satunya adalah instalasi pengolahan
air limbah (IPAL) biogas.
Penanganan limbah cair dari jenis dan jumlah proses pengolahan limbah
cair bergantung pada kualitas influen dan pemanfaatan efluen limbah cair. Jenis
teknologi yang digunakan bergantung pada analisis kualitas limbah cair serta
penggunaan efluen. Efluen limbah cair dengan konsentrasi tinggi yang dibuang di
sungai dapat dimanfaatkan sebagai air baku minum, namun memanfaatkan air
tersebut menuntut proses pengolahan yang lengkap dibandingkan limbah cair
yang dibuang ke dalam saluran irigasi untuk pertanian (Soeparman dan Suparmin,
2001: 92).
Limbah tahu dibedakan dua macam yaitu limbah padat dan limbah cair.
Limbah padat pabrik pengolahan tahu berupa kotoran hasil pembersihan kedelai
dan sisa saringan sari kedelai yang disebut ampas tahu. Kedua jenis limbah
tersebut harus ditangani agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Kotoran hasil pembersihan kedelai berupa tanah, kerikil, potongan-potongan
tangkai, dan kotoran lainnya ditampung, lalu dibuang ketempat pembuangan
sampah. Limbah padat berupa kulit biji kedelai dan ampas tahu ditangani secara
terpisah karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau ampas tahu diolah
menjadi tempe gembus atau oncom, sedangkan untuk limbah cair dari hasil
industri tahu pada suhu rata-rata berkisar 40-60 ∘c. Suhu tersebut lebih tinggi
15
dibandingkan suhu rata-rata air lingkungan membahayakan kelestarian
lingkungan hidup apabila pembuangan dilakukan secara langsung tanpa proses
(Suwarno dan Yan, 2001: 60-61).
Proses pengolahan limbah cair tahu dalam IPAL biogas yaitu pemisahan
benda-benda kasar yang terdapat dalam air buangan pada bak digester, dengan
cara penyaringan atau pemisahan padatan pada tahap awal sebelum air limbah
diproses lebih lanjut pada bak peluapan, bak perata, dan bak reactor. Proses
pemisahan pada bak digester mengurangi jumlah benda-benda kasar (padat) yang
terdapat dalam air buangan dapat menurunkan kadar polutan. Proses pengolahan
limbah cair tahu pada bak digester mengalami proses anaerobik dengan kedap
udara sehingga menghasilkan biogas (Pramudyanto, 1991: 16).
Arahan dan strategi pengolahan lingkungan untuk mengatasi permasalahan
lingkungan di Kelompok Pengrajin Tahu Ngudi Lestari Dusun Gunung Saren
Trimurti, Srandaan, Bantul Yogyakarta dapat dilakukan dengan pendekatan
bersifat fisik seperti pembangunan IPAL biogas untuk mengatasi limbah dan
pendekatan nonfisik dengan menekankan pembinaan kepada masyarakat pengrajin
tahu yang lain, sebagai penyebab terjadinya pencemaran. Pendekatan lebih
cenderung pendekatan kelembagaan menyangkut tugas pokok fungsi
pemerintahan daerah kabupaten bantul, baik melalui pembangunan IPAL ataupun
pembinaan sosial budaya sebagai penyebab terjadinya penurunan kualitas air yang
disebabkan oleh limbah cair (Mardiana, 2008: 106).
16
D. Landasan Teori
Kehancuran lingkungan disebabkan oleh profanasi dan eksploitasi alam
secara besar-besaran. Keserakahan dan keangkuhan manusia perlu dikoreksi
dengan pola pikir baru, misalnya dengan mengangkat kembali kearifan-kearifan
lokal yang menghormati alam (Sunarko dan Eddy, 2008: 189). Sikap menjaga dan
melindungi alam agar tidak rusak adalah wajib karena apabila manusia
mementingkan dirinya sendiri untuk mencapai kebahagiaan dengan
memanfaatkan alam secara besar-besaran maka ekosistem akan mengalami
kehancuran.
Alam merupakan penopang kehidupan, maka alam patut dihargai dan
diperlakukan dengan baik. Manusia harus menjaga dan memelihara alam untuk
kepentingan bersama atau kepentingan semua. Inilah yang ditekankan oleh etika
ekosentrisme (Borrong, 2000: 153). Manusia dianggap lebih unggul dari makhluk
lainnya, oleh karena itu manusia wajib untuk tidak memanfaatkan alam secara
berlebihan.
Konsep Ekosentrisme menggagas manusia sebagai bagian dari alam
ciptaan. Kesetaraan manusia dengan semua ciptaan lainnya dan tugasnya adalah
memelihara relasi harmonisnya dengan alam. Kesetaraan manusia dengan hewan-
hewan adalah dalam hal sumber kehidupan. Sama seperti semua hewan,
demikianlah manusia merupakan makhluk hidup, dengan ciptaan abiotik lainnya.
Manusia dalam kitab kejadian mempunyai arti “tanah” atau “bumi”. Manusia
memiliki kesetaraan dengan ciptaan-ciptaan lainnya, baik yang abiotik maupun
yang biotik, mungkin ungkapan klasik orang Dayak misalnya mengungkapkan
17
kesetaraan alkitabiah, yakni kami tidak tinggal di “hutan”, kami adalah” hutan”.
Etika Ekosentrisme perlu memperhatikan kebijakan lokal akan menunjukan
kedekatan manusia dengan alam sekaligus merupakan kekuatan resistensi untuk
melawan kebijakan manipulatif dari pihak asing, termasuk pemerintah pusat
(Sunarko dan Eddy, 2008: 194-195).
Ekosentrisme menempatkan alam itu sendiri menjadi pusat dari alam
semesta, karena manusia adalah bagian dari alam, maka manusia itu tidak jauh
berbeda dibandingkan dengan makhluk lain yang juga bagian dari alam. Makhluk
dalam definisi pemikiran Ekosentrisme juga mencakup benda mati. Benda mati
seperti batu, tanah, air, dan udara juga merupakan makhluk yang setara dengan
manusia. Hubungan manusia dengan alam tidak hanya merupakan hubungan
antara makhluk yang lebih mulia dengan makhluk yang rendah. Pandangan
Ekosentrisme memaksa manusia untuk juga menerapkan prinsip moralitas dan
hubungan etika dengan alam yang terdiri dari hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung
air, dan lain-lain (Faisal, 2010: 178).
Manusia mempunyai martabat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk
hidup lainnya. Manusia mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan,
walaupun manusia termasuk alam dan sepenuhnya dapat dianggap sebagai bagian
alam, namun hanya manusia yang sanggup melampaui status alaminya dengan
memikul tanggung jawab. Tanggung jawab dalam konteks ekonomi apabila
dikaitkan dengan adanya industri tahu adalah melestarikan lingkungan hidup atau
memanfaatkan sumber daya alam demikian rupa sehingga kualitas lingkungan
18
tidak dikurangi, tetapi bermutu sama seperti sebelumnya (Bertens, 2000: 325-
326).
Gerakan teori etika lingkungan Ekosentrisme yakni Deep Ecology, adalah
yang paling mungkin sebagai alternatif untuk memecahkan dilemma etis ekologis.
Hal yang paling penting dalam Ekosentrisme adalah tetap bertahannya semua
yang hidup dan tidak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat, seperti
halnya manusia, semua benda kosmis memiliki tanggung jawab moralnya sendiri
(J. Sudriyanto dalam Santosa, 2000: 71-72).
E. Metode Penelitian
1. Bahan dan Materi Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan model penelitian
masalah aktual dilakukan, melalui studi pustaka dan diperkuat dengan wawancara
dan observasi lapangan. Wawancara dan observasi lapangan dilakukan di
kelompok pengrajin Tahu Budi Lestari di Dusun Gunung Saren Trimurti,
Srandakan, Bantul Yogyakarta tentang Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
biogas dari limbah tahu sebagai pengendali pencemaran lingkungan sebagai objek
material, sedangkan teori etika lingkungan Ekosentrisme sebagai objek formal
(Kaelan, 2005: 292).
a. Sumber Primer
Sumber primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara dan observasi di lapangan dan juga buku-buku yang berkaitan
19
dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas. Buku-buku yang
membahas limbah cair tahu dapat juga dijadikan sebagai acuan. Sumber
tersebut antara lain:
1.) Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan
Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Jakarta: Kanisius.
2.) Mardiana, Hayya. 2008. Kajian Kerusakan Akibat Kegiatan
Industri Tahu terhadap Penurunan Kualitas Air Tanah (Kasus
Di Kawasan Sentra Industri Tahu Desa Trimurti Kecamatan
Srandakan Kabupaten Bantul). Tesis. Yogyakarta: Universitas
Gadjah Mada.
3.) Sarwono, B dan Yan Pieter Saragih. 2001. Membuat Aneka
Tahu. Bogor: PT Penebar Swadaya, anggota Ikapi Redaksi.
4.) Siregar, sakti.A. Instalasi Pengolahan Ar Limbah. 2005.
Yogyakarta: Kanisius.
5.) Yunus, Mokhammad. 1995. Teknik Membuat dan
Memanfaatkan Unit Gas Bio. Gadjah Mada University Press.
6.) Data dari Kecamatan Srandakan tentang IPAL Biogas yang
berada di kelompok pengrajin tahu Ngudi Lestari Dusun
Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta serta
pemberi dana pembuatan IPAL Biogas tersebut.
20
b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
referensi yang diperoleh dari berbagai tulisan, artikel, jurnal atau makalah,
juga internet. Sumber tersebut antara lain :
1.) Attfield, Robin. 2010. Etika Lingkungan Global. Yogyakarta:
Kreasi Wacana.
2.) Borrong, Robert. P. 2000. Etika Bumi Baru. Jakarta: PT. BPK
Gunung Mulia.
3.) Faisal. K, Moch. 2010. The End Of Future (rahasia di balik
peperangan, kehancuran dan kiamat di masa depan). Jakarta:
NF Media Center.
4.) Keraf, Sonny. 2006. Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.
5.) Sunarko. A, OFM. A Eddy Kristyanto, OFM . 2008. Menyapa
Bumi Menyembah Hyang Ilahi. Yogyakarta: Kanisius.
2. Jalan Penelitian
Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Inventarisasi dan kategorisasi: pengumpulan data kepustakaan yang
berkaitan dengan objek material maupun objek formal penelitian
sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dan juga data hasil
penelitian dilapangan berupa wawancara. Data kepustakaan dan
penelitian di lapangan berupa wawancara tentang Instalasi Pengolahan
21
Air Limbah (IPAL) biogas sebagai upaya pengendalian pencemaran
limbah cair tahu studi kasus kelompok pengrajin tahu Ngudi Lestari
Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandakan, Bantul Yogyakarta,
sehingga memperoleh gambaran lengkap tentang latar belakang adanya
IPAL biogas, proses pengolahan air limbah maupun biogas yang
dihasilkan sebagai objek material, dan memperoleh gambaran lengkap
dan menyeluruh tentang teori etika lingkungan Ekosentrisme sebagai
objek formal.
b. Klasifikasi: setelah data terkumpul, dilakukan pengelompokan data
menjadi bagian data primer dan sekunder.
c. Analisis-sintesis: menganalisa data, baik yang berasal dari data primer
maupun data sekunder. Data yang sekiranya kurang relevan akan
dieliminasi, sedangkan data yang sesuai dengan gagasan serta
memperkuat penelitian akan disintesiskan.
d. Evaluasi kritis: setelah melalui tahapan analisis-sintesis, dilakukan
verifikasi data dan gagasan atas penelitian ini sehingga menghasilkan
pemaparan hasil yang kritis secara berimbang dan objektif.
3. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat metode Kaelan
(2005: 297-299), sebagai berikut:
a. Verstehen: data yang dikumpulkan dipahami berdasarkan karakteristik
masing-masing. Penulis memahami IPAL biogas sebagai upaya
22
pengendalian lingkungan, serta memahami makna teori etika
lingkungan Ekosentrisme, sehingga mendapat gambaran tentang objek
material dan objek formal.
b. Interpretasi: dalam data yang diperoleh, penulis akan mencoba
menemukan gambaran yang jelas dan mendalam tentang hal-hal yang
melatar belakangi adanya IPAL Biogas sebagai upaya pengendalian
pencemaran limbah cair tahu studi kasus kelompok perajin tahu Ngudi
Lestari Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandaan, Bantul Yogyakarta,
proses pelaksanaan IPAL Biogas, Manfaat IPAL Biogas, kondisi
lingkungan sesudah dan sebelum adanya IPAL Biogas, peran
masyarakat dalam pengadaan dan perawatan IPAL Biogas. Gambaran
yang jelas dan mendalam dari data yang diperoleh selanjutnya ditinjau
menggunakan perspektif teori etika lingkungan Ekosentrisme.
c. Hermeneutika: penulis berusaha menangkap makna esensial dari teori
etika lingkungan Ekosentrisme dalam memandang IPAL bioagas
sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang disebabkan
limbah cair dari industri tahu.
d. Holistika: melihat data secara keseluruhan terutama tentang IPAL
Biogas dan peranan masyarakat kelompok perajin tahu Ngudi Lestari
Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandaan, Bantul Yogyakarta dalam
pengendalian pencemaran lingkungan serta analisa teori etika
lingkungan Ekosentrisme dalam memandang pengendalian
pencemaran limbah cair lalu dilakukan penyimpulan.
23
F. Hasil Yang Telah Dicapai
Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Memperoleh penjelasan yang mendalam tentang proses pengolahan air limbah
tahu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas pada kelompok
pengrajin tahu Ngudi Lestari Dusun Gunung Saren Trimurti, Srandakan,
Bantul Yogyakarta.
2. Memperoleh penjelasan tentang teori etika lingkungan Ekosentrisme.
3. Memperoleh pemahaman mengenai pandangan teori etika Ekosentrisme
tentang pengendalian limbah cair hasil pengolahan tahu melalui Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
permasalahan, rumusan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan
penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil yang ingin
dicapai, dan sistematika penulisan.
Bab II berisi tentang pengenalan tentang latar belakang adanya IPAL
Biogas di kelompok perajin tahu Ngudi Lestari di Bantul Yogyakarta, kemudian
akan dijelaskan tentang proses pengolahan limbah cair tahu pada IPAL Biogas,
uraian tentang kondisi lingkungan sebelum dan sesudah adanya IPAL biogas pada
kelompok pengrajin tahu Ngudi Lestari di Bantul Yogyakarta, manfaat Instalasi
24
Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas, serta dijelaskan tentang kepedulian warga
gunung saren terhadap limbah cair tahu serta dalam pembuatan ipal biogas.
Bab III berisi uraian mengenai teori etika lingkungan Ekosentrisme.
Namun juga akan diuraikan tentang pengertian etika lingkungan, ekologi dan
manusia, pencemaran dan krisis lingkungan, teori-teori etika lingkungan.
Bab IV berisi tentang penerapan pandangan Ekosentrisme dalam menilai
adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) biogas di kelompok pengrajin
tahu Ngudi Lestari di Bantul Yogyakarta sebagai upaya pengendalian pencemaran
limbah cair dari hasil pengolahan tahu, serta dijelaskan upaya pengelolaan limbah
tahu dengan IPAL biogas.
Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dengan
menjelaskan secara garis besar pembahasan penelitian.