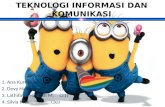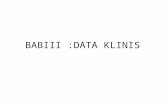BAB 3& 4
description
Transcript of BAB 3& 4

BAB 3
STRUKTUR GARIS
3.1. Tujuan
a. Mampu menggambarkan geometri struktur garis ke dalam
proyeksi dua dimensi (secara grafis).
b. Mampu menentukan plunge dan rake/pitch suatu garis pada
suatu bidang.
c. Mampu menentukan kedudukan struktur garis yang merupakan
perpotongan dua bidang.
3.2. Alat dan Bahan.
1. Penggaris, busur derajat
2. Jangka dan alat tulis lengkap
3.3. Definisi
Struktur garis adalah struktur batuan yang membentuk geometri garis,
antara lain gores garis, sumbu lipatan, dan perpotongan dua bidang.
Struktur garis dapat dibedakan menjadi stuktur garis riil, struktur garis
semu.
Pengertian :
Struktur garis riil : struktur garis yang arah dan
kedudukannya dapat diamati dan
diukur langsung dilapangan, contoh:
gores garis yang terdapat pada
bidang sesar.
Struktur garis semu :semua struktur garis yang arah atau
kedudukannya ditafsirkan dari
orientasi unsur-unsur struktur yang
membentuk kelurusan atau liniasi.
contoh: liniasi fragmen breksi sesar,
liniasi mineral-mineral dalam batuan
beku, arah liniasi struktur sedimen
(cross bedding, flute cast) dan
sebagainya.

Berdasarkan saat pembentukannya, struktur garis dapat dibedakan
menjadi struktur garis primer yang meliputi: liniasi atau penjajaran
mineral-mineral pada batuan beku tertentu, dan arah liniasi struktur
sediment. Struktur garis sekunder yang meliputi: gores garis, liniasi
memanjang fragmen breksi sesar, garis poros lipatan dan kelurusan-
kelurusan dari topografi, sungai dan sebagainya.
Kedudukan struktur garis dinyatakan dengan istilah-istilah : arah
penunjaman (trend), penunjaman (plunge, baca : planj), arah
kelurusan (bearing, baca : biring) dan rake atau pitch.
3.3.1. Definisi Istilah - istilah dalam Struktur Garis.
Arah penunjaman (trend) : Azimuth yang menunjukkan arah
penunjaman garis tersebut, dan hanya
menunjukkan satu arah tertentu (Gambar
3.1).
Arah kelurusan (bearing) : Azimuth yang menunjukkan arah kelurusan
garis tersebut. Kelurusan ini memiliki dua
pembacaan dimana salah satu arahnya
merupakan sudut pelurusnya (Gambar 3.1).
Plunge : Dip penunjaman (Gambar 3.1).
Rake/pitch : Besar sudut antara struktur garis dengan
garis horisontal yang diukur pada bidang
dimana garis tersebut terdapat dan
membentuk sudut terkecil (sudut lancip)
(Gambar 3.1).

Gambar 3.1
Struktur garis dalam blok tiga dimensi
Keterangan :
A – L : Struktur garis pada bidang ABCD
A – K : Arah penunjaman (trend)
A – L / K – A : Arah kelurusan (bearing) = azimuth NAK
Β : Penunjaman (plunge)
γ : Rake (pitch)
3.2. CARA PENGUKURAN STRUKTUR GARIS DENGAN KOMPAS
GEOLOGI

A.Cara pengukuran struktur garis yang mempunyai arah penunjaman
(trend)
B.Cara pengukuran struktur garis yang tidak mempunyai arah
penunjaman (trend)
A.CARA PENGUKURAN STRUKTUR GARIS YANG MEMPUNYAI
ARAH PENUNJAMAN (TREND)
Cara pengukuran arah penunjaman (trend ) : (Gambar 3.2)
1. Menempelkan alat bantu (buku lapangan atau “clipboard”)
pada posisi tegak dan sejajar dengan arah yakni struktur garis
yang diukur.
2. Menempelkan sisi “W” atau “E” kompas pada posisi kanan atau
kiri alat bantu dengan visir kompas (sigthing arm) mengarah
pada penunjaman struktur garis tersebut.
3. Menghorizontalkan kompas (nivo mata sapi dalam keadaan
horizontal/gelembung berada di tengah nivo), maka harga
yang ditunjuk oleh jarum utara kompas adalah harga arah
penunjamannya (trend).
Cara pengukuran sudut penunjaman (plunge) : (Gambar 3.2.a)
1. Menempelkan sisi “W” kompas pada sisi atas alat bantu yang
masih dalam keaadan vertikal.
2. Memutar “clinometer” hingga gelembung pada nivo tabung
berada di tengah nivo dan besar sudut penunjaman (plunge)
merupakan besaran sudut vertikal yang ditunjukkan oleh
penunjuk pada skala “clinometer”
Cara pengukuran Rake/Pitch : (Gambar 3.2.b)
1. Membuat garis horizontal pada bidang dimana struktur garis
tesebut terdapat ( dimana, garis horizontal sama dengan jurus
dari bidang tersebut) yang memotong struktur garis.
2. Mengukur besar dari sudut lancip yang dibentuk oleh garis
horizontal (dengan menggunakan busur derajat).
Cara pengukuran arah kelurusan (bearing) : (Gambar 3.2.a)

1. Arah visir kompas sejajar dengan unsur-unsur kelurusan struktur
garis yang akan diukur, misalnya sumbu terpanjang pada
fragmen breksi sesar.
2. Menghorizontalkan kompas (gelembung nivo mata sapi berada
di tengah nivo), dengan catatan, posisi kompas masih seperti
no.1 tersebut di atas, maka harga yang ditunjuk oleh jarum
utara kompas adalah harga arah bearing-nya.
B. CARA PENGUKURAN STRUKTUR GARIS YANG TIDAK
MEMPUNYAI ARAH PENUNJAMAN (TREND) / HORIZONTAL
(PENGUKURAN KELURUSAN/ LINEMENT)
Adapun yang termasuk struktur garis yang tidak mempunyai arah
penunjaman (trend) umumnya berupa arah-arah kelurusan, misalnya :
arah liniasi fragmen breksi sesar, arah kelurusan sungai, dan arah
kelurusan gawir sesar.
Jadi yang perlu diukur hanya arah kelurusan (bearing) saja (Gambar
3.2.c dan 3.2.d).

(a) (b)
(c)
(d)
Gambar 3.2
3.4. Aplikasi Struktur Garis
Aplikasi yang akan dibahas meliputi pemecahan dua masalah utama
struktur garis:
A. Menentukan plunge dan rake sebuah garis pada sebuah bidang.
B. Menentukan kedudukan garis hasil perpotongan dua buah bidang.

A. Menentukan plunge dan rake sebuah garis pada sebuah
bidang
Pada bidang ABCD dengan kedudukan N 000° E/45°, terletak garis AQ
dengan arah penunjaman N 135° E. Berapa besarnya plunge dan rake
garis AQ ?
Penyelesaian secara grafis: (Gambar 3.3)
1. Membuat proyeksi horisontal bidang ABCD dengan kedalaman 'd'.
2. Dari titik 'A' membuat garis dengan arah N 135°E, sehingga
memotong jurus pada kedalaman 'd' di titik 'P'.
3. Melalui 'P' membuat garis PQ ( panjang = d ) tegak lurus AP, maka
sudut PAQ adalah besarnya "plunge" = 35°.
4. Memutar bidang ABCD sampai posisinya horisontal dengan "folding
line" garis AB, yakni dengan memanjangkan garis AD, ke 'Dr'
dengan pusat putar titik A.
5. Dari 'Dr' membuat garis sejajar lurus (AB), maka garis ini
merupakan jurus pada kedalaman 'd' setelah bidang ABCD diputar
ke posisi horisontal.
6. Membuat melalui 'P' garis tegak lurus pada garis butir (5), serta
memotongnya dititik 'Qr'.
7. Menghubungkan 'Qr' dengan 'A', maka sudut 'BAQt' adalah
besarnya rake 54°.

Gambar 3.3
Penentuan plunge dan rake: (a) penggambaran dalam blok diagram
(b) analisis secara grafis
B. Menentukan Kedudukan Garis Perpotongan dari Dua buah
bidang
Dua buah bidang yang masing-masing kedudukannya diketahui, yaitu
bidang ABEK dan CDFK saling berpotongan tegak lurus. Perpotongan
antara keduanya merupakan suatu garis lurus dan dapat ditentukan
kedudukannya yaitu dinyatakan dengan : plunge, rake, bearing
(Gambar 3.4 dan Gambar 3.5)
Keterangan :

KL adalah trace (garis potong), sudut OKL adalah plunge ( β ), sudut δ1
adalah rake
KL pada bidang ABEK, sudut δ2 adalah rake KL pada bidang CDFK, arah
KO adalah bearing, diukur terhadap arah utara.
Contoh soal . :
Batugamping dengan kedudukan N 048°E / 300 NW terpotong intrusi
Dike dengan kedudukan N 021 °W / 50° NE, sehingga pada jalur
perpotongannya terdapat mineralisasi. Tentukan kedudukan jalur
perpotongannya !
Penyelesaian secara grafis: (Gambar 3.4)
1. Menggambar strike batugamping dan intrusi dike yang
berpotongan di O.
2. Menggambarkan proyeksi horisontal batugamping dan dike pada
kedalaman ‘d ' dengan menggunakan FLI dan FL2, sehingga
tergambar jurus dengan kedalaman 'd' dari batugamping dan
intrusi dike serta berpotongan di C.
3. Garis OC adalah proyeksi horisontal jalur perpotongan, yang
merupakan bearing-nya, yaitu dengan mengukur sudut antara
garis OC terhadap arah utara, terhitung 0°, jadi bearing-nya
adalah N 000° E.
4. Melalui C membuat garis CD (panjang = d) tegak lurus OC.
Sudut COD adalah plunge terhitung = 24°.
5. Memutar bidang batugamping dan dike sampai posisi horisontal,
maka tergambar rebahan masing-masing jurus pada kedalaman
'd'
6. Membuat garis CDrg dan CDrd yang masing-masing tegak lurus
pada garis jurus.
7. Garis ODrg adalah rebahan OD pada batugamping dan ODrd
adalah rebahan OD pada dike.
8. Sudut BODrg adalah rake pada batugamping = 53°
9. Sudut AODrd adalah rake pada dike = 32°
10.Jadi kedudukan garis potongnya adalah = 24°, N 000° E

Batugamping
Intrusi Dike
Gambar 3.4Penentuan unsur-unsur strukur garis perpotongan dari dua buah bidang
dengan menggunakan proyeksi grafis

Gambar 3.5Kedudukan struktur garis perpotongan dari dua buah bidang dalam
kenampakan tiga dimensiKeteranganK – L : Struktur garis dari perpotongan bidang
ABEK dan bidang CDEKK – O : Arah penunjaman (trend)K – O / O – K : Arah kelurusan (bearing) = azimuth NKOΒ : Penunjaman (plunge)α1 : Rake (pitch) terhadap bidang ABEKα2 : Rake (pitch) terhadap bidang CDFK
BAB 4
PROYEKSI STEREOGRAFIS DAN PROYEKSI KUTUB
4.1. Tujuan
a. Mampu memecahkan masalah geometri bidang dan geometri
garis secara stereografis.
b. Mampu menggunakan proyeksi stereografis sebagai alat bantu
dalam tahap awal analisis data yang diperoleh di lapangan untuk
berbagai macam data struktur.
4.2. Alat – alat praktikum

1. Alat tulis lengkap, stereonet dan paku pines
2. Kalkir ukuran 20 x 20 cm ( 4 lembar )
4.3. Proyeksi Stereografis
4.3.1. Definisi
Merupakan proyeksi yang didasarkan pada perpotongan bidang / garis
dengan suatu permukaan bola. Unsur struktur geologi akan lebih
nyata, lebih mudah dan cepat penyelesaiannya bila digambarkan
dalam bentuk proyeksi permukaan bola. Permukaan bola tersebut
meliputi suatu bidang dengan pusat bola yang terlihat pada bidang
tersebut maka bidang tersebut memotong permukaan bola sepanjang
suatu lingkaran, yaitu lingkaran besar. Gambar 4.1 menunjukkan
perbandingan antara proyeksi orthografi dengan proyeksi permukaan
bola.
Yang dipakai sebagai gambaran posisi struktur di bawah permukaan
adalah belahan bola bagian bawah. Selanjutnya proyeksi permukaan
bola digambarkan pada permukaan bidang horisontal dalam bentuk
proyeksi stereografis. Hal tersebut didapat dari perpotongan antara
bidang horisontal yang melalui pusat bola dengan garis yang
menghubungkan titik-titik pada lingkaran besar terhadap titik
zenithnya. Gambaran proyeksi yang didapat disebut dengan
stereogram dan hubungan sudut di dalam proyeksi stereografi seperti
nampak pada Gambar 4.2. Dari gambar tersebut tampak bahwa
pengukuran besar sudut selalu dimulai dari 0 di tepi lingkaran
(lingkaran primitif) dan 90° di pusat lingkaran.
Hubungan antara proyeksi permukaan bola dengan pembuatan
lingkaran besar dan lingkaran kecil seperti pada Gambar 4.3.

Gambar 4.1

Gambar 4.2
Gambar 4.3
Macam-macam proyeksi sterografi :
1. Equal angle projection net atau Wulf net.
2. Equal area projection net atau Schmidt net.
3. Orthographic net.
Dalam proyeksi ini, penggunaan ketiga jaring tersebut pada prinsipnya
sama, yaitu 0° dimulai dari lingkaran primitif dan 90° di pusat
lingkaran.
Wulf Net
Misalkan pada bidang kedudukan N 000° E/ 45° terletak garis dengan
arah N 045° E. Maka hubungan antara proyeksi gambaran orthografi,
stereografis, dan stereogramnya dapat dilihat pada Gambar 4.4.a,
4.4.b, dan 4.4.c.

(a) (b)
(c)
Gambar 4.4
Keterangan gambar :Struktur bidang : strike = NOE
dip = EC' atau sudut COC'

Struktur garis OB' : bearing = busur NF rake/pitch = busur NB' atau sudut.BON plunge = B'F Itau sudut BOB'
Stereogram struktur bidang adalah busur NB'C'SStereogram struktur garis adalah garis OB' .
4.3.2. Struktur Bidang
Stereogram struktur bidang selalu diwakili oleh lingkaran besar,
sehingga besar sudut kemiringan selalu diukur pada arah E - W jaring,
yaitu 0° pada lingkaran primitif dan 90° di pusat lingkaran.
Contoh:
Penggambaran stereogram bidang N 045° E/300 sebagai berikut :
Letakkan kertas kalkir di atas stereonet dan gambarkan lingkaran
primitifnya. Beri tanda N, E, S, dan W serta titik pusat lingkaran.
Gambar garis strike melalui pusat lingkaran sesuai dengan
harganya (Gambar 4.5.a).
Putar kalkir sampai garis strike berimpit dengan garis N - S jaring.
Lalu gambar garis busur lingkaran besar sesuai dengan besarnya
dip (ingat prinsip aturan tangan kanan) (Gambar 4.5.b).
Putar kalkir sehingga N kalkir berimpit dengan jaring, maka nampak
stereogram dari bidang N O45° E / 30° (Gambar 4.5.c).

(a) (b)
(c)
Gambar 4.5
Penggambaran stereogram bidang N 045° E/300
4.3.3. Struktur Garis

45 0N
F
F
E
D
F
O
O
D
3O
S
N45 0
F
EO
S
D
Plunge
Stereogram struktur garis berupa suatu garis lurus dari pusat
lingkaran. Besarnya plunge dihitung 0° pada lingkaran primitif dan 90°
di pusat lingkaran dan diukur pada kedudukan bearing berimpit
dengan N-S atau E-W jaring.
Contoh:
Penggambaran stereogram garis kedudukan 30° ,N 045° E sebagai
berikut :
Tentukan titik pada lingkaran primitif sesuai harga bearing, dan
hubungkan dengan pusat lingkaran, sehingga merupakan garis
lurus (Gambar 4.6.a).
Putar kalkir sehingga garis tersebut berimpit dengan N-S atau E-W
jaring, kemudian ukur besarnya plunge (Gambar 4.6.b).
Putar kalkir sehingga N-kalkir berimpit dengan N-jaring maka OD
merupakan stereogram garis kedudukan 30°, N 045° E (Gambar
4.6.c).

(a) (b)
(c)Gambar 4.6
Penggambaran stereogram garis kedudukan 30° ,N 045° E
4.4 Aplikasi Metode Stereografis Dalam Berbagai Jenis Kasus
Aplikasi metode Stereografis yang akan diterapkan pada praktikum ini
meliputi :
A. Menentukan Apparent Dip, Plunge dan Rake Suatu Garis
B. Menentukan Kedudukan Bidang Dari Dua Kemiringan Semu
C. Menentukan Kedudukan Garis Potong Dari Dua Bidang Yang
Berpotongan
Di bawah ini diberikan contoh-contoh cara penyelesaian kasus A – C.
A. Menentukan Apparent Dip, Plunge dan Rake Suatu Garis
Suatu bidang kedudukan N 050° E/50°. Tentukan apparent dip pada
arah N 080° E!
Penyelesaian :
Gambar stereogram bidang N 050° E / 50° dan garis arah apparent
dip N 080° E (Gambar 4.7.a).
Putar kalkir sampai garis arah N 080° E tersebut berimpit dengan E-
W jaring dan baca besarnya apparent dip pada garis tersebut
dimana 0° pada lingkaran primitif (Gambar 4.7.b).
Jika pada bidang N 050° E / 50° ini terletak garis yang arahnya N 080°
E, dengan cara seperti di atas didapat besarnya plunge garis tersebut
adalah 31° (Gambar 4.8.a dan 4.8.b). Sedangkan besarnya
rake/pitch didapat sebagai berikut:

a. Putar kalkir sehingga garis strike bidang N 050° E/ 50° berimpit
dengan N-S jaring. Dan besarnya rake dihitung pada busur
lingkaran besar bidang tersebut dengan menggunakan lingkaran
kecil serta dipilih yang lebih kecil dari 90°, yaitu dimulai dari N-
jaring sampai ke perpotongan garis dengan busur lingkaran besar
bidang tesebut, besarnya didapat 12° (Gambat 4.8.c).
Gambar 4.7Penggambaran stereogram bidang N 050° E / 50° dan garis arah apparent dip
N 080° E

Gambar 4.8Penentuan plunge dan rake/pitch dari garis N 080° E pada bidang N 050° E /
50°
B. Menentukan Kedudukan Bidang Dari Dua Kemiringan Semu
Dua kemiringan semu suatu lapisan batupasir diketahui sebagai
berikut :
A. 25° pada arah N 010° E
B. 34° pada arah N 110° E
Tentukan arah kedudukan batupasir tersebut!
Penyelesaian :
Gambar masing-masing arah kemiringan semunya, yaitu N 010° E
dan N ll0° E (Gambar 4.9.a).
Putar kalkir sehingga arah kemiringan semu N 010° E berimpit
dengan E-W jarring, plot besar kemiringan semu 25° dihitung dari
lingkaran primitif, yaitu titik A (Gambar 4.9.b).
Begitu juga untuk kemiringan semu 34° pada arah N llO° E, yaitu
titik B (Gambar 4.9.c).
Kalkir diputar-putar sehingga titik A dan B terletak dalam satu
lingkaran besar. Dan gambar lingkaran besar tersebut beserta garis
strike-nya, serta hitung besarnya dip, yaitu didapat 42° (Gambar
4.9.d).
Putar kalkir sehingga N kalkir berimpit dengan N jaring maka
kedudukan batupasir dapat dibaca, yaitu N 340° E / 42° (Gambar
4.9.e).

a b
(a) (b)
c d
(c) (d)
e
(e)

EW
N
S
EW
N
S
EW
N
S
10o
Gambar 4.9Menentukan Kedudukan Bidang Dari Dua Kemiringan Semu
C. Menentukan Kedudukan Garis Perpotongan Dari Dua Bidang
Suatu bidang A kedudukan N 010° E / 30° berpotongan dengan bidang
B kedudukan N 130° E/ 50°. Tentukan kedudukan garis potonganya!
Penyelesaian :
Gambarkan stereogram kedua bidang tersebut (Gambar 4.10.a).
OB adalah stereogram garis potongnya, sedangkan busur NEF
adalah bearing OB yang diukur pada saat N kalkir berhimpit N
jaring.
Busur BF adalah plunge, diukur pada posisi OF berhimpit dengan E-
W / N-S jaring (Gambar 4.10.b).
Busur CB adalah rake OB pada bidang N 010° E / 30°, diukur pada
posisi strike bidang tersebut berimpit dengan N-S jaring. Begitu
juga busur DB adalah rake OB pada bidang S 050° E / 50° SW
(Gambar 4.10.c).

(a) (b)
c

(c)
Gambar 4.10 Menentukan Kedudukan Garis Perpotongan Dari Dua Bidang
4.5. Proyeksi Kutub
4.5.1. Definisi
Proyeksi kutub suatu bidang berupa suatu titik hasil proyeksi
permukaan bola (Gambar 4.11), sedangkan proyeksi kutub suatu
garis merupakan suatu titik tembus suatu garis terhadap permukaan
bola pada bidang horizontal (Gambar 4.12).
Catatan :
Pengeplotan proyeksi kutub struktur bidang 0° dimulai dari pusat
lingkaran sedangkan 90° dimulai atau terletak pada lingkaran
primitif.
Pengeplotan proyeksi kutub struktur garis 0° dimulai dari lingkaran
primitif, sedangkan 90° terletak pada pusat lingkaran.
4.5.2. Schmidt Net
Dibuat berdasarkan luas daerah yang sama dari titik-titik proyeksi
pada kedudukan tertentu yang tercakup di dalamnya. Hal ini bertujuan
untuk menghindari distribusi yang tidak merata apabila diadakan
pengukuran dalam jumlah yang besar dalam analisa secara statistik.
Suatu bidang dengan jurus N-S dan dip ke arah E, proyeksi kutubnya
digambarkan sebagai titik pada garis E-W ke arah barat dimana harga

dip-nya dihitung 0° dari pusat lingkaran sedangkan 90° pada lingkaran
primitif (Gambar 4.13). Sedangkan suatu garis dengan plunge tepat
ke arah selatan, proyeksi kutubnya berupa titik pada garis N-S jaring
sebelah selatan dengan harga plunge 20° dimulai dari lingkaran
primitif dan 90° pada pusat lingkaran, dihitung dari S-jaring (Gambar
4.14).
Perbedaan Utama :
Wulf Net yaitu lingkaran besar dan lingkaran kecil didapat dari
proyeksi permukaan bola ke arah titik zenit.
Schmidt Net yaitu lingkaran besar dan kecil dibuat berdasarkan luas
yang mendekati kesamaan dari jaring yang dihasilkan oleh
perpotongannya sehingga interval tiap lingkaran akan merata pada
setiap kedudukan.
Gambar 4.11 Gambar 4.12 Proyeksi kutub struktur bidang Proyeksi kutub struktur garis

Gambar 4.13 Gambar 4.14Proyeksi kutub (P) bidang dengan Proyeksi kutub (P) garis
dengan arah ke jurus N-S dan dip ke arah E selatan dan plunge 20o
4.5.1.1. Penggambaran Proyeksi Kutub Pada Schmidt Net
1. Penggambaran struktur bidang:
Contoh:
Struktur Bidang N 135° E / 60° (Gambar 4.15)
Memutar kalkir berlawanan dengan arah jarum jam sehingga N
kalkir berimpit dengan harga strike.
Kemudian menentukan proyeksi kutubnya berdasarkan besar
dip (90° dari dip) , dimana 0° dimulai dari pusat lingkaran.
Memutar kalkir hingga N kalkir berimpit dengan jaring maka
kedudukan titik pada jaring (titik P) merupakan proyeksi kutub
dari bidang dengan kedudukan N 135° E/ 60°.
2. Penggambaran struktur garis:
Contoh:
Struktur garis 30°, N 225° E (Gambar 4.16)

Memutar kalkir berlawanan dengan arah jarum jam sehingga N
kalkir berimpit dengan harga bearing-nya.
Kemudian menentukan proyeksi kutubnya berdasarkan besar
plunge (90° dari plunge), dimana 0° dimulai dari lingkaran
primitif.
Memutar kalkir hingga N kalkir berimpit dengan N jaring maka
kedudukan yang diperoleh kedudukan titik P merupakan
proyeksi kutub dari garis 30°, N 225° E.
(a) (b)
Gambar 4.15Penggambaran proyeksi kutub pada Schmidt Net untuk bidang dengan
kedudukan N 135° E / 60°

(a) (b)
Gambar 4.16Penggambaran proyeksi kutub pada Schmidt Net untuk struktur garis 30°, N
225° E
4.5.1.2. Penggambaran Proyeksi Kutub Pada Polar Equal Area
Net
Dalam pengeplotan penggambarannya, kertas kalkir posisinya tetap
(tidak diputar-putar). Prinsip dan hasilnya sama dengan bila
menggunakan Schmidt Net, tetapi di sini lebih praktis.
1. Struktur bidang dengan sistem azimuth (Gambar 4.17)
Untuk mempermudah penggambarannya maka pembagian derajat
pada jaring dimulai dari titik W (jurus 0°) searah dengan jarum jam.
Sedangkan besar kemiringan 0° dihitung dari pusat lingkaran dan
90° pada tepi lingkaran. Proyeksi kutubnya berupa titik.
2. Struktur garis dengan sistem azimuth dan kwadran (Gambar 4.18)

Untuk mempermudah penggambarannya maka pembagian derajat
pada jaring dimulai dari titik N (bearing 0°) searah dengan jarum
jam. Sedangkan besar penunjaman 0° dihitung dari lingkaran luar
(Lingkaian primitif) dan 90° pada tengah lingkaran. Proyeksi
kutubnya berupa titik.
Gambar 4.17 Cara penggambaran proyeksi kutub suatu bidang dengan
kedudukan N040°E / 60°

Gambar 4.18Cara penggambaran proyeksi kutub suatu garis dengan
kedudukan 40°, N 60°E
Ringkasan cara penggunaan STEREONET
1. Proyeksi stereografis
a. Wulf Net
* Struktur Bidang.
- Strike : 0° dimulai dari arah utara / North (N) pada Wulf
Net.
- Dip : 0° dimulai dari lingkaran primitiv (tepi) dan 90°
berada di
pusat Wulf Net.
* Struktur Garis.
- Bearing : 0° dimulai dari arah utara North (N) pada Wulf
Net.
- Plunge : 0° dimulai dari lingkaran primitiv (tepi) dan 90°
berada pada pusat Wulf Net.
b. Smicdth Net.
* Struktur Bidang.

- Strike : 0° dimulai dari arah utara / North (N) pada
Smicdth Net.
- Dip : 0° dimulai dari lingkaran primitiv (tepi) dan.90°
berada di pusat Smicdth Net.
* Struktur Garis.
- Bearing : 0° dimulai dari arah utara / North (N) pada
Smicdth Net.
- Plunge : 0° dimulai dari lingkaran primitiv (tepi) dan 90°
berada pada pusat Smith Net.
2. Proyeksi Kutub (menggunakan Polar Equal Area Net)
* Struktur Bidang.
- Strike : 0° dimulai dari sisi West (W) pada Polar equal area
net.
- Dip : 0° dimulai dari pusat dan 90° berada di lingkaran
primitiv (tepi)
* Struktur Garis.
- Bearing : 0° dimulai dari North (N).
- Plunge : 0° dari ligkaran primitiv (tepi) dan 90° berada di pusat