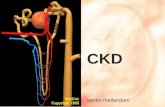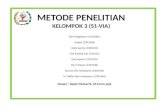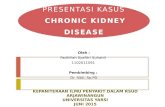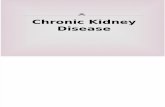BAB 2 Tinjauan Pustaka CKD
-
Upload
caturwulandari -
Category
Documents
-
view
286 -
download
5
Transcript of BAB 2 Tinjauan Pustaka CKD

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Ginjal
Ginjal adalah organ utama ekskresi dalam tubuh yang berperan penting untuk
mempertahankan keseimbangan lingkungan dalam tubuh. Sebagai bagian dari sistem urin,
ginjal berfungsi menyaring kotoran (terutama urea) dari darah dan membuangnya bersama
dengan air dalam bentuk urin (Benez Erza, 2008; Venofer, 2000).
Gambar 1 Letak Ginjal (Wikipedia, 2010).

Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal
ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas (superior)
ginjal terdapat kelenjar adrenal (juga disebut kelenjar suprarenal). Ginjal bersifat retroperitoneal,
yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal
terletak di sekitar vertebra T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal
kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke
sebelas dan duabelas. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak (lemak perirenal dan
lemak pararenal) yang membantu meredam goncangan. Pada orang dewasa, setiap ginjal
memiliki ukuran panjang sekitar 11 cm dan ketebalan 5 cm dengan berat sekitar 150 gram
(Wikipedia, 2010).
Gambar 2 Struktur Ginjal (Vencofer, 2007)
Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Di
tiap ginjal terdapat bukaan yang disebut hilus yang menghubungkan arteri renal, vena renal,
dan ureter. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut
medulla. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medulla ginjal manusia dapat pula

dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh
lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula (Wikipedia, 2010).
Gambar 3 Struktur Ginjal (Vencofer, 2007)
Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari satu juta
buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat
terlarut (terutama elektrolit) dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian
mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya
akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran
lawan arus dan kotranspor. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Sebuah
nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula (atau badan Malphigi)
yang dilanjutkan oleh saluran-saluran (tubulus).
Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang
berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen.
Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat
disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori dari glomerulus dan kapsula Bowman

karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah. Filtrat yang dihasilkan akan
masuk ke dalan tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat arteri
eferen (Wikipedia, 2010).
Di antara darah dalam glomerulus dan ruangan berisi cairan dalam kapsula Bowman
terdapat tiga lapisan:
1. Kapiler selapis sel endotelium pada glomerulus
2. Lapisan kaya protein sebagai membran dasar
3. Selapis sel epitel melapisi dinding kapsula Bowman (podosit)
Dengan bantuan tekanan, cairan dalan darah didorong keluar dari glomerulus, melewati
ketiga lapisan tersebut dan masuk ke dalam ruangan dalam kapsula Bowman dalam bentuk
filtrat glomerular. Filtrat plasma darah tidak mengandung sel darah ataupun molekul protein
yang besar. Protein dalam bentuk molekul kecil dapat ditemukan dalam filtrat ini. Darah
manusia melewati ginjal sebanyak 350 kali setiap hari dengan laju 1,2 liter per menit,
menghasilkan 125 cc filtrat glomerular per menitnya. Laju penyaringan glomerular ini digunakan
untuk tes diagnosa fungsi ginjal (Wikipedia, 2010).
Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan
filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvulasi proksimal. Bagian selanjutnya
adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvulasi distal. Lengkung Henle menjaga
gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi
tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan memungkinkan terjadinya
transpor aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral.
Sebagian besar air (97.7%) dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvulasi dan tubulus
kolektivus melalui osmosis (Wikipedia, 2010).
Cairan mengalir dari tubulus konvulasi distal ke dalam sistem pengumpul yang terdiri dari:
tubulus penghubung

tubulus kolektivus kortikal
tubulus kloektivus medularis
Tempat lengkung Henle bersinggungan dengan arteri aferen disebut aparatus
juxtaglomerular, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular
adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. (Wikipedia, 2010). Setiap harinya ginjal
akan memproses sekitar 200 liter darah untuk menyaring atau menghasilkan sekitar 2 liter
‘sampah’ dan ekstra (kelebihan) air. Sampah dan esktra air ini akan menjadi urin, yang mengalir
ke kandung kemih melalui saluran yang dikenal sebagai ureter. Urin akan disimpan di dalam
kandung kemih ini sebelum dikeluarkan pada saat berkemih.
Secara umum, fungsi ginjal adalah :
1. Menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh
2. Mengeksresikan zat yang jumlahnya berlebihan
3. Reabsorbsi elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal
4. Menjaga keseimbanganan asam basa dalam tubuh
5. Menghasilkan hormon yaitu
Eritropoietin (EPO), yang merangsang sumsum tulang membuat sel-sel darah
merah (eritrosit). Jika tingkat oksigen darah turun, tingkat-tingkat erythropoietin naik
dan tubuh mulai memproduksi lebih banyak sel-sel darah merah.
Renin, membantu mengatur tekanan darah
Bentuk aktif vitamin D (kalsitriol), yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga
keseimbangan kimia dalam tubuh .
6. Homeostasis Ginjal, mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam
darah
(Harnawatiaj, 2008. Sahabat ginjal, 2010).
Penyakit ginjal yang dapat terjadi, diantaranya :
Bawaan

Asidosis tubulus renalis
Kongenital hydronephrosis
Kongenital obstruksi traktus urinarius
Ureter ganda
Ginjal sepatu kuda
Penyakit ginjal polikistik : merupakan kelainan genetik yang ditandai oleh pertumbuhan
kista di ginjal. Kista dapat menggantikan massa ginjal, terjadi penurunan fungsi ginjal
dan menyebabkan gagal ginjal.
Renal dysplasia
Unilateral small kidney
Didapat
Diabetic nephropathy
Glomerulonephritis : adalah cedera pada glomeruli yang menyebabkan protein dan sel-
sel darah bocor ke dalam urin, sehingga mengganggu fungsi ginjal.
Hydronephrosis adalah pembesaran satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh
terhalangnya aliran urin.
Interstitial nephritis
Batu ginjal ketidaknormalan yang umum dan biasanya menyakitkan.
Tumor ginjal
o Wilms tumor
o Renal cell carcinoma
Lupus nephritis
Minimal change disease
Dalam sindrom nephrotic, glomerulus telah rusak sehingga banyak protein dalam darah
masuk ke urin.

Pyelonephritis adalah infeksi ginjal dan seringkali disebabkan oleh komplikasi infeksi
urinary tract.
Gagal ginjal
o Gagal ginjal akut : gangguan fungsi ginjal yang tiba-tiba (akut) dan dapat reversible.
Dapat terjadi karena :
operasi pembedahan yang rumit atau cedera hebat
sumbatan pada pembuluh darah yang menuju ginjal
sumbatan pada saluran kemih akibat batu, tumor, bekuan darah
penyakit ginjal, seperti glomerulonefritis akut
o Gagal ginjal kronis
(Harnawatiaj, 2008; Venofer, 2000; Wikipedia, 2009).
2.2 Penyakit Ginjal Kronis (Chronic Kidney Disease)
Gagal Ginjal Kronik merupakan sindroma klinis karena penurunan fungsi ginjal secara
menetap akibat kerusakan nefron. Proses penurunan fungsi ginjal ini berjalan secara kronis dan
progresif dimana ginjal tidak mampu lagi untuk mempertahankan metabolisme dan
keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen
lain dalam darah). Penumpukan sisa metabolik (toksik uremik) berakibat ginjal tidak dapat
memenuhi kebutuhan dan pemulihan fungsinya lagi (Soewanto dkk, 2008)
Pada tahun 2002, National Kidney Foundation (NKF) Kidney Disease Outcome Quality
Initiative (K/DOQI) telah menyusun pedoman mengenai penyakit ginjal kronik. Definisi PGK
menurut NKF-K/DOQI adalah:
a. kerusakan ginjal > 3 bulan, dan dijumpai kelainan struktur atau fungsi ginjal dengan atau
tanpa penurunan laju filtrasi glomerulus dengan salah satu manifestasi:
- kelainan patalogik

- petanda kerusakan ginjal termasuk kelainan komposisi darah atau urin, atau
kelainan radiologi
b. Laju filtrasi glomerulus < 60 ml/menit/1,73m2 selama > 3 bulan dengan atau tanpa
kerusakan ginjal
(Soewanto dkk, 2008)
Pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, klasifikasi stadium ditentukan oleh nilai laju
filtrasi glomerulus, yaitu stadium yang lebih tinggi menunjukkan nilai laju filtrasi glomerulus yang
lebih rendah. Klasifikasi tersebut membagi penyakit ginjal kronik dalam lima stadium yaitu :
Stadium Deskripsi GFR (ml/men/1,73m2)
1 Kerusakan ginjal dengan GFR
normal atau meningkat
>90
2 Kerusakan ginjal dengan
penurunan GFR ringan
60-89
3 Penurunan GFR sedang 30-59
4 Penurunan GFR berat 15-29
5 Gagal ginjal <15 atau dialysis
Pedoman K/DOQI merekomendasikan perhitungan GFR dengan nama Cockroft-Goult untuk
orang dewasa yaitu:
Klirens kreatinin (ml/men) =(140−umur)x berat badan
72 xkreatininureum
(Soewanto dkk, 2008)
2.3 Faktor Resiko
Faktor resiko gangguan ginjal :
- Menderita tekanan darah tinggi
- Menderita penyakit kencing manis
- Menderita penyakit jantung dan pembuluh darah

- Secara keturunan potensial menderita tiga penyakit atau gangguan di atas
- Salah satu anggota keluarga terkena penyakit ginjal
- Berusia lebih dari 60 tahun
- obesitas dan kelebihan lingkar pinggang (laki-laki = 90 cm, wanita = 80 cm)
- Resiko akan bertambah jika Anda memiliki batu ginjal, infeksi saluran kemih (lebih sering
diderita oleh wanita) yang berlangsung lama, dan sering menggunakan obat anti radang
dan anti nyeri, sakit lupus, otoimun, berat badan lahir rendah, trauma atau kecelakaan.
- Jumlah air yang diminum per harinya tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan tubuh
- Diet yang tidak seimbang (mengkonsumsi protein dalam kadar tinggi secara terus
menerus)
- Diet tinggi purin (kadar asam urat yang tinggi akan mengganggu ginjal)
(Annonymous, 2009).
2.4 Epidemiologi
Seorang individu dengan 2 ginjal sehat memiliki 100% fungsi ginjal. Penurunan fungsi
ginjal sampai 20% dari normal atau lebih rendah, akibat penyakit, cedera, keracunan, atau
trauma, dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius dan bahkan kematian. National
Kidney Foundation memperkirakan bahwa 1 di 9 Amerika memiliki penyakit ginjal kronis. Dari
20 juta orang Amerika hidup dengan penyakit ginjal, sekitar 470.000 hidup dengan penyakit
ginjal tahap akhir dan pada tahun 2030 diperkirakan, lebih dari 2 juta orang cenderung
menerima pengobatan untuk gagal ginjal (Thomas Cherly, 2007).
Penelitian di Canada pada tahun 2001 menunjukan bahwa penderita terbanyak penyakit
gagal ginjal kronik ini adalah pria (Banez Erza, 2008). Sejak April 2001, ada 48.639 orang di
Amerika Serikat menunggu transplantasi ginjal. Pada tahun 2003, menurut Amerika Network for
Organ Sharing 56.598 orang dengan stadium akhir penyakit ginjal sedang menunggu untuk
transplantasi ginjal di Amerika Serikat (Anonymous, 2010). Tanpa pengendalian yang tepat dan

cepat, pada tahun 2015 penyakit ginjal diperkirakan bisa menyebabkan kematian hingga 36 juta
penduduk dunia (Dhaniati Lis, 2009).
Dari data wilayah Jabar dan Banten dua tahun terakhir ini, pada tahun 2007 tercatat
2148 pasien dan meningkat menjadi 2260 pada tahun 2008. Dari jumlah itu, sekitar 30 persen
pasien berusia produktif, yakni kurang dari 40 tahun (Dhaniati Lis, 2009).
2.5. Etiologi
Penyebab penyakit ginjal kronis diberbagai negara hampir sama, akan tetapi berbeda
dalam perbandingan persentasenya. Berdasarkan penyebabnya, NKF K/DOQI membagi PGK
menjadi 3 kelompok besar.
Penyakit Contoh jenis-jenis terbanyak
Penyakit ginjal diabetic Diabetes tipe 1 dan 2
Penyakit ginjal non diabetic Penyakit glomerulus (penyakit outoimin, infeksi
sistemik, obat-obatan, keganasan)
Penyakit-penyakit pembuluh darah (penyakit pembuluh
darah besar, hipertensi, mikroangiopati)
Penyakit-penyakit tubulointersisiel (ISK, batu, obstruksi,
keracunan obat)
Penyakit-penyakit kista (penyakit ginjal polikistik)
Penyakit pada transplantasi Rejeksi kronik
Toksisitas obat (siklosporin atau takrolimus)
Penyakit rekuren (penyakit glomerulus)
Glomerulopati transplan
(Soewanto dkk, 2008)
2.6 Patofisiologi
Patofisiologi PGK melibatkan mekanisme awal yang spesifik, yang terkait dengan
penyebab yang mendasari, selanjutnya proses berjalan secara kronis progresif yang dalam
jangka panjang akan menyebabkan penurunan massa ginjal. Sejalan dengan menurunnya

massa ginjal, sebagai mekanisme kompensasi maka nefron yang masih baik akan mengalami
hiperfiltrasi oleh karena peningkatan tekanan dan aliran kapiler glomerulus dan selanjutnya
terjadi hipertropi. Hipertrofi struktural dan fungsional dari sisa nefron yang masih baik tersebut
terjadi akibat pengaruh molekul-molekul vasoaktif, sitokin serta Growth factor, hingga pada
akhirnya akan terjadi proses sklerosis. Aktivitas aksis Renin-Angiotensin internal juga ikut
berperan dalam terjadinya hiperfiltrasi-hipertrofi dan sklerosis (Soewanto dkk, 2008).
Pada gagal ginjal kronik fungsi renal menurun, produk akhir metabolisme protein yang
normalnya diekskresikan ke dalam urin tertimbun dalam darah. Terjadi uremia dan
mempengaruhi setiap sistem tubuh. Semakin banyak timbunan produk sampah, maka gejala
akan semakin berat.
Penurunan jumlah glomeruli yang normal menyebabkan penurunan klirens substansi
darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. Dengan menurunnya glomerulo filtrat rate
(GFR) mengakibatkan penurunan klirens kreatinin dan peningkatan kadar kreatinin serum. Hal
ini menimbulkan gangguan metabolisme protein dalam usus yang menyebabkan anoreksia,
nausea maupan vomitus yang menimbulkan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.
Peningkatan ureum kreatinin sampai ke otak mempengaruhi fungsi kerja,
mengakibatkan gangguan pada saraf, terutama pada neurosensori. Selain itu Blood Ureum
Nitrogen (BUN) biasanya juga meningkat. Pada penyakit ginjal tahap akhir urin tidak dapat
dikonsentrasikan atau diencerkan secara normal sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan
elektrolit. Natrium dan cairan yang tertahan meningkatkan resiko gagal jantung kongestif.
Penderita dapat menjadi sesak nafas, akibat ketidakseimbangan suplai oksigen dengan
kebutuhan. Dengan tertahannya natrium dan cairan bisa terjadi edema dan ascites. Hal ini
menimbulkan resiko kelebihan volume cairan dalam tubuh, sehingga perlu dimonitor balance
cairannya. Semakin menurunnya fungsi renal terjadi asidosis metabolik akibat ginjal
mengekskresikan muatan asam (H+) yang berlebihan. Terjadi penurunan produksi eritropoetin

yang mengakibatkan terjadinya anemia. Sehingga pada penderita dapat timbul keluhan adanya
kelemahan dan kulit terlihat pucat menyebabkan tubuh tidak toleran terhadap aktifitas.
Dengan menurunnya filtrasi melalui glomerulus ginjal terjadi peningkatan kadar fosfat
serum dan penurunan kadar serum kalsium. Penurunan kadar kalsium serum menyebabkan
sekresi parathormon dari kelenjar paratiroid. Laju penurunan fungsi ginjal dan perkembangan
gagal ginjal kronis berkaitan dengan gangguan yang mendasari, ekskresi protein dalam urin,
dan adanya hipertensi.
2.7 Gejala Klinis
Perjalanan umum gagal ginjal progresif dapat dibagi menjadi 3 atadium
a. Stadium I
Penurunan cadangan ginjal (faal ginjal antar 40 % - 75 %). Tahap inilah yang paling
ringan, dimana faal ginjal masih baik. Pada tahap ini penderita ini belum merasasakan
gejala gejala dan pemeriksaan laboratorium faal ginjal masih dalam masih dalam batas
normal. Selama tahap ini kreatinin serum dan kadar BUN (Blood Urea Nitrogen) dalam
batas normal dan penderita asimtomatik. Gangguan fungsi ginjal mungkin hanya dapat
diketahui dengan memberikan beban kerja yang berat, sepersti tes pemekatan kemih yang
lama atau dengan mengadakan test GFR yang teliti.
b. Stadium II
Insufiensi ginjal (faal ginjal antar 20 % - 50 %). Pada tahap ini penderita dapat
melakukan tugas tugas seperti biasa padahal daya dan konsentrasi ginjaL menurun. Pada
stadium ini pengobatan harus cepat dalam hal mengatasi kekurangan cairan, kekurangan
garam, gangguan jantung dan pencegahan pemberian obat obatan yang bersifat
menggnggu faal ginjal. Bila langkah langkah ini dilakukan secepatnya dengan tepat dapat
mencegah penderita masuk ketahap yang lebih berat. Pada tahap ini lebih dari 75 %
jaringan yang berfungsi telah rusak. Kadar BUN baru mulai meningkat diatas batas normal.

Peningkatan konsentrasi BUN ini berbeda beda, tergantung dari kadar protein dalam
diit.pada stadium ini kadar kreatinin serum mulai meningkat melebihi kadar normal.
Poliuria akibat gagal ginjal biasanya lebih besar pada penyakit yang terutama
menyerang tubulus, meskipun poliuria bersifat sedang dan jarang lebih dari 3 liter / hari.
Biasanya ditemukan anemia pada gagal ginjal dengan faal ginjal diantara 5 % - 25 % . faal
ginjal jelas sangat menurun dan timbul gejala gejala kekurangan darah, tekanan darah
akan naik, dan aktifitas penderita mulai terganggu.
c. Stadium III
Uremi gagal ginjal (faal ginjal kurang dari 10 %) Semua gejala sudah jelas dan
penderita masuk dalam keadaan dimana penderita tidak dapat melakukan tugas sehari-hari
sebagaimana mestinya. Stadium akhir timbul pada sekitar 90 % dari massa nefron telah
hancur. Nilai GFR nya 10 % dari keadaan normal dan kadar kreatinin mungkin sebesar 5-
10 ml / menit atau kurang.
Pada keadaan ini kreatinin serum dan kadar BUN akan meningkat dengan sangat
mencolok sebagai penurunan. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita mulai merasakan
gejala yang cukup parah karena ginjal tidak sanggup lagi mempertahankan homeostatis
caiaran dan elektrolit dalam tubuh. Pada stadium akhir gagal ginjal, penderita pasti akan
meninggal kecuali ia mendapat pengobatan dalam bentuk transplantasi ginjal atau dialisis
(Harnawatiaj, 2008).
Keluhan dan gejala klinis yang timbul pada penyakit ginjal kronis hampir mengenai
seluruh sistem, yaitu:
Gangguan pada sistem gastrointestinal
Anoreksia, nausea, dan vomitus yang berhubungan dengan gangguan metaboslime protein
dalam usus.
Mulut bau amonia disebabkan oleh ureum yang berlebihan pada air liur.
Cegukan (hiccup)

Gastritis erosif, ulkus peptik, dan kolitis uremik
Kulit
Kulit berwarna pucat akibat anemia. Gatal dengan ekskoriasi akibat toksin uremik.
Ekimosis akibat gangguan hematologis
Urea frost akibat kristalisasi urea
Bekas-bekas garukan karena gatal
Sistem Hematologi
Anemia
Gangguan fungsi trombosit dan trombositopenia
Gangguan fungsi leukosit
Sistem Saraf dan Otot
Restles leg syndrome : Pasien merasa pegal pada kakinya, sehingga selalu digerakkan.
Burning feet syndrome : Rasa semutan dan seperti terbakar, terutama ditelapak kaki.
Ensefalopati metabolic : Lemah, tidak bisa tidur, gangguan konsentrasi, tremor, asteriksis,
mioklonus, kejang. Miopati Kelemahan dan hipotrofi otot-otot terutama otot-otot ekstremitas
proksimal.
Sistem kardiovaskuler
Hipertensi
Akibat penimbunan cairan dan garam.
Nyeri dada dan sesak nafas
Gangguan irama jantung
Edema akibat penimbunan cairan
Perikarditis uremik
Tamponode
Sistem endokrin
Gangguan seksual: penurunan libido, infertilitas, amenorhoe, ginekomasti dan impotensi.

Gangguan metabolisme glukosa, resistensi insulin, dan gangguan sekresi insulin.
Gangguan metabolisme lemak (hiperlipidemi).
Gangguan metabolisme vitamin D.
Penurunan kadar estrogen dan testosteron
Gangguan sistem lain
Tulang : osteodistrofi renal, kalsifikasi d jaringan lunak, gout, pseudogout, kalsifikasi sendi.
Asidosis metabolik.
Farmasi : penurunan sekresi lewat ginjal.
(Setiyana Danang, 2008; Soewanto dkk, 2008)
)
Gambar 4 Gejala dan Tanda Penyakit Ginjal Kronis

2.8 Pemeriksaan
Sebagian besar individu dengan stadium dini penyakit ginjal kronik terutama di negara
berkembang tidak terdiagnosis. Deteksi dini kerusakan ginjal sangat penting untuk dapat
memberikan pengobatan segera, sebelum terjadi kerusakan dan komplikasi lebih lanjut.
Pemeriksaan skrinning pada individu asimtomatik yang menyandang faktor risiko dapat
membantu deteksi dini penyakit ginjal kronik (Soewanto dkk, 2008).
Perjalanan klinik penyakit penyakit ginjal kronik biasanya perlahan dan tidak dirasakan
oleh pasien. Oleh karena itu, pada semua pasien penyakit ginjal kronik, sebaiknya dilakukan
pemeriksaan penunjang.
a. Pemeriksaan laboratorium
Untuk menentukan ada tidaknya kegawatan, derajat penyakit ginjal kronis, gangguan
sistem, dan membantu menetapkan etiologi. Diantaranya pemeriksaan :
Kadar kreatinin serum untuk menghitung laju filtrasi glomerulus
Rasio protein atau albumin terhadap kreatinin dalam contoh urin pertama pada pagi
hari atau sewaktu
Pemeriksaan sedimen urun atau dipstick untuk melihat adanya sel darah merah dan
sel darah putih
Kadar elektrolit serum (natrium, kalium, klorida, dan bikarbonat)
b. Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)
Untuk melihat kemungkinan hipertrofi ventrikel kiri, tanda-tanda perikarditis, aritmia,
gangguan elektrolit (hiperkalemia, hipokalsemia). Kemungkinan abnormal menunjukkan
ketidakseimbangan elektrolit dan asam/basa.
c. Ultrasonografi (USG)
Dapat memperlihatkan ukuran ginjal yang mengecil, korteks yang menipis, adanya
hidronefrosis atau batu ginjal, kista, massa, kalsifikasi. Untuk mencari adanya faktor

yang reversibel seperti obstruksi oleh karena batu atau massa tumor, dan untuk menilai
apakah proses sudah lanjut.
d. Foto Polos Abdomen
Menilai bentuk dan besar ginjal dan apakah ada batu atau obstruksi lain. Sebaiknya
tanpa puasa, karena dehidrasi akan memperburuk fungsi ginjal.
e. Pieolografi Intra-Vena (PIV)
Menilai sistem pelviokalises dan ureter. Dapat dilakukan dengan cara intravenous
infusion pyelography.
f. Pemeriksaan Pielografi Retrograd
Dilakukan bila dicurigai ada obstruksi yang reversibel.
g. Pemeriksaan Foto Dada
Dapat terlihat tanda-tanda bendungan paru akibat kelebihan air (fluid overload), efusi
pleura, kardiomegali dan efusi perikadial.
h. Pemeriksaan Radiologi Tulang
Mencari osteodistrofi dan kalsifikasi metastatik.
(Setiyana Danang, 2008)
2.9 Penatalaksanaan
Pengobatan dapat dibagi 2 golongan:
a. Pengobatan konservatif
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pengobatan konservatif masih mungkin dilakukan,
bila klirens kreatinin lebih dari 5 ml/menit , tetapi bila sudah turun sampai kurang dari 5
ml/menit, harus ditetapkan apakah penderita tersebut mungkin diberi pengobatan
pengganti. Tujuan pengobatan konservatif adalah memanfaatkan faal ginjal yang masih
bisa, mencegah faktor-faktor pemberat dan di mana mungkin mencoba memperlambat
progresi gagal ginjal.

1. Pengobatan penyakit dasar
Pengobatan terhadap penyakit dasar yang masih dapat dikoreksi mutlak harus
dilakukan. Termasuk pengendalian tekanan darah, regulasi gula darah pada pasien DM,
koreksi jika ada obstruksi saluran kencing serta pengobatan infeksi saluran kemih (ISK).
2. Pengendalian keseimbangan air dan garam
Garam bersifat menahan air. Jika mengurangi asupan garam, cairan dalam tubuh juga
tidak terlalu banyak menumpuk, pembengkakan tangan dan kaki yang sering terjadi
manakala cairan tubuh berlebihan juga akan berkurang, dan kerja jantung serta paru-
paru juga menjadi lebih ringan sehingga mengurangi keluhan sesak dan sulit bernapas.
Selain itu, jika mengurangi garam, rasa haus juga akan berkurang sehingga otomatis
tidak terlalu banyak minum air. Pemberian cairan disesuaikan dengan produksi urine.
Yaitu produksi urine 24jam ditambah 500ml. asupan garam tergantung evaluasi
elektrolit, umumnya dibatasi 40-120 mEq (920-2760mg). diet normal mengandung rata-
rata 150 mEq (Sahabat Ginjal, 2010).
Furosemid dosis tinggi masih dapat digunakan pada awal PGK, akan tetapi pada fase
lanjut tidak lagi bermanfaat dan pada obstruksi merupakan kontraindikasi. Penimbangan
berat badan, pemantauan produksi urine serta pencatatan keseimbangan cairan akan
membantu keseimbangn cairan dan garam.
3. Diet rendah protein tinggi kalori
Rata-rata kebutuhan sehari pada penderita GGK adalah 20-40gr. Kebutuhan kalori
minimal 35 kcal/kgBB/hari.
Pembatasan Asupan Protein pada Penyakit Ginjal KronisGFR (mL/menit) Asupan protein (g/kg BB/hari)
>60 Pembatasan protein tidak dianjurkan
25-600.6 - 0.8 g/kg BB/hr, termasuk > 0.35 g/kg BB/hr protein dengan nilai biologis tinggi.

5-25
0.6 - 0.8 g/kg BB/hr, termasuk > 0.35 g/kg BB/hari protein dengan nilai biologis tinggi atau tambahan 0.3 g asam amino esensial atau asam keton.
<60 (Sindrom Nefrotik)
0.8 g/kg BB/hr (ditambah dengan 1g protein/g proteinuria atau 0.3 g/kg BB tambahan asam amino esensial atau asam keton)
(Sahabat Ginjal, 2010).
Diet rendah protein tinggi kalori akan memperbaiki keluhan mual, menurunkan BUN dan
akan memperbaiki gejala. Selain tiu diet rendah protein akan menghambat progresivitas
penurunan fungsi ginjal.
4. Pengendalian tekanan darah
Berbeda dengan pengendalian hipertensi pada umumnya, pada PGK pembatasan
cairan mutlak dilakukan. Target tekanan darah 125/75 diperlukan untuk menghambat
laju progresivitas penrunan faal paru. ACE-inhibitor dan ARB diharapkan dapat
menghambat progresivitas PGK. Pemantauan faal ginjal secara serial perlu dlakukan
pada awal pengobatan hipertensi jika digunakan ACE-inhibitor dan ARB. Apabila
dicurigai adanya stenosis erteria renal, ACE-inhibitor merupakan kontra indikasi.
5. Pengendalian gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa
Gangguan keseimbangan elektrolit utama pada PGK adalah hiperkalemi dan asidosis.
Hiperkalemi akan tetap asimtomatis walaupun telah mengancam jiwa. Perubahan
gambaran EKG baru terlihat setelah hiperkalemi membahayakan jiwa. Pencegahan
meliputi diet rendah kalium.
6. Pencegahan dan pengobatan osteodistrifi renal
a. Pengendalian Hiperphosphatemia
Kadar P serum harus dipertahankan <6mg/dl. Dengan cara diet rendah phosphor
saja kadang tidak cukup, sehingga perlu diberikan obat pengikat phosphat.
Aluminium hidroksida 300-1800 mg diberikan bersama makan. Cara ini sekarang

ditinggalkan karena efek samping terjadinya intoksikasi aluminium dan konstipasi.
Sebagai pilihan lain dapat diberikan kalsium karbonat 500-3000 mg bersama makan
dengan keuntungan menambah asupan kalsium dan juga untuk koreksi hipokalsemi.
Makanan yang mengandung tinggi phosphor harus dihindari misalnya susu, keju,
yogurt, es krim, ikan dan kacang-kacangan. Pengendalian hiperphosphotemia juga
dapat menghambat progresivitas penurunan faal ginjal.
b. Suplemen vitamen D3 aktif
1.25 Dihidroksi vitamin D3 (kalsitriol) hanya diberikan jika kadar P normal. Batasan
pemberian jika Ca x P <65. Dosis yang diberikan adalah 0,25 mikrogram/hari.
c. Paratiroidektomi
Dilakukan jika ODR terus berlanjut.
7. Pengobatan gejala uremik spesifik
Termasuk disini adalah pengobatan, simtomatis dari pruritus, keluhan gastrointestinal
dan penanganan anemia. Diet rendah protein, pengendalian P serta pemberian
dypenhidramine dapat memperbaiki keluhan pruritus. Diet rendah protein juga
memperbaiki keluhan anoreksia dan mual-mual. Anemia yang terjadi pada penyakit
ginjal kronis terutama disebabkan oleh defisiensi hormone eritropoitin. Selain itu juga
bisa disebabkan oleh defisiensi Fe, asam folat atau vitamin B12. Pemberian eritropoetin
rekombinan pada penderita penyakit ginjal kronis yang mengalami HD akan
memperbaiki kualitas hidup, dapat pula diberikan pada penderita penyakit ginjal kronis
pra-HD. Sebelum pemberian eritropoetin dan suplemen Fe diperlukan evaluasi kadar SI,
TIBC dan Feritin I.
8. Deteksi dini dan pengobatan infeksi

Penderita penyakit ginjal kronis merupakan penderita dengan respon imun yang rendah,
sehingga kemungkinan infeksi harus selaluu dipertimbangkan. Gejala febris terkadang
tidak muncul karena keadaan respon imun yang rendah.
b. Pengobatan pengganti (Replacement treatment)
Penderita PGK dan keluarga sudah harus diberitahu sejak awal bahwa pada suatu saat
penderita akan memerlukan HD atau transplantasi ginjal. Dialisis adalah metode terapi
yang bertujuan untuk menggantikan fungsi/kerja ginjal, yaitu membuang zat-zat sisa dan
kelebihan cairan dari tubuh. Dialisis dapat dilakukan untuk mencegah komplikasi gagal
ginjal yang serius, seperti hiperkalemia, perikarditis dan kejang.
Dialisis dapat berupa:
1. Hemodialisis
2. Dialisis peritoneal
3. Dialisis intestinal
4. Dialisis pleural
5. Dialisis perikardial
(Soewanto dkk, 2008)
2.10 Hemodialisa
Hemodialisis (HD) adalah dialisis dengan menggunakan mesin dialiser yang berfungsi
sebagai "ginjal buatan". Pada HD, darah dipompa keluar dari tubuh, masuk ke dalam mesin
dialiser. Di dalam mesin dialiser, darah dibersihkan dari zat-zat racun melalui proses difusi dan
ultrafiltrasi oleh dialisat (suatu cairan khusus untuk dialisis), lalu dialirkan kembali ke dalam
tubuh. Proses HD dilakukan 1-3 kali seminggu di rumah sakit dan setiap kalinya membutuhkan
waktu sekitar 2-4 jam (Sahabat Ginjal, 2010).

Gambar 4 Hemodialisa (Venofer, 2007)
Agar prosedur hemodialisis dapat berlangsung, sebelumnya perlu dibuatkan akses
untuk keluar dan masuknya darah dari tubuh. Akses untuk hemodialisis dapat bersifat temporer
(sementara) atau permanen. Pembuatan akses vaskuler sebaiknya sudah dikerjakan sebelum
klirens kreatinin dibawah 15 ml/menit. Dianjurkan pembuatan akses vaskuler jika klirens kreatini
telah dibawah 20 ml/menit. Akses temporer yaitu berupa kateter yang dipasang pada pembuluh
darah balik (vena) di daerah leher (Sahabat Ginjal, 2010).
Akses temporer yaitu berupa kateter yang dipasang pada pembuluh darah balik (vena) di
daerah leher (Sahabat Ginjal, 2010).

Gambar 5 Akses Vaskuler
Akses permanen biasanya dibuat dengan menghubungkan salah satu pembuluh darah balik
(vena) dengan pembuluh nadi (arteri) pada lengan bawah. Akses model Fistula ini populer
dengan nama Cimino (Sahabat Ginjal, 2010).
Gambar 6 Akses Permanen
2.11 Transplantasi Ginjal
Transplantasi ginjal adalah suatu metode terapi dengan cara "memanfaatkan" sebuah
ginjal sehat (yang diperoleh melalui proses pendonoran) melalui prosedur pembedahan. Ginjal
sehat dapat berasal dari individu yang masih hidup (donor hidup) atau yang baru saja
meninggal (donor kadaver). Ginjal ‘cangkokan’ ini selanjutnya akan mengambil alih fungsi
kedua ginjal yang sudah rusak. Kedua ginjal lama, walaupun sudah tidak banyak berperan tetap
berada pada posisinya semula, tidak dibuang, kecuali jika ginjal lama ini menimbulkan
komplikasi infeksi atau tekanan darah tinggi (Sahabat Ginjal, 2010).
Prosedur bedah transplantasi ginjal biasanya membutuhkan waktu antara 3 sampai 6
jam. Ginjal baru ditempatkan pada rongga perut bagian bawah (dekat daerah panggul) agar
terlindung oleh tulang panggul. Pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh darah balik (vena) dari
ginjal ‘baru’ ini dihubungkan ke arteri dan vena tubuh. Dengan demikian, darah dapat dialirkan
ke ginjal sehat ini untuk disaring. Ureter (saluran kemih) dari ginjal baru dihubungkan ke
kandung kemih agar urin dapat dialirkan keluar (Sahabat Ginjal, 2010).

Gambar 7 Transplantasi Ginjal (Sahabat Ginjal, 2010)
Transplantasi ginjal tidak dapat dilakukan untuk semua kasus penyakit ginjal kronik.
Individu dengan kondisi, seperti kanker, infeksi serius, atau penyakit kardiovaskular (pembuluh
darah jantung) tidak dianjurkan untuk menerima transplantasi ginjal karena kemungkinan
terjadinya kegagalan yang cukup tinggi (Sahabat Ginjal, 2010).
Transplantasi Ginjal dinyatakan berhasil jika ginjal tersebut dapat bekerja sebagai
‘penyaring darah’ sebagaimana layaknya ginjal sehat sehingga tidak lagi memerlukan tindakan
Dialisis (cuci darah). Karena ginjal ‘baru’ ini bukan merupakan ginjal yang berasal dari tubuh
pasien sendiri, maka ada kemungkinan terjadi reaksi tubuh untuk menolak ‘benda asing’
tersebut. Untuk mencegah terjadinya reaksi penolakan ini, pasien perlu mengonsumsi obat-obat
anti-rejeksi atau imunosupresan segera sesudah menjalani transplantasi ginjal (Sahabat Ginjal,
2010).
Obat-obat imunosupresan bekerja dengan jalan menekan sistem imun tubuh sehingga
mengurangi risiko terjadinya reaksi penolakan tubuh terhadap ginjal cangkokan. Obat
imunosupresan dapat membuat sistem imun (daya tahan tubuh terhadap penyakit) menjadi
lemah sehingga mudah terkena infeksi. Efek samping lainnya dari imunosupresan: wajah

menjadi bulat, berjerawat, atau tumbuh bulu-bulu halus pada wajah, juga dapat menyebabkan
peningkatan berat badan. Beritahu dokter jika Anda mengalami efek-efek samping seperti ini
untuk segera ditangani secara tepat (Sahabat Ginjal, 2010).
Rejeksi pada transplantasi tadinya diduga sesuatu proses arah dari sistema kekebalan
tubuh resipien untuk menolak ginjal donor. Akan tetapi kemudian disadari bahwa ada juga
proses yang mengurangi kemungkinan rejeksi atau inhibitor rejeksi. Imbangan kedua faktor
inilah yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya rejeksi.
Yang mendorong rejeksi adalah : Yang menghalangi rejeksi adalah:
1) Limfosit sitotoksik
2) Antibodi
3) Makrofag
4) Granulosik
5) Sel K dan sel N K
6) "Helper limfosit"
1) Antibodi enhancing
2) Limfosit Supresor T
3) Antibodi anti idiotype
4) Imun kompleks dalam sirkulasi
5) Limfokinesis
6) Efek inhibisi makrofag
7) Prostaglandin
8) Interferon
(RSUD Soetomo, 2008).
2.12 Modifikasi Gaya Hidup
Selain terapi konservatif dan terapi pengganti, perlu juga modifikasi gaya hidup pada
penderita penyakit ginjal kronis agar tidak mempercepat progesivitas dari penyakit dan
penderita mampu hidup dengan lebih baik. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain:
1. Diet
Perencanaan menu makanan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat
gizi. Kebutuhan akan zat gizi ini berbeda-beda, tergantung stadium penyakit ginjal kronik
yang dialami.
2. Berolahraga, baik untuk kesehatan tubuh secara umum. Terlebih lagi, saat ginjal
mengalami gangguan, mempertahankan kesehatan organ-organ tubuh lainnya menjadi
lebih penting lagi. Olahraga teratur akan menjaga kesehatan paru-paru dan jantung,

memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, sehingga memberi energi dan menjaga kinerja
seluruh organ tubuh. Olahraga juga memperbaiki kelenturan otot, yang akan membantu
memperkuat tulang-tulang Anda. Hal ini penting, karena penyakit ginjal kronik seringkali
memperlemah tulang. Olahraga aerobik (misalnya lari, berenang) juga membantu
mengurangi tekanan darah tinggi.
3. Menjaga berat badan dalam batas normal
Mengurangi kelebihan berat badan dapat membantu menurunkan tekanan darah dan kadar
kolesterol/lemak darah. Sebagai pedoman, indeks massa tubuh (body mass index) normal
yang dianjurkan: 18.5 sampai dengan 24.9 kg/m2.
4. Berhenti merokok
Merokok dapat mengakibatkan kerusakan pada dinding pembuluh darah sehingga
kolesterol mudah tersangkut dan membentuk timbunan plak pada dinding pembuluh darah.
Endapan kolesterol menyebabkan dinding pembuluh darah menebal dan mengeras
sehingga rongga pembuluh darah mengalami penyempitan. Keadaan ini menyebabkan
berkurangnya aliran darah yang menuju ginjal dan meningkatnya tekanan darah. Oleh
karena itu, individu dengan PGK yang memiliki kebiasaan merokok sangat dianjurkan untuk
sedapat mungkin berhenti merokok (Sahabat Ginjal, 2010)