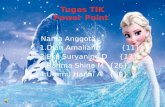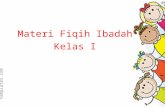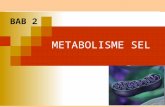Bab 2
-
Upload
tommymulyadin -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
Transcript of Bab 2
Laporan Akhir
PT. MUARA CONSULT
BAB IITINJAUAN UMUM GEMPABUMI, TSUNAMI DAN MITIGASI BENCANA
2.1Kajian PustakaDalam paradigma lama bencana (disaster) dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, terpisah dari kehidupan normal manusia. Pandangan kebanyakan orang, bencana masih dilihat sebagai peristiwa tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi, di mana, menimbulkan banyak persoalan besar maupun kecil melibatkan kerusakan fisik bahkan korban jiwa manusia sekalipun. Dalam paradigma baru dengan menggunakan kerangka kerja analisis bencana yang tepat, bencana tidak lagi dipandang sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang terpisah dari kehidupan normal manusia, tetapi lebih dari itu dipandang sebagai sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan normal manusia dan tidak serta merta terjadi dengan tiba-tiba (Blaikie et al, 1994) resikonya. Sifat atau penyebab bencana, tidak semata-mata dilihat sebagai peristiwa yang bersifat alamiah (natural disaster) tetapi sesuatu resiko (risk) yang tidak tertangani (unmanaged) oleh manusia dalam berbagai dimensi, yang berakar dari manusia-nya sendiri, baik secara pribadi, social maupun lembaga. Yodmani (2001) menjelaskan dengan istilah yang lebih tepat bahwa bencana tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang murni natural tetapi sebagai problema pembangunan yang tidak terselesaikan (unresolved problems of development). Faktor penyebab terjadinya bencana secara alami (natural hazard), boleh jadi merupakan faktor yang dianggap apa adanya (given) pada lingkungan tertentu, tetapi persoalannya adalah apakah faktor tersebut menimbulkan dampak merugikan bagi kehidupan manusia. Besar kecil-nya dampak yang muncul berupa kondisi yang tidak diinginkan (eksternalitas), akan lebih ditentukan dan dipengaruhi oleh manusia-nya sendiri dalam merespon bencana tersebut. Respon manusia terhadap persoalan yang muncul tercermin pada sikap manusia dalam melakukan pengelolaan bencana (disaster management) sebagai upaya meng-internalisasi eksternalitas. Pengelolaan bencana merupakan tindakan yang menekankan kesiapan manusia bersifat antisipatif dan pencegahan dalam menghadapi persoalan-persoalan bencana yang ditujukan bagi upaya mereduksi dampak yang muncul. Dalam perkembangannya, konsep pengelolaan bencana secara modern mulai berkembang dan baru popular pada dekade 90-an yang dikenal dengan Disaster Risk Management. Pada dasarnya, konsep ini mengedepankan resiko (risk) yang dikelola (managed) demi untuk menekankan, memperkecil kerugian secara fisik, social dan ekonomi. Begitu pentingnya upaya pengelolaan bencana dalam mereduksi dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana, hingga UN-ISDR (United Nations-International Strategy for Disaster Reduction) pada tanggal 13 Oktober 2004 mengkampanyekan reduksi bencana dunia yang memberi pesan kepada kita Belajar Dari Bencana Hari Ini Untuk Menghadapi Ancaman Esok (Learning from todays disaster for tomorrows hazards). Pesan yang disampaikan mengandung makna agar kita senantiasa bercermin dari pengalaman untuk lebih dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman bencana demi kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Selalu berusaha belajar mengenali dan memahami karakter lingkungan di sekitar kita. Dalam kegiatan ini dibatasi bencana hanya ditujukan pada bencana geologi , seperti letusan gunungapi (volcano), gempabumi (earthquake), gelombang pasang (tsunami), gerakantanah (landslide), dan khususnya pada bencana alam gempabumi dan tsunami serta site plan mitigasi bencana alam.2.1.1Geologi RegionalGambaran bentuk bentang alam dan tektonik suatu kawasan atau diketahui sebagai phisiografi suatu kawasan (Gambar 2.1) , ternyata daerah kabupaten Sukabumi termasuk zona Pisiografi pegunungan Selatan Jawa Barat dan Zona Bandung, Pegunungan Bayah (Bemmelen, 1949), dimana secara umum memiliki ciri morfologi perbukitan terjal, perbukitan bergelombang dan morfologi dataran tinggi atau plato Jampang dan Plato Bandung.Zona phisiografi Pegunungan Selatan Jawa Barat, terletak di sebelah selatan dari Zona Bogor. Daerah ini memanjang barat - timur melalui Ujung Kulon Pelabuhanratu sebelah Barat, bandung menerus sampai Bumiayu Segara Anakan di Jawa Tengah, dengan lebar berkisar 20 s/d 30 km. Di bagian utara dibatasi oleh Gunung Pangerango, Gunung Gede, Gunung Burangrang, Gunung Tangkubanperahu dan Gunung Bukittunggul . Perbukitan umumnya memanjang barat - timur dan secara setempat ditempati endapan Tersier yang terlipat dan tersesesarkan, ditutupi oleh endapan gunung api berumur Neogen dan diketahui terdapat beberapa intrusi yang membentuk morfologi tinggian dan kerucut intrusi batuan beku.
Sumber : Van Bemmelen, 1949Gambar 2.1Phisiografi Jawa BaratStruktur geologi regional Jawa Barat, menurut (Sukendar Asikin (1986) berdasar pola gaya berat M. Untung (1975) dikelompokkan menjadi 3 pola umum (Gambar 2.2), yaitu :1. Pola baratlaut tenggara (Pola Sumatra) diketahui pada daerah Bogor, Bandung, Purwakarta, Sumedang, Tasikmalaya, Banjar dan menerus sampai Jawa Tengah. 2. Pola timur barat (pola Jawa) diketahui memeotong jalur pegunungan Selatan berupa sesar normal dan bagian utara relatif turun terhadap selatan. 3. Pola utara- selatan hanya diketahui berdasar seimik. (pola Meratus).Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia yang bergerak saling menumbuk (Gambar 2.3). Akibat tumbukan antara lempeng itu maka terbentuk daerah penunjaman memanjang di sebelah Barat Pulau Sumatera, sebelah Selatan Pulau Jawa termasuk Cikakak Sukabumi, hingga ke Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah Utara Kepulauan Maluku, dan sebelah Utara Papua.
Sumber : Asikin, 1949Gambar 2.2Peta Pola Struktur Jawa Barat
Sumber : Minster dan Jordan, 1978 ; Simandjuntak & Barber, 1996Gambar 2.3Pertemuan Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng AustraliaKonsekuensi lain dari tumbukan itu terbentuk palung samudera, lipatan, punggungan dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunungapi, dan sebaran sumber gempabumi. Gunungapi yang ada di Indonesia berjumlah 129. Angka itu merupakan 13% dari jumlah gunungapi aktif dunia. Dengan demikian Indonesia rawan terhadap bencana letusan gunungapi dan gempabumi. Di beberapa pantai, dengan bentuk pantai sedang hingga curam, jika terjadi gempabumi dengan sumber berada di dasar laut atau samudera dapat menimbulkan gelombang Tsunami.2.1.2Geologi Kawasan Kabupaten Sukabumi
Sumber : Peta Geologi Lembar
Gambar 2.4Peta Geologi Daerah Sukabumi - JawaBarat
Gambar 2.5Peta Geologi Daerah Kecamatan Cikakak dan Sekitarnya
2.2 Pengertian Interior Bumi 2.2.1Bentuk dan Ukuran Bumi 1. Bumi yang kita tempati, berbentuk bulat seperti bola, tepatnya ellips dan relative rata di kutub-kutubnya (Gambar 2.6).2. Jari-jari bumi yang diukur di daerah khatulistiwa + 6.378 km, jari-jari kutub=6.356 km. 3. Lebih dari 70 % permukaan bumi diliputi oleh lautan.
Gambar 2.6Illustrasi Bentuk Bumi sebagai Alam Semesta
2.2.2.Struktur Dalam BumiBumi memiliki struktur dalam hampir sama dengan telur, dimana berperan sebagai kuning telurnya adalah inti bumi, putih telurnya adalah selubung, dan cangkang telurnya adalah kerak bumi, (Gambar 2.7).
Gambar 2.7Penampang Penyusun Interior Bumi
2.2.3Komposisi Kerak BumiBerdasarkan penyusunnya, lapisan bumi terbagi atas : litosfer, astenosfer, dan ionosfer. Litosfer atau kerak bumi adalah lapisan paling luar (tebal + 10 km), merupakan lapisan selubung, tempat terjadinya aktivitas alam yang bisa dilihat dan dilakukan manusia.
Gambar 2.8Gambar Penyusun Interior Bumi
Litosfer memiliki kemampuan menahan beban permukaan yang luas misalkan gunungapi, suhu dingin dan kaku. Di bawah litosfer pada kedalaman +70 km terdapat astenosfer. Astenosfer bersifat seperti fluida, mengalir /bergerak (dinamis) akibat tekanan yang terjadi sepanjang waktu.Lapisan berikutnya ionosfer, lebih kaku dibandingkan astenosfer akan tetapi lebih kental dibandingkan litosfer, merupakan selubung hingga inti bumi. 2.3Batas dan Pergerakan Lempeng Penyusun Kerak Bumi 2.3.1Pembentuk Kerak Bumi ( Teori Tektonik Lempeng) Menurut teori tektonik lempeng, permukaan bumi ini terbagi atas kira-kira 20 pecahan besar yang disebut lempeng yang selalu bergerak (dinamis) dengan ketebalan sekitar 70 km.(Gambar 2.9) Ketebalan lempeng diperkirakan hampir sama dengan litosfer yang merupakan kulit terluar bumi yang padat. Litosfer terdiri dari kerak dan selubung atas. Lempengnya kaku dan lempeng-lempeng itu bergerak diatas astenosfer yang lebih cair. (Gambar 2.10)
Gambar 2.9Lempeng Benua Sebagai Pembentuk Kerak Bumi
Gamba 2.10Potongan Kerak BumiDaerah tempat lempeng-lempeng itu bertemu disebut batas lempeng. Pada batas lempeng (Gambar 2.11) kita dapat mengetahui cara bergerak lempeng-lempeng itu. (bisa saling menjauh, bertumbukan, atau saling menggeser ke samping.)
Gambar 2.11Kondisi Batas Tumbukan Lempeng Benua
2.3.2Dinamika Kerak Bumi Pergerakan lempeng digambarkan diduga disebabkan oleh adanya arus konveksi yang disebabkan oleh terjadinya pemindahan panas di dalam bumi, melalui zat cair atau gas sebagaimana gambaran poci kopi menunjukkan dua arus konveksi dalam zat cair. Perhatikan, air dekat api akan naik, saat dingin air kembali turun. Ilmuwan menduga arus konveksi dalam selubung itu membuat lempeng-lempeng bergerak. (suhu selubung amat panas, bagian-bagian di selubung mengalir) ----Lempeng-lempeng bergerak seperti ban berjalan dalam ukuran besar (Gambar 2.12).
Gambar 2.12Illustrasi Pergerakan Lempeng dan Penyebabnya Gerakan Lempeng
2.3.3Tinjauan Mengenai Gempabumi 2.3.3.1 Pengertian Gempabumi 1. Gempabumi adalah berguncangnya bumi, bisa disebabkan oleh a) tumbukan antar lempeng bumi, b) pergerakan patahan aktif, dan c) aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan. 2. Kekuatan gempabumi akibat aktivitas gunungapi dan runtuhan batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempabumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. 3. Berdasar kedalaman pusat gempa dikenal : Dangkal ( 0-30) km, tengah (30 60) km dan dalam (> 60) km, 2.3.3.2 Proses Penyebab Terjadinya Gempabumi 1. Lempeng samudera yang rapat massanya lebih besar ketika bertumbukkan dengan lempeng benua di zona tumbukan (subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. 2. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukkan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. 3. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadi patahan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbukan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempabumi. (Gambar 2.13)
Gambar 2.13Sumber Gempabumi Tektonik pada Zona tumbukan Lempeng Samudra dan Lempeng Benua
2.3.3.3 Daerah Wilayah Rawan Gempabumi di Indonesia Kepulauan Indonesia diketahui menempati zona tektonik yang sangat aktif karena tiga lempeng besar dunia dan sembilan lempeng kecil lainnya saling bertemu di wilayah Indonesia (Gambar 2.14) dan membentuk jalur-jalur pertemuan lempeng yang kompleks (Bird, 2003). Keberadaan interaksi antar lempeng-lempeng ini menempatkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi (Milson et al., 1992).Lempeng Eruasia dan Australia bertumbukan di lepas pantai barat Pulau Sumatera, lepas pantai selatan Pulau Jawa, lepas pantai selatan Kepulauan Nusatenggara dan berbelok ke arah utara ke perairan Maluku sebelah selatan. Antara lempeng Australia dan Pasifik terjadi tumbukan di sekitar Papua.Kawasan pertemuan antara ketiga lempeng itu terjadi di sekitar Sulawesi, termasuk Daerah Kajian Sukabumi Jawa Barat. (Gambar 2.14). Daerah Kecamatan Cikakak, berada di bagian selatan pulau Jawa Bagian Barat, merupakan bagian Kepulauan Indonesia yang menempati pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu Australia, Eruasia dan Pasifik.
Gambar 2.14Peta tektonik kepulauan Indonesia dan sekitarnya (Bird et al., 2003)
Dampak dari benturan antar lempeng kerak bumi yang berbeda jenis tersebut mampu menimbulkan terjadinya penimbunan energi (stress energy) di dalam fitur-fitur geologi dan dalam kurun waktu tertentu akan dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk nilai besaran gempa yang beragam. Bahkan potensi-potensi gempa bumi yang besar (> 7.5) tersebut dapat terjadi di sepanjang batas lempeng kerak bumi (Ruff dan Kanamori, 1983 dan McCann et al., 1987). Zona subduksi yang terjadi di bagian selatan wilayah Indonesia dikenal dengan sumber gempa Busur Sunda yang membentang dari bagian barat Pulau Andaman di bagian barat sampai Pulau Banda di bagian timur. Zona-zona subduksi utama wilayah Indonesia tersebut merupakan zona-zona sumber gempa yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kejadian gempa yang telah lalu dan yang akan datang. 11 fault atau sesar yang terdapat di lempeng tektonik dalam perkembangannya juga mengalami pergerakan dan juga akan memberikan berkontribusi terhadap kejadian gempa. Besarnya magnituda gempa yang terjadi akibat mekanisme pergerakan fault ini bergantung pada luas bidang fault yang saling mengunci (asperity area) dimana makin luas area asperity-nya maka kemungkinan akan kejadian gempanya juga semakin besar. Mekanisme pergerakan fault ini bisa berupa srike-slip, reverse dan normal.
2.3.3.4 Model Sumber Gempa FaultModel sumber gempa fault ini juga disebut sebagai sumber gempa tiga dimensi karena dalam perhitungan probabilitas jarak, yang dilibatkan adalah jarak dari site ke hypocenter. Jarak ini memerlukan data dip dari fault yang akan dipakai sebagai perhitungan probabilitas tersebut.Parameter-parameter yang diperlukan untuk analisis probabilitas dengan model sumber gempa sesar adalah fault trace, mekanisme pergerakan, slip-rate, dip, panjang dan lebar fault. Penentuan lokasi sesar (fault trace) ini berdasarnya dari data-data peneliti yang sudah dipublikasi yang kemudian di trace ulang dengan menggunakan data Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) yang berbentuk peta geomorfologi dan data gempa historis yang sudah direlokasi. Dari hasil trace ini didapatkan panjang dari sesar yang dicari. Data-data yang lain didapatkan dari referensi yang sudah dipublikasi dan hasil diskusi dengan para ahli geologi, geofisika, geodinamika dan seismologi yang tergabung dalam Tim Teknis Revisi Peta Gempa Indonesia. 2.3.3.5 Analisis Kejadian Gempa IndependenKejadian-kejadian gempa dependent atau gempa ikutan (foreshock dan aftershock), harus diidentifikasi sebelum data-data kejadian gempa digunakan untuk menentukan tingkat hazard gempa. Beberapa kriteria empiris untuk mengidentifikasi kejadian gempa dependent telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Arabasz dan Robinson (1976), Garner dan Knopoff (1974) dan Uhrhammer (1986). Kriteria ini dikembangkan berdasarkan suatu rentang waktu dan jarak tertentu dari satu kejadian gempa besar.Dalam studi ini digunakan model Garner dan Knopoff (1974) untuk mencari gempa utama. Hal ini sesuai dengan berbagai analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan model-model di atas dan diketahui model Garner dan Knopoff (1974) memiliki hasil yang cukup baik. Katalog gempa yang diambil dari berbagai sumber di atas dikumpulkan sampai mencapai lebih dari 70.000 kejadian gempa untuk seluruh wilayah Indonesia dan disortir dengan model Garner & Knopoff (1974) hingga didapatkan main shock-nya dengan jumlah 8.151 kejadian gempa.2.3.3.6 Analisis Kelengkapan (Completeness) Data GempaProses analisis kelengkapan (completeness) data gempa juga dilakukan untuk mengetahui kelengkapan data yang diperlukan dalam proses analisis probabilistik. Ketidak lengkapan data gempa akan mengakibatkan parameter resiko gempa yang dihasilkan menjadi overestimated atau underestimated. Metode analisis kelengkapan data gempa yang digunakan pada studi ini mengikuti prosedur yang diusulkan oleh Stepp (1973). Hasil analisis kelengkapan data untuk wilayah Indonesia untuk rentang magnituda 5.0-6.0 adalah 44 tahun, rentang magnituda 6.0- 7.0 adalah 54 tahun, dan rentang magnituda lebih dari 7.0 adalah 108 tahun. Diketahui ada 25 daerah wilayah rawan bencana Gempabumi di Indonesia yaitu : Aceh, Sumatera Utara (Simeulue), Sumatera Barat - Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten Pandeglang, Jawa Barat, Bantar Kawung, Yogyakarta, Lasem, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kepulauan Aru, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sangir Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan, Kepala Burung-Papua Utara, Jayapura, Nabire, Wamena, dan Kalimantan Timur .Tingginya aktivitas kegempaan ini juga terlihat dari hasil pencatatan dimana dalam rentang waktu 1897-2009 terdapat lebih dari 14.000 kejadian gempa dengan magnituda M > 5.0. Kejadian gempa-gempa utama (main shocks) dalam rentang waktu tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.14. Dalam enam tahun terakhir telah tercatat berbagai aktifitas gempa besar di Indonesia, yaitu Gempa Aceh disertai tsunami tahun 2004 (Mw = 9,2), Gempa Nias tahun 2005 (Mw = 8,7), Gempa Jogya tahun 2006 (Mw = 6,3), Gempa Tasik tahun 2009 (Mw = 7,4) dan terakhir Gempa Padang tahun 2009 (Mw = 7,6).Gempa-gempa tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa, keruntuhan dan kerusakan ribuan infrastruktur dan bangunan, serta dana trilyunan rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
2.3.3.7 Goncangan Gempa di Permukaan Tanah dan Faktor Penguatan yang TerjadiPerambatan gelombang gempa yang terjadi dari batuan dasar ke permukaan tanah dipengaruhi oleh karakteristik lapisan tanah termasuk ; jenis, ketebalan dan kondisi muka airtanah yang ditafsirkan menjadi penyebab terjadinya perubahan getaran gempa mencapai permukaan tanah. Secara umum getaran gempa di permukaan tanah mengalami penguatan (amplifikasi) pada frekuensi tertentu. Faktor amplifikasi diberikan definisi sebagai rasio besar percepatan dan/atau spektra di permukaan dibagi percepatan dan/atau spektra di batuan dasar. (memiliki nilai berbeda tergantung dari jenis tanah dan modulus geser tanah sesuai level tegangan dan regangan yang terjadi). Sebagaimana yang diacu pada American Society of Civil Engineerrs (ASGE) 07 2010 dan International Building Code (IBC) 2009.Besar amplifikasi di permukaan ditentukan dengan melakukan analisis respon dinamik spesifik yaitu dengan melakukan pengujian perambatan gelombang dari batuan dasar ke permukaan. Bila tidak dilakukan analisis respon dinamik spesifik, besar amplifikasi yang terjadi pada permukaan tanah harus mengikuti petunjuk yang mengacu pada klasifikasii jenis tanah/batuan hingga kedalaman 30 m. Untuk memperoleh percepatan puncak dan respon spektra di permukaan tanah pada suatu lokasi harus ditentukan klasifikasi jenis tanah sesuai Tabel (2.1).
Gambar 2.15Sebaran Pusat Gempa di P. Jawa Indonesia, M > 5.0 (1900-2009)Table 2.1 Data dan parameter sumber gempa fault untuk daerah Jawa dan sekitarnya Fault Slip-Rate SenseID Name mm/yr Weight Mechanism Dip Top Bottom L (km) Mmax 30 Cimandiri 4 1 Strike-slip 90 3 18 62. 2 7.2031 Opak (Jogja) 2.4 1 Strike-slip 90 3 18 31.6 6.8032 Lembang 1.5 1 Strike-slip 90 3 18 34.4 6.6033 Pati 0.5 1 Strike-slip 90 3 18 51.4 6.8034 Lasem 0.5 1 Strike-slip 90 3 18 114.9 6.5035 Flores back-arc 28 1 Reverse-slip 45 3 20 504.6 7.8036 Timor back-arc 30 1 Reverse-slip 45 3 20 468.0 7.5037 Wetar back-arc 30 1 Reverse-slip 45 3 20 653.0 7.5038 Sumba normal 10 1 Normal-slip 60 3 18 339.9 8.3039 South Seramthrust 11 1 Normal-slip 45 3 20 415.5 7.50
Gambar 2.16Peta percepatan gempa maksimum di batuan dasar (SB) Indonesia dalam SNI 03-1726-2002 yang saat ini berlaku di Indonesia
2.3.3.8 Perkembangan Peta Hazard Gempa IndonesiaPeta percepatan maksimum gempa di batuan dasar untuk Indonesia pada tahun 1983 mulai digunakan untuk peraturan perencanaan melalui PPTI-UG (Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk Gedung) 1983. Peta gempa ini membagi Indonesia menjadi enam zona gempa. Dari peta ini dapat dipilih respon spektra di permukaan tanah dengan memperhitungkan kondisi tanah lokal. Dalam PPTI-UG ini, kondisi tanah lokal dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tanah keras (hard soil) dan tanah lunak (soft soil). (Gambar 2.17)2.3.3.9 Akibat Terjadinya GempabumiPermasalahan utama akibat dari peristiwa-peristiwa gempa adalah: 1) Sangat potensial mengakibatkan kerugian yang besar, 2) Merupakan kejadian alam yang belum dapat diperhitungkan dan diperki rakan secara akurat baik kapan dan dimana terjadinya serta magnitudanya, dan 3) Gempa tidak dapat dicegah. Karena tidak dapat dicegah dan tidak dapat diperkirakan secara akurat, usaha-usaha yang biasa dilakukan adalah menghindari wilayah dimana terdapat fault rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide : 1) Menghindari wilayah dimana terdapat fault rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide, 2) Serta bangunan sipil harus direncanakan dan dibangun tahan gempa.Pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar korban dan kerugian yang terjadi akibat gempa disebabkan oleh kerusakan dan kegagalan infrastruktur. Kerusakan akibat gempa dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: 1) Kerusakan tidak langsung pada tanah yang menyebabkan terjadinya likuifaksi, cyclic mobility, lateral spreading, kelongsoran lereng, keretakan tanah, subsidence, dan deformasi yang berlebihan, serta 2) Kerusakan struktur sebagai akibat langsung dari gaya inersia yang diterima bangunan selama goncangan. Pencegahan kerusakan struktur sebagai akibat langsung dari gaya inersia akibat gerakan tanah dapat dilakukan melalui proses perencanaan dengan memperhitungkan suatu tingkat beban gempa rencana.
Gambar 2.17Peta percepatan gempa maksimum Indonesia dalam PPTI-UG 1983Dalam perencanaan infrastruktur tahan gempa, analisis dan pemilihan parameter pergerakan tanah mutlak diperlukan untuk mendapatkan beban gempa rencana. Secara umum, dalam perencanaan infrastruktur tahan gempa, terdapat beberapa jenis metoda analisis dengan tingkat kesulitan dan akurasi yang bervariasi. Sesuai dengan metoda analisis yang digunakan, parameter pergerakan tanah yang diperlukan untuk perhitungan dapat diwakili oleh: 1) percepatan tanah maksimum, 2) respon spektra gempa, dan 3) riwayat waktu percepatan gempa (time histories).2.3.3.10 Intensitas dan Kekuatan Gempabumi Intensitas gempabumi : adalah tingkat kerusakan yang terasa pada lokasi terjadi gempabumi. Angkanya ditentukan dengan menilai kerusakan yang dihasilkannya, pengaruh pada benda-benda, bangunan, dan tanah, dan akibatnya pada orang-orang. Skala ini disebut MMI (Modified Mercalli Intensity) diperkenalkan oleh Giuseppe Mercalli pada tahun 1902. Magnituda adalah parameter gempa yang diukur berdasarkan yang terjadi pada daerah tertentu, akibat goncangan gempa pada sumbernya. Satuan yang digunakan adalah Skala Richter. Skala ini diperkenalkan oleh Charles F. Richter tahun 1934. Sebagai contoh, gempabumi dengan kekuatan 8 Skala Richter setara kekuatan bahan peledak TNT seberat 1 Gigaton atau 1 milyar ton.Jika sumber gempabumi berada di dasar lautan maka bisa membangkitkan gelombang tsunami yang tidak saja menghantam pesisir pantai di sekitar sumber gempa tetapi juga mencapai beberapa km ke daratan. Korban jiwa terbesar akibat gempabumi Indonesia terjadi di Nias pada bulan Maret 2005 sebanyak 300 jiwa. Sementara korban jiwa gempabumi yang kemudian membangkitkan tsunami terbesar memakan korban jiwa terjadi di Aceh dan Sumut pada Desember 2004, sebanyak 250.000 jiwa. Gambar (Foto 2.18 s/d 2.20). Usaha-usaha yang biasa dilakukan untuk mengantisipasi bencana gempabumi adalah: a) menghindari wilayah dimana terdapat fault rupture, kemungkinan tsunami, dan landslide, serta b) bangunan sipil harus direncanakan dan dibangun tahan gempa.
Gambar 2.18Kondisi Aceh Pada Saat Kejadian Tsunami
Gambar 2.19Kondisi Aceh Pada Saat Setelah Kejadian Tsunami
Gambar 2.20Kondisi Banda Aceh Sebelum dan Setelah TsunamiTabel 2.2Skala MMI (Modified Mercalli Intensity) oleh Giuseppe Mercalli pada tahun 1902
Sumber : (Papadopoulos & Imamura, 2001)
| LAPORAN AKHIRII-8