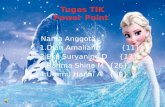Bab 1 Fraksionasi
-
Upload
arosyidin-ayef -
Category
Documents
-
view
34 -
download
1
description
Transcript of Bab 1 Fraksionasi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Percobaan
Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa mampu:
a. Menjelaskan pengaruh variabel terhadap produk fraksionasi
biomassa
b. Menghitung neraca massa pada sistem fraksionasi biomassa
c. Menghitung
d. Menghitung yield pada sistem fraksionasi biomassa
e. Menghitung persentase recovery komponen-komponen utama
biomassa
f. Bekerjasama dalam tim secara profesional
1.2 Pengenalan Biomassa
Perkembangan peradaban masyarakat yang mengeksploitasi sumber daya
alam secara berlebihan dan disertai dengan perusakan lingkungan yang serius
bukanlah sebuah fenomena baru. Untuk mengatasi risiko tersebut, masyarakat
harus mulai mempersiapkan transisi dari pembangunan yang didasarkan pada
sumber daya alam non-terbarukan, menuju sumber daya alam yang terbarukan
agar tidak lagi bergantung pada sumber fosil. Biomassa merupakan solusi yang
paling tepat untuk produksi energi yang berkelanjutan (Villaverde et al.,2010).
Biomassa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis,
baik berupa produk maupun buangan. Diantara sumber-sumber biomassa
terbarukan seperti kayu, non-kayu, rumput, pelepah sawit, pepohonan, umbi-
umbian, limbah pertanian, jerami gandum, ampas tebu, batang dan tongkol jagung
adalah contoh biomassa yang dapat diolah menjadi energi dan dapat menjadi
objek dari penelitian yang penting agar dapat memenuhi kebutuhan manusia.
Energi tersebut tergolong energi ramah lingkungan yang bahan dasarnya
disediakan alam. Namun, penggunaan energi dari biomassa kadang membawa
dampak sampingan yang tidak diinginkan. Dalam sektor energi, biomassa
merujuk pada bahan biologis yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar.

Sebelum mengenal bahan bakar fosil, manusia sudah menggunakan
biomassa sebagai sumber energi. Misalnya dengan memakai kayu untuk
menyalakan api unggun. Sejak manusia beralih pada minyak, gas bumi atau batu
bara untuk menghasilkan tenaga, penggunaan biomassa tergeser dari kehidupan
manusia. Namun, persediaan bahan bakar fossil sangat terbatas. Para ilmuwan
memperkirakan dalam hitungan tahun persediaan minyak dunia akan terkuras
habis. Karena itu penggunaan sumber energi alternatif kini digiatkan, termasuk di
antaranya penggunaan biomassa.
Biomassa dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam
penggunaan tidak langsung, biomassa diolah menjadi bahan bakar. Umumnya
yang digunakan sebagai bahan bakar adalah biomassa yang nilai ekonomisnya
rendah atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Contohnya,
kelapa sawit yang diolah terlebih dahulu menjadi biodiesel untuk kemudian
digunakan sebagai bahan bakar (Dimas, 2008).
Komponen utama penyusun biomassa adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
a. Selulosa
Selulosa merupakan komponen kimia biomassa yang terbesar, yang
jumlahnya mencapai hampir setengah bagian biomassa. Selulosa adalah
komponen dasar pada dinding sel dan serat. Selulosa terdapat pada semua
tanaman tingkat tinggi hingga organisme tumbuhan yang primitif. Selulosa juga
terdapat pada binatang yakni jenis tunicin, zat kutikula tunicat dalam jumlah yang
sedikit (Fengel dan Wegener, 1985).
Selulosa adalah polimer glukosa yang tidak bercabang. Bentuk polimer ini
memungkinkan selulosa saling menumpuk atau terikat menjadi bentuk serat yang
sangat kuat. Panjang molekul selulosa ditentukan oleh jumlah unit glucan di
dalam polimer, disebut dengan derajat polimerisasi. Derajat polimerisasi
selulosa tergantung pada jenis tanaman dan umumnya dalam kisaran 200– 27000
unit glucan (Sa’adah, 2010).

Gambar 1.1 Struktur Selulosa (Hu, 2008)
Sellulosa adalah polimer yang tidak bercabang yang terdiri dari 100-
14.000 monosakarida atau lebih (Beguin and Aubert, 1994 : Lehninger, 1982).
Ikatan β(1→4) tidak dapat diputuskan oleh enzim α-amilase (Lehninger, 1982).
Molekul-molekul sellulosa seluruhnya berbentuk linier, dimana setiap molekul
glukosa sebagai penyusun polimer dapat berotasi hingga 180° (Brown, 1996) dan
mempunyai kecenderungan kuat membentuk ikatan-ikatan hydrogen intra dan
intermolekul. Ikatan antar fibril ini yang kemudian membentuk selulosa
crystalline (Brown et al., 1996). Jadi berkas-berkas molekul sellulosa membentuk
agregat bersama-sama dalam bentuk mikrofibril. Mikrofibril mimiliki dimensi
antara 3-4 nm pada tanaman tingkat tinggi hingga 20 nm pada Valonia
macrophysa, dimana setiap mikrofibril terdiri dari beberapa rantai selulosa.
Mikrofibril ini memiliki oritentasi yang sangat besar untuk tersusun secara pararel
(Beguin and Aubert, 1994). Mikrofibril ini pada tempat-tempat tertentu memiliki
struktur yang teratur (crystalline) dan pada tempat-tempat tertentu memiliki
struktur yang kurang teratur (amorphous). Struktur amorphous terjadi karena
prose kristalisasi yang tidak berlangsung sempurna pada semua mikrofibril yang
terbentuk (Linder dan Teeri, 1997). Mikrofibril membentuk fibril-fibril dan
akhirnya serat-serat sellulosa. Struktur sellulosa yang berserat dan terdapat ikatan-

ikatan hidrogen yang kuat mengakibatkan dapat tahan terhadap tarikan tinggi
(Sjostrom, 1995 ; Beguin and Aubert, 1994). Jumlah selulosa amorphous dan
crystalline di alam sama banyak. Selulosa terakumulasi di alam karena relatif
resisten di dalam proses degradasi (proses degrdasi di alam berjalan lambat).
Dimensi serat selulosa dan proporsi dari bagian kristalin dan amorphous sangat
tergantung kepada keadaannya alami (jenis tanaman dan umur tanaman) (Linder
dan Teeri, 1997). Diperkirakan bahwa jumlah karbon terbanyak terdapat dalam
bentuk selulosa dan mayoritas terdapat di lingkungan teresrial (Levin et al., 2009).
Karena itu material selulosa berbeda menunjukkan sifat yang berbeda tergantung
kepada sumber yang digunakan dan metode ekstrasi yang dilakukan, dan jumlah
substrat berbeda yang digunakan dan jenis enzim selulosa yang digunakan (Linder
dan Teeri,1997).
Selulosa dapat larut dalam asam pekat (seperti asam sulfat 72%) yang
mengakibatkan terjadinya pemecahan rantai selulosa secara hidrolisis. Hidrolisis
selulosa ini dapat terhalang oleh lignin dan hemiselulosa yang ada di sekitar
selulosa. Namun laju hidrolisis selulosa akan meningkat seiring kenaikan
temperatur dan tekanan (Fengel dan Wegener, 1985).
Selulosa digunakan secara luas dalam industri tekstil, deterjen, pulp dan
kertas. Selulosa juga digunakan dalam pengolahan kopi dan kadang-kadang
digunakan dalam industri farmasi sebagai zat untuk membantu sistem pencernaan.
Selulosa juga dimanfaatkan dalam proses fermentasi dari biomassa menjadi
biofuel, seperti bioetanol. Saat ini, enzim selulosa juga digunakan sebagai
pengganti bahan kimia pada proses pembuatan alkohol dari bahan yang
mengandung selulosa (Sa’adah, 2010).
b. Hemiselulosa
Hemiselulosa adalah bagian dari kelompok polisakarida yang memiliki
rantai pendek dan bercabang. Pada tumbuhan, hemiselulosa berfungsi sebagai
bahan pendukung dinding sel. Hemiselulosa juga merupakan senyawa polimer
yang terdapat pada biomasa. Pada berbagai jenis tanaman, jumah dan jenis
monomer penyusun hemiselulosa berbeda-beda.

Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan polimer gula.
Namun, berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun dari glukosa, hemiselulosa
tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Monomer gula penyusun hemiselulosa
terdiri dari monomer gula berkarbon 5 (C-5) dan 6 (C-6), misalnya: xylosa,
mannose, glukosa, galaktosa, arabinosa, dan sejumlah kecil rhamnosa, asam
glukoroat, asam metal glukoronat, dan asam galaturonat (Sa’adah, 2010). Xylosa
adalah salah satu gula C-5 dan merupakan gula terbanyak kedua di biosfer setelah
glukosa. Struktur penyusun dari hemiseluloda dapat dilihat pada gambar 2.Jumlah
hemiselulosa di dalam biomassa lignoselulosa sebesar 11% hingga 37 % (berat
kering biomassa). Hemiselulosa lebih mudah dihidrolisis daripada selulosa, tetapi
gula C-5 lebih sulit difermentasi menjadi etanol daripada gula C-6.
Gambar 1.2 Struktur Hemiselulosa (Isroi, 2008)
c. Lignin
Lignin adalah molekul komplek yang tersusun dari unit phenylphropane
yang terikat di dalam struktur tiga dimensi. Lignin berfungsi sebagai pengikat
matrik selulosa. Unit-unit pembentuk lignin terdiri dari p-koumaril alkohol,
koniferil alkohol, dan sinapil alkohol yang merupakan senyawa induk pembentuk
makromolekul lignin. Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara
biologi, enzimatis, maupun kimia. Karena kandungan karbon yang relatif tinggi
dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa, lignin memiliki kandungan
energi yang tinggi (Sa’adah, 2010). Pada gambar 3 dapat dilihat stuktur dari
lignin.

Tabel 1.1 Kandungan Lignoselulosa Berbagai Biomassa
Biomassa Lignin
(%)
Selulosa
(%)
Hemiselulosa (%)
Rice straw 21 38 25
Oil palm empty fruit
bunches
10 50,4 21,9
Hardwoods stems 18 40 24
Softwoods stems 25 45 25
Nut Shells 30 25 25
Corn cobs 15 45 35
Grasses 10 25 35
Paper 0 85 0
Wheat straw 15 30 50
Sorted refuse 20 60 20
Leaves 0 15 80
Cotton seed hairs 0 80 5
Solid cattle manure 2,7 1,6 1,4
Coastal Bermuda Grass 6,4 25 35,7
Switch grass 12 45 31,4
Baggase 24,05 42,64 25,4
(Sumber : Isroi, 2008)
Untuk itu, lignoselulosa, terutama yang timbul dari residu pertanian, limbah
kehutanan, limbah kertas dan tanaman energi, dapat dijadikan sebagai sumber
daya energi potensial terbarukan. Lignoselulosa yang terdiri dari tiga komponen
yang dominan yakni, selulosa, hemiselulosa dan lignin, dapat digunakan untuk
tujuan lain selain produksi energi. Pada saat ini biomassa yaitu lignoselulosa dan
komponen fraksi merupakan sumber ekonomis bahan bakar cair, makanan, bahan
baku, dan serat. Proses pembuatan pulp secara komersial (kraft dan teknologi
sulfit) menghasilkan pulp berkualitas tinggi, tetapi fraksi seperti lignin dan

hemiselulosa ( berat sekitar 50% dari berat kering kayu) sering terbuang atau
pemanfaatannya belum optimal seperti sebagai sumber energi. Untuk itu
pembuatan pulp dengan organosolv (berdasarkan pemanfaatan pelarut organik
sebagai media delignifikasi) dapat dianggap sebagai teknologi pemurnian
biomassa , karena produk mengarah ke fase padat yang terdiri dari selulosa serta
liquor yang terdiri dari hemiselulosa dan lignin yang bebas dari belerang. Asam
hidrolisis dapat digunakan untuk menghidrolisis hemiselulosa menjadi monomer
pembentuk hemiselulosa.
1.3 Proses Organosolv
Proses organosolv adalah proses pemisahan serat dengan menggunakan
bahan kimia organik seperti metanol, etanol, aseton, asam asetat, dan lain-lain.
Proses ini telah terbukti memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan
sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Dengan menggunakan
proses organosolv diharapkan permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh
industri pulp dan kertas akan dapat diatasi. Hal ini karena proses organosolv
memberikan beberapa keuntungan, antara lain yaitu rendemen pulp yang
dihasilkan tinggi, daur ulang lindi hitam dapat dilakukan dengan mudah, tidak
menggunakan unsur sulfur sehingga lebih aman terhadap lingkungan, dapat
menghasilkan by-products (hasil sampingan) berupa lignin dan hemiselulosa
dengan tingkat kemurnian tinggi. Ini secara ekonomis dapat mengurangi biaya
produksi, dan dapat dioperasikan secara ekonomis pada kapasitas terpasang yang
relatif kecil yaitu sekitar 200 ton pulp per hari.
Penelitian mengenai penggunaan bahan kimia organik sebagai bahan
pemasak dalam proses pulping sebenarnya telah lama dilakukan. Ada berbagai
macam jenis proses organosolv, namun yang telah berkembang pesat pada saat ini
adalah proses alcell (alcohol cellulose) yaitu proses pulping dengan menggunakan
bahan kimia pemasak alkohol, proses acetocell (menggunakan asam asetat), dan
proses organocell (menggunakan metanol).
Proses alcell telah memasuki tahap pabrik percontohan di beberapa negara
misalnya di Kanada dan Amerika Serikat, sedangkan proses acetocell mulai
diterapkan dalam beberapa pabrik di Jerman pada tahun 1990-an. Proses alcell

yang telah beroperasi dalam skala pabrik di New Brunswick (Kanada) terbukti
mampu manghasilkan pulp dengan kekuatan setara pulp kraft, rendemen tinggi,
dan sifat pendauran bahan kimia yang sangat baik. (Isroi, 2008)
Gambar 1.3 Prosedur Fraksionasi Lignoselulosa oleh Asam Formiat dengan
Recycle Pelarut (Isroi, 2008)
Organosolv ekstraksi diakui sebagai metode alternatif yang efektif untuk
delignifikasi. Sebagai proses yang murah dan mudah tersedia pelarut organik,
asam formiat menunjukkan potensi sebagai agen kimia untuk fraksionasi
biomassa. Proses fraksionasi biomassa dengan pelarut asam formiat ditunjukkan
pada Gambar 1.3. Selama terjadi proses pembentukan pulp dengan pelarut asam
formiat, lignin larut ke dalam cairan hitam karena terjadi pembelahan lignin o-4
obligasi, sementara hemiselulosa terdegradasi menjadi mono- dan oligosakarida,
meninggalkan padatan selulosa dalam residu. Ketika air ditambahkan ke cairan,
lignin mengendap dan memisahkan dari cairan hitam. Setelah menghasilkan pulp,
asam formiat dapat di-recycle dengan proses distilasi untuk digunakan kembali.
Dalam sebuah proses organosolv, penghilangan lignin dari matriks padat dapat
dicapai dengan menggantikan senyawa sulfur oleh pelarut organik. Senyawa
organik ini menghasilkan delignifikasi dari bahan baku yang lebih baik dari pada
proses kraft. Dengan kata lain, organosolv proses dapat dirancang sebagai metode
fraksionasi lebih dari metode pulping. Artinya, proses fraksionasi ini dapat
dioperasikan pada hampir semua bahan baku untuk menghasilkan komponen
utama dari jaringan tumbuhan (selulosa, hemiselulosa dan lignin) dalam bentuk
yang lebih baik. Pada Tabel 2 ditampilkan hasil farksionasi biomassa dengan
berbagai macam umpan biomassa dan kondisi operasi tertentu.

Tabel 2. Hasil Percobaan Fraksionasi Biomassa dengan Berbagai Umpan dan
Kondisi Proses
(Sumber : Zhang et al.,2008)
1.3.1 Proses Acetosolv
Penggunaan asam asetat sebagai pelarut organik disebut dengan proses
acetosolv.Proses inimenggunakanpelarututamayaituasamasetat (93%) dan 0.5 -
3.0% HCI sebagaikatalisnya (Wistara, 2007). Proses acetosolv dalam pengolahan
pulp memiliki beberapa keunggulan, antara lain: bebas senyawa sulfur, daur ulang
limbah dapat dilakukan hanya dengan metode penguapan dengan tingkat
kemurnian yang cukup tinggi, dan nilai hasil daur ulangnya jauh lebih mahal
dibanding dengan hasil daur ulang limbah kraft (Simanjutak, 1994). Keuntungan
dari proses acetosolv adalah bahan pemasak yang digunakan dapat diambil
kembali tanpa adanya proses pembakaran bahan bekas pemasak. Selain itu proses
tersebut dapat dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan organik.(Isroi,
2008).Proses ini menghasilkan by-product berupa furfuraI, levulinic acid,
hydroxyl methyl furfural, metanol, dan methyl acetat (Wistara, 2007).
1.3.2 Ester Pulping
Kayu dimasak pada suhu tinggi (sampai dengan 200 oC) dengan pelarut
berupa air, ethyl acetate, dan asam asetat dengan komposisi yang sama. Ester
pulping ini dianggap memiliki keunggulan dalam recovery bahan kimianya.
Tetapi sampai saat ini proses ester pulping ini belum dikernbangkan lebih lanjut
(Wistara, 2007).
1.3.3 Proses Milox
Proses milox merupakan proses pemasakan tiga tahap yang terdiri dari
pemasakan dengan asam formiat - asam performiat - asam formiat. Proses ini

menghasilkan pulp dengan bilangan kappa sangat rendah, yaitu 7 - 11 yang
memungkinkan proses pemutihan pulp hanya dengan proksida dan atau ozon.
1.3.4 Process Alcell
Proses Alcell merupakan sebuah proses organosolv berpelarut etanol-air
yang ramah lingkungan. Adapun kelebihan dari proses ini adalah :
a) Dengan media pemasak berupa alcohol dan air, proses ini akan bebas dari
masalah bau akibat senyawa sulfur yang di alami proses kraft dan sulfit.
Emisi senyawa turunan sulfur yang berhubungan dengan hujan asam tidak
akan terjadi.
b) By-products Alcell bersifat renewable. Lignin Alcell dapat mengganti km
resin PF yang dibuat dari petrokimia yang bersumber pada bahan
nonrenewable. Asam asetat yang dihasil kan juga bias mengganti asam
asetat yang diproduksi dari methanol dan CO.
c) Limbah cair yang mengandung klor dapat dikurangi atau bahkan
dihilangkan. Penelitian menunjukkan bahwa derajat purih standar dapat
diperoleh tanpa menggunakan senyawa berklor.

DAFTAR PUSTAKA
Beguin, P. and Aubert, J. P. 1994. The biological degradation of cellulose. FEMS Microbiology Reviews, 13, 25-58.
Brown, M. R. Jr. 1996. The biosynthesis of cellulose. Journal macromol science-pure applied chemistry. A33:1345-1373.
Brunow, G., Karhunen, P., Lundquist, K., Olson, S., dan Stomberg, R, 1995, Investigation of Lignin Models of the Biphenyl Type by X-Ray Crystallographydan NMR Spectroscopy. J. Chem. Crystallogr, 25: 1-10.
Fadillah. 2008.Biodelignifikasi Batang Jagung dengan Jamur Pelapuk Putih Phanerochaete chrysosporium.Surakarta
Fengel, D dan Wegener, G, 1985, Kayu: Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-Reaksi, Translated from the English by H. Sastrohamidjojo, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Hu, G, 2008, Feedstock Pretreatment Strategies for Producing Ethanol from Wood, Bark, And Forest Residu, Bioresources 3(1): 270-294.
Isroi. 2008. “Karakteristik Lignoselulosa sebagai Bahan Baku Bioetanol”, http://isroi.wordpress.com/2008/05/01/karakteristik-lignoselulosa-sebagai-bahan-baku-bioetanol/, diakses pada 25 November 2014
Lehninger, A. L. 1982. Dasar-dasar biokimia jilid 1. Jakarta: Erlangga.Levin, D. B., Carere C. R., Cicek R., and Sparling R. 2009. Challenges
forbiohydrogen production via direct lignocellulose fermentation. International journal of hydrogen energy, 34:7390–7403.
Linder, M., and Teeri, T. 1997. The role and fungtion of cellulosebinding domains. Journal Biotechnology, 57:15-28.
Sa’adah. 2010.”Produksi Enzim Selulosa oleh Aspergillus niger”, http://eprints.undip.ac.id/13064/1/BAB_I_-_V.pdf,diakses pada 25 November 2014.
Sjostrom, E. 1995. Kimia kayu, dasar-dasar dan penggunaan. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Villaverde J J, Ligero P, de Vega A. 2009. Formic and Acetic Acid As Agents for A Cleaner Fractionation of Miscanthus x giganteus. Department of Physical Chemistry and Chemical Engineering, University of A Corun˜a, A Corun˜a 15071, Spain.
Wistara, N J, “KemampuanTeknologiPulp danKertasMutakhirDalamMewujudkanSuatuGreen Lndustri”, http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/24929/prosiding_prospekdantantangan_pengembangan_pulp-7.pdf?sequence=1, diaksespada 25 November 2014.
Zhang M, Qi W, Liu R, Su R, Wu, He Z. 2008. Fractionating lignocellulose by formic acid: Characterization of major components, School of Chemical Engineering and Technology, Tianjin University.