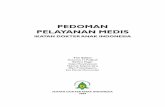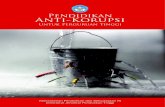Uji Potensi Anti Bakteri UJI POTENSI ANTI BAKTERI EKSTRAK ...
Anti-IdAI
-
Upload
sayuparyati -
Category
Documents
-
view
257 -
download
1
Transcript of Anti-IdAI
PRODUKSI ANTIBODI ANTI-IDIOTIPE SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN FLU BURUNGOleh Sayu Putu Yuni Paryati, Retno D. Soejoedono 2, Okti Nadia Putri 21 1
Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat.2
Laboratorium Imunologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Bogor
ABSTRAK
Virus Flu Burung atau Avian Influenza (AI) adalah virus influenza tipe A, pada awalnya hanya menyerang unggas namun belakangan terbukti bahwa AI bukan hanya menyebabkan kematian unggas namun juga telah menelan korban jiwa manusia. Mengingat sifat virus ini yang ganas dan dapat menular dengan cepat, serta kekhawatiran masyarakat akan flu burung , maka antibodi anti-idiotipe dari virus AI dapat digunakan sebagai alternatif pengganti virus yang aman untuk berbagai keperluan dalam upaya pencegahan flu burung. Penelitian ini bertujuan untuk memproduksi antibodi anti-idiotipe virus AI (H5N1) dari serum dan telur ayam serta mempelajari prospek penggunaan anti-idiotipe sebagai alternatif pengganti virus AI dalam upaya pencegahan flu burung. Produksi antibodi AI dilakukan dengan
mengimunisasi empat ekor marmot dengan satu dosis vaksin AI (0,5 ml) secara subkutan dan dilakukan pengulangan sebanyak dua kali dengan
interval satu bulan. Dua minggu setelah vaksinasi terakhir dilakukan booster. Serum marmot dipanen satu minggu setelah booster dan keberadaan antibodi dideteksi dengan Agar Gel Precipitation Test (AGPT), menunjukkan hasil positif yang ditandai dengan terbentuknya garis pre sipitasi. Purifikasi antibodi atau imunoglobulin G (IgG) dilakukan dengan menggunakan Montage Antibody Purification Kit with Prosep A , diperoleh konsentrasi IgG AI sebesar 10,276 mg/ml. Pemotongan IgG dengan enzim pepsin, diperoleh fragmen Fc dan F(Ab 2), selanjutnya F(Ab 2) digunakan untuk mengimunisasi ayam sehingga pada ayam akan terbentuk antibodi terhadap F(Ab 2) yang
merupakan antibodi anti-idiotipe AI. Reaksi identitas parsial yang terbentuk antara antigen AI dengan antibodi anti -idiotipe AI menunjukkan keduanya memiliki determinan antigenik bersama. Kesimpulannya, sebagian dari antibodi anti-idiotipe yang dihasilkan dari serum dan telur ayam merupakan mimikri dari virus AI dan memiliki determinan bersama, serta fragmen F(Ab 2) IgG bersifat antigenik dan
Penelitian ini dirancang dalam waktu satu tahun. Pada penelitian ini akan dilakukan produksi dan pemurnian antibodi anti -idiotipe virus Avian influenza H5N1 dari serum ayam. Kelinci disuntik dengan vaksin AI (killed vaccine) sehingga kelinci menghasilkan antibodi (Ab 1) terhadap virus H5N1. Antibodi anti-idiotipe (Ab2) dihasilkan dengan menyuntik ayam petelur dengan antibodi terhadap virus H5N1 (Ab 1). Selanjutnya akan dilakukan pemurnian antibodi anti idiotipe virus Avian influenza dengan kolom kromatografi, karakterisasi dari antibodi anti -idiotipe (Ab 2) menggunakan metode Agar Gel Prepicitation Test dan SDS Page, serta pengukuran konsentrasi Ab 2. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan untuk keperluan diagnostik.
TUJUAN PENELITIAN1. Memproduksi antibodi anti-idiotipe serum ayam. 2. Mempelajari prospek penggunaan antibodi anti -idiotipe sebagai alternatif pengganti virus Avian influenza untuk keperluan diagnostik yang aman, dan efektif. virus Avian Influenza (H5N1) dari
1
HASIL YANG DIHARAPKANHasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat diproduksi antibodi anti-idiotipe yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti virus Avian influenza untuk keperluan diagnostik.
STUDI PUSTAKAAntibodi
Jika hewan terpapar oleh suatu antigen, maka respon imun akan terjadi pada tubuh hewan tersebut. Respon humoral dari tubuh yang terinfeksi menghasilkan antibodi. Struktur molekul antibodi terdiri dari empat rantai protein berbentuk seperti huruf Y yang dihubungkan oleh ik atan disulfida. Satu molekul antibodi terdiri dari dua pasang rantai polipeptida berat (heavy = H) dan ringan (light = L), masing-masing mempunyai daerah variabel (V H dan V L) dan daerah konstan (C H dan CL). Daerah variabel (V) tersusun dari sekitar 110 sampai 130 asam amino, merupakan gugus NH 2 sebagai tempat ikatan antara rantai H dan L. Daerah konstan C pada rantai H meliputi daerah aktivasi komplemen dan molekul reseptor Fc dari berbagai jenis sel. Terdapat tiga kelas determinan antigenik yang diekspre sikan oleh daerah V dan C, yaitu : (1) determinan isotypic, membedakan rantai ringan menjadi dua klas, yaitu kappa ( ) dan lamda ( ), sedangkan rantai berat mempunyai lima isotipe berbeda yang membagi imunoglobulin menjadi lima klas yang berbeda dengan fungsi yang berbeda -beda pula (pada manusia, IgG, IgM, IgA, IgE, IgD) (Saldanha 2000) ; (2) determinan allotypic, dibedakan dari produk gen pada lokus yang sama (IgG1, IgG2a, IgG2b ) ; dan (3) determinan idiotypic, dihubungkan dengan spesifisitas ikatan antigen (Gambar 1).
Allotypic, variasi asam amino pada lokus yang sama Idiotypic, variasi dihubungkan dengan spesifisitas
2
Gambar 1. Skema antibodi dengan determinan isotypic, allotypic dan idiotypic.
Daerah variabel (V) selanjutnya dibagi menjadi daerah hipervariabel (HV) dan daerah framework (FR). Pada rantai berat dan ringan, ditemukan tiga daerah HV (HV1, HV2 dan HV3) dan empat daerah FR yang memiliki rangkaian asam amino yang lebih stab il. Daerah HV juga disebut complementarity determining region (CDR) karena daerah ini merupakan bagian yang mengalami kontak langsung dengan permukaan antigen, mempunyai panjang dan rangkaian asam amino berbeda pada antibodi yang berbeda (Anonim 2000). Hal ini menyebabkan antibodi mempunyai
spesifisitas dan afinitas yang berbeda -beda pula terhadap penanda target (target marker) pada antigen. Daerah spesifik untuk berikatan dengan antigen ini disebut paratop dan mengekspresikan beberapa kumpulan idiotop yang mampu meningkatkan produksi antibodi.
Idiotipe
Idiotope adalah determinan antigen ( antigenic marker) tunggal pada daerah hipervariabel molekul antibodi yang dapat ditemukan pada sel B dan T (Kennedy et al. 1983; Zhou et al. 1991; Mayer 2004). Idiotope berlokasi pada atau di dekat sisi pengikat antigen ( antigen combinating site), pada rantai berat maupun rantai ringan antibodi, namun kebanyakan idiotop terletak pada rantai berat (Ban et al. 1994) yang berpengaruh terhadap determinan idiotipik dari suatu a ntibodi (Sollazzo et al. 1990). Variasi idiotipe pada individu terletak di seluruh bagian hipervariabel antibodi dan dikode oleh gen. Bagian hipervariabel 1 (HV1) dan hipervariabel 2 (HV2) antibodi dikode langsung oleh gen segmen V pada garis benih ( germ line), sedangkan HV3 dibentuk dari kombinasi segmen ke 3 gen V, gen D (dari
3
rantai berat) dan gen J. Rekombinasi ini terjadi secara acak sehingga terjadi variabilitas. Ini bertanggung jawab terhadap tempat pengikatan antigen yang berbeda-beda dan menyebabkan bagian variabel antibodi suatu individu memiliki struktur yang mirip dengan individu lain (Male et al. 1987). Idiotipe digunakan untuk menerangkan hubungan antara asal usul gen daerah V dan C. Gen ini dipertahankan selama masa evolusi dari hewan dan perkembangannya tergantung kondisi lingkungan (Kennedy et al. 1983). Cara lain untuk memperoleh lebih banyak variasi repertoire germ-line adalah dengan rekombinasi batas segmen V, D dan J untuk menghasilkan berbagai sekuens junctional (Roitt et al. 1993). Diversitas antibodi juga dapat terjadi dengan adanya insersi nukleotida pada daerah N dari segmen D dan J, suatu proses yang berhubungan dengan ekspresi terminal deoxynucleotidyl transferase. Cara ini sangat meningkatkan repertoire gen dan reseptor -T. Sistem imun
mempunyai mekanisme pembentukan diversitas lebih lanjut, yaitu pada saat dua rantai yang berbeda digunakan untuk pengenalan molekul. Pada saat ini terjadi kombinasi yang menghasilkan variabilitas baru. Bila satu rantai berat berpasangan dengan rant ai ringan yang berbeda, spesifisitas akhir antibodi akan berubah (Roitt et al. 1993).
Antibodi Anti-idiotipe
Kumpulan beberapa idiotop disebut dengan idiotipe (Ab 1) yang mampu menginduksi antibodi anti -idiotipe (Ab 2) (Lin dan Zhou 1995). Apabila Ab1 murni disuntikkan kepada hewan lain, maka Ab 1 akan dikenali sebagai antigen asing dan menimbulkan respon kebal Ab 2 yang kuat (Harlow dan Lane 1988; Vizcaino 2004). Antibodi Ab 2 dapat mengenali daerah pengikatan antigen pada Ab 1 dan dapat berikatan dengan Ab 1 sebagaimana halnya Ab 1 berikatan dengan antigen (Field et al. 2002), menunjukkan bahwa Ab 2 memiliki struktur yang mirip dengan antigen. Selanjutnya, Ab 2 dapat menginduksi terbentuknya Ab 3 yang dapat mengenali Ab 2 dan seterusnya, sehingga pada akhirnya dapat menginduksi terbentuknya serangkaian
4
autoantibodi yang dapat saling mengenali satu sama lain membentuk suatu jaringan idiotipik (Jerne 1985). Interaksi determinan idiotipe dan antibodi anti -idiotipe dapat
mempengaruhi modulasi respon imun, mengaktivasi atau menekan respon imun humoral dan selular (Shoenfeld 2004). Pemberian anti -idiotipe dapat menekan ekspresi idiotipe dan memacu pembentukan idiotipe spesifik limfosit T suppressor. Mekanisme supresif dapat terjadi karena dua hal: pertama, anti-idiotipe memblok reseptor idiotipe pada sel B primer dan hanya merangsang pembentukan non -idiotipe; kedua, anti-idiotipe hanya menginduksi idiotipe spesifik sel T suppressor. Pada kondisi lain, anti-idiotipe meningkatkan ekspresi idiotipe dan pembentukan antigen spesi fik limfosit T helper. Mekanisme aktivasi yang terjadi seperti antigen asing yang merangsang pembentukan respon imun (Nisonoff 1991). Teori jaringan idiotipik Jerne (1985) juga menjelaskan, bahwa imunisasi dengan suatu antigen dapat menginduksi bukan hany a antibodi spesifik terhadap antigen (Ab1), tapi juga antibodi yang dapat mengenali Ab 1. Hal ini terjadi karena struktur khas (idiotipe) pada daerah pengikatan antigen dari Ab 1 mampu menginduksi sistem imun untuk membentuk Ab 2 yang meniru struktur antigen eksternal dan bahkan terjadi terhadap antigen sendiri (self antigen) (Roitt et al. 1993 ; Vogel et al. 2000). Melalui mekanisme yang sama, akan terbentuk Ab3. Ab 1 dan Ab3 mempunyai kemampuan berikatan yang sama dan dalam beberapa kasus, mempunyai susunan asam amino yang sama pada daerah pengikatan antigennya (Roitt et al. 1993). Anti-idiotipe yang hanya mengenali satu antibodi saja dikatakan mengenali idiotop pribadi (IdI) dan menyokong pendapat bahwa tiap antibodi mempunyai struktur yang unik. Sering juga molekul antibodi mempunyai struktur asam amino yang sangat mirip satu sama lain sehingga mempunyai idiotipe yang sama. Ini dikenal sebagai idiotipe public (umum) atau idiotipe cross reacting (IdX). Idiotipe umum juga sering disebut dengan common dan share idiotope. Respon kebal Ab 2 yang terbentuk dapat digolongkan berdasarkan topografi target idiotipe menjadi kelompok yang tidak mampu menghambat
5
antigen (antigen-noninhibitable group ) (Ab2 ) dan kelompok yang mampu menghambat antigen (antigen-inhibitable group) (Ab2 ). Kelompok ketiga disebut dengan Ab 2 , merupakan antibodi anti-idiotipe yang mengenali combinating site idiotop di dekat daerah pengikatan antigen dan mampu menghambat pengikatan antigen dengan pengaruh sterik, tetapi tidak membentuk struktur yang mirip dengan antigen asli. Jadi, hanya Ab 2 dan Ab2 yang dapat menghambat ikatan Ab1 dengan antigen (Ban et al. 1994). Karakteristik Ab2 disebut juga noninternal image karena ikatan tidak antibodi dengan anti -idiotipe terjadi di luar paratop, sehingga
menghalangi ikatan antigen dengan paratop dari antibodi (Male et al. 1987 ; Guancheng et al. 2001). Zhou et al. (1990) menyatakan, bahwa reaksi Ab 2 dengan idiotipe berlokasi di luar antigen-binding site dan tidak dihambat oleh antigen. Kemampuan Ab 2 terbatas dalam peningkatan respon imun pada spesies berbeda (Kennedy et al. 1986). Jika Ab2 berikatan di dekat paratop dari antibodi dan reaksinya dapat dihambat oleh antigen karena pengaruh sterik dan allosterik, maka Ab 2 ini disebut dengan Ab 2 (Guancheng et al. 2001). Sejumlah Ab2 yang terbentuk akibat responnya terhadap Ab 1 dapat mengekspresikan determinan idiotipe yang meniru antigen aslinya, disebut Ab2 . Antibodi anti-idiotipe Ab 2 mengandung internal image dari antigen
eksternal, sehingga disebut juga antibodi internal image (Guancheng et al. 2001). Interaksi antigen dengan Ab 1 dapat dihambat oleh Ab 2 , demikian juga interaksi Ab 2 dengan Ab 1 dapat dihambat oleh antigen. Antibodi Ab 2 mampu menimbulkan respon antibodi terhadap antigen asli pada he wan lain. Hal ini merupakan indikasi bahwa Ab 2 yang dihasilkan mengenali IdX yang berlokasi pada atau dekat antigen combinating site Ab1 (Zhou et al. 1994). Baik antigen maupun antibodi anti -idiotipe mempunyai tempat ikatan yang sama dan dapat berikatan secara kompetitif dengan idiotipe (Bentley et al. 1990). Antibodi Ab 2 memiliki struktur idiotipe yang menunjukkan internal image terhadap epitop antigenik yang dikenali dari Ab 1 dan mempunyai kemampuan meniru struktur tiga dimensi determinan antigen atau epitop
6
berdasarkan atas kemiripan struktur kimia hapten dan lekukan i diotop di atas permukaan imunoglobulin. Meskipun merupakan struktur tiga dimensi dari asam amino, namun antibodi internal image juga dapat meniru epitop protein, karbohidrat atau lemak (Ban et al. 1994). Struktur tiga dimensi Ab 2 menunjukkan, bahwa mimikri asam amino terletak pada lekukan antigen binding site dari daerah hipervariabel rantai berat (Luo et al. 2000). Ab2 meniru struktur antigen melalui proses saling melengkapi ( complementary) dan homobodies (Rico dan Hall 1989; Kennedy dan Attanasio 1990). Struktur antigenik yang potensial akan ditiru dan disajikan kembali dengan struktur yang mirip (internal image) oleh idiotipe (Zhou et al. 1991). Imunisasi dengan Ab 1 tidak hanya menghasilkan subset Ab 2 , tetapi juga menginduksi Ab 2 dan Ab2 . Antibodi Ab2 dengan beragam subset, dapat menginduksi terbentuknya anti -anti-idiotipe Ab 3 yang sangat kompleks. Hal ini terjadi terutama bila digunakan Ab 2 poliklonal yang mengandung beragam subset (Ab 2 , Ab 2 dan Ab 2 ). Pada Gambar 2 dapat dilihat skema kaskade idiotipe (Hiernaux 1988). Epitop dari suatu antigen asing menginduksi respon imun yang ditandai dengan terbentuknya antibodi Ab 1. Selanjutnya, Ab 1 menginduksi terbentuknya Ab 2 yang mengandung tiga subset, yaitu subset Ab 2 , Ab 2 dan Ab 2 . Setiap subset dari Ab2 akan menginduksi anti-anti-idiotipe Ab 3 yang sangat kompleks dan beragam.
7
Gambar 2. Skema kaskade idiotipe (Hiernaux 1988).
Suatu molekul antibodi internal image yang tepat dapat menginduksi respon imun yang sama dengan yang ditimbulkan oleh antigen eksternal, sehingga Ab 2 merupakan alternatif yang baik untuk vaksin. Antidodi anti idiotipe yang dihasilkan dari antibodi spesifik terhadap suatu antigen dapat menginduksi respon imun selular ( cell-mediated immune response) dan humoral (Kennedy et al. 1987). Respon imun selular ditandai dengan adanya proliferasi limfosit T yang dapat mengenali antigen yang berada pada permukaan molekul major histocompatibility complex (MHC) (Guancheng et al. 2001). Suatu subpopulasi limfosit T d isebut sel T helper akan mengenali dan mengikat suatu gabungan antigen dengan molekul MHC kelas II pada permukaan makrofag dan menghasilkan berbagai faktor yang larut dalam cairan tubuh yang disebut sitokin, misalnya -interferon dan faktor pengaktif makrofag lainnya yang mengaktifkan mekanisme mikrosidal dari makrofag. Di pihak lain, kelompok sel T sitotoksik hanya mengenali antigen dalam keadaan bergabung dengan molekul MHC kelas I. Melalui pengenalan terhadap antigen permukaan ini, sel-sel T sitotoksik menyerang dan membunuh sasarannya. Sel T sitotoksik juga melepaskan membantu memperkecil penyebaran virus ke sel-sel berdekatan (Roitt et al. 1993). -interferon yang lainnya yang
Antibodi Anti-idiotipe sebagai alternatif pengganti Antigen
Antibodi anti-idiotipe (Ab 2) mampu meniru struktur antigenik yang potensial dan memiliki internal image idiotop yang berbeda-beda (Zhou et al. 1991), sehingga dapat digunakan sebagai antigen pengganti dalam pemeriksaan serologis dan mendeteksi antibodi dari spesies hewan berbeda. Jika Ab2 digunakan sebagai imunogen, akan mengakibatkan peningkatan respon antibodi spesifik (Ab 3). Idiotipe Ab 1 identik dengan Ab 3 (Clark et al. 1996). Kekhasan reaksi idiotipe -anti-idiotipe ini digunakan sebagai dasar untuk menghasilkan reagen anti -imunoglobulin spesifik (Harlow dan Lane 1988).
8
Respon Ab2 yang hanya bereaksi terhadap epitop tunggal agen infeksius mampu memberikan perlindungan protektif terhadap antigen yang memiliki beragam epitop dan dapat mencegah timbulnya autoimun yang akan merusak jaringan inang dan komponen tubuh yang lain apabila digunakan agen penyakit yang memiliki determinan antigenik yang mirip dengan jaringan inang (Kennedy dan Attanasio 1990). Antibodi anti-idiotipe memiliki karakteristik serologis internal image (Perosa dan Dammaco 1994), sangat potensial digunakan sebagai imunogen (Fields et al. 2002) dan antigen dalam serodiagnostik, preparasi vaksin (Thanavala et al. 1985 ; Greenspan dan Bona; 1993; Qian et al. 1997), modulasi respon imun (Zhou et al. 1994; Mittelman et al. 1995), imunoterapi (Luo et al. 2000) termasuk terapi penyakit autoimun (Rico dan Hall 1988). Selain itu, Ab 2 juga dapat digunakan sebagai antigen pengganti pada imunisasi dengan antigen yang sulit didapat dalam jumlah banyak (Roitt 2003). Menurut Suartha (1999), Ab2 mampu memberikan perlindungan 88,8% terhadap serangan bakteri Streptococcus Group C (SGC) ganas dan dapat digunakan sebagai prekursor awal sistem imun inang terhadap agen infeksius. Pemberian Ab 2 pada simpanse sebelum pemberian antigen HBs mampu meningkatkan titer antibodi terhadap HBs dibandingkan dengan tanpa pemberian Ab 2 (Kennedy et al. 1984). Perkembangan anti-idiotipe yang mampu meniru antigen asli memiliki keuntungan : (1) anti-idiotipe dapat diproduksi dengan mudah dalam jumlah yang banyak; (2) kesulitan yang berhubungan dengan tenaga, biaya dalam penyediaan antigen dari agen penyakit dapat dieliminasi; (3) bahaya penyebaran agen infeksius dalam pelaksanaan di lapangan dapat dihindari (Lin dan Zhou 1995).
Produksi Antibodi Anti-idiotipe pada Ayam
Secara umum sistem imun pada ayam menyerupai sistem imun pada mamalia. Imunoglobulin pada ayam diberi nama imunoglobulin Y (IgY), merupakan salah satu kelas antibodi dalam serum dan kuning telur kelompok
9
amfibi, reptil dan aves. Kemiripan struktur ant ara IgY dan IgG mamalia menyebabkan IgY disetarakan dengan IgG (Narat 2003). Perbedaan utama antara IgG dan IgY terletak pada jumlah regio konstan (C) rantai berat. Imunoglobulin G mempunyai tiga regio konstan, yaitu C 1 C 3, sedangkan IgY mempunyai empat regio konstan, yaitu Cv1 Cv4. Pada IgY terdapat penambahan satu regio tambahan, yaitu antara Cv1-Cv2 dan Cv2-Cv3 yang mengandung residu proline dan glysine (Gambar 3). Regio tambahan ini menyebabkan fleksibilitas IgY terbatas (Narat 2003).
regio hinge
Gambar 3. Perbedaan struktur IgY dan IgG (Anonim 2002).
Pemilihan ayam untuk produksi Ab 2 memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah karena antibodi ayam (IgY) mempunyai afinitas dan aviditas yang lebih tinggi terhadap protein mamalia; tidak be rikatan dengan faktor rheumatoid dan reseptor Fc mamalia; tidak mengaktifkan sistem komplemen mamalia dan tidak berikatan dengan protein A dan G dari Staphylococcus aureus (Anonim 2004). Hal ini disebabkan karena
perbedaan secara struktural pada daerah Fc antara IgY dan IgG, karena fungsi biologi imunoglobulin diaktivasi oleh regio Fc. Sistem imun ayam sangat responsif terhadap protein asing atau mikroorganisme yang memaparnya, baik sebagai akibat vaksinasi ataupun infeksi alam. Carlander (2002) menyatakan , ayam memiliki sensitivitas tinggi terhadap protein asing, sehingga dengan jumlah sedikit dapat memberikan respon pembentukan antibodi. Keberadaan kelenjar Hadrian di daerah nasotrakheal dan Bursa Fabricius memungkinkan unggas sangat responsive
10
terhadap berbagai protein asing (Coleman 2000). Secara filogenik, antara ayam dan mamalia mempunyai jarak yang jauh menyebabkan aviditas antibodi ayam lebih tinggi terhadap protein mamalia dibandingkan aviditas antibodi mamalia terhadap protein mamalia. Antibodi aya m dapat mengenali lebih banyak epitop antigenik pada antigen mamalia. Produksi Ab2
pada
ayam juga sangat menguntungkan karena respon imun unggas (ayam) terbukti persisten. Antigen mamalia yang disuntikkan pada ayam mampu menginduksi titer IgY yang tinggi d an bertahan lama pada telur (Gassmann et al. 1990). Selain itu, IgY dapat diperoleh dari telur tanpa harus menyakiti hewan dan jumlah antibodi yang dihasilkan lebih banyak. Ayam biasanya bertelur 5 sampai 6 butir per minggu dan sebutir kuning telur yang me mpunyai volume 15 ml rata-rata mengandung 50 100 mg IgY, dimana 2% sampai 10% adalah antibodi spesifik (Schade et al. 1996). Keunggulan lainnya, karena pemeliharaan ayam lebih mudah dan murah.
Tiga Tipe Virus Influenza (A, B, dan C) Penyakit flu pada manusia dan hewan disebabkan oleh virus dalam famili Orthomyxoviridae, memiliki amplop (envelope), bersegmen dan memiliki negative-single strand RNA. Virus influenza terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Virus influenza tipe A dan B memiliki 8 segmen RNA, namun virus influenza tipe C hanya memiliki 7 segmen (Gambar 3) (Anonymous. 2004, Hoffmann et al., 2000.).
11
Gambar 3. Virus Influenza Tipe A, B, dan C
Virus influenza tipe A dapat menginfeksi bermacam jenis hewan mamalia seperti babi, kuda, kucing, harimau, macan tutul, mamalia laut serta jenis unggas; dan termasuk manusia. Virus influenza tipe A diklasifikasikan ke dalam beberapa subtipe, sesuai dengan kan dungan protein
permukaannya, yaitu haemagglutinin (HA) dan neuraminidase (NA). Hingga kini telah teridentifikasi sebanyak 15 subtipe HA (H1 -H15) dan 9 subtipe NA (N1-N9) pada unggas (Anonymous. 2005a,b). Antigen permukaan yang dimiliki virus influenza tersebut dapat berubah secara periodik yang lebih dikenal dengan istilah antigenic drift dan antigenic shift. Antigenic drift merupakan perubahan yang terjadi akibat
mutasi genetik struktur protein permukaan virus, sehingga antibodi yang telah terbentuk ole h tubuh akibat vaksinasi sebelumnya tidak dapat mengenali keberadaan virus tersebut, sedangkan antigenic shift merupakan perubahan genetik virus yang memungkinkan virus ini menginfeksi secara lintas spesies (Gambar 4 dan 5).
12
Gambar 4. Ilustrasi Antigenic Drift Virus Influenza
13
Gambar 5. Ilustrasi Antigenic Shift Virus Influenza
Berbeda dengan virus influenza tipe A, virus influenza tipe B tidak diklasifikasikan ke dalam subtipe dan hanya menyerang manusia. Namun, virus ini telah diketahui dapat menginfeksi anjing laut. Virus influenza tipe B dapat menyebabkan epidemi pada manusia, namun tidak sampai
menyebabkan pandemi. Virus influenza tipe C, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hanya memiliki 7 segmen RNA, tidak seperti virus influenza tipe A ataupun tipe B yang memiliki 8 segmen. Virus influenza tipe C tidak memiliki protein
14
permukaan HA dan NA seperti yang dimiliki oleh virus influenza tipe A dan B akan tetapi kedua segmen tersebut digantikan oleh glikoprotein tunggal ya ng disebut dengan haemagglutinin-esterase-fusion (HEF). Virus influenza tipe C hanya menyebabkan gejala penyakit ringan saja dan tidak menyebabkan epidemi maupun pandemi penyakit pada manusia.
Virus Avian Influenza atau Virus Flu Burung
Avian influenza (AI) menyebabkan angka kematian yang tinggi pada ayam di Italia pada tahun 1878. Namun baru diketahui pada tahun 1955 bahwa penyebab fowl plague sebenarnya adalah virus AI yang memiliki komposisi gen yang serupa (hampir identik) dengan virus influenza manu sia. Virus AI adalah virus influenza tipe A, pada awalnya hanya menyerang unggas, dan berdasarkan atas patogenitasnya dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI) dan Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI). Pada umumnya strain virus AI ada
dalam bentuk LPAI (H1-H4, H6, H8-H15) dan umumnya menyebabkan sedikit gejala klinis atau bahkan tidak memperlihatkan gejala klinis sedikitpun (Anonymous 2005b). Angka kematian hewan yang terinfeksi virus LPAI sangat rendah bila tidak terjadi infeksi sekunder. Beberapa strain LPAI mampu bermutasi di bawah kondisi lapang menjadi virus HPAI. Virus HPAI bersifat sangat
infeksius dan fatal pada unggas. Virus HPAI dapat menyebabkan kematian hingga 100% dalam waktu yang cepat pada unggas dengan at au tanpa memperlihatkan gejala klinis, dan ketika ini terjadi, maka penyakit dapat menyebar dengan cepat antar flock. Penyebaran virus HPAI antara lain melalui aktivitas migrasi burung -burung liar yang merupakan induk semang (inang) alami virus penyebab, kontak langsung dengan hewan terinfeksi, feses, air minum, udara di daerah tercemar, peralatan kandang tercemar, serta secara sekunder melalui pekerja kandang, kendaraan pengangkut, pakan, dan lain -lain yang berasal dari daerah tercemar. Virus HPAI ini d apat hidup pada suhu lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan dapat bertahan hidup pada bahan -bahan
15
yang telah dibekukan.
Satu gram feses hewan yang terinfeksi virus ini
mengandung virus yang cukup untuk menginfeksi satu juta unggas ( Federal Register Vol. 70, No. 20, 1 Februari 2005). Wood (2005) menyatakan bahwa virus AI dapat bertahan hidup pada feses sekurang-kurangnya hingga 35 hari pada suhu 4 oC. Pada karkas, virus tersebut dapat bertahan hidup hingga beberapa hari pada suhu rendah dan dapat bertahan hingga 23 hari pada suhu lemari pendingin ( refrigerator).
Faktor Virulensi Virus AI
Faktor virulen virus AI yang paling berperan adalah haemaglutinin (H) yang tersusun dari 560 asam amino. Asam amino yang menyusun regio cleavage site sangat menentukan keganasan virus ini. Virus HPAI memiliki multi basic amino acid (arginin dan lisin) pada cleavage site-nya sedangkan virus avirulen hanya memiliki arginin tunggal pada cleavage site-nya (Tabel 1) (Senne et al., 1996). Proses cleavage virus dipengaruhi oleh keberadaan enzim protease. Pada virus LPAI, proses cleavage hanya terbatas pada keberadaan enzim protease ekstraseluler seperti trypsin-like enzyme
(saluran pernafasan dan saluran pencernaan). Sedangkan proses cleavage virus HPAI dapat dipicu oleh keberadaan enzim protease yang tidak spesifik dengan purin sebagai kandidat utama. Kehebatan dari virus HPAI adalah kemampuannya untuk melakukan replikasi yang mengakibatkan kerusakan organ vital serta jaringan-jaringan hewan unggas yang rentan (Chen et al., 1998).
Patogenesis Virus AI
Perjalanan penyakit AI diawali dengan masuknya virus ke dalam tubuh yang dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan penderita dan melalui droplet ( fecal-oral) lewat leleran atau tinja. Adanya reseptor terhadap protein permukaan virus memungkinkan terjadinya perlekatan virus pada sel-sel inangnya. Reseptor pada permukaan sel inang berbeda antar spesies dan menjadikan virus bersifat host specificity. Dengan proses endositosis, virus masuk ke dalam sel dan kemudian proses uncoating pun
16
terjadi. Proses ini sangat tergantung pada derajat keasaman (pH). Proses uncoating menyebabkan terbebasnya genom virus pada sitoplasma sel inang dalam bentuk vRNP yang kemudian menuju ke inti sel inang untuk proses replikasi. Dari inti, mRNA membawa informasi genetik ke sitoplasma sel untuk memulai proses sintesis protein yang dibutuhkan untuk merakit virus virus baru. Beberapa protein hasil sintesis dibawa kembali ke inti sel dan berperan dalam proses replikasi RNA virus, sekaligus untuk merakit vRNP. Hasil rakitan yang berupa vRNP kemudian meninggalkan inti sel inang dan mulailah terjadi perakitan virus -virus baru yang akan melepaskan diri dari sel inang dengan cara budding (Gambar 6).
Gambar 6. Mekanisme Replikasi Virus pada Sel Inang
Replikasi virus terjadi secara terus menerus selama masa inkubasi penyakit hingga akhirnya timbul gejala klinis pada inang. Pada unggas yang terinfeksi akan tampak gejala klinis yang beragam seperti gangguan respirasi, penurunan produksi telur pada unggas hingga infeksi sistemik yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan pada manusia, virus ini menyerang saluran pernafasan dan saluran pencernaan orang yang terinfeksi yang
17
ditandai dengan pneumonia sehingga penderita mengalami kes ulitan bernafas, demam yang tinggi, batuk, nyeri pada bagian dada, serta diare. Beberapa gejala klinis yang seringkali tampak pada ayam ras yang terserang virus HPAI diantaranya adalah depresi, jengger berwarna biru, feses yang basah, terdapat bercak mera h pada bagian bawah kulit kaki, serta kematian hewan secara mendadak. Pada manusia, infeksi virus HPAI dapat menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang cepat.
Loncatan infeksi virus avian influenza antar spesies dari unggas ke manusia dimungkinkan melalui dua cara, yakni (1) akibat kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi, meskipun mekanismenya belum tuntas dapat dijelaskan dan (2) infeksi virus hasil pencampuran materi genetik ( genetic reassortment) antara virus avian influenza dengan virus influen za manusia pada babi (Gambar 7). Hal ini menerangkan tentang kemungkinan
penularan virus AI dari unggas ke manusia.
METODE PENELITIAN
Vaksin Avian Influenza
Dalam penelitian ini digunakan vaksin AI mati homolog (H5N1: PT IPB-Shigeta).Hewan Percobaan
Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam layer strain Isa Brown umur 22 minggu untuk pembuatan antibodi anti -idiotipe (Ab 2), kelinci New Zealand White berbobot 2,5 kg terhadap virus AI (Ab1).Produksi Antibodi (Ab1) flu burung pada kelinci
untuk pembuatan antibodi
Produksi antibodi Avian influenza dilakukan dengan menyuntik 1 ml suspensi vaksin (10 9 HA) secara intra muskular dan diulang 2 minggu
18
setelah penyuntikan pertama terhadap seekor kelinci New Zealand White. Jika titer antibodi tinggi dalam darah, maka serum dikoleksi dan disimpan hingga untuk penelitian selanjutnya.
Reidentifikasi Serum Kelinci anti flu burung
Reidentifikasi serum kelinci dilakukan dengan uji imunodifusi Agar Gel Precipitation Test (AGPT).Pemotongan Imunoglobulin dan Purifikasi Fragmen F(ab) 2
Pemotongan imunoglobulin kelinci ditujukan untuk memperoleh fragmen F(ab)2 dari imunoglobulin. Fragmen F(ab) 2, selanjutnya disebut Ab 1, akan digunakan untuk merangsang terbentuknya antibodi spesifik terhadap epitop Ab 1 pada ayam. Antibodi yang akan terbentuk oleh Ab 1 ini merupakan antibodi anti-idiotipe (Ab 2). Pemotongan dilakukan dengan menggunakan enzim pepsin, sehingga akan diperoleh 1 fragmen F(ab) 2 divalen yang mengandung 2 Fab dan 1 fragmen Fc.Produksi Antibodi Anti-Idiotipe (Ab 2)
Antibodi anti-idiotipe (Ab2) disiapkan dengan cara menyuntik ayam dengan Ab 1. Penyuntikan dilakukan selama 4 minggu. Pada minggu pertama, ayam disuntik secara intra vena dengan 0,5 ml Ab 1, kemudian pada minggu kedua, ketiga dan keempat dilakukan sebanyak 3 kali penyuntikan berturut-turut untuk setiap minggunya (Wibawan et al. 2003). Booster dilakukan 2 minggu berikutnya dengan menyuntikkan secara subkutan 0,5 ml Ab1 yang diemulsikan dalam 0,5 ml Freunds incomplete adjuvant (FIA). Jika titer antibodi tinggi dalam darah, maka serum dikoleksi dan disimpan hingga untuk penelitian selanjutnya..
Pengendapan Imunoglobulin Ayam (IgY = Ab 2) dengan Amonium Sulfat
Pemurnian antibodi anti-idiotipe Ab2 dari serum ayam dilakukan sesuai metode baku Harlow dan Lane (1988).
19
Pemurnian dengan Kolom Kromatografi Afinitas
Pemurnian
selanjutnya
dilakukan
pada
kolom
kromatografi
menggunakan matriks afinitas spesifik terhadap IgY. Pengukuran kadar IgY dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang g elombang 280 Lm. Selanjutnya dilakukan analisis pita protein menggunakan metode Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis (SDS -PAGE) (Hames dan Rickwood 1987).Karakterisasi Antibodi Anti-Idiotipe
Karakterisasi antibodi anti-idiotipe dilakukan dengan uji imunodifusi menggunakan metode AGP (Agar Gel Precipitation ) dan SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate Polyacrylamide Gel Electrophoresis ).
Pengukuran Konsentrasi Antibodi Anti -idiotipe (Ab 2)
Pengukuran konsentrasi Ab 2 dilakukan dengan metode Bradford (1976) menggunakan spektrofotometer.
RANCANGAN RISETPRODUKSI ANTIBODI FLU BURUNG PADA KELINCI
Reidentifikasi serum kelinci anti flu burung
PRODUKSI ANTIBODI ANT I IDIOTIPE (AB2) PADA AYAM
PEMURNIAN DAN KARAKTERISASI ANTIBODI ANTI IDIOTIPE (AB2)
Identifikasi Ab2
Penentuan Berat Molekul
20
RINCIAN ANGGARAN PENELITIAN
1. Bahan Habis dan Hewan Percobaan Nama Bahan Hewan coba 1. Kelinci New Zealand White 2. Ayam layer 4. Biaya pakan kelinci 5. Biaya pakan ayam Bahan kimia Vaksin AI PBS NaCl fisiologis Aquabidest Antigen virus AI H5N1 Agarose PEG-6000 2 Akuadestilata ddH2O K2SO4 Na2HCO3 Amonium sulfat SDS Tris Hcl Acrylamide-Bis Amonium Ferosulfat Tetra Methyl Etilen Diamin Bahan ELISA Eppendorf 1,5 ml Tip micropipet 1 ml Tip micropipet 100 mikroliter Tip micropipet 10 Ql Microplate Syringe 1 ml Syringe 3 ml Kapas Colum Hi-Trap IgY Kantong dialisis 1 rol 10 10 500 500 500 500 500 500 500 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 Volume Satuan Satuan Biaya (Rp) 50,000 50,000 150,000 150,000 Jumlah Biaya (Rp) 250,000 400,000 450,000 900,000 2.000.000 35,000 700,000 500.000 100,000 100,000 1,500,000 2,000,000 80,000 150.000 185,000 185,000 650,000 2,000,000 650,000 1,000,000 650,000 500,000 4,000,000 150,000 125,000 250,000 125,000 700,000 100,000 200,000 60,000 1,100,000 1,000,000
5 8 3 6
ekor ekor bulan karung
100 1 1 2 2 1
dosis Pak Pak pak botol kaleng (250 gr) kaleng (500 gr) liter liter gr gr gr gr gr gr gr Botol set dus Pak Pak Pak Pak boks boks kg buah
350 700,000 500.000 50,000 50,000 1,500,000 1,000,000 8,000 15.000 185,000 185,000 650,000 2,000,000 650,000 1,000,000 650,000 500,000 4,000,000 150,000 125,000 125,000 125,000 350,000 100,000 100,000 60,000 1,100,000 1,000,000
21
Nama Bahan alat-alat gelas Kapas, spirtus, tissue, alluminium foil, pipet Mohr Ig Y purification kit Magnetic stirer Ig Y control Marker umum SDS Page (Low) Marker umum SDS Page (High) 2. ATK dan Perbanyakan Nama Bahan ATK dan Bahan Komputer : kertas, pulpen, tinta komputer/toner, disket, map, map, flash disk, map, Perbanyakan laporan dokumentasi
Volume
Satuan
Satuan Biaya (Rp)
Jumlah Biaya (Rp) 1,000,000 8,000,000 50.000 1.500.000 500.000 500.000 30,970,000
1 2 1 100 100
set pcs ml l l
8,000,000 25,000 1.500.000 500.000 500.000
Volume 1
Satuan
Satuan Biaya (Rp) 2,000,000
Jumlah Biaya (Rp) 2,000,000
10
buah
25000 250,000 1,000,000
1 Gaji dan Upah Ketua Peneliti (1 0rg x 10 j/mgx 10 bl) Anggota Peneliti (2 orgx 4j/mg x 9bl) Teknisi laboratorium Teknisi pemelihara kelinci Teknisi pemelihara ayam 3 Perjalanan Transpor lokal Pemeliharaan Biaya sewa kandang ayam Biaya perawatan alat FPLC Biaya perawatan alat SDS-Page Seminar/Lokakarya Pembuatan poster Penyiapan bahan seminar Seminar 1 2
set
1,000.000 3,250,000 11000 11000 2500 150000 150000 3.520.000 3.168.000 1.350.000 450,000 450,000 8,938,000 100000 600,000 600,000
320 2 x 144 540 3
jam jam jam bulan bulan
6
bulan
6
bulan
150000
900,000 500,000 300,000 1,700,000 500000 500000
eks org 500000
1000000 2,000,000 49,458,000
Total
22
DAFTAR PUSTAKAAnonim. 2000. Antibody Structure. Protein Data Bank, Research Collaboratory for Structural Bioinforma tics. http://www.rcsb.org/pdb/ [7-09- 2005]. Anonim. 2002. Immunology. Departement of Veterinary Pathology, Veterinary Immunology. University of Glasgow. Anonim. 2004. Producing Polyclonal Antibodies : Advantages o f Using Chicken Egg-derived IgY Antibodies. Gallus Immunotech Inc. Anonim. 2004a. Producing Polyclonal Antibodies : Advantages of Using Chicken Egg-derived IgY Antibodies. Gallus Immunotech Inc. Anonim. 2005a. Avian influenza infection in humans. http://www.cdc.gov/flu/avian/gen.info/avian -flu-humans.htm Anonim.2005b. Influenza viruses, types, subtypes, and strains. http://www.cdc.gov/flu/avian/gen-info/flu-viruses.htm Ban N, Escobar C, Garcia R, Hasel K, Day J, Greenwood A, McPherson A. 1994. Crystal Structure of Idiotype -Anti-Idiotype Fab Complex. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 91:1604-1608. Bentley GA, Boulot S, Riottot MM, Poljak RJ. 1990. Three -dimensional Structure of An Anti-idiotope Complex. Nature 348(6298):254-257. Chen, J., K.H. Lee, D.A. Steinhauer, D.J. Stevens, J.J. Skehel, D.C. Wiley. 1998. Structure of the hemagglutinin precursor cleavage site, a determinant of influenza pathogenicity and the origin of the labile conformation. Cell, 95: 409-17. Carlander D. 2002. Avian IgY Antibody. In Vitro and In Vivo. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from Faculty of Medicine 119. ACTA Universitatis Uppsala, Center Texas A & M University Kingsville. Coleman MA. 2000. Using Egg Antibodis to Treat Diseases. In: Egg Nutrition and Biotechnology. Sim JS, Nakai JS, Guenter W (Eds). Wallingford. UK. CABI Publish. Fields BA, Goldbaum FA, Ysern X, Poljak RJ, Mariuzza RA. 2002. Molecular Basis of Antigen Mimicry by An Anti-idiotope. Nature 374(6524):739742. Gassmann, M., P Thommes, T. Weiser and U. Hubscher. 1990. Efficient production of chicken egg yolk Antibodies Against A conserved mammalian protein. FASEB Journal 4: 2528-2532 Greenspan NS, Bona CA. 1993. Idiotypes: Structure a nd Immunogenicity. FASEB J. 7(5):437-444. Guancheng L, Jinyue H, Guohua Z, Jiangao Z, Qubing S. 2001. Monoclonal Anti-idiotype Antibody Bearing The Internal Image of Nasopharyngeal Carcinoma Assosiated Antigen. Chin. Med. J. 114(9):962-966. Harlow E, Lane D. 1988. Antibodies a Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory. United States of America. Hiernaux J. 1988. Idiotypic Vaccine and Diseases. Infect. Immun. 56(6):1407-1413.
23
Hoffmann, E., G. Neumann, Y. Kawaoka, G. Hobom, R.G. Webster. 2000. A DNA transfection system for generation of influenza A virus from eight plasmids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97(11):6108 -13. Jerne NK. 1985. The Generative Grammar of The Immune System. Science. 229:1057-1059. Kennedy RC, Attanasio R. 1990. Concept of Idiotype -based Vaccines for Hepatitis B Virus and Human Immunodeficiency Virus. Can. J. Microbiol. 36(11):811-816. Kennedy RC, Eichberg JW, Lanford RE, Dreesman GR. 1986. Anti -Idiotypic Antibody Vaccine for Type B Viral Hepatitis in Chimpanzees. Science. 232:220-223. Kennedy RC, Storthz KA, Henkel RD, Dreesman GR. 1983. Characteristics of Shared Idiotype by Two IgM Anti-Herpes Simplek Virus Monoclonal Antibodies that Recognize Different Determinants. J. Immunol. 130(94):1943-1946. Lin M, Zhou EM. 1995. Internal Ima ge Rabbit Anti-Idiotypic Antibody Detects Sheep Antibodies to the Bluetongue Virus Core Protein VP7. Immunotechnol. 1:151-155. Luo D, Qi W, Ma J, Wang YJ, Wishart D. 2000. Molecular Mimicry of Human Tumor Antigen by Heavy Chain CDR3 Sequence of The Anti -Idiotypic Antibody. J. Biochem. 128:345-347. Male D, Champion B, Cook A. 1987. Advanced Immunology. Gower Med. Pub. London. Mayer G. 2004. The Structure and Function of Immunoglobulins Antibodies. The Board of Trustees of The University of South Carolina . http://www.med.sc.edu:85/mayer/IgTypes2000.htm. [07-09-2005]. Mittelman A, Chen GZ, Wong GY, Liu C, Hirai S, Ferrone S. 1995. Human High Molecular Weight-Melanoma Associated Antigen Mimicry by Mouse Anti-Idiotypic Monoclonal Antibody MK2-23: Modulation of The Immunogenicity in Patients with Malignant Melanoma. Clin. Can. Res. 1(7)705-713. Narat M. 2003. Production of Antibodies in Chickens. Food Technol. Biotechnol. 41(3):259-267. Nisonoff A. 1991. Idiotypes : Concepts and Aplications. J. Immunol. 147(8):2429-2438. Perosa F, Dammaco F. 1994. Human CD4 Internal Antigen Mimicry by Anti idiotypic Monoclonal Antibodies. Int. J. Clin. Lab. Res. 24(1):33-40. Qian H, Wang J, Feng J. 1997. Vaccination with Monoclonal Anti-idiotypic Antibody on Immunocompetent Mice Bearing Human Ovarium Carcinoma. Chin. Med. J. 110(4):259-263. Rico MJ, Hall RP. 1989. Anti-idiotypes Antibodies as Vaccine Candidates. The Immune Network. Arch. Dermatol. 125(2):271-275. Roitt IM. 2003. Imunologi 8 th ed. Harahap et al., penerjemah. Jakarta. Widya Medika. Terjemahan dari: Essential Immunology. Roitt IM, Brostoff J, Male DK. 1993. Immunology. Third Ed. London. Mosby Year Book Europe Ltd. Saldanha J. 2000. Brief Introductio n to Antibody Structure. Birkbeck College, London WCIE 7HX.
24
Senne, D.A., B. Panigrahy, Y. Kawaoka, J.E. Pearson, J. Suss, M. Lipkind, H. Kida, R.G. Webster. 1996. Survey of the hemagglutinin (HA) cleavage site sequence of H5 and H7 avian influenza virus es: amino acid sequence at the HA cleavage site as a marker of Pthogenicity potential. Avian Dis., 40(2):425 -37 Shoenfeld Y. 2004. The Idiotypic Network in Autoimmunity : Antibodies that Bind Antibodies. Nat. Med. 10:17-18. Sollazzo M, Castiglia D, Billetta R, Tramontano A, Zanetti M. 1990. Structural Definition by Antibody Engneering of an Idiotypic Determinant. Prot. Eng. 3:531-539. Suartha IN. 1999. Preparasi Antibodi Anti -Idiotype sebagai Dasar Pembuatan Vaksin untuk Pencegahan Streptokokosis. Tesis. Program Pascasarjana. IPB. Bogor. Thanavala YM, Bond A, Tedder R, Hay FC, Roitt IM. 1985. Monoclonal Internal Image Anti-idiotypic Antibodies of Hepatitis B Surface Antigen. Immunology 55(2):197-204. Vizcaino SMJ. 2004. How Many Types are Known? Course of Introduction to the Swine Immunology. http://www.sanidadanimal.info/inmun/elautor.htm [29-06-2004]. Vogel M, Miescher S, Kuhn S, Zurcher AW, Stadler MB, Ruf C, Effenberger F, Kricek F, Stadler BM. 2000. Mimicry of Human IgE Epitopes by Anti Idiotypic Antibodies. J. Mol. Biol. 298(5):729-735. Zhou EM, Afshar A, Heckert RA, Nielsen K. 1994. Anti-Idiotypic Antibodies Generated by Sequential Immunization Detect the Share Idiotype on Antibodies to Pseudorabies Virus Antigens. J. Virol. Methods. 48:301313. Zhou EM, Fischer MMD, Rector ES, Sehon AH, Kisil FT. 1991. A Murine Monoclonal Anti-Idiotypic Antibody Detects a Common Idiotope on Human, Mouse and Rabbit Antibodies to Allergen Lol p IV. Scand. J. Immunol. 34:307-316. Zhou EM, Lohman KL, Kennedy RC. 1990. Administration of Noninternal Image Monoclonal Anti-idiotypic Antibodies Induces Idiotype -Restricted Responses Spesific for Human Immunodeficiency Virus Envelope Glycoprotein Epitopes. Virology 174:9-17.
25
PERSONALIA PENELITIAlokasi Waktu (jam/minggu) 8 8 8
No. 1 2 3
Nama dan Gelar Dr. drh. Retno D. Soejoedono, MS
Bidang Keahlian Imunologi
Dr. drh Sayu Putu Yuni Paryati, Mikrobiologi MSi drh. Okti Nadia Poetri Imunologi
BIODATA PENELITI BIODATA PENELITI UTAMANama NIP Nomor Karpeg Pangkat Jabatan dan Gol. Ruang Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Laboratorium dan Bagian : Dr. drh. Retno D. Soejoedono, MS : 130 522 188 : B.535302 : Pembina (gol. IVb)/Lektor Kepala : Magelang, 7 Mei 1952 : Perempuan : Imunologi, Mikrobiologi Kesehatan
PENELITIAN No1
Judul PenelitianMempelajari sifat serologik beberapa virus Gumboro yang berasal dari daerah pada ternak ayam di Indonesia Isolasi dan identifikasi viral arthritis pada ayam Pembuatan vaksin Gumboro dengan virus bibit isolat Indon esia terpilih Pemanfaatan virus simbion dari beberapa spesies parasitoid untuk meningkatkankinerja Inareolata sp , dalam pengendalian Crosciloma binolatalis zeller Kekebalan tubuh yang diakibatkan vaksinasi vaksin IBD ditantang virus Gumboro asal lapang Kekebalan tubuh yang divaksinasi
Sumber DanaDikti
Kedudukan dalam timAnggota
Tahun1995 s/d 1996
2 3
Sendiri RUT 1
Anggota Anggota
1996 1996
4
RUT4
Anggota
1997 s/d 1998
5
Pascasarjana
Ketua
1998 s/d 2000 2000
6
Sendiri
Ketua
26
7
8
9
dengan vaksin IBD aktif dan inaktif ditantang isolat asal lapang Kekebalan tubuh yang divaksinasi dengan vaksin IBD aktif ditantang isolat asal lapang K -15 Pengaruh vaksin IBD aktif yang diatenuasi setelah tubuh ditantang dengan isolat asal lapang Pemanfaatan telur ayam sebagai pabrik biologis : Produksi Yolk Immunoglobulin (IgY) anti plak dan diare dengan titik berat pada anti Streptococcus mutan , Eschericia coli, dan Salmonella Enteritidis
Sendiri
Ketua
2000
Sendiri
Mandiri
2002
RUT12
Ristek
2005
PUBLIKASI ILMIAHNo1
JudulMempelajari sifat serologik beberapa virus Gumboro yang berasal dari daerah padat ternak unggas di Indonesia Isolasi dan identifikasi virus penyebab viral arthritis pada ayam Penyakit Gumboro dan akibat yang ditimbulkan baik pada ayam pedaging maupun a yam petelur Cross protection studies of chickens vaccinated with imported IBD vaccine and challenged with 3 pathogenic IBD isolates in Indonesia Uji netralisasi silang isolat virus IBD asal lapang ter hadap antisera vaksin impor Pembuatan vaksin Gumboro dengan virus bibit isolat lapang Indonesia terpilih Uji tantang dengan virus IBD isolat lapang pada ayam yang mendapatkan vaksin IBD aktif dan inaktif Isolasi Chicken Infectious Anemia Virus dan Reovirus pada ayam kerdil Pemanfaatan virus simbion dari beberapa spesies parasitoid untuk meningkatkan kinerja Inareolata sp dalam pengendalian Croscilomia binolatalis zeller Kekebalan ayam akibat vaksinasi IBD aktif yang ditantang dengan virus IBD isolat lapang
Nama Majalah IlmiahHemeraZoa, 77, 2:106 110
Tahun1996
2 3
HemeraZoa, 78:19 -27 HemeraZoa, 78:42 -57
1996 1996
4
HemeraZoa, 79:22 -29
1997
5
HemeraZoa, 79:135 -148
1997
6
Seri Abstrak RUT1 : 41
1997
7
Media Veteriner 5(4): 28 33
1998
8 9
HemeraZoa, 80:1-45 (28-33) Laporan RUT4
1998 1998
10
Proseding Seminar dan PIT/PERMI
2000
27
BIODATA ANGGOTA PENELITI1 Nama lengkap Tempat/tgl. lahir Jenis kelamin
Dr. drh. Sayu Putu Yuni Paryati, M.Si.
Tabanan, 4 Juni 1965
Perempuan
2 Pendidikan Tempat Pendidikan Univ. Udayana Gelar Sarjana Kedokteran Hewan Dokter Hewan Kota Denpasar, Bali Tahun Lulus 1988 Bidang Studi Kedokteran Hewan
Univ. Udayana
Denpasar, Bali Bogor Jawa Barat Bogor Jawa Barat
1990
Kedokteran Hewan Sains Veteriner
Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor
Magister Sains
2002
Doktor
2006
Sains Veteriner
3 INSTITUSI Kopertis Wil. IV dpk pada Akademi Medis Veteriner Puragabaya Bandung JABATAN Lektor kepala PERIODE KERJA Tahun 1993 - sekarang
Pengalaman Penelitian : 1. Penelitian tentang pengaruh penyimpanan vaksin ND yang sudah diencerkan pada suhu kamar terhadap titer antibodi ND. 2. Penelitian tentang Vaksinasi ND pada ayam melalui makanan. 3. Penelitian tentang prevalensi Toxoplasmosis pada kucing berdasarkan uji feses dan darah di Wilayah Kerja Poskeswan Cikole, Lembang. 4. Penelitian mengenai patogenesis mastitis subklinis yang disebabkan oleh S.
aureus.
28
5. Penelitian tentang bakteri pencemar daging yang dipotong di RPH Kodya Bandung 6. Isolasi dan karakterisasi imunoglobulin ayam SPF ( Spesific Pathogen Free ) 7. Antibodi anti -idiotipe sebagai vaksin rabies Karya Ilmiah dan Publikasi 1. Paryati, S.P.Y. 1990. Pengaruh Lama Penyimpanan Vaksin Newcastle Disease dalam Akuades steril dan Larutan NaCl Fisiologis terhadap Titer Antibodi ND pada Ayam Buras. Skripsi. Univ. Udayana. Denpasar. 2. Paryati, S.P.Y. 1997. Mastitis; Suatu Problema dalam Peternakan Sapi P erah. (tidak dipublikasikan). 3. Paryati, S.P.Y. 1997. Newcastle Disease dan Upaya Pengendaliannya dalam Peternakan Ayam (tidak dipublikasikan). 4. Paryati, S.P.Y. 1998. Infestasi Caplak Boophilus microplus pada Sapi (tidak dipublikasikan). 5. Paryati, S.P.Y. 1998. Infeksi Bovine Parvovirus pada Anak Sapi (tidak dipublikasikan). 8. Paryati, S.P.Y. 1999. Upaya Penanggulangan Rabies di Propinsi Jawa Barat (tidak dipublikasikan). 9. Paryati, S.P.Y. 1999. Seroepidemiologi Toxoplasmosis pada Kucing dan Penularannya pada Manus ia. Makalah Seminar. (tidak dipublikasikan). 10. Paryati, S.P.Y. 2000. Fungsi Hati dan Ginjal. Makalah Seminar. (tidak dipublikasikan). 11. Paryati, S.P.Y. 2000. Mekanisme Infeksi Streptococcus Pneumoniae . Makalah Seminar. (tidak dipublikasikan). 12. Paryati, S.P.Y. 2000. Waspada terhadap Penyakit Mulut dan Kuku Zoonosis Asal Hewan. Wawasan TRIDHARMA. Nomor 8 Tahun XII. Kopertis Wilayah IV. Bandung. ISSN 0215 8256. 13. Paryati, S.P.Y. 2000. Respon Kekebalan Inang terhadap Koksidiosis oleh Eimeria spp. Makalah seminar ( tidak dipublikasikan ). 14. Paryati, S.P.Y. 2002. Botulismus, Kelumpuhan Akibat Keracunan Makanan. Wawasan TRIDHARMA. Nomor 1 Tahun XV. Kopertis Wilayah IV. Bandung. 15. Paryati, S.P.Y. 2002. Pengaruh Infeksi Staphylococcus aureus terhadap struktur dan sekresi susu kelenjar ambing mencit. Laporan Penelitian ( tidak dipublikasikan ).
29
16. Paryati, S.P.Y. 2002. Penyakit Autoimun. Makalah. ( tidak dipublikasikan ). 17. Paryati, S.P.Y. 2002. Patogenesis Mastitis Subklinis yang Disebabkan oleh
Staphylococcus aureus pada Mencit Berdasarkan Gambaran Histopatologisebagai Hewan Model untuk Sapi Perah. Tesis. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 18. Paryati, S.P.Y. 2003.Glomerulonephritis (Suatu tinjauan secara Patologi seluler). Makalah. (tidak dipublikasikan). 19. Paryati, S.P.Y. 2003. Primary Immunodeficiesies. Makalah seminar ( tidak dipublikasikan ). 20. Paryati, S.P.Y. 2003. Gangguan Saluran Pencernaan oleh Staphylococcus
aureus. Makalah. (tidak dipublikasikan).21. Paryati, S.P.Y. 2003.
Squamous
Cell
Carcinoma .
Makalah.
(tidak
dipublikasikan). 22. Paryati, S.P.Y. 2003. Seleksi Positif dan Negatif dalam Kelenjar Timus. Makalah. (tidak dipublikasikan). 23. Paryati, S.P.Y. 2003. Bovine Spongiform Encephalopathy dan Creutzfeldt Jacob disease. Makalah. (tidak dipublikasikan). 24. Paryati, S.P.Y. 2003 . Keracunan Makanan oleh Bakteri . Jurnal Veteriner Vol. 4 Nomor 1. 25. Paryati, S.P.Y. 2004. Berbagai Aspek Menuju Jawa Barat sebagai Daerah Bebas Rabies. Wawasan TRIDHARMA Nomor 10 Tahun XVI Mei 2004. Kopertis Wilayah IV. Bandung. ISSN 0215 8256. 26. Paryati, S.P.Y. 2004. Keracunan Makanan oleh Staphylococcus aureus . Wawasan TRIDHARMA Nomor 7 Tahun XVII. Pebruari 2005. Kopertis Wilayah IV. Bandung. ISSN 0215 8256. 27. Paryati, S.P.Y. 2006. Antibodi Anti -Idiotipe sebagai Kandidat Vaksin Rabies.
Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.Bandung, Maret 2006 Yang membuat,
Sayu Putu Yuni Paryati
30
BIODATA ANGGOTA PENELITI1 Nama lengkap Tempat/tgl. lahir Jenis kelamin
drh. Okti Nadia Poetri
Depok, 1980
27
Oktober
Perempuan
2 Pendidikan Tempat Pendidikan Institut Pertanian Bogor Gelar Kota Tahun Lulus 2002 Bidang Studi
Sarjana Kedokteran Hewan Dokter Hewan
Bogor
Kedokteran Hewan
Bogor Institut Pertanian Bogor Institut Pertanian Bogor 2004 Kedokteran Hewan Sains Veteriner
Magister Sains (masih studi)
Bogor
2005 skrg
3 INSTITUSI Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesmavet Institut Pertanian Bogor JABATAN Ca. Asisten Ahli PERIODE KERJA Tahun 2005 - sekarang
Pengalaman Penelitian : 1. Studi Kasus Otodectic mange akibat infestasi Otodectis cynotis pada Anjing di Rumah Sakit Hewan Jakarta selama Periode Januari 1999 -Desember 2000. 2. Penelitian tentang Pemanfaatan telur ayam sebagai pabrik biologis : Produksi Yolk Immunoglobulin (IgY) anti pla k dan diare dengan titik berat pada anti Streptococcus mutan , Eschericia coli , dan Salmonella Enteritidis. 3. Kajian seroepidemiologi Avian influenza di Sumatera dan Kalimantan.
31
Karya Ilmiah, Tulisan Populer dan Publikasi 1. Poetri, ON. 2002. Studi Kasus Otodectic Mange Akibat Infestasi Otodectes cynotis pada Anjing di Rumah Sakit Hewan Jakarta selama Periode Januari 1999-Desember 2000. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2. Poetri, ON, Upik KH, Husnul H. 2003. Insidensi Penyakit Kudis Telinga (Otodectic mange) pada anjing di Rumah Sakit Hewan jakarta. Makalah. Disampaikan pada Seminar Ilmiah Nasional Seabad Kedokteran Hewan 26 Juli 2003. Bogor. 3. Poetri, ON. 2004. Ular Dapat Dinikmati Keindahannya. Majalah Satwa Kesayangan. Vol. 004 (40 -41).
Bogor, Yang membuat
Okti Nadia Poetri
JADWAL KEGIATAN
Jenis Kegiatan
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Produksi Ab1 dari kelinci Isolasi, identifikasi Ab1 Produksi Ab2 dari ayam Isolasi, Identifikasi karakterisasi Ab2 Seminar hasil dan
32