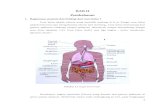86459270 BAB II Docxdit
-
Upload
devi-tias-melati-ii -
Category
Documents
-
view
61 -
download
12
Transcript of 86459270 BAB II Docxdit
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Teori
1. Kehamilan
a. Pengertian
Kehamilan Normal adalah masa kehamilan dimulai dari
konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 20 hari
(40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid
terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan yaitu triwulan pertama
dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan
keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9
bulan. (Saifuddin,2008 hal : 89)
Kehamilan adalah masa dimulai dari timbulnya ovulasi dimana
lamanya hamil normal adalah kira-kira 280 hari (40 minggu) dan tidak
lebih dari 300 hari (43 minggu), kehamilan 40 minggu ini disebut
kehamilan mater (cukugp bulan), bila kehamilan lebih dari 43 minggu
disebut kehamilan post mater. (Wiknjosastro, 2007 hal 125).
Kehamilan terjadi jika ada penyatuan ovum( oosit sekunder)
dan spermatozoa yang boasanya berlangsung diampula tuba (Sarwono,
2008 hal :141).
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine
mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan,
dimana lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu) dihitung
sejak hari pertama haid terakhir.
b. Etiologi
Untuk setiap kehamilan harus ada spermatozoa, ovum, pembuahan
ovum (konsepsi), dan nidasi hasil konsepsi. Tiap spermatozoa terdiri
dari tiga bagian yaitu : kaput/kepala yang berbentuk lonjong agak
gepeng dan mengandung bahan nucleus, ekor, dan bagian yang
silindrik menghubungkan kepala dengan ekor, dan getaran ekor
spermatozoa dapat bergerak cepat (Hanifa Wiknjosastro,2008 hal :139)
c. Fisiologi
1) Fertilisasi
- Proses penyatuan gamet pria dan wanita, terjadi didaerah
ampula tuba fallopii.
- Sekitar 100-120 juta tiap cc sperma berhasil mencapai telur,
namun hanya 1 sperma yang dapat membuahi sel telur.
Terdapat berbagai rintangan yang menghambat jalan sperma,
lapisan keras yang melindungi ovum sangat sukar untuk
ditembus, namun sperma dilengkapi sistem khusus untuk
membantunya memasuki sel telur yaitu di bawah lapisan
pelindung pada kepala sperma terdapat kantung-kantung kecil
yang berisi enzim-enzim pelarut yaitu enzim-enzim
hyaluronidase
- Sperma melepas enzim-enzim hyaluronidase untuk menembus
zona pellusida yaitu sebuah perisai glikoprotein disekeliling sel
telur yang mempermudah dan mempertahankan pengikatan
sperma dan menginduksi reaksi akrosom.
- Segera setelah spermatozoa menyentuh membrane sel oosit,
kedua selaput plasma sel menyatu. Karena selaput plasma yang
membungkus kepala akrosom telah hilang pada saat reaksi
akrosom. Reaksi akrosom yaitu reaksi yang terjadi setelah
penempelan ke zona pellusida dan induksi oleh protein-protein
zona. Penyatuan yang sebenarnya terjadi adalah antara selaput
oosit dan selaput yang meliputi bagian belakang kepala sperma.
Pada manusia, baik kepala dan ekor spermatozoa memasuki
sitoplasma oosit, tetapi selaput plasma tertinggal di permukaan
oosit. Sementara spermatozoa bergerak maju terus hingga dekat
sekali dengan pronukleus wanita. Intinya membengkak dan
membentuk pronukleus pria sedangkan ekornya lepas dan
berdegenerasi. Sperma melepaskan ekornya dan memasuki sel
telur dan melepaskan kromosom melalui lubang yang ia buka.
Sesudah itu pronukleus pria dan wanita saling rapat erat dan
kehilangan selaput inti mereka. Selama masa pertumbuhan,
baik pronukleus pria maupun wanita (haploid), masing-masing
pronukleus harus menggandakan DNA-nya. (Harry
Oxon.dkk.2010)
Gambaran 5. Sperma yang memasuki ovum
Gambaran 6. Skematik ketiga penetrasi oosit
2) Perkembangan Embrio
a) Pembelahan Zigot
Setelah pembuahan terjadi mulailah pembelahan zigot. Hal
ini dapat berlangsung karena sitoplasma ovum mengandung
banyak zat asam amino dan enzim. Setelah zigot mencapai
tingkat dua sel, ia menjalani pembelahan mitosis,
mengakibatkan bertambahnya jumlah sel dengan cepat. Sel
yang menjadi semakin kecil ini disebut blastomer dan sampai
tingkat delapan sel, sel-selnya membentuk sebuah gumpalan
longgar. Segera setelah pembelahan ini terjadi, maka
pembelahan-pembelahan selanjutnya berjalan dengan lancar,
dan dalam 3 hari terbentuk suatu kelompok sel-sel yang sama
besarnya. Sel-sel embrio yang termanfaatkan kemudian
membelah lagi, kemudian hasil konsepsi berada pada stadium
morula dengan 16 sel. Morula terdiri dari inner cell mass
(kumpulan sel-sel sebelah dalam, yang akan tumbuh menjadi
jaringan embrio sampai janin) dan outer cell mass (lapisan
sebelah luar yang akan membentuk trofoblas yang akan tumbuh
menjadi plasenta).
Gambar 7. Pembelahan Zigot
Pada stadium morula energi untuk pembelahan ini
diperoleh dari vitellus, hingga volume vitellus makin berkurang
dan terisi seluruhnya oleh morula. Dengan demikian, zona
pellusida tetap utuh, dengan kata lain, besarnya hasil konsepsi
tetap sama. Dalam ukuran yang sama ini hasil konsepsi
disalurkan melalui bagian tuba yang sempit dan terus kearah
kavum uteri. Kira-kira pada waktu morula memasuki rongga
rahim, cairan mulai menmbus zona pellusida masuk kedalam
ruang antar sel yang ada di massa sel dalam. Berangsur-angsur
ruang antar sel menyatu, dan akhirnya terbentuklah sebuah
rongga, blastokel. Pada saat ini mudigah disebut blastokista.
Sel-sel didalam massa sel dalam, yang sekarang disebut
embrioblas, terletak pada salah satu kutub, sedangkan sel-sel di
massa sel luar atau trofoblas, menipis dan membentuk dinding
epitel blastokista. Zona pellusida sekarang menghilang,
sehingga implantasi dapat dimulai. Dengan demikian,
menjelang akhir minggu pertama perkembangan, zigot manusia
telah melewati tingkat morula dan blastokista dan sudah mulai
berimplantasi di selaput lendir rahim ( Sarwono,2008)
b) Proses Implantasi
Kemudian blastula tersebut berimplantasi dalam
endometrium, dengan bagian dimana bagian inner cell mass
berlokasi. Hal inilah yang menyebabkan tali pusat berpangkal
sentral atau para sentral. Bila nidasi terjadi mulailah
diferensiasi sel-sel blastula. Sel-sel yang lebih kecil, yang dekat
dengan ruang eksoselom, membentuk entoderm dan yolk sac,
sedangkan sel-sel yang lebih besar menjadi ektoderm dan
membentuk ruang amnion.
Setelah minggu pertama (hari 7-8), sel-sel trofoblas yang
terletak di atas embrioblas yang berimplantasi di endometrium
dinding uterus, mengadakan proliferasi dan berdiferensiasi
menjadi dua lapis yang berbeda :
(1) sitotrofoblas : terdiri dari selapis sel kuboid, batas jelas,
inti tunggal, di sebelah dalam (dekat embrioblas).
(2) sinsitiotrofoblas : terdiri dari selapis sel tanpa batas jelas,
di sebelah luar (berhubungan dengan stroma endometrium).
Unit trofoblas ini akan berkembang menjadi plasenta.
hasil konsepsi
Gambar 8. Proses implantasi
Gambaran 9. Embrio yang berimplantasi pada endometrium
Gambaran yang memperlihatkan blastokista manusia
berusia 7 hari, sebagian terbenam didalam stroma
endometrium. Rongga amnion tampak sebagai sebuah celah
sempit.
Gambar 10. Inner cell mass dari embrio
c) Perkembangan Trofoblas
(1) Pembentukan Plasenta
Gambar 11. Plasenta dewasa
(a). Pertumbuhan plasenta makin lama makin besar dan
luas, umumnya mencapai pembentukan lengkap pada
usia kehamilan sekitar 16 minggu. (gambar).
(b). Plasenta mengelilingi embrio dalam rahim ibu.
(c). Plasenta berfungsi sebagai ginjal, paru-paru dan liver
buatan ia memiliki fungsi ini pada saat yang
bersamaan. Tugas lain plasenta ialah melindungi
embrio.
(d). Sel-sel bagian luar dari plasenta membentuk semacam
saringan yang terletak antara pembuluh darah ibu dan
embrio yang berfungsi mencegah bahaya dari luar.
Saringan ini meloloskan sel-sel makanan dan menahan
sel-sel imunitas.
PLASENTA DEWASA
(e). Dalam tali plasenta terdapat satu pembuluh darah vena
dan dua pembuluh darah arteri. Pembuluh darah vena
membawa makanan dan oksigen ke embrio dan
pembuluh darah arteri mengeluarkan karbon dioksida
dan sisa-sisa sampah dari tubuh sang bayi.
Gambar 12. Plasenta yang mengelilingi janin
(2) Tali Pusat
(a). Mesoderm connecting stalk yang juga memiliki
kemampuan angiogenik, kemudian akan berkembang
menjadi pembuluh darah dan connecting stalk tersebut
akan menjadi tali pusat. Pada tahap awal
perkembangan, rongga perut masih terlalu kecil untuk
usus yang berkembang, sehingga sebagian usus terdesak
ke dalam rongga selom ekstraembrional pada tali pusat.
(b). Kandung kuning telur (yolk-sac) dan tangkai
kandung kuning telur (ductus vitellinus) yang terletak
dalam rongga korion, yang juga tercakup dalam
connecting stalk, juga tertutup bersamaan dengan proses
semakin bersatunya amnion dengan korion.
(c). Setelah struktur lengkung usus, kandung kuning
telur dan duktus vitellinus menghilang, tali pusat
akhirnya hanya mengandung pembuluh darah umbilikal
( 2 arteri umbilikalis dan 1 vena umbilikalis) yang
menghubungkan sirkulasi janin dengan plasenta.
Pembuluh darah umbilikal ini diliputi oleh
mukopolisakarida yang disebut Wharton’s jelly.
(3) Selaput Janin (Amnion dan Korion)
(a). Pada minggu-minggu pertama perkembangan,
villi / jonjot meliputi seluruh lingkaran
permukaan korion. Dengan berlanjutnya
kehamilan:
1. jonjot pada kutub embrional membentuk
struktur korion lebat seperti semak-semak
(chorion frondosum sementara)
2. jonjot pada kutub abembrional mengalami
degenerasi, menjadi tipis dan halus disebut
korion leave.
(b).Seluruh jaringan endometrium yang telah
mengalami reaksi desidua, juga mencerminkan
perbedaan pada kutub embrional dan
abembrional :
1. Desidua di atas korion frondosum menjadi
desidua basalis
2. Desidua yang meliputi embrioblas / kantong
janin di atas korion laeve menjadi desidua
kapsularis.
3. Desidua di sisi / bagian uterus yang
abembrional menjadi desidua parietalis.
(c). Antara membran korion dengan membran
amnion terdapat rongga korion. Dengan
berlanjutnya kehamilan, rongga ini tertutup
akibat persatuan membran amnion dan membran
korion. Selaput janin selanjutnya disebut sebagai
membran korion-amnion Kavum uteri juga terisi
oleh konsepsi sehingga tertutup oleh persatuan
chorion laeve dengan desidua parietalis.
(d).Cairan Amnion
Rongga yang diliputi selaput janin disebut
sebagai Rongga Amnion. Di dalam ruangan ini
terdapat cairan amnion (likuor amnii). Asal
cairan amnion : diperkirakan terutama disekresi
oleh dinding selaput amnion / plasenta,
kemudian setelah sistem urinarius janin
terbentuk, urine janin yang diproduksi juga
dikeluarkan ke dalam rongga amnion.
Tabel 1. Perkembangan organ fetus sesui usia kehamilan ( Sinopsis
Obstetri,2008)
Umur
Kehamilan
Panjang
fetusPembentukan organ
4 minggu 7,5-10 mm Rudimental mata, telinga dan
hidung
8 minggu 2,5 cm Hidung, kuping, jari-jemari mulai
di bentuk. Kepala menekuk ke
dada.
12 minggu 9 cm Daun telinga lebih jelas, kelopak
mata melekat, leher mulai
terbentuk, alat kandungan luar
terbentuk namun belum
berdiferensiasi.
16 minggu 16-18 cm Genitalia eksterna terbentuk dan
dapat di kenal, kulit tipis dan warna
merah.
20 minggu 25 cm Kulit lebih tebal, rambut mulai
tumbuh di kepala dan rambut halus
(lanugo) tumbuh di kulit.
24 minggu 30-32 cm Kedua kelopak mata tumbuh alis
dan bulu mata serta kulit keriput.
Kepala besar. Bila lahir, dapat
bernapas tapi hanya beberapa jam
saja.
28 minggu 35 cm Kulit warna merah di tutupi verniks
kaseosa. Bila lahir, dapat bernapas,
menangis pelan dan lemah.
32 minggu 40-43 cm Kulit merah dan keriput. Bila lahir,
kelihatan seperti orang tua dan
kecil.
36 minggu 46 cm Muka berseri tidak keriput. Bayi
premature.
40 minggu 50-55 cm Bayi cukup bulan. Kulit licin,
verniks kaseosa banyak, rambut
kepala tumbuh baik, organ-organ
baik.
Tabel 2. Perkembangan Bentuk Janin
Gambar Keterangan
JANIN PADA BULAN KE-3
Pada akhir bulan ketiga, panjang tubuh
janin mencapai kira-kira 3 inci (7,62 cm) dan
berat badan kira-kira 1ons. Lengan, hasta dan
jari-jarinya, serta kedua kaki dan jemarinya
sudah ada, sedangkan kuku mulai terbentuk.
Demikian pula bagian luar telinga sudah ada
pada fase ini. Pangkal gigi pun mulai
terbentuk pada tulang rahang yang kecil, dan
Gambar Keterangan
organ-organ sex yang bagian dalam sudah
mulai tumbuh.
JANIN PADA BULAN KE-4
Pada fase ini, detak jantung janin sudah
dapat terdengar dengan menggunakan alat
khusus (dopller). Kepala yang bersambung
dengan bagian tubuh lainnya menjadi
bertambah besar pada bulan keempat, dan
panjang janin akan segera bertambah.
Pada akhir bulan keempat, panjang
tubuh janin akan mencapai kira-kira 7 inci
917,78 cm) dan berat badannya mencapai 4
ons. Ia sudah memiliki rambut, alis dan bulu
mata, serta mulai mengisap ibu jari tangannya.
JANIN PADA BULAN KE-5
Sepanjang bulan kelima, berat badan
janin berkisar pada 1/2 hingga 1 pon (0,24
hingga 0,45 kg) dan panjang tubuhnya antara
10 hingga 12 inci (25,4 hingga 30,5 cm).
Otot-ototnya sudah mulai berfungsi, sehingga
ia senantiasa bergerak. Biasanya pada bulan
kelima ini gerakan janin jelas dapat dirasakan
oleh ibunya.
Panjang tubuh janin berkisar antara 11
hingga 14 inci (27 hingga 35,5 cm) dan berat
Gambar Keterangan
JANIN PADA BULAN KE-6
badannya antara 1,5 hingga 2 pon (0,67
hingga 0,9). Kulitnya mengerut dan berwarna
kemerahan, serta dilapisi sejenis pelindung
yang disebut Vernix Caseosa.
JANIN PADA BULAN KE-7
Selama bulan ini janian terus tumbuh
dan bergerak. Apabila pada bulan ini janin
lahir maka masih dapat hidup, akan tetapi
harus dibantu dengan alat-alat pembantu dan
dampak lain dari kelairan janin pada bulan ini
adalah keadaanya masih lemah dan bayi
BBLR (Berat badan bayi lahir rendah),
sehingga harus di hangatkan kedalam
incubator agar suhu badan bayi bias mencapai
suhu yang normal.
JANIN PADA BULAN KE-8
Pada bulan ini janian sudah menjadi
lebih panjang dan lebih gemuk keadaannya.
Panjang tubuhnya mencapai 18 inci (45,7
sampai 5 pon atau 2,27 kg). Apabila janin
lahir pada fase ini, peluang untuk hidup lebih
besar, karena pertumbuhanya relative
sempurna.
Sepanjang bulan ini janin akan terus
tumbuh dan pada akhir bulan ini berat badan
Gambar Keterangan
JANIN PADA BULAN KE-9
janin umumnya berkisar antara 7 hingga 7,5
pon (3,18 hingga 3,40 kg) dan panjang
tubuhnya sekitar 20 inci 50 cm. Kulitnya
masih dilapisi cairan pelindung (liquor
Amnion). Posisi janin berubah sebagai
persiapan untuk lahir dan mulai turun
kebawah dengan kepala berada pada bagian
bawah dan janin sudah siap untuk dilahirkan.
(www.cakulobstetri.com).
d. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis pada ibu hamil
trimester I, II, III
System reproduksi dan payudara
1) Perubahan uterus
Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama dibawah
pengaruh estrogen dan progrsteron yang kadarnya meningkat.
Pembesran ini pada dasrnya disebabkan oleh hipertrofi otot polos
uterus, disamping itu, serabut-serabut kolagen yang adapun
menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga
uterus dapat mengikuti pertumbuhan janin. Bila ada kehamilan
ektopik, uterus akan membesar pula, karena pengaruh hormon-
hormon itu. Begitu pula endometrium menjadi desidua.
Berat uterus normal lebih kurang 30 gram, pada akhir
kehamilan (40 minggu) berat uterus ini menjadi 1000 gram, dengan
panjang lebih kurang 20 cm, dan dinding lebih kurang 2.5 cm.
Pada bulan-bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti buah
advokat, agak gepeng. Pada kehamilan 4 bulan uterus berbentuk
bulat. Selanjutnya, pada akhir kehamilan kembali seperti bentuk
semula, lonjong seperti telur. Hubungan antara besarnya uterus
dengan tuanya kehamilan sangat penting diketahui, antara lain
untuk membuat diagnosis apakah wanita tersebut hamil fisiologi,
atau hamil ganda, atau menderita penyakit seperti mola hidatidosa,
dan sebagainya.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dinding uterus terdiri
dari 3 lapisan otot. Lapisan otot longitudinal paling luar, lapisan
oto sirkuler paling luar, lapisan oto sirkuler paling dalam, dan
lapisan otot yang berbentuk oblik di antara kedua lapisan otot luar
dan dalam.ketika ada kehamilan ketiga lapisan ini tampak lebih
jelas.
Lapisan otot oblik berbentuk suatu anyaman seperti tikar,
memegang peranan penting pada persalinan disamping kedua
lapisan oto lainnya. Sinus-sinus pembuluh darah beraada diantara
anyaman otot oblik ini. Pospartum uterus berkontraksi dan pada
ketika ini sinus-sinus pembuluh darah yang terbuka terjepit,
sehingga perdarahan postpartum dapat dicegah.
Uterus pada wanita tidak hamil kira-kira sebesar telur ayam.
Pada kehamilan uterus tumbuh secara teratur, kecuali jika ada
gangguan pada kehamilan tersebut. Pada kehamilan 8 minggu
uterus membesar sebesar telur bebek, dan pada kehamilan 12
minggu kira-kira sebesar telur angsa. Pada saat ini fundus uteri
telah dapat diraba dari luar diatas simpisis. Pada pemeriksaan ini
wanita harus mengosongkan kandung kemihnya dahulu.
Pada minggu-minggu pertama ismus uteri mengadakan
hipertropi seperti korpus uteri. Hipertropi ismus pada triwulan
pertama membuat ismus menjadi panjang dan lebih lunak. Hal ini
dikenal dalam obstetri dengan tanda Hegar.
Pada kehamilan 16 minggu kavum uteri diisi oleh ruang
amnion yang berisi janin, dan ismus menjadi bagian korpus uteri.
Pada kehamilan 16 minggu besar uterus kira-kira sebesar kepala
bayi atau sebesar tinju orang dewasa. Dari luar fundus uteri kira-
kira terletak diantara setengah jarak pusat ke simpisis.
Pada kehamilan 20 minggu fundus uteri kira-kira terletak
dipinggir bawah pusat, sedangkan pada kehamilan 24 minggu
fundus uteri tepat berada dipinggir atas pusat.
Tanda Hegar
Pada kehamilan 28 minggu fundus uteri terletak kira-kira 3
jari diatas pusat atau sepertiga jarak antara pusat dan prosesus
xifoideus. Pada kehamilan 32 minggu fundus uteri terletak diantara
setengah jarak pusat dan prosesus xipoideus. Kehamilan 36 minggu
fundus uteri terletak kira-kira 1 jari dibawah prosesus xipoideus.
Dalam hal ini kepala bayi masih diatas pintu atas panggual.
Pemeriksaan tinggi fundus uteri dikaitkan dengan umur kehamilan
perlu pula dikaitkan dengan besarnya dan beratnya janin.
Dibawah ini ukuran tinggi fundus uteri dalam cm dikaitkan
dengan umur kehamilan dan berat bayi sewaktu dilahirkan.
Gambar 13. Tinggi fundus uteri dikaitkan dengan umur kehamilan
dan berat bayi sewaktu dilahirkan. Perhatikan kurve
bayi yang dilahirkan dengan berat badan 2500 g
Bila pertumbuhan janin normal maka tinggi fundus uteri pada
kehamilan 28 minggu sekurangnya 25 cm, pada 32 minggu 27 cm,
pada 36 minggu 30 cm. Pada kehamilan 40 minggu fundus uteri
turun kembali dan terletak kira-kira dibawah prosesus xipoideus.
Hal ini disebabkan oleh kepala janin yang pada primigravida turun
dan masuk kedalam rongga panggul.
Pada triwulan terakhir ismus lebih nyata menjadi bagian
korpus uteri, dan berkembang menjadi segmen bawah uterus. Pada
kehamilan tua karena kontraksi otot-otot bagian atas uterus,
segmen bawah uterus menjadi lebih lebar dan tipis, tampak batas
yang nyata antra bagian atas yang lebih tebal dan segmen bawah
yang lebih tipis. Batas itu dekaenal sebagai lingkaran retraksi
fisiologik. Dinding uterus diatas lingkaran ini jauh lebih tebal dari
pada dinding segmen bawah uterus.
Gambar 14. Perkembangan uterus pada beberapa tingkat
kehamilan; isinus uteri mulai menjadi bagian korpus
uteri
Gambar 15. Pembesaran uterus sampai kehamilan
Pada persalinan segmen bawah uterus lebih melebar lagi, dan
lingkaran retraksi fisiologik menjadi lebih tinggi. Postpartum pada
pemeriksaan dalam hanya dapat dikenal bagian atas uterus yang
berkontraksi baik, sedangkan bagian bawah uterus terba sebagai
bagian kantong yang lembek. Pada partus lama lingkaran retraksi
itu dapat naik tinggi sampai setengah pusat dan simfisis. .
(Sarwono Prawirohardjo 2007, hal.89-93)
Gambar 16. Kepala janin mulai masuk ruang panggul pada
kehamilan
Gambar 17. Ismus uteri berkembang menjadi segmen bawah uterus
2) Serviks uteri
Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan
karena hormon estrogen. Jika korpus uteri mengandung lebih
banyak jaringan otot, maka serviks lebih banyak mengandung
jaringan ikat, hanya 10% jaringan otot. Jaringan ikat pada serviks
ini banyak mengandung kolagen. Akibat kadar estrogen menigkat
dan dengan adanya hipervaskularisasi maka konsistensi serviks
menjadi lunak.
Serviks yang terdiri terutama atas jaringan ikat dan hanya
sedikit mengandung jaringan otot tidak mempunyai fungsi sebagai
sfingter. Pada partus serviks membuka saja mengikuti tarikan-
tarikan korpus uteri keatas dan rekanan bagian bawah janin
kebawah. Sesudah partus dapat pula dinyatakan bahwa serviks itu
berlipat-lipat dan tidak menutup seperti ditemukan pada sfingter.
Pada multipara dengan porsio yang bundar, porsio tersebut
mengalami cedera berupa lecet dan robekan, sehingga pospartum
tampak adanya porsio yang terbelah dua dan menganga. Hal ini
lebih jelas pada pemeriksaan postnatal, 6 minggu postpartum.
Perubahan-perubahan pada serviks perlu diketahui sedini mungkin
pada kehamilan, akan tetapi yang memeiksa hendaknya hati-hati
dan tidak dibenarkan melaksanakan secara kasar sehingga dapat
mengganggu kehamilan.
Kelenjar-kelenjar diserviks akan berfungsi lebih dan akan
mengeluarkan sekresi lebih banyak. Kadang-kadang wanita yang
sedang hamil mengeluh mengeluarkan cairan pervaginam lebih
banyak. Keadaan ini sampai batas tertentu masih merupakan
keadaan yang fisiologik. (Sarwono Prawirohardjo 2007, hal.94).
Dalam persiapan persalinan, estrogen dan hormon plasenta
relaksin membuat serviks lebih lunak. Sumbat mucus yang disebut
operculum terbentuk dari sekresi kelenjar serviks pada kehamilan
minggu ke-8. Sumbat mucus tetap berada dalam serviks sampai
persalinan dimulai, dan pada saat itu, dilatasi dilatasi serviks
menyebabkan sumbt tersebut terlepas. Terlihat mucus serviks
merupakan salah satu tanda dini persalinan (Harry
Oxon,dkk.2010).
3) Segmen Bawah Uterus
Segmen bawah uterus berkembang dari bagian atas kanalis
servikalis setinggi ostium interna bersama-sama isthmus uteri.
Segmen bawah lebih tipis dari pada segmen atas dan menjadi lunak
serta berdilatasi selama berminggu-minggu terakhir kehamilan
sehingga memungkinkan segmen tersebut menampung presenting
part janin. Serviks bagian bawah baru menipis dan menegang
setelah persalinan terjadi (Harry Oxon,dkk.2010).
4) Kontraksi Braxton – Hicks
Merupakan kontraksi tak teratur rahim dan terjadi tanpa rasa
nyeri di sepanjang kehamilan. Kontraksi ini barangkalimembantu
sirkulasi darah dalam plasenta (Harry Oxon.dkk.2010).
5) Vagina dan Vulva
Vagina dan serviks akibat hormone esterogen mengalami
perubahan pula. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina
dan vulva tampak lebih merah, agak kebiruan (livide)
Disebut tanda Chadwick. Vagina: Membiru karena pelebaran
pembuluh darah, PH 3.5-6 merupakan akibat meningkatnya
produksi asam laktat karena kerja lactobaci Acidophilus,
Keputihan, Selaput lender vagina mengalami edematous,
Hypertrophy, lebih sensitif meningkat seksual terutama triwulan III
(Prawirohardjo, 2007).
Pada awal kehamilan, vagina dan seriks memiliki warna
merah yang hampir biru (normalnya, bagian ini pada wanita yang
tidak hamil adalah merah muda). Warna kebiruan ini disebabkan
oleh dilatasi vena yang terjadi akibat kerja hormon progesteron
(Harry Oxon,dkk.2010).
Thrus merupakan infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan
jamur Candida Albicans secara berlebihan. Kehamilan dengan
kadar esterogen dan glukosa yang tinggi dalam sirkulasi darah
merupakan kondisi yang mendukung pertumbuhan candida dan
peningkatan pertumbuhan jamur ini menyebabkan iritasi lokal,
produksi sedikit secret yang berwarna seperti keju, timbulnya
bercak merah yang kadang-kadang terlihat pada dinding vagina
serta keluhan priritis hebat (Harry Oxon,dkk.2010).
6) Ovarium
Pada permulaan kehamilan masih didapat korpus luteum
graviditas samai terbentuknya plasenta pada kira-kira kehamilan 16
minggu. Korpus luteum graviditas berdiameter kira-kira 3 cm. Lalu
ia mengecil setelah plasenta terbentuk. Ditemukan pada awal
ovulasi hormon relaxing, suatu immunoreaktive inhibin dalam
sirkulasi maternal. Relaxin mempunyai pengaruh menenangkan
hingga pertumbuhan janin menjadi baik hingga aterm.
7) Mammae
Mammae akan membesar tegang akibat hormon
somatomammotropin, estrogen dan progesteron akan tetapi belum
mengeluarkan air susu. Pada kehamilan akan terbentuk lemak
sehingga mammae menjadi lebih besar. Apabila mammae akan
membesar, lebih tegang dan tampak lebih hitam seperti seluruh
areola mammae karena hiperpigmentasi. Pada kehamilan 12
minggu keatas dari putting susu dapat keluar cairan berwarna putih
agak jernih disebut colostrums.
Perubahan pada payudara yang membawa kepada fungsi
laktasi disebabkan oleh peningkatan kadar esterogen,
progesterone, laktogen plasental, dan prolaktin. Stimulasi
hormonal ini menimbulkan proliferasi jaringan, dilatasi pembuluh
darah dan perubahan sekretorik pada payudara, peningkatan
sensitivitas dan rasa geli mungkin dialami, khususnya oleh
primigravida pada kehamilan minggu ke-4 minggu, cairan yang
jernih ditemukan dalam payudara pada usia kehamilan 4 minggu
dan colostrum dapat diperah keluar pada usia kehamilan 16 minggu
(Harry Oxon,dkk 2010).
Payudara terus tumbuh disepanjang kehamilan dan ukuran
serta beratnya meningkat hingga mencapai
500 gram untuk masing-masing payudara. Areola menjadi
lebih gelap dan dikelilingi oleh kelenjar-kelenjar sebasea yang
menonjol (tuberkel Montgomery), kelenjar ini terlihat pada
kehamilan sekitar 12 minggu (Harry,Oxon .dkk 2010).
e. Tanda dan gejala kehamilan (diagnosa kehamilan) :
Tabel 3. Tanda dan gejala kehamilan
Minggu 0 4 8 12 16 20 24 26 32 36 40
Kehamilan Possible
- Tidak datang haid
- Payudara terasa geli
- Morning sickness
- Pembesaran payudara
- Sering buang air kecil
- Pigmentasi putting
- Kolostrum dalam payudara
- Quickening
Kehamilan Probable
- Tes kehamilan positif
- Uterus dapat diraba lewat
perut
- Kontraksi Braxton Hicks
Kehamilan Positif
- Denyut jantung janin
terdengar (auskultasi)
- Gerakan jantung janin
teraba oleh pemeriksa
- Bagian-bagian janin teraba
- Hasil pemeriksaan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
radiologi yang
membuktikan kehamilan
- Hasil pemeriksaan USG
yang membuktikan
kehamilan
√ √ √ √ √ √ √ √
1) Tanda Tidak Pasti Kehamilan
Subyektif
a) Amenorhoe
Berhentinya menstruasi pada seorang wanita yang sebelumnya
telah mengalami menstruasi sangat mendukung tenda
kehamilan. Oleh karena itu wanita harus mengetahui hari
pertama haid yang terakhir (HPHT) untuk dapat menentukan
umur kehamilan dan tanggal tafsiran persalinan (HTP). Apabila
HPHT dapat dipastikan maka dengan menggunakan rumus
Neegle, HTP juga dapat ditentikan. Cara menghitung dengan
rumus Neegle adalah sbb, tanggal HPHT ditambahkan dengan
7 dan bulannya dikurang 3.
Walaupun amenorhoe merupakan tanda penting untuk
mendiagnosa suatu kehamilan, tetapi kehamilan dapat juga
terjadi tanpa didahului dengan menstruasi, seperti pada :
(1) Seorang gadis yang menikah dini atau melakukan
hubungan seksual sebelum menarche. Kemungkinan
konsepsi/fertilisasi terjadi waktu ovulasi pertama kali.
(2) Ibu menyusui yang biasanya tidak menstruasi dalam masa
laktasi.
(3) Kadang-kadang terjadi pada wanita yang merasa yakin
telah menopause.
Amenorhoe dapat juga terjadi pada wanita yang tidak hamil,
hal ini dapat disebabkan oleh :
(4) Anovulasi (akibat dan adanya gangguan emosi, perubahan
lingkungan dan penyakit kronis)
(5) Pemakaian alat kontrasepsi hormonal.
b) Mual dengan atau tanpa muntah
Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan
menghilang pada akhir triwulan pertama. Oleh karena sering
terjadi pada pagi hari disebut dengan “morning sickness” atau
sakit pagi.
Mual (emesis) dan muntah (vomiting) yang normal pada
kehamilan biasanya tidak menimbulkan gangguan pada
metabolisme tubuh. Bila mual dan muntah berlebihan, terlalu
sering sehingga mengakibatkan gangguan pada metabolisme
tubuh, hal ini disebut sebagai hiperemesis
c) Ngidam
Ibu hamil sering menginginkan makan makanan dan atau
minuman tertentu, terutama pada bulan-bulan pertama
kehamilannya.
d) Sering kencing
Biasanya terjadi pada triwulan pertama yang disebabkan oleh
penekanan kandung kencing oleh pembesaran uterus. Gejala ini
akan berkurang sampai hilang pada triwulan kedua dan muncul
kembali pada akhir kehamilan yang disebabkan penekanan
kandung kencing oleh penurunan bagian terendah janin (kepala
atau bokong)
e) Konstipasi atau obstipasi
Ini disebabkan karena menurunnya tonus otot khusus oleh
pengaruh hormone steroid.
Objektif
a. Sinkope/pingsan
Terjadi oleh karena peningkatan jumlah volume darah
pencairan darah yang disebut sebagai hidremia.
b. Payudara tegang
Mamma akan membesar dan tegang akibat hormone
somatomammotropin, estrogen, dan progesteron.
Estrogen menimbulkan hipertrofi system caluran sedangkan
progesteron menambah ses-sel asinus pada mamma.
Somatomammotropin juga mempengaruhi pertumbuhan sesl-
sel asinus dan menimbulkan perubahan-perubahan dalam sel-
sel, sehingga terjadi pembuatan kasein, laktalbumin, dan
laktoglobulin, dimana tujuannya adalah untuk mempersiapkan
mamma untuk laktasi.
c. Pigmentasi kulit
Terjadi penumpukan melanin pada kulit dibagian tubuh
tertentu terutama dibagian pipi dan dahi yang disebut dengan
cloasma gravidarum.
Garis middle abdomen juga mengalami perubahan warna
menjadi lebih gelap yang disebut dengan linea nigra.
d. Epulis
Sering terjadi pada triwulan pertama yang disertai
pembengkakan dan perdarahan gusi. Pada keadaan wanita
hamil yang kekurangan vitamin C juga dapat terjadi
perdarahan pada gusi.
e. Varices
Sebagai pengaruh hormone, pelebaran pembulun darah juga
sering terjadi.
f. Rahim membesar, sesuai dengan tuanya kehamilan
Setelah 12 minggu kehamilan, uterus biasanya dapat diraba
melalui dinding abdomen, tepat diatas symfisis sebagai sebuah
tumor/massa. Kemudian uterus akan bertambah besar seiring
dengan tuanya umur kehamilan. Pada dasarnya pembesaran ini
disebabkan oleh hipertrofi otot polos uterus, disamping itu
serabut-serabut kolagen yang adapun menjadi higroskopik
akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga uterus dapat
mengikuti pertumbuhan janin. Bila ada kehamilan ektopik,
uterus tetap membesar karena pengaruh hormone tersebut
begitupula dengan endometrium yang menjadi desidua.
g. Perubahan pada organ pelvic.
Terjadinya peningkatan suplay darah keorgan pelvic,, dan
pengaruh hormon-hormon steroid reproduksi menyebabkan
adanya perubahan pada organ pelvic, seperti :
1) Tanda Chadwick
Vagina dan vula mengalamipeningkatan pembuluh darah
karena pangaruh estrogen sihingga nampak makin merah
dan kebiru-biruan.
2) Tanda Piskascek
Pertumbuhan rahim ternyata tidak sama kesemua arah,
terjadi pertumbuhan yang cepat didaerah implantasi
plasenta, sehingga rahim bentuknya tidak sama.
3) Kontraksi Braxton Hicks
Perimbangan hormone estrogen dan progesteron
mengakibatkan perubahan konsentrasi sehingga
progesteron mengalami penurunan dan menimbulkan
kontraksi rahim. Kontraksi Braxton Hicks tidak dirasakan
sakit dan terjadi bersamaan diseluruh rahim, kontraksi ini
akan berkelanjutan menjadi kontraksi untuk persalinan.
4) Tanda Goodells
Seviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan
karena hormone estrogen. Jika korpus uteri mengandung
lebih banyak jaringan otot, maka serviks uteri lebih
bangyak mengandung jaringan ikat,hanya 10% jaringan
otot. Jaringan ikat pada serviks ini banyak mengandung
kolagen. Akibat kadar estrogen meningkat, dan dengan
adanya hipervaskularisasi, maka konsistensi serviks
menjadi lunak.
5) Tanda Hegar
Pada minggu-minggu pertama kehamilan, ishmus uteri
mengadakan hipertrofi seperti pada korpus uteri. Hipertrofi
ishmus pada triwulan pertama membuat ishmus menjadi
panjang dan lunak.
6) Teraba Ballottement
Jika uterus diketuk, maka akan terjadi pantulan pada
tempat impalntasinya.
h. Pemeriksaan Tes biologis kehamilan positif
Pada kehamilan ditemukan peningkatan kadar HCG dalam
urine. Sebagian kemungkinan postif palsu.
2) Tanda-tanda mungkin kehamilan
Reaksi kehamilan positif : Dasar dari tes kehamilan adalah
pemeriksaan hormon Chorinik gonadotropin sub unit beta (beta
heg) dalam urine. Jika terjadi kehamilan terjadi reaksi antigen-
antibodi dengan beta heg, sebagai anti gen beta heg dapat di
deteksi dalam darah dan urine mulai enam hari setelah implantasi
(penanaman embrio di dalam rongga rahim).
Cara khas yang dipakai untuk menentukan adanya Human
Chorionic Gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing
pertama pagi hari. Dengan tes kehamilan tertentu air kencing pagi
hari ini dapat membantu membuat diagnosis kehamilan sedini-
dininya (Yuni kusmiati, 2008).
Suhu basal yang sesudah ovulasi tetap tinggi terus antara
37,2°C sampai 37, 8°C adalah salah satu tanda akan adanya
kehamilan. Gejala ini sering dipakai dalam pemeriksaan
kemandulan (Winkjosastro dalam Prawirohardjo, 2008).
a. Tanda Hegar yaitu segmen bawah rahim melunak, tanda ini
terdapat pada dua pertiga kasus dan biasanya muncul pada
minggu ke enam dan sepuluh serta terlihat lebih awal pada
perempuan yang hamilnya berulang. Pada pemeriksaan
bimanual, segmen bawah uterus terasa lebih lembek. Tanda ini
sulit diketahui pada pasien gemuk / dinding abdomen tegang.
b. Tanda Chadwick. Biasanya muncul pada minggu ke delapan
dan terlihat lebih jelas pada wanita yang hamil berulang. Tanda
ini merupakan perubahan warna. Warna pada vagina dan vulva
menjadi lebih merah dan agak kebiruan timbul karena adanya
vaskularisasi pada daerah tersebut.
c. Tanda Goodell. Biasanya muncul pada minggu ke enam dan
terlihat lebih awal pada wanita yang hamilnya berulang. Tanda
ini berupa serviks menjadi lebih lunak dan jika dilakukan
pemeriksaan dengan speculum, serviks terlihat berwarna lebih
kelabu kehitaman.
d. Tanda Piscaseck. Uterus membesar secara simetris menjauhi
garis tengah tubuh (setengah bagian terasa lebih keras dari yang
lainnya) bagian yang lebih besar tersebut terdapat pada tempat
melekatnya (implantasi) tempat kehamilan. Sejalan dengan
bertambahnya usia kehamilan, pembesaran uterus menjadi
semakin simetris. Tanda piscaseek, dimana uterus membesar ke
salah satu jurusan hingga menonjol ke jurusan pembesaran
tersebut (Winkjosastro dalam Prawirohardjo, 2008).
e. Tanda Braxton Hicks. Yaitu bila uterus dirangsang mudah
berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa hamil.
Pada keadaan uterus yang membesar tetapi tidak ada
kehamilan misalnya mioma uteri, tanda ini tidak ditemukan.
3) Tanda pasti kehamilan
Tanda pasti kehamilan dapat ditentukan dengan jalan :
a. Kerja jantung janin
Denyut jantung janin, dengan stetoskop pada usia kehamilan 17
– 19 minggu, dengan Doppler pada usia kehamilan 10 minggu,
dengan ecokardiografi dapat mendeteksi sejak 48 hari setelah
HPHT terakhir.
b. Persepsi gerakan janin
Gerakan janin terdeteksi oleh pemeriksa setelah usia kehamilan
sekitar 20 minggu.
c. Deteksi kehamilan secara ultrasonografik
Setelah 6 minggu, denyut jantung sudah terdeteksi. Kantung
gestasi mulai dapat dilihat sejak usia kehamilan 4 – 5 minggu
sejak menstruasi terakhir, dan pada minggu ke-8 , usia gestasi
dapat diperkirakan secara cukup akurat.
(Yuni kusmiati,2008).
f. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan
1) Faktor fisik : status kesehatan, status gizi, gaya hidup
Status kesehatan, kondisi kesehatan sangat penting dalam
kehamilan, baik kondisi kesehatan sebelum atau selama kehamilan.
Kehamilan dapat lebih berbahaya lagi jika wanita tersebut sedang
sakit. Serangan penyakit sebelum dan selama kehamilan yang
dapat membahayakan janin terbagi atas dua kategori utama, yaitu
penyakit umum seperti diabetes, anemia berat, penyakit ginjal
kronik, dan penyakit menular antara lain rubella, dan sifilis.
Status gizi. Selama kehamilan ibu merupakan sumber nutrisi
bagi bayi yang dikandungnya. Apa yang ibu makan akan
mempengaruhi kondisi bayi. Apabila wanita hamil memiliki status
gizi kurang selama kehamilannya maka ia berisiko memiliki bayi
dengan kondisi kesehatan yang buruk. Dan wanita dengan status
gizi baik akan melahirkan bayi yang sehat.
Gaya hidup seperti perokok, mengkonsumsi obat-obatan,
alkohol, adalah hal yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayinya.
Semua benda tersebut dapat terserap dalam darah bayi melalui
system sirkulasi plasenta selama kehamilan.
Terpapar zat kimia berbahaya. Diketahui bahwa beberapa zat
cukup berbahaya bagi wanita hamil. Zat tersebut sering berkaitan
dengan kerusakan pada janin. Golongan zat tersebut antara lain zat
fisik misalnya radiasi, fibrasi, pana, dan kebisingan. Zat kimia
seperti toluene (bahan perekat) dan timah. Untuk itu ibu hamil
perlu melindungi bayinya dari zat berbahaya dengan menghindari
lingkungan kerja yang terpapar polusi ataupun tidak menggunakan
bahan kimiawi berbahaya di rumah.
Hamil diluar nikah dan kehamilan yang tidak diharapkan.
Pada kehamilan tidak diharapkan dengan berbagai alasan dapat
menimbulkan berbagai masalah klinis yang dapat memberatkan
kehamilan. Misalnya “morning sickness” berlebihan yang dapat
menyebabkan hiperemesis gravidarum yang memerlukan
perawatan khusus hingga melahirkan bayi BBLR. Selain itu, usaha
untuk menggugurkan kandungannya akan membahayakan diri dan
dapat menyebabkan infeksi, cacat yang akhirnya justru akan
menjadi beban keluarga.
2) Faktor psikologi, stressor internal, eksternal, substance abuse,
partner abuse
a) Stressor internal dan external
Faktor psikologis yang berpengaruh dalam kehamilan dapat
berasal dari dalam diri ibu hamil (internal) dan dapat juga
berasal dari faktor luar diri ibu hamil. Faktor psikologis yang
berasal dari dalam diri ibu dapat berupa latar belakang
kepribadian ibu dan pengaruh perubahan hormonal yang terjadi
selama kehamilan. Sedangkan faktor psikologis yang berasal
dari luar diri ibu dapat berupa pengalaman ibu dan gangguan
emosi baik berupa stress atau depresi yang dialami pada
trimester pertama kehamilan akan berpengaruh pada janin.
b) Dukungan keluarga
Ibu merupakan salah satu anggota keluarga yang sangat
berpengaruh sehingga perubahan apapun yang terjadi pada ibu
akan mempengaruhi keadaan keluarga. Oleh sebab itu ibu
memerlukan dukungan keluarga agar kehamilan dapat berjalan
dengan lancer, antara lain : memberkan dukungan pada ibu
untuk menerima kehamilannya, memberikan dukungan pada
ibu untuk menerima dan mempersiapkan peran sebagai ibu,
memberikan dukungan pada ibu untuk menghilangkan ras takut
dan cemas terhadap persalinan, member dukungan pada ibu
untuk menciptakan ikatan yang kuat antara ibu dan anak yang
dikandungnya melalui perawatan kehamilan dan persalinan
yang baik, menyiapkan keluarga lainnya untuk menerima
kehadiran anggota keluarga baru.
c) Dukungan suami
Orang yang paling penting bagi wanita hamil adalah suaminya.
Banyak bukti yang ditunjukkan bahwa wanita yang
diperhatikan dan dikasihi oleh pasangannya selama kehamilan
akan menunjukkan lebih sedikit gejala emosi dan fisik, lebih
mudah melakukan penyesuaian diri selama kehamilan dan
sedikit resiko komplikasi persalinan. Hal ini diyakini karena
ada dua kebutuhan utama yang ditunjukkan wanita hamil
selama hamil yaitu menerima tanda-tanda bahwa ia dicintai dan
dihargai serta kebutuhan akan penerimaan pasangannya
terhadap anaknya.
3) Faktor lingkungan, sosial budaya, fasilitas kesehatan, ekonomi
a) Faktor lingkungan
Faktor lingkungan yang dimaksud antara lain karena
kemiskinan, kurangnya pelayanan medik, kurang pendidikan
dan pengetahuan, termasuk pengaruh sosial budaya berupa
kepercayaan yang merugikan atau membahayakan. Dalam hal
ini bidan perlu melibatkan keluarga dan masyarakat agar
memperhatikan kebutuhan dan keselamatan ibu hamil.
b) Kebiasaan adat istiadat
Bidan harus dapat mengkaji apakah ibu hamil menganut atau
mempunyai kepercayaan atau adat kebiasaan tabu setempat
yang berpengaruh terhaadap kehamilan. Kemudian menilai
apakah hal tersebut bermanfaat, netral (tidak berpengaruh
terhadap keamanan atau kesehatan), tidak jelas (efek tidak
diketahui/tidak dipahami) atau membahayakan. Terutama bila
faktor budaya tersebut dapat menghambat pemberian asuhan
yang optimal bagi ibu hamil. Bidan harus mampu mencari jalan
untuk menolongnya atau meyakinkan ibu untuk merubah
kebiasaan-kebiasaan dengan member penjelasan yang benar.
c) Fasilitas kesehatan
Hal ini berhubungan dengan tempat ibu mendapatkan
pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya
sampai ibu dapat melahirkan dengan aman. Maka dari itu harus
tersedia fasilitas kesehatan yang memadai dengan jarak yang
mudah terjangkau akan member kemudahan bagi ibu hamil
untuk sering memeriksakan kehamilannya dan untuk
mendapatkan penanganan dalam keadaan darurat.
d) Sosial ekonomi
Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi kehamilan ibu karena
berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ibu
selama kehamilan antara lain makanan sehat, bahan persiapan
kelahiran, obat-obatan, tenaga kesehatan, dan transportasi/
sarana angkutan.
Kebutuhan fisik ibu hamil
a. Oksigen
Kebutuhan oksigen selama kehamilan meningkat sebagai repon
tubuh terhadap akcelerasi metabolisme rate perlu untuk menambah
masa jaringan pada payudara, hasil konsepsi, dan masa uterus, dll.
b. Nutrisi
Diharapkan wanita hamil dapat meningkatkan asupan nutrisinya
dua kali lipat sebelum hamil, karena ibu hamil harus membagi dua
makanan yang dikonsumsinya.
c. Personal hygiene
Personal hygiene ini berkaitan dengan perubahan system pada
tubuh ibu hamil karena selama hamil PH vagina menjadi asam
akibatnya vagina mudah terkena infeksi, selain itu wanita juga
mengeluarkan keputihan. Oleh sebab itu wanita hamil diharapkan
dapat menjaga kebersihan diri dan pakaiannya.
d. Pakaian
Pakaian yang dikenakan ibu hamil harus nyaman tanpa sabuk,
harus longgar, dan tidak terlalu ketat. Pakaian wanita hamil harus
ringan dan menarik karena wanita hamil tubuhnya akan tambah
menjadi besar. Sepatu pun harus terasa pas, tidak bertumit tinggi
dan tidak berujung lancip. Desain BH harus disesuaikan agar dapat
menyangga payudara yang tambah menjadi besar pada kehamilan
dan memudahkan ibu ketika akan menyusui. Kemudian korset
yang khusus untuk ibu hamil dapat membantu menekan perut
bawah yang melorot dan mengurangi nyeri punggung.
e. Eliminasi
Berkaitan dengan adaptasi gastrointestinal sehingga menurunkan
tonus dan motility lambung dan usus terjadi reabsorbsi zat
makanan peristaltic usus lebih lambat sehingga menyebabkan
obstipasi. Selain itu penekanan kandung kencing karena pengaruh
hormon estrogen dan progesteron sehingga menyababkan ibu
hamil sering kencing.
f. Seksual
Meningkatnya vaskularisasi pada vagina dan visera pelvis dapat
mengakibatkan meningkatnya sensitifitas seksual sehingga
meningkatkan hubungan intercourse.
g. Istirahat/tidur
Berhubungan dengan kebutuhan kalori pada masa kehamilan,
mandi air hangat sebelum tidur, tidur dalam posisi miring ke kiri,
letakkan beberapa bantal untuk menyangga, pada ibu hamil
sebaiknya banyak menggunakan waktu luangnya untuk banyak
istirahat atau tidur walau bukan tidur betulan hanya baringkan
badan untuk memperbaiki sirkulasi darah, jangan bekerja terlalu
capek dan berlebihan.
h. Mobilisasi dan body mekanik
Pada ibu selama hamil terjadi pembesaran perut sehingga pusat
gravitasi berubah dan postur tubuh berubah. Terjadi perubahan
postur tubuh menjadi lordosis fisiologis. Penekanan pada ligament
dan pelvic, cara baring, duduk, berjalan, dan berdiri dihindari
jangan sampai mengakibatkan injuri karena jatuh.
i. Exercise
Pada wanita hamil terjadi peregangan otot-otot, perlunakan
ligament-ligament, dan perlonggaran persendian sehingga area
yang paling bawah terpengaruh adalah tulang belakang, otot-otot
abdominal, dan otot dasar panggul. Disini ibu hamil diharapkan
dapat mengikuti senam hamil yang berfungsi untuk menjaga
kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam proses
mekanisme persalinan.
Kebutuhan psikologis ibu hamil trimester I, II, dan III
a. Support keluarga dan support dari tenaga kesehatan
1) Dukungan suami
Dukungan suami yang diharapkan istri antara lain : suami
sangat mendambakan bayi dalam kandungan istri, suami
senang mendapat keturunan, suami menunjukkan kebahagiaan
pada kehamilan ini, suami memperhatikan kesehatan istri yakni
menanyakan keadaan istri/janin yang dikandung, suami tidak
menyakiti istri, suami menghibur/menenangkan ketika ada
masalah yang dihadapi istri, suami menasehati istri agar tidak
terlalu capek bekerja, suami membantu tugas istri, suami
berdoa untuk kesehatan istrinya dan keselamatannya, suami
menunggu ketika istrinya melahirkan, suami menunggu ketika
istrinya dioperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita
yang tidak mengalami depresi pada paska persalinan jika tidak
mengalami kepuasan dalam perkawinannya. Sebaliknya,
wanita yang mengalami depresi selama hamil dapat membaik
pasca persalinan apabila dalam perkawinan ia mengalami
kepuasan.
2) Dukungan keluarga
Ayah dan ibu kandung maupun mertua sangat mendukung
kehamilan ini, ayah dan ibu kandung serta mertua sering
berkunjung dalam periode itu, seluruh keluarga berdoa untuk
keselamatan ibu dan bayi walaupun ayah, ibu, dan mertua ada
di daerah lain, sangat didambakan dukungan melalui telepon,
surat ataupun doa dari jauh.
3) Dukungan lingkungan
Diperolehnya dari ibu-ibu pengajian/perkumpulan/kegiatan
yang berhubungan dengan keagamaan/sosial dalam bentuk doa
untuk kesehatan ibu hamil dan bayinya, membicarakan dan
menasehati tentang pengalaman hamil dan melahirkan, adanya
diantara mereka yang mau mengantarkan ibu hamil untuk
periksa, menunggu ketika melahirkan, mereka dapat menjadi
seperti saudara bagi ibu hamil.
Trimester I
Suami dapat memberikan dukungan dengan mengerti dan
memahami setiap perubahan yang terjadi pada istrinya,
memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang dan berusaha
untuk meringankan beban kerja istri. Sebagai tenaga kesehatan
dapat memberikan dukungan dengan menjelaskan dan meyakinkan
pada ibu bahwa apa yang terjadi padanya adalah sesuatu yang
sangat normal, sebagian besar wanita merasakan hal yang serupa
pada trimester pertama. Membantu ibu untuk memahami setiap
perubahan yang terjadi padanya baik fisik maupun psikologis.
Yakinkan bahwa kebanyakan ibu akan mulai merasa lebih baik dan
berbahagia pada trimester kedua.
Trimester II
Dukungan yang diberikan oleh suami dan keluarga pada trimester
ini adalah bersama-sama dengan ibu untuk merencanakan
persalinan, ikut mewaspadai adanya komplikasi dan tanda-tanda
bahaya, dan bersama-sama mempersiapkan suatu rencana apabila
terjadi komplikasi. Karena ibu merasa lebih sehat dan
menginginkan kehamilannya, petugas kesehatan dapat memberikan
dukungan dengan mengajarkan kepada ibu tentang nutrisi,
pertumbuhan bayi, tanda-tanda bahaya, rencana kelahiran, dan
rencana kegawatdaruratan, karena saat ini merupakan waktu dan
kesempatan yang paling tepat.
Trimester III
Keluarga dan suami dapat memberikan dukungan dengan
memberikan dukungan dengan memberikan keterangan tentang
persalinan yang akan ibu lalui dan itu hanya masalah waktu saja.
Tetap memberikan perhatian dan semangat pada ibu selama
menunggu persalinannya. Bersama-sama mematangkan persiapan
persalinan dengan tetap mewaspadai komplikasi yang mungkin
terjadi. Sebagai seorang petugas kesehatan dapat memberikan
dukungan dengan memberikan penjelasan bahwa yang dirasakan
oleh ibu adalah normal. Kebanyakan ibu memiliki perasaan dan
kekhawatiran yang serupa pada trimester ini. Menenangkan ibu
dengan mengatakan bahwa bayinya saat ini merasa senang berada
dalam perut ibu dan tubuh ibu secara alamiah akan menyiapkan
kelahiran bayi.
b. Rasa aman dan nyaman selama kehamilan
Selama kehamilan mungkin ibu mengeluhkan bahwa ia mengalami
berbagai ketidaknyamanan, yang walaupun bersifat umum dan
tidak mengancam keselamatan jiwa, tapi itu tetap saja dapat
menyulitkan ibu. Bidan sebagai tenaga kesehatan harus
mendengarkan ibu, membicarakan tentang berbagai macam
keluhan dan membantunya mencari cara untuk mengatasinya
sehingga ibu dapat menikmati kehamilannya dengan aman dan
nyaman. Keluarga dapat memberikan perhatian dan dukungan
sehingga ibu merasa aman dan tidak sendiri dalam menghadapi
kehamilannya.
Persiapan menjadi orang tua dan persiapan sibling
a. Persiapan menjadi orang tua
1) Bersama-sama dengan pasangan selama kehamilan dan saat
melahirkan untuk saling berbagi pengalaman yang unik tentang
setiap kejadian yang dialami oleh masing-masing.
2) Berdiskusi dengan pasangan tentang apa yang akan dilakukan
untuk menghadapi status sebagai orang tua seperti akomodasi
bagi calon bayi, menyiapkan tambahan penghasilan, bagaimana
apabila nanti bila tiba saat ibu harus kembali bekerja, apa saja
yang diperlukan untuk merawat bayi. Hubungan ini dapat
memperkokoh perasaan diantara pasangan, bahwa memiliki
bayi berarti saling membagi tugas. Yang tidak kalah penting
adalah persiapan psikologis dalam menghadapi perubahan
status dari hanya hidup berdua dengan pasangan, sekarang
datang anggota baru yang memiliki berbagai keunikan.
b. Persiapan sibling
Jika memutuskan untuk mempunyai bayi lagi, kekuatan dari ikatan
batin antara ibu dan anak pertama akan terbukti sangat penting.
Anak-anak yang lebih tua, yang telah membentuk semacam
independensi dan ikatan batin yang kuat biasanya tidak begitu
merasa terancam oleh kedatangan bayi baru daripada anak-anak
yang belum mencapai kekuatan ikatan batin yang sama. Untuk
mempersiapkan sang kakak dalam menerima kehadiran adiknya
dapat dilakukan dengan : ceritakan mengenai calon adik yang
disesuaikan dengan usia dan kemampuannya untuk memahami, tapi
tidak pada usia kehamilan muda karena anak akan cepat bosan,
jangan sampai dia mengetahui tentang calon adiknya dari orang
lain, biarkan dia merasakan gerakan dan bunyi jantung adiknya,
gunakan gambar-gambar mengenai cara perawatan bayi, sediakan
buku yang menjelaskan dengan mudah tentang kehamilan,
persalinan, dan perawatan bayi, menunjukkan foto anak semasa
bayi, sehingga dapat membantunya membayangkan kecilnya tubuh
adiknya, mengajaknya menengok teman yang mempunyai bayi,
sehingga anak dapat menyentuhnya dan melihat bagaimana bayi
disusui, diganti pakaiannya, dan dimandikan.
Asuhan kehamilan kunjungan awal
a. Tujuan kunjungan
Mengumpulkan informasi mengenai ibu hamil yang dapat
membantu bidan dalam membina hubungan yang baik dan rasa
saling percaya antara ibu dan bidan, mendeteksi komplikasi yang
mungkin terjadi, menggunakan data untuk menghitung usia
kehamilan, dan tafsiran tanggal persalinan, merencanakan asuhan
khusus yang dibutuhkan ibu. Tujuannya adalah memfasilitasi hasil
yang sehat dan positif bagi ibu dan bayi, menegakkan hubungan
saling percaya, mendeteksi komplikasi-komplikasi kehamilan,
mempersiapkan kelahiran, memberikan pendidikan.
b. Pengkajian data subyektif ibu hamil
1) Informasi biodata, identitas ibu dan suami (nama, umur, suku,
agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat)
2) Riwayat kehamilan sekarang (HPHT, siklus menstruasi,
gerakan janin, masalah dan tanda-tanda bahaya, keluhan-
keluhan lazim pada kehamilan, penggunaan obat-obatan
termasuk jamu, kakhawatiran yang dirasakan).
3) Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu (jumlah
kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan yang aterm,
persalinan yang prematur, keguguran atau kegagalan
kehamilan, persalinan dengan tindakan, riwayat perdarahan
pada kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, berat bayi
sebelumnya, masalah-masalah lain yang dialami).
4) Riwayat kesehatan/penyakit yang diderita sekarang dan dulu
(masalah kardiovaskuler, hipertensi, diabetes, malaria, PMS,
HIV/AIDS, imunisasi TT)
5) Riwayat sosial ekonomi (status perkawinan, respon ibu dan
keluarga terhadap kehamilan ibu, riwayat KB, dukungan
keluarga, kebiasaan makan dan gizi yang dikonsumsi dengan
fokus pada vitamin A dan zat besi, kebiasaan hidup sehat
meliputi kebiasaan merokok, minum obat atau alkohol, beban
kerja dan kegiatan sehari-hari, tempat melahirkan, dan
penolong yang diinginkan).
c. Pemeriksaan fisik
1) Pemeriksaan fisik umum : tinggi badan, berat badan, tanda-
tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu, respirasi).
2) Kepala dan leher : kepala meliputi
bersih/kotor,benjolan,lesi ,edema di muka, ikterus pada mata,
bibir pucat, leher meliputi pembengkakan kelenjar limfe dan
tiroid.
3) Payudara : ukuran, simetris, puting payudara menonjol/masuk,
keluarnya kolostrum atau cairan lain, retraksi, massa, nodul
axilla.
4) Abdomen : luka bekas operasi, tinggi fundus uteri (jika > 12
minggu), letak, presentasi, posisi, dan penurunan kepala (kalau
> 36 minggu), mendengar denyut jantung janin (kalau > 18
minggu).
5) Tangan dan kaki : edema di jari tangan, kuku jari pucat, varises
vena, refleks patella.
6) Genitalia luar (externa) : varises, perdarahan, luka, cairan yang
keluar, kelenjar bartholin, bengkak (massa).
7) Genitalia dalam (interna) : serviks meliputi cairan yang keluar,
luka, kelunakan, posisi, mobilisasi, tertutup atau terbuka,
vagina meliputi cairan yang keluar, luka, darah, ukuran
adneksa, bentuk, posisi, mobilitas, kelunakan, massa (pada
trimester pertama).
d. Tes laboratorium
1) Haemoglobin : normalnya 10,5-14,0
2) Protein urin : normalnya bening (-)
3) Glukosa urin : normalnya biru (-)
4) VDRL : normalnya (-)
5) Faktor rhesus : normalnya RH +
6) Gol darah
7) HIV
8) Rubella
9) Tinja/cacingan
e. Menentukan diagnosa, menetapkan normalitas kehamilan,
membedakan antara ketidaknyamanan dalam kehamilan dan
kemungkinan komplikasi, mengidentifikasi kemungkinan
kebutuhan belajar.
Diagnosis dibuat untuk menentukan hal-hal sebagai berikut :
1) Kehamilan normal dengan gambaran ibu sehat, tidak ada
riwayat obstetric buruk, ukuran uterus sama/sesuai usia
kehamilan, pemeriksaan fisik dan laboratorium normal.
(Saifuddin, 2008).
2) Kehamilan dengan masalah khusus, seperti masalah keluarga
atau psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan
financial.
3) Kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan
rujukan untuk konsultasi dan atau kerjasama penanganannya.
Seperti hipertensi, anemia berat, pre-eklampsia, pertumbuhan
janin terhambat, infeksi saluran kemih, penyakit kelamin, dan
kondisi lain-lain yang dapat memburuk selama kehamilan.
4) Kehamilan dengan kondisi kegawatdaruratan yang
membutuhkan rujukan segera. Seperti perdarahan, eklampsia,
ketuban pecah dini, atau kondisi-kondisi kegawatdaruratan lain
pada ibu dan bayi.
f. Mengembangkan perencanaan asuhan yang komprehensif,
menetapkan kebutuhan.
g. Melaksanakan asuhan sesuai dengan kebutuhan.
h. Menetapkan jadwal kunjungan sesuai dengan perkembangan
kehamilan.
Asuhan kehamilan kunjungan ulang
a. Pengkajian data fokus : riwayat
Riwayat kehamilan sekarang, menanyakan perasaan ibu saat ini,
menanyakan masalah yang mungkin timbul, pemeriksaan keadaan
umum, emosi, dan tanda-tanda vital.
b. Deteksi komplikasi
Perlu ditanyakan ada tidaknya komplikasi pada kehamilan, seperti
perdarahan dari vagina, pengeluaran cairan yang baunya berbeda
dengan bau urin dari vagina, nyeri yang hebat, gerakan janin yang
abnormal, tidak ada gerakan janin, suhu tubuh yang tinggi, demam,
menggigil, sakit kepala hebat, penglihatan kabur, pembengkakan
pada kaki, tangan, dan wajah.
c. Ketidaknyamanan
d. Pemeriksaan fisik
Keadaan umum, emosi, dan tanda-tanda vital, mengukur TFU,
palpasi abdomen, menghitung DJJ.
e. Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan ulang terhadap kadar protein urin, hemoglobin.
f. Mengembangkan rencana sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan kehamilan.
Penatalaksanaan pelayanan antenatal
Setiap wanita hamil menghadapi risiko komplikasi yang bisa
mengancam jiwanya. Oleh karena itu, setiap wanita hamil memerlukan
sedikitnya empat kali kunjungan selama periode antenatal :
1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14
minggu),
2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14-28),
3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28-36
dan sesudah minggu ke 36).
Pelayanan / asuhan standar minimal termasuk “8TSN” :
1. Timbang Berat Badan dan Ukur Tinggi Badan
Ukuran berat badan dalam kg tanpa sepatu dan memakai yang
seringan-ringannya. Berat badan kurang dari 45 kg pada trimester III
dinyatakan ibu kurus kemungkinan melahirkan bayi dengan berat
badan lahir rendah. Ukuran tinggi badan ibu hamil juga harus
diperhatikan, untuk dapat mengatahui apakah ibu dapat melahirkan
normal atau tidak.
2. Ukur Tekanan Darah
Untuk mengatahui setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan
mengenali tanda-tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta
mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.
3. Nilai Status Gizi (Ukur LILA )
Mengukur lila ( Lingkar lengan ) pada ibu hamil harus dilakukan untuk
mengatahui status gizi ibu. Ukuran yaitu 23,5 cm.
4. Ukur Tinggi Fundus Uteri
Mengukur tinggi fundus uteri dengan menggunakan meteran kain
( sesudah kehamilan ) dari 24 minggu TFU dalam cm di ukur dari
sympisis pubis sampai fundus uteri ( Rukiayah dkk, 2009 )
5. Tentukan Presentasi Janin Dan DJJ
Pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk
memperkirakan usia kehamilan serta bila umur kehamilan bertambah,
memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke
dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan
rujukan tepat waktu. Serta melakukan pemeriksaan DJJ untuk
mengatahui kesejahtraan janin.
6. Pemberian Imunisasi Tetanusteksoid
Pemberian imunisasi TT sesuai dengan ketentuan TT1 diberikan pada
kunjungan antenatal pertama, TT2 diberikan 4 minggu setelah TT1.
7. Pemberian Tablet Zat Besi, Minimum 90 Tablet Selama
Kehamilan.
Dimulai dengan pemberian satu tablet sesudah makan, tiap tablet
mengandung Fe.So4 Mg ( zat besi 60 mg ) dan asam folat 500 mg,
minimal 90 tablet, Tablet besi ini sebaiknya tidak diminum bersama
the atau kopi karena mengganggu penyerapan. ( saifuddin,2007)
8. Tes Laboratorium
Tes laboratorium penting juga dilakukan untuk digunaan menilai
adanya masalah pada ibu hamil dan jika tertangani, maka akan
mencegah kematian dan kesakitan pada ibu dan anak.
Tes yang dilakukan yaitu Haemoglobin (Hb), protein urine, Glukosa
dalam urine, VDRL/RPL, Golongan darah, Human Immunodeficiency
virus ( HIV), Rubella, tinja untuk ova/telur cacing dan parasit
( Rukiyah dkk, 2009).
9. Tatalaksana Kasus
Perubahan Paradigma menunggu terjadinya dan menangani kasus
komplikasi menjadi pencegahan terjadinya komplikasi dan dapat
membawa perbaikan kesehatan bagi kaum ibu di Indonesia.
Penyesuaian ini sangat penting dalam upaya menurunkan angka
kematian ibu dan bayi baru lahir karena sebagian besar persalinan di
Indonesia masih terjadi di tingkat pelayanan kesehatan primer dimana
tingkat keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan difasilitas
pelayanan tersebut masih belum memadai. Deteksi dini dan
pencegahan komplikasi dapat menurunkan angka kesakitan dan
kematian ibu serta bayi baru lahir, jika semua tenaga penolong
persalinan dilatih agar mampu untuk mencegah atau deteksi dini
komplikasi yang mungkin terjadi, merupakan asuhan persalinan secara
tepat guna dan waktu, baik sebelum atau saat masalah terjadi dan
segera melakukan rujukan saat kondisi masih optimal, maka para ibu
akan terhindar dari ancaman kesakitan dan kematian.
10. Temu wicara
Dalam persiapan rujukan termasuk perencanaan persalinan dan
pencegahan komplikasi serta KB pasca persalinan melakukan
anamnesis riwayat dan mengisi kartu ibu hamil/buku KIA secara
lengkap, dan memastikan bahwa kehamilan ibu diharapkan ( Rukiyah
dkk, 2009).
Cara menentukan umur kehamilan :
a. Naegele, yaitu hari + 7, bulan – 3, tahun + 1. Rumus ini digunakan
jika seorang wanita memiliki siklus haid yang teratur.
b. Jika seorang wanita memiliki siklus haid 35 hari, menurut rumus
Neagle HPHTnya akan ditambah 14 hari bukan 7 hari dan wanita
dengan siklus haidnya 21 hari, HPHTnya tidak perlu ditambah.
(Sarwono,2008)
c. Jika HPHT lupa, menggunakan patokan gerakan janin primigravida
dirasakan ibu pada kehamilan 18 minggu, multigravida pada
kehamilan 16 minggu. Dapat pula sebagai pegangan dipakai
perasaan nausea yang biasanya hilang pada kehamilan 12 – 14
minggu.
d. Penentuan umur kehamilan dengan ultrasonografi. Penentuan
kehamilan dengan ultrasonogtafi atau transabdomen dapat
digunakan pada usia kehamilan atau usia gestasinya kira-kira 5
minggu setelah hilangnya haid. (Linda Walsh, 2007, hal 101)
e. Tinggi fundus dengan menggunakan jari – jari tangan sesuai
dengan usia kehamilan (dengan cara leopold) :
Posisi uterus diketengahkan, letakkan ujung meteran pada simfisis,
kemudian diukur sampai fundus uteri maka akan terlihat hasil dalam
cm. TFU dengan cm dihitung mulai umur kehamilan >22 minggu.
Gambar 18. TFU menurut Mc. Donal dengan cm
Tabel 4. Tingggi Fundus Uteri diukur dengan jari
Umur
kehamilanTFU Keterangan
8 mgg Blm teraba Sebesar telur bebek
12 mgg 3 jari atas simfisis Sebesar telur angsa
16 mgg ½ pusat – simfisis Sebesar kepala bayi
20 mgg 3 jari bawah pusat -
24 mgg Sepusat -
28 mgg 3 jr ats pusat -
32 mgg ½ pusat – Px -
36 mgg 1 jr di bwh Px Kepala masih berada di atas
pintu panggul.
40 mgg 3 jr bwh Px Fundus uteri turun kembali,
karena kepala janin masuk ke
rongga panggul.
f. Tinggi fundus dengan menggunakan pita pengukur sesuai dengan
umur kehamilan pertama kali diperkenalkan oleh Mac Donald
pada dekade pertama abad ke-20.
Di bawah ini ukuran tinggi fundus uteri dalam cm dikaitkan
dengan umur kehamilan dan berat badan bayi sewaktu dilahirkan :
Bila pertumbuhan janin normal maka tinggi undus uteri pada
kehamilan pada 28 minggu 25 cm, pada 32 minggu 27 cm dan 36
minggu 30 cm. pada kehamilan 40 minggu fundus uteri turun
kembalidan terletak kira-kira 3 jari bawah Px, hal ini disebabkan
oleh kepala janin yang pada primigravida turun dan masuk ke
dalam rongga panggul. (Wiknjosastro, 2008 hal. 91)
Gambar 19 : posisi tangan untuk pengukuran tinggi fundus uteri
menggunakan pita pengukur
Palpasi abdomen :
Pemeriksaan Leopold :
Gambar 20. Leopold 1 sampai 4
Leopold I :
Gambar 21. Leopold 1
Untuk menentukan tinggi fundus uteri, menentukan usia kehamilan,
menentukan bagian janin yang ada pada fundus uteri.
Cara : Petugas menghadap kemuka ibu, uterus dibawa ketengah,
tentukan tinggi fundus uteri dan bagian apa yang terdapat di
dalam fundus
Hasil : Kepala teraba benda bulat dan keras
Bokong teraba tidak bulat dan lunak
Leopold II :
Gambar 22. Leopold 2
Untuk menetukan bagian yang ada di samping uterus, menetukan
letak.
Cara : Uterus didorong kesatu sisi sambil meraba bagian janin yang
berada disisi tersebut dengan cara yang sama pada sisi uterus
yang lain.
Hasil : Punggung janin teraba membujur dari atas kebawah pada
letak kepala. Pada letak lintang dapat ditemukan kepala.
Leopold III :
Gambar 23. Leopold 3
Menentukan bagian janin yang berada di uterus bagian bawah.
Cara : Tangan kanan diletakan diatas simfisis dengan ibu jari
disebelah kanan ibu dengan empat jari lainnya disebelah kiri
ibu sambil meraba bagian bawah tersebut.
Hasil : Teraba kepala/bokong/bagian kecil janin.
Leopold IV :
Gambar 24. Leopold 4
Menetukan seberapa jauh bagian terendah bagian janin masuk ke
dalam panggul.
(www.merck.com/.../MMPE_OBGYN_260_01_eps.gif)
PENURUNAN KEPALA DENGAN PERLIMAAN DAN
GAMBARNYA
Cara menentukan taksiran persalinan :
Menentukan tanggal perkiraan partus, dengan rumus Naegele , yaitu
hari + 7, bulan – 3, tahun + 1.
Jika HPHT lupa, menggunakan patokan gerakan janin primigravida
dirasakan ibu pada kehamilan 18 minggu, multigravida pada
kehamilan 16 minggu. Dapat pula sebagai pegangan dipakai perasaan
nausea yang biasanya hilang pada kehamilan 12 – 14 minggu.
Palpasi abdomen :
Pemeriksaan Leopold :
a. Leopold I : Untuk menentukan tinggi fundus uteri, menentukan
usia kehamilan, menentukan bagian janin yang ada
pada fundus uteri.
b. Leopold II : Untuk menetukan bagian yang ada di samping
uterus, menetukan letak.
c. Leopold III : Menentukan bagian janin yang berada di uterus
bagian bawah.
d. Leopold IV : Menetukan seberapa jauh bagian terendah bagian
janin masuk ke dalam panggul.
Cara menghitung berat badan janin dalam kandungan :
Menghitung perkiraan berat badan janin (PBBJ) menurut cara
Jonson:
a. Bila bagian terendah janin masuk pintu atas panggul :
PBBJ = ( TFU –11 ) x 155
b. Bila bagian terendah janin belum masuk pintu atas panggul :
PBBJ = ( TFU – 12 ) x 155
Cara menghitung denyut jantung janin :
Auskultasi :
Dengan stetoskop Laennec bunyi jantung janin baru dapat didengar
pada kehamilan 18 – 20 minggu. Dengan dopler dapat terdengar sejak
usia kehamilan 12 minggu.
DJJ = 1 menit penuh ( 60 detik)
Pemeriksaan hemoglobin :
Pemeriksaan Hb dilakukan 2 kali selama kehamilan, pada trimester
pertama dan pada kehamilan 30 minggu, karena pada usia 30 minggu
terjadi puncak hemodilusi. Ibu dikatakan anemia ringan Hb < 11 gr%,
dan anemia berat < 8 gr%. Dilakukan juga pemeriksaan golongan
darah, protein dan kadar glukosa pada urine. Untuk saat ini anemia
dalam kehamilan di Indonesia ditetapkan dengan kadar Hb < 11 gr%
pada trimester I dan III atau Hb < 10,5 gr% pada trimester. Anjuran
program nasional Indonesia adalah pemberian 60 mg/hari elemental
besi dan 50 g asam folat untuk profilaksis anemia. Program Depkes
memberikan 90 tablet besi selama 3 bulan. (Pengurus IBI, 2008)
Pertambahan berat badan selama hamil :
1) Pertambahan berat total selama kehamilan pada primigravida sehat
yang makan tanpa batasan adalah sekitar 12,5 kg. Dengan
distribusi pertambahan berat badan sebagai berikut :
(a). Payudara : 0,5 kg
(b).Fat/lemak : 3,5 kg
(c). Plasenta : 0,6 kg
(d).Fetus : 3,4 kg
(e). Cairan ketuban (amniotic fluid) : 0,6 kg)
(f). Pembesaran uterus : 0,9 kg
(g).Penambahan darah : 1,5 kg
(h).Cairan ekstraseluler : 1,5 kg
Total : 12,5 kg
(Cunningham, 2007)
2) Kenaikan berat badan wanita hamil rata – rata antara 6,5 kg sampai
16 kg. Bila berat badan naik lebih dari semestinya anjurkan untuk
mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Lemak
jangan dikurangi, terlebih – lebih sayur mayur dan buah-buahan.
(Wiknjosastro, 2008)
3) Kenaikan BB per Trimester :
Triwulan pertama 1.000 – 1.500 gr
Triwulan kedua 4.500 gr
Triwulan ketiga 5.000 – 5.500 gr
10.000 – 12.000 gr
(Sarwono,2008)
Kebutuhan gizi ibu hamil :
1) Trimester I (minggu 1-13)
Kebutuhan gizi masih tetap seperti biasa.
2) Trimester II (minggu 14-28)
Ibu memerlukan tambahan kalori 285 kal, protein lebih tinggi
dari biasa yaitu 1,5 gr/kg BB
3) Trimester III (minggu 28-lahir)
Kalori sama dengan trimester II tapi protein naik menjadi 2 gr/kg
BB.
4) Indeks Masa Tubuh (IMT)
Berat Badan
IMT = --------------------------------
Tinggi badan 2 (m)
Tabel 8. IMT Ibu Hamil
Sumber Data Kategori Rekomendasi kenaikan
berat
Depkes RI Normal (18,5 – 25
kg)
10 – 13 kg
Institute Of
Medicine
Rendah < 19,8 kg
Normal 19,8 – 26
kg
Tinggi > 26 kg
12,5 – 18 kg
11,5 – 16 kg
7 – 11,5
Sumber: Gizi Ibu Hamil, Edisi 1,3 G Publisher 2009, Jakarta
Tabel 5 . Kebutuhan gizi ibu hamil dalam ukuran rumah tangga
Bahan
Makanan
Ukuran Rumah
Tangga
Tidak
Hamil
Ibu hamil
TW I TW II TW III
Nasi
Ikan
Tempe
Sayuran
Buah
Gula
Susu
Air
Minyak
Piring
Potong
Potong
Mangkuk
Potong
Sdk mkn
Gelas
Gelas
Sdk mkn
3 ½
1 ½
3
1 ½
2
5
1
4
4
3 ½
1 ½
3
1 ½
2
5
1
4
4
4
2
4
3
2
5
1
6
6
3
3
5
5
2
5
1
6
6
(Gizi dalam Kespro,2009)
Kecukupan gizi yang dianjurkan untuk ibu hamil sesuai dengan
Gizi dalam kespro ,Gizi Ibu Hamil adalah:
c. Kalori : 2185 kal
d. Protein : 56 gram
e. Kalsium : 900 mg
f. Fosfor : 650 mg
g. Besi (Fe) : 46 µg
h. Iodium : 175 mg
i. Magnesium : 950 mg
j. Seng : 20 mg
k. Vitamin A : 750 RE
l. Vitamin B : 400-600 IU
m. Vitamin C : 60 mg
n. Vitamin B12 : 1,3 mg
o. Asam Folik : 300 µg
p. Casein : 10,2 mg
q. Riboflavin : 2,3 mg
r. Piridoksin : 2,6 mg
Contoh Menu Sehari Serta Nilai Gizi Yang Dikandungnya Untuk
Kehamilan Triwulan III
Tabel 6. Menu sehari serta nilai gizi untuk kehamilan triwulan III
Makanan Bahan Berat URT Kalori Protein Lemak HA
Sarapan
Pagi
Nasi
Telur
dadar
Teh manis
Beras
Telur ayam
Minyak
Teh dan gula
50
50
10
10
1 gls
1 btr
1 sdm
1 sdm
180
81
87
36,4
3,4
6,4
0,1
0,05
0,35
6
9,8
-
39,4
0,35
-
9,4
Jam
10.00
Pagi
Susu sapi Susu 10 2 sdm 6,1 6,32 0,35 0,45
Biskuit Gula
Biskuit
10
25
1 sdm
2,5 buah
36,4
114,5
-
1,725
-
36
9,4
18,77
Makan
Siang
Nasi
Empal
daging
Tempe
bacem
Sayur sop
Pepaya
Beras
Daging sapi
Minyak
Tempe
Wortel,
Kentang,
Buncis/kol
Pepaya
100
50
10
50
10
10
10
100
2 gls
1ktk korek
1 sdm
1 ktk korek
1 ptg bsr
1 buah bsr
1 genggam
1 ptg bsr
360
103,5
87
74,5
2,4
4,2
3,5
46
6.8
9,4
0,1
9,1
0,14
0,12
0,24
0,5
0,7
7
9,8
2
0,02
0,03
0,02
-
78,9
-
-
6,3
0,53
0,93
0,7
12,2
Jam
16.00
Teh manis
Jagung
rebus
Teh dan gula
Jagung muda
10
50
1 sdm
1 buah
36,4
64,5
-
2,5
-
0,65
9,4
15,15
Makan
Malam
Nasi
Daging
ayam
Telur
ceplok
Beras
Daging ayam
Minyak
Telur ayam
Minyak
100
50
10
50
10
2 gls
1 paha
1 sdm
1 btr
1 sdm
360
151
87
81
87
6,8
9,1
0,1
6,4
0,1
0,7
12,5
9,8
6
9,8
78,9
-
-
0,35
-
Sayur
urap
Pisang
Kacang pnjng
Toge
Kelapa
Pisang
50
25
15
30
1 genggam
1 genggam
1 genggam
1 buah
22
5,6
17
40
1,35
0,5
0,2
0,6
0,15
0,05
0,2
0,1
3,9
1,2
3,5
12,5
Jam
21.00
Singkong
rebus
Air Putih
Singkong
Air putih
50
200
1 ptg sdg
1 gelas
73
-
0,6
-
0.15
-
17
-
J U M L A H 2247,30 77 79,17 319,36
g. Prosedur Diagnostik
Prosedur Diagnostik dilakukan meliputi :
1) Anamnesa
a) Riwayat Kehamilan
b) Riwayat Kebidanan
c) Riwayat Kesehatan
d) Riwayat Sosial
2) Pemeriksaan Umum (Keseluruhan)
3) Pemeriksaan Kebidanan (Luar)
a) Inspeksi
b) Palpasi
c) Auscultasi
d) Perkusi
4) Pemeriksaan Kebidanan (Dalam)
5) Pemeriksaan Laboratorium
6) Pemeriksaan Penunjang : USG dan CTG
h. Prognosa dan Komplikasi
1) Prognosa
Setelah pemeriksaan selesai maka atas dasar pemeriksaan
harus dapat dibuat prognosa atau ramalan apakah nanti
kehamilannya akan berakhir dengan persalinan normal atau tidak.
Prognosa atau ramalan perlu untuk menentukan apakah
nantinya ibu hamil harus bersalin di Rumah Sakit atau boleh
melahirkan dirumah.
Berikut ini 19 penapisan dalam merujuk pasien, antara
lain:
a) Riwayat bedah besar
b) Perdarahan Pervaginam
c) Persalinan kurang bulan (usia kehamilan kurang dari 37
minggu)
d) Ketuban pecah dengan mekonium kental
e) Ketuban pecah lama
f) Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (usia kehamilan
kurang dari 37 minggu)
g) Ikterus
h) Anemia berat
i) Tanda / gejala infeksi
j) Preeklampsi / Hipertensi dalam kehamilan
k) Tinggi fundus uteri 40 cm atau lebih
l) Gawat janin
m) Primipara dalam fase aktif persalinan dengan palpasi kepala
masih 5/5
n) Presentasi bukan letak belakang kepala
o) Presentasi majemuk
p) Kehamilan gemeli
q) Tali pusat menumbung
r) Syok
s) Serotinus
2) Komplikasi
Pada kehamilan komplikasi yang sering ditemukan :
a) Perdarahan nidasi merupaskan hal yang fisiologis bila
jumlahnya sedikit, sebentar dan tidak berpengaruh buruk pada
kehamilan
b) Abortus
c) Kehamilan unembrionik (Blighted Ovom) dimana sejak awal
mudigah terbentuk kemudian mati
d) Molahidatidosa
e) Kehamilan Ektopik
f) Hiperemesis gravidarum
g) Preeklampsia dan Eklampsia
h) Perdarahan antepartum
i) Kehamilan kembar
j) Kelainan dalam lamanya kehamilan
k) Penyakit serta kelainan plasenta dan selaput janin
i. Kesimpulan hasil pemeriksaan hamil (Sarwono,2008 )
Setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, hasil akhir harus dapat
menjawab pertanyaan berkaitan dengan keadaan hamil sebagai berikut :
1) Umur ibu ( hanya dicantumkan bila umur ibu kurang dari 20 tahun
dan lebih dari 35 tahun )
a) Wanita hamil dibawah usia 20 tahun mempunyai resiko komplikasi
kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi. Mereka lebih mungkin
menderita hipertensi yang diinduksi kehamilan atau anemia dan
melahirkan bayi dengan BBLR
b) Primigravida tua (diatas 35 tahun ) mempunyai resiko lebih tinggi
menderita hipertensi essensial, hipertensi yang diinduksi kehamilan
diabetes kehamilan dan perdarahan antepartum. Kemungkinanan
mendapatkan bayi Down syndrome juga lebih besar serta
melahirkan dengan secio caesaria juga lebih besar.
2) Primigravida atau Multigravida
a) Definisi
Nuligravida : seorang wanita yang belum pernah hamil
Primigravida : seorang wanita yang hamil pertama kalinya
Multigravida : seorang wanita yang hamil dua kali atau lebih
b) Cara membedakan antara primigravida dan multigravida
Tabel 8: Perbedaan primigravida dengan multigravida
Primigravida Multigravida
Payudara tegang
Putting susu runcing
Perut tegang, menonjol
Stirae livide
Perineum utuh
Vulva tertutup
Vagina sempit dan rugae
Portio runcing, tertutup
Hamil pertama kali
Payudara lembek dan
menggantung
Putting susu tumpul
Perut lembek dan bergantung
Stirae livide dan albican
Perineum terdapat bekas robekan
Vulva terbuka
Vagina longgar dan tanpa rugae
Portio tumpul dan terbagi dalam
bibir depan belakng
Pernah hamil dan melahirkan
bayi genap bulan
Pada multigravida dilakukan pertanyaan tentang
persalinannya yang lampau, sebagai gambaran kerjasama antara 3
P, yaitu power( kekuatan his dan mengejan), passenger(besar dan
beratnya janin serta plasenta), passage( jalan lahir lunak dan tulang
panggul). Bila kehamilan dan persalinan yang lampau dijumpai
keadaan :
(1) Kehamilan dengan komplikasi atau penyakit
(2) Pernah mengalami keguguran
(3) Persalinan prematurus
(4) Kehamilan mati dalam rahim
(5) Persalinan dengan tindakan operasi
(6) Persalinan berlangsung lama, melebihi 24 jam
(7) Kehamilan lewat waktu
Dapat disimpulkan bahwa kehamilan yang sekarang
mempunyai resiko yang lebih tinggi.
3) Hamil atau tidak hamil
Untuk dapat menjawab pertanyaan ini perlu ditetapkan tanda –
tanda kehamilan, sebagai berikut :
a) Tanda kemungkinan kehamilan
(1) Tanda subyektife hamil
(a). Terlambat datang bulan
(b). Terdapat mual muntah
(c). Terasa sesak
(d). Terasa gerakan janin dalam perut
(e). Sering kencing
(2) Tanda obyektife hamil
(a). Pembesaran dan perubahan konsistensi rahim, dengan
memperhatikan tanda piskacek dan tanda hegar
(b).Perubahan warna dan konsistensi serviks
(c). Kontraksi braxton hicks
(d).Terdapat ballotement
(e). Teraba bagian janin
(f). Terdapat kemungkinan pengeluaran colostrum
(g).Terdapat hiperpigrmentasi kulit
(h).Terdapat warna kebiruan pada vagina / selaput lendir vulva
(tanda chadwik)
(i). Tes biologis positif
b) Tanda pasti kehamilan
1) Teraba gerakan janin dalam rahim
2) Terdengar denyut jantung janin
3) Pemeriksaan rontgen terdapat kerangka janin
4) Pemeriksaan USG
4) Umur kehamilan
Cara menentukan umur kehamilan (Manuaba, 2008. hal :120 )
a) Mempergunakan rumus naegle
(1) Hari + 7, Bulan +3, Tahun +1
(2) Hari + 7, Bulan + 9
b) Perkiraan tinggi fundus uteri
Tabel 9: Umur kehamilan berdasarkan TFU
Umur
kehamilan
TFU Keterangan
8 mgg Blm teraba Sebesar telur bebek
12 mgg Di atas simfisis Sebesar telur angsa
16 mgg ½ pusat - simfisis Sebesar kepala bayi
20 mgg Di pinggir bawah pusat --
24 mgg 24 minggu tepat di atas --
pinggir pusat
28 mgg 3 jr ats pusat / 1/3 pusat
– Px
--
32 mgg ½ pusat – Px --
36 mgg 1 jr di bwh Px Kepala masih
berada di atas pintu
panggul.
40 mgg 3 jr bwh Px Fundus uteri turun
kembali, karena
kepala janin masuk
ke rongga panggul.
(Wiknjosastro, 2008 hal. 91)
c) Dengan USG
Penentuan umur kehamilan dengan menggunakan USG
memerlukan ilmu pengetahuan yang lebih mendetail dan hanya
bisa dilakukan oleh orang atau ahli yang berkompeten didalam
bidangnya
5) Intrauterine atau ekstrauterine
a) Kehamilan diluar cavum uteri (ektopik ) sebagian besar tidak dapat
berlangsung sampai aterm dan pecah sampai umur hamil muda
b) Kehamilan intrauterine sejak hamil muda dapat dipastikan yaitu
perkembangan rahim sesuai dengan tuanya kehamila, janin teraba
intrauterine, dan pada palpasi terjadi kontraksi braxton hicks
c) Kehamilan abdominal yang mencapai aterm dapat dipastikan
dengan :
(1) gerakan janin terasa nyeri
(2) palpasi janin teraba dibawah kulit abdomen
(3) kontraksi braxton hicks tidak ada
(4) di samping janin teraba uterus yang kosong
(5) pemeriksaan USG didapatkan rahim kosong
(6) percobaan oksitosin 2 unit IV, kantung janin tidak terjadi
kontraksi
(7) foto rontgen dengan keras dan sonde ternyata rahim kosong
6) Tunggal atau ganda
Menetapkan kehamilan ganda pada umur kehamilan muda sulit
dilakukan, kecuali dengan USG. Dengan anamnesa dapat diduga hamil
kembar (ganda ) yaitu :
a) Perut cepat membesar
b) Gejala emesis gravidarum lebih cepat
c) Perut dirasakan lebih berat
d) Gerakan janin lebih banya
e) Dapat disertai sesak nafas
f) Pada hamil tua dengan pemeriksaan dijumpai gejala hamil ganda
yaitu:
(1) perut lebih besar dari tuanya kehamilan
(2) teraba tiga bagian besar atau dua bagian besar yang
berdampingan
(3) teraba banyak bagian kecil
(4) sering disertai hidramnion
(5) terdengar dua punctum maksimum denyut jantung janin dalam
perbedaan sekitar 10 denyutan
(6) dengan pemeriksaan USG dapat dipastikan hamil kembar,
dimana terdapat dua kepala dan kerangka janin, dan dua denyut
jantung janin berdenyut.
7) Hidup atau mati
a) Janin hidup
(1) TFU sesuai dengan umur kehamilan
(2) Palpasi janin dalam rahim jelas
(3) Terdengar DJJ
(4) Terasa adanya gerkan janin
b) Kematian janin dalam rahim dapat dilakukan pemeriksaan :
(1) Kehamilan sangat muda kurang dari 12 minggu
(a). Pemeriksaan USG
- bentuk kantong janin tidak normal, keriput
- air ketuban berkurang
- tidak terdapat denyut jantung janin
(b).Tes biologis negative setelah kehamilan mati dalam rahim
sekitar 10 hari
(2) Kehamilan diatas 16 minggu
(a). TFU tidak sesuai dengan umur kehamilan / fundus uteri
mengecil
(b).Palpasi janin dalam rahim tidak jelas
(c). Tidak terdengar denyut jantung janin
(d).Tidak terasa gerakan janin
(e). Pemeriksaan USG dan foto abdomen :
- Air ketuban berkurang
- Tanda spalding positif
- denyut jantung janin tidak ada
- kerangka janin sangat melengkung
- terdapat gelembung gas dalam usus janin
8) Letak anak
Letak janin dapat diketahui dengan :
a) Palpasi abdomen : Leopold I dan III
b) Mendengarkan tempat dimana paling jelas denyut jantung janin
terdengar
(1) Bila DJJ terdengar diatas pusat, maka letak janin adalah letak
sungsang
(2) Bila DJJ terdengar dibawah pusat, maka letak janin adalah
letak kepala
c) Pemeriksaan USG
9) Keadaan umum ibu dan janin
a) Pemeriksaan kesehatan umum ibu hamil dilakukan melalui
anamnese, pemeriksaan kesehatan umum ibu hamil dilakukan
melalui anamnesa, pemeriksaan fisik dan laboraturium
dasar.keadaan umum ibu dikatakan baik apabila hasil anannesa
pemeriksaan fisik dan laboratorium tidak didapatkan hasil
abnormal.
b) Sedangkan keadaan umum janin dikatakan baik apabila gerkan
janin dirasakan aktif oleh ibu dan DJJ dalam batas normal.
10) Kesan panggul
Fungsi Umum Panggul Wanita yang terdiri bagian keras
panggul wanita berfungsi untuk : Panggul Besar (pelvis mayor)
fungsinya adalah untuk sangga isi abdomen; Panggul kecil (pelvis
minor) fungsinya membentuk jalan lahir, serta merupakan tempat alat
genetalia; Bagian Lunak panggul wanita berfungsi: Membentuk
lapisan dalam jalan lahir, Menyangga alat genetalia dalam posisi
normal, Saat persalinan berperan dalam proses kelahiran (Prawiro-
hardjo, 2008).
Bentuk Panggul Wanita
Panggul Gynekoid: merupakan bentuk yang khas bagi wanita ukuran
diameter transversa kira-kira sama panjangnya dengan ukuran diameter
antero posterior hingga bentuk pintu atas panggul mendekati
Gambar 25. Panggul
lingkaran/bulat.
Panggul Android: segmen anterior sempit dan berbentuk segitiga,
sacrum letaknya ke depan, hingga ukuran diameter anteroposterior
sempit pada pintu atas panggul dan pintu bawah panggul.
Panggul Antropoid: ukuran antero posterior dari pintu atas panggul
lebih besar dari ukuran diameter transversa hingga bentuk pintu atas
panggul lonjong ke depan.
Panggul Platipeloid: seperti panggul gynekoid yang picak, ukuran
diameter antero posterior lebih kecil, ukuran diameter transversa biasa
(wijossastro 2008).
Ukuran Panggul Yang Sering Dipakai Dalam Kebidanan Ukuran
Panggul Dalam
a) Pintu Atas Panggul: Conjugata Vera (CD-1,5) yaitu Jarak dr tepi
atas symph-promont dengan ukuran normal : 11 cm, Conjugata
Diagonalis Jarak dad tepi bawah sympisis-promontorium.
b) Pemeriksaan Dalam Untuk Menentukan Ukuran dan Bentuk
Panggul Dalam: Apakah promontorium teraba; Apakah tidak ada
tumor; Apakah linea inominata teraba '/2 atau 1/3 bagian; Apakah
tulang sakrum mempunyai inklinasi ke depan atau ke belakang;
Apakah sudut arkus pubis cukup luas atau tidak.
c) Ukuran Panggul yang sering dipakai dalam kebidanan: ukuran
panggul luar. Distansia Spinarum merupakan jarak antara Spina
Iliaka Anterior Superior (SIAS) kiri dan kanan (Indonesia. 23cm,
Eropa. 26 cm). Distansia Cristarum: Jarak terjauh antara Crista
Iliaka kanan dan kiri (Indonesia 26 cm, Eropa. 29 cm). Conjugata
Eksterna: Jarak pinggir atas sympisis dan ujung Processus
Spinosus tulang lumbal ke-V (Indonesia 18 cm, Eropa 20 cm).
Lingkar Panggul: dari pinggir atas sympisis ke pertengahan antara
SIAS dan Trochanter Mayor sepihak dan kembali melalui tempat-
tempat yang sama di pihak lain. (Indonesia 80 cm, Eropa 90 cm)
(Wijosastro 2008)
Pada dasarnya pemeriksaan panggul tidak perlu dilakukan kecuali
jika adanya dugaan sempit panggul atau kelainan panggul, bila:
a) Pada primigravida, pada kehamilan 36 minggu atau lebih kepala
belum masuk PAP
b) Pada primigravida pada kehamilan aterm terdapat kelainan letak
c) Perasat osborn menunjukan hasil positif
Pada mutigravida pada kehamilan dahulu dengan secsio caesaria
oleh karena panggul sempit atau bayi besar
Cara menghitung perkiraan berat badan janin (PBBJ )
Dengan menggunakan rumus jhonson :
(1) Bila bagian terendah janin sudah masuk PAP :
(TFU – 11 ) X155
(2) Bila bagian terendah janin belum masuk PAP :
(TFU – 12 ) X 155
11) Penyulit atau penyerta ( seperti anemia, pre-eklampsia / eklampsia,
dan lain-lain).
2. Persalinan
a. Pengertian
1) Persalinan merupakan proses fisiologis normal yang diawali oleh
kontraksi dengan frekuensi lama serta nyeri yang meningkat, yang
memungkinkan pendataran dan pembukaan servik, sehingga janin
dapat melintas melewati jalan lahir dan selamat dilahirkan.
( Atlas tehnik kebidanan, 2007. hal. 21 )
2) Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang
dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar.
a) Persalinan immaturus kurang dari 28 minggu, lebih dari 20
minggu dengan berat janin antara 500-1000 gram.
b) Persalinan prematurus adalah lahinya bayi yang dapat hidup
namun belum cukup bulan.berat janin antara 1000-2500 gram
atau usia kehamilan antara 28-36 minggu.
c) Partus postmaturus atau serotinus adalah partus yang terjadi 2
minggu atau lebih dari waktu partus yang diperkirakan.
(Wiknjosastro, H. 2008. hal. 180).
3) Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya servik,dan
janin turun kedalam jalan lahir. Kelahiran adalah proses dimana
janin dan ketuban di dorong keluar melalui jalan lahir.
(Saifuddin, AB. 2008, hal. 100).
4) Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin
yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, lahir
spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18
jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin.
(Saifuddin, AB. 2008, hal. 100).
5) Persalinan normal adalah proses pengeluaran bayi dengan usia
kehamilan cukup bulan,letak memanjang atau sejajar sumbu badan
ibu, persentasi belakang kepala, keseimbangan diameter kepala
bayi, dan panggul ibu, serta dengan tenaga ibu sendiri.pada
persalinan normal dapat berubah menjadi persalinan patologi
apabila kesalahan dalam penilaian kondisi ibu dan janin atau juga
akibat kesalahan dalam memimpin proses persalinan.
(Saifuddin, AB. 2008, hal. 450)
6) Persalinan adalah proses alamiah dimana terjadi dilatasi servik,
lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu.
(Asuhan persalinan normal, halaman 2-1).
7) Persalinan adalah pengeluaran hasil suatu proses
pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hudup dari dalam
uterus melalui vagina kedunia luar.(Sarwono
Prawirohardjo, 2008. hal 180)
b. Etiologi
Sampai sekarang sebab-sebab mulai timbulnya persalinan tidak
diketahui dengan jelas, banyak teori yang dikemukakan antara lain :
Menurut (Wiknjosastro, 2008 hal 181) beberapa teori mengemukakan
etiologi dari persalinan adalah :
1) Penurunan kadar hormon estrogen dan progesterone
2) Pengaruh prostaglandin
3) Struktur uterus
4) Sirkulasi uterus
5) Pengaruh saraf dan nutrisi
Sedangkan menurut (Sarwono Prawirohardjo, 2008. hal. 181) sebab
terjadinya persalinan masih menjdi teori yang kompleks.
1) Faktor-faktor humoral
2) Pengaruh prostaglandin
3) Struktur uterus
4) Sirkulasi uerus
5) Pengaruh syaraf dan nutrisi
c. Fisiologis persalinan
(Wiknjosastro, 2008 hal 181)
Sebab-sebab terjadinya persalinan masih merupakan teori yang
komplek. Perubahan-perubahan dalam biokimia dan biofisika telah
banyak mengungkapkan mulai dari berlangsungnya partus antara lain
penurunan kadar hormon progesterone dan estrogen. Progesteron
merupakan penenang bagi otot – otot uterus. Menurunnya kadar
hormon ini terjadi 1-2 minggu sebelum persalinan. Kadar
prostaglandin meningkat menimbulkan kontraksi myometrium.
Keadaan uterus yang membesar menjadi tegang mengakibatkan iskemi
otot – otot uterus yang mengganggu sirkulasi uteroplasenter sehingga
plasenta berdegenerasi. Tekanan pada ganglion servikale dari fleksus
frankenhauser di belakang servik menyebabbkan uterus berkontraksi.
d. Tahap-Tahap Persalinan
Berlangsungnya persalinan dibagi dalam 4 kala yaitu:
1) Kala I
Disebut juga kala pembukaan dimulai dengan pembukaan serviks
sampai terjadi pembukaan 10 cm. Proses membukanya serviks
disebabkan oleh his pesalinan/kontraksi. Tanda dan gejala kala I :
a. His sudah teratur, frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit
b. Penipisan dan pembukaan serviks
c. Keluar cairan dari vagina dalam bentuk lendir bercampur darah
Kala I dibagi dalam 2 fase:
a) Fase laten
Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan
dan pembukaan servik secara bertahap, pembukaan servik
kurang dari 4 cm, biasanya berlangsung hingga 8 jam.
Prosedur dan diagnostik :
Untuk menentukan apakah persalinan sudah pada waktunya:
(Saifuddin AB. Buku acuan nasional pelayanan maternal dan
neonatal.2008) maka:
(1). Tanyakan riwayat persalinan :
Permulaan timbulnya kontraksi; pengeluaran pervaginam
seperti lendir, darah, dan atau cairan ketuban; riwayat
kehamilan; riwayat medik; riwayat social; terakhir kali
makan dan minum; masalah yang pernah ada.
(2). Pemeriksaan Umum :
Tanda vital, BB, TB, Oedema; kondisi puting susu;
kandung kemih.
(3). Pemeriksaan Abdomen :
Bekas luka operasi; tinggi fundus uteri; kontraksi;
penurunan kepala; letak janin; besar janin; denyut jantung
janin.
(4). Pemeriksaan vagina :
Pembukaan dan penipisan serviks; selaput ketuban
penurunan dan molase; anggota tubuh janin yang sudah
teraba.
(5). Pemeriksaan Penunjang :
Urine: warna, kejernihan, bau, protein, BJ, dan lain-lain;
darah: Hb, BT/CT, dan lain-lain.
(6). Perubahan psikososial
Perubahan prilaku; tingkat energi; kebutuhan dan
dukungan.
b) Fase aktif
Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus umumnya meningkat
(kontraksi dianggap adekuat jika terjadi tiga kali atau lebih),
serviks membuka dari 4 cm ke 10 cm, biasanya kecepatan 1 cm
atau lebih per jam hingga pembukaan lengkap ( 10 cm ) dan
terjadi penurunan bagian terbawah janin.
Pemantauan kala 1 fase aktif persalinan :
Penggunaan Partograf
Partograf adalah alat bantu yang digunakan selama fase aktif
persalinan. Tujuan utama dari penggunaan partograf adalah
untuk :
a. Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan
dengan menilai pembukaan serviks melalui
pemeriksaan dalam.
b. Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan
secara normal. Dengan demikian , juga dapat
melakukan deteksi secara dini setiap kemungkinan
terjadinya partus lama
.
Halaman depan partograf untuk mencatat atau memantau :
(1). Kesejahteraan janin
Denyut jantung janin (setiap ½ jam), warna air ketuban
(setiap pemeriksaan dalam), penyusupan sutura (setiap
pemeriksaan dalam).
(2). Kemajuan persalinan
Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus (setiap ½ jam),
pembukaan serviks (setiap 4 jam), penurunan kepala
(setiap 4 jam).
(3). Kesejahteraan ibu
Nadi (setiap ½ jam), tekanan darah dan temperatur tubuh
(setiap 4 jam), prodeksi urin , aseton dan protein (setiap 2
sampai 4 jam), makan dan minum.
2) Kala II (Kala Pengeluaran)
Kala II persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah
lengkap (10 cm) dan berakhir dengan lahirnya bayi.
Wanita merasa hendak buang air besar karena tekanan pada
rektum. Perinium menonjol dan menjadi besar karena anus
membuka. Labia menjadi membuka dan tidak lama kemudian
kepala janin tampak pada vulva pada waktu his.
Pada primigravida kala II berlangsung 1,5-2 jam, pada multi 0,5-1
jam.
Tanda dan gejala kala II :
(a). Ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya
kontraksi.
(b).Perineum terlihat menonjol.
(c). Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rectum dan
atau vaginanya.
(d).Ibu meraakan makin meningkatnya tekanan pada rectum dan atau
vaginanya.
(e). Vulva-vagina dan sfingkter ani terlihat emmbuka.
(f). Peningkatan pengeluaran lendir dan darah.
3) Kala III (Kala uri)
Kala III persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir
dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban (Wiknjosastro,
2008).
Dimulai segera setelah bayi lahir sampai dengan lahirnya placenta
( 30 menit). Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan fundus
uteri sepusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi
untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta
lepas dalam 6-15 menit setelah bayi lahir dan plasenta keluar
spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri (dorsokranial).
Penatalaksanaan aktif pada kala III (pengeluaran aktif plasenta)
membantu menghindarkan terjadinya perdarahan pasca persalinan.
Tanda – tanda pelepasan plasenta :
d. Perubahan bentuk dan tinggi fundus.
e. Tali pusat memanjang
f. Semburan darah tiba – tiba
Manejemen aktif kala III :
Tujuannya adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih
efektif sehingga dapat memperpendek waktu kala III dan
mengurangi kehilangan darah dibandingkan dengan
penatalaksanaan fisiologis, serta mencegah terjadinya retensio
plasenta.
Tiga langkah manajemen aktif kala III :
g. Berikan oksitosin 10 unit IM dalam waktu dua menit setelah
bayi lahir, dan setelah dipastikan kehamilan tunggal.
h. Lakukan peregangan tali pusat terkendali.
i. Segera lakukan massage pada fundus uteri setelah plasenta
lahir.
4) Kala IV (2 jam post partum)
Setelah plasenta lahir, kontraksi rahim tetap kuat dengan amplitudo
60 sampai 80 mmHg, kekuatan kontraksi ini tidak diikuti oleh
interval pembuluh darah tertutup rapat dan terjadi kesempatan
membentuk trombus. Melalui kontraksi yang kuat dan
pembentukan trombus terjadi penghentian pengeluaran darah post
partum. Kekuatan his dapat dirasakan ibu saat menyusui bayinya
karena pengeluaran oksitosin oleh kelenjar hipofise posterior
Tanda dan gejala kala IV : bayi dan plasenta telah lahir, tinggi
fundus uteri 2 jari bawah pusat.
Selama 2 jam pertama pascapersalinan :
Pantau tekanan darah, nadi, tinggi fundus, kandung kemih dan
perdarahan yang terjadi setiap 15 menit dalam satu jam pertama
dan setiap 30 menit dalam satu jam kedua kala IV. Jika ada temua
yang tidak normal, lakukan observasi dan penilaian secara lebih
sering.
Lamanya persalinan pada primigravida dan multigravida :
Tabel 10. Lamanya persalinan pada primigravida dan multigravida
Primigravida Multigravida
Kala I 10 – 12 jam 6-8 jam
Kala II 1-1,5 jam 0,5-1 jam
Kala III 10 menit 10 menit
Kala IV 2 jam 2 jam
Jumlah
(tanpa memasukkan kala IV
yang bersifat observasi)
12-14 jam 8-10 jam
e. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan
1) Power : His dan tenaga mengejan.
2) Passage : Ukuran panggul dan otot-otot persalinan.
3) Passenger : Terdiri dari janin, plasenta dan air ketuban.
4) Personality (kepribadian) : yang diperhatikan kesiapan ibu dalam
menghadapi persalinan dan sanggup berpartisipasi selama proses
persalinan.
5) Provider (penolong) : dokter atau bidan yang merupakan tenaga
terlatih dalam bidang kesehatan. (Wiknjosastro, 2008).
f. Mekanisme persalinan
1) Pengertian
Denominator atau petunjuk adalah kedudukan dari salah satu
bagian dari bagian depan janin terhadap jalan lahir.
Hipomoklion adalah titik putar atau pusat pemutaran.
2) Mekanisme persalinan letak belakang kepala
a. Engagement (fiksasi) = masuk
Ialah masuknya kepala dengan lingkaran terbesar (diameter
Biparietal) melalui PAP. Pada primigravida kepala janin
mulai turun pada umur kehamilan kira-kira 36 minggu,
sedangkan pada multigravida pada kira-kira 38 minggu,
kadang-kadang baru pada permulaan partus. (Wiknjosastro,
2008, h.129). Engagement lengkap terjadi bila kepala sudah
mencapai Hodge III. Bila engagement sudah terjadi maka
kepala tidak dapat berubah posisi lagi, sehingga posisinya
seolah-olah terfixer di dalam panggul, oleh karena itu
engagement sering juga disebut fiksasi. Pada kepala masuk
PAP, maka kepala dalam posisi melintang dengan sutura
sagitalis melintang sesuai dengan bentuk yang bulat lonjong.
Seharusnya pada waktu kepala masuk PAP, sutura sagitalis
akan tetap berada di tengah yang disebut Synclitismus. Tetapi
kenyataannya, sutura sagitalis dapat bergeser kedepan atau
kebelakang disebut Asynclitismus. Asynclitismus dibagi 2
jenis:
- Asynclitismus anterior : naegele obliquity yaitu bila sutura
sagitalis bergeser mendekati promontorium.
- Asynclitismus posterior : litzman obliquity yaitu bila sutura
sagitalis mendekati symphisis.
Gambar 26. Engagement
b. Descensus = penurunan
Ialah penurunan kepala lebih lanjut kedalam panggul. Faktor-
faktor yng mempengaruhi descensus : tekanan air ketuban,
dorongan langsung fundus uteri pada bokong janin, kontraksi
otot-otot abdomen, ekstensi badan janin.
Gambar 27. Penurunan kepala
c. Fleksi
Ialah menekannya kepala dimana dagu mendekati sternum
sehingga lingkaran kepala menjadi mengecil suboksipito
bregmatikus (9,5 cm). Fleksi terjadi pada waktu kepala
terdorong His kebawah kemudian menemui jalan lahir. Pada
waktu kepala tertahan jalan lahir, sedangkan dari atas
mendapat dorongan, maka kepala bergerak menekan ke
bawah.
Gambar 28. Fleksi
d. Putaran Paksi Dalam (internal rotation)
Ialah berputarnya oksiput ke arah depan, sehingga ubun -
ubun kecil berada di bawah symphisis (HIII). Faktor-faktor
yang mempengaruhi : perubahan arah bidang PAP dan PBP,
bentuk jalan lahir yang melengkung, kepala yang bulat dan
lonjong.
Gambar 29. Putaran paksi dalam
e. Ekstensi
Ialah mekanisme lahirnya kepala lewat perineum. Faktor
yang menyebabkan terjadinya hal ini ialah : lengkungan
panggul sebelah depan lebih pendek dari pada yang belakang.
Pada waktu defleksi, maka kepala akan berputar ke atas
dengan suboksiput sebagai titik putar (hypomochlion)
dibawah symphisis sehingga berturut – turut lahir ubun –
ubun besar, dahi, muka dan akhirnya dagu.
Gambar 30. Ekstensi
f. Putaran paksi luar (external rotation)
Ialah berputarnya kepala menyesuaikan kembali dengan
sumbu badan (arahnya sesuai dengan punggung bayi).
Gambar 31. Putaran paksi Luar
g. Expulsi : lahirnya seluruh badan bayi.
Gambar 32. Ekspulsi
(Sarwono,2008)
g. Tanda dan Gejala
Tanda dan gejala persalinan yaitu :
Kala I
1) His sudah teratur dan frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit
2) Penipisan dan pembukaan servik
3) Keluar cairan dari vagina dalam bentuk lendir bercampur darah.
Kala II
1) Ibu ingin meneran/mengejan
2) Perineum menonjol
3) Vulva dan anus membuka
4) Meningkatnya pengeluaran lendir
5) Kepala telah turun pada dasar panggul
Kala III
1) Tali pusat memanjang, terasa adanya pelepasan plasenta
2) Semburan darah tiba-tiba
Kala IV
Tingginya fundus uteri sepusat atau 1 jari dibawah pusat
(Asuhan Persalinan Normal, 2008 hal : 3-2)
h. Prosedur Diagnostik
Untuk menentukan persalinan sudah pada waktunya adalah :
(Saifuddin, AB. 2008 hal : 106)
1) Tanyakan :
a) Permulaan timbulnya kontraksi
b) Pengeluaran pervaginam seperti lendir, darah, dan atau cairan
ketuban
c) Riwayat kehamilan
d) Riwayat medik
e) Riwayat sosial
f) Terakhir kali makan dan minum
g) Masalah yang pernah ada
2) Pemeriksaan Umum :
a) Tanda vital, BB, TB. Oedema
b) Kondisi puting susu
c) Kandung kemih
3) Pemeriksaan Abdomen :
a) Bekas luka operasi
b) Tinggi Fundus Uteri
c) Kontraksi
d) Penurunan Kepala
e) Letak janin
f) Besar janin
g) Denyut jantung janin
4) Pemeriksaan vagina :
a) Pembukaan dan penipisan servik
b) Selaput ketuban penurunan dan molase
c) Anggota tubuh janin yang sudah teraba
5) Pemeriksaan Penunjang :
a) Urine : warna, kejernihan, bau, protein, BJ, dan lain-lain
b) Darah : Hb, BT/CT, dan lain-lain.
i. Asuhan dalam persalinan
Tujuan Asuhan Persalinan :
Mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat
kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya
yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip
keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang
optimal (Asuhan persalinan normal, 2008, hal. xiii)
Kala I
1) Memberikan dorongan emosional
Anjurkan suami dan anggota keluarga yang lain untuk
mendampingi ibu selama proses persalinan
2) Membantu pengaturan posisi
Anjurkan suami dan pendamping lainnya untuk membantu ibu
berganti posisi. Ibu boleh berdiri, berjalan-jalan, duduk, jongkok,
berbaring miring, merangkak dapat membantu turunnya kepala
bayi dan sering juga mempersingkat waktu persalinan
3) Memberikan cairan / nutrisi
Makanan ringan dan cairan yang cukup selama persalinan
memberikan lebih banyak energi dan mencegah dehidrasi. Apabila
dehidrasi terjadi dapat memperlambat atau membuat kontraksi
menjadi tidak teratur dan kurang efektif.
4) Keleluasaan ke kamar mandi secara teratur
Ibu harus berkemih paling sedikit setiap 2 jam atau lebih sering
jika ibu ingin berkemih. Jika kandung kemih penuh dapat
mengakibatkan :
a) Memperlambat penurunan bagian terendah janin dan
mungkin menyebabkan partus macet
b) Menyebabkan ibu merasa tidak nyaman
c) Meningkatkan resiko perdarahan pasca persalinan yang
disebabkan oleh atonia uteri
d) Mengganggu penatalaksanaan distosia bahu
e) Meningkatkan resiko infeksi saluran kemih pasca persalinan
5) Pencegahan infeksi
Pencegahan infeksi sangat penting dalam penurunan kesakitan
dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Upaya dan ketrampilan
menjelaskan prosedur pencegahan infeksi yang baik melindungi
penolong persalinan terhadap resiko infeksi
6) Pantau kesejahteraan ibu dan janin serta kemajuan persalinan
sesuai partograf
(Asuhan Persalinan Normal, 2008, hal : 2-5)
Kala II
1) Berikan terus dukungan pada ibu
2) Menjaga kebersihan ibu
3) Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan
atau ketakutan ibu
4) Mengatur posisi ibu
5) Menjaga kandung kemih tetap kosong, anjurkan ibu untuk
berkemih
6) Berikan cukup minum terutama minuman yang manis
7) Ibu dibimbing mengedan selama his dan anjurkan ibu untuk
mengambil nafas diantara kontraksi
8) Perikda DJJ setiap selesai kontraksi
9) Minta ibu mengedan saat kepala bayi nampak divulva
10) Letakkan satu tangan dikepala bayi agar defleksi tidak terlalu
cepat
11) Tahan perineum dengan satu tangan yang lain
12) Jika kepala telah lahir, usap dengan kasa dari lendir dan darah
13) Periksa adanya lilitan tali pusat
14) Biarkan kepala bayi mengadakan putaran paksi luar dengan
sendirinya
15) Tempatkan kedua tangan pada posisi biperietal bayi
16) Lakukan tarikan lembut kepala bayi kebawah untuk melahirkan
bahu anterior lalu keatas untuk melahirkan bahu posterior.
17) Sangga kepala dan leher bayi dengan satu tangan kemudian
dengan tangan yang lain menyusuri badan bayi sampai
seluruhnya lahir.
18) Letakkan bayi diatas perut ibu, keringkan sambil nilai
pernafasannya (Score APGAR) dalam menit pertama
19) Lakukan pemotongan tali pusat
20) Pastikan bayi tetap hangat
Kala III
1) Pastikan tidak ada bayi yang kedua
2) Berikan oksitosin 10 IU dalam 2 menit pertama segera setelah
bayi lahir.
3) Lalukan penegangan tali pusat terkendali, tangan kanan
menegangkan tali pusat sementara tangan kiri dengan arah
dorsokranial mencengkram uterus.
4) Jika plasenta telah lepas dari insersinya, tangan kanan menarik
tali pusat kebawah lalu keatas sesuai dengan kurve jalan lahir
sampai plasenta nampak divulva lalu tangan kanan menerima
plasenta kemudian memutar kesatu arah dengan hati-hati
sehingga tidak ada selaput plasenta yang tertinggal dalam jalan
lahir
5) Segera setelah plasenta lahir tangan kiri melakukan massase
fundus uteri untuk menimbulkan kontraksi
6) Lakukan pemeriksaan plasenta, pastikan kelengkapannya
7) Periksa jalan lahir dengan seksama, mulai dari servik, vagina
hingga perineum. Lakukan perbaikan/penjahitan jika diperlukan.
Kala IV
1) Bersihkan ibu sampai ibu merasa nyaman
2) Anjurkan ibu untuk makan dan minum untuk mencegah
dehidrasi
3) Berikan bayinya pada ibu untuk disusui
4) Periksa kontraksi uterus dan tanda vital ibu setiap 15 menit pada
jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua.
5) Ajarkan ibu dan keluarganya tentang :
b) Tanda bahaya bagi ibu dan bayi.
6) Pastikan ibu sudah buang air kecil dalam 3 jam pertama
Tanda-tanda bahaya dalam persalinan (Abdul Bari Saefudin, 2008)
Tabel 11. Tanda-tanda bahaya dalam Persalinan
ParameterTemuan
AbnormalTindakan Mandiri
Tindakan
dengan dokter
Tekanan
darah
>140/90 mmHg
dengan sedikitnya
tanda/gejala
preeklampsia
Rujuk ibu dengan
membaringkan
ibu miring kekiri
sambil diinfus
Sama seperti
tanpa dokter
Temperatur >38ºC Kompres,
rehidrasi, rujuk
Sama seperti
tanpa dokter
Nadi >100 ×/menit Rehidrasi, rujuk Sama seperti
tanpa dokter
DJJ <100×/menit atau
>180×/menit
Rehidrasi, ganti
posisi ibu tidur
terlentang atau
miring kekiri
Sama seperti
tanpa dokter
Kontraksi <3×/10 menit,
berlangsung <40
detik dan waktu
palpasi lemah
Ambulasi, ubah
posisi, kosongkan
kandung kemih
jika perlu dengan
kateterisasi.
Lakukan stimulasi
Sama seperti
tanpa dokter
putting susu,
berikan makan
minum, jika
partograf
melewati garis
waspada rujuk
Serviks Partograf
melewati garis
waspada
Rehidrasi, rujuk Sama seperti
tanpa dokter
Cairan amnion terdapat
mekonium, darah
dan berbau
Tetap monitor
DJJ, antisipasi
bayi, mengisap
lendir saat lahir.
Rehidrasi, rujuk
dengan posisi
miring kekiri dan
berikan antibiotik
Sama seperti
tanpa dokter
Urin Volume sedikit
dan pekat
Rehidrasi, jika
tidak ada
kemajuan setelah
4 jam, periksa dan
lakukan rujukan
Sama seperti
tanpa dokter
Penggunaan Partograf
Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan kala satu
persalinan dan informasi untuk membuat keputusan klinik.(APN, 2008
hal 55).
Tujuan utama dan penggunaan partograf adalah untuk:
(APN, 2008 hal 55)
a. Mencatat hasil observasi dan kemajuan persalinan dengan menilai
pembukaan serviks melalui pemeriksaan dalam.
b. Mendeteksi apakah proses persalinan berjalan secara normal. Dengan
demikian juga dapat mendeteksi secara dini kemungkinan ter adinya
partus lama.
c. Data pelengkap yang terkait dengan pemantuan kondisi ibu, kondisi
bayi, grafik kemajuan proses persalinan, bahan dan medikamentosa
yang diberikan, pemeriksaan laboratorium, membuat keputusan klinik
dan asuhan atau tindakan yang diberikan dimana semua itu dicatatkan
secara rinci pada status atau rekam medik ibu bersalin dan bayi barn
lahir.
Jika digunakan secara tepat dan konsisten, partograf akan
membantu penolong persalinan untuk: (APN,2008 hal 55)
a. Mencatat kemajuan persalinan
b. Mencatat kondisi ibu dan janinnya
c. Mencatat asuhan yang diberikan selama persalinan dan kelahiran
d. Menggunakan informasi yang tercatat untuk identifikasi dini penyulit
persalinan
e. Menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat keputusan klinik
yang sesuai dan tepat waktu.
Partograf harus digunakan: (APN,2008 hal 55)
a. Untuk semua ibu dalam fase aktif kala satu persalinan dan merupakan
elemen penting dari asuhan persalinan. Partograf harus digunakan untuk
semua persalinan, baik normal maupun patologis. Partograf sangat
membantu penolong persalinan dalam memantau, mengevaluasi dan
membuat keputusan klinik, baik persalinan dengan penyulit maupun
yang tidak disertai dengan penyulit.
b. Selama persalinan dan kelahiran di semua tempat (rumah, puskesmas,
klinik bidan swasta, rumah sakit, d1l).
c. Secara rutin oleh semua penolong persalinan yang memberikan asuhan
persalinan kepada ibu dan proses kelahiran bayinya (Spesialis Obstetri,
Bidan, Dokter Umum, Residen dan Mahasiswa Kedokteran).
Penggunaan partograf secara rutin dapat memastikan bahwa ibu
dan bayinya mendapatkan asuhan yang aman, adekuat dan tepat waktu
Berta membantu mencegah terjadinya penyulit yang dapat mengancam
keselamatan jiwa mereka. (APN,2008 hal 55).
A. Pencatatan selama Fase Laten Kala Satu Persalinan
Seperti yang sudah dibahas di awal bab ini, kala satu persalinan
terdiri dan dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif yang diacu pada
pembukaan serviks: (APN,2008 hal 55).
1. Fase laten : Pembukaan serviks kurang dan 4 cm
2. Fase aktif : Pembukaan serviks dan 4 sampai 10 cm
Selama fase laten, semua asuhan, pengamatan dan pemeriksaan
harus dicatat. Hal ini dapat direkam secara terpisah, baik di catatan
kemauan persalinan maupun di Kartu Menuju Sehat (KMS) Ibu Hamil.
Tanggal dan waktu harus dituliskan setiap kali membuat catatan
selama fase laten persalinan. Semua asuhan dan intervensi juga harus
dicatatkan. (APN,2008 hal 56).
Kondisi ibu dan bayi juga harus dinilai dan dicatat secara
seksama, yaitu: (APN,2008 hal 56)
a. Denyut jantung janin: setiap 1/2jam
b. Frekuensi dan lamanya kontraksi uterus: setiap 1/2 jam
c. Nadir setiap 1/2 j am
d. Pembukaan serviks: setiap 4 jam
e. Penurunan bagian terbawah janin: setiap 4 jam
f. Tekanan darah dan temperatur tubuh: setiap 4 jam
g. Produksi urin, aseton dan protein: setiap 2 sampai 4 jam
Jika ditemui gejala dan tanda penyulit, penilaian kondisi ibu
dan bayi harus lebih sering dilakukan. Lakukan tindakan yang sesuai
apabila pada diagnosis disebutkan adanya penyulit dalam persalinan.
Jika frekuensi kontraksi berkurang dalam satu atau dua jam pertama,
nilai ulang kesehatan dan kondisi aktual ibu dan bayinya. Bila tidak
ada tanda-tanda kegawatan atau penyulit, ibu boleh pulang dengan
instruksi untuk kembali jika kontraksinya menjadi teratur,
intensitasnya makin k-uat dan frekuensinya meningkat. Apabila asuhan
persalinan dilakukan di rumah, penolong persalinan hanya boleh
meninggalkan ibu setelah dipastikan bahwa ibu dan bayinya dalam
kondisi baik. Pesankan pada ibu dan keluarganya untuk menghubungi
kembali penolong persalinan jika terjadi peningkatan frekuensi
kontraksi. (APN,2008 hal 56)
Rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang sesuai jika fase laten
berlangsung lebih dan 8 jam. (APN,2008 hal 56)
B. Pencatatan Selama Fase Aktif Persalinan: Partograf
Halaman depan partograf menginstruksikan observasi dimulai
pada fase aktif persalinan dan menyediakan lajur dan kolom untuk
mencatat hasil-hasil pemeriksaan selama fase aktif persalinan, yaitu:
(APN,2008 hal 56)
Informasi tentang ibu:
1. Nama, umur;
2. Gravida, para, abortus (keguguran);
3. Nomor catatan medik/nomor puskesmas;
4. Tanggal dan waktu mulai dirawat (atau jika di rumah, tanggal dan
waktu penolong persalinan mulai merawat ibu);
5. Waktu pecahnya selaput ketuban.
Kondisi janin:
a. DJJ;
b. warna dan adanya air ketuban;
c. penyusupan (molase) kepala janin.
Kemajuan persalinan:
a. pembukaan serviks;
b. penurunan bagian terbawah atau presentasi janin;
c. garis waspada dan garis bertindak.
Jam dan waktu:
a. waktu mulainya fase aktif persalinan;
b. waktu aktual saat pemeriksaan atau penilaian.
Kontraksi uterus:
a. frekuensi dan lamanya.
b. lama kontraksi (dalam detik)
Obat-obatan dan cairan yang diberikan:
a. oksitosin;
b. obat-obatan lainnya dan cairan IV yang diberikan.
Kondisi ibu:
a. nadi, tekanan darah dan temperatur tubuh;
b. urin (volume, aseton atau protein).
Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya (dicatat
dalam kolom yang tersedia di sisi partograf atau di catatan kemajuan
persalinan). (APN,2008 hal 56)
C. Mencatat temuan pada Partograf
1. Informasi tentang ibu
Lengkapi bagian awal (atas) partograf secara teliti pada saat
memulai asuhan persalinan. Waktu kedatangan (tertulis sebagai:
'jam atau pukul' pada partograf) dan perhatikan kemungkinan ibu
datang dalam fase laten. Catat waktu pecahnya selaput ketuban.
(APN,2008 hal 57)
2. Kondisi janin (APN,2008 hal. 57)
Bagan atas grafik pada partograf adalah untuk pencatatan
denyut jantung janin (DJJ), air ketuban dan penyusupan (kepala
janin).
a. Denyut jantung janin (APN,2008 hal 57)
Dengan menggunakan metode seperti yang diuraikan
pada bagian Pemeriksaan fisik dalam bab ini, nilai dan catat
denyut jantung janin (DJJ) setiap 30 menit (lebih sering jika
ada tanda-tanda gawat janin). Setiap kotak di bagian atas
partograf menunjukkan waktu 30 menit. Skala angka di
sebelah kolom paling kiri menunjukkan DJJ. Catat DJJ dengan
memberi tanda titik pada garis yang sesuai dengan angka yang
menunjukkan DJJ. Kemudian hubungkan yang satu dengan
titik lainnya dengan garis dan bersambung. (APN,2008 hal 57)
Kisaran normal DJJ terpapar pada partograf di antara
garis tebal pada angka 180 dan 100. Sebaiknya, penolong
harus waspada bila DJJ mengarah hingga di bawah 120 atau di
atas 160. Lihat Tabel 2-1 untuk tindakantindakan segera yang
harus dilakukan jika DJJ melampaui kisaran normal ini. Catat
tindakan-tindakan yang dilakukan pada ruang yang tersedia di
salah satu clan kedua sisi partograf. (APN,2008 hal 58)
b. Warna dan adanya air ketuban (APN,2008 hal 58)
Nilai air kondisi ketuban setiap kali melakukan periksa
dalam dan nilai warna air ketuban jika selaput ketuban pecah.
Catat temuan-temuan dalam kotak yang sesuai di bawah lajur
DJJ. Gunakan lambang-lambang berikut ini:
a. U : selaput ketuban utuh (belum pecah)
b. J : selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban jernih
c. M : selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur
mekonium
d. D : selaput ketuban sudah pecah dan air ketuban bercampur
darah
e. K: selaput ketuban sudah pecah tapi air ketuban tidak
mengalir lagi ("kering")
Mekonium dalam cairan ketuban tidak selalu
menunjukkan adanya gawat janin. Jika terdapat mekonium,
pantau DJJ dengan seksama untuk mengenali tanda-tanda
gawat janin selama proses persalinan. Jika ada tanda-tanda
gawat janin (denyut jantung janin < 100 atau > 180 kali per
menit) maka ibu harus segera dirujuk. (APN,2008 hal 58)
Tetapi jika terdapat mekonium kental, segera rujuk ibu
ke tempat yang memiliki kemampuan penatalaksanaan gawat
darurat obstetri dan bayi baru lahir. (APN,2008 hal 58)
c. Penyusupan (Molase) Tulang Kepala Janin
Penyusupan adalah indikator penting tentang seberapa
jauh kepala bayi dapat menyesuaikan diri terhadap bagian
keras (tulang) panggul ibu. Semakin besar derajat penyusupan
atau tumpang tindih antar tulang kepala semakin menunjukkan
risiko disproporsi kapala-panggul (CPD). Ketidak-mampuan
untuk berakomodasi atau disproporsi ditunjukkan melalui
derajat penyusupan atau tumpang-tindih (molase) yang berat
sehingga tulang kepala yang saling menyusup, sulit untuk
dipisahkan. Apabila ada dugaan disproprosi kepala-panggul
maka penting untuk tetap memantau kondisi janin Berta
kemajuan persalinan. Lakukan tindakan pertolongan awal
yang sesuai dan rujuk ibu dengan dugaan proporsi kepala-
panggul (CPD) ke fasilitas kesehatan rujukan. (APN,2008 hal
58)
Setiap kali melakukan periksa dalam, nilai penyusupan
antar tulang (molase) kepala janin. Catat temuan yang ada di
kotak yang sesuai di bawah lajur air ketuban. (APN,2008 hal
58)
Gunakan lambang-lambang berikut ini: (APN,2008 hal 58)
0 : Tulang-tulang kepala janin terpisah, sutura dengan mudah
dapat dipalpasi
1 : Tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan
2 : Tulang-tulang kepala janin saling tumpang tindih tetapi
masih dapat dipisahkan
3 : Tulang-tulang kepala janin tumpang tindih dan tidak dapat
dipisahkan
Kemajuan Persalinan
Kolom dan lajur kedua pada partograf adalah untuk
pencatatan kemajuan persalinan. Angka 0 – 10 yang tertera di
kolom paling kiri adalah besarnya dilatasi serviks. Nilai setup
angka sesuai dengan besarnya dilatasi serviks dalam satuan
centimeter dan menempati lajur dan kotak tersendiri.
Perubahan nilai atau perpindahan lajur satu ke lajur yang lain
untuk menunjukkan penambahan dilatasi serviks sebesar 1 cm.
Pada lajur dan kotak yang mencatat penurunan bagian
terbawah janin tercantum angka 1-5 yang sesuai dengan
metode perlimaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya
(Menentukan Penurunan Janin). Setiap kota segi empat atau
kubus menunjukkan waktu 30 menit untuk pencatatan waktu
pemeriksaan, denyut jantung janin, kontraksi uterus dan
frekuensi nadi ibu. (APN,2008 hal 59)
1. Pembukaan serviks (APN,2008 hal 59)
Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di
bagian Pemeriksaan Fisik dalam bab ini, nilai dan catat
pembukaan serviks setiap 4 jam (lebih sering dilakukan jika
ada tanda-tanda penyulit). Saat ibu berada dalam fase aktif
persalinan, catat pada partograf setiap temuan dan setiap
pemeriksaan. Tanda 'X' hares dicantumkan di garis waktu
yang sesuai dengan lajur besarnya pembukaan serviks.
Perhatikan: (APN,2008 hal 59)
a. Pilih angka pada tepi kiri luar kolom pembukaan serviks
yang sesuai dengan besarnya pembukaan serviks pada
fase aktif persalinan yang diperoleh dan hasil periksa
dalam.
b. Untuk pemeriksaan pertama pada fase aktif persalinan,
temuan (pembukaan serviks) dan hasil periksa dalam
harus dicantumkan pada garis waspada. Pilih angka yang
sesuai dengan bukaan serviks (hasil periksa dalam) dan
cantumkan tanda 'X' pada ordinat atau titik silang garis
dilatasi serviks dan garis waspada
c. Hubungkan tanda 'X' clan setiap pemeriksaan dengan
garis utuh (tidak terputus).
Contoh: Perhatikan contoh partograf untuk Ibu
Rohati
Pada pukul 17. 00, pembukaan serviks 5 cm dan ibu
ada dalam fase aktif Pembukaan serviks dicatat di
"garis waspada" dan waktu pemeriksaan tuIiskan di
bawahnya. (APN,2008 hal 59)
2. Penurunan bagian terbawah janin
Dengan menggunakan metode yang dijelaskan di
bagian Pemeriksaan Fisik. Setiap kali melakukan periksa
dalam (setiap 4 jam), atau lebih Bering (jika ditemukan
tanda-tanda penyulit). Cantumkan hasil pemeriksaan
penurunan kepala (perlimaan) yang menunjukkan seberapa
jauh bagian terbawah janin telah memasuki rongga
panggul. Pada persalinan normal, kemajuan pembukaan
serviks selalu diikuti dengan turunnya bagian terbawah
janin. Tapi adakalanya, penurunan bagian terbawah janin
baru ter adi setelah pembukaan serviks mencapai 7 cm.
(APN,2008 hal 60)
Tulisan "Turunnya kepala" dan garis tidak putus dan
0-5, tertera di sisi yang sama dengan angka pembukaan
serviks. Berikan tanda '0' yang ditulis pada garis waktu
yang sesuai. Sebagai contoh, jika hasil pemeriksaan palpasi
kepala di atas simfisis pubis adalah 4/5 maka tuliskan tanda
"0" di garis angka 4. Hubungkan tanda '0' dan setiap
pemeriksaan dengan garis tidak terputus.(APN,2008 hal 60)
Contoh: catatan penurunan kepala pada partograf untuk Ibu
Rohati
Pada pukul 17.00 penurunan kepala 3/5
Pada pukul 2 1. 00 penurunan kepala 1/5
3. Garis waspada dan garis bertindak
Garis waspada dimulai pada pembukaan serviks 4
cm dan berakhir pada titik di mana lengkap diharapkan
terjadi jika laju pembukaan adalah 1 cm per jam. Pencatatan
selama fase aktif persalinan harus dimulai di garis waspada.
Jika pembukaan serviks mengarah ke sebelah kanan garis
waspada (pembukaan kurang dan 1 cm per jam), maka
harus dipertimbangkan adanya penyulit (misalnya fase aktif
yang memanjang, serviks kaku, atau inersia uteri hipotonik,
d1l.). Pertimbangkan perlunya melakukan intervensi
bermanfaat yang diperlukan, misalnya: persiapan rujukan ke
fasilitas kesehatan rujukan (rumah sakit atau puskesmas)
yang memiliki kemampuan untuk menatalaksana penyulit
dan gawat darurat obstetri. Garis bertindak tertera sejajar
dan di sebelah kanan (bedarak 4 jam) garis waspada. Jika
pembukaan serviks telah melampaui dan berada di sebelah
kanan garis bertindak maka hal ini menunjukkan perlu
dilakukan tindakan untuk menyelesaikan persalinan.
Sebaiknya, Ibu harus sudah berada di tempat rujukan
sebelum garis bertindak terlampaui. (APN,2008 hal 61)
Jam dan waktu
1. Waktu Mulainya Fase Aktif Persalinan
Di bagian bawah partograf (pembukaan serviks dan
penurunan) tertera kotak-kotak yang diberi angka 1-12.
Setiap kotak menyatakan sate jam sejak dimulainya fase
aktif persalinan. (APN,2008 hal 61)
2. Waktu Aktual Saat Pemeriksaan atau Penilaian
Di bawah lajur kotak untuk waktu mulainya fase aktif,
tertera kotak-kotak untuk mencatat waktu aktual saat
pemeriksaan dilakukan. Setiap kotak menyatakan satu
jam penuh dan berkaitan dengan dua kotak waktu tiga
puluh menit yang berhubungan dengan lajur untuk
pencatatan pembukaan serviks. DJJ di bagian atas dan
lajur kontraksi dan nadi ibu di bagian bawah. Saat ibu
masuk dalam fase aktif persalinan, cantumkan
pembukaan serviks di garis waspada. Kemudian catatkan
waktu aktual pemeriksaan ini di kotak waktu yang
sesuai. (APN,2008 hal 61)
Sebagai contoh, jika hasil periksa dalam menunjukkan
pembukaan serviks adalah 6cm pada pukul 15.00,
cantumkan tanda X di garis waspada yang sesuai dengan
lajur angka 6 yang tertera di sisi luar kolom paling kiri
dan catat waktu aktual di kotak pada lajur waktu di
bawah lajur pembukaan (kotak ketiga dan kiri).
(APN,2008 hal 61)
Kontraksi uterus
Di bawah lajur waktu partograf, terdapat lima kotak
dengan tulisan "kontraksi per 10 menit" di sebelah luar
kolom paling kiri. Setiap kotak menyatakan satu
kontraksi. Setiap 30 menit, raba dan catat jumlah
kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kontraksi dalam
satuan detik. Nyatakan jumlah kontraksi yang terjadi
dalam waktu 10 menit dengan cara mengisi kotak
kontraksi yang tersedia dan disesuaikan dengan angka
yang mencenninkan temuan dan hasil pemeniksaan
kontraksi. Sebagai contoh jika ibu mengalami 3
kontraksi dalam waktu satu kah 10 menit, maka lakukan
pengisian pada 3 kotak kontraksi. (APN,2008 hal 61)
Nyatakan lamanya kontraksi dengan:
Beri titi-titik di kotak yang sesuai untuk menyatakan
kontraksi lamanya kurang dari 20 detik.
Beri garis-garis di kotak yang sesuai untuk menyatakan
kontraksi yang lamanya 20 – 40 detik
Isi penuh kotak yang sesuai untuk menyatakan kontraksi
yang lamanya lebih dari 40 detik.
Dalam waktu 30 menit pertama terjadi dua
kontraksi dalam 10 menit dan lamanya kurang dari 20
detik
Dalam waktu 30 menit kelima terjadi tiga kontraksi
dalam waktu 10 menit dan lamanya menjadi 20-40 detik
Dalam waktu 30 menit ketujuh terjadi lima kontraksi
dalam 10 menit dan lamanya lebih dari 40 detik
(APN,2008 hal 63)
Catat frekuensi dan lamanya kontraksi uterus setiap 30 menit dalam
5
4
3
2
1
0
persalinan aktif (APN,2008 hal 62)
INGAT:
1. Periksa frekuensi dan lama kontraksi uterus setiap jam selama
fase laten dan setiap 30 menit selama fase aktif.
2. Nilai frekuensi dan lama kontraksi yang terjadi dalam 10 menit
observasi
3. Catat lamanya kontraksi menggunakan lambang yang sesuai:
< 20 detik 20-40 detik > 40 detik
4. Catat temuan-temuan di kotak yang sesuai dengan waktu
penilaian.
(APN,2008 hal 62)
Obat-obatan dan cairan yang diberikan (APN,2008 hal 63)
Di bawah lajur kotak observasi kontraksi uterus tertera lajur
kotak untuk mencatat oksitosin, obat-obat lainnya dan cairan IV.
1. Oksitosin
Jika tetesan (drip) oksitosin sudah dimulai, dokumentasikan
setiap 30 menit jumlah unit oksitosin yang diberikan per volume
cairan IV dan dalam satuan tetesan per menit.
2. Obat-obatan lain dan cairan IV
Catat semua pemberian obat-obatan tambahan dan/atau
cairan IV dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya.
Kondisi Ibu (APN,2008 hal 63)
Bagian terbawah lajur dan kolom pada halaman depan
partograf, terclapat kotak atau ruang untuk mencatat kondisi kesehatan
dan kenyamanan ibu selama persalinan.
1. Nadi, tekanan darah dan suhu tubuh (APN,2008 hal 63)
Angka di sebelah Uri bagian partograf ini berkaitan dengan nadi
dan tekanan darah ibu.
a. Nilai dan catat nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif
persalinan (lebih sering jika diduga adanya penyulit). Beri
tanda titik (•) pada kolom waktu yang sesuai
b. Nilai dan catat tekanan darah ibu setiap 4 jam selama fase aktif
persalinan (lebih sering jika diduga adanya penyulit). Beri
tanda panah pada partograf pada kolom waktu yang sesuai:
c. Nilai clan catat temperatur tubuh ibu (lebih sering jika terjadi
peningkatan mendadak atau diduga adanya infeksi) setiap 2 jam
clan catat temperatur tubuh dalam kotak yang sesuai.
2. Volume urin, protein atau aseton (APN,2008 hal 63)
Ukur clan catat jumlah produksi urin ibu sedikitnya setiap
2 jam (setiap kali ibu berkemih). Jika memungkinkan, setiap kali
ibu berkemih, lakukan pemeriksaan aseton dan protein dalam urin.
Asuhan, pengamatan dan keputusan klinik lainnya
Catat semua asuhan lain, hasil pengamatan dan keputusan
klinik di sisi luar kolom partograf, atau buat catatan terpisah
tentang kemajuan persalinan. Cantumkan juga tanggal dan waktu
saat membuat catatan persalinan. (APN,2008 hat 63)
Asuhan, pengamatan dan/atau keputusan klinik mencakup:
a. Jumlah cairan per oral yang diberikan
b. Keluhan sakit kepala atau pengelihatan (pandangan) kabur
c. Konsultasi dengan penolong persalinan lainnya (Obgin,
bidan, dokter umum)
d. Persiapan sebelum melakukan rujukan
e. Upaya Rujukan
INGAT: (APN,2008 hal 64)
1. Fase laten persalinan didefinisikan sebagai pembukaan serviks
kurang dari 4 cm. Biasanya fase laten berlangsung tidak lebih
dari 8 jam.
2. Dokumentasikan asuhan, pengamatan dan pemeriksaan selama
fase laten persalinan pada catatan kemajuan persalinan yang
dibuat secara terpisah atau pada kartu KMS.
3. Fase aktif persalinan didefinisikan sebagai pembukaan serviks
dan 4 sampai 10 cm. Biasanya pembukaan serviks selama fase
aktif sedikitnya 1 cm/jam.
4. Saat persalinan maju dan fase laten ke fase aktif, catatkan hasil
periksa dalam (pembukaan serviks) pada garis waspada di
partograf.
5. Jika ibu datang pada saat fase aktif persalinan, langsung
catatkan pembukaan serviks pada garis waspada.
6. Pada persalinan tanpa penyulit, catatan pembukaan serviks
umumnya tidak akan melewati garis waspada.
D. Pencatatan pada lembar belakang Partograf
Halaman belakang partograf merupakan bagian untuk mencatat
hal-hal yang terjadi selama proses persalinan dan kelahiran bayi, serta
tindakan-tindakan yang dilakukan sejak kala I hingga kala IV dan bayi
baru lahir). Itulah sebabnya bagian ini disebut sebagai Catatan Persalinan.
Nilai dan catatkan asuhan yang diberikan kepada ibu selama masa nifas
(terutama pada kala empat persalinan) untuk memungkinkan penolong
persalinan mencegah terjadinya penyulit dan membuat keputusan klinik
yang sesuai. Dokumentasi ini sangat penting, terutama untuk membuat
keputusan klinik (misalnya, pencegahan perdarahan pada kala IV
persalinan). Selain itu, catatan persalinan (lengkap dan benar) dapat
digunakan untuk menilai/memantau sejauh mana pelaksanaan asuhan
persalinan yang aman dan bersih telah dilakukan. (APN,2008 hal 64)
Catatan persalinan adalah terdiri dan unsur-unsur berikut:
(APN,2008 hal 64)
a. Data atau Informasi Umum
b. Kala I
c. Kala 11
d. Kala III
e. Bayi baru lahir
f. Kala IV
Cara pengisian:
Berbeda dengan pengisian halaman depan (harus segera diisi di
setiap pemeriksaan), pengisian data di lembar belakang partograf baru
1. Tanggal: .......................................................................................
2. Nama bidan...................................................................................3. Tempat persalinan:.......................................................................
Rumah Ibu PuskesmasPolinde Rumah SakitKlinik Swasta Lainnya: .......................................................
4. Alamat tempat persalinan.............................................................
5. Catatan: rujuk, kala: I/II/111/IV...................................................
6. Alasan merujuk.............................................................................7. Tempat rujukan.............................................................................8. Pendamping pada saat merujuk-...................................................
bidan temansuami dukun
9. partograf melewati garis bahaya : Y/T………………………........10. Masalah lain, sebutkan : ………………………………………….11. Penatalaksanaan masalah tersebut ……………………….………12. Hasilnya : …………………………………………………………
dilengkapi setelah seluruh proses persalinan selesai Informasi yang
dicatatkan di halaman belakang partograf akan meliputi unsur-unsur beikut
ini: (APN,2008 hal 64)
Data dasar
Data dasar terdiri dari tanggal, nama bidan, tempat persalinan,
alamat tempat persalinan, catatan dan alasan merujuk, tempat rujukan dan
pendamping pada saat merujuk. Isikan data pada masing-masing tempat
yang telah disediakan, atau dengan cara memberi tanda pada kotak di
samping jawaban yang sesuai. Untuk pertanyaan nomor 5,lingkari jawaban
yang sesuai dan untuk pertanyaan nomor8 jawaban bisa lebih dari satu.
(APN,2008 hal 67) Data dasar yang perlu dipenuhi adalah sebagai berikut:
Kala I
Kala I terdiri dari pertanyaan-pertanyaan tentang Partograf saat
melewati garis waspada, masalah-masalah lain yang timbul,
penatalaksanaannya, dan basil penatalaksanaan. tersebut. Untuk
pertanyaan nomor 9, lingkari jawaban yang sesuai. Pertanyaan lainnya
hanya diisi jika terdapat masalah lainnya dalam persalinan.
Pertanyaan pada kala I adalah sebagai berikut: (APN,2008 hal 67)
Kala II
Kala II terdiri dan episiotomi, pendamping persalinan, gawat janin,
distosia bahu, masalah lain, penatalaksanaan masalah dan hasilnya. Beri
tanda pada kotak di samping jawaban yang sesuai. Bila
pertanyaan nomor 13, jika jawabannya "Ya", tulis indikasinya. Untuk
nomor 15 dan 16 jika jawabannya "Ya", isi jenis tindakan yang
dilakukan. Khusus pada nomor 15 tambahkan ruang barn untuk
menekankan upaya deteksi dini terhadap gangguan kondisi kesehatan
janin, atau tidak dapat dievaluasi). Bagian ini dapat menjadi pelengkap
bagi informasi pada kotak 'Ya' maupun 'Tidak' untuk pertanyaan nomor
15. Jawaban untuk pertanyaan nomor 14, mungkin lebih dan 1. Untuk
`masalah lain' pada normor 17 hares dijelaskan jenis masalah yang
terjadi. (APN,2008 hal 68)
Kala III
WaktuTekanan
darahNadi Suhu
Tinggi fundusUteri
Kontraksiuterus
Kandungkemih
Perdarahan
Data untuk Kala III terdiri dari lamanya kala 111, pemberian oksitosin,
penegangan tali pusat terkendali, rangsangan pada fundus, kelengkapan
plasenta saat dilahirkan, retensio plasenta yang > 30 menit, laserasi,
atonia uteri, jumlah perdarahan, masalah lain, penatalaksanaan dan
hasilnya. Isi jawaban pada tempat yang disediakan dan beri tanda
pada kotak di samping jawaban yang sesuai. Untuk nomor 25,26 dan 28
lingkari jawaban yang benar. (APN,2008 hal 69)
perdarahan pascapersalinan. Pemantauan kala IV dilakukan setiap 15
menit dalam I jam pertama setelah melahirkan, dan setiap 30 menit
pada satu jam berikutnya. Isikan hasil pemeriksaan pada kolom atau
ruang yang sesuai. Bila timbul masalah selama kala IV, tuliskan jenis
dan cara menangani masalah tersebut pada bagian masalah kala IV dan
bagian berikutnya. Bagian yang digelapkan tidak usah diisi. (APN,2008
hal 70)
Tinggi fundus, kontraksi uterus, kandung kemih dan perdarahan.
Pemantauan pada kala IV ini sangat penting terutama untuk menilai
deteksi dini risiko atau kesiapan penolong mengantisipasi komplikasi
Catatan semua temuan selama persalinan kala empat di bagian ini:
(APN,2008 hal 71)
Masalah kala IV: .................................................................................
Penatalaksanaan masalah tersebut-
Hasilnya-
3. Bayi Baru Lahir
a. Pengertian
Asuhan Bayi Baru Lahir (BBL) adalah asuhan yang diberikan
pada bayi tersebut selama jam pertama setelah kelahiran walaupun
sebagian besar proses persalinan terfokus pada ibu tetapi karena proses
tersebut merupakan proses pengeluaran hasil kehamilan (bayi) maka
penatalaksanaan suatu persalinan baru dikatakan berhasil apabila
selama ibu dan bayi yang dilahirkannya juga dalam kondisi yang
optimal. (Buku Panduan Praktis Yankes Maternal dan Neonatal, 2008).
Neonatal adalah masa bayi selama 28 hari pertama setelah bayi
lahir (usia 0-28 hari). (Pusdiknakes, 2008)
b. Fisiologi
Saat bayi dilahirkan dan sirkulasi fetoplasenta berhenti
berfungsi, bayi mengalami perubahan fisiologis yang besar sekali dan
sangat cepat. Segera setelah pola pernafasan bergeser dari satu
inspirasi episodic dangkal menjadi pola inhalasi lebih dalam dan
teratur.
Neonatus mulai bernafas dan menangis segera setelah lahir
yang menunjukkan terbentuknya mekanisme pada thoraks sewaktu
melalui jalan lahir. Penurunan kadar oksigen dan kenaikan
karbondioksida merangsang kemoreseptor pada sinus karotis (stimulasi
kimiawi) dan rangsangan dingin di daerah muka dapat merangsang
permulaan gerakan pernafasan (stimulasi sensorik).
Dengan terpotongnya tali pusat bayi maka sirkulasi plasenta
terhenti. Aliran darah ke atrium kanan menurun sehingga tekanan
jantung menurun, tekanan darah di aorta hilang sehingga tekanan
jantung kiri meningkat. Paru-paru mengalami retensi dan aliran darah
keparu-paru meningkat yang menyebabkan tekanan ventrikel kiri
meningkat. Hal tersebut mengakibatkan duktus botalii tidak berfungsi
dan foramen ovale menutup.
Dalam 24 jam pertama neonatus akan mengeluarkan tinja yang
berwarna hijau kehitam-hitaman. Ini dinamakan mekonium. Frekuensi
pengeluaran tinja pada neonatus dipengaruhi oleh pemberian makanan
atau minuman. Enzim pada saluran pencernaan biasanya sudah ada
pada neonatus kecuali enzim amilase.
Enzim hepar pada neonatus belum aktif betul misalnya enzim
G6PD yang berfungsi dalam sintesis bilirubin sehingga neonatus
memperlihatkan gejala ikterus fisiologis.
Neonatus memiliki luas permukaan tubuh yang luas sehingga
metabolisme perkilogram berat badannya besar. Pada jam-jam
pertama, energi didapatkan dari pembakaran karbohidrat dan pada hari
kedua energi berasal dari pembakaran lemak.
Apabila neonatus mengalami hipotermia, tubuhnya akan
mengadakan penyesuaian suhu terutama dengan cara pembakaran
cadangan lemak coklat yang memberikan energi lebih banyak dari
pada lemak biasa.
Hormon yang didapatkan dari ibu masih berfungsi, hal ini
terlihat dari adanya pembesaran kelenjar mammae, kadang-kadang
adanya pengeluaran darah dari vagina yang menyerupai darah haid.
Ginjal pada neonatus baru bisa memproses air yang didapat
setelah 5 hari kelahiran. Ginjal pada neonatus belum sepenuhnya
berfungsi karena jumlah nefronnya masih belum sebanyak orang
dewasa dan tidak seimbangnya antara luas permukaan glomerulus dan
volume tubulus proksimal. Aliran darah ginjal pada neonatus relatif
kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa.
c. Penilaian Klinik
Tujuannya adalah mengetahui derajat vitalitas dan mengukur
reaksi bayi terhadap tindakan resusitasi. Derajat vitalitas bayi adalah
kemampuan sejumlah fungsi tubuh yang bersifat esensial dan
kompleks untuk berlangsungnya kelangsungan hidup bayi seperti
pernapasan, denyut jantung, sirkulasi dan refleks-refleks primitif
seperti menghisap dan mencari putting susu.
d. Penanganan bayi baru lahir
Tujuan utama perawatan bayi segera sesudah lahir, ialah:
1) Membersihkan jalan napas
2) Memotong dan merawat tali pusat
3) Mempertahankan suhu tubuh bayi
4) Identifikasi
5) Pencegahan infeksi
Pembersihan jalan nafas, perawatan tali pusat, perawatan mata dan
identifikasi adalah rutin segera dilakukan, kecuali bayi dalam
keadaan kritis dan dokter memberikan instruksi khusus.
e. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada bayi baru lahir
Penilaian bayi baru lahir dilakukan dengan sistem nilai APGAR/Apgar
Score yaitu:
Tabel 12. Penilaian bayi baru lahir dilakukan dengan sistem nilai
APGAR/Apgar Score
NoAspek Yang
Dinilai
Nilai
0 1 2
1
2
3
4
5
Apperence
(Penampilan)
Pulse (Denyut
jantung)
Grimace (Reaksi
terhadap
rangsangan)
Activity (Otot)
Respiration
(Pernafasan)
Biru/pucat
Tidak ada
Tidak ada
Lemas
Tidak
bernafas
Badan merah,
ekstremitas
biru
Tidak teratur
<100x/mnt
Menyeringai
Fleksi sedikit
Lemah
Seluruh badan dan
ekstremitas merah
Teratur >100x/mnt
Menangis kuat
Aktifitas kuat
Teratur
Batasan normal ukuran kepala :
1) Diameter suboksipito – bregmatika (± 9,50 cm), bila dilahirkan
dalam presentasi belakang kepala.
2) Diameter oksipito – frontalis (± 11,75 cm), bila dilahirkan dalam
presentasi puncak kepala.
3) Diameter oksipito – mentalis (± 13,50 cm), bila dilahirkan dalam
presentasi dahi.
4) Diameter submento – bregmatikus (± 9,50 cm), bila dilahirkan
dalm presentasi muka.
5) Diameter biparietalis (± 9,50 cm).
6) Diameter bitemporalis (± 8 cm)
Disamping diameter-diameter yang merupakan garis lurus
terdapat sirkumferensia yang merupakan ukuran lingkaran pada bidang
yang bersangkutan, dinamakan :
1) Sirkumferensia suboksipito – bregmatikus (32 cm)
2) Sirkum ferensia submento – bregmatikus (± 32 cm)
3) Sirkumferensia oksipito – frontalis (± 34 cm)
4) Sirkumferensia mento – oksipitalis (± 35 cm)
Letak, presentasi, posisi dan sikap badan janin:
1) Letak janin ialah bagaimana sumbu janin berada terhadap sumbu
ibu, yaitu letak memanjang, letak lintang atau letak oblik (miring)
2) Sikap badan (attitude) hubungan bagian-bagian janin terhadap
sumbunya, khususnya terhadap tulang punggungnya, misalnya
fleksi.
3) Presentasi ialah bagian janin yang ada dibawah uterus, misalnya
presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu dan
presentasi muka.
4) Posisi ialahuntuk menetapkan apakah bagian janin yang ada di
bawah uterus sebelah kiri,sebelah kanan, sebelah belakang atau
depan terhadap sumbu tubuh ibu, misalnya ubun-ubun kiri depan.
Menilai refleks pada bayi :
a. Refleks babinski : menggores permukaan plantar kaki dengan
benda runcing, (+) bila ibu jari akan terangkat, jari lainnya
meregang.
b. Refleks rooting : menyentuhkan sesuatu ke sudut mulut. (+) bila
bayi menengok ke arah rangsangan dan berusaha memasukannya
ke dalam mulut.
c. Refleks suching : (+) bila bayi menghisap kuat.
d. Grasp refleks : meletakkan sesuatu di telapak tangan bayi, (+) bila
bayi menggenggam benda yang diletakkan pada telapak tangan.
e. Refleks moro : mengejutkan bayi, (+) bila kaget disertai lengan
direntangkan dalam posisi abduksi ekstensi dan tangan disertai
gerakan lengan adduksi dan fleksi.
f. Refleks tonic neck : menengokkan kepala bayi ke kiri/ ke kanan,
(+) bila kepala ditengokkan ke kanan, (+) bila kepala ditengokkan
ke kanan, anggota gerak bagian kanan akan melakukan ekstensi
dan anggota gerak lainnya melakukan fleksi.
g. Refleks plantar grasp : meletakkan sesuatu pada telapak kaki bayi,
(+) bila terjadi fleksi pada jari – jari kaki.
h. Refleks palmar grasp : meletakkan sesuatu pada telapak tangan
bayi, (+) bila terjadi felksi pada jari – jari tangan.
Pemeriksaan fisik :
a. Kepala
1) Lingkar kepala oksipito – frontal harus selalu diukur dan
dicatat pada semua neonatus.
2) Deteksi apakah ada caput suksedanum (cairan efusion terletak
di atas periosteum dan terdiri dari cairan edema, melewati batas
sutura, tidak tamapk jelas), atau sefalohematoma (cairan yang
berupa darah terletak di bawah periosteum dan tidak melewati
sutura, tamapk jelas dan lembek jika diraba).
3) Sutura tulang tengkorak harus diperiksa untuk melihat apakah
sutura melebar atau tumapng tindih. Fontanella yang terbuka
penuh menunjukkan adanya kenaikan tekanan intrakranial
(TIK) yang bisa disebabkan oelh perdarahan intrakranial,
edema otak, atau hidrosefalus.
4) Periksa adanya massa massa di garis tengah yang keluar dari
tulang kepala mungkin suatu omfalokel dan perlu pemeriksaan
yang lengkap.
5) Ubun – ubun yang cekung menandakan bayi dehidrasi dan
terlalu cembung disertai badan demam menandakan bayi
terkena infeksi.
b. Mata
6) Adanya perdarahan subkonjungtiva, mata yang menonjol,
katarak, kesimetrisan kedua mata, keluarnya sekret mata,
pergerakan kelopak mata yang seimbang.
c. Telinga
1) Posisi, rotasi dan letak telinga harus dicatat. Letak telinga yang
lebih rendah harus cepat diperiksa dengan teliti kemungkinan
adanya tanda dismorfik lainnya.
2) Pada bayi sangat prematur, pinnanya pendek, datar, dan mudah
terlipat ke belakang.
3) Pada bayi matur, heliks luar dari pinna akan membentuk
kurvatura yang jelas.
4) Telinga harus diamati dengan teliti untuk memastikan tidak ada
kelainan pada kanalis auditoris eksterna.
d. Mulut
Pemeriksaan yang harus diperiksa meliputi lengkung palatum dan
bibir (labioskisis atau labiognatopalatoskisis), bentuk dan gerakan
lidah, adanya massa abnormal di daerah mulutdan faring
membutuhkan perhatian segera terhadap kemungkinan terjadi
obstruksi jalan nafas.
e. Leher
Apakah ada gumapalan atau pembengkakan pada leher, deteksi
adanya kemungkinan hematoma sternokleidomastoideus, duktus
tiroglosus, higroma koli.
f. Dada
1) Bentuk, pembesaran buah dada, adanya massa pada dinding
dada.
2) Pernafasan : nafas yang bunyi (grunting) terjadi karena udara
yang dikeluarkan bayi mengenai glotis yang tertutup sebagian
dan merupakan petunjuk terjadinya proses – proses yang
menyebabkan kolaps atau atelektasis. Stridor terjadi karena
berbagai sebab obstruksi jalan nafas, akan tetapi pada bayi
yang pernapasannya sangat lemah mungkin tidak terdengar
atau sulit didiagnosis.
3) Gerakan dinding dada yang asimetris pada pernafasan tterjadi
pada beberapa lesi diafragma atau ruangan intra pleura
unilateral. Retraksi supra sernal bisa terjadi pada distres
respirasi berat.
4) Mendengarkan suara jantung bayi dengan menggunakan
stetoskop, irama dan keteraturannya untuk mendeteksi kelainan
bunyi jantung, normal : 120 – 160 kali/menit.
5) Pernafasan normalnya : 40-60 kali/menit.
g. Abdomen
1) Inspeksi apakah ada pembesaran pada perut ( membuncit yang
terjadi kemungkinan karena pembesaran hati, limfe, tumor,
asites). Pembesaran hati tampak dari pemebesaran 1-2 cm di
bawah batas kosta kanan. Sedang limpa biasanya tidak teraba.
2) Hernia diafragmatika dapat menyebabkan abdomen
membentuk skapoid akibat protrusi isi abdomen ke dalam
rongga toraks. Usu yang tampak di permukaan usus
memberikan adanya obstruksi usus, khususnya bila terjadi
emesis bilius (muntah empedu)atau aspirat lambung.
3) Periksa tali pusat, jangan sampai terjadi pedarahan dari tali
pusat, bernanah, ataupun berbau. Permukaan tali pusat juga
perlu diperhatikan, warna kemerahan disertai suhu meningkat
merupakan tanda infeksi tali pusat.
h. Alat kelamin
1) Wanita : bila cukup bulan. labia mayora lebih menonjol
dibandingkan labia minora dan umumnya menutupi labia
minora. Tonjolan mukosa vagina umumnya tejadi karena
pengaruh hormonalibu terhadap janin. Pada bayi prematur,
labia minoranya lebih menonjol dan klitoris relatif mengalami
protusi ke dalam lipatan labia. Pada bayi wanita normalnya
gonad berada dalam kanalis inguinalis atau lipatan labia yang
tidak teraba.
2) Laki – laki : harus diperiksa apakah ada hipospadia atau
epispodia. Penis yang terlalu kecil menunjukkan
hipopituitarisme. Testis bayi laki – laki cukup umur biasanya
berada dalam kantong skrotum. Penurunan skrotum yang tidak
komplet dan testis pada kanalis inguinalis dapat diketahui
melalui palpasi.
3) Pastikan pula, bahwa tidak ada kelainan, misalnya bayi wanita
tidak mengalami maskulinisasi, atau bayi yang memiliki alat
kelamin dua, jenis kelamin tidak dapat ditentukan samapi
dilakukan pemeriksaan yang lebih komplit lagi.
i. Punggung
Punggung harus diinspeksi dan kolumna vertebralis harus
dipalpasi. Harus dicatat keabnormalannya seperti:
meningomielokel, skoliosis dan defek kulit pada linea mediana.
Deteksi pula adanya spina bifida, pilonidal sinus atau dimple.
j. Ekstremitas
Inspeksi yang cermat biasanya cukup untuk memastikan apakah
bentuk ekstremitas baik. Beberapa abnormalitas struktur yang jelas
atau pemendekkan anggota gerak dapat dievaluasi lebih lanjut
dengan palpasi dan pemeriksaan radigrafi. Harus dicatat juga
kontraktur sendi, asimetris, atau distorsi. Abnormalitas jari – jari
(pemendekkan, lancip, sindaktili, polidaktili), lipatan palmar,
hipoplasi kuku merupakan petunjuk penting adanya sindrom
dismorfik.
k. Anus
Diperhatikan apakah ada lubang pada anus atau tidak, ini bisa kita
tunggu sampai bayi mengeluarkan mekonium dalam 24 jam
(asuhan sayang bayi). Pastikan tidak terjadi atresia ani dan
obstruksi usus.
l. Kulit
1) Pada bayi prematur (usia kehamilan 23 –28 minggu) dengan
sedikit lemak subkutan, kulit bayi akan transulen dan terlihat
vena –vena superfisial. Karena stratum korneum sangat tipis,
kulit bayi prematur mudah terluka oleh karen atindakan atau
manipulasi yang tampaknya tidak berbahaya sehingga
menyebabkan kerusakan stratum korneum dan permukaan
kasar.
2) Saat usia kehamilan 35 –36 minggu bayi dilapisi verniks.
Lapisan verniks tipis muncul pada kehamilan matur dan
biasanya menghilang pada postmatur.
3) Bayi postmatur memiliki kulit seperti kertas dengan kerut –
kerut tajam pada badan dan ekstremitas. Pada bayi postmatur
juga terdapat kuku jari atau pengelupasan kulit pada distal
ekstremitas.
4) Kulit bayi juga ditumbuhi oleh lanugo, yang banyak terdapat
pada punggung.
5) Perlu diinspeksi seluruh kulit untuk mencari adanya tanda lahir,
ataupun bercak-bercak pada kulit seperti milia (papula
keputihan 1 –2 mm, umumnya ditemukan pada wajah bayi) dan
bercak mongol (suatu daerah hiperpigementasi yang tidak
menonjol (datar), lebih banyak terjadi di seluruh pantat atau
badan; umumnya terjadi pada bayi kulit hitam atau oriental.
f. Penatalaksanaan
1. Segera setelah bayi lahir, nilai pernafasannya. Letakkan bayi diatas
perut ibu
2. Keringkan bayi dengan kain bersih dan kering. Periksa ulang
pernafasan bayi
3. Klem tali pusat dengan 2 klem dan potong diantara kedua klem dan
pertahankan kebersihannya
4. Pastikan bayi tetap hangat dan terjadi kontak antara kulit bayi
dengan kulit ibu
5. Gantilah handuk/kain yang basah dan bungkus bayi dengan
selimut hangat
6. Pastikan bayi tetap hangat dengan memeriksa telapak kaki bayi
setiap 15 menit
7. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya
8. Berikan obat mata eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% untuk
mencegah penyakit karena klamidia
9. Hindari memandikan bayi dalam 24 jam pertama
10. Lakukan perawatan tali pusat :
a) Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena
udara dan tutupi dengan kain bersih yang longgar
b) Cuci tali pusat dengan sabun dan air bersih lalu keringkan
sampai betul-betul kering
11. Ajarkan tanda-tanda bahaya dan segera rujuk apabila ditemukan
tanda bahaya
a) Pernafasan sulit atau > 60x/mnt
b) Hipotermi atau hipertermia
c) Hisapan lemah dan atau muntah
d) Tali pusat merah, bengkak, bernanah dan atau berbau busuk
e) Tidak buang air kecil dalam 24 jam, tinja lembek, kering serta
terdapat lendir dan darah dalam tinja
f) Aktivitas lemah, lunglai, atau kejang
12. Ajarkan pada orang tua cara merawat bayinya sehari-hari
a) Berikan ASI sesuai kebutuhan setiap 2-3 jam mulai hari
kelima
b) Pertahankan bayi selalu dengan ibu
c) Jaga bayi selalu dalam keadaan bersih
d) Jaga tali pusat agar selalu bersih dan kering
e) Jaga keamanan bayi terhadap trauma dan penyakit
f) Awasi masalah dan kesulitan pada bayi
g. Penilaian bayi untuk tanda-tanda kegawatdaruratan
Semua bayi baru lahir harus dinilai adanya tanda-tanda
kegawatan/kelainan yang menunjukkan suatu penyakit. Bayi baru lahir
dinyatakan sakit apabila mempunyai salah satu atau beberapa tanda-
tanda berikut:
1. Sesak napas
2. Frekuensi pernapasan 60 kali/menit
3. Gerak retraksi di dada
4. Malas minum
5. Panas atau suhu badan bayi rendah
6. Kurang aktif
7. Berat lahir rendah (1500-2500 gram) dengan kesulitan minum
Tanda-tanda bayi sakit berat
Apabila terdapat salah satu atau lebih tanda-tanda berikut:
1. Sulit minum
2. Sianosis sentral (lidah biru)
3. Perut kembung
4. Periode apneu
5. Kejang/periode kejang-kejang kecil
6. Merintih
7. Perdarahan
8. Sangat kuning
9. Berat badan lahir < 1500 gram
h. Prognosa dan Komplikasi
Prognosis
Keadaan bayi sangat tergantung pada pertumbuhan janin dalam uterus,
kualitas pengawasan antenatal, penyakit-penyakit yang diderita ibu
saat hamil serta penanganan persalinan dan perawatan sesudah lahir .
Komplikasi
Komplikasi yang terjadi pada neonatus yaitu :
a) Infeksi neonatal
b) Ikterus neonatal
c) Kesulitan bernafas
d) Perdarahan
e) Muntah
f) Sianosis
g) Kejang/tremor
h) Tidak mau menetek
a. Perubahan Patofisiologis dan Gambaran Klinik
Pernafasan spontan bayi baru lahir bergantung pada kondisi janin
pada masa kehamilan dan persalinan. Proses kelahiran sendiri selalu
menimbulkan asfiksia ringan yang bersifat sementara pada bayi.
Proses ini dianggap sangat perlu untuk merangsang kemoreseptor
pusat pernafasan agar terjadi „Primary Gasping“yang kemudian akan
berlanjut dengan pernafasan teratur (Jumes. 1958).
Sifat asfiksia ini tidak mempunyai pengaruh buruk karena reaksi
adaptasi bayi dapat mengatasinya. Bila terdapat gangguan pertukaran
gas atau pengangkutan oksigen selama kehamilan atau persalinan akan
terjadi asfiksia yang lebih berat. Keadaan ini akan mempengaruhi
fungsi sel tubuh dan bila tidak teratasi akan menyebabkan kematian.
Asfiksia yang terjadi dimulai dengan suatu periode apne disertai
dengan penurunan frekuensi jantung, selanjutnya bayi akan diikuti
pernafasan teratur. Pada penderita asfiksia berat usaha bernafas ini
tidak nampak dan bayi selanjutnya berada pada periode kedua. Pada
tingkat ini disamping bradikardi ditemukan pula penurunan tekanan
darah. Disamping adanya perubahan klinis akan terjadi pula gangguan
metabolisme dan perubahan keseimbangan asam-basa pada tubuh bayi.
b. Tanda dan Gejala
1. Pernafasan cuping hidung.
2. Pernafasan cepat.
3. Nadi cepat.
4. Nilai apgar < 6.
c. Penatalaksanaan
1. Menerima bayi dengan kain hangat.
2. Letakkan bayi pada meja resusitasi.
3. Berikan O2 2 ltr/mnt, bila berhasil teruskan perawatan selanjutnya.
4. Bila belum berhasil, rangsang pernafasan dengan menepuk-nepuk
telapak kaki, bila tidak berhasil juga pasang penlon masker
dipompa 60 x/mnt.
5. Bila bayi sudah mulai bernafas tetapi masih sianosis, biasanya
diberikan terapi natrium bikarbonat 7,5% sebanyak 6 cc
disuntikkan melalui vena umbilikalis, masukkan perlahan-lahan
untuk mencegah terjadinya perdarahan intrakranial karena
perubahan PH darah mendadak.
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal
Tabel 13. Asuhan Neonatal
Saat lahirKN1
Pada 6-48 jam
KN2
Hari ke 3-7
KN3
Hari ke 8-28
1. Manajemen
2. Inisiasi asfiksia
bayi
3. Pemeriksaan
segera saat lahir
4. Menjaga bayi
tetap hangat
5. Salep
mata,vitamin
K1 injeksi &
imunisasi
Hepatitis B
6. Konseling
1. Pemeriksaan
bayi baru
lahir
2. ASI eksklusif
3. Menjaga
bayi tetap
hangat
4. Perawatan
bayi
5. Tanda sakit
dan bahaya
6. Konseling
1. Pemeriksaan
ulang
2. ASI ekslusif
3. Tanda sakit
dan bahaya
4. Konseling
1. Pemeriksaan
ulang
2. ASI ekslusif
3. Tanda sakit
dan bahaya
4. Konseling
5. Nifas
a. Pengertian
Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah partus
selesai, dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu (Hanifa W, 2007: hal
237).
Istilah puerperium (berasal dari kata puer artinya anak, parele
artinya melahirkan) menunjukkan periode 6 minggu yang berlangsung
antara berakhirnya periode persalinan dan kembalinya organ-organ
reproduksi wanita ke kondisi normal seperti sebelum hamil (Anik
Maryunani, 2009 hal : 5)
Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah
kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali
seperti keadaan sebelum hamil. Masa Nifas berlangsung selama kira-
kira 6 minggu (Saiffudin, 2008 hal : 122).
Masa nifas didefinisikan sebagai periode selama dan setelah
kelahiran. Namun secara popular, diketahui istilah tersebut mencakup
6 minggu berikutnya saat terjadi involusi kehamilan normal.
(Cunningham FG. 2008, hal. 443).
b. Etiologi
Lahirnya hasil konsepsi
c.Fisiologi
Setelah plasenta dilahirkan fundus uteri kira-kira setinggi pusat,
segera setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri kira-kira ± 2 jari di
bawah pusat. Uterus menyerupai suatu buah advokat gepeng berukuran
panjang ± 15 cm, lebar ± 12 cm, dan tebal ± 10 cm. Sedangkan pada
bekas implantasi plasenta lebih tipis dari bagian lain. Korpus uteri
sekarang sebagian besar merupakan miometrium yang dibungkus
serosa dan dilapisi desidua. Dinding anterior dan posterior menempel
dengan tebal masing-masing 4-5 cm. Oleh karena adanya kontraksi
rahim, pembuluh darah tertekan sehingga terjadi ischemia. Selama 2
hari berikut uterus tetap dalam ukuran yang sama baru 2 minggu
kemudian turun kerongga panggul dan tidak dapat diraba lagi diatas
symfisis dan memncapai ukuran normal dalam waktu 4 minggu.
Setelah persalinan uterus seberat ± 1 kg, karena involusio 1
minggu kemudian beratnya sekitar 500 gram, dan pada akhir minggu
kedua menjadi 300 gram dan segera sesudah minggu kedua menjadi
100 gram. Jumlah sel-sel otot tidak berkurang banyak hanya saja
ukuran selnya yang berubah.
Setelah 2 hari persalinan desidua yang tertinggal dalam uterus
berdeferensiasi menjadi 2 lapisan. Lapisan superficial menjadi nekrotik
terkelupas keluar bersama lochea sementara lapisan basalis tetap utuh
menjadi sumber pembentukan endometrium baru. Proses regenerasi
endometrium berlangsung cepat kecuali tempat plasenta. Seluruh
endometrium pulih kembali dalam minggu ketiga.
Segera setelah persalinan tempat plasenta kira-kira berukuran
sebesar telapak tangan. Pada akhir minggu kedua ukuran diameternya
2-4 cm.
Setelah persalinan tempat plasenta terdiri dari banyak
pembuluh darah yang mengalami trombus. Setelah kelahiran, ukuran
pembuluh darah ekstra uteri mengecil menjadi sama atau sekurang-
kurangnya mendekati ukuran sebelum hamil.
Servik dan segmen bawah uterus menjadi struktur yang tipis,
kolaps dan kendur setelah kala II persalinan. Mulut servik mengecil
perlahan-lahan. Selama beberapa hari setelah persalinan, porsio masih
dapat dimasuki 2 jari, sewaktu mulut servik sempit, servik kembali
menebal dan salurannya akan terbentuk kembali.
Miometrium segmen bawah uterus yang sangat tipis
berkontraksi tetapi tidak sekuat korpus uteri. Beberapa minggu
kemudian segmen bawah menjadi isthmus uteri yang hampir tidak
dapat dilihat.
Vagina dan pintu keluar vagina akan membentuk lorong yang
berdinding lunak yang ukurannya secara perlahan-lahan mengecil.
Rugae terlihat kembali pada minggu ketiga, hymen muncul kembali
sebagai potongan jaringan yang disebut sebagai carunculae
mirtiformis.
Pada dinding kandung kencing terjadi edema dan hyperemia,
disamping itu kapasitasnya bertambah besar dan relatif tidak sensitif
terhadap tekanan cairan intravesika.
d. Tanda dan Gejala
Nifas ditandai dengan :
(Saifuddin AB, 2008 hal : 122)
1) Adanya perubahan fisik
a) Uterus (Rahim)
Setelah persalinan uterus seberat ± 1 kg, karena involusio 1
minggu kemudian beratnya sekitar 500 gram, dan pada akhir
minggu kedua menjadi 300 gram dan segera sesudah minggu
kedua menjadi 100 gram. Jumlah sel-sel otot tidak berkurang
banyak hanya saja ukuran selnya yang berubah.
Setelah persalinan tempat plasenta terdiri dari banyak
pembuluh darah yang mengalami trombus. Setelah kelahiran,
ukuran pembuluh darah ekstra uteri mengecil menjadi sama
atau sekurang-kurangnya mendekati ukuran sebelum hamil.
b) Serviks (Leher rahim)
Serviks menjadi tebal, kaku dan masih terbuka selama 3 hari.
Namun ada juga yang berpendapat sampai 1 minggu. Bentuk
mulut servik yang bulat menjadi agak memanjang dan akan
kembali normal dalam 3-4 bulan.
c) Vagina
Vagina yang bengkak serta lipatan (rugae) yang hilang akan
kembali seperti semula setelah 3-4 minggu.
d) Abdomen
Perut akan menjadi lembek dan kendor. Proses involusio
pada perut sebaiknya diikuti olahraga atau senam penguatan
otot-otot perut. Jika ada garis-garis biru (striae) tidak akan
hilang, kemudian perlahan-lahan akan berubah warna
menjadi keputihan.
e) Payudara
Payudara yang membesar selama hamil dan menyusui akan
kembali normal setelah masa menyusui berakhir. Untuk
menjaga bentuknya dibutuhkan perawatan yang baik.
f) Kulit
Setelah melahirkan, pigmentasi akan berkurang, sehingga
hiperpigmentasi pada muka, leher, payudara dan lainnya akan
menghilang secara perlahan-lahan.
2) Involusio uterus dan pengeluaran lochea
Dengan involusio uteri, maka lapisan lapisan luar dari
desidua yang mengelilingi situs plasenta akan menjadi nekrotik.
Desidua yang mati akan keluar bersama-sama dengan sisa cairan,
campuran antara darah yang dinamakan lochea. Biasanya
berwarna merah, kemudian semakin lama semakin pucat, dan
berakhir dalam waktu 3-6 minggu.
a) Lochea Rubra
Sesuai dengan namanya yang muncul pada hari pertama post
partum sampai hari keempat. Warnanya merah yang
mengandung darah dan robekan/luka pada tempat perlekatan
plasenta serta serabut desidua dan korion.
b) Lochea Serosa
Berwarna kecoklatan, mengandung lebih sedikit darah,
banyak serum, juga lekosit. Muncul pada hari kelima sampai
hari kesembilan.
c) Lochea Alba
Warnanya lebih pucat, putih kekuning-kuningan dan
mengandung leukosit, selaput lendir servik serta jaringan
yang mati. Timbulnya setelah hari kesembilan.
3) Laktasi atau pengeluaran ASI
Selama kehamilan hormon estrogen dan progesteron
menginduksi perkembangan alveolus dan duktus laktiferus
didalam payudara dan juga merangsang produksi kolostrum.
Namun produksi ASI akan berlangsung sesudah kelahiran bayi
saat kadar hormon estrogen dan progesteron menurun.
Pelepasa ASI berada dibawah kendali neuro-endokrin,
rangsangan sentuhan payudara (bayi mengisap) akan merangsang
produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel mioepitel
Hisapan bayi memicu pelepasan ASI dari alveolus
mammae melalui duktus kesinus lactiverus.
Cairan pertama yang diperoleh bayi sesudah ibunya
melahirkan adalah kolostrum, yang mengandung campuran yang
lebih kaya akan protein, mineral, dan antibody daripada ASI yang
telah mature. ASI yang mature muncul kira-kira pada hari ketiga
atau keempat setelah kelahiran.
4) Perubahan sistem tubuh lain
a) Endokrin
Endokrin diproduksi oleh kelanjar hypofise anterior,
meningkat dan menekan produksi FSH (Folicle Stimulating
Hormon) sehingga fungsi ovarium tertunda. Dengan
menurunnya hormon estrogen dan progesteron, kondisi ini
akan mengembalikan fungsi ovarium kepada keadaan semula.
b) Hemokonsentrasi
Volume darah yang meningkat saat hamil akan kembali
normal dengan adanya mekanisme kompensasi yang
menimbulkan hemokonsentrasi, umumnya terjadi pada hari
ketiga dan kelima.
e.Aspek Psikologis Post Partum
Dibagi dalam beberapa fase yaitu :
1) Fase “Taking In”
a) Perhatian ibu terhadap kebutuhan dirinya, fase ini
berlangsung selama 1-2 hari.
b) Ibu memperhatikan bayinya tetapi tidak menginginkan kontak
dengan bayinya. Ibu hanya memerlukan informasi tentang
bayinya.
c) Ibu memerlukan makanan yang adekuat serta istirahat/tidur.
2) Fase “Taking Hold”
a) Fase mencari pegangan, berlangsung ±10 hari.
b) Ibu berusaha mandiri dan berinisistif.
c) Perhatian terhadap kemampuan diri untuk mengatasi fungsi
tubuhnya seperti kelancaran bab, bak, duduk, jalan dan lain
sebagainya.
d) Ibu ingin belajar tentang perawatan diri dan bayinya.
e) Timbul rasa kurang percaya diri.
3) Fase “Letting Go”
a) Ibu merasakan bahwa bayinya terpisah dari dirinya.
b) Ibu mandapatkan peran dan tanggung jawab baru
c) Terjadi peningkatan kemandirian diri dalam merawat diri dan
bayinya.
d) Terjadi penyesuaian dalam hubungan keluarga dan bayinya
Ada yang membagi aspek psikologis masa nifas adalah sbb :
1) Fase Honeymoon
Yaitu fase setelah anak lahir dimana terjadi kontak yang lama
antara ibu, ayah dan anak pada fase ini.
a) Tidak memerlukan hal-hal yang romantis
b) Saling memperhatikan anaknya dan menciptakan hubungan
yang baru.
2) Bonding and Attachment
Menurut Nelson Attachment, bonding adalah dimulainya interaksi
emosi sensorik fisik antara orang tua dan bayi segera setelah lahir.
Menurut Nelson Attachment adalah ikatan aktif yang terjadi antara
individu.
3) Post Partum Blues
Adalah dimana wanita :
a) Kadang-kadang mengalami kekecewaan yang berkaitan dan
mudah tersinggung dan terluka
b) Nafsu makan dan pola tidur terganggu, biasanya terjadi di
Rumah Sakit karena adanya perubahan hormon dan perlu
transisi.
c) Adanya rasa ketidaknyamanan, kelelahan, kehabisan tenaga
yang menyebabkan ibu tertekan
d) Dapat diatasi dengan menangis. Bila tidak teratasi dapat
menyebabkan depresi.
e) Dapat dicegah dengan memberikan penyuluhan sebelumnya
bahwa hal tersebut diatas adalah normal.
f. Tahapan Masa Nifas
Nifas terbagi menjadi tiga tahap :
1. Puerperium dini
2. Kepulihan dimana ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berj alan-
jalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja
setelah 40 hari.
3. Puerperium intermedial
4. Kepulihan dari alat-alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu 3.
Remote puerperium
5. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama
bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami
komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu,
bulanan, tahunan.
(Eny Ratna Ambarwati dan Diah Wulandari, 2009: hal 3-4).
g. Asuhan masa nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai
standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga
kesehatan, untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan
pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan
kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu
Tabel 14. Kunjungan masa nifas
KUNJUNGAN WAKTU ASUHAN
I 6 jam - 3 hari
PP
a. Mencegah perdarahan masa nifas
karena atonia uteri.
b. Mendeteksi dan perawatan
penyebab lain perdarahan serta
melakukan rujukan bila
perdarahan berlanjut.
c. Memberikan konseling pada ibu
atau salah satu anggota keluarga
bagaimana mencegah perdarahan
masa nifas karena atonia uteri.
d. Pemberian ASI awal.
e. Melakukan hubungan antara ibu
dan bai baru lahir.
f. Menjaga bayi tetap sehat dengan
cara pencegahan hipotermia
g. Jika petugas kesehatan menolong
persalinan, ia harus tinggal
dengan ibu dan bayi baru lahir
untuk 2 jam pertama setelah
kelahiran, atau sampai ibu dan
bayi dalam keadaan stabil.
II 2 minggu PP
(8 – 14 hari)
a. Memastikan involusi uterus
barjalan dengan normal, uterus
berkontraksi dengan baik, tinggi
fundus uteri di bawah umbilikus,
tidak ada perdarahan abnormal.
b. Menilai adanya tanda-tanda
demam, infeksi dan perdarahan
abnormal.
c. Memastikan ibu mendapat cukup
makanan, cairan dan istirahat.
d. Memastikan ibu menyusui
dengan baik dan tak
memperlihatkan tanda-tanda
penyulit.
e. Memberikan konseling pada ibu
mengenai asuhan pada bayi, tali
pusat, menjaga bayi tetap hangat
dan merawat bayi sehari-hari.
III 6 minggu PP
(36 – 42 hari)
a. Menanyakan pada ibu tentang
penyulit-penyulit yang ia alami.
b. Memberikan konseling KB
secara dini.
(Suherni, Perawatan Masa Nifas. 2009).
Tindakan yang baik untuk asuhan masa nifas normal pada ibu hamil :
(Suherni, Perawatan Masa Nifas. 2009).
1) Kebersihan diri
a) Anjurkan ibu bagaiman membersihkan daerah kelamin
dengan air dan sabun didaerah vulva terlebih dahulu, dari
depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah
anus. Dibersihkan setiap kali setelah selesai buang air kecil
dan buang air besar.
b) Sarankan ibu untuk mengganti pembalut setidaknya 2 kali
sehari
c) Sarankan ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dengan air
mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah
kemaluan.
d) Jika ibu mempunyai luka operasi atau laserasi, tidak
diperkenankan untuk menyentuh daerah luka.
2) Istirahat
a) Anjurkan kepada ibu untuk beristirahat dengan cukup guna
mencegah kelelahan yang berlebihan. Ibu tidur pada saat
bayinya juga tidur.
b) Sarankan ia kembali ke kegiatan rumah tangga biasa secara
bertahap.
3) Latihan
a) Diskusikan pentingnya mengembalikan otot-otot perut dan
panggul, kembali seperti keadaan sebelum hamil.
b) Jelaskan bahwa latihan tertentu beberapa menit setiap hari
akan sangat membantu, seperti misalnya latihan kegel.
4) Gizi
a) Mengkonsumsi tambahan 500 kalori setiap hari
b) Makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein,
mineral dan vitamin yang cukup
c) Minum sedikitnya 3 liter air setiap hari (anjurkan ibu minum
setiap kali setelah selesai menyusui)
d) Pil besi harus di minum untuk menambah zat gizi setidaknya
selama 40 hari pasca persalinan
e) Minum kapsul vitamin A (200.000 IU)
5) Perawatan payudara
a) Menjaga payudara tetap bersih
b) Menggunakan bra yang menyokong payudara
c) Rawat payudara bila bengkak atau lecet
6) Hubungan intim (suami istri)
Begitu darah merah sudah tidak lagi keluar, dan ibu tidak merasa
ada ketidaknyamanan, maka hubungan intim sudah dapat dimulai
atau sesuai dengan kepercayaan yang dianut ibu.
h. Prognosa dan Komplikasi
1) Prognosis
Masa nifas normal, jika involusio uterus, pengeluaran lochea,
pengeluaran ASI dan perubahan sistem tubuh, termasuk keadaan
psikologis ibu normal. (Saifuddin AB. 2008 hal : 122)
2) Komplikasi
Komplikasi pada masa nifas yang biasa terjadi adalah :
a. Infeksi nifas
b. Kelainan atau gangguan pada mammae
1) Mastitis
2) Bendungan ASI
3) Kelainan puting susu
c. Sub involusio
d. Perdarahan nifas skunder
e. Tromboflebitis
4. Keluarga Berencana (KB)
a. Pengertian
Keluarga berencana adalah salah satu usaha untuk mencapai
kesejahteraan dengan jalan memberikan nasehat perkawinan,
pengobatan kemandulan dan penjarangan kehamilan.
(Perawatan Ibu Paska Melahirkan, 2008 haL: 107)
b. Tujuan
(WHO Expert Commite 2007)
Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau
pasangan suami istri untuk :
1) Mendapatkan obyek tertentu
2) Menghindari kehamilan yang tidak diinginkan
3) Mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan
4) Mengatur interval diantara kehamilan
5) Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan suami
istri
6) Menentukan jumlah anak yang diinginkan
c. Macam-macam Macam-macam metode kontrasepsi
1) Kontrasepsi Hormonal
Kontrasepsi ini tersedia dalam bentuk oral, suntikan, dan mekanik.
Kontrasepsi oral adalah kombinasi dari hormon estrogen dan
progestin atau hanya progestin-mini pil. Suntikan dan kontrasepsi
implant (mekanik) mengandung progestin saja atau kombinasi
progestin dan estrogen.
(a). Kontrasepsi oral kombinasi (pil) : Mengandung sintetik
estrogen dan preparat progestin yang mencegah kehamilan
dengan cara menghambat terjadinya ovulasi (pelepasan sel telur
oleh indung telur) melalui penekanan hormon LH dan FSH,
mempertebal lendir mukosa servikal (leher rahim), dan
menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium. Pil kombinasi
ada yang memiliki estrogen dosis rendah dan ada yang
mengandung estrogen dosis tinggi. Estrogen dosis tinggi
biasanya diberikan kepada wanita yang mengkonsumsi obat
tertentu (terutama obat epilepsy). Selain untuk kontrasepsi, oral
kombinasi dapat digunakan untuk menangani dismenorea
(nyeri saat haid), menoragia, dan metroragia. Oral kombinasi
tidak direkomendasikan untuk wanita menyusui, sampai
minimal 6 bulan setelah melahirkan. Pil kombinasi yang
diminum oleh ibu menyusui bisa mengurangi jumlah air susu
dan kandungan zat lemak serta protein dalam air susu. Hormon
dari pil terdapat dalam air susu sehingga bisa sampai ke bayi.
Karena itu untuk ibu menyusui sebaiknya diberikan tablet yang
hanya mengandung progestin, yang tidak mempengaruhi
pembentukan air susu. Wanita yang tidak menyusui harus
menunggu setidaknya 3 bulan setelah melahirkan sebelum
memulai oral kombinasi karena peningkatan risiko
terbentuknya bekuan darah di tungkai. Apabila 1 pil lupa
diminum, 2 pil harus diminum sesegera mungkin setelah ingat,
dan pack tersebut harus dihabiskan seperti biasa. Bila 2 atau
lebih pil lupa diminum, maka pack pil harus tetap dihabiskan
dan metode kontrasepsi lain harus digunakan, seperti kondom
untuk mencegah kehamilan.
Jika menstruasi terakhir terjadi dalam waktu kurang dari 12
minggu setelah persalinan, maka pil KB bisa langsung
digunakan. Jika menstruasi terakhir terjadi dalam waktu 12-28
minggu, maka harus menunggu 1 minggu sebelum pil KB
mulai digunakan, sedangkan jika menstruasi terakhir terjadi
dalam waktu lebih dari 28 minggu, harus menunggu 2 minggu
sebelum pil KB mulai digunakan. Pil KB tidak berpengaruh
terhadap obat lain, tetapi obat lain (terutama obat tidur dan
antibiotik) bisa menyebabkan berkurangnya efektivitas dari pil
KB. Obat anti-kejang (fenitoin dan fenobarbital) bisa
menyebabkan meningkatkan perdarahan abnormal pada wanita
pemakai pil KB. Beberapa kondisi dimana kontrasepsi oral
kombinasi tidak boleh diigunakan pada wanita dengan :
menyusui atau kurang dari 6 minggu setelah melahirkan, usia
>35 tahun dan merokok 15 batang sehari, faktor risiko multipel
untuk penyakit jantung (usia tua, merokok, diabetes, hipertensi)
, tekanan darah sistolik ≥ 160 atau TD diastolik ≥ 100 mmHg,
riwayat trombosis vena dalam atau emboli paru, operasi besar
dengan istirahat lama di tempat tidur , riwayat sakit jantung
iskemik, stroke, penyakit jantung katup komplikasi, migrain
dengan gejala neurologi fokal (dengan aura), migrain tanpa
gejala neurologi fokal dan usia = 35 tahun, riwayat kanker
payudara, diabetes dengan nefropati, retinopati, neuropati,
penyakit vaskular, atau diabetes > 20 tahun, sirosis berat,
kanker hati
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 0,1 – 5 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama
2) Keuntungan : sangat efektif, mencegah kanker indung telur
dan kanker endometrium, menurunkan ketidakteraturan
menstruasi dan anemia yang berkaitan dengan menstruasi,
menghaluskan kulit dengan jerawat sedang.
3) Kerugian : tidak direkomendasikan untuk menyusui,
tidak melindungi dari Penyakit Menular Seksual (PMS),
harus diminum setiap hari, membutuhkan resep dokteran.
4) Efek samping lokal : mual, nyeri tekan pada payudara,
sakit kepala.
5) Efek samping : perdarahan tidak teratur (umumnya
menghilang setelah 3 bulan pemakaian), meningkatkan
tekanan darah (dapat kembali normal bila oral kombinasi
dihentikan), bekuan darah pada vena tungkai (3-4 kali pada
pil KB dosis tinggi), meningkatkan faktor risiko penyakit
jantung, risiko stroke (pada wanita usia > 35 tahun).
6) Pengembalian kesuburan : ketika dihentikan maka
kesuburan akan kembali seperti semula. Kesuburan ini
bervariasi, dalam waktu 3-12 bulan setelah dihentikan maka
tidak ada perbedaan kesuburan antara wanita yang memakai
kontrasepsi oral dan yang tidak.
(b).Kontrasepsi oral progestin (pil) : Dimana suatu pil yang
berisi hormon estrogen dan progesteron atau progesteron saja
yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari yang bekerja
menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur
perempuan dari indung telur, mengendalikan lendir mulut
rahim sehingga sel mani/sperma tidak dapat masuk ke dalam
rahim, dan menipiskan lapisan endometrium/ selaput lendir di
vagina dengan tingkat keberhasilan/ efektivitas 92-99%.
Kontrasepsi ini diberikan pada wanita yang menginginkan
kontrasepsi oral namun tidak bisa menggunakan oral kombinasi
karena pengaruh estrogen dapat membahayakan, misalnya pada
wanita yang sedang menyusui.
Gambar 33. pil KB
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 0,5 – 5 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama.
2) Keuntungan : mula kerja cepat (24 jam setelah pemakaian
pil), menurunkan kejadian menoragia dan anemia. Dapat
digunakan pada wanita menyusui. Mencegah terjadinya
kanker endometrium, tidak memiliki efek samping yang
berkaitan dengan estrogen (bekuan darah di vena tungkai).
3) Kerugian : harus diminum di waktu yang sama setiap hari,
kurang efektif dibandingkan oral kombinasi, membutuhkan
resep dokter.
4) Efek samping : penambahan berat badan, jerawat,
kecemasan, angka kejadian terjadinya perdarahan tidak
teratur tinggi.
5) Pengembalian kesuburan cepat ketika pil dihentikan
(c). Kontrasepsi suntikan progestin: Hormon progesteron yang
disuntikkan ke bokong/otot panggul lengan atas setiap 3 bulan
atau hormon estrogen yang disuntikkan setiap satu bulan sekali.
Cara kerja suntikan adalah mencegah lepasnya sel telur dari
indung telur perempuan, mengentalkan lendir mulut rahim
sehingga spermatozoa (sel mani) tidak masuk ke dalam rahim,
menipiskan endometrium/selaput lendir sehingga tidak siap
untuk hamil. Dengan tingkat keberhasilan/efektifitas lebih dari
99%. Mencegah kehamilan dengan mekanisme yang sama
seperti progestin pil namun kontrasepsi ini menggunakan
suntikan intramuskular (dalam otot <bokong atau lengan
atas>). Yang sering digunakan adalah medroxyprogesterone
asetat (Depo-Provera), 150 mg yang diberikan setiap 3 bulan.
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 0,3 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama.
2) Keuntungan : mula kerja cepat dan sangat efektif, bekerja
dalam waktu lama, tidak mengganggu menyusui, dapat
dipakai segera setelah keguguran atau setelah masa nifas.
3) Kerugian : suntikan harus dilakukan oleh tenaga
kesehatan secara teratur, tidak melindungi dari PMS.
4) Efek samping lokal : peningkatan berat badan,
rambut rontok.
5) Efek samping : tulang menjadi keropos, kelainan
metabolisme lemak, ketidakteraturan menstruasi termasuk
menometroragi (umumnya beberapa bulan pertama) dan
amenorea ( 1 tahun pertama), jika pemakaian suntikan KB
dihentikan, siklus menstruasi yang teratur akan kembali
terjadi dalam waktu 6 bulan-1 tahun.
6) Pengembalian kesuburan 5-7 bulan setelah penghentian
suntikan
(d).Kontrasepsi suntikan estrogen-progesteron : suntikan ini
diberikan secara intramuskular setiap bulan, mengandung 25
mg depo medroxyprogesteron asetat dan 5 mg estradiol
cypionat. Mekanisme kerja, efek samping, kriteria, dan
keamanan sama seperti kontrasepsi oral kombinasi. Siklus
menstruasi terjadi lebih stabil setiap bulan. Pengembalian
kesuburan tidak selama kontrasepsi suntikan progestin.
Gambar 34. Kontrasepsi Suntikan
(e). Implant progestin : Satu kapsul, dua kapsul dan enam kapsul
yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan
melepaskan hormon progesteron selama 3 atau 5 tahun.
Dengan cara kerja menghambat terjadinya ovulasi,
menyebabkan endometrium/selaput tidak siap untuk
nidasi/menerima pembuahan, mempertebal lendir
serviks/rahim, menipiskan lapisan endometrium/selaput lendir
dengan tingkat keberhasilan 97-99%. Yang mengandung 36mg
levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam kulit lengan wanita.
Setelah diberi obat bius, dibuat sayatan dan dengan bantuan
jarum dimasukkan kapsul implan. Tidak perlu dilakukan
penjahitan. Kapsul ini melepaskan progestin ke dalam aliran
darah secara perlahan dan biasanya dipasang selama 5 tahun.
Mencegah kehamilan dengan cara menghambat terjadinya
ovulasi (pelepasan sel telur oleh indung telur), mempertebal
lendir mukosa leher rahim, mengganggu pergerakan saluran
tuba, dan menghalangi pertumbuhan lapisan endometrium.
Kontrasepsi ini efektif dalam waktu 48 jam setelah diimplan
dan efektif selama 5-7 tahun.
Gambar 35. Implant
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 0,05 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama.
2) Keuntungan : Sangat efektif, bekerja untuk jangka waktu
lama.
3) Kerugian : Membutuhkan prosedur operasi kecil untuk
pemakaian dan pelepasan, tidak melindungi dari PMS.
4) Efek samping lokal : Sakit kepala, payudara menjadi keras,
peningkatan berat badan, kerontokan rambut, jerawat,
perubahan mood.
5) Efek samping : Gangguan metabolisme lemak,
hirsutisme, gangguan menstruasi (memanjang, tidak
teratur).
6) Kesuburan baru kembali 1 bulan setelah kapsul diambil
2) Kontrasepsi Barrier (penghalang)
(a). Kondom (pria dan wanita) àdalah metode yang
mengumpulkan air mani dan sperma di dalam kantung
kondom dan mencegahnya memasuki saluran reproduksi
wanita. Kondom pria harus dipakai setelah ereksi dan
sebelum alat kelamin pria penetrasi ke dalam vagina yang
meliputi separuh bagian penis yang ereksi. Tidak boleh
terlalu ketat (ada tempat kosong di ujung untuk menampung
sperma). Kondom harus dilepas setelah ejakulasi.
Cara pemakaian kondom :
1) Gunakan kondom seiap kali berhubungan seksual
2) Buka kondom secara perlahan untuk mencegah kerusakan
(jangan menggunakan gigi atau benda tajam)
3) Pasang kondom dalam keadaan penis ereksi dan sebelum
kontak dengan pasangan
4) Pastikan tidak ada udara yang terjebak di ujung kondom
5) Pastikan penggunaan pelumas yang cukup (dapat
menggunakan pelumas tambahan)
6) Gunakan hanya pelumas dengan bahan dasar air ketika
menggunakan kondom (pelumas dengan bahan dasar
minyak dapat melemahkan lateks)
7) Pegang kondom dengan hati-hati setelah ejakulasi, dan
untuk mencegah terlepasnya kondom, keluarkan kondom
dari vagina dalam keadaan penis ereksi
8) Efktivitas : kehamilan terjadi pada 3-14 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama
9) Keuntungan : dapat digunakan selama menyusui, satu-
satunya kontrasepsi yang mencegah PMS, infeksi GO,
klamidia
10) Kerugian : kegagalan tinggi bila tidak digunakan dengan
benar, alergi lateks pada orang yang sensitif
Gambar 37. Kontrasepsi Kondom
(b).Diafragma dan cervical cap : kontrasepsi penghalang yang
dimasukkan ke dalam vagina dan mencegah sperma masuk
ke dalam saluran reproduksi. Diafragma terbuat dari lateks
atau karet dengan cincin yang fleksibel. Diafragma
diletakkan posterior dari simfisis pubis sehingga serviks
(leher rahim) tertutupi semuanya. Diafragma harus diletakkan
minimal 6 jam setelah senggama. Cervical cap (penutup
serviks) adalah kop bulat yang diletakkan menutupi leher
rahim dengan perlekatan di bagian forniks. Terbuat dari karet
dan harus tetap di tempatnya lebih dari 48 jam
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 6-40 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama
2) Keuntungan : dapat digunakan selama menyusui, tidak
ada risiko gangguan kesehatan, melindungi dari PMS
3) Kerugian : angka kegagalan tinggi, peningkatan risiko
infeksi, membutuhkan evaluasi dari tenaga kesehatan,
ketidaknyamanan
Gambar 38. Kontrasepsi Diafragma dan Cervical Cap
3) Spermisida
Agen yang menghancurkan membran sel sperma dan
menurunkan motilitas (pergerakan sperma). Tipe spermisida
mencakup foam aerosol, krim, vagina suposituria, jeli, sponge
(busa) yang dimasukkan sebelum melakukan hubungan seksual.
Terutama mengandung nonoxynol 9
(a). Efektivitas : kehamilan terjadi pada 6-26 per 100 wanita
pada 1 tahun penggunaan pertama
(b).Keuntungan : tidak mengganggu kesehatan, berfungsi
sebagai pelumas, dapat mencegah PMS bakterial
(c). Kerugian : angka kegagalan tinggi, dapat meningkatkan
transmisi virus HIV, hanya efektif 1-2 jam.
4) Metode amenorea menyusui
Selama menyusui, penghisapan air susu oleh bayi
menyebabkan perubahan hormonal dimana hipotalamus
mengeluarkan GnRH yang menekan pengeluaran hormone LH
dan menghambat ovulasi. Ini adalah metode yang efektif bila
kriteria terpenuhi : menyusui setiap 4 jam pada siang hari, dan
setiap 6 jam pada malam hari. Makanan tambahan hanya
diberikan 5-10% dari total.
(a). Efektivitas : kehamilan terjadi pada 2 per 100 wanita pada 6
bulan setelah melahirkan, 6 per 100 wanita setelah 6-12
bulan setelah melahirkan
(b).Keuntungan : pencegahan kehamilan segera setelah
melahirkan, tidak mengganggu kesehatan, ekonomis,
merangsang seorang wanita untuk menyusui
(c). Kerugian : tidak sepenuhnya efektif, harus memenuhi
criteria, tidak melindungi dari PMS.
5) Kontrasepsi darurat
(a). Kontrasepsi darurat hormonal àdalah estrogen dosis tinggi
atau progestin diberikan dalam waktu 72 jam setelah
senggama tidak terproteksi, dengan cara kerja mencegah
ovulasi dan menyebabkan perubahan di endometrium. 4 pil
kombinasi yang mengandung 30-35μg ethinyl estradiol,
diulangi 12 jam kemudian. 2 pil kombinasi mengandung
50μg levonorgestrel, diulangi 12 jam kemudian. Tidak boleh
digunakan pada wanita yang alergi kontrasepsi pil hormonal.
Tidak boleh digunakan sebagai kontrasepsi rutin.
1) Efektivitas : kehamilan terjadi pada 2 per 100 wanita pada
bila digunakan dalam waktu 72 jam
2) Keuntungan : sangat efektif untuk situasi darurat
3) Kerugian : mual hebat dan perdarahan
(b).Kontrasepsi darurat IUD àdalah dimasukkan 5 hari setelah
senggama tidak terproteksi untuk mengganggu implantasi,
kehamilan terjadi kurang dari 1 per 100 wanita bila
dimasukkan dalam waktu 5 hari.
Gambar 39. Pemasangan IUD
6) Sterilisasi / KONTAP
(a).Pengertian
Kontrasepsi mantap (kontap ) adalah suatu tindakan untuk
membatasi keturunan dalam jangka waktu yang tidak
terbatas; yang dilakukan terhadap salah seorang dari
pasangan suami isteri atas permintaan yang bersangkutan,
secara mantap dan sukarela. Kontap dapat diikuti baik oleh
wanita maupun pria. Tindakan kontap pada wanita disebut
kontap wanita atau MOW (Metoda Operasi Wanita ) atau
tubektomi, sedangkan pada pria MOP (Metoda Operasi Pria)
atau vasektomi.
Kontrasepsi mantap pada wanita atau MOW
(Metoda Operasi Wanita) atau tubektomi, yaitu tindakan
pengikatan dan pemotongan saluran telur agar sel telur tidak
dapat dibuahi oleh sperma. Kontrasepsi mantap pada pria
atau MOP (Metoda Operasi Pria) atau vasektomi., yaitu
tindakan pengikatan dan pemotongan saluran benih agar
sperma tidak keluar dari buah zakar.
(b).Cara Kerja
- Tubektomi (MOW) Perjalanan sel telur terhambat
karena saluran sel telur tertutup
Gambar 40. Tubektomi (MOW)
- Vasektomi (MOP)
Gambar 41. Vasektomi (MOP)
Saluran benih tertutup, sehingga tidak dapat menyalurkan
sperma
(c). Keuntungan
Secara umum keuntungan kontap wanita dan pria
dibandingkan dengan kontrasepsi lain adalah : Lebih aman,
karena keluhan lebih sedikit dibandingkan dengan cara
kontrasepsi lain, Lebih praktis, karena hanya memerlukan
satu kali tindakan saja, Lebih efektif, karena tingkat
kegagalannya sangat kecil dan merupakan cara
kontrasepsi yang permanen, Lebih ekonomis, karena hanya
memrlukan biaya untuk satu kali tindakan saja. Secara khusus
keuntungan kontap wanita dan pria adalah :
Keuntungan Tubektomi(MOW) :
1) Sangat efektif dan “permanen”
2) Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
3) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang
4) Tidak mempengaruhi proses menyusui
5) Pembedahan sederhana, dapat dilakukan dengan anestesi
lokal
6) Tidak menggangu hubungan seksual
Keuntungan Vasektomi (MOP)
1) Sangat efektif dan “permanen”
2) Tidak ada efek samping dalam jangka panjang
3) Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
4) Tidak menggangu hubungan seksual
5) Tindakan bedah yang aman dan sederhana
(d).Kerugian
Tubektomi (MOW)
1) Rasa sakit/ketidak nyamanan dalam jangka pendek
setelah tindakan
2) Ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan
Vasektomi (MOP)
1) Tidak dapat dilakukan pada orang yang masih ingin
memiliki anak
2) Harus ada tindakan pembedahan minor.
(e). Syarat
Setiap peserta kontap harus memenuhi 3 syarat, yaitu:
1) Sukarela
Setiap calon peserta kontap harus secara sukarela
menerima pelayanan kontap; artinya sedcara sadar dan
dengan kemauan sendiri memilih kontap sebagai cara
kontraseps
2) Bahagia
Setiap calon peserta kontap harus memenuhi syarat
bahagia : artinya : calon peserta tersebut dalam
perkawinan yang sah dan harmonis dan telah dianugerahi
sekurang-kurangnya 2 orang anak yang sehat rohani dan
jasmani, bila hanya mempunyai 2 orang anak, maka anak
yang terkecil paling sedikit, umur sekitar 2 tahun, umur
isteri paling muda sekitar 25 tahun
3) Kesehatan
Setiap calon peserta kontap harus memenuhi syarat
kesehatan; artinya tidak ditemukan adanya hambatan atau
kontraindikasi untuk menjalani kontap. Oleh karena itu
setiap calon peserta harus diperiksa terlebih dahulu
kesehatannya oleh dokter, sehingga diketahui apakah
cukup sehat untuk dikontap atau tidak. Selain itu juga
setiap calon peserta kontap harus mengikuti konseling
(bimbingan tatap muka) dan menandatangani formulir
persetujuan tindakan medik (Informed Consent).
(f). Yang Dapat Menjalani
Tubektomi (MOW)
1) Usia lebih dari 26 tahun
2) Sudah punya anak cukup (2 anak), ank terkecil harus
berusia minimal 5 (lima) tahun
3) Yakin telah mempunyai keluarga yag sesuai dengan
kehendaknya
4) Pada kehamilannya akan menimbulkan risiko
kesehatan yang serius
5) Ibu pasca persalinan
6) Ibu pasca keguguran
7) Vasektomi (MOP) Untuk laki-laki subur sudah punya
anak cukup (2 anak) dan istri beresiko tinggi
(g).Yang Sebaiknya Tidak Menjalani
1) Tubektomi ( MOW )
(a). Hamil (sudah terdeteksi atau dicurigai)
(b). Menderita tekanan darh tinggi
(c). Kencing manis (diabetes)
(d). Penyakit jantung
(e). Penyakit paru-paru
(f). Perdarahan vaginal yang belum terjelaskan (hingga
harus dievaluasi)
(g). Infeksi sistemik atau pelvik yang akut (hingga
masalah itu disembuhkan atau dikontrol)
(h). Ibu yang tidak boleh menjalani pembedahan
(i). Kurang pati mengenai keinginannya untuk fertilisasi
di masa depan
(j). Belum memberikan persetujuan tertulis
2) Vasektomi (MOP)
(a). Infeksi kulit atu jamur di daerah kemaluan
(b). Menderita kencing manis
(c). Hidrokel atau varikokel yang besar
(d). Hernia inguinalis
(e). Anemia berat, ganguan pembekuan darah atau sedang
menggunakan antikoagulansia.
(h). Waktu pelaksanaan
1) Tubektomi (MOW)
(a). Setiap waktu selama siklus menstruasi apabila diyakini
secara rasional klien tersebut tidak hamil
(b).Hari ke-6 hingga ke-13 dari siklus menstruasi
(c). Pascapersalinan
(d).Minilap: di dalam waktu 2 hari atau setelah 6 minggu
atau 12 minggu
(e). Laparoskopi: tidak tepat unntuk klie-klien pasca
persalinan
(f). Pasca keguguran
(g).Triwulan pertama: dalam wakru 7 hari sepanjang tidak
ada bukti infeksi pelvik) minilap atau laparoskopi)
(h).Triwulan kedua: dalam waktu 7 hari sepanjang tidak
ada bukti infeksi pelvik (minilap saja)
2) Vasektomi (MOP)
(a). Tidak ada batasan usia, dapat dilaksanakan bila
diinginkan. Yang penting sudah memenuhi syarat
sukarela, bahagia, dan kesehatan.
(b). Istri beresiko tinggi
(i). Tempat Pelayanan
1) Tubektomi (MOW)
Rumah sakit. Jika ada keluhan, pemakai harus ke Rumah
Sakit
2) Vasektomi (MOP)
Rumah Sakit, puskesmas dan klinik KB.
(j). Persiapan Sebelum Tindakan
1) Tubektomi (MOW)
Hal-hal yang perlu dilakukan oleh calon peserta kontap
wanita adalah:
(a). Puasa mulai tengah malam sebelum operasi, atau
sekurang-kurangnya 6 jam sebelum operasi. Bagi
calon akseptor yang menderita Maag (kelaianan
lambung agar makan obat maag sebelum dan
sesudah puasa
(b).Mandi dan membersihkan daerah kemaluan dengan
sabun mandi sampai bersih, dan juga daerah perut
bagian bawah
(c). Tidak memakai perhiasan, kosmetik, cat kuku, dll
(d).Membawa surat persetujuan dari suami yang sudah
ditandatangani atau di cap jempol
(e). Menjelang operasi harus kencing terlebih dahulu
(f). Datang ke rumah sakit tepat pada waktunya, dengan
ditemani anggota keluarga; sebaiknya suami.
2) Vasektomi (MOP)
Hal-hal yang perlu dilakukan oleh calon peserta kontap pria
adalah:
(a). Tidur dan istirahat cukup
(b). Mandi dan memebersihkan daerah sekitar kemaluan
(c). Makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke klinik
(d). Datang ke klinik tempat operasi dengan pengantar
(e). Jangan lupa membawa surat persetujuan isteri yang
ditandatangani atau cap jempol.
(k).Perawatan Setelah Tindakan
Tubektomi (MOW)
1. Istirahat selama 1-2 hari dan hindarkan kerja berat selama
7 hari
2. Kebersihan harus dijaga terutama daerah luka operasi
jangan sampai terkena air selama 1 minggu (sampai
benar -benar kering)
3. Makanlah obat yang diberikan dokter secara teratur
sesuai petunjuk
4. Senggama boleh dilakukan setelah 1 minggu, yaitu
setelah luka operasi kering. Tetapi bila tubektomi
dilaksanakan setelah melahirkan atau keguguran,
senggama baru boleh dilakukan setelah 40 hari
Vasektomi (MOP)
1. Istirahat selama 1-2 hari dan hindarkan kerja berat selama
7 hari
2. Jagalah kebersihan dnegan membersihkan diri secara
teratur dan jaga agar luka bekas operasi tidak terkena air
atau kotoran
3. Makanlah obat yang diberikan dokter secara teratur sesuai
petunjuk
4. Pakailah celana dalam yang kering dan bersih, dan jangan
lupa menggantinya setiap hari
5. Janganlah bersenggama bila luka belum sembuh. Boleh
berhubungan seksual setelah tujuh hari setelah operasi.
Bila isteri tidak menggunakan alat kontrasepsi, senggama
dilakuakn dengan memakai kondom sampai 3 bulan
setelah operasi. Vasektomi dan sterilisasi tuba adalah
metode kontrasepsi permanen dan hanya dilakukan pada
pria maupun wanita yang sudah diberikan penjelasan
mengenai metode ini dan berkeinginan untuk secara
permanen mencegah kehamilan.
Beberapa metode sterilisasi ada yang bersifat
reversibel tergantung dari panjang saluran tuba, usia wanita,
dan jangka waktu antara sterilisasi dan pengembalian
kesuburan. Sterilisasi pada pria dilakukan melalui vasektomi,
sedangkan pada wanita dilakukan prosedur ligasi tuba
(pengikatan saluran tuba). Vasektomi sendiri dilakukan
dengan bius lokal sedangkan ligasi tuba menggunakan
prosedur intraabdominal. Konseling sebelum melakukan
prosedur ini sangat diperlukan. Bukan hanya konseling
mengenai risiko ataupun keuntungan operasi, namun juga
kemungkinan menyesali keputusan ini di masa depan nanti.
7) Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)
1. Profil
Gambar 42. IUD
a. Sangat efektif, reversibel dan berjangka panjang (dalam
sampai 10 tahun : CuT 380A)
b. Haid menjadi lebih lama dan banyak
c. Pemasangan dan pencabutan memerlukan pelatihan
d. Dapat dipakai oleh semua perempuan usia reproduksi
e. Tidak boleh dipakai oleh perempuan yang terpapar pada
Infeksi Menular Seksual (IMS)
2. Jenis
a. AKDR CuT-380A
Gambar 43. AKDR CuT-380A
Kecil, kerangka dari plastik yang fleksibel, berbentuk
huruf T diselubungi oleh kawat halus yang terbuat dari
tembaga Cu. Tersedia di Indonesia dan terdapat di mana-
mana.
b. AKDR lain yang beredar di Indonesia ialah NOVA T
(Schering)
c. Selanjutnya yang akan dibahas adalah khusus CuT-
380A
3. Cara kerja
a. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba
falopii.
b. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kacum
uteri.
c. AKDR bekerja terutama mencegah sperma dan ovum
bertemu, walaupun AKDR membuat sperma sulit masuk
kedalam sel alat reproduksi perempuan dan mengurangi
kemampuan sperma untuk fertilisasi.
d. Memungkinkan untuk mencegah implementasi telur
dalam rahim
4. Keuntungan
a. Sangat kontrasepsi, efektivitas tinggi.
b. Sangat efektif → 0,6 – 0,8 kehamilan /100 perempuan
dalam 1 tahun pertama (1 kegagalan dalam 125 – 170
kehamilan ).
c. AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan.
d. Metode jangka panjang (10 tahun proteksi dari CuT-380A
dan tidak tidak perlu diganti).
e. Sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat.
f. Tidak mempengaruhi hubungan seksual
g. Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu
takut untuk hamil.
h. Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah
abortus (apabila tidak terjadi infeksi)
i. Tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI
j. Dapat digunakan sampai menopause ( 1 tahun atau lebih
setelah haid terakhir)
k. Tidak ada efek samping hormonal dengan Cu AKDR
(CuT-380A)
l. Tidak ada interaksi dengan obat-obatan.
m. Membantu mencegah kehamilan ektopik.
5. Kerugian
a. Efek samping yang umum terjadi :
1) Perubahan siklus haid (umumnya pada 3 bulan pertama
dan akan berkurang setelah 3 bulan )
2) Haid lebih lama dan banyak
3) Perdarahan (spotting) antar menstruasi
4) Saat haid lebih sakit
b. Komplikasi lain
1) Merasakan sakit dan kejang selama 3 sampai 5 hari
setelah pemasangan.
2) Perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang
memungkinkan penyebab anemia.
3) Perforasi dinding uterus (sangat jarang apabila
pemasangannya banar).
4) Tidak mencegah IMS termasuk HIV/AIDS.
5) Penyakit radang panggul terjadi sesudah perempuan
dengan IMS memakai AKDR, PRP dapat memici
infertilitas.
6) Prosedur medis, termasuk pemeriksaan pelvik diperlukan
dalam pemasangan AKDR, seringkali perempuan takut
selama pemasangan.
7) Sedikit nyeri dan perdarahan (spotting) terjadi segera
setelah pemasangan AKDR. Biasanya menghilang dalam
1 – 2 hari.
8) Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri, dan hanya
boleh di lepas oleh petugas kesehatan yang terlatih.
9) Tidak mencegah kehamilan ektopik karena fungsi
AKDR untuk mencegah kehamilan normal.
10) Pasien harus memeriksakan posisi benang AKDR dari
waktu ke waktu. Untuk melakukan ini pasien harus
memasukkan jarinya ke dalam vagina. Sebagian
perempuan tidak mau melakukan hal ini.
6. Persyaratan pemakaian
a. Yang dapat mengguanakan
1) Usia produktif
2) Keadaaan nulipara
3) Menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka
panjang.
4) Menyusui yang menginginkan menggunakan
kontrasepsi
5) Setelah melahirkan dan tidak menyusui bayinya.
6) Setelah mengalami abortus dan tidak terlihat adanya
infeksi.
7) Resiko rendahdari IMS
8) Tidak menghendaki metode hormonal.
9) Tidak menyukai mengingat-ingat minum pil setiap
hari.
10) Tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari
senggama ( lihat kontrasepsi darurat).
Pada umumnya ibu dapat mengguanakan AKDR Cu dengan
aman dan efektif. AKDR dapat digunakan pada ibu dalam
segala kemungkinan keadaaan misalnya :
1) Perokok
2) Pasca keguguran atau kegagalan kehamilan apabila tidak
terlihat adanya infeksi.
3) Sedang memakai antibiotik atau anti kejang
4) Gemuk ataupun kurus
5) Sedang menyusui
Begitu juga dalam keadaan seperti dibawah ini dapat
memggunakan AKDR :
1) Penderita tumor jinak payudara
2) Penderita kanker payudara
3) Tekanan darah tinggi
4) Varises tungkai atau di vulva.
5) Penderita penyakit jantung
6) Pernah menderita stroke
7) Penderita Diabetes
8) Penderita penyakit hati atau empedu
9) Malaria
10) Skistosomiasis (tanpa anemia)
11) Penyakit tiroid
12) Epilepsi
13) Nonpelvik TBC
14) Setelah kehamilan ektopik
15) Setelah pembedahan pelvik.
7. Yang tidak diperkenankan menggunakan AKDR
a) Sedang hamil (diketahui hamil atau kemungkinan hamil).
b) Perdarahan vagina yang tidan diketahui
c) Sedang menderita infeksi genital ( vaginitis, servisitis)
d) Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering
menderita PRP atau abortus septik.
e) Kelainan bawaan utedapat mempengaruhi kavum uteri.
f) Penyakit trofoblas yang ganas
g) Diketahui menderita TBC pelik
h) Kanker alat genital
i) Ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm.
8. Waktu penggunaan
a) Setiap waktu dalam siklus haid yang dapat dipastikan klien
tidak hamil.
b) Hari pertama sampai ke 7 siklus haid.
c) Segera setelah melahirkan, selama 48 jam pertama atau
setelah 4 minggu pasca persalinan : 6 bulan apabila
menggunakan metode amenorea laktasi (MAL). Perlu
diingat, angka ekspulsi tinggi pada pemasangan segera atau
selama 48 jam pasca persalinan.
d) Setelah menderita abortus (segera atau dalam waktu 7 hari)
apabila tidak ada gejala infeksi.
e) Selama 1 sampai 5 hari setelah senggama yang tidak
dilindungi.
9. Petunjuk bagi klien
a) Kembali memeriksakan diri setelah 4 sampai 6 minggu
pemasangan AKDR
b) Selama bulan pertama menggunakan AKDR, Periksalah
benang AKDR secara rutin setelah haid, mengalami :
(1).Kram/kejang diperut bagian bawah
(2).Perdarahan (spotting) diantara haid atau setelah
senggama.
(3).Nyeri setelah senggama atau apabila pasangan
mengalami tidak nyaman selama melakukan hubungan
seksual.
c) Cupper T-380A perlu dilepas setelah 10 tahun pemasangan,
tetapi dapat dilakukan lebih awal apabila dilakukan.
d) Kembali ke klinik apabila :
(1).Tidak dapat meraba benang AKDR
(2).Merasakan bagian yang keras dari AKDR
(3).AKDR terlepas
(4).Siklus terganggu/meleset
(5).Terjadi pengeluaran dari vagina yang mencurigakan.
(6).Adanya infeksi
10. Informasi Umum
a. AKDR bekerja langsung efektif segera setelah pemasangan
b. AKDR dapat keluar dari uterus secara spontan, khusus
selama beberapa bulan pertama.
c. Kemungkinan terjadi perdarahan (spooting) beberapa hari
setelah pemasangan.
d. Perdarahan menstruasi biasanya akan lebih lama dan lebih
banyak.
e. AKDR mungkin dilepas setiap saat atas kehendak klien.
f. Jelaskan pada klien jenis AKDR apa yang digunakan, kapan
akan dilepas dan berikan kartu tentang semua informasi ini.
g. AKDR tidak melindungi diri terhadap IMS termasuk virus
AIDS, apabila pasangan berisiko, mereka harus
mengguanakan kondom seperti halnya AKDR.
B. Konsep Manajemen Pendokumentasian SOAP
1. Pendokumentasian SOAP
Manajemen kebidanan merupakan suatu metode atau bentuk
pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan
kebidanan. Asuhan yang telah dilakukan harus dicatat secar benar, jelas,
singkat, logis dalam suatu metode pendokumentasian.
Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian yang
dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah
dilakukan pada seorang klien, yang dialamnya tersirat proses berpikir yang
sistematis seorang bidan dalam menghadapi seorang klien sesuai langkah-
langkah dalam proses manajemen kebidanan.
Menurut Helen Varney, alur berpikir saat menghadapi klien
meliputi 7 langkah.Untuk orang lain mengetahui apa yang telah dilakukan
oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan
dalam bentuk SOAP, yaitu :
S = Subyektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien
melalui anamnese sebagai langkah I Varney.
O = Obyektif
Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien,
hasil laboratorium dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam
data focus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney.
A = Assesment
Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interprestasi
data subyaktif dan obyektif dalam suatu identifikasi :
a. Diagnosa/masalah.
b. Antisipasi diagnosa/masalah potensial.
c. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/
kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4
Varney.
P = Plan
Menggambarkan pendokumentasian dari tindakan (1) dan Evaluasi
perencanaan (E) berdasarkan assesmen sebagai langkah 5, 6, dan 7
Varney.
Beberapa alasan penggunaan SOAP dalam pendokumentasian :