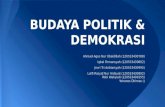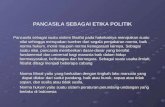4 demokrasi dan etika politik
-
Upload
wanda-ramadhan -
Category
Education
-
view
47 -
download
20
Transcript of 4 demokrasi dan etika politik
1. DEMOKRASI DAN ETIKA POLITIK Oleh Mulyadi J. Amalik, Peneliti dan Sekretaris Empowering Society Institute (ESI), Jakarta. Sejarah Demokrasi. Secara historis, demokrasi memang berkembang lebih dulu di dunia Barat, baik dalam teori maupun praktik. Pada mulanya demokrasi berkembang di Yunani sekitar abad ke-5 Sebelum Masehi (SM). Socrates (469-399 SM), Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan lain-lain adalah filsuf-filsuf yang memikirkan demokrasi. Fase ini disebut demokrasi zaman klasik. Fase demokrasi zaman modern dimulai sejak Abad Pencerahan (Abad ke-15 M hingga awal abad ke-18 M) di Eropa. Pada fase ini, perjuangan demokrasi dilakukan untuk melawan sistem pemerintahan monarkhi absolut yang dikuasai para bangsawan yang dilegitimasi lembaga gereja. Para tokoh pembahas demokrasi yang ngetop pada Abad Pencerahan ini ialah Niccolo Machiavelli (1469-1527) tentang republikanisme, Thomas Hobbes (1588-1679) tentang negara berdaulat yang kuat, John Locke (1632-1704) tentang liberalisme, dan Montesquieu (1689-1755) tentang Trias Politica. Konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu yang dikenal sebagai Trias Politica (pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif) itu dianut dalam sistem politik Indonesia. Masa demokrasi modern ini ditandai oleh Revolusi Amerika (1776) yang melahirkan demokrasi liberal dan federalisme, dan Revolusi Perancis (1789) yang melahirkan konsep undang-undang sipil dan hak asasi manusia universal dalam politik. Sistem peradilan Indonesia saja, misalnya, hingga kini mengadopsi sistem Eropa Kontinental dan produk hukum Indonesia setelah merdeka mewarisi produk hukum Belanda, sedangkan hukum Belanda dipengaruhi konsep Code Civil (Undang-undang Sipil) di Perancis. Pada awal abad ke-19 dan 20 pemikiran demokrasi bertumbuhan dengan wilayah pembahasan yang lebih luas. Konsep negara, sistem pemerintahan, ideologi (politik dan ekonomi), kelas dan konflik kelas, militer, partai politik, pemilihan umum, hubungan antarnegara, lembaga perdamaian internasional, dan lain-lain merupakan isu-isu yang bermunculan dari pemikiran para tokohnya. Pemikir-pemikir demokrasi di abad ini, antara lain JJ. Rousseau (1712-1778) dengan konsep kontrak sosial antara rakyat dan penguasa, John S. Mill (1806-1873) dengan konsep kebebasan (hak-hak individu) dalam demokrasi liberal dan demokrasi perwakilan, Alexis de Tocqueville (1805-1859) dengan konsep masyarakat sipil yang mandiri, Karl Marx (1818-1883) dan F. Engels (1820-1895) dengan konsep demokrasi langsung dan masyarakat sosial-komunal modern tanpa negara, atau Max Weber (1864-1920) dan J. Schumpeter (1883-1946) dengan konsep demokrasi perwakilan sebagai ajang kompetisi kaum elit. Di Indonesia, pemikiran demokrasi yang lebih beragam dan luas berkembang deras setelah masa kemerdekaan, sementara sebelumnya hanya berupa cita-cita membentuk negara merdeka atau berdaulat dari kungkungan penjajah. Para pemikir demokrasi kita tentu tak asing dan mereka adalah sarjana-sarjana yang banyak mempelajari pemikir-pemikir dunia, baik melalui sekolah formal maupun otodidak (belajar sendiri). Soekarno, Hatta, M. Natsir, Syahrir, Tan Malaka, D.N. Aidit, dan seterusnya adalah sebagian kecil dari banyak tokoh bangsa Indonesia yang memikirkan, menuliskan, dan memeraktikkan pandangan-pandangan demokrasi mereka sesuai ideologi masing-masing. Dinamika ideologis di kalangan pejuang demokrasi bangsa Indonesia itu tercermin pada substansi Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi semangat: 1) nasionalisme-sosialis; 2) sosialisme-demokrasi, dan 3) 1 2. nasionalisme-religius. Skema historis perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada tabel! Tidak adakah demokrasi di negara-negara miskin dan berkembang di Asia, Afrika, atau Amerika Latin sejak abad ke-18 hingga kini? Tentu ada cikal demokrasi asli yang bersumber dari kearifan lokal (tradisi/adat), agama, atau norma komunitas, tetapi itu tidak berkembang karena negara-negara miskin di benua tersebut kebanyakan berada di bawah jajahan bangsa- bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Nilai-nilai demokrasi pun tidak akan muncul dan berkembang di sebuah negara merdeka dan berdaulat bila pemerintahannya dipimpin oleh penguasa yang otoriter atau diktator. Secara teoretik, istilah demokrasi berada dalam bahasan tentang sistem politik, sedangkan istilah sosialisme atau kapitalisme masuk dalam bahasan tentang sistem ekonomi. Khusus tentang istilah komunisme cenderung atau sering dicampurkan sebagai bahasan sistem politik sekaligus sistem ekonomi. Penjelasan ini penting mengingat istilah- istilah tersebut memiliki banyak variasi di setiap negara dan merupakan ide-ide besar atau ideologi yang mempunyai landasan sejarah dan filsafat yang kuat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat, orang-orang, atau kelompok orang, sedangkan kratein berarti memerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan yang ditentukan oleh rakyat. Pada titik ini jelas bahwa demokrasi bertentangan dengan kekuasaan yang bersifat absolut, seperti kediktatoran, feodalisme, dan sejenisnya semisal fasisme (militerisme) atau tirani minoritas/mayoritas. Kunci demokrasi setidaknya terpaut pada 3 (tiga) prinsip besar, yaitu 1) konstitusional; 2) partisipatoris; dan 3) akuntabilitas. Demokrasi yang berjalan baik akan menghasilkan keseimbangan pergiliran kepentingan dan pemenuhan kebutuhan diantara pihak-pihak yang bersaing. Pada tingkat rakyat, demokrasi yang berjalan baik akan memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan atau pemerataan kesejahteraan karena negara atau pemerintah mesti mengaturnya setidaknya berdasarkan tiga prinsip besar itu. Di sinilah pemenuhan hak-hak asasi manusia mendapatkan wujud yang nyata dan demokrasi substansial pun sejalan lurus dengan demokrasi prosedural. Demokrasi substansial menyangkut pembentukan dan penegakan hukum, norma-norma atau nilai kebebasan, persamaan, kedaulatan rakyat, kesejahteraan bersama, atau hak-hak individu dan kolektif yang terangkum dalam hak asasi manusia universal. Demokrasi prosedural menyangkut hal-hal, seperti proses pemilihan umum, partai politik, parlemen atau lembaga legislatif/eksekutif, peran lembaga yudikatif, partisipasi rakyat, peran masyarakat sipil atau pelaku usaha, kelompok oposisi, lembaga pengawas, posisi media massa, dan semacamnya. Etika Politik Demokrasi di sini akan saya maknai lebih luas dan mendalam, yaitu sebagai proses kultural atau budaya. Lantaran itu, demokrasi seabagai perilaku atau norma budaya tersebut bisa dibahas dan dipraktikkan di lingkup-lingkup terkecil kehidupan kita, seperti dalam keluarga, dalam kelas di sekolah, di lingkup RT/RW, dalam organisasi adat, atau dalam kelompok pergaulan sehari-hari, dan seterusnya. Dengan demikian, demokrasi sebagai proses politik akan menjadi bagian kecil saja dari proses kultural atau budaya kita dalam hidup sehari-hari. Sebagai proses budaya, maka praktik demokrasi layak menghasilkan perilaku- perilaku beradab, bermoral, atau manusiawi, baik diperlihatkan oleh individu-individu maupun kelompok. Negarawan ialah seorang atau kelompok politisi yang menjadikan demokrasi sebagai proses budaya, meski diwarnai konflik dan perbedaan yang tajam. Itu tercermin dari para Bapak Bangsa kita, seperti Soekarno, Hatta, M. Natsir, dan lain-lain. Pada konteks inilah etika politik sangat berperan mengontrol sikap, pilihan, dan tindakan yang bersifat individual dan kelompok. 2 3. Apa itu etika? Sebelum masuk ke pembahasan tentang etika politik, kolom di bawah ini akan menjelaskan perbedaan mendasar antara etika dan moral (etiket): ETIKA MORAL (ETIKET) Bukan ajaran moral atau sistem nilai/norma, tetapi ilmu filsafat (filsafat moral) yang membahas ajaran moral atau sistem nilai/norma secara kritis dan sistematis. Merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai ajaran moral atau sistem nilai/norma yang terwujud dalam sikap/perilaku manusia sehari-hari (individu maupun kelompok). Memberikan pertanyaan fundamental pada ajaran moral atau sistem nilai/norma yang siap pakai bagi individu atau kelompok. Mengapa saya/kelompok harus memilih langkah atau cara berdasarkan sistem nilai/norma itu, dan apa alasan mendasar saya/kelompok melakukan tindakan itu? Menggugah pilihan sadar dan tanggung jawab seseorang/kelompok atas tindakan/perilakunya dalam menerapkan suatu ajaran moral atau nilai/norma tertentu. Membongkar kesadaran semu dan memberikan orientasi/arah ke mana dan bagaimana seseorang/kelompok harus melangkah dalam hidupnya. Merupakan ajaran moral atau sistem nilai/norma yang berisi anjuran pada individu/kelompok untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Memiliki sumber atau acuan yang sudah diterima masyarakat, seperti petuah, wejangan, peraturan, nasihat, kitab adat, atau kitab suci. Merupakan tindakan/perilaku atau kebiasaan yang diwariskan turun-temurun ke setiap generasi melalui sistem adat, agama, tradisi atau budaya, dan hukum. Memberikan perintah dan petunjuk dalam bertindak/berperilaku secara langsung dan praktis sehingga siap pakai bagi setiap individu atau kelompok dalam menentukan langkah yang baik dan buruk dalam hidup sehari-hari. Inilah cara atau jalan yang benar yang harus dipilih dan dilakukan! Berfungsi memberikan orientasi atau arahan pada manusia (individu maupun kelompok) untuk melangkah/bertindak ke mana dan bagaimana seharusnya dalam sepanjang hidup. Merupakan tindakan/perilaku yang berasal dari suara hati nurani, bukan emosional. Sumber: A. Sony Keraf, Etika Bisnis, 1991: 20-21; F. Magnis-Suseno, Berfilsafat Dari Konteks, 1992: 10-11; dan Majid Fakhry, Etika Dalam Islam, 1996: xv-xvi. Isi kolom diolah oleh MJA dari sumber-sumber tersebut. Berangkat dari kolom pembeda di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika politik merupakan pandangan filosofis yang merefleksikan secara kritis dan rasional sikap atau perilaku manusia sehari-hari (individu maupun kelompok) dalam proses demokrasi. Etika politik akan mengajukan pertanyaan fundamental pada sistem nilai atau norma yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam berpolitik atau proses demokrasi. Atas dasar apa dan mengapa sebuah kebaikan atau tindakan bermoral dilakukan seorang/sekelompok politisi dalam ranah politik dan proses demokrasi? Apakah tindakan moral itu asli dan dilakukan sebagai pilihan sadar atau palsu/semu dan dilakukan dalam keterpaksaan atau tekanan lingkungan/kelompok? Pertanyaan-pertanyaan etis di atas akan mengarah pada pilihan jawaban yang berasal dari suara hati nurani ataukah tindakan emosional. Dalam hal ini, etika politik berfungsi sebagai alat pembongkar atau penyingkap selimut-selimut palsu dan semu atas tindakan moral/norma atau kebaikan yang diterapkan seorang individu atau kelompok dalam berdemokrasi. Namun, etika politik tidak menjatuhkan vonis atau sanksi atas kepalsuan/kesemuan itu, melainkan 3 4. memberikan arah atau orientasi kepada sistem nilai/norma moral yang sejatinya, yaitu nilai/norma yang berasal dari suara hati nurani (beradab dan mengandung kebaikan untuk bersama dan orang lain). Meminjam opini Dr. Haryatmoko yang mengutip Paul Ricoeur (1990) dalam artikel Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus (www.duniaesai.com/filsafat/fil1.html, diakses Senin, 1 Maret 2010) bahwa tujuan etika politik terarah pada (1) hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka (2) memperluas lingkup kebebasan dan (3) membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tujuan ini saling terkait. Bagi Ricoeur, etika politik bukan cuma meneropong perilaku individual saja. Akan tetapi, etika politik pun meneropong tindakan kolektif sebab etika politik ialah etika sosial. Pada etika individual, seseorang dapat langsung bertindak menerapkan pandangannya di lapangan. Namun, pada etika politik (etika sosial), penerapan pandangan seseorang dalam tindakan memerlukan kesepakatan dan persetujuan warganegara sebanyak mungkin sebab sifatnya kolektif. Karena sifat hubungan antara pandangan hidup seseorang dan tindakan kolektif itu tidak langsung, maka memerlukan perantara sebagai jembatan penghubung. Simbol agama, sistem nilai atau norma, lembaga keadilan, nilai kebebasan, prinsip kesetaraan, dan sebagainya dapat berfungsi sebagai jembatan penghubungnya. Dengan demikian, etika politik berfungsi sebagai alat analisis dan refleksi kritis/rasional atas korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan institusi-institusi di masyarakat. Pancasila Sebagai Etika Politik. Cukup lama Pancasila mengalami kemerosotan citra akibat salah guna pada masa Orde Baru. Pancasila dijadikan alat pemukul oleh penguasa dalam bentuk asas tunggal untuk seluruh organisasi sosial dan politik. Pihak yang tidak setuju dianggap subversi sehingga harus direpresi dengan kekuatan militer dan birokrasi. Kini sudah saatnya Pancasila dikembalikan ke tempatnya yang mulia, yaitu sebagai fundamen etika politik khas Indonesia. Makna sila-sila Pancasila cukup menyuratkan dan menyiratkan sistem nilai yang relevan bagi praktik politik dan proses demokrasi nasional di Indonesia. Namun, Pancasila harus dipahami dulu dalam dua konteks yang niscaya. Pertama, konteks historis, yaitu Pancasila sebagai kontrak politik di antara para tokoh politik nasional Indonesia yang berbeda suku, bahasa, agama, dan ideologi. Di sini, Pancasila disepakati menjadi basis sistem nilai atau norma politik negara-bangsa Indonesia yang berisi substansi visi-misi negara Republik Indonesia masa depan. Kedua, konteks tekstual, yaitu Pancasila sebagai jiwa konstitusi negara-bangsa Indonesia atau merupakan dasar/sistem nilai bagi Batang Tubuh dan pasal-pasal dalam UUD 1945, termasuk hasil amandemen. Jadi, sila-sila Pancasila tidak bisa dipahami secara lepas terpisah dari keseluruhan teks Pembukaan UUD 1945 dan kemudian tidak dapat dilepaskan pula dari teks Batang Tubuh dan pasal-pasalnya. Pemahaman pada Pancasila berdasarkan dua kerangka itulah yang akan menjadikan dasar negara tersebut utuh-menyeluruh. Dengan begitu, cukup alasan menjadikan Pancasila sebagai dasar atau sistem nilai/norma berbangsa dan bernegara, baik dalam praktik politik (proses demokrasi) maupun praktik ekonomi. Bila Pancasila ditafsirkan terpisah dari teks Pembukaan UUD 1945 serta Batang Tubuh dan pasal-pasalnya sebagaimana terjadi pada era Orde Baru yang dipecah menjadi 36 butir nilai, maka akan terjadi kekaburan dalam praktik karena kehilangan konteks. Pancasila hanya menjadi slogan indah bak puisi saja. Padahal, tafsir konstitusional Pancasila sudah termaktub dalam Batang Tubuh dan pasal-pasal UUD 1945 sendiri yang selanjutnya harus menjadi rujukan bagi pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah di bawahnya. Inilah stadtfundamentalnorm masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara atau norma fundamental yang melandasi etika politik (proses demokrasi) Indonesia. 4 5. Dengan demikian, Pancasila sebagai etika politik khas Indonesia merupakan alat refleksi kritis dan rasional atas tindakan-tindakan moral para politisi atau penyelengara negara dan masyarakat. Etika politik berbasis nilai Pancasila itu dapat memeriksa apakah norma dan tindakan moralis yang diterapkan setiap insan/kelompok politik dalam proses politik/demokrasi mengandung kesesatan ataukah sesuai dengan Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pertanyaan-pertanyaan fundamental etika politik Pancasila pun menyediakan orientasi bagi para pelaku kesesatan itu agar kembali ke jalan yang benar, yaitu visi-misi bangsa sesuai pesan Pembukaan UUD 1945 serta Batang Tubuh dan pasal- pasalnya.** Catatan: Paper disampaikan pada peserta SEKOLAH DEMOKRASI OGAN ILIR oleh Yayasan PUSPA Indonesia dan KID di Inderalaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu, 20 Maret 2010. Daftar Pustaka. Anhar Gonggong, 2005. Soekarno dan Demokrasi Indonesia: Sebuah Pencarian (Presiden RI 1945- 1965) dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 5 No. 1/2005, Jakarta: The Habibie Center. Budi Setiawan, Pdt., Sejarah Demokrasi, dalam http://cwsgading.com/2009/08/31/sejarah- demokrasi/ tanggal 31 Agustus 2009, diakses Senin, 1 Maret 2010. Fatih Syuhud, A., Islam dan Demokrasi dalam Harian PELITA, 9 Nopember 2005. Hikam, Muhammad AS., Perkembangan Pemikiran dan Praktik Demokrasi dari Era Klasik Sampai Kontemporer, paper untuk Sekolah Demokrasi, Pertemuan II, diselenggarakan oleh Yayasan Averroes di Malang, 15 Maret 2008. Haryatmoko, Etika Politik, Bukan Hanya Moralitas Politikus dalam http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm atau http://www.duniaesai.com/filsafat/fil1.html, diakses Senin, 1 Maret 2010. Junarto Imam Prakoso, Memahami Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Bung Hatta (Wakil Presiden RI 1945-1956, Perdana Menteri RIS 1948-1950) dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 5 No. 1/2005, Jakarta: The Habibie Center. Magnis-Suseno, F., 1992. Berfilsafat Dari Konteks, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Majid Fakhry, 1996. Etika Dalam Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meyer, Thomas, 2002. Cara Mudah Memahami Demokrasi, Jakarta: Freidrich Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia. Omar Farooq, Mohammad, Islam and Democracy: Perceptions and Misperceptions, dalam Message International (Mei 2002) atau dalam serial The Independent Bangladesh (16 Juni 2002). Sony Keraf, A., 1991. Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur, Yogyakarta: Kanisius. Sastrapratedja, M., Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik dan Acuan Kritik Ideologi dalam http://www.psp.ugm.ac.id, diakses Senin, 1 Maret 2010. Teguh Apriliyanto, Mohammad Natsir: Islam, Kebangsaan, dan Demokrasi (Perdana Menteri NKRI, 6 September 1950-27 April 1951) dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 5 No. 1/2005, Jakarta: The Habibie Center. _________ dan Tata Mustasya, Sjahrir dan Sosialisme Indonesia (Perdana Menteri, 14 Nopember 1945-26 Juni 1947) dalam Jurnal Demokrasi & HAM Vol. 5 No. 1/2005, Jakarta: The Habibie Center. 5 6. Lampiran: SEGITIGA GOOD GOVERNANCE (TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK) NEGARA Masyarakat SipilPengusaha/ Pemilik Modal Sumber hukum: Pancasila & UUD 1945 Tata Kepemerintahan yg Baik: - Distribusi kekuasaan/kekayaan, Partisipasi rakyat, Pengawasan kebijakan, Konstitusional, Akuntabilitas, Penegakan hukum, kesetaraan, dst. Negara: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif; TNI, Polri, Komisi-komisi Negara. Pengusaha/Pemilik Modal: Konglomerat (Individu/Pelaku Usaha), BUMN, BUMD, Usaha Kecil (Rakyat), Perusahaan Swasta Nasional, Koperasi. Masyarakat Sipil: Media Massa, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Mahasiswa, Lembaga/Institusi/Paguyuban Rakyat, dsb. SISTEM POLITIK DAN EKONOMI Sistem Politik: - Demokrasi (Liberal, Perwakilan, Sosialis, Pancasila); - Monarkhi/Feodalisme; - Fasisme; - Teokrasi; - Komunisme. Sistem Ekonomi: - Kapitalisme/Liberalisme; - Neokapitalisme (Neoliberalisme); - Sosialisme; - Kesejahteraan; - Komunisme. 6 7. PRINSIP/NILAI DALAM DEMOKRASI Dalam praktek/proses berdemokrasi setidaknya ada tiga nilai atau prinsip yang diperlukan: 1. Kompromi. Dalam pemerintahan presidensil yang terbentuk melalui koalisi-multipartai seperti Indonesia saat ini, kompromi politik tdk bisa dihindari. 2. Toleransi. Nilai toleransi ini berguna untuk mendasari perilaku politik setiap orang agar terbiasa menerima perbedaan pendapat/ pandangan atau kepentingan orang lain. 3. Respek (Sikap hormat). Sikap hormat ini diperlukan dalam praktek/proses demokrasi agar setiap perbedaan sikap/pendapat atau pertentangan pilihan mendapat perlakuan yang manusiawi (adil dan beradab). 7