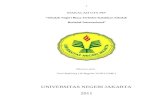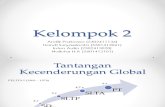06 Bab 6_Konsep Pengembangan_Akhir PIP Smg_Final
-
Upload
andon-setyo-wibowo -
Category
Documents
-
view
50 -
download
14
description
Transcript of 06 Bab 6_Konsep Pengembangan_Akhir PIP Smg_Final

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 1
BAB VI KONSEP PENGEMBANGAN PIP SEMARANG
6.1. Konsep Tata Tapak
6.1.1. Konsep Intensitas Bangunan
Lahan kampus PIP Semarang pada Tahun 2013 lebih kurang seluas 743.400 m2,
dengan luas daerah terbangun (KDB) lebih kurang 21829,50 m2 atau 29,36%. Luasan
RTH yang ada saat ini tersisa lebih kurang 17,27%. Sedangkan luasan terbesar adalah
perkerasan halaman termasuk lapangan parkir, lapangan olah raga dan lapangan upacara
dan perkerasan jalan dengan total luasan 56,44%. Gambaran lengkap luasan lahan dan
bangunan yang ada pada saat ini di PIP Semarang dapat dilihat pada Tabel 4.7 pada Bab
IV.
Ditinjau dari KDB, kondisi intensitas bangunan PIP Semarang masih cukup
memadai sesuai dengan ketentuan tata ruang setempat. Namun RTH yang tersedia
kurang dari standar penyediaan RTH untuk kawasan perkotaan yang minimal 30% untuk
RTH Publik dan Privat. Sedangkan luasan perkerasan lahan jauh melebihi standar
penyediaan prasarana jalan.
Sebagai dampak daripada kondisi ini, maka luasan daerah untuk peresapan air
hujan pada lahan PIP sangat kurang, dan menjadi salah satu penyebab lamanya genangan
air hujan yang terjadi pada lokasi lahan.
Jarak antar massa bangunan pada beberapa kondisi eksisting lokasi kurang dari
3,00 meter bahkan hanya 2,00 meter. Ditinjau dari keselamatan kebakaran, jarak
bangunan yang terlalu dekat akan lebih mempercepat penjalaran kebakaran. Meskipun
demikian pengelola PIP berusaha mengantisipasi keadaan ini dengan memperbanyak
jumlah hidran kebakaran khususnya pada lorong-lorong bangunan yang berdekatan.
Ditinjau dari tampak/façade bangunan yang berdekatan sangat mengganggu
estetika setiap bangunan. Selain itu dampak lain daripada saling berdekatannya massa
bangunan satu dengan lainnya adalah berkurangnya kenyamanan bagi setiap pengguna
bangunan ditinjau dari aliran udara, pencahayaan, penghawaan, dan gangguan
pandangan.
Oleh karena itu konsep penataan tapak untuk jarak-jarak antar bangunan sesuai
dengan ketentuan minimum jarak antar bangunan untuk bangunan dengan ketinggian 6
lantai adalah 6.00 meter, dan seterusnya sesuai dengan Permen PU Nomor
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 2
Gedung dan Lingkungan, untuk memberikan ruang akses keselamatan kebakaran dan
prasarana pemadam kebakaran, termasuk mobil PMK.
Gambar 6.1. Jarak antar bangunan gedung bertingkat
Tabel 6.1. Jarak Minimum Antar Bangunan
Sumber: Permen PU Nomor 26/PRT/M/2008
6.1.2. Penataan Site/Zoning
Zoning penataan massa pada kondisi eksisting tidak mengelompok sesuai dengan
fungsi kegiatannya. Misalnya bangunan Pusat Administrasi dan Pimpinan PIP berdekatan
dengan Asrama mahasiswa Putra. Asrama mahasiswa sendiri yang seharusnya terletak
pada zona privat saat ini tersebar pada beberapa lokasi, bahkan berada pada zona publik
yang mempunyai tingkat kebisingan lebih tinggi dan sedikitnya privacy.
Fasilitas Poliklinik sebagai sarana pelayanan publik yang ada saat ini berada pada
zona semi publik yang melintasi zona privat. Masyarakat sekitar yang hendak ke Poliklinik
harus masuk melalui Lapangan Upacara dan garasi kendaraan. Sementara untuk
Workshop dan garasi kendaraan yang seharusnya berada di zona semi publik berada pada
zona semi privat yang harus melintasi zona privat.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 3
Fasilitas penunjang pendidikan seperti Perumahan Dosen dan Karyawan serta
Wisma Tamu yang ada menempati lahan yang cukup luas di sisi selatan dan timur
kompleks, berada pada zona semi publik dengan gangguan kebisingan dari luar, karena
berdekatan dengan jalan lokal kota. Sementara itu lokasi-lokasi untuk laboratorium
tersebar di sisi utara hingga sisi selatan kompleks PIP. Gambaran zoning penataan massa
bangunan kompleks PIP Semarang dapat dilihat pada Gambar 6.2. dan Gambar 6.3.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 4
Gambar 6.2. Analisa Tatanan Massa dan Zoning Bangunan di dalam Kompleks PIP Semarang
Gambar 6.3. Analisa Zoning Massa Asrama Kompi PIP Semarang.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 5
Dengan mempertimbangkan efisiensi lahan dan tata letak bangunan eksisting yang
baru, maka konsep zoning yang diusulkan untuk rencana pengembangan PIP Semarang
hingga Tahun 2034 adalah memisahkan Zona untuk Pembentukan Taruna dan Zona
untuk Diklat Lanjutan Pasis, serta Zona untuk kegiatan Administrasi Akademik dan
Ketarunaan. Adapun konsep zoningnya adalah sebagaimana tergambar pada Gambar 6.4
di bawah ini.
Gambar 6.4. Konsep Zoning PIP Semarang.
6.1.3. Konsep Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Pada awal hingga pertengahan usia PIP Semarang ini, masih Nampak jejak
tatanan massa membentuk cluster-cluster dengan orientasi pada RTH-RTH yang ada,
meliputi RTH Lapangan Upacara, RTH Lapangan Sepak Bola dan RTH Lapangan Tennis.
Pada tahun 2011 terdapat pengembangan Gedung Sistem Navigasi Terpadu dengan
ketinggian 4 lantai, menempati lahan lapangan Tennis seluas dua lanes, sehingga
mengurangi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada.
Proporsi penyediaan RTH pada setiap cluster kelompok bangunan tidak merata.
Pada cluster bangunan Administrasi Pusat, Gedung Pollux, Auditorium, PMMK dan
Asrama Kompi C, terdapat RTH dengan luasan sangat kecil, dan yang terluas
dipergunakan untuk RTNH Lapangan Upacara dan lapangan olah raga bola. Pada saat
siang hari udara disekitar RTNH terasa panas. Beberapa bangunan tanpa barrier RTH
yaitu bangunan PMMK dan Gedung Administrasi Pusat. Padahal intensitas penggunaan
bangunan-bangunan ini pada siang hari sangat tinggi, kecuali Gedung Auditorium yang
jarang dipergunakan untuk keperluan kegiatan harian.
Zona Privat
(Taruna)
Zona Privat
(Taruna)
Zona Semi Publik
(Pasis)
Zona Semi Privat
(Taruna)
Zona Semi Privat
(Taruna)
Zona Semi Privat
(Taruna)
Zona Privat
(Dosen-
Karyawan)
Zona Servis
Zona
Servis
Zona Buffer
Zona
Buffer

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 6
Sebaliknya pada zona banguna-bangunan dengan intensitas kegiatan yang rendah
pada siang hari, mempunyai RTH Lapangan Sepak Bola yang luas. Bangunan-bangunan
yang mengelilinginya yaitu kompleks perumahan dosen dan karyawan, Asrama Kompi A
dan Asrama Taruni, dan Kolam Renang.
Gambar 6.5. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan RTH PIP Semarang.
Konsep penyediaan RTH PIP Semarang didasarkan pada analisis perhitungan
RTH yang dilakukan pada Bab 3 sebelumnya, memperoleh luasan yang mendekati ideal
30% yaitu sebesar 28,51%. Upaya pendekatan ke luasan ideal dilakukan dengan
memperluas permukaan hijau, sehingga permukaan peresapan air tetap terjaga.
Perkerasan jalan direncanakan lebih efisien dengan memperpendek akses area servis dan
pedestrian penghubung antar bangunan.
Adapun konsep penyediaan RTH adalah sebagai berikut pada Gambar 6.6.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 7
Gambar 6.6. Konsep Penyediaan RTH PIP Semarang.
Konsep penyediaan RTH PIP Semarang meliputi juga konsep pemanfaatan
tanaman yang berfungsi sebagai pelindung/peneduh, barrier/penahan terhadap
kebisingan, penyerap polusi udara, barrier untuk zona yang harus dipisahkan, pengarah
sirkulasi, dan estetika taman. Pemilihan jenis tanaman mengikuti bentuk RTH yang
direncanakan sebagai hasil bentukan massa-massa bangunan baru, mengikuti jenis tanah
dan iklim mikro setempat. Konsep rencana RTH juga mempertimbangkan peningkatan
fungsi taman sebagai salah satu ruang belajar Taruna pada zona-zona asrama.
6.1.4. Konsep Sirkulasi dan Aksesibilitas
Sirkulasi pada kompleks PIP Semarang dibedakan menjadi sirkulasi kendaraan
dan orang. Sirkulasi kendaraan terdiri dari kendaraan pribadi berupa mobil dan sepeda
motor, kendaraan umum, kendaraan servis. Sedangkan sirkulasi orang dibedakan untuk
sirkulasi pengguna fasilitas PIP dan sirkulasi tamu.
Sirkulasi kendaraan mobil pribadi tamu dan dosen/karyawan hanya
diperbolehkan berada pada sisi barat lahan PIP Semarang. Untuk sirkulasi kendaraan
pribadi pengguna fasilitas perumahan boleh memasuki kawasan perumahan dosen dan
karyawan pada zona perumahan di sisi selatan dan timur. Jalan lingkungan ke perumahan
in juga dipergunakan oleh kendaraan servis untuk kegiatan penyediaan catering.
Sedangkan kendaraan sepeda motor untuk mahasiswa training profesi dan tamu berada
pada zona parkir sisi barat, dimana yang ada pada bagian utara berada pada zona publik,
sedangkan pada sisi selatan berada pada zona privat. Kondisi parkir sepeda motor pada
sisi selatan ini kurang menguntungkan dan mengganggu kegiatan belajar siswa pada
Gedung Betelgeuse.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 8
Pintu masuk dan keluar untuk kendaraan mobil dibedakan. Kendaraan masuk dari
sisi pintu utara, sedangkan kendaraan keluar dari sisi selatan. Sedangkan untuk sepeda
motor masuk dan keluar dari sisi utara sama dengan pintu masuk mobil. Kendaraan servis
juga masuk dari pintu utara. Untuk memudahkan pengontrolan secara tersentralisasi,
disarankan pintu keluar dan masuk untuk kawasan PIP ini dari satu pintu saja, sedangkan
pintu lainnya disediakan untuk kebutuhan darurat.
Sirkulasi Mobil Pribadi
Sirkulasi Kendaraan Servis
Gambar 6.7. Analisa Sirkulasi Kendaraan pada PIP Semarang
Pejalan kaki disediakan jalan dan koridor yang semuanya diperkeras. Namun
untuk hubungan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, pedestrian yang
disediakan tidak beratap, sehingga pada saat musim hujan pejalan kaki tidak terlindungi.
Seharusnya setiap bangunan dengan bangunan lainnya dapat dihubungkan dengan
koridor selasar beratap.
Konsep penediaan pedestrian pejalan kaki untuk rencana pengembangan PIP
Semarang hingga Tahun 2034 adalah menata pedestrian eksisting yang ada dengan
mengurangi perkerasan yang tidak efektiv. Lebar pedestrian efektif 1.80 meter dengan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 9
diberi atap sehingga pejalan kaki terlindung dari hujan. Gambaran konsep pengembangan
sirkulasi kendaraan dan orang dapat dilihat pada Gambar 6.8 di bawah ini.
Sirkulasi Mobil/Motor
Sirkulasi Kendaraan Servis
Sirkulasi Kendaraan PMK
Sirkulasi Pejalan Kaki
Gambar 6.8. Konsep Sirkulasi Kendaraan dan Orang pada PIP Semarang
Sirkulasi pejalan kaki disediakan pula untuk penyandang cacat dengan penyediaan
ramp pada perbedaan ketinggian lantai dari trotoar di luar bangunan menuju ke dalam
bangunan, dilengkapi dengan railing pembatas ramp untuk pegangan penyandang cacat
sebagaimana dicontohkan pada Gambar 6.9 berikut ini.
Gambar 6.9. Contoh Railing Pembatas Ramp bagi Penyandang Cacat pada PIP Semarang

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 10
6.1.5. Konsep Ketinggian Bangunan
Evaluasi skala ruang pada kondisi susunan massa eksisting dibagi menjadi 2 yaitu
skala ruang sisi luar (dekat dengan jalan raya) dan skala ruang sisi dalam (antar bangunan
dalam area).
1. Skala Ruang Sisi Luar
Ada 4 sisi yang akan dievaluasi yaitu sisi barat, utara, timur dan selatan
a. Sisi barat
Bangunan-bangunan PIP Semarang adalah Laboratorium Dynamic Positioning,
ruang kelas Betelgeuse, ruang kelas Pollux, laboratorium skoci, dan laboratorium
meti. Bangunan-bangunan tersebut memiliki ketinggian 2 hingga 4 lantai.
Bangunan yang paling dekat dengan badan jalan adalah gedung Laboratorium
Dynamic Positioning. Gedung ini memiliki pemunduran hanya 15,00 m dari badan
jalan dengan tinggi bangunan keseluruhan adalah 20,00 m (termasuk atap) , maka
bila dihitung skala ruang yang tercipta adalah D/H = /= (>1). Dengan demikian
skala ruang di sisi barat masih terasa agak lebar.
b. Sisi utara
Bangunan-bangunan PIP Semarang yang berada di sisi utara adalah Laboratorium
navigasi. Gedung Laboratorium navigasi memiliki tinggi total bangunan 15 m
(termasuk atap) dengan pemunduran 15,00 m. Skala ruang yang tercipta di sisi
utara PIP Semarang adalah sebagai berikut:
• D/H Gedung Laboratorium navigasi = 15/15 = 1,0 (=1)
Dari perhitungan, maka dapat dilihat bahwa skala ruang bangunan di sisi utara
masih cukup lebar.
c. Sisi timur
Bangunan-bangunan PIP Semarang yang berada di sisi timur adalah asrama
kompi F, engine hall, laboratorium bengkel, lab.komputer, poliklinik, asrama
kompi C, asrama kompi B, dan komplek perumahan dinas. Bangunan-
bangunan tersebut memiliki ketinggian 2 lantai. Bangunan yang paling dekat
dengan badan jalan adalah gedung asrama kompi B. Ada gedung yang tidak berada
dalam satu tapak yaitu gedung asrama kompi F berada di seberang jalan kawasan
pendidikan dengan ketinggian 3 lantai.
Gedung tersebut memiliki pemunduran m dari badan jalan dengan tinggi
bangunan keseluruhan adalah 12,00 m (termasuk atap) , maka bila dihitung skala
ruang yang tercipta adalah D/H = /= (>1). Dengan demikian skala ruang di sisi
barat masih terasa agak lebar.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 11
d. Sisi selatan
Bangunan-bangunan PIP Semarang yang berada di sisi selatan adalah bangunan
perumahan dinas. Bangunan-bangunan tersebut memiliki ketinggian 1 - 2 lantai.
Bangunan yang paling dekat dengan badan jalan adalah gedung Maisone B.
Gedung tersebut memiliki pemunduran 15,00 m dari badan jalan dengan
tinggi bangunan keseluruhan adalah 12,00 m (termasuk atap) , maka bila dihitung
skala ruang yang tercipta adalah D/H = /= (>1). Dengan demikian skala ruang di
sisi barat masih terasa lebar.
Pengaturan ketinggian bangunan dilakukan dengan menata jarak bangunan tinggi
terhadap zona-zonanya. Untuk zona publik, disisi timur ketinggian bangunan sampai
dengan 6 lantai dengan jarak minimum D = H sehingga fasade bangunan pada bagian atas
masih dapat dilihat dengan nyaman dari jalan di sekitar kawasan. Untuk bangunan
dengan ketinggian 8 lantai dimundurkan terhadap sempadan pagar kawasan sehingga
masih tercapai D = H. Sedangkan untuk bangunan di sisi timur, utara dan selatan dengan
kelas jalan lingkungan ketinggian bangunan 5 lantai dengan jarak D = 2/3 H.
6.2. Konsep Arsitektural
6.2.1. Konsep Tampilan Arsitektur
Rancangan arsitektur sebuah kawasan pendidikan selain menekankan kelancaran
dan keefektifan beroperasi unit/bagian secara menyeluruh dan intergratif juga
memperhatikan penampilan arsitektur, yang berpengaruh pada respon subyektif
pengguna maupun pengamat.
Dalam perancangan sebuah kawasan pendidikan ada tiga aspek yang menjadi
pertimbangan, yakni efektifitas (effectiviness), kedekatan/keterhubungan (contiguity),
dan kemungkinan tumbuh/pengembangan (expansion). Ketiga aspek ini dikaji pada dua
skala arsitektur sebagai berikut:
1. Ruang, yang memperhatikan permasalahan-permasalahan sirkulasi pengguna (civitas
akademik, pengunjung, bahan/alat, kendaraan, informasi, dsb), kenyamanan
pengguna secara umum maupun civitas akademik khususnya, dan fleksibilitas
(kemampuan rancangan untuk tumbuh dan berubah).
2. Bangunan, yang melihat permasalahan-permasalahan citra/image (identitas dan
kesan visual), kemudahan pengenalan (legibility) dan pencarian/berorientasi
(wayfinding).
Evaluasi pada dua skala arsitektur di atas (ruang dan bangunan) adalah untuk
mengungkap permasalahan dan potensi arsitektural pada eksisting PIP Semarang.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 12
Evaluasi arsitektural dibatasi pada evaluasi terhadap kondisi fisik bangunan, sedangkan
evaluasi fungsi akan diberikan pada bagian lain yang memfokuskan pada aspek program
arsitektur (architectural programming). Beberapa bagian evaluasi yang terkait dengan
evaluasi tata tapak akan dibahas secara umum.
a. Kenyamanan
Yang dimaksud dengan kenyamanan adalah tampilan bangunan yang
mencerminkan adaptasi dengan iklim mikro dengan bukaan dan ventilasi silang
sebanyak mungkin. Hal ini dapat diterapkan pada massa bangunan-bangunan
yang ruangnya berjajar maksimum dua baris yang masih memungkinkan
terjadinya pertukaran udara. Pada bangunan asrama taruna kenyamanan ruang
hunian dicapai dengan memberikan perteduhan berupa selasar di sekeliling
bangunan guna mengisolir terjadinya paparan sinar matahari langsung.
Pada bangunan-bangunan yang direncanakan dengan massa yang kompak dan
besar untuk mencapai kenyamanan optimal digunakan pengkondisian udara
buatan, walaupun digunakan permukaan dinding dengan banyaknya bukaan kaca
untuk mendapatkan kenyamanan penerangan matahari tidak langsung dan
penghematan penggunaan energi listrik, khususnya untuk mengantisipasi pada
saat kondisi listrik mengalami gangguan.
b. Fleksibilitas
Fleksibilitas penggunaan ruang direncanakan dengan konsep menggunakan sekat
dinding non permanen sebanyak mungkin dan menghidari penggunaan sekat
dinding permanen pada fungsi-fungsi ruang yang membutuhkan fleksibilitas
tinggi. Ruang-ruang yang dimaksud adalah:
• Auditorium, dan ruang-ruang untuk pertemuan sedang dan besar,
• Ruang kerja dengan karyawan yang banyak,
• Kelas yang membutuhkan ruangan besar,
• Laboratorium yang membutuhkan ruangan yang tidak menghambat
instalasi peralatan dan penggunaannya, dan
• Fungsi rekreatif untuk olah raga dan pertemuan untuk orang banyak
6.2.2. Skala Bangunan
a. Citra (image)
Dua hal penting yang dapat dicatat dari kesan visual yang dapat ditangkap dari PIP
Semarang adalah pertama sudah berkurangnya kesan menerima yang diharapkan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 13
pada sebuah fasilitas pelayanan pendidikan pelayaran, kedua ketidak serasian
pada sebagian arsitektur bangunan eksisting dengan bangunan baru.
Walaupun secara umum kesan ramah, bersih, nyaman dan lapang yang
diharapkan pada sebuah kawasan pendidikan sudah tercipta di PIP Semarang ,
kesan menerima di bagian depan komplek sudah mengalami penurunan kualitas.
Arsitektur bangunan utama lebih menonjolkan fungsi awal sebagai kantor,
administrasi dan rekam medik, yang kurang terintegrasi pada keseluruhan citra
kawasan pendidikan pelayaran. Permasalahan kedua yang terkait dengan
ketidakserasian arsitektur di dalam komplek PIP Semarang sesungguhnya timbul
karena belum adanya panduan umum untuk pengembangan kawasan pendidikan
pelayaran. Sehingga yang terjadi adalah setiap bangunan baru cenderung
menampilkan kesan visual baru. Hal ini akan mempengaruhi citra komplek secara
menyeluruh.
Gaya arsitektur modern dengan penggunaan material ramah lingkungan dan
modern dengan sentuhan Arsitektur bercirikan tradisional dan ornamen pada
masa lalu perlu diterapkan untuk menciptakan citra kekhasan keadaan lokal dan
lingkungannya. Ciri-ciri lokalitasnya dapat ditampilkan pada penggunaan elemen
finishing bagian bawah bangunan, kolom, bagian luar jendela/pintu dan bagian
atap. Sedangkan nuansa elemen arsitektur Jawa Tengah dapat diterapkan lebih
kental pada bagian interior setiap bangunan, khususnya untuk bangunan Gedung
Direktorat dan Gedung Auditorium.
b. Kemudahan Pengenalan (Legibility) dan Pencarian/ Berorientasi
(Wayfinding)
Faktor lain yang terkait langsung dengan citra atau kesan visual arsitektur adalah
kemudahan pengenalan dan pencarian/berorientasi. Perlu menghadirkan ikon
khusus sebagai penanda keberadaan PIP Semarang pada lingkungannya sehingga
dapat memberikan arahan yang jelas bagi pengguna. Pola tata masa di dalam
bangunan dengan zoning yang jelas membantu kemudahan pengguna untuk
berorientasi (wayfinding) dan menuju tempat/ bangunan yang dikehendaki.
Sistem penandaan arah ataupun nama tempat/bangunan masih di rasa kurang di
PIP Semarang. Pemberian nama pada tiap bangunan, peta atau penunjuk arah
pada simpul-simpul sirkulasi selain untuk kemudahan kontrol keamanan, juga
untuk menghindarkan pengguna untuk menempuh jalur-jalur sirkulasi yang tidak
diperlukan.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 14
6.3. Konsep Mekanikal dan Elektrikal
Kebutuhan pengembangan mekanikal dan elekteikal pada PIP Semarang
didasarkan pada kebutuhan penyediaan/daya tampung maksimal taruna yang harus
dilayani sesuai dengan SPM PIP, dan kebutuhan pasokan daya listrik dan sumber air
untuk penyelenggaraan kegiatan rutin akademik. Untuk memenuhi kebutuhan mekanikal
dan elektrikal yang direncanakan berikut ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi
secara kuantitas.
A. Perhitungan Kebutuhan Listrik
Estimasi perhitungan daya listrik PIP Semarang hingga pada Tahun 2034 didasarkan
pada perhitungan dengan pendekatan luas per meter persegi kebutuhan penerangan,
beban pengkondisian udara (AC) untuk bangunan-bangunan gedung yang
membutuhkan persyaratan ini, dan muatan untuk titik-titik sambungan listrik.
Dari hasil perhitungan beban listrik yang direncanakan per-bangunan selanjutnya
dihitung total kebutuhan daya untuk seluruh bangunan untuk mendapatkan
gambaran kapasitas trafo yang harus disediakan dan kapasitas genset sebagai back-
upnya. Dari total kapasitas yang diperoleh disesuaikan dengan ketersediaan trafo dan
genset di pasaran, selanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub-zona pelayanan. Dari
kondisi eksisting PIP disuplai daya dari 2 jalur PLN yang berasal dari Jl. Sriwijaya dan
Jl. Mataram. Maka untuk penambahan daya yang dibutuhkan pada perhitungan
rencana nantinya juga bersumber dari dua sambungan yang tersedia tersebut.
B. Perhitungan Kebutuhan Air Conditioning
Estimasi perhitungan kebutuhan AC untuk PIP Semarang hingga pada Tahun 2034
didasarkan pada kebutuhan pendinginan dari bangunan-bangunan yang
membutuhkan persyaratan pengkondisian udara yang meliputi:
1) Gedung Direktorat pada Lantai 1 – 8.
2) Gedung Auditorium pada Lantai 2 – 6, Lantai 1 untuk kantin/pujasera
menggunakan fan karena dinding bangunan terbuka.
3) Gedung Perkuliahan Betelgeuse Baru pada Lantai 2 – 5. Lantai 1 untuk parkir
kendaraan bermotor, dan Lantai 6 untuk Aula menggunakan fan dengan ventilasi
udara pada jendela sisi memanjang untuk mendapatkan penghawaan silang.
4) Gedung Perkuliahan Pollux Baru pada Lantai 1 – 5. Lantai 6 untuk Aula
menggunakan fan dengan ventilasi udara pada jendela sisi memanjang untuk
mendapatkan penghawaan silang.
5) Gedung Diklat Pasis pada Lantai 2 – 6. Lantai 1 untuk parkir kendaraan bermotor.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 15
6) Gedung Laboratorium Terpadu pada Lantai 1 – 3 untuk keseluruhan ruangan.
7) Gedung Poliklinik pada Lantai 1 – 3.
8) Apartemen Dosen pada Lantai 2 – 7. Lantai 1 untuk kebutuhan parkir kendaraan
bermotor.
9) Rusun Karyawan hanya sebagai opsi diperhitungkan penyediaan daya untuk
sambungan AC sebesar 50% dari jumlah seluruh unit hunian yang membutuhkan.
Bentuk gedung Rusunnya sendiri dirancang dengan menggunakan sistem ventilasi
mekanis.
10) Guest House pada Lantai 1 – 3.
11) Sedangkan untuk gedung-gedung asrama tidak memerlukan pengkondisian udara,
kecuali hanya sistem ventilasi mekanis.
Perhitungan instalasi tata udara untuk proyek ini bertujuan untuk mengkondisikan
udara didalam ruangan sesuai dengan standar kenyamanan penghuni, atau pun
keperluan kebutuhan pengkondisian peralatan yang ada diruangan. Sistem
pengkondisian di dalam gedung ini meliputi usaha- usaha sebagai berikut :
a) Menjaga dan mengatur temperatur udara didalam ruangan pada yang relatife
konstan sesuai dengan standar kenyamanan penghuni ataupun kebutuhan
bagi peralatan.
b) Menjaga dan mengatur kelembaban relatif udara didalam ruangan pada batas-
batas yang masih memenuhi sesuai dengan standar kenyamanan yang berlaku
bagi penghuni ataupun kebutuhan peralatan.
c) Membuat aliran udara luar yang segar dan bersih dalam jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan.
d) Menambahkan udara luar yang segar dan bersih dalam jumlah yang sesuai
dengan kebutuhan.
e) Menjaga dan mengusahakan agar kebisingan maupun getaran – getaran yang
yang ditimbulkan oleh instalasi tata udara dan ventilasi mekanis, berada pada
tingkat kebisingan yang rendah sesuai dengan noise level yang ditentukan bagi
ruang-ruang tersebut.
Sistem ventilasi mekanis yang akan dirancang antara lain adalah berupa:
a) Mengadakan pertukaran udara secara mekanis/natural di ruang-ruang
seperti, toilet/WC, dapur, dengan tujuan menambah oxygen dan membuang
bau yang tidak sedap, menambahkan O2 serta menurunkan akumulasi panas
(temperature) di ruang M&E.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 16
b) Memberikan tekanan lebih pada tangga kebakaran saat terjadi kebakaran.
Dengan standard maksud agar asap tidak masuk kedalam tangga saat terjadi
evakuasi.
c) Melakukan pengendalian terhadap asap pada saat kebakaran pada lantai yang
bersangkutan maupun lantai lainnya.
Sistem tata udara pada bangunan-bangunan yang menggunakan pengkondisian udara
dengan menggunakan AC Single Split/duct/center. Sistem tata udara yang
direncanakan sesuai dengan standard yang berlaku.
C. Perhitungan Kebutuhan Tata Suara
1) Dasar Perhitungan
Sebagai dasar perencanaan digunakan referensi sebagai berikut :
a. Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000
b. Simens Catalog TS 1, part 4, 2nd edition
c. Buyer, A Guide to electro acoustic
Dasar Perencanaan ini dipilih sesuai dengan fungsi ruangan dan fungsi peralatan
serta didasarkan pada beberapa patokan/asumsi sebagai berikut :
1. Noise Level
• Pantry 40 – 45 dB
• M/E Room 45 – 55 dB
• Parkir 60 – 75 dB
• Lobby 40 – 60 dB
• Koridor 40 – 45 dB
• Office 30 - 40
2. Agar suara dari speaker terdengar jelas, maka sound levelnya minimal
mempunyai margin 6 dB diatas noise level. Agar terdengar jelas dan enak
untuk suara music maka margin haruslah 10 dB, sedangkan untuk suara
panggilan/pengumuman, margin haruslah 15 – 20 dB diatas noise.
Margin = Sound Level – Noise level atau
Sound level = Noise Level + Margin (dB)
3. Daya yang keluar dari Power Amplifier harus tidak lebih kecil dari jumlah daya
yang diperlukan oleh loud speaker dalam keadaan emergency warning.
Po (amplifier) > P (emergency)
4. Lebar Frekuensi untuk music Hifi 16 Hz – 16 kHz
Lebar frekuensi untuk paging/public address 100 Hz – 10 kHz

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 17
5. Karena kabel antara amplifier dan speaker cukup jauh maka dipilih
pengiriman sinyal suara pada saluran independensi tinggi atau line sinyal
voltage 100 volt.
6. Diusahakan digunakan sebanyak mungkin peralatan dengan spesifikasi yang
sama, untuk memudahkan pemeliharan.
2) Sistem yang Dibutuhkan
1. Program : Car Call, Emergency/Evacuation, Paging.
2. Direncanakan sentral Sound System di ruang Kontrol kantor manajemen.
Sentral Sound System diruang Kontrol digunakan untuk panggilan darurat
(Emergency Paging)
3. Tanda bahaya dan Pengumuman Keadaan Darurat
Keadaan darurat/bahaya misalnya karena adanya gejala sumber kebakaran,
gangguan keamanan atau huru – huru. Informasi yang disampaikan berupa
penjelasan mengenai situasi, pengarahan untuk penyelamatan (evakuasi) atau
tanda bahaya bila keadaan telah betul – betul gawat.
Cara menyampaikan bisa secara selektif atau all-call. Selektif dipilih bila untuk
menghindari kepanikan dan kemacetan pada satu pintu atau jalan keluar.
All-call dipilih bila keadaan sudah tak terkendali lagi.
Emergency call merupakan prioritas pertama yang dapat meng-override
semua siaran.
4. Car Call System
Speaker tersebar diseluruh daerah parkir mobil.
3) Peralatan yang Dipakai
1. Mikrofon : alat transducer yang merubah kekuatan suara (audio), dari orang
atau instrumen musik menjadi besaran arus listrik sehingga bias diperkuat /
diproses oleh peralatan elektronik.
2. Pre-Amplifer : Alat elektronik yang memperkuat singnal listrik dari mikrofon
atau dari sumber signal lainnya pada tahap awal (pendahuluan) sehingga
tegangan output cukup kuat untuk di beri penguat daya (power).
3. Power Amplifier : Alat elektronik yang memperkuat tegangan output dari pre-
amplifier sehingga di dapat daya output signal litrik yang kuat sesui
kebutuhan.
4. Speaker : Alat transducer yang merubah sinyal listrik yang keluar dari power
amplifier menjadi sinyal suara yang kuat sesui dengan kebutuhan pendengar.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 18
5. Mixing : Alat elektronik yang menampung beberapa input sumber sinyal audio
untuk di perkuat oleh pre-amplifier baik secara bersamaan ataupun sendiri-
sendiri berdasarkan pilihan operator.
6. Speaker selector : Alat unuk memilih kesaluran mana sinyal suara akan
diteruskan, apakah akan disalurkan per-lantai (selective) ataukah sekaligus
serentak keseluruh lantai (all- call).
7. M D F : Terminal utama untuk kabel-kabel yang keluar dan sentral sound
system di lantai-lantai tertentu menuju ke masing-masing speaker, atau kabel
sinyal dari program di tempat lain yang akan di interkoneksikan ke sentral
tesebut.
D. Perhitungan Kebutuhan Telepon/Data Komputer/CCTV
Perhitungan kebutuhan telepon/data computer/CCTV didasarkan pada 1 (satu)
pesawat cabang telephone /data computer/CCTV untuk melayani lantai seluas = 30
m2. Kebutuhan totalnya dihitung dengan mengalikan jumlah yang diperoleh pada
setiap gedung ditambah dengan total kebutuhan pada gedung-gedung lainnya.
E. Kebutuhan Air Bersih
Estimasi perhitungan kebutuhan air bersih PIP Semarang hingga pada Tahun 2034
didasarkan pada kebutuhan untuk konsumsi air bersih pengguna bangunan gedung
dan kebutuhan air bersih untuk pemadam kebakaran.
1) Untuk bangunan gedung dengan fungsi hunian yang terdiri dari Asrama Kompi A,
B, C, D, E dan F, dan Rumah Susun Karyawan, Apartemen Dosen dan Guest House
membutuhkan air bersih dengan standar pemakaian 120 L/orang.hari. Sedangkan
untuk aktivitas non hunian pada lantai atas Asrama menggunakan standar
penggunaan air bersih 40 L/orang.hari.
2) Untuk bangunan gedung dengan fungsi kelas dan laboratorium membutuhkan air
bersih dengan standar pemakaian 80 L/orang.hari.
3) Untuk bangunan gedung dengan fungsi perkantoran dan auditorium
menggunakan standar pemakaian air bersih sebesar 40 L/orang.hari.
4) Untuk kebutuhan pemadaman kebakaran diperlukan penyediaan air bersih
dengan menggunakan standar dari Permen PU Nomor 20/PRT/M/2009 tentang
Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan dengan
menggunakan rumus:

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 19
Dimana:
V = Volume total bangunan (M3)
ARK = Angka Klasifikasi Risiko Kebakaran
AKK = Angka Klasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung
FB = Faktor Bahaya dari Bangunan berdekatan sebesar 1,5 kali.
F. Kebutuhan Pengolahan Air Kotor
Estimasi perhitungan kebutuhan pengolahan air kotor diperoleh dari konsumsi air
bersih pada setiap bangunan dikalikan dengan dengan 80% untuk air yang dibuang.
Hasil air kotor yang diolah menjadi air jernih dipergunakan kembali untuk kebutuhan
penyiraman tanaman dan penggelontoran pada closet. Instalasi untuk pengolahan air
kotor menggunakan Bio-tank. Air keluaran dari Bio-tank selanjutnya diolah di dalam
bak penjernih untuk kebutuhan daur ulang diatas.
6.4. Konsep Struktur dan Konstruksi
6.4.1. Konsep Sistem Struktur
Perencanaan suatu struktur bangunan baru memerlukan kajian tersendiri
terhadap model struktur yang direncanakan. Kajian tersebut dilakukan secara integrated
antara struktur atas (upper structure) yang berupa rangka ruang maupun pada struktur
bawah/pondasi (sub structure). Demikian pula halnya pada bangunan kampus PIP,
dimana bangunan tersebut secara fungsional akan memanfaatkan beberapa peralatan
untuk menunjang proses pembangunan mutakhir dengan berat struktur yang sangat
signifikan.
Pembebanan yang diberikan pada struktur terdiri dari berat sendiri struktur
(balok, kolom, pelat beton, dinding bata), beban mati tambahan, beban hidup, beban
angin, dan beban gempa. Besarnya beban yang digunakan dalam perencanaan struktur
adalah sebagai berikut:
1. Beban Mati.
• Berat sendiri struktur: pelat lantai, balok induk, balok anak, dan kolom.
• Beban mati tambahan: spesi, tegal, plumbing, ducting, plafon dan penggantung
plafon.
2. Beban Hidup.
Beban hidup untuk gedung PIP ditentukan berdasarkan Peraturan Pembebanan
Indonesia untuk Gedung 1983, yaitu:
- Lantai dengan Ruang Pertemuan : 400 kg/m2

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 20
Koefisien reduksi pembebanan terhadap distribusi beban hidup,
- Untuk perencanaan balok induk dan portal : 0,70
- Untuk peninjauan gempa : 0,30
3. Beban Gempa.
Peninjauan beban gempa pada perencanaan struktur bangunan PIP ini ditinjau
secara analisa dinamis 3 dimensi. Fungsi response spectrum ditetapkan sesuai peta
wilayah gempa untuk daerah Balikpapan adalah wilayah gempa 2 sebagaimana
ketentuan dalam Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur
Bangunan Gedung SNI 03 1726 2012 serta mempertimbangkan kondisi tanah
dilokasi rencana bangunan akan dibangun yaitu jenis tanah liat dan gambut.
Parameter-parameter perhitungan gaya gempa berupa base shear mengacu pada
ketentuan yang telah diatur dalam SNI 03 1726 2012.
Peraturan yang digunakan dalam merencanakan sistem struktur:
a. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-2847-
2002. Peraturan ini meliputi persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan-
ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur beton untuk bangunan
gedung atau struktur bangunan lain yang mempunyai kesamaan karakter dengan
struktur bangunan.
b. Tata Cara Perhitungan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung, SNI 03-1729-
2002. Peraturan ini meliputi persyaratan-persyaratan umum serta ketentuan-
ketentuan teknis perencanaan dan pelaksanaan struktur baja untuk bangunan
gedung atau struktur bangunan lain yang mempunyai kesamaan karakter dengan
struktur bangunan.
c. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung, SNI
03-1726-2012. Peraturan ini memuat syarat-syarat untuk perencanaan tahan
gempa dari struktur-struktur gedung.
d. Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Peraturan ini masih digunakan untuk
mendukung Peraturan yang baru dan mengisi hal-hal yang tidak diatur dalam SNI
03-2847-2002.
e. Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung 1983. Peraturan ini berisi
tentang segala ketentuan mengenai beban yang dikenakan pada suatu struktur.
Dalam upaya melakukan perancangan diperlukan konsep rancangan yang mampu
menjawab permasalahan dengan memahami syarat utama utilitas bangunan. Persyaratan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 21
tersebut adalah bahwa rancangan bangunan dengan pemanfaatannya harus memenuhi 3
aspek penting yaitu:
a. Keselamatan (Safety)
b. Keberlanjutan (Sustainability)
c. Keamanan (Security)
Aspek keselamatan mencakup pengertian keselamatan jiwa dan kesehatan
terhadap masyarakat umum dan staf pelaksana (operator) gedung. Aspek keberlanjutan
ditujukan untuk minimalisasi dampak bagi lingkungan sekitarnya serta mengoptimalkan
sisi operasional dan perawatan bagi fasilitas tersebut. Aspek keamanan ditujukan untuk
melindungi fasilitas dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selain melindungi isi
bangunan, faktor keamanan dimaksudkan juga untuk melindungi akses-akses terbatas
terkait dengan uraian pada aspek keselamatan.
6.4.2. Konsep Perencanaan Pondasi Bangunan
Dalam perencanaan Pondasi untuk suatu konstruksi dapat digunakan beberapa
macam type pondasi . Pemilihan type pondasi ini didasarkan atas :
• Fungsi bangunan atas yang akan dipikul oleh pondasi tersebut
• Besarnya beban dan beratnya bangunan atas
• Keadaan tanah dimana bangunan tersebut akan didirikan
• Biaya dari pondasi yang dipilih
Dengan penjelasan tersebut diatas, maka dapat dipilih suatu alternatif pondasi
yang sesuai dengan kondisi di lapangan yang tentunya memenuhi kriteria dan sesuai
dengan soil test yang dilakukan fihak laboratorium di lokasi tersebut. Secara umum ada
dua tipe pondasi yang dapat digunakan, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam.
A. Pondasi Dangkal
Pondasi dangkal dapat digunakan pada suatu bangunan yang mempunyai reaksi
perletakan yang relatif kecil serta daya dukung tanah permukaan yang cukup tinggi.
Berdasarkan kondisi tanah hasil soil test tipe pondasi dangkal yang dapat digunakan pada
bangunan kampus PIP adalah tipe pondasi telapak (foot plate) yang terbuat dari beton
bertulang. Ilustrasi dari pondasi dangkal tipe telapak beton dapat dilihat pada gambar
berikut:

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 22
Gambar 6.10. Ilustrasi Bentuk Pondasi Telapak Beton Bertulang
B. Pondasi Dalam
Pondasi dalam dapat digunakan pada bangunan kampus PIP yang mempunyai reaksi
perletakan yang cukup besar. Penggunaan pondasi dalam tipe tiang pancang atau tiang
bor secara umum dapat digunakan. Proses pelaksanaan pondasi dalam juga perlu
diperhatikan. Untuk pelaksanaan pada daerah yang masih banyak terdapat lahan kosong
dapat menggunakan mesin hammer. Sedangkan pelaksanaan pada wilayah yang sudah
banyak terdapat bangunan di sekitarnya, pemasangan pondasi dalam harus menggunakan
mesin hidrolis dengan sistem injeksi. Ilustrasi dari pondasi dalam tipe tiang pancang
dapat dilihat pada gambar berikut.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 23
Gambar 6.11. Ilustrasi Bentuk Pondasi Tiang Pancang
6.4.3. Konsep Perencanaan Kolom Balok
Kolom sebagai elemen tekan juga merupakan elemen penting pada konstruksi.
Sistem post and beam terdiri dari elemen struktur horisontal (balok) diletakkan
sederhana di atas dua elemen struktur vertikal (kolom) yang merupakan konstruksi dasar
yang digunakan sejak dulu. Pada sistem ini, secara sederhana balok dan kolom digunakan
sebagai elemen penting dalam konstruksi.
Banyak faktor yang mempengaruhi beban tekuk (Pcr) pada suatu elemen struktur
tekan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1. Panjang Kolom
Pada umumnya, kapasitas pikul-beban kolom berbanding terbalik dengan kuadrat
panjang elemennya. Selain itu, faktor lain yang menentukan besar beban tekuk
adalah yang berhubungan dengan karakteristik kekakuan elemen struktur (jenis
material, bentuk, dan ukuran penampang).
2. Kekakuan
Kekakuan elemen struktur sangat dipengaruhi oleh banyaknya material dan
distribusinya. Pada elemen struktur persegi panjang, elemen struktur akan selalu
menekuk pada arah seperti yang diilustrasikan pada di bawah bagian (a). Namun
bentuk berpenampang simetris (misalnya bujursangkar atau lingkaran) tidak

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 24
mempunyai arah tekuk khusus seperti penampang segiempat. Ukuran distribusi
material (bentuk dan ukuran penampang) dalam hal ini pada umumnya dapat
dinyatakan dengan momen inersia (I).
3. Kondisi ujung elemen struktur
Apabila ujung-ujung kolom bebas berotasi, kolom tersebut mempunyai kemampuan
pikul-beban lebih kecil dibandingkan dengan kolom sama yang ujung-ujungnya
dijepit. Adanya tahanan ujung menambah kekakuan sehingga juga meningkatkan
kestabilan yang mencegah tekuk. Pengekangan suatu kolom pada suatu arah juga
meningkatkan kekakuan. Fenomena tekuk pada umumnya menyebabkan terjadinya
pengurangan kapasitas pikul-beban elemen tekan. Beban maksimum yang dapat
dipikul kolom pendek ditentukan oleh hancurnya material, bukan tekuk.
Kolom biasanya terdiri dari 2 jenis yaitu kolom pendek dan kolom panjang.Analisis
pada kolom pendek dibagi atas analisa terhadap dua jenis beban yang terjadi pada elemen
tekan tersebut, yaitu:
a. Beban Aksial
Elemen tekan yang mempunyai potensi kegagalan karena hancurnya material
(tegangan langsung) dan mempunyai kapasitas pikul-beban tak tergantung pada
panjang elemen, relatif lebih mudah untuk dianalisis. Apabila beban yang bekerja
bertitik tangkap tepat pada pusat berat penampang elemen, maka yang timbul
adalah tegangan tekan merata yang besarnya.
b. Beban Eksentris
Apabila beban bekerja eksentris (tidak bekerja di pusat berat penampang
melintang), maka distribusi tegangan yang timbul tidak akan merata. Efek beban
eksentris adalah menimbulkan momen lentur pada elemen yang berinteraksi
dengan tegangan tekan langsung. Bahkan apabila beban itu mempunyai
eksentrisitas yang relatif besar, maka di seluruh bagian penampang yang
bersangkutan dapat terjadi tegangan tarik Aturan sepertiga-tengah, yaitu aturan
yang mengusahakan agar beban mempunyai titik tangkap di dalam sepertiga
tengah penampang (daerah Kern) agar tidak terjadi tegangan tarik.
Analisis pada kolom panjang dibagi atas analisa terhadap dua faktor yang terjadi
pada elemen tekan tersebut, yaitu :

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 25
a. Tekuk Euler
Beban tekuk kritis untuk kolom yang ujung-ujungnya sendi disebut sebagai beban
tekuk Euler, yang dinyatakan dalam Rumus Euler .Dengan rumus tersebut, dapat
diprediksi bahwa apabila suatu kolom menjadi sangat panjang, beban yang dapat
menimbulkan tekuk pada kolom menjadi semakin kecil menuju nol, dan
sebaliknya. Rumus Euler ini tidak berlaku untuk kolom pendek, karena pada
kolom ini yang lebih menentukan adalah tegangan hancur material. Bila panjang
kolom menjadi dua kali lipat, maka kapasitas pikulbeban akan berkurang menjadi
seperempatnya. Dan bila panjang kolom menjadi setengah dari panjang semula,
maka kapasitas pikul beban akan meningkat menjadi 4 kali. Jadi, beban tekuk
kolom sangat peka terhadap perubahan panjang kolom.
b. Tegangan Tekuk Kritis
Beban tekuk kritis kolom dapat dinyatakan dalam tegangan tekuk kritis (fcr), yaitu
dengan membagi rumus Euler dengan luas penampang A. Jadi persamaan tersebut
adalah :
Unsur L/r disebut sebagai rasio kelangsingan kolom. Tekuk kritis berbanding
terbalik dengan kuadrat rasio kelangsingan. Semakin besar rasio, akan semakin
kecil tegangan kritis yang menyebabkan tekuk. Rasio kelangsingan (L/r) ini
merupakan parameter yang sangat penting dalam peninjauan kolom karena pada
parameter inilah tekuk kolom tergantung. Jari-jari girasi suatu luas terhadap suatu
sumbu adalah jarak suatu titik yang apabila luasnya dipandang terpusat pada titik
tersebut, momen inersia terhadap sumbu akan sama dengan momen inersia luas
terhadap sumbu tersebut. Semakin besar jari-jari girasi penampang, akan semakin
besar pula tahanan penampang terhadap tekuk, walaupun ukuran sebenarnya dari
ketahanan terhadap tekuk adalah rasio L/r.
c. Kondisi Ujung
Pada kolom yang ujung-ujungnya sendi, titik ujungnya mudah berotasi namun
tidak bertranslasi. Hal ini akan memungkinkan kolom tersebut mengalami
deformasi.
d. Bracing
Untuk mengurangi panjang kolom dan meningkatkan kapasitas pikul bebannya,
kolom sering dikekang pada satu atau lebih titik pada panjangnya. Pengekang
(bracing) ini merupakan bagian dari rangka struktur suatu bangunan gedung.
Pada kolom yang diberi pengekang (bracing) di tengah tingginya, maka panjang
efektif kolom menjadi setengah panjangnya, dan kapasitas pikul-beban menjadi
empat kali lipat dibandingkan dengan kolom tanpa pengekang. Mengekang kolom

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 26
di titik yang jaraknya 2/3 dari tinggi tidak efektif dalam memperbesar kapasitas
pikul-beban kolom bila dibandingkan dengan mengekang tepat di tengah tinggi
kolom.
e. Kekuatan Kolom Aktual vs Ideal
Apabila suatu kolom diuji secara eksperimental, maka akan diperoleh hasil yang
berbeda antara beban tekuk aktual dengan yang diperoleh secara teoritis. Hal ini
khususnya terjadi pada pada kolom yang panjangnya di sekitar transisi antara
kolom pendek dan kolom panjang. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor
seperti eksentrisitas tak terduga pada beban kolom, ketidak-lurusan awal pada
kolom, adanya tegangan awal pada kolom sebagai akibat dari proses
pembuatannya, ketidakseragaman material, dan sebagainya. Untuk
memeperhitungkan fenomena ini, maka ada prediksi perilaku kolom pada selang
menengah (intermediate range).
f. Momen dan Beban Eksentris
Banyaknya kolom yang mengalami momen dan beban eksentris, dan bukan hanya
gaya aksial. Untuk kolom pendek, cara memperhitungkannya adalah dinyatakan
dengan M = Pe , dan dapat diperhitungkan tegangan kombinasi antara tegangan
aksial dan tegangan lentur. Untuk kolom panjang, ekspresi Euler belum
memperhitungkan adanya momen.
Gambar 6.12. Ilustrasi Bentuk Sambungan Kolom Balok
6.4.4. Sistem Infrastruktur
Sistem infrastruktur yang perlu direncanakan meliputi mekanikal plumbing,
elektrikal, sistem air bersih dan sanitasi lingkungan, sistem jaringan air kotor dan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 27
drainase, sistem pengolahan limbah dan sampah, sistem dinding panahan tanah terhadap
galian dan timbunan, sistem perkerasan jalan dan jembatan, serta sistem dan jaringan
telekomunikasi.
6.5. Konsep Sistem Utilitas Lingkungan
Kelengkapan Jaringan Utilitas akan mendukung maksimalnya fungsi operasional
suatu bangunan, gedung atau kawasan yang mencakup Instalasi Mekanikal, Elektrikal,
Plumbing, Sistem Ventilasi dan Sistem Air Conditioning (MEP dan VHC). Lingkungan
dengan fasilitas akademik yang didukung prasarana laboratorium akan membututuhkan
sistem MEP dengan jaringan kompleks, sehingga harus merupakan suatu sistem yang
handal karena terkait langsung oleh pelayanan.
Adapun jaringan instalasi MEP tersebut adalah :
1. Mekanikal dan Plumbing
a. Sistem Penyedian Air Bersih
b. Instalasi Air Bekas dan Air Kolor
c. Instalasi Perlawanan Kebakaran (Hydrandt dan Sprinkler)
d. Elevator Escalator dan Dumb Waiter
e. Sistem Generating Set (Genset)
f. Instalasi Gas
g. Instalasi Air Conditioning
h. Sistem Pengolahan Limbah (STP)
i. Sistem Drainage Site
2. Elektrikal
a. Sistem Penyediaan Daya Listrik
b. lnstalasi Penerangan dan Daya
c. Sistem Penangkal Petir
d. Instalasi Telepon
e. Instalasi Pengindera Kebakaran (Fire Alarm)
f. Instalasi Tata Suara
g. Sistem Jaringan Komputer (LAN)
h. lnstalasi Master Antena Televisi (MATV)
i. Instalasi Closed Circuit Television (CCTV)
6.5.1. Sistem Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan
Kajian penyediaan dan distribusi air bersih meliputi kajian sebagai berikut:

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 28
• Kebutuhan air bersih untuk berbagai fungsi sarana bangunan dalam kawasan
kampus
• Kebutuhan air bersih untuk fungsi laboratorium khusus
• Kebutuhan air untuk sistem pemadam kebakaran
• Kebutuhan air untuk sistem penggelontoran, penyiraman tanaman dan
kebersihan
• Kajian sistem distribusi dan reservoir
Perancangan sistem/prasarana sanitasi didasarkan atas peraturan-peraturan dan
standar-standar serta referensi-referensi sebagai berikut:
• Pedoman Plumbing Indonesia 1979.
• Peraturan Pokok Teknik Penyehatan mengenai air minum dan air buangan,
rancangan 1968 Dirjen Cipta Karya, Direktorat Teknik Penyehatan.
• Peraturan Instalasi Air Minum dari PAM Jawa Tengah.
• Algemeene Voorwarden Voor Drink Water Instalatir (AVWI).
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
173/Men.Kes/Per/VIII/77, tentang Pengawasan Pencemaran Air dari Badan
Air untuk berbagai kegunaan yang berhubungan dengan kesehatan.
• Peraturan Perburuhan Departemen Tenaga Kerja.
• Peraturan peraturan lain yang berlaku setempat.
• SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000
• Perencanaan dan Pemeliharaan sistem Plambing ( Soufyan & Morimura)
• National Plumbing Code Hand Book
Direncanakan kebutuhan air bersih bagi seluruh bangunan akan dicatu oleh
jaringan air bersih PDAM, dan penampungan aliran air hujan ke dalam kolam
penampung.
Untuk menampung air bersih akan disediakan tangki bawah tanah (ground
reservoir) di masing-masing bangunan yang dirancang menampung kebutuhan 1 (satu)
hari operasional jika penyediaan air terjamin. Tetapi jika penyediaan kebutuhan air tidak
selalu lancar, maka perlu dipertimbangkan untuk menambahkan faktor keamanan
terhadap penyediaan air. Penyiraman taman dan cadangan pemadam kebakaran dengan
penggunaan water level control agar cadangan untuk pemadam kebakaran tidak terpakai.
6.5.2. Sistem Jaringan Drainase dan Air Kotor
Dalam merencanakan sistem dan jaringan drainase dan air kotor diperlukan
kajian pendahuluan terhadap:

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 29
• Tinggi curah hujan
• Debit aliran permukaan
• Koefisien aliran permukaan
• Banjir tahunan
Penggunaan saluran drainase tipe U-gutter yang terbuat dari bahan beton pracetak sangat
disarankan, seperti pada gambar berikut. Untuk U-gutter ini pada jarak tertentu
dibuatkan lubang-lubang peresapan ke dalam permukaan tanah untuk mempercepat
peresapan air ke dalam tanah manakala terjadi genangan.
Pembangunan long storage dan bosem / tampungan air diperlukan dalam
pembangunan saluran drainase kampus PIP. Long storage dan bosem ini berfungsi untuk
menampung air sementara apabila debit aliran yang terjadi melebihi dari debit rencana.
Pembangunan sistem pintu air juga perlu digunakan pada saat air menggenang tinggi di
dalam PIP Semarang. Pintu air ini berfungsi untuk mengendalikan tinggi air di
lingkungan kampus PIP pada saluran-saluran drainase dari dalam ke luar saluran kota,
dan pada pintu-pintu keluar masuk kendaraan dan orang.
Gambar 6.13. Sistem saluran dari beton pracetak (U gutter) dengan lubang peresapan
Dalam perencanaan drainase digunakan data dari stasiun pengamatan hujan yang
diperoleh dari kantor Badan Meteorologi dan Geofisika di Semarang. Dari catatan data
curah hujan harian maksimum diperoleh curah hujan harian maksimum sebagaimana
berikut:
Curah hujan untuk perencanaan adalah curah hujan harian maksimum dengan periode
ulang 5 tahun. Untuk memperoleh curah hujan maksimum dengan periode ulang tertentu

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 30
perlu dilakukan analisa frekuensi. Salah satu metoda analisis harga ekstrim adalah dengan
menggunakan distribusi Gumbel. Untuk dapat melakukan analisis frekuensi ini
diperlukan data dengan panjang minimum 10 tahun.
Persamaan untuk analisis frekuensi dengan metoda Gumbel:
xTr SKXX .+=
Dimana:
TrX : besar curah hujan untuk periode ulang Tr tahun, dalam mm
rT : periode ulang, dalam tahun
X : curah hujan harian maximum rata-rata, dalam mm
xS. : standar deviasi
K : faktor frekuensi
n
nTr
S
YYK
−=
nYdan nS
merupakan fungsi dari besar sampel/data.
−+−=
1loglog303,2834,0
r
rTr T
TY
A. Perhitungan Debit Aliran
Untuk perhitungan debit aliran pada lahan dengan luas kurang dari 80 hektar dapat
menggunakan persamaan debit rasional.
360
CIAQ =
Dimana ;
Q : debit dalam, m3/s
C : koefisien limpasan
I : intensitas hujan, mm/jam
A : luas lahan, hektar
Intensitas curah hujan dapat diperoleh berdasarkan base curve dalam SNI No. 03-3424-
1994 dan curah hujan maksimum harian 24 jam dengan periode ulang 5 tahun.
Berdasarkan curah hujan harian maksimum 24 jam dan asumsi bahwa 90% dari curah
hujan tersebut akan turun dalam empat jam, suatu kurva intensitas durasi hujan dapat

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 31
diperoleh dengan menggeser koordinat dari base curve sebesar perbedaan intensitas
hujan untuk durasi 4 jam.
Untuk dapat memperoleh besar intensitas curah hujan perencanaan, maka diperlukan
adanya waktu konsentrasi aliran. Waktu konsentrasi ini merupakan waktu yang
diperlukan dari air dari titik terjauh menuju outlet dimana debit drainase akan dihitung.
Waktu konsentrasi dihitung dengan persamaan berikut :
Tc = t1+t2
T1, Overland flow:
167.0
1 28.33
2
×××=S
nLt d
o
dimana:
t1 = waktu aliran pada permukaan lahan, menit
Lo = panjang jalur lintasan di permukaan lahan, m
nd = koefisien penghambat
S = slope permukaan lahan
Aliran pada saluran:
V
Lt
602 =
dimana:
t2 = waktu tempuh di saluran, menit
L = panjang saluran, m
V = kecepatan aliran yang direncanakan, m/s
Dengan menggunakan waktu konsentrasi maka dapat ditentukan besarnya intensitas
curah hujan dengan menggunakan kurva intensitas – durasi. Harga debit yang harus
dialirkan dari suatu lahan dapat dihitung dengan persamaan rasional dengan
menggunakan koefisien limpasan, C, yang sesuai. Harga koefisien limpasan C untuk
berbagai jenis permukaan lahan adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 32
Tabel 6.2. Koefisien Limpasan
No. Kondisi Permukaan
Tanah
Koefisien
Pengaliran (C)
BAHAN
1 Jalan beton & aspal 0,70 – 0,95
2 Jalan kerikil & jalan tanah 0,40 – 0,70
3 Bahu jalan :
- Tanah berbutir halus 0,40 - 0,65
- Tanah berbutir kasar 0,10 – 0,20
- Batuan masif keras 0,70 – 0,85
- Batuan masif lunak 0,60 – 0,75
TATA GUNA LAHAN
1 Daerah perkotaan 0,70 – 0,95
2 Daerah pinggir kota 0,60 – 0,70
3 Daerah industri 0,60 – 0,90
4 Permukiman padat 0,40 – 0,60
5 Permukiman tidak padat 0,40 – 0,60
6 Taman da kebun 0,20 – 0,40
7 Persawahan 0,45 – 0,60
8 Perbukitan 0,70 – 0,80
9 Pegunungan 0,75 – 0,90
Sumber : Pedoman Sistem Drainase Jalan Pd. 02-2006-B, Dep. PU.
Tabel 6.3. Curah Hujan Harian Maksimum dengan Berbagai Periode Ulang.
T
(years)
YT XT
(mm)
I 4hrs
(mm/hr)
2 0.3665 92.0 20.7
5 1.4999 120.5 27.1
10 2.2502 139.4 31.4
25 3.1985 163.2 36.7
50 3.9019 180.9 40.7
100 4.6001 198.4 44.7

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 33
Gambar 6.14. Kurva Intensitas – Durasi Hujan.
B. Dimensi Saluran
Perhitungan dimensi saluran dilakukan dengan menggunakan persamaan aliran
seragam sebagaimana berikut:
Persamaan Manning:
SP
A
nV
3/21
=
Di mana:
n : kekasaran Manning
A : luas penmapang basah, m2
P : panjang keliling basah, m
S : kelandaian saluran
Persamaan debit aliran (kontinuitas):
Q = A V
Di mana:
Q : debit aliran, m3/s
V : kecepatan aliran, m/s
6.5.3. Sistem Pengolahan Limbah
Kajian timbulan dan pengumpulan limbah cair meliputi:
• Kajian timbulan air kotor dari sistem sarana sanitasi bangunan
• Kajian timbulan limbah cair dari sarana laboratorium dan workshop

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 34
Unit timbulan air buangan dapat diperkirakan dengan mengacu pada jenis
penggunaan lahan dan/atau bangunan tersebut Secara rinci unit timbulan untuk
bermacam-macam penggunaan lahan/bangunan dijelaskan dalam Unit Timbulan Air
Buangan untuk Berbagai Jenis Penggunaan Lahan
Dalam rancangan jaringan pengumpul air buangan, Faktor Puncak perlu
diperhitungkan untuk mengatasi jumlah air buangan rata-rata harian dan musiman yang
sangat berfluktuasi. Faktor Puncak yang Disarankan, menyarankan faktor puncak untuk
berbagai jenis pembangunan.
Limbah B3 yang diproduksi dari laboratorium harus disimpan dengan perlakuan
khusus sebelum akhirnya diolah di unit pengolahan limbah. Penyimpanan harus
dilakukan dengan sistem blok dan tiap blok terdiri atas 2×2 kemasan. Limbah-limbah
harus diletakkan dan harus dihindari adanya kontak antara limbah yang tidak kompatibel.
Bangunan penyimpan limbah harus dibuat dengan lantai kedap air, tidak bergelombang,
dan melandai ke arah bak penampung dengan kemiringan maksimal 1%. Bangunan juga
harus memiliki ventilasi yang baik, terlindung dari masuknya air hujan, dibuat tanpa
plafon, dan dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Limbah yang bersifat reaktif atau
korosif memerlukan bangunan penyimpan yang memiliki konstruksi dinding yang mudah
dilepas untuk memudahkan keadaan darurat dan dibuat dari bahan konstruksi yang tahan
api dan korosi untuk selanjutnya diangkut dan diolah oleh pihak ketiga.
Mengenai pengangkutan limbah B3, Pemerintah Indonesia belum memiliki
peraturan pengangkutan limbah B3 hingga tahun 2002. Namun, kita dapat merujuk
peraturan pengangkutan yang diterapkan di Amerika Serikat. Peraturan tersebut terkait
dengan hal pemberian label, analisa karakter limbah, pengemasan khusus, dan
sebagainya.
6.5.4. Sistem Penanganan Sampah
Pengelolaan sampah di kampus PIP dilakukan untuk mewujudkan lingkungan
kampus yang bersih. Untuk mencapai proses pengolahan sampah yanyg berkelanjutan,
perlu dilakukan kajian perencanaan pengelolaan sampah di kampus PIP dengan tetap
mengedepankan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Perencanaan yang akan
dilakukan mencakup pengumpulan, pewadahan, pengangkutan, dan pengolahan secara
mandiri di lingkungan kampus yang direncanakan dikelola secara mandiri.
Muara dari perencanaan pengelolaan sampah ini adalah pembangunan Instalasi
Pengolah Sampah Terpadu (IPST) yang berlokasi dl dalam Komplek Kampus sendiri.Jenis
pengolahan sampah pada IPST adalah pengolahan sampah organik dan

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 35
anorganik.Sampah yang dihasilkan oleh kampus terlebih dahulu dipilah berdasarkan
komponen organik dan anorganik, sebelumnya di sumber telah disediakan pewadahan
yang terpilah yang disinkronisasikan dengan fasilitasi sarana pengumpulan/
pengangkutan yang terpilah juga. Selanjutnya secara umun sampah organik diolah
menjadi kompos, diolah menjadi pupuk cair, ataupun dimanfaatkan sebagai bahan pakan
ternak. Sedangkan sampah anorganik yang bernilai ekonomi dikumpulkan dan dljual ke
bandar untuk didaur ulang. Sampah anorganik yang tidak bernllai ekonomi dibuang ke
TPS sampah kota, atau apabila akan dikelola sendiri maka diperlukan pengadaan
insinerator khusus untuk limbah medis dari poliklinik.
Estimasi timbunan dan komposisi sampah:
a. Timbunan sampah dari sumber gedung perkuliahan dan perkantoran
b. Timbunan sampah dari sumber fasilitas umum
c. Timbunan sampah dari sumber asrama
d. Timbunan sampah dari sumber tempat umum dan lapangan terbuka
Pelaksanaan pengangkutan sampah dalam perencanaan sampah ini yaitu
mengangkut sampah dari bin kontainer dan kontainer dibawa menuju ke IPST. Jenis
kendaraan pengangkut sampah yang digunakan untuk pola pengumpulan komunal
langsung adalah jenis compactor truck dengan kapasitas 6 m3 dan arm roll truck yang
berkapasitas 4 m3. Kendaraan jenis compactor truck memiliki kelebihan dapat
melakukan pengepresan sampah sehingga kapasitas daya tampungnya dapat
ditingkatkan. Dalam pemuatan maupun pembongkaran sampah, compactor truck dan
arm roll truck dilengkapi dengan lengan tarik hidrolik sehnigga dapat bergerak secara
otomatis yang dikendalikan oleh sopir sehingga tidak bersentuhan langsung dengan
sampah.
Sampah diangkut dengan menggunakan compactor truck dan arm roll truck. Pola
pengangkutan yang digunakan untuk kendaraan compactor truck adalah pola
pengangkutan dengan sistem kontainer tetap.
6.6. Konsep Pemgembangan Ruang Sosial
Luasan ruang sosial sebagai wadah kegiatan olah raga dan kegiatan sosial lainnya
pada ruang lantai atas bangunan diestimasi akan dapat menampung kegiatan yang
diharapkan agar para taruna tidak ada yang mempunyai waktu idle pada saat sore hari
diluar jam perkuliahan. Dengan adanya ruang-ruang pada atap ini energi positif dapat

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 36
tersalurkan dan ikatan sosial diantara taruna dalam satu angkatan menjadi kuat.
Kompetisi antar angkatan secara positif juga akan dapat tercipta.
Gambar 6.15. Ruang Sosial di Lantai atas Bangunan
Adapun estimasi luas ruang di lantai atas bangunan adalah sebagai berikut:
Tabel 6.4. Luasan Ruang Sosial pada Lantai Atas Bangunan.
NO NAMA BANGUNAN GEDUNG LUAS RUANG SERBAGUNA
(m2)
ESTIMASI FUNGSI
1 Asrama Kompi A Lantai 5 1.525 Futsal, Volley, Bulutangkis, Tennis Meja, Bela Diri
2 Asrama Kompi B Lantai 5 740 Futsal, Volley, Bulutangkis, Tennis Meja, Bela Diri
3 Asrama Kompi C Lantai 5 740 Futsal, Volley, Bulutangkis, Tennis Meja, Bela Diri
4 Asrama Kompi D Lantai 5 450 Futsal, Bela Diri, Tennis Meja 5 Asrama Kompi E Lantai 5 450
6 Asrama Taruni Lantai 4 450 Tennis Meja, Bela Diri,
7 Gedung Jurusan Teknika (Betelgeuse) Lantai 6 1.565 Aula Seminar/OR 8 Gedung Jurusan Nautika (Pollux Baru) Lantai 6 1.565 Aula Seminar/OR 9 Gedung Auditorium Lantai 6 1.350 Auditorium 10 Gedung Direktorat Lantai 8 1.290 Aula Seminar TOTAL 10.125
Sumber: Hasil Analisis, 2013

Penyusunan Studi Kelayakan dan Master Plan PIP SEMARANG
Tahun 2013
VI - 37
Dengan luas total 10.125 m2 dan dipergunakan oleh Taruna sejumlah 2.035 orang
yang ada di darat, maka luasan rata-rata per siswa adalah 5 m2/orang, atau dua kali luas
daripada kondisi eksisting.
6.7. Konsep Pemgembangan Kesehatan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Poliklinik PIP Semarang
ditingkatkan kelas pelayanannya dari Poliklinik Pratama pada saat ini menjadi Poliklinik
Utama. Peningkatan kelas ini akan dibarengi dengan penambahan pelayanan Poli Rawat
Jalan dengan penambahan Poli Spesialis Mata dan Poli Spesialis THT, selain Poli yang
saat ini sudah ada yaitu Poli Umum, Poli Gigi, Poli Mata dan THT ( dengan status kerja
sama). Kelengkapan Laboratorium ditambah untuk melayani pemeriksaan laboratorium
lengkap. Laboratorium juga ditambah dengan peralatan rontgen dan ECG, selain
Spirometri dan Audiometri.
Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, Poliklinik akan dilengkapi dengan
penambahan jumlah kamar menjadi 8 sampai 16 TT. Dan sebagai upaya peningkatan
kualitas lingkungan akan dilengkapi dengan IPAL untuk limbah cair medis.