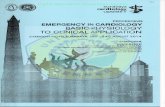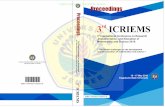Win Usuluddin - UIN KHAS Jember
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Win Usuluddin - UIN KHAS Jember
ii
SERPIHAN-SERPIHAN FILSAFAT
Hak penerbitan ada pada STAIN Jember PressHak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
Editor:Hafidz Hasyim
Layout:Khoiruddin
Cetakan I:Mei 2013
Foto Cover:Internet
Penerbit:STAIN Jember Press
Jl. Jumat Mangli 94 Mangli JemberTlp. 0331-487550 Fax. 0331-427005
e-mail: [email protected]
ISBN: 978-602-8716-66-6
Penulis:Win Usuluddin
iii
PENGANTAR PENULIS
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadliratTuhan ‘azza wa jalla karena hanya berkat perkenan-Nya bukuini dapat hadir ke tengah-tengah para pembaca yang budiman.Buku ini sesungguhnya merupakan kumpulan yang semulaberserakan dari serpihan-serpihan pemikiran kefilsafatan parafilsuf yang coba penulis kumpulkan dari beberapa karya penu-lis lain yang diacu dalam buku ini, dan telah pernah dipresen-tasikan tatkala penulis mendapatkan tugas individu saat ngang-su kaweruh filsafat di program pascasarjana Universitas GadjahMada Yogjakarta, sebagian yang lain juga sudah pernah diter-bitkan dalam jurnal ilmiah beberapa waktu yang lalu. Denganmaksud ingin berbagi pemikiran meskipun tentu saja tidakmencukupi, maka buku ini pun diterbitkan.
Buku ini disusun sedemikian rupa dengan sedapat mung-kin mengaju pada pilar-pilar filsafat tetapi tetap saja “bersera-kan” sehingga lebih berkesan suka-suka dan tidak sistematis.Namun demikian semoga buku ini bermanfaat adanya.
iv
Dalam kesempatan ini secara tulus penulis menyampaikanterima kasih kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. BabunSuharto, SE, MM., selaku Ketua STAIN Jember yang telah ber-kenan memberi arena yang mencukupi bagi aktualisasi diri me-lalui penerbitan buku ini. Juga kepada saudara MuhibbinM.Si., sang kandidat doktor ilmu budaya, semoga segera ram-pung disertasinya, selaku direktur STAIN Jember Press yangtelah memfasilitasi bagi penerbitan buku ini.
Kepada semua pihak yang telah berjasa bagi penulisandan penerbitan buku ini disampaikan terima kasih semoga Tu-han ‘azza wa jalla memberi kabaikan yang terbaik.
Jember, Mei 2013Penulis,
Win Usuluddin
v
PENGANTAR KETUA STAIN JEMBER
Sejatinya, perguruan tinggi bukan sekedar lembaga pela-yanan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai pusatpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat. STAIN Jembersebagai salah satu pusat kajian berbagai disiplin ilmu keislam-an, selalu dituntut terus berupaya menghidupkan budaya aka-demis yang berkualitas bagi civitas akademikanya, terutamabagi para dosen dengan beragam latar belakang kompetensiyang dimiliki.
Setidaknya, ada dua parameter untuk menilai kualitas do-sen. Pertama, produktivitas karya-karya ilmiah yang dihasilkansesuai dengan latar belakang kompetensi keilmuan yang dimi-liki. Kedua, apakah karya-karya tersebut mampu memberi pen-cerahan kepada publik --khususnya kepada para mahasiswa--,yang memuat ide energik, konsep cemerlang atau teori baru.Maka kehadiran buku ilmiah dalam segala jenisnya bagi dosenmerupakan sebuah keniscayaan.
vi
Program GELARKU ini diorientasikan untuk meningkat-kan iklim akademis di tengah-tengah tantangan besar tuntu-tan publik yang menginginkan“referensi intelektual”dalammenyi-kapi beragam problematika kehidupan masyarakat dimasa-masa mendatang.
Untuk itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak kepadaseluruh warga kampus untuk memanfaatkan GELARKU inise-bagai pintu kreatifitas yang tiada henti dalam mengalirkanga-gasan, pemikiran, dan ide-ide segar dan mencerdaskanuntuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan pe-radaban bangsa.
Kepada STAIN Jember Press, program GELARKU tahunpertama ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam membe-rikan pelayanan prima kepada karya-karya tersebut agar da-pat terwujud dengan tampilan buku yang menarik, layoutyang cantik, perwajahan yang elegan, dan mampu bersaingdengan buku-buku yang beredar di pasaran. Melalui karya-karya para dosen ini pula, STAIN Jember Press memiliki ke-sempatan untuk mengajak masyarakat luas menjadikan karyatersebut sebagai salah satu refensi penting dalam kehidupanakademik pembacanya.
Akhir kata, inilah karya yang bisa disodorkan kepada
Meski buku yang ditulis Saudara Win Usuluddin inimerupakan kumpulan tulisan yang berserakan dariserpihan-serpihan pemikiran kefilsafatan para filsuf, setidaknyapenulis sedapat mungkin memberikan gambaran peta pemiki-ran para filsof dengan mengaju pada pilar-pilar filsafat. Tentusaja, karya ini diharapkan akan memberikan kontribusi positifbagi masyarakat dan atau dunia akademik bersamaan deng-an program GELARKU (Gerakan Lima Ratus Buku) yang di-canangkan STAIN Jember dalam lima tahun ke depan.
vii
masyarakat luas yang membaca buku ini sebagai bahan refe-rensi, di samping literatur lain yang bersaing secara kompetitifdam alam yang semakin mengglobal ini. Selamat berkarya.
Jember, Mei 2013Ketua STAIN Jember
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM
ix
DAFTAR ISI
Pengantar Penulis iiiPengantar Ketua STAIN Jember vDaftar Isi ix
BAGIAN PERTAMAARISTOTELES DAN BENTUK
Pengantar 1Bentuk dan Kategori 2Empat Kausa 4Yang Terbatas dan Yang Tidak Terbatas 5Penggerak yang Tak Digerakkan 7Bacaan Pendukung 9
BAGIAN KEDUAALAM PIKIRAN DAN EPISTEMOLOGI AL GHAZALI
Pengantar 11Riwayat Singkat Al Ghazali 13
x
Beberapa Pemikiran Al Ghazali 15Epistemologi Al Ghazali 22Penutup 28Bacaan Pendukung 28
BAGIAN KETIGAPERSIMPANGAN RASIONALISME-EMPIRISISME:REFLEKSI KRITIS ATAS SUMBER-SUMBER PENGE-TAHUAN
Pengantar 31Rasionalisme 32Empirisisme 35Metode Rasional dan Metode Empiris 38Akal atau Indera 39Segitiga Sumber Pengetahuan 44Bacaan Pendukung 53
BAGIAN KEEMPATPEMIKIRAN IBNU SINA TENTANG ALAM DAN JIWA
Pengantar 55Riwayat Singkat dan Karya Tulisnya 56Memahami Alam Melalui Al Qur’an 57Tentang Alam Semesta 62Tentang Jiwa 66Penutup 68Bacaan Pendukung 69
BAGIAN KELIMATHOMAS AQUINAS DAN PEMIKIRANNYA
Pengantar 71Teori Pengetahuan 73
xi
Tentang Semesta Raya 76Tentang Relasi Jiwa-Raga 77Tentang Etika dan Hukum 80Tentang Gereja 84Tentang Essentia dan Existentia bagi Allah 85Tentang Penciptaan 86Penutup 87Bacaan Pendukung 89
BAGIAN KEENAMPERDEBATAN SEPUTAR ANGGAPAN POKOK FIL-SAFAT ILMU PENGETAHUAN ABAD XX
Pengantar 89Karl Raimund Popper 90Thomas Samuel Kuhn 93Imre Lakatos 96Penutup 100Bacaan Pendukung 101
BAGIAN KETUJUHSENI-SENI SPIRITUALIS: MENYELAM KE DASARPEMIKIRAN SENI IQBAL DAN SCHUON
Pengantar 103Muhammad Iqbal dan Karya-karyanya 104Iqbal dan Pemikiran Seninya 112Frithjof Schuon dan Karya-karyanya 118Schuon dan Pemikiran Seninya 123Penutup 125Bacaan Pendukung 128
xii
BAGIAN KEDELAPANKARL MARX DAN MARXISME: SEBUAH CATATAN
BAGIAN KESEMBILANPOROS BARU FILSAFAT SEJARAH KARL JASPERS
Pengantar 137Riwayat Singkat dan Karyanya 139Batu Pijak Filsafat Jaspers 141Filsafat Sejarah 145Penutup 148Bacaan Pendukung 151
BAGIAN KESEPULUHMAZHAB FRANKFURT: DESKRIPSI KEPENDIDIKANERICH FROMM
Pengantar 153Mazhab Frankfurt 154Modus ‘menjadi’ dan Cinta 156Pendidikan yang Membelenggu 158Beberapa Metoda Pendidikan Dewasa ini 160Kewenangan dan Kebebasan 163Penutup 164Bacaan Pendukung 164
BAGIAN KESEBELASJEAN PAUL SARTRE: EKSISTENSIALIS YANG ME-NANGKAP HAKIKAT MANUSIA
Pengantar 167Jean Paul Sartre Dan Karyanya 168Tentang Hakikat Manusia 172 Dilema Kebebasan Menuju Pembebasan 173
xiii
L’étre Pour-Soi dan L’étre-En-Soi 176 Beban Kebebasan 179Hakikat Manusia dan Existence Precede Essence:Sebuah Upaya Reflektif 181 Tentang Hakikat Manusia yang Dipersoalkan 181 Tentang Eksistensi Mendahului Essensi (Existence Recede
Essence) 185Penutup 192Daftar Bacaan 195
BAGIAN KEDUABELASKRISIS DALAM HUMANISME
Pengantar 199Kilas Balik Sejarah 202Menelusuri Semangat Dasar Humanisme 204Antihumanisme 207Penutup 208Bacaan Pendukung 208
BAGIAN KETIGABELASPOSTMODERNISME
Deskripsi 211Periodisasi atau Epistemologi ? 214Problematika Postmodernisme 216Penutup 221Bacaan Pendukung 223
TENTANG PENULIS
Serpihan-Serpihan Filsafat | 1
BAGIAN PERTAMA
ARISTOTELES DAN BENTUK)
PENGANTAR
Menurut Frederick Sontag, ada dua alasan mengapa Aris-toteles (384-322 SM) menempati posisi khusus dalam sejarahmetafisika, pertama, istilah metafisika muncul dari pengertianyang diberikan terhadap pemikirannya mengenai ‘di luar fisika’(beyond physic), kedua, Aristoteleslah yang telah memberikankepada kita istilah-istilah secara teknis untuk metafisika.
Istilah metafisika itu sendiri sebenarnya bukanlah istilahyang berasal dari Aristoteles melainkan hanyalah suatu sebutanyang dimunculkan secara kebetulan saja oleh Andronikos (±70 SM) dari Rhodos, sekitar tiga abad setalah kematian Aristo-teles. Andronikos adalah pemimpin Lyceum terakhir, dan ke-
Disarikan oleh penulis dari: Sontag, F., 1970, Problems of Me-taphysics yang sudah diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, 2001,Pengantar Metafisika, diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit PustakaPelajar.
2 | Win Usuluddin Bernadien
padanyalah kita berhutang budi atas dilahirkannya istilah me-tafisika, judul yang diberikannya terhadap salah satu kelompokkarya Aristoteles. Dalam versi aslinya, karya ini tidak berjuduldan hanyalah disertakan dalam karya fisika, sehingga Andro-nikos memberi label ‘di luar fisika’ yang memuat risalah-risalahAristoteles mengenai Ontologi serta seluruh kodrat yang sebe-narnya atas berbagai hal. Ia menyusun karya-karya Aristotelesdengan cara demikian, bahwa karya-karya Aristoteles tentang‘filsafat pertama’ yang mengenai hal-hal yang gaib ditempat-kan sesudah karya-karyanya tentang fisika (meta ta fusika). Ka-ta meta bisa berarti sesudah dan bisa pula berarti di belakang.Judul meta ta fusika ketika itu dipandang tepat sekali untukdipakai guna mengungkapkan isi pandangan-pandangan me-ngenai ‘hal-hal yang di belakang gejala-gejala fisik’. Jadi, katayang selama berabad-abad ini telah menjadi sinonim dengankata filsafat, sebenarnya tak ada urusan dengan filsafat yang di-lukiskannya. Seperti halnya dengan filsafat, metafisika dimulaidengan suatu kekeliruan dan masih terus berkembang sepertiitu hingga saat ini.
Ada empat hal yang digunakan oleh Sontag untuk menje-laskan metafisika Aristoteles, yaitu: konsep ‘bentuk’ (form) dankategori, empat kausa, Yang Terbatas dan Yang Tidak Terba-tas, dan Penggerak yang Tidak Digerakkan.
BENTUK DAN KATEGORI
Menurut Aristoteles, bentuk selalu bersama materi. Materidan bentuk tidak dapat dipisahkan, sebab materi tidak dapatberada tanpa bentuk demikian pula sebaliknya bentuk tidakdapat berada tanpa materi. Setiap benda yang dapat diamatidisusun dari bentuk dan materi. materinya adalah rangkumansegala yang belum ditentukan dan yang belum terwujud, se-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 3
dangkan bentuknya memberi kesatuan kepada benda itu. Se-tiap benda yang telah berbentuk dapat juga menjadi materibagi benda yang lain. Bentuk (morphe, form) oleh Aristotelesdianggap sebagai yang memberi ‘aktualitas’ pada setiap benda(juga individu) yang bersangkutan. Sedangkan materi (Hyle,matter) seakan-akan menyediakan ‘kemungkinan’ (Yunani: dy-namis, Latin: potentia) untuk pengejawantahan bentuk dalamsetiap benda (juga individu) dengan cara yang berbeda-beda.Materi bukan merupakan sesuatu yang ada dalam dirinya sen-diri, karena materi itu tidak lepas dari objek aktual; namun,baik materi maupun bentuk sama-sama merupakan konsepdasar yang dengannyaberbagai objek dan hal dapat dimengertidan dianalisis. Dengan demikian, apa yang merupakan bentukdalam satu situasi mungkin menjadi materi dalam situasi yanglain.
Analisis Aristoteles sebagaimana tersebut di atas memba-wanya kepada pemikiran tentang kategori, yaitu: suatu konsepyang berguna untuk mengklasifikasi dan menganalisis setiapobjek atau hal dalam dunia. Bagi Aristoteles kategori adalahseperangkat pernyataan yang mampu mengklasifikasikan se-mua pernyataan yang lain. Kategori pokoknya adalah substan-si (oasia, atau hypokeimenon, atau hypostasis artinya sesuatuyang tanpanya sesuatu yang lain tidak akan pernah ada, se-suatu yang menjadi dasar penopang semua segala, hakikat, halyang primer). Aristotelas mengutarakan bahwa istilah substansimenunjuk pada empat hal yang berbeda: esensi (eidos), yanguniversal, genus, dan subjek. Selanjutnya empat hal tersebutdireduksi menjadi dua: ‘substansi pertama’ (oasia prote), sub-jek prediksi, dan ‘substansi kedua’ (oasia deutere) yaitu refe-rensi yang lain yang darinya muncul istilah-istilah umum, yangsanggup mempresentasikan ‘substansi pertama’ hanya secara
4 | Win Usuluddin Bernadien
tidak lengkap.Selanjutnya, Aristoteles mengutarakan bahwa kategori
berasal dari abstraksi dunia fisis yang hadir dihadapan kita, danjuga abstraksi tersebut merupakan fungsi utama bagi pemikirankita. Kategori membentuk batasan yang tegas yang perlu dite-tapkan pada pikiran dan rujukan utama yang dikehendaki jikapertanyaan untuk pengetahuan tertentu hendak dicapai.
EMPAT KAUSA
Kita dapat dikatakan mengetahui manakala kita telah mencapai kausa dari sesuatu. Kausa membentuk suatu perangkatyang tidak dapat direduksi, mendalam, eksklusif, dan lengkapsecara bersama-sama. Dalam kaitan ini Aristoteles membagisemua kausa menjadi empat:1. Kausa material sesuatu (sebab bahan), yaitu: sesuatu yang
darinya sesuatu itu terbuat. Misalnya: kain untuk bahanbaju, kata untuk membentuk kalimat, batu sebagai bahanuntuk membuat rumah.
2. Kausa formal (sebab bentuk), yaitu: bentuk atau strukturyang diberikan kepada materi. Misalnya: idea tentang ru-mah, pola dalam akal, logika dalam wacana.
3. Kausa efisien (sebab kerja), yaitu: sarana yang dengannyakejadian itu dihasilkan. Misalnya: manusia yang membuatrumah, kemampuan pembicara menyusun kata.
4. Kausa final (sebab tujuan), yaitu: suatu tuntutan yang men-dasari pemahaman untuk menentukan batas luar yang di-perlukan guna mencapai pengatahuan. Misalnya: tujuanmanusia membuat baju, tujuan mendirikan rumah, tujuanmerangkai kata-kata.Dalam pandangan Sontag, yang terpenting bagi kita da-
lam kaitannya dengan pembahasan poin B ini bukanlah untuk
Serpihan-Serpihan Filsafat | 5
mengkritisi atau mengajukan keberatan atas konsep Aristotelestersebut, tatapi bagaimana empat kausa itu dapat kita gunakanuntuk menemukan cara fundamental memahami segala sesua-tu, dan bagaimana mempelajari fungsi serta tuntutan metafisikamelalui empat kausa tersebut. Dengan pemahaman yang padudan ketat terhadap empat kausa Aristoteles ini, kita akan de-ngan mudah menentukan batasan dan aspek setiap peristiwaatau objek secara jelas sehingga memungkinkan kita untukmemperoleh pengetahuan yang luas.
Kemudian Sontag menambahkan bahwa di antara empatkausa itu kausa final agaknya memiliki perluasan yang tidaktentu, jauh dari pembatasan, membawa kita melampaui objekitu sendiri. Pemecahan persoalan pembatasan tersebut tergan-tung pada kemampuan Aristoteles dalam membatasi keselu-ruhan sistemnya tanpa harus terjerumus ke langkah munduryang tidak terbatas, dengan kata lain Aristoteles perlu melibat-kan prinsip metafisis lain sebagai pendukungnya.
YANG TERBATAS DAN YANG TIDAK TERBATAS
Pada bagian ini Sontag mempertanyakan mengapa peru-bahan eksistensi ketidakterbatasan aktual diperlukan dalamprinsip pertama Aristoteles?.
Aristoteles menyadari bahwa, mustahil untuk menghilang-kan setiap jejak ketidakterbatasan, sehingga dia berkompromidengan ketidakterbatasan yang dikonsepsikan sebagaimanaadanya hanya secara potensial dan tidak pernah sepenuhnyaaktual. Secara potensial, waktu itu bergerak tanpa batas, de-mikian pula objek atau bilangan, secara teoritis, dapat dibagihingga tak terbatas, namun hal tersebut hanya bersifat po-tensial dan tidak pernah utuh secara aktual. Untuk membatasipelacakan sebab mundur secara tak terbatas, Aristoteles meng-
6 | Win Usuluddin Bernadien
gunakan konsep empat kausa, sehingga memungkinkan semuaperistiwa dianalisis secara komprehensif rasional tanpa terusmeluas kebelakang.
Aristoteles berpendapat bahwa rasio (akal) perlu kepas-tian, sehingga dengan kepastian itu akal akan mampu mendefi-nisikan dan memberi batasan jelas terhadap segala sesuatu.Dalam kaitan kepastian dan pembatasan ini Aristoteles meno-lak atribut ‘ke-tidak-ter-batas-an’ karakteristik Tuhan. Sesung-guhnya, tidak akan pernah terjadi bahwa Tuhan itu akan me-rupakan sesuatu yang lain daripada yang terbatas, dan argu-men Aristoteles bagi Penggerak yang Tak Digerakkan didasar-kan pada kebutuhan untuk memberi batas pada seluruh pro-ses. Tegasnya, ‘bukti’ eksistensi Penggerak yang Tak Digerak-kan merupakan argumen lemah bagi Tuhan yang tak terbatas.Ia menghindari jalan mundur sebab yang tak terbatas atau ma-ta rantai yang tak berujung dalam usaha untuk mengerti.
Dalam kaitan perlu batas dan ketidakterbatasan ini, me-nurut Sontag, kita mengahadapi salah satu persoalan kunciyang mendasari dan membentuk arah metafisika. Jika kitamengangkat pembatasan dan pemenuhan sebagai tujuan uta-ma, kita bebas mengembangkan metafisika dan filsafat denganmenggunakan lebih dari satu cara. Namun jika tujuan utamakita adalah mencapai kepastian dan ketentuan, maka prinsipmetafisis dan pendekatan filsafat dasar kita harus berubah ka-renanya. Tentang masalah kemampuan pikiran adalah masa-lah yang dapat diselesaikan hanya oleh teori pengetahuan,namun sulit diketahui apakah pikiran itu dapat atau tidak dapatmengerti hingga kita tahu susunan dan jenis objek yang ter-buka bagi kita. Dengan demikian, teori pengetahuan tidak da-pat mulai tanpa pertama-tama memerikan struktur dunia kita.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 7
PENGGERAK YANG TAK DIGERAKKAN
Poin ini dimaksudkan oleh Sontag untuk mengantarkankita pada tempat dan fungsi konsep Penggerak yang Tak Ber-gerak dalam pemikiran Aristoteles.
Perubahan dan gerak dalam arti luas mencakup hal ‘men-jadi’ dan ‘binasa’ serta segala perubahan lainnya. Tiap geraksebenarnya mewujudkan perubahan dari apa yang ada seba-gai potensi ke apa yang ada secara terwujud. Oleh karena itusetiap gerak mewujudkan suatu perpindahan dari apa yangada sebagai potensi ke apa yang ada secara terwujud. Dari diri-nya sendiri apa yang ada secara terwujud tidak dapat meng-usahakan perubahannya. Untuk itu diperlukan adanya pengge-rak yang pada dirinya sendiri telah memiliki kesempurnaan,yang tidak perlu disempurnakan. Penggerak pertama, yang ti-dak digerakkan oleh penggerak lain ini tidak mungkin dibagi-bagi, tidak mungkin memiliki keluasan serta bersifat fisik. Kua-sanya tak terhingga dan kekal. Ia tidak berasal dari dalam du-nia, sebab di jagad raya ini tiap gerak digerakkan. Penggerakpertama ini adalah Allah, Penyebab gerak abadi, yang sendiritidak digerakkan, karena bebas dari materi. Dialah Actus Pu-rus, Aktus Murni. Penggerak yang Tidak Digerakkan menye-babkan gerakan tanpa dirinya sendiri harus bergerak, dia me-rupakan pikiran murni yang beraktualisasi dan berpikir hanyapada dirinya sendiri.
Tentang ‘yang ada sebagai potensi’ dan ‘yang ada secaraterwujud’, menurut Aristoteles, keduanya merupakan sebutanyang melambangkan materi (hule, hyle) dan bentuk (eidos,morfe). Pengertian materi dan bentuk, asas gerak dan tujuan,dipakai untuk mengembalikan segala sesuatu kepada dasaryang terakhir. Bentuk ‘ada’ dan asas ‘ada’ (eidos, morfe) tidaksama dengan pengertian Plato tentang Idea. Bagi Plato Idea
8 | Win Usuluddin Bernadien
atau Eidos adalah pola segala sesuatu yang tempatnya beradadi luar dunia ini, yang berdiri sendiri, lepas dari benda kongkrit.Sedangkan bagi Aristoteles Eidos adalah asas yang imanenatau yang berada dalam benda yang kongkrit, yang secarasempurna menentukan jenis benda itu, yang menjadikan ben-da yang kongkrit itu disebut demikian (misalnya disebut; baju,rumah, kertas, dsb.). Jadi, segala pengertian kita bukanlah se-suai dengan realitas idea yang berada di dunia idea, tetapi se-suai dengan jenis benda yang tampak pada benda yang kon-krit.
Aristoteles mengkhawatirkan gerakan lebih dari apa yangdilakukan Plato, dan dengan demikian, Aristoteles merasa per-lu mengeliminasi gerakan sebagai prinsip ultimate yang meru-pakan penghalang inteligibilitas. Baginya gerakan itu funda-mental dan bukan sebagai sesuatu yang memiliki sifat ilahisebagaiman Plato mamandang ‘jiwa’. Penggerak yang TidakDigerakkan memberi batas pada rangkaian sebab dunia yangtidak berujung, oleh karenanya Aristoteles memandang gerak-an itu senantiasa mengindikasikan kekurangan dan ketidak-lengkapan. Gerakan mengindikasikan ketidak sempurnaan da-lam sesuatu sekaligus sebagai penghalang bagi pengetahuan,kecuali ‘dihentikan’ dengan mengacu pada sesuatu yang telahselesai, yang tidak bergerak. Perhentian, menurutnya, lebihsempurna daripada gerakan.
Aristoteles mengilustrasikan fungsi Tuhan secara metafisis.Penggerak yang Tidak Digerakkan tidak diperlukan secara re-ligius, bahkan tidak berguna secara religius, namun orangdapat melihat yang terefleksikan dalam karakteristik Tuhan-nyatentang adanya asumsi dasar metafisika Aristoteles. Jika hanyasatu konsep tuhan yang mungkin, situasi ini secara metafisisakan sangat berbeda. Setidak-tidaknya konsep tentang tuhan
Serpihan-Serpihan Filsafat | 9
itu banyak sebanyak asumi metafisis yang ada, sehingga tuhantidak dapat hanya dimasukkan atau dihilangkan dari skemametafisis sebagai konsep yang pasti. Namun, konsep tentangtuhan itu mencerminkan skema total dalam sesuatu yang men-jadi pusat perhatian. Jika suatu pandangan metafisis tidak me-miliki konsep tentang tuhan maka pandangan itu anti metafi-sika. Tujuan yang ingin dicapai dari sketsa prinsip metafisisAristoteles adalah pembatasan, pemenuhan, dan rasionalitasmelalui titik acuan yang pasti bagi semua gerakan, dan aktua-litas yang penuh dilawankan dengan potensialitas. TuhannyaAristoteles menunjukkan tujuan ini.[*]
BACAAN PENDUKUNG
Hadiwijono, Harun., 2000, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Ka-nisius: Yogyakarta
Honderich, Ted., 1995, The Oxford Conpanion to Philosophy,Oxford University Press: Oxford, New York.
Pasaribu, Saut., 2002, Sejarah Filsafat, Bentang Budaya: Jog-yakarta
Stevenson, Leslie & Habermen, David L., 2001, Sepuluh TeoriHakikat Manusia, diterjemahkan: Saut Pasaribu & Yudi,Yayasan Bentang Budaya: Jogyakarta
Solomon, Robert C., Higgin Kathleen M., 1996, A Short His-tory of Philosophy, Oxford University Press: Oxford, NewYork.
Sutrisno, Mudji dan Hardiman, Budi., 2001, Para Filsuf Pe-nentu Gerak Zaman, Kanisius: Yogyakarta.
Titus H., Smith M.S., Nolan, Richard T., 1984, Persoalan Per-soalan Filsafat, diterjemahkan Rasjidi H.M., Bulan Bin-tang: Jakarta.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 11
BAGIAN KEDUA
ALAM PIKIRAN DAN EPISTEMOLOGI AL GHAZALI
PENGANTAR
Penulisan mengenai Al Ghazali, meskipun sudah sangatbanyak, tetapi agaknya selalu menarik, karena memang selalusaja terdapat penilaian yang kontroversial terhadap Al Ghazali.Hal ini terjadi karena di satu pihak ada yang menilai bahwa AlGhazali adalah pangkal kemunduran Islam. Para tokoh orien-talis berpendapat bahwa kegiatan intelektual Islam telah matikarena Al Ghazali dinilai anti intelektualisme, apalagi setelahIbnu Rusyd yang oleh kaum orientalis dianggap sebagai simbolrasionalisme Islam mangkat, anggapan semacam itu semakinmenguat. Ada pula yang bahkan menyatakan penyesalannyaatas kehadiran Al Ghazali di dunia Islam dengan alasan bahwaseletah terbit buku Tahafut Al Falasifah, salah satu karya AlGhazali, pemikiran dalam dunia Islam telah mengalami stag-
12 | Win Usuluddin Bernadien
nasi.1 Dari zaman Al Ghazali lah kegiatan dunia Islam dalamfilsafat berakhir, kemerdekaan dan kebebasan berfikir pun ber-henti.2 Namun demikian, di pihak lain ada yang membela danmenyatakan bahwa Al Ghazali adalah Hujjatul Islam (PembelaAgama dan Umat Islam), Mujaddid Islam (Pembaharu Islam),Bahrun Mughriq (Samudera yang Menghanyutkan) dan se-orang Zainuddin (Hiasan Agama). Bagi mereka Al Ghazaliadalah manusia kedua setelah Rasulullah SAW.3 Philip K. Hittidalam bukunya yang berjudul History of Arabs menyatakan“…if there have been the man could have been a prophet afterMuhammad, al Ghazzali would have…”. (jika ada Nabi setelahMuhammad, maka Al Ghazali lah orangnya)” (pen.).4
Benarkah pemikiran intelektual Islam telah mengalami ke-matian atau sekurang-kurang disebut telah mengalami stagna-si?.Ternyata tudingan yang disampaikan oleh para tokoh orien-talis itu banyak mengandung cacat dan tidak dapat dipertang-gung jawabkan. Ternyata model, jaringan, dan tradisi Islam te-rus berjalan hingga saat ini, hanya saja kurang mendapat so-rotan dan publikasi yang memadai sehingga jarang terdengardi banyak negeri yang jauh dari penulisnya.5
Tulisan ini semoga adequate untuk membantu bagi upayamemahami alam pikiran Al Ghazali serta konfigurasi epistemo-
1Selengkapnya silahkan baca: Al Ahwani, Ahmad Fuad, 1988,Filsafat Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.
2Hoesin, Oemar Amin, 1975, Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bintang,hlm. 21.
3Rusn, Abidin Ibnu, 1998, Pemikiran Al Ghazali tentang Pendidik-an, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 2.
4Philip K. Hitty, 1937, History of Arabs, London: Macmilan & CoLtd., hlm. 431.
5Bagus Takwin, 2001, Filsafat Timur, Yogyakarta: Jala Sutra, hlm.75-77.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 13
liginya, suatu epistemologi yang bersifat Islami.
RIWAYAT SINGKAT AL GHAZALI6
Al Ghazali atau di Barat terkenal dengan sebutan Al Gazeldan di kalangan Islam lebih dikenal dengan Hujjatul Islam AsySaykh Al Imamul Jalil Al Ghazali yang biasa disingkat dengansebutan Imam Ghazali, memiliki nama lengkap Muhammadbin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al Ghazali. NamaAl Ghazali kadang diucapkan dengan Ghazzali (double ‘z’) arti-nya si tukang pintal benang, karena ayahnya adalah seorangtukang pintal dan penjual benang wol terkenal di kampungnya.Penulisan namanya yang lazim dilakukan orang adalah Gha-zali (satu ‘z’) saja, yang diambil dari kata Ghazalah yaitu namakampung tempat dia dilahirkan.7
Di samping tiga nama Muhammad berturut-turut, yaitunamanya sendiri, nama ayahnya, dan nama kakeknya barulahdi atasnya lagi bernama Ahmad seperti tersebut di atas. Dikalangan tertentu Al Ghazali juga dikenal dengan sebutan ‘AbuHamid’ artinya ‘Ayah si Hamid’, sayang sekali anak Al Ghazaliitu meninggal saat masih kecil, dan tinggal tiga anak perem-puanya yang masing-masing namanya tidak tercatat dalamsejarah. Adapun sebutan ‘Al Ghazali’, sebagamana yang dise-butkan dalam penulisan adalah sebutan yang dibangsakan ke-pada nama asal daerah kelahirannya, yaitu Ghazalah.8
Al Ghazali lahir pada tahun 450 H/1058 M (tidak diketa-
6Ahmad Maimun, 2010, Tahâfut al-Falâsifah, Kerancuan ParaFilsuf, Bandung: Marja, hlm. 17-18.
7Rusn, op.cit., hlm. 9. Pada halaman judul Tahâfut al-Falâsifah,yang diterbitkan oleh Dârul Ma’ârif Kairo tertulis nama beliau denganAbû Hamid Al Ghazzâlî. (pen.)
8Ahmad Zainal Abidin, 1975, Riwayat Hidup Imam Al Ghazali,Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 27-28.
14 | Win Usuluddin Bernadien
hui tanggal dan tahunnya), di Kampung Ghazalah, KabupatenThus, Propinsi Khurasan, Persia (Iran, sekarang). Ayahnya ber-kebangsaan Persia bernama Muhammad bin Muhammad, se-orang buta huruf dan pedagang miskin tetapi ahli memintal be-nang wol dan sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Halini terbukti saat menjelang kematiannya, Muhammad bin Mu-hammad berwasiat kepada sahabatnya yang sufi bernama Ra-zakani Ahmad bin Muhammad Razkafi agar memberikan pen-didikan kepada Al Ghazali dan Ahmad (Adik Al Ghazali, ber-gelar ‘Abul Futuh’ Sang Juru Da’wah yang Besar, yang di ke-mudian hari terkenal dengan ‘Mujiduddin’). Bersama-sama de-ngan adiknya itulah ia belajar agama kepada Sang Guru Raz-kafi, kemudian ilmu tasawwuf kepada Yusuf en Nassaj.9 Sete-lah itu Al Ghazali melanjutkan studinya ke Jurjan di bawahbimbingan Abu Nasher Isma’ili untuk kemudian meningkatkanpendidikannya di Neisabur (Nishapur) di bawah bimbinganAbdul Malik bin Abdillah bin Yusuf yang bergelar Abul Ma’aliDhiauddin Syaikh Imamul Haramain Al Juwayni. SetelahSyaikh yang paling alim di Neisabur itu mangkat, Al Ghazalimenemui Perdana Menteri Saljuk (saat itu Nizhamul Muluk)untuk dipromosikan dan diangkat menjadi dosen di UniversitasNizhamiyah, Baghdad. Atas prestasinya yang semakin cemer-lang pada tahun 484 H/1091 M, di saat usianya yang masihrelatif muda yaitu 34 tahun dia diangkat menjadi rektor padaUniversitas tersebut. Selama menjabat rektor, Al Ghazali ba-nyak menulis buku-buku agama dan filsafat Islam. Hanya em-pat tahun menjabat rektor di sana untuk kemudian melanglangbuana menuruti kata hati yang sedang krisis rohani. Al Ghazalimenuju Damaskus kemudian Baitul Maqdis, lalu berhaji ke
9Ahmad, ibid, hlm. 31.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 15
Mekkah, kemudian menuju Medinah dan Hijaz.10 Setelah me-langlang buana selama kurang lebih sepuluh tahun, atas desak-an Fakhrul Muluk, Al Ghazali kembali ke Neisabur, tampil se-bagai tokoh pendidikan dan mengarang buku berjudul AlMunqidz Min al-Dhalal, (Bangkit Dari Kegelapan) yang olehWilliam Montgemory Watt telah diterjemahkan ke dalam ba-hasa Inggris dan digabung dengan ‘Bidayatul Hidayah’ (Thebeginning of Guidence) dengan judul ‘The faith and the prac-tice of Al Gazel’.11
Tidak diketahui secara persis berapa lama Al Ghazalimemberi kuliah di Nizhamiyah setelah pengembaraannya itu,tetapi tak lama kemudian setelah Fakhrul Muluk wafat karenaterbunuh pada tahun 500 H/1107 M, Al Ghazali kembali ketanah asalnya, Thus, hingga akhir hayatnya. Al Ghazali wafatpada hari Senin tanggal 14 Jumadatsaniyah 505 H bertepatandengan tanggal 18 Desember 1111 M dalam usia 55 tahunmenurut perhitungan tahun Hijriyah atau 53 tahun menurutperhitungan tahun Miladiyah.12
BEBERAPA PEMIKIRAN AL GHAZALI
Dalam memahami alam pikiran Al Ghazali perlu kiranyaditinjau beragam unsur pemikirannya baik yang ditentang maupun yang mempengaruhi filsafatnya dalam mencapai kebenar-an. Dalam pada itu Widyastuti menyebutkan bahwa terdapatempat macam unsur pemikiran yang mempengaruhi alam pi-kiran Al Ghazali, yaitu:
10Ismail Jakub, t.t., Mencari Makam Imam Al Ghazali, Surabaya:CV. Faisan, hlm. 111.
11Ahmad, op.cit., hlm. 69.12Rusn, op.cit., hlm. 13, sementara itu Ahmad Zainal Abidin, op.cit,.
pada halaman 53, menyebut kemangkatan Al Gahazali adalah padatanggal 14 Jumadil Akhir 505 H/19 Desember 1111 M.
16 | Win Usuluddin Bernadien
1. Unsur pemikiran Mutakallimin2. Unsur pemikiran Filsuf3. Unsur pemikiran kaum Bathiniyah4. Unsur pemikiran kaum Sufi (mysticus).13
Sebagai seorang teolog, mula-mula Al Ghazali mendalamipemikiran kaum Mutakallimin dari berbagai macam aliran,dengan tujuan memelihara aqidah umat Islam dari pengaruhbid’ah yang saat itu telah merajalela. Dia berusaha mengem-balikan aqidah umat Islam kepada ajaran Rasulullah SAW, danberhasil meletakkan warisan Rasulullah SAW, yaitu: Al Qurandan Al Sunnah, di samping ulama, sebagai standar untuk me-nilai seluruh madzhab dan aliran di dalam kalangan Mutakal-limin yang berkembang saat itu. Al Ghazali berhasil menengahiliteralisme tradisional (para pengikut Hambali) dan liberalismerasional (para pengikut Mu’tazilah) berangkat dari metode ber-pikirnya yang ilmiah dan rasional serta diilhami oleh Al Qu’-ran.14 Jelasnya, Al Ghazali mendalami pemikiran kaum Muta-kallimin dengan segala macam alirannya, kemudian melihatbe-tapa perbedaan itu terjadi karena kaum Mutakallimin salingberbeda dan berlainan pendapat dalam menghadapi persoalanmasing-masing. Al Ghazali tidak puas dengan argumentasikaum Mutakallimin saja, kemudian dia pun lalu mempelajarifilsafat dengan seksama dan mengambil kesimpulan bahwamenggunakan akal semata-mata dalam masalah ketuhananadalah seperti menggunakan alat yang tidak mencukupi ke-butuhan.
13Widyastuti, “Nilai-nilai Moral Terkandung dalam Tasawuf Al Gha-zali dan Pengaruhnya Terhadap Etika Islam” 2000, dalam Jurnal Filsafat,Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Filsafat Universitas GadjahMada, hlm. 212.
14Rusn, op.cit., hlm. 13-15.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 17
Setelah mengadakan koreksi total terhadap kaum Muta-kallimin dengan ilmu kalamnya, Al Ghazali mulai berfikir danmendalami filsafat. Sejumlah karangan ahli filsafat, terutamakarya Ibnu Sina, dibaca dan dikaji dengan tekun. Saat itulah AlGhazali menghentikan aktivitasnya dalam mengkaji ilmu-ilmusyari’ah bahkan kegiatan mengarangnya yang telah berlang-sung lama; perhatiannya dipusatkan secara total kepada filsa-fat.15 Sebagai seorang filsuf di masa kejayaan Islam, Al Ghazaliberusaha meletakkan kaidah-kaidah berfikir yang benar sesuaidengan sumber dan dasar ajaran Islam yang kebenarannya bersifat mutlak, yaitu Al Qur’an. Baginya, manusia wajib meneri-ma kebenaran Al Quran secara utuh, sehingga apapun aktivi-tasnya, termasuk aktivitas berfikir, harus bersandar kepada danberdasar atas Al Quran, tanpa ada satupun yang mendahului.Al Ghazali mendasarkan argumentasinya pada ayat Al Quran,yang artinya sebagai berikut:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalia men-dahulukan sesuatu yang tidak layak (baik perkataan maupu per-buatan) di hadapan Allah dan rasul-Nya, dan takutlah kepadaAllah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Menge-tahui. (Q.S. Al Hujurat: 1) (pen.)
Dalam kaitan itu, Al Ghazali menolak pemikiran yang ti-dak berlandaskan atas dan menyimpang dari Al Quran.16 AlGhazali menegaskan bahwa pemikiran yang disebarluaskanoleh para penerjemah dan komentator karya dan filsafat Aris-toteles, terutama Al Farabi dan Ibnu Sina, terbagi menjadi tigakelompok:
1. Filsafat-filsafat yang dipandang kufur
15Rusn, ibid, hlm. 16.16Al Ghazali, 1986, Metode Pemikiran Islam, diindonesiakan oleh
Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 4-13.
18 | Win Usuluddin Bernadien
2. Filsafat-filsafat yang menurut Islam bid’ah3. Filsafat-filsafat yang sama sekali tidak perlu disangkal.
Di dalam karyanya yang berjudul Tahafut al Falasifah (Ke-rancuan Para Filsuf),17 Al Ghazali juga mengingkari pembahas-an yang dilakukan oleh para filsuf di zamannya, kecuali dalamfilsafat ketuhanan atau metafisika, itupun yang harus ditolakkarena dianggap sebagai kekufuran dan keingkaran terhadapnash syar’i. Hanya ada tiga persoalan yang disangkal oleh AlGhazali, yaitu:
1. Masalah ke-qadim-an alam2. Pernyataan bahwa pengetahuan Allah tidak meliputi
individu-individu.3. Pengingkaran para filsuf terhadap kebangkitan tubuh.18
Tidak puas dengan hasil-hasil filsafat, kemudian Al Gha-zali menyelidiki pemikiran kaum Bathiniyah. Para penganut pe-mikiran kaum Bathiniyah berpendapat bahwa ilmu yang sejatiatau Kebenaran yang Mutlak itu hanya dapat ditemukan daripara ‘Imam Al Ma’shum’ yang suci dari kesalahan dan dosa.19
Al Ghazali anti aliran kebatinan. Mula-mula Al Ghazalimelakukan penelitian terhadap berbagai literatur yang dijadi-kan dasar oleh kaum kebatinan.20 Dari penelitian yang dilaku-kan, Al Ghazali berkesimpulan bahwa ternyata tak satupun
17Abû Hamid Al Ghazzâlî, tt, Tahâfut al-Falâsifah, Kairo, DârulMa’ârif. Buku ini telah diindonesiakan oleh Ahmad Maimun, berjudulTahâfut al-Falâsifah, Kerancuan Para Filsuf, dan diberi kata pegantaroleh Dr. Sulaiman Dunya, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Marja,pada tahun 2010.
18Buka Abu Hamid Al Ghazzâlî, ibid, hlm. 55-59, buka juga: Rusn,op.cit., hlm. 17-18.
19Widyastini, op.cit., hlm. 212-21.20Rusn, op.cit., hlm. 20-21.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 19
pengikut kebathinan bisa menunjukkan siapa yang dimaksuddengan ‘Imam Al Ma’shum’. Mereka ‘hanya’ berkeyakinan se-cara a priori saja adanya. Padahal sesungguhnya menurut AlGhazali yang dimaksud ‘Imam Al Ma’shum’ adalah RasulullahSAW, bukan yang lain. Ketidakmampuan para pengikut keba-thinan untuk mengemukakan argumentasi dan menunjukkanbukti siapa dan di mana ‘Imam Al Ma’shum’, maka Al Ghazaliakhirnya berkesimpulan pula bahwa Imam Yang Ma’shum ituhanyalah ‘tokoh’ ideal saja yang hanya ada dalam anggapantidak, dalam kenyataan. Belum puas dengan ketiga macam pe-nyelidikan itu, Al Ghazali kemudian mengikuti pemikiran kaumsufi dan menjalani hidupnya sebagai seorang sufi, yang padaakhirnya mendapatkan hakikat kebenaran yang selama ini diacari. Al Ghazali menghadapkan seluruh hati dan kemauannyahanya kepada Allah SWT. semata-mata serta meningalkan se-luruh persoalan duniawi dengan seluruh godaannya.21 Al Gha-zali memutuskan untuk hidup zuhud dan ‘uzlah yang pada ak-hirnya mencapai haqqul yaqin (keyakinan yang hakiki) yangdidahului oleh ainul yaqin dan ilmu yaqin. Semua pendapatdan pengalamannya tentang tasawwuf itu dituangkannya da-lam karya terbesarnya berjudul Ihya’ ‘Ulumiddin (Menghidup-kan kembali Ilmu agama).22
Al Ghazali merasa berhasil dengan tasawwuf ini dan me-rasa dibukakan oleh Allah SWT. suatu pengetahuan ajaib yangbelum pernah dialaminya. Pengetahuan tasawwuf-lah yang diaanggap sebagai rahasia hakikat kebenaran yang selama ini diacari. Kesan yang diperoleh Al Ghazali adalah ahli tasawwufsungguh-sungguh berada di atas jalan yang benar, berakhlaq
21 Bakry, Hasbullah, 1973, Di Sekitar Filsafat Skolastisk Islam,Jakarta: Tinta Mas, hlm. 49-50.
22 Rusn, op.cit., hlm. 21-23.
20 | Win Usuluddin Bernadien
baik, dan mendapat pengetahuan yang tepat.Sementara itu, ada orang berpendapat bahwa Al Ghazali
bukan seorang filsuf tetapi seorang sufi. Hal ini dapat dime-ngerti karena Al Ghazali dalam Tahafut al Falasifah telah me-nentang secara terang-terangan berbagai hasil pemikiran filsa-fat Yunani dan menganggap bahwa akal dan filsafat bukanlahalat yang paling utama baginya.Tetapi sesungguhnya pendapatsemacam itu tidak benar, karena sesungguhnya Al Ghazalitidak hanya bersandar pada akal dan filsafat saja. Toh, seluruhprestasi Al Ghazali dalam buku-bukunya dapat dianggap se-bagai hasil akal dan karya filsafat yang sesuai dengan prinsipagama Islam. Kesimpulan ‘kebenaran’ Al Ghazali yang dina-makan orang ‘tasawwuf’ pada umunya lebih banyak memakai‘perasaan’ daripada ‘pemikiran’, namun perlu diketahui bah-wasanya dalam ‘mistik’ (tasawwuf) Al Ghazali jelas sekali faktor‘pemikiran’ lebih daripada faktor ‘perasaan’nya. Hal tersebutsesuai dengan tuntunan Al Quran betapa pentingnya faktor‘akal’.23 Besarnya pengaruh Al Ghazali dalam dunia Islam da-pat dilihat dari gelarnya yaitu: Zainuddin yang artinya ‘HiasanAgama’ dan Hujjatul Islam yang artinya ‘Pembela Islam’.24
Gelar itu diberikan padanya karena dia telah dianggap sebagaimuslim terbesar sesudah Rasulullah SAW. Ini berarti kalangandunia Islam pada umumnya menyukai amal dan ilmu Al Gha-zali serta telah dianggap sebagai seorang pemikir Islam yangmempunyai pengaruh besar dalam pemikiran dan pemaham-an ajaran-ajaran Islam. Hampir sepanjang hidupnya, Al Gha-zali telah berhasil menjadi ‘pembela’ yang berhasil menentangunsur-unsur luar yang membahayakan keyakinan umat Islam.
Masih berkait dengan Tahafut al-Falasifah, dapat ditam-
23Widyastini, op.cit. hlm. 213.24Rusn, op.cit., hlm. 9.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 21
bahkan bahwa secara etimologi Tahafut berarti keguguran dankelemahan .25 Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Al Ghazalimenulis Tahafut Falasifah untuk menolak dua puluh kesalahanpara filsuf muslim dan pendahulu mereka yang Theistik diYunani.26 Al Ghazali mengelompokkan mereka dalam tiga go-longan:
1. Golongan Dhahriyyun (para filsuf Materialis-atheis), me-reka adalah para atheis yang anti Tuhan dan merumus-kan bahwa alam terjadi dengan sendirinya serta yakinakan keabadian alam.
2. Golongan Tabi’iyyun (para filsuf Naturalis Deistik), yangmelakukan riset atas alam semesta dan segala yangmenakjubkan dalam dunia flora dan fauna.
3. Golongan Ilahiyyun (para filsuf Theis) Yunani sepertiSocrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka, terutama Aris-toteles, ditentang oleh Al Ghazali karena mengatakanalam ini qadim (tidak bermula).
Dalam bidang filsafat terutama yang berkaitan denganilmu pengetahuan, Al Ghazali mengemukanan enam lapanganpenyelidikan, yaitu: matematika, logika, fisika, metafisika (Ke-tuhanan), politik, dan etika. Jelasnya, meskipun dalam wawas-an yang terbatas yaitu wilayah ilmu yang berkaitan denganmasalah agama, etika, dan filsafat, tetapi Al Ghazali memilikikemampuan ilmu pengetahuan yang multidimensional. Lebihdari itu ide-idenya bersifat crusial, kritis, dan verifikatif terhadapdisiplin ilmu yang dihadapinya dengan prinsip seluruh kajian-nya selalu diparalelkan dengan prespektif agama dalam bingkaisufistik, karena itu di kalangan umat Islam Al Ghazali dikenal
25Dawdy, Ahmad, 1984, Segi-segi Pemikiran Filsafat dalam Islam,Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 12-13.
26Ahmad Maimun, op.cit., hlm. 55-59.
22 | Win Usuluddin Bernadien
sebagai ahlush sufah (mysticus) terbesar.27
EPISTEMOLOGI AL GHAZALI
Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistemeartinya pengetahuan, dan logos artinya ilmu. Dalam bahasaInggris disebut Theory of Knwoledge yang dalam bahasa Indo-nesia diterjemahkan dengan Filsafat Pengetahuan. Sebagai sa-lah satu cabang filsafat, kajian epistemologi meliputi segala halihwal pengetahuan, yaitu: hakikat pengetahuan, sumber pe-ngetahuan, masalah-masalah kebenaran, bahkan hubunganantara pengetahuan dengan moral; terutama saat pengetahuansudah menjadi ilmu terapan. Epistemologi merupakan salahsatu cabang filsafat yang menganalisis pengertian pengetahuansampai ke faktor-faktor pengetahuan yang terdalam, yaitu:sumber pengetahuan. Epistemologi menghasilkan pengertiansumber pengatahuan yang beragam dengan paradigma ilmupengetahuan bahkan lebih lengkap dari ilmu pengetahuan.Dengan epistemologi dapat dibuktikan bahwa sumber pengeta-huan itu bukan hanya empiri (alirannya disebut empiricism) te-tapi juga akal (alirannya disebut rasionalism), kombinasi antarakeduanya disebut Criticism. Pendapat Empirisisme dan Rasio-nalisme merupakan dua titik ekstrim, sehingga untuk meng-analisis kekurangan paradigma ilmu pengetahuan tentunya ku-rang adil jika dikonfrontasikan atau dibandingkan ataupun di-lengkapi dengan Kritisisme.
Sementara itu ada yang berpendapat bahwa dalam pemi-kiran Islam, belum ditemukan bentuk nyata epistemologi yangIslami. Dengan kata lain paradigma epistemologi Islam belum
27Amien, Miska M., 1992, Kerangka Epistemologi Al Ghazali,dalam Jurnal Filsafat, Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas FilsafatUniversitas Gadjah Mada hlm. 13-14a.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 23
ada.28 Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa Al Ghazalisebagai seorang filsuf besar dunia masih mempersalahkan ilmupengetahuan, seperti para filsuf pada umumnya. Meskipun de-mikian nampak jelas juga bahwa Al Ghazali memiliki konsepepistemologi, yang sudah barang tentu pemikirannya didasar-kan itu pada ajaran-ajaran Islam, dan karenanya epistemologiAl Ghazali adalah epistemologi Islam. Dengan demikian epis-temologinya bersifat Islami bahkan Qurani. Kenyataan ini bu-kan berarti Al Ghazali mengabaikan berbagai sumber ilmu pe-ngetahuan yang lainnya. Al Ghazali tetap tetap mengakui eksis-tensi akal, indra, dan intuisi. Dalam Ihya Ulumuddin Juz I pada‘Kitabul Ilmi’ halaman 5–17 Al Ghazali menjelaskan bahwasecara epistemologis ilmu pengetahuan itu terbagi menjadidua, yaitu syar’iyah dan dan ghairu syar’iyah atau disebutnyapula sebagai ilmu aqliyah. Ilmu Syar’iyah adalah pengetahuanyang diperoleh dari para nabi tidak dari akal manusia belaka,meliputi;
1. ilmu ushul, terdiri atas kitabullah, sunnah rasul, dan ij-ma’, serta sejarah awal Islam peninggalan para sahabat.
2. ilmu furu’ terdiri atas fiqh (untuk kepentingan duniawi)dan ilmu mukasyafah (untuk kepentingan ukhrawi, yangoleh Al Ghazali disebut pula ilmu bathiny, ilmu ma’rifat),serta ilmu mu’amalah (untuk kepentingan dunia danakhirat).
3. ilmu muqaddimah (ilmu yang berfungsi sebagai alat un-tuk mengetahui isi Kitabullah dan sunnah rasul).
4. ilmu mutammimah yaitu semua ilmu yang berkenaandengan Al Quran, baik bacaan (qiraat) maupun tafsir.
28As Shadr, Muhammad Bagir, 1991, diindonesiakan oleh M. NurMufid bin Ali, Falsafatuna: Pandangan uhammad Bagir Ash Sadr ter-hadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia, Bandung: Mizan, hlm.14.
24 | Win Usuluddin Bernadien
Sedangkan ilmu ghairu syar’iyah atau aqliyah adalah il-mu yang bersumber dari akal baik secara dlaruri (instink,innate idea) maupun iktisabi (melalui belajar dan ber-pikir).
Selanjutnya, Al Ghazali menjelaskan pembagian pengeta-huan yang berkenaan dengan tugas dan tujuan hidup manu-sia.Dalam membahas masalah ini Al Ghazali berpijak pada duahadits nabi, sebagai berikut:
][Artinya: Mencari ilmu (pengetahuan) itu wajib atas setiap muslim
(diriwayatkan oleh Baihaqy dari Ibnu Abdil Bari).
][Artinya: ‘Tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu berada di negeri China’.
(diriwayatkna oleh Imam As Suyuthi).
Dari dua hadits tersebut di atas, secara ontologi Al Ghazalimembagi pengetahuan menjadi dua:
1. pengetahuan fardlu ‘ain, maksudnya pengetahuan yangharus (wajib) dimiliki oleh setiap individu. Pengetahuanini meliputi ilmu tauhid (pengetahuan tentang pokok-po-kok keyakinan kepada Tuhan dan rasul-Nya), ilmu sya-riat (pengetahuan tentang segala hal yang menjadi ke-wajiban manusia kepada Tuhan-nya), dan ilmu sirri (pe-ngetahuan tentang status kehambaan manusia di bawahTuhan).
2. pengetahuan fardlu kifayah maksudnya pengetahuanmanusia yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan-nya di dunia, tetapi setiap individu tidak harus memiliki-nya, antara lain: geografi, matematika, fisika, kimia, ke-dokteran, ekonomi, filsafat, bahasa, sejarah, etika, pen-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 25
didikan, politik, antroplogi, psikologi, astrologi, keteram-pilan, dan lain sebagianya.
Demikian, sebagaimana yang telah disebutkan di atasbahwa Al Ghazali tetap mengakui eksistensi akal, indra, danintuisi sebagai sumber pengetahuan. Menyangkut akal ini, AlGhazali mengklasifikasikan menjadi empat pengertian:
1. Sebutan yang memisahkan manusia dengan semuabinatang.
2. Pengetahuan yang muncul saat seseorang memasukifase dewasa (‘aqil baligh) sehingga dapat membedakanperbuatan yang boleh dilakukan dan yang tak mungkindilaksanakan.
3. Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman.4. Kekuatan menghentikan dorongan naluriah untuk me-
nerawang jauh ke angkasa, mengekang dan menunduk-kan syahwat yang selalu mengagungkan kenikmatansesaat.29
Di samping akal, Al Ghazali juga menganggap indera se-bagai sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini merupa-kan satu tingkat perkembangan manusia yang dilengkapi de-ngan ‘mata’ untuk dapat melihat berbagai bentuk yang dapatdipahami (ma’qul). Manusia mengetahui dirinya melalui per-sepsi (idrak), dari idrak ini manusia mengenal ‘alam’ tertentudengan suatu eksistensi tertentu. Indra pertama yang dicipta-kan dari dalam diri manusia adalah indra peraba.30 Lebih jauhlagi Al Ghazali menempatkan sumber pengetahuan lain yang
29Amien, Miska M, op.cit., hlm. 15.30Othman, Ali Issa, 1981, diindonesiakan oleh Johan Smit, Anas
Mahyuddin, Yusuf, Manusia menurut Al Ghazali, Bandung: Pustaka,hlm. 16.
26 | Win Usuluddin Bernadien
cukup berperan yang disebut Syar, yaitu: wahyu ilahy, sunnahnabi SAW, serta intuisi (dzawaq).
Tentang teori-teori kebenaran, seperti teori kebenaran ko-respondensi, koherensi, maupun teori pragamatis, Al Ghazalisecara eksplisit tidak menjelaskan. Namun demikian jika dicer-mati secara seksama agaknya teori kebenaran Al Ghazali lebihmengacu pada metode teologi yang dianut oleh kaum sufi. AlGhazali lalu menyebutkan Istisyhad (deduktif) sebagai metodeuntuk mencapai kebenaran dan kecintaan kepada Allah. Se-lanjutnya dia menjelaskan tiga unsur penting yang harus dimi-liki manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu:
1. Objek pengetahuan yang bersifat eksternal2. Subjek pengamat objek3. Proses pemahaman/pengertian, baik internal maupun
eksternal.
Masih dalam pembahasan mengenai epistemologi, seba-gaimana yang telah penulis sampaikan pada bagian terdahulubahwa alam pemikiran Al Ghazali dipengaruhi oleh empat un-sur, yaitu Mutakallimin, Bathiniyah, Ahli Filsafat, dan para Sufi(mysticus). Menurut Al Ghazali empat unsur (kelompok) manu-sia tersebut memiliki corak karakteristik sendiri-sendiri dalammencari kebenaran. Para Mutakallimin (ahli teologia) menyata-kan dirinya sebagai eksponen dari pengetahuan dan pemikiranintelektual, kaum Bathiniyah yang merupakan kelompok ‘pe-ngajar’ menyatakan bahwa mereka mendapatkan kebenarandari ‘Imam al Ma’shum’ (Imam yang sempurna dan tersem-bunyi), sedangkan para ahli filsafat menganggap dirinya seba-gai eksponen logika dan membuktikannnya, serta para mys-ticus (kaum sufi) menyatakan bahwa merekalah yang menca-pai tingkat ‘hadlir’ dengan Allah dan memiliki penglihatan sertapengertian secara bathiniyah. Keempat kelompok tersebut di
Serpihan-Serpihan Filsafat | 27
atas masing-masing memiliki cara untuk mencapai kebenaran.Kaum Mutakallimin dengan cara Jadal (desputatio/debat ataudiskusi), kaum Bathiniyah menggunakan cara ta’lum yaitu me-ngandalkan kebenaran dari seorang yang dianggap memilikiotoritas untuk menyampaikan kebenaran yang disebut ustadz(guru), sedangkan para ahli filsafat berpandangan bahwa ke-benaran satu-satunya dan paling valid adalah akal dengandaya nalarnya, dan kaum sufi (para mysticus) mengandalkancontemplation (perenungan) untuk mendapatkan kebenaran.Masing-masing golongan menganggap bahwa pendirian yangmereka anut itu benar, sedangkan pendapat yang lain salah.Untuk itu Al Ghazali melakukan penyelidikan terhadap pendiri-an mereka itu satu per satu dengan metode ilmiah yang biasadipakai dalam dunia pengetahuan, yaitu:
1. Tajribah (empiricism), ialah penelitian berdasarkan pe-ngalaman dan hasil cerapan inderawi.
2. ‘Aqly (rationalism), penelitian yang berdasarkan akal(rasio)
3. Ilhamy (intuitionism), berdasar pada inspirasi yang tim-bul dari dalam kalbu.
Dalam kaitan ini, secara ringkas dapat dikutip pendapatWilliam Montgomery Watt yang menulis, sebagai berikut:31
“…looking for necessary truths, Al Ghazali came, like Descartes, todoubt the infallibiality of sense perception, and to rest his phi-losophy rather on principles which are intuitively certain. With thisin mind Al Ghazali divided the various ‘seekers’ after truth into thefour distinct group of Theologians,Philosophers, Authotarians, andMystics” (…untuk mencari kebenaran, Al Ghazali, sebagaimanaDescartes, menyangsikan kekebalan dari pengertian fikiran, danmendasarkan filsafatnya pada prinsip-prinsip ilham yang pasti.
31Watt, William Montgomery, 1963, Muslim Intelectual: Study of AlGhazali, Edinburgh: Edinburgh University Press, hlm. 11-12).
28 | Win Usuluddin Bernadien
Atas dasar inilah Al Ghazali membagi ‘para pencari’ kebenaran itudalam empat kelompok yang jelas, yaitu: Alim ulama Mutakal-limin, para Ahli filsafat, kaum Bathiniyah, dan para Sufi”.(pen.)
PENUTUP
Pandangan epistemologi Al Ghazali memang sangat luas.Beberapa butir pemikiran epistemologi masih sangat relevandengan perkembangan filsafat pengetahuan masa kini, mes-kipun memang harus diakui sisi-sisi kelemahannya. Pandanganepistemologi Al Ghazali yang sufistik tentu bukan hal yangmudah bahkan sangat rumit dan sulit dipahami oleh kalanganluar sufi. Karenanya research mengenai epistemologi Al Gha-zali, sang hujjatul Islam wa bahrul al mughriq khususnya bagimereka yang berkecimpung di dunia filsafat, bisa jadi masihperlu untuk selau digalakkan.[*]
BACAAN PENDUKUNG
Ahmad Maimun, 2010, Tahâfut al-Falâsifah, Kerancuan ParaFilsuf, Bandung: Marja.
Al Ghazali, 1986, Metode Pemikiran Islam, diindonesiakanoleh Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Panjimas.
Al Ahwani, Ahmad Fuad, 1988, Filsafat Islam, Jakarta: PustakaFirdaus.
Al Ghazzâlî¸ Abû Hamid, t.t., Tahâfut al-Falâsifah, Kairo: DârulMa’ârif.
Amien, Miska M., 1992, Kerangka Epistemologi Al Ghazali,,dalam Jurnal Filsafat, Yogyakarta: Yayasan PembinaFakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
As Sayuti, Imam, t.t., Al Jami Al Shaghir, Juz Al Tsani, DarulFikri.
As Shadr, Muhammad Bagir, 1991, diindonesiakan oleh M.Nur Mufid bin Ali, Falsafatuna: Pandangan Muhammad
Serpihan-Serpihan Filsafat | 29
Bagir Ash Sadr terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia,Bandung: Mizan.
Bakry, Hasbullah, 1973, Di Sekitar Filsafat Skolastisk Islam, Ja-karta: Tinta Mas.
Dawdy, Ahmad, 1984, Segi-segi Pemikiran Filsafat dalam Is-lam, Jakarta: Bulan Bintang.
Hitty, Philip K., 1937, History of Arabs, London: Macmilan &Co Ltd.
Hoesin, Oemar Amin, 1975, Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bin-tang.
Ismail Jakub, t.t., Mencari Makam Imam Al Ghazali, Surabaya:CV. Faisan.
Watt., William Montgomery, 1963, Muslim Intelectual: Study ofAl Ghazali, t.t., Edinburgh: Edinburgh University Press.
Othman, Ali Issa, 1981, diindonesiakan oleh Johan Smit, AnasMahyuddin, Yusuf, Manusia menurut Al Ghazali, Ban-dung: Pustaka.
Rusn, Abidin Ibnu, 1998, Pemikiran Al Ghazali tentang Pendi-dikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Takwin, Bagus, 2001, Filsafat Timur, Yogyakarta: Jala Sutra.Widyastuti, Nilai-nilai Moral Terkandung dalam Tasawuf Al
Ghazali dan Pengaruhnya Terhadap Etika Islam, 2000,dalam Jurnal Filsafat, Yogyakarta: Yayasan PembinaFakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Zainal Abidin, Ahmad, 1975, Riwayat Hidup Imam Al Ghazali,Jakarta: Bulan Bintang.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 31
BAGIAN KETIGA
PERSIMPANGAN RASIONALISME-EMPIRISISME:REFLEKSI KRITIS ATAS SUMBER-SUMBER
PENGETAHUAN
PENGANTAR
Epistemologi dapat dimengerti sebagai bidang ilmu yangmembahas pengetahuan manusia, dalam berbagai jenis danukuran kebenarannya. Berdasarkan pengertiannya, epistemo-logi jelas merupakan bagian dari filsafat yang berusaha untukmenelaah hakikat, jangkauan, pengandaian, dan pertanggung-jawaban pengetahuan.32 Sebagai cabang filsafat, epistemologijuga mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan,berbagai ragam pengandaian dan dasarnya, dann sudah ba-rang tentu berbagai bentuk pertanggungjawaban atas pernya-taan mengenai pengetahuan. Di dalam epistemologi juga selaludipersoalkan mengenai apakah indera memberi pengetahuan?
32Protasius Hardono Hadi, dalam Aholiab Watloly, TanggungjawabPengetahuan, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 5.
32 | Win Usuluddin Bernadien
Dapatkah budi memberi pengetahuan? Apakah hubungan an-tara pengetahuan dan keyakinan yang benar? Persoalan-per-soalan itulah yang antara lain digulati oleh epistemologi.33 Ringkasnya, epistemologi dapat dimengerti sebagai teori pengeta-huan yang membicarakan tentang sumber, bentuk, dan caramemperoleh pengetahuan. Tulisan ini, meskipun tidak secaraholistik tetapi akan mencoba untuk mengeksplorasi beberapahal pokok epistemologi, khususnya tentang sumber-sumberpengetahuan bagi Rasionalisme dan Empirisisme, kemudianpada bagian akhir tulisan ini akan dieksplorasi seperlunya ten-tang sumber pengetahuan selain akal dan indera, yaitu hati;dengan harapan persimpangan rasio dan empiri dapat dielabo-rasi secara mencukupi.
RASIONALISME
Renê Descartes (1596-1650) sebagai tokoh sentral alirasnrasionalisme, dengan gaya skeptisnya mula-mula mempersoal-kan apakah pengetahuan itu ada (whether there is any know-ledge). Pertanyaan ini dia maksudkan sebagai pintu masuk ba-gi jawaban bahwa manusia memiliki pengetahun. Sejalan den-gan hal tersebut, kemudian dia menyatakan bahwa rasio me-rupakan sumber utama dan pangkal pengetahuan, rasio ada-lah dasar kepastian pengetahuan dan karena itu rasio merupa-kan satu-satunya pengukur kebenaran pengetahuan. Baginya,rasio adalah instrumen dalam diri manusia yang mampu men-getahui kebenaran tanpa melalui pengalaman.34
Searah dengan hal tersebut kemudian terungkap bahwa
33Protasius Hardono Hadi, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan, Yo-gyakarta: Kanisius, 1994, hlm. 5-6.
34Selebihnya dapat dibaca terutama Bab I karya Renê Descartesyang telah diindonesiakan oleh Ahmad Faridl Ma’ruf dengan judul Dis-kursus & Metode, Yogyakarta: IRCisoD, 2012, hlm. 26-38.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 33
untuk dapat memahami dan menjelaskan apa yang dialami,ternyata mau tidak mau manusia perlu melakukan kegiatanberpikir, dan sudah barang tentu dalam hal ini, mengandaikanadanya pikiran.35 Pengalaman yang dialami oleh manusia danjuga rasa ingin itu sesungguhnya sudah mengandaikan pikiran.Dorongan rasa ingin tahu mengantarkan pikiran untuk menga-jukan pertanyaann yang relevan denga persoalan yang diha-dapi. Dalam arti yang lebih luas berpikir itu lebih dari sekedarbernalar, tetapi kegiatan pokok pikiran dalam mencari penge-tahuan adalah penalaran. Oleh karena itu pikiran dan penala-ran menjadi dasar bagi kemungkinan pengetahuan, atau deng-an kata lain tidak mungkin ada pengetahuan tanpa ada pemi-kiran dan penalaran.
Penalaran tentu saja dapat dimengerti sebagai proses ba-gaimana pikiran menarik kesimpulan dari berbagai datum yangtelah diketahui sebelumnya, baik melalui jalan induksi, deduksimaupun abduksi.36 Induksi adalah penalaran yang berangkatdari suatu bagian suatu keseluruhan, dari contoh-contoh khu-sus menuju pernyataan umum tentangnya; dari hal-hal indi-vidual atau partikular menuju hal-hal universal, atau bisa jugadipahami sebagai proses penalaran untuk menarik kesimpulanumum (universal) dari berbagai kejadian khusus (partikular).Misalnya: Semua logam akan memuai bila dipanasi, nah uangDinar terbuat dari logam maka bila dipanasi uang Dinar punakan memuai. Ringkasnya, induksi dapat didefinisikan sebagaipenalaran dari contoh-contoh partikular menuju ke kesimpulan
35J. Sudarminta, Epistemologi Dasar, Yogyakarta: Kanisius, 2002,hlm. 38-40.
36Selengkapnya dapat dibaca terutama Bab IX karya ProtasiusHardono Hadi, Op. cit., hlm. 135, juga Loren Bagus, Kamus Filsafat,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 1, 149, dan 341.
34 | Win Usuluddin Bernadien
umum.Selanjutnya, induksi dapat dibagi dua, yaitu: induksi sem-
purna dan induksi cacat. 37
Induksi sempurna mengasumsikan bahwa semua individudiperiksa dan suatu ciri khas teramati pada seluruh individu itu.Dalam prakteknya, meskipun seluruh contoh individual dapatdiamati tetapi mustahil rasanya bisa memeriksa semua contohindividualnya di masa lalu maupun di masa depan. Setidak-tidaknya selalu terbuka kemungkinan adanya sejumlah contohindividual di masa lalu ataupun di masa depan yang tidak te-ramati dalam proses induksi. Adapun induksi cacat terjadi tat-kala sekian banyak contoh suatu esensi diamati dan ciri umumdisematkan pada seluruh individunya. Pola penyimpulan se-perti ini senyatanya tidak membuahkan kepastian, karena sela-lu saja ada peluang, betapa pun kecilnya, salah satu dari indi-vidu yang tidak teramati tidak berciri khas sama. Karena itupulalah, dalam praktiknya keyakinan dan kepastian evidensitidak diperoleh melalui jalan ini. Sedangkan deduksi adalahpenyimpulan yang berangkat dari universal menuju partikularatau juga bisa dikatakan bentuk penalaran yang berangkat darisuatu pernyataan umum ke kejadian khusus yang secara nis-caya dapat diturunkan dari pernyataan umum tersebut. Misal-nya dari pernyataan umum semua logam akan memuai biladipanasi maka secara deduktif pun dapat disimpulkan bahwabesi akan memuai bila dipanasi, karena besi merupakan salahsatu dari logam. Adapun abduktif adalah penalaran untuk me-rumuskan sebuah hipotesis berupa pernyataan umum yangkemungkinan kebenarannya masih perlu diuji, dengan kata
37Selebihnya dapat dibandingkan dengan induksi lengkap daninduksi tak-lengkap, pada Bab IX dalam Protasius Hardono Hadi, loc.cit., hlm. 135.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 35
lain, sifat pembuktiaanya masih lemah. Misalnya: “Semua pro-duk dalam negeri kwalitasnya tidak lebih baik bila dibanding-kan dengan produk luar negeri”. Pernyataan ini tentu masihperlu diuji kebenarannya, karena beberapa kwalitas produkdalam negeri nyatanya tidaklah demikian.
Berkat berbagai kemampuan penalaran-penalaran seba-gaimana tersebut di atas maka manusia pun mampu mengem-bangkan pengetahuannya. Berkat pikiran dan kemampuanpenalarannya pula manusia tidak harus selalu beradaptasidengan lingkungannya tetapi bahkan bisa mengubah lingkun-gan alam dan lingkungan sosialnya sesuai dengan kepentingandan kebutuhannya, meskipun memang harus diakui bahwakemampuan ini bukan tanpa masalah; baik masalah lingkun-gan maupun masalah sosial.
EMPIRISISME
Empirisisme menegaskan bahwa sumber seluruh pengeta-huan harus dicari di dalam atau dari pengalaman. Semua pen-getahuan, selain logika dan matematika, turun secara langsungatau disimpulkan secara tidak langsung dari data inderawi. Da-lam empirisisme diyakini bahwa pengetahuan yang sebenar-nya adalah pengatahuan yang diterima melalui persentuhanindera dengan fakta. Dengan kata lain empiri adalah peme-gang peranan penting bagi pengetahuan karena empiri meru-pakan sumber pengetahuan, bukan rasio. Hal ini berarti bahwasemua bentuk penyelidikan kearah pengetahuan dimulai daripengalaman, karena itulah maka hal pertama dan utama yangmendasari dan yang memungkinkan adanya pengetahuanadalah pengalaman, yaitu keseluruhan peristiwa yang terjadipada manusia dalam interaksinya dengan dirinya, denganalam, dan dengan seluruh kenyataan yang dialami.
Dalam pada itu John Locke (11632-1704) membagi pen-
36 | Win Usuluddin Bernadien
galaman menjadi dua, yaitu: pengalaman sensasi (sensation,lahiriyah) dan pengalaman refleksi (reflextion, batiniyah).38
Locke kemudian menegaskan bahwa akal tidak akan melahir-kan pengetahuan dari dalam dirinya melainkan berasal daridorongan sensasi dan refleksi. Pengalaman sensasi merupakanpengalaman primer, karena merupakan pengalaman langsungakan persentuhan inderawi dengan benda-benda konkrit diluar manusia, pengalaman tentang peristiwa yang disaksikansendiri. Mata melihat, telinga mendengar, jemari meraba ada-lah pengalaman-pengalaman akan peristiwa yang disaksikanlangsung oleh diri sendiri. Pengalaman refleksi (reflextion, bati-niyah) merupakan pengalaman sekunder, karena merupakanpengalaman yang tak langsung; pengalaman yang diperolehmelalui refleksi atas pengalaman-pengalaman primer. Tatkalaseseorang melihat benda, mendengar suara, atau meraba se-suatu maka tatkala itu pula seseorang sadar akan apa yang di-lihat, didengar, dan akan apa yang diraba. Seseorang sadarakan adanya kenyataan lain di luar dirinya yang menstimulasiorgan-organ tubuhnya, dan dia pun sadar akan kesadarannyaitu.
Ada tiga hal yang dapat diungkapkan mengenai pengala-man manusia, yakni: pengalaman itu beragam, pengalaman ituselalu berkait dengan objek di luar subjek, dan pengalaman ituselalu bertambah. Keberagaman pengalaman ditandai denganberagamnya peristiwa yang dialami di sepanjang hidupnya;sedih, gembira, terharu, melihat, mendengar, mengerti, me-nyanyi, memilih, mencicipi, membayangkan, memikirkan, ber-jalan, berlari, berkhotbah, berdoa, memuji, bahkan menceladan mengumpat serta beragam peristiwa yang lain selalu saja
38Solomon, Robert, C,. Introducing Philosophy, New York: Har-court Brace Jovanovich, Inc., 1981, p. 108.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 37
dialami oleh manusia di sepanjang hidupnya. Dalam keseluru-han peristiwa itu manusia berhadapan dengan sesuatu “yanglain” yang berada di luar dirinya.39 Seseorang tidaklah mung-kin akan sertamerta bersedih tanpa ada sesuatu “yang lain”yang menyebabkan kesedihan itu menghampirinya. Hal iniberarti seseorang itu sesungguhnya mengerti akan “yang lain”di luar dirinya yang adanya tidak tergantung darinya. Sesuatu“yang lain” itu merupakan penyebab formal terjadinya penga-laman sekaligus sebagai isi pengalaman. Dalam hal ini dapatdikatakan bahwa: “aku bukanlah satu-satunya sumber penga-lamanku”. Kesadaran akan aku sebagai subjek penahu selalusudah mengandaikan adanya yang bukan aku, entah itu aku-aku yang lain atau pun benda atau pun sesuatu yang bukanmanusia di sekitarku. Jelaslah sudah bahwa aneka ragam haldan peristiwa akan menambah pengalaman manusia, danpengalamann itu pun akan terus bertambah seiring denganbertambahnya usia, kesempatan, dan kedewasaannya. Tam-bahan pengalaman tersebut bukan sekedar menjadi tumpukanpengalaman demi pengalaman melainkan bisa menjadi pa-duan harmoni yang memperkaya dan menumbuhkan pribadiyang mengalami, sepanjang pengalaman itu direfleksikan dandiolah menjadi pengetahuan. Dalam hal ini nampak betapapengalaman itu lebih luas dari pada pengetahuan, karena nya-tanya tidak semua pengalaman bisa menjadi pengetahuan.Hanya pengalaman yang diolah menjadi pengetahuan sajalahyang dapat berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.Ringkasnya, apabila seseorang memiliki pengalaman tetapipengalaman itu tidak pernah disadari dan tidak pernah dimen-gerti apalagi tidak pernah diungkapkan, maka pengalaman itu
39Untuk pemahaman lebih lanjut dapat dibaca pula Bab III karyaProtasius Hardono Hadi, ibid, hlm. 43-56.
38 | Win Usuluddin Bernadien
tidak akan berguna. 40
METODE RASIONAL DAN METODE EMPIRIS
Pengalaman bukanlah metode tandingan atas metode de-duktif, karena di dalam pengalaman itu sendiri terkandung de-duktif. Atas dasar ini maka menyetarakan induksi dengan pen-galaman atau pun mempertentangkan deduksi dengan penga-laman jelas tidak tepat. Mempertentangkan metode rasionaldengan metode empiris biasanya berasal dari pertimbanganbahwa metode rasional merupakan deduksi yang terdiri ataspremis-premis rasional belaka. Jelasnya, metode rasional danmetode empiris memiliki watak dan ruang lingkup yang tidaksama. Ilmu-ilmu alam tentu saja menuntut pemecahan denganmetode empiris dan sudah barang tentu premis-premis yangdiperoleh melalui pengalaman inderawi, karena konsep-konsepyang digunakan dalam ilmu-ilmu kealaman dan yang menjadisubjek-predikat proposisinya berasal dari objek-objek inderawi(sensible thing) pula. Oleh karena itu wajarlah bila pengala-man-pengalaman inderawi mesti diberlakukan untuk membuk-tikan kebenaran proposisi-proposisinya.41
Demikian halnya dengan metode rasional, dengan rasiosaja seseorang tidak akan bisa mengungkapkan bahwa benda-benda itu terdiri atas timbunan molekul dan atom. Denganhanya mengandalkan rasio saja seseorang tidak akan menge-tahui elemen-elemen apa yang diperlukan untuk membuat se-nyawa kimiawi. Rasio juga tidak bisa mengungkap komposisikimiawi suatu makhluk hidup sehingga makhluk itu bisa berta-
40J. Sudarminta, op. cit., hlm. 32-33, dan untuk pemahaman lebihlanjut dapat dibaca pula Bab XI dan Bab XII karya P. Hardono Hadi, op.cit., hlm. 159-179.
41M.T. Mishbah Yazdi, Buku Daras Filsafat Islam, diindonesiakanoleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 56-59.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 39
han hidup. Rasio pun nyatanya juga tidak mampu menyibaktabir rasa sakit dan bagaimana pula menyembuhkan rasa sakititu, semuanya memerlukan perpaduannya dengan pengala-man, bukan rasio saja. Pada sisi lain, berbagai hal yang terkaitdengan intelligible thing sudah barang tentu tidak bisa dipe-cahkan begitu saja dengan melalui pengalaman inderawi, ataudinafikan begitu saja dengan bidang ilmu empiris. Misalnyatentang jiwa tidak mungkin dapat dihadirkan di laboratorium,tatkala ingin dibuktikan keberadaanya. Atau tentang mimpidan berbagai hal yang immaterial lain tentu tidak bisa ditentu-kan ada tidaknya bila menggunakan perangkat ilmiah empiri-sistik. Ringkasnya, proposisi filsafat atau pun semua konsepyang diperoleh dengan melalui analisis rasional hanya bisa di-benarkan atau disalahkan dengan cara-cara rasional, artinya:hanya bisa dipecahkan dengan metode rasional yang sudahbarang tentu mengandalkan proposisi-proposisi aksiomatis.Dengan demikian, sekali lagi, jelas tidak mungkin untuk secaraserampangan mencampur adukkan jangkauan metode rasionaldengan metode empiris, serta mencoba menegakkan keunggu-lan metode empiris atas metode rasional; demikiann pula seba-liknya.
AKAL ATAU INDERA
Peran akal dan penginderaan dalam ide seolah telah men-jadi persoalan perennial filsafat. Descartes, misalnya, begitupercaya bahwa akal mampu mencerap sederet konsep tanpabantuan penginderaan, bahkan dia yakin bahwa dalam kai-tannya dengan konsep Tuhan dan jiwa dari hal-hal immaterial,juga tentang konsep lebar dan bentuk dari hal-hal material da-pat dicerap oleh akal; meski tidak secara langsung. Desacartesmenyebut berbagai kualitas yang tidak langsung dicerap olehpenginderaan ini dengan nama “kualitas primer”. Sebaliknya,
40 | Win Usuluddin Bernadien
dia menyebut “kualitas sekunder” untuk kualitas yang langsungbisa dicerap oleh penginderaan, misalnya warna, bau, dan ra-sa.42 Tegasnya, Desacartes meyakini sisi keunggulan akal se-raya meyakini bahwa pencerapan kualitas-kualitas sekunderyang diperoleh melalui pancaindera cenderung keliru dan tidakdapat diandalkan. Berbeda dengan Descartes, Jhon Locke ber-sikukuh bahwa benak dan pikiran manusia tercipta dalam lak-sana papan kosong yang tak tergores sedikitpun. Persentuhandengan berbagai ragam wujud luar melalui panca inderalahyang menyebabkan kemunculan berbagai citra dan goresanpadanya; dengan cara inilah persepsi itu terjadi. Locke yakinbahwa sejatinya segala yang berada dalam akal telah terlebihdahulu berada dalam penginderaan. Hal ini berarti bahwakonsep-konsep mental adalah bentuk-bentuk inderawi yangtelah terolah; seluruh pencerapan indrawi diubah dan dialihbentuk oleh akal menjadi cerapan intelektual persis seperti un-dagi mengolah balok kayu menjadi meja, kursi, pintu dan jen-dela. Jelasnya, persepsi-persepsi inderawi merupakan landasandan modal bagi persepsi-persepsi intelektual meski hal ini tidakberarti bahwa bentuk-bentuk inderawinya telah betul-betul di-olah dan diubah menjadi konsep-konsep intelektual. Lockepun kemudian mengakui keberadaan pengalaman-pengalam-an batin.
Dalam pada itu dengan pandangan yang sedikit berbedaBerkeley berpendapat bahwa terbatasnya pengalaman-penga-laman manusia pada pengalaman batin, lantaran dia menafi-kan keberadaan benda-benda material, karena itu pengalamaninderawi tidaklah mungkin berlangsung. Hal itu berarti bahwatidak selamanya kaum empirisistik menolak pengalaman batin,
42Protasius Hardono Hadi telah banyak menguraikan hal ini dalamBab IV, op. cit., hlm. 57-78.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 41
dan hal itu berarti pula bahwa kaum empirisistik berada padapersimpangan: meragukan perkara yang tidak bisa langsungdialamai secara inderawi, tetapi juga tidak menyangkalnya.
Untuk lebih memperjelas peran indera dan akal dalamide, dapat kiranya diungkap kembali gambaran berikut.43 Tat-kala seseorang melihat-lihat pemandangan indah sebuah ta-man, beragam warna bunga dan daun akan menarik perha-tiannya. Berbagai ragam kesan akan terbanyang dalam benak-nya. Begitu seseorang itu memejamkan mata, gebyar warna-warni yang menawan dalam taman itu pun akan menghilangdari pandangannya. Persepsi inderawinya pun lenyak seiringputusnya hubungan indera penglihatannya dengan dunia luar.Namun demikian, dia masih saja tetap bisa membayangkanbunga-bunga yang serupa dan mengingat pemandangan in-dahnya dalam dalam benaknya; inilah apa yang disebut den-gan persepsi imajiner. Arti penting persepsi imajiner adalahkemampuannya untuk menghubungkan alam nyata dengantataran ide dan abstraksi. Hal ini sebagaimana dapat dipahamibahwa imajinasi merupakan daya kreatif yang memudahkanseseorang untuk menyaring beraneka ide dari alam nyata danmenerapkannya pada pengalaman.44
Di samping bentuk-bentuk inderawi dan imajiner, manu-sia juga mencerap serangkaian konsep universal yang tidakmemerikan hal-hal spesifik, seperti konsep tentang warna me-rah, kuning, hijau, dan sebagainya. Demikian halnya dengankonsep warna yang tidak dapat diterapkan pada berbagai co-
43Selengkapnya dapat dibaca dalam M.T. Mishbah Yazdi, PeranAkal dan Pengindraan dalam Ide, diindonesiakan oleh Musa Kazhim danSaleh Bagir, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 131-134.
44Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah PendekatanTematis, diindonesiakan oleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir, Bandung:Mizan, 2003, hlm. 78-79.
42 | Win Usuluddin Bernadien
rak yang berbeda dan bahkan berlawanan. Konsep ini tidakbisa dianggap sebagaimana bentuk samar dan pudar dari salahsatu konsep warna tersebut di atas. Jelasnya, bilamana seseo-rang tidak pernah melihat warna dedaunan atau benda ber-warna lain maka seseorang itu tidak akan pernah mampumenganggit bentuk-bentuk imajiner maupun intelektual. Wal-hasil, seseorang yang tidak berindera penglihatan atau berinde-ra penglihatan tetapi tidak normal maka seseorang itu tentutidak bisa membayangkan indahnya warna-warni bunga, de-mikian juga seseorang yang tidak berindera pendengaran atauberindera pendengaran tetapi tidak normal tentu seseorangtersebut tidak bisa menciptakan image tentang merdunya suaramusik. Ringkasnya, siapa saja yang tidak memiliki salah satuinderanya maka akan kehilangan salah satu pengetahuannya,dan hal itu berarti dia tidak akan pernah memiliki satu jeniskonsep dan kesadaran.
Memang tidak dapat disangkal, kemunculan jenis konsepuniversal itu bergantung pada berlangsungnya persepsi-per-sepsi partikular namun demikian hal itu bukan berarti bahwapersepsi inderawi teralih-bentuk menjadi persepsi intelektualsebagaimana sebalok kayu menjadi meja-kursi, atau materimenjadi energi, atau satu macam energi menjadi energi yanglain. Karena, alih-bentuk semacam itu menuntut perubahanpada keadaan semula benda yang berubah, padahal persepsi-persepsi inderawi tetap seperti sedia kala setelah muncul kon-sep-konsep intelektual. Terlebih, sesungguhnya peralihan ben-tuk itu pada dasarnya bersifat material sedangkan persepsimutlak bersifat abstrak. Oleh karena itu, peran indera dalampenciptaan konsep universal hanya sebatas landasan dan sya-rat pendukung, bukan syarat mutlak.
Ada konsep lain yang tidak berhubungan dengan benda-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 43
benda terinderai (sensible thing) tetapi dapat dicerap oleh pen-galaman batin, misalnya saja takut, benci, cinta, nikmat, sakit.Konsep-konsep tersebut hanya mungkin dapat dicerap denganperasaan-perasaan batin. Dengan kata lain, kalau seseorangtidak memiliki perasaan-perasaan batin, tentu dia tidak akanbisa mencerap konsep-konsep universal dari berbagai keadaanjiwa termaksud. Seorang anak kecil misalnya, tidak mungkinmampu memahami bentuk-bentuk kenikmatan tertentu sampainanti ia beranjak dewasa. Karena itulah, meskipun konsep-konsep termaksud memerlukan persepsi individual pendahu-luan, tetapi tidak memerlukan sarana-sarana inderawi. Dengankata lain, pengalaman inderawi tidak berperan apa-apa dalammemperoleh konsep-konsep sebagaimana tersebut diatas. Pa-da gilirannya, persepsi inderawi tidak memainkan peran apa-apa dalam pembentukan konsep-konsep seperti kebutuhan,kemandirian, kewaspadaan, sebab, dan akibat. Hal ini karenakonsep-konsep tersebut tidak berawal dengan pencerapan in-derawi atas contoh individual eksternalnya. Pengetahuan den-gan kehadiran dan pengalaman batin terhadap setiap konseptidak cukup mengabstraksikannya. Pembandingan tiap-tiapkonsep diperlukan dalam rangka mengabstraksikan konsep-konsep tersebut. Oleh karena itulah, konsep-konsep tersebutdikatakan tidak memiliki padanan objektif walaupun penyifa-tannya bersifat eksternal. Akhirnya, dapat digarisbawahi bahwasetiap konsep intelektual menuntut persepsi individual sebe-lumnya, persepsilah yang melapangkan jalan bagi pengab-straksian konsep tertentu. Dan persepsi ini adakalanya berupapersepsi inderawi adakalanya berupa pengetahuan dengankehadiran dan penyaksian batin (inner intution). Dengan de-mikian, penginderaan memiliki peran sebagai penyedia landa-san bagi pembentukan konsep-konsep universal, sedangkan
44 | Win Usuluddin Bernadien
akal memainkan peran utama dalam pembentukan konsep-konsep universal.
SEGITIGA SUMBER PENGETAHUAN
Tidak dapat dipungkiri bahwa akal dan indera senyatanyamemiliki peran yang tidak sama bagi pengetahuan manusia,nyatanya pula akal dan indera tidak bisa saling menafikan,dua-duanya bisa berperan sebagai sumber pengetahuan. Se-lanjutnya, ada baiknya diungkapkan pada bagian ini satu lagisumber pengetahuan yang belum diungkap secara eksplisit pa-da bagian sebelumnya, yaitu: hati, sehingga dapat disebutkanbahwa sesungguhnya ada tiga sumber pengetahuan bagi ma-nusia, yaitu: indera, akal, dan hati. Memang bila diperluas, se-jatinya sumber-sumber pengetahuan itu tidak hanya indera,akal, dan hati. Ada yang lain, yang bisa disebutkan sebagaisumber pengetahuan, yaitu: commonsense, testimoni, otoritas,dan juga wahyu. Namun demikian, semua itu tidak menemu-kan urgensinya bilamana indera, akal, dan hati tidak mengam-bil peran.
Pertama, Indera. Bagi empirisisme, indera tidak hanyadiyakini sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan tetapilebih dari itu indera telah ditahbiskan sebagai satu-satunyasumber pengatahuan. Empirisisme meyakini hanya melaluiindera sajalah manusia bisa mengenal dunia sekelilingnya. Me-lalui mata manusia bisa mengetahui bentuk dan karakteristiksegala benda yang ada di dunia, melalui telinganya manusiabisa mendengar suara dan padu padan alunan nada-nada,melalui lidahnya manusia bisa mengecap dan merasakan ma-nis, asin, masam, pahit dan sebagainya, melalui hidungnyamanusia bisa mencium bau busuk dan aroma wangi parfum,begitu seterusnya sehingga panas, dingin, lunak, keras, kasar,halus dan sebagainya pun dapat dicerap dengan indera pera-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 45
banya. Jelasnya, selain sebagai sumber pengetahuan inderajuga berfungsi sebagai instrumen yang dimiliki manusia untukberadaptasi dengan lingkungan sekaligus sebagai alat kelang-sungan dan pertahanan hidup bagi manusia. Mata, hidung,telinga, lidah, dan juga indera peraba yang dimiliki manusiasemuanya bisa berfungsi sebagai instrumen yang penting bagistrugle for life sehingga bisa tetap survive. Namun demikianbeberapa pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah in-dera telah cukup memenuhi kebutuhan manusia akan ilmusebagai pengetahuan sebagaimana adanya? Apakah setiapkesan inderawi yang ditangkap manusia dilaporkan sama per-sis dengan kenyataan dan keadaan benda itu sebagaimanaadanya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut sudahpasti: tidak, kesan-kesan inderawi itu senyatanya tidak selalusesuai dengan keadaan benda-benda sebagaimana adanya.Warna biru pada langit, atau bentuk langit yang seperti kubah,atau bulan yang nampak pipih, atau pensil yang nampak ber-kelok saat dimasukkan gelas berisi penuh air, misalnya, ternya-ta tidaklah demikian adanya. Kekeliruan serupa juga bisa di-alami oleh indera pendengar tatkala menangkap suara dentu-man dari jarak jauh.45Ternyata “diam-diam” akallah yang bisa
45Terinspirasi dari kelakar Pak Don, sapaan akrab Dr. ProtasiusHardono Hadi, tatkala menceriterakan seorang kakek yang bergumamsaat melihat kilatan cahaya petir berulang-ulang tetapi tidak mendengardengan jelas suaru guntur, sang kakek pun bergumam: “apa dunia saka-rang ini sudah mau kiamat ya, kok suara bledeg-nya sekarang tidak lagijemblegur (menggelegar)”, padahal ternyata indera dengar sang kakekyang sudah tak lagi normal, bukan semakin melemahnya suara petir.Terlepas dari kelakar tersebut, menurut para ahli, pada diri manusiapendengaran terjadi tatkala getaran frekwensi yang berkisar dari 15 Hzhingga 20.000 Hz akan mencapai bagian dalam telinga. Inilah yang dis-ebut dengan frekwensi audio. Gelombang suara yang melebihi rentangtersebut disebut ultrasonik, dan yang kurang dari itu disebut infrasonik.
46 | Win Usuluddin Bernadien
menjawab persoalan-persoalan tersebut. Akallah yang akanmelaporkan bahwa langit tidak bisa didefinisikan warna danbentuk aslinya, akal pula yang melaporkan bahwa telah terjadipembiasan pada pensil dalam gelas yang penuh air itu, danakal juga yang bisa melakukan penghitungan atas kecepatanrambat bunyi.46 Dari sini dapatlah kiranya disadari betapa pan-caindera sejatinya tidak mencukupi untuk mengetahui sesuatusebagaimana adanya.
Pancaindera, memang bisa saja tidak mencukupi untukmengetahui sesuatu sebagaimana adanya. Namun demikianada hal lain yang bisa dijelaskan bahwa dalam diri manusiaada kecakapan mental yang secara efektif mampu melakukanoptimalisasi bagi kinerja indera lahir, yaitu apa yang disebutsebagai indera batin.
Ibnu Sina (370-428 H/910-1037 M) yang di Barat dikenaldengan nama Avicenna,47 menyebut lima indera batin yang di-miliki oleh manusia. Pertama: yaitu, apa yang oleh Ibnu Sinadisebut sebagai al-ẖiss al-musytarak (indera bersama) atauyang di Barat disebut sebagai commonsense. Mata, hidung,telinga, kulit, dan lidah memang bekerja hanya secara individ-ual dan parsial tetapi nyatanya manusia bisa menangkap ber-bagai ragam kesan inderawi yang dilaporkan oleh pancainderatersebut secara sintesis dan utuh, maka al-ẖiss al-musytarak-lahyang mengantarkan objek inderawi muncul sebagai kesatuanutuh dengan segala dimensinya dan tidak lagi parsial oleh mas-ing-masing indera lahir, karena memang senyatanya tak satupun dari instrumenn inderawi yang dapat bekerja secara me-
46 Dalam ilmu fisika terungkap bahwa kecepatan rambat bunyi me-lalui udara adalah 1.190 km/jam.
47 Peter Heath, Allegory and Philosophy in Avicenna, Philadelphia:University of Pennsylvania Press, 1992, p. 62-63.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 47
nyatu apalagi berkoordinasi ataupun bersintesis, semua instru-men inderawi tersebut bekerja secara individual dan parsial.Kedua: al-khayàl atau daya imajinasi retentif (retentive imagin-ative faculty) yang berfungsi sebagai alat perekam bagi setiapobjek yang ditangkap oleh indera lahir. Al-khayàl inilah yangakan melestarikan setiap memori sehingga manusia selalumemiliki ingatan atas datum-datum yang ditangkap oleh inderalahirnya. Ketiga: Mutakhayyilah (compositive imaginative facul-ty) yaitu daya imajinasi yang dapat menangkap bentuk(shûrah) secara komprehensif. Daya ini dapat mengabstraksi-kan beragam bentuk dari bendanya bahkan menggabungkanberagam bentuk itu sesuai selera yang dikehendaki. Gatutkaca,Sphinx, Pegasus, juga Unicorn48 dapat dijadikan contoh betapasesungguhnya manusia itu memang memiliki daya mutak-hayyilah. Keempat: Wahm atau daya estimasi (estimative facul-ty). Dengan daya estimasinya manusia mampu menangkapmaksud yang tersembunyi di balik benda. Dengan daya inimanusia bisa menilai apakah benda tersebut bermanfaat atauberbahaya sehingga bisa mengambil tindakan yang diperlukanbagi kelangsungan hidupnya. Arti penting wahm ini terutamauntuk tujuan praktis bagi kehidupan manusia, misalnya ketikawahm menyimpulkan bahwa api itu panas maka manusia punlalu mengambil tindakan yang diperlukan, mungkin menjauhiagar tidak terbakar atau mungkin justru dimanfaatkan untukmemanggang makanan. Atau pada saat manusia menyadari
48Gatutkaca adalah tokoh yang bisa terbang dalam cerita pe-wayangan Jawa, dia adalah anak Wrekudara. Sphinx adalah karya senipatung berbentuk manusia tetapi berkepala singa, di Mesir. Pegasus ada-lah kuda jantan bersayap yang bisa terbang, dalam mitos Yunani. Un-icorn adalah kuda bertanduk satu yang terdapat di dahinya, dalam ceri-ta rakyat di Eropa (pen.).
48 | Win Usuluddin Bernadien
bahwa tubuh membutuhkan nutrisi maka wahm mendoronguntuk menyantap makanan dan minuman, sehingga manusiabisa bertahan hidup. Kelima: al-ẖâfizhah (memori). Citra yangmuncul dalam al-ẖiss al-musytarak, demikian juga bentuk-bentuk imajiner dalam mutakhayyilah tidak dapat direkam tan-pa peran al-khayàl. Seluruh rekaman yang dilakukan oleh al-khayàl ini kemudian tersimpan di dalam quwwat al-ẖâfizhah,dan berfungsi sebagai alat pelestari bagi bentuk-bentuk imajin-er rekaman al-khayàl dan bentuk-bentuk fisik yang ditangkapoleh al-ẖiss al-musytarak. Memori (al-ẖâfizhah) inilah yang me-nyebabkan manusia bisa mengingat tidak saja bentuk-bentukfisik tetapi juga bentuk-bentuk abstrak. Memori merupakan in-dera batin terakhir dalam sistem yang dibangun oleh Ibnu Si-na.
Kedua, Akal. Filsafat membagi akal menjadi dua, yaitu:akal teoretis yang berkaitan dengan sumber pengetahuan danakal praktis yang berkaitan dengan tindakan (etika). Bagian iniakan difokuskan pada akal sebagai sumber pengetahuan. Se-bagaimana telah diungkapkan di atas bahwa dapat menyem-purkan cerapan indera dan memperbaiki kekeliruan kesanyang diterima oleh indera. Hal ini berarti akal dapat melaku-kan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh indera, baik inderalahir maupun indera batin. Bila mata bisa melihat, hidung bisamembau, dan lidah bisa mengecap maka akal bisa bertanyamengapa dan bagaimana semua itu bisa terjadi, bahkan bisabertanya apa dan dimana mata, hidung, dan lidah itu. Akaltidak hanya mampu bertanya tentang apa, dimana, kapan,mengapa, bagaimana, dan siapa tetapi ternyata akal jugamampu berperan sebagai pemasok informasi yang luar biasadengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Halini semua bisa terjadi karena akal memiliki konstruksi mental
Serpihan-Serpihan Filsafat | 49
atau perangkat yang bisa melakukan pengkategorian-pengka-tegorian atas apa yang diterima dari indera, bahkan akal bisamenangkap esensi dari sesuatu yang diamati. Dengan kemam-puan ini, akal manusia dapat mengetahui konsep universal dariobjek yang diamati lewat indera yang bersifat abstrak dan tidaklagi berhubungan dengan data partikular. Tatkala seseorangmemahami “esensi” manusia, sebenarnya seseorang itu bukanlagi berbicara tentang manusia partikular “polan” atau “po-han” melainkan berbicara tentang manusia secara universal.Tatkala manusia berbicara tentang meja, maka sesungguhnyadia bukan lagi berbicara tentang bentuk meja yang persegi,yang bulat, atau yang oval melainkan bicara tentang esensimeja yang meliputi semua meja partikular. Dengan kemam-puan menangkap esensi dari benda-benda dan bentuk-bentukyang diamati ini, manusia dengan akalnya mampu menyimpanmakna tentang berbagai objek ilmu yang bersifat abstrak se-hingga tidak perlu ruang fisik yang luas dalam pikirannya.Ringkasnya, akal memiliki kemampuan dan fungsi yang sangaturgen bagi manusia, yakni: sebagai sumber pengetahuan. Na-mun demikian Ibnu Sina, Rûmî, Blaise Pascal, dan Henri Berg-son masih saja melihat “kelemahan” akal yang telah melebihikemampuan indera tersebut. Akal memang sangat kompetenuntuk memahami pengalaman fenomenal tetapi akal tidak cu-kup daya untuk memahami pengalaman eksistensial.49 IbnuSina, dalam kaitan ini menyatakan bahwa akal memang sangatpantas diagungkan tetapi masih harus tetap diakui bahwa adadaya yang lebih kuat dari pada akal, yaitu al-ẖad al quds (intui-si suci). Al-ẖad al quds inilah yang merupakan daya linuwih
49Mulyadi Kartanegara, Menyibak Tirai Kejahilan, Pengantar Epis-temologi Islam, Bandung: Mizan, 2003, hlm. 25-29.
50 | Win Usuluddin Bernadien
yang digunakan oleh para nabi saat menerima wahyu dari Tu-han. Sejalan dengan Ibnu Sina, Blaise Pascal pun mengung-kapkan bahwa di tengah-tengah jagat raya ini manusia bukan-lah “apa-apa” namun demikian manusia adalah satu-satunyamakhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, secara in-duktif. Akal dapat memberi pengetahuan tetapi tidak dapatmerumuskan pengertian. Karena itu harus dibantu dengan ha-ti. Hati letaknya lebih dalam daripada akal, yang di dalamnyamanusia “berhadapan” dengan Tuhan, dan merupakan “tem-pat” manusia “berdialog” dengan-Nya.
Hal serupa diungkapkan oleh Rûmî, yang meyakini bah-wa akal mampu saja menguasai seribu cabang ilmu tetapi ten-tang hidupnya sendiri, akal tidak tahu apa-apa. Sebagai sumb-er pengetahuan, akal tidak perlu disangsikan lagi tetapi akalsering tidak berdaya tatkala berhadapan dengan sisi emosionalmanusia. Tatkala cinta berlabuh, misalnya, akal tidak mampuberkata apa-apa, pikiran bagai labirin buntu dan lidah pun te-rasa kelu. Akal ternyata tidak mengerti banyak tentang penga-laman eksistensial, yakni pengalaman yang langsung dirasakanoleh manusia. Hanya hati (intuisi) yang bisa melakukannya.Akal memang mampu melakukan spatilize terhadap apapunyang menjadi objeknya tetapi hal ini dilakukan secara generaldan homogen, akibatnya keunikan masing-masing objek akanterabaikan. Akal tidak bisa menjelaskan apresiasi estetis yangdiberikan seniman saat senja hari mentari kembali kepera-duannya.50 Akal pun bagai kehilangan daya saat seseorangmenangis dalam doanya. Ringkasnya, bagi Rûmî dan jugaBergson akal tidak mampu memahami setiap objek penelitian-nya secara langsung karena akal tidak pernah secara langsung
50Inspirasi yang lebih luas dapat dibaca karya P. Hardono Hadi,Op. cit., terutama bab V, hlm. 79-92
Serpihan-Serpihan Filsafat | 51
menyentuhnya, akal hanya menangkap simbol-simbolnya. Halini berarti bahwa pengenalan akal terhadap objeknya adalahpengenalan yang bersifat simbolis, yakni melalui kata-kata te-tapi kata-kata saja tidak akan pernah memberi pengetahuanyang sejati sebagaimana adanya tentang objek yang diama-tinya itu. Secara ironis, Rûmî bertanya: “Dapatkah Anda me-nyunting sekumtum mawar dari M.A.W.A.R? Tidak, Anda barumenyebut nama, cari yang empunya nama”.51
Ketiga, Hati. Tatkala akal tidak mampu memahami ke-hidupan emosional manusia, maka hati kemudian mengambilperannya. Tatkala akal hanya berkutat pada area kesadaranmaka hati mampu menyusup ke area ketidaksadaran, atauarea keghaiban dalam istilah agama atau oleh Wittgenstein di-sebut sebagai yang mistik,52 sehingga mampu memahami ber-bagai ragam pengalaman non-inderawi bahkan berkomunikasidan berdialog dengan yang Maha Ghaib, yaitu: Tuhan, demi-kian menurut Pascal.
Hati bisa memilah dan memilih objek sehingga manusiaterhindar dari generalisasi dan spasialisasi rasionalistik, dan ka-renanya hati mampu menangkap dan menghayati keunikandari setiap objek yang dihadapi maupun peristiwa yang diala-minya secara istimewa dan partikular. Hati pulalah yang me-
51Nicholson, The Mathnawi of Jalal Al-Din Rûmî, 1st edision, Lon-don: Luzac&Co. Ltd., 1997, p. 188, sebagaimana juga telah dikutip olehMulyadi Kartanegara, dalam salah satu karyanya. Hal serupa juga diung-kapkan oleh Ludwig Wittgenstein dalam karya Investigation. Baginya,sebuah kata hanya akan menemukan maknanya dalam kehidupan, bu-kan dalam tulisan belaka.
52Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, London:Routledge & Kegan Paul Ltd., 1951, p. 187. Dalam versi bahasa Inggrispada aphorisma 6.522 Wittgenstein menyatakan: ”There is indeed theinexpressible. This shows itself; it is the mystical”.
52 | Win Usuluddin Bernadien
nyebabkan seorang ibu berteriak histeris saat menyaksikanbayinya akan dibelah oleh Nabi Sulaiman, dan merelakanbayinya itu diberikan kepada wanita yang lainnya asal tidakdibelah bayinya. Hanya hatilah yang bisa mengatakan bahwaanak-anak biologis “kita” itu lucu dan menggemaskan sehinggarindu “kita” selalu mengundang untuk bercanda serta berbagitawa dengan mereka. Dan hanya hati sajalah yang bisa men-gungkapkan bahwa Tuhan, malaikat, bidadari, surga bahkanneraka itu benar-benar ada; bukan indera sensasional juga bu-kan akal rasional.
Ada satu lagi yang dapat dijelaskan mengenai hati, bahwasejatinya hati memiliki kemampuan untuk mengenal objek se-cara intim dan langsung. Dari sini dapat dijelaskan bahwa pen-getahuan intuitif adalah pengetahuan eksperiensial, yaitu: pen-getahuan yang didasarkan pada pengalaman. Manusia “rindu”bukan karena telah menemukan R.I.N.D.U dengan indera sen-sionalnya tetapi karena menemukan dan merasakan kehadiranrindu dalam hatinya. Demikian juga dengan cinta. Manusiamengerti cinta bukan karena telah membaca teori tentang cintatetapi karena hati memahami dengan sungguh-sungguh men-galami cinta. Akal tidak pernah mengerti “mengapa dua jan-tung berdetak satu, sehingga meskipun jauh dimata tetapi de-kat di hati”. Akal tidak akan pernah bisa menjelaskan indahnyacinta, karena sejatinya cinta itu adalah situasi pressensial yangdisebabkan objeknya sungguh-sungguh hadir secara intim da-lam diri sehingga tak ada lagi jarak yang membentang antarasubjek yang mencinta dan objek yang dicinta. Itulah sebabnyamengapa Tuhan terasa selalu hadir dan intim bahkan dihayatitelah “manunggal” di setiap insan yang sungguh-sungguh be-riman. Manusia yang sungguh-sungguh beriman pun akan se-lalu menyatakan hidup dalam rengkuh kasih Tuhan.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 53
Begitulah indera, akal, dan hati bagaikan segitiga emas,yang tiga-tiganya telah menjadi sumber pengetahuan bagi ma-nusia sesuai karakter dan peran masing-masing. Pengetahuaninderawi, pengetahuan akali, dan pengetahuan hati semuanyamemiliki peran dan karakter yang tidak sama, tetapi tiga-tigatelah sama-sama meneguhkan manusia menjadi ciptaan Tu-han yang paling sempurna.[*]
BACAAN PENDUKUNG
Descartes, Renê, 2012, Diskursus & Metode, diindonesiakanoleh Ahmad Faridl Ma’ruf, Yogyakarta: IRCisoD.
Ha’iri Yazdi, Mehdi, 2003, Epistemologi Iluminasionis dalamFilsafat Islam, Menghadirkan Cahaya Tuhan, diindone-siakan oleh Ahsin Muhammad, Bandung: Mizan.
Heath, Peter, 1992, Allegory and Philosophy in Ibnu Sina, Phi-ladelphia: University of Pennsylvania Press.
Leaman, Oliver, 2003, Pengantar Filsafat Islam: Sebuah Pen-dekatan Tematis, diindonesiakan oleh Musa Kazhim danSaleh Bagir, Bandung: Mizan.
Loren Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
Mishbah Yazdi, M.T. 2003, Peran Akal dan Pengindraan dalamIde, diindonesiakan oleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir,Bandung: Mizan.
Mishbah Yazdi, M.T., 2003, Buku Daras Filsafat Islam, diindo-nesiakan oleh Musa Kazhim dan Saleh Bagir, Bandung:Mizan.
Mulyadi Kartanegara, 2003, Menyibak Tirai Kejahilan: Pengan-tar Epistemologi Islam, Bandung: Mizan.
Nicholson, 1997, The Mathnawi of Jalal Al-Din Rûmî, 1st edi-sion, London: Luzac&Co. Ltd.
54 | Win Usuluddin Bernadien
P. Hardono Hadi, 1994, Epistemologi: Filsafat Pengetahuan,Yogyakarta: Kanisius.
P. Hardono Hadi, dalam Aholiab Watloly, 2001, Tanggungja-wab Pengetahuan, Yogyakarta: Kanisius.
Solomon, Robert, C,. 11981, Introducing Philosophy, NewYork: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Sudarminta, J., 2002, Epistemologi Dasar, Yogyakarta: Kani-sius.
Wittgenstein, Ludwig, 1951, Tractatus Logico-Philosophicus,London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 55
BAGIAN KEEMPAT
PEMIKIRAN IBNU SINATENTANG ALAM DAN JIWA
PENGANTAR
Filsafat alam yang penulis maksud dalam tulisan ini meru-pakan filsafat alam dalam pemikir Islam abad pertengahan,khususnya Ibnu Sina, yang secara terang-terangan terrefleksi-kan dan tertuang secara sistematis dalam bahasa teologis danmistis tentang jagad raya. Kemudian, dalam rangka usahamemahami dan menggaris bawahi pandangan Ibnu Sina, ma-ka terlebih dahulu penulis mengetengahkan bagaimana alamdapat dipahami menurut Al Quran, setelah itu riwayat singkatdan karya-karya Ibnu Sina, baru kemudian pandangan IbnuSina tentang alam dan jiwa, dan sebagai penutup perlu kiranyapenulis ketengahkan sekilas hubungan antara filsafat dengansusunan ilmu agama Islam.
RIWAYAT SINGKAT DAN KARYA TULISNYA
Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu ’Ali Huseyn bin
56 | Win Usuluddin Bernadien
‘Abdullah bin Hasan bin ‘Ali bin Siena. Dengan merujuk padabahasa Latin, di Barat dikenal dengan nama Avicenna, dandalam bahasa Hebrew (Ibrani) Aven Siena. Lahir pada bulanShafar 370 H atau bulan Agustus 910 M, di desa Afshanah,wilayah Belkh (Afghanistan) propinsi Bukhara (Rusia). Tidaksatupun catatan yang menunjukkan hari dan tanggal kecualibulan dan tahun kelahirannya saja, demikian pula mangkatnyakecuali tertulis Hamadan bulan Ramadlan 428 H/1037 M.53
Ibnu Sina merupakan seorang tokoh filosof sains Islamyang terkenal dan berpengaruh. Ia adalah ’Sang Maestro ‘yangtak tertandingi dalam bidang filsafat, sains, fisika, dan kedokte-ran. Dua buku karya Ibnu Sina yang terkenal adalah The Bookof Healing dan The Canon of Medicine. Karya pertama meru-pakan ensiklopedia saintifik yang mencakup logika, sains alam,psikologi, geometri, astronomi, aritmetika, dam musik. Karyayang kedua merupakan buku yang memuat segala hal ihwalkedokteran yang hingga saat ini masih bertahan sebagai bukuacuan kedokteran.
Sepeninggal ayahnya, kehidupan Ibnu Sina berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain di Khorasan.Pada siang hari ia bekerja sebagai dokter dan petugas admini-strasi sedangkan pada malamnya digunakan untuk mengajarfilsafat dan sains. Setelah masa berpindah-pindah itu berlalu,Ibnu Sina pergi ke Hamadan di Iran-Barat Tengah dan mene-tap di sana untuk bekerja sebagai dokter sebuah pengadilan.
53Seyyed Hossein Nasr, 1978, An Introduction to Islamic Cosmo-logical Doctrin, Colorado: Shambhala Boulder, hlm. 180, dan beberapasumber yang lain, diantaranya: Simon Blackburn, 2008, The OxfordDictionary of Philosophy, Oxford: Oxford University Press, diindonesia-kan oleh Yudi Santoso, 2013, Kamus Filsafat, Yogyakarta: Pustaka Pe-lajar, hlm. 474-475, serta dari bacaan-bacaan pendukung sebagaimanayang disebutkan dalam bagian akhir tulisan ini.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 57
Situasi politik agaknya tidak menguntungkan sehingga terpaksaia bersembunyi bahkan sempat menjadi tahan politik untuk be-berapa waktu. Setelah keluar dari penjara (pada tahun 1022),ia memutuskan untuk meninggalkan Hamadan menuju Isfa-han. Di Isfahan, ia merampungkan pekerjaannya yang telah di-mulai di Hamadan dan juga menulis banyak buku tentang fil-safat, kedokteran, dan bahasa Arab. Bukunya yang berjudulAsy Syifa (Sufficientia) atau dikenal dengan Kitab al Syifa, di-pandang sebagai ensiklopedia ilmiah terpanjang yang pernahditulis oleh seorang pengarang. Buku ini memaparkan secaratuntas mengenai pengetahuan tentang hewan, tumbuhan, geo-logi, dan psikologi. Khusus dalam bidang kedokteran ia menu-lis buku yang berjudul al Qānūn (Kitab Al Qānūn fl al Thibb).54
Buku ini banyak mengulas tentang sejarah kedokteran dan ma-sih dipelajari hingga sekarang. Buku lain yang ia tulis adalah AlArjuzah. Buku ini berisi bait-bait syair bersajak yang memapar-kan dasar-dasar kedokteran. Di samping itu ia juga menulissejumlah lagu dan nyanyian (Qashidah) dalam bahasa Arabdan Persia.
MEMAHAMI ALAM MELALUI AL QUR’AN
Dalam rangka memahami pandangan para pemikir Islam,tak terkecuali Ibnu Sina, unsur pertama yang akan kita temuidalam filsafat alam adalah kitab sucinya, yaitu Al Qur’an. Halini tentu saja dengan mudah dapat dimengerti,sebab Al Qur’anmerupakan kitab suci yang secara jelas memuat sederetan per-nyataan asasiah mengenai Allah, alam, dan manusia. Misalnyasaja dalam surat Al Fatihah ayat 1, jelas dinyatakan bahwa Al-
54Kata al Qānūn dalam bahasa Arab diambil dari bahasa Yunani:Kanōn yang artinya seperangkat aturan (a set of principles), op.cit., hlm.178.
58 | Win Usuluddin Bernadien
lah adalah لمیـــن ــا العـ رب (Tuhan seru sekalian alam). Kekua-saan-Nya tidak mengenal batas, sebagaimana tertuang dalamAl Qur’an surat Al Baqarah ayat 283:
وهللا على كّل شئ قدیرKuasa ciptaan-Nya menyatakan diri dalam gejala-gejala
kehidupan, dalam alam semesta, Allah berfirman sebagaimanadalam Al Qur‘an surat Al Waqi‘ah ayat 57:
نحن خلقناكم فلول التصدقونdan sebagaiman dalam Al Qur‘an surat Al Waqi‘ah ayat 72:
تم شجرتھآ ام نحن المنشـؤن انشــأءأنتم Al Qur‘an juga menyatakan bahwa sebelum penciptaan,
langit dan bumi merupakan gumpalan asap yang membentuksuatu massa yang terpadu lalu Allah memisahkan keduanyalalu diciptakan segala kehidupan ini dari air, atau dengan katalain, air adalah asas berawalnya segala kehidupan, sebagaia-mana firman dalam Al Qur‘an surat Ha Mim ayat 11 berikutini:
وھو د خان الّسـماءثم استـوآي الي dan dalam Al Qur‘an surat Al Anbiya ‘ayat 30, sebagaimanaberikut ini:اولم یراّلـذین كفروآ اّن الّسـموات واأل رض كانتا رتقاففتقنھماوجعلنا من
المآء كّل شیئ حّي yang diciptakannya dalam enam hari tanpa lelah dan henti se-bagaimana tertuang dalam Al Qur‘an surat Al A‘raf ayat 54:
اّن رّبـكم هللا الّذي خلق الّسـموت واألرض في سّتة اّیام Allah menurunkan air hujan dari langit lalu menjadikan
bumi hijau karena ditumbuhi segala jenis tumbuhan dan ta-naman, sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur’an surat Al
Serpihan-Serpihan Filsafat | 59
Hajj ayat 63, berikut ini:
اولم تر اّن هللا انزل من الّسـمآء مآء فتصبح اآلرض مختضـّرة اّن هللا لطیـف خبیر
Al Qur‘an juga menyatakan bahwa semua yang ada di ja-gad raya ini, tunduk menyembah kepada-Nya karena kekua-saan-Nya yang memang tak terbatas, sebagaimana dalam AlQuran Surat 22 ayat 18, berikut:
الم تر اّن هللا یسجد لھ من في الّسـموت واألرض والِشمـس والـقمر والنجوم والجبال والشجر والدوآب وكثیر من الـّناس وكثیر حق علیھ
ا یشآءالعذاب ومن یھن هللا فما لھ من مكرم اّن هللا یفعل مBintang gemintang diciptakan oleh Allah dan diberi-Nya
hukum tertentu agar menjadi petunjuk arah perjalanan manu-sia baik di daratan maupun di lautan pada gelapnya malam,sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur‘an surat Al An‘am ayat97 berikut ini:
الّـذي جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البر والبحروھوAllah juga memerintahkan bulan untuk memantulkan ca-
haya matahari serta menentukan fase-fasenya dan musim-musimnya (manazil al Qamar) agar manusia mengetahui bi-langan tahun dan perhitungan hari, sebagaimana termaktubdalam Al Qur‘an surat Yunus ayat 5, berikut:
وقـّدره منازل لتعلموا عدد الّسـنین والحسـابLebih jauh, tentang planet Bumi yang dipahami sebagai
tempat tidur (firasy: permadani, buaian: mahd) dan dipermu-kaannya dipancangkan gunung-gunung dan dibentangkansungai, selengkapnya diciptakan oleh Tuhan dalam masa duahari. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur‘an surat HaMim ayat 9, sebagaimana berikut ini:
60 | Win Usuluddin Bernadien
خلق األرض في یومینDemikian juga Allah menciptakan tujuh langit, yang dicip-
takanNya dalam dua hari pula, sebagaimana firman Allah da-lam Al Qur‘an surat Ha Mim ayat 12, Al Mu‘minun ayat 17,dan Al Naba ‘ayat 12, berikut ini:
فقضاھن سبع سمـوات في یومین
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرآئق
وبنینا فوقكم سبعاشـداداPenciptaan tidak boleh dipahami sebagai suatu tindakan
Allah yang telah usai dikerjakan-Nya selama enam hari, tetapipenciptaan harus dimengerti sebagai suatu pengakuan kedau-latan Allah dan kerahiman-Nya terhadap makhluk-makhluk-Nya. Manusia adalah puncak dari penciptaan, Allah berfirmansebagaimana dalam Al Qur‘an surat Al Tiin ayat 4, berikut:
لقد خلقنا اإلنسـان في احسـن تقویم Pada manusialah Allah memberikan kebaikan dan kera-
himan-Nya, sebagaimana tertuang dalam Al Qur‘an surat AlNahl ayat 7, berikut ini:
اّن رّبـكم لرؤوف رحیـمAlam dan segala isinya telah dipertaklukkan kepada ma-
nusia (musakhkhara laha) karena manusia memiliki peran se-bagai khalifatullah di bumi, yang karenanya justru manusia ha-rus mengakui dan menyembah Allah. Dalam perspektif antro-pologis, penciptaan Adam dan Hawa ditampilkan oleh Al Qu-ran secara detail, yang di kemudian hari menjadi inspirasi ataspenelitian struktur psikhis dan fisik manusia oleh para pemikirIslam, dengan bahasa simbolis, Al Qur‘an menjelaskan bahwa
Serpihan-Serpihan Filsafat | 61
manusia berasal dari Ruh-Nya sendiri (Wanafakha min rühihi)agar manusia mampu melaksanakan ke-khalifahan-nya, dankarenanya Allah memberi manusia penglihatan (‘ain) dan hati(Qalb wa Fuad). Satu hal yang mesti harus dipahami dalamkerangka moral bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yangpaling sempurna dan karenanya Allah perintahkan kepada pa-ra malaikat, juga Iblis meskipun ia tak mau, untuk bersujud ke-pada-Nya (Al Qur’an surat Thaha ayat 116), akan tetapi kare-na faktor lingkungan tempat dia hidup maka manusia menjadilemah namun juga sombong bahkan tidak sabar, sehingga ha-rus selalu memperjuangkan kelangsungan hidupnya secara te-rus menerus. Ini tentu dimaksudkan agar terangkat harkat danmartabatnya, mampu menguasi dirinya dan kembali kepadakeadaan kesempurnaan asalinya.
Jelasnya, secara implisit filsafat alam yang tertuang di da-lam kitab suci Al Qur’an adalah bersifat teosentris, dalam pen-gertian bahwa Allah Maha Sempurna dan transenden menjadipusat ciptaan dan segala penciptaan selalu berada dalam titikacuan dengan-Nya. Lebih dari itu hal lain yang dapat dilihat didalam Al Qu’ran adalah bahwa filsafat alam diarahkan padasuatu target dan pengertian konteks finalis. Alam diciptakan-Nya secara bijaksana dalam suatu keserasian yang seragamdan keteraturan hukum yang baku namun terbuka bagi kebe-basan ilahi. Filsafat alam pada sisi yang lain yang dapat dijum-pai di dalam Al Qur’an adalah aspek antroposentris, dalampengertian seluruh alam yang dicipta-Nya mengabdi kepadamanusia. Allah berfirman sebagaimana dalam Al Qur’an suratYaa Siin ayat 71 berikut ini:
اولم یروا اّنـا خلقنالھم ّمّما عملت ایدینآ انعاما فھم لھامالكونdan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Sebagai-mana dijelaskan di dalam Al Qur‘an surat Al Baqarah ayat 164,
62 | Win Usuluddin Bernadien
sebagaimana berikut ini:ھاروالفلك الّـتي ان في خلق الّسـموات واألرض واختالف اللّیل والّنـ
تجري في البحر بما ینفع الـّناس ومآ انزل هللا من الّسـمآء من مآء فأحیا بھ األرض بعد موتھا وبّث فیھا من كّل دآّبـة وتصریف الّریاح
والّسـحاب المسّخـربین الّسـمآءواألرض آلیة لقوم یعقلـونDan juga dalam surat Ali Imran ayat 26 berikut ini:
الّلھـم مالك الملك تؤتى الملك من تشـآء وتنزع الملك ممن تشـآء قل وتعّز من تشـآء وتذّل من تشـآء بیدك الخیراّنك على كّل شئ قدیر Jadi, seluruh ciptaanNya dipergunakan untuk menyusun
kosmologi yang sifatnya jelas religius. Wallahu a‘lam bi al-Shawaab.
TENTANG ALAM SEMESTA
Menurut Ibnu Sina, Tajalli (proses penciptaan, sebagai ke-jelasan tanda-tanda kekuasaan Allah) berhubungan langsungdengan fungsi dan perbuatan malaikat. Malaikat merupakanmakhluk (alat) yang bertugas (berfungsi) melaksanakan proseskejadian ini dengan perantaraannya. Malaikat juga melak-sanakan tugas penyelesaian pada setiap ilmu (kejadian) alamdan proses pelaksanaan dzat yang bersifat ruhani serta mempe-roleh ma’rifat. Ibnu Sina memotifisir proses timbulnya alam se-mesta dengan memanfaatkan prinsip yang menyatakan: YangEsa menimbulkan yang satu, حد الوا الواحدالیصــــــدرعنھإال dan pro-ses penciptaan itu terlaksana dengan cara pemikiran.
Proses penciptaan atau limpahan wujud dan proses pemi-kiran adalah sesuatu yang satu. Dengan perantaraan pemiki-ran, martabat-martabat yang hakikatnya tinggi dapat menim-bulkan martabat-martabat dunia (yang rendah) dalam bentukwujudnya. Berdasarkan prinsip ini maka Yang Esa, Yang MahaWajib Wujud-Nya adalah asal mula semua yang ada. Semua
Serpihan-Serpihan Filsafat | 63
berasal dari satu maujud. Dialah yang oleh Ibnu Sina dinama-kan Akal-Pertama yang dipandang sebagai ‘semulia-mulianyamalaikat’.Disini, akal memikirkan yang wajib, dengan apa yangdianggap wajib. Kemudian, hakikat materi yang dianggap wa-jib itu, dengan maujud yang wajib. Maka hakikat materi yangdianggap maujud mumkin, adalah dengan dzatnya. Demikian-lah, maka menurut Ibnu Sina ada tiga dimensi ma’rifat yangdarinya tumbuh Akal-Kedua, yang kemudian (dilanjutkan) olehjiwa-falak-pertama, lantas planet-falak-pertama, dan seterusnyasesuai urutannya. Akal-Kedua yang timbul pada sisi ini juga di-pikirkan oleh Akal-Pertama. Kemudian, lahirlah Akal-Ketiga,jiwa-falak-kedua, dan planetnya. Begitu seterusnya hingga muncul Akal-Kesepuluh dan falak-kesembilan, yang disebut denganfalak bulan. Di sini, tidak ada ketetapan pada jauhar (inti) alamsemesta, yang cukup memiliki kejernihan untuk timbulnya falaklain, alam semesta, dan kerusakan (lahiri) dari sisa-sisa ‘ke-mungkinan (terjadinya) alam semesta’.
Akal-Kesepuluh, terdapat pada alam di bawah bulan, ya-itu alam-perpindahan yang meliputi kehidupan dunia untukmanusia, yang menyediakan tugas-tugas asasi, yang tidak ha-nya memberi alam ini berupa wujudnya saja melainkan jugamenimbulkan secara berkelanjutan bentuk-bentuk yang penya-tuannya dengan materi mewujudkan makhluk-makhluk di dae-rah ini, yang juga merupakan bagian dari alam semesta. Makaketika makhluk terbentuk, Akal-Kesepuluh melimpahkan ben-tuknya yang lazim bagi kemungkinan wujudnya, dan ketikamakhluk layu dan mati dikembalikanlah bentuknya, oleh kare-na itu Ibnu Sina menamakanya ‘Pemberi bentuk-bentuk’ atauDatum Formarum الصـــور) جب -Misalnya: jika air telah mem .(الواbeku menjadi salju maka bentuk air itu sesungguhnya telahhilang karena ‘Pemberi bentuk’ telah mengembalikannya, yang
64 | Win Usuluddin Bernadien
kemudian dimasukanlah bentuk salju yang baru pada hiyulisebelumnya, yaitu air sehingga berubahlah menjadi salju.
Pengkajian Ibnu Sina tentang alam semesta dimotivasioleh kesadaran yang utuh akan perbedaan antara Penciptadan ciptaanNya. Ia berupaya mencari kejelasan bagaimanabisa tampak adanya yang banyak dan beragam di alam semes-ta, sementara pada saat yang sama Pencipta Yang Satu terbe-bas dari kejamakan ini. Untuk ini, ia mempelajari proses pen-ciptaan alam semesta dengan bertumpu pada prinsip filsafatyang mengatakan bahwa Yang Satu itu hanya menghasilkansatu pula. Dengan paradigma filosofis ini, ia kemudian meng-kaji alam semesta dengan berbagai fenomena di dalamnya.
Selanjutnya, pemikiran Ibnu Sina dapat dirumuskan bah-wa:
1. Apa saja yang ada terbagi secara langsung dan nyata da-lam ada yang kontingensi الوجـود) كن (المم dan yang ada ab-solut دالوجــو) (Necessary ,الواجـب yaitu ada yang tidak bisaada. Ada yang absolut pada gilirannya masih terbagi atasWajib al Wujud (Necessary Being, Allah) dan ada absoluteyang tergantung pada sesuatu yang lain الممكـن) جب .(الوا
2. Perlu adanya perantara dari ada yang mutlak dengan caraemanasi yang terus mengalir (Fayd). Ibnu Sina tidak me-nyentuh Keesaan Allah yang sempurna, karenanya ia me-makai emanasi yang berlipat ganda. Kelipatgandaan dankeragaman ini bisa dilihat di dunia ini. Ibnu Sina juga me-nganggap penting akan adanya asas dasariyah dari neo-platonisme: ex uno non fit nisi unum حد الوا إال الواحدالیصــــــدرعنھ(Yang satu tidak akan menghasilkan darinya kecuali yangsatu pula, maksudnya dari yang satu hanya menghasilkanyang satu pula). Keabadian dunia, posisi bumi sebagai pu-sat, masing-masing badan jagad raya mempunyai bentuk,
Serpihan-Serpihan Filsafat | 65
jiwa, dan akalnya yang abadi.55
Ibnu Sina meminjam jalan emanasi yang digunakan guru-nya, Al Faraby. Ia mencoba menjelaskan bagaimana yanganeka berasal dari Yang Esa, yang baru dari Nan Awal,sebagaimana berikut: Dari pengetahuan diri Wajib al-Wujud الوجــود) جب (الوا mengalirlah secara mutlak akal awalـــل) العـقـ (األول yang berstatus wajib al-mumkin كن) المم جب .(الواYang wajib al-mumkin mengetahui perihal dirinya sendiridan tahu pula tentang Wajib al-Wujud (Allah). Dari penge-tahuan tentang Allah, wajib al-mumkin menghasilkan akalkedua melalui emanasi. Sejauh wajib al-mumkin menge-tahui dirinya sebagai yang wajib, mutlak perlu, maka akanmenghasilkan jiwa (النـفــــــس) falak yang terjauh. Sejauhwajib al-mumkin mengetahui dirinya sebagai yang mung-kin, maka akan melahirkan materi falak terjauh itu (badan-badan jagad raya). Dari akal kedua itu beralihlah jiwa danakal serta bentuk-bentuk material. Ini disebut Wajib ash-Shuwar الصـــور) جب (الوا yang dalam bahasa Latin diterje-mahkan dengan Datum Formarum (pemberi bentuk-ben-tuk).
3. Kendati ada struktur emanasi namun dunia tetap berbedadengan Allah karena ‘di dalam’ Allah essensi dan eksisten-si itu identik, sedangkan pada ciptaan, eksistensi merupa-kan suatu aksiden yang ditambahkan pada essensi. Allahdianggap terlalu tinggi untuk menciptakan alam secaralangsung.
4. Dari sudut padangan kosmologis dan metafisis tesis-tesistersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:a) Allah dalam jalan emanasi (Fayd) ada secara mutlak.
55Inocentio, Joao., t.t, Filsafat Alam Dalam Pemikir-Pemikir IslamAbad Pertengahan, artikel, hlm. 19-20.
66 | Win Usuluddin Bernadien
Tidak akan ada kebebasan pada-Nya jika Dia bukanabsolut adanya.
b) Dunia tidak secara langsung diciptakan oleh Allah tetapimelalui emanasi.
c) Dunia sifatnya abadi.
TENTANG JIWA
Menurut Ibnu Sina, jiwa mempunyai dua kekuatan, yaitukekuatan untuk bekerja dan kekuatan untuk berteori. Kekuatanbekerja adalah sumber segala gerak yang dilakukan oleh ba-dan sehingga manusia bisa mengatur ritme hidupnya. Kekua-tan teori adalah akal, yang terbagi ke dalam empat fase: faseterendah, yaitu ‘aql hiyulani: merupakan tenaga dan kekuatanyang diberikan kepada manusia untuk memperoleh ma’rifat.Manusia dalam hal ini seluruhnya sama. Fase kedua ialah akaldengan bakat. Fase ini merupakan fase ketika manusia mem-pelajari prinsip-prinsip asasi tentang ma’rifat dan pemikiranyang benar. Fase akal sebenarnya. Jika manusia maju selang-kah dengan gerakan aktivitas akal-pemikirannya yang khusus,sampailah ia pada ma’rifat akan dirinya. Fase terakhir danyang tertinggi yang diberikan kepada manusia (sedangkan ke-pada para nabi diberikan kenikmatan khusus, karena kesem-purnan tabi’at mereka yang paripurna), yang demikian ini me-rupakan fase akal yang dapat dimanfaatkan, yang di dalamnyaterdapat alam wujud yang dipenuhi oleh diri manusia, sedang-kan manusia sebagai satu naskhah dari alam yang objektif. Diatas fase-fase tersebut terdapat akal totalitas atau akal yang ak-tif, yang dengan jalan (proses)-nya dan perantaraanya, emana-si ma’rifat-ma’rifat didapatkan, dan dengan kesatuannya makaakal akan sampai pada fase tertinggi. Kemudian, dalam pan-dangan Ibnu Sina perjalanan hidup manusia tak lain adalah
Serpihan-Serpihan Filsafat | 67
usaha untuk semakin melepaskan diri dari dunia inderawi gu-na mengambil bagian dalam asas tersebut secara intelektual.Manusia merupakan suatu kesatuan dari jiwa rohani dan ba-dan. Jiwa menjadi asas intern dan langsung dari gerakan-gerakan badan. Jiwa adalah kesempurnaan, karenanya jiwamampu mengatur, menumbuhkan, dan memberi makan padabadan. Oleh karena itu jiwa dan badan saling melengkapi danmengabdi. Badan merupakan wahana bagi jiwa, karenanyamelalui badan pacaindera dapat ditangkap oleh akal budi yangmemungkinkannya untuk berfungsi, misalnya pembentukanberbagai konsep dan putusan pencapaian suatu pengenalaneksperimental akan keyakinan-keyakinan yang mungkin adapada orang lain.
Berbagai aktivitas akal, budi baik secara langsung mau-pun secara tidak langsung diwujudkan oleh Intelelectus Agensyang terpisah. Namun manusia tidak dilengkapi dengan me-mori intelektual intensional sebagai objek yang dikenal, tetapiakal insani menerima pengetahuan secara langsung dari Inte-lectus Agens tersebut. Karena itulah, maka sesungguhnya ma-nusia itu tidak bisa mengatakan “aku mengetahui” tetapi diahanya boleh mengatakan “tibalah pengetahuan padaku”.
Kebahagian yang dicari, juga kemampuan akal untukmemahami berbagai macam bentuk dan perubahan dunia,termasuk juga mukjizat dan lain sebagainya berasal dari dandiselenggarakan oleh Nan Awal. Lebih dari itu, kemampuanuntuk menyatakan diri dengan Datum Formarum “Sang Pem-beri bentuk” الصـــور) جب (الوا berbeda dari orang yang satu den-gan yang lain dalam beberapa kategori: orang biasa yang misi-kin secara rohani, kaum gnostik, dan para nabi. Nabi meng-atasi manusia biasa karena mempeoleh kesempurnaan akal.Agaknya, kosmologi, metafisika, dan Antropologi yang dikem-
68 | Win Usuluddin Bernadien
bangkan oleh Ibnu Sina sangat erat dan bermuara pada mistikdan kenabian.
PENUTUP
Kiranya perlu digaris bawahi bahwasanya Ibnu Sina mem-pertahankan pendapat tentang gejala kosmik dan alamiahyang tidak bergantung pada Penyelenggaraan Allah, karenapengetahuan Allah hanya mencakup yang universal, bukanyang singular. Menurut Ibnu Sina universalia itu memiliki tigajenis keberadaan, yaitu keberadaan dalam rasio ilahi, dalambenda, dan dalam akal budi. Materi ditakdirkan untuk meneri-ma bentuk-bentuk, bukan dari dalam dirinya sendiri melainkanmenerima dari luar. ‘Sang Pemberi bentuk’ الصـــور) جب (الوا bagi‘dunia di bawah bulan’ adalah apa yang dinamakan rasio aktif,yang juga melahirkan jiwa manusia yang kekal abadi, tidakbisa mati apalagi hancur. Tujuan manusia adalah mengenalrasio aktif ini.56 Manusia berkemungkinan untuk merenungkandan melebur dengan yang ilahi, serta terbebas dari belenggudunia material. Ringkasnya, Ibnu Sina telah membangun kon-sep filosofisnya tentang alam, manusia, dan Allah secara reflek-tif rasionalistis atas keseluruhan keadaan untuk mencapai haki-kat dan memperoleh hikmat. Satu hal yang menarik adalahunsur rasional ini merupakan syarat mutlak sehingga filsafatmenjadi kegiatan otonom yang dapat berinteraksi dengan il-mu-ilmu lain, termasuk di dalamnya ilmu agama. Kemudiandalam bingkai ilmu agama Islam, filsafat dipandang sebagaiilmu yang berasal dari ‘luar’ ilmu agama Islam. Namun demi-kian filsafat mendapatkan tempat yang terhormat, yaitu seba-gai alat untuk lebih mendalam memasuki labirin ilmu agama
56Lorens Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia PusatakaUtama, hlm. 256-257.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 69
Islam. Filsafat pada akhirnya bahkan dianggap mempunyai ke-terkaitan dengan agama, yaitu sebagai pendukung dan pembe-la agama. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Blackburn, Simone 2008, The Oxford Dictionary of Philoso-phy, Oxford: Oxford University Press.
Dammen Mc Auliffe, Jane., 2001, Encyclopaedia of TheQur’an, Volume One A-D, Washington D.C: GeorgetownUniversity.
Honderich, Ted., 1995, The Oxford Companion to Philosophy,Oxford-New York: Oxford University Press.
Inocentio, Joao., t.t, Filsafat Alam Dalam Pemikir-Pemikir IslamAbad Pertengahan, artikel, hlm. 19-20.
Lorens Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia Pusta-ka Utama.
Marmura, M.E., 1964, Avicenna’s Theory or Prophecy in theLight of Ash’arite Theology, in W.S. McCullouogh (ed.),The Seed of Wisdom, Toronto.
Nasr, Sayyed Husein, 1986, Tiga Pemikir Islam: Ibnu Sina Su-hrawardi Ibnu Arabi, Bandung: Risalah.
Nasr, Seyyed Hossein, 1978, An Introduction to Islamic Cos-mological Doctrin, Colorado: Shambhala Boulder.
Wicken, G. M., (ed.), 1952, Avicenna, Scientist, and Philoso-pher: A Millenary Symposium, London.
Yudi Santoso, 2013, Kamus Filsafat, Yogyakarta: Pustaka Pela-jar.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 71
BAGIAN KELIMA
THOMAS AQUINAS DAN PEMIKIRANNYA
PENGANTAR
Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225, dari kalangan ke-luarga bangsawan di kastil Roccasecca, kerajaan Naples Italiaselatan.57Menjelang usia 20 tahun ia bergabung dengan tarekatSanto Dominikus (ordo Dominikan) dan menjadi murid Alber-tus Magnus di Paris dan Köln. Semasa mudanya ia hidup den-gan pamannya itu, seorang pemimpin ordo di Monte Cassino.Ia berada di sana selama sembilan tahun, yakni dari tahun1230 hingga tahun 1239. Pada tahun 1239 hingga tahun 1244Aquinas belajar di Universitas Napoli, tahun 1245 sampai ta-hun 1248 di Universitas Paris di bawah bimbingan Sang GuruAlbertus Magnus (St. Albert The Great). Sampai tahun 1252 ia
57Baca pula karya Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Phi-losophy, 2008, Oxford: Oxford University Press, telah diindonesiakanoleh Yudi Santoso, Kamus Filsafat, 2013, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,hlm. 49-51.
72 | Win Usuluddin Bernadien
bersama Albertus berada di Cologne. Tahun 1252 kembali be-lajar di Universitas di Paris, Fakultas Teologia. Tahun 1256 di-beri Licencia Docendi (ijazah bidang Teologia) dan mengajar disana hingga tahun 1259. Antara tahun 1269 hingga tahun1272 ia mengajar di Universitas Paris. Sejak tahun 1272 meng-ajar di Universitas Napoli. Thomas Aquinas meninggal duniadalam usia yang masuh relatif muda, 49 tahun, pada tahun1274 di Lyons, meninggalkan banyak karya tulisan. Dalam edi-si modern semua karya itu dikumpulkan dalam 34 jilid. Karya-karyanya antara lain: Komentar atas “Sententiae” karanganPetrus Lombardus, “Summa Contra Gentiles” (Ikhtisar Mela-wan Orang-orang Kafir), dan karyanya yang utama adalah“Summa Theologiae I-III” (Ikhtisar Teologi I-III). Karya-karyaThomas Aquinas termasuk dalam karangan-karangan terpen-ting kesusasteraan Kristiani. Dari karya-karyanya, Aquinasnampak mempunyai maksud utama untuk menciptakan suatuteologi, dengan tetap mengakui otonomi filsafat yang menda-sarkan diri pada kemampuan akal budi yang dimiliki manusiademi kodratnya. Aquinas berkeyakinan bahwa akal menyebab-kan manusia mampu untuk mencapai kebenaran dalam kawa-sannya yang alamiah. Sebaliknya, teologi memerlukan wahyuadikodrati. Berkat wahyu adikodrati, teologi dapat mencapaikebenaran yang bersifat misteri dalam arti ketat, misalnya tri-nitas, inkarnasi, dan sakramen, oleh karena itu teologi memer-lukan iman. Iman adalah suatu sikap penerimaan atas dasarwibawa Allah. Dengan beriman manusia dapat mencapai pe-ngetahuan yang mengatasi akal, pengetahuan yang tidak dapatditembus oleh akal semata. Walaupun misteri iman ini meng-atasi akal, tetapi iman tidak bertentangan dengan akal. Imantidak anti akal. Meskipun akal tidak dapat menemukan misteri,tetapi dapat ‘meratakan jalan’ yang menuju misteri (praeam-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 73
bulum fidei). Dengan kata lain Aquinas menunjukkan dua ma-cam pengetahuan yang tidak saling bertentangan melainkanberdiri sendiri secara berdampingan. Menurutnya pengetahuanitu dapat dibagi dua yaitu pertama: pengetahuan alamiah,yang berpangkal pada akal budi, yang sasarannya hal-hal yangyang bersifat insani, dan kedua: pengetahuan iman, yang ber-pangkal pada wahyu adikodrati yang sasarannya adalah hal-hal yang diwahyukan Allah secara khusus disampaikan kepadamanusia melalui Kitab Suci di dalam tradisi Gereja. Jelasnya,Aquinas adalah seorang filsuf sekaligus sebagai seorang teo-log.58
TEORI PENGETAHUAN
Dalam teorinya tentang pengetahuan, Aquinas dibimbingoleh pandangannya bahwa rasio dan iman tidak bertentangan,akan tetapi di antara keduanya memiliki batas yang jelas. Ba-ginya, semua objek yang tidak diindera tidak akan dapat dike-tahui secara pasti oleh akal. Dengan begitu pula kebenaranajaran Tuhan tidak mungkin dapat diketahui dan diukur deng-an akal. Kebenaran ajaran Tuhan hanya dapat diterima deng-an iman. Sesuatu yang tidak dapat diteliti dengan akal adalahobjek iman. Pengetahuan yang diterima atas dasar iman tidaklebih rendah daripada pengetahuan yang diterima dari akal.Setidaknya kebenaran akali tidak akan bertentangan denganajaran wahyu.59 Menurut Aquinas, manusia harus menyeim-bangkan antara akal dan iman: akal membantu membangundasar-dasar filsafat Kristiani. Akan tetapi, harus selalu disadari
58F.X Mudji Sutrisno, & F. Budi Hardiman, (ed.), Para Filsuf Pe-nentu Gerak Zaman, Yogyakarta: Kanisius, 1992, hlm 39-41.
59Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sampaiCapra, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990, hlm. 104.
74 | Win Usuluddin Bernadien
bahwa hal itu tidak dapat selalu dilakukan karena akal memilikiketerbatasan untuk menjangkau ke-ilahi-an. Akal tidak mampumenjelaskan konsep kehidupan kembali dan penebusan dosa.Akal juga tidak akan mampu memberikan bukti pada kenyata-an essensial keimanan Kristiani. Oleh karenanya, Aquinas ber-pendirian bahwa dogma-dogma Kristiani itu tepat sebagaima-na yang disebutkan dalam firman-firman-Nya. Dari uraiansingkat di atas dapat diambil gambaran bahwa bagi ThomasAquinas ada dua jalur pengetahuan dalam filsafat. Pertama,jalur akal yang dimulai dari diri manusia sendiri dan berakhirpada Tuhan. Kedua, jalur iman yang dimulai dari Tuhan lewatwahyu, dan didukung oleh akal. Selanjutnya, Aquinas mem-bagi pengetahuan menjadi tiga bagian yakni fisika, matema-tika, dan metafisika. Dari ketiganya itu yang paling mendapatperhatiannya adalah metafisika, karena baginya metafisika da-pat menyajikan abstraksi tingkat tertinggi.60 Lebih lanjut Aqui-nas berpendapat bahwa filsafat dapat dibedakan dari agamadengan melihat penggunaan akal. Baginya filsafat ditentukanoleh penjelasan sistematis akali, sedangkan agama ditentukanoleh keimanan. Meski demikian, perbedaan itu tidak sebegitujelas karena pada hakikatnya pengetahuan adalah gabungankedua-duanya. Agama pun menurut Aquinas dapat dibagimenjadi dua golongan, yakni agama natural yang dibentang-kan di atas akal, dan agama wahyu yang dibentangkan atasdasar iman. Di dalam doktrin tentang pengetahuannya, Aqui-nas nampak sebagai seorang realis yang moderat. Ia mengajar-kan bahwa jagad raya ini berada dalam tiga cara. Pertama,sebagai sebab-sebab di dalam pemikiran Tuhan (ante rem).
60Frederick Mayer, A History of Ancient & Medieval Philosophy,New York: American Book Company, 1950, p. 461. Baca pula AhmadTafsir, op.cit., hlm. 113.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 75
Kedua, sebagai idea dalam pemikiran manusia (post rem).Ketiga, sebagai esensi sesuatu (in rem). Dapat dimengerti darisini bahwa Aquinas berusaha menjembatani dua ekstrimitas,pertama: Extreme Nominalisme yaitu: suatu ajaran dalamfilsafat skolastik yang menyatakan bahwa tidak ada eksisitensiabstrak yang sungguh-sungguh objektif, yang ada hanyalahkata-kata dan nama-nama, yang benar-benar real adalah fisikyang particulair ini saja, dan yang kedua: Extreme Realismmerupakan salah satu dari ajaran filsafat yang menyatakanbahwa realitas universal abstrak sama dengan atau lebih tinggidari realitas fisik. Aquinas melakukan harmonisasi antara ke-duanya dengan cara menjelaskan bahwa jagad raya ini me-miliki berbagai pengertian manakala diterapkan pada Tuhan,manusia, dan alam. Sains menurutnya berkenaan denganalam jenis ketiga, yaitu alam sebagai eseensi. Konsep-konsepsains tidak a priori sebab setiap insan terlahir tidak membawaidea-idea immaterial. Menurut Aquinas, pikiran tidak akanberisi apa-apa bila tidak menggunakan indera. Proses pengeta-huan dimulai dari penginderaan, yang memberi kepada kitapersepsi tentang suatu objek di dalam alam. Persoalannya se-karang ialah bagaimana persepsi itu diterjemahkan ke dalamidea-idea yang dapat dipikirkan. Untuk menyelesaikan masalahini Aquinas menggunakan istilah intelek aktif (active intellect)yang bertugas mengabstraksikan unsur-unsur dalam jagadraya, lalu menciptakan berbagai pembagian jenis yang dapatdipikirkan. Aquinas pun kemudian menjelaskan susunan jagadraya dengan intelek aktif. Menurutnya dengan intelek aktifmanusia dapat memahami prinsip pertama pengatur seluruhkenyataan.
Selanjutnya, Aquinas menjelaskan bahwa pengalamanbukanlah prosesi yang kacau karena pengalaman dapat me-
76 | Win Usuluddin Bernadien
nyatakan berbagai prinsip universal tentang eksistensi. Kualitas-kualitas particulair tidaklah terpisah-pisah tetapi memiliki kuali-tas esensial dalam keseluruhan. Dalam kaitan ini sains bersang-kutan (concern) dengan jagad raya. Oleh karena itu manakalasains memiliki universalitas maka semakin penting kedudukan-nya bagi kesejahteraan umat manusia. Dari sini nampak bah-wa teori Aquinas tentang sains sangat berbeda dengan pan-dangan filsafat sains modern yang menganggap bahwa penca-pain terbaik pada sains ialah manakala sains tersebut lebihmenjurus pada objek-objek yang partikulair. Sains moderntidak memberikan apresiasi yang tinggi kepada masalah-masa-lah immaterial sebab immaterial itu, bagi sains modern, meru-pakan bagian pembahasan metafisika, sedangkan bagi Aqui-nas sains akan semakin memiliki nilai yang tinggi manakalasains itu semakin universal.
TENTANG SEMESTA RAYA
Ada hal terpenting yang dapat ditemui di dalam pemikirankosmologi Aquinas yakni pandangannya tentang matter danform. Baginya, matter tidak dapat terpisah dari form, karenajika hal itu terjadi tentu akan terdapat kontradiksi sebab mattermenjadi tidak jelas. Dari sini terlihat perbedaan antara Aquinasdengan Aristoteles yang memandang bahwa matter dan formmasing-masing terpisah dan otonom. Pemikiran Aquinas bah-wa matter dan form dapat dipisahkan bisa dipahami karenasetiap benda terdiri atas bahan (matter) dan sifat (form) sebagaimisal manakala kita melihat sepotong emas maka zat (matter)emas ialah bendanya itu, sedangkan warna kuningnya emas,susunan kimianya dan sifat-sifat lainnya adalah form. Demi-kianlah jalan pikiran Aquinas yang lebih mudah dipahami daripada teori Aristoteles. Menurut Aquinas perbedaan antara ma-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 77
laikat dan manusia ialah karena malaikat tidak memiliki tubuh,malaikat tidak memiliki matter, mereka form semata-masa,sedangkan manusia memiliki kedua-duanya (matter dan form).Dalam masalah ruang dan waktu Aquinas memiliki kesamaanpandangan dengan Aristoteles. Baginya ruang tidak dapat dipi-kirkan terlepas dari eksistensi benda. Ia tidak sepaham denganajaran yang mengatakan bahwa ruang tidak terbatas karenahal ini berlawanan dengan ajaran Kristiani. Adapun waktumenurut Aquinas ditentukan oleh gerak. Baik ruang maupunwaktu, menurut Aquinas kedua-duanya merupakan persoalanfilsafat yang sulit dipecahkan.
TENTANG RELASI JIWA-RAGA
Menurut Aquinas jiwa dan badan (raga) memiliki hubung-an yang pasti. Baginya, raga menghadirkan matter dan jiwamenghadirkan form yaitu prinsip-prinsip hidup yang aktual.Hubungan antara jiwa dan raga merupakan kesatuan yangterjalin dengan tidak secara kebetulan, tetapi kesatuan antarakeduanya memang diperlukan untuk mewujudkan kesempur-naan hidup manusia. Ia menjelaskan bahwa jiwa adalah kapa-sitas intelektual (pikir) dari vital kejiwaan lainnya, karenanyamanusia disebut makhluk berakal. Oleh karena itu jiwa harusmembimbing raga, sebab jiwa kedudukannya lebih tinggi dari-pada raga, meskipun sesungguhnya jiwa itu sebenarnya ter-gantung juga pada raga, bahkan kegiatan raga mempengaruhijiwa. Dalam kaitan ini Aquinas mengajarkan bahwa nisbah(pertautan) antara jiwa dan raga manusia harus dilihat sebagaihubungan antara form dan matter. Atau juga hubungan antarajiwa dan raga itu bisa dilihat dalam hubungan antara aktus (pe-realisasian) dan potensi (bakat). Jadi, manusia itu satu substan-si saja, sehingga jiwalah yang menjadi bentuk badan (anima
78 | Win Usuluddin Bernadien
forma corporis). Dengan kata lain, jiwalah yang menjadikanraga sebagai realitas. Jiwa menjalankan aktivitas-aktivitas yangmelebihi sifat ragawi belaka, yaitu berfikir dan berkehendak.Aktivitas jiwa bersifat rohani, karenanya jiwapun harus bersifatrohani. Ini sesuai dengan prinsip agere sequitur esse yang arti-nya cara bertindak itu sesuai dengan cara beradanya. Karenajiwa bersifat rohani maka manusia setelah mati jiwanya hidupterus, kekal selamanya. Kemudian, Aquinas membedakan de-ngan tegas tipe-tipe jiwa menjadi tiga.
1. Jiwa Vegetatif, yaitu jiwa pengatur tetumbuhan.2. Jiwa Sensitif, yaitu jiwa yang mengatur kehidupan hewan.3. Jiwa Rasional, yaitu jiwa yang mengatur kehidupan ma-
nusia. Jiwa Rasional inilah yang memiliki kedudukan ter-tinggi, yang merupakan manifestasi kehidupan manusia.Jiwa ini menghadirkan supremasi intelek di atas jiwa te-tumbuhan (vegetatif) dan jiwa hewan (sensitif). Pembeda-an jiwa seperti tersebut di atas sebenarnya merupakanpembagian kemampuan, sebab sesungguhnya jiwa itumemiliki kesatuan (jiwa itu satu).61
Lebih jauh Aquinas menjelaskan bahwa jiwa itu mempu-nyai kemampuan pikir (reason) dan nafsu (appateit) termasukkemauan atau keinginan. Baginya jiwa itu imaterial. Imaterialdalam bahasa Inggris immaterial, dari bahasa Latin im, suatubentuk yang diasimilasikan dari in (tidak), dan materialis (ma-terial, bahan yang darinya hal-hal dibuat). Jadi, imaterail ber-arti tidak terdiri dari material. Sinonim-sinonimnya: tidak jas-mani, rohani, bukan material, bukan fisik. Hal-hal yang dipan-dang sebagai immaterial adalah Allah, roh, malaikat, jiwa,hantu, penyebab atau prinsip formal dalam hal-hal, élan vital,pikiran, kesadaran, kehendak, intelek, emosi, perasaan, pence-
61Mayer, op.cit., p. 459.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 79
rapan, yang kesemuanya itu tergantung pada aktivitaas mate-rial dari suatu hal untuk bereksistensi atau beraktivitas.62
Dalam kaitan dengan jiwa immaterial ini Aquinas mem-buktinya: jiwa dapat memikirkan objek-objek imaterial danmampu memikirkan yang universal. Jiwa dalam raga, menurutAquinas, hanya bergantung secara ekstrinsik, karena itu jiwabersifat immortal (tidak rusak, hidup terus tiada akhir). Argu-men yang ia ajukan adalah sebagai berikut: Jiwa manusia tidakdapat rusak. Sesuatu itu dapat rusak karena dua sebab. Per-tama, dari dirinya sendiri. Sebab dari dirinya tidak mungkin ka-rena jiwa itu pemberi hidup pada raga, sebagai pemberi hidupharus selalu hidup. Jiwa merupakan form sedangkan raga ada-lah matter yang memperoleh form dari jiwa kemudian men-gak-tual. Manakala raga rusak, maka jiwa akan memisahkan(melepaskan) diri dari raga. Kedua, dari luar dirinya yakni dariraga. Hal ini tidak mungkin karena raga kedudukannya lebihrendah daripada jiwa. Raga diberi form oleh jiwa untuk aktual,yang sangat ditentukan oleh jiwa. Aquinas mengakui bahwajiwa adalah gabungan atau kesatuan antara matter dan formyang immortal. Untuk mempertahankan pengakuanya ini, di-kemukakan argumen sebagai berikut: sesuatu bisa rusak jikaada suatu pertentangan. Generation (berkembang) dan Corruption (menurun) adalah dua sifat yang bertentangan.Jiwa hanyamenerima sesuatu yang tidak bertentangan, karenanya dalamjiwa tak ada pertentangan dan karenanya pula jiwa itu tidakakan mengalami rusak. Manakala dalam jiwa terdapat penge-tahuan yang nampak saling bertentangan, menurut Aquinas,sebenarnya tidaklah demikian halnya, karena yang sesungguh-nya terjadi, pertentangan itu berlangsung di luar jiwa, yang adaadalah pertentangan kebenaran di luar jiwa, yaitu di dalam
62Loren Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 326.
80 | Win Usuluddin Bernadien
sains atau filsafat. Aquinas menambahkan bahwa usaha untukhidup abadi merupakan keinginan yang sia-sia bila nyatanyajiwa itu mortal, sedangkan keinginan itu bersifat umum, semuamanusia ingin abadi.63 Atas dasar ajaran Kristiani, ThomasAquinas berpendapat bahwa jiwa akan hidup kembali sesudahkematiannya dan kelak di sana akan disatukan dengan jasad.Setelah kematian jiwa akan hidup terus dalam ujudnya sebagaiform. Ini berarti bahwa jiwa tetap memiliki keterarahan kepadamatter. Dan, hal ini rupanya cocok dengan ajaran Kristianimengenai adanya kebangkitan badan.
TENTANG ETIKA DAN HUKUM
Thomas Aquinas berpendapat bahwa nilai etika tertinggiadalah Kebaikan Tertinggi. Kebaikan ini menurutnya tidak mu-ngkin dapat diraih manusia pada masa sekarang ini, karenanyamanusia harus menunggu hingga saatnya kelak di kala iamemperoleh pandangan yang sempurna tentang Tuhan. Aqui-nas memiliki lima argumen tentang Allah yang dikenal dengannama Quenque Viae (lima jalan): (1) bahwa seri gerak tidakdapat berlangsung tanpa batas, (2) bahwa seri sebab tidakdapat berjalan terus tanpa akhir, (3) bahwa konsepsi mengenaidunia yang kontingen tidak konsisten, dunia menyiratkan ada-nya yang-ada yang niscaya, (4) bahwa aspek-aspek normatifpengalaman menyiratkan eksistensi yang-ada yang normative,(5) bahwa aspek-aspek teleologis (keteraturan) eksistensi me-nyiratkan seorang penganut yang intelijen.64
Ajaran etika Aquinas sesuai dengan ajarannya mengenaimanusia. Menurutnya, moral diturunkan dari cara ber-ada-nyamanusia diciptakan oleh Allah, yakni sebagai makhluk berakal
63Ahmad Tafsir, op.cit., hlm.103.64Lorens Bagus, op. cit., hlm. 81.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 81
budi yang bersifat sosial. Tujuan akhir hidup manusia adalahmemandang Allah. Oleh karenanya hidup perorangan harusdiarahkan ke sana. Seluruh masyarakat harus diatur sesuaidengan tuntutan tabiat manusia. Dengan begitu, masyarakatakan membantu orang perorang untuk menaklukkan nafsu-nafsunya kepada akal dan kehendak. Menurut Aquinas nafsuitu pada dirinya sendiri baik. Nafsu menjadi jahat kalau me-langgar kawasan masing-masing dan tidak mendukung akaldan kehendak. Cita-cita kesusilaan bukanlah untuk mematikannafsu, melainkan untuk mengatur sedemikian rupa sehingganafsu dapat membantu manusia dalam usahanya merealisasi-kan tugas terakhir hidupnya. Bagaimanapun juga kejahatantidak berada sebagai kekuatan yang berdiri sendiri. Kejahatantidak diciptakan oleh Allah, melainkan muncul dan ada mana-kala tiada kebaikan. Demikian, dalam hal etika Aquinas mene-kankan superioritas kebaikan keagamaan. Karenanya ia ba-nyak membahas masalah iman. Bagi Aquinas manusia yangtidak beriman adalah kafir. Manusia yang kafir akan meng-alami lepas hubungan dengan Tuhan, jika mereka mati masihdalam kondisi demikian maka kelak akan mendapatkan hu-kuman dari Tuhan. Meskipun demikian, sebagai sesama ma-nusia, selama hidup di dunia orang beriman tidak dilaranguntuk bekerja sama dengan orang kafir. Aquinas berpendapatbahwa dasar kebaikan adalah charity (kemurahan hati) yangterdapat dalam jiwa yang penuh cinta, kedermawanan danbelas kasihan. Cinta kepada Allah adalah cinta yang pertamakali datang, kemudian muncul cinta kepada yang lain. Namundemikian, konsep cinta Aquinas tidak menyeluruh, sebab tidakmencakup orang kafir, bahkan Aquinas setuju kepada St. Au-gustinus yang mengajarkan kehidupan membujang (Celebacy)dan memandang hidup dalam perkawinan itu rendah. Dari sisi
82 | Win Usuluddin Bernadien
ini nampak bahwa kehidupan pertapa (Ascetis) memainkanperanan yang kuat dalam konsep etikanya.
Dalam perkembangannya, pengaruh terhadap pemaham-an etika Aquinas ini adalah munculnya anggapan bahwa mo-nogami adalah watak asli manusia. Karena itu dalam perka-winan tidak boleh ada perceraian sebab hal itu melawanhukum masyarakat dan hukum Allah. Aquinas juga menentangkeras Birth Control (Pengaturan Kelahiran, di Indonesia popu-ler dengan program Keluarga Berencana) yang cenderungmenjadi pembatasan kelahiran. Sebagai pendukung patrialkhalia berpendapat bahwa dalam keluarga kedudukan ayah adalahyang tertinggi.
Mengenai free will (kebebasan berkehendak) Aquinas ber-pendapat bahwa sesungguhnya manusia itu berada padaposisi yang berbeda dengan Allah. Dalam konteks ini Allahselalu benar sedangkan manusia tidaklah demikian. Manusiamasih bisa benar pun pula masih bisa salah. Allah mengetahuiesensi segala sesuatu, Allah mengetahui hal-hal khusus melaluipengetahuan tentang diriNya sendiri dan tentang esensi hal-halyang termuat dalam pengetahuan, sedang manusia tidak. Allahsebagai Yang Kekal dan Absolut, sedangkan manusia dalamhidup dan kehidupannya seringkali dihadapkan pada berbagaikenyataan dan pilihan. Di dalam memilih manusia itu dipenga-ruhi oleh tuntutan materi. Seringkali manusia dihinggapi olehkeraguan tentang dirinya, tentang hidup dan kehidupannya.Hal ini bisa menyebabkan manusia memilih sesuatu yang ren-dah, yang pada implikasinya manusia menjauhi Allah. Manusiasebenarnya dapat memperoleh kebebasan sempurna dengancara memilih sesuatu yang dapat membawa kepada kebaha-giaan abadi dan mendekatkan manusia pada sifat-sifat Ilahy.Toh, kemauan manusia tidak ditentukan oleh sesuatu dari luar
Serpihan-Serpihan Filsafat | 83
dirinya. Oleh karenanya manakala manusia memilih yang sa-lah, layaklah mendapatkan hukuman. Manusia itu pada akhir-nya akan mampu mengenal Allah, manakala berusaha denganakalnya, wahyu atau dengan intuisi. Sebenarnya ThomasAquinas tidak percaya pada adanya pencerahan ilahi (ilmumukasyafah dalam tashawuf Islam), dia juga tidak begitu ter-tarik pada intuisi. Baginya akal (pikiran) lebih penting daripadakemauan atau kehendak, karena yang benar (kebenaran) itulebih tinggi daripada yang baik (kebaikan) oleh karena itu jugamengenal adalah perbuatan yang lebih sempurna daripadamengehendaki. Jelasnya, melalui pikiran itulah manusia akansampai pada kepastian.65
Mengenai hukum, Aquinas membaginya menjadi empatmacam, yaitu: hukum abadi (lex aeterna), hukum alam (lexnatura), hukum Tuhan (lex devina), dan hukum manusia (lexhumana). Menurutnya, dalam penciptaan dan pengaturanalam semesta harus ada hukum yang pasti. Inilah yang dimak-sud hukum abadi, yaitu blue print (suatu rencana) yang meng-atur penciptaan dan pengaturan alam semesta ini. Esensihukum ini tidak dapat dipahami oleh manusia, kecuali hanyapada citranya yang tercermin pada hukum alam. Hukum alammenyebabkan seluruh makhluk di alam semesta ini mendapatkesempurnaannya, mencari kebajikan dan menjauhi kejahat-an. Hukum alam menyediakan kehidupan bagi manusia de-ngan segala haknya seperti berketurunan dan hidup dalam ma-syarakatnya. Hukum Tuhan adalah hukum Kristiani yang ber-kedudukan sangat istimewa, karena dikenal melalui wahyuAllah yang diberikan kepada manusia dengan segala keagung-an dan kemurahan-Nya. Adapun di dalam hukum manusia,hadir hukum alam dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya me-
65Ahmad Tafsir, op. cit., hlm. 106-107.
84 | Win Usuluddin Bernadien
nurut hukum alam membunuh adalah perbuatan salah tetapiini terserah pada hukum manusia untuk menjatuhkan hukum-an apa yang sesuai bagi pelanggar. Hukum manusia tidakberwenang melanggar prinsip-prinsip fundamental seperti me-rampas atau membunuh. Manakala dilanggar maka runtuhlahsemua kerangka pengaturan alam.
Moral yang merupakan bagian dari etika memiliki hubu-ngan yang erat dengan agama. Aquinas yakin terhadap hu-bungan antara keduanya. Baginya tingkah laku moral dapatdikembangkang secara penuh manakala penguasa menghor-mati dan mematuhi agama serta menyatukan diri secara pastidengan undang-undang Gereja. Menghukum orang kafir ada-lah tugas raja, yang harus dilakukan atas dasar keimanan.Keberhasilan penguasa bergantung pada kebaikan moralnya,yang merupakan ciri kewibawaan bagi seorang penguasa.Penguasa harus memiliki rasa keadilan (sense of justice) danharus bertaqwa kepada Allah serta hormat pada hukum moral.Seorang penguasa harus sederhana dalam kehidupannya danmenghindari sifat tamak. Penguasa yang baik akan mendapatpahala surga, bukan hanya sekedar kebesaran atau keme-nangan duniawi yang semu. Kedudukan Sang Raja adalahmewakili sebagian kedudukan Allah yaitu mengatur alam se-mesta. Oleh karena itu raja harus menerapkan ajaran Allahmelebihi orang lain yang bukan raja.
TENTANG GEREJA
Thomas Aquinas berkeyakinan bahwa manusia tidak akandapat diselamatkan tanpa perantaraan gereja. Karena itu ritualsakramen gerejani itu perlu dilakukan. Sakramen sebagai suaturitual pemberkatan atas nama Allah mempunyai tujuan: me-nyempurnakan manusia dalam penyembahan kepada Allah,serta menjaganya dari dosa. Baptis mengatur permulaan hi-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 85
dup, confirmation (penyesalan) untuk keperluan pertumbuhanmanusia, dan sakramen mahakudus (eucharist) untuk me-nguatkan jiwa manusia. Dosa hanya dapat dihilangkan dengandua cara: Perance yaitu penebusan dosa, dengan cara pe-nyesalan terhadap dosa-dosa yang telah diperbuat, dan deng-an extreme unction yaitu dengan perminyakan suci yang mem-persiapkan untuk keabadian hidup. Lebih dari itu sakramenmempunyai pengertian kemasyarakatan. Ordination (pentah-bisan) diperlukan untuk memperkuat jiwa para pendeta, se-dangkan sakramen perkawinan diadakan tidak sekedarnyamelainkan sebagai hukum alam, yang menunjukkan kesadaranmanusia tentang pengaturan Allah mengenai reproduksi manu-sia. Bukankah Yesus Kristus datang untuk melayani manusiasebagai seorang perantara antara Allah dan manusia?. Diaadalah pendamai antara Allah dengan manusia. Bagi Aquinas,manusia tidak akan dapat mencapai kebahagiaan bilamanaterpisah dengan Katholik, karunia Allah tidak diberikan kepadaseseorang secara individu, melainkan diberikan kepada Kristussebagai kepala Gereja, sebagaimana yang telah dilakukan oleholeh para pendeta, wakil-wakil Allah di bumi.
TENTANG ESSENTIA DAN EXISTENTIA BAGI ALLAH
Menurut Aquinas, Allah adalah aktus yang paling umum,actus purus (aktus murni) artinya Allah sempurna adanya, tiadaperkembangan pada-Nya, karena pada-Nya tiada potensi. Se-gala sesuatu pada-Nya telah sampai kepada perealisasianyayang sempurna. Tiada sesuatupun pada-Nya yang masih da-pat berkembang. Pada-Nya tiada kemungkinan. Allah adalahaktualitas semata-mata, oleh karena itu pada Allah hakikat(essentia) dan eksistensi (existential) adalah identik, bertindihtepat. Keadaan yang tidak mungkin terjadi pada makhluk. Ek-sistensi bagi makhluk adalah sesuatu yang ditambahkan pada
86 | Win Usuluddin Bernadien
hakikatnya (essentia). Pada makhkuk nisbah antara hakikatdan eksistensi seperti materi dan benda, atau seperti potensidan aktus, atau seperti bakat dan perealisasinya. Pada Allahtiada sesuatu pun yang berada sebagai potensi yang belummenjadi aktus.66
TENTANG PENCIPTAAN
Hal yang dapat diperhatikan dalam ajaran Thomas Aqui-nas mengenai penciptaan adalah sebagai berikut:
Allah menciptakan dari ‘yang tidak ada’ (creatio ex nihilo).Jelasnya, sebelum dunia ini diciptakan tidak ada apa-apa,sehingga tidak ada pula dualisme yang asasi antara Allah danbenda, antara yang baik dan yang jahat. Segala sesuatu diha-silkan oleh Allah dengan jalan mencipta. Karena itu segala se-suatu berpartisipasi atau mendapatkan bagian dari kebaikanAllah, sekalipun cara makhluk memiliki kebaikan itu berbedadengan cara-Nya. Penciptakan, bukanlah perbuatan pada saattertentu, dan setelah itu dunia dibiarkan pada nasibnya sendiri.Penciptaan merupakan perbuatan Allah yang terus menerus.Dengan penciptaan, Allah terus menerus menghasilkan dan se-kaligus memelihara segala yang bersifat sementara. Dari keke-kalan, Allah menciptakan jagad raya dan waktu, serta segala-nya sesuai dengan bentuknya atau ideanya yang berada dalamroh Allah. Idea-idea itu bukan berada di samping Allah, me-lainkan identik dengan Dia, satu dengan hakikat-Nya. Ini tidakberarti bahwa dunia telah ada sejak kekal. Dunia ada awalnya.Hanya saja Filsafat tidak dapat membuktikannya. Karena jagadraya ini adalah ciptakaan Allah maka Allah bukanlah jagadraya, dan jagad raya bukanlah Allah, meskipun memang men-dapat bagian dari “ada” Allah. Partisipasi ini bukan bersifat
66Ibid, hlm. 106.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 87
kuantitatif. Dus, bukan seakan-akan tiap-tiap makhluk mewakilisebagian kecil tabi’at ilahi. Makhluk berpartisipasi dengan Allahitu hanya sekedar analogia, sekedar kesamaan, kiasan antaraAllah dengan mahkuk-Nya. Analogia ini justru menunjuk padaperbedaan antara Allah dengan makhuk-Nya. Analogia ini bu-kan mengenai perkara yang sampingan akan tetapi mengenaiperkara yang paling hakiki yaitu mengenai “ada”nya Allah dan“ada”nya makhluk (analogia entis). Analogia ini di satu sisimenampakkan adanya jarak tak terhingga antara Allah denganmakhluk, tetapi di sisi yang lain para makhluk itu sekedar me-nampakkan kesamaanya dengan Allah.67
PENUTUP
Seberapa pun cemerlang pemikiran Thomas Aquinassehingga sejak zaman pertengahan sampai kini masih banyakpengikutnya, namun ternyata banyak pula yang menentangpemikiran-pemikirannya. Paling tidak ada dua alasan sehinggaterjadi perlawanan terhadap pemikirannya, yaitu: alasan filo-sofis dan alasan pribadi.68 Sejak Thomas Aquinas menjadi Do-minikan, banyak orang Fransiskan yang menentang pemikiran-nya. Sejak tahun 1277 filsafatnya di kutuk di Paris. Di Inggristerutama di Oxford filsafatnya hampir-hampir masuk tong sam-pah. Pemikiran dan ajarannya yang lebih menonjolkan akal,dan sedikit menggunakan intuisi bahkan nyaris tidak percayapada intuisi, telah menyebabkan Aquinas banyak mendapat-kan perlawanan filosofis. Banyak pemikir lain yang meng-anggap Aquinas terlalu dipengaruhi oleh alam pemikiran Yu-nani yang berakibat terhadap inkonsistensi pada keimanan
67Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta: Ka-nisius, 1980, hlm.109.
68Ahmad Tafsir, op.cit., hlm. 112.
88 | Win Usuluddin Bernadien
Kristiani. Pendekatannya yang rasional merupakan penyebabpenolakan sepanjang abad pertengahan yang telah terlanjurmengikuti St. Bernandus yang meyakini bahwa iman dapat di-gunakan sebagai dasar bagi segala urusan manusia. Banyakorang yang menemukan kontroversi dalam pemikiran Aquinas.Di samping itu pemikiranya sangat ortodoks. Ia tidak ber-keyakinan bahwa manusia dengan dirinya mampu mengenalAllah. Aquinas berkeyakinan bahwa hanya dengan gerejalahmanusia dapat mengenal Allah. Meskipun demikian popula-ritas Aquinas seakan tak memudar, karena sifatnya yang mo-derat. Ia mengakui kehidupan escetis, tetapi juga mengakuiperkawinan dan sistem keluarga yang menduduki posisi sen-tral, bahkan ia berpendapat bahwa keturunan adalah sebagaindari hukum alam. Titik tolak Aquinas jelas empiris, karenanyasebagian teorinya dapat dikombinasikan dengan riset-riset ilmumodern masa kini. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Ahmad Tafsir, 1990, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Tha-les sampai Capra, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Blackburn, Simon, 2008, The Oxford Dictionary of Philosophy,Oxford: Oxford University Press, dan telah diindonesia-kan oleh Yudi Santoso, 2013, Kamus Filsafat, Yogyakar-ta: Pustaka Pelajar.
F.X Mudji Sutrisno, & F. Budi Hardiman, (ed.), 1992, ParaFilsuf Penentu Gerak Zaman, Yogyakarta: Kanisius.
Harun Hadiwijono, 1980, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogya-karta: Kanisius.
Honderich, Ted, (ed.), 1995, The Oxford Companion to Philo-sophy, Oxford-New York: Oxford University Press.
Lorens Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 89
BAGIAN KEENAM
PERDEBATAN SEPUTAR ANGGAPAN POKOKFILSAFAT ILMU PENGETAHUAN ABAD XX
PENGANTARArah dan fungsi filsafat ilmu adalah memberi landasan fi-
losofik untuk paling tidak memahami berbagai konsep dan teo-ri suatu disiplin ilmu, sampai membekalkan kemampuan untukmembangun teori ilmiah. Fungsi pengembangan tersebut se-cara substantif memperoleh pembekalan dan disiplin ilmumasing-masing agar dapat menampilkan teori substantif pula,yang secara teknis diharapkan dengan dibentuknya metodo-logi pengembangan ilmu dapat mengoperasionalkan pengem-bangan konsepsi dan teori ilmiah dari disiplin ilmu masing-masing.69
Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba memahami pe-mi-kiran tiga tokoh terkemuka mengenai ‘perdebatan’ merekaseputar anggapan pokok filsafat ilmu pengetahuan, mereka itu
69Muhadjir, Noeng, Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, danPostModernisme, Edisi II, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2001, hlm. 2.
90 | Win Usuluddin Bernadien
adalah Karl Raimund Popper, Thomas Samuel Kuhn, dan ImreLakatos. Penekanan tulisan ini pada kritik Lakatos terhadapdua tokoh yang disebutkan sebelumnya, dan sebagai penutupdicoba untuk menampilkan gambaran perkembangan ilmupengetahuan pada akhir abad XX yang sangat pesat danagaknya telah menghadapkan manusia pada berbagai masalahyang sebelumnya tak terbayangkan. Mungkin kurang adequatesebab referensi yang penulis rujuk memang tidaklah banyakkecuali hanya beberapa buku sebagaimana yang dicantumkandalam daftar pustaka, Namun demikian, semoga tulisan inibermanfaat adanya.70
KARL RAIMUND POPPER (1904-1994)Karl R. Popper lahir di Wina, Austria. Seorang ahli logika
dan filsafat ilmu baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Karenakeahliannya, sejak tahun 1949 di Universitas London iadiangkat menjadi profesor bidang logika dan metode ilmiah.71
Popper menentang pemikiran Lingkaran Wina yang me-misahkan antara ungkapan yang bermakna (meaningful) dariyang tidak bermakna (meaningless) berdasarkan kriterium da-pat tidaknya dibenarkan secara empiris. Pembedaan berdasar-kan kriterium empiris berarti bahwa suatu ungkapan harus da-pat diverifikasi berdasarkan pengalaman yang mengenal datainderawi (pandangan Lingkaran Wina ini disebut empirisisme
70Melalui artikel ini penulis menyampaikan terima kasih yang tuluskepada sahabat Novella Parciano, yang telah memberikan inspirasi daninsight sangat berharga. Semoga Tuhan selalu memberkahi (pen).
71Mudhofir, Ali, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001, hlm. 408. Baca pula: Simon Blackburn, 2008, The Oxford Dic-tionary of Philosophy, Oxford: Oxford University Press, dan telah diindo-nesiakan oleh Yudi Santoso, Kamus Filsafat,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013, hlm. 474-475.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 91
logis). Dalam Lingkaran Wina, prinsip verifikasi ini didasarkanpada pandangan bahwa pengetahuan pada umumnya tidakdapat melampui batas-batas pengalaman inderawi. Dalam pa-da itu dikenal dua verifikasi, yaitu: pertama, verifikasi langsung,maksudnya suatu pernyataan yang memaparkan pengalamaninderawi (Lingkaran Wina ini disebut neopositivisme atau posi-tivisme logis), dan Kedua, verifikasi tak langsung maksudnyamembuat verifikasi dengan berangkat dari reduksi logis terha-dap suatu pandangan menjadi pernyataan yang dapat diveri-fikasi. Dalam rangka tersebut, ada dua pertanyaan yang berar-ti: pertama, “How do you know?” (lebih dalam yang dimaksudialah “bagaimana Anda memverifikasi?”) dan kedua, “What doyou mean?” (lebih dalam yang dimaksud: berilah uraian atauanalisa logis dari pernyataan anda).72 Popper menentang pem-bedaan seperti dikemukakan oleh Lingkaran Wina dan meng-gantinya dengan pembedaan antara ilmiah dan tidak ilmiah.Demarkasi tersebut terletak pada ada tidaknya dasar empirisbagi ungkapan yang bersangkutan.Hanya saja dasar empirismetersebut tidaklah berhubungan dengan bermakna atau tidakbermakna, tapi berhubungan dengan sifat ilmiah atau tidak il-miah. Karena, menurut Popper, ungkapan yang tidak ilmiah,artinya: tidak ada dasar empirisnya, bisa saja amat bermakna(meaningful). Dengan demikian, sebenarnya Popper tidaklahmenolak dasar empiris sebagaimana Lingkaran Wina, hanyasaja demarkasi empiris atau tidaknya suatu ungkapan tidaklahditentukan berdasarkan asas pembenaran (verifikasi) yang di-gunakan oleh Lingkaran Wina. Asas pembenaran (verifikasi)tersebut berlandaskan pada proses ‘induksi’, jadi untuk mengo-
72Verhaak, C, dan Imam, Haryono, R., Filsafat Ilmu Pengetahuan,Telaah Atas Kerja Ilmu Ilmu, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hlm. 155-159.
92 | Win Usuluddin Bernadien
kohkan suatu pendapat atau hipotesa atau teori, kaum posi-tivisme logis berusaha untuk mencari data atau fakta sebanyakmungkin untuk membenarkan (melakukan verifikasi) penda-pat atau hipotesa atau teorinya. Popper menolak hal itu danmenggantinya dengan prinsip falsifiabilitas yang dianggapnyasebagai ciri-ciri pengetahuan ilmiah, yaitu suatu pengetahuanyang dapat dibuktikan salah (it can be falsified). Cukuplah satuobservasi terhadap seekor angsa hitam untuk menyangkal pen-dapat bahwa semua angsa berwarna putih. Menurut Popper,dengan cara itulah hukum atau teori ilmiah berlaku: bukannyadapat dibenarkan melainkan dapat dibuktikan salah. Dengancara ini pulalah ilmu pengetahuan akan dapat berkembangmaju. Dari sini, agaknya memang Popper memasukkan unsurbaru dalam filsafat ilmu, yaitu perhatian akan sejarah ilmu.Prinsip falsifiabilitas ini dapat disaksikan dengan jelas dalamsejarah ilmu-ilmu, yang menunjukkan bahwa: bukan hanyahipotesa namun juga hukum dan teori yang kalah dalam pro-ses falsifikasi akan ditinggalkan. Sebuah teori baru akan diteri-ma kalau teori tersebut dapat meruntuhkan teori lama yangada sebelumnya. Pengujian kekuatan dua teori tersebut dilaku-kan dengan suatu tes empiris, yang direncanakan untuk mem-buktikan salah apa yang diujinya (memfalsifikasi). Kalau dalamtes tersebut sebuah teori terbukti salah, maka teori tersebutdianggap batal, sedang teori yang bertahan dan lolos dalam testersebut akan diterima sampai adanya cara pengujian yanglebih ketat. Dengan demikian, pengujian yang dilakukan secaraterus menerus, menjadikan sejarah ilmu berkembang majusehingga kadar kesalahan dapat dikurangi (error elimination)sampai sejauh mungkin dan makin mendekati kebenaran ob-jektif. Keilmiahan suatu teori akan selalu bersifat sementara,hasil kemajuan ilmu selalu negatif, sedangkan hasil positif pada
Serpihan-Serpihan Filsafat | 93
dasarnya selalu bersifat sementara. Jelasnya, Popper ingin me-nggaris bawahi bahwa setiap hipotesis, teori, ataupun hukumhanya diterima sebagai kebenaran sementara, sejauh belumditemukan kesalahannya (prinsip falsifikasi), kemudian selamahipotesis, teori, ataupun hukum yang difalsifikasi tersebut be-lum ditemukan kesalahannya, maka akan mengalami pengu-kuhan (korroborasi), akhirnya apabila ditemukan hipotesa, teo-ri, atau hukum baru maka harus lebih baik daripada hipotesa,teori, atau hukum yang lama sehingga mendapat derajat pe-ngukuhan yang lebih tinggi. Ringkasnya, teori falsifikasi adalahsebuah pengandaian untuk menerima kebenaran suatu teoriatau hipotesis sebelum ditemukan kesalahannya. Hal ini berartisetiap teori atau hipotesis atau ungkapan atau pernyataan pa-da dasarnya dapat dibuktikan salah. Teori ini berfungsi untukmenentukan ilmiah-tidaknya pernyataan atau teori atau hipote-sis maupun ungkapan. Dalam pada itu bagi Popper, teori atauhipotesis tidak bersifat ilmiah karena sudah dibuktikan, melain-kan dapat diuji. Jika teori atau hipotesis setelah diuji tetaptahan maka berarti kebenarannya diperkokoh (Corroboration).Jadi, suatu teori atau hipotesis bersifat ilmiah bila ada ke-mungkinan untuk menyangkalnya, makin besar kemungkinanuntuk menyangkal sebuah teori atau hipotesis maka makin ko-kohlah kebenarannya. Inilah yang oleh Popper disebut sebagaiThe Thesis of of Refutability.
THOMAS SAMUEL KUHN (1922-1996)Perhatian terhadap sejarah ilmu tersebut memberikan
arah baru bagi perkembangan filsafat ilmu, yang kemudian di-teruskan oleh Thomas S. Kuhn, seorang filsuf ilmu dari Ame-
94 | Win Usuluddin Bernadien
rika.73
Menurut Thomas S. Kuhn, Popper telah menjungkirbalik-kan kenyataan dengan terlebih dahulu menguraikan terjadinyailmu empiris melalui jalan hipotesa yang disusul dengan falsifi-kasi, kemudian hal itu diklaim Popper sebagai ikhtisar perkem-bangan ilmu. Setelah itu barulah ia memilih beberapa contohdalam sejarah ilmu pengetahuan yang dipakainya sebagai‘bukti’ untuk mempertahankan dan membela anggapannya.Bila itu yang terjadi, maka posisi Popper sebenarnya tidakterlalu berbeda dengan Lingkaran Wina, yaitu untuk mengo-kohkan anggapannya, Popper mencari ‘bukti-bukti’ yang men-dukung anggapannya. Hal itu berarti sesungguhnya Popperjuga melakukan prinsip pembenaran (verifikasi) bukan memfa-lsifikasi anggapannya, yaitu dengan cara melakukan tes empirisyang memungkinkan anggapannya lolos uji tes. Menurut Kuhn,agar filsafat ilmu bisa semakin mendekati kenyataan ilmu danaktivitas ilmiah yang sesungguhnya, maka filsafat ilmu harusberguru pertama-tama pada sejarah ilmu sebagai titik pangkalsegala penyelidikan, bukan menetapkan ilmu empiris lebih da-hulu, baru kemudian ‘meminta’ sejarah ilmu untuk ‘mendu-kung’nya. Berdasarkan hal tersebut, Kuhn menyatakan bahwaperubahan-perubahan dalam ilmu tidaklah terjadi karena upa-ya empiris yang membuktikan salah suatu teori, melainkan ter-jadi melalui revolusi-revolusi ilmiah yang terjadi karena para-digma yang membimbing ilmu-ilmu pada masa normal (nor-mal sciences) sudah tidak mampu lagi menerangkan anomali-anomali yang terjadi pada masa normal tersebut. Revolusi ilmi-ah terjadi bila paradigma yang baru (tandingan) bisa meme-cahkan kebuntuan dan membimbing riset yang berikutnya atau
73Ali Mudhofir, op. cit., hlm. 296, Blackburn dan Yudi Santoso, op.cit., hlm. 483.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 95
dengan kata lain revolusi ilmiah bisa terjadi manakala terjadiakumulasi anomali (situation that is different form usual or ac-cepted type) sebagai bentuk krisis paradigma ilmiah. Peralihanparadigma tersebut terjadi tidak semata-mata karena alasanlogis-rasional, namun mirip dengan proses pertobatan dalamagama. Dengan begitu Kuhn juga menekankan aspek psiko-logis dan komunal dalam perkembangan ilmu pengetahuan.Karena alasan itulah maka Popper menyebut Kuhn sebagaipsychology of discovery, dan Popper menamakan posisinyasebagai logic of discovery.74
IMRE LAKATOS (1922-1974)Akhirnya seorang filsuf matematika dari Hungaria,75 Imre
Lakatos, mengkritik sekaligus ‘memperbaiki’ tokoh-tokoh di-atas. Pertama-tama Lakatos mengkritik pembedaan teori il-miah dan yang tidak ilmiah (atau pseudo ilmiah menurut istilahLakatos), dengan menyatakan bahwa falsifikasi semacam itutidaklah menentukan suatu teori ilmiah atau tidak, akan tetapilebih merupakan pembedakan antara metode ilmiah dan me-tode tidak ilmiah. Lakatos, sebagaimana yang dikutip oleh LiekWilardjo76 dari Science and Pseudo-Science (sebuah transkriphasil dari wawancara Lakatos pada sebuah radio di Jepangdalam suatu acara kuliah universitas terbuka) menjelaskan bah-wa: Sebuah teori bisa disebut ‘ilmiah’ manakala teori tersebutbersedia untuk terlebih dahulu menentukan suatu eksperimenpenting (atau observasi) yang mampu memfalsifikasi teori itu
74Verhaak, op.cit., hlm. 165-166.75Blackburn dan Yudi Santoso, op. cit., hlm. 485.76Lakatos, Science and Pseudo-Science dalam Liek Wilardjo, Diktat
Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, Program Magister Ilmu Religi danBudaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2000, hlm. 117.
96 | Win Usuluddin Bernadien
sendiri, dan sebuah teori disebut pseudo ilmiah manakala teoritersebut menolak untuk menentukan berbagai ‘kekuatan falsi-fier’. Namun demikian, kita tidak perlu membuat garis pemba-tas antara teori ilmiah dan pseudo ilmiah tetapi cukuplah me-tode ilmiah dan metode non-ilmaih saja’ (A theory is ‘scientific’if one is prepared to specify in advance a crucial experiment (orobservation) which can falsify it, and it is pseudoscientific if onerefuses to specify such a ‘potential falsifier’. But if so, we do notdemarcate scientific theories from pseudoscientific ones, butrather scientific method from non-scientific method)’. Lakatosmencontohkan bahwa Marxisme dapat bersifat ilmiah, apabilamereka dapat menyusun fakta-fakta (yang kemudian diobser-vasi) yang dapat digunakan untuk memfalsifikasi teori mereka.Akan tetapi seringkali ilmuwan bersikap ‘keras kepala’ dan‘bandel’, sehingga mereka tidak akan begitu saja meninggalkanteori mereka hanya karena adanya fakta-fakta yang menentangteorinya, mereka dapat menemukan hipotesa-hipotesa penye-lamat. Lakatos menuliskan: Scientists have thick skins. They donot abandon a theory merely because facts contradict it. Theynormally either invent some rescue hypothesis to explain whatthey then call a mere anomaly or, ...dst.77 Bagi Lakatos, bukanteori tunggal yang harus dinilai sebagai ilmiah atau tidak il-miah, melainkan rangkaian teori yang dihubungkan menjadisuatu program riset (...great scientific achievements is not anisolated hypothesis but rather a research programme). Risetprogram tersebut mempunyai lapisan inti, yang dilindungi dariancaman falsifikasi oleh suatu lapisan pelindung yang terdiriatas hipotesa pendukung, kondisi-kondisi awal dan lain seba-gainya (this hard core is tenaciously protected from refutation
77Liek Wilardjo, ibid, hlm. 117.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 97
by a vast ‘protective belt’ of auxiliary hypotheses). Selain itu,dan yang lebih penting lagi adalah bahwa suatu riset programjuga mempunyai suatu ‘heuristika’, yaitu perlengkapan untukmemecahkan suatu problem yang dibantu dengan teknik ma-tematika akan dapat mengolah anomali-anomali, bahkan men-jadikannya suatu bukti yang positif. Misalnya, para ilmuwanNewtonian akan mengecek kembali anggapan yang berhubu-ngan dengan pembiasan atmosfer atau yang berhubungan de-ngan perambatan cahaya dalam atom-atom magnetik, jikasuatu planet tidak bergerak sesuai dengan teori mereka. Mere-ka juga mungkin menemukan suatu planet yang belum dikenalsampai sekarang dan memperhitungkan posisi, kecepatan, danmasanya untuk menerangkan anomali tersebut. Lakatos me-ngemukakan: And, even more importantly, the research prog-ramme has also a ‘heuristic’, that is, a powerful problem-solvingmachinery, which, with help of sophisticated mathematical tech-niques, digests anomalies and even turns them into positive evi-dence. For instance, if a planet does not move exactly as itshould, the Newtonian scientist checks his conjecture concer-ning atmospheric refraction, concerning propagation of light inmagnetic atoms,..... He may invent a hitherto unknown planetand calculates its position, mass and velocity in order to explainanomaly.78
Berdasarkan alasan diatas, pembedaan antara yang ilmiah(atau menurut Lakatos, riset program yang progresif) dan yangtidak ilmiah (atau riset program yang merosot) bukanlah hanyakarena adanya serangkaian dugaan atau anggapan dan penya-ngkalan semata-mata tetapi bahkan semua teori berawal danberakhir dengan penyangkalan. Lakatos menulis: Science is notsimply a trial and error, a series of conjectures and refutations...
78Liek Wilardjo, ibid, hlm. 118.
98 | Win Usuluddin Bernadien
All Theories, in this sense, are born refuted and die refuted.Lebih dari itu, alasan lain yang dapat dikemukakan adalahkarena riset program dapat memprediksikan adanya fakta-faktabaru yang tak terbayangkan sebelumnya (They all predictnovel facts, facts which had been either undreamt of ...), karenadalam suatu riset program sebuah teori akan membawa padasuatu penemuan fakta baru yang sampai sekarang belumdikenal, dan sebaliknya riset program merosot, jika teori yangdisusun hanyalah digunakan untuk mengakomodasi fakta yangtelah dikenal (Thus, in a progressive research programme theo-ry leads to the discovery of hitherto unknown facts. In degene-rating programme, however, theories fabricated only in orderto accommodate known facts).79
Lakatos, dalam kaitan dengan hal di atas memberikangambaran bahwa ketika Newton mempublikasikan bukunyayang berjudul Principia, bahkan tidak dapat menjelaskan teori-nya secara tepat perihal gerakan bulan, pada kenyataannyagerakan bulan ‘menyangkal’ teori Newton. Tapi yang mem-buat teori Newton ‘bertahan’ adalah karena teori tersebutdapat memprediksikan fakta baru, sebagaimana digunakanoleh Halley untuk memperhitungkan, berdasarkan pengamatanatas ‘sepotong’ lintasan komet (yg kemudian dinamakan sesuaidengan namanya, Komet Halley), bahwa komet tersebut akankembali tujuh puluh dua tahun lagi, bahkan Halley dapatmemperhitungkan sampai ke hitungan menit dan lokasi yangtepat dimana komet tersebut akan terlihat (When Newtonpublished his Principia, it was common knowledge that it couldnot properly explain even the motion of the moon; in fact, lunarmotion refuted Newton) dan (Halley, working in Newton’sprogramme, calculated on the basis of observing a brief strech
79Liek Wilardjo, ibid, hlm. 119.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 99
of a comet’s path that it would return in seventy-two years’time: he calculated to the minute when it would be seen againat a well-defined point of sky. Contoh riset program yangmerosot adalah Marxisme, yang hanya mampu menerangkanfakta-fakta yang telah terjadi (The Newtonian programme ledto novel facts; the Marxian lagged behind the facts and hasbeen running fast to catch up with them).80
Lakatos juga mengkritik Kuhn, dengan menyatakan bah-wa bila Kuhn benar bahwa revolusi ilmiah merupakan suatuperubahan yang irasional, maka tidak ada suatu demarkasiyang jelas antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah (ataupseudo ilmiah), tidak ada perbedaan antara perkembanganilmiah dan kebusukan intelektual (But if Kuhn right, then thereis no explicit demarcation between science and pseudo science,no distinction between scientific progress and intellectual decay,...). Juga adalah merupakan revolusi ilmiah yang rasional jikapara ilmuwan lebih memilih riset program yang progresif di-bandingkan dengan riset yang merosot (If we have two rivalresearch programme, and one is progressing while the other isdegenerating, scientist tend to join the progressive programme.This is the rationale of scientific revolution).81
Selain kritik dan koreksi diatas, Lakatos juga mempunyaiposisi yang mirip dengan orang-orang yang dikritiknya di atas,dengan menyatakan bahwa nilai ilmiah dari suatu teori ituindependen dari pikiran manusia yang menciptanya atau yangmemahaminya (...scientific value of a theory is independent ofhuman mind). Namun demikian Lakatos sekaligus juga, sepertiKuhn, mengakui bahwa masalah ilmu pengetahuan bukanlahhanya urusan orang-orang filsafat akan tetapi mempunyai rele-
80Liek Wilardjo, ibid, hlm. 119.81Ibid, hlm. 120.
100 | Win Usuluddin Bernadien
vansi dan implikasi politik, sosial dan etik yang penting (...is notmerely a problem of armchair philosophy: it is of vital socialand political relevance) (is not pseudo-problem of armchair phi-losophers: it has grave ethical dan political implications).82
PENUTUP
Sebagai akhirul kalam dari tulisan ini kiranya dapat digarisbawahi bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada akhirabad XX yang sangat pesat itu agaknya telah menghadapkanmanusia pada berbagai masalah yang sebelumnya tak terba-yangkan. Berbagai persoalan tersebut agaknya pula telah me-rasuk ke setiap relung kehidupan dan saling bersilang mem-bentuk jaringan kompleks yang hampir tak memungkinkan un-tuk menghindarinya. Pandangan Aristoteles yang menyatakanbahwa baik ilmu teoritis maupun empiris adalah tidak berpam-rih sudah menjadi kuno, dan setelah itu terbitlah pan-danganbaru dari Francis Bacon yang menyatakan bahwa “Knowledgeis power”. Ilmu pengetahuan kemudian diterapkan dalam ber-bagai bidang, seperti teknik dan industri, yang dampaknya da-pat dirasakan sekarang: revolusi indusri pertama (mesin meka-nis), revolusi ke dua (listrik dan pemakaian sinar), revolusi ke-tiga (atom, komputer, chips), dan mungkin akan diteruskan kerevolusi keempat: manusia berada di pinggir kematian. Per-kembangan tersebut pada akhirnya akan berhadapan denganmatra etis: pertama, dalam diri ilmuwan yang mengembangkanilmu (dengan prinsipnya ‘lakukan apa saja sejauh mungkindilakukan’); dan kedua, dalam diri manusia lain yang beradadalam dunia modern ini (dengan prinsipnya ‘lakukan sesuatuasalkan semakin meningkatkan kemanusiaan’).83
82Ibid, hlm. 114-115, dan 121.83Verhaak, op. cit., hlm. 183.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 101
Lebih dari itu, setelah melihat perkembangan ilmu penge-tahuan pada akhir abad XX dan dampaknya, ada dua kecen-derungan yang dapat disebut: pertama, kecenderungan yangterjalin pada jantung setiap ilmu pengetahuan untuk maju terusseakan tanpa henti dan tanpa batas; kedua, kecenderunganatau hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmupengetahuan, baik dalam dunia mikro maupun makro. Duakecenderungan itulah yang harus dicermati dan disadari olehmanusia agar kecenderungan tersebut tidak digunakan untukhal-hal yang justru akan menghancurkan umat manusia sendiri(seperti perlombaan senjata), tapi tetap harus digunakan demikesejahteraan manusia sendiri. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Blackburn, Simon, 2008, The Oxford Dictionary of Philosophy,Oxford: Oxford University Press diindonesiakan oleh Yu-di Santoso, 2013, Kamus Filsafat, Yogyakarta: PustakaPelajar.
Kuhn Thomas S., 1993, Peran Paradigma Dalam RevolusiSain, penerjemah: Tjun Surjaman, Bandung: RemajaRosda Karya
Lakatos, Science and Pseudo-Science dalam Liek Wilardjo,2000, Diktat Kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, ProgramMagister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas SanataDharma, Yogyakarta.
Mudhofir, Ali, 2001, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarta: PustakaPelajar
Muhadjir, Noeng, 2001, Filsafat Ilmu: Positivisme, Post-Posi-tivisme, dan PostModernisme, Edisi II, Yogyakarta: RakeSarasin.
Mustansyir, Rizal, t.t., Materi Kuliah Filsafat Ilmu, Program S2
102 | Win Usuluddin Bernadien
Ilmu Filsafat, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.Verhaak, C, dan Imam, Haryono, R., 1992, Filsafat Ilmu
Pengetahuan, Telaah Atas Kerja Ilmu-Ilmu, Jakarta: PT.Gramedia.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 103
BAGIAN KETUJUH
SENI SENI SPIRITUALIS:MENYELAM KE DASAR PEMIKIRAN SENI
IQBAL DAN SCHUON)
PENGANTAR
Kecenderungan relijiusitas di dalam seni seyogyanya di-pandang sebagai sebuah realitas yang harus dipandang secarautuh. Sebab sesungguhnya antara seni dan agama bertaut kuatpada kedalaman jiwa dan perasaan yang sangat indah, suatuzona khusus di balik realitas alam ini. Sejujurnya memang ha-rus diakui bahwa seni-seni keislaman belum banyak disentuholeh para seniman kita untuk diberi warna seni secara ter-sendiri. Secara murni mereka masih dalam taraf pencarian atauandai pun rona-rona itu telah mereka taburkan, barulah seke-dar mengimbangi ‘pihak lain’ yang tidak diwarnai oleh nilai-nilai yang khas itu. Ataukah memang senyatanya seni itu se-
)Tulisan ini pada tahun 2002, pernah dimuat dalam Jurnal HAR-MONIA, UNESA, Semarang.
104 | Win Usuluddin Bernadien
sungguhnya merupakan ‘wilayah terlarang’ yang hanya bolehdimasuki dan dinikmati oleh sekelompok tertentu saja, sebabnyatanya hanyalah kaum sufi saja yang telah secara berhasilmenemukan keindahan ketuhanan melalui olah batini mereka.Sastra sufi merupakan titik temu yang mempertautkan duniaseni dan wilayah ketuhanan sehingga mampu memberikan se-bingkai kepuasan puncak keindahan dan kenikmatan keiman-an. Mereka kaum sufilah yang secara menggema telah mampumenggaungkan innallaha jamyl wa tuhibbu al jamaal sehinggamereka pun memiliki peran yang cukup penting dalam sejarahIslam, terutama dalam penyebaran agama Islam di berbagaibelahan di bumi.
Tulisan yang sesungguhnya merupakan saduran dari be-berapa bacaan ini,84 meskipun tidak mengungkapkan setiap sisisecara mendetail tetapi merupakan usaha untuk mencoba me-nyelami pada kedalaman dasar pemikiran dua tokoh muslimterkemuka, yaitu Muhammad Iqbal dan Frithjof Schuon, khu-susnya pemikiran mereka tentang seni.
MUHAMMAD IQBAL DAN KARYA-KARYANYA
Ada beberapa pendapat seputar hari kelahiran Iqbal. Mi-salnya saja Miss Luce-Claude Maitre menulis bahwa Iqbal lahirpada tanggal 22 Pebruari 1873 di Sialkot Punjab.Sementara ituada yang menulis bahwa Iqbal lahir di Sialkot pada tanggal 9November 1877. Sementara itu pula ada catatan lain yangmengutip tahun tahun 1876 dan 1887 adalah sebagai tahunkelahiran Iqbal. Yang jelas, seorang sarjana Pakistan yang di-nilai paling kompetens dan orotitatif mengenai Iqbal bernamaS.A. Vahid telah menetapkan tahun kelahiran Iqbal adalah
84Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberkati kepada parapenulis yang tulisannya disadur dalam tulisan ini. (pen.)
Serpihan-Serpihan Filsafat | 105
tahun 1877. Ayah Iqbal bernama Syaikh Nur Muhammad, se-orang lelaki yang cerdas, gagah, tetapi santun dan memiliki pe-rasann mistik yang luar biasa meskipun tidak pernah menge-nyam pendidikan formal. Di kalangan teman-temannya ia di-juluki Un Parh Falsafi (Si Filsuf tanpa Guru). Ibunda Iqbal ber-nama Imam Bibi seorang wanita yang sangat relijius danmemiliki kesadaran yang mendalam mengenai iman dan ihsan.Kedua orang tuanya inilah yang telah meletakkan fondasi yangkokoh bagi bangunan pemikiran Iqbal kelak.
Iqbal, meskipun leluhurnya keturunan Brahmana Kasymirtetapi keluarganya telah menganut agama Islam sejak bebera-pa generasi sebelumnya. Sang Pujangga ini mendapat pendidi-kan dasar dan menengah di Sialkot. Sejak masih belia dia me-nulis puisi. Agaknya dia bernasib baik sebab mendapatkan se-orang guru yang dapat melihat bakat kemampuannya danmemberinya semangat di setiap kesempatan, dialah SayyidMaulana Mir Hasan (1844-1929) seorang professor sastra Ti-mur pada Scotch Mission College, tokoh yang pertama kali me-ngenali bakat puisi Iqbal. Sayyid Maulana Mir Hasan memangsudah kenal ayah Iqbal, Syaikh Nur Muhammad, sejak lama.Ketika Iqbal lulus dengan pujian (cumlaude) dari sekolah me-nengah pada tahun 1892 dan memperoleh beasiawa ScotchMission College, Mir Hasan membujuk Syaikh Nur Muham-mad untuk mengizinkan Iqbal melanjutkan studinya. Oleh ka-rena itu sejak 5 Mei 1893, Iqbal secara resmi menjadi maha-siswa perguruan tinggi tersebut, dengan mengambil kuliah il-mu-ilmu humaniora. Intelektualitas Iqbal mulai berkembangpe-sat dari perguruan ini. Di bawah bimbingan Mir Hasan,Iqbal bersama-sama murid yang lain mempelajari puisi-puisiArab dan Persi. Beliau pulalah yang mengajari Iqbal cara me-nggubah puisi Klasik Urdu dan Persi. Iqbal kemudian menda-
106 | Win Usuluddin Bernadien
patkan bimbingan dari pakar puisi Urdu dan penyair yang taktertandingi, Nawab Mirza Khan Dagh (1831-1905). Bersama-nya Iqbal berada pada jalan sukses dan popularitas interna-sional.
Pada tahun 1892, ketika Iqbal belum merampungkan stu-dinya di Scotch Mission College, oleh orang tuanya dinikahkandengan Karim Bibi anak perempuan seorang dokter kaya yangtinggal di Gujarat bernama Bahadur ’Atta Muhammad Khan.Pasangan ini hidup harmonis selama lebih dari dua dasawarsadengan dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernamaMi’raj Begum (1895-1914), anak perempuan yang cerdas inimeninggal setelah sebelas kali gagal operasi akibat serangankelenjar limfa. Anak yang kedua laki-laki bernama Aftab Iqballahir pada tahun 1923 satu-satunya anak Iqbal yang hidup danberhasil memperoleh Magister Filsafat. Sedangkan anak ketigalahir pada tahun 1901 tetapi anak laki-laki ini wafat beberapawaktu berselang setelah kelahiranya. Kehidupan rumah tanggaIqbal makin tak tertahankan setalah ia dan istrinya menuaibanyak perbedaan dan akhirnya pada tahun 1916 merekapunmemutuskan untuk hidup berpisah.85
85Iqbal memiliki sahabat karib wanita yang tidak dinikahinya karenaego yang ‘harus’ dia pertahankan, namanya Faizee, seorang wanitamuslim Avant-Garde India yang dikenalnya saat studi di Eropa. Wanitalain yang pada tahun 1909 sempat dinikahinya adalah Sardar Begum,seorang wanita cantik dari keluarga terhormat Kashmir. Karena beberapahal, Iqbal menikahi wanita itu dua kali. Setelah pernikahannya yangkedua dengan wanita itu pada tahun 1913 Iqbal dikaruniai seorang putrabernama Javid Iqbal (lahir 1924), dan seorang putri bernama Munirah(lahir 1930). Seperti juga ayahnya Javid memperoleh gelar Doktor dariUniversitas Cambridge, dan menjadi pengacara di Lahore, setelah men-dapatkannya dari Lincoln’s Inn London. Sardar Begum memberi kepadaIqbal cinta, kedamaian, dan pengabdian hingga wanita itu meninggalpada 23 Mei 1935.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 107
Pada tahun 1895 Iqbal pindah ke Lahore dan memasukiGovernment College. Dengan wawasan dan pengalaman inte-lektualitasnya, dari Government College, Iqbal secara perla-han-lahan menggantikan bahasa Persi dengan bahasa Urdu diseluruh India. Di Lahore ia berkenalan dengan seorang misio-naris Barat yang monumental yang kemudian masuk Islam danmenjadi gurunya. Professor filsafat modern terkemuka itu ber-nama Sir Thomas Arnold. Bila Mir Hasan telah mengajarinyaesensi kebudayaan Islam, maka Sir Thomas Arnold mengenal-kan kepadanya kesusasteraan dan pemikiran Barat. Dalam diriArnold, Iqbal mendapatkan sosok guru yang patut dicintai,yang telah memadukan dalam dirinya pengetahuan yang luastentang filsafat Barat dan pengertian mendalam atas kebudaya-an Islam dan kesusasteraan Arab. Arnold jugalah yang men-dorong Iqbal untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggidi Eropa. Maka selama tiga tahun sejak 1905, ia melanjutkanstudinya di Eropa. Masa tiga tahun ini merupakan masa yangcukup penting dan menentukan bagi perkembangan pemiki-ran-nya. Di Cambridge ia belajar kesusasteraan Persi di bawahbimbingan dua orang orientalis, yaitu E.G. Browne dan Rey-nold A. Nicholson, juga filsafat di bawah bimbingan ProfessorJohn Mac Taggart dan James Ward, lalu memperoleh gelardoktor bidang filsafat dictoris philsiphiae gradum pada 4 No-vember 1907 di Universitas Munich dengan judul disertasi TheDevelopment of Metaphysics in Persi. Disertasi ini diterbitkan diLondon dan dipersembahkan untuk Sir Thomas W. Arnold. DiUniversitas London ia ditunjuk sebagai guru besar bidang ba-hasa Arab, tetapi enam bulan kemudian ia meletakkannya un-tuk kemudian mengabdikan diri dalam bidang hukum. Iqbaladalah seorang jenius yang memiliki kecakapan tak tertandingi,filsuf, ahli bahasa, ahli hukum, guru, politisi, penyair, dan pe-
108 | Win Usuluddin Bernadien
nulis prosa. Sajak-sajaknya banyak ditulis dalam dua bahasa,yaitu Inggris dan Urdu dengan subjek filsafat, sastra, politik,dan ekonomi.
Ada satu keputusan penting dalam perkembangan puisi-nya selama di Eropa, yaitu beralih dari bahasa Urdu ke bahasaPersi. Iqbal merasa bahasa Persi merupakan media yang palingsesuai bagi pengungkapan inspirasi puitisnya.
Tahun 1915 Iqbal menerbitkan magnum opusnya berju-dul Rahasia Diri (The Secret of the Self atau Asrar-i-Khudi), diLahore. Ia pun menjelaskan kepindahannya dari bahasa Urduke bahasa Persi86 dengan untaian kata-kata berikut ini:
Puitisasi bukanlah tujuan matsnawi iniPemujaan keindahan ataupun pernyataan cinta bukantujuannya.Aku orang India: Persi bukanlah bahasa ibuku;Aku ini bagai bulan sabit: cawanku belum lagi penuh.Jangan cari keindahan gaya dalam pengungkapan,
86Mengutip Sadiq dalam A History of Urdu Literature, Hafeez Malikdalam Ihsan Ali Fauzi dan Nurul Agustina (ed.), menjelaskan bahwa parakritikus sastra Urdu tidak sependapat dengan Iqbal yang memandang ba-hasa Urdu tidak memadai ‘bagi beban ketegangan perasaan dan imaji-nasinya’ karena ‘beberapa puisi dalam Bang-i-Dara adalah bukti salah-nya pandangan itu’. Kemungkinan Iqbal menginginkan publik pembacayang lebih luas ketimbang masyarakat Muslim berbahasa Urdu di Indiasaja, dan baginya bahasa Urdu adalah bahasa pengantar di dunia Islam.Dan memang nyatanya peralihannya ke bahasa Persi telah memungkin-kannya untuk mendapat banyak pengikut di dunia Islam, terbukti hampirtak satupun negara Islam di dunia yang tak menerbitkan karyanya, baikdalam bahasa asli maupun dalam terjemahannya ke bahasa setempat.Selbihnya silahkan baca: Malik, Hafeez dan P. Lynda. Malik, 1992,Filosof-Penyair dari Sialkot, dalam Ihsan Ali Fauzi&Nurul Agustina (ed.),Sisi Manusiawi Iqbal, Bandung: Mizan, hlm. 34.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 109
Jangan cari dalam diriku, Khansar87dan IsfahanMeski bahasa India semanis gula, Yang lebih manisadalah tutur kata Persi.Benakku terpaku oleh keindahannya.Penaku menjadi ranting kecil di tengah Semak ter-bakar,Karena pikiranku yang anggun, hanya Persi yang se-suai untuknya.Duhai pembaca! jangan salah menilai cawan anggur,Tapi timbanglah dengan cermat rasa anggur itu.88
Asrar-i-Khudi berisi gambaran tentang tema sentral filsafatIqbal yang begitu orisinal dan memiliki kekuatan sehingga Pro-fessor Reynold A. Nicholson pun menerjemahkannya ke dalambahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1920. Karya Iqballainnya yang bertemakan filsafat adalah berjudul Rumuz-i-Be-khudi (Misteri Peniadaan Diri) terbit tahun 1918, berisi imbau-an untuk peningkatan individu yang ditujukan pada kebangkit-an kembali setiap insan dalam suatu masyarakat Islami yangsejati. Sementara itu Bang-i-Dara (Pangilan Lonceng) adalahkaryanya yang berisi kumpulan sajak berbahasa Urdu. Karyaini menampakkan Iqbal dalam bingkai yang penuh keseimba-ngan antara sosok penyair dan filsuf. Karya lain yang memper-lihatkan kecakapan tingkat tinggi dan penguasaan yang sem-purna dalam berbahasa terbit pada tahun 1823, karya ini ber-judul Payam-i-Masyriq (Risalah Timur) dan ditulis sebagai pa-sangan Divan-nya Goethe, berisi kumpulan sajak berbahasa
87Nama sebuah kota yang berada pada jarak sekitar seratus kilo-meter arah Barat Laut kota Isfahan tempat kelahiran para penyair Persi.(pen.)
88Hafeez dan Lynda, ibid, hlm. 32.
110 | Win Usuluddin Bernadien
Persi. Setelah terbit Zabur-i-Ajam (Kidung Persi), Iqbal kembalimenghasilkan karya besar yang ia sebut sebagai ‘buku yang tu-run dari langit yang lain’ berjudul Javid Nama (Kitab Keabadi-an) yang merupakan Divine Comedia dari Timur. Tahun 1935dan 1936 menerbitkan dua kumpulan sajak berbahasa Urdumasing-masing berjudul Bal-i-Jibril (Sayab Jibril) dan Zarb-i-Kalim(Tongkat Musa). Kumpulan sajaknya yang berbahasa Ur-du dan Persi yang terakhir dan diterbitkan setelah kemangkat-annya berjudul Armughan-i-Hijaz (Pemberian dari Hijaz).
Iqbal menerima gelar kebangsawanan pada tahun 1922.Pada tahun 1926 menulis serangkaian teks ceramah yang di-ter-jemahkan ke dalam bahasa Inggris berjudul Reconstructionof Religious Thuogh in Islam. Sebenarnya Iqbal merasa tidakbe-gitu akrab dengan politik, akan tetapi terkadang terseretjuga ke dalam kancah politik. Setahun setelah kehadirannya diInggris, All-India Muslim League berdiri di India. Dua tahun ke-mudian (Mei 1908) di London dibuka British Committee ofthe All-India Muslim League di bawah pimpinan Sayyid AmirAly, seorang mantan hakim di Pengadilan Tinggi Calcutta danpenulis beberapa studi ilmiah mengenai hukum dan sejarahIslam, diantaranya berjudul The Spirit of Islam dan A Historyof Saracens.89 Tiga bulan sebelum meninggalkan Inggris, Iqbalterpilih sebagai anggota komite eksekutif, dan bersama SayyidHassan Bilgrami serta Sayyid Amir Aly dicalonkan sebagaianggota subkomite yang akan membuat rancangan peraturanKomite Liga Muslim India di Inggris. Sesampai di negeri India,lalu terpilih menjadi anggota Majelis Legislatif Punjab padatahun 1927, dan pada tahun 1930 terpilih sebagai Presiden si-dang tahunan Liga Muslimin. Tak pelak Iqbal pun ambil ba-
89Ibid, hlm. 36.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 111
gian dalam kehidupan politik di negerinya. Dalam periodisasiinilah ia merencanakan pemecahan persoalan bagi permasa-lahan politik di India, mendukung gagasan sebuah Negara Is-lam di Timur Laut India. Sejak itulah para pendukung Pakistanmenganggapnya sebagai pemimpin mereka. Tahun 1932 iaikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di London sebagaianggota delegasi. Konferensi ini merencanakan pembentukanpemerintahan yang konstitusional di India. Pada tahun 1932ini pula mengetuai Konferensi Islam. Tahun 1935 memperolehgelar Doktor bidang Kesusasteraan dari Universitas Punjab.
Sejalan dengan perjalanan waktu, seiring dengan semakinmenurunnya kesehatan dan usia yang semakin senja, padatanggal 21 April 1938, Tuhan ‘Azza wa Jalla berkenan mema-nggil Iqbal ke haribaan-Nya. Saat ajal menjelang, dengan bibirtersenyum, Iqbal mengucapkan kata-kata Rumi, gurunya:90
Telah beta lungsurkan sifat-sifat binatang,dan betapun menjadi oranglalu mengapa beta harus takut menyusutketika ajal kematian datang menjemput
Inilah untaian kata-kata sang penyair yang sempat ditulisbeberapa saat sebelum dia mangkat pulang ke pangkuanabadi Sang Kekasih:
Bila beta telah pergi meninggalkan dunia ini,Tiap orang kan berkata ia telah mengenal beta,Tapi sebenarnya tak seorangpun kenal kelana ini,Apa yang ia katakan, siapa yang ia ajak bicara, dandari mana ia datang
90Miss Luce-Claude Maitre, 1981, Introduction to the Thought ofIqbal, diindonesiakan oleh Johan Effendi Pengantar ke Pemikiran Iqbal,hlm. 18-19.
112 | Win Usuluddin Bernadien
Iqbal memang telah pergi mendahului kita, namun takbisa disangkal bahwa dia semakin terkenal dan dipuja.
Apakah kau sekedar butiran debu?Kencangkan simpul pribadimu, pegang selalu wujudmuyang alit,Betapa keagungan memulas pribadi seseorang,Dan menguji kilau cahayanya di kehadiran surya,Lalu pahatkan kembali rangka lama kepunyaanmu,Dan bangunlah wujud baru, wujud yang bukan semu,Atau pribadimu cuma lingkaran asap
(Javid Nama)Kenali dirimu baik-baik!Kaulah bunga alam semesta, Kaulah sari pati bangsaWahai insan! Kau adalah murid mata dunia
(Ghalib)
IQBAL DAN PEMIKIRAN SENINYA
Fungsi seni dalam kehidupan sosial dapat berperan seba-gai alat untuk perubahan, baik berubahan sosial, budaya, maupun politik. Seni juga dapat bermain sebagai pemacu prosesperkembangan peradaban. Dalam pada itu, setiap kita barang-kali sepakat bahwa ekspresi seseorang tentang seni tidak akanterlepas dari karakter dan pengalaman yang tercermin dan di-peroleh sepanjang kehidupan seseorang itu, artinya lingkunganseseorang akan banyak mempengaruhi nafas dan jiwa seninya,dan harus diakui bahwa jiwa seseorang, apalagi jiwa seorangseniman yang pada umumnya memang sangat peka, sangatdipengaruhi oleh setting sosial tempat mereka hidup dan bera-da. Dengan kata lain, ekspresi seni seseorang itu pada dasar-nya adalah tanggapan atas impresi lingkungan sosial merekayang pada gilirannya akan menentukan nafas, jiwa, dan struk-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 113
tur seninya. Demikian pula dengan Iqbal, pandangan seninya,atau lebih tepatnya doktrin keseniannya, merupakan cerminankepribadiannya yang sudah barang tentu banyak dipengaruhioleh kondisi dan suituasi sosial yang berlangsung di kala masahidupnya. Pada sudut tertentu, pandangannya terhadap senijelas merupakan gambaran yang mencerminkan situasi masya-rakat yang baru keluar dari masa kemundurun. Dan inilah satuhal yang memang dicita-citakan oleh Iqbal, lewat puisi-puisi-nya, bangkit dan keluar dari masa kemunduran, sebagaimanayang ia tuliskan dalam prologue Asrar-i-Khudi, berikut:
....Dengan mata yang cerah dan rangkum alamPandanglah dunia,Dan bangunlah!Bangunlah dari tidur lelapBangunglah dari lena sekejapBangkitlah!Bangunlah dari lena sekejapBangkitlah!
Dalam kaitannya dengan pandangan Iqbal terhadap seni,ada satu hal yang mesti harus dimengerti bahwa pandanganseninya itu tidak terlepas pula dari pandangan filsafatnya. Fil-safat Iqbal adalah filsafat yang mampu menyingkap gambaranmasa depan secara menakjubkan. Ia memerdekakan manusiadengan mengajarkan: bagaimana menjadi tuan bagi nasibnyasendiri. “Mawar-mawar yang belum mekar tersembunyi dalamjubahku” ujar sang filsuf penyair itu suatu ketika, dan kini ma-war-mawar itu telah mekar terangkai begitu indahnya. Me-mang, bagi Iqbal puisi merupakan lingkaran cahaya dalam fil-safat yang sesungguhnya. Padahal, puisi dan filsafat oleh ba-nyak kalangan dinilai sebagai dua hal yang memiliki wilayahintelektual yang tidak sama dalam diri manusia, dua hal yang
114 | Win Usuluddin Bernadien
sangat kontradiktif. Puisi berada dalam wilayah ‘rasa’ yangspontan, halus, melodis dengan media spiritual yang tak mu-dah terungkap lewat mediasi prosa, sedangkan filsafat beradapada wilayah rasional yang kering, dingin, tanpa emosi, danlogis. Namun demikian, nyatanya Iqbal mampu memadukankeduanya. Filsafat Iqbal mampu merengkuh mesra puisi danterpadu dalam paduan karakter yang sangat mulia. Dalam diriIqbal tercatat prestasi yang luar biasa. Jika filsafat dikatakanberasal dari dan berada dalam pikiran sementara kedudukanpuisi berada dalam kalbu, maka Iqbal mampu menciptakanlingkaran yang melingkup keduanya dan bisa saling menam-bah serta melengkapi sehingga terciptalah puisi filsafat yangberkelas tinggi.
Pandangan seni Iqbal nampaknya memang sejalan deng-an filosofinya yang dinamis dan penuh vitalitas. Iqbal mampumemanfaatkan kekuatan ‘intuisi massa’ yang terpendam dalammasyarakat muslim dan dibimbingnya menuju ke arah kese-jahteraan umat manusia. Ia yakin bahwa kehidupan umat ma-nusia itu sesungguhnya dipenuhi dengan berbagai kemungkin-an yang tak terbatas, bahwa manakala manusia mau danmampu menggunakan kekuatan yang ada dalam dirinya (khu-di) maka akan memperoleh kekuasaan atas alam semesta. Ke-yakinannya itu ia tuangkan dalam bingkai media puisi, bukanmelalui logika ataupun diskusi rasional. Baginya perasaan pui-tis memiliki kekuatan daya tembus yang sanggup merasuk kedalam relung hati yang paling dalam dan pada saatnya akanmuncul sebagai ‘kesatuan spiritual’ yang dahsyat untuk menca-pai ide-ide mulia, dan memang Iqbal mampu membuktikan di-rinya sebagai seorang seniman yang memiliki kekuatan untukmembuat orang lain ikut merasakan tingkat intuisi dalam pe-ngalaman penghayatan pentingnya. Ia mendasarkan seninya
Serpihan-Serpihan Filsafat | 115
pada perhatiannya terhadap kehidupan manusia secara luas.Baginya, dogma Victor Hugo: seni untuk seni adalah keboho-ngan yang menipu dan mengajak manusia kepada kemerosot-an kehidupan. Seni bukanlah semacam tempat pelarian darikenyataan hidup, tetapi seni itu merupakan bagian dari kehi-dupan dan kepribadian. Seni adalah cerminan citra gerakan-jiwa yang ideal dalam cinta yang mengungkapkan dirinyasebagai kesatuan dari kehidupan dan kekuatan. Oleh karenaitu fungsi dan tujuan seniman sejati adalah mengekspresikanbentuk seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Muraqqa-i-Chugtal, dalam Asif Iqbal: 111-112). Iqbal telah membawaangin perubahan untuk keluar dari menara gading estetikayang telah menjadi tempat hidup bagi penyair-penyair Urdudari generasi ke generasi seperti dalam surga orang-orang tolol,sementara perubahan sosial dan politik besar-besaran terjadi disekitar mereka.91 Dengan ketetapan hati yang kokoh, Iqbal me-ngangkat syair Urdu dari lubang kemerosotan. Baginya tujuanseni, termasuk syair, adalah memperkaya kehidupan dan dirimanusia. Seni yang gagal memberikan sumbangan kelengkap-an dan kebenaran hidup, maka seni tersebut tidak memiliki artiapa-apa bagi kehidupan. Fungsi utama seni bukan saja kese-nangan atau kegembiraan akan tetapi fungsinya berperan se-bagai media pengembang sikap yang penuh dengan vitalitasdan dinamis. Seni, terutama puisi dan kesusasteraan, adalahalat yang berfungsi untuk memberikan kekuatan hidup yangmempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan. Seni ternyata tidak ter-lepas dari kehidupan oleh karena itu seniman harus selalumendekati kehidupan. Hanya dengan menjadi orang yang me-miliki kekuatan kehidupan, seniman dapat mengekspresi-kanpengalaman hidupnya dengan perasaan yang dirasakan. Seni
91Hafeez dan Linda, op.cit., hlm. 346.
116 | Win Usuluddin Bernadien
akan mengalami kemerosotan apabila terlepas dari kenyataankehidupan manusia sebagai pencipta dan pelaku seni, sebabsesungguhnya seni bukanlah hayalan semu semata. Justru le-wat senilah seorang seniman (seharusnya) menemukan duniabaru dalam kenyataan biasa yang terjadi dalam hidupnya,yang akan ia tampilkan melalui pengalaman intuitifnya dalamrealitas yang hidup dan kreatif. Dalam ekspresi seni semacaminilah kebenaran dan keindahan akan berpadu mesra seakantanpa batas.
Iqbal menolak ‘seni untuk seni’ dan mendukung ‘seni un-tuk kehidupan’. Ia mengkritik pandangan Plato tentang seniyang menganggap imajinasi untuk imajinasi, dari bayanganuntuk bayangan, dan dari illusi untuk illusi. Ia mencela ingatanspiritual dan kepasifan moral yang dibangkitkan dari duniahayali utopis. Baginya, seni itu tidak bisa menjadi tiruan daritiruan. Tujuan seni adalah menciptakan masyarakat yang majudan sehat dalam perspektif dasar sejarah realistis yang sesuaidengan kenyataan hidup. Tegasnya, tujuan seni adalah hidupitu sendiri. Seni harus menciptakan kerinduan kepada hidupyang abadi, karena itu seniman haruslah mampu membangunkepribadian, pelopor fajar kebangkitan dan harus mampu me-mompa semangat kejantanan dan keberanian menuju kema-juan sosial. Fungsi sejati seni adalah menghidupkan gairah ke-hidupan. Seniman yang sejati adalah seniman yang dirahmatiTuhan dan menjadi teman kerja-Nya, seniman yang sebenar-nya adalah seniman yang bertujuan mencapai asimilasi sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya dan mampu memberi aspirasi takterbatas kepada sesamanya. Lewat seni, Iqbal ingin mencapaiide renaissance kebudayaan Islam. Itulah beberapa fungsi dantujuan seni dalam pemikiran Iqbal.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 117
Dalam sebuah tulisannya yang berjudul About Iqbal andHis Thought, M. M. Syarif menuliskan bahwa Iqbal adalah se-orang seniman ekspresionis. Sebagaimana dipahami bahwadoktrin seni ekspresionis memiliki empat bagian pokok, perta-ma: seni adalah aktivitas yang mandiri dan steril dari segalamacam etis, kedua: seni adalah aktivitas yang tidak sama de-ngan kegiatan intelek, ketiga: seni adalah aktivitas yang diten-tukan oleh perkembangan kepribadian pemiliknya (seniman),keempat: apresiasi adalah penghidupan kembali pengalamanseniman dalam diri penanggap. Dalam kaitan ini, Iqbal menen-tang doktrin pertama sebab baginya seni itu berada di bawahnaungan moralitas bukan merupakan wilayah yang steril dariberbagai macam etis. Dalam pada itu sebagaimana yang ia tu-liskan dalam Reconstruction of Thought in Islam, ia mendu-kung doktrin kedua sepanjang doktrin itu membawakan pan-dangan bahwa kerja intelek bersifat memotong-motong; danmenangkap Hakikat hanya sepotong-sepotong, sedangkan in-tuisi menangkap keseluruhan. Iqbal sependapat dengan Berg-son yang menempatkan intuisi sebagai bentuk yang lebih tinggidari pada intelek. Terhadap doktrin ketiga dan keempat Iqbalsepenuhnya setuju sebab memang baginya seni adalah ekpre-si-diri sang seniman. Dari posisi ini kita dapat melihat Iqbal se-bagai seorang ekpresionis.
Nampak jelas bahwa Iqbal, di satu sisi menempatkan senidi bawah moralitas dan pada sisi yang lain menganggap senisebagi ekspresi-diri sang seniman. Sebagai bawahan moral,baginya tak satupun yang bisa disebut dengan seni jika sesuatuitu tak mampu menimbul nilai-nilai cemerlang dan mencipta-kan harapan baru kerinduan dan aspirasi baru bagi peningkat-an hidup manusia, betapapun ekpresifnya kepribadian seni-man itu. Pada sisi yang lain, setiap karya yang mengekspresi-
118 | Win Usuluddin Bernadien
kan kepribadian seniman tentulah secara moral baik, jelek,atau biasa saja adalah karya seni yang seseungguhnya. Bisajadi, baris-baris syair yang tidak puitis dilihat dari sisi panda-ngan fungsionalisme vitalistis Iqbal, akan tetapi merupakanpuisi yang bernilai tinggi dari sisi ekspresionismenya sebagaiteori seni.
Iqbal telah menempatkan seni pada jalan yang benar,yakni ke arah pencapaian kehidupan dan pemikiran yang pa-ling tinggi. Dengan tuntunannya, ia telah mengantarkan kitamelewati jalan panjang. Kemudian ia ‘meninggalkan’ kita se-raya berkata:
Janganlah berhenti, teruslah berjalan.Engkau mencapai tingkat demi tingkatan.Jangan berhenti diantara salah satu tingkatan itu,Ambillah selalu yang paling akhir,Teruslah mendaki dan mendaki hingga ke ketinggian yanglebih tinggi dan lebih tinggi lagi.
FRITHJOF SCHUON DAN KARYA-KARYANYA
Frithjof Schuon, yang berganti namanya menjadi Muham-mad Isa Nuruddin setelah memeluk agama Islam, lahir di BasleSwitzerland pada tanggal 18 Juni 1907. Ayahnya seorang pe-musik biola konser keturunan Jerman Selatan yang sangat me-minati sastra dan bergelut dalam kehidupan spiritual. Dia ada-lah figur ayah yang banyak mewariskan inspirasi dan gairahspiritual pada diri Schuon, setelah dewasa kelak. Ibunya ada-lah seorang keturunan dari keluarga Altasia yang telah pindahke Mulhouse Perancis sepeninggal suaminya itu. Di kota inilahSchuon melanjutkan pendidikan formalnya hingga perguruantinggi, setelah mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman.Tak heran bila ia mampu menguasai dua bahasa itu secara fa-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 119
sih yang kelak sangat membantunya untuk dapat membacadengan serius karya-karya metafisika filsuf kedua negeri terse-but, bahkan mampu mengartikulasikan kembali hasil bacaan-nya itu ke dalam bentuk buku-buku dalam kedua bahasa itusecara lancar.
Dengan berbekal minat yang begitu besar pada pelacakankebenaran metafisika ‘warisan’ ayahnya, Schuon mampu mencermati secara serius atas karya-karya besar seperti Upanishaddan Bhagavat Gita, juga karya-karya besar filsuf Perancis se-perti Rene Gueneon, sehingga benar-benar semakin menguat-kan intuisi intelektualnya. Dia adalah sosok yang gemar mela-kukan penelusuran literatur dan perjalanan ke berbagai tempatpenting di dunia sehingga menyebabkan ia memiliki kontaklangsung dengan berbagai otoritas spiritual serta menyaksikanberbagai budaya di berbagai tempat yang ia kunjungi.
Setelah satu setengah tahun mengabdikan diri kepadaangkatan bersenjata Perancis, Schuon mengundurkan diri danbekerja sebagai desainer pakaian sambil belajar bahasa Arabpada sekolah-sekolah masjid di Perancis. Di samping itu iapunsecara lebih mendalam semakin menekuni seni tradisional Pe-rancis sehingga semakin implikatif antara apa yang ia pelajaridi masa mudanya dulu dan yang ia temukan saat di Peranciskini. Pada tahun 1932, ia sempat menjalani perjalanan ke Al-geria yang mengantarkannya pada puncak pertumbuhan inte-lektual dan keakraban artistik dunia tradisional. Di sanalah iabertemu dengan Syaikh Ahmad al ’Alawi, seorang pemimpinsufi yang darinya ia cerap banyak wawasan dan pemikiran spi-ritualnya. Pada tahun 1935, ia lalu mengadakan perjalanan keMarokko Afrika Utara, dan pada tahun 1938-1939 ke Mesiryang menyebabkan ia bertemu dengan Rene Gueneon se-orang tokoh yang telah lama dikaguminya. Pertemuan dengan
120 | Win Usuluddin Bernadien
sang tokoh ini pun berlanjut dengan saling berkirim surat yangberlangsung hingga tahun 1950-an. Pada tahun 1939 ia ber-kunjung ke India, tetapi perang dunia kedua telah memaksa-nya kembali ke Eropa dan mengulangi pengabdiannya yangkedua kepada militer Perancis bahkan sempat menjadi tawan-an Jerman. Ia pun lalu mencari suaka ke Switzerland untukmendapatkan status kewarganegaraan dan tinggal di sana se-lama lebih kurang empat puluh tahun dengan penuh wibawasebagai pemikir terkenal, baik di mata orang Timur maupunorang Barat sendiri.
Schuon menikah dengan seorang wanita keturunan Jer-man-Swiss, wanita pelukis berbakat yang memiliki minat tinggiterhadap agama dan metafisika. Pucuk dicinta ulam pun tiba,pasangan harmonis ini merengkuh kebahagiaan mendalamkarena selalu seiring dan sejalan. Berkat istrinya ini Schuon se-makin produktif menulis dan bersamanya pula ia semakinsering menjalani ziarah spiritual. Pada tahun 1959-1963 ia me-nerima undangan dari koleganya yang berasal dari suku Siouxdan Crow di Amerika Barat. Bersama isterinya, selama kurunwaktu empat tahun itu ia menyaksikan berbagai aspek tradisisakral suku-suku daratan tersebut dan secara sungguh-sungguhmempelajari dan menghayati kebudayaan keluarga-keluargaIndia itu, terutama keluarga James Red Cloud, kepala sukuSioux, dan keluarga Thomas Yellowtail, kepala suku Crowyang memiliki masyarakat dengan tradisi tari-tarian dan pengo-batan. Seluruh rekaman ziarah spiritualnya itu ia tuangkan da-lam beberapa karya khusus yang berkisah tentang cara hidupdan ritus pokok reliji Indian, serta keindahan berbagai lukisanartistik. Ziarah spiritualnya di Negeri Indian itu, secara intelek-tual telah semakin memperkokoh keyakinannya akan pertalianyang kuat (afinity) antara spiritualitas Indian dengan universali-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 121
tas spiritual esoteris. Bersama isterinya pula, pada tahun 1969,Schuon menjalani ziarah spiritual ke Andalusia dan singgahpula ke kediaman Sang Perawan Suci di Ephesus. Pada tahun1980, mereka beremigrasi dan menetap di Amerika Serikatseraya tetap aktif menulis. Frithjof Schuon, sang MuhammadIsa Nuruddin pulang ke rahmatullah dengan tenang di sanapada tahun 1998. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
Seluruh karya-karya Schuon selalu memancarkan univer-salitas inteletektual dan esetoris spiritual yang tercermin sebagaicitra indah pengalaman peziarahan spiritualnya. Satu di antarapengalamannya ialah saat ia bertemu dengan seorang tuaNegro dan sangat dihormati di komunitas masyarakat AfrikaSinegal yang singgah ke Switzerland. Darinya Schuon menda-patkan jawaban bahwa: ‘Tuhan adalah pusat, dan semua ber-gerak menuju kepada-Nya’. Karyanya yang berjudul Islam andthe Perennial Philosophy92 mengetengahkan persoalan menge-
92Buku ini diberi kata pengantar oleh Sayyed Hosen Nashr danditerbitkan oleh World of Islam Festival Publishing Company, Ltd., padatahun 1976. Karya ini pada tahun 1993 telah diterjemahkan ke dalamBahasa Indonsia oleh Rahmani Astuti dengan judul Islam dan Filsafat Pe-renial diterbitkan di Bandung oleh penerbit Mizan. Dalam kata pengantaritu Sayyed Hosen Nashr mengatakan bahwa Leibniz memang telahmenggunakan istilah the Perennial Philosophy tersebut sebagai metodepencarian jejak-jejak kebenaran di kalangan para filsuf masa-masa ter-dahulu, dan pembicaraan tentang pemisahan antara yang terang danyang gelap. Akan tetapi, sesungguhnya jauh sebelum Leibniz bahkan se-belum Steuchus, seorang filsuf muslim Persi yang hidup pada tahun 932-1030 M bernama Ibnu Maskawaih telah mengenalkan Javidan Khiradyang dalam bahasa Arab berarti al-Hikmat al-Khalida yang artinya DePerenni Philosophia (Steuchus), Filsafat Perenial. Maskawaih dalam kar-yanya itu mengulas berbagai pemikiran para filsuf suci Persi Kuno, India,dan Romawi. Lebih jauh, sebenarnya ratusan tahun sebelum Maska-waih, para pemeluk Hindu Vedanta telah menghayati Sanatana Dharma‘agama abadi’. Doktrin tersebut kemudian menjadi fundamen filsafat
122 | Win Usuluddin Bernadien
nai Tuhan, manusia, dan alam dalam kerangka spiritualitasuniversal dan relijiusitas transhistoris. Tentang philosophia pe-rennis didefinisikan Schuon dalam karyanya yang berjudulEchoes of Perennal Wisdom (1992) sebagai ‘Pengetahuan mis-tik universal yang telah ada sejak dulu dan akan selalu hidupuntuk selamanya’ (the universal Gnonis which always hasexisted and always will exist). Scientia Sacra, demikian SayyedHosen Nashr menyebut filsafat perenial, merupakan sebuahistilah yang menggambarkan perspektif tradisionalis yang diBarat mulai bergaung pada awal abad XX lewat karya-karyaRene Gueneon dan seorang profesor Orientalis bernamaAnanda Comaraswamy. Istilah ini diduga digunakan pertamakali oleh Agustinus Steuchus (1497-1548) untuk judul sebuahbukunya De Perennia Philosophia (1540).
Karya Schuon yang lain berjudul The Transfiguration ofMan, berisi refleksinya yang terus mengembangkan wawasanspiritualitas dan kerja intelektual dengan sikap sadar dan kritisdalam rangka menemukan hakikat diri manusia. Penemuan inidilakukan lewat pencariannya dalam tradisi filsafat perenial,sebab baginya tak ada filsafat kecuali satu filsafat tunggal dansatu-satunya agama yang memiliki integritas tinggi, yaitu So-phia Perennis. Ia sangat yakin hanya dengan filsafat perenialsajalah manusia bisa memahami kompleksitas diferensiasiyang ada di antara tradisi dan agama yang berlainan. Schuonagaknya memang terlahir untuk menjadi seorang manusia bi-jak, seorang Gnostik, seorang Sufi, yang mampu mengaktuali-
perenial yang banyak ditemukan dalam tradisi Yunani Klasik (Plato),juga dalam tradisi Kristiani lewat mistikus dan teolog Jerman terkemuka:Miester Eckhart. Pandangan yang secara tradisional dipelihara sebagaipedoman dan pegangan hidup ini, dalam Islam dikenal dengan istilah‘Sufi’ dan ‘Gnostis’ dalam tradisi Kristiani. (pen.)
Serpihan-Serpihan Filsafat | 123
sasikan semua kekayaan batinnya, yang lahir ke alam nyata.
SCHUON DAN PEMIKIRAN SENINYA
Pemikiran Schuon mengenai seni tidak terlepas dari carapandangnya terhadap manusia. Ia meyakini bahwa manusiaitu adalah homo sapien, yaitu makhluk yang memiliki kemam-puan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan. Ia juga yakinbahwa manusia adalah homo faber, yaitu makhluk yang me-miliki kapasitas mental dan kemampuan mencipta baik berupaalat-alat praktis teknis maupun kreasi artistik. Karena daya ar-tistiknya inilah maka seringkali pula manusia disebut sebagaimakhluk berkesenian, dengan objek dan inspirasi utama alamraya. Sejalan dengan itu, tidaklah mengherankan manakalamanusia seringkali ‘menjiplak’ alam untuk menciptakan karya-karya seninya. Dari sisi spiritual hal ini dapat dipahami sebabsecara hakiki manusia itu tercipta dari ‘Citra Tuhan’, dan ka-renanya manusia memiliki kapasitas dan hak untuk mencip-ta.93 Namun seringkali hal ini dimengerti secara berlebihanoleh para naturalis, seolah-olah merekalah yang mempunyaiseni yang bernilai estetik paling mutlak. Padahal hal itulahyang justru mengantarkan mereka pada ‘titik kematian’ dima-na karya mereka tak lagi berguna apalagi bernilai spiritual.Toh, mereka tidak akan pernah mampu menghidupkan lukisandan patung-patung manusia yang mereka ciptakan, sebab me-
93Dari sini nampak jelas perbedaan antara daya cipta manusia dandaya cipta Tuhan. Manusia menciptakan sesuatu, termasuk seni, dari se-suatu yang telah ada lalu dicipta menjadi sesuatu yang baru, sedangkanTuhan menciptakan sesuatu dari yang belum ada sebelumnya (creatio exnihilo) menjadi sesuatu yang baru melalui proses yang telah ditentukan-Nya (Sunnatullah) sehingga hasil kreasi manusia sampai kapanpun danbagaimanapun juga tidak akan pernah sama dengan hasil kreasi Tuhan.Wallahu a’lam bi al shawab.
124 | Win Usuluddin Bernadien
mang mereka tidak mampu menghidupkan tubuh-tubuh yangtak bernyawa. Seni naturalistik total memang sering meng-abaikan sisi-sisi spiritual sehingga tidak ada yang sakral dan taklagi memiliki binar ‘cahaya’, dan oleh karenanya efek ‘keda-laman’ seni naturalistik tinggal menjadi model tanpa maknaapa-apa.
Sebuah karya seni dianggap ‘valid’ bukan karena kemam-puan senimannya menjiplak alam, akan tetapi lebih karena iamampu menerjemahkan apa yang ia pahami ke dalam satubahasa yang baru. Karya seni juga dianggap ‘valid’ manakalasang seniman mampu menunjukkan perhatiannya yang men-dalam terhadap apapun, dan karya seni itu dapat dibenarkanmanakala ditampilkan sebagai produksi asli manusia, sebagaihasil imajinasi dan kontemplasi bukan menjiplak alam semata-mata. Seni bukanlah semata-mata estetika, tetapi lebih dari ituseni memiliki fungsi magis dan fungsi spiritual. Fungsi magisseni merupakan persembahan prinsip, kekuatan dan segalayang menarik serta simpatik secara magis, dan dalam fungsispiritual seni menampilkan kebenaran dan keindahan darikedalaman dimensi batininya. Dari fungsi spiritual inilah senimenggiring manusia kembali kepada ‘diri-Ku yang “bersema-yam” di dalam dirimu’. Kembali pada peng-aku-an Aku yangmeng-aku-i diri-Ku.
Schuon juga menyoroti persoalan yang sering terjadi da-lam dunia seni modern. Misalnya saja karya sastra modernyang ia nilai terlalu banyak menggunkan kata-kata murahan,dangkal, dan nyaris tak bermakna apa-apa. Perbendaharaankosa katanya seringkali dipaksakan dan sangat jauh dari intitulisan sehingga mengaburkan pesan yang ingin disampaikan.Sang pengarang terlalu mengosongkan diri, memudarkan kete-nangan dan menghilangkan pengendalian diri, dengan demiki-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 125
an sama saja dengan ia mengundang orang lain untuk mengo-songkan diri mereka. Maka tercabiklah esensial, musnahlah pe-mahaman terhadap yang ‘tersembunyi’, dan memadamlah apipemahaman dimensi batini, kecenderungan seperti itu munculpula pada karya puisi dan musik,94 padahal kesejatian karyaseni itu manakala dilakukan interiorisasi terhadap seni itu se-cara kontemplatif dan unitif, yaitu penggalian kedalaman batinsang seniman melalui permenungan yang terpadukan denganYang Mahaestetik. Menurut Schuon, seni-seni modern yangdihasilkan oleh seniman modernistik telah lama meniadakanmakna dan dasar-dasar spiritual akibat pengaruh kebebasanyang mereka imani. Ini adalah tragedi ‘budaya’ modern yangkini tinggal menunggu saat-saat kehancurannya. Saat-saat ke-hancuran itu akan segera datang manakala mereka masih te-tap mempertahankan hak-hak yang mereka klaim sebagi milik-nya tetapi abai terhadap kewajiban-kewajiban yang harusmereka penuhi.
PENUTUP
Sebelum mengakhiri tulisan ini perlu kiranya digaris ba-wahi bahwa terdapat dua bentuk tujuan kosmis kegiatan seni,pertama: tujuan kosmis yang muncul dari ketidaksadaran, di-mana seni adalah latihan untuk hidup lewat perburuan spon-tan atas dataran imajinasi, meningkatkan kehidupan denganmemberi kelegaan, dengan membebaskan hasrat-hasrat ter-pendam atau dengan pencurahan energi dalam kepribadiansang seniman. alam hal ini tentulah berpretensi biologis yangsungguh tidak disadari oleh sang seniman. Kedua: tujuan kos-
94Silahkan dibaca pula wawancara khusus antara Goenawan Mo-hamad dengan wartawan Jurnal Ulumul Qur’an, Edy A. Effendi, terbitanNomor 1, Vol IV, Th. 1993.
126 | Win Usuluddin Bernadien
mis sebagai bagian intuisi lewat kesadaran yang disadari se-penuhnya oleh sang seniman, yaitu tujuan kosmis sebagaisuatu ramuan objektif dalam intuisinya terhadap alam raya se-bagai keseluruhan. Dalam intuisi sang seniman terkandung ga-gasan-gagasan kosmis sebagai pokok ekspresi seninya. Di sini-lah seni mengandung muatan didaktis, sebab jiwa sang seni-man terkuasai oleh dan terhiasi dengan etika yang sangat luas.Seni menjadi sebuah ekspresi impresi sang seniman terhadapsang Hakiki, yang indah-mendalam-penuh makna. Lewat seniIqbal telah menuntun kita pada jalan yang benar menujutingkat kehidupan dan pemikiran yang tinggi, Hakikat.
Hasil pencarian rasionalisme Cartesianistik adalah ma-nusia modern yang sangat mengagungkan nalar dan tak lagimemiliki horizon spiritual yang sesungguhnya telah mengabai-kan dimensi Transendental dan mengagungkan animalitas se-mata-mata. Manusia modern telah terpasung dalam kealfaandiri, sekularistik-materialistik yang pada gilirannya menjerem-babkan mereka pada jurang yang full of crisis.Manusia moderntelah benar-benar gagal menemukan hakikat dirinya yang ber-pangkal pada kerapuhan jatidiri dan krisis spiritual. Menyadariakan hal ini semua, Schuon lewat karya-karyanya mencobauntuk mencari dan menemukan jawab atas persoalan-persoal-an penting yang sedang melanda manusia modern. Lewatkarya-karyanya pula, Schuon menunjukkan jalan alteri bagimanusia kontemporer yang tak berdaya menghadapi persoal-an pelik sains dan rasa was-was akan iklim nihilisme yang me-nggelayuti pikiran mereka. Atas dasar keprihatinannya terha-dap manusia modern yang sibuk mencari pandangan hidupholistik dan hasrat kembali pada integritas dirinya, Schuon me-nggoreskan karya-karyanya. Dalam pandangannya sebagai se-orang perenialis manusia masa kini telah benar-benar berada
Serpihan-Serpihan Filsafat | 127
pada lembah kemorosotan karena telah kehilangan pengeta-hu-an dan kesadaran akan dirinya serta terlalu bergantungpada sisi eksternal dirinya. Peradaban modern yang merekaciptakan sendiri nyatanya tak mampu memberi pemenuhanakan kebutuhan spiritual dan transendental dalam kehidupan-nya di zaman modern. Modernitaspun semakin dangkal dannaif sebab tercerabut dari akar tradisional yang sesungguhnyamerupakan induk semang yang telah melahirkan peradabanmodern itu sendiri. Schuon menegaskan dalam perspektif per-enial bahwa sesungguhnya abad modern itu tidaklah kehilang-an bingkai-bingkai spiritual akan tetapi manusia modern yangtelah mengaku menemukan The New Age itulah yang sedangberdiri rapuh di pinggiran bingkai-bingkai spiritual sehinggamerekapun hidup pada sisi marginal lingkaran eksistensinya,tidak pada sentral spiritualitas dirinya dan merekapun semakintak mengerti siapa jati dirinya. Schuon mengajak manusiamodern yang Cartesianistik kembali kepada jalan yang lurus,dan menelusuri Kebenaran transenden serta Realitas ilahiah,meski hanya lewat media kata yang serba relatif dan terbatas.Schuon memberikan obat penawar racun dan penyembuhluka manusia modern yang terkoyak akibat nalar rasionalisme-empirisme dengan intuisi intelektual dan pandangan mata hatisehingga mampu menempuh perjalanan pulang kembali ke‘rumah asal’-nya, pulang menuju sang Diri, menuju pusat Diri.Dengan sinar cahaya ruh Ilahiah, dengan segenap sakralitasdunia, al Hikmatu al Khalida atau Sophia Perennis mengajakmanusia menuju Kebenaran, Keindahan, dan Cinta yangmelimpah ruah dalam penciptaan.[*]
128 | Win Usuluddin Bernadien
BACAAN PENDUKUNG
Honderich, Ted., (ed.) 1995, The Oxford Companion to Philo-sophy, New York, Oxford University Press.
Malik, Hafeez dan P. Lynda. Malik, 1992, Filosof-Penyair dariSialkot, dalam Ihsan Ali Fauzi&Nurul Agustina (ed.), SisiManusiawi Iqbal, Bandung, Mizan.
Miss Luce-Claude Marite, 1981, Introduction to the Thought ofIqbal, diindonesiakan oleh Djohan Effendi: Pengantar kePemikiran Iqbal, Jakarta, Pustaka Kencana.
Schuon, Frithjof, 1995, The Transfiguration of Man, diindone-siakan oleh Fakhruddin Faiz, Transfigurasi Manusia, Ref-leksi Antrophosophia Perennialis, Yogyakarta, Qalam.
Schuon, Frithjof, 1976, Islam and the Perennial Philosophy,Word of Islam Festival Publishing Company Ltd.
Schuon, Frithjof., (Muhammad Isa Nuruddin), 1993, diindone-siakan oleh Rahmani Astuti, Islam dan Filsafat Perennial,Bandung, Mizan.
Schuon, Frithjof., 1996, Ringkasan Metafisika yang Integral,dalam Ahmad Norma Permata (ed.) Perennialisme Me-lacak Jejak Filsafat Abadi, Yogyakarta, Tiara Wacana.
Syarif, M. M., 1976, About Iqbal and His Thought, Lahore,Institute of Islamic Culture.
Yusuf Jamil, 1984, Iqbal: Tentang Tuhan dan Keindahan, Ban-dung, Mizan.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 129
BAGIAN KEDELAPAN
KARL MARX DAN MARXISME:SEBUAH CATATAN)
Nama lengkapnya Karl Heinrich Marx, lahir tanggal 5 Mei1818 di Kota Renish, Trier, Prusia (Jerman sekarang). Ayahnyaseorang pengacara Yahudi sukses yang telah menjadi KristenProtestan. Dalam perkembangan keagamaannya Marx malahmeninggalkan agamanya itu, bahkan semua agama. Sejak ke-cil ia nampak telah memiliki kemampuan intelektual. Pada usia18 tahun (1836) ia diterima sebagai mahasiswa pada FakultasHukum Universitas Berlin dan pada usia 23 tahun (1841) iatelah dipromosikan menjadi doktor bidang filsafat. Tak lamakemudian ia memimpin sebuah harian di Jerman yang radikal
)Catatan ini disandarkan pada beberapa tulisan, diantaranya duakarya Franz Magnis-Suseno yang diterbitkan oleh PT. Gramedia PustakaUtama Jakarta pada tahun 2001 dan 2003 masing berjudul: “PemikiranKarl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Reviosionisme”, dan“Dalam Bayangan Lenis, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampaiTan Malaka”. (pen.)
130 | Win Usuluddin Bernadien
liberal. Beberapa saat kemudian ia pindah Paris. Di sinilahMarx berkenalan dengan seseorang yang pada saatnya nantimenjadi sahabat karibnya Friedrich Enggel (1820-1895). Ber-sama karibnya ini Marx menggabungkan diri dengan kalangansosialis, dan di kemudian hari tampil sebagai tokoh sosialisme.Marx banyak menulis naskah tentang filsafat dan ekonomi na-sional yang banyak memuat pemikirannya tentang keterasing-an. Tahun 1845 Marx di usir oleh Pemerintahan Perancis danpindah ke Brussel. Ia menulis naskah ‘Ideologi Jeman’ yangmemuat pokok pikirannya tentang Materialisme Sejarah. Ta-hun 1847, ia pun diusir dari Brussel menuju London, danmenjalani hidup sebagai orang yang miskin, hingga kematianmenjemputnya pada tahun 1883.
Jauh sebelum ajal menjelang, bersama dengan EngelMarx menerbitkan Manifesto Komunis (1848), lalu memper-dalam ilmu ekonomi dan menerbitkan jilid pertama Das Kapital(1867) yang telah dirintisnya sejak tahun 1864 saat ia menjadiKetua Assosiasi Buruh Internasional. Marx memang banyakterlibat dengan praktek organisasi gerakan sosialis dan komuniskarena yakin bahwa dengan karya-karya itu ia dapat meng-interprestasikan dunia bahkan mengubah dunia. Marx yakinbahwa sejarah sedang bergerak menuju arah revolusi yang me-nggunakan kapitalisme untuk membuka jalan lebar menuju ko-munisme. Karenanya Marx mengorganisir dan mendidik kaumproletar untuk memenangkan revolusi. Sayangnya, revolusiyang ia maksudkan justru banyak menuai kegagalan, terutamadi negara-negara Eropa dan memilih untuk mengasingkan dirike Inggris untuk menghabiskan sisa-sisa hidupnya.
Di dalam Manifesto Komunis-nya kita dapat melihat Marxmeletakkan seluruh dasar dan praktek komunisme, di sampingitu juga ditemukan di dalamnya filsafat Jerman, sosialisme Pe-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 131
rancis, dan ekonomi politik Inggris tiga pilar terbesar yang mempengaruhi Marx dan meresapi seluruh teori sejarah, ekonomi,sosiologi, dan politiknya. Hal ini sesuai dengan deskripsi Engelyang menyebut kondisi tersebut sebagai ‘sosialisme ilmiah’(scientific socialism). Mereka berdua mengklaim telah menemu-kan metode ilmiah yang benar bagi studi masyarakat dandengan itu dapat membangun kebenaran objektif atas karya-karya mereka di masa kini serta perkembangan masyarakat dimasa depan tempat mereka hidup.
Memang harus diakui bahwa karya-karya Marx banyakdiilhami oleh pemikiran Hegel, sehingga pemikirannya pun sa-ngat Hegelian. Sebagaimana Hegel, Marx yakin bahwa setiapzaman memiliki karakter khas dan hanya hukum universal da-lam sejarah yang berhubungan dengan setiap proses perkem-bangan yang satu tahapnya memberikan jalan bagai tahap be-rikutnya. Inilah yang ia sebut sebagai ‘konsepsi material seja-rah’ (materialist conception history).
Ada satu hal yang baru dalam pemikiran Marx yang be-lum pernah ada sebelumnya, yaitu; pencarian metode ilmiahyang benar untuk mempelajari perkembangan sejarah umatmanusia. Marx yakin bahwa terdapat hukum-hukum sosial-ekonomi umum yang berlaku dalam sejarah umat manusiadan perubahan-perubahan utama sosial-politik serta kegaga-lan-nya, dapat dijelaskan dengan menggunakan hukum ilmualam (fisika, kimia, biologi, psikologi, dan sosiologi). Hukum-hukum itu tidak terkait dengan proses jiwa, melainkan denganproses ekonomi di alam.
Dalam bingkai sosial, manusia masuk ke dalam relasi-relasi yang telah ditentukan, terpisahkan dari keinginan pribadimereka; relasi-relasi itu berhubungan dengan tahap perkem-bangan kekuatan produksi yang telah ditentukan. Totalitas re-
132 | Win Usuluddin Bernadien
lasi ini membentuk dasar struktur ekonomi masyarakat, fondasisebenarnya tempat superstruktur hukum dan politik berdiri danyang padanya bentuk-bentuk tertentu kesadaran sosial berkait-an. Mode produksi kehidupan material membatasi karakterumum proses-proses hidup sosial, politik, dan spiritual. Bukan-lah kesadaran manusia yang membatasi ada-mereka, melain-kan ada-sosial mereka yang membatasi kesadaran. Di kalang-an kaum marxisme pada umumnya, pernyataan ini seringkalidiartikan bahwa dasar ekonomi masyarakat membatasi segalasesuatu hingga detail terakhirnya. Akan tetapi penyataan Marxsendiri malah lebih samar sehingga tidak mengikatnya padadeterminisme yang terlalu kuat.
Memang, faktor ekonomi sangat penting dan tidak dapatdiabaikan, tetapi apakah benar bahwa dasar ekonomi memba-tasi superstruktur ideologi?. Dalam kaitan ini sangatlah sulit un-tuk menafsirkan pernyataan Marx tersebut sebab tidak ada de-markasi yang jelas antara fondasi dan superstruktur agar dapatberjalan sebagaimana mestinya. Di satu sisi Marx berbicaramengenai ‘kekuatan material produksi’ yang meliputi sumberdaya alam dan sumber daya manusia, dan pada sisi yang lainia juga berbicara mengenai ‘struktur ekonomi’ yang meliputi‘relasi-relasi produksi’ yang kira-kira berari cara kerja yang di-organisir. Marx memberikan tiga tingkat kekuatan-kekuatan:material produksi, relasi-relasi produksi, dan superstrukturideologis.
Mark menerapkan konsep materialisme sosialnya dengandua jalan, yaitu secara sinkronis (peninjauan ahistoris) dansecara diakronis (peninjauan historis). Pada saat tertentu, basisekonomi dilihat sebagai pembatas karakteristik superstrukturideologis pada tahapan masyarakat. Namun, sejalan beriring-nya waktu perubahan: sistem ekonomi mungkin stabil untuk
Serpihan-Serpihan Filsafat | 133
beberapa saat, akan tetapi sistem tersebut membiarkan prosesteknologi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perubahansosial dalam skala besar. Sejarah oleh Marx telah dibagi secarakasar ke dalam periode yang diidentifikasikan dengan perbe-daan sistem-sistem ekonominya, Asiatik, masa lalu, feodal, dan‘borjuis’ atau fase kapitalis, dan yakin setiap fase membukajalan bagi fase berikutnya saat kondisi ekonomi sudah matang.Kapitalisme membukan jalan bagi Komunisme.
Seberapa determinisme yang dituntut oleh Marx, baik se-cara sinkronis maupun secara diakronis? Bukankah setiap ma-syarakat harus mampu memproduksi kebutuhan hidupnyaagar bisa bertahan dan ber reproduksi?. Kita harus makan jikakita berpikir harus makan, bukannya mengikuti apa yang akankita makan atau bagaimana kita memproduksi apa yang akankita makan, sebab keduanya membatasi apa yang kita pikir-kan. Tidak semua aspek budaya, politik, dan agama dibatasisecara penuh oleh aspek ekonomi. Marx sendiri tidak mene-gaskan hal ini, dalam menganalisis episode-episode khususdalam sejarah, dan membiarkan pengaruh faktor budaya se-perti agama dan nasionalisme terlibat. Jelas ia mempossisikanteorinya dengan teori evolusi Darwin, sebuah teori yang yangmembuat kerangka besar mekanisme umum yang di dalamnyaperubahan dapat dijelaskan, namun tidak menawarkan sebuahmetode untuk memprediksi hal yang sangat detail mengenaihubungan kondisi khusus. Dengan demikian sebanarnya Marxsendiri nampaknya berusaha menyatakan dengan hati-hatibahwa basisi ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadapsegala sesuatu, artinya faktor ekonomi dapat mempengaruhiunsur-unsur kehidupan lainnya.
Sejarah adalah studi empiris yang proposisinya harus diujioleh fakta yang sebenarnya terjadi. Sejarah bukan hanya seke-
134 | Win Usuluddin Bernadien
dar ilmu yang memformulasikan hukum-hukum alam, suatugeneralisasi universalitas yang tak terikat. Sejarah adalah studimengani apa yang telah terjadi pada manusia dalam sebuahperiode waktu tertentu. Masalah yang diangkat memang luasakan tetapi tetap merupakan kejadian khusus yang tidak dapatdicari persamaannya di seluruh alam ini.
Di atas basis teori umum sejarahnya, Marx mengarapkankapitalisme menjadi semakin tidak stabil secara ekonomis se-hingga pertentangan kelas, antara kelas borjuis pemilik modaldengan anggota kelas proletariat yang telah menjual tenagamereka, makin meruncing seiring bertambahnya miskin danbertambahnya jumlah proletariat sehingga pada suatu revolusisosial besar-besaran para pekerja akan mengambil alih ke-kuasaan dan mendirikan instrumen baru menuju fase komonisdalam sejarah. Namun demikian, di dalam ‘Manifsto Kumu-nis’nya sendiri ‘Sang Nabi’ ini tidak yakin dengan prediksibahwa revolusi akan muncul pertama-tama di negara-negarakapitalis (Inggris, Perancis, dan AS). Jermanlah yang saat itumasih semi feudal yang jusrtu dijadikan ‘tanah harapan’ bagiMark untuk dijadikan tempat ‘persemaian’ dan hadirnya re-volusi borjuis yang segera diikuti oleh revolusi proletariat de-ngan cepat. Dalam beberapa naskah jurnalistiknya, bahkanChina adalah yang diyakini sebagai negeri pertama tempatkomunisme benar-benar tercapai. Dalam pandangannya, ide-ide sosialis mumungkinkan masuk ke dalam dunia kapitalisterutama di negara yang memiliki proletariat yang relatif kecil,bergabung dengan para petani miskin, dan merebut kekuasaankelas tradisional yang sedang berkuasa. Pada tahun 1917,keyakinan Marx benar-benar terjadi dalam dua kali revolusiyang terjadi di Rusia.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 135
Kapitalisme seperti yang dikenal Marx sudah tidak adalagi, sebaliknya reformasi bertahap dan damai secara radikaltelah mengubah wajah sistem ekonomi saat ini.
Jikalau manusia telah ‘dibentuk’ oleh keadaan, maka ke-adaan itu haruslah manusiawi sifatnya. Jikalau keterasinganmerupakan sebuah masalah sosial yang disebabkan oleh ha-kikat sistem ekonomi kapitalis, maka solusi yang terbaik adalahmenegasikan sistem tersebut dan menggantikannya dengan sis-tem yang lebih baik. Pergantian ini, menurut Marx, pasti ter-jadi, bahwa kapitalisme akan mengalami kehancuran karenakontradiksi internalnya lalu komunis akan tampil melayani ma-syarakat dengan tatan baru. Marx bahkan mengklaim bahwajawaban atas persoalan kapitalisme telah ada di depan kita, ko-munisme. Oleh karena itu, bersama-sama dengan para pengi-kutnya, Marx selalu berusaha menunjukkan kepada masyara-kat agar menyadari arah sejarah bergerak, bertindak, danmembantu membawa revolusi komunis.
Di dalam gerakan marxisme terjadi pertentangan. Kalang-an koservatif menekankan perlunya menunggu tahap perkem-bangan ekonomi yang tepat sebelum melakukan revolusi, se-mentara itu kalangan modern (Lenin dan Stalin) menekankanperlunya ‘bertindak’ untuk mengadakan revolusi secepatnya.Namun demikian kontradiksi seperti itu tidak menjadi persoal-an sebab Marx sendiri mengatakan bahwa revolusi itu akanterjadi cepat atau lambat, yang terpenting adalah menyadarkanmasyarakat dan mengorganisasikan kelompok-kelompok yangdapat menyambut jedatangan dan ‘mempermudah kelahiran’revolusi. Marx yakin bahwa hanya revolusi atas sistem ekono-mi yang akan menyelesaikan seluruh masalah dengan tepat.Menaikkan upah, mengurangi jam kerja, jaminan pensiun, danmembatasi bentuk-bentuk kapitalisme lainnya tidak akan dapat
136 | Win Usuluddin Bernadien
mengembangkan hakikat dasar manusia. Di sinilah perbedaanradikal antara Partai Komunis di satu sisi dengan kesatuan-kesatuan perdagangan dan demokrasi sosial atau partai-partaisosial demokrat di sisi lainya dimulai. Marx berpendapat bah-wa mengkombinasikan masalah-masalah yang muncul di seki-tar pekerja dengan usaha mereformasi sistem akan ‘membang-kitkan kesadaran’ dan menciptakan ‘solidaritas kelas’ yangbaru di antara mereka sehingga memampukan mereka untuksadar akan kekuatan yang mereka miliki untuk melakukanrevolusi yang benar-benar mengubah segalanya.
Marx yakin hanya Komunisme sajalah satu-satunya ‘solusiatas teka-teki sejarah’ sebab penghapusan kepemilikan pribadidiharapkan akan dapat menghilangkan keterasingan dan me-munculkan masyarakat tanpa kelas. Sayangnya, Marx tidakmemiliki konsep dan cara yang jelas untuk mewujudkan utopiaini.[*]
Serpihan-Serpihan Filsafat | 137
BAGIAN KESEMBILAN
POROS BARU FILSAFAT SEJARAHKARL JASPERS)
Manusia itu tidak selesai, dia tidak bisa diselesaikan,dan masa depannya tidak bisa diselesaikan.
Tidak ada manusia total, dan tidak pernah ada.[Karl Jaspers]
PENGANTAR
Karl Jaspers dianggap sebagai filsuf Jerman yang palingpenting di abad kedua puluh. Sebelum menjadi profesor filsa-fat, dia sudah terkenal luas sebagai seorang psikolog dan psi-kiater. Jaspers banyak menulis buku yang diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, meskipun sesungguhnya sulit dipero-
)Tulisan ini sesungguhnya memang terinspirasi dari karya Rigali,Norbert, J., yang diterbitkan pada 1962, dengan judul A New Axis: KarlJaspers’ Philosophy of History, oleh International Philosophy Quarterly,Los Angeles: Loyola University Press.
138 | Win Usuluddin Bernadien
leh darinya sebentuk ajaran yang sistematis dalam buku-buku-nya itu.
Jaspers seringkali digolongkan sebagai filsuf Eksistensialis,sejajar dengan Sartre, meskipun dia sendiri tidak senang de-ngan istilah Eksistensialisme, oleh karena itu pemikirannya dianamai ‘filsafat eksistensi’. Bahkan dia sedikit berseberangan de-ngan Sartre dalam memahami kebebasan manusia. Baginyamanusia menjadi bebas karena Tuhan hadir dan ‘Melingkupi’kita, tetapi bagi Sartre manusia itu justru akan bebas jika tuhantidak hadir dalam diri kita, toh tuhan tidak diperlukan oleh kita.
Filsafat eksistensi, sesungguhnya bermuara ke dalam suatu ‘kepercayaan filosofis’, sebuah ‘kepercayaan’ yang meng-ajak manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Bagi Jaspers filsa-fat eksistensi mengajak (appeal) manusia untuk menjadi danmenghayati ‘aku yang sebenarnya’. Eksistensi adalah pengha-yatan akan kebebasan total yang merupakan inti manusia.Martabat manusia, bagi Jaspers, kini sedang terancam, danhanya dapat diselamatkan manakala kebebasan dapat disela-matkan dengan cara percaya kepada dirinya sendiri.
Karya Jaspers, baik berupa buku maupun artikel banyaksekali. Salah satunya berjudul: Vom Ursprung Ziel der Ges-chichte (Origin and Goal of History, (Asal Usul dan TujuanSejarah), yang dipublikasikan pada tahun 1849. Dari (terje-mahan) tulisan itulah, yang penulis ambil dari tulisan Rigali,dan juga dari beberapa bacaan pendukung lainnya, tulisan inidikutip dan disarikan.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 139
RIWAYAT SINGKAT DAN KARYANYA95
Nama lengkapnya adalah Karl Theodor Jaspers, lahir diOldenburg, Jerman Utara, pada tanggal 23 Pebruari 1883.Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang bekerja sebagai di-rektur sebuah bank merangkap pimpinan dewan kota, berna-ma Carl Wilhelm Jaspers, dan ibunya bernama Henriette Tant-zen. Mereka beragama Protestan liberal. Suasana religius yangdialaminya ini mengantarkan Jaspers menjadi seorang yangtidak fanatik beragama, ia pun memperistri seorang wanita Ya-hudi, yaitu pada tahun 1910, bernama Gertrud Mayer, kakakperempuan sahabatnya, Ernst Mayer.
Pada tahun 1892 hingga 1902 Jaspers sekolah di Gymna-sium di Oldenburg, tetapi tidak senang dengan sekolah itu,sebab semua murid dipaksa untuk aktif masuk organisasi siswayang berstruktur hirarkhis. Karenanya Jaspers memilih sendiri-an, apalagi memang dia sudah terjangkiti penyakit bronkhitiesdan jantung lemah. Namun demikian, Jaspers termasuk orangyang mendapatkan “Berkah yang tersembunyi’ (blessing in dis-guise) dari Allah sebab nyatanya dia bisa bertahan hidup hing-ga mencapai usia lanjut, 86 tahun. Jaspers adalah sosok yangtidak memiliki kontak sosial baik karena penyakitnya itu, tetapidia mengimbanginya dengan interest kepada ilmu pengetahu-an, sastra dan seni, dan dengan rasa cinta kepada alam. Ia ba-nyak belajar tentang hukum di Heidelberg dan München, se-
95Bertens, K, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman, Jakarta: Gra-media, 1981, hlm. 127., Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat2, Yogyakarta: Kanisius, 1980, hlm. 164., Ted Honderich, (ed.), The Ox-ford Companion to Philosophy, Oxford-New York: Oxford UniversityPress, 1995, p. 428, Simon Blackburn, The Oxford Dictionary of Philo-sophy, Oxford: Oxford University Press, 2008, telah diindonesiakan olehYudi Santoso, Kamus Filsafat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm.49-51.
140 | Win Usuluddin Bernadien
lama tiga semester, lalu tertarik dan pindah ke bidang kedokter-an karenanya dia pindah ke Berlin, Göttingen, dan akhirnyakembali lagi ke Heidelberg. Studinya ini diselesaikan pada ta-hun 1908. Setahun setelah itu, Jaspers mempertahankan tesis-nya berjudul Heimweh und Vebrechen, (Homesickness andEvil, Kerinduan dan Kejahatan). Selanjutnya sejak tahun 1909hingga 1915 Jaspers bekerja sebagai assisten di sebuah klinikpsikiatri Heidelberg. Jaspers pun kemudian semakin tertarikpada persoalan-persoalan psikologis dan filsafat, yang kemudi-an mengantarkannya menjadi seorang dosen psikologi di Uni-versitas Heidelberg, dengan tetap aktif sebagai psikiater. Tahun1921 dia menjadi profesor filsafat di Heidelberg. Sebagai se-orang ilmuwan dan filsuf dia tidak pernah merasa puas denganpengetahuan yang tidak menyeluruh. Barangkali karena alasanitulah dia pindah dari hukum ke kedokteran, dari kedokteranke psikiatri, dari psikiatri lalu ke psikologi dan ke filsafat. KarlTheodor Jaspers meninggal dunia di Basel pada tanggal 26Pebruari 1969.
Beberapa karyanya yang dapat disebutkan di sini antarlain: Allgemeine Psychopathologi (Psikopatologi Umum)(1913), dan Psychologi der Weltanschauungen (Psikologi Pan-dangan-pandangan Dunia) (1919), keduanya merupakan bukuyang menjadi pedoman dan berpengaruh luas meskipun Jas-pers sendiri kemudian tidak begitu puas lagi dengan buku itu.Tahun 1931 diterbitkan Die geistige Situation der Zeit (SituasiRohani Zaman Kita) berisi diagnosa kebudayaan Barat yangmemprihatinkan akibat totalitarisme dalam bentu Marxismedan Nazisme. Buku ini merumuskan untuk pertama kalinya‘filsafat eksistensi’ Jaspers, kemudian diuraikan secara panjanglebar dalam buku besarnya, berjudul Philosophie (1932) yangterdiri atas tiga jilid: Philosophisce Weltorientieruung (Orientasi
Serpihan-Serpihan Filsafat | 141
Filosofis dalam Dunia), Existenzerhellung (Penerangan Eksis-ten-si), dan Metaphysik (Metafisika). Dari ketiganya yang palingpenting menurut Jaspers adalah Philosophie. Tahun 1935 me-nulis Vernunft und Existenz (Rasio dan Eksistensi), lalu Exis-tenzphilosophie (Filsafat Eksistensi) (1938), Von der Wahrhei(Mengenai Kebenaran) (1948), sebagai bagian pertama dariPhilosophisce Logik (Logika Filosofis). Tulisan tersebut berisianalisa-analisa kebenaran dan karenanya Jaspers menamainyadengan ‘Periechontologie’,ajaran mengenai transendensi ‘yangmelingkupi’ kita (dari kata Yunani periechien, ‘melingkupi’,‘mengelilingi’), Der Philosophische Glaube (Kepercayaan Filo-sofis) (1948), dan Der Philosophische Glaube angesichts derOffenbarung (Kepercayaan Filosofis di Hadapan Wahyu)(1962). Jaspers juga menulis filsafat sejarah berjudul VomUrsprung Ziel der Geschichte (Origin and Goal of History, AsalUsul dan Tujuan Sejarah) (1949).
BATU PIJAK FILSAFAT JASPERS
Menurut Jaspers, Filsafat adalah suatu gerakan pikiranyang tiada pernah henti, membebaskan manusia dan menga-jarnya untuk melihat kenyataan sebagai suatu bahasa simbol-simbol, suatu ‘naskah’ oleh transendensi yang harus ‘dibaca’oleh manusia. ‘Bacaan’ ini merupakan sesuatu yang terbuka,bagai cakrawala yang terbentang luas seakan tak bertepi. Ba-ginya, sebagai seorang ilmuwan, filsafat dan ilmu pengetahuanmerupakan dua sisi yang tak mungkin terpisahkan. Segala apayang dapat diselidiki secara ilmiah harus diselidiki oleh ilmupengetahuan, baru setelah itu filsafat tampil mengambil peran-nya. Filsafat yang mengambil alih peranan ilmu pengetahuan,atau dengan kata lain ‘ilmu filsafat’ bagi Jaspers tidak relevan.Filsafat baru relevan manakala manusia harus memutuskan
142 | Win Usuluddin Bernadien
dan menggunakan kebebasannya. Hal ini berarti bahwa manu-sia harus mempelajari hasil ilmu-ilmu agar diketahui di manabatas antara yang dapat diketahui dan yang tak dapat dike-tahui. Manusia harus mulai ‘melayang’ untuk semakin banyakmengetahui dan terus mempertanyakan eksistensi. Manusiamenjadi eksistensi melalui pilihan-pilihan. Eksistensi hanya adabersama transendensi, yaitu Allah. Bagi Jaspers, filsafat tidakperlu menjadi ilmu, sebab filsafat bukanlah sistem rumus-rumus, melainkan penerangan ‘tindakan batin’ yang merupa-kan dasar hidup manusia. Filsafat lebih tua daripada ilmu pe-ngetahuan, meskipun pada mulanya kedua-duanya merupa-kan kesatuan, sebab masing-masing memiliki tugas yang ber-beda. Pengetahuan dan sikap ilmiah merupakan syarat untukkesungguhan filsafat, tetapi selalu akan ada pertanyaan yangharus dijawab oleh filsafat karena pengetahuan ilmiah tidakpernah lengkap. Jaspers berpendapat bahwa filsafat eksistensiadalah pemikiran yang memanfaatkan sekaligus mengatasisemua pengetahuan objektif. Melalui pemikiran itu manusiaingin menjadi dirinya sendiri. Pemikiran itu tidak mengenalobjek-objek melainkan menerangkan sekaligus mengerjakanadanya orang yang berfikir dengan cara itu.
Ada dua poin penting dalam filsafat Jaspers, yaitu Eksis-tensi dan Transendensi.96 Bereksistensi berarti berdiri di hadap-an transendensi. Transendensi menyembunyikan diri dan de-ngan demikian justru merupakan kebebasan manusia. Seba-gaimana Kant, Jaspers juga berpendapat bahwa kebijaksanaanilahi itu nampak kelihatan bukan hanya dalam segala sesuatuyang diberikan kepada manusia akan tetapi juga dalam apayang disembunyikannya. Transendensi tersembunyi dan berbi-
96Jaspers, Karl., trans. E.B. Ashton, Philosophy, Vol. 1-3, Chicago:The University of Chicago Press., 1971.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 143
cara melalui sandi-sandi, chiffer-chiffer yang terbaca oleh ma-nusia sejauh ia menjadi eksistensi. Artinya sejauh ia mengisikebebasannya. Wahyu Allah tidak terbatas pada periode waktutertentu dalam sejarah. Segala sesuatu dapat saja menjadiwahyu, segala sesuatu dapat saja menjadi chiffer, menjadi’bayang’, menjadi ‘gema’, ataupun ‘jejak’ dari transendensi.Menurut Jaspers eksistensi merupakan sesuatu yang palingberharga dan paling otentik dalam diri manusia. Eksistensi ada-lah aku yang sebenarnya, yang bersifat unik dan sama sekalitidak objektif, serta dengan tiada henti-hentinya terbuka bagikemungkinan-kemungkinan baru. Eksistensi dapat dihayati,dapat diterangi melalui refleksi filosofis dan dapat bekomuni-kasi dengan orang lain. Eksistensi dan transendensi dalambahasa mistisnya disebut ‘jiwa’ atau ‘Allah’. Eksistensi manusiamerupakan bentuk ‘ada’ yang memutuskan dalam waktu apa-kah dan bagaimanakah ia ingin menjadi abadi. Adanya manu-sia termasuk dunia empiris oleh Jaspers disebut Dasein. Na-mun ‘eksistensi’ itu berupa ‘kemungkinan’, kemajuan, atau ke-munduran dalam jalan menuju ‘ada’ abadi. Eksistensi ada-ahkebebasan yang diisi, termuat dalam waktu sekaligus meng-atasi waktu. Jaspers membedakan Existenz dengan Dasein.Dasein adalah keberadaan empiris manusia sejauh memilikiciri-ciri khusus dan dapat digambarkan dari luar. Eksistensi itusulit untuk diwujudkan dan jarang sekali dicapai. Oleh karenaitu Jaspers sering mengatakan möglische Existenz (eksistensiyang mungkin).Pada kenyataannya seringkali eksistensi itu me-rupakan kemungkinan saja, tidak sampai terealisasikan secaranyata. Dasein dapat menjadi objek pendekatan teoritis. Men-campuradukkan keduanya akan menyebabkan materialismedan mengorbankan Dasein kepada eksistensi akan berakhir de-ngan nihilisme. Filsafat eksistensi itu bukan merupakan filsafat
144 | Win Usuluddin Bernadien
yang ‘merenungkan kebenaran’ melainkan filsafat praksis, yaitumenghayati kebenaran cara berfikir manusia yang dibuktikanmelalui tindakan yang didasarkan pada pemikiran tersebut.
Lebih jauh, menurut Jaspers, agama tidak bisa dilepaskandari unsur mistis, karenanya mitologi harus tetap dianggaphakiki bagi agama. Demikian juga filsafat spekulatif besar harusdipandang sebagai usaha membaca tulisan sandi (tentangTransendensi) meskipun akhirnya filsafat-filsafat itupun menja-di tulisan sandi pula. Agama sesungguhnya adalah pencariankebenaran secara bersama-sama bukan kepercayaan kepadaYesus dari Nazareth, juga bukan dalam agama-agama resmiatau agama-agama wahyu lainnya. Yang sekarang ini lebih di-butuhkan manusia sesungguhnya adalah dialog universal da-lam bingkai ‘agama falsafi’ sebagai dasar relegius umum, yangmengatasi semua perbedaan agama-agama besar. Kepercaya-an filosofis merupakan dasar atas semua tindakan, sumberkepastian yang hakiki dan mutlak. Filsafat yang diartikan seba-gai ‘cinta kepada hikmat’ atau ‘cinta kepada kebenaran’ tetap-lah sebagai arti yang paling tepat. Manusia bukan philos tetapiphilo-sophos, pencari kebenaran, pencarian yang tak pernahberakhir dan dunia bukanlah kenyataan terakhir, bahasa cintakasih sudah merupakan suatu bukti bahwa Allah ada. Olehkarena itu semua bentuk dogmatisme adalah ‘pengkhianatan’sebab membekukan sesuatu yang tak dapat dibekukan. Tran-sendensi tidak dapat ditangkap, apalagi menjadi objek. Olehkarena itu pemikiran tentang tansendensi selalu berstatus ‘ke-percayaan’. Melalui filsafat rahasia kebenaran sedikit dapatdibuka. Urutan waktu, di sini, menjadi tidak penting sebab‘kerajaan rasio’ merupakan sesuatu ‘di dalam waktu sekaligusdi atas waktu’. Manusia di hadapan transendensi ‘sama usia-nya’. Bahasa chiffer-chiffer menjadi penengah antara eksistensi
Serpihan-Serpihan Filsafat | 145
dan transendensi. Keilahian tetap tersembunyi dan ‘mengge-ma’ melalui chiffer-chiffer.
FILSAFAT SEJARAH
Menurut Jaspers, di dalam diri manusia dapat ditemukanaku empiris (empirical self) yang sudah dikondisikan oleh se-jarah, aku yang telah dikondisikan oleh latar belakang fisik danfisiologi serta lingkungan budaya. Aku yang ini dapat diselidikioleh psikologi. Di samping itu ada aku otentik yang tak dapatoleh sain, inilah aku yang memberi arti bagi kehidupan. Setiapindividu memiliki eksistensi sementara yang hidup dalam kurunwaktu tertentu, tetapi tidak sementara semata-mata; manusiadapat merasakan keabadian eksistensial. Penerobosan akuotentik kepada proses sejarah dan empiris telah memungkin-kan pilihan dan kebebasan.
Jaspers, dalam Vom Ursprung und Ziel der Geschichte(1949) menulis bahwa salah satu tugas filsafat sejarah adalahmencari struktur sejarah sedunia sebagai keseluruhan.97 Selan-jutnya dia membagi sejarah atas empat periode sebagaimanaberikut ini:
Periode pertama merupakan zaman pra-sejarah. Padaperiode ini tidak ditemukan peninggalan dokumen tertulis, na-mun bahasa-bahasa sudah berkembang, alat-alat telah banyakditemukan, api sudah dipergunakan. Menurut Jaspers, periodeprahistoris ini merupakan dasar bagi seluruh sejarah di masa-masa mendatang. Pada periode ini manusia sudah mampumengatasi keadaan biologis dan telah menjadi manusia dalamarti yang sesungguhnya. Tidak dapat diketahui secara persisberapa lama bentangan waktu zaman prasejarah ini, yang jelas
97Bertens, ibid, hlm. 138.
146 | Win Usuluddin Bernadien
terbentang amat panjang sehingga sejarah yang berdasarkandokumen tertulis belum memiliki umur yang berarti.
Periode kedua disebut Abad Promethean, berlangsungantara tahun 5000 dan 3000 sebelum Masehi. Pada abad iniMesir telah memiliki kebudayaan dan peradaban adiluhung,demikian juga Mesopotamia, tepian sungai Hindus dan tepiansungai Huangho di Tiongkok. Kebudayaan dan peradaban ter-sebut bagaikan cahaya-cahaya cerah cemerlang di tengah ke-gelapan dunia yang telah dihuni oleh manusia, bumi.
Periode ketiga adalah periode poros (Axial Periode).Periode ini berlangsung antara tahun 800 dan 200 sebelummasehi. Pada periode ini proses-proses spiritual manusia telahdan sedang berlangsung, dasar-dasar rohani dan intelektualumat manusia telah diletakkan pada periode ini. Manusia telahmemasuki ke-ber-ada-an-nya. Dari tempat yang saling berjauh-an dan tidak saling berhubungan Tiongkok, India, Persia,Palestina, dan Yunani kita menimba sumber yang berpancaranhingga kini. Menurut Jaspers, periode ketiga ini memainkanperanan sentral dan merupakan poros seluruh sejarah, karena-nya dia menamai periode ini dengan Achsenzeit (The AxialPeriod, Jaman Poros). Dari zaman ini muncul dan tumbuhdengan subur berbagai ciptaan rohani dan intelektual serta re-legius hingga zaman sekarang ini. Secara detail, di Tiongkokhadir Kung Fu-tzu (Konfusius) dan Laotze berikut seluruh aliranfilsafat Tionghoa. Di tanah Hindustan tercipta Upanishad-upa-nishad, Buddha hidup di sana dan seluruh aliran filsafat Indiadikembangkan. Di Persia hidup Zarathustra yang menggaris-kan sebuah pandangan dunia yang berkisar pada pertempuranpanjang antara yang baik dan yang jahat. Di Palestina tampilpara nabi besar: Elia, Yeyasa, Yeremia, sampai deotero-Yesa-ya. Pada jaman inilah Kitab Perjanjian Lama sebagaian besar
Serpihan-Serpihan Filsafat | 147
ditulis dan dikodifikasikan.Sementara itu di belahan dunia yanglain, Yunani, tampil pula Homeros. Filsafat Yunani lahir ber-sama Parmenides, Herakleitos, Plato, dan lain-lain, hidup pulapada zaman ini para ahli sastera dan pengarang sandiwaratragedi, termasuk juga hidup pada zaman ini Thucydides danArchimedes. Dalam jangka waktu beberapa abad saja kitamenjumpai seluruh kekayaan rohani itu di berbagai tempat,tanpa saling mengenal apalagi tahu menahu antara satu de-ngan yang lain. Dalam zaman poros inilah terbentuknya berba-gai kategori pemikiran yang masih relevan hingga zaman se-karang ini. Di zaman ini pula lahir agama-agama besar yangtetap masih menandai kehidupan kerohanian hingga zamansekarang ini.
Periode keempat disebut dengan Abad Scientifik-tech-nologi. Periode ini kehadirannya disokong sepenuhnya olehPeriode Poros. Zaman ilmiah-teknis ini agaknya yang palingsiap adalah daratan Eropa karena memang telah dipersiapkandi sana sejaka Abad Pertengahan, yang didasari dalam abadke-17 Masehi dan selanjutnya berkembang secara lebih meluaspada akhir abad ke-18 Masehi.
Sudah sejak beberapa dasawarsa terakhir periode ini me-ngalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam zaman ilmiah-teknis ini umat manusia benar-benar memasuki dan mengala-mi babak kehidupan baru, bahkan seolah-olah umat manusiakini sedang memasuki episode ‘poros baru’ yang akan mele-takkan dasar rohani baru pula bagi kita. Jaspers memang tidakmenyatakan demikian, akan tetapi jelas kemungkinan itu nam-pak hadir di hadapan umat manusia zaman sekarang. Umatmanusia kini hidup dalam era yang penuh dengan berbagaigejolak dan malapetaka. Dunia telah dilanda dua kali perang(perang dunia I dan II) yang telah hampir melumpuhkan se-
148 | Win Usuluddin Bernadien
luruh tatanan perikehidupan umat manusia, pengalaman pahitnasionalisme-sosialisme, perang dingin blok Barat dan Timur,dan masih banyak lagi.
PENUTUP98
Realitas keadaan zaman yang hadir sekarang ini tidakmenjadikan Jaspers jatuh ke dalam pesimisme steril, dia justruingin membuka pemikiran bagi berbagai kemungkinan yangtak mudah diduga yang kini mungkin masih tersimpan sebagaikekuatan terpendam bagi sejarah masa mendatang.
Sejarah dunia, menurut Jaspers, sesungguhnya tak laindaripada penggabungan sejarah-sejarah lokal, padahal bumikini telah ‘menjadi satu’. Oleh karena itu dalam zaman kitasekarang ini sesungguhnya sejarah dfunia masih baru mulai.Sejak lima ribu tahun yang lalu hingga sekarang rupanyahanya merupakan persiapan untuk sejarah sedunia.
Lalu apa sesungguhnya makna sejarah itu? Jaspers tidakmemberi jawaban yang tegas. Dia hanya menjelaskan filsafatsejarah sebagai sebuah transformasi pengetahuan kesejarahanyang menjelma ke dalam kesadaran-diri. Untuk mengekspresi-kan kesadaran eksistensi kesejarahan agar dapat menerobospengetahuan jauh ke depan, di mana pengetahuan masa lalumenjadi sebuah kesadaran masa kini. Dia juga berpandanganbahwa kita tidak bisa menentukan tujuan sejarah, karena asalusul dan tujuan sejarah itu suatu kesatuan tunggal, yaitu YesusPutra Allah. Seluruh sejarah itu goes toward and come from
98Bagian ini banyak dikutip dari karya Rigali, Norbert, J., yangditerbitkan pada tahun 1962, dengan judul A New Axis: Karl Jaspers’Philosophy of History, oleh International Philosophy Quarterly, LosAngeles: Loyola University Press, terutama hlm. 443, 448, dan 449, jugakarya Ankersmit, F,R., Refleksi tentang Sejarah, diindonesiakan olehDick Hartoko, Jakarta: PT. Gramedia, 1987, terutama hlm. 45-46 (pen.).
Serpihan-Serpihan Filsafat | 149
Christ, dan penampakan Yesus Putra Allah adalah poros seja-rah dunia (The appearance of the Son of God is the axis ofworld history). Oleh karena itu yang mungkin sekarang bisakita lakukan terhadap sejarah adalah memandangnya sebagaipanggung kehidupan umat manusia. Di dalam sejarahlah ma-nusia akan kelihatan keterbukaanya bagi Transendensi. Dalamsejarahlah kesatuan umat manusia diperlukan, kesatuan yangdidasarkan atas suatu agama universal, kesatuan yang didasar-kan atas akal budi, kesatuan yang didasarkan atas komunikasiyang sejati. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kesa-tuan tersebut jelas diperlukan sebuah bingkai politik yang dapatmenjamin kebebasan selonggar mungkin bagi semua individu,yaitu negara hukum yang legitimated, yang jauh dari berbagaikekerasan. Demikian pandangan Jaspers, yang sudah barangtentu pandangannya ini didasarkan pada ‘kepercayaan filoso-fis-nya’ yang mendambakan keterbukan umat manusia bagiTransendensi Yang Melingkupi segala sesuatu.
Sebelum penulis mengakhiri tulisan ini perlu kiranya me-negaskan bahwa yang maksud dengan poros baru sejarah se-bagaimana yang digambarkan oleh Jaspers, dapat dijelaskansebagai berikut:
Sejarah adalah serangkaian peristiwa Penciptaan, Kejatuh-an Manusia (dari langit), Inkarnasi, Hari Kiamat, dan HariPembalasan (Events the Creation, the Fall of Man, the Incar-nation, the End of the World, and the Last Judgement. Padahalaman yang sama, Rigali menambahkan pandangan Jasperstentang filsafat sejarah, bahwa the Philosophy of history as totalknowledge of human events (Filsafat sejarah adalah sebagaikeseluruhan pengetahuan manusia terhadap rentetan peristiwatersebut).
150 | Win Usuluddin Bernadien
Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan porosbaru itu?: The appearence of the Son of God is the axis worldhistory. The axis marks the birth of new man, and the new manis existence (Hadirnya Putra Allah merupakan poros sejarahdunia. Poros dunia ditandai oleh kelahiran manusia baru, danmanusia baru itu adalah eksistensi)(pen.).
Selanjutnya, sebagaimana telah disinggung di atas bahwabagi Jaspers sejarah itu tidak dapat diketahui tujuannya secarapasti. Baginya, kesadaran sejarah adalah kesadaran eksistensidalam konteks hanya masa lalu dan masa kini (Existentialphilosophy of history and existential historical consciuosnesswithin the context of only past and present). Oleh karena itu,Jaspers does not see any future, meskipun sebenarnya iamengakui bahwasanya masa depan adalah masa yang serbamungkin dan tak dapat dielakkan kehadirannya. Namun jelasbahwa Jaspers mengenalkan kepada kita akan kesadaran ek-sis-tensi manusia sebagai yang bereksistensi di bawah naunganTransendensi.
Akhirnya, berdasarkan uraian di atas dapat kiranya diga-risbawahi bahwa pandangan filsafat sejarah Jaspers bukanlahmerupakan pandangan sejarah spekulatif. Dalam ‘deskripsi’ se-jarahnya yang terdiri atas empat periode itu, Jaspers agaknyatidak berperan sebagai filsuf sejarah tetapi sebagai ahli sejarahyang ‘hanya sekedar’ mengumpulkan dan melaporkan sejum-lah data dalam sejarah, seolah-olah lepas yang satu dari yanglain dan tidak menyusun sebuah sintesis. Jaspers, meminjampikiran Dick Hartoko, seolah-olah bagaikan seekor semut yangmengangkut butir-butir gula tanpa perduli dari mana gula ituberasal dan kemana gula itu akan diangkut, meskipun dia me-ngakui periode III sebagai periode poros, dan periode penyo-kong bagi periode IV. Namun demikian, menurut hemat penu-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 151
lis, Jaspers mendua hati dalam memandang sejarah. Di satusisi dia mengakui sejarah sebagai keseluruhan rangkaian peris-tiwa kehidupan manusia sejak Penciptaan hingga kelak di HariPembalasan, tetapi pada sisi yang lain hanya dan lebih mene-kankan pada kesadaran akan masa lalu agar dapat lebih berek-sistensi pada masa sekarang. Lalu bagaimana cara manusiabereksistensi pada ‘Masa Depan’nya di hadapan Transenden-si?. Bukankah sejarah itu memiliki tiga dimensi yang sangatketat yang mengharuskan manusia dapat bereksistensi padamasing-masing dimensi: masa lalu-masa kini-masa depan?.Agaknya, Jaspers kurang menghiraukan bahwa manusia ituberasal dari-Nya dan akan kembali pada-Nya, yang hal itu ber-arti bahwa eksistensi sejarah manusia sesungguhnya tetaplah dibawah naungan-Nya dan akan selalu berada dalam bingkaimasa lalu-masa kini-masa depan, bukan masa lalu dan masakini saja. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Ankersmit, F,R., 1987, Refleksi tentang Sejarah, diindonesia-kan oleh Dick Hartoko, Jakarta: PT. Gramedia.
Ali Mudhofir, 2001, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarta: PustakaPelajar
Blackburn, Simon., The Oxford Dictionary of Philosophy,Oxford: Oxford University Press, 2008, telah diindonesia-kan oleh Yudi Santoso, Kamus Filsafat, 2013, Yogya-karta: Pustaka Pelajar.
Bertens, Kees, 1990, Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman,Jakarta: PT. Gremedia
Hamersa, Harry, 1983, Tokoh Tokoh Filsafat Barat Modern,Jakarta: PT. Gremedia
Hamersa, Harry, 1985, Filsafat Eksistensi Karl Jaspers, Jakarta:
152 | Win Usuluddin Bernadien
PT. GremediaHarun Hadiwijono, 1980, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yog-
yakarta: KanisiusHonderich, Ted, 1995, The Oxford Companion Philosophy,
New York: Oxford University Press.Jaspers, Karl, 1967, Philosophical Faith and Revelation, Trans-
lated by E.B. Ashton, London: CollinJaspers, Karl, 1967, The Future of Mankind, Translated by E.B.
Ashton, Chicago: University of Chicago Press.Jaspers, Karl., 1971, trans. E.B. Ashton, Philosophy, Vol. 1-3,
Chicago: The University of Chicago Press.Kaufmann, Walter, 1975, Existensialism From Dostoevsky to
Sartre, New York: A Meridian Book New American Lib-rary.
Rigali, Norbert, J., 1962, A New Axis: Karl Jaspers’ Philosophyof History, International Philosophy Quarterly, Los Ange-les: Loyola University Press.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 153
BAGIAN KESEPULUH
MAZHAB FRANKFURT:DESKRIPSI KEPENDIDIKAN ERICH FROMM
Sesungguhnya pendidikanbukanlah pemberangusan spontanitas anak,
bukan pula pencekokan pikiran, perasaan, dan harapan yangdipaksakan dari luar dirinya
[Erich Fromm]
PENGANTAR
Mazhab Frankfurt merupakan suatu trend dalam pemikir-an sosio-filosofis radikal Kiri di Barat. Aliran yang disebut se-bagai Neo-Marxisme ini menyatakan “menemukan sekali lagi”serta memulihkan “gagasan sejati” Marx, meskipun dalam ke-nyataannya menyimpang dan memalsukan marxisme. Tulisanini tidak akan memaparkan penyimpangan dan pemalsuan di-maksud, juga bukan merupakan tulisan tentang mazhab Frank-
154 | Win Usuluddin Bernadien
furt secara mendetail, tetapi lebih menyorot salah seorang to-kohnya yaitu Erich Fromm terutama pandangannya mengenaikependidikan.
Erich Fromm (1900-1980) adalah seorang ahli psikologidan filsafat yang dilahirkan di Frankfurt, Jerman. Dia adalahseorang ahli psikoanalisa yang menjadi salah seorang rekanMax Horkheimer, direktur Mazhab Frakfurt tahun 1930. Dalambidang pendidikan, dia berpandangan bahwa sebuah sistempendidikan seyogyalah diarahkan pada kesadaran akan kebe-basan dan kemandirian, bukan pemaksaan sehingga pendidik-an bukanlah sebuah sistem yang menjadikan manusia hanyasebagai mesin sosial yang kehilangan daya dan otoritas, me-lainkan pendidikan itu merupakan proses pembebasan. Frommdianggap liberasionis dalam dunia pendidikan. Sebelum lebihjauh memperbincangkan pemikiran Fromm tentang pendidik-an, terlebih dahulu kami paparkan sedikit tentang MazhabFrankfurt.
MAZHAB FRANKFURT99
Sebutan Mazhab Frankfurt (Die Frankfurter Schule) meru-juk pada sekelompok sarjana yang bekerja pada LembagaPenelitian Sosial (Institut für Sozialforschung) di Frankfurt, Jer-man. Lembaga tersebut didirikan pada tahun 1923 oleh FelixWeil, seorang sarjana politik yang berhaluan kiri, dengan tuju-an membentuk sebuah lembaga pusat penelitian masalah-ma-salah sosial yang independen dan mempunyai dasar finansialyang independen pula. Oleh karena itu lembaga penelitian ini
99Bertens, K,. Filsafat Barat Abad XX, Inggris-Jerman, Jakarta: PT.Gramedia, 1990, hlm. 178. Juga: Suseno-Magnis, Franz,. Marxisme danTeori Kritis Mazhab Franfurt, dalam Mudji Sutrisno & Budi Hardiman,Para Filsuf Penentu Gerak Zaman, Jogyakarta: Kanisius, 1992, hlm. 152.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 155
tidak mau tergantung pada Universitas Frankfurt, meskipun be-berapa anggotanya ada yang mengajar di universitas tersebut.Lembaga penelitian sosial ini kebanyakan anggotanya simpatikepada marxisme sehingga oleh para mahasiswa lembaga pe-nelitian ini dijuluki Café Max.
Pada tahun 1930, di bawah kepemimpinan Max Horkhei-mer lembaga ini mencapai kejayaan, karena menjadi tempatberkumpulnya para sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan bi-dang keahlian sehingga berbagai persoalan yang menyangkutmasyarakat, dapat dipelajari dari berbagai segi ilmiah. KeahlianHokheimer sendiri adalah filsafat sosial. Sementara itu teman-teman terdekatnya, seperti Theodor W. Adorno: musikologi, fil-safat, psikologi, dan antropologi, Erich Fromm: psikoanalisa,Herbert Marcuse: filsafat, Friedrich Pollock: ekonomi.
Lembaga penelitian ini ternyata menentang nasional-so-sialisme yang dikembangkan oleh Hitler yang itu saat berkuasa(1933)oleh karenanya lembaga penelitian ini lalu dibredel. Halini mengharuskan mereka hengkang ke Paris lalu ke New Yorkkarena ternyata Perancis tidak aman untuk mereka. Di NewYork lembaga ini bernama International Institute of Social Re-search. Setelah semuanya memungkinkan, pada tahun 1949dan 1950 Horkheimer, Adorno dan Pollock kembali ke Jermandan Institut für Sozialforschung di bangun kembali, akan tetapiberafiliasi ke Universitas. Dalam perkembangannya lembagapenelitian ini memiliki pengaruh yang luas terutama di kala-ngan mahasiswa. Terbukti lembaga penelitian ini telah menjadiinspirasi Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Situasi ter-sebut berlangsung hingga tahun 1967. Pada ketika itu terjadiperpecahan di antara para aktivis mahasiswa dan pemimpinMazhab Frankfurt, sebab Horkheimer diangkat menjadi Rektormeskipun masih menjadi warga negara Amerika. Sementara
156 | Win Usuluddin Bernadien
itu Fromm dan Marcuse masih tetap tinggal di Amerika.Filsafat yang dikembangkan di dalam Mazhab Frankfrut
dikenal sebagai “Teori Kritis” yang mencita-cita sebuah eman-sipasi dari sebuah sistem ekonomi yang menjadi komoditasmanusia, oleh karena itu manusia harus terbebas dari peng-hisapan ekonomis, lebih dari itu manusia juga harus berjuangmembebaskan diri dari segala macam ancaman, dan oleh ka-rena itu pula manusia harus memperoleh “penerangan budi”sehingga bisa lebih jelas melihat kenyataan, terbebas dari mitosdan mengembangkan rasionalitas. Pembebasan selalu dipaha-mi sebagai kemajuan dalam rasionalitas. Rasionalitas adalahaufklärung terhadap kekuatan-kekuatan mitos.
MODUS ‘MENJADI’ DAN CINTA
Erich Fromm adalah seorang ahli psikologi dan filsafat so-sial yang dilahirkan di Frankfrut, Jerman. Dia belajar psiko-analisa di Universitas Munchen dan di Institut für Psycoanalysedi Berlin. Pada tahun 1952 dia mulai praktek di bidang psiko-nalisa sebagai pengikut Freud, tetapi berangsung-angsur berse-berang pendapat disebabkan Freud dinilai mengabaikan pen-ga-ruh faktor sosial ekonomi terhadap pikiran manusia.
Sigmund Freud memiliki pemikiran bahwa manusia ituberada dalam Jiwa. Jiwa terdiri atas 3 sistem, yaitu: Id, Super-ego, dan Ego. Id merupakan dorongan primitif yang belum di-pengaruhi oleh kebudayaan yaitu life instinc (libido) dan deathinstinc (agretion). Id menganut prinsip kesenangan (pleasureprinciple) yang bertujuan memuaskan seluruh dorongan primi-tif. Superego adalah sistem yang dibentuk oleh kebudayaanberupa dorongan berbuat baik dan dorongan memenuhi nor-ma.Superego menekan Id sehingga selalu terjadi pertentangan.Saling tekan dan saling dorong antara Id dan Superego disebut
Serpihan-Serpihan Filsafat | 157
Ego. Dengan demikian fungsi Ego adalah menyeimbangkandua sistem tersebut dengan .kenyataan di dunia luar. AkibatEgo yang lemah adalah tidak mampu menjaga keseimbanganantara Id dan Superego. Jika Id yang lebih dominan makaseseorang itu akan cenderung mengabaikan segala bentuk nor-ma (psikopat), dan jika Superegonya yang dominan maka se-seorang itu akan menjadi psikoneuros artinya tak mampumenyalurkan sebagian besar dorongan primitifnya.100
Tentang manusia, Fromm berpandangan bahwa manusiaadalah makhluk yang ‘menjadi’. Dalam modus ini manusiamengarahkan diri kepada usaha aktualisasi potensi diri tanpadikuasasi oleh apa yang dimilikinya.Prasyarat modus ‘menjadi’adalah kemandirian, kebebasan, dan penalaran kritis. Ciri khasyang fundamental adalah keadaan aktif bathini dan produkti-vitas. Bagi Fromm cinta adalah kekuatan yang aktif dalam dirimanusia yang mendobrak benteng pemisah antara seseorangdengan seseorang yang lainnya, yang menyatukan seseorangdengan seseorang yang lainnya. Cinta membuat seseorang sa-nggup mengatasi rasa keterpisahan dan alienasi diri, tetapi se-kaligus sanggup menjadikan diri yang mampu mempertahan-kan keutuhannya. Dalam cinta terjadi paradoks: dua makhlukmenjadi satu namun tetap tinggal dua. Cinta yang matang itumanakala seseorang tetap mempertahankan keutuhan indivi-dualitasnya. Cinta yang yang paling tinggi adalah cinta kepadaTuhan. Cinta ini berasal dari kebutuhan untuk mengatasi keter-pisahan dan untuk mencapai penyatuan. Tuhan berarti nilaiyang tertinggi, kebaikan yang didamba dan yang paling dirin-
100Honderich, Ted., The Oxford Conpanion to Philosophy, NewYork: Oxford University Press, 1995, hlm. 300-3001.
158 | Win Usuluddin Bernadien
dukan bagi setiap pribadi.101
PENDIDIKAN YANG MEMBELENGGU
Cakrawala demokrasi modern telah menaungi manusiauntuk dapat secara bebas dan bertanggung jawab mengung-kapkan gagasan dan pikirannya. Namun demikian, betapapunkekebasan itu telah menjadi garansi bagi individualitas, tidakakan memiliki arti apa-apa manakala individu itu tidak memi-liki kemampuan untuk berpikiran secara mandiri, kebebasanitu tidak bermakna apa-apa bagi seseorang manakala sese-orang itu tidak mampu menetapkan individualitas dirinya.Apalagi situasi ekonomi saat ini telah mengantarkan sebagainbesar manusia pada kondisi tidak berdaya dan teralienasi yangpada gilirannya memaksa berkompromi untuk menjadi diriyang hidup dan berpikir serupa mesin yang serba otomatis, ser-ta kehilangan harkat dan martabat dirinya. Ironisnya, manusiaseperti itu justru terbenam dalam khayal kejayaan individua-litas.102
Situasi seperti itu memastikan setiap diri yang berkesadar-an untuk berpikir bagaimana budaya memupuksuburkan ke-cenderungan individu menjalani konformitas dengan sesama-nya, melecutkan setiap perkembangan individualitas sejati se-jak dini sehingga tidak terjadi ‘pengkerdilan’ di kemudian hari,lewat proses pendidikan yang dijalaninya. Sasaran pendidikanadalah mengokohkan individualitas sejati dan kemandirian se-jati anak, mengokohkan dan mengintegralkan secara kental
101Fromm, Erich., Seni Mencinta, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1987, hlm. 182.
102Baca pula: Formm, Erich., Mendidik Si Automaton, dalam OmiIntan Naomi, Menggugat Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999,hlm. 343.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 159
perkembangan kejiwaan anak. Sesungguhnya pendidikan bu-kanlah pemberangusan spontanitas anak, bukan pula penceko-kan pikiran, perasaan, dan harapan yang dipaksakan dari luardirinya.Pendidikan, jelas bukan merupakan penerapan metodayang melegalkan pengancaman, penghukuman, menakut-na-kuti, ataupun “penjelasan” yang menyebabkan anak menang-galkan sikap “menentang”, dan tidak memiliki kemampuanuntuk mengungkapkan perasaan-perasaan sejatinya, bahkanakhirnya kèlangan roso pangrasanè, sehingga anak tidak mam-pu mencapai ‘kematangan’, kehilangan kemampuan untukmembedakan sosok pribadi yang baik dan yang tidak baik.Seiring dengan itu, anak diajar untuk menekan kesadaran akansikap menentang dan ketidaktulusan orang lain. Anak diajariuntuk berperasaan sesuai dengan apa yang dijejalkan kepadamereka yang sama sekali bukan sikap orisinalnya sehinggaanak kehilangan kesadaran untuk dapat membedakan kerama-han yang tulus atau perasaan gadungan yang penuh kepalsuandan basa basi yang tanpa makna. Padahal pada dasarnyaanak-anak itu sesungguhnya mampu menangkap dengan ce-pat sisi negatif dalam diri orang lain dan tidak mudah tertipudan terkelabui oleh kata-kata. Anak-anak pada dasarnya lebihmudah menangkap pancaran kekasaran atau kepalsuan dariorang-orang yang tidak mereka sukai.
Menurut Fromm, dalam masyarakat pada umumnya,emosi tak didorong. Berpikir dan hidup tanpa emosi sudahmenjadi pola ideal sehingga individu menjadi sangat lemah,datar, dan tandus pemikirannya. Pada sisi yang lain, karenaemosi tidak dapat dilenyapkan sepenuhnya maka emosi ter-gusur ke ranah keberadaan yang seutuhnya terpisah dari sisiintelektual dalam kepribadian manusia. Akibatnya sentimentali-tas ‘kacangan’ yang tak tulus. Lebih jauh, Fromm mengemuka-
160 | Win Usuluddin Bernadien
kan bahwa sejak langkah awal, pendidikan telah terjadi pene-kanan dan pembengkokan terhadap pemikiran orisinal. Kedalam benak ‘anak-anak’ dijejali berbagai gagasan siap pakai.Padahal sesungguhnya ‘anak-anak’ itu memiliki rasa ingin tahuyang meluap-luap, mereka sesungguhnya punya keinginan un-tuk dapat menangkap kebenaran semua realitas baik secarafisik maupun secara intelektual. Akan tetapi keinginan merekaitu tak pernah terpenuhi secara serius. Mereka justru seringkalidimarahi manakala menanyakan hal-hal yang ingin merekaketahui atau mungkin dengan santun perhatian mereka dialih-kan pada suatu hal yang lain. Akibatnya pemikiran orisinalmereka semakin terbelenggu.103
BEBERAPA METODA PENDIDIKAN DEWASA INI
Beberapa metode pendidikan yang digunakan dewasa ini,menurut Formm adalah sebagai berikut:
Pertama: Mengedepankan pengetahuan tentang faktaatau pengetahuan tentang informasi. Metode ini mengandai-kan bahwa semakin banyak mengetahui dan makin banyakfakta anak akan sampai pada pengetahuan tentang kenyataan.Metode seperti ini menurut Formm hanyalah akan mengantar-kan anak pada keputusasaan karena hanya akan membuang-buang energi secara percuma, dan pemikiran orosinal anakakan semakin terbelenggu. Semakin banyak fakta yang dijejal-kan di kepala anak maka semakin sempit ruang yang tersisauntuk berpikir. Memang berpikir tanpa tahu tentang fakta akankosong melompong, akan tetapi jika hanya ‘informasi sajayang ditelan’ maka akan menghalangi tindakan berpikir.
Hal lain yang merintangi pemikiran orisinal adalah ang-gapan bahwa seluruh kebenaran itu bersifat relatif, kebenaran
103Naomi, ibid, hlm. 347.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 161
itu hanyalah konsep metafisis, dan sepenuhnya bersifat sub-jektif. Oleh karena itu penyelidikan ilmiah harus steril dari fak-tor subjektif. Kelompok ini diwakili oleh kaum relativism atauyang lebih sering dikenal dengan empirisism atau positivismeAnggapan semacam itu hanya akan melenyapkan rangsanganesensial bagi kegiatan berpikir, dan hanya menjadikan anak se-bagai mesin penyimpan fakta. Padahal sesungguhnya pencari-an kebenaran itu berakar pada kepentingan dan kebutuhanindividu serta kelompok sosial, tanpa kepentingan semacam ituakan kurang stimulasi untuk mencari kebenaran. Satu hal yangharus dipahami oleh semua adalah bahwa dalam diri setiapmanusia tersimpan damba akan kebenaran sebab setiap ma-nusia, termasuk pula anak-anak, memang mendambakan ke-benaran. Pengetahuan tentang kebenaran yang menyangkutdiri merupakan kekuatan yang luar biasa untuk mendongkrakkelemahannya. Kekuatan terbesar individu didasari oleh maksi-malisasi integritas kepribadian. Gnothi Se Auton merupakan‘perintah’ yang mendasari analisis diri dan pemahaman diriuntuk mencapai pengetahuan dan tingkah laku lebih baik. Pe-rintah fundamental ini tujuannya adalah kekuatan dan keba-hagian bagi umat manusia.104
Kedua: metoda pendidikan yang mengaburkan dan me-nyulut kesimpangsiuran. Metoda ini menyatakan bahwa berba-gai persoalan kehidupan ini sedemikian rumit untuk bisa dipa-hami rata-rata individu kecuali hanyalah oleh segelintir pakaratau spesialis saja yang bisa mengerti. Ini seringkali dilakukandengan sengaja untuk melemahkan semangat orang awam se-hingga mereka tidak berdaya pada kemampuan diri merekasendiri, secara naïf menunggu sampai sang pakar menemukan
104Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2000, hlm. 281. Baca juga Naomi, op.cit., hlm. 349.
162 | Win Usuluddin Bernadien
jalan yang harus ditempuh. Hal ini berdampak pada skeptisis-me, sinisme,105 dan sikap kekanak-kanakan. Perpaduan antarakenaifan dan kesinisan adalah tipikal manusia modern. Hasil-nya, manusia yang tidak memiliki dorongan untuk berpikir dantidak mampu mengambil keputusan sendiri. Cara lain untukmelumpuhkan berpikir kritis adalah menghancurkan gambaranterstruktur manapun tentang dunia, akibatnya individu tidaklagi merasa memiliki keterkaitan orisinal dengan apa yang di-dengar dan dilihat. Individu tak lagi merasakan gejolak hati,emosi, dan penilaian kritisnya menjadi datar, akhirnya munculsikap hampa dan tak perduli dengan segala apa yang berlang-sung disekitarnya. Atas nama kebebasan hidup ini kehilanganstrukturnya, hidup ini dirasakan sebagai serpihan-serpihan kecilyang tidak saling terkait satu dengan lainnya, hidup ini menjadiseakan tanpa makna. Akibatnya hidup menjadi gelisah dantakut seakan tanpa ada pelipur.
Pada sisi yang lain, manusia modern seolah terlalu banyakberharap dan berkehendak, tanpa tahu persis apa makna ha-rapan dan kehendak itu bagi dirinya. Manusia modern seakantelah kehilangan arti dan pengetahuan tentang apa yangsesungguhnya menjadi kehendak sejatinya. Manusia modernhidup di bawah ilusi, bagai seorang aktor yang mati-matianmemerankan lakon yang ia mainkan atas skenario yang di-rancang oleh orang lain.106
105Skeptisisme adalah pandangan bahwa akal tak mampu sampaipada kesimpulan, atau kalau tidak, akal tidak mampu melampui hasil-hasil yang paling sederhana. Manusia tidak dapat mencapai kebenaran.Sedangkan Sinisme dapat dimengerti sebagai keyakinan bahwa manusiamelulu terpusat pada diri sendiri, munafik, tidak tulus, dan hanya baikpada dirinya sendiri. (Lorens, 2000: 1017 dan 1012).
106Naomi, ibid, hlm. 352.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 163
KEWENANGAN DAN KEBEBASAN
Menurut Erich Formm kesulitan yang dihadapi manusiasaat ini adalah membedakan apakah keinginan, pikiran, danperasaan yang ada pada dirinya masing itu benar-benar di-miliki oleh dirinya sendiri atau suntikan orang lain. Kesulitanini berkait erat dengan kewenangan dan kebebasan.
Dalam sejarah modern, terpapar jelas bahwa otoritas ge-reja telah digantikan negara, lalu kewenangan negara diganti-kan oleh otoritas kesadaran, dan kini otoritas kesadaran telahdigantikan oleh kewenangan akal sehat dan pendapat umum.Kini, setelah manusia membebaskan diri dari kekangan otoritaslama, secara tak sadar telah menjadi mangsa kewenangan ba-ru. Kita menjadi automaton yang hidup di bawah khayalanakan ‘kehendak bebas’ sebagai individu. Masing-masing indi-vidu merasa telah kehilangan sifat saling terkait, bahkan indi-vidu telah kehilangan diri yang menjadi dasar rasa aman sejatisesosok individu merdeka.
Lenyapnya jatidiri menjadikan orang hanya bisa yakinakan dirinya sendiri manakala ia mencocokkan diri dengan ha-rapan orang lain, dan dengan begitu hilanglah ketidaksetujuanorang lain dan keterpencilan, meski harus kehilangan jatidirikepribadian.Dengan menyesuaikan diri kesangsian akan jatidiriakan terbungkam dan rasa aman pun akan tercapai. Tapiharganya mahal: hilangnya spontanitas dan individualitas yangberarti pula mengerdilkan makna hidup, dan hanya menjadiautomaton yang secara biologis hidup tetapi secara psikologis(mental dan emosional) mati. Automaton tak bisa mengalamihidup dalam citarasa spontanitas, sehingga hidupnya kalangkabut, fiktif, dan putus asa.
164 | Win Usuluddin Bernadien
PENUTUP
Pendidikan dapat dimengerti sebagai bimbingan yangdiberikan seseorang agar ia berkembang secara maksima.107
Pendidikan adalah refleksi kebudayaan, artinya bahwa pendi-dikan merupakan cerminan kebudayaan yang menjadi sum-bernya.108 Pendidikan juga berarti upaya membebaskan manu-sia dari penindasan yang tak disadari, karena itu pendidikanharus menjadikan anak sadar akan jatidirinya juga bagaimanahubungan antara dirinya dan dunia di luar dirinya sehinggaanak didik tergugah sadar bahwa kebebasan diri itu ternyatidak sebebas yang dibayangkan, kebebasan itu ternyata terba-tasi oleh kebebasan pula. Pendidikan juga seharusnya mampupula menyadarkan bahwa pemaksaan dan penindasan itutidak hanya mengenai fisik dan luaran saja tetapi merasuk ke-dalam relung jiwa dan kesadaran manusia. Maka tugas da-sariah pendidikan adalah membantu manusia untuk membe-baskan diri dari penindasan yang tidak disadari itu. Pendidikanharus membuat manusia bebas menemukan dan menjadi diri-nya sendiri sekaligus menghargai orang lain untuk dapat men-jadi dirinya. Begitulah deskripsi yang dicita-citakan oleh ErichFromm dalam kaitannya dengan pendidikan. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Ahmad Tafsir, 1992, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam,Bandung: Rosda Karya
Ali Mudhofir, 2001, Kamus Filsafat Barat, Yogyakarta: PustakaPelajar
107Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Ban-dung: Rosda Karya, 1992, hlm. 24-27.
108Imam Barnadib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogya-karta: Yayasan FIP-IKIP Yogyakarta, 1982, hlm. 27.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 165
Bertens, K,. 1990, Filsafat Barat Abad XX, Inggris-Jerman,Jakarta: PT. Gramedia.
Fromm, Erich,.1987, Seni Mencinta, Jakarta: Pustaka SinarHarapan
Formm, Erich,. 1999, Mendidik Si Automaton, dalam Omi In-tan Naomi, Menggugat Pendidikan, Yogyakarta: PustakaPelajar.
Honderich, Ted., 1995, The Oxford Conpanion to Philosophy,New York: Oxford University Press
Imam Barnadib, 1982, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan,Yogayakarta: Yayasan FIP-IKIP Yogyakarta
Lorens Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama
Suseno-Magnis, Franz,. 1992, Marxisme dan Teori Kritis Maz-hab Franfurt, dalam Mudji Sutrisno & Budi Hardiman,Para Filsuf Penentu Gerak Zaman, Jogyakarta: Kanisius
Serpihan-Serpihan Filsafat | 167
BAGIAN KESEBELAS
JEAN PAUL SARTRE: EKSISTENSIALIS YANGMENANGKAP HAKIKAT MANUSIA
“Jika Allah ada maka tiada lagi peluangbagi kebebasan manusia.
Karenanya hanya ada dua pilihan:tunduk pada-Nya atau menjadi Dia”
[Sartre]
PENGANTAR
Tulisan ini difokuskan pada pemikiran Sartre, yang ber-pandangan bahwa setelah selesai diciptakan manusia memilikikebebasan untuk ‘menjadi dirinya sendiri’, memiliki kemampu-an untuk memutuskan kebenaran apa yang diinginkan atauyang ‘seharusnya’ ia lakukan. Sartre merumuskan: EksistensiMendahului Essensi, artinya manusia tidak pernah memiliki ha-
168 | Win Usuluddin Bernadien
kikat essensial dan tidak pernah diciptakan untuk tujuan ter-tentu oleh Tuhan ataupun oleh kekuatan lain, tetapi manusiajustru harus menciptakan essensi dirinya sendiri. Inti pemikiraneksistensialisme Sartre adalah kebebasan manusia yang berke-mampuan memilih sikap, tujuan, nilai, serta tindakannya. Me-nurut dia kebebasan adalah kebenaran.
Setiap aspek kehidupan jiwa manusia, bagi Sartre, meru-pakan sesuatu yang dipilih dan dipertanggung jawabkan seu-tuhnya oleh diri manusia. Tegasnya, manusia adalah makhlukyang dalam eksistensinya harus dapat ‘membuat diri sendiri’menjadi apa yang ia inginkan. Dengan kata lain dan yangmenjadi kata kuncinya ialah bahwa hakikat eksistensi manusiaadalah kebebasan absolut.
JEAN PAUL SARTRE DAN KARYANYA
Sartre adalah tokoh eksistensialis yang mencapai tingkatpopularitas luar biasa. Tidak banyak filsuf yang dapat menya-mai popularitasnya sepanjang abad XX yang lalu.109 Dia lahirpada tanggal 21 Juni 1905 dalam lingkungan keluarga cendi-kiawan yang borjuis menengah di Paris, dari seorang ibu yangbernama Anne Marie Schwietzer anak bungsu dan satu-satu-nya perempuan dari Charles Schwietzer. Ayahnya bernamaJean Baptiste seorang perwira Angkatan Laut Prancis yang ber-tugas di Indocina dan telah meninggal dunia saat Sartre masih
109FX. Mudji Sutrisno & F. Budi Hardiman (ed.), 1992, hlm. 100-101. Tentang Sartre lihat pula: Dr. P.A. van der Weij, Filsuf-Filsuf Be-sar tentang Manusia, Diindonesiakan oleh K. Bertens, Yogyakarta: Ka-nisius, 2000, hlm. 145, dan K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX, Jilid II,Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 81-87.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 169
berusia dua tahun.110 Sartre kemudian diasuh oleh ibunya dirumah kakeknya. Di bawah pengaruh kakeknya ini Sarte didi-dik dan dikembangkan bakatnya secara maksimal. Pengala-man masa kecilnya ini telah banyak memberikan inspirasi pa-danya untuk masa-masa selanjutnya. Kisah hidup masa kanak-kanak ini kelak ditulis dalam bukunya yang berjudul Lest Most(Kata-Kata). Buku ini bernada negatif terhadap masa kanak-kanaknya. Penderitaan pada masa kanak-kanaknya dipandangenteng dan ringan, dipandang sebagai pemutusan hubunganyang mendalam dan kejam dengan kenyataan yang disajikandengan gaya yang sangat menarik dan menyenangkan. Dalamkarya itu disajikan rasa kehilangan Sartre, bukan penderitaan-nya. Juga disajikan dalam buku itu ke-tidak-riil-annya, bukankerasingannya. Dalam buku itu pula digambarkan masa kanak-kanaknya yang tersiksa dan penuh perlawanan menjadi indahdan disepuh dengan khayalan. Kata-Kata merupakan karyanyayang berupaya untuk menemukan diri sendiri yang menjadipelarian diri dalam seni.111
Sebenarnya Sartre berasal dari keluarga Kristen Protestandan ia sendiri dibaptis menjadi Katholik, akan tetapi dalamperkembangan pemikirannya ia malah tidak menganut agamaapa pun. Sartre tidak percaya kepada Tuhan. Ia adalah seo-rang atheis konsekwen yang telah dijalaninya sejak usia duabelas tahun. Baginya, dunia sastra adalah agama baru, karenaitu ia menginginkan untuk menghabiskan hidupnya sebagai
110Fuad Hasan, 1992, hlm. 131.111lihat Kata Pengantar dalam Jean Paul Sarte, Kata-kata, alih
bahasa: Jean Couteau, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.xxxvii.
170 | Win Usuluddin Bernadien
pengarang.112 Meski pun lama kelamaan ia juga menyadaribahwa kepercayaan seperti itu keliru.113
Sartre menjalani pendidikan informal hingga berusia sepu-luh tahun empat bulan bersama ibu dan kakeknya. Kemudianmemasuki pendidikan formal di Lycée Henri IV di Paris. Bebe-rapa tahun kemudian disekolahkan di Lycée Louis-le-Grand,lalu selama empat tahun yaitu pada tahun 1924-1928, Sartrebelajar di Perguruan tinggi terkemuka dan paling selektif, ÉcoleNormale Supérieure. Setelah menamatkan studinya, denganmemperoleh Agrégation de philisophie yaitu sebuah gelar yangdiperoleh setelah lulus pendidikan tinggi dalam bidang filsafatuntuk para pengajar, ia mengajar di Lycée Prancis.114 Padatahun 1931 Sartre mengajar sebagai guru filsafat di Laon danParis. Pada periode inilah Sartre bertemu dengan Husserl yangpadanya ia mendalami fenomenologi dalam mengungkapkanfilsafat eksistensialisme-nya.115 Pada tahun 1933-1935 melan-jutkan program doktornya di Jerman.
Menjelang perang dunia II (1938-1941) Sartre menjalaniwajib militer sebagai tentara, ia sempat menjadi tawanan pe-rang. Pasca PD II, ia terkenal sebagai pemikir yang unggul lan-taran pada tahun 1945 menerbitkan majalah ‘Lés Temps Mo-dérnes’ (Era Modern) bersama dengan dua teman karibnya,Maurice Merleau Ponty (1908-1961) dan Simon de Beauvoir
112Dagun, Save M., Fisafat Eksistensialisme, Jakarta: Rineka Cip-ta, 1990, hlm. 94.
113Couteau, op. cit, hlm. viii.114Couteau, ibid, hlm.viii-ix. Lycée adalah sejenis sekolah persia-
pan masuk perguruan tinggi, selebihnya bisa dibaca: Paul Strathern,90 Menit Bersama Sartre, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm. 8.
115Dagun, op. cit., hlm. 95.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 171
(1908-1986). Majalah inilah yang kemudian menjadi corongbagi pemikiran eksistensialismenya yang bertitik tolak pada pa-ham kebebasan manusia. Baginya, manusia setelah diciptakanmemiliki kebebasan untuk menentukan dan mengatur hidup-nya sendiri. Kesadaran ini adalah hasil dari tempaan pengala-man-pengalaman hidupnya selama ia menjalani dinas kemilite-ran. Perang, kekejaman, penderitaan, penganiayaan, dan se-gala bentuk penindasan eksistensi manusia mengantarkannyauntuk mampu melihat problematika kemanusiaan dalam be-reksistensi: Kebebasan. Majalah ‘Lés Temps Modérnes’ yangditerbitkan pada saat ia telah berhenti menjadi tentara tersebutjelas berhaluan kiri. Tujuannya adalah memberikan tanggapanatas pelbagai peristiwa serta perkembangan penting dalam bi-dang budaya dan politik. Beberapa karya besarnya yang da-pat disebutkan disini, antara lain adalah: L’etre et le neant. Es-sai d’ontologie phenomenologique (1943), Vérité et existence(1948) Les Mots (1964), dan lain-lainnya baik yang berupaskenario film (misalnya Baudelaire, 1947), maupun filsafat (mi-salnya: L’existentialisme est un humanisme, 1943).
Pada tahun 1964 ia dipilih menjadi pemenang HadiahNobel bidang sastra, akan tetapi ia menolak sebab baginyamenerima hadiah itu sama saja artinya dengan memasukkandiri dalam kalangan borjuis atau kapitalis dan kegiatannya se-bagai pengarang akan dibekukan. Sartre pun tidak segan me-masuki dunia politik dalam negeri Prancis maupun interna-sional. Sartre adalah seorang berhaluan kiri dan penuh simpatipada partai-partai kiri. Dalam pada itu pada tahun 1966 ia ikutambil bagian dalam International Tribunal against war crimesin Vietnam, sebuah lembaga yang bermaksud menyelidiki ke-jahatan perang yang dilakukan serdadu Amerika Serikat di
172 | Win Usuluddin Bernadien
Vietnam dengan bantuan norma-norma yang diciptakan nege-ra-negera demokrasi. Demikian juga saat ‘revolusi mahasiswa’pecah di Paris (Mei 1968) ia mengikuti dengan penuh perha-tian terhadap peristiwa yang berlangsung, serta mengecamberbagai tindakan kejam yang dilakukan polisi Prancis. Sartrebahkan mendukung para mahasiswa untuk ‘menghancurkan’Universitas Sorbonne dalam bentuknya yang lama.116 Di saatusianya mencapai 75 tahun, tepatnya pada tanggal 15 April1980, Jean Paul Sartre menghembuskan nafas terakhir untukkembali ke alam baka setelah menjalani perawatan untuk suatupenyakit yang tidak diketahui, di rumah sakit selama sebulan.
TENTANG HAKIKAT MANUSIA
Sartre menolak teori ‘hakikat manusia’ yang benar atausalah, suatu sikap khas eksistensialisme terhadap pernyataanumum mengenai manusia dan kehidupannya. Sartre mengek-spresinya dalam rumusan: ‘eksistensi mendahului essensi’117,artinya manusia tidak pernah memiliki hakikat ‘essensia’ dantidak pernah diciptakan untuk tujuan tertentu oleh Tuhan, ke-kuatan evolusi, atau yang lainnya. Dengan kata lain manusiamenemukan dirinya ada tanpa pilihan, manusia sendiri danmemutuskan apa yang membuat dirinya seperti ini, masing-masing harus menciptakan ‘essensia’ sendiri-sendiri. Sartredengan tegas menolak adanya essensia universal manusia. Ba-ginya tidak ada kebenaran-kebenaran umum mengenai apa
116Couteau, op. cit., hlm. xii-xiii117Sartre, Being and Nothingness,An Essay on Phenomenological
Ontology, translated and with an introduction by Hazel E. Barnes,New York: Philosophical Library, 1943, p. 438-439. Pada tahun 2003,buku ini diterbitkan kembali.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 173
yang diinginkan atau yang seharusnya dilakukan manusia.Namun demikian, sebagai seorang eksistensialis, Sartre tetapharus membuat beberapa pernyataan umum mengenai hakikatdan kondisi manusia yang senyatanya. Penekanan utamanyaadalah pada kebebasan manusia. Sartre mengatakan bahwamanusia ‘dikutuk untuk menjadi bebas’. Kebebasan itu tidakada batasnya, karena memang tidak ada batasan bagi kebeba-san, yang ada adalah berhenti menjadi bebas.118
a. Dilema Kebebasan menuju PembebasanJika dicermati secara seksama akan dapat dimengerti
bahwa seluruh pemikiran Sartre selalu bermuara pada konsepkebebasan. Kebebasan absolut adalah kata kunci seluruh filsa-fat Sartre. Baginya manusia adalah diri yang berkebebasan.Manusia adalah satu-satunya makhluk yang eksistensinya men-dahului essensinya. Manusia tidak memiliki kodrat karena ma-nusia selalu memiliki kemungkinan untuk mengatakan ‘tidak’.Selagi manusia masih hidup, manusia dapat mengatakan ‘ti-dak’. Manusia is not what he is. Baru setalah mati, manusia da-pat dilukiskan ciri-ciri hakiki yang menandai hidupnya.
Bagi Sartre kematian adalah sesuatu yang absurd, karenakematian adalah kenyataan yang tidak bisa ditunggu saat ti-banya meskipun dapat dipastikan akan tibanya. Kematian me-rupakan ekspentansi yang selalu samar dalam antisipasi manu-sia. Manusia tidak bisa memilih tibanya kematian sebab kema-tian bukanlah sebuah kemungkinan, melainkan sebuah kepas-tian nistanya manusia sebagai eksistensi. Lebih dari itu kema-
118Ibid, hlm. 439, Sartre menuliskan: Iam condemned to exist forever beyond my essence,...Iam condemned to be free. This means thatno limits to my freedom can be found except freedom it-self or, if youprefer, that ew are not free to cease being free.
174 | Win Usuluddin Bernadien
tian datangnya di luar dugaan dan di luar pilihan kita sendiri.Sartre mengambil contoh, seorang yang menyiapkan dirinyasebagai pengarang maka ia akan belajar dan terus menerusberlatih, tetapi bisa saja ia mati sebelum sempat menulis hala-man yang pertama.119 Kematian, bagi Sartre, tidak bermaknaapa-apa bagi eksistensi sebab begitu kematian tiba eksistensipun selesai dan diganti essensi. Dengan kata lain kematian me-rupakan kenyataan yang berada di luar eksistensi. Kematianmanusia itu bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk merekayang ditinggalkan. Jadi, untuk orang lain. Merekalah yangakan memberi arti pada kematian kita masing-masing, bukankita sendiri. Inilah yang ia maksud dengan l’etreautrui (being-for-other).
Tentang kebebasan, pemikiran Sartre mengalami pergese-ran dari kebebasan ‘liberté’ menuju pembebasan ‘libération’.120
Mula-mula Sartre mendewakan kebebasan sebagai inti eksis-tensi manusia. Kemudian perhatiannya dipusatkan pada per-soalan pembebasan. Kebebasan manusia itu tampak dalamkecemasannya. Untuk dapat menyembunyikan kecemasannyadan melarikan diri dari kebebasannya, manusia harus menge-tahui baik-baik apa yang disembunyikan dan dijauhkan. Mela-rikan diri dari kebebasan dan menjauhkan diri dari kecemasansecara serentak berarti manusia menyadari akan kebebasandan kecemasannya. Dengan demikian manusia mengakui se-rentak kebebasan dan ketidakbebasannya. Sikap ini oleh Sartredisebut mauvaise foi (sikap malafide, bad faith), yaitu mengakui
119Fuad Hasan, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Jakarta:Pustaka Jaya, 1992, hlm. 143.
120Bertens, K, Fenomenologi Eksistensialisme¸ Jakarta: PT. Gra-media, 1987, hlm. 165-166
Serpihan-Serpihan Filsafat | 175
sekaligus menyangkal terhadap apa yang dihayati. Jadi, me-nurut Sartre, manusia itu sesungguhnya menipu dirinya sendiri.
Kebalikan dari kecemasan, menurut Sartre, adalah espritde sérieux (spirit of seriousness: suasana pikiran yang serius).Tatkala kecemasan menunjukan kebebasan yang tidak berda-sar, maka esprit de sérieux memandang nilai dan makna seba-gai data objektif, tak tergantung pada subjek yang menilai. Ma-nusia menjadi objek yang ditentukan oleh faktor objektif yanglain. Manusia diberi suatu kodrat yang dianggap merupakanasal muasal perbuatan, keinginan, dan penghayatannya.
Singkatnya, menurut Sartre manusia itu sebenarnya me-nghadapi dilema sebagai berikut: manusia itu sama sekali be-bas atau tidak bebas sama sekali. Tidak ada kemungkinan keti-ga. Kebebasan manusia benar-benar absolut. Tidak ada batas-batas kebebasan kecuali batas-batas yang ditentukan oleh ke-bebasan itu sendiri. Pandangan inilah yang mengantarkan Sar-tre untuk berkesimpulan bahwa: Seandainya Allah ada tidakmungkin saya bebas. Allah itu Mahatahu yang sudah menge-tahui segala-galanya sebelum aku melakukan dan Allah pula-lah yang akan menentukan hukum moral. Kalau begitu, tidakada peluang lagi bagi kreativitas kebebasan. Allah sebagai AdaAbsolut tidak boleh tidak akan memusnahkan kebebasan ma-nusia.121Lebih dari itu, Sartre menyatakan: But the idea of Godis contradictory and we lose ourselves in vain.122 Ide terdalammengenai Tuhan mengalami kontradiksi dalam dirinya sendiridan sia-sia belaka serta tidak bermakna apa-apa dalam hidupmanusia. Dalam pandangannya, tidak ada nilai-nilai transen-den objektif yang tersedia bagi manusia, termasuk hukum-hu-
121Bertens, ibid, hlm. 81-87.122Sartre, op. cit. hlm. 615.
176 | Win Usuluddin Bernadien
kum Allah sekalipun. Tidak ada makna paling tinggi atau tu-juan yang inheren dalam eksistensi manusia. Hidup manusiadi dunia ini ‘absurd’, sedih dan kesepian, tidak ada Bapa Sur-gawi yang harus mengatakan kepada kita apa yang harus dila-kukan dan membantu kita untuk melakukan keharusan itu.Manusia harus memutuskan apa yang harus ia putuskan untukdirinya sendiri dan bertanggung jawab untuk dan kepada di-rinya sendiri. Pondasi semua nilai hanya ada dalam diri ma-nusia sendiri dan dalam kebebasan manusia untuk memilihsehingga sebenarnya tidak ada pembenaran eksternal ataupunpembenaran objektif atas nilai, tindakan, dan jalan hidup yangdianut oleh seorang manusia.123 Karena itu, sekali lagi, Sartremenolak teori ‘hakikat manusia’ yang benar atau salah.
b. L’étre pour-soi dan L’étre-en-soiSartre mendefinisikan ontologinya dalam bingkai perten-
tangan antara mengada untuk dirinya sendiri (Being-for-itself-L’étre pour-soi) dan mengada dalam dirinya sendiri (Being-in-inself -L’étre-en-soi).124
Kesadaran akan diri sendiri (cogito) merupakan titik tolakfilsafat modern. Menurut Sartre kesadaran (akan) diri beradasebagai kesadaran sesuatu. Kesadaran adalah kesadaran diri.Tetapi kesadaran (akan) dirinya tidak sama dengan pengala-man tentang dirinya: mengambil dirinya sebagai obyek penge-nalan. Cogito bukanlah pengenalan diri, melainkan kehadirankepada dirinya secara non-tematis.125 Dengan demikian, harus
123Sartre, ibid. hlm. 38.124Solomon, Robert C., Higgin, Kathleen M., A Short History of
Philosophy, New York: Oxford University Press, 1996, p. 281.125Karena itu kata ‘akan’ oleh Sartre ditulis dalam tanda kurung,
ibid, hlm. 91.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 177
dibedakan antara kesadaran tematis dan kesadaran non-tematis: kesadaran akan sesuatu dan kesadaran (akan) dirinya.Kesadaran (akan) dirinya tidak menunjuk pada suatu relasipengenalan, melainkan pada suatu relasi Ada. Kesadaran ada-lah kehadiran (akan) dirinya. Kehadiran (pada) dirinya meru-pakan syarat kesadaran.
Sartre mempunyai pandangan tersendiri dalam melihatkeberadaan suatu ada atau yang ada. Ia melihat ada atau yangada dengan dua sudut pandang. Pertama: ada dilihatnya seba-gai ada yang hidup dan berada untuk dirinya (L étre por-soi).Kedua: sebagai ada yang identik dengan dirinya, tidak aktif,tidak pasif, tidak afirmatif, dan tidak negatif (étre-en-soi).126
Sartre menjelaskan bahwa manusia adalah étre-por-soi (ada-untuk-diri) bukan étre-en-soi (ada-dalam-diri). Hal itu artinyamanusia adalah suatu proyek. Manusia memproyeksikan di-rinya kepada cita-cita dan nilai-nilai yang nun jauh di sana.Hidupnya adalah suatu gerakan tanpa berhenti untuk menjadisesuatu yang belum ia miliki. Manusia, menurut Sartre, menen-tukan kodratnya sendiri. Jika suatu proyek sudah selesai, makamanusia menuntut proyek yang baru, begitu seterusnya. Kege-lisahan merajalela; manusia senantiasa tidak tenang, bergiatterus. Dia mendefinisikan dirinya dengan memilih dalam ke-cemasan (Angst). Kecemasan itu tetap. Manusia terhukum olehkecemasan sebagaimana ia tersiksa dalam kebebasan. Létrepor-soi bagi Sartre adalah ungkapan untuk menyatakan eksis-tensi manusia sebagai subjek murni yang sadar, yang mampumemilih secara bebas dan bertanggung jawab atas pilihannyaitu atas dirinya sendiri, tidak pada orang lain. L’étre por-soi
126Loren Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 2000,hlm. 202-203 dan hlm. 875.
178 | Win Usuluddin Bernadien
hanya dimiliki oleh manusia. Manusia adalah ‘berada-untuk-diri’ (étre por-soi), oleh karenanya manusia terwujud karena‘berada’ itu meniadakan diri (se néantise). Manusia sebagaimanusia (l’étre por-soi).
L-étre-en-soi (berada-dalam-diri) ialah semacam beradaan sich, berada itu sendiri. ‘Berada’ mewujudkan segala cirijasmani (materi). Semua benda ada dalam dirinya sendiri. Ti-dak ada dasar atau alasan mengapa benda-benda itu ada. Se-gala yang berada-dalam-dirinya sendiri itu tidak aktif, akan te-tapi juga tidak pasif, tidak afirmatif juga tidak negatif. L’étre-en-soi adalah It is what it is.127 Benda-benda itu tidak ada keterkai-tan sama sekali dengan apalagi bertanggungjawab atas kebe-radaannya. Sartre menggunakan istilah étre-en-soi untuk me-nunjukkan pribadi yang hanya berada dalam dirinya sendiri,untuk menunjukkan pribadi yang pasif dan tak bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Ini adalah penipuan-diri. Penghindaran tanggungjawab pada diri sendiri dan jugaorang lain itu tak lain adalah usaha manusia untuk lari dari ke-cemasan, lari dari kusakaran, lari dari kegelisahan, atau rasatak enak yang menyertai tindakannya. Sartre mengajarkanbahwa manusia berbeda dengan makhluk yang lain karenakebebasannya. Dunia di luar manusia hanya sekedar ada,hanya disesuaikan, dan diberikan sedangkan manusia mencip-takan dirinya sendiri dalam pengertian bahwa ia menciptakanhakikat keberadaannya sendiri. Having, Doing, and Being arecardinal categories of human reality.128 Dengan kebebasan un-
127Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogyakarta:Kanisius, 1980, hlm. 157-159.
128Ini adalah judul dan sekaligus kalimat pertama yang mengawa-li part four dalam bukunya Being and Nothingness (pen.).
Serpihan-Serpihan Filsafat | 179
tuk menentukan menjadi manusia seperti ini-itu, dengan kebe-basan memilih bagi dirinya sendiri benda-benda atau nilai-nilaiuntuk dirinya sendiri, maka ia sesungguhnya telah membentukdirinya sendiri: bukan diciptakan tetapi menciptakan dirinyasendiri.
Jelasnya, bagi Sartre manusia itu bereksistensi sebagaiL’étre por-soi (ada-untuk-diri) bukan L’étre-en-soi (ada-dalam-diri). Manusia adalah makhluk bebas, berkesadaran, dan mer-deka untuk dirinya sendiri. Dengan menyadari bahwa dirinyasebagai makhluk ‘bagi dirinya’ maka manusia akan terus beru-saha untuk mempertahankan otonominya dan berusaha untukterus menegasi atau menolak cara pandang sesamanya yangmau mengurangi atau menggerogoti kemandiriannya.
Pangkal tolak manusia, bagi Sartre, adalah pada dirinya.Orang lain adalah ancaman bagi kebebasannya. Hubungandengan yang lain pada dasarnya adalah hubungan saling me-negasi. Selalu ada konflik dalam setiap relasi yang terjalin anta-ra manusia yang satu dengan manusia yang lain, karenanyaharus ada ketertiban eksistensial.
c. Beban KebebasanSartre menggabungkan semua tema eksistensialisme ateis-
tik: kebebasan radikal manusia, dan posisinya sebagai ‘ketia-daan yang meniadakan’; kematian Allah, pencarian nilai, oten-tisitas, adanya Angst (kecemasan mendalam), dan ketiadaan.Bereksistensi berarti dinamis, artinya manusia menciptakandirinya sendiri secara aktif, berbuat, menjadi, dan merencana-kan. Manusia adalah realitas yang terbuka dan belum selesai.Pemahaman Sartre mengenai kebebasan yang hanya dapatdipahami lewat pandangan mengenai manusia sebagai adauntuk dirinya (no-thingness¸ étre por-soi) justru karena adanya
180 | Win Usuluddin Bernadien
kesadaran pada manusia. Wujud kedirian (eksistensi) manusiaitu justru terbentuk karena manusia berkemauan yang ber-sumber pada kemerdekaan. Dengan kemerdekaanya manusiamencipta dirinya terus menerus tanpa habis-habisnya. Inilaheksistensi manusia itu. Perwujudan kebebasan manusia yangterus menerus itulah yang justru karena manusia adalah sangada yang tidak pernah bisa identik dengan dirinya. Dalamproses melangsungkan diri, seringkali manusia berusaha men-jadi identik dengan dirinya seringkali pula kesadarannya men-jadikannya mengambil jarak, mempertanyai dirinya lagi, se-hingga tiap saat (karena kesadaranya) manusia lalu tidak per-nah menyatu-identik dengan dirinya. Dia senantiasa beradadalam posisi mengambil jarak, membikin dirinya di depannya.Tiap saat manusia selalu menidakkan dirinya. Manusia, menu-rut Sartre, selalu dalam ziarah yang terus menerus (aneantisa-tion). Disitulah tempat tinggal kebebasan manusia.
Perbedaan antara pour-soi dan en-soi terletak dalam ada-tidaknya kesadaran. Dalam en-soi tidak ada kesadaran, se-hingga padat, beku, sepi. Sebaliknya dalam pour-soi ada kesa-daran, sehingga menjadikan manusia membuat jarak. Ia sela-lu mempertanyakan eksistensinya, atau membuat retak dirinya.Justru karena sadar itulah manusia merasa selalu dikejar, tiapkali masih saja belum utuh, mau meng-utuh tetapi belum lagi.Aneantisation itu berlangsung terus tanpa henti. Aneantisationmenuju titik identitas tetapi tak pernah sampai pada apa yangdicita-citakan. Masalahnya terletak dalam realitas bahwa tidakpernahlah ia sama dengan ia. Inilah tragika eksistensi manusia.Ia harus terus begitu dengan kemerdekaan. Manusia adalahpeziarah merdeka yang tak pernah sampai (comdamné a êtrelibre), ziarah yang sia-sia. Karena itulah maka manusia dalam
Serpihan-Serpihan Filsafat | 181
menjalani eksistensinya sebagai pour-soi, ada untuk dirinyadengan kesadaran dan kebebasan itu, mengalami ketakutanterhadap tanggung-jawabnya sendiri bahwa ia harus memilihsecara bebas, padahal pilihan-pilihannya tidak pernah identikdengan dirinya, sia-sia saja. Dalam peziarahannya manusiamerasakan kebebasan sebagai beban yang membuatnya takut(angoisse, resah, gelisah, khawatir). Karena itu banyak orangyang lari dari tanggung jawab penghayatan ziarah kebebasanitu. Ia menyangkalnya, menundanya, atau melarikan dirinya.Sikap ini adalah sikap pengecut, menipu diri sendiri (mauvaisefoi). Sikap yang tidak mampu menghadapi dan menerima fak-tisitas eksistensi aslinya. Sikap yang ditegaskan oleh Sartre ialah‘orang harus’ berani menerima situasi keterlemparan dalamkebebasan ini. Ia dalam faktisitas ziarah merdeka yang sia-siatak pernah identik dengan dirinya ini toh harus menjalani den-gan berani (meskipun sia-sia). Bila ia berani menyongsong te-rus menerus, menerima faktisitas untuk menindak ini, disana-lah manusia baru bisa disebut bereksistensi’.129
HAKIKAT MANUSIA DAN EXISTENCE PRECEDE ESSENCE:SEBUAH UPAYA REFLEKTIF
a. Tentang Hakikat Manusia yang DipersoalkanSebagaimana telah disinggung di atas bahwa manusia
oleh Sartre diekspresikan sebagai ‘eksisten yang mendahuluiessensi’ artinya kita tidak pernah memiliki hakikat ‘essensial’dan tidak pernah diciptakan untuk tujuan tertentu oleh Tuhan,kekuatan evolusi, atau yang lainnya. Bagi Sartre, kita harusmenemukan diri kita ada tanpa pilihan, kita sendiri dan memu-tuskan apa yang membuat kita seperti ini, masing-masing harus
129FX Mudji Sutrisno, op. cit., hlm. 104.
182 | Win Usuluddin Bernadien
membuat ‘essensi’ diri sendiri. Bagi Sartre, tidak ada kebena-ran umum mengenai yang diinginkan atau yang seharusnyadilakukan manusia. Namun demikian, manusia memiliki kebe-basan. Sartre merumuskan: ‘manusia dikutuk untuk menjadibebas’. Tidak ada batasan kekebasan, yang ada adalah kitatidak dapat berhenti menjadi bebas. Manusia adalah makhlukyang memiliki kesadaran, berpikir, dan berkomunikasi dengankata-kata, dan kadang-kadang mungkin percaya pada apayang tidak dapat diterima. Menurut Sartre, setiap aspek kehi-dupan jiwa manusia merupakan sesuatu yang dipilih dan di-pertanggung jawabkan seutuhnya oleh manusia. Sartre meno-lak pandangan umum tentang emosi yang sering dipikirkanberada di luar kontrol kehendak. Ia mencontohkan:
If I make myself sad, I must continue to make myself sad frombeginning to end. I can not treat my sadness as an impulse fi-nally avhieved and put in file withuot recreating it, nor can Icarry it in the manner of an inert body which continues itsmovement after the initial shock. There is no inertia in con-sciousness. If I make myself sad, it is be cause I am notsad...(manakala aku bersedih, aku harus ‘menjalani’ kesedi-han itu sepenuhnya dari awal hingga akhir. Aku tak bisamembiarkan kesedihan itu akhirnya membelenggu dirikuhingga tak berdaya, tidak pula kesedihan itu harus menjadi-kan tubuhku lembam dan terus membikin diriku shock. Ti-dak boleh ada kelembaman dalam kesadaran. Jika aku ber-sedih sebenarnya justru karena aku tidak bersedih...).
Tegasnya, jika seseorang itu sedih maka kesedihan itu ter-jadi karena ia telah memilih untuk membuat dirinya bersedih,bukan karena yang lain. Manusia bertanggung jawab atasemosinya karena emosi merupakan salah satu jalan yang dipi-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 183
lih untuk bereaksi atas dunia.130 Manusia pun bertanggung ja-wab untuk mempertahankan karakternya lebih lama. Manusiadapat tidak hanya menyatakan ‘saya malu’ seakan-akan hal inimerupakan fakta psikologis yang tak terubahkan seperti per-nyataan ‘kulit saya hitam’, karena rasa malu tersebut merupa-kan jalan yang dimiliki manusia dalam sebuiah relasi, dan ma-nusia dapat memilih untuk memiliki dengan cara lain. Bahkan,pernyataan ‘saya jelek’ atau ‘saya bodoh’ tidaklah menambahsuatu fakta yang sudah ada dalam eksistensi, namun untukmengantisipasi bagaimana orang akan melakukan reaksi kepa-da seseorang yang lain di masa depan, dan hal ini hanya dapatdiuji dengan pengalaman aktual.131
Persoalannya sekarang adalah jika mungkin manusia hi-dup tanpa Tuhan, apakah kemungkinan ultim dan makna ke-hidupan manusia?.
Sebagaimana sudah dikatakan bahwa seorang manusiadapat memberi makna kepada keberadaannya dengan merea-lisasikan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dengan meran-cang dirinya. Namun itu tidak bisa dilakukan perseorangan sa-ja, harus intersubjektive. Memang, Sartre pernah menyebutorang lain sebagai neraka, tetapi nyatanya ia menginginkansuatu ikatan dan ia menemukan orang lain sebagai syarat un-tuk eksistensi dirinya. Bahkan untuk sekedar memperoleh ke-benaran tentang dirinya, ia memerlukan orang lain. Intersubjektivitas termasuk situai mendasar manusia dalam dunia ini.Dengan bertolak dari situasi umum itu, kita harus berusahamemungkinkan serta merencanakan kehidupan manusiawi.Jadi, Sarte sebagai atheis ingin menciptakan suatu way of life
130Sartre, op. cit., hlm. 61 dan 445.131Ibid, hlm. 459.
184 | Win Usuluddin Bernadien
(moral manusiawi?) yang baru.Walhasil, jika kita menelusuri arus pemikiran Sartre, nam-
pak sekali manusia dipahami dalam prespektif yang negatif.Manusia berada dalam situasi keterlemparan akibat beban ke-bebasan yang dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepa-danya, sejak setelah kelahirannya. Manusia kini, dipahami,tinggal seorang diri saja dan dengan potensi kebebasannya iasiap memangsa sesamanya. Sesama ada tidak lain sebagai ob-jek yang memuaskan kebutuhan objek yang menatapnya. Na-mun manusia sadar bahwa dirinyapun setiap saat bisa bisa di-objekkan oleh sesamanya. Apabila Sartre mempunyai pandan-gan yang begitu pesimis terhadap hidup di dunia ini, agaknyamemang wajar.Bayangan kekejaman perang yang dialami saatmenjalani tawanan perang pada PD II, menggelantungkan se-juta bayangan kegelisahan yang panjang yang pada gilirannyajustru semakin menggumpalkan perasaannya yang muak ter-hadap segala bentuk penyalahgunaan kebebasan.
Jelasnya, Sartre tidak menginginkan kebebasan itu diram-pas dan diinjak-injak oleh siapapun, termasuk Tuhan. Manusiaharus selalu berusaha dan memperjuang-kan eksistensinyaagar selalu terus bisa bereksistensi. Manusia adalah penciptadirinya sendiri dan pencipta semua aturan di alam ini. Tiap-tiap manusia adalah pembuat tertinggi moralitas karena setiapmanusia adalah pencipta nilai. Tendensi negatif dari sikap yangradikal ini membuat orang selalu ingat pada Sartre, dan samasekali tidak peduli terhadap adanya Sesama sebagai Subjekyang sama.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 185
b. Tentang Eksistensi Mendahului Essensi (Exis-tence Precede Essence)Filsafat eksistensialisme terutama membicarakan cara be-
rada manusia di dunia ini. Dengan kata lain, filsafat eksistensia-lisme menempatkan cara wujud-wujud manusia sebagai temasentral pembahasan, bukan pada yang lain sebab hanya ma-nusia sajalah yang dianggap bereksistensi. Eksistensialismemendamparkan manusia ke dalam dunianya dan menghadap-kan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensialisme menga-jarkan bahwa eksistensi manusia mendahului essensinya.
Tatkala kita berfikir secara teologis bahwa Tuhan adalahPencipta maka kita akan membayangkan bahwa Tuhan men-getahui secara persis apa yang akan dicipta-Nya. Dengan katalain, ‘konsep’ sesuatu yang akan diciptakan oleh Tuhan itu te-lah ada sebelum sesuatu itu diadakan. Demikian pula, Tuhantentu telah memiliki ‘konsep’ saat Dia akan mencipakan manu-sia. Akan tetapi cara berfikir yang sedemikian ini tidak diakuibahkan ditentang oleh Sartre, karena dalam kenyataannya,menurut Sartre, tidaklah demikian. Dia berkeyakinan bahwamanusia adalah yang pertama dari semua yang ada, mengha-dapi dirinya, menghadapi dunia, dan mengenal dirinya sesu-dah itu. Manakala seorang manusia melihat dirinya sebagai ti-dak dapat dikenal itu karena ia mulai dari ketiadaan. Dia tetaptidak akan ada sampai suatu saat ia ada seperti yang diper-buatnya terhadap dirinya. Oleh karena itu, tidaklah ada kekhu-susan kemanusiaan karena tidak ada Tuhan yang mempunyaikonsep tentang manusia.132 Formula ini bagi Sartre penting,sebab bila eksistensi manusia mendahului esesensinya berarti
132Struhl, Paula Rotehrnberg, Kersten J. Stuhrl, Philosopy Now,New York: Random, Inc., 1971, p. 36-37.
186 | Win Usuluddin Bernadien
manusia harus bertanggung jawab untuk apa ia ada. Sartre lalumenjelaskan, karena manusia mula-mula sadar bahwa dirinyaada, itu artinya manusia menyadari bahwa dirinya mengaha-dapi masa depan, dan ia sadar ia berbuat begitu. Hal ini mene-kankan suatu tanggung jawab pada manusia.Dengan kata lain,manakala manusia bertanggungjawab atas dirinya sendiri itumaka bukan berarti ia hanya bertanggung jawab kepada di-rinya sendiri saja tetapi juga kepada semua manusia.
Sebagai seorang atheis yang konsekwen, Sartre menyata-kan Tuhan tidak ada, atau sekurang-kurangnya ia menyatakanbahwa manusia bukan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu konsep-nya tentang manusia adalah eksistensi manusia itu mendahuluiessensianya. Eksistensi manusia menunjukkan kesadarannyaterutama pada dirinya sendiri bahwa ia berhadapan dengandunia, berhadapan dengan sesuatu, dan menyadari telah me-milih untuk berada, dan bertanggung jawab kepada dirinyadan seluruh manusia tetapi sekaligus menyadari bahwa dirinyatidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab menyeluruh.Manusia itu merdeka dan bebas menentukan serta memutus-kan. Dalam menentukan serta memutuskan itu manusia ber-tindak sendirian tanpa orang lain yang menolong atau bersa-manya. Manusia harus menentukan untuk dirinya sendiri danuntuk seluruh manusia. Oleh karena itu, bagi Sartre, manusiaitu tidak solider tetapi soliter (tidak bersatu padu tetapi bermainsendiri-sendiri) dan harus memikul beban berat dunia seorangdiri. Seluruh kenyataan nasib manusia itu diserahkan sepenuh-nya pada dirinya sendiri tanpa bantuan yang lain. Manusia ha-rus memutuskan tanpa perlu bukti maupun alasan apakah pu-tusan itu benar atau salah, sebab hanya dirinyalah yang men-jamin dan bertanggung jawab atas putusannya itu. Tetapi kon-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 187
sekwensi dari itu semua adalah munculnya rasa takut. Takutbukanlah suasana batin yang biasa, melainkan suasana batinyang pokok. Rasa takut berbeda dengan gentar, sebab gentarjelas objeknya sedangkan takut tidak menentu objeknya, tidakjelas takut terhadap apa. Takut datangnya secara tiba-tiba, dansecara tiba-tiba pula menghilang. Seolah-olah manusia takutpada yang tidak ada, seperti takut pada gelap. Takut itu sebe-narnya adakah takut kepada wujud. Wujud itulah yang telahmengasingkan manusia dan membuatnya menjadi terpencil.133
Akan tetapi mestikah demikian dan hanya demikian?. Bukan-kah di samping rasa takut, manusia juga memiliki rasa beranidan gembira karena ia boleh bertanggung jawab?. Sartre men-gatakan bahwa dalam memutuskan itu, manusia berdiri sendi-ri. Ini karena dia adalah seorang atheis. Seandainya theis ma-ka tentu saja manusia akan tahu bahwa dalam memutuskan iatidak sendirian; ajaran Tuhan bersamanya dalam memutuskan.Rasa takut iu muncul karena adanya kesadaran pada manusiabahwa ia manusia bukan hewan, tetumbuhan, bukan pula be-batuan yang tak punya rasa seperti itu.134
Persoalannya menjadi rumit karena bagi Sartre manusiaitu ’étre-por-soi. Manusia adalah pengada yang sadar. Karenaberke-sadar-an maka muncullah tanggung jawab, karena tang-gungjawab maka manusia harus menentukan.Dari sini munculkesendirian (kesepian), lalu rasa takut muncul, lalu manusiamelakukan penyangkalan (neantiser). Menurut Sartre manusiajuga sadar akan adanya sesuatu di luar dirinya, sesuatu yangbukan dirinya. Manusia menyadari bahwa ia tidak berdiri sen-
133Ibid, hlm. 223-224.134Ahmad Tafsir, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales sam-
pai Capra, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990, hlm. 225-228.
188 | Win Usuluddin Bernadien
diri, sebab nyatanya manusia termuat dalam kompleks perbua-tan. Manusia sadar ia berbuat, artinya manusia menyadari bahwa dirinya selalu dalam peralihan. Disitulah, menurut Sartre,letak kerumitan manusia. Manusia setelah menyadari dirinya,lalu membantah dan menyangkanya dengan mengalih padayang lain dan selalu menuju yang lain. Setelah yang lain itu ter-capai ia akan menyangkalnya pula. Tegasnya, manusia itu se-lalu meluncur, selalu berubah, selalu menuju kepada. Hakikatpenyangkalan itu dapat dirumuskan: ‘Yang ada tidak dimaui,yang dimaui belum ada’. Jadi, manusia itu bagaikan pengejarbayang-bayang. Itulah hakikat manusia, menurut Sartre.
Sungguh dilematis, karena kesadarannya maka manusiaberbuat. Berbuat berarti berubah. Apa yang dicapai pasti di-ingkari. Manusia harus berbuat sementara sebab ia sudah me-ngetahui hasil perbuatannya tidak akan memuaskan dirinya.Berbuat bagi manusia seolah-olah merupakan hukuman yangtak terelakkan. Semua yang dilakukan manusia hanya akanberakhir dengan kesia-siaan, meskipun demikian manusia ha-rus tetap berbuat. Itulah hukuman bagi manusia. Menurut Sar-tre manusia dihukum untuk berbuat (bebas). Manusia harusdemikian. Manusia dihukum oleh kesadarannya untuk terusberbuat hingga terengah-engah kepayahan. Untuk membe-baskan diri dari hukuman itu hanya ada dua kemungkinan:menjadi yang tak berkesadaran (en-soi, hewan, tetumbuhan,bebatuan) atau bunuh diri. Padahal untuk menjadi en-soi ti-dak mungkin maka tinggallah satu pilihan: bunuh diri.135
Benarkah hakikat beradanya manusia itu demikian ada-nya? Barangkali Sartre lupa bahwa manusia bisa membangun.
135Ibid, hlm. 229.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 189
Berbuat memang berarti mengalih, menuju kepada yang lain.Memang tidak semua perbuatan itu membangun, akan tetapibukan berarti manusia tidak dapat membangun. Bukankahmanusia, bagi Sartre, harus bertanggung jawab, yang berartiharus membangun dirinya dan dunia? Di sinilah nampak jelasSartre mengalami kontradiksi.
Tatkala Sartre mengandaikan semua perbuatan manusiatanpa tujuan, karena tidak ada yang tetap, selalu disangka dantanpa tujuan, maka hal itu bukan harus berarti manusia putusasa. Bukankah manusia memiliki dinamika hidup dan inginmembangun dirinya serta membangun dunia? Persoalannyajelas, dapatkah manusia merasa puas? Jawabannya terletakpada diri masing-masing, artinya jika seseorang dijajah naf-sunya tentu tidak pernah merasa puas. Inilah sebenarnya yangdialami Sartre yang atheis itu. Dia berpandangan manusia ha-rus berbuat dan harus pula mengingkari hasilnya. Ini hukumanyang bisa menimbulkan rasa muak, mual, jemu, rasa hendakmuntah (la nausee).
Bagi Sartre manusia hidup dalam suatu konstruksi yangdiciptakan sendiri dan menjalani eksistensinya dalam konstruk-si itu, membuat hukum, aturan, konvensi, lalu memberi namadan memberi tujuan. Bukankah ini berarti manusia dapat men-jalankan eksistensinya dengan leluasa? Namun demikian bilakonstruksi itu berubah tentu yang terjadi adalah kekacauan,semua menjadi semua, semua dapat terjadi. Manusia harusmenghadapi kenyataan ini, dan menjadi mual. Padahal sifateksistensi manusia selalu ingin mengubah. Kenyataan itu terasamembeban berat dan menindas. Itulah pada dasarnya yang
190 | Win Usuluddin Bernadien
dimaksud nausee oleh Sartre.136 Nausee terjadi karena tidakada harapan. Manusia itu dihukum dan harus menghadapi ke-nyataan, mengadakan perubahan, sehingga muncul ketidakte-tapan, kekacauan dan karenanya pula, sekali lagi, tidak adayang diharapkan. Jelas semua itu akan menimbulkan la nau-see, sebuah realitas hidup yang dialami Sartre. Pikiran yang se-kaligus menjadi realitas hidup Sartre mengantarkan pada ke-simpulannya bahwa hakikat wujud manusia adalah: ‘yang adatidak dimaui dan yang dimaui ialah yang belum ada’. Manusiaselalu mem-belum, selalu menjadi.
Pikiran Sartre seperti itu jelas tidak sesuai dengan kenya-taan, sebab nyatanya banyak orang yang hidupnya penuh ha-rapan dan tidak merasa hidupnya kosong. Gambaran hakikatkeberadaan manusia sebagaimana yang dipikir Sartre jelas ku-rang cermat. Sartre berseberangan dengan pandangan deter-minisme dan free will.Dia berpandangan manusia itu menjala-ni eksistensinya dalam perbuatan. Perbuatan itu tindakan yangsyarat utamanya adalah kemerdekaan. Oleh karena itu Sartremenghantam setiap bentuk determinisme. Dia mengatakan:“jika aku menjerumuskan kesusilaanku itu karena aku mau, ji-ka tidak maka tidaklah berdaya dorongan-dorongan yang adadalam badanku”.137 Jika aku jatuh cinta itu karena aku merde-ka memilih jatuh cinta.138 Jelasnya, bahwa ke-apa-an manusiabergantung pada kemauannya yang berasal dari kemerdeka-annya.
136Drijarkara, Percikan Filsafat, Djakarta: Pembangunan, 1966,hlm. 74-75.
137Baca Titus, Persoalan-persoalan Filsafat, diterjemahkan olehH.M. Rosyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hlm. 396.
138Drijarkara, op. cit., hlm. 83-84.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 191
Selanjutnya Sartre menjelaskan bahwa kemerdekaan ituharus diartikan merdeka dalam keterbatasannya (dalam kondi-sinya). Orang yang sedang lumpuh, merdeka dalam kelumpu-hannya, seorang narapidana dalam sel penjara merdeka dalamkeadaannya, oleh karena kemerdekaannya itu maka manusiaharus mempertanggungjawabkan semua tindakannya.
Dalam kaitannya dengan kehidupan bersama, Sartre be-ranggapan bahwa kehidupan bersama itu diperlukan tetapiada bersama itu merupakan neraka bagi manusia, karena ba-ginya manusia adalah neraka bagi manusia yang lain. Realitasini sungguh bertentangan dengan apa yang ia jalani denganmahasiswinya yang kemudian menjadi pasangan kumpul ke-bonya, Simone de Beauvoir. Bersamanya Sartre bisa ‘menik-mati’ kehidupan bagai pasangan suami isteri yang sah. Kalausudah begitu bagaimana orang lain dianggap neraka, bukan-kah dia bisa hidup berdampingan hingga akhirnya pada tahun1980 wanita itu harus ditinggalkan untuk selamanya.139
Hanya Sartre sajalah yang paling tahu dan paling ber-tanggungjawab atas filsafatnya. Tetapi kembali pada konsep-nya tentang relasi antar manusia, dia berpandangan bahwa re-lasi antar manusia pada dasarnya diasalkan pada konflik. Kon-flik adalah inti setiap relasi intersubjektif. Ini erat kaitannyadengan kesadaran. Aktivitas kesadaran yang khas adalah ‘me-nidak’. Ini berlangsung dalam setiap perjumpaan di antara ke-sadaran. Setiap kesadaran itu mempertahankan subjektivitas-nya sendiri. Kesadaran lain harus dijadikan objek bagi saya.Demikian setiap perjumpaan antar kesadaran tidak lain dari-pada suatu dialektika subjek-objek dimana yang satu berusaha
139Paul Strathern, 90 Menit Bersama Sartre, Jakarta: Airlangga,2001, hlm. 16-19.
192 | Win Usuluddin Bernadien
mengalahkan yang lain.140
PENUTUP
Sebelum mengakhiri tulisan tentang filsafat eksistensia-lisme Sartre, ada yang perlu disadari oleh siapa saja bahwaSartre dengan filsafatnya sangat penuh dengan kontradiksidengan realitas kebanyakan orang, khususnya mereka yangtheistik, karena memang dia adalah seorang atheis yang sangatkonsekwen. Filsafat Sartre merupakan psikologi atheis. Keba-nyakan karyanya klise, dan sudah barang tentu sering mengu-lang-ulang tema yang telah dia munculkan sebelumnya. Sean-dainya dia bersama dengan eksistensialismenya menjadi san-gat tenar baik di kalangan para mahasiswa, intelektual, kaumrevolusioner maupun di kalangan publik di seluruh dunia itulebih karena dia berada pada situasi yang memang sedangmenguntungkan bagi dirinya.
Akhirnya, dapat digaris bawahi bahwa eksistensialismebrarti sebuah minat yang menggebu terhadap persoalan hidupmanusia, sebuah minat yang menuntut agar setiap aktivitasmanusia lainnya dihilangkan atau diposisikan sekunder. Eksis-tensialis mengajukan tekad kehidupan manusia seharusnyamenjadi suatu kehidupan yang penuh, sebuah kehidupan yangdijalani, kehidupan yang terdiri atas pilihan dan keputusan.Eksistensialis selalu mencemaskan kebebasan manusia. Kepe-dulian kaum eksistensialis terhadap kesempurnaan eksistensimanusia benar-benar telah memunculkan kesadaran untukdapat memainkan seluruh peranan kehidupannya. Mereka me-nganggap bahwa kesejatian hidup hanyalah kehidupan yangsadar, eksistensi berarti sadar terhadap setiap moment eksis-
140Ali Mudofir, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001, hlm. 461.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 193
tensinya, terhadap makna menjadi seorang manusia. Merekamenuntut kesadaran manusia untuk memiliki kesempurnaanhidup, yakni menjadi ‘tuhan’ bagi dirinya sendiri, dan bagi se-muanya. Berikut beberapa ajaran pokok Jean Paul Sartre, sangeksistensialis yang menangkap hakikat manusia itu:
1. Ada dan Kesadaran. Ada merupakan syarat bagi tampak-nya sesuatu, bersifat transfenomenal bukan satu fenomensaja. Kesadaran (akan) dirinya berada sebagai kesadaranakan sesuatu. Kesadaran adalah kesadaran diri. Kesada-ran (akan) dirinya tidak sama dengan pengalaman akandirinya. Kesadaran adalah kehadiran (pada) dirinya. Ke-hadiran (pada) dirinya merupakan syarat yang perlu dancukup untuk kesadaran. Tidak perlu Subjek Transenden-tal, sebagai mana dalam idealisme.
2. L’étre-en-soi. Semuanya ber-ada-dalam-diri-sendiri. Tidakada dasar atau alasan mengapa demikian. Semua L’étre-en-soi ini tidak aktif, tetapi juga tidak masif. Semuanyapadat, beku, lepas dari yang lain, tertutup tanpa salingberhubungan. Semua benda tidak memiliki hubungan de-ngan keberadaanya.
3. L’étre-pour-soi. Ber-ada-untuk-diri-sendiri. Artinya sadarakan dirinya. Ini merupakan cara berada manusia. Manu-sia mempunyai hubungan dengan keberadaannya, ber-tanggungjawab atas keberadaannya. Dalam kesadaranreflektif ini ada yang menyadari dan ada yang disadari,ada subjek dan ada objek. Manusia memiliki dua kesada-ran, yaitu: kesadaran reflektif dan kesadaran pra-reflektif.Kesadaran pra-reflektif adalah kesadaran yang belum di-pikirkan kembali, sedangkan kesadaran reflektif adalahkesadaran yang difikirkan kembali, kesadaran yang telahkembali pada diri sendiri.
194 | Win Usuluddin Bernadien
4. Kesadaran dan Ketiadaan. Kesadaran manusia bukanlahkesadaran akan dirinya (conscience de soi) tetapi kesada-ran diri (conscience (de) soi). Jika seseorang secara reflek-sif menginsafi cara mengarahkan dirinya kepada objek,maka kesadaran itu merupakan kesadaran akan diri. Didalam kesadaran seperti itu selalu ada jarak, yaitu ketia-daan (le neant). Di dalam kesadaran seseorang senantiasaada ketiadaan, sehingga membuat ia dari ’étre-en-soimenjadi ’étre-pour-soi.
5. Kebebasan dan Kecemasan. Manusia mampu memilihdalam kebebasan. L’étre-pour-soi sama dengan kebeba-san. Kebebasan adalah hakikat manusia. Karena kesada-ran-nya manusia selalu berbuat, berarti ia selalu meniada-kan diri. Manusia tidak terikat, ia bebas, dan tidak ‘telahditentukan’. Kesadaran ini justru membuatnya cemas. Ke-cemasan merupakan ketakutan yang asasi.
6. Lari dari Kebebasan. Agar kecemasannya tersembunyimaka manusia melarikan diri dari kebebasannya. Melari-kan diri dari kebebasan dan menjauhkan diri dari kece-masan serentak berarti juga sadar akan kebebasan, kece-masan, dan pelarian. Manusia mengakui kebebasannyasekaligus menyangkal kebebasan itu (mauvaise foi).
7. Relasi antar Manusia, yang pada dasarnya dapat diasal-kan pada konflik sebagai inti relasi intersubjektif. Ini terkaiterat dengan kesadaran yang khas ‘menidak’ dalam setiapperjumpaan diantara kesadaran. Setiap kesadaran akanmempertahankan subjektivitasnya sendiri,sedangkan yanglain hanya dijadikan objek diri. Setiap perjumpaan antarkesadaran adalah dialektika subjek-objek yang ingin salingmengalahkan.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 195
8. Tuhan Tidak Pernah Menjadi Objek. Tuhan adalah Sub-jek absolut, tak mungkin dijadikan objek. Menerima Tu-han berarti mengakui diri dan orang lain menjadi objek-Nya. ‘Sorotan mata’-Nya yang tembus ke hati akan men-jadikan manusia menjadi suatu kodrat yang hancur kebe-basannya. Hanya ada dua pilihan: tunduk padaNya ataumenjadi Dia.
9. Kebebasan dan Moral. Semua norma dan nilai tidak ob-jektif. Moral yang sejati haruslah mengakui eksisistensimanusia sebagai asal-usul nilai. Manusia bertanggungja-wab sepenuhnya pada dirinya sendiri, juga pada oranglain. Norma tidak ada yang abadi, semua sementara, ter-masuk perintah Tuhan sekalipun. Nilai dan Norma dicip-takan oleh kebebasan moral manusia. Fundamen moralhanyalah kebebasan. [*]
DAFTAR BACAAN
a. bacaan utamaSartre, Jean Paul, 1943, Being and Nothingness, An Essay on
Phenomenological Ontology, translated and with an in-troduction by Hazel E. Barnes, New York: PhilosophicalLibrary.
_________, 2003, translated and with an introduction by HazelE. Barnes Being and Nothingness, An Essay on Pheno-menological Ontology, New York: Philosophical Library.
_________, 1995, Truth and Existentialism, Chicago: The Uni-versity of Chicago Press.
_________, 2001, dindonesiakan oleh Jean Coutean: Kata-Kata, Jakarta; Gramedia
196 | Win Usuluddin Bernadien
b. bacaan pendukungAhmad Tafsir, 1990, Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Tha-
les sampai Capra, Bandung: Remaja Rosda Karya.Ali Mudofir, 2001, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.Arrington, R.L, (ed.), 2001, A Companion the Philosophers,
Blackwell: Massachussetts.Ayer, A.J. and O’Grady, J. (ed.), 1997, Dictionary of Philo-
sophical Quotations, Blackwell: Massachussetts.Bertens, K, 1987, Fenomenologi Eksistensialisme¸ Jakarta: PT.
Gramedia.________, 1987, Panorama Filsafat Modern, Jakarta: PT. Gra-
media________, 1996, Filsafat Barat Abad XX Jilid II Prancis, Yog-
yakarta: Kanisius.Borchet, D. M., (ed. In chief), 1996, The Encyclopedia of Phi-
losophy: Suplement, New York: Macmillan ReferenceUSA.
Dagun, Save M., 1990, Fisafat Eksistensialisme, Jakarta: Rine-ka Cipta.
Drijarkara, 1966, Percikan Filsafat, Djakarta: PembangunanFuad Hasan, 1992, Berkenalan Dengan Eksistensialisme, Ja-
karta: Pustaka Jaya.F.X Mudji Sutrisno, & F. Budi Hardiman, (ed.), 1992, Para Fil-
suf Penentu Gerak Zaman, Yogyakarta: Kanisius.Harun Hadiwijono, 1980, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, Yogya-
karta: Kanisius.Honderich, Ted, (ed.), 1995, The Oxford Companion to Phi-
losophy, Oxford-New York: Oxford University Press.Kaufman, W., 1975, Existetialism From Dostoevsky to Sartre,
New York: New American Library.Loren Bagus, 2000, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia.M.O.P., Vincent, 2001, diterjemahkan oleh: Taufiqur rohman,
Filsafat Eksistensialism: Kierkegaad, Sartre, Camus, Yog-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 197
yakarta: Pustaka Pelajar.Monasterio, Xavier O., 1981, Sartre and Existential Approach,
New York: Fordham UniversityStrathern, Paul., 2001, 90 Menit Bersama Sartre, Jakarta: Air-
langga.Solomon, Robert C., Higgin, Kathleen M., 1996, A Short Histo-
ry of Philosophy, New York: Oxford University Press.Stevenson, Leslie & Haberman, Davi L., 2001, diterjemah kan
oleh Yudi Santoso dan Saut Pasaribu Sepuluh Teori Ha-kikat Manusia, Joygakarta: Bentang Budaya.
Struhl, Paula Rotehrnberg, Kersten J. Stuhrl, 1971, PhilosopyNow, New York: Random, Inc,.
Titus, Harold, H., Smith, Marilyn S., Nolan, Richard T., 1994,diterjemahkan oleh H.M. Rosyidi, Persoalan-persoalanFilsafat, Jakarta: Bulan Bintang.
van der Weij, P.A., 2000, diindonesiakan oleh Bertens, K,. Fil-suf-Filsuf Besar tentang Manusia, Yogyakarta: Kanisius.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 199
BAGIAN KEDUABELAS
KRISIS DALAM HUMANISME
PENGANTAR
Secara terminologi humanisme mempunyai arti mengang-gap individu rasional sebagai nilai paling tinggi, atau mengang-gap individu sebagai sumber nilai terakhir. Humanisme meng-abdi pada pemupukan perkembangan kreatif dan perkemba-ngan moral individu secara rasional dan berarti tanpa acuanpada konsep-konsep tentang adikodrati. Istilah humanisme da-lam renaissance menunjuk pada gerak balik menju sumber-sumber Yunani, dan kritik individu serta interpretasi individualkontras dengan tradisi dan otoritas religius.141 Humanisme da-pat pula dimengerti sebagai sebuah tendensi bagi manusia un-tuk menekankan statusnya, kepentingan, kekuasaan, prestasi,interest, maupun otoritasnya. Memang, agaknya humanisme
141Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 2000, Jakarta: Gramedia, 2000,hlm. 295-296.
200 | Win Usuluddin Bernadien
memiliki berbagai macam konotasi yang beragam, tergantungpada persoalan apa yang hendak dipertaruhkan dengannya.Sebagaimana juga klaim khusus tentang manusia, humanismedapat pula menunjuk pada sebuah studi tentang manusia se-cara keseluruhan. Para tokoh Yunani Kuno telah mengawalipemikiran tentang sebuah studi kealaman sebagai suatu kese-luruhan dan sekaligus partikulasi fenomena di dalamnya, mi-salnya saja tentang air, gempa bumi, dan lain sebagainya se-rasa memunculkan berbagai macam persoalan logika dan me-tafisika, meskipun kemudian apa yang disebut dengan gerakanhumanis baru muncul pada abad kelima sebelum masehi, yaitusaat kaum Sophist dan Socrates memahami filsafat sebagaisesuatu yang turun dari langit ke bumi dan menjelma menjadipersoalan-persoalan sosial, politik, dan moral. Humanisme da-pat pula dimengerti sebagai renaissance, terutama ketika hu-ma-nisme menunjukkan sebagai sebuah ‘gerakan’ yang cende-rung meninggalkan seluruh ‘persoalan’ ketuhanan dan melulumemusatkan perhatiannya pada manusia sebagai pusat sega-lanya.Manusia dengan akalnya adalah subjek bagi dirinya yangmampu mengatasi dan mengontrol dirinya sekaligus terhadapalam semesta.142
Humanisme dapat dipahami pula sebagai sebuah upayauntuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berlan-daskan pada empat fondasi kebijakan utama, yaitu: kebijak-sanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Humanis-me kemudian in concrito merupakan langkah desisif penolakanterhadap bentuk apapun diskriminasi serta mentahkik-kan ma-nusia sebagai kesatuan tunggal yang menembus batas kelas,ras, bangsa, budaya, agama, dan primordialisme yang lainnya,
142Honderich, Ted., The Oxford Companion to Phylosophy, NewYork: Oxford University Press, 1995, p. 375-376.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 201
bahkan kemudian berkembang menjadi sebuah faham pelu-cut-an segala bentuk ordo sakral dan transendensi. Manusiatelah mendeklarasikan diri sebagai makhluk yang berkesadarandiri, yang berpotensi untuk mencapai berbagai kualitas.143
Dalam perkembangan selanjutnya, berbagai paham hu-manisme menyeruak dengan berbagai alat konstruksi danorientasi empiris yang beragam, misalnya saja humanisme li-beralis yang menganggap humanisme merupakan prinsip-prinsip filsafat moral dan kultural yang secara berkesinam-bungan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno dan mene-kankan pada penguasaan alam, kebebasan berfikir (Gnothi SeAuthon, Socrates), dan ekonomi produksi. Kemudian munculhumanisme Marxis yang menggugat kapitalisme dan mereaksigereja, berontologis atheis serta mencita-citakan masyarakattanpa kelas. Dua kutub di atas kemudian direaksi pula olehSartre dengan humanisme eksistensialismenya yang menjun-jung tinggi kebebasan manusia untuk memilih, mencipta, danmembangun realitas. Sementara itu muncul pula humanismeagama yang menekankan pada filsafat penciptaan, yaitu ma-nusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan kare-nanya memiliki hubungan yang khas dengan-Nya. Jelasnya,humanisme merupakan cita-cita manusia untuk mewujudkansuatu landasan bersama dalam rangka pemikiran pembangun-an masyarakat yang baru dan hari depan umat manusia yanglebih baik. Namun demikian, sejalan dengan perjalanan waktuposisi humanisme yang semula dinobatkan sebagai pilar utamamegaproyek peradaban modern yang memanusiakan manusiajustru masuk pada lembah dehumanisasi yang parah dan
143Moh. Musoffa Ihsan, Humanisme Spiritual, Antagonisme atauIntegralisme Sejarah, dalam Jurnal Filsafat Fakultas Filsafat UGM, 1996,hlm. 53-54.
202 | Win Usuluddin Bernadien
berskala global sedemikian rupa sehingga dewasa ini humanis-me lebih sering menjadi target serangan yang bertubi-tubi.
KILAS BALIK SEJARAH
Bagi kaum intelektual Eropa, abad XIV merupakan masa-masa yang mengasyikkan namun sekaligus juga menggelisah-kan. Pola pikir teologis dan metafisis sungguh telah mencapaititik paramount of state of art-nya sedemikian rupa sehingga se-tiap perbincangan intelektual telah sedemikian rinci dan cang-gih namun sekaligus nyinyir, abstrak, dan melangit. Lebih dariitu, seluruh pemikiran teologis metafisis-transendental bahkanbertendensi menafikan nilai-nilai manusiawi yang sesungguh-nya amat nyata, dan secara implisit maupun eksplisit cende-rung melegitimasikan pola kehidupan yang hierarkhis feodalis-tis. Keberagamaan terlalu didominasi oleh rasa takut dan dosa.Maka realitas manusia dan dunia pun cenderung dilihat seba-gai ancaman yang menakutkan.144 Di dalam situasi yang sede-mikian itu, secara bertahap justru mulai tersingkap kenyataanmanusia yang amat penting bahwa berkat rasionalitasnyamanusia itu sesungguhnya adalah makhluk yang secara asasiberkebebasan, tetapi telah tergilas dan tenggelam oleh tradisigereja abad pertengahan yang teosentris dan feodalistis. Ke-sadaran akan kebebasan yang secara kodrati dimiliki oleh ma-nusia ini telah membidani lahirnya kehidupan intelektual abadXIV itu. Kesadaran tersebut telah melepaskan manusia daribelenggu kerangka teologis-metafisis dogmatis menuju pemikir-an yang antroposentris kritis dan memposisikan manusia se-bagai titik berangkat maupun titik pusat pemikiran, bukan Tu-
144Bambang Sugiharto, “Humanisme Dulu, Kini, dan Esok”, dalammajalah BASIS Nomor 09-10 Tahun ke-46, September-Oktober, 1997,hlm. 39
Serpihan-Serpihan Filsafat | 203
han. Akibatnya manusia dan dunia menjadi sedemikian sentraldan berharga. Manusia semakin menyadari dirinya sebagaimahkluk yang memiliki historisitas, artinya manusia menjadisadar bahwa masa lalunya bisa dimanipulasi dan masa depan-nya pun dapat dirancang oleh manusia sendiri. Dengan katalain, manusia dibentuk dan membentuk sejarahnya sendiri.Begitulah, manusia memiliki kesadaran baru bahwa ia memilikikebebasan, rasionalitas, historisitas, dan sentralitas. Manusiasebagai individu akhirnya mencipta keyakinan bahwa padahakikatnya hidup manusia adalah proyek pribadinya sendiri.Manusia diberi bentuk dan makna oleh apa yang dipilihnyasendiri. Beranjak dari pemikiran seperti itu maka humanismepun kemudian meluas menjadi kultural yang mendominasiEropa saat itu. Satu hal yang menarik, walaupun kaum hu-manis cenderung mencibir gereja sebagai organisasi dan hie-rarkhis, namun mereka tidak lantas menjadi atheis.145 Sekali-pun kaum humanis melepaskan diri dari kerangka pikir teo-logis-metafisis, akan tetapi mereka tidak lalu menjadi imoral.146
Dalam kerangka humanistik itu mereka justru menemukanmakna yang lebih mendasar dari religiositas dan moralitas.Agama justru memberi dukungan penting bagi usaha maksimalkarya terbaik manusia di dunia ini, kehidupan dunia yang‘surgawi’ penuh kasih, toleransi, dan kedamaian.
Dalam perkembangan lebih lanjut, budaya modern sema-kin sekular, rasional, dan antrophosentris. Tak pelak kondisi inimengantarkan pada konflik antara sains dan agama.147 Otoritasagama dan seluruh prespektif transendental semakin digeseroleh dominasi rasionalitas, akibatnya humanisme tidak lagi
145Honderich, op.cit., hlm. 375.146Bambang Sugiharto, op.cit. hlm. 40.147Honderich, Ted., op.cit,. hlm. 376.
204 | Win Usuluddin Bernadien
menjadi gerakan kultural melainkan telah menjelma sebagaigaya hidup manusia modern. Pada tataran praksis agamasemakin tergeser dan pada tataran teoritis kecenderungan ituterungkap dalam berbagai aliran filsafat yang mengarah keatheisme.
MENELUSURI SEMANGAT DASAR HUMANISME
Semangat humanisme semenjak PD II berakhir, munculdalam berbagai ‘wajah’ yang lebih beragam: tidak lagi selaluatheistik, melainkan bisa pula agnostik bahkan justru theistik.Sementara itu pada penghujung abad XX humanisme harusmenerima berbagai kritik mendasar yang muncul atas berbagaisisi peradaban modern. Gelombang kritik tersebut umumnyatampil dalam berbagai nama dengan menggunakan istilah‘post’, seperti postindustri, postmodern, postwestern, postme-tafisik, bahkan posthistory yang mengganggap seolah kiniwaktu telah berhenti total. Humanisme telah dituduh terlaluantrophosentris dan tanpa ruang transendensi, subjektivistisdan melepaskan pola hubungan penguasaan, individualistisdan anti komutarian, egologis dan anti ekologis, antifeminisme,eurosentris, borjuis dan mementingkan kesatuan absolut,mengabaikan pluralisme hakiki, logosentris, narsistis, dan sete-rusnya.148 Diskursus kritik atas kemodernan dan humanismeseperti ini segera akan menjadi jelas bahwa simpang-siurserangan itu sesungguhnya penuh dengan paradoks dan kon-tradiksi, tidak jelas diarahkan pada humanisme yang mana.Karenanya jelas dibutuhkan analisis mendalam dan esensial.
Semangat dasar humanisme agaknya ada dalam keyakin-an bahwa martabat manusia terletak pada kebebasan danrasionalitas yang inheren pada setiap individu. Tidak bisa di-
148Bambang Sugiharto, op.cit,. hlm. 41
Serpihan-Serpihan Filsafat | 205
sangkal bahwa manusia mesti dipandang sebagai individu oto-nom yang defacto otonomi itu relatif menurut konteks sosialmaupun alami, namun hal itu tidak perlu dikontraskan denganotonomi individu. Konteks sosio-kultural justru merupakan pe-luang dan tantangan yang memberi bentuk dan makna bagiotonomi tersebut. Keyakinan semacam itu memungkin oranguntuk mengambil jarak terhadap setiap sistem dogmatik danotoritas dari luar, apapun dan siapapun, termasuk Tuhan. Ka-renanya peluang kearah atheisme memang besar, namun be-gitu peluang religiositas yang lebih otentik dan mendalam punsama besarnya, sehingga para humanis mudah dicap ‘mba-lelo’, padahal keyakinan seperti itu pula yang telah melindungimartabat manusia dari segala bentuk manipulasi, penjajahan,dan kesewenangan berbagai sistem kekuasaan termasuk sistemkekuasaan sistem religius yang sakral transendendtal. Dari siniagaknya humanisme tidak dapat dipandang sebagai sebuahideologi, bukan pula gerakan lokal Eropa pada masa tertentu,juga bukan aliran filsafat. Humanisme merupakan keyakinanreflektif atas nilai-nilai asasiah yang inheren dalam proses ke-hidupan manusiawi konkret, artinya keyakinan tersebut meru-pakan dasar minimal untuk mengukur validitas dan kebenaransetiap sistem nilai, serta kepercayaan dan otoritas yang dike-nakan dari luar terhadap individu. Karena itulah maka sebetul-nya tidak perlu humanisme sertamerta dipandang telah meng-abaikan bahkan menafikan kenyataan transendental, baik Tu-han maupun alam semesta.
Ada satu hal yang menarik, humanisme menampilkanparadoks yang penting. Di satu sisi humanisme tampil sebagaisebuah kesadaran akan ‘prespektif’ yang melahirkan kesadarantentang status manusia sebagai ‘pusat’, dan di sisi yang lain se-kaligus disadari pula bahwa ‘pusat’ itu ternyata demikian relatif
206 | Win Usuluddin Bernadien
terhadap historisitas, sosialitas dan Tuhan. Artinya, di satu sisimanusia menyadari dirinya sebagai ‘pencipta’ dunia maknadan nilainya sendiri tetapi di sisi yang lain disadari pula bahwaia pun ‘diciptakan’ oleh segala unsur realitas di luar dirinya.Oleh karena itu, sifat ‘antroposentris’ humanisme tidak harusdilawankan secara radikal dengan aspek ‘teosentris’ dalam ge-rakan ekologi. Humanisme semacam ini akan dengan mudahdipadukan dengan keyakinan bahwa martabat manusia itusesungguhnya merupakan anugerah Tuhan. Karenanya tidak-lah mengherankan manakala eksistensialisme bisa sangat the-istik dan sebaliknya gereja Katolik tampil sebagai yang sangathumanistik.149
Manusia tidak pernah hanya berfungsi sebagai sekedarsatu atom atau sekrup dalam masyarakat, namun dalam setiaptindakannya ia selalu sebagai ‘individu’ dan ‘subjek’ yang oto-nom dan memiliki integritas diri yang dibentuk dan dicapaimelalui interaksi dialogis dalam komunitas. Ini berarti bahwakebebasan individu dapat dicapai lewat upaya saling membe-baskan antara individu dengan individu juga antara individudengan alam. Semangat humanisme semacam inilah yang se-sungguhnya telah membuat manusia lebih peka terhadap se-gala bentuk penjajahan dan kesewang-wenangan. Jelasnya,humanisme adalah ‘pagar’ yang melindungi kultur dan religitetap ‘beradab’. Sebab sangat mungkin religi yang tanpa pres-pektif humanisitik akan mudah bahkan niscaya akan menjadikejam dan bengis, dan tanpa disadari akan mudah membu-nuh, memperkosa, serta menghancurkan Tuhan.
Humanisme sesungguhnya merupakan ‘ruh’ yang tersim-puh dalam haribaan kemanusiaan yang agung dan bersifat
149Bambang Sugiharto, ibid, hlm. 43.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 207
universalis-kosmopolit.150 Kehadirannya tidak disekat oleh zonaspasio temporal atau terbekam secara locally determined. Hu-manisme merupakan ‘kerinduan perennial’ terhadap idealismeoptimal bentuk kemanusiaan.
ANTIHUMANISME
Istilah antihumanisme baru dapat dimengerti manakalaunsur ‘humanisme’ ditafsirkan sebagai humanisme ideologis,yaitu humanisme sebagai paham yang ‘berpusat pada subjek’yang dianggap ‘bebas’ melampui segala keterbatasan yang rea-listis, dan yang memandang ‘rasio’ gaya zaman Pencerahan,sebagai apa yang menentukan ‘kodrat’ manusia. Pokoknya,humanisme ditolak karena mengandung segala macam ‘abso-lutisme’ konseptual dan dapatlah pula menjadi absolutismedalam sistem sosial, terutama politik.151 Dalam perkembanganselanjutnya aliran antihumanisme menjadi ‘ironisme’ dan di-anggap sebagai ‘kematian manusia’. Memang antihumanismetelah menghilangkan tanda-tanda terakhir kemodernan sebagaitradisi hasil skeptisisme Cartesian dan ideologi tentang ‘rasio’zaman Pencerahan. Meskipun antihumanisme mulai lepas dariperkembangan yang menghasilkan purnamodern, namun la-ma-kelamaan ‘melebur’ diri pada kepurnamodernan itu. Aki-batnya manusia dipandang, secara non-ideologis, dalam keter-batasannya, dalam kelemahannya, dan dalam konteks penga-ruh hidup masyarakat terhadap otonomi pribadi, baik individumaupun dalam golongan yang bersifat pribadi. Pokoknya ma-nusia diakui sebagai ‘kontingen’. ‘Kematian manusia’ sebenar--nya tidak lain adalah kematian absolutisme ideologis, meng-
150Moh. Musoffa Ihsan, op.cit., hlm. 57.151Jo Verhaar, “Antihumanisme dan Liberalisme”, dalam majalah
BASIS Nomor 09-10 Tahun ke-46, September-Oktober, 1997.
208 | Win Usuluddin Bernadien
hasilkan akhir optimisme yang tidak berguna bahkan berba-haya.
PENUTUP
Pertanyaan yang muncul kemudian: adakah sebenarnyaterjadi krisis dalam humanisme?. Pada tataran teoritis, barang-kali sebenarnya krisis yang dialami humanisme tidaklah terjadi.Tetapi siapa yang sekarang ini bisa menjamin ‘The Declarationof The Human Right’ yang sedianya hendak dijadikan pilarutama Perserikatan Bangsa Bangsa (PPB) menjadi sebuahkenyataan. Masih adakah jaminan keadilan sosial dan ekononidapat terwujud nyata. Tak satu pun yang dapat ‘menjawab’persoalan-persoalan semacam itu secara adequate. Jelasnya,pada tataran praksis jelas terjadi krisis di dalam humanisme.152
Sudah saatnya kini setiap kita mampu memadukan se-cara integralistik holistik agama, filsafat, ilmu pengetahuan danteknologi sehingga tidak ada lagi ‘kegelisahan’ kemanusiaan dimasa-masa mendatang. [*]
BACAAN PENDUKUNG
Bambang Sugiharto, “Humanisme Dulu, Kini, dan Esok”, da-lam majalah BASIS Nomor 09-10 Tahun ke-46, Sep-tember-Oktober, 1997.
Jo Verhaar, “Antihumanisme dan Liberalisme”, dalam majalahBASIS Nomor 09-10 Tahun ke-46, September-Oktober,1997.
Jon Avery dan Hasan Askari, 1995, Menuju Humanisme Spi-ritual, penerjemah Arif Hoetoro, Surabaya: Risalah Gusti.
Kees Bertens, 1987, Panorama Filsafat Modern, Jakarta: P.T.
152Kees Bertens, Panorama Filsafat Modern, Jakarta: P.T. Gra-media, 1987, hlm. 42.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 209
GramediaLorens Bagus, 2000, Kamus Filsafat, 2000, Jakarta: Gramedia.Moh. Musoffa Ihsan, 1996, Humanisme Spiritual, Antagonis-
me atau Integralisme Sejarah, dalam Jurnal Filsafat,Fakultas Filsafat UGM.
Ted Honderich, 1995, The Oxford Companion to Phylosophy,New York: Oxford University Press.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 211
BAGIAN KETIGABELAS
POSTMODERNISME
DESKRIPSI
Postmodernisme, atau lebih sering disingkat Posmo, ada-lah aliran yang sekaligus menjelma menjadi sebuah gerakanyang bereaksi terhadap kegagalan manusia dalam menciptadunia yang lebih baik. Gerakan ini hadir karena rasa kecewaterhadap peradaban modern yang telah gagal menghadirkan‘tanah impian’ yang telah dijanjikan lewat ilmu pengetahuanrasional. Memang, Posmo tidak memberikan resep baru, bah-kan mengingkari kesanggupan manusia untuk menemukanresep apapun. Bagi penganut Posmo, manusia siapapun tidakakan mengetahui realitas yang objektif dan benar. Yang dike-tahui manusia hanyalah sebuah versi dari realitas. Ibarat tekssebuah bacaan, realitas yang diketahui manusia merupakanteks yang sudah dibentuk oleh pengarangnya. Jelasnya, dalamkondisi ini, Posmo telah masuk ke relativisme.
212 | Win Usuluddin Bernadien
Secara garis besar, gerakan Posmo terpecah menjadi duakelompok, yaitu: Posmo Skeptis dan Posmo Affirmatif. PosmoSkeptis berhenti pada perdebatan epistemologi tentang penger-tian manusia. Melalui metode dekonstruksi (analisis kritis), me-reka menunjukkan adanya kontradiksi dalam teori apapun, te-tapi tidak memberikan alternatif apapun sehingga kelompok inimengesankan diri sebagai sebuah aliran yang larut kedalampemikiran nihilisme. Sedangkan Posmo Affirmatif muncul se-bagai sebuah aliran pemikiran yang seringkali ‘hanya’ meng-hadirkan berbagai issue kecil yang selama ini luput dari perha-tian ‘khalayak’ karena dianggap lemah dan tidak ilmiah. Gera-kan ini tidak percaya pada kebenaran teori yang ada, terutamateori besar. Kian besar sebuah teori yang kebenarannya men-cakup ruang dan waktu yang luas, kian lemah pulalah adanya,sebab akan semakin abstrak dan kian jauh dari apa yang ingindipresentasikannya. Sebaliknya teori kecil lebih dekat denganapa yang ingin dipresentasikan karena cakupannya yang serbaterbatas. Posmo Affirmatif kemudian memunculkan berbagaimacam dialog baru dengan mengikutsertakan pelbagai macamteori yang tadinya tidak pernah didengar. Discourse tentangfeminisme, pengetahuan lokal yang tidak ilmiah, bahkan ten-tang ilmu klenik dan black magic serta agama-agama primitif,merupakan hasil dari gerakan Posmo Affirmatif.153
Ada yang perlu dicatat bahwa sesungguhnya aliran PosmoAffirmatif bukan ingin mencipta sebuah teori baru yang lebihbaik dan benar, meskipun tanpa sadar, gerakan ini memilikikecenderungan ke arah ini. Jika ini yang terjadi maka sudahbarang tentu Posmo Affirmatif telah keluar dari prinsip dasar
153Arif Budiman, Posmo: Apa Sih, dalam Suyoto, dll., (ed.), Post-modernisme dan Masa Depan Peradaban, Yogyakarta: Aditya Media,1994, hlm. 22.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 213
Posmo yang ingin menyatakan sebagai sebuah gerakan yangmenolak terhadap kepastian sebuah teori. Posmo Affirmatifsekedar menyatakan bahwa kita akan lebih aman tatkala ber-pegang pada teori kecil yang jangkauan tentu juga terbatas.Meskipun hal ini bagi Posmo Skeptis merupakan sebuah peng-khiatan pada prinsip dasar Posmo. Posmo Skeptis mengang-gap Posmo Affirmatif mengkhianati prinsip dasar Posmo kare-na pada saat yang bersamaan menutup diri pada ‘persoalan-persoalan kecil’ tetapi sekaligus membuka diri untuk berdialogdengan teori yang lain secara dialogis berkesinambungan.
Deskripsi di atas agaknya mengantarkan kita pada sebuahpemahaman bahwa Posmo merupakan aliran atau gerakanyang dapat ‘diterjemahkan’ oleh siapapun. Dengan kata lain,arti Posmo merupakan ‘kata-kata’ yang mengambang, tergan-tung pada siapa pemberi arti tersebut. Sebagai misal, bagi ka-langan kaum feminisme, gerakan pelestarian hidup, atau gera-kan pencari pola hidup alternatif, Posmo merupakan pemikiranbaru yang sangat berguna, sebab Posmo memberikan legalitaspada mereka untuk didengarkan dan diperhatikan, serta mem-berikan self confidence yang lebih mantap. Bagi mereka Pos-mo memberikan peluang untuk memasuki ruang dialog yangluas bagi umat manusia. Bagi kalangan ahli ilmu sosial, Posmodengan metode dekonstruksinya menjadikan kita berfikir seca-ra mendasar tentang banyak hal yang selama ini dianggap su-dah pasti. Gerakan ini juga membuat kita peka terhadap pen-dapat lain yang selama itu kurang diperhatikan. Lebih dari itugerakan ini telah menjadi vehicle bagi kita untuk bersikap kritis,demokratis, dan rendah hati, yang pada gilirannya akan meng-hantar kita pada kepedulian untuk mendengarkan suara-suara’baru’, suara-suara jeritan kaum yang secara struktural tertin-das. Di lingkungan ilmuwan eksakta yang segalanya ‘serba ma-
214 | Win Usuluddin Bernadien
ti’ dalam lingkaran sebab-akibat, agaknya Posmo sulit berposi-si, sebab Posmo ‘anti’ pada pengetahuan rasional yang sema-ta-mata.
PERIODISASI ATAU EPISTEMOLOGI ?Istilah postmodernisme konon mulanya muncul dalam ar-
sitektur. Lalu menjadi istilah populer di dunia sastra-budayasejak 1950-an. Sementara di bidang filsafat dan ilmu-ilmu so-sial, istilah posmodernisme baru menggema pada tahun 1970-an. Tak ditemukan definisi yang pasti mengenai istilah post-modernisme, sebab sejak istilah itu dilabelkan pada berbagaibidang tersebut, terjadi pertentangan pendapat.154
Selanjutnya dapat diketengahkan pula pendapat Tyonbee,bahwa istilah postmodernisme yang dalam bahasa Indonesiaditerjemahkan menjadi pascamodern adalah periodisasi seja-rah yang dimulai sejak tahun 1875 dengan asumsi masa mod-ern telah berlangsung pada tahun 1475 hingga 1875. Satu halyang penting dan menarik disini adalah pengertian Toynbeetentang pascamodern, yaitu masa yang ditandai dengan pe-rang, gejolak sosial, dan revolusi yang menimbulkan anarkhidan relativisme total. Masa ini bertolak belakang dengan ciri-cirikeemasan kaum borjuis yang ditandai dengan stabilitas, rasio-nalisme, dan kemajuan. Pascamodern, bagi Tyonbe, adalahmasa yang ditandai dengan runtuhnya rasionalisme dan etospencerahan.155
Ada dua segi yang dapat diketengahkan berkenaan den-
154Ibrahim Ali-Fauzi, dalam: Suyoto, dll (ed.), Postmodernisme danMasa Depan Peradaban, Yogyakarta: Aditya Media, 1994, hlm. 26
155M. Dawam Rahardjo, Posmo: Apa Lagi Ini, dalam Suyoto, dll.,(ed.), Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban, Yogyakarta: AdityaMedia, 1994, hlm. 16.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 215
gan postmodernisme. Pertama segi periodisasi dan kedua segiepistemologi.Dari sudut periodisasi postmodernisme dapat dije-laskan sebagai berikut: jika dunia modern ditandai oleh dife-rensia maka dunia postmodernisme ditandai oleh de-diferensiayang bisa dilihat melalui jelasnya batas-batas antar bangsa, an-tar agama, antar ras, antar suku dan antar golongan.DikhotomiBarat-Timur, kulit putih-kulit berwarna, negara maju-negaraberkembang adalah contoh-contoh yang bisa memberikan legi-timasi terhadap ide diferensiasi. Berdeda dengan diferensiasi,maka de-diferensiasi bisa dimengerti sebagai sebuah periodisa-si yang menjadikan batas-batas tersebut menjadi semakin sa-mar. Semua macam dikhotomi menjadi sangat problematikkarena semuanya serba bercampur-baur. Apa yang terjadi pa-da belahan dunia tertentu akan segera cepat ‘merambat’ danmemberi imbas pada belahan dunia yang lainnya. RuntuhnyaSosialisme-Kapitalisme era modern telah menjadi contoh nyatayang menandai hadir postmodern.156 Sementara itu, Jean-Francois Lyotard menjelaskan bahwa posmodernisme sering-kali disalahmengerti. Postmodernisme bukanlah suatu periodebaru yang harus ditempatkan sesudah periode modernitas.Postmodernisme tidak boleh dipahami sebagai sebuah permu-laan baru, sebagai dimulainya periode berikutnya. Kata ‘mod-ern’ berasal dari kata Latin Modus artinya ‘cara’. Postmoderni-tas mengungkap beberapa perkembangan dan transformasitertentu yang berlangsung dalam rangka modernitas itu sendiri.Postmodernisme adalah merupakan cara yang sebagai ke-mungkinan sebenarnya sudah terkandung dalam modernitas.Karena itu, Lyotard menegaskan bahwa postmodernisme tidak
156Gede Prama, Postmodernisme, Ke arah Pemahaman tentangPostmodernisme: Refleksi Politik, Yogyakarta: Aditya Media, 1994, hlm.10.
216 | Win Usuluddin Bernadien
saja menunjukkan kepada suatu keadaan, melainkan juga se-bagai suatu tugas kepada apa yang harus dikerjakan seka-rang.157 Dalam segi epistemologi, menurut Lyotrad, Postmo-dernisme berarti pencarian instabilities. Jika pengetahuan mo-derm mencari kestabilan melalui metodologi, dengan ‘kebena-ran’ sebagai paramount akhir pencarian, maka pengetahuanpostmodern ditandai oleh runtuhnya kebenaran, rasionalitas,dan objektivitas. Prinsip dasarnya bukan salah-benar, tetapiapa yang oleh Lyotard disebut dengan paralogy atau mem-biarkan segalanya terbuka adanya untuk kemudian sensitif pa-da pelbagai macam perbedaan. Stabilitas dan kebenaran men-jadi problematik dalam pengetahuan postmodern, disebabkankarena bahasa dan pikiran manusia yang tidak bebas dari dis-torsi. Di dalam bahasa dikenal perbedaan baik-buruk, tepat-tidak tepat, dan lain sebagainya, akan tetapi di lain pihak, reali-tas sosial selalu muncul dalam bentuk yang serba tercampur. Disamping itu realitas sosial tampil tanpa kerangka, tetapi olehbahasa dicoba dikerangkakan sebelum memasuki benak piki-ran manusia. Inilah yang menyebabkan hubungan antara worddan world menjadi problematik.158
PROBLEMATIKA POSTMODERNISME
Postmodernisme sebagaimana gerakan yang lain tak luputdari reaksi pro-kontra.Gerakan ini kadangkala dianggap seba-gai sebuah kemandulan dan kemandekan pemikiran Baratyang tak mampu (lagi) menghasilkan gagasan baru apalagi ga-gasan besar. Kadang pula postmodernisme dipahami sebagaisebuah mata rantai keniscayaan akibat rasionalisme yang ber-
157Bertens, K., Filsafat Barat Abad XX Jilid II Prancis, Jakarta: P.TGramedia, 1996, hlm. 351.
158Gede Prama, op.cit., hlm. 11.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 217
lebihan dan aniaya (repressive). Modernisme muncul pada ab-ad XVIII dengan Aufklärung-nya dipahami sebagai sebuahproses berkembang dan menyebarnya rasionalitas Barat kesegala segi kehidupan manusia dan tindakan sosialnya.159 Ra-sio manusia telah diimani sebagai kekuatan otonom dan satu-satunya yang mampu menjadi sumber utama ilmu pengeta-huan, mengatasi kekuatan metafisis dan transendental, danmengatasi semua pengalaman yang partikulair sehinggamenghasilkan kebenaran mutlak, universal, terbebas dari ika-tan waktu.160
Berkaitan dengan hal itu, maka kaum postmodernis me-nolak semua asumsi tersebut dan berusaha membebaskan diridari semua dominasi konsep dan praktek kebudayaan modern.Mereka menyadari bahwa seluruh budaya modernisme yangbersumber pada iptek, pada titik tertentu, sudah tak mampulagi menjelaskan kriteria ataupun measurment epistemologibahwa yang benar itu adalah yang real dan yang real itu ada-lah yang rasional, atau lebih tepatnya sebagaimana yang diya-kini Hegel: The rasional is real and The real is rasional.161 Halini mengandung arti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidakdapat dimengerti. Segala sesuatu mengejawantahkan suatuide, suatu unsur rasional. Hal itulah, bagi Hegel, yang justrumemungkingkan pada terwujudnya tujuan filsafat yaitu: men-gangkat segala sesuatu ke taraf pengertian atau menempatkansegala sesuatu dalam suatu sistem pemikiran yang menyeluruh.
Jean-Francois Lyotard, lewat karyanya yang berjudul ThePostmodern Condition: A Report on Knowledge (1984) meng-
159Bertens, K., op. cit., hlm. 348.160Ibrahim Ali-Fawzi, op.cit., hlm. 25.161Rauch, Leo., Introduction to The Philosophy of History, Indian-
apolis & Cambridge: Hackert Publishing Company, 1998, p. x.
218 | Win Usuluddin Bernadien
garis bawahi bahwa postmodernisme adalah sebuah gerakanglobal renaissance atas renaissance (pencerahan atas pencera-han). Ia menolak ide dasar modern sejak renaissane sampaineo-marxis yang dilegitimasi prinsip kesatuan ontologis. Dalamkondisi yang dipengaruhi teknologi informasi dewasa ini, me-nurut Lyotard, prinsip semacam itu tak lagi relevan dengan rea-litas kontemporer. Untuk itu harus dilegitimasi oleh ‘paralogi’atau ide ‘pluralitas’. Tujuannya agar kekuasaan tidak lagi jatuhpada sistem totaliter.162
Menurut Lyotard, modernitas adalah situasi yang men-jadikan filsafat berfungsi memberikan wacana metailmiah dandapat melegitimasi berbagai ragam prosedur dan kesimpulandari sains. Wacana metailmiah itu mendasarkan diri pada sua-tu grand-narrative atau meta-narrative. Dialektika roh, eman-sipasi subjek yang rasional, misalnya menjadi patokan filsafatmodern. Grand-narative menjadi penuntun segalanya, yangmampu membawahi, mengorganisasi, menerangkan narasi-narasi lainnya serta melegitimasi pada ilmu pengetahuan. Si-tuasi yang seperti inilah yang dicurigai dan ditolak oleh Lyo-tard. Ia berpendapat bahwa berbagai metanarasi modern se-perti kesatuan, pembebasan manusia, atau kemajuan ke arahpengetahuan yang semakin total itu kini telah kehilangan ke-kuatannya dan tak lebih dari sebuah illusi belaka. Prinsip pen-getahuan dalam postmodern bukan lagi dilegitimasi oleh ho-mologi melainkan pada paralogi. Homologi (usaha pen-total-an sistem) mengandalkan adanya sang legitimator yang mem-baptiskan berbagai ragam teorinya sebagai sifat normatif. Den-gan demikian menunjukkan adanya usaha stabilitas. Sejarahilmu telah membuktikan bahwa teori apapun tidak dapat mun-cul dalam stabilitas. Ketidakstabilan diperlukan untuk mencip-
162Ibrahim Ali-Fauzi, op. cit., hlm. 27.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 219
takan teori-teori yang relevan dengan kondisi yang ada. Legi-timasi Homologi perlu didelegitimasikan dengan Paralogi yaitusistem pemikiran plural.163
Pada masa sekarang ini yang ada hanyalah narasi-narasikecil (mini-narrative) yang melegitimasikan berbagai macampraktek pengetahuan tanpa perlu persetujuan dari grand-nar-ratives. Karena itu istilah-istilah kunci postmodernisme, antaralain, adalah: pluralisme, fragmentasi, heterogenitas, skeptisis-me, interminasi, ketidakpastian, dan perbedaan.
Bahasa merupakan perantara setiap pengetahuan. Den-gan menggunakan prinsip langauge game dari Wittgenstein,Lyotard menggambarkan fenomena pengetahuan kontempor-er. Analisis khas dari language game ialah membuka prespektifkesadaran dalam menerima realitas pluralitas. Lyotard yakinbahwa setiap pengetahuan itu sebenarnya bergerak dalam lan-guage gamenya masing-masing. Karena itu setiap kebenaranselalu terkait pada penilaian subjektive yang digunakan, se-hingga kebenaran itu tidak bisa tidak merupakan sesuatu yangditentukan secara lokal (locally determined). Jika kaum mod-ernis melihat realitas sebagai sebuah teks dan kebenaran inhe-ren terdapat didalamnya, dan mencari kebenaran berartimempelajari teks itu secara objektif tanpa unsur subjektif inter-pretatif, maka bagi kaum postmodernis memandang bahwakebenaran itu tidak pada teks melainkan pada peristiwa pem-bacanya, pada interaksi timbal balik anatara pembaca danteks. Penafsiran dalam hermeneutika mencakup moment dis-tansiasi, yaitu saat karya dikaji dan seakan-akan dimiliki lewatpemahaman interpretasi tersebut.
Pro kontra terhadap pandangan postmodernisme tak da-
163Ali Mudhofir, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarat: Pustaka Pelajar,2001, hlm. 329.
220 | Win Usuluddin Bernadien
pat dihindari. Menurut Jurgen Habermas, yang sesungguhnyaterjadi di dunia Barat adalah ‘Pencerahan yang sedang ber-langsung’ bukan stagnasi sebagaimana yang dituduhkan olehsementara orang. Rasionalisasi (moderniasi) sebagai ‘proyekpencerahan’ belumlah usai (modernity as unfinished project),terlebih-lebih di negara-negara yang baru beranjak ke eramodernisasi. Karena itu, menurut Habermas, seluruh patologimodernitas harus ditindaklanjuti dan sembuhkan dengan pen-cerahan lebih lanjut, bukan meninggalkannya dan menuju kepostmodernisme. Era sekarang ini, menurut Giddens, bukan-lah era pascamodern tetapi sebagai high moderninity. Secarakritis dan tajam, Jurgen Habermas mengamati berbagai ten-densi postmodernisme dan menunjukkan berbagai kelema-hannya. Habermas berpendapat bahwa konsep posmodernis-me adalah sebagai sebuah konsep yang abstrak dan a-historis.Kelemahan mendasar postmodernisme yang ahistoris dan ne-tral atas konsep modernitas, karenanya, menurut Habermas,postmodernitas termasuk dalam modernitas. Patologi moderni-tas yang ada bukanlah harus didekonstruksi tetapi direkon-struksi. Rekonstruksi menuntut suatu pergeseran paradigmadari pola pemikiran filsafat kesadaran yang digerakkan ‘rasio-nalitas instrumental’ menuju kepada pemikiran filsafat komuni-katif yang bersumber pada ‘rasional komunikatif’ untuk men-capai konsensus. Jelasnya, bagi Habermas modernisasi harusdilanjutkan dengan kritik berkelanjutan atas seluruh manifestasirasio yang bertumpu pada subjek dengan tindakan komunika-tif. Patologi modenitas bisa dan harus disembuhkan denganmembangun dan menghidupkan seluruh struktur komunikasirasional intersubjektive dalam interaksi sosio-kultural yang(mungkin) selama ini dikolonisasi oleh rasio yang berpusat pa-da subjek. Akar seluruh kebingungan dan krisis yang terjadi da-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 221
lam modernitas adalah kesalahpahaman mengenai rasionali-tas. Rasionalitas manusia tidaklah sesempit ‘rasionalitas instru-mental’ yang mendasari masyarakat modern sekarang ini. Kinimuncul label lain untuk rasionalitas instrumental yaitu ‘rasioyang berpusat pada subjek’. Inilah yang dialami oleh kaumpostmodernis. Mereka merasa kesulitan untuk meninggalkanmodernitas dan kesadaran historisnya. Postmodenisme adalahgejala (symptom) dan krisis dalam sebuah paradigma ‘rasioyang berpusat pada subjek’, sebuah paradigma yang diper-sempit secara mutlak dalam proyek-proyek modernisasi selamaini. Akan tetapi krisis ini bukanlah krisis yang akan menghan-curkan modernitas, melainkan krisis dalam paradigma moder-nitas. Rasionalisasi sebagai ‘proyek pencerahan yang belumusai’.164
PENUTUP
Bentangan sejarah telah menunjukkan bahwa tak satupungagasan atau pemikiran ataupun konsep yang hadir begitu sajatanpa penyebab yang mendahuluinya. Begitupun postmoder-nisme yang muncul sebagai sebuah agenda diskursus filsafatakhir-akhir ini, lahir dan berdiri sebagai sebuah reaksi dan jeri-tan protes di tengah-tengah kompleksitas modernitas yang tira-nik. Postmodernisme adalah sebentuk pemberontakan terha-dap keangkuhan epistemologis mega-proyek modernisme-wes-ternisme yang didirikan di atas pondasi rasionalisme Cartesianyang telah menghantarkan manusia pada sebuah pemahamanrealitas dunia ini secara subjektive. Epistemologi Cartesian san-gat memuja subjek ‘aku’, yaitu I am the thinking thing, yangpada saatnya kemudian mengantarkan manusia pada situasikesepian, teralienasi, nyaris steril dari spiritualitas. Pendeklara-
164Ibrahim Ali-Fauzi,op. cit., hlm. 36.
222 | Win Usuluddin Bernadien
sian rasionalisme-positivisme sebagai satu-satunya mistifikasiterhadap validitas, dan di luar itu tak ada kebenaran telah‘menjerumuskan’ manusia pada situasi imperialisme kultural-epistemologis.
Stigma modernisme, bagi kaum Posmo, tidak hanya padalevel epistemologi saja, tetapi juga telah melahirkan kecongka-kan politis-ekonomis yang western-centris. Di luar itu tak ada‘language-game’ yang valid yang dapat dimainkan jika tidakberstandard Barat. Sudah dapat diduga akibatnya adalah ruleof the game menjadi monoton, absolut, dan dunia di luar me-reka bukanlah dunia yang beradab yang patut didengar, yangberhak menafsirkan realitas dengan caranya sendiri, bahkanmenciptakan narasi serta ‘grammar of life’ tersendiri. Karenaitulah postmodernisme hadir dengan seberkas harapan untukbisa tampil sebagai sebuah gerakan yang membela sebuah na-rasi dan komunitas yang tergilas dan tersingkir oleh narasi be-sar modernisme-westernisme dengan berbagai dominatif danimperialistiknya. Arus pemikiran posmo bagaikan sebuah pro-tes terhadap berbagai pemikiran yang absolutistik, dan sebagaisubstitusinya tak lain adalah pendekatan relativistik dan plura-listik yang rendah hati mendengarkan serta apresiatif terhadap‘yang lain’ di luar mereka165.
Persoalannya sekarang adalah sudahkah Posmo memilikiseperangkat sistem yang mampu mengatasi anarkhisme dannihilisme yang telah menghadang di depannya? sudahkahpostmodernisme memiliki misi dan komitmen moral pendu-kung bagi kelangsungan dan kejayaan yang diharapkannya?.Let’s wait and see. [*]
165Komarudin Hidayat, dalam Suyoto, (ed.), Postmodernisme danMasa Depan Peradaban, Yogyakarta: Aditya Media, 1994, hlm. 62.
Serpihan-Serpihan Filsafat | 223
BACAAN PENDUKUNG
Ali Mudhofir, 2001, Kamus Filsuf Barat, Yogyakarat: PustakaPelajar.
Arif Budiman, 1994,Posmo: Apa Sih, dalam Suyoto, dll., (ed.),Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban, Yogyakar-ta: Aditya Media.
Bambang Sugiharto, 1996, Postmodernisme: Tantangan BagiFilsafat, Yogyakarta: Kanisius.
Bertens, K., 1996, Filsafat Barat Abad XX Jilid II Prancis, Jakar-ta: P.T Gramedia.
Gede Prama, 1994, Postmodernisme, Ke arah Pemahamantentang Postmodernisme: Refleksi Politik, Yogyakarta:Aditya Media.
Gellner, Ernest, 1994, Menolak Postmodernisme: Antara Fun-damentalisme Rasional dan Fundamentalisme Relegius,Bandung: Mizan.
Honderich, Ted., 1995, The Oxford Companion to Philosophy,New York: Oxford University Press.
Ibrahim Ali-Fauzi, 1994, dalam: Suyoto, dll (ed.), Postmoder-nisme dan Masa Depan Peradaban, Yogyakarta: AdityaMedia.
Komarudin Hidayat, 1994, dalam Suyoto, (ed.), Postmoder-nisme dan Masa Depan Peradaban, Yogyakarta: AdityaMedia.
M. Dawam Rahardjo, 1994, Posmo: Apa Lagi Ini, dalam Suyo-to, dll., (ed.), Postmodernisme dan Masa Depan Perada-ban, Yogyakarta: Aditya Media.
Rauch, Leo., 1998, Introduction to The Philosophy of History,Indianapolis & Cambridge: Hackert Publishing Compa-ny.
Suyoto, dll (ed.), 1994, Postmodernisme dan Masa Depan Pe-
Serpihan-Serpihan Filsafat | 225
TENTANG PENULIS
biologis dari Eliya Anastasiya Billyn dan Herjuna KuncaraMukti Be-nadien ini sekarang sedang mendedikasikankompetensinya di STAIN Jember. Beberapa karya penulisyang pernah dipub-likasikan, diantaranya: Sintesis Pendidikan Islam Asia Afrika, 2002, Paradigma
Yogyakarta. Filsafat Sejarah (Introduction To The Philosophy History
GWF Hegel), 2002, buku yang diterbitkan oleh Pantha-ReiYogyakarta ini diterjemahkan bersama Harjali DosenSTAIN Ponorogo. Dance Of God, Tarian Tuhan, 2003, karya yang diberi kata
Serpihan-Serpihan Filsafat | 225
TENTANG PENULIS
biologis dari Eliya Anastasiya Billyn dan Herjuna KuncaraMukti Be-nadien ini sekarang sedang mendedikasikankompetensinya di STAIN Jember. Beberapa karya penulisyang pernah dipub-likasikan, diantaranya: Sintesis Pendidikan Islam Asia Afrika, 2002, Paradigma
Yogyakarta. Filsafat Sejarah (Introduction To The Philosophy History
GWF Hegel), 2002, buku yang diterbitkan oleh Pantha-ReiYogyakarta ini diterjemahkan bersama Harjali DosenSTAIN Ponorogo. Dance Of God, Tarian Tuhan, 2003, karya yang diberi kata
WIN USULUDDIN adalahlulusan dengan predikat Clumlaude padaProgram Pasca Sarjana (S2) Ilmu FilsafatUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun2004, dan sekarang sedang menempuh pro-gram doktor pada almamater yang sama.Suami Inayatul Anisah, M.Hum serta ayah
WIN USULUDDIN adalahlulusan dengan predikat Clumlaude padaProgram Pasca Sarjana (S2) Ilmu FilsafatUniversitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun2004, dan sekarang sedang menempuh pro-gram doktor pada almamater yang sama.Suami Inayatul Anisah, M.Hum serta ayah
pengantar oleh Prof. Dr. HM. Amin Abdullah, MA, ini diter-bitkan oleh Apeiron Philotes Yogyakarta, ditulis bersamadengan teman-teman seangkatan penulis saat “ngangsukawruh” filsafat di PPS S2 Ilmu Filsafat UGM Yogyakarta,mereka adalah dosen PTN/PTS di Jawa dan Bali. Ludwig Wittgenstein: Pemikiran Ketuhanan dan Implikasi-
nya Terhadap Kehidupan di Era Modern, 2004, diterbitkanoleh Pustaka Pelajar Yogyakarta. Membuka Gerbang Filsafat, 2011, diterbitkan oleh STAIN
Jember Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Yogya-karta. Buku yang sedang berada di tangan para pembacayang budiman ini adalah karya ke dan saat ini sedangmenunggu terbitnya buku ketujuh.
Karya publikasi yang lain di antaranya: (1) Seni-Seni Spi-ritualis: Menyelam Ke Dasar Pemikiran Seni Iqbal dan Frit-chuof Schuon, 2002, Harmonia UNES Semarang, (2) Mem-bangun Etika Dialogis-Kritis Bagi Dunia Pendidikan, 2006,Jurnal Al Fithrah Jurusan Tarbiyah STAIN Jember, (3) AxiologiKomunikasi Dalam Perspektif Islam: Sebuah Alternatif Bar-gaining Bagi Etika Periklanan, 2006, Jurnal Al Hikmah JurusanDakwah STAIN Jember, (4) Distingsi Ontologis Antara Demok-rasi dan Agama, 2006, Jurnal Al Adalah STAINPres, STAINJember, (5) Pengayaan Intelektual dan Kultural: Upaya MenitiJalan Lintas Pluralisme Keberagamaan Era Posmodern, 2006,Jurnal Al ‘Adalah STAINPress, STAIN Jember, (6) Agama danNilai Humanistik: Sebuah Pendekatan Filsafat Perennial, 2009,Jurnal Al ‘Adalah STAINPress, STAIN Jember, (7) Sex Edu-cation: Memahami Bahasa Kitab Uqud Allujainy, 2010, dan (8)Prespektif Riffat Hasan Atas Konstruksi Teologis Gender, 2010,keduanya diterbitkan dalam Jurnal AN NISA Pusat StudiGender STAIN Jember [*]
226 | Win Usuluddin