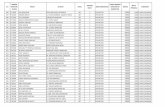Volume 4, Nomor 1, April 2020 P–ISSN - Portal Publikasi ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Volume 4, Nomor 1, April 2020 P–ISSN - Portal Publikasi ...
ii
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (JPPDAS) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Balai
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS) kerjasama dengan
Masyakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI). Terbitan ini telah mendapatkan P-ISSN: 2579-6097 dan
E-ISSN: 2579-5511. Terbitan pertama jurnal ini adalah Volume 1 Nomor 1 yang diluncurkan pada tanggal 28
April 2017. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu setiap Bulan April dan Oktober. Setiap terbitan
berisi 6 Karya Tulis Ilmiah (KTI).
SASARAN DAN RUANG LINGKUP
Karya Tulis Ilmiah yang diterbitkan dalam JPPDAS merupakan hasil-hasil penelitian yang memberikan
kontribusi secara ilmiah dalam pengelolaan DAS. Ruang lingkup jurnal meliputi bidang pengelolaan lahan dan
vegetasi, konservasi tanah dan air, rehabilitasi lahan, hidrologi, sosial, ekonomi, kelembagaan, penginderaan
jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang mendukung teknologi pengelolaan DAS.
TERBITAN
JPPDAS diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS), Badan Litbang dan Inovasi
(BLI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerjasama
dengan Masyarakat Konservasi Air dan Tanah Indonesia (MKTI).
ISSN print/ P-ISSN : 2579-6097
ISSN electronic/ E-ISSN : 2579-5511
Edisi elektronik tersedia di
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS
Seluruh KTI yang diterbitkan diberi nomor DOI yang digabungkan dengan awalan DOI
Crossreff http://dx.doi.org/10.20886/jppdas
FREKUENSI PENERBITAN
Jurnal diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu April dan Oktober.
KEBIJAKAN PEER REVIEW
Setiap KTI yang diterbitkan di JPPDAS akan ditelaah awal meliputi kesesuaian ruang lingkup jurnal dan tata cara
penulisan menurut petunjuk penulisan. Selanjutnya telaah dilakukan minimal oleh dua reviewer dengan
mempertimbangkan kebaruan, orisinalitas, metode, dan dampak keilmuan.
AKREDITASI
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (JPPDAS) telah terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14/E/KPT/2019 tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 3 Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019. Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu mulai Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.
iii
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
ALAMAT KORESPONDENSI
Sekretariat Redaksi JPPDAS:
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS
Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta 57102, Jawa Tengah-Indonesia
Telepon: +62-271-716709
Fax:+62-271-716959
Jam Kerja: Senin - Jumat, 07.30 -16.00 WIB
Email:[email protected]
Website:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS
PENYERAHAN ONLINE
Penulis yang akan menyerahkan KTI ke JPPDAS perlu melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan
password.
Registrasi pada:
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS/user/register
Login pada:
http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS/login
Karya tulis ilmiah harus dikirim secara daring. Penulis dapat memantau status dan proses telaah KTI dengan
login dalam jurnal tersebut.
CHECKLIST PERSIAPAN PENYERAHAN
Sebelum mengunggah KTI, penulis diminta untuk mengecek kelengkapan penyerahannya dengan seluruh item
di bawah ini. Apabila KTI tidak sesuai dengan petunjuk jurnal, maka akan dikembalikan ke penulis
1. Karya tulis ilmiah harus ditulis berdasarkan template JPPDAS dan sesuai dengan pedoman bagi penulis.
2. Format referensi berdasarkan gaya American Psychological Association (APA) edisi ke 6 dan dikelola
dengan perangkat lunak Mendeley.
3. Delapan puluh persen dari referensi yang digunakan merupakan referensi primer terbitan 10 tahun
terakhir.
4. Formulir pernyataan etis (Formulir JPPDAS 01_paper) dan formulir transfer hak cipta (Formulir JPPDAS
06_copyright Kesepakatan transfer) harus dilampirkan saat penyerahan KTI.
PROSES PENGEDITAN (COPY EDITING) DAN KOREKSI CETAKAN (PROOFREADING)
Setiap KTI yang diterima oleh JPPDAS akan dilakukan pengeditan untuk peningkatan kualitas tata bahasa oleh
tim editorial.
iv
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
PEMERIKSAAN PLAGIARISME Pemeriksaan plagiarisme dilakukan oleh tim editorial JPPDAS. Apabila terindikasi plagiarisme, maka KTI akan ditolak. PENGELOLAAN REFERENSI Untuk ketepatan pengambilan sumber informasi,
silakan menggunakan perangkat lunak pengelola
referensi Mendeley dalam membuat bibliografi,
referensi dan kutipan dalam teks. Format referensi
berdasarkan gaya APA ke 6. Mendeley adalah
manajer referensi gratis yang dapat diunduh pada:
https://www.mendeley.com/Download-mendeley-
desktop.
KEBIJAKAN AKSES TERBUKA
Karya tulis ilmiah dalam JPPDAS dapat
diakses secara terbuka dengan tujuan
mendukung pertukaran informasi dan pengetahuan
secara global.
IZIN CC
Jurnal Penelitian Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dikelola
oleh BPPTPDAS, BLI, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan di bawah CC BY-NC-SA Creative
Commons Attribution Non Komersial Berbagi
seperti attribution 4.0 internasional.
PENGELOLAAN BIAYA
Jurnal ini tidak membebankan pembiayaan dalam pemrosesan. Karya tulis ilmiah yang diterbitkan secara elektronik tersedia secara bebas pada website. Penulis dapat menggunakan file dengan ekstensi .pdf yang telah diterbitkan untuk keperluan non-komersial pada website institusi atau pribadi.
PROSES INDEX DAN ABSTRAK
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
telah terindeks dari layanan berikut: Cross Ref, Google
Scholar, Mendeley, Indonesian Scientific Journal
Database (ISJD), PKP Publishing Services, Cite Factor,
Bielefeld Academic Search Engine (BASE), dan
Scientific and Literature (SCILIT).
HAK CIPTA
Jurnal ini dan kontribusi individu yang terkandung di
dalamnya dilindungi oleh hak cipta BPPTPDAS, BLI,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hak
cipta tersebut mengikuti ketentuan dan kondisi yang
berlaku dalam penggunaannya.
PERNYATAAN PRIVASI
Nama dan alamat email yang masuk dalam jurnal ini
akan digunakan secara eksklusif untuk kebutuhan
jurnal dan tidak akan digunakan untuk kebutuhan
pihak lain.
v
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
EDITORIAL TEAM
Editor in-Chief
Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc. (Scopus ID=26030255700)
Hidrologi dan Konservasi Tanah Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS)
Editor
Dr. Ir. Irdika Mansur, M.For.Sc. (Scopus ID=6603222376)
Rehabilitasi Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB)
Dr. Ir. Suria Darma Tarigan, M.Sc. (Scopus ID=57073753500)
Hidrologi dan Konservasi Tanah IPB, Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI)
Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., P.hD. (Scopus ID=55266523600)
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Dr. Ishak Yassir, S.Hut., M.Si. (Scopus ID=25930199200)
Rehabilitasi Lahan Hidroklimatologi
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi KSDA
Dr. Muhammad Anggri Setiawan, M.Sc. (Scopus ID=23487125500)
Geografi UGM
Dr. Agung Budi Supangat, S.Hut., M.T. Hidrologi BPPTPDAS
Dr. rer. Agr. Evi Irawan, SP., M.Sc. Ekonomi Lingkungan BPPTPDAS
Dr. Ir. Dewi Retna Indrawati, M.P. Sosial Ekonomi BPPTPDAS
Dr. Irfan Budi Pramono, M.Sc. (Scopus ID=57194592259)
Hidrologi BPPTPDAS
Saut A. Sagala, ST., M.Sc., Ph.D. (Scopus ID=35323035100)
Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung (ITB)
Nunung Puji Nugroho, S.Hut., M.Sc., Ph.D. (Scopus ID=56991068300)
Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografi
BPPTPDAS
Dr. S. Andy Cahyono, SP., M.Si. Ekonomi Kehutanan BPPTPDAS
Yongky Indrajaya, S. Hut., M.T., M.Sc. (Scopus ID=57189633934)
Perencanaan Hutan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestri
Dr. Ir. Hunggul Yudono S.H. Nugroho, M.Si. (Scopus ID=57194607752)
Hidrologi dan Konservasi Tanah Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar
vi
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
Copy Editor
Dr. Ir. Endang Savitri, M.Sc. Hidrologi dan Konservasi Tanah BPPTPDAS
Dr. Ir. Nining Wahyuningrum, M.Sc. Hidrologi dan Konservasi Tanah BPPTPDAS
Advisory
Slamet Edi Sumanto, S.Sos, M.Si. BPPTPDAS
Journal Manager
Ir. Salamah Retnowati, M.Si. BPPTPDAS
Tri Hastuti Swandayani, S.Kom., M.Si. BPPTPDAS
Section Editor Web Admin
Esa Bagus Nugrahanto, S.Hut. BPPTPDAS R.M. Tommy Kusuma BPPTPDAS Alvian Febry Anggana, S.Hut. BPPTPDAS Agung Budi Kuwadto BPPTPDAS Arina Miardini, S.Hut., M.Sc. BPPTPDAS
Baharinawati W. Hastanti, S.Sos., M.Sc. BPPTPDAS Secretariat
Diah Auliyani, S.Hut., M.Si. BPPTPDAS Ir. Salamah Retnowati, M.Si. BPPTPDAS Upik Pramuningdiyani, S.Kom. BPPTPDAS Upik Pramuningdiyani, S.Kom. BPPTPDAS Tri Hastuti Swandayani, S.Kom., M.Si. BPPTPDAS Proofreaders Haryani Ambarwati, S.Kom. BPPTPDAS
Esa Bagus Nugrahanto, S.Hut. BPPTPDAS
Alvian Febry Anggana, S.Hut. BPPTPDAS Layout Editor
Arina Miardini, S.Hut., M.Sc. BPPTPDAS Wahyu Wisnu Wijaya, S.Hut. BPPTPDAS Baharinawati W. Hastanti, S.Sos., M.Sc. BPPTPDAS Uchu Waluya Heri Pahlana, S.Hut. BPPTPDAS Diah Auliyani, S.Hut., M.Si. BPPTPDAS Eko Priyanto, S.P., M.GIS BPPTPDAS
Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc. BPPTPDAS
Sekretariat Redaksi JPPDAS: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta / 57102 Telepon/Fax: (0271) 716709 dan 716959 E-mail: [email protected]; Website:http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS
Diterbitkan di Surakarta, Indonesia ©2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS
vii
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
REVIEWER
Prof. Dr. Hidayat Pawitan, M.Sc. (Scopus ID=55177185300)
Hidrologi Sumberdaya Air IPB
Prof. Dr. Ir. Putu Sudira, M.Sc. Hidroklimatologi UGM
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S. (Scopus ID = 57195307987)
Sosial Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS)
Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.Si. (Scopus ID=56469817600)
Konservasi Tanah dan Air IPB, MKTI
Prof. Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. (Scopus ID=48461414700)
Kebijakan Kehutanan UGM
Prof. Dr. rer. nat. Junun Sartohadi, M.Sc. (Scopus ID=24766831900)
Geografi Tanah dan Lingkungan UGM, MKTI
Prof. Dr. rer.nat Muh Aris Marfa’i, M.Sc. (Scopus ID=22951320200)
Penginderaan Jauh dan Kebencanaan UGM
Prof. Dr. I.G.A. K.R. Handayani, S.H., M.H. (Scopus ID = 56460408200)
Aspek Hukum Pengelolaan DAS UNS
Dr. Ir. Ai Dariah, M.Si. (Scopus ID=55366276400)
Konservasi Tanah dan Air Balai Penelitian Tanah (Balittanah), Badan Litbang Pertanian, MKTI
Projodanoedoro, M.Sc., Ph.D. (Scopus ID= 54083041300)
Penginderaan Jauh UGM
Dr. Ir. Maswar, M.Agric.Sc. (Scopus ID = 56527177600)
Konservasi Tanah dan Air Balittanah, Badan Litbang Pertanian
Dr. Prabang Setyono, S.Si., M.Si. (Scopus ID=56179823100)
Ekologi Pemodelan dan Rekayasa Lingkungan
UNS
Dr. Sapja Anantanyu, S.P., M.Si. (Scopus ID = 57188728132)
Sosial dan Kelembagaan UNS
Sekretariat Redaksi JPPDAS: Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Alamat: Jl. Jend. A. Yani – Pabelan, Kartasura PO BOX 295 Surakarta / 57102 Telepon/ Fax: (0271) 716709 dan 716959 E-mail : [email protected]; Website: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPPDAS
Diterbitkan di Surakarta, Indonesia ©2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS
viii
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Editor dan Mitra Bestari yang
telah menyunting dan memberi saran yang konstruktif terhadap Karya Tulis Ilmiah dalam Jurnal
Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Volume 4 Nomor 1, April 2020.
1. Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.
2. Prof. Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, M.Si.
3. Dr. Agung Budi Supangat, S.Hut., M.T.
4. Dr. Ir. Ai Dariah, M.Si.
5. Dr. Ir. Dewi Retna Indrawati, M.Si.
6. Dr. Ir. Hunggul Yudono S.H. Nugroho, M.Si.
7. Dr. S. Andy Cahyono, S.P., M.Si.
8. Dr. Ir. Tyas Mutiara Basuki, M.Sc.
9. Nunung Puji Nugroho, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
10. Yongky Indrajaya, S. Hut., M.T., M.Sc.
ix
Volume 4, Nomor 1, April 2020
P–ISSN: 2579-5511
E–ISSN: 2579-6097
DAFTAR ISI (CONTENTS)
Judul Halaman
IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR (Implication of Goverment Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental Economical Aspect Towards Water and Soil Conservation)
AL. Sentot Sudarwanto ________________________________________________ 1-16
MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN (Developing a participatory planning process of micro-watershed management: a lesson learned)
Agung Budi Supangat, Dewi Retna Indrawati, Nining Wahyuningrum, Purwanto, dan Syahrul Donie_____________________________________________________ 17-36
STUDI KARAKTERISTIK HIDROLOGI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JIRAK MENGGUNAKAN TIME SERIES ANALYSIS (Hydrological Characteristics Study of Jirak Sub Watershed Using Time Series Analysis)
Bayu Argadyanto Prabawa ______________________________________________ 37-52
POLA HUJAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DALAM PERENCANAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR (Rainfall pattern for water resources utilization planning in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum __________________________________ 53-62
FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS BERBASIS MORFOMETRI UNTUK PRIORITAS PENANGANAN EROSI DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO (Fuzzy analytic hierarchy process based on watershed morphometry for erosion priority mapping in Oyo Sub Watershed)
Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini _________________________________ 63-78
APLIKASI METODE SIDIK CEPAT JASA LINGKUNGAN PADA DAS MIKRO (Rapid assessment method of environmental services in the micro catchment)
Anang Widicahyono, San Afri Awang, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan___ 79-102
x
JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)
ABSTRAK
P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020
E-ISSN : 2579-6097
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya
UDC/ ODC: 631.4+630*116 AL. Sentot Sudarwanto 1 1Fakultas Hukum, dan Peer group PPLH LPPM Universitas Sebelas Maret IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG INSTRUMEN EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 1 - 16 Apabila masyarakat wilayah hulu melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA), masyarakat bagian hilir ikut merasakan manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat hulu perlu diberi Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Penulisan ini bertujuan menganalisis konsekuensi logis pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup terhadap KTA khususnya terkait dengan jasa lingkungan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan IJL telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tetapi belum ada pengaturan secara rinci terkait penghitungan jasa lingkungan KTA yang dilakukan oleh masyarakat hilir kepada masyarakat hulu. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama pemerintah membentuk tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola dana jasa lingkungan. Masyarakat hilir membayar jasa lingkungan kepada masyarakat hulu sebagai penyedia jasa melalui lembaga pengelola jasa lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perlu segera menyusun peraturan teknis tentang mekanisme dan penghitungan IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah hulu. Kata kunci: Implikasi; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; KTA; DAS
UDC/ ODC: 556.51 Agung Budi Supangat1, Dewi Retna Indrawati1, Nining Wahyuningrum1, Purwanto1, dan Syahrul Donie 1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPPTPDAS) MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 17 - 36 Tahapan perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala operasional (DAS mikro). Kesulitan dan kegagalan pengelolaan DAS mikro seringkali bermula dari kegagalan dalam membangun proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan kolaboratif dengan para pihak terkait. Kegiatan penelitian tindakan (action research) ini bertujuan untuk menemukan proses/tahapan perencanaan partisipatif yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman dan evaluasi proses yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan di DAS Mikro Naruan, Sub DAS Keduang, DAS Bengawan Solo Hulu. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Basis data dasar (baseline data) detil terkait karakteristik potensi dan kerentanan wilayah DAS mikro sangat penting diketahui sebelum proses perencanaan; 2) Proses perencanaan pengelolaan DAS mikro tidak dapat sepenuhnya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi perlu kombinasi antara sistem top down dan partisipatif; 3) Perencanaan yang sifatnya top down menyangkut pemberian rambu-rambu pengelolaan lahan yang benar di wilayah hulu DAS; 4) Perencanaan partisipatif dilakukan pada saat penyusunan rencana penggunaan/ pemanfaatan lahan, jenis kegiatan konservasi yang sesuai serta andil sumber daya dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi; 5) Rencana kolaboratif perlu dibangun dengan para pihak terkait dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan DAS mikro. Kata kunci: Kolaborasi, DAS mikro, partisipasi, perencanaan
xi
JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)
ABSTRAK
P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020
E-ISSN : 2579-6097
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya
UDC/ ODC: 556(594.59) Bayu Argadyanto Prabawa1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi Yogyakarta STUDI KARAKTERISTIK HIDROLOGI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JIRAK MENGGUNAKAN TIME SERIES ANALYSIS Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 37 - 52
Sub Daerah ALiran Sungai (DAS) Jirak adalah salah satu aliran sungai yang muncul kembali di Gunungkidul. Aliran sungai mengalir ke dalam. Gua Kalisuci, dan menjadi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini digunakan untuk kegiatan pariwisata yang dikenal sebagai Cave Tubing. Masalah utama dari kegiatan pariwisata ini adalah terjadinya banjir. Banjir ini berasal dari debit yang berasal dari Sungai Jirak sebagai hulu dari Gua Kalisuci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrologis Sub DAS Jirak di lokasi Wisata Gua Kalisuci dengan harapan akan menambah pemahaman pengelola wisata Gua Kalisuci terkait pengaturan sistem peringatan dini dan sistem evakuasi ketika terjadi banjir. Karakteristik hidrologi ditentukan dari rating curve, jeda waktu (Tlag) dan perhitungan curah hujan efektif (Pe). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jeda waktu antara kejadian hujan dan kejadian banjir awal di Sub DAS Jirak berkisar antara 2,5 hingga 3 jam. Respon debit puncak yang cepat mengindikasikan bahwa Sub DAS Jirak memiliki sistem drainase yang cepat merespon hujan di musim hujan. Persentase curah hujan efektif ditentukan dari 17 hidrograf banjir terpilih yang nilainya meningkat dari fase awal hingga akhir musim hujan. Karakteristik hidrologi Sub DAS Jirak ini dapat digunakan oleh tim manajemen pariwisata Gua Kalisuci sebagai peringatan dini dan untuk evakuasi ketika banjir terjadi. Kata Kunci: banjir, karakteristik hidrologi, jeda waktu, hujan efektif
UDC/ ODC: 556.12(594.55) Diah Auliyani1 dan Nining Wahyuningrum1 1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS (BPPTPDAS) POLA HUJAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DALAM PERENCANAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 53 - 62 Informasi mengenai fluktuasi hujan sangat penting terutama bagi masyarakat lokal yang masih bergantung pada sumberdaya alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hujan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya air. Data curah hujan tahun 1990-2016 dari 14 stasiun penakar hujan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui fluktuasi hujan dan pergeseran musim. Curah hujan tahunan di hulu DAS Bengawan Solo bervariasi antara 1.433,5 mm hingga 3.231,2 mm dengan rerata mencapai 2.224,6 mm. Tidak terjadi perubahan awal musim hujan maupun musim kemarau, namun demikian durasi musim hujan mengalami peningkatan dari 7 bulan (Oktober-April) pada periode 1990-1998 dan 1999-2007, bertambah menjadi 8 bulan (Oktober-Mei) pada periode 2008-2016. Sebesar 90% curah hujan terkonsentrasi pada musim hujan. Pemanenan air hujan dapat dilakukan untuk mengurangi runoff di musim hujan sekaligus sebagai upaya penyediaan sumberdaya air di musim kemarau. Kata kunci: curah hujan; pergeseran musim; sumberdaya air; Bengawan Solo
xii
JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (JPPDAS)
ABSTRAK
P-ISSN : 2579-5511 Vol.4 No.1, April 2020
E-ISSN : 2579-6097
Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh disalin tanpa izin dan biaya
UDC/ ODC: 631.459(594.59) Alfiatun Nur Khasanah1 dan Arina Miardini2
1 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS (BPPTPDAS) FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS BERBASIS MORFOMETRI UNTUK PRIORITAS PENANGANAN EROSI DI
SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 63 - 78
Erosi merupakan salah satu indikasi kerusakan DAS. Dalam pengelolaan DAS perlu dilakukan urutan prioritas penanganan dengan memperhatikan karakteristik DAS, salah satunya yaitu karakter morfometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi prioritas penanganan erosi di Sub DAS Oyo berdasarkan data morfometri dengan menggunakan pemodelan Fuzzy AHP. Parameter morfometrik yang mempengaruhi erosi adalah Rbm (bifurcation ratio), Rc (circulatory ratio), Dd (drainage density), T (texture), Su (gradient), dan Rn (rugness number). Nilai tertinggi dari hasil analisis menunjukkan lokasi prioritas yang harus didahulukan penanganan erosinya. Tingkat prioritas tinggi terdapat pada 21 sub-sub DAS dengan luas 3.82 ha, tingkat sedang pada 35 sub-sub DAS dengan luas 17.780,21 ha, tingkat rendah pada 106 sub-sub DAS dengan luas 48.974,46 ha. Urutan prioritas penanganan erosi pada tingkat sub DAS sangat penting untuk menyusun rencana pengelolaan DAS dalam rangka pengendalian erosi tanah yang sesuai sebagai upaya perlindungan tanah dari erosi lebih lanjut.
Kata kunci: fuzzy-AHP; morfometri; prioritas; erosi; Sub DAS Oyo
UDC/ ODC : 556.51 Anang Widicahyono1, San Afri Awang2, Ahmad Maryudi2, dan M. Anggri Setiawan3 1Program Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 2Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 3Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada APLIKASI METODE SIDIK CEPAT JASA LINGKUNGAN PADA DAS MIKRO Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Vol.4 No.1, April 2020, p. 79 - 102
Wilayah DAS terbagi habis oleh ekosistem dengan keragaman jasa lingkungan yang dapat dijadikan sebagai kerangka dasar kegiatan pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta mengaplikasikan metode sidik cepat identifikasi dan penilaian jasa lingkungan pada level DAS mikro di Sub DAS Cebong, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini menggunakan tiga prinsip dasar: (i) spasial dan hubungan antar wilayah, (ii) mekanisme hubungan sebab akibat, serta (iii) nilai potensi dan dampak. Metode sidik cepat jasa lingkungan merupakan kombinasi analisis spasial dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis, analisis hubungan sebab akibat dengan metode system thinking, serta valuasi ekonomi. Hasil identifikasi sidik cepat menunjukkan keragaman jasa lingkungan di Sub DAS Cebong berupa: 1) jasa penyediaan dengan jasa utama sumber makanan dan air domestik, 2) jasa regulasi dengan jasa utama cadangan karbon dan pengendalian erosi sedimentasi, 3) jasa habitat dengan jasa utama biodiversitas, dan 4) jasa budaya dengan jasa utama pariwisata. Jasa penyediaan makanan dalam bentuk pertanian kentang memberikan nilai manfaat paling tinggi, namun memunculkan penurunan potensi jasa lingkungan lainnya. Jasa budaya berupa pariwisata, meskipun nilai manfaat langsungnya lebih rendah, namun dapat mendukung keberlanjutan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam DAS. Penelitian ini menjadi sebuah inisiasi petunjuk teknis rencana pengelolaan DAS mikro berbasis jasa lingkungan.
Kata kunci: metode sidik cepat; jasa lingkungan; DAS Mikro
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.1-16
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 1
IMPLIKASI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG
INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KONSERVASI TANAH DAN AIR
(Implication of Goverment Regulation Number 46 of 2017 Concerning Environmental
Economical Aspect Towards Water and Soil Conservation)
AL. Sentot Sudarwanto1 1Fakultas Hukum, dan Peer group PPLH LPPM Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami No.36 A, Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126, Email: [email protected]
Diterima: 1 November 2019; Direvisi: 26 Maret 2020; Disetujui: 30 Maret 2020
ABSTRACT
If the upstream community carries out the Soil and Water Conservation (SWC), whereas the downstream community participates in the benefits, therefore the upstream community needs to be rewarded with Payment Environmental Services (PES). This writing aims to analyze the logical consequences of the regulation of environmental economic instruments toward the SWC, especially related to environmental services. The research method is a normative juridical approach, using secondary data consisting of primary and secondary legal materials using qualitative analysis techniques. The results of the study show that the PES has been regulated in Government Regulation Number 46 of 2017 on Environmental Economic Instruments but there is no detailed regulation related to the calculation of SWC environmental services performed by downstream communities toward upstream communities. The Watershed Management Coordination Forum together with the government formed an Ad Hoc team whose task was to manage environmental service funds. Downstream communities pay for environmental services to the upstream communities as service providers through the environmental service management agencies. Therefore, the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia needs to immediately compile technical regulations on the mechanism and calculation of SWC from communities and governments in the downstream region to the government and communities in the upstream region. Keywords: Implication; instruments of living environmental economic; soil and water
conservation
ABSTRAK
Apabila masyarakat wilayah hulu melakukan Konservasi Tanah dan Air (KTA), masyarakat bagian hilir ikut merasakan manfaatnya, oleh sebab itu masyarakat hulu perlu diberi Imbal Jasa Lingkungan (IJL). Penulisan ini bertujuan menganalisis konsekuensi logis pengaturan tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup terhadap KTA khususnya terkait dengan jasa lingkungan. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan IJL telah diatur dalam Peraturan
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
2 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup tetapi belum ada pengaturan secara rinci terkait penghitungan jasa lingkungan KTA yang dilakukan oleh masyarakat hilir kepada masyarakat hulu. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama pemerintah membentuk tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola dana jasa lingkungan. Masyarakat hilir membayar jasa lingkungan kepada masyarakat hulu sebagai penyedia jasa melalui lembaga pengelola jasa lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI perlu segera menyusun peraturan teknis tentang mekanisme dan penghitungan IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di wilayah hilir kepada pemerintah dan masyarakat di wilayah hulu. Kata kunci: Implikasi; Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; KTA; DAS
I. PENDAHULUAN
Sumber daya alam bisa diartikan
sebagai segala sesuatu yang berada di
lingkungan alam, dan manusia bisa
memanfaatkannya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Meningkatnya
jumlah manusia berdampak pada semakin
besarnya pemanfaatan sumber daya alam
untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.
Hal ini akan diikuti dengan munculnya
berbagai permasalahan lingkungan yaitu
menurunnya daerah resapan, penurunan
kualitas lingkungan, dan berubahnya pola
cuaca sehingga menyebabkan
ketidakseimbangan antara pemanfaatan
dan ketersediaan sumber daya dalam
kuantitas dan kualitas yang memadahi.
Hal ini merupakan ciri bahwa daya dukung
Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun,
yang dapat mengakibatkan terganggunya
perekonomian dan tata kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu, daya dukung
DAS harus ditingkatkan dengan
pengelolaan yang melibatkan masyarakat
dan berbagai institusi yang punya tugas
pokok fungsi terkait pengelolaan DAS.
Pengelolaan DAS merupakan upaya
manusia dalam mengatur hubungan
timbal balik antara sumber daya alam dan
manusia di dalam DAS serta segala
aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan
keserasian ekosistem serta meningkatnya
kemanfaatan sumber daya alam bagi
manusia secara berkelanjutan.
Kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan hidup telah diatur, namun
permasalahan lingkungan masih terus
terjadi. Kebijakan yang mengatur tidak
cukup untuk mengendalikan dan
menyelesaikan permasalahan lingkungan,
jika pelaksanaan dan pengawasannya
cenderung normatif, sementara
eksploitasi sumber daya terus dilakukan,
maka terjadi degradasi lingkungan. Tanah
dan air merupakan sumber daya vital
sebagai penyangga kehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya. Solusi
permasalahan degradasi lingkungan
khususnya tanah dan air adalah peraturan
perundang-undangan terhadap
perlindungan konservasi lingkungan, dan
kebijakan publik lembaga pengelola KTA
yang berkualitas, responsif dan aplikatif.
(Samedi, 2015) menyebutkan faktor sosial
dan ekonomi merupakan faktor dominan
yang menjadi tantangan besar dalam
upaya konservasi. Efektivitas pelaksanaan
konservasi dapat dicapai dengan
kelengkapan hukum yang memadai untuk
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 3
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
membuat sumber daya alam bermanfaat
secara berkelanjutan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,
pembayaran jasa lingkungan merupakan
salah satu instrumen ekonomi sebagai
bagian dari instrumen pengelolaan
lingkungan hidup. Lingkungan beserta
segenap komponen didalamnya memiliki
peran dalam mendukung kehidupan,
tetapi belum dipertimbangkan dalam
sistem ekonomi. Hal ini menjadi dasar
bagi konsep pembayaran jasa lingkungan.
Perwujudan pembayaran jasa lingkungan
berupa penghargaan atau reward yang
diberikan oleh para pemanfaat air karena
keberadaan air di dataran rendah dalam
hal ini hilir sangat bergantung pada
ketersediaan air yang ada di kawasan hulu
(Sutopo, Sanim, Saukat, & Mawardi,
2011). Selama ini masyarakat daerah hulu
diminta untuk melakukan KTA, sedangkan
masyarakat bagian hilir ikut merasakan
manfaatnya. Masyarakat hilir sebagai
penerima manfaat perlu membayar dana
kompensasi sebagai imbal jasa kepada
masyarakat hulu sebagai pengasil jasa
lingkungan.
Pembayaran jasa lingkungan atau
Payment for Environment Service (PES)
merupakan pemberian penghargaan
kepada pengelola atau penghasil jasa
lingkungan dari suatu lahan atau
ekosistem berupa pembayaran dana
kompensasi/insentif atau dana konservasi
untuk kepentingan pengelolaan. Salah
satu program PES yang sudah
dilaksanakan di Indonesia adalah Program
Pengembangan Kebijakan dan
Percontohan PES atau IJL di DAS Krueng
Montala, Jantho, Kabupaten Aceh Besar
oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Komisi Ekonomi dan Sosial untuk
Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) bersama
World Wide Fund for Nature (WWF)
Indonesia Kantor Program Aceh dan
Badan Pengelola Dampak Lingkungan
Daerah (Bapedalda) Aceh sejak Desember
2011 (Wardah & Farsia, 2013). Menurut
Wardah dan Farsia (2013), pelaksanaan
Program PES di Krueng Montala ini,
terdapat beberapa hal yang perlu
dievaluasi antara lain, pertama perangkat
hukum di tingkat nasional dan lokal belum
mendukung pelaksanaan program PES
khususnya untuk jasa lingkungan air,
karena belum adanya mekanisme standar
yang disepakati untuk pelaksanaan PES.
Kedua, mekanisme dan standar
pembayaran PES di Krueng Montala masih
pada tahap awal, sehingga masyarakat
belum mendapatkan manfaat ekonomi
secara langsung.
Program IJL saat ini telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Konservasi Tanah dan Air dan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan
DAS selama ini masyarakat daerah hulu
melakukan KTA dan masyarakat bagian
hilir ikut merasakan manfaatnya.
Masyarakat hilir sebagai penerima
manfaat perlu membayar dana
kompensasi sebagai imbal jasa kepada
masyarakat hulu, maka perlu dipikirkan
mekanisme pemberian kompensasinya.
Sampai saat ini, pengaturan mengenai
mekanisme pemberian dan penghitungan
IJL KTA dari masyarakat dan pemerintah di
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
4 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
wilayah hilir kepada pemerintah dan
masyarakat di wilayah hulu belum ada.
Berdasarkan masalah tersebut di atas,
tujuan dari penelitian ini adalah
menganalisis konsekuensi logis
pengaturan tentang instrumen ekonomi
lingkungan hidup terhadap KTA khususnya
terkait dengan IJL.
II. BAHAN DAN METODE
Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan
mencermati pijakan yuridis yang
mengatur tentang topik persoalan
penelitian.
Jenis data dalam penelitian ini adalah
data sekunder yaitu data yang diperoleh
dari kajian literatur, sedangkan sumber
data terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer terdiri dari Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014
tentang Konservasi Tanah dan Air, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup. Bahan hukum
sekunder terdiri dari literatur dan jurnal
nasional maupun internasional yang
mengkaji tentang IJL.
Setelah data sekunder yang
diperlukan di dalam penelitian ini
terkumpul, maka selanjutnya dilakukan
analisis data menggunakan analisis
kualitatif.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konservasi Tanah dan Air
Tanah dan air merupakan sumberdaya
alam utama sebagai penyokong
kehidupan makhluk hidup di bumi. Kedua
sumber daya tersebut mudah mengalami
kerusakan dan terdegradasi terutama
karena berbagai aktivitas pembangunan
seperti kegiatan pertanian, industri,
infrastuktur, serta perumahan. Degradasi
lahan juga dapat disebabkan oleh
pembukaan atau pemanfaatan hutan yang
hanya berorientasi ekonomi tanpa
memperhatikan kaidah lingkungan baik
melalui kegiatan pengusahaan hutan,
konversi kawasan hutan menjadi areal
pertambangan, perkebunan, dan
pemukiman yang kurang terencana
dengan baik. Kerusakan tanah bisa terjadi
karena hilangnya unsur hara, erosi tanah,
serta pencemaran tanah. Adapun
kerusakan air dapat berupa mengeringnya
mata air atau berkurangnya debit air,
penurunan kualitas air akibat sedimentasi,
dan pencemaran air. Jika tanah dan air
mengalami kerusakan maka fungsi utama
tanah sebagai penopang kehidupan akan
terganggu. Oleh karena itu, diperlukan
upaya KTA untuk menjaga kualitasnya
agar dapat dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Hal ini merupakan
tanggung jawab dan kewajiban
pemerintah bersama masyarakat.
Konservasi sumber air penting untuk
dilakukan salah satunya dengan cara
vegetatif melalui penanaman lahan kritis
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 5
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
di daerah tangkapan air. Salah satu contoh
upaya konservasi air yang berpotensi
untuk pengembangan IJL (payment for
enviromental services) sekaligus upaya
dalam menekan deforestasi adalah
kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air
di Kawasan Suaka Alam Marapi Provinsi
Sumatera Barat (Riska, Bambang, &
Budiyono, 2013). Penerapan pembayaran
jasa lingkungan untuk kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan merupakan salah satu
solusi untuk mengatasi kerusakan fungsi
hidrologi Sub DAS Way Betung Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung dengan
bentuk pembayaran berupa uang tunai,
pembangunan pedesaan, bantuan bibit
dan pupuk dan hewan ternak (Arafat,
Wulandari, & Qurniati, 2015).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Konservasi Tanah dan Air,
menyebutkan bahwa KTA merupakan
upaya pelindungan, pemulihan,
peningkatan, dan pemeliharaan fungsi
tanah pada lahan sesuai dengan
kemampuan dan peruntukan lahan untuk
mendukung pembangunan yang
berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
Berbagai tindakan konservasi tanah juga
merupakan tindakan konservasi air
dimana setiap perlakuan yang diberikan
pada suatu wilayah DAS, akan
mempengaruhi tata air pada wilayah
tersebut dan tempat-tempat di hilirnya.
Kegiatan KTA antara lain meliputi
pengendalian erosi dan banjir, pengaturan
pemanfaatan air, peningkatan daya guna
lahan, peningkatan produksi dan
pendapatan petani termasuk peningkatan
peran serta masyarakat (Wahyudi, 2014).
Salah satu upaya untuk meningkatkan
produksi pangan, meningkatkan
produktivitas lahan secara berkelanjutan
dan menjaga kelestarian lingkungan dapat
dilakukan dengan pemanfaatan lahan
kering berlereng dengan menerapkan
teknologi KTA yang tepat (Heryani &
Sutrisno, 2013). Penelitian yang dilakukan
Katharina (2007) pada usaha tani kentang
menunjukkan bahwa usaha pertanian
yang menerapkan teknik konservasi
memperoleh pendapatan yang lebih
rendah daripada yang tidak menerapkan
teknik konservasi. Namun demikian
analisis jangka panjang (20 tahun ke
depan), usaha tani yang menerapkan
teknik konservasi memberikan
keuntungan yang lebih tinggi daripada
tidak mengadopsi teknik konservasi. Hal
ini menunjukkan bahwa konservasi yang
dilakukan petani sekarang atau saat ini
merupakan investasi jangka panjang dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, petani
yang menerapkan teknik konservasi
terhadap lahan usahataninya harus
diberikan insentif dan kepada masyarakat
yang melakukan kegiatan konservasi
diberikan imbal jasa terhadap konservasi
yang dilakukannya.
Koordinasi di antara para stakeholder,
instansi terkait dan peningkatan peran
serta masyarakat dalam penerapan KTA
diperlukan untuk pengembangan
teknologi KTA dalam sistem usaha tani
yang berkelanjutan. Peran serta
masyarakat di dalam KTA melalui berbagai
upaya pemberdayaan yang diarahkan dan
digerakkan oleh pemerintah melalui
penyuluhan dan pelatihan. Untuk
mengikutsertakan masyarakat dalam
penyelenggaraan KTA maka dilaksanakan
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
6 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
pendekatan pengelolaan DAS terpadu
berbasis masyarakat.
Pengelolaaan DAS berbasis masyarakat
dilaksanakan secara terencana dan
terpadu bersifat parsitipatif dengan
melibatkan peran serta berbagai unsur
masyarakat bersama–sama pemerintah
baik provinsi maupun kabupaten/kota
serta unsur swasta yang berpengaruh
terhadap keberhasilan pengelolaan DAS.
Para pihak terkait pengelolaan DAS yaitu
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,
LSM Pemerhati Lingkungan Hidup, sektor
swasta/pelaku usaha, Kelompok tani dan
masyarakat, akademisi, Lembaga
Masyarakat Desa dan Hutan (LMDH) dan
Forum Koordinasi pengelolaan DAS. Hal
tersebut dimaksudkan agar semua
institusi yang berkepentingan bersama-
sama dengan masyarakat untuk
melakukan pengelolaan DAS secara
terintegerasi. Oleh karena sistem
pemerintahan di Indonesia berbasis
administrasi maka perlu pijakan yuridis
berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang
pengelolaan DAS, dimana salah satu
klausul pasalnya menyebutkan kerjasama
lintas daerah dalam pengelolaan DAS
antar wilayah. Oleh karena itu, kegiatan
KTA melalui pengelolaan DAS berbasis
masyarakat yang dilaksanakan secara
terencana dan terpadu perlu dilakukan
dengan sistem partisipatif agar
masyarakat sadar terhadap pentingnya
lingkungan, terutama tanah dan air,
sehingga masyarakat tergerak untuk
melaksanakan konservasi di lingkungan
sekitarnya melalui kerjasama antar
pemilik kepentingan, yakni masyarakat,
swasta dan pemerintah.
B. Imbal Jasa Lingkungan Sebagai
Kewajiban Kompensasi Pemerima
Kemanfaatan Hasil Konservasi Tanah
Dan Air
1. Pijakan yuridis pengaturan imbal jasa
lingkungan
a) Undang-undang Nomor 37 Tahun
2014 Tentang Konservasi Tanah dan
Air
Penyelenggaraan KTA diatur dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014
Tentang Konservasi Tanah dan Air
(UUKTA). Konservasi tanah dan air
dilaksanakan berdasarkan asas:
partisipatif, keterpaduan, keseimbangan,
keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal,,
dan kelestarian.
Pasal 3 UUKTA, disebutkan bahwa
tujuan penyelenggaraan konservasi tanah
dan air adalah melindungi permukaan
tanah dari pukulan air hujan yang jatuh,
meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah,
dan mencegah terjadinya konsentrasi
aliran permukaan; menjamin dan
mengoptimalkan fungsi tanah pada lahan
agar mendukung kehidupan masyarakat
untuk mewujudkan manfaat ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup secara
seimbang dan lestari; meningkatkan daya
dukung DAS; meningkatkan kemampuan
untuk mengembangkan kapasitas dan
memberdayakan keikutsertaan masya-
rakat secara partisipatif; dan menjamin
kemanfaatan KTA secara adil dan merata
untuk kepentingan masyarakat.
Pasal 5 dan 6 UUKTA memberi
kewenangan kepada Pemerintah untuk
mengatur dan menyelenggarakan KTA
atau dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada perangkat
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 7
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
Pemerintah atau wakil Pemerintah di
daerah atau dapat menugaskannya
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya di dalam Pasal 7,
disebutkan bahwa yang bertanggung-
jawab terhadap penyelenggaraan KTA
adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah,
pemegang hak atas tanah, pemegang
kuasa atas tanah, pemegang izin,
dan/atau pengguna lahan yang wajib
mengikuti prinsip konservasi dan
menghormati hak yang dimiliki setiap
orang. Pelaksanaan penyelenggaraan KTA
dilaksanakan berdasarkan unit DAS,
ekosistem, dan satuan lahan yang
dilakukan dengan menggunakan
pendekatan pengelolaan DAS secara
terpadu dan berbasis masyarakat.
Dalam hal pendanaan sebagaimana
diatur pada Pasal 31 UUKTA, Pendanaan
penyelenggaraan KTA menjadi tanggung
jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah, pemegang hak atas tanah,
pemegang kuasa atas tanah, pemegang
izin, dan/atau pengguna lahan, baik
sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
Sumber pendanaan dapat berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), badan hukum, badan usaha,
perseorangan, dan/atau sumber lain yang
sah dan tidak mengikat berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Sumber
lain yang sah dan tidak mengikat,
termasuk yang berasal dari pembayaran
IJL terhadap penyelenggaraan konservasi
tanah dan Air. Pengelolaan sumber
pendanaan, harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel.
Pembayaran IJL dalam penyeleng-
garaan KTA dikenakan kepada Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dan
penerima manfaat atas sumber daya
Tanah dan Air sebagaimana diatur dalam
Pasal 32 UUKTA. Selanjutnya dalam Pasal
33 UUKTA, kewajiban/tanggung jawab
membayar pemanfaat jasa lingkungan
yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah untuk penyelenggaraan KTA
terkait kewajiban pelayanan publik yang
menyangkut hajat hidup orang banyak
dan penerima manfaat atas sumber daya
tanah dan air bertanggung jawab
membayar untuk kepentingan penyeleng-
garaan KTA.
Berdasarkan hal tersebut penyeleng-
garaan KTA dalam pengelolaan DAS
menjadi tanggungjawab semua pihak yang
berkepentingan dan yang mendapat
manfaat dari kelestarian lingkungan DAS,
maka pemerintah kabupaten/kota dan
masyarakat yang mendapat manfaat atau
memanfaatkan tanah dan air
berkewajiban untuk turut serta dalam
upaya KTA melalui pembayaran IJL kepada
pemerintah atau masyarakat penghasil
jasa lingkungan. Peran aktif masyarakat
dalam pengelolaan DAS dapat berupa
pengelolaan jasa lingkungan dan
partisipasi aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan KTA.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup di dalam Pasal 4,
menyebutkan bahwa IJL merupakan salah
satu instrumen perencanaan
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
8 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
pembangunan dan kegiatan ekonomi
yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
dan daerah. Perencanaan dan
penyelenggaraan pembangunan dan
kegiatan ekonomi antara lain pengelolaan
Sumber Daya Alam (SDA), penataan
ruang, konservasi SDA dan pelestarian
fungsi lingkungan hidup.
Pasal 10, kompensasi/IJL antar daerah
diberikan oleh Pemanfaat Jasa Lingkungan
Hidup atas manfaat dan/atau akses
terhadap Jasa Lingkungan Hidup yang
dikelola dan/atau dipulihkan oleh
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup. Salah
satu jasa lingkungan hidup yang diberikan
imbal jasa adalah perlindungan tata air.
Selanjutnya di Pasal 11, bentuk
kompensasi/IJL antar daerah meliputi
uang; atau sesuatu lainnya yang dapat
dinilai dengan uang yang nilainya
ditentukan dengan mempertimbangkan
biaya ekonomi upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup; biaya pemberdayaan
masyarakat; dan biaya pelaksanaan
kerjasama.
Pasal 14, kompensasi/IJL antar daerah
antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah serta antar
Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui
mekanisme: hibah daerah dari Pemerintah
Pusat selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan
Hidup kepada Pemerintah Daerah selaku
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup atau
sebaliknya; atau hibah daerah atau
belanja bantuan keuangan urusan
lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah
selaku Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup
kepada Pemerintah Daerah selaku
Penyedia Jasa Lingkungan Hidup
dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
Perjanjian kerjasama paling sedikit
memuat: para pihak; tujuan; jumlah;
sumber pendanaan; persyaratan; tata cara
penyaluran; tata cara pelaporan dan
pemantauan; dan hak dan kewajiban
pemberi dan penerima sebagaimana
diatur dalam Pasal 15. Selanjutnya pada
Pasal 16, disebutkan bahwa dalam
melaksanakan kerjasama kompensasi/ IJL
antar daerah antara Penyedia Jasa
Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa
Lingkungan Hidup dapat membentuk
wadah atau forum kerjasama
Kompensasi/lmbal Jasa Lingkungan Hidup
Antar Daerah; dan/atau meminta
bantuan fasilitator. Sebagai fasilitator
yaitu Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah Provinsi sesuai kewenangannya;
dan/atau fasilitator yang berasal dari
orang perseorangan, organisasi
lingkungan hidup, perguruan tinggi, atau
organisasi lain yang disepakati.
Pasal 47, diatur mengenai pembayaran
jasa lingkungan hidup yaitu berupa
fasilitasi mekanisme pengalihan sejumlah
uang dari Pemanfaat Jasa Lingkungan
Hidup kepada Penyedia Jasa Lingkungan
Hidup dalam perjanjian terikat berbasis
kinerja guna mendorong masyarakat
untuk melaksanakan upaya Konservasi
Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup dan mendukung kinerja
pelaksanaan Kompensasi/lmbal Jasa
Lingkungan Hidup Antar Daerah.
2. Pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan di
beberapa daerah
Pemanfaatan sumber daya alam yang
melampaui batas akan mempengaruhi
ketersediaan jasa lingkungan di masa yang
akan datang. Pemanfaatan kawasan
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 9
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
hutan, sumber daya air dan sumber daya
alami lainnya memungkinkan adanya IJL
untuk diterapkan sehingga berkelanjutan.
IJL diartikan sebagai sistem pemberian
imbalan kepada penghasil jasa lingkungan
untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas jasa lingkungan. Instrumen IJL
sebagai instrumen pengelolaan
lingkungan yang strategis dalam
perlindungan sumberdaya alam dan
lingkungan yang sekaligus akan
memberdayakan dan memperbaiki
kehidupan sosial ekonomi masyarakat
sekitarnya (Sudarma, 2014). Dalam
pelaksanaan sistem pembayaran jasa
lingkungan perlu diidentifikasi agen
ekonomi yang bertanggungjawab sebagai
penyedia jasa dan agen lain sebagai
penerima manfaat dengan membangun
hubungan sebab-akibat yang diperlukan
yaitu hubungan antara wilayah hulu
(upstream) kepada keadaan sumberdaya
air di wilayah hilir (down-stream) dalam
DAS yang bersangkutan (Dasrizal,
Ansofino, Juita, & Jolianis, 2012).
Pada dasarnya tujuan dari IJL adalah
untuk merestorasi dan melindungi
ketersediaan barang dan jasa lingkungan
yang berkelanjutan. Misalnya,
pembayaran jasa lingkungan di
Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera
Barat sebagai perlindungan ekosistem
mangrove yang memberikan manfaat
sebagai sumber air, tambak, wisata,
maupun sebagai perlindungan daerah
pesisir (Idrus, Ismail, & Ekayani, 2016).
Peraturan perundangan yang mengatur
mengenai IJL sudah ada yaitu Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Instrumen Ekonomi Ligkungan
Hidup. Konsep IJL sudah dilakukan di
beberapa wilayah di Indonesia. Namun,
dalam pelaksanaan IJL, masing-masing
daerah memiliki mekanismenya sendiri
didasarkan pada kebutuhan serta kearifan
lokalnya.
Di Kabupaten Lombok Barat sudah
membentuk suatu wadah organisasi
pengelolaan jasa lingkungan sumberdaya
air untuk melestarikan kawasan
konservasi melalui kesediaan untuk
membiayai kegiatan konservasi dan
perbaikan ekonomi bagi kelompok
masyarakat miskin di daerah hulu melalui
penarikan uang pembayaran jasa
lingkungan sebesar antara Rp 500,- - Rp
5.000,- bagi pelanggan Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM), dari dana
yang terkumpul sebesar 75% akan
digunakan untuk upaya konservasi dan
pengentasan kemiskinan, dan 25% akan
disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah
(Sudiyono, 2012). Sebagai dasar
hukumnya adalah Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Jasa Lingkungan, Peraturan Bupati
Lombok Barat Nomer 7 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Tugas dan Wewenang Institusi Multi Pihak
(IMP) sebagai petunjuk pelaksanaannya.
Serta Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomer 1072/207/Dishut/2009 tentang Pembentukan Institusi Multi Pihak
Pengelolaan Jasa Lingkungan Kabupaten
Lombok Barat, serta Peraturan Bupati
Lombok Barat Nomer 42 tahun 2008
Tentang Obyek, Tarif, Tata Cara
Pembayaran dan Sanksi Administratif.
Program IJL di Krueng Montala Aceh
dalam pelaksanaannya terdapat beberapa
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
10 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
hal yang perlu dievaluasi, pertama
perangkat hukum di tingkat nasional dan
lokal karena belum adanya mekanisme
standar yang disepakati. Kedua,
mekanisme dan standar pembayaran PES
di Krueng Montala masih pada tahap
awal, sehingga masyarakat belum
mendapatkan manfaat ekonomi secara
langsung (Wardah & Farsia, 2013). Contoh
lain adalah kesepakatan program IJL di
Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat antara
Kelompok Tani Giri Putri Desa Cikole
dengan Pustanling, serta Kelompok Tani
Syurga Air Desa Suntenjaya sebagai
penyedia jasa dengan PT. Aetra Air Jakarta
sebagai pemanfaat jasa dan Badan
Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
(BPLHD) Kabupaten Bandung berperan
sebagai mediator dalam kesepakatan ini.
Pada pelaksanaannya, mekanisme IJL di
Sub-DAS Cikapundung dikategorikan
sebagai mekanisme IJL yang belum
sepenuhnya mencerminkan mekanisme
IJL yang berkelanjutan, karena masalah
kelembagaan dalam pengelolaan dan
monitoring perkembangannya di
lapangan. Selain itu dana yang diberikan
kepada kelompok tani juga masih
tergolong belum mencukupi untuk
aktivitas konservasi lahan (Napitupulu,
Asdak, & Budiono, 2013). Penerapan
pembayaran jasa lingkungan juga
dilakukan di Kecamatan Jailolo Kabupaten
Halmahera Barat. Pembayaran jasa
dilakukan terhadap dua jenis jasa yang
menjadi potensi untuk diinisiasi
pembayaran jasa lingkungan yaitu jasa
pengatur dari intrusi air laut dan jasa
budaya dari wisata mangrove. Penerapan
pembayaran jasa sangat ditentukan dari
bagaimana mengidentifikasi jasa
potensial, yaitu dengan menentukan nilai
ekonomi, pemanfaat, dan penyedia jasa
lingkungan mangrove serta mekanisme
pembayaran (Idrus et al., 2016).
Berdasarkan beberapa permasalahan
yang terjadi dalam implementasi IJL, maka
partisipasi berbagai pihak perlu dilakukan
secara terpadu dan terintegerasi,
diperlukan peningkatan kapasitas
kelembagaan, dan yang paling penting
adalah pemerintah harus memberikan
payung hukum baik ditingkat nasional
maupun daerah sebagai dasar pijakan bagi
pelaksanaan IJL agar berkelanjutan.
C. Norma Hukum/ Peraturan
Pelaksanaan yang Diharapkan.
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah
dan Air mengamanatkan pengaturan lebih
lanjut mengenai IJL dan pendanaan
penyelenggaraan KTA dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan perlu diatur
lebih lanjut secara teknis dalam bentuk
peraturan menteri. Sampai saat ini
Peraturan Pemerintah yang dimaksud
belum terwujud sebagaimana amanat
UUKTA
Pengaturan mengenai imbal jasa
lingkungan telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan
Hidup sebagai pelaksanaan ketentuan
Pasal 43 Ayat (4) dan Pasal 55 Ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Sebagaimana
disebutkan pada Pasal 47, bahwa IJL hidup
merupakan salah satu instrumen ekonomi
lingkungan hidup sebagai insentif dengan
pengembangan sistem pembayaran jasa
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 11
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
lingkungan hidup. Selanjutnya pada Pasal
48 Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2017 mengamanatkan pengaturan
lebih lanjut mengenai pengembangan
sistem Pembayaran Jasa Lingkungan
Hidup dalam bentuk Peraturan Menteri
dalam hal ini Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan berkewajiban untuk
menterjemahkan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017
tersebut untuk dibuat sebuah petunjuk
pelaksanaan tentang pengaturan
mekanisme atau penghitungan IJL yang
sampai saat ini belum ada. Hal tersebut
karena Kementerian Lingkungan Hidup
sedang disibukkan dengan pembuatan
berbagai peraturan teknis sebagai amanat
dari peraturan pemerintah tentang
Perizinan Berusaha Terintegerasi Secara
Elektronik atau Online Single Submission
(OSS). Akibatnya persoalan pemberian IJL
ini belum bisa dilaksanakan dengan baik
dan benar oleh masyarakat dan
pemerintah wilayah hilir.
Peraturan Menteri lingkungan hidup
dan kehutanan mengenai pengembangan
sistem Pembayaran Jasa Lingkungan
Hidup, sebagai pelaksanaan dari amanat
yang ada pada Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup, belum ada.
Apabila kepentingan daerah mendesak
terkait dengan pembayaran IJL hidup,
maka daerah bisa membuat peraturan
daerah yang mengatur mengenai para
pihak, tujuan, jumlah, sumber pendanaan,
persyaratan, tata cara penyaluran, tata
cara pelaporan dan pemantauan, serta
hak dan kewajiban pemberi dan penerima
IJL. Peraturan Daerah tersebut dibuat
sesuai dengan kebutuhan pengaturan IJL
yang spesifik untuk masing-masing
daerah.
D. Model Mekanisme Pembayaran Imbal
Jasa Lingkungan Konservasi Tanah Dan
Air
Kerjasama antara hulu dan hilir juga
menjadi salah satu indikator keterpaduan
dalam pengorganisasian pengelolaan DAS.
Selama ini kerjasama pembayaran jasa
lingkungan belum dapat berjalan karena
partisipasi para pihak masih rendah dan
belum berjalan secara kontinyu dan
terkoordinasi. Skema kerjasama melalui
pembayaran jasa lingkungan adalah
dengan membangun kerjasama para pihak
yang mendapatkan manfaat yaitu
masyarakat bagian tengah dan hilir
berkontribusi dalam perbaikan kerusakan
DAS bagian hulu sehingga ketersediaan air
dapat terjaga (Fatahilah, 2013). Untuk
menginisiasi dan menjembatani
kerjasama antara pihak yang
membutuhkan jasa lingkungan yang
berada di hilir DAS dengan pengelola
lingkungan yang berada di ekosistem DAS
hulu dan tengah, diperlukan pihak ketiga
baik dari pihak pemerintah maupun pihak
lain, sehingga kerjasama yang disepakati
dapat saling menguntungkan kedua belah
pihak, mampu beroperasi dan berjalan
berkelanjutan (Komarawidjaja, 2017).
Pengelolaaan DAS berbasis masyarakat
dilaksanakan secara terencana dan
terpadu dengan melibatkan peran serta
berbagai unsur masyarakat bersama–
sama Pemerintah Kabupaten/Kota serta
unsur swasta yang didukung oleh Forum
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
12 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Koordinasi Pengelolaan DAS
Kabupaten/Kota melalui kerjasama lintas
daerah dengan mengembangkan sistem
kompensasi/IJL (Sudarwanto, 2018).
Wadah kerjasama kompensasi/IJL
dalam kegiatan KTA melalui pengelolaan
DAS dikoordinasi oleh Forum Koordinasi
Pengelolaan DAS. Forum ini memiliki
tujuan untuk memberikan arahan yang
efektif sebagai bagian dari pengembangan
kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari
hulu ke hilir secara utuh sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.61/Menhut-II/2013 Tentang Forum
Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai. Pasal 10 Peraturan Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.61/Menhut-II/2013 menyebutkan
bahwa salah satu fungsi Forum Koordinasi
Pengelolaan DAS adalah melaksanakan
koordinasi dan konsultasi untuk
menyelaraskan kepentingan antar sektor,
antar wilayah dan antar pemangku
kepentingan dalam Pengelolaan DAS
Terpadu baik Tingkat Provinsi maupun
Tingkat Kabupaten/Kota. Selain diatur
dalam Peraturan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor P.61/Menhut-
II/2013 Tentang Forum Koordinasi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, fungsi
forum sebagai koordinator ditegaskan
pula dalam Surat Edaran Kementerian
Dalam Negeri tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis
Masyarakat Nomor 413.2/8162/PMD.
IJL kegiatan KTA dari masyarakat hilir
sebagai penerima manfaat kepada
masyarakat hulu sebagai penyedia jasa
dilakukan melalui pengelolaan DAS
Terpadu berbasis masyarakat dan
berkelanjutan, sebagai koordinator yaitu
Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
Bersama pemerintah provinsi dan/atau
pemerintah kabupaten/kota, Forum
Koordinasi Pengelolaan DAS membentuk
tim Ad Hoc yang memiliki tugas mengelola
dana Jasa Lingkungan. Mekanisme sistem
pembayaran jasa lingkungan dapat dilihat
dalam skema berikut ini:
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 13
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
Gambar (Figure) 1. Mekanisme tarif jasa konservasi air dan lingkungan (Mechanism of the service fee
of water and environment conservation)
Sumber (Source) : Analisis data (Data analysis), 2019
Konsep pembayaran dana IJL dilakukan
oleh masyarakat hilir sebagai penerima
manfaat kepada masyarakat hulu sebagai
penyedia jasa. Sistem pembayaran jasa
lingkungan dilakukan melalui lembaga
pengelola jasa lingkungan (Tim Ad Hoc)
yang dikoordinasikan oleh Forum
koordinasi Pengelolaan DAS, kemudian
diberikan kepada masyarakat hulu
(penyedia jasa) untuk dimanfaatkan dalam
kegiatan konservasi di wilayah hulu.
Adapun realisasi pembayaran jasa
lingkungan didasarkan pada peraturan
perundang-undangan, dalam bentuk
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang pengembangan sistem
Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup
sebagai amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup.
IV. KESIMPULAN
Pijakan yuridis mengenai IJL kegiatan
KTA sudah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi
Tanah dan Air serta Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen
Ekonomi Lingkungan Hidup, namun belum
ada pengaturan mekanisme
standar/teknis dalam pelaksanaan
penghitungan dan pembayaran IJL. Oleh
karena itu pembayaran jasa lingkungan
dilakukan melalui lembaga pengelola jasa
lingkungan (Tim Ad Hoc) yang
dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi
Pengelolaan DAS bersama pemerintah
provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
14 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
kota. Pembayaran IJL dari masyarakat hilir
sebagai penerima manfaat kepada
masyarakat hulu sebagai penyedia jasa
perlu diatur dalam suatu Peraturan
Daerah (Perda) tentang pengelolaan DAS,
dimana salah satu klausul pasalnya
menyebutkan kerjasama lintas daerah
dalam pengelolaan DAS antar wilayah.
Sebagai saran, Pemerintah perlu segera
mewujudkan Peraturan Pemerintah
sebagai aturan pelaksanaan IJL dan
pendanaan penyelenggaraan KTA dan
perlu diatur lebih lanjut secara teknis
dalam bentuk peraturan menteri.
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu segera menindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Sistem Pembayaran Jasa
Lingkungan Hidup sebagai pengaturan
dalam pelaksanaan mekanisme IJL
kegiatan KTA, dari penerima manfaat KTA,
kepada masyarakat yang melakukan jasa
KTA. Selain itu, Forum Koordinasi
Pengelolaan DAS dengan tugas dan fungsi
memberikan masukan dalam pengelolaan
DAS bersama pemerintah perlu segera
mewujudkan tim Ad Hoc pengelola dana
jasa lingkungan dalam upaya pengelolaan
dan pemanfaatan DAS berkelanjutan.
UCAPAN TERIMAKASIH :
Penulis sampaikan ucapan terimakasih
kepada Pengurus Pusat Masyarakat
Konservasi Tanah dan Air Indonesia
(MKTI) serta Ketua Panitia Penyelenggara
Seminar Nasional ke IX dan Kongres
Nasional X MKTI 2019.
DAFTAR PUSTAKA
Arafat, F., Wulandari, C., & Qurniati, R. (2015). Kesediaan menerima pembayaran jasa lingkungan air sub das way betung hulu oleh masyarakat kawasan hutan register 19 (studi kasus di Desa Talang Mulya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). Jurnal Sylva Lestari, 3(1), 21-30.
Dasrizal, Ansofino, Juita, E., & Jolianis. (2012). Model Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan dalam Kaitannya dengan Konservasi Sumberdaya Air dan Lahan: Studi Kasus pada Batang Anai Sumatera Barat. Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat, 1(1), 14-31.
Fatahilah, M. (2013). Kajian Keterpaduan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Garang Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian, 10(2), 136-153.
Heryani, N., & Sutrisno, N. (2013). Teknologi Konservasi Tanah dan Air untuk Mencegah Degradasi Lahan Pertanian Berlereng. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 32(3), 122-130.
Idrus, S., Ismail, A., & Ekayani, M. (2016). Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan Mangrove di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 21(3), 195-202.
©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 15
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No. 1, April 2020 : 1-16
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097
Katharina, R. (2007). Adopsi Konservasi Sebagai Bentuk Investasi Usaha Jangka Panjang (Studi Kasus Usahatani Kentang Lahan Kering Dataran Tinggi Pangalengan). Jurnal Manajemen & Agribisnis, 4(1), 32-45.
Komarawidjaja, W. (2017). Prospek Pemanfaatan Penyaring Sampah Sungai dalam Implementasi Imbal Jasa Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Ciliwung Segmen 2 Kota Bogor. Jurnal Teknologi Lingkungan, 18(1), 37-44.
Napitupulu, D. F., Asdak, C., & Budiono, B. (2013). Mekanisme Imbal Jasa Lingkungan di Sub-DAS Cikapundung (Studi Kasus pada Desa Cikole dan Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Ilmu Lingkungan, 11(2), 73-83.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.61 Tahun 2013. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS. 1 November 2013. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. 10 November 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228. Jakarta.
Riska, Y., Bambang, A. N., & Budiyono. (2013). Identifikasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di KSA/KPA Merapi Propinsi Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Semarang.
Samedi, S. (2015). Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2), 1-28.
Sudarma, I. M. (2014). Pembayaran Jasa Lingkungan Sebagai Instrumen Ekonomi Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Integrasi Keanekaragaman Hayati Dan Kebudayaan Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, Bali.
Sudarwanto, A. S. (2018). Pijakan Yuridis dan Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Berbasis Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Menuju Kelestarian Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat”, Surakarta.
Sudiyono, S. (2012). Pengelolaan Sumberdaya Air di Kabupaten Lombok Barat: Sebuah Potret Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau (Water Resources Management In West Lombok District: A Portrait Of Green Economy Policy Implementation). Jurnal Masyarakat dan Budaya, 14(3), 571-598.
Sutopo, M. F., Sanim, B., Saukat, Y., & Mawardi, M. I. (2011). Analisis kesediaan membayar jasa lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya air minum terpadu di indonesia (studi kasus DAS cisadane hulu). Jurnal Teknologi Lingkungan, 12(1), 17-23.
Implikasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017...................................................( AL. Sentot Sudarwanto)
16 ©2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014. Konservasi Tanah dan Air. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299. Jakarta.
Wahyudi, W. (2014). Teknik Konservasi Tanah serta Implementasinya pada Lahan Terdegradasi dalam Kawasan Hutan. Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, 6(2), 71-85.
Wardah, W., & Farsia, L. (2013). Penerapan Imbal Jasa Lingkungan dalam Pelestarian Daerah Aliran Sungai di Aceh. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 115-129.
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.17-36
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 17
MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN
(Developing a participatory planning process of micro-watershed management:
a lesson learned)
Agung Budi Supangat1, Dewi Retna Indrawati1, Nining Wahyuningrum1, Purwanto1, dan Syahrul Donie
1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Jl. A. Yani – Pabelan, PO BOX 295, Surakarta
Alamat email: [email protected]
Diterima: 08 Januari 2020; Direvisi: 04 Maret 2020; Disetujui: 23 Maret 2020
ABSTRACT
Planning is one of the very important stages in the micro watershed management. Difficulties and failures in the management of micro watershed are often caused by failures in the building of participatory planning processes with the community as well as a collaborative mechanism with relevant parties. This action research aims to find the applicable processes or stages of participatory planning based on the experience and evaluation of existing processes. The research was carried out in the Naruan micro watershed, Keduang sub-watershed, Bengawan Solo upper watershed. Some lessons learned that can be found from this research are as follows: 1) detailed baseline data related to the potential and vulnerability characteristics of micro watershed is very important to be understood before planning process; 2) micro watershed planning process cannot fully rely on community participation, but it should be a combination of top-down and participatory mechanism; 3) top-down planning is related to the provision of proper land management guidelines in the upstream area; 4) participatory planning is carried out when preparing of land use plans, determining the appropriate types of soil and water conservation activities, as well as identifying the resources contribution from the community as a form of participation; 5) collaborative action plans are needed to be built with relevant parties to support integrative and sustainable micro watershed management.
Keywords: Collaboration; micro watershed; participation; planning
ABSTRAK
Tahapan perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala operasional (DAS mikro). Kesulitan dan kegagalan pengelolaan DAS mikro seringkali bermula dari kegagalan dalam membangun proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan kolaboratif dengan para pihak terkait. Kegiatan penelitian tindakan (action research) ini bertujuan untuk menemukan proses/tahapan perencanaan partisipatif yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman dan evaluasi proses yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan di DAS Mikro Naruan, Sub DAS
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
18 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Keduang, DAS Bengawan Solo Hulu. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Basis data dasar (baseline data) detil terkait karakteristik potensi dan kerentanan wilayah DAS mikro sangat penting diketahui sebelum proses perencanaan; 2) Proses perencanaan pengelolaan DAS mikro tidak dapat sepenuhnya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi perlu kombinasi antara sistem top down dan partisipatif; 3) Perencanaan yang sifatnya top down menyangkut pemberian rambu-rambu pengelolaan lahan yang benar di wilayah hulu DAS; 4) Perencanaan partisipatif dilakukan pada saat penyusunan rencana penggunaan/ pemanfaatan lahan, jenis kegiatan konservasi yang sesuai serta andil sumber daya dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi; 5) Rencana kolaboratif perlu dibangun dengan para pihak terkait dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan DAS mikro.
Kata kunci: Kolaborasi; DAS mikro; partisipasi; perencanaan
I. PENDAHULUAN
Masih maraknya berbagai bencana
alam khususnya bencana hidrometeo-
rologi, menjadi indikasi bahwa
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di
Indonesia masih perlu pembenahan.
Dalam infografis tren bencana di
Indonesia periode tahun 2003 sampai
2017, kecenderungan jumlah kejadian
bencana alam menunjukkan grafik yang
meningkat. Di antara bencana alam
tersebut, dominasi bencana
hidrometeorologi tetap yang terbesar,
seperti banjir, tanah longsor dan angin
puting beliung (Adi, 2013; Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, 2017;
Jayawardena, 2015; Purwanto &
Supangat, 2017). Selain banjir dan tanah
longsor, bencana hidrometeorologi yang
lain terkait pengelolaan DAS adalah
kekeringan dan sedimentasi. Fenomena
sedimentasi, meskipun banyak yang
belum mengkategorikan sebagai sebuah
bencana alam, tetapi bahaya yang
ditimbulkan sangat signifikan, seperti
terganggunya pasokan listrik akibat
terganggunya turbin penggerak PLTA di
bendungan karena menumpuknya
sedimen. Permasalahan sedimentasi
sering menjadi isu utama pengelolaan DAS
(Alemu, 2016; Junaidi, 2013; Nourani &
Kalantari, 2010; Rodríguez-Blanco,
Taboada-Castro, & Taboada-Castro, 2013;
Shi et al., 2013; Vigiak et al., 2016),
terutama di kawasan hulu sebagai daerah
penyumbang/asal sedimen, yaitu dari
proses erosi tanah di lahan-lahan
budidaya dan pemukiman.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
(Perdirjen RLPS) No. P.15/V-SET/2009
dinyatakan bahwa DAS mikro merupakan
bagian wilayah dalam DAS yang berada di
hulu sungai, yang dalam klasifikasi
(Strahler, 1983) meliputi orde 1 sampai 3.
Dalam suatu DAS, wilayah hulu memiliki
fungsi strategis, yaitu sebagai daerah
resapan, area konservasi dan penyangga
bagi daerah di bawahnya (tengah dan
hilir) (Asdak, 2014), dan daerah yang
paling rentan mengalami degradasi
(Achouri, 2005). Lokasi DAS mikro yang
berada di hulu DAS sering menjadi ujung
tombak pengelolaan sumber daya alam
dalam DAS, dan sangat strategis menjadi
penentu penyelesaian masalah DAS
melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan
yang menyasar pada sumber-sumber
masalah, seperti erosi dan kemiskinan.
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 19
Hasil dari pengelolaan DAS mikro dapat
menjadi bahan pengambilan kebijakan
sampai ke tingkat nasional (Anwar, 2005).
Kegagalan dalam mengidentifikasi akar
masalah di hulu DAS, serta lemahnya
proses perencanaan partisipatif dapat
berujung pada kegagalan penyelesaian
masalah (Dodds, 2019; Wolfgramm,
2015), seperti pengendalian erosi-
sedimentasi dan rendahnya produktivitas
lahan. Proses partisipatif menjadi elemen
yang sangat penting dalam pengelolaan
sumber daya air dan DAS (Stålnacke et al.,
2014; Warren, 1998).
Menurut Peraturan Pemerintah (PP)
No. 37 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan
DAS meliputi unsur-unsur mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi (monev) serta pembinaan
dan pengawasan. Perencanaan menjadi
salah satu kunci dari keberhasilan
kegiatan pengelolaan DAS. Dengan
perencanaan yang baik, maka kegiatan
implementasi akan mudah dilaksanakan.
Namun demikian, perencanaan sering
menjadi kelemahan utama dalam kegiatan
pengelolaan DAS karena kurangnya
inovasi (Mika, Dymond, Aguilar, & Hodges,
2019). Demikian juga, kondisi
perencanaan pengelolaan DAS di
Indonesia masih perlu dievaluasi. Prinsip
partisipatif masih lemah dan belum sesuai
dengan prinsip pemberdayaan secara
benar (Indrawati, Awang, Faida, &
Maryudi, 2016), sehingga berdampak
pada rencana yang kurang sesuai
kebutuhan sehingga tidak menyelesaikan
akar masalah pengelolaan DAS.
Dalam kegiatan pengembangan ini
dipelajari kelemahan proses perencanaan
pengelolaan DAS di tingkat operasional
yang ada, serta dilakukan evaluasi untuk
mencarikan solusi perbaikannnya. Tujuan
kegiatan adalah untuk menemukan
proses/tahapan perencanaan partisipatif
yang lebih aplikatif berdasarkan
pengalaman dan evaluasi proses yang
sudah ada. Diharapkan hasil kegiatan ini
dapat menjadi masukan kebijakan untuk
memperbaiki sistem perencaaan yang
ada.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Kegiatan dilaksanakan pada tahun
2015-2016. Lokasi penelitian berada di
DAS Mikro Naruan, yang merupakan
wilayah hulu Sub DAS Keduang, DAS Solo
bagian hulu. Secara geografis, lokasi
berada antara 7°74’30” – 7°70’40” LS dan
111°10’50 - 111°10’60” BT, sedangkan
secara administrasi, DAS Mikro Naruan
terletak pada Wilayah Kabupaten
Wonogiri (Desa Bubakan, Kecamatan
Girimarto, dan Kabupaten Karanganyar
(Desa Wonokeling dan Wonorejo,
Kecamatan Jatiyoso) (Gambar 1).
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
20 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Gambar (Figure) 1. Lokasi kegiatan DAS Mikro Naruan (Research site in Naruan Micro Catchment)
Sumber (Source): Modifikasi dari (Modified from) Wahyuningrum & Supangat (2016a)
C. Metode Penelitian
Kegiatan perencanaan pengelolaan
DAS mikro secara umum dimulai dari
orientasi dan pemilihan lokasi DAS mikro
yang akan dikelola, kemudian dilanjutkan
pada kegiatan penyusunan rencana secara
partisipatif. Dalam tulisan ini, lokasi DAS
mikro sudah ditentukan dari hasil kajian
sebelumnya (Supangat et al., 2015), yaitu
DAS Mikro Naruan, yang diperoleh melalui
serangkaian analisis pemilihan lokasi
dengan kriteria didasarkan pada pedoman
pembangunan area DAS mikro sesuai
Perdirjen RLPS No. P.15/V-SET/2009.
Salah satu yang telah dihasilkan dalam
kajian Supangat et al. (2015) adalah
karakteristik DAS Mikro Naruan, yang
merupakan basis data dasar terpenting
sebelum dilakukan proses perencanaan
partisipatif. Karakterisasi DAS dilakukan
dengan menggunakan alat analisis “Sidik
Cepat Degradasi Sub DAS” (Paimin,
Purwanto, & Sukresno, 2010), untuk
kemudian dapat dirumuskan potensi dan
kerentanan masing-masing aspek dalam
pengelolaan DAS, yaitu lahan, tata air dan
sosek-kelembagaan.
Secara ringkas telah disimpulkan
berdasarkan Wahyuningrum & Supangat
(2016a) bahwa kondisi DAS Mikro Naruan
yang berada di hulu DAS memerlukan
pengelolaan secara tepat. Terdapat lebih
dari 50% lahan memerlukan perbaikan
tutupan lahan, yang terdiri dari 38% dan
23% (kebun campur). Sebesar 56,24% dari
penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan klas kemampuan lahannya, di
mana 33,14% di antaranya mengalami
erosi pada taraf sangat berat (>480
ton/ha). Sebagai akibat penggunaan lahan
yang tidak sesuai tersebut, di beberapa
area telah terjadi erosi tahap lanjut
berupa jurang, terutama di batas-batas
pemilikan lahan. Selanjutnya, Nining
Wahyuningrum & Supangat (2016b),
menambahkan meskipun wilayah DAS
Mikro Naruan tidak terlalu rentan longsor
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 21
(kategori agak rentan sebanyak 64,2% dan
sisanya 35,8% sedikit rentan), namun
terdapat titik-titik yang telah terjadi
longsoran baik di lahan sawah maupun
tegal yang perlu direkonstruksi.
Kondisi tata air permukaan (aliran
sungai) secara umum menunjukkan
kuantitas yang cukup berlimpah
sepanjang tahun untuk memenuhi air
baku pertanian dan pemukiman. Namun
secara kualitas di musim hujan
menunjukkan kandungan sedimen yang
cukup besar (keruh) yang melebihi
ambang batas yang diperkenankan.
Adapun karakteristik sosek-kelembagaan
menunjukkan aspek kelembagaan yang
agak buruk disebabkan oleh tidak
berperannya lembaga informal dalam
kegiatan KTA. Lembaga informal yang
khusus bergerak dalam kegiatan
konservasi tanah dan air belum ada
(Supangat et al., 2015).
Karakter DAS Mikro Naruan seperti di
atas tidak terlepas dengan pola
pengelolaan yang dilakukan masyarakat
yang memberikan dampak negatif
terhadap tingkat erosi dan sedimentasi.
Lahan yang tidak sesuai kelas
kemampuannya sebagian besar adalah
tegalan, dan sebagian besar adalah lahan
milik masyarakat. Oleh karena itu, perlu
dilakukan kompromi pemanfaatan lahan
untuk mengurangi dampak negatif berupa
erosi yang tinggi, dengan pengembangan
pola hutan rakyat (agroforestri) untuk
memperbaiki tutupan lahan sekaligus
menurunkan tingkat erosi tanah. Hal ini
menjadi salah satu modal dalam proses
perencanaan partisipatif yang dilakukan.
Tulisan ini fokus mengulas proses
tahapan perencanaan partisipatif.
Berbekal basis data dasar yang telah
dikumpulkan, kemudian dilanjutkan
dengan rangkaian diskusi (FGD) baik
dengan masyarakat maupun dengan para
pihak terkait. Secara lengkap tahapan
kegiatan disajikan pada diagram alir pada
Gambar 2.
Berdasarkan data dasar karakteristik
DAS mikro, kemudian dilakukan
perumusan isu dan masalah utama
sebagai dasar penentuan tujuan
pengelolaan DAS mikro ke depan. Isu dan
masalah utama tersebut juga
dikonfirmasikan dengan rencana makro
yang ada, baik rencana pengelolaan DAS
maupun rencana tata ruang, dilengkapi
dengan informasi dari lapangan
(masyarakat). Kegiatan selanjutnya
meliputi pertemuan-pertemuan kelompok
dalam rangka proses diskusi perencanaan
partisipatif. Pertemuan dalam bentuk FGD
dilakukan baik dengan masyarakat petani
untuk menyusun rencana pengelolaan
lahan, maupun dengan para pihak terkait
dalam rangka sosialisasi rencana dan
mendiskusikan peran para pihak. Para
pihak terkait tersebut meliputi perwakilan
institusi pusat (Balai Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Hutan
Lindung/BPDASHL, Balai Besar Wilayah
Sungai/BBWS, Perum Jasa Tirta, serta
Perum Perhutani), perwakilan pemerintah
daerah propinsi (Balai Pusdataru dan
Dinas Kehutanan/CDK), perwakilan
pemerintah daerah kabupaten
(Bappeda/Baperlit- bangda serta
OPD/dinas tenik terkait), serta
pemerintah desa. Kegiatan diakhiri
dengan formulasi rencana kegiatan
pengelolaan DAS mikro yang disepakati
bersama para pihak.
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
22 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Gambar (Figure) 2. Diagram alir kegiatan perencanaan partisipatif DAS mikro (Flow chart of micro watershed
participatory planning)
Sumber (Source): Supangat et al. (2018)
Isu/Masalah Pengelolaan DAS Mikro
Formulasi Rencana Partisipatif (Matriks kegiatan)
- Perangkat desa - PKL
FGD Masyarakat - Pembangunan komitmen - Perencanaan Partisipatif
Persiapan
DAS Mikro terpilih (Naruan)
Data KarDAS Mikro
Input pengetahuan: - Pengelolaan DAS - KTA di hulu DAS - Pengembangan ekonomi - Model partisipatif - Peran kelembagaan
FGD Instansi - Sosialisasi rencana - Pembangunan komitmen - Penggalangan dukungan
Reformulasi Rencana Pengelolaan - Rencana kegiatan - Rencana kolaboratif/ partisipatif - Rencana pembinaan
- Rencana monev
- RPDAS - RTR
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 23
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perumusan Isu/Masalah dan Tujuan
Pengelolaan
Perumusan isu dan masalah utama
dalam pengelolaan penting untuk
dilakukan, sebagai dasar untuk
menentukan fokus tujuan pengelolaan
(Warren, 1998). Isu dan masalah dapat
diidentifikasi melalui fenomena yang
berkembang di khalayak ramai, dan sering
diangkat menjadi bahan penelitian serta
pemberitaan. Penentuan isu/masalah juga
harus mengacu pada rencana yang lebih
makro yang telah disusun, seperti
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu
(RPDAS-T), serta Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) kabupaten setempat.
Selanjutnya isu yang teridentifikasi dapat
diverifikasi dan diklarifikasi melalui
penelusuran karakteristik DAS untuk
mengetahui akar masalah yang akan
dijadikan titik tuju pengelolaan DAS.
Isu/masalah yang ingin diselesaikan dalam
pengelolaan DAS mikro bisa lebih dari
satu. Berdasarkan Perdirjen RLPS No. P.15
tahun 2009, terdapat 10 isu/masalah yang
sebagian besar terkait dengan fenomena
bencana hidrometeorologi, serta
penyebab dan dampaknya. Namun, harus
ditentukan satu masalah yang menjadi isu
utama untuk dipecahkan melalui kegiatan
pengelolaan DAS.
Berdasarkan basis data dasar yang
terkumpul beserta fenomena
pemberitaan dan didukung banyak data
dan informasi hasil penelitian terdahulu,
isu utama DAS Mikro Naruan adalah
fenomena “erosi-sedimentasi”. Berkaitan
dengan tingginya tingkat sedimentasi di
hilir Sub DAS Keduang, yaitu di Waduk
Gajah Mungkur, disinyalir disebabkan oleh
tingginya tingkat erosi tanah dari wilayah
hulunya, seperti di DAS Mikro Naruan. Hal
tersebut diperkuat dengan hasil
identifikasi potensi erosi tanah yang
sangat tinggi di DAS Mikro Naruan
(Wahyuningrum & Supangat, 2016a). Isu
ini dapat berdampak pada masalah ikutan
seperti produktivitas lahan yang rendah
serta kemiskinan. Pemilihan isu utama ini
disetujui oleh petani dan para pihak
melalui forum FGD dan sosialisasi.
Berdasarkan masalah utama tersebut,
kemudian dirumuskan tujuan pengelolaan
DAS Mikro Naruan bersama para pihak,
yaitu “memperbaiki tutupan lahan di hulu
DAS dalam rangka mengendalikan laju
erosi-sedimentasi serta meningkatkan
produktivitas lahan secara partisipatif”.
B. Perencanaan Partisipatif dengan
Masyarakat
Masyarakat petani (pemilik atau
penggarap) lahan adalah pihak yang
paling mengetahui kondisi lahan budidaya
mereka, dan yang paling berhak
menentukan pola pengelolaan yang akan
dilakukan. Namun demikian, pengetahuan
tentang rambu-rambu tata pengelolaan
secara ideal dan konservatif perlu
diberikan kepada mereka. Kegiatan FGD
perencanaan partisipatif dengan
masyarakat (petani) dilakukan dalam 3
tahapan, yaitu: 1) penyamaan persepsi
dan pembekalan; 2) evaluasi pemahaman,
identifikasi permasalahan teknis serta
penggalian preferensi petani; dan 3)
perumusan rencana pengelolaan lahan
secara partisipatif. Dalam diskusi, dibuat
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
24 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
kelompok-kelompok petani berdasarkan
hamparan (kedekatan lahan olah), kurang
lebih beranggotakan 10-15 orang/
kelompok. Tim peneliti, penyuluh
kehutanan lapangan (PKL) dan perangkat
desa bertindak sebagai fasilitator.
Kegiatan penyamaan persepsi dan
pembekalan petani sangat penting
dilakukan karena kondisi status
pengetahuan dan motivasi tiap-tiap petani
berbeda-beda, atau bahkan masih banyak
kesalahan pemahaman tentang prinsip-
prinsip konservasi tanah dan air (KTA)
serta cara pengelolaan lahan yang benar.
Beberapa materi pembekalan yang
disampaikan antara lain:
1. Pengelolaan DAS, serta hubungan
hulu dan hilir dalam pengelolaan DAS
2. Karakteristik lahan di hulu DAS dan
upaya KTA yang dapat diterapkan
3. Partisipasi masyarakat dalam upaya
pengelolaan lahan dan KTA
4. Peran kelembagaan masyarakat
dalam pengelolaan DAS di wilayah
hulu DAS
5. Peluang ekonomi dalam pengelolaan
lahan di hulu DAS
Pada pertemuan selanjutnya, dilakukan
evaluasi pemahaman petani terhadap
pengelolaan DAS dan KTA, serta pola
pengelolaan lahan di hulu DAS, terutama
di lahan-lahan berlereng terjal. Pada
diskusi ini juga dilakukan identifikasi
kondisi lahan dan permasalahan yang ada
di masing-masing anggota kelompok,
seperti erosi, keberadaan jurang, longsor,
rendahnya produktivitas, kurangnya
modal usahatani, dan lain-lain. Selain itu
juga digali informasi tentang keinginan
dan harapan masyarakat terhadap lahan
mereka serta jenis andil petani sebagai
bentuk partisipasi jika lahannya
mendapatkan bantuan dari kegiatan RHL,
seperti tenaga kerja, pupuk dasar (pupuk
kandang) maupun obat-obatan.
Proses perencanaan diakhiri dengan
diskusi perumusan rencana pengelolaan
lahan. Berbekal kondisi ideal hasil analisis,
pemahaman petani serta peluang pasar,
para petani diajak menyusun rencana
untuk pengelolaan DAS mikro Naruan
yang meliputi pemilihan jenis tanaman
kayu, model/pola pertanaman, andil
petani dan dukungan pemerintah yang
diharapkan. Rencana tersebut disajikan
dalam bentuk matriks rencana (Lampiran
1.). Rencana partisipatif ini yang akan
dibawa pada sosialisasi ke para pihak di
tingkat kabupaten.
Pemilihan model pengelolaan lahan
secara vegetatif dilakukan secara
partisipatif. Berdasarkan diskusi
partisipatif, disepakati dua macam pola
yang diinginkan masyarakat, yaitu pola
campuran atau tumpangsari (agroforestri)
tanaman kayu dengan tanaman semusim,
serta pola hutan rakyat monokultur
(murni tanaman kayu-kayuan). Pola
campuran juga dibagi menjadi dua
macam, yaitu pola tumpangsari biasa dan
pola surjan (selang-seling antara blok
tanaman kayu dan blok tanaman
semusim). Pola agroforestri ini merupakan
salah satu bentuk kompromi antara
kepentingan ekonomi pemenuhan
kebutuhan rumah tangga petani dengan
kepentingan lingkungan dalam
pencegahan erosi sedimentasi, yang
diejawantahkan dalam tanaman kayu-
kayuan (Junaidi, 2013; Mayrowani &
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 25
Ashari, 2011; Suryanto & Putra, 2012).
Kepentingan ekonomi mengarah pada
kepentingan jangka pendek dan panjang.
Pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka
pendek dapat dipenuhi dari tanaman
semusim, sedangkan untung jangka
panjang dari tanaman kayu-kayuan. Selain
itu, juga dilakukan penanaman rumput
agar meningkatkan upaya pengendalian
erosi.
Model kedua, monokultur tanaman
kayu (murni tanaman kayu-kayuan),
banyak diaplikasikan terutama pada lahan
yang sangat miring yang tidak
memungkinkan untuk melakukan
penanaman tanaman semusim pada
bidang olahnya. Pertimbangan lainnya
adalah petani sebagai pengambil
keputusan di lapangan tidak memiliki
cukup ketersediaan tenaga kerja dan
modal untuk melakukan pertanian
semusim. Pertimbangan ini didukung
dengan fakta bahwa banyak anggota
rumah tangga petani yang merantau ke
daerah lain yang memiliki prospek
ekonomi lebih baik. Lahan yang dimiliki
ditanami dengan tanaman kayu-kayuan,
karena pada kondisi ini setelah menanam
kemudian tidak membutuhkan perhatian
dan curahan tenaga kerja yang intensif.
Selain pertimbangan model
pengelolaan lahan, petani berkepentingan
pula dengan tanaman yang diusahakan.
Petani berusaha meningkatkan potensi
ekonomi dari pengelolaan lahan yang
dilakukan melalui pemilihan tanaman
yang memiliki prospek ekonomi tinggi
baik secara nilai jual produk,
kelangsungan produk, dan resiko tanaman
yang rendah. Tanaman yang memenuhi
kriteria tersebut antara lain tanaman
sengon, alpukat, durian, empon-empon.
Tanaman sengon dipilih karena nilai jual
kayunya yang relatif tinggi dengan masa
panen cukup pendek. Durian dan alpukat
dipilih karena terus berproduksi/berbuah
dan memiliki nilai jual tinggi serta relatif
sedikit berisiko terserang hama penyakit.
Tanaman empon-empon diinginkan petani
karena relatif cepat panen (2 tahunan),
nilai jual produk yang tinggi dan mudah
perawatan selain risiko terserang hama
penyakit yang rendah. Pemilihan
komoditi yang dipilih untuk dikembangkan
tersebut dipengaruhi oleh informasi pasar
yang diperoleh petani, pengalaman
pribadi atau pengalaman petani lain.
Berdasarkan kesimpulan diskusi
partisipatif yang dilakukan, kemudian
disepakati untuk mengelompokkan lahan
calon kegiatan agroforestri ke dalam dua
kriteria berdasarkan kemiringan lahan,
yaitu < 45 % dan > 45%, masing-masing
pada dua jenis tutupan lahan aktual yaitu
tanaman semusim dan kebun campur.
Alokasi lahan tersebut sebagai masukan
bagi para pihak yang berkepentingan
untuk merencanakan kegiatan
pengelolaan ke depan, seperti disajikan
pada Gambar 3.
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
26 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
(a) Lokasi Desa Bubakan (Bubakan Village)
(b) Lokasi Desa Wonokeling (Wonokeling Village)
(c) Lokasi Desa Wonorejo (Wonorejo Village)
Gambar (Figure) 3. Alokasi kegiatan agroforestri di masing-masing desa di DAS Mikro Naruan (Allocation of agroforestry activities in each village in the Naruan Micro Catchment)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2018
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 27
C. Sosialisasi dan Diskusi dengan Para
Pihak yang Berkepentingan
Peran pihak yang berkepentingan
(Stakeholders) sangat penting dalam
pengelolaan DAS terutama di wilayah hulu
(Alviya, Suryandari, Maryani, & M.Z.
Muttaqin, 2016). Pelibatan para pihak
yang berkepentingan sangat mutlak
diperlukan dalam pengelolaan DAS mikro
sebagai konsekuensi beragamnya
pemanfaatan lahan di hulu DAS.
Pravongviengkham, Khamhung,
Sysanhouth, & Qwist-Hoffmann (2005)
menjelaskan bahwa konsep DAS mikro
adalah yang paling tepat dan dapat
dikelola untuk mengembangkan rencana
pengelolaan DAS integratif, melalui
dukungan kegiatan dari para pihak secara
kolaboratif di wilayah desa.
Sosialisasi rencana partisipatif
dilakukan di tingkat kabupaten, dengan
fasilitator Bappeda/Bapperlitbang
kabupaten sebagai coordinating agency
dalam kegiatan pengelolaan DAS mikro.
Para pihak yang diundang meliputi
perwakilan instansi pusat (BPDASHL, dan
BBWS), perwakilan instansi daerah
(propinsi) yaitu Dinas kehutanan propinsi
yang diwakili oleh cabang dinas kehutanan
(CDK) setempat, Balai Pusdataru, instansi
daerah (kabupaten) yaitu Bappeda dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait, serta swasta (Perum Jasa Tirta,
Perum Perhutani) dan LSM.
Sosialisasi rencana partisipatif ini juga
sekaligus sebagai bentuk proses
pelembagaan rencana yang telah disusun
masyarakat, ke tingkat para pihak yang
diharapkan akan mendukung kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi)
masing-masing lembaga. Selain itu,
sosialisasi dan diskusi juga sebagai sarana
penggalangan dukungan para pihak
berkepentingan melalui pembangunan
komitmen bersama para pihak untuk
mengelola hulu secara bersama-sama,
dengan pola pengelolaan kolaboratif.
Upaya diskusi ini diharapkan dapat
menjadi jaminan keberlanjutan dalam
pengelolaan DAS ke depan, khususnya di
wilayah hulu pada skala mikro.
D. Formulasi Rencana Pengelolaan DAS
Mikro
Tahap terakhir dari proses
perencanaan pengelolaan DAS mikro
adalah melakukan reformulasi rencana
(partisipatif) ke dalam bentuk rencana
indikatif pengelolaan DAS mikro. Rencana
indikatif tersebut berisi rencana kegiatan
(vegetatif/agroforestri dan kegiatan KTA
sipil teknis), rencana kolaboratif para
pihak yang terkait dengan masing-masing
kegiatan, rencana pembinaan/pember-
dayaan masyarakat, serta rencana monev.
Matriks rencana indikatif disajikan pada
Lampiran 2.
Rencana indikatif ini diharapkan
dapat ditindaklanjuti oleh para pihak,
melalui fasilitasi BPDASHL atau CDK
bekerja sama dengan
Bappeda/Baperlitbang Kabupaten, dalam
penyusunan Rencana Induk Pengelolaan
DAS Mikro (RIP-DAS Mikro). Untuk
kemudian RIP-DAS Mikro secara idealnya
akan disahkan oleh kepala daerah
kabupaten (Bupati), agar dapat diacu oleh
para pihak terutama Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana
kegiatan sektoral. Sebagai lembaga
implementator, OPD dan institusi terkait
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
28 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
lainnya dapat menyusun rencana detail
dan rencana teknis kegiatan bersama
masyarakat di mana lokasi DAS mikro
berada.
E. Pembelajaran dari Kegiatan
Penelitian Aksi
Pelajaran yang dapat diambil dari dari
kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Basis
data dasar (baseline data) detil terkait
karakteristik potensi dan kerentanan
wilayah DAS mikro sangat penting
diketahui; 2) Proses perencanaan
pengelolaan DAS mikro tidak dapat
sepenuhnya mengandalkan partisipasi
masyarakat, tetapi perlu kombinasi antara
sistem top down dan partisipatif; 3)
Perencanaan yang sifatnya top down
menyangkut pemberian rambu-rambu
pengelolaan lahan yang benar di wilayah
hulu DAS; 4) Perencanaan partisipatif
dilakukan dalam penyusunan rencana
penggunaan/pemanfaatan lahan, jenis
kegiatan konservasi yang sesuai serta
andil sumber daya dari masyarakat
sebagai bentuk partisipasi; 5) Rencana
kolaboratif perlu dibangun dengan para
pihak terkait dalam rangka keterpaduan
dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan
DAS mikro.
IV. KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, telah diperoleh
tahapan proses serta pembelajarannya
dalam kegiatan perencanaan pengelolaan
DAS mikro, yang menjadi rekomendasi
penelitian agar terwujud pola
perencanaan yang partisipatif-kolaboratif
yaitu: (i) penyediaan basis data dasar
secara detil-spasial, (ii) perumusan isu-
masalah-tujuan-strategi pengelolaan, (iii)
perencanaan partisipatif dengan
masyarakat dan para pihak, (iv)
pelembagaan rencana di tingkat tapak dan
para pihak terkait, serta tindaklanjut oleh
lembaga terkait sampai diperoleh
legalisasi rencana di tingkat administrasi
kabupaten.
Hasil temuan penelitian ini dapat
diimplementasikan oleh para pelaksana
lapangan khususnya BPDASHL di lokasi
DAS mikro yang lain. Selain bertujuan
mendapatkan rencana yang lebih
partisipatif-kolaboratif, implementasi di
banyak lokasi akan memvalidasi temuan
tersebut agar mendapatkan koreksi guna
penyempurnaan rekomendasi.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih disampaikan kepada Balai
Litbang Teknologi Pengelolaan DAS
(BPPTPDAS) dan lembaga donor APFNet
yang telah memberikan dana untuk
kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga
disampaikan pada seluruh peneliti dan
teknisi, lembaga terkait baik pusat,
propinsi dan kabupaten (Wonogiri dan
Karanganyar), serta masyarakat yang
terlibat pada kegiatan ini di 3 desa
(Bubakan, Wonokeling dan Wonorejo).
DAFTAR PUSTAKA
Achouri, M. (2005). Preparing the Next Generation of Watershed Management Programmes. In M. Achouri, L. Tennyson, K. Upadhyay, & R. White (Eds.), Proceedings of The Asian Regional Workshop “Preparing For the Next Generation of Watershed Management Programmes and Projects (ASIA)”
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 29
(pp. 11–18). Kathmandu, Nepat: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Adi, S. (2013). Karakteristik Bencana Banjir Bandang di Indonesia. Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia, 15(1 A), 32–45.
Alemu, M. M. (2016). Integrated Watershed Management and Sedimentation. Journal of Environmental Protection, 07(04), 490–494. https://doi.org/10.4236/jep.2016.74043
Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & M.Z. Muttaqin, M. Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 13, 121–134.
Anwar, S. (2005). Watershed Management in Indonesia. In M. Achouri, L. Tennyson, K. Upadhyay, & R. White (Eds.), Proceedings of The Asian Regional Workshop “Preparing For the Next Generation of Watershed Management Programmes and Projects (ASIA)” (pp. 93–103). Kathmandu, Nepat: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Asdak, C. (2014). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). Data Bencana Indonesia 2017. Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Jakarta.
Dodds, R. (2019). Using a participatory integrated watershed management
approach for Tourism. Tourism Planning & Development. https://doi.org/10.1080/21568316.2018.1556327
Indrawati, D. R., Awang, S. A., Faida, L. R. W., & Maryudi, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan Implementasi. Jurnal Kawistara, 6(2), 113–224.
Jayawardena, A. W. (2015). Hydro-meteorological Disasters: Causes, Effects and Mitigation Measures with Special Reference to Early Warning with Data Driven Approaches of Forecasting. Procedia IUTAM, 17, 3–12. https://doi.org/10.1016/j.piutam.2015.06.003
Junaidi, E. (2013). Peranan Penerapan Agroforestry terhadap Hasil Air Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane. Jurnal Penelitian Agroforestry, 1(1), 41–53.
Mayrowani, H., & Ashari. (2011). Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 29(2), 83–98.
Mika, M. L., Dymond, R. L., Aguilar, M. F., & Hodges, C. C. (2019). Evolution and application of urban watershed management planning. Journal of the American Water Resources Association, July 2019, 1–19. https://doi.org/10.1111/1752-1688.12765
Nourani, V., & Kalantari, O. (2010). Integrated Artificial Neural Network for Spatiotemporal Modeling of Rainfall–Runoff–Sediment Processes. Environtmental Engineering Science, 27(6), 411–422.
Membangun Proses Perencanaan ............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
30 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Paimin, Purwanto, & Sukresno. (2010). 2010. Sidik Cepat Degrasi Sub Daerah Aliran Sungai (Edisi Revisi). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
Pravongviengkham, P., Khamhung, A., Sysanhouth, K., & Qwist-Hoffmann, P. (2005). Integrated Watershed Management for Sustainable Upland Development and Poverty Alleviation in LAO People’s Democratic Republic. In M. Achouri, L. Tennyson, K. Upadhyay, & R. White (Eds.), Proceedings of The Asian Regional Workshop “Preparing For the Next Generation of Watershed Management Programmes and Projects (ASIA)” (pp. 105–118). Kathmandu, Nepat: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Purwanto, & Supangat, A. B. (2017). Perilaku Konsumsi Air Pada Musim Kemarau Di Dusun Pamor, Kabupaten Grobogan. Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 14(3), 157–169. https://doi.org/10.20886/jpsek.2017.14.3.157-169
Rodríguez-Blanco, M. L., Taboada-Castro, M. M., & Taboada-Castro, M. T. (2013). Linking the Field to the Stream: Soil Erosion and Sediment Yield in a Rural Catchment, NW Spain. Catena, 102, 74–81.
Shi, Z. H., Ai, L., Li, X., Huang, X. D., Wu, G. L., & Liao, W. (2013). Partial Least-squares Regression for Linking Land-cover Patterns to Soil Erosion and Sediment Yield in Watersheds. Journal of Hydrology, 498, 165–176.
Stålnacke, P., Nagothu, U. S., Deelstra, J., Thaulow, H., Barkved, L. J., Berge, D., … Portugués. (2014). Integrated Water Resources Management:
STRIVER Efforts to Assess the Current Status and Future Possibilities in Four River Basins. European Research on Sustainable Development. https://doi.org/10.1007/978-3-642-19202-9_11
Strahler, A. N. (1983). Element of Physical Geography. New York: John Willey and Sons.
Supangat, A. B., Donie, S., Purwanto, Wahyuningrum, N., Cahyono, S. A., Sulasmiko, E., … Putro. (2015). Pengelolaan DAS Mikro di Daerah Tangkapan Air Waduk Gajah Mungkur, DAS Bengawan Solo. Surakarta.
Supangat, A. B., Donie, S., Purwanto, Wahyuningrum, N., Indrawati, D. R., Sulasmiko, E., … Ardianto, W. (2018). Development participatory management of micro catchment at the Bengawan Solo Upper Watershed. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS. Surakarta (tidak dipublikasikan).
Suryanto, P., & Putra, E. T. S. (2012). Traditional Enrichment Planting in Agroforestry Marginal Land Gunung Kidul, Java, Indonesia. Joumal of Sustainable Development, 5(2).
Vigiak, O., Malagó, A., Bouraoui, F., Grizzetti, B., Weissteiner, C. J., & Pastori, M. (2016). Impact of Current Riparian Land on Sediment Retention in the Danube River Basin. Sustainability of Water Quality and Ecology. https://doi.org/10.1016/j.swaqe.2016.08.001
Wahyuningrum, N., & Supangat, A. B. (2016). Analisis Spasial Kemampuan Lahan dalam Perencanaan Pengelolaan DAS Mikro: Kasus di DAS Mikro Naruwan, Sub DAS Keduang,
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 31
DAS Solo. Majalah Ilmiah Globe, 18(1), 43–52.
Wahyuningrum, N., & Supangat, A. B. (2016). Identifikasi tingkat bahaya longsor dengan skala data berbeda untuk perencanaan DAS Mikro Naruan, Sub DAS Keduang. Majalah Ilmiah Globe, 18(1), Oktober 2016, 53–60.
Warren, P. (1998). Developing Participatory and Integrated Watershed Management, A case
study of the FAO/Italy inter-regional. Project for Participatory Upland Conservation and Development (PUCD). Community Forestry Case Study Series. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
Wolfgramm, B. (2015). Pathways to Effective Integrated Watershed Management (IWSM policy brief No2). Bern, Switzerland.
Membangun Proses Perencanaan ............................................................................................................ ..(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
32 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Lampiran 1. Rencana partisipatif hasil FGD dengan masyarakat (A participatory plan as the result of community FGD)
Desa (Villages)
Penggunaan lahan
(Land use)
Kele-rengan (Slope)
Kegiatan (Activities)
Luas (Area) (ha)
Jenis tanaman (Plant types)
Keterangan (Remarks)
Identifikasi instansi pendukung
(Identification of supporting agencies)
Kayu/buah (Trees) Semusim (Seasonal crops)
Bubakan
Tegal
>45%
HR (full kayu) 12,4 Sengon - BPTKPDAS BPDAS Dishutbun Distan BBWS Jasa tirta Swasta
HR (tumpangsari) 30,5 Sengon Palawija, kolonjono, PB
HR (surjan) 22,8 Sengon, suren, alpokat Palawija, kolonjono Rumput utk tampingan
<45%
HR (full kayu) 4,4 Sengon -
HR (tumpangsari) 25,5 Sengon Palawija, kolonjono, PB
Penanaman kayu di batas pemilikan
75,5 Sengon, suren, alpokat
Kebun
>45%
HR (full kayu) 13,1 Sengon, suren Sulaman, pengkayaan BPTKPDAS BPDAS Dishutbun Distan BBWS Jasa tirta Swasta
HR (tumpangsari) 10,0 Sengon Jahe Sulaman, pengkayaan
<45%
HR (full kayu) 18,1 Sengon, suren Sulaman, pengkayaan
HR (tumpangsari) 45,5 Sengon, alpokat Jahe Sulaman, pengkayaan
Wonokeling
Tegal
>45%
HR (full kayu) 2,1 Sengon Rumput BPTKPDAS BPDAS Dishutbun Distan BBWS Jasa tirta Swasta
HR (tumpangsari) 13,5 Sengon Empon-2 (jahe & Kunyit) Strip rumput (galengan & tampingan)
HR (surjan) 6,4 Sengon Empon-2 (jahe & Kunyit)
<45%
HR (full kayu) 4,8
HR (tumpangsari) 35,7 Sengon, durian, alpokat Empon-2 (jahe & Kunyit) Strip rumput (galengan & tampingan)
Penanaman kayu di batas pemilikan
65,9 Sengon, suren, durian alpokat
Rumput
Kebun >45%
HR (full kayu) 6,7 Sengon Sulaman, pengkayaan BPTKPDAS BPDAS Dishutbun
HR (tumpangsari) 10,7 Sengon, durian kapulaga, sambiloto Sulaman, pengkayaan
<45% HR (full kayu) 13,7 Sengon Sulaman, pengkayaan
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 33
HR (tumpangsari) 73,5 Sengon, durian kapulaga, sambiloto
Sulaman, pengkayaan Distan BBWS Jasa tirta Swasta
Wonorejo
Tegal
>45%
HR (full kayu) 1,5 Sengon, jabon, alpokat BPTKPDAS BPDAS Dishutbun Distan BBWS Jasa tirta Swasta
HR (tumpangsari) 11,3 Sengon, kopi Jahe, kapulaga, palawija Strip rumput (galengan & tampingan)
<45%
HR (surjan) 10,1 Sengon, jabon, alpokat Jahe, kapulaga, palawija
HR (full kayu) 2,8 Sengon -
HR (tumpangsari) 14,5 Sengon, kopi Jahe, kapulaga, bambu Strip rumput (galengan & tampingan)
Penanaman kayu di batas pemilikan
30,5 Sengon, jabon, alpokat
Kebun
>45%
HR (full kayu) 2,5 Sengon, kopi - Sulaman, pengkayaan BPTKPDAS BPDAS Dishutbun Distan BBWS Jasa tirta Swasta
HR (tumpangsari) 5,8 Sengon, kopi Jahe, kapulaga Sulaman, pengkayaan
<45%
HR (full kayu) 3,5 Sengon, kopi - Sulaman, pengkayaan
HR (tumpangsari) 21,1 Sengon, kopi Jahe, kapulaga Sulaman, pengkayaan
Membangun Proses Perencanaan ............................................................................................................ ..(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
34 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Lampiran 2. Matriks rencana indikatif pengelolaan lahan (Matrix of indicative plan of land management)
Desa (Villages)
Kel. (Group)
Kelerengan (Slope)
Vegetasi (Vegetation) Sipil Teknis (Civil engineering)
(Teras, SPA, DPn, gullyplug)
Partsipasi masyarakat
(Farmer participation)
Harapan (Expectation)
Pihak terkait (Stakeholders)
Pola (Model)
Jenis Tanaman (Plant types)
Kayu (Wood)
Buah (Fruits) Semusim
(Seasonal) Bawah
(Understorey)
Bubakan
I
> 45% Campuran, Full Kayu
Sengon, Suren
Durian, Alpokat Jagung, Singkong
Jahe, Lengkuas Teras, Gullyplug Tenaga & Pupuk Kandang
Bantuan Ternak BPDASHL Bapperlitbang Dishut prop CDK DLH kab. Distan-bun Pusdataru BBWS-BS Jasa Tirta I Swasta
< 45% Campuran, Full Kayu
Sengon, Suren
s.d.a Jagung, Singkong
s.d.a Teras s.d.a s.d.a
II
> 45% Full Kayu, Campuran
Sengon Durian, Mangga, Jeruk, Cengkeh
Jagung, Singkong
Jahe, Rumput SPA Tenaga & Pupuk Kandang
Bantuan Ternak, Pupuk
< 45% Full Kayu, Campuran
Sengon s.d.a Jagung, Singkong
s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
III > 45%
Full Kayu Sengon Alpokat, Durian - Jahe, Lengkuas, Talas, Rumput
Gullyplug - Bantuan Ternak (Sapi)
< 45% Full Kayu Sengon s.d.a - s.d.a s.d.a - s.d.a
Wonokeling
I
> 45% Campuran, Full Kayu
Sengon Alpokat, Petai, Durian, Coklat, Mangga
Jagung Jahe, Rumput Spa, Bronjong Kawat
Tenaga Kerja & Lahan
Bantuan Ternak BPDASHL Bapperlitbang Dishut prop CDK DLH kab. Distan-bun Pusdataru BBWS-BS Jasa Tirta I Swasta
< 45% Campuran Sengon,
Suren S.D.A Jagung, Padi
Gogo Jahe, Rumput, Kunyit
s.d.a s.d.a s.d.a
II
> 45%
Campuran Sengon, Suren
Alpokat, Petai, Durian, Coklat, Klengkeng, Sukun, Cempedak
Jagung Jahe, Rumput, Kunyit
SPA Tenaga, Pupuk Kandang, Rumput, Obat-Obatan
Bantuan Ternak, Pupuk
< 45% Campuran Sengon,
Jati s.d.a Jagung, Padi
Gogo s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
III
> 45% Campuran Sengon,
Jati Alpokat, Petai, Durian, Coklat, Kopi
Jagung Jahe, Kunyit Bronjong Kawat Tenaga Kerja Bantuan Ternak, Bibit Ikan, Pupuk, Bibit Rumput
< 45% Campuran Sengon,
Jabon s.d.a Jagung, Padi
Gogo s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 17-36
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 35
IV
> 45% Campuran, Full Kayu
Sengon Petai, Durian Jagung, Singkong
Jahe, Kunyit, Rumput
Bronjong Kawat Tenaga, Pupuk Kandang, Singkong
Bantuan Ternak, Bibit Ikan, Pupuk, Bibit Rumput
< 45% Campuran Sengon s.d.a Jagung,
Singkong s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
Wonorejo
I > 45%
Campuran, Full Kayu
Sengon, Suren
Alpokat, Durian Jagung Jahe Spa/Paciran + Rumput, Bronjong Kawat
Tenaga Kerja, Pupuk Kandang, Perawatan
Bantuan Ternak Sapi
BPDASHL Bapperlitbang Dishut prop CDK DLH kab. Distan-bun Pusdataru BBWS-BS Jasa Tirta I Swasta
< 45% Campuran Sengon s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
II
> 45%
Campuran Sengon, Jabon, Suren
Alpokat, Durian Jagung, Sayuran, Tembakau
Jahe, Rumput, Kunyit, Kapulaga
Spa, Sgp, Teras Bangku
Tenaga, Pupuk Kandang, Rumput, Obat-Obatan
Bantuan Ternak Sapi, Kambing, Bibit
< 45% Campuran s.d.a Jagung, Padi
Gogo s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
III
> 45% Full Kayu, Surjan
Sengon, Jabon, Suren
Alpokat, Durian Jagung, Cabai
Jahe, Kapulaga
Teras Gulud Tenaga Bantuan Ternak Sapi, Bibit, Jalan Angkut
< 45% Full Kayu, Surjan
s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
IV > 45%
Campuran Sengon, Suren, Jabon
Alpokat, Durian, Petai
Jagung Jahe Emprit Spa dan Rumput Tenaga, Pupuk Kandang
'Bibit Tanaman Yang Bagus
< 45% Campuran s.d.a Jagung s.d.a s.d.a s.d.a s.d.a
Membangun Proses Perencanaan.............................(Agung B. S, Dewi R.I, Nining W, Purwanto, dan Syahrul Donie)
36 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Halaman ini sengaja dibiarkan kosong
E-ISSN:2579-5511/P-ISSN:2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.37-52
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 37
STUDI KARAKTERISTIK HIDROLOGI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) JIRAK
MENGGUNAKAN TIME SERIES ANALYSIS
(Hydrological Characteristics Study of Jirak Sub Watershed
Using Time Series Analysis)
Bayu Argadyanto Prabawa1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Teknologi Yogyakarta, Indonesia Jl. Ring Road Utara, Jombor Lor, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55285 Email: [email protected]
Diterima: 1 November 2019; Direvisi: 26 Maret 2020; Disetujui: 30 Maret 2020
ABSTRACT
Jirak Sub Watershed is one of the resurgence river in Gunungkidul. This river flow into Kalisuci Cave, and becomes an underground river. This underground river is used for tourism activities known as CaveTubing. The main problem of this tourism activities is frequent flood events. This flood comes from input discharge originating from Jirak River as the upstream of Kalisuci Cave. This research aim is to determine the hydrological characteristics of Jirak Sub Watershed in Kalisuci Cave Tourism area with the hope in increasing the understanding of the tourism operators regarding regulation of the flood early warning and evacuation systems. Hydrological characteristics were determined from the discharge rating curve, time lag (Tlag) and effective rainfall (Pe) calculation. The result of this research shows that the time lag between the rain occurrence and early flood occurrence at Jirak Sub Watershed ranged from 2,5 to 3 hours. Fast response of peak discharge indicates that Jirak Sub Watershed has a fast response drainage system to rainfall in rainy season. The effective rainfall percentage was determined from the 17 selected flood hydrograph which the value increased from the early phase until the end of rainy season. This hydrological characteristic of Jirak Sub Watershed can be used by Kalisuci Cave tourism management team as flood early warning and evacuation system.
Keywords: flood; hydrological characteristic; time lag; effective rainfall
ABSTRAK
Sub Daerah ALiran Sungai (DAS) Jirak adalah salah satu aliran sungai yang muncul kembali di Gunungkidul. Aliran sungai mengalir ke dalam. Gua Kalisuci, dan menjadi sungai bawah tanah. Sungai bawah tanah ini digunakan untuk kegiatan pariwisata yang dikenal sebagai Cave Tubing. Masalah utama dari kegiatan pariwisata ini adalah terjadinya banjir. Banjir ini berasal dari debit yang berasal dari Sungai Jirak sebagai hulu dari Gua Kalisuci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik hidrologis Sub DAS Jirak di lokasi Wisata Gua Kalisuci dengan harapan akan menambah pemahaman pengelola wisata Gua Kalisuci terkait pengaturan sistem peringatan dini dan sistem evakuasi ketika terjadi banjir. Karakteristik
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak…………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
38 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
hidrologi ditentukan dari rating curve, jeda waktu (Tlag) dan perhitungan curah hujan efektif (Pe). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jeda waktu antara kejadian hujan dan kejadian banjir awal di Sub DAS Jirak berkisar antara 2,5 hingga 3 jam. Respon debit puncak yang cepat mengindikasikan bahwa Sub DAS Jirak memiliki sistem drainase yang cepat merespon hujan di musim hujan. Persentase curah hujan efektif ditentukan dari 17 hidrograf banjir terpilih yang nilainya meningkat dari fase awal hingga akhir musim hujan. Karakteristik hidrologi Sub DAS Jirak ini dapat digunakan oleh tim manajemen pariwisata Gua Kalisuci sebagai peringatan dini dan untuk evakuasi ketika banjir terjadi.
Kata kunci: banjir; karakteristik hidrologi; jeda waktu; hujan efektif
I. PENDAHULUAN
Kawasan karst Gunungsewu
membentang dari Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi DIY (Daerah
Istimewa Yogyakata) hingga Kabupaten
Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Kawasan
karst Gunungsewu telah diusulkan kepada
UNESCO sebagai salah satu kawasan
geopark yang tergabung dalam Global
Geopark Network. Hal ini menjadikan
kawasan karst Gunungsewu merupakan
kawasan yang harus dilindungi kelestarian
alamnya. Salah satu kekayaan kawasan
karst Gunungsewu adalah kekayaan gua-
gua karstnya yang sangat melimpah. Salah
satu potensi yang dapat dikembangkan
dari gua-gua karst adalah potensi wisata,
baik itu ekowisata maupun wisata minat
khusus (Goldscheider, 2012). Eksplorasi
gua-gua karst Gunungsewu yang
dilakukan oleh Macdonald & Patners
(1984) telah menemukan kurang lebih 58
gua dan luweng di kawasan karst
Gunungsewu pada Kabupaten
Gunungkidul, dan masih banyak lagi gua-
gua yang belum terpetakan.
Topografi karst hampir tidak memiliki
aliran sungai permukaan. Topografi karst
salah satunya dicirikan oleh pola aliran
multi basinal yang ditunjukkan oleh
cekungan-cekungan tertutup (doline)
diantara bukit-bukit karst serta adanya
sinking stream (Bailly-Comte , Martin,
Jourde, Screaton, Pistre, Langston, 2010;
Ford & Williams, 2013). Sistem drainase
karst dimulai dari pengisian zona-zona
rekahan pada batuan karbonat yang akan
diteruskan ke zona jenuh air dalam sungai
bawah tanah (White, 1988). Drainase
karst berdasarkan sumber daerah
tangkapannya dibagi menjadi dua tipe,
yaitu karst allogenik dan autogenik. Karst
allogenik merupakan karst yang memiliki
daerah tangkapan yang berasal dari
kawasan non-karst, sedangkan karst
autogenik memiliki daerah tangkapan
yang berasal dari kawasan karst itu sendiri
(Ford & Williams, 2013).
Gillieson (2009) menyebutkan sistem
drainase pada akuifer karst terbagi
menjadi 3 sifat aliran, yaitu aliran diffuse,
aliran fissure, dan aliran konduit. Aliran
diffuse memiliki respon yang lambat
terhadap aliran masukan dan merupakan
karakterisktik dari rembesan dan tetesan
air dari atap gua (Putro, 2012). Sistem
aliran fissure yaitu aliran yang berupa
retakan dengan lebar kurang dari 10 mm,
yang dikontrol oleh perlapisan batuan
(Gillieson, 2009). Aliran utama dalam
sistem hidrologi karst adalah aliran
konduit yang memiliki sifat aliran turbulen
yang memiliki respon cepat terhadap
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 39
masukan (Dewaide, Banniver, Rochez, &
Hallet, 2016; Reh, Liche, Geyer, Nödler, &
Sauter, 2013). Aliran konduit terbentuk
pada gabungan antara rekahan atau
bidang perlapisan batuan yang melebar
karena proses pelarutan yang membentuk
lorong-lorong yang memiliki lebar hingga
beberapa meter (Hartmann, Goldscheider,
Wagmer, Lange, & Weiler, 2015; White,
1988).
Keberadaan tipe aliran konduit
menunjukkan tingkat perkembangan karst
yang telah berkembang lanjut akibat
proses solusional yang berkembang,
sedangkan tipe aliran diffuse
menunjukkan bahwa kawasan karst
tersebut kurang mengalami
perkembangan (Panagopoulos &
Lambrakis, 2006). Sistem hidrologi karst
pada umumnya tidak hanya terbentuk
dari salah satu tipe aliran saja, baik diffuse
maupun konduit, namun kebanyakan
merupakan campuran dari tipe-tipe aliran
tersebut (White, 1988).
Wisata Cave Tubing di Gua Kalisuci
merupakan salah satu wisata andalan di
Kabupaten Gunungkidul. Wisata Cave
Tubing ini memanfaatkan aliran sungai
bawah tanah yang merupakan tipe aliran
konduit yang berasal dari aliran sungai
permukaan dari Sub DAS Jirak yang masuk
ke dalam sistem sungai bawah tanah Gua
Kalisuci. Kawasan wisata karst ini berada
di Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Kegiatan wisata yang dilakukan dalam
gua dapat berdampak terhadap
perubahan kondisi hidrologi gua tersebut.
Oleh karena itu, wisata minat khusus
untuk gua memiliki beberapa persyaratan
dalam pengelolaannya, antara lain adanya
kajian tingkat kesulitan dan bahaya gua,
kemampuan operator wisata gua dan
peralatan penelusuran, peta gua,
peringatan kepada operator untuk selalu
menaati kode etik penelusuran gua,
kejelasan sistem perijinan oleh SAR dan
instansi terkait, dan pengecekan berkala
tingkat kerusakan dan pencemaran gua
(Samodra, 2001). Permasalahan dalam
pengelolaan wisata Gua Kalisuci adalah
kurangnya pemahaman pengelola wisata
terhadap sistem hidrologi sungai bawah
tanahnya. Permasalahan sistem hidrologi
pada aliran Gua Kalisuci adalah kejadian
banjir yang sering terjadi pada Sub DAS
Jirak yang merupakan hulu sungai bawah
tanah Kalisuci. Kejadian banjir di sungai
Jirak ini tentu akan mengganggu kegiatan
wisata di Gua Kalisuci, karena sungai
bawah tanah yang meluap tidak dapat
digunakan untuk penelusuran wisata gua.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
karakteristik hidrologis Sub DAS Jirak di
Wisata Gua Kalisuci, dengan harapan akan
menambah pemahaman pengelola wisata
Gua Kalisuci terkait pengaturan sistem
peringatan dini dan sistem evakuasi ketika
terjadi banjir.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Sub DAS Jirak merupakan sistem DAS
yang aliran hulunya berasal dari
perbukitan karst Gunungsewu serta
dataran fluvio-karst Ponjong yang berada
di sisi timur laut outlet sungai. Selain itu,
batas Sub DAS Jirak di sisi utara dibatasi
oleh sistem aliran irigasi persawahan di
Kecamatan Ponjong. Sungai Jirak yang
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak…………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
40 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
merupakan hulu sungai bawah tanah
Kalisuci memiliki aliran air yang cukup
turbulen, sehingga memerlukan
kecermatan pemilihan lokasi stasiun
pencatat tinggi muka air (water level data
logger). Lokasi yang dipilih tepat pada
utara bendungan terakhir di Sungai Jirak
yang berjarak ± 100 meter dari tempat
masuk Gua Kalisuci. Selain stasiun
pencatat tinggi muka air (TMA), dipasang
penakar hujan merekam data hujan yang
jatuh di hulu dan hilir dari Sub DAS Jirak.
Penakar hujan di hulu diletakkan di Desa
Sidorejo, Kecamatan Ponjong. Pencatatan
data hujan dan TMA sungai dilakukan
mulai bulan Juni 2015 sampai dengan Juni
2016. Peta lokasi pemasangan alat
pemantauan hujan dan muka air sungai
ditunjukkan dalam Gambar 1.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Peta RBI digital skala 1:25.000 Lembar Karangmojo dan Semanu sheet 1408-312 dan 1408-321) tahun 1998 dan 1999 (BAKOSURTANAL), untuk data dasar pada peta tentatif.
b. Peta Gua Kalisuci Gunungsewu Cave Survey 1982 (MacDonalds & Patners, 1984), sebagai acuan lokasi pemasangan alat pengamatan.
b. Pustaka penelitian sebelumnya, sebagai referensi pendukung penelitian.
Gambar (Figure) 1. Peta lokasi pemasangan alat penakar hujan di hulu dan alat pencatat tinggi
muka air Sub DAS Jirak (Map of the location of rainfall gauge in the upstream
and water level data logger installed in Jirak Sub Watershed).
Sumber (Source): Google Earth yang dianalisis (Analyzed of Google Earth), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 41
Alat yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain:
a. GPS (Global Positioning System), untuk
plotting lokasi penelitian.
b. Penakar hujan otomatis (data logging
rain gauge) tipe RG3, sebagai pencatat
data hujan.
c. HOBO Water Level Data Logger,sebagai
pencatat TMA sungai bawah tanah gua.
d. Seperangkat peralatan fotografi,
sebagai alat dokumentasi lapangan.
e. Perangkat lunak (Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, dan
ArcGIS 10.2, SPSS 17, Compass, Corel
Draw X5, dan HOBOware PRO), sebagai
alat pendukung pengolahan data
lapangan dan penulisan laporan.
C. Metode Penelitian
Pengukuran debit air sungai bawah
tanah dilakukan secara systematic
sampling pada outlet sungai yaitu pada
entrance Gua Kalisuci bagian hilir Sub DAS
Jirak yang digunakan sebagai lokasi awal
jalur penelusuran wisata. Data TMA
direkam dengan interval waktu ± 30
menit. Pengukuran debit langsung di
lapangan juga dilakukan sebagai acuan
untuk melakukan konversi data TMA dari
logger menjadi data debit air. Pengukuran
di lapangan menggunakan metode
velocity area method dengan media
pelampung. Ilustrasi pengukuran metode
velocity area method ditunjukkan oleh
Gambar 2.
Data curah hujan didapatkan melalui
pemasangan stasiun penakar hujan
otomatis tipe RG3 yang berada di hulu
Sub DAS Jirak. Data curah hujan diambil
secara temporal selama 1 tahun dengan
interval waktu ± 30 menit.
Analisis karakteristik banjir dilakukan
untuk mengetahui waktu jeda kenaikan
TMA sungai (Tlag) mencapai bagian hilir
DAS dan jumlah kejadian banjir selama
penelitian. Perhitungan Tlag dilakukan de-
Gambar (Figure) 2. Ilustrasi (A) penampang melintang pelampung untuk perhitungan koefisien pelampung, (B) lintasan penampang, dan (C) luas penampang basah (Illustration of (A) cross section of floating object for floating method coefficient calculation, (B) transverse trajectory, and (C) wet perimeter area)
Sumber (Source): Analisis data (Data Analysis), 2019
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak…………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
42 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
ngan metode statistik analisis deret waktu
(time series analysis) (Zhang, Chen, Shi, &
Chen, 2013; Nurkholis, Adji, & Haryono,
2019). Analisis deret waktu ini dipilih
karena dapat digunakan untuk
mengetahui lama respon debit sungai
terhadap kejadian hujan di hulu DAS.
Metode yang digunakan dalam analisis
deret waktu ini adalah metode cross-
correlation.
1. Lengkung Aliran Debit Sungai
Data TMA yang didapatkan dari logger
pencatat yang terpasang di sungai
dikonversi menjadi data debit aliran
setelah dilakukan perhitungan lengkung
debit aliran (stage-discharge rating curve).
Persamaan rating curve menggunakan
persamaan regresi adalah sebagai berikut:
Q = f x TMA……………………………………………………..(1)
Keterangan:
Q = debit aliran (m3/s)
f = fungsi regresi linier TMA dengan debit
aliran
TMA = tinggi muka air sungai
Perhitungan regresi ini perlu
memperhatikan nilai koefisien
determinasi (R2) untuk mengetahui
perbedaan varian dari data pengukuran
variabel Y pada garis regresi nilai
persamaan variabel X (Soewarno, 1991).
2. Korelasi Dua Variabel (Hujan dan Debit
Aliran)
Analisis ini digunakan untuk
mengetahui hubungan antara hujan di
hulu sungai Kalisuci pada Sub DAS Jirak
dan debit aliran rata-rata Sungai Kalisuci,
sehingga dapat diketahui gambaran awal
arah korelasi kedua variabel tersebut.
Korelasi antara dua variabel terjadi
apabila nilai probabilitas dari hasil
perhitungan kurang dari 0,05 dan nilai
korelasi harus lebih besar dibanding taraf
signifikansi 5%.
3. Analisis Deret Waktu dengan Cross-
Correlation
Analisis deret waktu biasa digunakan
untuk mengetahui hubungan linier antara
input dan output dalam kajian hidrologi.
Kajian hidrologi karst biasanya
menggunakan metode ini untuk
mengetahui respon debit mata air
terhadap hujan (Zhang et al. 2013).
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah korelasi silang (cross-
correlation). Persyaratan data dalam
melakukan analisis korelasi silang ini
adalah seri data harus memiliki interval
waktu yang sama dan diasumsikan
stasioner dalam nilai mean dan varians
(Cowpertwait dan Metcalfe, 2009 dalam
Thomas, 2010).
Hubungan antara dua variabel dapat
didefinisikan dengan rumus:
…………..……………………….(2)
Cxy adalah cross correlogram,
sedangkan puncak dari cross correlogram
(nilai rxy (k) tertinggi) merupakan estimasi
waktu tunda (time lag (Tlag)) yang
menunjukkan korelasi silang antara
variabel input dan output pada suatu
sistem.
Apabila:
……………………………(3)
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 43
Cx (0) dan Cy (0) adalah rumus standar
deviasi untuk masing-masing seri data
variabel x dan variabel y.
Korelasi silang diturunkan dengan
menggunakan bahasa R. Nilai R memiliki
besaran nilai mulai dari -1 hingga 1. Nilai R
yang mendekati 1 dan -1 menandakan
adanya hubungan yang kuat antar
variabel, baik positif (1) maupun negatif (-
1). Nilai R yang mendekati atau sama
dengan 0 menunjukkan hubungan yang
lemah atau tidak ada hubungan antara
kedua variabel (Fiorillo & Doglioni, 2010).
Nilai korelasi positif menunjukkan
hubungan linier antara dua variabel,
sedangkan nilai korelasi negatif
menunjukkan hubungan terbalik antara
dua variabel.
4. Analisis Hidrograf Satuan Kejadian
Banjir
Curah hujan yang jatuh tersebut
menjadi beberapa komponen limpasan,
yaitu aliran permukaan langsung, aliran
antara, dan aliran air tanah. Komponen-
komponen aliran ini merupakan
komponen penyusun hidrograf (Cheng,
Cheng, Wen, & Lee, 2013; Sofyan, Saidi,
Istijono, & Herdianto, 2017). Analisis
hujan efektif dilakukan dengan
memisahkan direct runoff dengan aliran
dasar.
Hidrograf satuan terpilih dianalisis
volume direct runoff (DRO), baseflow
(BF), hujan efektif (Pe), dan phi indeksnya.
Nilai direct runoff, baseflow, dan phi
indeks selanjutnya digambarkan dalam
hidrograf satuan (Unit Hydrograph /UH).
Hidrograf satuan ini dapat
menggambarkan besarnya waktu tunda
(Tlag) yang dilihat dari waktu hujan
tertinggi hingga waktu menuju puncak
banjir. Selain hujan efektif, juga digunakan
analisis statistik korelasi dan regresi untuk
menentukan hubungan antara debit
puncak dengan beberapa komponen
hujan. Ilustrasi hidrograf banjir
ditunjukkan oleh Gambar 3.
Gambar (Figure) 3. Ilustrasi hidrograf satuan banjir (Illustration of flood unit hydrograph)
Sumber (Source): Modifikasi dari Harto, 1993 (Modified from Harto, 1993)
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak…………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
44 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
DRO = Q x BF..........................................(4)
Keterangan :
DRO = direct runoff (m3)
Q = debit sungai (m3/s)
BF = baseflow (m3/s)
VDRO = Σ (DRO x ΔT)...............................(5)
Keterangan: VDRO = volume direct runoff (m3)
DRO = direct runoff (m3/s)
ΔT = interval perekaman debit (menit)
Pe = VDRO .............................................(6)
A
Keterangan :
Pe = hujan efektif (mm)
VDRO = volume direct runoff (m3)
A = luas DAS (m2)..........................(7)
Keterangan:
Ø = nilai phi indeks (mm/jam)
Ptot = hujan total (mm)
Pe = hujan efektif (mm)
ΔT = interval waktu perekaman (jam)
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai tinggi muka air (TMA) berdasarkan
pencatatan alat dengan interval
perekaman 30 menit selama 1 tahun
mulai tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan
20 Juni 2016. Gambar 4 menunjukkan
grafik lengkung aliran dengan persamaan
regresi linier antara TMA dan debit Sungai
Jirak. Persamaan regresi dari lengkung
aliran yang menunjukkan hubungan TMA
dan debit sungai Jirak adalah:
Q = 1.2355e3.1771(h) ............................................(8)
Keterangan :
Q = debit aliran (m3/s) h = tinggi muka air sungai (m) e = nilai eksponensial
Nilai lengkung aliran ini digunakan
untuk menentukan debit sub DAS Jirak
selama masa pengukuran. Hidrograf aliran
Sub DAS Jirak ditunjukkan oleh Gambar 5.
Gambar (Figure) 4. Grafik dan persamaan lengkung aliran sungai Jirak (Jirak river’s rating curve
equation and graph)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 45
Gambar (Figure) 5. Hidrograf aliran Sub DAS Jirak perekaman 1 tahun (Hydrograph of one-year
recorded discharge data in Jirak Sub Watershed)
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
Perhitungan korelasi silang ini
menggunakan nilai time lag hingga 15 jam
(nilai waktu tunda 30). Hasil pengolahan
data ini menghasilkan grafik yang
menghubungkan nilai ksorelasi dengan
waktu tunda antara kenaikan debit dan
kejadian hujan. Fungsi korelasi silang
antara hujan dan debit aliran
menunjukkan nilai k (waktu tunda) positif
yang menandakan bahwa hujan di daerah
hulu mempengaruhi kenaikan debit di hilir
sub DAS Jirak. Nilai korelasi (rxy(k))
tertinggi sebesar 0,245 berada pada angka
waktu tunda ke-6. Data dengan interval
30 menitan menunjukkan bahwa nilai
waktu tunda adalah selama 3 jam. Grafik
analisis korelasi silang debit Sub DAS Jirak
terhadap kejadian hujan ditunjukkan oleh
Gambar 6.
Gambar (Figure) 6. Grafik cross correlation debit sub DAS Jirak terhadap kejadian hujan (Cross-correlation
graph between Jirak Sub Watershed discharge and rainfall occurrence)
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
0,245
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak…………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
46 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Analisis deret waktu (time series
analysis) di kawasan karst umumnya
digunakan untuk membagi tipe akuifer
karst berdasarkan karakteris- tik
hidrologinya, terutama dilakukan pada
sistem mata air dan sungai bawah tanah
(Nurkholis, Adji, & Haryono, 2019).
Penelitian ini menggunakan analisis deret
waktu untuk mengetahui karakteristik
sungai permukaan yang masuk ke sistem
sungai bawah tanah karst. Perhitungan
korelasi silang dalam analisis deret waktu
juga dilakukan dengan membagi musim
penghujan menjadi tiga fase, yaitu fase
awal musim hujan, fase pertengahan
musim hujan, dan fase akhir musim hujan.
Pembagian fase hujan ditunjukkan oleh
Gambar 7. Perhitungan analisis silang
pada fase awal hujan menunjukkan nilai
korelasi (rxy(k)) tertinggi pada nilai positif.
Nilai korelasi (rxy(k)) tertinggi sebesar
0,109 berada pada angka waktu tunda ke-
166, atau nilai waktu tunda adalah selama
83 jam atau 3 hari lebih 11 jam. Hal ini
dimungkinkan saat fase awal hujan, curah
hujan yang jatuh ke permukaan tanah
tidak langsung menjadi aliran permukaan,
namun mengisi rongga-rongga tanah
hingga jenuh atau masuk ke dalam sistem
epikarst terlebih dahulu. Perhitungan
waktu tunda pada fase tengah hujan
menunjukkan nilai korelasi (rxy(k)) (rxy(k))
tertinggi sebesar 0,263 berada pada
angka time lag ke-5, atau nilai waktu
tunda adalah selama 2,5 jam. Perhitungan
waktu tunda pada fase akhir hujan
menunjukkan nilai korelasi (rxy(k))
tertinggi sebesar 0,401 berada pada
angka time lag ke-6, atau nilai waktu
tunda adalah selama 3 jam. Respon debit
yang bertambah cepat di tiap fase hujan
ini disebabkan karena kondisi permukaan
tanah yang telah jenuh air, sehingga curah
hujan yang turun langsung menjadi aliran
permukaan. Grafik analisis korelasi silang
debit pada tengah dan akhir musim hujan
ditunjukkan oleh Gambar 8.
Pemilihan kejadian banjir dengan satu
puncak tunggal (single peak discharge)
pada data perekaman debit aliran Sub
DAS Jirak selama 1 tahun menemukan
sebanyak 17 hidrograf kejadian banjir.
Fase awal musim hujan memiliki
persentase hujan efektif dari tebal hujan
yang terjadi pada satu kejadian hujan
yang lebih kecil dibandingkan curah hujan
yang hilang (tidak menjadi limpasan).
Pemilihan kejadian banjir pada fase ini
mendapatkan persentase hujan efektif
sebesar 30-36% saja. Persentase hujan
efektif pada fase tengah musim hujan
sebesar 18-96,9% dengan rata-rata
sebesar 55% yang menjadi hujan efektif.
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 47
Gambar (Figure) 7. Pembagian fase musim hujan pada data hujan (The division of the rainy season phase on
the rain data)
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
Gambar (Figure) 8. Grafik cross correlation debit Sub DAS Jirak pada fase tengah dan akhir hujan(Cross-correlarion graph of Jirak Ssub Watershed discharge in the mid-phase and the end-phase of rainy season)
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
Beberapa variabel hujan yang diuji
statistik adalah variabel durasi hujan,
tebal hujan, puncak hujan, dan hujan
efektif. Hasil perhitungan statistik antara
debit puncak aliran dengan komponen-
komponen hujan di hulu Sub DAS Jirak
menunjukkan hubungan yang positif
antara variabel-variabel bebas (durasi
hujan, tebal hujan, hujan efektif, dan
puncak hujan) dengan variabel terikat
(debit puncak Sub DAS Jirak). Variabel
tebal hujan dan curah hujan efektif
memiliki nilai korelasi dan regresi yang
cukup kuat terhadap kejadian debit
puncak banjir di hilir Sub DAS Jirak. Kedua
variabel tersebut dapat dijadikan
patokan/referensi bagi pengelola wisata
Cave Tubing Kalisuci untuk memprediksi
kejadian banjir di Sungai Kalisuci
berdasarkan tebal hujan dan hujan efektif
yang terjadi. Nilai hujan efektif minimal
sebesar 5 mm dengan tebal hujan sebesar
minimal sebesar 14,5 mm bahkan sudah
menyebabkan banjir di hilir Sub DAS Jirak.
Hasil analisis korelasi dan regresi variabel
komponen hujan terhadap debit puncak
di Sub DAS Jirak ditunjukkan oleh Tabel 2.
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
48 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 1. Penentuan komponen hujan pada seluruh kejadian banjir terpilih selama periode penelitian (Determination of rain componenst in all selected flood events during the research period)
Fase Musim Hujan
Waktu Awal Hujan
Waktu Banjir (Debit Puncak)
Tebal Hujan (mm)
Puncak Hujan (mm)
Durasi Hujan (jam)
Debit Puncak
(Lt/detik)
Time lag (jam)
Hujan Efektif (mm)
Hujan Efektif
(%)
Ploss (mm)
Ø indeks
Awal Musim Hujan
12/16/2015 16:30 12/16/2015 18:30 42,5 6,5 5,5 1503,2192 1,0 15,5 36,5 27,0 2,5
12/21/2015 14:00 12/21/2015 16:30 14,5 9,5 2,0 1015,1888 2,0 5,5 37,7 9,0 2,3
1/11/2016 13:00 1/11/2016 14:30 48 26 4,0 1464,0944 1,0 14,7 30,6 33,3 4,9
Tengah Musim Hujan
1/22/2016 16:30 1/22/2016 20:00 23,5 7 3,5 2485,4576 2,5 22,8 96,9 0,7 0,1
2/1/2016 19:00 2/1/2016 20:00 16,5 12,5 3,5 1826,5136 1,0 9,7 58,8 6,8 1,0
2/5/2016 14:00 2/5/2016 22:30 35 7,5 8,0 1958,3024 5,0 19,0 54,4 16,0 1,0
3/26/2016 18:00 3/26/2016 21:30 106,5 47 2,0 3261,776 3,5 49,9 46,9 56,6 14,8
3/30/2016 16:30 3/30/2016 20:30 66 44,5 5,5 3103,22 2,5 31,5 47,7 34,5 3,1
4/1/2016 13:30 4/1/2016 17:00 27,5 17 1,5 1114,03 3,0 5,0 18,1 22,5 5,5
4/6/2016 12:00 4/6/2016 16:00 16 17,5 2,5 1239,6416 3,0 8,6 53,6 7,4 3,5
4/8/2016 16:00 4/8/2016 19:00 37,5 19,5 2,5 2201,29 2,5 23,9 63,6 13,6 2,7
Akhir Musim Hujan
4/11/2016 16:00 4/11/2016 18:30 83 44,5 3,5 2833,46 2,5 64,7 78,0 18,3 2,6
4/12/2016 14:30 4/12/2016 17:30 83,5 26,5 3,5 2870,53 3,0 59,2 70,9 24,3 3,5
4/13/2016 17:00 4/13/2016 22:00 91,5 29 6,0 3482,11 4,5 77,1 84,3 14,4 1,2
4/16/2016 17:00 4/16/2016 18:30 33,5 28 3,5 2586,3584 1,5 31,0 92,5 2,5 0,4
4/26/2016 15:00 4/26/2016 18:00 44 24 2,0 1494,9824 3,0 30,4 69,1 13,6 6,3
4/30/2016 0:00 4/30/2016 3:30 47,5 5,5 2,5 1647,3632 4,0 16,1 33,9 31,4 1,5
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 49
Tabel (Table) 2 Nilai korelasi dan regresi komponen hujan terhadap debit puncak Sub DAS Jirak (Correlation and regression value between rainfall components and peak discharge of Jirak Sub Watershed)
Data 30 menitan Tebal Hujan
Puncak Hujan
Durasi Hujan
Hujan Efektif
Debit Puncak r 0,784 0,678 0,328 0,855
R² 0,6806 0,5207 0,1564 0,7803
Sumber (Source): Analisis data primer (Primary data analysis), 2019
Hasil perhitungan dengan analisis deret
waktu tidak menyimpang jauh dari hasil
perhitungan menggunakan hidrograf
satuan banjir terpilih. Hasil perhitungan
dengan analisa deret waktu, korelasi
silang menghasilkan waktu tunda selama
2,5 hingga 3 jam, sedangkan hasil
hidrograf banjir menunjukkan waktu
tunda rata-rata selama 2,7 jam. Respon
cepat ini menandakan sistem drainase
dari Sub DAS Jirak yang cepat. Selain
dipengaruhi oleh faktor hujan, sistem
pengatusan ini terkait oleh penggunaan
lahan, material permukaan, kemiringan
lereng, topografi DAS, bentuk dan ukuran
DAS (Dharmananta, Suyarto, & Trigunasih,
2019). Nilai waktu tunda ini dapat
dijadikan sebagai referensi waktu bagi
pengelola wisata di Kalisuci dalam
melakukan kegiatan evakuasi bilamana
terjadi banjir, sehingga pengelola dapat
mengantisipasi kejadian banjir akan
terjadi pada 2,5 – 3 jam setelah kejadian
hujan di hulu sungai.
Hasil korelasi dan regresi yang
menunjukkan hubungan dan pengaruh
kuat dari komponen tebal hujan dan
curah hujan efektif ini perlu diperhatikan
pengelola, di mana hujan dengan nilai
tersebut sudah menyebabkan banjir. Hal
ini dapat dijadikan referensi bagi
pengelola apabila akan memasang sistem
peringatan dini (Early Warning System)
banjir dengan menggunakan patokan nilai
hujan tersebut sebagai upaya untuk
kesiapsiagaan terhadap kejadian bencana
banjir di Sub DAS Jirak.
IV. KESIMPULAN
Banjir Sub DAS Jirak menunjukkan
bahwa waktu tunda antara kejadian hujan
dan awal kejadian banjir di sub DAS Jirak
berkisar 2,5 hingga 3 jam dengan nilai
korelasi yang meningkat hingga fase akhir
hujan. Persentase hujan efektif yang jatuh
di Sub DAS Jirak menjadi total run off yang
semakin meningkat pada fase akhir hujan.
Seluruh parameter hujan di Sub DAS Jirak
memiliki korelasi positif dengan kejadian
debit puncak. Parameter yang paling
mempengaruhi kejadian banjir di Sub DAS
Jirak adalah tebal hujan dan curah hujan
efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa Sub DAS Jirak cepat merespon
terjadinya hujan di hulu sungai menjadi
debit aliran. Pengelola wisata di Gua
Kalisuci yang memanfaatkan aliran Sub
DAS Jirak dapat menggunakan patokan
waktu tunda untuk memperkirakan
kejadian banjir yaitu 2,5 - 3 jam setelah
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak……………….…………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
50 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
kejadian hujan di hulu. Tebal hujan dan
hujan efektif dapat digunakan sebagai
variabel acuan dalam pembangunan
sistem peringatan dini banjir di Sub DAS
Jirak. Untuk yang akan datang masih
diperlukan penelitian yang berkaitan
pengembangan sistem peringatan dini
yang mudah diterapkan untuk masyarakat
setempat berdasarkan hasil temuan
ilmiah penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
Bailly-Comte, V., Martin, J.B., Jourde, H., Screaton, E.J., Pistre, S., & Langston, A. (2010). Water exchange and pressure transfer between conduits and matrix and their influence on hydrodynamics of two karst aquifers with sinking streams. Journal of Hydrology 386, 55–66. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.03.005
Dewaide, L., Bonniver, I., Rochez, G., & Hallet, V. (2016). Solute transport in heterogeneous karst system: Dimensioning and of the transport parameters vi multi-sampling tracer-test modelling using OTIS (One-dimensional Transport with Inflow and Storage) Program. Journal of Hydrology 534, 567-578. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.01.049
Dharmananta, I. D. P. G. A., Suyarto, R., & Trigunasih, N. M. (2019). Pengaruh morfometri DAS terhadap debit dan sedimentasi DAS Yeh Ho. Agroekoteknologi Tropika 8(1), 32–42
Fiorillo, F., & Doglioni, A. (2010). The relation between karst spring discharge and rainfall by cross-correlation analysis (Campania, Southern Italy). Hydrogeology Journal. https://doi.org/10.1007/s10040-010-
0666-1
Ford, D., & Williams, P. (2013). Karst Hydrogeology and Geomorphology. In Karst Hydrogeology and Geomorpho- logy. https://doi.org/10.1002/9781118684986
Gillieson, D. (2009). Caves: Processes, Development and Management. In Caves: Processes, Development and Management. https://doi.org/10.1002/9781444313680
Gill, L.W., Babechuck, M.G., Kamber, B.S., McCormeck, T., & Murphy, C. (2018). Use of trace and rare earth elements to quantify autogenic allogenic inputs within a lowland karst network. Applied Geochemistry 90, 101-114. http://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.01.001
Goldscheider, N. (2012). A holistic approach to groundwater protection and ecosystem services in karst terrains. AQUA mundi-am06046, 117-124. https://doi.org/10.1007/s13146-019-00492-5
Harmann, A., Goldscheider, N., Wagener, T., Lange, J., Weiler, M. (2014). Karst water resources in a changing world: Review of hydrological modeling approaches. Reviews of Geophysics 52, 218-242, https://doi.org/10.1002/2013RG000443
Harto, S.B. (1993). Analisis hidrologi. Jakarta: Gramedia
Kusumayudha, S. B. (2005). Hidrogeologi Karst dan Geometri Fraktal di Daerah Gunungsewu. Yogyakarta: Adicita.
Macdonald, S.M.& Patners. (1984). Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study (Volume 3C: Cave
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 37-52
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 51
Survey). In Greater Yogyakarta Groundwater Resources Study. Yogyakarta: P2AT, Ministry of Public Works
Nurkholis, A., Adji, T. N., & Haryono, E. (2019). Time series analysis application for karst aquifer characterisation in Pindul Cave Karst System, Indonesia. Acta Carsologica 48 (1), 69-84. https://doi.org/10.3986/ac.v48i1.6745
Panagopoulos, G., & Lambrakis, N. (2006). The contribution of time series analysis to the study of the hydrodynamic characteristics of the karst systems: Application on two typical karst aquifers of Greece (Trifilia,Almyros Crete). Journal of Hydrology. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.02.023
Putro, S. T. (2012). Analysis of Organic Carbon Flux in the Gilap Cave, Ponjong Sub-District, Gunungkidul District, Yogyakarta, Indonesia. Tesis S2, Fak. Geografi. Universitas Gadjah Mada
Reh, R., Liche, T., Geyer, T., Nödler, K., & Sauter, M. (2013). Occurrence and spatial distribution of organic micro-pollutants in a complex hydrogeological karst system during low flow and high flow periods, results of a two-year study. Science of the Total Environment 443, 438–445. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.11.005
Samodra, H. (2001). Nilai Strategis Kawasan Karst di Indonesia :
Pengelolaan dan Perlindungan. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
Soewarno. (1991). Hidrologi : Pengukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai (Hidrometri). Bandung: Penerbit Nova
Sofyan, E.R., Saidi, A., Istiyono, B., & Herdianto, R. 2017. Model hidrograf akibat perubahan tataguna lahan DAS Batang Kuranji (Studi kasus Sub DAS Danau Limau Manis). Poli Rekayasa 13 (1), 1-10
Thomas, B. C. (2010). Comparison of two physically-based spatially distributed hydrology models in contrasting geo-climatic settings. Thesis S2, ITC The Netherlands
White, W. B. (1988). Geomorphology and hydrology of karst terrains. Geomorphology and Hydrology of Karst Terrains. https://doi.org/10.1002/jqs.3390040211
You, Z., Chen, W., & Song, L. (2011). Evaluating ecological tourism under sustainable development in karst area. Journal of Sustainable Development. https://doi.org/10.5539/jsd.v4n2p234
Zhang, Z., Chen, X., Shi, P., & Chen, X.
(2013). Quantifying time lag of
epikarst-spring hydrograph response
to rainfall using correlation and
spectral analyses. Hydrogeology
Journal.
https://doi.org/10.1007/s10040-013-
1041-9
Studi Karakteristik Hidrologi Sub DAS Jirak……………….…………………..…….………………….(Bayu Argadyanto Prabawa)
52 @2019 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Halaman ini sengaja dibiarkan kosong
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.53-62
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 53
POLA HUJAN DI BAGIAN HULU DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DALAM PERENCANAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR
(Rainfall pattern for water resources utilization planning in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Diah Auliyani1 dan Nining Wahyuningrum1
1Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan DAS Jl A Yani. Pabelan, Kartasura. PO.BOX 295 Surakarta/ 57102.Telp (0271)716709, 716959
Email: [email protected]
Diterima: 27 November 2019; Direvisi : 12 Februari 2020; Disetujui : 17 Maret 2020
ABSTRACT
Information about rainfall fluctuations is essential especially for local people who are still depend on natural resources. This study aims to analyze rainfall pattern in the upper stream of Bengawan Solo Watershed. This information can be used as a basis for water resources utilization planning. We analyze the rainfall data from 14 rain gauge stations descriptively to determine rainfall fluctuations and seasonal shifts. Annual rainfall in the upper stream of Bengawan Solo Watershed varies between 1,433.5 mm to 3,231.2 mm with an average of 2,224.6 mm. The beginning of the rainy or dry seasons did not change, however, the duration of the rainy season increased from 7 months (October-April) in 1990-1998 and 1999-2007 to 8 months (October-May) in 2008-2016. About 90% of rainfall was concentrated in the rainy season. Rainwater harvesting should be done to reduce runoff in the rainy season as well as efforts to provide water resources in the dry season. Keywords: Rainfall; Seasonal shift; Water resources; Bengawan Solo
ABSTRAK
Informasi mengenai fluktuasi hujan sangat penting terutama bagi masyarakat lokal yang masih bergantung pada sumberdaya alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola hujan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya air. Data curah hujan tahun 1990-2016 dari 14 stasiun penakar hujan dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui fluktuasi hujan dan pergeseran musim. Curah hujan tahunan di hulu DAS Bengawan Solo bervariasi antara 1.433,5 mm hingga 3.231,2 mm dengan rerata mencapai 2.224,6 mm. Tidak terjadi perubahan awal musim hujan maupun musim kemarau, namun demikian durasi musim hujan mengalami peningkatan dari 7 bulan (Oktober-April) pada periode 1990-1998 dan 1999-2007, bertambah menjadi 8 bulan (Oktober-Mei) pada periode 2008-2016. Sebesar 90% curah hujan terkonsentrasi pada musim hujan. Pemanenan air hujan dapat dilakukan untuk mengurangi runoff di musim hujan sekaligus sebagai upaya penyediaan sumberdaya air di musim kemarau. Kata kunci: Curah hujan; Pergeseran musim; Sumberdaya air; Bengawan Solo
Pola Hujan di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai………………………………………….…… (Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum)
54 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
I. PENDAHULUAN
Hujan memiliki dua sisi yang saling
bertolak belakang dalam hal bencana
hidrometeorologis. Dalam jumlah
berlimpah, hujan mampu menjadi agen
bagi bencana banjir, erosi, serta longsor,
sebaliknya, pengurangan jumlahnya secara
terus menerus akan mengakibatkan
bencana kekeringan. Penelitian
sebelumnya menyebutkan pengaruh
perubahan iklim terhadap variabilitas
hujan yang pada akhirnya menjadi pemicu
terjadinya berbagai bencana alam (Arnaud
et al., 2002; Narulita et al., 2010;
Olanrewaju et al., 2017). Masyarakat yang
kehidupan sehari-harinya masih
bergantung pada sumberdaya alam
menjadi sangat rentan terhadap
perubahan curah hujan tersebut (Adger et
al., 2003; Boissière et al., 2013; Lintner et
al., 2012). Oleh sebab itu, hujan menjadi
salah satu variabel iklim yang penting
untuk dipelajari.
Indonesia rentan terhadap perubahan
pola curah hujan (Nuryanto, 2013). Sebagai
pulau terpadat di Indonesia, Pulau Jawa
memiliki kerentanan yang tinggi terhadap
perubahan curah hujan. Pada 2015, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
mencatat bahwa Jawa menjadi pulau yang
paling sering terpapar banjir dengan
kerugian fisik mencapai Rp. 65,4 Trilyun
dan kekeringan dengan kerugian mencapai
Rp. 56,5 Trilyun (Amri et al., 2016).
Mengingat tingginya kepadatan penduduk
di Pulau Jawa, kerugian yang dapat muncul
karena bencana alam akibat fluktuasi
hujan akan menjadi semakin besar. Oleh
karena itu, fluktuasi dan tren perubahan
curah hujan menjadi semakin penting
untuk dipelajari lebih lanjut.
Dalam pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS), hujan berperan penting
sebagai input bagi sistem hidrologi. Setiap
DAS memiliki respon yang berbeda
terhadap hujan dengan jumlah dan
intensitas tertentu. Bengawan Solo
merupakan DAS terbesar di Pulau Jawa.
Wilayahnya membentang dari Provinsi
Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dengan
luas wilayah 20.125 km2 atau sekitar 12%
dari luas keseluruhan Pulau Jawa
(Kementerian PUPR, 2010). Pada musim
kemarau, wilayah DAS ini sering
mengalami kekeringan, sedangkan pada
musim hujan terjadi bencana banjir.
Penelitian sebelumnya menyebutkan
bahwa Kabupaten Wonogiri menjadi salah
satu area yang paling sering mengalami
kekeringan (Pramono & Savitri, 2019).
Sebagian besar Kota Solo pernah dilanda
banjir besar pada tahun 1966
(Kementerian PUPR, 2010). Berdasarkan
hal tersebut, tren fluktuasi hujan di DAS ini
perlu dipelajari lebih lanjut untuk rencana
mitigasi dan adaptasi terhadap bencana
yang berpotensi terjadi, maupun
perencanaan pemanfaatan air hujan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis pola hujan di bagian hulu DAS
Bengawan Solo. Informasi ini dapat
digunakan sebagai dasar dalam
perencanaan pemanfaatan sumberdaya
air. Seperti disampaikan oleh Adi (2009),
bagian hulu suatu DAS memiliki fungsi
utama sebagai daerah resapan. Diharapkan
dengan perencanaan pemanfaatan
sumberdaya air yang tepat akan
membantu mengontrol dampak buruk dari
fluktuasi hujan.
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 53-62
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 55
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan di bagian
hulu DAS Bengawan Solo. Secara geografis,
bagian hulu DAS Bengawan Solo
membentang antara 110026’27” –
111027’21” BT dan 7014’17” – 806’41” LS
(Gambar 1). Secara administratif, lokasi
penelitian terletak di beberapa
Kabupaten/kotamadya, yaitu: Klaten,
Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri,
Karanganyar, Sragen, dan Ngawi. Sebagian
besar lokasi penelitian dimanfaatkan
sebagai kawasan pertanian, berupa tegalan
(38%) dan sawah (33%) (Wahyuningrum &
Basuki, 2019). Lebih lanjut disebutkan juga
penutupan lahan lainnya, yaitu
permukiman (13%), hutan produksi (10%),
permukiman perkotaan (2%), perkebunan
(1%), dan tubuh air (1%) (Wahyuningrum &
Basuki, 2019).
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan adalah data
curah hujan harian tahun 1990-2016 yang
diperoleh dari 14 stasiun penakar hujan.
Lokasi penakar hujan ditunjukkan pada
Gambar 1. Curah hujan diukur secara
manual menggunakan ombrometer.
Penakaran jumlah curah hujan harian
dilakukan setiap pagi pukul 07.00 WIB.
Data tersebut selanjutnya dikalkulasi
menjadi data hujan bulanan. Untuk
Gambar (Figure) 1. Letak penakar hujan di bagian hulu DAS Bengawan Solo (Rainfall station position in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Sumber (Source) : Analisis data (Data analysis), 2019
Pola Hujan di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai………………………………………….…… (Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum)
56 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
mendapatkan besarnya hujan wilayah hulu
DAS Bengawan Solo dilakukan dengan
menggunakan metode Polygon Thiessen.
Curah hujan di hulu DAS Bengawan Solo
dihitung menggunakan Persamaan 1,
dimana R adalah curah hujan (mm),
sedangkan Rn adalah curah hujan dari
stasiun penakar (mm), dan An adalah luas
daerah yang diwakili oleh stasiun penakar
(km2).
……….(1)
C. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini disajikan analisis
deskriptif terhadap fluktuasi curah hujan
bulanan maupun tahunan. Pergeseran
musim dianalisis secara statistik maupun
deskriptif. Untuk mengetahui pergeseran
musimnya, data curah hujan bulanan
terlebih dahulu dibagi menjadi 3 periode,
yaitu 1990-1998, 1999-2007, dan 2008-
2016.
Dalam analisis statistik pergeseran
musim, data hujan dibagi menjadi 2 (dua),
yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan
musim kemarau (April-September).
Pergeseran musim diketahui menggunakan
Paired Sample T Test. Uji ini digunakan
untuk mengukur perubahan curah hujan
dalam dua periode yang berbeda.
Dikatakan telah terjadi pergeseran musim
jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05.
Secara deskriptif, pergeseran musim
diketahui dengan mengelompokkan curah
hujan bulanan berdasarkan klasifikasi
Schmidt dan Fergusson. Menurut klasifikasi
Schmidt dan Ferguson, bulan basah
memiliki curah hujan lebih dari 100 mm,
sedangkan curah hujan kurang dari 60 mm
dikategorikan sebagai bulan kering. Curah
hujan diantara keduanya merupakan bulan
lembab atau pancaroba (Hermawan,
2010).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan
Solo bagian hulu memiliki tipe curah hujan
monsoonal. Tipe hujan ini memiliki satu
puncak musim kemarau dan satu puncak
musim hujan dengan perbedaan yang jelas
antara kedua musim tersebut (Mamenun
et al., 2014). Gambar 2 menunjukkan
distribusi curah hujan bulanan di hulu DAS
Bengawan Solo selama 1990-2016. Rerata
curah hujan pada musim hujan mampu
mencapai lebih dari 300 mm. Vernimmen
et al. (2012) menjelaskan bahwa bulan
paling kering di Indonesia terjadi antara
Juni-Oktober. Mengacu pada Gambar 2,
Gambar (Figure) 2. Fluktuasi curah hujan bulanan di
DAS Bengawan Solo bagian hulu
(Monthly rainfall fluctuation in
the upperstream of Bengawan
Solo)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis),
2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 53-62
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 57
terlihat tidak terjadi hujan (nilai = 0)
terutama antara Juni- September,
sedangkan curah hujan tertinggi (lebih dari
600 mm) terjadi pada Januari 2014. Hal ini
senada dengan penelitian sebelumnya
bahwa puncak musim hujan pada tipe
curah hujan monsoonal berlangsung
antara Desember hingga Februari (Aldrian
& Djamil, 2008; Aldrian & Susanto, 2003).
A. Fluktuasi curah hujan
Curah hujan tahunan di hulu DAS
Bengawan Solo bervariasi antara 1.433,5
mm hingga 3.231,2 mm dengan rerata
tahunan mencapai 2.224,6 mm. Dalam
rentang waktu pengamatan, curah hujan
tahunan terlihat mengalami kenaikan
(Gambar 3), begitu juga curah hujan
bulanannya (Gambar 4). Peningkatan
seperti ini telah terjadi secara global
Gambar (Figure) 3. Curah hujan tahunan di DAS Bengawan Solo bagian hulu (Annual rainfall
in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Gambar (Figure) 4. Curah hujan bulanan di DAS Bengawan Solo bagian hulu (Monthly rainfall (in blue) and average monthly rainfall (in red) in the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Pola Hujan di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai………………………………………….…… (Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum)
58 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
seiring terjadinya perubahan iklim (Alam et
al., 2011). Meningkatnya curah hujan ini
akan diikuti dengan peningkatan jumlah
tanah yang tererosi. Tanpa teknik
konservasi tanah dan air secara terpadu
pada lahan pertanian, erosi tersebut dapat
mengakibatkan penurunan produktivitas
lahan pertanian yang berdampak pada
kesejahteraan masyarakat lokal terutama
petani (Nugroho, 2000).
B. Pergeseran Musim
Distribusi temporal curah hujan pada
tiga periode menunjukkan bahwa lebih
dari 90% curah hujan tahunannya terjadi
pada musim hujan (Gambar 5). Hal ini
berarti bahwa terdapat perbedaan yang
sangat mencolok antara musim hujan dan
kemarau di hulu DAS Bengawan Solo.
Melimpahnya ketersediaan sumberdaya air
pada musim hujan ini dapat dikelola untuk
memenuhi kebutuhan sumberdaya air
pada musim kemarau. Salah satu langkah
yang bisa dilakukan adalah memperbanyak
jumlah air hujan yang meresap ke dalam
tanah dari pada yang mengalir menjadi
runoff. Wahyuningrum (2016) menyatakan
bahwa pengendalian runoff dapat
dilakukan dengan memperbanyak luas
hutan. Bagi hulu DAS Bengawan Solo yang
sebagian besar merupakan kawasan
pertanian, upaya pengurangan runoff
dapat dilakukan dengan penerapan teknik
konservasi tanah dan air secara terpadu.
Curah hujan berfluktuasi secara terus
menerus yang dapat menyebabkan
terjadinya pergeseran musim. Setiawan
(2012) menjelaskan bahwa pergeseran
awal musim hujan maupun kemarau dapat
diakibatkan oleh adanya perubahan
fluktuasi curah hujan bulanan. Hasil uji
statistik menunjukkan tidak terjadi
pergeseran musim hujan maupun kemarau
antara periode 1 (1990-1998) dan 2 (1999-
2007) di bagian hulu DAS Bengawan Solo.
Tabel 1 menjelaskan bahwa pergeseran
musim hanya terjadi antara periode 2
(1999-2007) dan 3 (2008-2016), yang
ditunjukkan dengan nilai signifikansi (2-
tailed) sebesar 0,011 (< 0,05).
Gambar (Figure) 5. Distribusi temporal curah hujan dalam tiga periode yang berbeda (Rainfall temporal distribution in three different periods)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 53-62
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 59
Secara deskriptif, tidak terlihat adanya
pergeseran awal musim hujan maupun
kemarau. Bulan Mei yang pada dua
periode pertama merupakan masa
peralihan (pancaroba, curah hujan antara
60 – 100 mm), namun pada 2008-2016,
curah hujannya meningkat menjadi 164,5
mm sehingga dapat dikategorikan sebagai
bulan basah. Gambar 6 memperlihatkan
adanya penambahan durasi musim hujan
tersebut. Musim hujan yang semula
berlangsung selama 7 bulan (Oktober -
April) pada dua periode pertama
bertambah menjadi 8 bulan (Oktober-Mei)
pada periode terakhir.
Musim kemarau yang ditandai dengan
curah hujan kurang dari 60 mm
berlangsung selama 4 bulan, yaitu Juni -
September. Berdasarkan data curah hujan
harian, pada bulan tersebut beberapa kali
tidak terjadi hujan. Disebutkan bahwa
rendahnya curah hujan yang terjadi selama
3 bulan berturut-turut mengakibatkan
berkurangnya kelembaban tanah, sehingga
mempengaruhi pertumbuhan tanaman
(Okpara et al., 2017; Spinoni et al., 2014).
Teknik konservasi air dapat menjadi
alternatif penyediaan sumberdaya air pada
musim kemarau. Distribusi temporal curah
hujan yang terkonsentrasi pada musim
hujan akan mempertinggi runoff yang
berpotensi menyebabkan banjir baik di
hulu maupun hilir DAS Bengawan Solo.
Pemanenan Air Hujan (PAH) merupakan
salah satu teknik dalam konservasi air.
Selain mampu mengurangi runoff pada
musim hujan, kegiatan PAH juga mampu
mendukung pengelolaan lahan pertanian
secara berkelanjutan (Fachruddin et al.,
2015; Maarif, 2011; Yulistyorini, 2011).
Tabel (Table) 1. Hasil Paired Sample T Test (Result of the Paired Sample T Test)
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed) Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
95% Confidence Interval of the Difference
Lower Upper
Pair 1 Musim_Hujan_1 - Musim_Hujan_2
-24,41216 128,42327 17,47619 -59,46496 10,64065 -1,397 53 0,168
Pair 2 Musim_Hujan_2 - Musim_Hujan_3
-49,28347 137,38146 18,69525 -86,78139 -11,78555 -2,636 53 0,011
Pair 3 Musim_Kemarau_1 - Musim_Kemarau_2
-7,14879 47,17939 6,42030 -20,02629 5,72870 -1,113 53 0,271
Pair 4 Musim_Kemarau_2 - Musim_Kemarau_3
-27,71278 76,96264 10,47329 -48,71954 -6,70602 -2,646 53 0,011
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
2008-2016
1999-2007
1990-1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bulan Ke -
Bulan basah Bulan lembab Bulan kering
Gambar (Figure) 6. Pergeseran musim di DAS Bengawan Solo bagian hulu (Seasonal shift in
the upperstream of Bengawan Solo Watershed)
Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Pola Hujan di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai………………………………………….…… (Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum)
60 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
IV. KESIMPULAN
Tren curah hujan di hulu DAS Bengawan
Solo mengalami peningkatan dalam kurun
1990-2016. Dalam periode tersebut tidak
terjadi pergeseran awal musim hujan
maupun kemarau. Peningkatan curah
hujan yang terjadi menyebabkan musim
hujan berlangsung lebih lama, yaitu 7
bulan (Oktober-April) pada 1990-1998 dan
1999-2007, bertambah menjadi 8 bulan
(Oktober-Mei) pada 2008-2016. Sebesar
90% curah hujan terkonsentrasi pada
musim hujan. Teknik konservasi air, seperti
Pemanenan Air Hujan (PAH) dapat
dilakukan untuk mengurangi runoff pada
musim hujan, sekaligus sebagai penyedia
sumberdaya air pada musim kemarau.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini dibiayai oleh DIPA Balai
Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(BPPTPDAS) Surakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Adger, W. N., Huq, S., Brown, K., Conwaya, D., & Hulmea, M. (2003). Adaptation to climate change in the developing world. Progress in Development Studies, 3(3), 179–195. https://doi.org/10.1191/1464993403ps060oa
Adi, R. N. (2009). Pembuatan peta tingkat kerawanan banjir sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat kerugian akibat bencana banjir. Ekspose Hasil Litbang Teknologi Pengelolaan DAS Dalam Upaya Pengendalian Banjir Dan Erosi-Sedimentasi, 283–291.
Alam, M. M., Toriman, M. E., Siwar, C., & Talib, B. (2011). Rainfall variation and
changing pattern of agricultural cycle. American Journal of Environmental Sciences, 7(1), 82–89. https://doi.org/10.3844/ajessp.2011.82.89
Aldrian, E., & Djamil, Y. S. (2008). Spatio-temporal climatic change of rainfall in East Java. International Journal of Climatology, 28, 435–448. https://doi.org/10.1002/joc.1543
Aldrian, E., & Susanto, R. D. (2003). Identification of three dominant rainfall regions within Indonesia and their relationship to sea surface temperature. International Journal of Climatology, 23(12), 1435–1452. https://doi.org/10.1002/joc.950
Amri, M. R., Yulianti, G., Yunus, R., Wiguna, S., Adi, A. ., Ichwana, A. ., Randongkir, R. ., & Septian, R. . (2016). Risiko bencana Indonesia (R. Jati & M. . Amri (eds.)). Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Arnaud, P., Bouvier, C., Cisneros, L., & Dominguez, R. (2002). Influence of rainfall spatial variability on flood prediction. Journal of Hydrology, 260, 216–230. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(01)00611-4
Auliyani, D., & Wijaya, W. W. (2017). Perbandingan prediksi hasil sedimen menggunakan pendekatan model universal soil loss equation dengan pengukuran langsung. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research), 1(1), 61–71. https://doi.org/10.20886/jppdas.2017.1.1.61-71
Boissière, M., Locatelli, B., Sheil, D., Padmanaba, M., & Sadjudin, E. (2013). Local perceptions of climate variability and change in tropical forests of Papua, Indonesia. Ecology
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 53-62
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 61
and Society, 18(4). https://doi.org/10.5751/ES-05822-180413
Chang, J., Guo, A., Wang, Y., Ha, Y., Zhang, R., Xue, L., & Tu, Z. (2019). Reservoir operations to mitigate drought effects with a hedging policy triggered by the drought prevention limiting water level. Water Resources Research. https://doi.org/10.1029/2017WR022090
Fachruddin, Setiawan, B. I., Prastowo, & Mustafril. (2015). Pemanenan air hujan mengunakan konsep Zero Runoff System (ZROS) dalam pengelolaan lahan pala berkelanjutan. Jurnal Teknik Sipil, 22(2), 127–136. https://doi.org/10.5614%2Fjts.2015.22.2.6
Febrianti, N., & Sulma, S. (2013). Analisis kejadian banjir di DAS Bengawan Solo. INDERAJA, IV(6), 38–45. https://www.researchgate.net/publication/323800043_Analisis_kejadian_banjir_di_DAS_Bengawan_Solo
Hermawan, E. (2010). Pengelompokan pola curah hujan yang terjadi di beberapa kawasan Pulau Sumatera berbasis hasil analisis teknik spektral. Jurnal Meteorologi Dan Geofisika, 11(2), 75–85. https://doi.org/10.31172/jmg.v11i2.67
Kementerian PUPR. (2010). Pola pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Bengawan Solo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat. http://sda.pu.go.id/
Lintner, B. R., Biasutti, M., Diffenbaugh, N. S., Lee, J. E., Niznik, M. J., & Findell, K. L. (2012). Amplification of wet and dry month occurrence over tropical land regions in response to global
warming. Journal of Geophysical Research Atmospheres, 117(11). https://doi.org/10.1029/2012JD017499
Maarif, S. (2011). Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi resiko bencana kekeringan. Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia, 13(2), 65–73. https://doi.org/10.29122/jsti.v13i2.886
Mamenun, Pawitan, H., & Sophaheluwakan, A. (2014). Validasi dan koreksi data satelit TRMM pada tiga pola hujan di Indonesia (Validation and correction of TRMM satellite data on three rainfall patterns in Indonesia). Jurnal Meteorologi Dan Geofisika, 15(1), 13–23. https://doi.org/10.31172/jmg.v15i1.169
Mawardi, I. (2010). Kerusakan daerah aliran sungai dan penurunan daya dukung sumberdaya air di Pulau Jawa serta upaya penanganannya. Jurnal Hidrosfir Indonesia, 5(2), 1–11.
Narulita, I., Maria, R., & Djuwansah, R. (2010). Karakteristik curah hujan di Wilayah Pengaliran Sungai (WPS) Ciliwung Cisadane. Riset Geologi Dan Pertambangan, 20(2), 95–110. https://doi.org/10.14203/risetgeotam2010.v20.37
Nugroho, S. P. (2000). Minimalisasi lahan kritis melalui pengelolaan sumberdaya lahan dan konservasi tanah dan air secara terpadu. Jurnal Teknologi Lingkungan, 1(1), 73–82. https://doi.org/10.29122/jtl.v1i1.165
Nuryanto, D. E. (2013). Karakteristik curah hujan abad 20 di Jakarta berdasarkan kejadian iklim global (20th century rainfall characteristic in Jakarta based on global climate events). Jurnal
Pola Hujan di bagian Hulu Daerah Aliran Sungai………………………………………….…… (Diah Auliyani dan Nining Wahyuningrum)
62 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Meteorologi Dan Geofisika, 14(3), 139–147. https://doi.org/10.31172/jmg.v14i3.165
Okpara, J. N., Afiesimama, E. A., Anuforom, A. C., Owino, A., & Ogunjobi, K. O. (2017). The applicability of standardized precipitation index: Drought characterization for early warning system and weather index insurance in West Africa. Natural Hazards, 89(2), 555–583. https://doi.org/10.1007/s11069-017-2980-6
Olanrewaju, R., Ekiotuasinghan, B., & Akpan, G. (2017). Analysis of rainfall pattern and flood incidences in Warri Metropolis, Nigeria. Geography, Environment, Sustainability, 10(4), 83–97. https://doi.org/10.24057/2071-9388-2017-10-4-83-97
Pramono, I. B., & Savitri, E. (2019). Modification method of drought vulnerability at Wonogiri District, Central Java, Indonesia. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8(6S3), 551–555. https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i6s3/F11080486S319.pdf
Setiawan, O. (2012). Analisis variabilitas curah hujan dan suhu di Bali. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 9(1), 66–79.
Spinoni, J., Naumann, G., Carrao, H., Barbosa, P., & Vogt, J. (2014). World drought frequency, duration, and severity for 1951-2010. International Journal of Climatology, 34, 2792–2804. https://doi.org/10.1002/joc.3875
Vernimmen, R. R. E., Hooijer, A., Mamenun, Aldrian, E., & Van Dijk, A. I. J. M. (2012). Evaluation and bias correction of satellite rainfall data for drought monitoring in Indonesia. Hydrology and Earth System Sciences, 16(1), 133–146. https://doi.org/10.5194/hess-16-133-2012
Wahyuningrum, N. (2016). Pengembangan model pendugaan aliran permukaan dan sedimen pada beberapa skenario penggunaan lahan pada Sub DAS Wuryantoro. http://etd.repository.ugm.ac.id/
Wahyuningrum, N., & Basuki, T. M. (2019). Analisis kekritisan lahan untuk perencanaan rehabilitasi lahan DAS Solo bagian hulu. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 3(1), 27–44. https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.27-44
Yulistyorini, A. (2011). Pemanfaatan air hujan sebagai alternatif pengelolaan sumberdaya air di perkotaan. Teknologi Dan Kejuruan, 34(1), 105–114. http://journal.um.ac.id/index.php/teknologi-kejuruan/article/view/3024
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.63-78
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 63
FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS BERBASIS MORFOMETRI UNTUK PRIORITAS PENANGANAN EROSI DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI OYO
(Fuzzy analytic hierarchy process based on watershed morphometry for erosion priority mapping in Oyo Sub Watershed)
Alfiatun Nur Khasanah 1 dan Arina Miardini 2 1Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada
Gedung SV UGM Sekip Unit 1 Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta 2Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Jl. A. Yani, Pabelan, P.O.BOX 295 Surakarta57102 Email: [email protected]
Diterima: 05 Februari 2020; Direvisi: 19 Mei 2020; Disetujui: 26 Juni 2020
ABSTRACT
Erosion is an indication of watershed degradation. In a watershed management, it is necessary to prioritize the handling that takes into account the characteristics of the watershed, one of which is morphometric character. This study aims to determine the priority location of erosion management in Oyo Watershed based on morphometric data using Fuzzy AHP modeling. Morphometric parameters that affect erosion are Rbm (bifurcation ratio), Rc (circulatory ratio), Dd (drainage density), T (texture), Su (Gradient) and Rn (Rugness Number). The highest value of the output shows the priority location that should be controlled. The high priority levels are found in 21 sub-watersheds with an area of 3,82 ha, medium levels are in 35 sub-watersheds with an area of 17,780.21 ha, low levels are in 106 sub-sub Watersheds with an area of 48,974.46 ha. The priority order for erosion management at the sub-watershed level is very important to prepare a watershed management plan in order to control soil erosion that is appropriate to protect the soil from further erosion.
Keywords: fuzzy-AHP; morphometry; priority; erosion; Oyo Sub-watershed
ABSTRAK
Erosi merupakan salah satu indikasi kerusakan DAS. Dalam pengelolaan DAS perlu dilakukan urutan prioritas penanganan dengan memperhatikan karakteristik DAS, salah satunya yaitu karakter morfometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi prioritas penanganan erosi di Sub DAS Oyo berdasarkan data morfometri dengan menggunakan pemodelan Fuzzy AHP. Parameter morfometrik yang mempengaruhi erosi adalah Rbm (bifurcation ratio), Rc (circulatory ratio), Dd (drainage density), T (texture), Su (gradient), dan Rn (rugness number). Nilai tertinggi dari hasil analisis menunjukkan lokasi prioritas yang harus didahulukan penanganan erosinya. Tingkat prioritas tinggi terdapat pada 21 sub-sub DAS dengan luas 3.82 ha, tingkat sedang pada 35 sub-sub DAS dengan luas 17.780,21 ha, tingkat rendah pada 106 sub-sub DAS dengan luas 48.974,46 ha. Urutan prioritas penanganan erosi pada tingkat sub DAS sangat penting untuk menyusun rencana pengelolaan DAS dalam
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
64 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
rangka pengendalian erosi tanah yang sesuai sebagai upaya perlindungan tanah dari erosi lebih lanjut.
Kata kunci: fuzzy-AHP; morfometri; prioritas; erosi; Sub DAS Oyo
I. PENDAHULUAN
Alih fungsi lahan dan pengelolaan
sumberdaya lahan yang tidak sesuai
dengan kaidah konservasi merupakan
salah satu penyebab terjadinya kerusakan
Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini
berdampak pada tingginya laju erosi
terutama di daerah hulu dan sedimentasi
pada bagian hilir (Miardini & Khasanah,
2017). Kerusakan DAS ditandai dengan
adanya penurunan fungsi hidrologi,
berkurangnya sumber daya air, tingginya
laju erosi tanah, rendahnya tutupan
vegetasi, dan terjadinya kerusakan
infrastruktur (Aglanu, 2014). Erosi memiliki
beragam faktor pemicu, salah satunya
adalah air hujan. Erosi lahan akibat air
merupakan proses rusaknya agregat tanah
menjadi fraksi yang lebih halus akibat
tekanan air hujan yang dipindahkan oleh
air aliran permukaan pada lereng bagian
atas menuju lereng bagian bawah
(Kasmawati, Hasanah, & Rahman, 2016).
Erosi membawa partikel sedimen yang
terbawa oleh aliran dan mengendap pada
bagian tertentu di sungai. Hal ini
berpengaruh pada penurunan daya
tampung sungai (Miardini, 2019).
Erosi merupakan masalah serius di
negara-negara berkembang yang memiliki
sumber daya teknis dan keuangan yang
terbatas (Hammad, 2009), termasuk di
Indonesia. Adanya keterbatasan tersebut
dapat disiasati melalui pemanfaatan
teknologi Penginderaan Jauh (PJ) dan
Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam
mengekstraksi parameter yang
berhubungan dengan erosi. Salah satunya
adalah melalui pendekatan geomorfologi
dengan analisis morfometri DAS.
Morfometri merupakan analisis kuantitatif
(matematis) dari suatu bentuk lahan
(Asfaw & Workineh, 2019). Morfometri
dapat menggambarkan perilaku hidrologi
dalam DAS, sehingga dapat digunakan
sebagai dasar pengelolaan saat data yang
tersedia tidak memadai (Gajbhiye, Mishra,
& Pandey, 2013).
Analisis morfometri mampu
memberikan gambaran mengenai kondisi
topografi DAS salah satunya adalah indeks
kemiringan. Indeks ini dapat membantu
dalam identifikasi risiko erosi dan
konservasi tanah dalam kaitannya dengan
pengelolaan sumber daya air (Mohammed,
Adugna, & Takala, 2018). Analisis ini juga
dapat membantu mengungkapkan fitur
penting DAS yang berhubungan dengan
proses hidrologi dan degradasi lahan,
sehingga sangat sesuai untuk menentukan
daerah yang mengalami kehilangan tanah
berat akibat erosi (Kadam et al., 2019).
Parameter morfometri yang dapat
menjelaskan tentang erosi antara lain:
nisbah percabangan (bifurcation ratio/Rb),
frekuensi sungai (stream frequency/Fs),
faktor bentuk DAS (form factor/Rf), nisbah
kebulatan (circularity ratio/Rc), rasio
elongasi (elongation ratio/Re), rasio
tekstur (texture ratio/T), koefisien
kekompakan (compactness coefficient/T),
rasio relief (relief ratio/Rh), panjang aliran
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 65
permukaan (length of overland flow/Lof),
dan kerapatan aliran (drainage density/
Dd) (Prabhakar, Singh, Lohani, &
Chandniha, 2019).
Penentuan prioritas sering dilakukan
dengan metode skoring dan pembobotan.
Pada kenyataannya, metode skor memiliki
kelemahan, di antaranya adalah kurang
memiliki landasan ilmiah yang kuat dalam
pembobotan atau bersifat subjektif dan
pemberian skor serta hasil akurasi peta
tergantung cara pemberian skor
(Malczewski, 2004). Metode ini juga sangat
sensitif terhadap perbedaan kelas
(Morgan, 2005). Pemodelan tidak akan
realistis apabila menggunakan metode
tersebut karena keterbatasan dari data
yang tersedia (baik dari segi temporal
maupun spasial), dan karena adanya
ketidakpastian dalam asosiasi di setiap
parameter.
Pengembangan metode kecerdasan
buatan (artificial intelegence) dapat
membantu dalam membuat simulasi
kondisi permukaan bumi yang bersifat
kompleks. Salah satu pemodelan dengan
sistem cerdas adalah dengan
menggunakan pendekatan Logika Fuzzy.
Logika tersebut diperkenalkan oleh Zadeh
(1965) dan merupakan perluasan dari teori
himpunan tegas (crisp) (Kusumawati &
Hartati, 2010). Ide dari Logika Fuzzy
(Zadeh, 1965) adalah dengan
mempertimbangkan objek spasial dalam
suatu peta menjadi suatu anggota dari satu
set data (Tangestani, 2009). Ambiguitas
dalam penilaian secara kualitiatif yang
bersifat subjektif dapat ditangani dengan
nilai probabilitas dan statistik berdasarkan
derajat keanggotaan Fuzzy (Govindan,
Khodaverdi, & Jafarian, 2013). Logika fuzzy
dapat dikombinasikan dengan Analytical
Hierarchy Proses (AHP) dan dikenal dengan
Fuzzy AHP (FAHP). FAHP telah digunakan
dalam penentuan potensi lokasi
penggurunan (Kacem et al., 2019),
pemodelan erosi (Haidara, Tahri, Maanan,
& Hakdaoui, 2019; Saha, Gayen,
Pourghasemi & Tiefenbacher, 2019) dan
potensi air tanah (Chaudhry, Kumar, &
Alam, 2019).
Berdasarkan latar belakang di atas,
tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui lokasi prioritas penanganan
erosi di Sub DAS Oyo berdasarkan data
morfometri dengan penilaian skor kriteria
menggunakan metode FAHP tersebut.
Urutan sub DAS prioritas penanganan erosi
berguna dalam penyusunan langkah-
langkah konservasi tanah dalam konsep
DAS berkelanjutan.
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
66 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilakukan pada tahun
2019 di Sub DAS Oyo yang merupakan
bagian dari DAS Opak-Oyo. Peta lokasi
penelitian ditunjukkan pada Gambar 1. Sub
DAS Oyo memiliki luas 77.047,19 ha
dengan lokasi dominan terdapat di
Kabupaten Gunungkidul (77,06%) dan
Kabupaten Bantul (13,85%). Berdasarkan
hasil pengolahan data oleh Khasanah &
Wicaksana (2019), Sub DAS Oyo memiliki
pola aliran dendritik dengan sebaran orde
sungai 1 hingga 8 dengan total panjang
aliran 3.099 km dan jumlah cabang sungai
sebanyak 8.575 cabang. Sub DAS Oyo
terdiri dari 157 sub DAS dengan luasan
antara 14,64 ha hingga 3.638,16 ha.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data morfometri Sub DAS Oyo
yang berasal dari ekstraksi DEM Nasional
(DEMNAS)1, tides.big.go.id. Data
morfometri merupakan hasil dari
penelitian sebelumnya (Khasanah &
Wicaksana, 2019). Selain itu, dibutuhkan
pula data peta jaringan sungai, jalan,
toponimi, dan batas administrasi dari Peta
Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000.
Peta RBI tersebut diperoleh melalui
halaman resmi Badan Informasi Geospasial
(BIG), tanahair.indonesia.go.id. Peta batas
DAS dan peta erosi untuk proses pemetaan
dan validasi model diperoleh dari Balai
Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
(BPDASHL) Serayu Opak Progo. Alat yang
digunakan adalah Software ArcGIS 10.2
Gambar (Figure) 1. Lokasi penelitian di Sub DAS Oyo (Research location in Oyo Sub-Watershed) Sumber (Source): Analisis data (Data analysis), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 67
untuk membuat peta, Software Microsoft
Excel untuk perhitungan FAHP, serta
Microsoft Word untuk penulisan jurnal.
C. Metode Penelitian
Metode FAHP yang diusulkan oleh Lu et
al. (2007) merupakan pengembangan dari
metode AHP oleh Saaty (2012).
Pengembangan dilakukan pada unsur
matriks penilaian antar parameter yang
diwakili oleh bilangan fuzzy (0-1)
sedangkan pada AHP menggunakan nilai
tegas (crisp value). Metode ini
menggunakan persamaan Triangular Fuzzy
Number (TFN) dengan mempertimbangkan
nilai terendah, nilai tengah, dan nilai
tertinggi dari matriks Saaty dalam satu
parameter. Pada umumnya terdapat tiga
komponen penting dalam penilaian AHP,
yaitu: (1) tujuan, (2) kriteria dan sub
kriteria, serta (3) pilihan. Pada penelitian
ini komponen tujuan, kriteria dan pilihan
secara berturut-turut adalah prioritas
penanganan erosi, parameter morfometri
terpilih dan sub-sub DAS Penelitian ini
merupakan modifikasi dari FAHP dengan
hanya mempertimbangkan pairwaise
comparison pada level kriteria. Prosedur
penggunaan FAHP berbeda dengan
prosedur pemetaan menggunakan metode
AHP, hal ini dikarenakan transformasi dari
nilai tegas menuju nilai fuzzy memiliki
beragam metode. Contohnya penelitian
yang dilakukan oleh Faisol et al. (2014) dan
Govindan et al. (2013) menggunakan
metode TFN pada data non spasial. Oleh
karenanya, uji coba perlu dilakukan untuk
menilai apakah prosedur TFN tersebut
dapat diterapkan pada data spasial.
Limitasi metode yang diterapkan pada
penelitian ini adalah penerapan FAHP
hanya pada level bobot kriteria oleh
karenanya pengembangan metode masih
perlu dilakukan.
Parameter morfometri yang digunakan
dalam penelitian ini mengacu pada
publikasi Khasanah & Wicaksana (2019).
Aspek morfometri dibagi menjadi: 1)
morfometri linier, 2) morfometri relief dan
3) morfometri area. Parameter morfometri
linier terdiri dari: orde sungai, panjang
sungai (Lu), rata-rata panjang sungai (Lsm),
Rasio Panjang Sungai (RL), dan bifurcation
ratio (Rb). Parameter morfometri relief
meliputi: basin relief (Bh), relief ratio (Rh)
dan ruggedness number (Rn). Parameter
morfometri area terdiri dari: drainage
density (Dd), stream frequency (Fs), texture
ratio (T), form factor (Rf), circularity ratio
(Rc), elongation ratio (Re), length of over
landflow (Lof), constant channel
maintenance (C), dan basin shape (BS).
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa
tahapan, yaitu:
1. Pemilihan Parameter (Kriteria)
Pemilihan parameter morfometri yang
berpengaruh terhadap proses erosi
dilakukan dengan melakukan studi literatur
serta pengujian korelasi. Jika dua
parameter memiliki korelasi tinggi (nilai
koefisien korelasi (r) > 0,5), maka hanya
akan dipilih salah satu sebagai input dalam
model. Korelasi dikatakan tinggi apabila
memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari
0,5 dan signifikansi lebih dari 0,05 (Hadi,
2015). Metode korelasi yang digunakan
adalah Pearson Correlation, dengan syarat
kriteria yang akan diuji terdistribusi secara
normal. Data morfometri terpilih yang
belum memenuhi syarat tersebut di
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
68 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
transformasikan ulang sehingga dapat
memenuhi asumsi distribusi normal, dan
hal ini tergantung pada jenis kurva
persebaran data. Transformasi dilakukan
dengan menggunakan metode Square Root
hingga memperoleh nilai signifikansi lebih
dari 0,05.
2. Penilaian Antar Parameter
Setiap parameter morfometri terpilih
akan dibandingkan dengan parameter
terpilih lainnya. Hasil pembandingan
tersebut digunakan sebagai acuan dalam
penilaian bobot. Penilaian dilakukan
menggunakan acuan dari tabel skoring
yang dikembangkan oleh Saaty (2012)
(Tabel 1) dengan modifikasi transformasi
dalam kurva triangular fuzzy (Gambar 2).
Gambar (Figure) 2. Kurva Nilai Keanggotaan Triangular
Fuzzy A (Triangular Fuzzy Membership Value Curve A)
Sumber (Source): Govindan et al., 2013
Penelitian ini tidak menguji Indeks
Konsistensi (CI) dan Rasio Konsistensi (CR)
dengan menguji konsistensi terhadap nilai
pembanding. Hal ini dikarenakan uji coba
yang dilakukan pada penelitian hanya
menggunakan satu masukan nilai.
Perhitungan CI dan CR dilakukan bila
terdapat sejumlah responden (lebih dari 1)
yang melakukan penilaian terhadap model.
Tabel (Table) 1. Deskripsi parameter morfometri terpilih (Description of morphometric parameter)
Parameter (Parameter) Rumus
(Formula) Sumber Data (Data source)
Referensi (Reference)
Linier Bifurcation Ratio (Rb) Rb = Nu/ (Nu-1)
Perhitungan Nu (jumlah segmen sungai) dan Nu+1 (Jumlah segmen sungai dengan orde yang lebih tinggi)
Schumn (1956)
Relief Ruggedness Number (Rn) Rn = Bh x Dd
Nilai Bh (basin relief) dan Dd (Kerapatan aliran)
Schumn (1956)
Texture Ratio (T) T = N1/P Perhitungan N1 (Jumlah sungai orde 1) dan P (keliling DAS)
Horton (1932)
Kemiringan Aliran (Su)
(Su) = (H85-H10)/ (0,75)Lb
Perhitungan gradien sungai rata – rata adalah dengan slope faktor
Benson (1962)
Area Kerapatan Aliran (Drainage Density/Dd)
Dd = Ln/A Perhitungan jumlah panjang semua sungai dibagi dengan luas DAS (km2)
Horton (1932)
Circularity Ratio (Rc) Rc = A/Adp
Perhitungan A (Luas DAS) dan Adp (Luas Lingkaran dengan Pb (km))
Cooke dan Dornkamp (1974)
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 69
…………………………(1)
3. Pengubahan Skor Antar Parameter
menjadi Nilai Keanggotaan Fuzzy
Setiap skor parameter yang digunakan
untuk pemodelan diubah ke dalam rentang
nilai fuzzy. Fuzzy set merupakan data
kontinum dengan nilai rentang 0 hingga 1.
Rentang keanggotaan yang bernilai 1
berarti parameter tersebut memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap erosi.
Fungsi keanggotaan fuzzy (Gambar 2)
ditentukan berdasarkan Persamaan 1
(Govindan et al., 2013). Nilai a, b dan c
merupakan skala penilaian antar
parameter pada Tabel 2. Apabila nilai
antara 2 kriteria adalah sangat penting,
maka nilai a,b, dan c berturut turut adalah
6,7,8.
Apabila terdapat dua fungsi triangular
atau dua nilai intensitas kepentingan pada
satu kriteria, misal fungsi A (a,b,c) dan B
(a1,b1,c1), maka fungsi matematika
(penjumlahan, perkalian, pembagian, dll)
yang berlaku dalam dua fungsi tersebut
dijelaskan dengan Persamaan 2, 3, 4, 5, 6,
dan 7 (Govindan et al., 2013). A dan B
dapat diasumsikan sebagai dua matriks
penilaian untuk 1 kriteria yang sama,
sehingga apabila terdapat 6 kriteria, maka
terdapat 6 (enam) matriks yang harus
diselesaikan.
A+B=(a,b,c)+(a1,b1,c1)(a+a1,b+b1,c+c).……………..(2)
A-B=(a,b,c)-(A1,b1,c1)(a-a1,b-b1,c-c1)………………..(3)
A*B=(a,b,c)*(A1,b1,c1)(a*a1,b*b1,c*c1)…………….(4)
A/B=(a,b,c) / (A1,b1,c1)(a/a1,b/b1,c/c1)…………….(5) K*B=(k*a,k*b,k*c) …………………………….……………….(6) (A)-1 =(1/c, 1/b, 1/a) …………………………….…………….(7)
Jarak dari fungsi keanggotaan A dan B dinilai
dengan Persamaan 8 (Govindan et al., 2013).
….(8)
Tabel (Table) 2. Skala penilaian antar parameter (Pair parameter assestment scale) Skala
(Scale) Intensitas kepentingan (Intensity of interest)
Keterangan (Information)
1,1,1 Sama Kedua elemen sama pentingnya dan mempunyai pengaruh yang sama
2,3,4 Sedikit Lebih Penting Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, penilainya sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lain.
4,5,6 Lebih Penting Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya, penilainya sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya.
6,7,8 Sangat Penting Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, elemen yang kuat disokong dan dominan.
9,9,9 Mutlak Penting Satu elemen mutlak lebih penting dibandingkan elemen lainnya,bukti pendukung elemen yang satunya terhadap yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi
1,2,3 3,4,5 5,6,7 7,8,9
Nilai Penengah Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, nilai ini diberikan bila ada dua komponen di antara dua pilihan.
1/n Kebalikan Jika untuk aktivitas 1 mendapatkan satu angka dibanding dengan aktivitas J, maka J mempunyai kebalikan dibandingkan i
Sumber (Source): Analis data (Data analysis), 2019
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
70 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
..(9)
4. Perhitungan Nilai Keanggotaan fuzzy
dengan Metode Geometric Means
Nilai keanggotaan fuzzy Geometric
Means untuk satu kriteria (A) terhadap
kriteria lainnya (B) dihitung berdasarkan
nilai perkalian menggunakan Persamaan 4
(Govindan et al., 2013). Proses ini
dilakukan untuk seluruh hasil penilaian di
setiap kriteria morfometri.
5. Normalisasi Nilai Bobot pada 1 (Satu)
Kriteria
Normalisasi nilai bobot untuk satu
kriteria dilakukan agar memiliki kombinasi
nilai kenggotan fuzzy antara 0-1. Caranya
dengan menjumlahkan nilai lower (a),
middle (b), dan upper (c) menggunakan
Persamaan 2. Hasil penjumlahan dari
seluruh nilai bobot pada enam kriteria
akan didapat nilai fuzzy total yang
digunakan untuk menormalisasi nilai bobot
fuzzy di tiap kriteria. Normalisasi (G) antara
bentuk keanggotaan fuzzy dari satu kriteria
(A) dengan jumlah keseluruhan nilai
keanggotaan fuzzy (p,q,r) dihitung dengan
Persamaan 9 (Govindan et al., 2013).
6. Defuzzyfikasi
Proses ini merupakan proses
mentransformasikan ulang nilai
keanggotaan fuzzy setiap elemen kriteria
ke dalam bobot tegas (W) menggunakan
rumus rata-rata Center of Area (COA) pada
Persamaan 10. Jumlah dari keseluruhan
bobot dinormalisasikan kembali untuk
mendapat total bobot sebesar 1.
Normalisasi dilakukan dengan membagi
nilai bobot (W) dengan jumlah bobot
keseluruhan elemen kriteria. Govindan et
al. (2013) melakukan pembobotan pada
level alternatif kriteria namun pada
penelitian ini hanya terbatas pada level
kriteria disebabkan keterbatasan telaah
pustaka terkait hubungan secara langsung
antara kelas pada masing masing kriteria
morfometri dengan laju erosi.
…………………………………………(10)
7. Reklasifikasi: Penilaian Prioritas
Penanganan
Penentuan prioritas penanganan
erosi pada masing-masing sub-sub DAS
didasarkan pada hasil perkalian antara
bobot dengan nilai kriteria. Hasil penilaian
bobot pada tahap 6 (Persamaan 10)
diaplikasikan ke dalam data kriteria
morfometri, sehingga diperoleh hasil
berupa skor prioritas pada setiap sub-sub
DAS. Klasifikasi prioritas penanganan
dilakukan dengan membagi area menjadi 3
kelas dengan metode equal interval. Selisih
nilai maksimum dan nilai minimum dibagi
dengan jumlah kelas yang diinginkan (3
kelas) untuk mendapatkan interval kelas.
Prioritas tinggi merupakan sub-sub DAS
dengan nilai skor mendekati maksimum.
Diagram alir dari penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar 3
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 71
Gambar (Figure) 3. Diagram alir penelitian (Research flow chart)
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pemilihan Kriteria
Rangkuman hasil penilaian morfometri
untuk 6 kriteria yang terpilih (Rbm, Rc, Dd,
T, Rn, dan Su) dapat dilihat pada Tabel 3.
Nilai tersebut didapat dari penelitian
Khasanah & Wicaksana (2019). Uji korelasi
antar parameter morfometri dilakukan
untuk mendapatkan nilai hubungan antara
masing masing parameter. Syarat uji ini
adalah data terdistribusi secara normal.
Proses transformasi data dilakukan agar
data dapat memenuhi persyaratan
tersebut. Berdasarkan hasil uji korelasi
(Tabel 4) dapat diketahui bahwa variabel
morfometri terpilih memiliki korelasi yang
rendah (r < 0,05) dengan berbeda nyata
pada taraf uji 5%. Hal ini menunjukkan
bahwa masing masing kriteria tidak saling
mempengaruhi satu sama lainnya sehingga
kriteria terpilih tersebut dapat dijadikan
sebagai acuan dalam input pemetaan.
Nilai rata-rata nisbah percabangan sungai (RBm) berhubungan dengan pelolosan air sebagai agen erosi.Nilai ini menunjukkan integrasi antara segmen sungai pada orde yang berbeda (Guatemala et al, 2017)dan berhubungan dengan struktur geologi serta kondisi iklim dalam DAS. Hasil nilai RBm di Sub DAS Oyo bervariasi dari nilai 1 hingga 6,7. Nilai tersebut mengindikasikan bervariasinya pengaruh faktor geologi pada masing masing sub-sub DAS. Nilai RBm tinggi ( >5) menunjukkan bahwa limpasan air permukaan tinggi sejalan dengan
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
72 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 3. Nilai koefisien korelasi antar parameter terpilih (Coefficient correlation value of selected parameter)
RBm RC DD T Su Rn
RBm Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
1
150
-.169’ .038 150
-.007 .934 150
.135
.101 150
-.096 .243 150
.001
.987 150
RC Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
-.169’ .038 150
1
150
-.134 .102 150
-.055 -502 150
.185’ .024 150
-.049 .555 150
DD Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
-.007 .934 150
-.134 .102 150
1
150
.314” .000 150
.005
.952 150
.227” .005 150
T Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.135
.101 150
-.055 .502 105
.314” .000 150
1
150
-.187’ .022 150
.556” .000 150
Su Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
-.096 .243 150
-.185’ .024 150
.005
.952 150
-.187’ .022 150
1
150
.487” .000 150
Rn Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
.001
.987 150
-.049 .555 150
.227” .005 150
.556” .000 150
.487” .000 150
1
150
Sumber (Source): Khasanah & Wicaksana (2019).
banyaknya anak sungai yang terbentuk
(Gajbhiye & Ashish, 2014), kenaikan muka
air dapat terjadi secara cepat dengan
penurunan muka air yang cepat pula.
Bentuk DAS, diwakili oleh kriteria nisbah
kebulatan (Rc) yang dipengaruhi oleh
panjang dan frekuensi aliran, struktur
geologi, penggunaan lahan/tutupan lahan,
iklim, dan kemiringan DAS (Gajbhiye &
Ashish, 2014). Nilai Rc berkisar antara 0-1.
Semakin besar nilai tersebut maka DAS
akan memiliki bentuk mendekati bulat
sempurna. Perhitungan ini menghasilkan
nilai bentuk DAS yang bervariasi. Sebagian
besar DAS memiliki bentuk irregular
dengan nilai nisbah sebesar 0,4-0,8.
DAS dengan nilai Dd rendah dan
didominasi sungai Ordo 1 cenderung
memiliki limpasan permukaan yang tinggi,
sehingga meningkatkan risiko banjir, erosi,
dan tanah longsor (Chandramohan &
Vijaya, 2016). Dd menggambarkan jarak
antar percabangan sungai. Hasil
perhitungan didapat bahwa nilai Dd
berkisar antara 2-5,8 km/km2. Nilai
tersebut termasuk ke dalam kategori
sedang dan secara keseluruhan sub DAS
memiliki nilai Dd pada rentang ini. Artinya,
pada kondisi ini alur sungai melewati
batuan dengan resistensi yang lebih lunak
sehingga sedimen yang terangkut menjadi
lebih besar.
Rasio tekstur (T) berhubungan dengan kapasitas infiltrasi dan frekuensi aliran yang menyiratkan besarnya risiko erosi tanah (Albaroot, Al-areeq, Aldharab, Alshayef, & Ghareb, 2018). Kemiringan DAS merupakan salah satu faktor terpenting untuk identifikasi zona erosi yang berafiliasi dengan karakteristik morfometri seperti rasio panjang aliran, rasio elongasi, jumlah aliran permukaan, dan rasio relief (Saranaathan & Manickaraj, 2017). Ruggedness number (Rn) merupakan derivasi dari Dd dan H yang berguna untuk menilai kecuraman dan kemiringan jaringan drainase. Nilai Rn yang tinggi menunjukkan kerentanan erosi tanah yang lebih tinggi (Albaroot et al., 2018).
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 73
b. Perhitungan Bobot FAHP
Percobaan perhitungan bobot FAHP
menggunakan metode triangular fuzzy
hanya dilakukan pemberian bobot pada
level kriteria. Perhitungan bobot
parameter morfometri menggunakan
teknik ini dimulai dengan memberikan
asumsi skor 1 hingga 9 bergantung pada
kekuatan hubungan antar dua kriteria.
Hasil penilaian didasarkan pada
pengetahuan pakar, namun pada
penelitian ini didasarkan pada telaah
pustaka. Hasil penilaian menggunakan
metode Saaty (2012) dapat dilihat
padaTabel 4. Semakin tinggi skor, maka
aspek morfometri terkait lebih
berpengaruh terhadap laju erosi
dibandingkan kriteria lain.
Nilai pada Tabel 4 diubah menjadi nilai
fuzzy dengan mempertimbangkan grafik
linier dari pengaruh morfometri terhadap
erosi. Proses ini masuk dalam penilaian
antar parameter morfometri dengan
mempertimbangkan modifikasi
transformasi dalam kurva triangular fuzzy
(Tabel 2). Hasil dari proses fuzzyfikasi dan
hasil perhitungan bobot akhir dapat dilihat
berturut-turut pada Tabel 5 dan Tabel 6.
Tabel (Table) 4. Analisis perbandingan antar kriteria menggunakan Skor Saaty (Comparative analysis between variables using Saaty Score)
Aspek morfometri (Morphometric aspects)
Rbm (Mean bifurcation
ratio)
Rc (Circularity
ratio)
Dd (Drainage density)
T (Drainage texture)
Su (Gradient)
Rn (Ruggedness
number)
Rbm (Mean bifurcation ratio)
1 5 3 6 1/4 1/5
Rc (Circularity ratio)
1/5 1 1/6 1/4 1/6 1/7
Dd (Drainage density)
1/3 6 1 2 1/4 1/6
T (Drainage texture)
1/6 4 1/2 1 1/6 1/8
Su (Gradient)
4 6 4 6 1 1/3
Rn (Ruggedness number)
5 7 6 8 3 1
Sumber (Source): Analis data (Data analysis), 2019
Tabel (Table) 5. Hasil fuzzyfikasi nilai Skor Saaty (Fuzzyfication results Score Saaty)
Aspek morfometri (Morphometric aspects)
Rbm (Mean bifurcation
ratio)
Rc (Circularity
ratio)
Dd (Drainage density)
T (Drainage texture)
Su (Gradient)
Rn (Ruggedness
number)
Rbm (Mean bifurcation ratio)
1 4,5,6 2,3,4 5,6,7 1/3,1/4,1/5
1/4,1/5,1/6
Rc (Circularity ratio)
1/4,1/5,1/6 1 1/5,1/6,1/
7 1/3,1/4,1/5
1/5,1/6,1/7
1/6,1/7,1/8
Dd (Drainage density)
1/2,1/3,1/4 5,6,7 1 1,2,3 1/3,1/4,1/5
1/5,1/6,1/7
T (Drainage texture)
1/5,1/6,1/7 3,4,5 1/1,1/2,1/
3 1
1/5,1/6,1/7
1/7,1/8,1/9
Su (Gradient)
3,4,5 5,6,7 3,4,5 5,6,7 1 1/2,1/3,1/4
Rn (Ruggedness number)
4,5,6 6,7,8 5,6,7 7,8,9 2,3,4 1
Sumber (Source): Analis data (Data analysis), 2019
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
74 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 6. Perhitungan bobot pada parameter terpilih (Calculation of weight on
selected parameters)
Aspek Morfometri (Morphometric aspects)
NIlai rata-rata Fuzzy Geometrik (Fuzzy geometric mean value)
Bobot Fuzzy (Fuzzy
Weight)
Bobot rata-rata
(Mean weight)
1 2 3 1 2 3
Rbm (Mean bifurcation ratio)
1.222 1.285 1.333 0.145 0.139 0.118 0.13
Rc (Circularity ratio)
0.286 0.242 0.209 0.034 0.026 0.018 0.03
Dd (Drainage density)
0.742 0.742 0.729 0.088 0.080 0.064 0.08
T (Drainage texture)
0.508 0.437 0.395 0.060 0.047 0.035 0.05
Su (Gradient)
2.197 2.402 2.596 0.261 0.259 0.229 0.25
Rn (Ruggedness number)
3.448 4.141 6.036 0.410 0.448 0.534 0.46
8.404 9.247 11.298 1
Sumber (Source): Analis data (Data analysis), 2019
c. Penentuan Prioritas Penanganan Erosi
Nilai tertinggi dari output menunjukkan
prioritas yang harus didahulukan
penanganan erosinya. Hasil dari
pembobotan tersebut diklasifikasikan
menjadi 3 tiga zona prioritas, yaitu: 1)
prioritas tinggi (> 32), 2) prioritas sedang
(32-16.2), dan 3) prioritas rendah (< 16.2).
Prioritas tinggi menunjukkan adanya
tingkat erosi tanah yang tinggi dan
merupakan sub-sub DAS area potensial
untuk menerapkan tindakan konservasi
tanah, sehingga perlu penanganan terlebih
dahulu. Pada Sub DAS Oyo terdapat 21
sub-sub DAS dengan luas total 3.823,47 ha
yang merupakan prioritas tinggi. Pada
kelas prioritas sedang terdapat sekitar 35
sub-sub DAS dengan luas 17.780,21 ha,
sedangkan prioritas rendah terdapat pada
94 sub-sub DAS dengan luas 48.974,46 ha.
Daftar sub-sub DAS prioritas penanganan
erosi dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar (figure) 4. Sub sub DAS prioritas penanganan erosi di Sub DAS Oyo (Priority management of erosion
sub-watersheds in Oyo Sub-watershed)
Sumber (Source): Analis data (Data analysis), 2019
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 75
Sub-sub DAS yang memiliki nilai total
penilaian prioritas penanganan erosi
tertinggi antara lain: 1) Sub-sub DAS Oyo
turunan 3 meliputi Desa Banyusuko
(214,94 ha) dan Girisuko (29,29 ha)
Kecamatan Paliyan Kabupaten
Gunungkidul, 2) Sub-sub DAS Oyo Turunan
2 meliputi Desa Banyusuko (46,23 ha) dan
Girisuko (39,56 ha) Kecamatan Paliyan
Gunung Kidul, dan 3) Sub-sub DAS Oyo
Dayaan meliputi Desa Mangunan
Kecamatan Dlingo Bantul (0,10 ha),
Selopamioro Kecamatan Purwosari Bantul
(52,69 ha), dan Desa Girisuko Kecamatan
Paliyan Gunung Kidul (98,07 ha).
IV. KESIMPULAN
Parameter penentu prioritas
penanganan erosi pada 150 sub-sub DAS di
Sub DAS Oyo secara berurutan dari yang
paling besar pengaruhnya adalah aspek
kekasaran permukaan, kemiringan sungai,
rerata rasio bifurkasi, kerapatan aliran,
tekstur aliran, dan rasio kebulatan.
Penentuan prioritas penanganan
diperlukan dari sisi manajemen
untukuntuk mengalokasikan sumber daya
yang bersifat terbatas sehingga dapat lebih
efektif dalam mengatasi masalah erosi.
Sub-sub DAS prioritas tinggi teridentifikasi
sebanyak 21 sub-sub DAS dengan
karakteristik morfometri memiliki bentuk
iregular dan nilai kerapatan drainase yang
cenderung sedang, relief beragam dari
landai hingga curam, sehingga memiliki
potensi aliran permukaan dan erosi yang
besar. Kombinasi parameter morfometri
dapat digunakan dalam menentukan lokasi
prioritas penanganan erosi pada tingkat
sub-sub DAS, namun kajian ini masih perlu
penelitian lanjutan mengenai perhitungan
bobot pada setiap sub kriteria dan uji
akurasi untuk meningkatkan hasil
permodelan sebagai data masukan dalam
pemodelan menggunakan FAHP.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada Sekolah
Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun
2019 dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak
Progo Solo atas dukungan data.
DAFTAR PUSTAKA
Aglanu, L. M. (2014). Watersheds and Rehabilitations Measures - A Review, Resources and Environment.4(2), 104–114. https://doi.org/10.5923/j.re.20140402.04
Asfaw, D., & Workineh, G. (2019). Quantitative analysis of morphometry on Ribb and Gumara watersheds: Implications for soil and water conservation. International Soil and Water Conservation Research, 7(2), 150–157. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2019.02.003
Albaroot, M., Al-areeq, N. M., Aldharab, H. S., Alshayef, M., & Ghareb, S. A. (2018). Quantification of Morphometric Analysis using Remote Sensing and GIS Techniques in the Qa ’ Jahran Basin , Thamar Province Yemen. International Journal of New Technology and Research (8), 12–22.
Chandramohan, K., & Vijaya, R. (2016). An analysis of geomorphic quantitative study of bifurcation ratio and drainage pattern by using remote sensing and GIS techniquae: a case study in Sirumalai Hill Environs, Tamil
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
76 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Nadu, India. African Journal of Geo-Science Research, 4(1), 12–15.
Chaudhry, A. K., Kumar, K., & Alam, M. A. (2019). Mapping of groundwater potential zones using the fuzzy analytic hierarchy process and geospatial technique. Geocarto International, 1–22. https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1695959
Faisol,A.,Muslim,M.A.,Suyono,H. (2014).Komparasi Fuzzy AHP dan AHP pada sistem pendukung keputusan investasi properti. Jurnal EECCIS 8 (2)
Gajbhiye, S., Mishra, S., & Pandey, A. (2013). Effects of Seasonal/Monthly Variation on Runoff Curve Number for Selected Watersheds of Narmada Basin. International Journal of Environmental Sciences Vol 3, No 6: 2019-2020.
Gajbhiye, S., & Ashish, S. K. M. (2014). Prioritizing erosion-prone area through morphometric analysis : an RS and GIS perspective. Applied Water Science 4: 51–61. https://doi.org/10.1007/s13201-013-0129-7
Cooke, R.U. dan Doorkamp, J.C. 1974. Geomorpology in Environment Management, An Introduction. Oxford.Clarendon Press.
Govindan, K., Khodaverdi, R., & Jafarian, A. (2013). A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach. Journal of Cleaner Production, 47, 345–354. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.014
Hadi, Sutrisno. (2015). Statistik (Edisi
Revisi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Haidara, I., Tahri, M., Maanan, M., &
Hakdaoui, M. (2019). Efficiency of
Fuzzy Analytic Hierarchy Process to
detect soil erosion vulnerability.
Geoderma, Vol. 354.
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.
2019.07.011
Hammad, A. A. (2009). Watershed erosion risk assessment and management utilizing revised universal soil loss equation-geographic information systems in the Mediterranean environments, Water and Environment Journal 1–14. https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2009.00202.x
Horton, R.E. 1932. Drainage Basin Characteristics. Tansactions of American Geophysical Association, 13,pp. 350-36.1
Kacem, H. A., Fal, S., Karim, M., Alaoui, H. M., Rhinane, H., & Maanan, M. (2019). Application of fuzzy analytical hierarchy process for assessment of desertification sensitive areas in North West of Morocco. Geocarto Internationa, 1–18. https://doi.org/10.1080/10106049.2019.1611949
Kadam, A. K., Jaweed, T. H., Kale, S. S., Bhavana, N., Sankhua, R. N., Kadam, A. K., … Kale, S. S. (2019). Identification of erosion-prone areas using modified morphometric prioritization method and sediment production rate : a remote sensing and GIS approach. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 986–1006. https://doi.org/10.1080/19475705.2018.1555189
Kasmawati, Hasanah, U., & Rahman, A. (2016). Prediksi erosi pada beberapa penggunaan lahan di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Agrotekbis, 4(6), 659–666.
Kusumadewi, S. dan Hartanti, S., 2010, Neuro-Fuzzy Integrasi Sistem Fuzzy
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 63-78
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 77
dan Jaringan Syaraf Tiruan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Lu,Je dan Zang,G.,2006 Multi-Objective Group Decision Making Methods, Software and Applications With Fuzzy Set Technique. London : Imperial Colledge Press
Malczewski, J., 2004, “GIS-Based Land-Use Suitability Analysis: A Critical Overview”. Journal Progress in Planning, Vol. 62, hal: 3-64.
Miardini, A., & Khasanah, alfiatun nur. (2017). Penentuan prioritas penanganan serta upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam pengendalian erosi dan sedimentasi di Sub DAS Slahung. Prtosiding Seminar Nasional Ke-3 Pengelolaan Pesisir Dan DAS.
Miardini, A. (2019). Dinamika bentukan lahan fluvial akibat sedimentasi di sungai Grindulu, segmen Arjosari-Pacitan.Jurnal Penelitian Pengelolaan DAS, Vol. 3 No. 1, 13-25. doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.13-26
Mohammed, A., Adugna, T., & Takala, W. (2018). Morphometric analysis and prioritization of watersheds for soil erosion management in Upper Gibe catchment. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 6(1), 1419–1426. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2018.061.1419
Prabhakar, A. ., Singh, K. ., Lohani, A. K., & Chandniha, S. K. (2019). Study of Champua watershed for management of resources by using morphometric analysis and satellite imagery. Applied Water Science, 9(5), 1–16. https://doi.org/10.1007/s13201-019-1003-z
Morgan, R.C.P., 2005,Soil Erosion and Conservation Third Edition, Amerika : Blackwell Publishing.
Saaty, T., & Vargas, L. (2012). Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process. In … -Driven Demand and Operations Management Models (Vol. 175). https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3597-6
Saha, S., Gayen, A., Pourghasemi, H. R., & Tiefenbacher, J. P. (2019). Identification of soil erosion-susceptible areas using fuzzy logic and analytical hierarchy process modeling in an agricultural watershed of Burdwan district, India. Environmental Earth Sciences, 78(23), 1–18. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8658-5
Saranaathan, S. ., & Manickaraj, S. (2017). Morphometric Analysis approach for Recharge and Soil Erosion potential in Morphometric Analysis approach for Recharge and Soil Erosion Potential in Agaram Watershed , Javadi Hill Range , Vellore District , Tamil Nadu , India. International Journal of Earth Sciences and Engineering, 10(2), 298–303. https://doi.org/10.21276/ijee.2017.10.0222
Schumm, S.A. 1956. Evolution of Drainage Systems and Slopes in Badlands at Perth Amboy. Geological Society of America, New Jersey. Vol .67
Tangestani, M. H. (2009). A comparative study of Dempster-Shafer and fuzzy models for landslide susceptibility mapping using a GIS: An experience from Zagros Mountains, SW Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 35(1), 66–73. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2009.01.002
Zadeh, L.A., 1965, Fuzzy Set, Journal
Information and Control, Vol. 8, hal:
338-353.
Fuzzy Analytic Hierarchy Process Berbasis Morfometri…………………………………… (Alfiatun Nur Khasanah dan Arina Miardini)
78 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Halaman ini sengaja dibiarkan kosong
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097 doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2020.4.1.79-102
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 79
APLIKASI METODE SIDIK CEPAT JASA LINGKUNGAN PADA DAS MIKRO
(Rapid assessment method of environmental services in the micro catchment)
Anang Widicahyono1, San Afri Awang2, Ahmad Maryudi2, dan M. Anggri Setiawan3 1Program Doktor Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
2Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta, 55281 3Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Sekip Utara Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281 4Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt.13 Jl. Gatot Subroto-Jakarta 10270 Email:[email protected]
Diterima: 11 September 2018; Direvisi: 15 Juni 2020; Disetujui: 22 Juni 2020
ABSTRACT
Watershed areas are used for a variety of environmental services that become a basic framework for
watershed management activities. This study aims to develop and apply the rapid identification and
assessment of environmental services at micro catchment level at Cebong Sub-watershed, Wonosobo
Regency. This study uses three basic principles: (i) spatial and inter-regional relationships, (ii) causal
relationship mechanism, and (iii) potential and impact values. This method is a combination of
spatial analysis using Geographic Information Systems, causal relationship analysis using systems
thinking, and economic valuations. The results indicated that the diversity of environmental services
in the Cebong Sub-watershed are in the forms of: 1) provision services for food and water sources; 2)
regulatory services for carbon stocks, and erosion and sedimentation control, 3) habitat services for
biodiversity, and 4) cultural services for tourism. As food supply services, potato farming provides the
highest benefit value although generate other potential environmental services. As cultural services,
tourism share lower value of direct benefits, but support the sustainable use of environmental
services in the watershed. This is an initiative research to develop a technical guide in managing the
micro catchment based on environmental services.
Keywords: rapid assesment method; environmental services; micro-catchment
ABSTRAK
Wilayah DAS terbagi habis oleh ekosistem dengan keragaman jasa lingkungan yang dapat
dijadikan sebagai kerangka dasar kegiatan pengelolaan DAS. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan serta mengaplikasikan metode sidik cepat identifikasi dan penilaian jasa
lingkungan pada level DAS mikro di Sub DAS Cebong, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini
menggunakan tiga prinsip dasar: (i) spasial dan hubungan antar wilayah, (ii) mekanisme
hubungan sebab akibat, serta (iii) nilai potensi dan dampak. Metode sidik cepat jasa
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ……......…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
80 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
lingkungan merupakan kombinasi analisis spasial dengan pemanfaatan Sistem Informasi
Geografis, analisis hubungan sebab akibat dengan metode system thinking, serta valuasi
ekonomi. Hasil identifikasi sidik cepat menunjukkan keragaman jasa lingkungan di Sub DAS
Cebong berupa: 1) jasa penyediaan dengan jasa utama sumber makanan dan air domestik,
2) jasa regulasi dengan jasa utama cadangan karbon dan pengendalian erosi sedimentasi, 3)
jasa habitat dengan jasa utama biodiversitas, dan 4) jasa budaya dengan jasa utama
pariwisata. Jasa penyediaan makanan dalam bentuk pertanian kentang memberikan nilai
manfaat paling tinggi, namun memunculkan penurunan potensi jasa lingkungan lainnya.Jasa
budaya berupa pariwisata, meskipun nilai manfaat langsungnya lebih rendah, namun dapat
mendukung keberlanjutan pemanfaatan jasa lingkungan di dalam DAS. Penelitian ini
menjadi sebuah inisiasi petunjuk teknis rencana pengelolaan DAS mikro berbasis jasa
lingkungan.
Kata kunci: metode sidik cepat; jasa lingkungan; DAS Mikro
I. PENDAHULUAN
Konsep Daerah Aliran Sungai (DAS)
telah menjadi salah satu instrumen dalam
pembangunan nasional yang
berkelanjutan (Paimin et al., 2012; Ratna
Reddy et al., 2017). Penerapan
pengelolaan DAS di Indonesia memiliki
beberapa tantangan dan kesulitan dalam
penerapannya. Permasalahan tersebut
mencakup kompleksitas permasalahan
kondisi DAS seperti peningkatan erosi,
sedimen, banjir, longsor, dan pencemaran
air (Karuniasa & Prambudi, 2019). Potensi
DAS yang belum dimanfaatkan secara
berkelanjutan. Millennium Ecosystem
Assessment (MEA) menyimpulkan dua
pertiga (2/3) jasa lingkungan yang terkait
dengan kesejahteraan manusia sedang
mengalami degradasi atau dimanfaatakan
secara tidak berkelanjutan (MEA, 2005)
Pengelolaan DAS membutuhkan suatu
pendekatan spatial-temporal yang
interaktif dengan analisis pengelolaan
dimulai dari skala regional menuju skala
detail. Untuk mengatasi masalah tersebut
diperlukan pendekatan kolaboratif kondisi
fisik DAS dengan kondisi sosial, ekologi
DAS. Sudah saatnya kebijakan
pengelolaan DAS betul-betul dipahami
dan diterapkan pada level yang lebih kecil
yaitu DAS Mikro (<5000 Ha) (Marshall&
Bayliss, 1994).
Pengelolaan DAS bukan semata
mengelola sumberdaya, namun lebih
kepada mengelola aktivitas manusia
karena akan berdampak pada kelestarian
sumberdaya yang tersedia (Salampessy &
Lidiawati, 2017). Pada level desa,
masyarakat telah mendapatkan dan
terlibat langsung pada kegiatan-kegiatan
kolaboratif pengelolaan DAS, namun pada
kenyataannya mereka hanya melihat
bentuk sosialisasi hingga bantuan
infrastruktur yang didapat tanpa
memahami peranannya secara langsung
pada proses pengelolaan DAS (Jariyah,
2014; Napitupulu et al., 2014).
Pendekatan yang digunakan dalam
pengelolaan DAS masih terlalu
berorientasi pada keberadaan dan
intensitas masalah. Penentuan sebuah
DAS masuk kategori “dipertahankan”
ataupun “dipulihkan” didasarkan pada
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 81
berbagai indikasi degradasi ataupun
kebencanaan. Konsekuensi logisnya
adalah kebijakan pengelolaan DAS selalu
diarahkan untuk mengatasi berbagai
dampak yang ditimbulkan oleh masalah
lingkungan erosi (Setiawan, 2012; Paimin
et al., 2012, Sihite, 2001), banjir
(Sudaryono, 2012), tanah longsor
(Halengkara et al., 2012), kekeringan
(Legowo, 2005; Falah & Purwanto, 2018),
hingga lemahnya fungsi kelembagaan
(Ulya et al., 2017). Implementasi
pengendalian permasalahan tersebut
seringkali banyak mengalami kendala
karena harus berbenturan dengan
kebutuhan pemenuhan ekonomi dan
sosial budaya masyarakat (Ulya et al.,
2017). Sebagai contoh, program
rehabilitasi hutan lahan pada area
pertanian intensif sebagai sumber erosi
dan limpasan, tidak berjalan optimal
karena harus berhadapan dengan pola
tanam masyarakat lokal (Hafizi et al.,
2016).
Pada kenyataannya, komponen dari
DAS tidak hanya berisi “masalah”, namun
juga memiliki sisi “potensi” (Ulya et al.,
2017). Potensi DAS berupa ekosistem
yang menyimpan berbagai sumberdaya
yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
lokal. Ekosisitem dalam DAS bervariasi
dalam hal kompleksitas, ukuran, dan
fungsinya yang digunakan manusia
melalui pemanfaatan jasa lingkungan
(TEBB, 2010). Ekosistem menyediakan
berbagai layanan jasa lingkungan yang
dapat dikategorikan sebagai penyediaan,
pengaturan, dan layanan budaya (CICES,
2013; Haines-Young & Potschin, 2013;
Mustajoki et al., 2020). Paradigma
pengelolaan DAS seharusnya berlaku
secara proposional dari sisi pengendalian
masalah dan optimalisasi potensi jasa
lingkungan DAS (Dasrizal et al., 2012;
Indrawati, 2016).
Perkembangan penelitian terkait jasa
lingkungan sudah banyak dilakukan (Groot
et al., 2017). Pada umumnya penilaian
jasa lingkungan selalu dikaitkan dengan
kerangka imbal jasa lingkungan sebagai
mekanisme untuk mempromosikan
praktik penggunaan lahan, sarana
konservasi yang ramah lingkungan dan
efisien (Garcia-Amando et al., 2011;
Kaplowitz et al., 2012; Wegner, 2016). Di
Indonesia,belum banyak penelitian yang
mengkaitkannya secara langsung untuk
dasar pengelolaan DAS mikro. Penelitian
ini memiliki tujuan utama untuk
mengembangkan serta mengaplikasikan
sebuah metode sidik cepat untuk
identifikasi dan penilaian jasa lingkungan
pada level DAS mikro.
Metode yang dikembangkan dalam
penelitian diterapkan pada sebuah DAS
mikro yang terletak pada salah satu DAS
yang memiliki variasi jenis ekosistem dan
pemanfaatan lahan. Di dalam penelitian
ini, beberapa prinsip dasar digunakan
untuk merumuskan tahapan metode dan
kerangka analisis yang sistematis.
Keberadaan metode sidik cepat ini
merupakan sebuah inisiasi penting untuk
sinkronisasi konsep pengelolaan DAS
dalam proses pembangunan desa yang
berkelanjutan.
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ……......…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
82 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan
Januari sampai dengan September tahun
2017. Lokasi penelitian dilakukan di Sub
DAS Cebong (104,49 ha) yang terletak di
Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar
Kabupaten Wonosobo (Gambar 1). Secara
astronomis, Sub DAS Cebong terletak
antara 7o14’29,85” LS - 7o14’33,78” LS dan
109o55’30,31”BT-109o54’51,99” BT.
Wilayah ini merupakan bagian hulu dari
DAS Serayu yang telah ditentukan sebagai
DAS Prioritas Nasional (RPJMN Tahun
2015-2019 & SK Menhut No
SK.328/MenhutII/2009).
Dibandingkan dengan daerah lainnya
di dalam DAS Serayu, Sub DAS Cebong
memiliki keragaman ekosistem yang lebih
lengkap terdiri dari hutan lindung, lahan
pertanian, danau, dan permukiman.Di
samping itu, kawasan hutan lindung yang
dikelola Perum Perhutani saat ini telah
dikelola bersama masyarakat menjadi
salah satu ikon obyek wisata yang cukup
terkenal di Dieng, yaitu Golden Sunrise di
Gunung Sikunir.
Gambar (figure) 1. Lokasi DAS Mikro Cebong, Desa
Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
Sumber (Source): BPDASHL Serayu Opak Progo, 2017.
B. Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuisioner, alat tulis,
kamera, recorder, laptop, perangkat lunak
Arc Gis, peta rupa bumi Indonesia tahun
2017, citra google earth/ citra Sas Planet
dan data DEM SRTM.
Kuisioner digunakan sebagai pedoman
wawancara selama pengambilan data di
lapangan. Kamera dan recorder digunakan
untuk dokumentasi dan perekaman data
melalui wawancara mendalam. Peta rupa
bumi Indoensia, citra google earth, dan
DEM SRTM digunakan untuk membuat
peta lokasi penelitian dan untuk
menganalisis tutupan lahan di lokasi
kajian. Laptop dan software arcGIS
digunakan untuk mengolah data yang
telah dikumpulkan.
C. Metode
Kajian jasa lingkungan yang bertujuan
untuk menyediakan data yang
komprehensif pada level DAS mikro tidak
cukup hanya dibatasi pada upaya
penyediaan data terkait besaran nilai
manfaat ekonomi. Prinsip utama yang
perlu diperhatikan di dalam kajian jasa
lingkungan pada suatu DAS mikro antara
lain: i) spasial dan hubungan antar
wilayah, ii) hubungan sebab akibat antara
proses dan hasil proses pemanfaatan jasa
lingkungan, dan iii) nilai manfaat dan
dampak. Keberadaan ketiga prinsip
tersebut dapat menjadi data dasar dalam
pembangunan yang berkelanjutan di
dalam cakupan DAS yang dikaji.
Prinsip spasial dan hubungan antar
wilayah akan memberikan gambaran
secara utuh mengenai keberadaan dan
karakteristik DAS mikro yang dilihat pada
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 83
skala regional (misalnya: posisi terhadap
DAS utama, iklim, genesis bentukahan,
material batuan ataupun tanah,
administrasi, hingga sosial budaya)
ataupun skala detail di dalam DAS mikro
(jenis, batas, luas, jumlah, hingga
distribusi dari jasa lingkungan).
Penggunaan prinsip yang kedua dan
ketiga didasarkan pada bahwa setiap
proses dan hasil proses pemanfaatan jasa
lingkungan selalu muncul sebagai
mekanisme hubungan sebab akibat.
Hubungan sebab akibat antara manusia
dan lingkungan di setiap cakupan wilayah
cenderung kompleks dan mempunyai ciri
yang khas tergantung dari ketersediaan
jasa lingkungan. Informasi terkait
hubungan sebab akibat pemanfaatan jasa
lingkungan pada DAS mikro akan dapat
digunakan sebagai dasar penilaian
berbagai manfaat dan dampak yang
muncul baik yang bersifat langsung
ataupun tidak langsung.
Berdasarkan ketiga prinsip tersebut
maka penelitian ini merumuskan tahapan
metode sidik cepat jasa lingkungan pada
DAS mikro yang tersusun dan dikaji secara
urut yaitu:
1. Pemahaman wilayah DAS kajian
terhadap sistem lanskap regional
(Analisis data sekunder dan spasial
terkait posisi terhadap DAS utama dan
kondisi geomorfologis, iklim, tanah,
administrasi, hingga sosial budaya);
2. Identifikasi tipologi jasa lingkungan
pada wilayah DAS mikro (dilakukan
dengan analisis peta tutupan lahan
meliputi jenis, batas, luas, aransemen/
distribusi);
3. Analisis mekanisme pemanfaatan jasa
lingkungan (dilakukan dengan survei
lapangan dan wawancara mendalam
terhadap para pemangku kebijakan);
4. Penilaian jasa lingkungan dan
dampaknya (dilakukan dengan analisis
nilai manfaat ekonomi dengan
pendekatan market price);
5. Analisis keberlanjutan pemanfaatan
jasa lingkungan (dilakukan dengan
analisis secara deskriptif menggunakan
perbandingan/matriks nilai manfaat
dan dampak yang dapat ditimbulkan
dari pemanfaatan jasa lingkungan).
Metode sidik cepat ini secara teknis
memanfaatkan teknologi Sistem Informasi
Geografis dan analisis manfaat ekonomi
secara komprehensif untuk mendukung
proses analisis. Tabel 1 menguraikan
secara lebih spesifik berbagai metode
sidik cepat nilai manfaat langsung ataupun
tidak langsung. Secara umum metode
pengambilan data yang dipakai di
lapangan yaitu menggunakan sidik cepat
sehingga mendapatkan hasil langsung
dilapangan. Perhitungan yang digunakan
yaitu berbatas pada jasa lingkungan saja;
belum menghitung shadow price dan
valuasi ekonomi imbal jasa lingkungan.
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ……..................................................................................................................…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
84 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table)1: Fungsi jasa lingkungan di Sub DAS Cebong (The function of environmental services in The Cebong Micro-Catchment).
Fungsi jasa lingkungan
(Environmental services function)
Jasa utama (Main
services)
Deskripsi (Description)
Metode survei dan analisis (Survey method and analysis)
Keterangan (Explanation)
Penyediaan (Provision)
Sumber Makanan
Kentang Purposive sampling (wawancara dengan pengepul kentang di Desa Sembungan)
Pengepul kentang adalah orang yang membeli kentang langsung dari para petani dan menjualnya kepada calo.
Carica Purposive sampling (wawancara dengan pengepul carica di Desa Sembungan)
Pengepul carica adalah orang yang membeli carica dari petani untuk dijual kepada home industy carica
Sumber Air Air Minum Domestik
Purposive sampling (wawancara dengan masyarakat tiap KK yang menggunakan air bersih dari sumur)
Wawancara 24 KK (yang memiliki 99 angota keluarga) warga Desa Sembungan yang memiliki Sumur
Air Irigasi Purposive sampling (wawancara dengan petani yang menggunakan air Telaga untuk pertanian)
Pendekatan dilakukan dengan biaya swadaya yang dikeluarkan petani untuk pengerukan Telaga Cebong
Pengaturan (Control)
Pengikat dan Cadangan karbon
Kandungan karbon pada tanaman semusim dan semua tipe tanaman yang terdapat di hutan
Biomassa 0,11 x x D2,62 Ketterings, et al., 2001 Pengukuran cadangan karbon dilakukan dengan melakukan sampling berdasarkan kerapatan tanaman yang ada di Sub DAS Cebong. Sampling vegetasi dibagi untuk mendapatkan data biomassa jenis pohon, tiang, pancang, semai. Jumlah sampel Jenis Pohon 173, pancang 7, tiang 27 dan semai sama dengan luas tegalan yang ditanami kentang
Biomassa (Jenis yang tidak diketahui spesiesnya)
0,118 x D2,53 Hairiyah dan Rahayu, 2007
Serapan CO2 C x 3,67 Morikawa, 2003., Usmadi, et al., 2011
Karbon Tersimpan Biomassa x 0,46 Yuliasmara and Wibawa, 2007
Harga Karbon 5 US$/ton Kemeterian Lingkungan Hidup, 2012 (Nilai 1 US$ = Rp14.537,-)
Keterangan:
ρ Kerapatan Pohon (g/cm3)
D diameter tanaman (cm)
Jenis Tanaman Semai Y=(0,11ρ D2.62)/4
Winastuti, 2017
Jenis Tanaman Pancang Y=(0,11ρ D2.62)/2.5
Jenis Tanaman Tiang Y=(0,11ρ D2.62)/10
Jenis Tanaman Pohon Y=(0,11ρ D2.62)/40
Habitat (Habitat) Biodiversitas Berbagai satwa di hutan Sikunir dan sekitarnya
Data Sekuder dari Perum Perhutani Kedu Utara
Budaya (Culture) Wisata Data dari Perum Perhutani Kedu Utara
Data Sekunder hasil penjualan tiket kujungan ke Gunung Sikunir
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 85
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pemahaman Wilayah Sub DAS Cebong
Terhadap Sistem Lanskap Regional
Pemahaman jasa lingkungan DAS mikro
dari sisi skala regional akan dapat
memberikan informasi awal terkait
potensi jasa lingkungan serta sekaligus
menunjukkan arti penting posisi dan
pengaruh jasa lingkungan yang terdapat di
dalamnya terhadap keberlanjutan DAS
utama (Mustajoki et al., 2020). Artinya
kajian jasa lingkungan pada DAS mikro
seharusnya dimulai dari pemahaman skala
regional ke skala yang lebih detail.
Sub DAS Cebong merupakan DAS mikro
yang merupakan bagian dari sistem DAS
Serayu. Posisi Sub DAS Cebong yang
terletak di bagian hulu DAS Serayu
tentunya akan memberikan pengaruh
terhadap dinamika lingkungan DAS Serayu
di bagian tengah hingga hilir (Jariyah &
Pramono, 2013). Sub DAS Cebong terletak
di pegunungan Dieng Jawa Tengah yang
secara fisiografis termasuk pada sistem
Pegunungan Serayu Utara (Jariyah &
Pramono, 2013). Secara genesis regional
wilayah Sub DAS Cebong terbentuk dari
serangkaian proses vulkanik Gunung Api
Dieng periode kaldera dan paska kaldera
yang dibuktikan dengan keberadaan
Gunung Api Sikunang, Gunung Api
Pakuwaja, Gunung Api Prambanan,
Gunung ApiSikunir dan Gunung Api Seroja
(Gambar 2). Proses vulkanisme yang
intensif membentuk material dasar Sub
DAS Cebong berupa material vulkanik
hasil letusan gunungapi yang berumur
kwarter (Sartohadi, 2004).
Kondisi tanah di Sub DAS Cebong
berasal dari proses pelapukan intensif
pada material piroklastik dari aktivitas
vulkanik. Menurut Sartohadi (2004)
Gambar (Figure) 2. Posisi Sub DAS Cebong pada bentuklahan DAS Serayu(Cebong Sub-Watershed position in the Serayu Watershed landsystem).
Sumber (Source): Analisis (Analysis result), 2020 dimodifikasi dari Sartohadi (Modified from Sartohadi), 2004.
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa …..........(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
86 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
satuan tanah tingkat ordo yang terdapat
pada satuan bentuklahan asal vulkanik
adalah andisols pada kawasan dengan
ketinggian diatas 900 mdpl. Selain andisol
alfisol umumnya terdapat pada bagian
yang umur batuannya relatif tua seperti di
kompleks Gunungapi Sindoro dan
Sumbing. Kondisi elevasi Sub DAS Cebong
yang berada sekitar 2.260 mdpl memiliki
suhu antara 7oC -10o C dengan curah
hujan mencapai lebih dari 3000
mm/tahun.
Pola sistem aliran air tanah Desa
Sembungan Sub DAS Cebong mengalir
dari daerah utara yang merupakan daerah
imbuhan menuju ke arah barat daya yang
merupakan daerah lepasan dengan mata
air (Putri et al., 2018). Kondisi akuifer di
Desa Sembungan Sub DAS Cebong
merupakan akuifer bebas dengan
ketebalan akuifer jenuh 3-7,8 m.
Akuifer yang mendominasi tersebut
terdiri atas lapisan lempung, air tanah,
andesit basalt, dan endapa tuffan alterasi
(Risanti et al., 2018). Sub DAS Cebong
memiliki mata air yang digunakan dan
dimanfaatkan masyarakat untuk
kebutuhan domestik, pertanian, dan
pariwisata. Sub DAS Cebong menyimpan
berbagai potensi pariwisata. Berbagai
wilayah yang sudah dikembangkan yaitu
wisata alam Sikunir yang dikelola bersama
LSM dengan Kelompok Sadar Wisata
(Pokdarwis) di Desa Sembungan atas
seizin Perum Perhutani KPH Kedu Utara.
Secara garis besar pariwisata di Desa
Sembungan Sub DAS Cebong dapat
dikelompokkan menjadi wisata alam,
wisata buatan, wisata budaya, dan wisata
edukasi (Budiani et al., 2018). Masing-
masing wisata tersebut
memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri
sebagai destinasi wisata. Kawasan wisata
budaya yaitu sebuah atraksi wisata yang
mengangkat kebudayaan masyarakat
Desa Sembungan Sub DAS Cebong.
Kebudayaan Desa Sembungan Sub DAS
Cebong yang mampu menjadi atraksi
seperti Tarian Ludrak, Tarian Imo-Imo, dan
Ruwatan Gimbal serta wisata religi makam
Joko Sembung (Budiani et al., 2018).
Kekayaan wisata budaya tersebut diikuti
dengan keramahan, sopan santun dan
budaya masyarakat yang masih baik.
Berdasarkan analisis regional lanskap,
Sub DAS Cebong memberikan jasa
lingkungan yang cukup beragam terhadap
keberadaan dan keberlanjutan DAS Serayu
dan pemerintah daerah Kabupaten
Wonosobo. Jasa lingkungan penyediaan
yang utama adalah: i) penyediaan bahan
pangan yang berkualitas (didukung oleh
material tanah vulkan andisol dengan
kesuburan tanah yang baik dan kondisi
iklim yang khas) dan ii) penyediaan air
bersih untuk kebutuhan domestik
masyarakat hilir (posisi sub das cebong di
hulu menjadi area imbuhan air tanah).
Keberadaan fungsi hutan lindung yang
masih terdapat di sekitar Sub DAS Cebong
menentukan jasa lingkungan berupa
pengendalian i) perlindungan dari
kejadian bencana tanah longsor dan
banjir, ii) cadangan karbon, dan iii)
pengendalian terhadap erosi serta jasa
lingkungan penyangga sistem/habitat bagi
berbagai biodiversitas endemik. Sub DAS
Cebong juga memiliki beberapa aset
potensi wisata yang muncul sebagai jasa
lingkungan budaya untuk pembangunan
ekonomi.
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 87
B. Identifikasi Tipologi Jasa Lingkungan di
Dalam Sub DAS Cebong
Jasa lingkungan secara sederhana
dapat dijelaskan sebagai manfaat yang
diambil oleh manusia dari ekosistem
(Kasim et al., 2015; Nyongesa et al., 2016;
Subramanian & Jana, 2019). Konsep jasa
lingkungan mencakup pemanfaatan
penyampaian, penetapan, produksi,
perlindungan, atau pemeliharaan dari
kumpulan barang dan jasa penting bagi
manusia yang berasal dari
lingkungan(Martin-Ortega et al., 2019).
Sifat jasa lingkungan secara terbuka
digunakan untuk umum; mengakibatkan
jasa lingkungan cenderung tidak memiliki
hak kepemilikan namun dikenakan biaya
transaksi yang mahal dan cenderung
mangalami perubahan (Khairiah et al.,
2016). Data hasil valuasi jasa lingkungan
berupa nilai ekologi, sosial, dan ekonomi
dapat digunakan sebagai dasar dalam
menyusun kebijakan, keputusan dan
membantu proses perencanaan hingga
monitoring evaluasi untuk mengatur
strategi pembangunan wilayah daerah
aliaran sungai dan menjaga keberlanjutan
ekosistem (Chintantya& Maryono, 2017;
Khairiah et al., 2016).
Gambar 3 menunjukkan peta hasil
interpretasi tutupan dan pemanfaatan
lahan di Sub DAS Cebong yang terdiri dari
area permukiman, telaga, tempat wisata,
hutan lindung, dan tegalan (tanaman
holtikultura). Keempat tutupan lahan ini
menggambarkan secara cepat variasi
ketersediaan jasa lingkungan Sub DAS
Cebong. Telaga dan hutan lindung dapat
memiliki potensi jasa lingkungan yang
lengkap dari jasa penyediaan, pengaturan,
habitat sekaligus jasa budaya.
Gambar (Figure) 3. Peta sebaran jasa lingkungan di Sub-DAS Cebong. (Environmental services distribution map in the Cebong Sub-Watershed).
Sumber (Sources): Hasil analisis (Analysis result), 2020.
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa …..........(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
88 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 2. Luasan fungsi jasa lingkungan di Sub-DAS Cebong (The area of environmental services function
in Cebong Sub Watershed)
Sumber (Sources): Hasil analisis (Analysis result), 2020.
Di sisi lain, lahan tegalan menunjukkan
dominasi pemanfaatan jasa penyediaan
pangan (Tabel 2). Aktivitas pertanian yang
intensif di Sub DAS Cebong dapat
berlangsung karena dukungan kesuburan
tanah dan kondisi iklim yang telah
dijelaskan pada sub bab sebelumnya.
Adanya luasan lahan pertanian yang
dominan di sekitar ekosistem alami telaga
dan kawasan hutan yang posisinya
menempati bagian hulu DAS Serayu telah
mengindikasikan ketidakseimbangan dari
pemanfaatan jasa lingkungan di Sub DAS
Cebong. Keberadaan lahan terbangun
berupa permukiman yang mengelompok
dan lahan pertanian yang luas
menunjukkan adanya akses air (untuk
kebutuhan domestik ataupun pertanian)
yang mencukupi di Sub DAS Cebong (jasa
penyediaan air bersih).
Hasil analisis spasial detail di dalam Sub
DAS Cebong dapat memberikan gambaran
secara utuh terkait variasi jenis, luasan,
dan susunan keruangan dari setiap jasa
lingkungan. Hasil ini penting sebagai data
kuantitatif pendukung analisis manfaat
dan dampak (Mustajoki et al., 2020;
CICES, 2013). Meski demikian, hasil
analisis tipologi jasa lingkungan ini masih
tentatif dan belum dapat secara rinci
menjelaskan intensitas pemanfaatan,
sehingga membutuhkan analisis yang
lebih detail terkait proses dan hasil proses
pemanfaatan jasa lingkungan di Sub DAS
Cebong pada sub bab selanjutnya.
C. Analisis Mekanisme Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
Kondisi keberagaman jasa lingkungan
yang ditemukan di Sub DAS Cebong dapat
dipengaruhi oleh kondisi komponen
ekosistem. Semakin lengkap komponen
suatu ekosistem, maka akan semakin baik
kualitas jasa lingkungannya dan
begitupula sebaliknya (Ulya et al., 2017).
Jasa lingkungan di Sub DAS Cebong
sebagian besar dimanfaatkan oleh
manusia untuk kelangsungan hidup.
Manusia dalam hal ini bersifat sebagai
pengguna jasa lingkungan. Jasa lingkungan
yang tersedia di Sub DAS Cebong
berdasarkan fungsi dan jasa utamanya
dapat dilihat pada Tabel 3.
No Informasi tutupan lahan (Land cover information)
Jasa lingkungan (Environmental Services)
Luas area (area) (Ha)
1 Lahan Tegalan (dry land) Penyediaan (sumber pangan, air bersih) 69,26 (65,11%)
2 Lahan hutan (Forest)
Penyediaan(air bersih) Regulasi (pengendalian erosi sedimentasi, cadangan karbon) Habitat Wisata
23,38 (24,10%)
3 Lahan terbangun untuk permukiman dan wisata (settlement and tourism)
Budaya (wisata) 9,79
(10,77%)
Total 104,49
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 89
Tabel (Table) 3. Jasa lingkungan di Sub DAS Cebong (Environmental services in Cebong Sub Watershed)
Fungsi jasa lingkungan (Environmental services function)
Jasa utama
(Main services)
Keterangan
(Explanation)
Penyediaan (Provision service) Sumbermakanan Kentang
Carica
Air domestik Air bersih
Regulasi(Regulatingservice) Cadangankarbon Kandungan karbon pada tanamansemusim dan semua tipe tanaman yang terdapat di hutan
Air telaga Sarana irigasi
Habitat(Habitatorsupportingsystem)
Biodiversitas/ keragaman jenis
Berbagai satwa di Hutan Sikunir dan sekitarnya
Religi/Sosial budaya (Cultural service)
Wisata Pendapatan tiketwisatawan
Sumber (Sources): Hasil Analisis (Analysis result), 2020
Berdasarkan Tabel 3, jasa lingkungan
utama yang dimanfaatkan oleh
masyarakat adalah sumber makanan,
berupa tanaman kentang dan carica, air
domestik, caadangan karbon, air telaga,
biodiversitas dan wisata. Mekanisme
pemanfaatan jasa lingkungan dianalisis
dan diuraikan dengan menggunakan
system thingking yang dihasilkan pada
Gambar 4.
Berdasarkan Gambar 4 diketahui
bahwa mekanisme pemanfaatan jasa
lingkungan di Sub DAS Cebong diawali dari
pemanfaatan lahan sebagai pertanian
untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Jasa lingkungan berupa penyedia
makanan menjadi sumberdaya utama
masyarakat Desa Sembungan Sub DAS
Cebong.
Pemanfaatan lahan kemudian
berkembang dengan keterlibatan
parapemangku kepentingan dalam
pengelolaan kawasan hutan. Pemanfaatan
jasa lingkungan hutan sebagai penyedia
karbon dihutan kemudian mengalami
perkembangan sebagai penyedia jasa
wisata. Pemanfaatan jasa wisata
berkembang seiring berjalannya waktu
karena menyediakan keindahan alam
Bukit Sikunir. Aktifitas pemanfaatan jasa
lingkungan di Sub DAS Cebong diikuti oleh
berbagai kalangan masyarakat lokal
dengan menyediakan jasa penyedia
penginapan dan tempat makan.
Perkembangan mekanisme pemanfaatan
lahan ini akibat adanya potensi lain dari
lahan selain untuk kegiatan pertanian.
Aktifitas ekonomi pertanian dan non
pertanian seperti pariwisata muncul
sebagai bentuk tumbuh dan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat
(Sharma et al., 2012; Pramanik &
Ingkadijaya, 2017).
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa …..........(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
90 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Gambar (Figure) 4. Mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan di Sub DAS Cebong (Environmental services
utilization mechanism in Cebong Sub Watershed).
Sumber (Source): Widicahyono et al., 2018.
1. Fungsi Penyediaan
Fungsi jasa lingkungan penyediaan
merupakan jasa utama yang menyediakan
sumber makanan dan air domestik yang
ada di Sub DAS Cebong. Sumber makanan
utama di Sub DAS Cebong yaitu kentang
dan carica. Tanaman kentang merupakan
tanaman budidaya yang menjadi tanaman
unggulan masyarakat di Desa Sembungan
Sub DAS Cebong dan intensif dilakukan
sejak 1985 (Arbangiyah, 2012).
Berdasarkan Gambar 3, jasa lingkungan
berupa sumber makanan kentang dan
carica tersebar di berbagai wilayah yang
merupakan area dengan penggunaan
lahan berupa tegalan. Area tegalan
merupakan lahan pertanian kering yang
digunakan masyarakat untuk menanam
kentang dan carica. Penanaman kentang
dilakukan pada teras dengan pemanenan
dua kali dalam satu tahun, sedangkan
carica dapat dipanen sebanyak satukali
dalam satu tahun.
Kontrol harga pasar digunakan untuk
menilai harga jasa lingkungan dari fungsi
penyediaan makanan. Harga pasar ini
dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari
jumlah permintaan masyarakat, musim
atau iklim serta panjangnya proses
pendistribusian dari petani hingga ke
tangan masyarakat (Gambar 5).
2. Fungsi Regulasi
Cadangan karbon dan air telaga
merupakan jasa utama dari fungsi jasa
lingkungan Regulasi. Cadangan karbon
diidentifikasi dari tersedianya hutan
dengan berbagai vegetasi sebagai
penyedia karbon utama. Hutan di Sub Das
Cebong tersebar di wilayah utara hingga
timur pada Bukit Sikunir. Air telaga
menyediakan sumberdaya air yang
berlimpah untuk sarana irigasi bagi
masyarakat Desa Sembungan. Keberadaan
Telaga Cebong berada di tengah Sub DAS
Cebong dan merupakan outlet DAS.
Persentase fungsi jasa lingkungan regulasi
memiliki luasan wilayah sebesar 24,1%
dari seluruh wilayah Sub DAS Cebong
(Tabel 4).
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 91
Gambar (Figure) 5. Proses distribusi kentang dari petani hingga masyarakat (Potatoes distribution process).
Sumber (Sources): Analisis lapangan (field analysis), 2019.
Tabel (Table) 4: Persentase nilai jasa lingkungan di Sub DAS Cebong (Environment services percentage value in Cebong Sub Watershed)
Fungsi jasa lingkungan
(Environmentalservicesfunction)
Nilai
(Value)
Persentase (Percentage)
Penyedia- makanan (Provision-food) Rp.2.220.000.000,00 53,80
Penyedia-air bersih (Provision-clean water) Rp.175.989.860,00 4,26
Regulasi-cadangan karbon (Regulation-carbon stock) Rp.280.137.810,00 6,78
Regulasi-air telaga (Regulation-lake water) Rp.500.000.000,00 13,21
Sosial budaya-wisata (Social culture-tourism) Rp.905.000.000,00 21,93
Sumber (Sources): Hasil analisis (Analysis result),2020.
3. Fungsi Habitat
Fungsi habitat menyediakan jasa utama
yaitu keragaman jenis satwa di hutan
Sikunir. Adanya hutan lindung di Sub DAS
Cebong menyediakan jasa lingkungan
utama yang mendukung kehidupan baik
dari segi ekologis maupun ekonomis.
Dalam mendeliniasi fungsi habitat pada
peta jasa lingkungan, fungsi habitat tidak
dapat berdiri sendiri melainkan termasuk
dalam sistem hutan di Sub DAS Cebong
dantidak dapat dipisahkan. Hutan
memiliki peranan penting bagi
keberagaman jenis satwa di Sub DAS
Cebong. Dari segi ekologis, keberadaan
tutupan lahan hutan memberikan fungsi
pengendali limpasan permukaan dan
bahaya bencana erosi, pengikat karbon
dan habitat bagi satwa-satwa liar.
4. Fungsi Religi/ Sosial Budaya
Fungsi jasa budaya meliputi
pemanfaatan lahan Perum Perhutani
untuk kegiatan ekowisata. Selain itu Desa
Sembungan merupakan lokasi wisata desa
tertinggi di Pulau Jawa yang menyediakan
berbagai tempat penginapan, sarana dan
prasarana wisata. Hutan lindung bukit
Sikunir juga merupakan area yang
dimanfaatkan masyarakat untuk tujuan
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa …..........(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
92 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
ekowisata. Kondisi sosial masyarakat desa
Sembungan memiliki berbagai budaya
yang dapat dimanfaatkan sebagai fungsi
sosial budaya.
Pengelola wisata dikelola oleh
Pokdarwis Desa Sembungan. Pemanfaatan
wisata Bukit Sikunir masuk dalam fungsi
jasa lingkungan wisata. Pendekatan untuk
melihat pemanfaatan dari jasa lingkungan
ini pembayaran pajak retribusi (pajak dari
tiket wisata).
Berbagai kelompok sosial di Desa
Sembungan Sub DAS Cebong yaitu seperti
adanya kelompok tani, gabungan
kelompok tani dan kelompok wanita tani.
Jumlah kelompok Tani di Desa Sembungan
Sub DAS Cebong sebanyak 3 kelompok
dengan jumlah anggota sebanyak 161
orang. Sedangkan jumlah kelompok tani
wanita sebanyak 1 kelompok dengan
jumlah anggota sebanyak 21 orang. Usaha
sektor industri rumah tangga di desa
Sembungan Sub DAS Cebong sebanyak 6
lokasi.
Selain wisata alam Sikunir yang
terkenal, terdapat berbagai potensi wisata
di Desa Sembungan Sub DAS Cebong yang
masih dapat dikembangkan lagi Secara
garis besar pariwisata di Desa Sembungan
Sub DAS Cebong dapat dikelompokkan
menjadi wisata alam, wisata buatan,
wisata budaya, dan wisata edukasi
(Budiani et al., 2018). Masing-masing
wisata tersebut memiliki keunikan dan ciri
khas tersendiri sebagai destinasi wisata.
Kawasan wisata budaya merupakan
atraksi wisata yang mengangkat
kebudayaan masyarakat Desa Sembungan
Sub DAS Cebong. Kebudayaan Desa
Sembungan Sub DAS Cebong yang mampu
menjadi atraksi seperti Tarian Ludrak,
Tarian Imo-Imo, dan Ruwatan Gimbal
serta wisata religi makam Joko Sembung
(Budiani et al., 2018).
Budaya di Desa Sembungan Sub DAS
Cebong tergolong masih cukup kental. Hal
ini dapat dilihat dari adat yang masih
dilakukan di Desa Sembungan. Adat yang
masih dilestarikan hingga saat ini yaitu
berupa upacara ruwat rambut gimbal.
Upacara ini merupakan acara tahunan
yang berisikan upacara ruwatan untuk
anak-anak yang berambut gimbal.
Upacara ruwat rambut gimbal ini sudah
diangkat menjadi salah satu ciri khas di
Kawasan Dataran Tinggi Dieng, bahkan
juga turut ditampilkan pada saat event
Dieng Culture festival yang merupakan
event terbesar tahunan di Kawasan
Dataran Tinggi Dieng.
D. Nilai Jasa Lingkungan di Sub DAS
Cebong
Nilai jasa lingkungan di Sub DAS
Cebong merupakan estimasi nilai jasa
lingkungan dengan pendekatan sidik cepat
untuk mendukung analisis dalam peran
jasa lingkungan. Nilai jasa lingkungan juga
menjelaskan sebesar apa jasa lingkungan
apabila dihitung dengan nilai rupiah
sehingga dapat diketahui seberapa besar
persentase jasa lingkungan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
Penilaian jasa ekosistem dan
keanekaragaman hayati dapat menjadi
sarana dalam membuat kebijakan yang
menyebabkan keluarnya biaya bagi
masyarakat (TEBB, 2010). Berdasarkan
Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai jasa
lingkungan yang memiliki nilai paling
tinggi yaitu penyedia makanan (kentang
dan carica) dengan persentase 53,8%.
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 93
Nilai fungsi jasa lingkungan dengan
persentase terbanyak kedua yaitu sosial
budaya dengan pariwisatanya yang
mencapai 21,93%. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa jasa lingkungan
berupa penyediaan makanan dan jasa
sosial budaya berupa wisata menyediakan
nilai jasa lingkungan dan keuntungan yang
tinggi kepada masyarakat.
1. Penyediaan Sumber Makanan dan Air
Bersih
Jasa penyediaan bahan pangan di Sub
DAS Cebong dihitung berdasarkan hasil
pertanian kentang dan tanaman carica.
Jumlah produksi kentang yang berada di
Desa Sembungan tahun 2017 sebesar 10
ton/ha dalam sekali panen. Jumlah
produksi tersebut didistribusikan untuk
dijual ke berbagai wilayah di kota Solo,
Tasikmalaya, Bandung dan Jakarta.
Berdasarkan data yang telah dihimpun
dari wawancara masyarakat di Desa
Sembungan (Gambar 6), bahwa mereka
sekali panen mendapatkan keuntungan
bersih 20 juta rupiah. Nilai tersebut
dikurangi dengan biaya produksi baik
untuk biaya bibit, pupuk (kandang, TSP,
Urea), obat-obatan (pestisida, fungisida),
plastik, mulsa, tenaga (cangkul,
pemanenan, pengobatan, dan penyiraman
maupun panen) yang mencapai Rp 40
juta.
Nilai jasa lingkungan yang diperoleh
masyarakat dari hasil jumlah produksi
penjualan per panen sebesar 10 ton/ha
dengan luas lahan pertanian kentang 68
ha dan dengan harga jual mencapai Rp.
5.000,00/kg. Dari harga tersebut
diperolehnilai jasa lingkungan sebesar
Rp.6.800.000.000,00/tahun. Nilai ini
merupakan pendapatan bersih (Tabel 5).
Selain untuk kentang, petani lokal juga
memanfaatkan lahannya untuk menanam
tanaman carica di sela-sela lahan
pertanian kentang. Tanaman carica
merupakan tanaman yang telah
beradaptasi di kawasan Gunung Api Dieng
yang memiliki daya tahan yang lebih baik
terhadap cuaca ekstrem. Tanaman carica
ditanam sebagai tanaman sela pada
tanaman hortikultura. Carica hampir tidak
memerlukan biaya perawatan seperti
untuk perawatan tanaman kentang.
Tanaman carica juga memiliki nilai
ekonomi yang tinggi sebagai makanan
khas Dataran Tinggi Dieng. Hasil
perhitungan imbal jasa lingkungan untuk
produksi carica mentah (bukan olahan)
mencapai Rp.1.440.000.000,00/tahun
(Tabel 5).
Nilai jasa lingkungan air bersih dihitung
berdasarkan kebutuhan yang diperoleh
masyarakat dari penggunaan air domestik.
Penyediaan air domestik dihitung dari
penggunaan sebanyak 241 rumah x Rp.
2000,00 (harga per m3) = Rp.
482.164,00/hari. Apabila dikalkulasikan
selama satu tahun maka penggunaan air
bersih memiliki jasa lingkungan senilai Rp.
175.989.860,00
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa …......................................................................................................................…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
94 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 5. Perhitungan nilai imbal jasa lingkungan di Sub DAS Cebong, Kec Kejajar Kab. Wonosobo (Environmental services calculation value in the Cebong Sub-
watershed, Wonosobo District).
Sumber (Source): Hasil analisis (Analysis result), 2020.
Keterangan:
***: Kerugian erosi akibat pendangkalan Telaga Cebong diambil dari jumlah biaya swadaya masyarakat Desa Sembungan untuk mengeruk Telaga Cebong dan dibandingkan dengan terakhir kali waktu pengerukan telaga sebelumnya
a : Biaya swadaya masyarakat Tahun 2015 untuk pengerukan Telaga Cebong : Rp. 500.000.000,00 b : Tahun 2009 dilakukan pengerukan Telaga Cebong yang dibantu oleh PT. Geodipa Energy
Pelayanan (Services)
Nilai (Value)
Satuan produksi/ penggunaan
(Production unit/ usage)
Harga/nilai (Cost)
Harga jasa lingkungan
(Environmental services
value)(Rp)
Keterangan (Explanation)
Keuntungan ekonomi
(Economic benefits)
Satuan Luas Harga Satuan Total Satuan
Makanan
a. Kentang
Keuntungan kotor 10 Ton/ha 68 7.000 Per kg 4.760.000.000 Per 5 bulan 9.520.000.000 Ada risiko gagal panen (harga kotor)
Keuntungan bersih
10 Ton/ha 68 5.000 Per kg 3.400.000.000 Per 5 bulan 6.800.000.000 Keuntungan bersih dg pertimbangan (BEP Rp 5000)
a. Carica 30 Ton/bulan 4.000 Per kg 456.320.000 Per bulan 1.440.000.000 Tidak ada risiko gagal panen
Air
a. Air domestik 241 m3/hari 2.000 Per m3 482.164 Rp/hari 175.989.860 Kebtuhan air 167,771 l/hr darijumlah penduduk 1437 jiwa
b. Air pertanian 500.000.000 Biaya pengerukan Telaga Cebong
Karbon total $ 5 Per Ton 3.854,14 Ton/ha 280.137.810 Harga Carbon 5 US$/ton dan kurs dollar-rupiah (Tahun 2018 bulan Desember) Rp 14.537
a. Hutan 18,22 62.869.116
b. Tegalan 67,53 6.210.983
Regulasi (Regulation)
Kerugian erosi akibat pendangkalan telaga
500.000.000 ***
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 95
Gambar (Figure) 6. a).Wawancara Petani Kentang(Interview with Potatoes Farmer), b). Wawancara dengan pemilik rumah produksi carica(interview with carrica production house owner),c). Cemara Hutan di Sikunir(Forest Pine in Sikunir),d).Pertanian/ hortikultura di sekitar Danau Cebong(Farming/horticultural around Lake Cebong).
Sumber (Source): Dokumentasi (Documentation), 2017.
2. Fungsi Regulasi
Fungsi regulasi yang menghasilkan
cadangan karbon dihitung pada dua
tutupan lahan yang berbeda, yakni pada
hutan memiliki cadangan karbon senilai
141,83 ton/ha dan serapan karbon yang
mencapai 400,57 ton/ha. Cadangan
karbon pada tegalan memiliki nilai37,96
ton/ha dan serapan karbon mencapai
139,31 ton/ha. Nilai harga cadangan
karbon apabila dijumlahkan dan
dirupiahkan akan menunjukkan nilai jasa
lingkungan mencapai angka Rp.
280.137.810,49 (Perhitungan dapat dilihat
pada Tabel 5). Fungsi regulasi yang lain
yaitu nilai dari air Telaga Cebong yang
digunakan untuk sarana irigasi masyarakat
di Desa Sembungan. Apabila dirupiahkan
yaitu dengan mengestimasi biaya yang
dikeluarkan apabila terjadi pendangkalan
telaga Cebong. Data yang diperoleh dari
hasil wawancara dengan pihak Desa
Sembungan diketahui biaya pengerukan
sebesar Rp. 500.000.000,00/tahun.
3. Sosial Budaya
Dari segi sosial budaya, hutan lindung
di Sub DAS Cebong yang termasuk dalam
lingkungan area Bukit Sikunir
dimanfaatkan dan difungsikan oleh
masyarakat lokal sebagai daerah tujuan
ekowisata. Pendapatan yang dihasilkan
dari pengelolaan kawasan ekowisata ini
berasal dari tiket masuk dan pemanfaatan
toilet. Dengan jumlah pengunjung
mencapai 90.500 orang pertahun di tahun
2016.Pembukaan kawasan wisata Sikunir
telah menghasilkan nilai jasa lingkungan
sebesar Rp. 905.000.000,00 dari penjualan
tiket masuk dan Rp. 4.445.300,00 dari
pemanfaatan toilet.
E. Peran dan Manfaat Nilai Jasa
Lingkungan dalam Perencanaan di Sub
DAS Cebong
Jasa lingkungan di Sub DAS Cebong
merupakan komponen yang tidak dapat
dipisahkan dari masyarakat di Desa
Sembungan. Variasi nilai jasa lingkungan
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ….........…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
96 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Tabel (Table) 6. Analisis manfaat, potensi dan dampak dalam penggunaan jasa lingkungan (Analysis of benefits,
potential and impacts in the use of environmental services)
Jasa lingkungan utama (Main
environmental services)
Manfaat
(Benefits)
Potensi
(Potency)
Dampak
(Impact)
Sumber makanan
(Foodsources)
Sebagai pendapatan perekonomian masyarakat
Peningkatan kualitas produk olahan sehingga meningkatkan harga jual
Ketergantungan masyarakat tinggi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi dan degradasi lahan
Air domestik
(Water domestics)
Sebagai Sarana pemenuhan kehidupan sehari-hari
Sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal maupun wisatawan
Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kelangkaan air bersih
Cadangan karbon
(Carbonstock)
Sebagai penyedia oksigen dan penyerap karbon
Sebagai hutan lindung yang mampu mengatur lingkungan
Pembukaan lahan dan ekspansi lahan dapat menyebabkan berkurangnya luasan lahan hutan sehingga penyerapan karbon rendah
Air telaga (Lake water)
Sebagai sarana irigasi Sebagai sarana pariwisata baru
Permasalahan pendangkalan telaga muncul sebagai dampak dari sedimentasi. Pencemaran air telaga juga dapat terjadi apabila kegiatan pariwisata tidak disediakan fasilitas kebersihan
Biodiversitas (Biodiversity)
Sebagai estetika Sebagai sarana edukasi Ancaman perburuan dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati
Wisata (Tourism)
Sebagai pendapatan perekonomian masyarakat
Dapat dikembangkan dengan berbagai paket perjalanan dan jasa wisata lain
Degradasi lingkungan seperti erosi antropogenik dapat terjadi, ekspansi lahan baru dapat memicu menyempitnya lahan hutan.
Sumber (Source): Hasil analisis (Analysis result), 2020
di Sub DAS Cebong menggambarkan
keragaman lingkungan biofisik DAS Mikro
yang memiliki karakteristik geomorfologi
yang kompleks. Jasa lingkungan secara
langsung maupun tidak langsung memiliki
peran dan manfaat bagi kehidupan
masyarakat desa Sembungan.
Berdasarkan hasil analisis Tabel 5 bahwa
nilai jasa lingkungan untuk penyedia
makanan berupa kentang dan carica
ketika panen masing-masing sebesar
Rp.6.800.000.000,00 dan
Rp.1.440.000.000,00 dengan persentase
paling tinggi yaitu 53,8% (Tabel 4).
Tingginya persentase dan nilai jasa
lingkungan penyedia makanan
menunjukkan bahwa kondisi
perekonomian masyarakat bergantung
pada lingkungan yang menyediakan bahan
makanan. Perkembangan wisata ini
berada di tengah pemanfaatan lahan
pertanian holtikultura intensif yang sudah
berjalan selama beberapa generasi. Sub
DAS Cebong memiliki luasan yang tidak
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 97
besar namun memiliki potensi dan
permasalahan lingkungan yang beragam.
Analisis peran dan manfaat nilai jasa
lingkungan dalam perencanaan di Sub DAS
Cebong dianalisis secara tabulasi
kualitatifdan dijelaskan secara kualitatif.
Tabel 6 menunjukkan bahwa jasa
lingkungan harus dimanfaatkan secara
bijak dan berkelanjutan untuk
meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Kerugian dan akibat dampak yang
ditimbulkan akan membuat nilai jasa
lingkungan tersebut turun baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Penilaian
jasa lingkungan dapat digunakan sebagai
pembayaran untuk mengganti kerugian
yang ditimbulkan akibat kerusakan
lingkungan. Pembayaran dapat berupa
upaya konservasi. Tindakan pencegahan
pendangkalan telaga dilakukan dengan
melakukan pengerukan sedimen telaga
Cebong. Upaya konservasi merupakan
cara untuk mempertahankan jasa
lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan seperti
perlindungan telaga, perlindungan mata
air, peningkatan kapasitas masyarakat
dapat dilakukan untuk melindungi jasa
penyediaan sumber air (Rismunandar et
al., 2016). Pembayaran kerugian akan
mengalami penurunan apabila
penggunaan jasa lingkungan mengarah
kepada keberlanjutan lingkungan. Hal ini
dapat dilakukan dengan adanya program
jasa lingkungan seperti rehabilitasi hutan
dan lahan yang ditekankan pada penyedia
jasa ekosistem, habitat dan spesies yang
terancam mengalami degradasi (Aguilar et
al., 2018). Dari hasil penelitian (Duong &
De Groot, 2020) diketahui bahwa
keberlanjutan melalui program jasa
lingkungan melalui konservasi dapat
menciptakan karakter masyarakat untuk
melindungi hutan.
IV. KESIMPULAN
Sidik cepat inventarisasi jasa
lingkungan terbukti dapat digunakan
sebagai informasi dasar dalam rencana
pengelolaan DAS mikro. Inventarisasi jasa
lingkungan harus dimulai dari pemahaman
spasial secara regional (untuk mengetahui
secara umum kaitan jasa lingkungan DAS
mikro terhadap DAS utama) dan secara
detail (untuk melihat jenis, luas, serta pola
susunan setiap jasa lingkungan di dalam
DAS mikro). Analisis spasial terhadap
keragaman jasa lingkungan harus
dilengkapi dengan analisis hubungan
sebab akibat dalam proses dan hasil
proses pemanfaatan jasa lingkungan
untuk mendapatkan berbagai nilai
manfaat dan dampak setiap jasa
lingkungan. Penilaian ekonomi dari
manfaat langsung berdasar harga pasar
bisa digunakan dalam proses sidik cepat
asalkan dilengkapi dengan informasi
berbagai dampak pemanfaatan jasa
lingkungan.
Sub DAS Cebong merupakan contoh DAS
mikro yang mengalami
ketidakseimbangan pemanfaatan jasa
lingkungan. Fungsi jasa penyediaan
makanan jauh lebih intensif dibandingkan
dengan keberadaan jasa lingkungan
lainnya. Tanaman kentang memberikan
nilai manfaat langsung yang sangat tinggi
bagi masyarakat, namun mengganggu
keberlangsungan jasa lingkungan regulasi
dan habitat secara signifikan. Optimalisasi
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ….........…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
98 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
jasa budaya berupa aktivitas ekowisata di
Sub DAS Cebong dapat memberikan
manfaat langsung yang cukup tinggi tanpa
harus merusak jasa lingkungan yang lain.
Kajian ambang batas pemanfaatan jasa
lingkungan budaya di Sub DAS Cebong
perlu dilakukan untuk antisipasi
pembangunan fasilitas wisata yang
berlebihan dan menjadi masalah baru.
Metode sidik cepat jasa lingkungan perlu
diuji pada variasi kondisi lanskap DAS
mikro yang berbeda sebagai contoh di
karst, gambut, pesisir.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Rizal Faozi Malik,
Riha Ali Muhammad, Bayu Bima Yusufa,
Alzanea Ulya Rusmidi yang telah
membantu selama pengambilan data di
lapangan dan masyarakat desa
Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten
Wonosobo yang bersedia diwawancarai
dan berdiskusi tentang produksi kentang,
carica, dan penggunaan air bersih di
lingkungan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Aguilar, F. X., Obeng, E. A., & Cai, Z. (2018). Water quality improvements elicit consistent willingness-to-pay for the enhancement of forested watershed ecosystem services. Ecosystem Services, 30, 158–171. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2018.02.012
Ainun Jariyah, N. & Pramono, B. (2013). Kerentanan sosial dan biofisik di DAS Serayu: Collaborative management. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol.10 No. 3 September 2013, Hal. 141-156.
Ainun Jariyah, N. (2014). Karakteristik masyarakat Sub DAS Pengkol dalam
kaitannya dengan pengelolaan DAS (Studi kasus di Sub DAS Pengkol, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah). Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan, 11(1), 59–69. https://doi.org/10.20886/jsek.2014.11.1.59-69
Arbangiyah, R. (2012). Perubahan pola pertanian rakyat di Desa Sembungan Dataran Tinggi Dieng (1985-1995). Skripsi. Universitas Indonesia.
Brown, S. (1990). Guideline for inventorying and monitoring carbon offsets in forest-based projects. World Bank, (September).
Budiani, S.R., Wahdaningrum, W., Yosky, D., Kensari, E., Pratama, H.S., Malandari, H., Iskandar, H.T., Alphabettika, M., Maharani, N., Febriani, R.F., Kusminati, Y. (2018). Analisis potensi dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas di Desa Sembungan Wonosobo Jawa Tengah. Majalah Geografi Indonesia Vol. 32, No.2, September 2018 (170-176).
CICES, (2013). The CommonInternational Classification of Ecosystem Services (CICES) V4.3. January 2013. http://cices.eu/.
Chintantya, D. & Maryono, M. (2017). Peranan jasa ekosistem dalam perencanaan kebijakan publik di perkotaan. Proceeding Biology Education Conference Volume 14 (1), 144- 147
Dasrizal., Ansofino., Juita, Erna., Jolianis. (2012). Model sistem pembayaran jasa lingkungan dalam kaitannya dengan konservasi sumberdaya air dan lahan: Studi kasus pada Batang Anai Sumatera Barat. Economica, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 1, Oktober 2012
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 99
Duong, N. T. B., & De Groot, W. T. (2020). The impact of payment for forest environmental services (PFES) on community-level forest management in Vietnam. Forest Policy and Economics, 113 (December 2019), 102135. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102135
Falah. F., & Purwanto. (2018). Kelembagaan mitigasi kekeringan di Kabupaten Grobogan. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. https://doi.org/10.20886/jppdas.2018.2.2.151-172
García-Amado, L. R., Pérez, M. R., Escutia, F. R., García, S. B., & Mejía, E. C. (2011). Efficiency of payments for environmental services: Equity and additionality in a case study from a biosphere reserve in Chiapas, Mexico. Ecological Economics, 70(12), 2361–2368. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.07.016
Hafizi, M.Z., Golar., & Sudhartono, A. (2016). Pola pemberdayaan masyarakat di Hulu Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Penerapan Program SCBFWM di Desa Winatu Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Selawesi Tengah). Warta Rimba. Volume 4, Nomor 1 Juni 2016.
Hairiyah, K., & Rahayu, S., (2007). Measurement of carbon stored in use various land. Bogor: World Agroforestry Centre. ISBN 978-979-319853-8.
Halengkara, Listumbinang, Totok Gunawan, & Setyawan Purnama. (2012). Analisis kerusakan lahan untuk pengelolaan daerah aliran sungai melalui integritasi teknik penginderaan jauh dan sistem
informasi geografis.Majalah Geografi Indonesia Vol 26, No. 2 September 2012 (149-173).
Indrawati, D.R., Awang, S.A., Faida, L.R.W., & Maryudi, A. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS Mikro: Konsep dan implementasi. (2016). Kawistara, Vol. 6, No. 2, Agustus 2016: 175-187.
IPCC. (2000). IPCC Special report on emissions scenarios: A special report of Working Group III of the Intergovernmental Panel in Climate Change. Emissions Scenarios, 608.
Kaplowitz, M. D., Lupi, F., & Arreola, O. (2012). Local markets for payments for environmental services: Can small rural communities self-finance watershed protection? Water Resources Management, 26(13), 3689–3704. https://doi.org/10.1007/s11269-012-0097-y
Karuniasa, M., & Prambudi, P.A. (2019) Transition of primary forest to secondary forest and impact for water resources conservation. Journalof Environmental Science and Sustainable Development, 2(1) 15-25. https://doi.org/10.7454/jessd.v2i1.34
Ketterings, Q. M., Coe, R., Noordwijk, M. v., Ambagau,Y., & Palm, C. A. (2001). Reducing uncertainty in the use of allometric biomass equations for predicting above-ground tree biomass in mixed secondary forest. Forest Ecology and Management, 146: 199-209.
Khairiyah, R.N., Prasetyo, L.B., Setiawan, Y. Kosmaryandi, N., (2016). Minitoring model of payment for Environmental Service (PES) implementation in Cidanau
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ….........…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
100 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Watershed with stands density approach. Procedia Environmental Sciences 33 (2016) 269-278.
Legowo., (2005). Konsep teknologi pengendalian banjir dan mengatasi kekeringan. Seminar Pengelolaan DAS Citarum dalam rangka pengendalian banjir dan mengatasi kekeringan. Aula Pusdiktek, 26 Mei 2005. Cicaheum Bandung.
Marshall, D.C.W., & A.C., Bayliss. (1994). Flood estimation for small catchments. Institute of Hydrology Oxford.
Mawahan, Annazili & Soedarjanto. (2019) Model pengelolaan terbaik untuk keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pada Sub DAS Ciliwung Hulu. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Doi https://doi.org/10.20886/jppdas.2019.3.1.79-88
MEA (Millenium Ecosystem Assessment). (2005). Ecosystem and human well-being. Island Press. Washington, DC.
Mustajoki, J., Saarikoski, H., Belton, V., Hjerppe, T., & Marttunnen, M. (2020). Utillizing ecosystem services classificacions in multi-criteria decision analysis-experiences of peat extraction case in Finland. Ecosystem Services. 41 (2020) 101049.
Napitupulu, D. F., Asdak, C., & Budiono, B. (2014). Mekanisme imbal jasa lingkungan di Sub DAS Cikapundung (Studi kasus pada Desa Cikole dan Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Ilmu Lingkungan, 11(2), 73. https://doi.org/10.14710/jil.11.2.73-83
Nurfahmi, Putri, Rizal Faozi Malik, Ratih Paniti Sari, & Afid Nurkholis. (2015).
Influence of local wisdom to prevent disappearance of Cebong Lake in Sembungan Village Wonosobo District. Proceedings of International Confrence on Appropriate Technology Development, pp.165-168.
Nurviana, Vina. (2016). Analisis biaya
manfaat pengelolaan hutan di Sub
DAS Prambanan Kecamatan Kejajar,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi awa
Tengah.Tesis.Sekolah Pasca Sarjjana
Fakultas Geografi: Universitas
Gadjah Mada.
Permen No P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai
Permen No P.67/Menhut-II/2014 tentang Sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai
Putri, M.A., Risanti, A.A., Cahyono, K.A., Latifah, L., Rahmawati, N., Ariefin, R.F., Prameswari, S., Waskita, W.A., Adjie, T.N., & Cahyadi, A. (2018). Sistem aliran dan potensi air tanah di Sebagian Desa Sembungan Ditinjau dari Aspek Kuantitas dan Kualitas. Majalah Geografi-Indonesia Vol. 32, No.2, September 2018 (155-161).
Pramanik, P.D., & Ingkadijaya, R. (2017) The impact oftourism on village society and its environmental. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 145 (2018) 012060. https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012060
Risanti, A.A., Cahyono, K.A., Latifah., Putri, M.A., Rahmawati, N., Ariefin, R.F., Prameswari, S., Waskito, W.A., Adjie, & T.N., Cahyadi, A. (2018). Hidrostratigrafi akuifer dan estimasi potensi air tanah bebas guna
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol. 4 No.1, April 2020 : 79-102
E-ISSN: 2579-5511/ P-ISSN: 2579-6097
@2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license. 101
mendukung kebutuhan air Desa Sembungan. Majalah Geografi Indonesia Vol. 32, No.1, Maret 2018 (108-114).
Ratna Reddy, V., Saharawat, Y.S., & George, B. (2017) Watershed management in South Asia: A Synoptic Review. Journal of Hydrology 551 (2017) 4-3
Rismunandar, Kusmana, C., & Syaufina, L. (2016). Strategi kebijakan jasa lingkungan secara berkelanjutan di Taman Nasional Gunung Ciremai Kuningan - Jawa Barat (Policy strategy for sustainable water environment services management at Mount Ciremai National Park Kuningan-West Java). Jurnal Penglolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 6(2), 187–199.
Sartohadi, J. (2004). Geomorfologi tanah DAS Serayu Jawa Tengah. Majalah Geografi Indonesia. Volume 18 Nomor 2 September 2004. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur. Yogyakarta.
Setiawan, M.A. (2012). Integrated soil rsk management. PhD Thesis. University of Innsbruck, Austria.
Sihite, Jamartin. (2001). Evaluasi dampak erosi tanah model pendekatan ekonomi lingkungan dalam perlindungan DAS: kasus Sub-DAS Besai DAS Tulang Bawang Lampung. Disertasi. Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor.
Sharma, A., & Kukreja, S. (2012) Economic contribution of tourism industry towards society. International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 10, October-2012.
Sudaryono. (2012). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu konsep
pembangunan berkelanjutan.Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.3, No. 2, Mei 2002: 153-158.
SK Menhut No SK.328/MenhutII/2009 tentang Penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014.
TEBB. (2010). The Economics of ecosystems and biodiversity. Ecological and Economic Foundations. United Nations Environmnetal Programme. New York.
Ulya, Nur Arifatul, Efendi Agus Waluyo, Adi Kunarso, & Tubagus Angga Anugrah Syabana. (2017) .Bagaimana imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS secara terpadu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Fakta dan potensi DAS Musi. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu. LPPM Universitas Riau.
Widicahyono, A., Awang, S.A., Maryudi, A., Setiawan, M.A., Rusmidi, A.U., Handoko, D., & Muhammad, R.A. (2018). Achieving sustainable ese of environment: a Framework for payment for protected forest ecosystem service. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 148(2018) 012019. https://doi.org/10.1088/1755-1315/148/1/012019
Winastuti, R. (2017). Analisis cadangan carbon atas permukaan pada kebun campuran di DAS Bompon dengan pendekatan sistem dinamik. Skripsi. Fakultas Geografi: Universitas Gadjah Mada.
Aplikasi Metode Sidik Cepat Jasa ….........…(Anang Widicahyono, San Afri Awang,, Ahmad Maryudi, dan M. Anggri Setiawan)
102 @2020 JPPDAS All rights reserved. Open access under CC BY-NC-SA license.
Wegner, G. I. (2016). Payments for ecosystem services (PES): a flexible, participatory, and integrated approach for improved conservation and equity outcomes. Environment, Development and Sustainability, 18(3), 617–644. https://doi.org/10.1007/s10668-015-9673-7.
Yuliasmara, F., and Dignity, A. (2007). Measurement of carbon stored in cocoa pantation biomass plant approach. Warta The research center Indonesian Coffee and Cocoa, 3.pp. 149-158.
PEDOMAN BAGI PENULIS (AUTHOR GUIDELINES) JURNAL PENELITIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
BAHASA: Karya Tulis Ilmiah (KTI) ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris
LANGUAGE: Scientific paper (KTI) is written in Indonesian or English
FORMAT: Naskah diketik pada kertas A4 (210 x 297 mm), huruf Calibri, ukuran font 12 dan dengan spasi 1,15. Pada semua tepi disisakan ruang kosong 2,5 cm. KTI diserahkan dalam format Microsoft Words.
FORMAT: The manuscript is typed on an A4 paper (210 x 297 mm), calibri size 12, and 1.15 space. Margin on all edges are 2.5 cm. The manuscript is submitted in MS words format.
JUDUL: Judul KTI harus singkat dan informatif, tidak lebih dari dua baris dan mencerminkan isi tulisan. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan ukuran font 12 dan menggunakan huruf kapital semua (terjemahan dalam bahasa Inggris ditulis miring dengan huruf kapital hanya pada permulaan judul atau yang menyatakan suatu nama, diletakkan di antara tanda kurung), hindari pemakaian kata kerja, rumus, singkatan, dan bahasa tidak resmi.
TITLE: Title of the scientific paper should be short and informative, no more than two lines and reflects the contents. The title is in Indonesian and English. The title in Indonesian is written in Calibri, font size 12, bold, uppercase, center. The title in English is written in calibri, font size 12, italics, sentence case, placed between parentheses. Avoid the use of verbs, formulas, abbreviations, and unofficial language.
NAMA PENULIS: Dicantumkan di bawah judul, ditulis lengkap tanpa gelar akademik, urutan berdasarkan penulis pertama, kedua dan seterusnya, disertai alamat lengkap instansi (Italic font) dan email penulis (Italic font).
NAME OF AUTHOR(S): Listed below the title, complete name without the academic degrees, the sequence based on the first author, second etc., accompanied by complete institution addresses (Italic font) and email addresses (Italic font).
ABSTRAK: Penulisan abstrak Bahasa Inggris (Italic font) dan Bahasa Indonesia, tidak lebih dari 250 kata, ditulis dalam satu paragraf, secara ringkas, jelas, utuh, mandiri, dan terdiri dari permasalahan, tujuan, metoda, dan hasil penelitian.
ABSTRACT: Abstract is written in English (Italic font) and Indonesian, no more than 250 words, written in one paragraph, concise, clear, and complete, . It consists of research problems, methods, and research findings.
KATA KUNCI: Tiga sampai lima kata kunci yang mencerminkan substansi naskah ditulis terpisah dengan menggunakan titik koma.
KEY WORD: Three to five key words reflect the substantive of the research, separated by semicolon.
PENDAHULUAN: Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang ada, hasil - hasil penelitian terkait sebelumnya (state of the art), pentingnya penelitian yang dilakukan dan tujuan penelitian.
INTRODUCTION: Introduction must contain background of the existing problems, state of the art, important of the research and the purpose of the research.
BAHAN DAN METODE: Lokasi penelitian diterangkan secara geografis disertai peta lokasi penelitian, bahan dan alat yang digunakan diterangkan dengan jelas. Metode penelitian dijelaskan secara detil (desain penelitian, perlakuan, rancangan percobaan, metode dan skala analisis, dan lain-lain yang terkait metode) sehingga dapat diulang oleh peneliti lain. Metode yang sudah dipublikasikan harus dicantumkan sumbernya.
MATERIALS AND METHODS: Location of the research is described geographically completed with a map of the study sites. Materials and instruments used should be clearly defined. Research methods are described in detail (research design, treatments, experimental design, methods and scale of analysis, and other related methods) so that it can be repeated by other researchers. Published methods must be included the source.
HASIL DAN PEMBAHASAN: Hasil penelitian disampaikan secara singkat dan jelas. Data yang ditampilkan sudah dianalisis dan relevan, disusun sesuai tujuan penelitian. Data dan informasi dalam Tabel, grafik, dan gambar dilengkapi tafsiran yang benar. Dalam pembahasan data hasil penelitian ditafsirkan dan dikaitkan dengan tujuan, hipotesis (jika ada), diberikan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi, dikemukakan hubungan dengan hasil penelitian sebelumnya, dan dikemukakan sitasi dari literatur yang sesuai.
RESULT AND DISCUSSION: The research results must be clear and short. The presented data have been analyzed and relevant, prepared according to the purpose of the research. Data and information in the tables, graphs, and pictures need to be conveyed with the correct meaning or interpretation. In the discussion, data are interpreted according to the objectives, the hypothesis (if any), explained why it happened, put forward relationship with the results of previous research, and proposed citation of the appropriate literatures.
KESIMPULAN: Hasil terpenting dari penelitian disampaikan dalam kesimpulan yang digunakan untuk menjawab tujuan, hipotesis serta temuan lain selama penelitian. Kesimpulan bukan merupakan ulangan dari abstrak, tetapi mengelaborasi hasil-hasil penelitian yang signifikan. Kesimpulan memuat saran-saran yang merupakan implikasi penelitian yang harus dilakukan lebih lanjut.
CONCLUSIONS: The most important results of the research are presented in the conclusions used to answer the objectives, hypotheses and other findings during the study. Conclusion is not a repetition of the abstract, but elaborates of significant research results. The conclusions contain suggestions which are the implications on further research.
TABEL: Judul tabel, kolom, lajur, dan sumber data serta keterangan ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (dicetak miring) dengan singkat tetapi jelas serta tidak tebal. Judul tabel ditulis dengan font ukuran 10, spasi 1 dan huruf capital pada awal kalimat. Tabel diberi nomor urut sesuai dengan keterangan di dalam teks. Penggunaan tanda koma (,) dan titik (.) pada angka di dalam tabel masing-masing menunjukkan nilai pecahan/ desimal dan kebulatan seribu. Keterangan tabel diletakkan di bawah tabel. Tabel harus dalam format Microsoft Words. Tabel tidak menggunakan garis vertikal. Garis horizontal terletak pada judul kolom atas, sub judul dan akhir tabel (garis penutup tabel). Apabila tabel terpotong karena pergantian halaman, header ditampilkan kembali pada halaman selanjutnya. Tabel dapat diunggah menggunakan file terpisah (supplementary materials) dengan memberi tanda posisi tabel pada naskah. Tabel harus mencantumkan sumber. Apabila tabel merupakan hasil analisis primer, maka dapat ditulis sebagai analis data beserta tahun.
TABLES: The title of table, column, row, data source and description are written in
Indonesian and English (Italic font), short but
clear and not bold. The font size of the table title is 10 with spaces 1 and capital letter at the beginning of the sentences. The table is given number according to the description in the text. The use of comma (,) and dot (.) in the table indicate the value of fraction/ decimal and roundness of a thousand. Table descriptions are placed under the table. The table should be in MS Word format. Tables can be uploaded using a separate file (supplementary materials) by giving mark table positions on the manuscript. Table does not use vertical lines. The horizontal line lies in the top column heading, subheadings and at the end of the table (the closing table). If the table is cut off due to page changes, the header is displayed again on the next page. The table should mention its source. If the table is the result of primary data analysis, then it can be written as a data analysis and accompanied with the year.
GRAFIK/GAMBAR/FOTO : Grafik, peta, dan ilustrasi lain yang berupa gambar garis harus kontras, diberi nomor urut. Judul beserta isinya ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris dicetak miring), diberi nomor urut. Judul gambar ditulis dengan ukuran 10 dengan huruf kapital pada awal kalimat. Grafik dapat diunggah secara terpisah (supplementary materials) dari file utama (naskah KTI) dalam format MS Words dengan memberi tanda posisi grafik pada naskah. Resolusi gambar minimal 300 dpi. Gambar dan judul diletakkan pada posisi tengah/center. Gambar harus mencantumkan sumber. Apabila gambar berasal dari foto koleksi pribadi maka dapat ditulis sebagai koleksi pribadi beserta tahun.
GRAPHS/FIGURES/PHOTOS: Graphs, maps and other illustrations in line drawings should be in contrasted, numbered sequentially. Title and contents are written in two languages, Indonesian and English (in italic), numbered sequentially with its explanatory. The title is in font size 10 with capital letter at the beginning of the sentences. Graphs can be uploaded separately (supplementary materials) from the main file (KTI manuscipt) in MS word format by giving mark the chart position in the script. Image resolution is at least 300 dpi. The titles and graphs are placed in the center. The image must specify the sources. If the image comes from a private collection, it can be written as a private collection with year.
Rumus :Rumus ditulis dengan ukuran font 10. Setiap rumus yang ditampilkan harus diberi nomor sesuai urutan dalam naskah. Nomor urut diberi tanda kurung dan berada sejajar dengan rumus yang dihubungkan tanda titik sampai batas kanan naskah.
FORMULA: Formula is typed in font size 10. Each presented formula should be numbered sequentially in the script. The sequential number is bracketed and parallel to the formula connected with dots to the right margin of the manuscript.
UCAPAN TERIMA KASIH : Disarankan menyampaikan ucapan terimakasih kepada organisasi atau person yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun.
ACKNOWLEDGEMENT: It is recommended to convey gratitudes to the organization or person who has assisted the author in any form.
DAFTAR PUSTAKA : Memuat pustaka yang benar-benar dirujuk, dengan demikian pustaka yang dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis pada bagian–bagian sebelumnya. Cara penyitiran dan penulisan daftar pustaka merujuk kepada The American Psychological Association (APA) style 6th. Untuk mempermudah dan menjaga konsistensi pengutipan serta penulisan daftar pustaka perlu menggunakan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis seperti Mendeley https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/). Daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang, 80% dari pustaka merupakan terbitan 5 tahun terakhir dan 80% berasal dari sumber acuan primer, kecuali buku teks ilmu-ilmu tertentu.
REFERENCES: It contains all references that are actually referred to. Thus the references included in this section will be found written in the previous sections. The way to edit and write a bibliography refers to The American Psychological Association (APA) style 6th. To make it easier and keep consistency of citation and bibliography writing, it is necessary to use free downloadable applications such as Mendeley (https://www.mendeley.com/ download-mendeley-desktop/). The references are arranged according to author's name alphabet. Eighty % of the literature is published in the last 5 years and 80% comes from primary reference sources, except for textbooks of certain sciences.