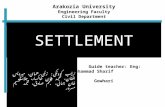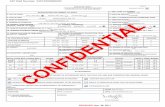Valuasi Human Settlement Delta Api
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Valuasi Human Settlement Delta Api
Valuasi Ekonomi Pengembangan ‘Human Settlement’ Di Wilayah Pesisir Kajian Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Pesisir Desa Gondang Sebagai
Bagian Dari Desa Ekologis Tangguh dan Adaptif Perubahan Iklim (Delta
Api) Kabupaten Lombok Utara
Gendewa Tunas Rancak
4113205004
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Program Studi Pasca Sarjana Teknik manajemen Pantai
Fakultas Teknologi Kelautan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2013
BAB 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 13.446
(nationalgeographic.co.id, 2012) dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000.
Indonesia memiliki 33 Provinsi dan lebih dari 400 kabupaten berada di 5 pulau
(daratan) besar (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua) dan sebagaian besar
lainnya berada di kepulauan.
Modernisasi dan kemajuan zaman adalah suatu keniscayaan dan telah memberikan
kontribusi bagi kita. Namun jika tidak disertai dengan tindakan yang bijak, maka sangat
dimungkinkan akan menjadi satu masalah baru dalam masyarakat kita, khususnya di
daerah perdesaan, marginal perkotaan dan kawasan sumberdaya alam. Masyarakat
desa (masyarakat adat) telah memiliki sistem tersendiri dalam membangun dan
mengelola kawasan hidupnya, yaitu dengan mengembangkan suatu kearifan, turun
temurun, yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadukan dengan norma
adat, nilai budaya, dan aktivitas pengelolaan lingkungan guna mencukupi kebutuhan
hidupnya.
Namun, apa yang terjadi saat ini, sungguh disayangkan bahwa modernisasi (Orba) telah
merusak apa yang telah dihasilkan oleh masyarakat atau warga kepulauan. Sistem
formal yang dikembangkan oleh pemerintah ternyata justru mengubah, bahkan
menyeragamkan sistem lokal yang ada. Perubahan ini dikhawatirkan akan merubah
karakter warga desa menjadi karakter yang oportunis dan eksploitatif bahkan
destruktif terhadap alam, karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup.
Ditilik dari kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana, maka kawasan pesisir
merupakan daerah yang memiliki resiko lebih besar dibanding dengan daratan besar
atau pedalaman. Oleh karena pertimbangan hal ini, Kementrian Kelautan Perikanan
(KKP) menggagas dan mengembangkan Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh
(PDPT). Jika tidak dilakukan secara matang, tidak menutup kemungkinan akan terjadi
hal yang sama dengan gagasan besar lainnya, yakni menjadi monumen nama tanpa
karya nyata yang berhasilguna dan termanfaatkan secara berkelanjutan.
Sejumlah 8 provinsi kepulauan (Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Kepri, Babel, dan
Sulut) di Indonesia memiliki ekosistem dengan satuan sistem lokal yang unik. Daratan
dengan penduduk dan ketersediaan pangan, air, dan energi yang tidak seimbang antara
gugus pulau yang satu dengan yang lainnya (untuk Provinsi Bali masih terjadi
pemaknaan yang berbeda antara warga dan Pemerintah Provinsi Bali). Hal ini
menyebabkan bertumbuh kembangnya kearifan lokal yang saling bergantung. Kekayaan
ragam hayati yang dimiliki bisa menjadi alternatif sumber pangan, terlebih di kawasan
lautannya. Namun harus diakui selain terbatas (daratan) apa yang ada sesunguhnya
memiliki kerentanan yang tinggi, terlebih jika dikaitkan dengan perubahan iklim dan
bencana.
Gambar1. Sunda Kecil-Maluku
Pulau Lombok, walaupun menurut UU No 27 tahun 2007 tidak terkategorikan sebagai
pulau kecil, namun menurut United Nation Convention on the law of Sea (UNCLOS)
termasuk dalam kategori pulau kecil karena luasnya kurang dari 10.000 km2. Gugusan
pulau ini memiliki desa dan dusun kepulauan , seperti Desa Gili Matra (KLU) dan Gili
Gede (Kabupaten Lombok Barat). Sebagaian pantai bertautan dengan laut lepas dan
sebagaian bentukan pantai berbentuk teluk dan tanjung merupakan potensi pangan
yang belum tergarap secara optimal, baik sebagai sumber pangan, ekonomi, maupun
energi. Sebagian telah tergarap sebagai kawasan wisata, namun belum memberikan
manfaat yang memadai bagi masyarakat. sebagian besar masyarakat miskin justru
berada di kawasan pesisir, termasuk di kawasan wisata ini. Bentang lanskap daratan
yang terbatas (telah mengalami degradasi dan deforestasi) dengan bentang laut lepas
sangat mempengaruhi iklim mikro.perubahan iklim, telah menyebabkan perubahan dan
dampak signifikan, dengan cuaca yang tidak bisa lagi diprediksi.
Gambar 2. Pulau Lombok
Pembelajaran yang dilakukan di Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Utara
(KLU), telah melahirkan konsep Eco-Climate Village (ECV) yang diharapkan dapat
menjawab persoalan, kebutuhan, hak dan kemampuan berpengalaman warga pesisir
dalam menghadapi perubahan iklim.
Gambar 3. Eco-Climate Village Dusun Jambianom, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara
KLU adalah kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan daerah
pemekaran di Pulau Lombok, NTB. Sebagai Kabupaten Baru, kondisi ekonomi
masyarakatnya masih subsisten dan merupakan tingkat kemiskinan terendah di NTB
(43,13%). Posisi KLU sedemikian rupa sehinga kerentanan yang lebih tinggi terhadap
dampak kebencanaan dan akibat perubahan iklim, terutama tentu saja di wilayah
pesisir. namun, dibanding dengan kabupaten lainnya di Lombok dan NTB secara umum,
kearifan lokal di KLU masih lebih utuh dan eksis, termasuk dalam menghadapi
perubahan iklim dan kebencanaan. Namun harus diakui bahwa kondisi saat ini mulai
mengalami degradasi dan marginalisasi. Baik yang dikarenakan ketidak tepatan ruang
dan waktu, maupun karena cepatnya perkembangan informasi global dan kuatnya
dominasi kebijakan dan program nasional.
Karena alasan-alasan ini, kabupaten ini dipilih untuk bisa dikembangkan dan menjadi
role model dalam kerangka pengembangan kawasan yang komprehensif, perspektif
kepulauan dan responsif perubahan iklim dan kebencanaan, sesuai dengan agenda
perubahan yang diusung dalam Konferensi Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2010 dan
Kongres Warga Sukma++ (Sunda Kecil Maluku plus pulau-pulau kecil lainnya) pada
tahun 2012
Konsep ECV merupakan sebuah konsep pengelolaan pesisir terpadu dan adaptif
terhadap perubahan iklim yang disusun dengan pertimbangan aspek legalitas, ekologis,
ekonomi, sosiologis, dan kearifan lokal (local wisdom). Konsep ini mengintegrasikan
antara bottom-up concept, yaitu konsep (pemetaan partisipatif) dan keinginan jangka
panjang masyarakat pesisir dengan top-down concept, yaitu konsep pengelolaan pesisir
terpadu sebagai sebuah upaya sustainable development. Konsep ini memperoleh respon
positif dari berbagai pihak, karenanya layak untuk dilanjutkan implementasi dan
penyebarannya. Konsep ini juga sangat memungkinkan untuk diintegrasikan dalam
PDPT ataupun skala yang lebih luas, bahkan gabungan dari beberapa desa dapat
menjadi bagian (entry point) untuk pengembangan kawasan mina politan.
Berangkat dari kedua konsep ini (ECV dan PDPT), maka lahirlah sebuah formula baru
berupa Delta Api (Desa Ekologis Tangguh dan Adaptif Perubahan Iklim) yang
diwujudkan dalam bentuk Scalling up konsep menjadi kawasan, dimana satu kawasan
terdiri dari 3 Desa. Desa Gondang (Spesifikasi di Dusun Lekok), Desa Medana, dan Desa
Gili indah dipilih sebagai role model pengembangan Delta Api di wilayah Kabupaten
Lombok Utara. Ketiga desa ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya,
untuk itu, konsep pengembangannya juga harus sesuai dengan kondisi eksisting,
partisipatif, dan karakteristik yang dapat dikembangkan.
Selain itu, replikasi dan scalling up dilakukan di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku
Utara. Desa Pulau Koloray dan Desa Pulau Galo-Galo menjadi role model kawasan Delta
Api di Maluku Utara. Konsep pengelolaan kawasan ini berperspektif pada persiapan
masayrakat Desa Pesisir untuk menyambut mega konsep nasional dalam pemanfaatan
Doc. Rumah Alir
sumber daya kelautan di Kabupaten Pulau Morotai, Megaminapolitan Morotai yang
akan di realisasikan pada tahun 2016.
Model yang sedang dan akan dikembangkan dilakukan di kawasan yang dianggap
memiliki resiko tinggi terhadap perubahan iklim, namun memiliki potensi untuk
pembelajaran baik dalam pengelolaan ekologi, pemberdayaan ekonomi maupun
penguatan social dan kebijakan.
Konsep ini juga akan disinergikan dengan analisa kerentanan terhadap dampaj
perubahan iklim dengan metode I- CATCH (Indonesia-Climate Adaptation Tools for
Coastal Habitat) yang telah dilakukan di 25 desa di Pulau Lombok, dimana 10 Desa
berada di wilayah Kabupaten Lombok Utara, dan merupakan lokus kawasan Delta Api.
Sebelumnya, tools ini disesusaikan fungsi dan peruntukannya sehinga lebih sesuai
dengan konsep Delta Api.
Kolaborasi, sinergi, dan integrasi ketiga ‘wadah’ tersebut (ECV, PDPT, dan I-CATCH
menjadi Delta Api) harapannya dapat menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan, dan
menjadi stimulus bagi perencanaa pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil
sebagai adaptasi perubahan iklim
Saat ini, ketiga sinergi ini lebih disempurnakan dengan menambahkan Pemetaan
partisipatif dan advokasi Anggaran ketika Replikasi dan scalling up di Dompu, Sumba,
dan Bali. Kedepannya dirasa perlu untuk menambahkan analisis Valuasi Ekonomi dalam
Konsep Delta Api. Untuk itu, sebagai awal, maka valuasi ekonomi akan diujicobakan
pada satu lokus Delta Api di Kabupaten Lombok Utara, yakni Desa Gondang.
1.2 Output
Master Plan Kawasan dan Perdesaan yang berperspektif kepulauan dan adaptif
perubahan iklim/ kebencanaan yang sekiranya dapat dijadikan acuan bersama;
pengeimplementasian program yang sistemik dan kolaboratif. Valuasi Ekonomi SUmber
Daya Alam Pesisir dalam pengembangan Desa Ekologis Tangguh dan Adaptif Perubahan
Iklim di Desa Gondang, Kabupaten Lombok utara.
1.3 Outcome
Pengelolaan SDA dan rung hidup Kawasan perdesaan dapat menjamin keselamatan
warga, daya pulih produktifitas warga dan daya pulih jasa lingkungan secara
berkelanjutan. Utamanya dalam bidang pangan, air, energy dan matapencaharian untuk
pemenuhan pangan dan sandang; Kepemimpinan yang berkemampuan untuk
melakukan ‘Self Organizing Capability’ dalam membangun kemandirian warga dan
keberlanjutan kawasan perdesaan kepulauan.
BAB 2. Gambaran Umum Kondisi Eksisting dan Iklim Desa Gondang
2.1 Gambaran Umum Desa Gondang
Desa Gondang terletak di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Desa Gondang
merupakan wilayah dengan luas sebesar 29,20 Km2. Kondisi alam di desa ini masih
didominasi oleh tanah kering dan hanya sebagian kecil saja yang menjadi areal
persawahan. Gondang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utaranya, oleh
karenanya sebesar 75 % masyarakat yang berada di wilayah pesisir Desa Gondang
mengandalkan laut sebagai pusat penghidupan. Jika sedang tidak melaut (cuaca buruk)
masyarakat nelayan Desa Gondang menjadi tukang bangunan, buruh tani, buruh
bangunan, buruh pasar
Gambar 4. Lokasi Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok utara
Sebagai masyarakat nelayan, penduduk Gondang melakukan aktifitas terkait dengan
pesisir dan laut. Seiap pagi pukul 05.00 nelayan Gondang setiap berada di perahu
masing-masing. Mereka melaut sampai sejauh 1 jam perjalanan dari tepi pantai,
sesampainya di darat pukul 08.00 membawa ikan (I-CATCH Desa Gondang, 2012).
Gambar 5. Sketsa Desa Gondang
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012
Berdasarkan Sketsa desa yang dibuat oleh peserta, terdapat dua penghidupan besar
bagi masyarakat Gondang yaitu penghidupan pesisir/laut sebagai nelayan dan
penghidupan sebagai petani persawahan. Nelayan Gondang mencari ikan diperairan
sebelah Utara Desa Gondang (laut jawa). Mereka mencari ikan di perairan dekat pantai
bahkan mampu berlayar sampai ke kejauhan (ke tengah laut) hingga darat tidak bisa
terlihat.
Selain itu, Desa Gondang juga memiliki areal persawahan kurang lebih seluas 400 ha.
Lokasi arel persawahan ini tersebar di beberapa lokasi, termasuk diantaranya di
sepanjang pesisir laut bagian utara desa. Curah hujan rata-rata 1.958,5 mm/tahun
dengan suhu rata-rata hariannya 28 – 350 C.
Di desa juga terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD) 2 buah,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 buah, Kantor Posyandu 1 buah (Azzahra),
Puskesmas 1 buah, dan Kantor Polisi Sektor Kecamatan. Terdapat pula kantor Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Utara. Selain itu, terdapat fasilitas
sosial keagamaan seperti masjid besar sebanyak 2 buah dan satu bidang tanah sebagai
tempat pemakaman umum yang terletak di bagian selatan Desa Gondang (I-CATCH
Desa Gondang, 2012)
2.2 Kondisi Iklim Desa Gondang
Tabel 1. Kalender Musim Desa Gondang
MUSIM Bulan
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANGIN BARAT
- Melaut di dekat pantai - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Sebagai buruh tani - Sebagai buruh bangunan
ANGIN BARAT LAUT
- Melaut hanya ± 10 hari - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Sebagai buruh tani - Sebagai buruh bangunan - Budidaya ikan nila di keramba
TIMUR LAUT
- Melaut normal seperti biasa - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Budidaya ikan nila di keramba
ANGIN TIMUR
- Melaut normal seperti biasa - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Budidaya ikan nila di keramba
ANGIN SAYONG
- Melaut normal seperti biasa - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Budidaya ikan nila di keramba
BARAT DAYA
- Melaut normal seperti biasa - Bertani bagi yang punya sawah - Istri berjualan di pasar - Budidaya ikan nila di keramba
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012
Berdasarkan kalender musim di atas, pada bulan Desember, Januari dan Februari terjadi musim angin barat di mana pada kondisi ini terjadi cuaca buruk seperti; angin kencang dan ombak besar. Aktifitas masyarakat nelayan yang biasanya melaut ke tengah akan berpindah di daerah dekat pantai, dampak secara langsung yang dirasakan yaitu berkurangnya hasil tangkapan ikan bahkan ada juga yang tidak melaut sama sekali, masyarakat nelayan yang memiliki lahan pertanian, mereka lebih memilih menggarap sawahnya untuk menanam padi dan kacang tanah. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan, begitu juga dengan istri nelayan yang ikut serta membantu suaminya berjualan dipasar tradisional (I-CATCH Desa Gondang, 2012). Pada bulan Februari tahun 2009, daerah kawasan pesisir desa Gondang pernah terjadi banjir bandang yang cukup besar. Peristiwa ini disebabkan oleh karena hujan dan angin
yang berlangsung selama 3 (tiga) minggu dan permukaan air laut meningkat. Hal ini menyebabkan rumah-rumah penduduk dan lahan-lahan pertanian disekitar wilayah pesisir terendam, begitu juga dengan perahu-perahu nelayan banyak yang hanyut, yaitu ± sekitar 22 perahu yang ikut terbawa arus. Setelah banjir bandang terjadi yaitu pada bulan Maret, pada kalender musim menunjukkan musim barat laut, aktifitas masyarakat nelayan kembali seperti biasa namun ombak juga masih pada kondisi musim angin laut dan nelayan hanya menangkap ikan di pinggir pantai. Nelayan melaut hanya berlangsung selama ± 10 hari, hal ini disebabkan karena banyak kotoran seperti lumpur (lebok) yang nyangkut di jaring nelayan yang disebabkan oleh banjir. Pada musim ini aktivitas pertanian sudah kembali normal, istri-istri nelayan membantu sebagai penjual di pasar dan ada juga yang bekerja sebagai buruh tani. Selain itu juga masyarakat mencoba untuk membuat keramba untuk budidaya ikan nila. Musim angin timur terjadi pada bulan Mei dan Juni, aktifitas masyarakat di Desa Gondang normal yaitu melaut, bertani dan budidaya ikan nila di keramba. Begitu juga dengan istri-istri nelayan tetap membantu suami berjualan ikan di pasar tradisional. Bulan Juli dan Agustus berada pada musim angin selatan (sayong), aktifitas masyarakat juga normal seperti pada musim angin timur. Hal yang sama juga pada musim angin barat daya, tidak ada perubahan yang terjadi yaitu aktifitas masyarakat juga normal. Dampak yang paling menonjol dan membebani masyarakat di Desa Gondang pada saat angin barat yaitu berkurangnya hasil tangkapan ikan dan hasil-hasil pertanian lainnya seperti beras dan kacang tanah karena sawah-sawah pertanian juga banyak yang terendam air hujan dan air laut yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut, tetapi pada saat banjir kecil terjadi, masyarakat memanfaatkan banjir untuk mencari kayu bakar bahkan kayu bangunan yang ikut hanyut bersama arus air dari luar Desa Gondang melewati sungai. Adapun harapan yang diinginkan oleh masyarakat wilayah pesisir Desa Gondang pada kondisi angin barat yaitu adanya peran pemerintah daerah terkait yang menangani masalah kondisi iklim di daerahnya seperti adanya penyuluhan atau sosialisasi dari BMKG setempat agar supaya masyarakat memahami kondisi atau tanda-tanda cuaca buruk yang akan terjadi sebelumnya (I-CATCH Desa Gondang, 2012).
2.2.1 Kondisi Iklim Desa Gondang
Tabel 2. Pola Musim Desa Gondang
Musim
Perubahan yang terjadi
saat ini di banding dahulu
Perubahan yang akan
terjadi di masa yang akan
datang
Keterangan
Lamanya musim kemarau
Semakin panjang
Semakin panjang Tahun 2012 kemarau panjang
Lamanya musim hujan Semakin pendek
Semakin pendek Tahun 2009 sampai 2010, hujan terus sampai banjir bandang.
Awal musim kemarau Tidak teratur Tidak teratur Bulan Mei tidak teratur dan sebentar (tahun 1990), semakin panjang , panas dan angin
Awal musim hujan Tidak teratur Tidak teratur Bulan Oktober, musim hujan panjang (Tahun 1990)
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012
Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2010 musim hujan
yang panjang hingga terjadi banjir bandang yang menghanyutkan kapal nelayan ±
sekitar 22 buah. Awal musim kemarau pada tahun 1990 tidak teratur, bahkan dirasakan
oleh masyarakat Desa Gondang pada tahun 2012 terjadi musim kemarau panjang (I-
CATCH Desa Gondang, 2012).
Tabel 3. Perubahan Komponen Cuaca Desa Gondang
Komponen Cuaca Saat Ini Perubahan yang akan datang
Suhu udara Meningkat Semakin meningkat
Suhu laut Masih normal Tidak tau / naik apa turun Curah hujan - Semakin tinggi
- Tidak beraturan - Jangka hujan semakin pendek
Tidak tau
Kecepatan Angin Normal tergantung musim Masih normal/tetap Tinggi Gelombang Masih stabil Masih stabil 1990 Perubahan yang terjadi saat ini
dibandingkan dengan dahulu 2012 : Perubahan yang akan berlangsung di masa mendatang menurut perkiraan masyarakat : 1. Jembatan rusak 2. Irigasi rusak 3. Keramba hanyut 4. Longsor 5. Utang 6. Gali lobang tutup lobang 7. Pendapatan kurang 8. Ibu-ibu :Tidak bisa jualan di pasar
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012 Kecenderungan kondisi cuaca menurut sepengetahuan masyarakat dari dulu hingga sekarang dirasakan semakin meningkat, begitu juga dengan suhu air laut. Curah hujan dirasakan semakin besar pada saat musim hujan dan tidak teratur. Kecepatan angin juga dirasakan bertambah kencang tetapi tinggi gelombang dari dulu hingga sekarang dirasakan tidak ada perubahan, sama seperti biasanya. Beberapa identifikasi masyarakat perubahan yang akan berlangsung dimasa mendatang ketika bencana besar terjadi seperti; banjir bandang, kebakaran, hujan dan angin kencang, tanah longsor, dll. adalah jembatan dan saluran irigasi akan rusak. Dampak yang akan ditimbulkan dari kejadian ini yaitu seluruh aktifitas akan terhenti sehingga menyebabkan pendapatan nelayan maupun petani berkurang, sehingga masyarakat Desa Gondang mencari pinjaman untuk menyambung hidup mereka (Gali lobang tutup lobang) dan juga ibu-ibu yang bisa berjualan dipasar-pasar tradisional tidak bisa menjual ikan karena tidak adanya hasil tangkapan. Dari tahun ke tahun, kondisi cuaca di Kecamatan ini tidak banyak berubah. Jumlah hari hujan maupun curah hujan yang terjadi sepanjang tahun tidak mengalami banyak perubahan setiap tahunnya, namun fluktuatif data hari hujan selama setahun mengalami perubahan yang tajam. Berikut disampaikan data hari hujan dan curah hujan dalam kurun waktu tahun 2009 (I-CATCH Desa Gondang, 2012).
Grafik 1. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kecamatan Gangga
per Bulan Tahun 2009 (Sumber: Klimatologi Pos Sotak Kabupaten Lombok Utara 2011)
2.2.2 Analisis perubahan iklim
Proses interaksi laut dan atmosfer terjadi dalam berbagai skala waktu untuk mengontrol baik temperatur udara maupun temperatur muka laut. Skala waktu ini bermacam-macam mulai dari variasi harian (siang-malam, air pasang-air surut) hingga fluktuasi skala antara dekade (10 tahunan) dan abad (100 tahunan). Fluktuasi skala sangat panjang tersebut dapat diamati dengan menganalisis tren dari data suhu yang cukup panjang. Kondisi suhu udara di Pulau Lombok tidak banyak bervariasi secara temporal, sedangkan variasi keruangan (spasial) suhu udara lebih ditentukan oleh faktor topografi (ketinggian tempat). Dari tabel dapat dilihat bahwa di Stasiun Selaparang, mulai dari tahun 1985-2008 terdapat kenaikan suhu rata-rata bulanan sebesar 0,4°C dan suhu minimum bulanan sebesar 0,7°C, sedangkan suhu maksimum bulanan mengalami penurunan 0,5°C. Data ini mendukung hasil diskusi kelompok, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masayrakat
Tabel 4. Suhu Udara Stasiun Selaparang
Sumber: Nandini dan Narendra, 2011
219,2
357,35
161,8
85,15 102,6
43,05 15,5 8
30,65 18,25
133,85
352,2
21 28 18 14 10 5 3 6 4 6 17 26 0
50
100
150
200
250
300
350
400
Cu
rah
Hja
n (
mm
) Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Kecamatan Gangga per Bulan
Tahun 2009
Curah Hujan
Hari Hujan
Jika diamati secara lebih jauh, mulai dari tahun 1985-2008, suhu rata-rata mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Pada periode tahun 1985 suhu rata-rata adalah 26oC, kemudian naik menjadi 26,2oC di periode tahun 1992-1999, dan terakhir meningkat menjadi 26,4oC di periode tahun 2000-2008. Dengan kondisi ini, kuat dugaan bahwa suhu akan selalu naik seiring bertambahnya tahun. Aldrin dan Arifian (2008) memperlihatkan tren kenaikan muka laut di beberapa titik pantai di wilayah tengah dan Barat perairan Indonesia (Gambar 6.a). Sedangkan hasil pengukuran diperlihatkan pada Gambar 6.b, dengan laju kenaikan tempertur laut untuk masing-masing station disajikan dalam Gambar 6.c. Sofian (2009) dengan menggunakan model proyeksi kenaikan temperatur muka laut di bagian Utara dan Selatan pulau Lombok seperti terlihat pada Gambar 2.8 yang menunjukkan adanya kenaikan temperatur laut rata-rata sebesar 1,3oC di bagian Utara dan 0,2 oC di pantai Selatan pulau Lombok dalam kurung waktu 1980 sd 2008. Seiring dengan pola angin musiman maka pola SPL digambarkan pada Grafik 2.
Gambar 6. (a) Posisi titik mooring pengukuran temperatur laut, (b) hasil pengukuran
temperatur muka laut, dan (c) laju kenaikan temperatur untuk setiap stasion Sumber: Aldrin dan Arifian, 2008 dalam Analisis dan Proyeksi Hujan dan Temperatur
Pulau Lombok-GTZ, 2012
Grafik 2. SPL di Pantai Utara dan Selatan Pulau Lombok berdasarkan data NOAA OI SST
dari Januari 1961 sampai dengan September 2008 Sumber: Sofian, 2009 dalam Analisis dan Proyeksi Hujan dan Temperatur Pulau
Lombok-GTZ, 2012
Data yang ditampilkan menunjukkan bahwa terjadi kenaikan suhu air laut, walaupun pada data terakhir (Grafik 2) diukur pada wilayah utara dan selatan Pulau Lombok. Dari kedua data yang ada, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan suhu air laut secara umum di wilayah Pulau Lombok. Kenaikan suhu air laut ini mengakibatkan sejumlah ikan karang tidak dapat bertahan hidup, terutama di wilayah Desa Gili Gede Indah. Di beberapa lokasi, juga terjadi pemutihan karan (coral bleaching) akibat meningkatnya suhu air laut.
Grafik 3. Grafik komposit rata-rata bulanan curah hujan (kiri) dan temperatur (kanan)
berdasarkan data observasi di stasiun Selaparang/Ampenan untuk periode baseline 1961-1990 (biru) dan 1991-2007 (merah). Garis vertikal (error-bar) menunjukkan
standar deviasi Sumber: Analisis dan Proyeksi Hujan dan Temperatur Pulau Lombok-GTZ, 2012
Grafik 3 memperlihatkan grafik komposit rata-rata curah hujan bulanan untuk periode baseline 1961-1990 dan periode 1991-2007. Dari gambar ini dapat dilihat jelas adanya
perubahan pola curah hujan terutama di bulan Januari. Jadi dibandingkan dengan baseline, curah hujan di bulan-bulan Agustus, September (musim kering), serta Desember, Januari (musim penghujan) cenderung berkurang, sedangkan di bulan-bulan Oktober, November, Maret, dan April (musim transisi) cenderung naik. Di musim penghujan, hanya curah hujan bulan Februari yang cenderung naik. Perlu diperhatikan juga adanya kenaikan variansi (standar deviasi) untuk curah hujan di bulan-bulan Oktober dan November. Curah hujan yang terdapat pada grafik merupakan curah hujan rata-rata untuk wilayah
pulau Lombok. Hasi diskusi kelompok kajian di Desa GIli Gede Indah menunjukkan jika
curah hujan menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya (1990-an). Jika
dibandingkan dengan grafik rata-rata curah hujan di pulau Lombok, secara umum data
di grafik menunjukkan dalam setahun terdapat 6 bulan dengan curah hujan menurun
dari sebelumnya (baseline), sedangkan terdapat 6 bulan dengan kondisi curah hujan
yang justr meningkat.
2.2.3 Kejadian Bencana akibat perubahan iklim/cuaca buruk
Tabel 5. Sejarah Kejadian Bencana Desa Gondang
Bencana Dahulu Saat ini Persepsi Masyarakat
Kecenderungan di Masa datang
Akibat
Banjir bandang
Tahun 2009 saja
Tidak pernah Tidak tahu Hutan semakin gundul, berkurangnya pohon
Banjir kecil Setiap tahun Setiap tahun Semakin sering Hutan semakin gundul, berkurangnya pohon
Kebakaran Tahun 1979 Tidak pernah Tidak tahu Kelalaian ibu rumah tangga (1 dusun terbakar)
Abrasi pantai Setiap tahun Setiap tahun Semakin sering Hutan semakin gundul, berkurangnya pohon
Gempa Setiap tahun Setiap tahun Semakin sering Kondisi alam yang tidak bisa dihindari
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012
Data perubahan kejadian bencana atau gangguan atau cuaca buruk yang terjadi di Desa Gondang sebagai berikut: pada tahun 1979 pernah terjadi kebakaran yang mengakibatkan satu dusun habis terbakar yaitu Dusun Lekok Timur, Desa Gondang. Pada kejadian tersebut pemerintah setempat membangunkan tempat pengungsian bagi masyarakat korban kebakaran. Pada tahun 2009, terjadi banjir bandang yang mengakibatkan seluruh aktifitas masyarakat terhenti baik itu nelayan maupun petani. Kejadian banjir bandang ini mengakibatkan kerugian besar baik bagi masyarakat nelayan maupun yang bertani. Aktivitas pertanian terganggu karena banyak areal pertanian yang tergenangi oleh air banjir bandang. Usaha pertanian menjadi rugi akibat tanaman banyak yang rusak dan puso akibat digenangi oleh banjir. Sementara kondisi di pesisir juga terdanpak dari kejadian banjir bandang. Selain keramba yang ada di kali (sungai) hilang terbawa arus banjir, banyak perahu nelayan
yang hilang karena dibawa banjir. Sebaaagian nelayan Gondang memarkir perahu mereka di muara, oleh karenanya ketika banjir bandang datang semua perahu yang diparkir di muara hilang terbawa banjir ke laut (I-CATCH Desa Gondang, 2012).
Tabel 6. Dampak Kejadian Bencana dan Kegiatan Penghidupan Masyarakat
Bulan Kegiatan Penghidupan Dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat
1 - 3
Ombak
besar
- Tidak ada aktivitas
- Nganggur di rumah
- Main sama keluarga
- Masyarakat tidak bisa melaut
- Penghasilan tidak ada
- Banyak utang
- Jual perhiasan
- Jual alat/perkakas rumah tangga
- Cari kayu bakar
4 - 6
Nelayan pergi melaut
- Nelayan Melaut
- Pendapatan Bertambah
- Bayar utang (utang pada saat tidak melaut)
7 - 9
Angin sayong (nelayan hanya
melaut di pinggir)
- Nelayan melaut, tapi hasil kurang
- ikan di laut kurang
9-11
Nelayan melaut seperti biasa,
keadaan laut tenang
- Jenis ikan yang banyak pada musim ini yaitu ikan tongkol
- hasil ikan yang didapatkan nelayan banyak
- pendapatan hasil melaut cukup memuaskan
12
Ombak
besar
Tidak ada aktifitas melaut - Para nelayan memanfaatkan simpanan uangnya untuk
kelangsungan hidup pada saat tidak melaut
- Para nelayan tidak menghutang
- Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari setelah uang simpanan
mereka habis, bapak-bapak mencari kayu di pinggir pantai
untuk dijual dan ibu-ibu mencari botol-botol bekas
(pemulung)
Sumber: I-CATCH Desa Gondang, 2012
Bersadarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa ketergantungan masyarakat terhadap musim dan angin yang mempengaruhi mereka melaut sangat menetukan kehidupan para nelayan. Pada bulan 12-3 nelayan sama sekali tidak bisa melaut karena ombak yang begitu besar. Namun ada beberapa orang diantara para nelayan Gondang yang berani melaut dengan cara menghitung arah angin dan cuaca dengan baik. Hasil dari tangkapan musim ini sangat mahal karena tidak banyak nelayan yang berani melaut. Hanya mereka yang sudah berpengalaman (senior) yang berani melaut. Bagi nelayan yang tidak bisa melaut, mereka terpaksa harus menjual perhiasan, barang rumah tangga dan jika belum cukup maka mereka akan berutang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada bulan 4 -11 para nelayan beraktivitas normal, pergi melaut di sore hari, pulang
pagi hari. Kegiatan ini mereka lakukan hampir setipa hari. Ada juga yang melaut pagi
pulang sore hari (I-CATCH Desa Gondang, 2012).
BAB III Konsep Pengembangan Delta Api Desa Gondang
Delta Api dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik dan Politik. Ketiganya
dilakukan dengan mengkolaborasikan perencanaan Bottom-up dan Top-down.
Pendekatan ini sama dengan apa yang di rencanakan dalam a UU No 25 tahun 2004
tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di poin ke-3 mengenai Proses
Perencanaan. Di Poin ke-3 ini, yang ditulis adalah: (1) Pendekatan Partisipatif; (2)
pendekatan Teknokratik; (3) Pendekatan Politik; (4) pendekatan Top-Down; (5)
pendekatan Bottom-up.
Berdasarkan integrasi dan kolaborasi proses perencanaan tersebut, konsep yang
menjadi acuan Delta Api adalah “Ekowisata Berbasis Adaptif Perubahan Iklim,
Pengelolaan SDA dan Kebudayaan lokal 2013-2023”
3.1 Konsep Pembangunan Desa Gondang
Dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penataan Desa Gondang di Kecamatan
Tanjung untuk menuju desa yang memiliki konsep ekowisata berbasis adaptif
perubahan iklim, pengelolaan SDA dan Kebudayaan lokal, maka konsep yang
dirumuskan antara lain
3.1.1 Konsep Utama
Pengembangan pusat kajian kebudayaan lokal pesisir ;
Pusat kajian pengelolaan SDA baik dari laut maupun dari daratan yang
mendukung dari Perda no 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
KLU, jika menetapkan wilayah agroindutri di Kecamatan Gangga, Kecamatan
Kayangan dan Kecamatan Bayan;
Pusat penginternalisasi kajian dan hasil kajian serta informasi tentang
perubahan iklim;
Pusat ecotourism berbasis adaptif perubahan iklim, perubahan pengelolaan
SDA, dan kebudayaan lokal;
Meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (livelihood dan
wellbeing) melalui pengeloaan pangan, air, energy dan mata pencaharian;
Memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembangunan desanya;
Menciptakan lingkungan yang, aman, lebih baik, tertata, lengkap dengan sarana
dan prasarana dasar.
3.1.2 Konsep Khusus
Mengoptimalkan produktifitas kelautan, perairan darat, pertanian, peternakan
dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Desa Gondang;
Proses pembangunan harus cepat dan tepat sasaran (tidak menyalahi aturan
tata ruang dll);
Perencanaan dan pembangunan wilayah desa harus bersifat lebih baik (tertata,
dilengkapi dengan fasilitas pendukung) sehingga tidak membangun kekumuhan
yang ada sebelumnya;
Pendidikan yang memiliki kurikulum yang diintegrasikan dengan kelautan dan
kepulauan;
Memperkuat nilai-nilai budaya dan adat istiadat melalui kesepakatan.
3.2 Skenario Pengembangan Tata Ruang Desa Gondang
3.2.1 Skenario Pengembangan Sistem dan Struktur Desa Gondang
1. Tema Pembangunan Desa Gondang
Skenario pengembangan Desa Gondang menjadi desa dengan tema ekowisata, adaptif
perubahan iklim, pengelolaan SDA (laut, perairan darat, pertanian dan perkebunan) dan
kebudayaan lokal hal ini tercermin dari lokasi dan potensi, pengembangan konsep
tersebut diatas didukung dengan :
Keunggulan ekosistem dan kondisi alam lingkungan;
Masyarakat beserta perangkat desa berkomitmen tinggi untuk mengembangkan
desanya karena melihat potensi desa yang besar;
Pertanian dan nelayan sebagai sektor mata pencaharian sebagai keahlian utama
masyarakat;
Keinginan yang besar dari masyarakat untuk mengelola dan mengkonservasi
SDA berupa laut, pertanian, perkebunan dan perairan air tawar;
Arah dan orientasi usaha masyarakat mampunyai pandangan kedepan melalui
kedaulatan pangan, air, energy dan mata pencaharian.
2. Kerangka Utama Desa Gondang
Memperkuat desa melalui pengelolaan SDA berupa kelautan dan perikanan, pertanian,
perkebunan, dan perairan air tawar, beserta kearifan lokal pada kegiatan kelautan yang
masih melekat pada kehidupan masyarakat KLU khusunya di Desa Gondang yang
menjadi pedoman “hukum” mengatur kehidupan masyarakat Desa Gondang.
Pengembangan kerangka utama desa melalui :
Mengembangkan kefungsian kelembagaan yang ada di Desa Gondang sehingga
menjadi mediator dan dinamisator kemajuan desa Gondang diantaranya :
a. Bidang pertanian berupa subak, pekaseh, P3A
b. Bidang perikanan berupa Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara,
kelompok nelayan Muara Tunggal, kelompok pengolahan ikan;
c. Balai pemberdayaan masyarakat pesisir;
d. Banjar (kelembagaan lokal masyarakat Lombok dan Bali).
Mengembangkan dan mengelola SDA dengan baik sehingga Desa Gondang
menjadi icon pusat kajian pengelolaan SDA sehingga menghasilkan product yang
dapat dipelajari dan dipasarkan baik secara regional, maupun nasional.
Pengelolaan SDA yang dimaksud adalah berupa
a. Sumber daya perikanan laut;
b. Sumber daya alam darat yaitu pertanian, perkebunan dan perternakan;
c. Sumber daya alam Kali Segara yaitu kawasan wisata, dan budidaya keramba;
d. Sumber daya kali Orong yaitu pemanfaatan mata air sebagai lokasi budidaya
keramba
e. Sumber daya mata air Songkong
Kearifan lokal sebagai ‘hukum” yang harus ditaati, dan dimiliki sanksi di
masyarakat yang dapat dijadikan pusat pembelajaran bagaimana masyarakat
desa Gondang memelihara dan melaksakan kearifan lokal dalam kehidupan
sehari-harinya, misalkan masih adanya budaya tradisi nyongkolan, pemayun,
pembaca hikayat dan serah adat.
Adanya pusat kajian mengenai perubahan iklim sehingga masyarakat desa
menjadi tangguh dalam menghadapi perubahan iklim yang akan terjadi baik
disaat ini maupun dimasa akan datang.
3. Ruang Utama Desa Gondang
Pengembangan kawasan pelayanan masyarakat seperti : balai pemberdayaan
perempuan, tempat pembuangan sampah sementara, MCK, PAUD berbasis
pesisir kelautan, Madrasah berpresfektif dan kepulauan, Pembuatan taman
bermain anak-anak, pemasangan drainase komunal terbuka, balai pertemuan
nelayan, dan balai pemberdayaan peternak dan pembuatan kandang kolektif +
digaster biogas;
Gambar 7. PAUD yang terintegrasi dengan taman bermain anak dan balai
pemberdayaan perempuan
Gambar 8. Desain Kandang Kolektif yang terintegrasi digester Biogas
Areal persawahan dan areal perkebunan sebagai areal kedaulatan pangan
pendukung dari agroindustri yang telah ditetapkan pada Perda no 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KLU, jika menetapkan wilayah agroindustri
di Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan;
Laut dan sungai merupakan area konservasi untuk menghindari abrasi dan
ancaman banjir ketika hujan besar mendatang.
4. Integrasi Desa Gondang Dengan Wilayah Sekitarnya
Meningkatkan aksesbilitas Desa Gondang dengan desa sekitarnya untuk
kepentingan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
Mengangkap peluang keunggulan kedekatan lokasi desa;
Melakukan koordinasi dengan desa-desa sekitar dalam pembangunan di Desa
Gondang;
Melakukan kerjasama dengan desa-desa di sekitar dalam kenservasi laut dan
daratan dalam hal ini laut, sungai, pertanian dan perkebunan.
3.2.2 Skenario Pengembangan Tata Guna Lahan Desa Gondang
1. Permukiman
Prinsip pengembangan perumahan terbagi atas :
Peningkatan kontruksi rumah penduduk yang belum menggunakan bangunan
dengan kontruksi tahan gempa;
Pembangunan rumah tahan gempa berkontruksi seperti rumah di Desa adat
Karang Bajo, yang disebut dengan nama rumah risa (Rumah Knock Down – hasil
kajian bersama BPTPT PU Denpasar) dan rumah panggung yang terintegrasi
homestay (mengacu pada desain homestay Dusun Jambianom sebagai role
model Eco-Climate Village;
Gambar 9. Rumah Risa (bangunan Knock-down tahan gempa)
Gambar 10. Desai Rumah yang Terintegrasi Homestay
Peningkatan kualitas perumahan, menuju tingkat rumah sehat;
Menata tata letak dan arah bangunan rumah;
Memisahkan fungsi rumah tinggal dengan kandang melalui penyediaan kandang
ternak secara komunal;
Menata drainase pembuangan limbah rumah tangga;
Melengkapi lokasi permukiman dengan halaman rumah dengan penghijauan;
Pembangunan rumah mengikuti aturan sempadan sungai dan pantai
2. Perdagangan dan jasa
Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dipusatkan di Tanjung, namun desa
Gondang dikhususkan untuk mendukung perekonomian masyarakat, pengembangan
berupa :
Toko maupun warung makan, warung kopi sederhana yang bisa mendukung
kebutuhan warga dan pendatang (rest area);
Fasilitas jasa komersial yang dapat memenuhi kebutuhan selain kebutuhan
pokok;
Mendorong home industry hasil pengelolaan SDA yang ada di laut, perairan
darat, pertanaian, perkebunan dan jasa;
Mengembangkan jasa simpan pinjam berupa koperasi untuk meminimalisr
peran tengkulak.
3. Fasilitas Umum dan Sosial Desa Gondang
Skenario pengembangan fasilitas desa dengan melihat kebutuhan dan keinginan
masyarakat desa diantaranya :
Perawatan atau renovasi dari tempat ibadah dan kantor Desa Gondang pada
bagian-bagian rusak;
Mempersiapkan sarana dan prasarana olah raga dan tempat bermain anak;
Pembangunan balai pertemuan;
Meningkatkan fasilitas air bersih (mata air songkang) dan penerangan desa
(PLN);
Gambar 11. Desain Pemanfaatan Mata Air Songkang sebagai sumber kebutuhan
air Bersih
Mengembangkan akses transportasi yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4
Pembangunan kandang komunal;
Gambar. 12. Perkiraan Akses Transportasi yang dapat dilalui oleh kendaraan
roda 4
4. Fasilitas sarana Pendukung Pariwisata
Skenario pengembangan fasilitas sarana pendukung pariwisata desa dengan melihat
kebutuhan dan keinginan masyarakat desa diantaranya:
Penyediaan fasilitas bangunan sebagai pusat kajian kebudayaan lokal pesisir,
yang bertujuan sebagai :
a. Pusat kegiatan pengkajian dan pengembangan budaya lokal;
b. Pusat tukar informasi tentang kebudayaan lokal, kearifan lokal dalam
menanggapi perubahan iklim, dll
c. Pusat kegiatan pemuda dan kegiatan masyarakat;
d. Media pelatihan SDM para nelayan Desa Gondang;
e. Pusat kegiatan belajar masyarakat luar tentang kebudayaan lokal serta
kearifan lokal masyarakat Desa Gondang dalam menanggapi perubahan
iklim, dll
• Penyediaan fasilitas bangunan sebagai pusat kajian pengelolaan SDA seperti :
a. Mengembangkan wahana yang re-creative dan rekreasi yang dapat
dipergunakan untuk pengkajian dan pengembangan pengelolaan SDA Desa
Gondang terutama pengelolaan SDA air.
b. Berupaya untuk menyediakan fasilitas yang mewadahi kegiatan pengelolaan
SDA berupa pangan bagi kaum perempuan di Desa Gondang dalam bentuk
bangunan khusus balai pemberdayaan perempuan;
c. Menyiapkan dusun yang bersih dan edukatif di Desa Gondang sehingga
banyak yang mengunjungi dusun sebagai pusat pengelolaan SDA baik
pengelolaan SDA berupa air, pangan, energy dan mata pencaharian.
d. Menyiapkan lokasi lahan yang khusus berupa kandang komunal yang dapat
menampung kegiatan pengelolaan SDA berupa energy dari kotoran sapi.
• Persiapan desa menjadi desa ekowisata dengan kegiatan berikut :
a. Menyiapkan kampung menjadi desa pariwisata “ecotourism” berbasis
kebudayaan dan sumber daya alam;
b. Menyiapkan dusun yang tertata rapi, bersih dan sehat;
c. Menyiapkan sarana pembuangan sampah yang lebih permanen berupa
tempat penampungan sampah, sehingga masyarakat tidak membuang
sampah di pinggir kali Songkang;
d. Menyiapkan sarana sistem penyaluran air buangan berupa SPAB dan IPAL;
e. Menyiapkan Pembuatan drainase komunal terbuka;
e. Menyiapkan tambahan KM dan MCK bersama di sekitar Kali Orong;
f. Meyiapkan ruang terbuka hijau di setiap fasilitas umum yang terbangun;
• Pusat penginternalisasi kajian dan hasil kajian serta informasi tentang
perubahan iklim dengan cara :
a. Meningkatkan dan menguatkan simpul belajar kritis bagi warga masyarakat
setempat tentang perubahan iklim;
b. Membiasakan masyarakat untuk selalu mengkonservasi SDA setelah
dimanfaatkan, sehingga tidak terjadi bencana alam;
c. Memilitansikan generasi selanjutnya untuk lebih memahami pengetahuan
perubahan iklim, dengan menambahkan kurikulum tentang perubahan iklim
khususnya pesisir di setiap sekolah yang ada di Desa Gondang.
d. Melakukan serial diskusi kampong/desa yang kemudian dilanjutkan dengan
diskusi kecamatan dan kabupaten, dimana diskusi ini melibatkan stake
holder kunci di level-level tersebut;
e. Melakukan diskusi team ahli mutipihak untuk melakukan kajian kritis dan
memberikan masukan (berdasarkan hasil kajian dan assement sebelumnya)
yang konstruktif terhadap draft Perda RTRW dan Perda pengembangan
kawasan yang disusun oleh konsultan swasta;
f. Melakukan hearing dan advoksi ke DPRD dan eksekutif.
• Adanya ruang bermukim yang berkontruksi anti gempa seperti yang ada di desa
Karang Bajo yang disebut rumah Risa;
5. Konservasi lahan pertanian dan perkebunan
Lahan pertanian dan perkebunan tetap diperhatikan, karena merupakan salah satu
mata pencaharian penduduk. Penataan dan pengelolaan kembali seperti peremajaan
atau perluasan disesuaikan.
Skenario pengembangan lokasi aktivitas pertanian dan perkebunan melalui :
Mengatur pola tanam;
Pendistribusian insektisida ramah lingkungan;
Mengembangkan varietas tanaman yang resisten terhadap hama dan penyakit;
Mempertahankan area pertanian dan dikembangkan lebih baik dengan
peremajaan;
Merehabilitasi kavling pertanian yang rusak dan lingkungan sekitar dengan
melakukan penanaman kembali;
Perluasan pertanian padi sawah tanpa merubah kondisi lingkungan yang ada;
Pengelolaan lahan pertanian yang lebih baik atau lebih maju dalam pengelolaan
hasil pertanian;
Mengembangkan tanaman unggul yang merupakan tanaman lokal dari desa
Gondang sehingga tidak bergantung untuk membeli pada tanaman non lokal,
serta penghijauan hutan dengan tanaman lokal;
Budidaya tanaman obat di kebun masing-masing;
Mengembangkan rawa-rawa untuk kolam ikan dan perluasan padi sawah.
6. Konservasi SDA Laut
Konsep ini tidak memisahakan laut dan daratan sebagai dua hal yang tidak saling
berkaitan, maka dari itu laut tetap diperhatikan, karena merupakan salah satu sumber
mata pencaharian pendudu yaitu nelayan.
Skenario pengembangan lokasi aktivitas kalautan melalui :
Mengatur pola tangkap;
Penataan pantai (zonasi terestial pantai) dengan tanaman pantai yang adaptif
terhadap perubahan iklim;
Zonasi pantai untuk ruang dan wilayah pantai;
Penguatan sanksi sosial terhadap pelanggaran awiq-awiq yang mengatur tentang
aturan penangkapan ikan;
Adanya hari libur khusus untuk tidak melaut untuk memberi kesempatan laut
bersitirahat sehingga ikan-ikan dapat berkembang biak dengan baik;
Adanya kegiatan rutin bersih laut;
LMNLU dan kelompok nelayan harus focus juga dalam menangani masalah
konservasi laut
7. Konservasi wilayah Sungai
Sungai tetap diperhatikan, karena merupakan salah satu potensi yang dapat
dikembangkan di desa Gondang. Skenario konservasi sungai melalui :
Restorasi bantaran dan catchment area sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong;
Normalisasi aliran sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong ;
Pengembangan budidaya ikan air darat;
Penanaman tanaman bergizi dan apotek hidup di sepanjang pinggir sungai.
Adanya awiq-awiq (kearifan lokal) yang mengatur untuk tidak membuang
sampah di sungai;
Adanya kelembagaan yang khusus konsen terhadap konservasi sungai.
3.2.3 Infrastruktur dan utilitas Desa Gondang
1. Jalan
Konsep dasar:
1. Merancang perencanaan pengembanan jalan baik jalan di sekitar dusun maupun
jalan yang menuju jalan utama/jalan besar;
2. Jalan merupakan sarana transportasi juga berfungsi sebagai sarana penyelamat;
3. Jalan yang merupakan ruang sirkulasi kendaraan pribadi sekaligus sarana
pejalan kaki yang aman;
4. Jalan merupakan ruang gerak linier baik bagi kendaraan maupun manusia,
dimana jalan harus dibebaskan dari segala macam instalasi infrastruktur.
Prinsip :
1. Jalan harus dimanfaatkan secara benar dengan peruntukannya dan
kapasitasnya;
2. Lebar jalan harus menampung kapasitas lalu lintas sampai dengan umur rencana
yang direncanakan;
3. Perkerasan jalan/badan jalan harus mampu menampung beban lalu lintas sesuai
dengan kelas jalan yang ada;
4. Jalan sebagai prasarana transportasi yang lancer, aman dan nyaman.
Skenario :
a. Peningkatan kualitas jalan yang sudah ada
1. Jalan tanah ditingkatkan kelasnya dengan kontruksi rabat beton yang
menghubungkan desa Gondang dengan desa lainnya;
2. Peningkatan kualitas jalan yang sudah ada;
b. Pembuatan jalan baru
Rencana pembangunan jalan lingkungan di desa Gondang;
2. Drainase dan Irigasi Desa GOndang
Konsep dasar
Perencanaan sistem jaringan drainase kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan
luas daerah pelayanan (catchment area), jenis lapisan permukaan terbangun, bentuk
serta jenis saluran yang digunakan.
Prinsip
Drainase kawasan dipisahkan dengan pembuangan air kotor (rumah tangga);
Drainase harus dapat mengalirkan air secepat mungkin sesuai kapasitas
tampungannya;
Kecepatan aliran tanpa menimblkan kerusakan pada dinding dan dasar saluran;
Kemiringan saluran disesuaikan dengan fungsi saluran;
Arah pengaliran air menggunakan pola pengaliran gravitasi dengan
memperhatikan kecepatan yang terjadi;
Saluran dibangun pada sisi pematang dan disesuaikan dengan kondisi
lingkungannya.
Skenario
Pembangunan saluran drainase baru kanan-kiri jalan dengan lebar tertentu disesuaikan
dengan kondisi lingkungan :
Pembangunan saluran drainase untuk saluran air hujan kiriman yang datang
dari desa lainnya;
Restorasi sempadan sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong ;
Normalisasi aliran sungai dan pendalaman sungai agar tidak gagal panen akibat
banjir akibat luapan sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong di Persawahan;
Pembuatan talud.
3. Air Minum
a. Jangka pendek
Pembuatan jaringan disribusi air bersih ke rumah-rumah penduduk;
Rata-rata jumlah air yang digunakan untuk minum, memasak, dan kebersihan
pribadi masing-masing rumah tangga;
Jarak terjauh antara rumah tangga dan titik air terdekat;
Air sumur yang selalu terjaga
Sumber dan sistem air dipelihara sedemikian rupa sehingga volume air yang
tepat secara konsisten atau secara berkala.
b. Jangka panjang
Berdasarkan prediksi perkembangan jumlah penduduk, sumber air yang ada
tidak mencukupi maka harus ada penambahan desa air. Sumber air minum yang
dihunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di desa Gondang yaitu berasal
dari beberapa mata air dan aliran sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong
4. Persampahan
Dari proyeksi timbulan sampah dan pelayanan prasarana persampahan, maka program
pengelolaan persampahan sampai akhir tahun 2023 dalam pengelolaannya ditangani
oleh desa Gondang sendiri dan menertibkan kembali agar tidak ada pembuangan
sampah ke sungai oleh tiap keluarga. Selain itu pembuatan TPS (tempat penampungan
sementara) sebanyak 2 kontainer dan pengadaan 8 unit kereta sampah
5. Air Limbah
Untuk jangka pendek diterapkan skenario sebagai berikut :
1. Tahap awal bisa 1 : 20 dan ditinggalkan maksimum 5 orang pengguna untuk 1
jamban;
2. Penggunaan jamban diatur oleh rumah – rumah tangga dan atau terpisahkan
menurut jenis kelamin;
3. Jamban kolektif/umum dibersihkan atau dipelihara sedemikian rupa sehingga
mereka tetap digunakan oleh sasaran pengguna;
4. Jamban berjarak tidak lebih dari 25 meter dari tempat tinggal, sedangkan untuk
jangka panjang diterapkan scenario setiap rumah mempunyai 1 WC.
Pembangunan jamban di masing-masing rumah harus memenuhi standar yang
berlaku.
Untuk jangkan panjang diterapkan scenario sebagai berikut:
1. Pembangunan IPAL sederhana (desain mengacu IPAL pada role model Eco-
Climate Village)
Sa
lura
n lim
ba
h
Denah
Pengolahan
Limbah Cair
Dengan
Menggunakan
Wetland
Keterangan
Permukiman
Dusun
Jambianom
Pipa pengumpul
limbah cair
Filter 1
Vegetasi
Filter 2
Inlet Wetland
Wetland
Eceng Gondok
Outlet Wetland
Sungai
Arah Aliran
Kolam Eceng
gondok
Sa
lura
n c
ad
an
ga
n
Gambar 13. Skema Pengolahan Limbah Cair dengan menggunakan Wetland
(fitoremediasi)
Skema pengolahan limbah cair dengan metode wetland sebagai berikut:
Grey water dari permukiman disalurkan melalui sebuah pipa penyalur
limbah cair menuju ke saluran limbah.
Sebelum masuk ke dalam saluran limbah, terdapat filter sederhana berupa
batu batu alam, batok kelapa, dan kerikil.
Saluran limbah terbuat dari tanah tanpa plengsengan. Tujuannya adalah agar
vegetasi-vegetasi yang adaptif terhadap limbah domestik. Vegetasi ini
nantinya juga berperan dalam mereduksi jumlah polutan dalam grey water
karena mengambil sumber nutrien dari air limbah.
Sebelum masuk ke dalam wetland, air limbah harus melalui filter yang lebih
halus daripada filter pada saluran pengumpul limbah cair. Filter ini tersusun
atas arang, kerikil, serabut kelapa, dan pasir.
Pada saat memasuki wetland aliran air akan melambat karena telah
mengalami filtrasi. Melambatnya aliran air ini akan memaksimalkan kinerja
eceng gondok sebagai organisme pereduksi limbah cair. Eceng gondok
mampu mengadsorpsi senyawa organik dan kandungan lain (suspended
solid). Penggunaannya sebagai penyerap nutrisi, eceng gondok ikut berperan
dalam eutrofikasi di perairan karena dapat mengabsorpsi nitrogen dan
fosfor sehingga kemampuan mereduksi eutrofikasi lebih maksimal.
Berdasarkan hasil kajian terhadap perubahan kualitas air irigasi eceng
gondok dapat menurunkan kadar COD sebesar 21,59%, yaitu dari 40,34
mg/L menjadi 31,63 mg/L serta TSS sebesar 41,3% menjadi 31,63% (Fauzi
dkk., 2011).
Eceng Gondok harus diganti secara berkala, karena eceng gondok muda lebih
efektif dalam menyerap polutan dibandingkan yang tua. Eceng gondok muda
dapat langsung diambil pada kolam eceng gondok. Eceng gondok yang sudah
terlalu besar (tua) dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan yang
mendukung ekonomi kreatif dusun dan meningkatkan pendapatan warga
Dusun Jambianom.
Outlet wetland akan terhubung dengan badan air penerima, yaitu Kali Orong
(Desa Gondang).
Saluran cadangan difungsikan ketika dilakukan pembersihan dan perawatan
saluran limbah.
2. Pengembangan Septic Tank Komunal untuk mengolah Black water (air limbah
feses)
6. Listrik
Kebutuhan daya listrik didasarkan pada standar yang berlaku
Jangka pendek
Penyediaan genset untuk memenuhi kebutuhan warga, sehingga bisa terlayani
sepanjang hari;
Mengembangkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang bersumber dari
laut;
Penyediaan kilometer listrik dengan sistem kredit;
Penyediaan listrik dengan sistem pulsa.
Jangka panjang
Penyediaan tenaga listrik melalui jaringan listrik yang baik;
Memanfaatkan laut untuk pembangkit listrik tenaga air;
Kondisi jaringan direncanakan sedemikian rupa suoaya teratur dan aman
terutama di permukaan padat;
Lampu penerangan jalan ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu dan
melengkapi penerangan di ruang-ruang pertemuan umum.
3.3 Skenario Pengembangan Ekonomi dan Sosial Desa Gondang
3.3.1 Skenario Pengembangan Ekonomi Desa Gondang
1 Mempertahankan ekisisting mata pencaharian penduduk, seperti petani, pedagang,
peternak, dan nelayan;
2 Meningkatkan kemampuan/kapasitas penduduk, melalui :
Pelatihan enterpiunersip bagi dan manajemen usaha ekonomi mikro bagi
kelompok perempuan dalam memasarkan hasil pengelolaan ikan menjadi abon,
bakso, krupuk dll;
Pembentukan dan pemberdayaan kelompok perempuan;
Penyediaan modal usaha melalui koperasi;
Pelatihan pengolahan ikan sebagai usaha alternative;
Pengembangan budidaya ikan (kerapu) dengan sistem KJA;
Pembentukan dan pemberdayaan kelompok perikanan budidaya;
Membentuk kemitraan usaha dan pemasaran dengan instansi dan swasta;
Pelatihan atas pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berusaha;
Pengembangan sifat enterprenuerhip dari penduduk yang ingin
berusaha/swadaya;
Pengadaan tenaga penyuluhan untuk pertanian.
3. Menyediakan wadah/tempat usaha, antara lain melalui :
Penataan area usaha warga (perdagangan dan jasa) menjadi kawasan yang
terintegrasi dengan rencana desa dan lingkungan alam sekitarnya;
Melengkapi area dengan sarana dan prasarana pendukung;
4. Meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan warga, melalui :
Penambahan modal usaha;
Pemanfaatan teknologi yang lebih baik;
Bantuan alat kerja;
Bantuan benih unggul tanpa pupuk dan tahan terhadap hama;
Manajemen dan marketing yang lebih baik dan pangsa pasar yang lebih luas
3.3.2 Skenario Pengembangan Sosial dan Budaya Desa Gondang
Menguatkan kegiatan sosial, budaya dan peribadatan penduduk seperti :
Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengembangkan aktivitas sosial dan
seni budaya masyarakat;
Penguatan sistem dan struktur pemerintahan desa;
Megembangkan sifat/rasa memiliki terhadap masa depan desa melalui peran
aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik desa serta
kerelaan sumbangan masyarakat desa untuk kepentingan umum/desa;
Menjaga nilai-nilai atau norma yang berlaku di kehidupan masyarakat desa
Gondang;
Saling menghargai, menghormati dan kerja sama antar umat beragama.
3.3.3 Skenario Pengembangan Pendidikan di Desa Gondang
Pemerataan mutu pendidikan bagi anak usia sekolah, antara lain :
Sosialisasi dan penyuluhan tentang pendidikan dan bahaya dari pergaulan bebas
dan bahaya dari miras dan narkoba;
Pelibatan peran dan aspirasi pemuda dalam proses pembangunan;
Penyediaan bantuan bagi rumah tangga miksin melalui program beasiswa;
Program biaya pendidikan murah melalui subsidi dana BOS, BLSM pendidikan,
dan PNPM GSC;
Sekolah yang memiliki Kurikulum yang diintegrasikan dengan kelautan dan
kepulauan
3.4 Skema Konservasi Desa Gondang
3.4.1 Arahan dan Penyelamatan Lingkungan Desa Gondang
Arahan dan Penyelamatan Lingkungan mengacu pada Sungai, terrestrial dan laut
Menyelamatkan dan mempertahankan daerah bantaran sungai dan hulu sungai
Kali Segara dan sungai Kali Orong ;
Mempertahankan kondisi lingkungan ekisting dan tidak boleh dirubah baik
tutupan vegetasi alami sesuai bentang alamnya;
Meningkatkan dan mempertahankan debit potensi air sungai dengan
penghijauan;
Mengembangkan objek alami misalkan pada mata air songkang;
Penataan pantai (zonasi terrestrial) dengan tanaman pantai yang adaptif
perubahan iklim
Zonasi pantai untuk ruang hidup dan wilayah pantai dengan konsep
pelestariannya
3.4.2 Lokasi Penyelamatan
Meningkatkan aksesbilitas masyarakat dalam penyelamatan lingkungan alam dan
lingkungan sosio-budaya. Berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam aturan adat
desa Gondang, mesyarakat setuju untuk melestarikan lingkungan alam dan lingkungan
budaya sehingga perlu difasilitasi dalam penerapan program pembangunannya.
Meningkatkan kreativitas warga dan mengembangkan keswadayaan dalam rangka
penyelamatan lingkungan alam dan lingkungan budaya melalui :
Penghijauan pada hulu-hulu sungai dan bantaran sungai;
Mendekumnetasikan nilai budaya dan adat desa Gondang;
Mengakses sarana dan prasarana informasi dan jalan-jalan buntu;
Kawasan permukiman di tata rapi dan meningkatkan sanitasi lingkungan
permukiman;
Pemeliharaan ternak dibuat kandang dan dipisahkan dari rumah induk.
Rehabilitasi terumbu karang;
Restorasi bantaran sungai Kali Segara dan sungai Kali Orong ;
Pengembangan rumah berkontruksi anti gemmpa
Penanaman kebun gizi dan apotek hidup.
3.4.3 Unsur Perlindungan Lingkungan Hidup
Perlindugan berupa kumpulan pepohonan/vegetasi merupakan salah satu upaya untuk
memperkecil dampak, maka berdasarkan hasil diskusi antara lain ;
Penanaman pohon di sepanjang jalan di area perumahan warga, ruang ruang
terbuka desa;
Mempertahankan pohon-pohon/vegetasi alami yang menjadi pohon-
pohon/vegetasi unggulan di desa Gondang;
Tidak melakukan penebangan hal-hal yang merusak alam untuk kepentingan
pribadi dan mempertahankan rawa-rawa untuk pengembangan ikan air tawar;
Mempertahankan daerah tangkapan air di bagian hulu dan sepanjang aliran
sungai yang mengalir di desa Gondang;
Menata potensi wisata alam dan budaya tanpa merubah kondisi lingkungan atau
bentang alamnya;
Melestarikan laut dengan adanya awiq-awiq yang telah ada;
Penguatan kapasitas kelembagaan yang mengatur tentang perlindungan
lingkungan hidup baik yang ada di laut, sungai, maupun pertanian dan
perkebunan.
BAB IV Analisa Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Desa Gondang
Penilaian ekonomi sudah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi demi semakin
sempurnanya perencanaan pembangunan suatu wilayah. Sejak Indonesia mengalami
krisis ekonomi semakin terasa bahwa pembangunan ekonomi dalam dasawarsa yang
lalu telah banyak memanfaatkan sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang
tidak terbaharui.
Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan meningkatkan pemanfaatan
sumberdaya alam laut dan pesisir. Agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
alam laut dan pesisir dapat dilakukan secara optimal maka diperlukan adanya neraca
sumberdaya alam kelautan dan pesisir. Neraca tersebut disusun tidak hanya
dalam
bentuk neraca fisik dan spasialnya namun juga dalam bentuk moneter. Untuk dapat
menyusun neraca moneter diperlukan adanya penilaian (valuasi) ekonomi terhadap
cadangan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
Berdasarkan Akses Utilitas dan mobilitas, panjang jalan di Desa Gondang dapat dibagi
menjadi: (1) jalan Negara sepanjang 7,50 km; (2) Jalan Provinsi sepanjang 7,00 km; (3)
Jalan Kabupaten sepanjang 4,00 km; dan (4) jalan desa sepanjang 7,50 km.
4.1 Potensi Produktifitas
1. Pertanian
Luas areal Desa Gondang adalah 29,20 Km2 atau 2920 Ha (18,56%) dari luas total
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok utara). Luas wilayah Desa Gondang jika dirinci
menurut penggunaan lahan sampai dengan tahun 2009 terdiri dari; (1) tanah sawah
seluas 400 Ha; (2) tanah kering seluas 405 Ha; (3) bangunan/pekarangan seluas 24 Ha;
dan (4) lainnya (perkebunan, pantai, dll) seluas 2091 Ha.
Untuk lahan pertanian, beberapa produksi tanaman pertanian tidak di gunakan
sebagai barang produksi, namun digunakan untuk konsumsi. Penjualan beras dari Padi
sawah seringkali menggunakan sistem ijon dengan harga yang jauh lebih rendah
disbandingkan harga panen. Secara lebih jelas, produktifitas lahan pertanian Desa
Gondang berdasarkan luas lahan dan jumlah produksi (ton) dapat dilihat dalam Tabel 7.
Tabel 7. Luas Areal Tanaman Produksi (dan Konsumsi) serta jumlah Produksi di Desa
Gondang
Produksi Luas Tanam Jumlah Produksi (ton)
Harga (Rp/Kg)
Nilai Produksi (Rp 000)
Padi (sawah dan ladang)
660 Ha (Musim tanam pertama seluas 400 dan musm tanam kedua seluas 260)
7.063 8.000 56.504.000
Ubi Kayu 25 Ha - 1.500 1.500 Ubi Jalar 3 Ha - 6.000 6.000 Kacang Tanah
320 Ha 84 16.672 1.400.448
Total 1008 Ha 7147 Ton 57.911.948
Sumber: Kecamatan Gangga dalam Angka, 2009 diolah
2. Peternakan
Kandang Komunal dengan Instalasi Digester Biogas
Populasi ternak sapi di Desa Gondang cukup tinggi dibadingkan beberapa desa lain di
wilayah Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Sapi-sapi ini dipelihara dengan
menggunakan kandang di masing-masing rumah peternak. Oleh karena alasan
kesehatan dan lingkungan serta estetika, maka perlu rasanya untuk membuatkan
sebuah kandang komunal yang dapat menampung sapi-sapi ini. Kandang komunal
direncanakan akan diintegrasikan dengan digester biogas untuk kebutuhan memasak
masayrakat. Untuk wilayah Desa Gondang, sapi-sapi ini ditaksir berjumlah 776 ekor.
Kandang komunal dan instalasi digester biogas direncanakan diletakkan di beberapa
dusun, dengan satu kandang komunal berisi 10 ekor sapi.
Instalasi pemroses biomasa (digester) adalah tipe fixed dome yang dirancang untuk 10
ekor sapi (dengan kotoran sapi 20 kg/hari/ekor dengan retention time 45 hari) maka
kapasitas digester adalah 18 m³. Skema pemanfaatan energi biogas dari kotoran
sapi adalah seperti pada gambar 10.
Produksi gas metana tergantung pada kondisi input (kotoran ternak), residence time,
pH, suhu dan toxicity. Suhu digester berkisar 25-27°C menghasilkan biogas dengan
kandungan gas metana (CH4) sekitar 77%. Berdasarkan perhitungan produksi
biogas yaitu 6 m³/hari (untuk rata-rata produksi biogas 30 liter gas/kg kotoran
sapi), sedangkan hasil pengukuran tanpa beban menunjukkan laju aliran gas 1,5
m³/jam dengan tekanan 490 mmH2O (lebih besar daripada perkiraan). Penggunaan
lampu penerangan diperlukan biogas 0.23 m³/jam dengan tekanan 45 mmH2O dan
untuk kompor gas diperlukan biogas 0.30 m³/jam dengan tekanan 75 mmH2O.
Tabel 8. Unjuk Kerja instalai Biogas
Sumber: Anan, 1997
Analisa dampak lingkungan dari lumpur keluaran dari digester menunjukkan
penurunan COD sebesar 90% dari kondisi bahan awal dan pebandingan BOD/COD
sebesar 0,37 lebih kecil dari kondisi normal limbah cair BOD/COD=0,5. Sedangkan
unsur utama N (1,82%), P (0,73%) dan K (0,41%) tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata dibandingkan pupuk kompos (referensi: N (1,45%), P (1,10%) dan K
(1,10%). Berdasarkan hasil penelitian, hasil samping pupuk ini mengandung lebih
sedikit bakteri pathogen sehingga aman untuk pemupukan sayuran/buah, terutama
untuk konsumsi segar.
Pendapatan yang diperoleh dari instalasi biogas adalah sekitar Rp 600 000,-/
bulan bila dikonversikan dengan harga dan nilai kalori LPG (Liquefied Petroleum
Gas). Dengan menggunakan parameter dan analisa kelayakan ekonomi seperti pada
Tabel 2 diperoleh B/C Rasio 1,35 yang berarti secara ekonomi investasi tersebut
layak. Demikian pula dari hasil analisa simple payback diketahui bahwa modal
investasi pembangunan konstruksi digester akan kembali pada tahun ke-4 (umur
ekonomi digester: 20 tahun). Hasil pendapatan ini belum termasuk hasil samping
berupa pupuk cair/padat.
Gambar 14. Pemanfaatan Energi Biogas
pemanfaatan biogas yang dihasilkan direncanakan untuk beberapa kegunaan
seperti untuk kemasan tabung (masak) dan sumber energi motor penggerak (daya
listrik/ mekanis).
Tabel 9. Parameter hasil Analisis Valuasi Nilai Ekonomi Instalasi Biogas Desa Gondang
Parameter Nilai Ekonomi Biaya Investasi Rp 18.448.000 Biaya Operasional dan perawatan Rp 2.767.200/tahun Pendapatan Rp 7.051.800/tahun Keuntungan Rp 4.284.600/tahun Umur Ekonomi 20 tahun Produksi gas per hari 6 m3/hari Produksi gas per tahun 2190 m3/tahun Suku bunga 12 % per tahun Hasil Analisis Kelayakan Ekonomi Net Present Worh (NPW) Rp 13.555.578 Net Present Cost (NPC) Rp 39.117.444 B/C Ratio 1,35 Simple Payback 4,3 tahun Internal rate Return (IRR) 23,70%
SIstem ini diberlakukan hanya untuk 10 ekor sapi, maka dari itu, jika di Desa Gondang
terdapat 776 ekor sapi, maka Net Present Cost (NPC) yang didapatkan adalah Rp
3.035.513.654
Sistem Integrasi Ternak dan Tanaman
Usaha peternakan sapi telah banyak berkembang di Indonesia, namun petani pada
umumnya masih memelihara ternak sebagai usaha sambilan atau tabungan,
sehingga manajemen pemeliharaannya masih dilakukan secara konvensional.
Permasalahan utama yang dihadapi petani yaitu belum adanya keterpaduan usaha
ternak dengan tanaman. Sehingga jumlah pakan secara memadai terutama pada
musim kemarau tidak tersedia. Konsekuensinya banyak petani yang terpaksa
menjual ternaknya walaupun dengan harga relative murah .
Upaya mengatasi permasalahan tersebut, petani di beberapa lokasi di Indonesia
sejak dulu telah
mengembangkan sistem integrasi tanaman ternak (Crops Livestock System, CLS). CLS
pada umumnya telah berkembang di daerah dimana terdapat perbedaan nyata antara
musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) dengan bulan kering lebih dari 3 bulan
berturut-turut .
Pengembangan kawasan sistem peternakan pertanian terintegrasi merupakan suatu
model yang integratif dan sinergis atau keterkaitan yang saling menguntungkan
antara tanaman dan ternak. Petani memanfaatkaan kotoran ternak sebagai bahan
biogas, sisa hasil proses biogas yang berupa padatan dan cairan bisa digunakan sebagai
pupuk organik untuk tanamannya, kemudian memanfaaatkan limbah pertanian
sebagai pakan ternak. Kadar unsur hara dalam pupuk kandang yang berasal dari
beberapa jenis ternak adalah seperti pada Tabel 9. Apabila diketahui produksi pupuk
kandang per ekor ternak sapi sekitar 26 kg/hari/ekor dan kambing/domba sekitar 1,5
kg/hari/ekor, maka jumlah zat hara yang dihasilkan per tahun dapat diperhitungkan.
Tabel 10. Kadar N, P, dan K Dalam Pupuk Kandang dari Beberapa Jenis Ternak
Sumber: Saleh, 1997
Pada model integrasi tanaman ternak, petani mengatasi permasalahan ketersediaan
pakan dengan memanfaatkan limbah tanaman seperti jerami padi, jerami jagung,
limbah kacang-kacang, dan limbah pertanian lainnya. Terutama pada musim kering,
limbah ini bisa menyediakan pakan berkisar 33,3 persen dari total rumput yang
dibutuhkan (Kariyasa, 2005). Kelebihan dari adanya pemanfaatan limbah adalah
disamping mampu meningkatan ketahanan pakan khususnya pada musim kering, juga
mampu menghemat tenaga kerja dalam kegiatan mencari rumput, sehingga memberi
peluang bagi petani untuk meningkatkan jumlah skala pemeliharaan ternak atau
bekerja di sektor non pertanian. Beberapa potensi pakan ternak dari limbah
pertanian di Desa Gondang seperti pada Tabel 11.
Tabel 11. Potensi Limbah pertanian Untuk Pakan Ternak
No Komoditas Potensi
1 Jagung Bobot daun dibawah tongkol 2,2-2,6 ton/ha Bobot brangkasan diatas tongkol 1,3-2,0 ton/ha Tongkol (ratio to product ratio/RPR = 0,273) 1,6 ton/ha 2 Padi 3,78-5,1 ton/ha 3 Kelapa (bahan kering dari daun tanpa lidi, pelepah,
solid, bungkil, serat perasan, dan tandan kosong) 10,011 ton/ha/tahun
Catatan: Konsumsi Pakan setiap 1 unit ternak (UT) adalah 35% bobot hidup
Sistem integrasi ternak-tanaman (Crop Livestock System/CLS) yang diusahakan
secara intensif merupakan salah satu contoh populer Sistim Usahatani Intensifikasi
Diversivikasi (SUID) (Simatupang, 2004). Strategi diversifikasi usaha dalam
spektrum luas dapat bermanfaat untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya
maupun untuk mengurangi resiko usaha. Hal ini sangat penting mengingat usaha
dibidang pertanian memerlukan jangka waktu tertentu untuk memperoleh hasil dan
tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, dalam tataran usahatani keluarga skala
kecil, maka usahatani yang akan dikembangkan adalah pola usaha SUID-keluarga,
seperti pada skema (Gambar 15).
Gambar 15. Contoh pemanfaatan Energi Biogas untuk Mendukung Agribisnis Berbasis
Jagung
Sumber: Simatupang, 2004
3. Perikanan
Perikanan juga merupakan sumber penghasilan sebagian besar penduduk di Desa
Gondang. Produksi sektor perikanan paling banyak berasal dari ikan tangkap dari
laut. Sejauh ini, hasil tangkapan nelayan biasa langsung dijual ke pasar atau on site
kepada pemborong. Ketika musim panen ikan, harga ikan di pasar menjadi turun karena
secara kuantitas banyak. Harga persatuan ikan bisa mencapai Rp 5.000 – Rp 15.000
bergantung pada ukuran ikan yang dijual. Biasanya, ikan kembali meningkat ketika
tidak pada musim ikan berkisar antara Rp 15.000 – Rp 30.000 bergantung pada ukuran
ikan.
Jika dibandingkan dengan harga ikan yang berada di Kota Mataram, harga ikan yang
dijual masyarakat nelayan di Gondangg jauh dari kata ideal. Jika harga ikan Rp 10.000 di
Pasar Kecamatan Gangga (wilayah Administratif Desa Gondang), maka harga ikan di
Kota Mataram bisa mencapai Rp 30.000-50.000. Hal ini diakibatkan faktor jarak
tempuh, harga kesetimbangan setelah terjadi kesepakatan harga, tingkat ekonomi (daya
beli) masayarakat, serta jumlah peminat barang komoditas ini.
Jarak Desa Gondang menuju Kota Mataram adalah 40 km. Jika Ditempuh menggunakan
kendaraan roda 4, dengan kecepatan konstan, asumsinya adalah 40 Km/jam, maka
perajalanan yang akan ditempuh untuk mencapai Kota mataram adalah 1 jam.
Jika membandngkan antara pembakaran mesin yang membutuhkan bahan bakar dalam
jumlah kilometer per liter, asumsi yang digunakan adalah 10:1, maka pengeluaran
transport mengantar hasil laut adalah Rp 26.000 yang dapat ditempuh selama 1 jam
perjalanan.
Permasalahan yang diahadapi masyarakat saat ini adalah perubahan iklim yang
berdampak pada tidak menentunya musim dan cuaca. Akibatnya waktu dimana nelayan
biasa melaut, menjadi tidak dapat melaut, sehingga pendapatan pun semakin menurun.
Kejadian cuaca buruk kerap kali menjadi masalah bagi masayrakat nelayan. Akibatnya
ketika mendapatkan ikan, tidak lagi menjual per satuan jumlah, namun per ikat, Diana
satu ikat ikan berkisar antara 3-5 ikan, dengan harga yang jauh lebih rendah yaitu
sekitar Rp 15.000 – Rp 30.000 per ikat.
Jika dilakukan analisis valuasi pendapatan ideal masayrakat nelayan, dengan menjual di
pasar menggunakan angkutan Kota, Nilai ekonomi perikanan Desa Gondang menuju
Pasar Kecamatan, pasar perkotaan Tanjung, dan mataram jika dimanfaatkan secara
optimal dan dalam kondisi ideal dapat dilihat dalam tabel 12.
Tabel 12. Analisa Nilai Ekonomi Produksi Perikanan berdasarkan musim dan rute
angkutan
Rute angkutan
Jarak tempuh
Jumlah yang
dijual/hari
Pengeluaran untuk
angkutan/ hari
Pendapatan/ hari
Pendapatan / bulan
Gondang – kecamatan
Gangga 1 Km 10 Ikan Rp 4.000 x 2
Musim Panen: Rp 42.000
Rp 1.260.000
Musim non panen: Rp 142.000
Rp 4.260.000
Gondang – pasar
perkotaan Tanjung
5 Km 10 Ikan Rp 4.000 x 2
Musim panen: Rp 42.000
Rp 1.260.000
Musim non panen: Rp 142.000
Rp 4.260.000
Gondang - mataram
40 Km 10 ikan Rp 15.000 x 2
Musim panen Rp 120.000
Rp 3.600.000
Musim non panen Rp 270.000
Rp 8.100.000
On site 0 km 10 ikan Rp 0-
Musim Panen: Rp 50.000
Rp 1.500.000
Musim non panen Rp 50.000
Rp 1.500.000
TOTAL 25.740.000 Catatan:
Diasumsikan dalam kondisi ideal
Jumlah ikan yang dijual adalah rata-rata jumlah penjualan
Harga pada pendapatan yang digunakan adalah harga jual ikan terendah
yakni Rp 5000 pada musim panen, dan Rp 15.000 pada musim non panen
Variable harga kesetimbangan (P) untuk kota mataram adalah Rp
35.000/ikan, ini berarti senilai Rp 5.000 untuk setiap ikan, karena Rp
30.000 adalah harga jual termurah di mataram
Saat ini, untuk membantu peningkatan pendapatan keluarga, masayrakat Desa Gondang
melakukan pemberdayaan perempuan dengan melakukan pengolahan hasil laut. Ikan
yang didapatkan para nelayan tidak semua di jual, melainkan disishkan sebagian untuk
diolah menjadi Abon dan pentol ikan. Perempua Desa GOndang dapat menghasilkan
sekitar 100 kemasan abon perharinya, yang dijual dengan harga Rp 15.000. Artinya,
dalam sehari, kelompok perempua dapat menghasilkan Rp 1.500.000. Jika
diakumulasikan selama satu bulan, maka kelompok perempuan menghasilkan Rp
45.000.000 yang dibagi kepada 30 orang anggota kelompok. Dalam 1 bulan, 1 orang
anggota kelompok perempuan dapat menghasilkan Rp 1.500.000. Untuk pemasaran,
setiap harinya selalu ada pemborong yang mengambil abon untuk didistribusikan ke
seluruh Kabupaten Lombok Utara.
Jadi, total nilai ekonomi perikanan Desa Gondang adalah Rp 45.000.000 + Rp
25.740.000 = Rp 70.740.000
4.2 Nilai Cadangan Sumber Daya Alam
Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai tingkat kesejahteraan
yang ada di Desa Gondang, sebaiknya tidak hanya diperhatikan nilai dari hasil-hasil
kegiatan usaha dalam perekonomian Desa tersebut, tetapi juga bagaimana keadaan
sumberdaya alam yang ada di Desa ini. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai
cadangan sumberdaya alam pesisir dan laut pada tahun 2013 sebesar Rp 54,5 milyar
untuk sumberdaya hutan mangrove, Rp 1,02 trilyun untuk terumbu karang Rp
70.740.000 untuk perikanan dan Rp 65,86 milyar untuk lahan pesisir. Secara
keseluruhan nilai ekonomi cadangan sumberdaya alam pesisir dan laut di Desa
Gondang pada tahun 2013 adalah Rp 1,13 trilyun.
Sedangkan nilai produksi bruto yang diciptakannya untuk tahun 2013 sebesar Rp 57,9
milyar berasal dari sektor pertanian ditambah Rp 70.740.000 berasal dari sektor
perikanan, Kemudian ditambahkan lagi dengan 3,03 Milyar dari sector peternakan,
sehingga seluruhnya sama dengan Rp 61,05 milyar. Bila nilai ini dibandingkan
dengan nilai cadangan sumberdaya alam pesisir dan laut sebesar Rp 1,13 trilyun,
maka nilai ekonomi hasil kegiatan produksi hanya kurang dari 0,05 persen.
Perlu diteliti secara mendalam lagi mengenai sumberdaya alam apa saja yang perlu
dihitung nilainya. Sebenarnya tidak semua sumberdaya alam diperhitungkan dalam
suatu perekonomian, karena semua itu tergantung pada derajat kepastian geologinya
serta derajat nilai ekonominya. Seperti halnya dengan terumbu karang misalnya. Jika
masyarakat tidak menggunakannya sebagai sumber batuan untuk bahan bangunan
sebenarnya tidak perlu diperhitungkan nilainya sebagai bahan bangunan, walaupun
secara fisik batu karang terumbu karang itu ada. Demikian pula walaupun nilai
ekonominya tinggi tetapi bila secara fisik tidak ada, maka tidak perlu diberikan
penilaian.
Tabel 12. Nilai Ekonomi Sumber Daya Alam Desa Gondang
No Sumber Daya Alam Pesisir Kegunaan Nilai Ekonomi (Rp)
1 Hutan Mangrove Produsen Kayu 12.994.620.000 Nuresry Ground 15.094.400.000 Pelindung Abrasi 26.407.920.000 Sub total 54.496.940.000
2 Terumbu Karang Produsen Batu karang 995.520.000.000
Nursery ground 19.520.000.000 Sub total 1.015.040.000.000
3 Perikanan Ikan Tangkapan 25.740.000
Pengolahan Ikan 45.000.000 Sub total 70.740.000
4 Lahan Pesisir Pertanian dan Perkebunan 57.911.948.000
Nursery Ground 7.934.052.000 Sub total 65.864.000.000
Total 1.135.471.680.000
Kesimpulan
Salah satu aspek Delta Api adalah keberlanjutan mata pencaharian. Jika dilihat dari
pemetaan poteni Sumber Daya Alam, jumlah potensi SDA dirasa dapat mencukupi
kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan catatan, kualitas SDM harus baik
ketika mendayagunakan SDA yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan analisa valuasi
ekonomi untuk Potensi SDA di Desa Gondang. Berdasarkan hasil analisa Valuasi
Ekonomi, nilai ekonomi SDA Desa Gondang mencapai 1,13 Trilyiun rupiah. Catatannya
adalah SDM haru mampu untuk mengelola SDA secara optimal dan berasaskan
keberlanjutan.
Saran
Untuk pengembangan Delta Api kedepannya, dirasa penting untuk melakukan analisa
valuasi ekonomi secara lebih mendetail. Untuk kasus Desa Gondang, valuasi ekonomi
potensi SDA harus dikaji secara lebih mendalam, karena jika ditelaah lebih mendalam,
banyak faktor yang terkait SDA namun belum terhitung secara mendetail, misalnya
adalah potensi Sungai, Mata Air, serta perkebunan yang lebih luas.
Kedepannya, valuasi tidak hanya dilakukan berdasarkan potensi SDA saja, namun harus
diperhitungkan secara menyeluruh, karena pesisir merupakan wilayah yang kompleks.
Sehingga, kedepannya Nilai Ekonomi dapat menjadi masukan bagi perencanaan
pembangunan daerah.
Jika telah dilakukan secara mendetail, masterplan Delta Api dapat menjadi salah satu
role model pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil yang dapat mencadi acuan
bersama, namun replikasi dan scalling up nya tetap harus menyesuaikan karakteristik
dan cirikhas lokus dimana pesisir dan pulau kecil tersebut berada.
Daftar Pustaka
Adrianto, Luky., Mujio., Wahyudin, Yudi. 2004. Model Pengenalan Konsepdan
Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut. PKSPL-IPB
Anon. 1997. Biogas Utilization. GTZ.
http://ww5.gtz.de/gate/techinfo/biogas/appldev/operation/utilizat.html.
Fauzi, Ahmad., Halawa, C., Herdiana, L. 2011. Pengolahan Air Limbah Domestik Dengan
Metode Biologi Irrigation Memanfaatkan Enceng Gondok di Bak Penampung
Sebagai Penyerap Polutan Untuk Mengurangi Limbah Organik dan Anorganik.
Program Kreatifitas Mahasiswa Institut Pertanian Bogor
GTZ dan WWF NTB. 2010. Synthesis Report Risk and Adaptation Assessment to Climate
Change in Lombok Island, West Nusa Tenggara Province
Kariyasa, K. 2005. Sistem Integrasi Tanaman Ternak dalam Perspektif Reorientasi
Kebijakan Subsidi Pupuk dan Peningkatan Pendapatan Petani. Analisis
Kebijakan Pertanian. Volume 3 No.1, Maret 2005 :6– 80.
Saleh, E. 1997. Pengembangan Ternak Ruminansia Besar di Daerah Transmigrasi.
Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Simatupang, P. 2004. Prima Tani Sebagai Langkah Awal Pengembangan Sistem dan
Usaha Agribisnis Industrial. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial
Ekonomi Pertanian.
Suparmoko, M., Ratnaningsih, Maria., Setyarko, Yugi., Widyantara, Gatot. 2003. Valuasi
Ekonomi Sumber Daya Alam dan Pesisir Pulau Kangean. Seminar Nasional I
Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kongres I organisasi Profesi
Praktisi Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Indonesia. Baturaden,
Purwokerto, 12-14 Desember 2003