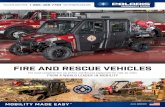Rescue II, The Last
Transcript of Rescue II, The Last
BAB IPENDAHULUAN
“Komputer membuat kita bisa melakukan banyak hal menjadi lebihmudah, namun sebagian besar hal-hal yang dipermudah itu ialah hal
yang tidak perlu untuk dilakukan.”– Andy Rooney
1.1 Latar belakang
Berbicara mengenai teknologi dan peradaban umat
manusia dari berbagai zaman merupakan materi monodualis
yang teramat sulit untuk dipisahkan perspektifnya, baik
secara antropologis, historis, maupun sosiologis. Jika
kita sering meng-update informasi lewat media elektronik
maupun media massa secara umum, maka dapat dipastikan
bahwa kita akan disodorkan dengan berita-berita tentang
perkembangan teknologi di berbagai belahan dunia yang
seringkali berorientasi futuristik. Perkembangan ini erat
kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan manusia dari
berbagai aspek hidupnya, karena teknologi memang
sejatinya diciptakan untuk mempermudah manusia dalam
menjalankan kehidupannya, mulai dari keinginan hingga
kebutuhan manusia secara individual maupun secara
komunal.
Dewasa ini perkembangan teknologi, informasi dan
komunikasi tumbuh semakin canggih, bahkan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTek) dapat sedemikian
1
cepatnya mengalahkan perkembangan peradaban masyarakat.
Pengaruhnya terhadap pola hidup masyarakat juga semakin
kuat, pola hidup yang dahulunya tradisional sekarang
berkembang menjadi semakin kompleks dan modern (Maryan,
2012:2).
Teknologi informasi ialah salah satu hal yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia, karena ia
sudah ada sejak berabad-abad lalu dan hingga kini masih
berkembang, tanpa adanya teknologi ini, manusia akan
sulit berkomunikasi dan menyampaikan informasi dalam
batasan tertentu. Teknologi ini banyak sekali memiliki
peranan hingga dampaknya dalam berbagai bidang, baik itu
pendidikan, kesehatan, politik, sosial-budaya, keamanan,
ekonomi bahkan hiburan. Berbagai peristiwa terkini yang
terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat kita ketahui
bahkan hanya berselang beberapa menit setelah informasi
atau peristiwa tersebut berlangsung hingga di-upload pada
jejaring sosial, ini berkat kemajuan teknologi.
Menurut Fauziah (2013:2), perubahan ini juga
memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi
nilai-nilai yang ada pada masyarakat, khususnya
masyarakat adat dan kebudayaan timur seperti Indonesia.
Saat ini, di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar
pengaruh kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai
kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, baik di perkotaan
2
maupun di pedesaan, seperti pengaruh televisi, telepon,
radio, telepon genggam, gadget, i-pad, bahkan internet
bukan hanya melanda masyarakat di perkotaan namun juga
dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa,
akibatnya segala informasi yang bersifat positif maupun
negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat dan
diakui atau tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola
hidup dan pola pemikiran masyarakat bahkan hingga lifestyle.
Pada masyarakat kontemporer, internet menjadi salah satu
kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat modern untuk
menunjang segala sektor kebutuhan hidup mereka, baik itu
untuk keperluan promosi bisnis, pendidikan, komunikasi,
hingga hiburan, membuat internet menjadi semakin diminati
oleh semua kalangan, salah satu layanan yang disediakan
oleh internet ialah fasilitas game online.
Game online bukan seperti game biasa yakni manusia
hanya melawan “otak” komputer, namun game online ialah
manusia melawan manusia dengan perantara komputer yang
terhubung dengan jaringan komputer dunia (international
network). Hebatnya lagi, game online tidak hanya satu lawan
satu, namun ada bahkan ribuan orang bermain pada saat
yang sama dari berbagai belahan dunia dalam satu area
game (field), artinya pertarungan atau interaksi lain
berlangsung bisa berbentuk individu dengan individu,
individu dengan kelompok bahkan kelompok dengan kelompok,
hal ini persis seperti proses interaksi di dunia nyata.3
Terpenuhinya kebutuhan sosial di dalam game online
serta “dibumbuhi” petualangan seru yang berfantasi tinggi
mengkontruksi pemikiran gamer bahwa dunia game online
adalah dunia mereka yang sebenarnya, hingga seringkali
membuat sebagian gamer tidak mampu meninggalkan game yang
sedang mereka mainkan, sama halnya seperti manusia yang
ketergantungan terhadap zat adiktif.
Sumber : APJII, 2012.
Dari data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna
aktif internet Indonesia saat ini diproyeksikan sudah
mencapai 107 juta orang, atau sekitar 24% dari total
populasi Indonesia. Dari data pengguna internet aktif
tersebut, diperkirakan pemain game online aktif Indonesia4
berkisar 10,7 juta orang, atau sekitar 10% dari total
jumlah pengguna internet. Pengertian aktif di sini adalah
mereka yang hampir setiap hari bermain game online. Untuk
pemain game online pasif, diperkirakan mencapai sekitar 15
jutaan. Perkiraan ini didapat dari data pengguna facebook
di indonesia yang telah tembus di atas 30 juta orang, di
mana 50% penggunanya pernah memainkan game online yang
terdapat di situs jejaring sosial tersebut.
Dilihat dari grafik pertumbuhan pengguna internet
dari tahun 1998 hingga proyeksi sampai tahun 2015
tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan
pengguna internet dari tahun ke tahun perlu
dipertimbangkan dampaknya terhadap perubahan pola
interaksi dari realitas yang riil menjadi “realitas”
virtual yang tentu telah banyak berkontribusi dalam
rekonstruksi nilai dan norma nyata ke dalam kebebasan
nilai dan norma dalam interaksi virtual tersebut.
5
Sumber : APJII, 2012
Penetrasi pengguna internet di Sumatera tergambar
pada skema di atas, yakni rata-rata 20%-30% di setiap
Propinsi. Propinsi Bengkulu sendiri menempati posisi
keempat dalam persentase pengguna internet tertinggi di
pulau Sumatera yaitu persentase pengguna sebesar 26,1%
dengan jumlah pengguna yakni 88.000 jiwa dari total
penduduk yang berjumlah 338.000 jiwa pada tahun 2012.
Memperkuat data tersebut, berdasarkan mini-survei
yang dilakukan oleh peneliti pada akhir Desember 2014,
bahwa dari 20 orang mahasiswa universitas Bengkulu yang
dipilih secara acak, 70% di antaranya menyatakan pernah
bermain game online dan 30% dari keseluruhan sampel masih
bermain game tersebut hingga saat ini. Hal tersebut6
membuktikan bahwa fenomena bermain game online hingga
kemungkinan mengalami kecanduan game online sedang
berlangsung di sekitar kita, dengan atau tanpa kita
sadari (Survei, Desember 2014).
Pemain game online merupakan bagian dari pengguna
internet, setiap tahunnya pemain game Indonesia
diperkirakan meningkat sekitar 5-10% seiring dengan
semakin pesatnya infrastruktur internet
(http://www.ligagame.com) Game online merupakan salah satu
pasar yang paling banyak diminati di dunia maya, sebagian
besar dampak positif dari bermain game online terhadap
kehidupan sosial gamer bahwa game online ternyata dapat
mendorong terjadinya interaksi sosial di dunia virtual,
tentunya antar sesama gamer, namun dibalik itu juga
terdapat dampak negatif bagi pemain game online, yakni
terjadi kecanduan terhadap game online dan seluruh
aktivitas di dalam game tersebut mengganti kebutuhan
sosialnya di dunia nyata. Game online sudah tidak asing
lagi bagi kehidupan anak-anak, remaja, bahkan orang
dewasa, karena saat ini, game dapat dengan mudah dijumpai
di rumah dengan komputer pribadi yang berfasilitas wifi,
warung internet, atau melalui smartphone yang
berspesifikasi tinggi.
Gamer dan pecandu game online adalah konsep berbeda,
seorang pecandu game online adalah gamer sedangkan gamer
7
belum tentu pecandu game. Untuk membedakan kedua konsep
tersebut, maka penting untuk mengetahui beberapa
karakteristik pecandu game online. Menurut Suler (dalam
Soebastian, 2010:76) aspek-aspek yang nampak ketika
seseorang mengalami kecanduan game online yakni adanya
perubahan gaya hidup yang drastis untuk menghabiskan
lebih banyak waktu melakukan memainkan game online, artinya
ialah terjadi peningkatan secara signifikan intensitas
bermain game online mengalahkan intensitas kegiatan rutin
lainnya dalam kehidupan harian pecandu game online.
Selanjutnya ialah gamer pecandu mengalami penurunan
aktivitas fisik dan mengabaikan kesehatan, hal tersebut
dapat dilihat dari munculnya berbagai penyakit yang
mengancam pecandu game antara lain radiasi mata,
pembengkakan jari, obesitas, dan lain sebagainya akibat
bermain game online secara berlebihan, kemudian
permasalahan kurang tidur atau perubahan pola tidur untuk
menghabiskan waktu bermain game online, hal tersebut
merujuk pada lamanya waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan game online dan banyaknya target-target yang
perlu dicapai gamer untuk tantangan game pada periode
tertentu, yang demikian jelas menyita banyak waktu.
Akibatnya waktu tidur seringkali dikorbankan untuk
bermain game. Secara sosial, pecandu game online akan
mengalami penurunan proses sosialisasi, mengabaikan
keluarga dan teman serta lingkungan sekitar. Orang-orang
8
yang mengalami kecanduan game online yang akut tak ubah
dengan mereka yang kecanduan zat adiktif dilihat dari
perilaku psikologis. Depresi berat dan tidak dapat
mengendalikan emosi menjadi salah satu karakteristik
pecandu game online ketika ia tidak dapat memenuhi
kebutuhan bermain, mereka dapat melakukan tindak kriminal
hanya untuk memenuhi hasrat bermain. Kasus-kasus gamer
yang mencuri atau menjual barang-barang milik pribadinya
atau milik orang lain demi membeli chip game atau membayar
warnet sudah sering muncul di media massa.
Secara umum, terdapat dua dampak bermain game yang
dijabarkan oleh para ahli di atas, yakni dampak positif
dan dampak negatif. Terkait dengan itu, maka peneliti
perlu melakukan penelitian untuk menggali apa saja
gejala-gejala hingga dampak-dampak bermain game online yang
berlebihan di wilayah penelitian. Selain alasan tersebut,
alasan lain yang mendorong perlunya dilakukan penelitian
ini ialah: pertama, dengan membangun model teoritikal
yang dikembangkan dari penelitian ini, diharapkan dapat
membantu para akademisi (dalam konteks sosiologi) untuk
melakukan pengembangan pada penelitian yang akan datang.
Penelitian terhadap fenomena kecanduan game online masih
sangat menarik untuk dibahas dari perspektif sosial,
sebab selama ini, fenomena tersebut hanya gencar diteliti
dari perspektif medis dan psikologi saja, sedangkan
dimensi sosial masih belum banyak digali. Kelangkaan9
studi tentang fenomena kecanduan game online membuat
penelitian ini perlu untuk dilakukan, sehingga temuan
penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan
sumbangan kepada tidak hanya pembaca namun pemerintah
untuk membuat kebijakan strategis terkait pembatasan game
online dan game center di kota Bengkulu.
Penelitian sebelumnya mengenai “Kecanduan Mahasiswa
terhadap Game Online: Studi tentang kebiasaan mahasiswa
bermain game online di Seturan Sleman” telah dilakukan oleh
Widyastuti pada tahun 2012 silam. Pada penelitian
tersebut, Widyastuti menyarankan kepada peneliti
selanjutnya agar memberikan lebih banyak lagi penjelasan
mengenai kecanduan mahasiswa terhadap game online agar
dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dalam studi
sosiologi. Ini artinya, penelitian sebelumnya belum dapat
menjelaskan fenomena kecanduan game online secara
komprehensif, hal ini wajar mengingat belum banyak
penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan
literatur. Untuk itu peneliti melakukan penelitian
tentang kecanduan game online agar dapat membantu peneliti
dan pembaca nantinya dalam memahami konteks kecanduan
game online secara sosiologis.
Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan teknik penentuan sampel yakni purposive
sampling. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
10
faktor bermain game dan dampak perilaku sosial yang
ditimbulkan oleh penggunaan game online. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong mahasiswa
menjadi kecanduan bermain game online yaitu tekanan teman
sebaya, dimana adanya solidaritas atau tanggung jawab
moral tertentu pada kelompok pergaulan gamers tersebut
serta keinginan-keinginan untuk mengaktualisasikan diri
dalam pergaulan teman sebaya, selanjutnya jenis game online
yang mendorong mahasiswa menjadi kecanduan bermain game
online, kemudian banyaknya waktu luang yang dimiliki
mahasiswa didukung dengan kurangnya variasi kegiatan
sehari-hari sehingga menempatkan kegiatan bermain game
sebagai alasan untuk mengisi banyaknya waktu luang
tersebut, lalu kurangnya pengawasan dari orangtua, baik
faktor melemahnya fungsi lembaga pengawas seperti
keluarga, masyarakat dan pemerintah serta kondisi ekonomi
gamer itu sendiri berpengaruh pada lamanya aktivitas para
gamer di dunia game, terakhir ialah kebijakan pengelola
game centre yang tidak membatasi gamer dalam melakukan
permainan.
Selain faktor-faktor pendorong di atas, hasil
penelitian tersebut juga menjabarkan tentang dampak-
dampak perilaku sosial para mahasiswa yang mengalami
kecanduan game online. Dampak-dampak tersebut ialah
kehidupan real gamer menjadi berantakan dan membuat gamer
11
terisolisir dengan lingkungan sekitar, mengganggu
kesehatan, dan mengakibatkan pola makan dan tidur yang
tidak teratur sehingga mudah terserang penyakit. Dampak
yang ditimbulkan dari sebuah jenis permainan online ini
makin lama akan makin terlihat jelas.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang
kecanduan game online pada mahasiswa dari aspek sosiologis.
Metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi.
Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan
penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus
kajiannya, jika penelitian yang lalu melihat faktor
bermain game online dan dampak penggunaan game online dari
aspek perilaku sosial, maka peneliti akan meneliti
tentang aspek sosiologis dari gejala kecanduan game online
dan ditujukan pada dampak akademis akibat kecanduan game
online pada mahasiswa.
Penelitian lain yang relevan dengan penelitian yang
akan dilakukan peneliti ialah penelitian Soebastian
(2010) dengan judul “Dampak Psikologis Negatif Kecanduan
12
Permainan Online Pada Mahasiswa”, penelitian tersebut
jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan, sebab disiplin ilmunya sudah berbeda. Ada
beberapa penelitian lagi yang meneliti tentang adiksi
game online namun objek penelitiannya adalah siswa SMA
dan remaja awal seperti penelitian Suvereniam (2011),
Pratiwi dkk. (n.d), Maryan (2012), Febrian (2011) dan
Fauziah (2013). Penelitian-penelitian ini juga memiliki
perbedaan disiplin ilmu dan fokus kajian serta informan
dengan penelitian yang akan dilakukan, sebab penelitian-
penelitian tersebut ialah riset psikologi, kedokteran dan
hukum.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka menjadi
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini
adalah:
1. Mengapa mahasiswa dapat mengalami kecanduan game
online dan apa bentuk-bentuk (karakteristik)
kecanduan game online?
2. Bagaimana dampak akademis bagi mahasiswa yang
mengalami kecanduan game online?
1.3 Tujuan penelitian
Mendeskripsikan dan menganalisis kecanduan game online
dan bentuk-bentuk kecanduan game online serta dampak-
13
dampak secara akademis kecanduan game online bagi
gamer.
1.4 Manfaat penelitian
1.4.1 Manfaat praktis
Mamberikan gambaran serta penjelasan analitis
tentang kecanduan game online, bentuk-bentuk kecanduan
game online serta dampak-dampak akademis kecanduan
game online bagi mahasiswa pecandu game online.
1.4.2 Manfaat teoritis
Untuk memperkaya literatur dan informasi yang
bermanfaat bagi pengembangan teori dan konsep
sosiologi mengenai fenomena kecanduan game online.
1.5 Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, tepatnya
di Kelurahan Kandang Limun, mengingat wilayah ini
merupakan lingkungan mahasiswa dan pelajar karena
berdampingan langsung dengan Universitas Bengkulu.
Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat strategis
karena terdapat banyak warnet game online dan mewakili
dari populasi gamer di Kota Bengkulu, menurut
pengamatan peneliti, di area Kandang Limun terdapat
beberapa warung internet (warnet) yang bukan hanya
untuk browsing biasa melainkan warnet yang juga
menyediakan fasilitas game online dan secara kasat
mata warnet ini dipadati pengunjung setiap harinya
untuk bermain game, dan mayoritas gamer disini
14
berstatus mahasiswa dan pelajar. Adapun jumlah
warnet game online berdasarkan lingkungan universitas
ialah:
Tabel 1.1Jumlah warnet game online berdasarkan lingkungan
universitas di Kota Bengkulu 2015
No Universitas Jumlah1 IAIN Bengkulu 32 STIKES TSM 23 UNIVED 34 UNIHAZ 16 UMB 27 UNIB 12
Sumber : Data pra-penelitian, 2015.
Fenomena game online di kota Bengkulu masih sedikit
diangkat sebagai tema penelitian oleh akademisi,
terutama akademisi sosial seperti mahasiswa dan
dosen sosiologi, sedangkan kita tahu bahwa hal ini
merupakan suatu permasalahan sosial kontemporer yang
serius karena menyangkut masa depan generasi muda.
15
BAB IITINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan pustaka
2.1.1 Mahasiswa
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa
adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi.
Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang
tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam
bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan
tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri
setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling
melengkapi. Mahasiswa adalah manusia yang tercipta untuk
selalu berpikir yang saling melengkapi (Widyastuti,
2012:9). Tapi pengertian itu tidak hanya sebatas itu,
Mahasiswa itu mengandung pengertian yang lebih luas dari
sekedar terdaftar secara administrasi, akan tetapi
menjadi mahasiswa itu mengandung arti yang sangat luas,
mahasiswa adalah agen pembawa perubahan. Menjadi
mahasiswa itu merupakan kebanggaan dan juga sebagai
16
tanggung jawab besar sebagai agen pembawa perubahan.
Menjadi seseorang yang akan memberikan solusi terhadap
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagai kaum
intelektual, mahasiswa memiliki peranan yang sangat
penting dalam kehidupan berbangsa. Pertama sebagai agent of
change, mahasiswa sebagai agen perubahan dituntut bersifat
kritis dan diperlukan implementasi yang nyata. Mahasiswa
adalah garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak
rakyat, mengembalikan nilai-nilai kebenaran yang
dilakukan oleh kelompok-kelompok elit yang hanya
mementingkan dirinya dan nasib kelompoknya. Harapan
bangsa terhadap mahasiswa adalah menjadi generasi penerus
yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa.
Kedua adalah sebagai social control, mahasiswa sebagai
penengah antara pemerintah dan masyarakat, disinilah
peranan mahasiswa sebagai pengontrol. Mahasiswa
menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan
juga mahasiswa menunjukkan sikap yang baik terhadap
masyarakat sebagai kontrol sosial. Sebagai pengontrol
sosial mahasiswa juga memiliki tugas mengontrol peraturan
dan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan pribadi dan
kelompok. Ketiga adalah iron stock, yaitu mahasiswa
diharapkan menjadi manusia tangguh yang memilik kemampuan
dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan
generasi sebelumnya.
17
Karakteristik mahasiswa secara umum yaitu stabilitas
dalam kepribadian yang mulai meningkat, karena
berkurangnya gejolak-gejolak yang ada didalam perasaan.
Mereka cenderung memantapkan dan berpikir dengan matang
terhadap sesuatu yang akan diraihnya, sehingga mereka
memiliki pandangan yang realistik tentang diri sendiri
dan lingkungannya. Selain itu, para mahasiswa akan
cenderung lebih dekat dengan teman sebaya untuk saling
bertukar pikiran dan saling memberikan dukungan, karena
dapat kita ketahui bahwa sebagian besar mahasiswa berada
jauh dari orang tua maupun keluarga. Karakteristik
mahasiswa yang paling menonjol adalah mereka mandiri, dan
memiliki prakiraan di masa depan, baik dalam hal karir
maupun hubungan percintaan. Mereka akan memperdalam
keahlian dibidangnya masing-masing untuk mempersiapkan
diri menghadapi dunia kerja yang membutuhkan mental
tinggi. Sedangkan karakteristik mahasiswa yang mengikuti
perkembangan teknologi adalah memiliki rasa ingin tahu
terhadap kemajuan teknologi. Mereka cenderung untuk
mencari bahkan membuat inovasi-inovasi terbaru di bidang
teknologi. Mahasiswa menjadi mudah terpengaruh dengan apa
yang sering marak pada saat itu, misalnya game online.
Mereka akan mengikuti atau setidaknya hanya mencoba untuk
mengetahuinya.
2.1.2 Game online
18
Game adalah aktivitas yang dilakukan untuk
kesenangan seseorang atau kelompok yang memiliki aturan
tersendiri sehingga ada yang menang dan ada yang kalah
(kamus macmillan dalam Suveraniam, 2011:4), sedangkan
menurut Putra (dalam Praditasari, 2009:9), game berarti
hiburan namun juga merujuk pada pengertian sebagai
“kelincahan intelektual” (intellectual playability). Sementara kata
game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi
pemainnya serta ada target-target yang ingin dicapai
pemainnya. Kelincahan intelektual, pada tingkat tertentu,
merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk
dimainkan secara maksimal, selain itu, game membawa arti
sebuah kompetisi, fisik atau mental, menurut aturan
tertentu, untuk hiburan, rekreasi, atau untuk menang
taruhan. Menurut Eddy Liem (dalam Febrian, 2011:6),
direktur Indonesia Gamer, sebuah organisasi pencinta
games di indonesia, game online adalah sebuah permainan
yang dimainkan secara online via internet, bisa
menggunakan PC (personal computer) atau konsul game biasa
seperti PS (playstation), X-Box dan sejenisnya, biasanya
internet game dimainkan oleh banyak pemain dalam waktu
yang bersamaan dimana satu sama lain bisa saja tidak
saling mengenal. Game online adalah bentuk teknologi yang
hanya bisa diakses melalui jaringan komputer, Andrew
Rollings dan Ernest Adams membenarkan itu dalam
pernyataanya (dalam Tampubolon, 2012), yakni game online
19
lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi dibandingkan
sebagai sebuah genre atau jenis permainan, yakni sebuah
mekanisme untuk menghubungkan banyak pemain bersamaan
dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.
2.1.3 Sejarah perkembangan game online
Perkembangan game online tidak lepas dari perkembangan
teknologi komputer dan jaringan komputer, karena kedua
hal ini sangat erat hubungannya apalagi terkait
pembahasan mengenai sejarah perkembangan game online.
Meledaknya game online merupakan cerminan dari pesatnya
perkembangan teknologi jaringan komputer yang dahulunya
berskala kecil hingga menjadi internet dan terus
berkembang hingga sekarang. Pada saat muncul pertama kali
pada tahun 1969, komputer hanya bisa dipakai oleh dua
orang saja untuk bermain game, lalu kemudian mulailah
dikembangkan komputer dengan kemampuan time-sharing
sehingga pemain memainkan game tersebut bisa lebih banyak
dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama
(multiplayer games) (Mulligan dalam Suveraniam, 2011:4).
Pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis
paket (packet based computer networking), jaringan komputer
tidak hanya sebatas LAN (local area network) yang hanya
menghubungkan komputer lewat kabel saja tetapi sudah
mencakup WAN (wide area network) yang bersifat nirkabel
dengan jangkauan luas. Game online yang pertama kali muncul
20
kebanyakan adalah game-game jenis simulasi perang atau
pun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer saja
yang akhirnya dikomersialkan untuk umum. Game-game ini
kemudian menginspirasi game yang lain untuk muncul dan
berkembang.
“...online games really blossomed after the year 1995 when the restrictionsimparted by the NSFNET (national science foundation network) wereremoved. This resulted in the access to the complete domain of the internetand hence multi-player games became online 'literally' to the maximumpossible degree of realism. The monetary success of the parent companieswho first launched these games were ample source of encouragement forother companies to venture in this field. Hence competition continues togrow from that moment to even as this article is being written. The featureshence became more advanced in an effort to implement immaculateproduct differentiation and the resulting games became more and moreadvanced. Today most of the online games that are present are also freeand hence they are able to provide ample resources of enjoyment withoutthe need to spend a single penny.” (Aradhana Gupta, History ofonline game, 2008)1.
Dalam potongan artikel tersebut, Aradhana Gupta
(2008) menyebutkan bahwa pada tahun 1995, NSFNET (National
Science Foundation Network) telah membatalkan peraturan-
peraturan yang diperkenalkan sebelumnya dalam industri
game. Setelah pembatalan ini, ketercapaian para pemain
1 Game online benar-benar berkembang setelah tahun 1995 ketika pembatasan yangdiberikan oleh NSFNET (National Science Foundation Network) telah dihapus. Hal inimengakibatkan akses ke domain lengkap dari internet dan karenanya game multi-player secara online 'secara harfiah' menjadi maksimum. Keberhasilanperusahaan induk yang pertama kali meluncurkan game ini yang cukup untukmenjadi sumber dorongan bagi perusahaan lain untuk berusaha di bidang ini.Oleh karena itu kompetisi terus tumbuh dari saat itu bahkan hingga artikelini ditulis. Fitur game online menjadi lebih maju dalam upaya untuk menerapkandiferensiasi produk yang rapi dan permainan yang dihasilkan menjadi lebihmaju. Saat ini sebagian besar game online yang hadir juga bebas biaya dankarenanya mereka dapat menyediakan sumber daya yang cukup untuk kenikmatanbermain tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun.”
21
dalam online gaming dan perkembangannya maju begitu pesat
hingga saat ini. Trismarindra (dalam Soebastian, 2010:19)
menyatakan bahwa perkembangan permainan online yang cukup
pesat ditunjang oleh penambahan pemain dan variasi
permainan yang diciptakan bagi para pemain. Bermain game
online saat ini diyakini bukan hanya sebagai hiburan
semata, namun secara tidak langsung sebagai ajang untuk
mengasah kemampuan kecepatan berpikir dan melakukan
latihan strategi saat bermain serta untuk membentuk
komunitas tertentu, baik komunitas in-game maupun out-game
(Aji, 2012:42).
Fenomena game online sebagai gaya hidup di berbagai
belahan dunia saat ini cukup mencengangkan, dimana game
online yang mulanya diperuntukkan bagi anak-anak dan
remaja, kini bahkan telah dimainkan dan sangat diminati
oleh orang-orang dewasa. Maraknya game online ini diikuti
juga dengan munculnya berbagai studi dan pendapat
mengenai efek dari game online itu. Ada sebagian masyarakat
yang menyatakan bahwa game online berdampak buruk bagi
anak-anak dan remaja, namun ada pula yang mengungkapkan
bahwa game online dapat memberi efek positif bagi para
penggemarnya. Salah satu efek dari maraknya perkembangan
permainan online adalah terciptanya komunitas-komunitas
game online yang memfasilitasi para pemain untuk menuangkan
segala pengalaman mereka seputar bermain game. Bukan
hanya itu, komunitas-komunitas tersebut akhirnya menjadi22
ajang komunikasi multikultural yang dapat menjelma
sebagai gaya hidup dan penyambung hubungan sosial antar
sesama pemain, hal ini tentu akan semakin menarik jika
diulas lebih mendalam oleh ilmuan-ilmuan sosial.
Menurut Ligagame Indonesia (ligagames.com), game
online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan
masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia
sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action,
sport, maupun RPG (role-playing game). Tercatat lebih dari 20
judul game online yang beredar di Indonesia. Ini menandakan
betapa besarnya antuiasme para gamer di Indonesia dan
juga besarnya pangsa pasar game di Indonesia. Berikut
adalah game online yang pernah hadir di Indonesia2:
No Nama Game Tahun Rilis
Lisensi Tipe Game
TipeGrafis
Status
1 Nexia 2001 BolehGame RPG 2D Ditutup 2004
2 RedMoon 2002 - RPG 2,5D Ditutup 2005
3 Laghaim 2003 BolehGame RPG 3D Ditutup 2006
4 Ragnarok 2003 Lyto RPG 3D Masih5 GunBound 2004 BolehGame Action
RPG3D Masih
6 Xian 2004 BolehGame Strategy RPG
3D Masih
7 Risk Your Life
2004 DreamWebTech Action RPG
3D Masih
8 Tantra 2004 Playon RPG 3D Masih
2 Data ini bersifat fleksibel, karena cepat mengalami perubahan mengikutiperkembangan game online di Indonesia.
23
9 Survival Project
2004 Playon RPG 2D Ditutup 2006
10 GetAmped 2005 Lyto RPG 2,5D Masih11 Stargate 2005 Borneo X RPG 2D Ditutup
200612 TS 2005 Global World
TechnologyRPG 2D Ditutup
200613 O2jam 2005 Infomedia
NusantaraMusical 3D Masih
14 Pangya 2005 BolehGame Sport 3D Ditutup 2008
15 Knight 2005 Infomedia Nusantara
RPG 3D Ditutup 2007
16 Vital Sign 2005 - FPS 3D Ditutup 2007
17 SEAL 2006 Lyto RPG 3D Masih18 RAN 2006 Jaspace RPG 3D Masih19 Deco 2006 Playon RPG 3D Masih20 Ayo Dance 2006 Maxus Infotech Musical 3D Masih21 DOMO 2007 Datakom Wijaya
PratamaRPG 3D Masih
22 Angle Love 2007 WaveGame RPG 3D Masih23 Rising
Force2007 Lyto RPG 3D Masih
24 Ghost 2007 Kreon RPG 2D MasihSumber : Adiguna, 2010 (http://ryan-adi.blogspot.com/).
2.1.4 Jenis-jenis game online
Menurut Suveraniam (2011:2) secara umum, game online
terbagi menjadi dua jenis yaitu web based game (WBG) dan
text based game (TBG). WBG adalah aplikasi yang diletakkan
pada server di internet dimana pemain hanya perlu
menggunakan akses internet dan browser untuk mengakses
game tersebut. Jadi tidak perlu di install3 atau patch pada
perangkat lunak komputer untuk memainkan game-nya. Namun
3 Install adalah suatu istilah dalam dunia komputer dimana tujuannya ialahuntuk menanam aplikasi atau program tertentu pada sistem komputer agar bisadigunakan.
24
seiring dengan perkembangan game online, ada beberapa fitur
yang perlu di download untuk memainkan sebagian game,
seperti java player, flash player, maupun shockwave player, yang
biasanya diperlukan untuk tampilan grafis saja. Selain
itu, game seperti ini juga tidak menuntut spesifikasi
komputer yang canggih, dan tidak lagi membutuhkan bandwith
yang besar. Selain itu, sebagian besar WBG adalah
gratis. Pembayaran hanya diperlukan untuk fitur-fitur
tambahan dan mempercepat perkembangan akun pada game
tersebut. Sedangkan TBG bisa dibilang sebagai awal dari
WBG. TBG sudah ada sejak lama, dimana saat sebagian
komputer masih berspefikasi rendah dan sulit untuk
memainkan game-game dengan grafis beresolusi tinggi,
sehingga dibuatlah game-game dimana pemain hanya
berinteraksi dengan teks-teks yang ada dan sedikit atau
tanpa gambar (Bartle; Bruckman; Curtis; dalam Suveraniam,
2011). Memang setelah masa tersebut, TBG hampir tidak
pernah dilirik lagi oleh para gamer, namun ternyata saat
ini mulai marak TBG yang beredar yang sekarang kita kenal
sebagai WBG. Tentu saja dengan format yang lebih modern,
grafis diperbanyak dan dipercantik, menggunakan koneksi
internet dan developer game yang makin kreatif.
Berdasarkan genre, game online memiliki jenis yang
banyak, mulai dari permainan sederhana berbasis teks
sampai permainan yang menggunakan grafik kompleks dan
membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain25
sekaligus. massively multiplayer online games (MMOG) adalah game
online dengan jumlah pemain di atas seratus orang. pemain
bermain dalam dunia yang skalanya besar, di mana setiap
pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia
nyata. MMOG muncul seiring dengan perkembangan akses
internet broadband di negara maju, sehingga memungkinkan
ratusan, bahkan ribuan pemain untuk bermain bersama-sama.
MMOG sendiri memiliki banyak jenis seperti:
1. Massively Multiplayer Online First-Person Shooter
(MMOFPS)
Game online jenis ini mengambil sudut pandang orang
pertama sehingga seolah-olah pemain berada dalam
permainan tersebut dalam sudut pandang tokoh karakter
yang dimainkan, di mana setiap tokoh memiliki kemampuan
yang berbeda dalam tingkat akurasi, refleks, dan lainnya.
Permainan ini dapat melibatkan banyak orang dan biasanya
permainan ini mengambil setting peperangan dengan
senjata-senjata militer. Contoh permainan jenis ini
antara lain Counter Strike, Call of Duty, Point Blank, Quake, Blood dan
Unreal.
2. Massively Multiplayer Online Real-Time Strategy
(MMORTS)
Game jenis ini menekankan kepada kehebatan strategi
pemainnya. Permainan ini memiliki ciri khas di mana
pemain harus mengatur strategi permainan. Dalam RTS, tema
permainan bisa berupa sejarah (misalnya seri Age of26
Empires), fantasi (misalnya Warcraft), dan fiksi ilmiah
(misalnya Star Wars).
3. Massively Multiplayer Online Role-Playing Games
(MMORPG)
Game jenis ini biasanya memainkan peran tokoh-tokoh
khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita
bersama. RPG biasanya lebih mengarah ke kolaborasi sosial
daripada kompetisi. Pada umumnya dalam RPG, para pemain
tergabung dalam satu kelompok. Contoh dari genre
permainan ini Ragnarok Online,The Lord of the Rings
Online: Shadows of Angmar, Final Fantasy, dan DotA.
4. Cross-platform online play
Jenis ini dapat dimainkan secara online dengan
perangkat yang berbeda. Saat ini mesin permainan konsol
(console games) mulai berkembang menjadi seperti komputer
yang dilengkapi dengan jaringan sumber terbuka (open source
networks), seperti Dreamcast, PlayStation 2, dan Xbox yang
memiliki fungsi online. misalnya Need for Speed
Underground, yang dapat dimainkan secara online dari PC
maupun Xbox 360.
5. Massively Multiplayer Online Browser Game
Game jenis ini dimainkan pada browser seperti
Mozilla Firefox, Opera, atau Internet Explorer. Game
sederhana dengan pemain tunggal dapat dimainkan dengan
browser melalui HTML dan teknologi scripting HTML27
(JavaScript, ASP, PHP, MySQL). Perkembangan teknologi
grafik berbasis web seperti Flash dan Java menghasilkan
permainan yang dikenal dengan “Flash games” atau “Java
games” yang menjadi sangat populer. Permainan sederhana
seperti Pac-Man bahkan dibuat ulang menggunakan pengaya
(plugin) pada sebuah halaman web. Browser games yang baru
menggunakan teknologi web seperti Ajax yang memungkinkan
adanya interaksi multiplayer.
6. Simulation games
Game jenis ini bertujuan untuk memberi pengalaman
melalui simulasi. Ada beberapa jenis permainan simulasi,
di antaranya life-simulation games, construction and management
simulation games, dan vehicle simulation. Pada life-simulation games,
pemain bertanggung jawab atas sebuah tokoh atau karakter
dan memenuhi kebutuhan tokoh selayaknya kehidupan nyata,
namun dalam ranah virtual. Karakter memiliki kebutuhan
dan kehidupan layaknya manusia, seperti kegiatan bekerja,
bersosialisasi, makan, belanja, dan sebagainya. Biasanya,
karakter ini hidup dalam sebuah dunia virtual yang
dipenuhi oleh karakter-karakter yang dimainkan pemain
lainnya. Contoh permainannya adalah Second Life.
2.1.5 Pendorong kecanduan game online
2.1.5.1 Interaksi sosial virtual dalam cyberspace
Menurut Piliang (2012:145), Perkembangan teknologi
informasi telah menciptakan sebuah “ruang baru” yang28
bersifat artifisial (buatan) dan maya, yaitu cyberspace.
Cyberspace telah mengalihkan berbagai aktivitas manusia
dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kultural,
spiritual bahkan seksual yang ada di dunia nyata ke dalam
berbagai bentuk substitusi artifisialnya, sehingga apapun
yang dapat dilakukan di dunia nyata kini dapat dilakukan
dalam bentuk artifisialnya di dalam cyberspace. Sebuah
migrasi besar-besaran kehidupan manusia tampaknya tengah
berlangsung, yaitu migrasi dari “jagad nyata” ke “jagad
maya”.
Migrasi humanitas ini telah menimbulkan perubahan
besar tentang bagaimana setiap orang menjalani dan
memaknai “kehidupan”. Berbagai cara hidup dan bentuk
kehidupan yang sebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-
relasi alamiah (natural), kini dilakukan dengan cara yang
baru, yaitu cara artifisial. Cyberspace menciptakan sebuah
kehidupan yang dibangun sebagian besar—mungkin nanti
seluruhnya—oleh model kehidupan yang dimediasi secara
mendasar oleh teknologi, sehingga berbagai fungsi alam
kini diambil alih oleh substitusi teknologis-nya, yang
disebut kehidupan artifisial (artificial life).
Tidak saja berbagai aktivitas manusia kini dilakukan
dengan cara yang baru, lebih dari itu, kini tengah
berlangsung semacam transformasi terminologis dan
epistemologis tentang apa yang disebut sebagai
29
“masyarakat”, “komunitas”, “komunikasi”, “ekonomi”,
“politik”, “budaya”, “spiritual” dan “seksual”. Ada
“migrasi terminologis” besar-besaran yang juga
berlangsung kini, yaitu pemberian awalan cyber untuk
hampir seluruh bidang kehidupan nyata, yang kini telah
bertransformasi menjadi kehidupan maya, antara lain:
cyber-society, cyber-community, cyber-economy, cyber-politics, cyber-culture,
cyber-spirituality, cyber-sexuality. Singkatnya, berilah awalan cyber
untuk setiap kata di dalam kamus, maka itulah migrasi
yang tengah berlangsung menuju dunia cyberspace (Piliang,
2012:145).
Menurut Muttaqin (n.d., Hal. 4), realitas-realitas
sosial-budaya yang ada di dunia nyata kini mendapatkan
tandingan-tandingannya, yang pada akhirnya mengaburkan
batas di antara keduanya. Cyberspace yang terbentuk oleh
jaringan komputer dan informasi yang terhubungkan secara
global telah menawarkan bentuk-bentuk “komunitas” sendiri
(virtual community), bentuk “realitas” nya sendiri (virtual
reality) dan bentuk “ruang” nya sendiri (cyberspace). Dalam
konteks ini, realitas maya di jagad cyber bisa kita lihat
sebagai refleksi dari realitas nyata dalam kehidupan
sehari-hari.
Berbagai persoalan di dunia nyata, mulai dari yang
besar seperti terorisme sampai yang kecil dan remeh
seperti bagaimana mengatasi sisa makanan yang nyangkut di
30
gigi, menjadi pembicaraan menarik di dunia maya. Jadi,
realitas maya ini adalah cermin yang paling komplit dari
realitas nyata. Karena itu para penghuni dunia maya tidak
merasa hidup di planet lain atau dunia lain. Mereka
merasa hidup di dunia dan planet yang sama dengan yang
mereka huni dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sifat
nyata dunia virtual ini bukan hanya karena ada korelasi
langsung dengan realitas nyata tapi dunia virtual memang
mampu menjadi realitas kedua yang bisa menggantikan
realitas nyata sehari-hari. Karenanya, bukan hal aneh
jika ada orang yang lebih banyak menjalani hidup di dunia
maya daripada dunia nyata seperti pada kasus yang sedang
penulis teliti, yakni mengenai kecanduan game online yang
mendeskripsikan bagaimana fenomena internet addiction pada
sektor game online dapat terjadi di kalangan mahasiswa. Ini
bisa terjadi karena cyberspace menawarkan keasyikan
tersendiri bagi para penggunanya. Cyberspace menawarkan
cara baru dalam menjalani dan mengalami hidup.
Hidup di dunia cyber, bagi banyak orang sangat
mengasyikkan, bahkan dirasakan lebih menjanjikan
keintiman. Ngobrol itu biasa, tapi ketika dilakukan di
jagad raya cyber dengan teman-teman maya kita, ada
keasyikan tersendiri. Diskusi itu fenomena yang biasa
kita saksikan di kalangan terpelajar tapi kalau
diskusinya melalui twitter, ada aspek lain yang ikut serta:
rekreatif, menyenangkan dan menggoda. Terlebih jika31
dilakukan dengan cara anonim seperti ketika orang ngobrol
via mIRC (Internet Relay Chat) atau Yahoo Messenger, orang akan
merasa lebih bisa terbuka dan tak jarang sangat
ekspressif. Karena anonimitasnya, orang dapat saja
tergoda dan merasa aman untuk mengungkapkan bagian-bagian
dari dirinya yang tidak terungkapkan di dunia nyata.
Sumber : Muttaqin, n.d., Hal. 4.
Skema interaksi virtual tersebut memberikan gambaran
bahwa “para penduduk” dunia maya seakan memiliki dua
identitas dan kepribadian yang bisa jadi sangat berbeda.
Kita tidak bisa sekedar menilai mana diantara dua
indentitas dan kepribadian ini yang asli karena bisa jadi
dua-duanya memang mencerminkan dirinya yang sebenarnya,
32
hanya berbeda sisi. Semua orang mempunyai dua sisi yang
berbeda atau bahkan bertentangan, sisi gelap dan terang,
sisi hitam dan putih, sisi introvet dan ekstrovet, sisi
ilahi dan syaitoni. Di dunia nyata, karena kontrol nilai dan
norma-norma dalam masyarakat, ia mungkin hanya akan
menampilkan bagian dirinya yang direstui secara sosial
saja. Di dunia maya, kontrol semacam ini sangat longgar
atau bahkan tidak ada sama sekali. Karena itu ia merasa
bebas untuk mengekspresikan bagian dirinya yang
terpendam. Terlebih jika dia masuk dalam jagad raya cyber
dalam situasi anonim (tidak bernama/nama samaran), ia
tidak lagi merasa perlu mengindahkan nilai dan norma–
norma yang ada karena tidak ada seorang pun yang
mengenalnya. Situasi tidak dikenal atau anonim inilah
yang membuat banyak orang merasa aman jika melakukan
tindakan-tindakan yang secara sosial tidak direstui atau
tidak bertanggungjawab.
Inilah yang disebut virtual reality, sebuah realitas baru
era informasi. Tujuan utama virtual reality pada dasarnya
adalah untuk menciptakan ilusi keterlibatan dalam sebuah
lingkungan yang dapat dirasakan sebagai tempat yang
sebenarnya, dengan sejumlah interaktifitas yang cukup
untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cara yang
efisien dan menyenangkan.
33
Menurut Michael Heim (dalam Muttaqin n.d., hlm. 5),
virtual reality memiliki beberapa sifat. Pertama, simulation.
Realitas virtual berbentuk simulasi dari kehidupan nyata.
Jika tampak sesosok manusia, ini hanyalah simulasi dari
manusia yang sebenarnya, dalam bentuk grafis. Jika
terdengar suara manusia, ini hanya simulasi suara manusia
yang diproduksi oleh teknologi simulasi. Kedua, Interaction.
Virtual reality menawarkan interaksi antara pengguna dengan
dunia virtual. Kita dapat menghadiri kuliah dalam sebuah
universitas secara online tanpa harus hadir di kelas yang
sesungguhnya. Manusia juga dapat bersosialisasi dengan
komunitas maya seperti situs-situs jejaring sosial
(facebook, twitter, dan lain-lain), mailing list atau chatting.
Ketiga, Artificiality. Kenyataan yang ditawarkan virtual reality
sesungguhnya hanyalah kenyataan buatan, semuanya hasil
konstruksi manusia. Keempat, Immersion. Masuk dalam virtual
reality berarti terlibat didalamnya, merasa seakan hidup
dalam alam virtual. Ini yang disebut dengan the illusion of
immersion. Kelima, Telepresence. Virtual reality memungkinkan kita
hadir dari jarak jauh tanpa harus berada di dalamnya
secara fisik. Hadir di sini berarti bahwa kita tahu dan
sadar dengan apa yang terjadi, dapat melakukan sesuatu
dengan cara mengamati, meraih, memegang dan memindahkan
sesuatu dengan tangan kita sendiri seakan kita berada di
dekatnya. Keenam, Networked communications. Dalam dunia
virtual, komunikasi selalu dijalankan dengan menggunakan
34
jaringan komputer. Artinya, orang tidak bertemu langsung
dalam sebuah komunikasi, tapi hanya melalui jaringan
komputer, persis seperti dua orang yang sedang berbicara
via telepon.
a. Ontologi cyberspace
Cyberspace adalah sebuah “ruang imajiner”, yang di
dalamnya setiap orang dapat melakukan apa saja yang bisa
dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara
yang baru, yaitu cara artifisial. Cara artifisial adalah
cara yang mengandalkan pada peran teknologi, khususnya
teknologi komputer dan informasi dalam mendefinisikan
realitas, sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di
dalamnya: bersenda-gurau, berdebat, diskusi, bisnis,
brainstorming, gosip, pertengkaran, protes, kritik,
bermain, bermesraan, bercinta, menciptakan karya seni,
semuanya dapat dilakukan di dalam ruang cyberspace.
Disebabkan sifat artifisialnya, cyberspace telah
membentangkan sebuah persoalan fenomenologis dan
ontologis tentang “ada” dan “keberadaan” di dalamnya.
Keberadaan cyberspace telah membentangkan sebuah persoalan
mendasar tentang “dunia kehidupan” itu sendiri (lifeworld).
“Dunia kehidupan” adalah sebuah dunia yang kompleks, yang
melibatkan berbagai model kesadaran (consciousness),
pengalaman (experiences) dan persepsi. Sebagaimana
dikatakan Alfred Schutz & Thomas Luckmann di dalam The35
Structure of the Life World (dalam Piliang, 2012:146), di dalam
dunia kehidupan dibedakan antara dunia harian yang
melibatkan kesadaran dan “dunia lain” yang melibatkan
ketidaksadaran (unconsciousness) seperti mimpi, atau bawah
sadar (subcosciousness).
Kesadaran manusia adalah selalu “kesadaran akan
sesuatu”, yaitu kesadaran kognitif yang “menangkap obyek-
obyek” di sekitar. Bila kesadaran kognitif itu tidak
berlangsung, maka artinya manusia berada di dalam alam
bawah sadar atau ketaksadaran. Dunia fantasi adalah dunia
kesadaran yang diarahkan bukan pada obyek obyek di dunia
nyata, melainkan obyek-obyek fantasi yang bersifat
internal di dalam ruang pikiran. Dunia tidur adalah dunia
bawah sadar, yaitu dunia ambang antara sadar dan tak
sadar. Dunia mimpi adalah dunia ketaksadaran, yang di
dalamnya obyek-obyek ditangkap pikiran lewat mekanisme
ketaksadaran. Cyberspace adalah dunia yang dimasuki manusia
dengan kesadaran, akan tetapi ia berbeda dengan dunia
harian (everyday lifeworld), yang merupakan dunia yang
dibangun berdasarkan “kesadaran atas obyek-obyek nyata”.
Obyek-obyek di dalam cyberspace, sebaliknya, adalah obyek-
obyek “tak nyata”, yang ditangkap pengalaman hanya dalam
wujud halusinasi (hallusination).
Cyberspace bukan mimpi, tetapi ia bukan pula “yang
nyata” dalam pengertian dunia harian, disebabkan ia
36
dibangun oleh ruang-ruang artifisialitas teknologis. Bila
dikaitkan dengan arus kesadaran dalam durasi kehidupan
manusia, cyberspace bukanlah dunia ketaksadaran atau bawah
sadar, melainkan dunia kesadaran, yang di dalamnya
seseorang mengalami sebuah “obyek” di luar dirinya lewat
mekanisme penginderaan (Gestalt). Akan tetapi, “pengalaman”
yang dialami seseorang di dalam cyberspace berbeda dengan
pengalaman di dunia nyata, disebabkan perbedaan “obyek”
yang ditangkap oleh pengalaman. Di dalam cyberspace setiap
orang lewat kesadarannya menangkap “obyek-obyek”, akan
tetapi semuanya bukanlah obyek-obyek nyata, melainkan
“obyek-obyek maya” yang terbentuk lewat bit-bit komputer.
Di dalam cyberspace, arus kesadaran yang menangkap
obyek-obyek nyata (termasuk manusia lain sebagai obyek)
dialihkan ke dalam kesadaran yang menangkap dunia
“halusinasi”.Oleh sebab itu, perbedaan “pengalaman” di
dunia cyberspace dengan di dunia nyata terletak bukan pada
perbedaan tingkat kesadaran itu sendiri (tak sadar, bawah
sadar atau sadar) melainkan perbedaan “kualitas” obyek
yang ditangkap oleh kesadaran. Obyek yang ditangkap
kesadaran di dunia nyata adalah obyek-obyek yang
mengikuti hukum-hukum fisika: ia dibentuk oleh partikel-
partikel atom dan substansi-substansi yang membangun
struktur bentuknya; ia meruang, dalam pengertian,
menempati sebuah volume ruang tertentu sebagai “wadah
obyek-obyek” ia mengikuti hukum-hukum alam seperti hukum37
gravitasi, inersia dan percepatan. Sehingga, secara
fenomenologis, pengalaman di dunia nyata ini adalah
pengalaman “nyata”, dalam pengertian pengalaman yang
mengikuti hukum-hukum alam (melihat, menyentuh, bergerak
di dalam ruang). Sebaliknya, obyek-obyek di dalam
cyberspace, meskipun bukan mimpi, adalah obyek-obyek yang
dibentuk oleh satuan-satuan informasi di dalam sistem
pencitraan komputer yang disebut bit (byte), yang tidak
mengikuti hukum-hukum fisika di atas. Oleh karena ia
tidak mengikuti hukum fisika, maka pengalaman “hidup” di
dalam cyberspace sesungguhnya bukanlah pengalaman fisik
(meruang, mewaktu, mendunia) melainkan pengalaman yang
disebut oleh berbagai pemikir cyberspace sebagai pengalaman
“halusinasi”, yaitu mengalami sesuatu yang sesungguhnya
tidak ada wujud fisiknya.
Cyberspace dijelaskan oleh William Gibson (dalam
Piliang, 2012:147) sebagai sebuah “halusinasi” yang
dialami oleh jutaan orang setiap hari (berupa)
representasi grafis yang sangat kompleks dari data di
dalam sistem pikiran manusia yang diabstraksikan melalui
bank data setiap komputer. Akan tetapi, pengertian
“halusinasi” di dalam konteks cyberspace harus dibedakan
dengan pengertian halusinasi di dalam dunia harian.
Halusinasi di dalam dunia harian adalah semacam
“interupsi kesadaran”, yang di dalamnya kesadaran akan
obyek-obyek nyata (eksternal maupun internal) secara38
temporer “diganggu” oleh kesadaran akan obyek-obyek yang
tak berwujud materi, yang segera hilang ketika manusia
kembali ke dalam kesadaran hariannya. Sebaliknya,
halusinasi di dalam cyberspace adalah halusinasi yang
“diproduksi” secara teknologis berupa citra-citra di
dalam sistem komputer (mass produced hallusination), sehingga
ia dapat disimpan (save), diperbanyak, disalin, dikirim,
dan dialami kembali di masa mendatang.
b. Cyberspace dan perubahan sosial
Perkembangan cyberspace telah mempengaruhi kehidupan
sosial di dalam berbagai tingkatnya. Keberadaan cyberspace
tidak saja telah menciptakan perubahan sosial yang sangat
mendasar, malahan oleh berbagai pemikir dikatakan telah
menggiring pada kondisi ekstrim “kematian sosial” (death of
the social). Terlepas dari pemikiran ekstrim ini, pengaruh
cyberspace terhadap kehidupan sosial setidak-tidaknya
tampak pada tiga tingkat : tingkat individu, antar-
individu dan komunitas (Piliang, 2012:147).
Pertama, tingkat individu. Cyberspace menciptakan
perubahan mendasar terhadap pemahaman kita tentang diri
(self) dan identitas (identity). Struktur cyberspace membuka
ruang yang lebar bagi setiap orang untuk menciptakan
secara “artifisial” konsep tentang diri dan identitas.
39
Kondisi demikian menjadikan konsep diri dan identitas di
dalamnya menjadi sebuah konsep yang tanpa makna. Artinya,
bila setiap orang dapat menciptakan berbagai identitas
dirinya secara tak berbatas, maka hakikat identitas itu
sendiri tidak ada lagi. Sebagai sebuah konsep (maupun
realitas), identitas masih ada bila ada perbedaan
(difference), yaitu prinsip “perbedaan” atau “pembedaan”,
yang membedakan seseorang dengan orang-orang lainnya.
Bila setiap orang dapat menjadi setiap orang lainnya
adinfinitum, maka kita menghadapi sebuah kondisi matinya
perbedaan (death of difference), yang berarti mati pula
identitas.
Kekacauan identitas akan mempengaruhi persepsi,
pikiran, personalitas dan gaya hidup setiap orang. Bila
setiap orang bisa menjadi siapapun, ini sama artinya
semua orang bisa menjadi beberapa orang yang berbeda pada
suatu ketika. Artinya, tidak ada lagi identitas. Yang ada
di dalam cyberspace adalah permainan identitas : identitas
baru, identitas palsu, identitas ganda, identitas jamak.
Inilah yang di dalam psikoanalisis disebut R.D. Laing
(dalam Piliang, 2012:147) sebagai diri terbelah (divided
self), yang di dalamnya setiap orang dapat “membelah
pribadi”nya menjadi pribadi-pribadi yang tak berhingga.
Kedua, tingkat interaksi antar individu. Hakikat cyberspace
sebagai dunia yang terbentuk oleh jaringan (web) dan
hubungan (connection)—bukan oleh materi—menjadikan40
kesalingterhubungan (interconnectedness) dan
kesalingbergantungan (interdependency) secara virtual
merupakan ciri dari dunia cyberspace.
Cyberspace adalah “dunia antara”, yaitu dunia bit-bit
informasi yang mampu menciptakan berbagai hubungan dan
relasi sosial yang bersifat virtual. Oleh karena
hubungan, relasi dan interaksi sosial di dalam cyberspace
bukanlah antar fisik di dalam sebuah wilayah atau
teritorial tertentu, maka ia menciptakan semacam
deteritorialisasi sosial (social deterritorialisation) , yaitu
interaksi sosial yang tidak dilakukan di dalam sebuah
teritorial yang nyata (dalam pengertian konvensional)
akan tetapi di dalam sebuah halusinasi teritorial
(territorial hallucination). Di dalam halusinasi teritorial
tersebut, orang boleh jadi lebih dekat dan akrab secara
sosial dengan “sesorang” di dalam cyberspace yang secara
teritorial hidup dalam jarak ribuan kilometer, ketimbang
tetangga dekatnya sendiri.
Relasi sosial jarak jauh ini mempunyai implikasi
yang luas terhadap berbagai hubungan sosial, termasuk
hubungan komunikasi sosial. Bentuk komunikasi sosial di
dalam cyberspace telah menciptakan sebuah situasi
komunikasi yang sangat di bentuk oleh peran citra di
dalamnya. Dalam kaitannya dengan “situasi komunikasi”
ini, Jurgen Habermas (dalam Piliang, 2012:148), di dalam
41
The Theory of Communicative Action, menjelaskan sebuah situasi
komunikasi ideal” (ideal communicative situation), berdasarkan
sarana, relasi sosial dan aktor-aktor yang terlibat di
dalamnya, yang dapat menghasilkan sebuah tindak
komunikatif yang rasional. Dari segi sarana, sarana
komunikasi ideal harus memungkinkan terciptanya sebuah
ruang publik yang terbuka, yang dapat diakses secara luas
dan memungkinkan partisipasi publik yang luas di
dalamnya. Dari segi relasi sosial ideal, di dalam ruang
publik tersebut tidak dibenarkan adanya tekanan,
pemaksaan dan dominasi kelompok masyarakat atas kelompok-
kelompok lainnya. Dari segi aktor, seorang aktor di dalam
sebuah relasi komunikasi harus berbicara dengan betul
(right) mengikuti norma yang ada, harus mengemukakan
pernyataan yang benar (true), dan harus berbicara dengan
jujur dan penuh kebenaran (truthfull).
Berdasarkan karakter medianya, cyberspace memang dapat
menjadi ruang ideal untuk sebuah komunikasi yang terbuka
dan “demokratis”, yaitu ruang yang setiap orang dapat
berperan di dalamnya, selama ia mempunyai akses, sarana
dan kompetensi di dalam bahasanya. Dari segi relasi
sosial, cyberspace dapat mengurangi berbagai bentuk
pemaksaan, tekanan, dan represi, meskipun ia tidak lepas
dari berbagai bentuk hegemoni. Mungkin yang paling
problematik di dalam cyberspace adalah dari segi aktor-
aktor yang berperan di dalamnya. Disebabkan karakter42
media cyberspace sebagai ruang image yang direkayasa secara
artifisial, maka ia adalah sebuah ruang, yang paling
terbuka terhadap berbagai bentuk penipuan, pemalsuan dan
simulasi realitas. Ketimbang menjadi ruang di mana orang
dapat berbicara dengan betul, jujur dan benar, cyberspace
sebaliknya menjadi sebuah ruang yang di dalamnya
direkayasa berbagai bentuk kepalsuan, kesemuan, dan
simulasi. Ketiga, pada tingkat komunitas. Cyberspace dapat
menciptakan satu model komunitas demokratik dan terbuka
yang disebut Howard Rheingold sebagai komunitas imaginer
(imaginary community). Ada perbedaan mendasar antara
komunitas imajiner ini dengan komunitas yang
konvensional. Di dalam komunitas konvensional, masyarakat
memiliki rasa kebersamaan menyangkut tempat—rumah, desa
atau kota—yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang
bersifat langsung dan tatap muka (face to face) di sebuah
tempat (place) yang dibatasi ruang-waktu. Di dalam
komunitas imajiner ini diperlukan “imajinasi” tentang
“tempat” tersebut, oleh karena “tempat” tersebut bukanlah
tempat yang nyata dalam pengertian konvensionalnya,
melainkan tempat imajiner yang berada di dalam bit-bit
komputer. Meskipun sebuah “tempat nyata”, seperti sebuah
negara-bangsa (nation-state) masih memerlukan imajinasi
anggota masyarakatnya tentang “bangsa yang
diimajinasikan” (imagining nation), tetapi negara-bangsa
yang diimajinasikan itu ada wujud konkritnya (wilayah,
43
teritorial, batas geografis). “Tempat yang
diimajinasikan” (imagining places) di dalam cyberspace,
sebaliknya tidak ada wujud konkrit atau fisiknya,
melainkan wujud yang terbentuk berupa citraan grafis di
dalam sistem komputer.
Disebabkan komunitas virtual dibangun bukan di dalam
teritorial yang konkrit, maka persoalan utama di dalamnya
adalah persoalan normatif, pengaturan dan kontrol. Sebuah
masyarakat mengharuskan adanya pemimpin (ruler), konvensi
sosial (adat, tabu, hukum, aturan main) dan adanya
lembaga hukum (judikatif) sebagai lembaga pengaturan. Di
dalam komunitas virtual cyberspace, pemimpin, aturan main
dan kontrol sosial tersebut bukanlah berbentuk lembaga
(institution), sehingga keberadaannya sangat lemah. Di
dalam cyberspace, setiap orang seakan-akan menjadi
“pemimpin”, “pengontrol” dan “penilai” dirinya sendiri,
yang menciptakan semacam demokrasi radikal, yang di
dalamnya segala tindakan sosial (social action) tidak ada
yang mengatur, mengontrol dan memberi penilaian. Di
dalamnya seakan-akan “apapun boleh” (anything goes).
c. Cyberspace dan imagologi
Dunia cyberspace telah menimbulkan persoalan besar
pada apa yang selama ini disebut “dunia representasi”
(representation). Representasi adalah satu model “penampakan
ontologis”, yaitu menampilkan “ada” dalam wujud44
representasinya. Representasi adalah “pelukisan kembali
realitas” yang tidak dapat “dihadirkan” (to present),
sehingga diperlukan “model penghadiran kembali realitas”
(to represent) lewat berbagai model bahasanya (verbal,
visual, gambar, citra). Dalam representasi, relasi antara
yang merepresentasikan dan yang direpresentasikan adalah
relasi relatif-simetris, seperti refleksi cermin (mirror
image), yaitu berdasarkan prinsip kesamaan, keserupaan
dan ikonisitas (iconicity). Representasi menjadikan realitas
sebagai rujukannya dan tidak dapat melepaskan dirinya
dari rujukan itu. Bila wujud representasi telah lepas
dari rujukannya, maka sesungguhnya tidak ada lagi
representasi (Piliang, 2012:148).
Dunia cyberspace adalah dunia yang di dalamnya model
(representasi) itu tidak lagi mempunyai relasi dengan
realitas. Ia bahkan terputus sama sekali dengan dunia
realitas, yang menciptakan sebuah relasi yang
bertentangan dengan representasi, yang disebut
“simulasi”. Dunia “simulasi” dalam konteks cyberspace,
adalah sebuah dunia yang di dalamnya setiap “ada” (beings)
dirubah wujudnya menjadi “ada citra” (being images), setiap
ontologi dirubah menjadi “ontologi citraan” (ontology of
image); setiap realitas dibuatkan substitusi-
substitusinya berupa “citra realitas” (image of reality);
setiap wujud fisik ditransformasikan ke dalam wujud
halusinasi. Cyberspace adalah sebuah migrasi besar-besaran45
dari dunia tubuh (fisik) ke dalam dunia citraan, sehingga
di dalamnya segala yang ada dalam dunia realitas (bahkan
yang belum ada sama sekali) menemukan eksistensinya dalam
wujud realitas artifisial.
Dunia cyberspace adalah sebuah dunia yang di dalamnya
setiap orang dikondisikan untuk menampilkan eksistensi
dirinya lewat “ontologi citra”, yang diandaikan sebagai
lukisan dari citra “diri sejati” (true self), dalam rangka
mendapatkan “makna eksistensial” yang otentik, padahal
palsu. Dalam hal inilah, “ada” di dalam cyberspace menjadi
sebuah model keber”ada”an yang palsu (pseudoexsistence),
yaitu ada dalam kategori “ontologi citra”.
Cyberspace adalah upaya manusia melepaskan manusia
dari penjara tubuh, untuk kemudian memerangkap mereka di
dalam penjara yang lain, yaitu penjara citraan. Para
visioner cyberspace melihat begitu terpenjaranya manusia di
dalam penjara keterbatasan tubuh fisik, sehingga tidak
memungkinkannya untuk melakukan banyak hal : terbang,
hidup di dalam air, berubah wujud, hidup di dua tempat
sekaligus. Obsesi melawan penjara tubuh inilah yang
menjadi impian utama cyberspace, yaitu dengan mengembangkan
berbagai bentuk-bentuk kehidupan artifisial, sehingga di
dalamnya tubuh tidak lagi dibatasi oleh keterbatasan
arsitektural dan alam. Di dalam cyberspace orang bisa
“terbang”, “berubah wujud”, “hidup di dalam air”, “hidup
46
di dalam berbagai ruang yang berbeda dalam waktu yang
sama”, meskipun semuanya dalam wujud citraan.
Segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan di dalam
dunia nyata (dunia fisik) kini dapat dilakukan di dalam
dunia simulasi cyberspace. Cyberspace menjadikan orang
terbebas (release) dari berbagai hambatan dunia nyata,
termasuk berbagai hambatan psiko-sosial yang dihadapi
manusia. Salah satu hambatan psiko-sosial itu adalah
hambatan yang diciptakan oleh masyarakat industri, yang
menggiring orang ke dalam cara-cara kehidupan industrial
dan rasional, akan tetapi menemukan di dalamnya kehampaan
psiko-sosial (psychosocial vacuum).
Sebagaimana dikatakan oleh Margaret Wertheim (dalam
Piliang, 2012:150), cyberspace seperti kegiatan bermain
game online atau membuka jejaring sosial merupakan tempat
pelepasan diri dari beban kerja, tekanan jiwa, tekanan
politik, tekanan keluarga masyarakat industri yang sangat
menekan. Cyberspace menjelma menjadi sebuah tempat
penjelajahan psikososial, yaitu penjelajahan untuk
menemukan diri (self), peran, identitas, dan eksistensi.
Akan tetapi, disebabkan karakter cyberspace itu sendiri
yang sangat menggantungkan dirinya pada ontologi citra—
yang di dalamnya terbentang luas berbagai kemungkinan
rekayasa dan manipulasi citra—maka yang ditemukan setiap
orang di dalamnya, bukanlah konsep “diri” yang utuh atau
47
esensial, melainkan diri yang jamak (multiple self) yang
dapat berubah-ubah secara cepat sesuai dengan tuntutan
komunitas virtual di dalamnya.
Cyberspace adalah sebuah ruang yang di dalamnya setiap
orang dapat bermain di dalam berbagai bentuk fantasi
kelompok (group fantasy) atau drama kolektif (collective drama)
yang bersifat virtual. Cyberspace secara cepat dapat
membentuk komunitas-komunitas global lewat berbagai
bentuk permainan, diskusi, tontonan, dan hiburan, yang di
dalamnya setiap orang dapat merealisasikan segala
fantasinya, termasuk fantasi-fantasi liar tentang
kekerasan, seks dan kebebasan.
Ragnarok Online (RO) adalah contoh game online
cyberspace yang sedang menjamur di Indonesia, yang di
dalamnya berbagai fantasi manusia dapat disalurkan,
sehingga dapat menghanyutkan ribuan orang ke dalam ruang-
ruang mayanya.
d. Cyberspace dan otentisitas
Dunia otentik adalah dunia yang menghasilkan
pengalaman otentik dan “diri otentik”, yaitu diri yang
tidak bergantung pada eksistensi lain, yang dibedakan
“diri umum”, yaitu model diri yang mengikuti
kecenderungan umum, yang dicirikan oleh keseragaman,
kesamaan, dan kepublikan, yang oleh Heidegger disebut
48
sebagai “dunia mereka” (the they). Otentisitas, dalam hal
ini dipertentangkan dengan “publisitas” (publicity). Akan
tetapi, konsep “otentisitas” itu dapat pula dengan konsep
“artifisialitas” (Piliang, 2012:150)
Diri otentik adalah diri yang “tidak umum‟, tetapi
bisa juga sekaligus yang “tidak artifisial”, karena
artifisialitas mengkonotasikan “ketidakaslian”.
“Artifisial” biasanya dipertentangkan dengan “alam”. Para
visioner cyberspace membayangkan cyberspace secara teoritis
sebagai sebuah ruang yang di dalamnya setiap orang dapat
menemukan “diri otentik”, oleh karena di dalamnya setiap
orang “dapat menavigasi diri mereka sendiri”, tanpa ada
seorangpun yang dapat mengontrol dan mengendalikan
mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya, cyberspace justeru
tidak menawarkan sebuah dunia otentik itu, oleh karena di
dalamnya ia mengundang setiap orang untuk menjadi diri
umum dan diri artifisial (artificial self) sekaligus—sebuah
konsep diri yang sangat dibentuk oleh manipulasi citra
(image) di dalamnya. Inilah semacam “kontradiksi budaya
cyberspace” (cultural contradiction of cyberspace). Di dalam
cyberspace, konsep diri kini diambilalih oleh konsep citra
diri (self image), yaitu diri yang ditampilkan dalam
wujud ontologi citra. Mediasi teknologis memungkinkan
setiap orang untuk menciptakan citra diri mereka sendiri.
Cyberspace menawarkan berbagai konsep diri (mutiple self),
49
yang menciptakan berbagai kemungkinan peran, identitas
dan keyakinan (multiple identity).
Dunia cyberspace yang dibangun oleh ontologi citra
adalah dunia yang “tak otentik”, oleh karena ia adalah
dunia “simulakrum”, yang di dalamnya setiap diri (self)
terserap ke dalam apa yang disebut Heidegger “dunia
mereka”, sebuah dunia umum yang kini dicetak dan
dikendalikan sepenuhnya oleh citra dan citra harian
(everyday image). Dunia simulakrum cyberspace yang dikuasai
oleh citra tidak menyisakan lagi ruang di dalamnya bagi
pencarian “diri otentik”, disebabkan membiak dan
menyebar-luasnya model-model simulakrum ke dalam setiap
ruang-ruang mikro cyberspace, sehingga ruang-ruangnya
seakan-akan dipenuhi oleh jutaan citra setiap harinya,
yang saling bersaing mendapatkan perhatian.
Citra-citra di dalam cyberspace saling berlomba
mendapatkan perhatian dalam kecepatan tinggi, sehingga
kesadaran dan pengalaman manusia di dalamnya hanyut di
dalam arus kecepatan ini, sehingga tidak menyisakan
tempat di dalamnya bagi perenungan eksistensial.
Keotentikan yang diimajinasikan oleh para visioner
cyberspace adalah keotentikan yang dikembangkan oleh para
penganjur keontentikan yang radikal, seperti Nietzsche,
Derrida, Deleuze dan Guattari (Piliang, 2012:151). Bagi
mereka, keontentikan adalah cara untuk menolak segala
50
bentuk otoritas dan kekuasaan, dalam rangka menciptakan
sebuah ruang, yang di dalamnya setiap orang dapat
“mengekspresikan dirinya secara bebas”, tanpa bergantung
pada otoritas kekuasaan tertentu di luar dirinya (negara,
agama, keluarga). melepaskan segala dorongan hasrat dan
mewujudkan segala kehendak manusia di dunia ini. Ketika
otoritas keluarga, agama dan sosial tidak lagi ada, maka
setiap orang dapat melepaskan segala dorongan hasratnya,
yang selama ini ditolak oleh keluarga, masyarakat dan
agama, karena dianggap bersifat abnormal, menyimpang, a-
moral dan a-sosial.
Tidak seperti yang dibayangkan oleh para visionaris
cyberspace, struktur dunia kehidupan di dalam cyberspace
(cyber-lifeworld) tidak berbeda dengan struktur dunia
kehidupan harian manusia, yang di dalamnya justeru
berkembang luas “dunia umum”, yang menciptakan berbagai
bentuk budaya publik (public cyber-culture) dan budaya populer
(popular cyber-culture). Di dalamnya—seperti di dunia
kehidupan harian—terbentuk relasi-relasi bintang dan
fans, produser dan konsumer, elit dan massa, penguasa dan
yang dikuasai, yang di dalamnya perilaku meniru,
mengimitasi, mengkopi menjadi perilaku yang biasa,
sebagaimana di dalam fenomena budaya populer pada
umumnya. Cyberspace sama sekali bukanlah ruang bagi
pembentukan keotentikan, oleh karena di dalamnya setiap
diri “dihisap” oleh lubang hitam dunia citra dan tontonan51
massa kapitalisme itu sendiri, yang sangat berjiwa
totalitarian.
e. Simulasi sosial dan cybersociety
Di dalam era artifisial dewasa ini, berbagai ruang
sosial yang ada di dunia nyata, kini dapat dicarikan
substitusinya di dalam dunia informasi digital, dalam
wujudnya yang artifisial, yaitu wujud simulasi sosial
(social simulation). Cyberspace adalah sebuah ruang utama yang
di dalamnya berbagai simulasi sosial menemukan tempat
hidupnya. Perkembangan ruang-ruang simulasi sosial di
dalam cyberspace telah mempengaruhi kehidupan sosial di
luar ruang tersebut pada hampir semua tingkatnya.
Setidak-tidaknya terdapat tiga tingkat pengaruh tersebut:
tingkat individual, tingkat antar-individual dan tingkat
masyarakat.
Pertama, pada tingkat individual, cyberspace telah
menciptakan perubahan mendasar terhadap pemahaman kita
tentang “identitas”. Sistem komunikasi sosial yang
dijembatani oleh komputer (computer mediated communication)
telah melenyapkan batas-batas identitas itu sendiri di
dalamnya. Di dalam ruang-ruang sosial cyberspace setiap
orang dapat memainkan berbagai peran sosial yang berbeda-
beda, artinya menjadi beberapa orang yang berbeda
identitasnya pada waktu yang bersamaan. Yang tercipta
adalah semacam kekacauan identitas, yang akan52
mempengaruhi persepsi, pikiran, personalitas dan gaya
hidup setiap orang. Bila setiap orang bisa memakai baju
identitas apapun, artinya, tidak ada lagi identitas.
Identitas hanya dimungkinkan, bila ada sesuatu (bentuk,
nilai, gaya, ideologi, makna) yang dipakai secara
konsisten, sebab konsistensi merupakan ciri utama dari
identitas.
Cyberspace—dan komunitas virtual yang terbentuk di
dalamnya—memungkinkan berlangsungnya “permainan
identitas” di dalamnya: identitas baru, identitas palsu,
identitas ganda, yang semuanya merupakan bagian dari
identitas budaya cyberspace. Di dalam psikoanalisis,
situasi pergantian identitas tanpa batas seperti ini pada
seorang individu, disebut oleh Lacan sebagai skizofrenia.
Bahkan, setiap individu tidak saja dapat “membelah
pribadi”nya menjadi pribadi ganda, akan tetapi juga
pribadi-pribadi yang terbelah menjadi keping-keping yang
jamak (multiple self).
Dunia komunikasi virtual di dalam cyberspace pada
tingkat individu dapat pula menciptakan semacam
ketergantungan, atau semacam “candu cyber” (cyber-
addiction), khususnya dalam bentuk “kecanduan komunikasi”
(communication addiction). Kecanduan ini telah menggiring
orang untuk duduk berjam-jam di depan komputer, bahkan
ada yang sampai tujuh puluh jam per minggu menghabiskan
waktunya di dunia maya.53
Kedua, pada tingkat antar-individual, perkembangan
komunitas virtual di dalam cyberspace telah menciptakan
relasi-relasi sosial yang bersifat virtual di ruang-ruang
virtual : virtual shopping, virtual game, virtual conference, virtual sex
dan virtual mosque. Relasi-relasi sosial-virtual tersebut
telah menggiring ke arah semacam “deteritorialisasi
social”, dalam pengertian, bahwa berbagai interaksi
sosial kini tidak memerlukan lagi ruang dan teritorial
yang nyata (dalam pengertian konvensional), melainkan
“halusinasi territorial”. Di dalam halusinasi teritorial
tersebut, orang boleh jadi lebih dekat secara sosial
dengan seseorang yang jauh secara teritorial, ketimbang
seseorang yang dekat secara teritorial, akan tetapi jauh
secara sosial.
Ketiga, pada tingkat komunitas, cyberspace diasumsikan
dapat menciptakan satu model komunitas demokratik dan
terbuka yang disebut Rheingold “komunitas imaginer”
(imaginary community). Di dalam komunitas konvensional,
anggota masyarakat memiliki kebersamaan sosial dan
solidaritas sosial menyangkut sebuah “tempat” (desa,
kampung, atau kota) yang di dalamnya berlangsung
interaksi sosial face to face. Di dalam komunitas virtual
diperlukan “imaginasi kolektif'” tentang “tempat”
tersebut, yang tidak ada di dalam sebuah ruang nyata,
melainkan sebuah tempat imajiner yang berada di dalam
“ruang” bit-bit komputer.54
Komunitas virtual yang terbentuk di dalam cyberspace,
bentuk, struktur dan sistemnya tidak sama dengan
komunitas konvensional di dunia nyata. Bila komunitas
konvensional pada umumnya memiliki struktur kepemimpinan
(rulling structure); struktur normatif (normative structure)
seperti adat, tabu, hukum, rule; lembaga normatif
(normative institution), seperti pengadilan, kehakiman, yang
semuanya merupakan mekanisme kontrol sosial; di dalam
komunitas virtual pemimpin, norma, dan institusi kontrol
tersebut nyaris tidak ada. Di dalamnya, setiap orang
seakan menjadi “pemimpin”, “pengontrol” dan “penilai”
dirinya sendiri. Bila cyberspace seringkali dikata kan
sebagai sebuah “ruang alternative” tempat berlangsungnya
demokratisasi, akan tetapi, pengertian “demokrasi” di
dalam cyberspace tidak sama dengan yang di dunia nyata. Di
dalam cyberspace dan komunitas virtual, demokrasi dan
masyarakat madani berkembang ke dalam wujudnya yang
paling ekstrim, yaitu “demokrasi radikal” atau
“masyarakat madani radikal”, yang di dalamnya ekspresi,
ekspresi, hasrat, keinginan, tuntutan, gagasan, ide,
protes yang datang dari masyarakat sipil tidak ada yang
mengatur, mengontrol dan memberi penilaian. Demokrasi di
dalam cyberspace berkembang ke arah hiper-demokrasi (hyper-
democracy), dalam pengertian, bahwa konsep-konsep kunci
demokrasi seperti kebebasan (liberation), hak azasi (right)
dan kekuasaan rakyat (demos), berkembang dalam bentuknya
55
yang ekstrim, yang tanpa batas dan kontrol. Singkatnya,
di dalam cyberspace “apapun boleh” (anything goes).
Dalam dunia kehidupan sosial dan politik pada
umumnya, terutama dalam konteks masyarakat demokratis,
“ruang publik” (public sphere) mempunyai peran yang sangat
sentral, yang melaluinya komunikasi sosial dan politik
dapat berlangsung. “Ruang publik” adalah ruang konkrit
sekaligus abstrak, yang di dalamnya “opini publik”
dibentuk. Ruang publik terbentuk ketika dalam satu
masyarakat berkembang minat bersama (common interest), dan
mengkomunikasikan serta mensosialisasikan minat bersama
tersebut, tanpa ada paksaan apapun. Cyberspace sering pula
dilihat sebagai sebuah “ruang publik alternatif”, yang di
dalamnya berbagai komunikasi sosial dan politik dapat
berlangsung. Ia dilihat sebagai sebuah jaringan
komunikasi yang bebas, informal dan personal, tanpa ada
paksaan dan kekerasan di dalamnya. Habermas melihat ada
hubungan antara “jaringan komunikasi tanpa hambatan”
dengan landasan masyarakat demokratis. tanpa ada paksaan
dan kekerasan. Pengaturan sosial hanya dimungkinkan bila
ada komunikasi di antara berbagai pihak di dalam ruang
publik. Untuk itu diperlukan jaminan akses yang terbuka
terhadapnya, partisipasi publik yang luas dalam berbagai
debat, penciptaan opini publik yang melibatkan masyarakat
luas di dalam debat rasional, kebebasan mengeluarkan
pendapat. Di dalam “ruang publik virtual”, opini publik56
dibentuk seakan-akan tanpa norma, realitas dapat
dikonstruksi atau dimanipulasi, kejahatan dapat dilakukan
secara tersembunyi, sehingga meskipun tampaknya tidak ada
pemaksaan (coersion) dan kekerasan (violence) di dalamnya,
sesungguhnya terdapat berbagai bentuk kekerasan
(pencurian, perusakan, pemalsuan, pembajakan situs,
hingga kecanduan game online) dan pemaksaan dalam bentuknya
yang virtual. Impian cyberspace sebagai ruang publik ideal
tampaknya masih jauh dari kenyataan.
2.1.5.2 Konformitas
Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial
ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka
agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Tekanan untuk
melakukan konformitas berasal dari kenyataan bahwa di
beberapa konteks terdapat aturan-aturan baik yang
eksplisit maupun tidak terucap. Aturan-aturan ini
mengindikasikan bagaimana individu seharusnya dan
sebaiknya bertingkah laku (Hurlock dalam Sukmawati).
Aturan-aturan yang mengatur bagaimana individu seharusnya
dan sebaiknya berperilaku disebut dengan norma sosial
(social norms). Aturan-aturan ini juga kerap kali memberikan
efek yang kuat pada tingkah laku individu. Pada dasarnya
ada beberapa norma sosial. Namun demikian, ada satu norma
sosial yang berkaitan erat dengan konformitas, yaitu
norma injungtif (Wikipedia, 2014).
57
Norma ini adalah suatu jenis norma yang memberi tahu
kita mengenai apa yang seharusnya kita lakukan pada
situasi-situasi tertentu. Beberapa contoh dari norma
sosial ini adalah seperti peraturan untuk tidak bersuara
berisik saat menonton bioskop, dan perilaku-perilaku
tertentu di jalan raya. Norma lain yang tidak tertulis
antara lain adalah “jangan berdiri terlalu dekat dengan
orang asing”, dan sebagainya. Tanpa memedulikan apakah
norma sosial itu eksplisit atau implisit namun satu
kenyataan tampak dengan jelas, yaitu sebagian besar orang
mematuhi norma-norma tersebut hampir setiap saat.
Awalnya, kecenderungan yang kuat terhadap konformitas ini
di mana kita mengikuti harapan masyarakat atau kelompok
mengenai bagaimana seharusnya kita bertindak di berbagai
situasi membuat kita dengan secara sengaja menghindari
kekacauan sosial.
a. Konformitas teman dan kelompok sosial gamer
Teman sebaya adalah sekelompok orang yang memiliki
usia yang sama dengan kita, dan memiliki kelompok sosial
yang sama pula, misalnya teman sekolah atau teman kuliah
(Mu’tadin dalam Hartati, 2013). Teman sebaya juga dapat
diartikan sebagai kelompok orang yang mempunyai latar
belakang, usia, pendidikan, dan status sosial yang sama,
dan mereka biasanya dapat mempengaruhi perilaku dan
keyakinan masing-masing anggotanya. Dalam kelompok teman
58
sebaya biasanya mereka saling bercerita tentang
kesenangan dan latar belakang anggotanya. Asmani (dalam
Hartati, 2013) menambahkan selain tingkat usia yang sama,
teman sebaya juga memiliki tingkat kedewasaan yang sama.
Memasuki masa remaja, individu akan mulai belajar tentang
hubungan timbal balik yang akan di dapatkan ketika mereka
melakukan interaksi dengan orang lain maupun dengan
temannya sendiri. Selain itu mereka juga belajar untuk
mengobservasi dengan teliti mengenai minat dan pandangan
temannya, ini dilakukan agar remaja mudah ketika ingin
menyatu atau beradaptasi dengan temannya (Piaget dan
Sullivan dalam Hartati, 2013).
Lingkungan pergaulan remaja tentu berperan dalam
pembentukan sikap kebiasan perilaku remaja. Lingkungan
tersebut seperti lingkungan rumah, sekolah, organisasi
dan kelompok-kelompok tertentu. Keikutsertaan remaja pada
lingkungan yang lebih luas ini tidak terlepas dari tugas
perkembangan remaja yang berada pada tahap membangun
relasi dengan orang lain. Hal ini menjadi salah satu
penyebab kedekatan remaja dengan temannya lebih akrab
dibandingkan dengan orang tua maupun anggota keluarga
lain. Tentu waktu yang dihabiskan bersama teman
memungkinkan remaja lebih terbuka antar sesamanya, teman
menjadi tempat kepercayaan untuk saling berbagi dan
kecenderungan untuk sama. Remaja juga cenderung untuk
mencoba sesuatu yang baru bersama dengan temannya, dimana59
dengan cara mencoba-coba bersama dengan teman akan terasa
ramai, mirip, tidak kesepian maupun berbeda. Bagi remaja,
waktu dengan teman merupakan bagian penting bagi remaja
dalam kesehariannya. Teman dan kelompok sosial gamer
merupakan tempat menghabiskan waktu, berbicara, berbagi
kesenangan dan kebebasan. Teman sebaya dapat menjadi
kelompok yang memberikan pengaruh negatif terhadap
remaja. Mereka mendorong ke arah kualitas yang kadangkala
tidak diharapkan seperti bermain game online secara
berlebihan atau kenakalan remaja lainnya, terutama pada
remaja yang kurang mendapat pengarahan dari orang tua
(Fadiki dalam Samri, 2013).
Banyaknya waktu yang dihabiskan remaja bersama
dengan teman dan kelompoknya serta kondisi yang sering
mencoba hal baru perlu mendapat perhatian. Ada
kemungkinan dalam komunitas remaja terdapat perilaku dan
kebiasaan yang menyimpang dari norma yang ada. Hasil
penelitian di Amerika (Fadiki dalam Samri, 2013) misalnya,
menyebutkan bahwa remaja dalam komunitasnya atau sesama
remaja yang lingkungannya sering menggunakan kokain
cenderung untuk melakukan hal serupa. Peran orang tua dan
lingkungan dalam hal ini akan memberikan kontribusi
terhadap perkembangan perilaku remaja dalam
bersosialisasi. Segala bentuk yang di lihat dan di alami
pada lingkungan terutama bila perilaku tersebut mendapat
respon yang positif atau pun tidak mendapat hukuman, maka60
perilaku tersebut cenderung menguat. Remaja yang berada
dalam lingkungan pergaulan bebas, setidaknya mendapat
pemahaman tentang kondisi sekitar, disinilah peran orang
tua dan masyarakat untuk memberikan masukan dalam
membangun sikap remaja.
Menurut Hurlock (dalam Samri, 2013:12), setidaknya
ada tiga derajat konformitas teman sebaya, yaitu : Konformitas yang tepat, yakni dapat menerima dan
mengikuti standar kelompok tanpa kehilangan identitaspribadinya. Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkunganmenjadi penting pada tahap ini, sehingga memberikanperasaan aman dan diakui sebagai bagian dari kelompoktersebut.
Konformitas rendah, yakni remaja tidak mampu menyesuaikandiri dengan baik berdasarkan standar kelompok, tahapanini seringkali mengakibatkan penolakan sosial darikelompok.
Konformitas tinggi, yakni ketika remaja secara penuhmengikuti dan taat kepada standar kelompok sehinggamengakibatkan hilangnya identitas pribadi sebagaiindividu, biasanya menjadi ketakutan tersendiri ketikaanggota kelompok tersebut bertingkah laku salah dan tidaksesuai dengan harapan kelompok, hingga ia mengalamiketergantungan pada kelompoknya.
Myers (dalam Samri, 2013:13) mendefinisikan konformitas
pada lima aspek, yakni: Pengetahuan; yakni informasi yang dimiliki individu
mengenai kelompoknya, mencakup anggota, aktifitas, tujuan, serta pemahaman terhadap aturan kelompok.
Pendapat; adalah suatu kepercayaan individu terhadap kelompok secara menyeluruh meskipun masih bersifat tentatif.
Keyakinan; ialah anggapan individu terhadap kelompok, bahwa kelompoknya dianggap benar sehingga timbul keta’atan terhadap kelompoknya.
61
Ketertarikan; adalah perasaan senang seorang individu terhadap kelompoknya.
Konatif; ialah kecenderungan individu untuk berinteraksi,beradaptasi dan bekerjasama dengan anggota kelompok.
b. Konformitas media
Sumber : https://www.facebook.com/gan.lawliet
Seringkali ketika sedang online pada jejaring sosial,
muncul iklan terkait game online dari berbagai genre. Hal
ini kerap membuat web gamer biasa menjadi tertarik
memainkan game online dengan konten yang lebih variatif dan
lebih menarik. Rating game online juga merupakan faktor
penting dalam konformitas media, rating merupakan
prestise tersendiri bagi gamer.
2.1.5.3 Disfungsi keluarga
62
Keluarga merupakan agen sosialisasi primer bagi
setiap orang, disanalah tempat seseorang membangun dasar
gagasan untuk menjalankan kehidupannya. Situasi dan
kondisi yang dialami oleh seseorang sejak lahir, masa
kanak-kanak hingga masa dewasa baik dalam lingkungan
keluarga maupun lingkungan sekitarnya akan memberikan
pengaruh yang berbeda pada perkembangan masing-masing
orang (David. O. Sears dalam Yurita, 2014:10). Menurut
Engel, Blackwell dan Miniard (dalam Yurita, 2014:4)
keluarga merupakan tempat nilai-nilai kelas sosial serta
pola-pola tingkah laku yang diwariskan kepada generasi
selanjutnya. Dalam keluarga umumnya terjadi proses
sosialisasi yang memungkinkan seorang anak mendapatkan
kemampuan, pengetahuan dan sikap yang diperlukannya untuk
berfungsi sebagai anggota masyarakat.
Kurangnya komunikasi antara anggota keluarga dapat
menjadi penyebab utama dari timbulnya berbagai masalah
antara orangtua dan anaknya. Hasil survei menunjukkan
bahwa 94,5 persen gamer membenci orang tua mereka dan
52,3 persen merasa kehidupan keluarga kurang kehangatan
dan pengertian. Remaja pecandu game menemukan teman yang
dapat mengerti mereka hanya dari dunia maya, mereka
seakan menemukan “keluarga baru” di dunia maya dan hal
ini lah yang menjadi salah satu penyebab mereka mengalami
kecanduan game online (Praditasari, 2009:20). Perilaku
kecanduan game online merupakan salah satu manifestasi dari63
kurang efektifnya komunikasi dalam keluarga. Hal ini
dapat berakar pada kurangnya dialog dalam masa kanak-
kanak dan masa berikutnya, karena orangtua telah sibuk
dengan berbagai aktivitas, padahal keluarga merupakan
lingkungan yang paling utama bagi seorang anak (Afriani
dalam Yurita, 2014).
a. Pudarnya fungsi afeksi
Seperti halnya lembaga sosial lainnya, keluarga juga
memiliki fungsi-fungsi terkait pemenuhan kebutuhan
anggota-anggotanya, salah satu fungsi keluarga yang
paling vital ialah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ialah
cara lembaga keluarga untuk memenuhi kebutuhan anggotanya
dalam aspek perasaan dan kasih sayang sehingga muncul
rasa nyaman pada diri anggota keluarga terutama untuk
sang anak. Keluarga berfungsi memberikan cinta kasih pada
anak. Anak yang kekurangan kasih sayang akan tumbuh
secara menyimpang, kurang normal, atau mengalami suatu
gangguan baik kesehatan fisik maupun psikis dalam
masyarakat (Rizky, 2014).
Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat modern
tidak dapat kita pungkiri juga turut berkontribusi pada
perubahan pola interaksi pada lembaga keluarga. Hal ini
tentu erat kaitannya dengan penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi pada remaja awal (12-16 tahun) dan remaja
akhir (17-25 tahun) (Klasifikasi usia menurut Departemen64
Kesehatan). Mahasiswa rata-rata berada pada usia remaja
akhir, usia ini rentan terhadap delinkuensi, kecanduan
game termasuk didalamnya. Perubahan pola interaksi pada
lembaga keluarga turut bertanggungjawab terhadap pudarnya
fungsi afeksi yang semestinya dapat dipenuhi, hal ini
membuat para gamer yang notabene masih membutuhkan kasih
sayang atau perasaan yang sebanding, mereka berusaha
mencarinya pada kelompok lain, dan mereka menemukan
perasaan yang sebanding pada komunitas game dan kepuasan
memainkan game online.
b. Orang tua yang sibuk bekerja
Penyebab kasus di atas dominan disebabkan oleh
meningkatnya kebutuhan hidup pada masyarakat modern, hal
yang demikian seringkali memaksa orang tua untuk
meningkatkan jam kerja di luar rumah demi ketercapaian
target pemenuhan kebutuhan keluarga. Kondisi ini kerap
memunculkan masalah-masalah internal keluarga, seperti
kesalahpahaman, sikap individual, dan masalah-masalah
lain akibat kurangnya waktu untuk berkomunikasi.
Munculnya masalah tersebut tidak heran jika membuat anak
kehilangan kenyamanan di rumah mereka sendiri, hal inilah
yang membuat mereka berusaha mencari kenyamanan di tempat
lain dengan aktifitas yang membuat mereka bisa melupakan
permasalahan di rumah.
2.1.5.4 Perkembangan teknologi game online65
Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kecanduan game
online erat kaitannya dengan perkembangan teknologi game
online dari masa ke masa. Penilaian game online oleh gamer
senantiasa di ukur tidak hanya melalui jalan cerita game
namun juga kemudahan dalam bermain dan kualitas grafis
atau visual game serta kualitas suara yang bagus.
Berbicara game online tentu tak jauh dengan berbicara
tentang pembaharuan game yang terjadi setiap periode
tertentu, modifikasi-modifikasi kreatif semakin membuat
gamer online tidak mampu meninggalkan setiap sesi cerita
dalam game, developer game online sengaja melakukan
pembaharuan berkala agar game tidak membosankan dan
semakin seru untuk menyita waktu gamer agar duduk di
depan monitor dan bergelut dengan keyboard dan mouse. Game
online sangat sulit untuk tamat, dan gamer rata-rata
memainkan lebih dari satu game online, jika berfikir
deterministik, maka faktor kecanduan game online kebanyakan
berasal dari perkembangan teknologi game online tersebut.
2.1.6 Kecanduan game online
Ketika kondisi ketika tubuh atau pikiran manusia
dengan parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu,
itulah kecanduan. Seseorang bisa disebut pecandu bila ia
memiliki ketergantungan fisik hingga psikologis terhadap
zat psikoaktif dan atau aktifitas tertentu. Jika bicara
zat, maka zat ini akan melintasi saluran darah ke
66
otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di
otak secara sementara hingga pikiran menstimulir tubuh
supaya dapat memenuhi kebutuhan akan zat serupa
(Wikipedia, 2014). Lalu jika bicara aktifitas, maka
keterlibatan terus-menerus dengan sebuah aktifitas
adiktif mesti dilakukan meskipun mengakibatkan
konsekuensi negatif. Ketika kecanduan sesuatu, seseorang
bisa sakit bahkan kehilangan nyawanya jika mereka tidak
mendapatkan atau melakukan hal yang adiktif itu. Dewasa
ini, para pakar psikologi memaksudkan kecanduan sebagai
ketergantungan psikologis yang abnormal pada beberapa hal
seperti judi, makanan, obat, komputer, spiritual, melukai
diri, berbelanja, dan sejenisnya. Dalam kamus kesehatan
(http://kamuskesehatan.com/), kecanduan dapat diartikan
sebagai kebutuhan yang kompulsif untuk menggunakan suatu
zat atau aktivitas pembentuk kebiasaan, atau dorongan tak
tertahankan untuk terlibat dalam perilaku tertentu.
Ada yang aneh ketika penulis searching literatur di
internet mengenai dampak negatif dari kecanduan game
online, karena kebanyakan yang muncul ialah penanganan
kesehatan psikologis atau konseling terhadap anak-anak,
hal tersebut jelas berbeda dengan kasus yang terjadi di
lapangan, fakta bicara lain, saat ini rata-rata gamer
berada pada usia remaja hingga usia dewasa. Arthur T.
Hovart (dalam Suveraniam, 2011:4) menyatakan bahwa
kecanduan adalah “an activity or substance we repeatedly crave to67
experience, and for which we are willing to pay a price (or negative
consequence)”, maksudnya ialah suatu aktivitas atau
substansi yang dilakukan berulang-ulang dan dapat
menimbulkan dampak negatif. Hovart juga menjelaskan bahwa
contoh kecanduan bisa bermacam-macam, bisa ditimbulkan
akibat zat atau aktivitas tertentu seperti yang
dijelaskan sebelumnya. Salah satu perilaku yang termasuk
di dalamnya ialah ketergantungan pada game (Keepers dalam
Suveraniam, 2011:4). Menurut Lance Dodes dalam bukunya
yang berjudul “the heart of addiction” (Yee dalam Suveraniam,
2011:4), ada dua jenis kecanduan, yaitu adiksi fisikal
seperti kecanduan terhadap alkohol atau kokaine, dan
adiksi non-fisikal seperti kecanduan terhadap game online.
Kecanduan bermain game secara berlebihan dikenal dengan
istilah game addiction (Grant, J.E. & Kim, S. W dalam
Suveraniam, 2011:5). Artinya seseorang seakan tidak ada
hal yang ingin dikerjakan selain bermain game, dan
seolah-olah game ini adalah hidupnya. Hal semacam ini
sangat riskan bagi perkembangan seseorang tersebut,
apalagi yang perjalanan hidupnya masih panjang seperti
mahasiswa.
Menurut Cromie (dalam Suveraniam, 2011:5)
karakteristik kecanduan cenderung progresif dan seperti
siklus. Menurut Suler (dalam Soebastian, 2010) aspek-
aspek yang nampak ketika seseorang mengalami kecanduan
permainan online adalah:68
Adanya perubahan gaya hidup yang drastis untukmenghabiskan lebih banyak waktu melakukan permainan online;
Mengalami penurunan aktivitas fisik dan mengabaikankesehatan;
Menghindari aktivitas kehidupan yang penting dalam rangkauntuk menghabiskan waktu melakukan permainan online;
Kurang tidur atau perubahan pola tidur untuk menghabiskanwaktu melakukan permainan online;
Penurunan proses sosialisasi, mengabaikan keluarga danteman;
Menolak menghabiskan waktu selain untuk melakukanpermainan online;
Adanya hasrat untuk lebih banyak waktu melakukanpermainan online;
Mengabaikan kewajiban pekerjaan dan pribadi.Sumber : Lihat Widyastuti, 2012. Hal-26
Lihat Soebastian, 2010. Hal-102Lihat Pratiwi. Hal-8
2.1.7 Dampak kecanduan game online
69
Menjadi seorang gamer pecandu bukanlah tanpa
konsekuensi yang berat, banyak hal yang dikorbankan
selagi gamer masih mengalami adiksi game online. Hasil
wawancara (September, 2014) peneliti pada salah seorang
gamer pecandu beberapa waktu lalu mengindikasikan bahwa
hampir semua aspek kehidupan gamer pecandu teralihkan
oleh permainan game online yang ia mainkan. Secara sosial.
Hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena
waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Pergaulan
hanya di game, sehingga membuat para pecandu game jadi
terisolir dari teman-teman dan lingkungan pergaulan
nyata. Keterampilan sosial berkurang, sehingga semakin
merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Perilaku jadi
kasar dan agresif karena terpengaruh oleh apa yang mereka
lihat dan mainkan di game (Efendi, 2014:7).
Suler dan Yaoung (dalam Modul Kecanduan PDE, 1996)
menyatakan bahwa beberapa orang pecandu game online
mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan harus berhenti
menggunakan internet, sebab di sana tidak berbeda jauh
dengan dunia nyata secara interaksi, adanya aspek sosial
bagi hubungan secara interpersonal dengan orang lain,
yang dirasa oleh pecandu sedemikian menstimulasi dan
menguntungkan (rewarding and reinformcement) membuat para
pecandu game online lupa bahwa mereka tidak dalam kondisi
yang sebenarnya.
70
Pada tataran individu, orang yang memainkan game
online akan mengalami realitas di luar apa yang
dijalaninya sehari-hari. Pada titik-titik tertentu,
orang-orang yang mengakses game online menjadi tidak peduli
dengan tatanan moral, sistem nilai dan norma yang telah
disepakati dalam masyarakat, intinya tidak lagi peduli
pada aturan sosial yang ada, belum lagi sikap
individualisme yang makin meninggi ditunjang dengan sifat
internet sebagai komunikasi interaktif yang tidak
mengharuskan komunikasi pertemuan fisik. Game online
menjadi salah satu penyebab utama timbulnya sikap dan
perilaku kompulsif, agresif, dan tidak acuh pada kegiatan
lain. Demikian pula munculnya gejala aneh, seperti rasa
tak tenang, gelisah ketika hasrat bermain tidak segera
terpenuhi.
Game online muncul karena semakin sedikitnya interaksi
sosial terhadap orang yang sama sekali belum dikenal dan
mereka bekerja hampir sama seperti chatting. Menurut fauzi
(2010) game online mempunyai aspek interaksi sosial sebagai
berikut: Adanya suatu hubungan timbal balik antar game; Adanya suatu individu atau kelompok/institusi; Tujuan dari proses interaksi itu sendiri; Ada hubungan dengan struktur dan fungsi komunitas.
Komunitas ini terjadi karena individu tidak dapat
terpisahkan dari suatu kelompok interaksi sosial, dan
71
juga karena individu tersebut memiliki fungsi dan
kedudukan dalam komunitas tersebut.
a. Disfungsi peran mahasiswa
Bicara masyarakat tidak pernah jauh dari struktur
sosial. Selagi individu hidup ditengah-tengah masyarakat,
ia mau tidak mau akan berada pada struktur masyarakat
itu, dimana ia memiliki status tertentu pada struktur
tersebut. Setiap individu dalam masyarakat memiliki
status sosialnya masing-masing. Status merupakan
perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban
individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula
disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat
seseorang dalam kelompok masyarakatnya (Heriyanto,
2013:8). Konsekuensi individu terhadap status sosial yang
diembannya disebut peran sosial. Peranan merupakan aspek
dinamis dari suatu status (kedudukan). Apabila seseorang
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan
status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan
peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan
dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara
kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada
peranan tanpa kedudukan. Kedudukan tidak berfungsi tanpa
72
peranan (Heriyanto, 2013:10). Peran sosial individu pada
masyarakat dominan tidak hanya satu peran saja, hal ini
disebabkan oleh jumlah status sosial individu tersebut
yang lebih dari satu. Ketika tingkah laku seseorang tidak
sesuai atau bahkan bertolak belakang dengan status yang
dimilikinya, maka itu disebut disfungsi peran sosial.
Pada kasus kecanduan game online, gamer pecandu sebagian
besar melupakan peran sosial mereka dalam masyarakat, hal
ini disebabkan oleh tersitanya waktu bangun mereka untuk
bermain game dengan intensitas tinggi, akibatnya
kewajiban-kewajiban mereka terkait tanggungjawab
akademik, pekerjaan, keluarga, hubungan sosial dan lain
sebagainya dilalaikan akibat hanya memenuhi kepuasan
bermain.
b. Social Cyberbullying
Istilah tersebut mengacu pada tindakan seseorang
atau kelompok yang menggunakan media teknologi informasi
dan komunikasi untuk sengaja mendukung perilaku
bermusuhan oleh seorang individu atau kelompok, yang
dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau kelompok
sosial lain, dengan kata lain, penggunaan layanan
internet dan teknologi mobile seperti halaman web dan grup
diskusi serta pesan atau SMS pesan instan teks dengan
maksud merugikan orang lain (Kompas TV, 18 Oktober 2014
pukul 13.00 WIB “Berbagi Curhat : Bullying”).
73
Contoh apa yang merupakan cyberbullying termasuk
komunikasi yang berusaha untuk mengintimidasi,
mengontrol, memanipulasi, meletakkan, mendiskreditkan
palsu (memfitnah), atau mempermalukan penerima. Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) BAB VII
Perbuatan Yang Dilarang Pasal 28 menyatakan bahwa
cyberbullying adalah :(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkanberita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkaninformasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencianatau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakattertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, danantargolongan (SARA).
Dalam game online, pelecehan seksual, berkata kotor,
menghina atau merendahkan lawan main untuk menjatuhkan
mental pesaing pada seseorang atau kelompok sebagai
bentuk cyberbullying adalah umum atau “biasa” dalam budaya
game online (Journal of Experimental Social Psychology dalam
Wikipedia, 2014), sedangkan sebuah studi dari National
Sun Yat-sen University mengamati bahwa anak-anak yang
menikmati video game kekerasan jauh lebih mungkin untuk
mendapat pengalaman sebagai korban atau sebagai pelaku
cyberbullying.
c. Efek Hikikomori
74
Hikikomori ( ひ ひ ひ ひ ひ ) (arti harfiah : menarik diri,
mengurung diri) adalah istilah Jepang untuk fenomena di
kalangan remaja atau dewasa muda yang menarik diri dari
kehidupan sosial. Istilah hikikomori merujuk kepada
fenomena sosial secara umum sekaligus sebutan untuk
orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok sosial ini.
Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan
Kesejahteraan Jepang (dalam Wikipedia, 2014), definisi
hikikomori adalah orang yang menolak untuk keluar dari
rumah, dan mengisolasi diri mereka dari masyarakat dengan
terus menerus berada di dalam rumah untuk satu periode
yang melebihi enam bulan. Menurut psikiater Tamaki Saitō,
hikikomori adalah sebuah keadaan yang menjadi masalah pada
usia 20-an akhir, berupa mengurung diri sendiri di dalam
rumah sendiri dan tidak ikut serta di dalam masyarakat
selama enam bulan atau lebih, tetapi perilaku tersebut
tampaknya tidak berasal dari masalah psikologis lainnya
sebagai sumber utama. Pada penelitian lebih mutakhir,
enam kriteria spesifik diperlukan untuk mendiagnosis
hikikomori :
Menghabiskan sebagian besar waktu dalam satu hari dan hampir setiap hari tanpa meninggalkan rumah,
Secara jelas dan keras hati menghindar dari situasi sosial,
Simtom-simtom yang mengganggu rutinitas normal orang tersebut, fungsi pekerjaan (atau akademik), atau kegiatansosial, atau hubungan antarpribadi,
Merasa penarikan dirinya itu sebagai sintonik ego, Durasi sedikitnya enam bulan, dan
75
Tidak ada ganguan mental lain yang menyebabkan putus sosial dan penghindaran.
Meski tingkatan fenomena ini bervariasi, bergantung
kepada individunya, sejumlah orang bertahan mengisolasi
diri selama bertahun-tahun atau bahkan selama berpuluh-
puluh tahun. Hikikomori sering bermula dari enggan
sekolah (istilah Jepang futōkō ( ひ ひ ひ ) atau istilah
sebelumnya: tōkōkyohi ( ひ ひ ひ ひ ). Menurut penelitian yang
dilakukan NHK untuk acara Fukushi Network,
penduduk hikikomori di Jepang pada tahun 2005 mencapai
lebih dari 1,6 juta orang. Bila penduduk semi-
hikikomori (orang jarang keluar rumah) ikut dihitung, maka
semuanya berjumlah lebih dari 3 juta orang. Total
perhitungan NHK hampir sama dengan perkiraan Zenkoku
Hikikomori KHJ Oya no Kai sebanyak 1.636.000 orang. Menurut
survei Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan
Kesejahteraan, 1,2% penduduk Jepang pernah
mengalami hikikomori; 2,4% di antara penduduk berusia 20
tahunan pernah sekali mengalami hikikomori (1 di antara
40). Dibandingkan perempuan, laki-laki hikikomori
jumlahnya empat kali lipat. Satu di antara 20 anggota
keluarga yang orang tuanya berpendidikan perguruan tinggi
pernah mengalami hikikomori. Tidak ada hubungannya antara
keluarga berkecukupan atau tidak berkecukupan secara
ekonomi, fakta hikikomori menunjukkan bahwa :
76
Jumlah laki-laki hikikomori lebih banyak daripada perempuan;
Kebanyakan berasal dari golongan berusia 20-29 tahun (adapula kasus dari orang berusia 40 tahunan);
Kebanyakan berasal dari orang tua berpendidikan perguruantinggi.
Hal serupa mirip dengan kasus yang terjadi pada
pecandu game online, sebab enam kriteria spesifik hikikomori
pada penjelasan sebelumnya tergambar jelas pada pecandu
game online. Seperti :
1) Menghabiskan sebagian besar waktu dalam satu hari
dan hampir setiap hari tanpa meninggalkan rumah; gamer
pecandu menghabiskan sebagian besar waktu dalam satu hari
dan hampir setiap hari memainkan game di dalam ruangan
tanpa interaksi dengan dunia nyata atau masyarakat.
2) Secara jelas dan keras hati menghindar dari
situasi sosial; seperti pada poin satu, gamer pecandu
tidak dapat mengendalikan emosi untuk bermain game, dan
secara jelas menolak untuk terlibat pada hal-hal yang
tidak terkait dengan bermain game online.
3) Simtom-simtom yang mengganggu rutinitas normal
orang tersebut, fungsi pekerjaan (atau akademik), atau
kegiatan sosial, atau hubungan antarpribadi; hal serupa
juga terjadi pada gamer pecandu, rutinitas sosial yang
dilakukan oleh orang normal pada umumnya rela dikorbankan
demi memenuhi kebutuhan bermain, seringkali hal inilah
yang menjadi sumber masalah pada kehidupan gamer.
77
Akademik yang kacau disertai rusaknya hubungan sosial
dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, teman
bahkan kekasih membuat gamer menjadi depresi namun di
sisi lain tidak dapat meninggalkan game online yang menjadi
penyebab permasalahan hidupnya.
4) Merasa penarikan dirinya itu sebagai sintonik
ego4,
5) Durasi sedikitnya enam bulan; gamer pecandu
bahkan melampaui batas durasi tersebut. Rata-rata gamer
pecandu menarik diri dari kehidupan sosial lebih dari
satu tahun, hal ini erat kaitannya dengan pembaharuan
game online secara berkala oleh developer game online
tersebut. Game online sangat sulit untuk tamat, ini
dikarenakan pembaharuan tersebut untuk meraup untung
sebesar-besarnya dari gamer oleh developer. Sedangkan
gamer pecandu pada umumnya memainkan lebih dari satu game
4 Egosyntonic adalah istilah psikologis mengacu pada perilaku, nilai-nilai,perasaan yang selaras dengan atau diterima dengan kebutuhan dan tujuan dariego, atau konsisten dengan seseorang yang ideal berdasarkan citra diri;Egodystonic (atau ego alien ) adalah kebalikan dari egosyntonic dan mengacu padapikiran dan perilaku (misalnya, mimpi, impuls, dorongan, keinginan, danlain-lain) yang bertentangan, atau disonan, dengan kebutuhan dan tujuan dariego, atau, lebih lanjut, bertentangan dengan citra diri seseorang yangideal. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untukmenangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id danmemastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapatditerima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dantidak sadar. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang berusaha untukmemuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan sosial yangsesuai. Prinsip realitas beratnya biaya dan manfaat dari suatu tindakansebelum memutuskan untuk bertindak atas atau meninggalkan impuls. Dalambanyak kasus, impuls id itu dapat dipenuhi melalui proses menunda kepuasan–ego pada akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam waktu dantempat yang tepat.
78
online, ini jelas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
menyelesaikan game online tersebut.
6) Tidak ada gangguan mental lain yang menyebabkan
putus sosial dan penghindaran; memang benar, tidak ada
gangguan mental lain selain kecanduan game online dalam
kasus hikikomori game online ini, tidak ada riwayat penyakit
mental dalam diri gamer. Kecanduan game online adalah
konstruksi mental yang dilakukan berulang-ulang sehingga
mengalami adiksi.
d. Judi online
Judi online merupakan dampak sosial negatif yang
dianggap biasa dalam dunia game online oleh pelakunya.
Dalam materi game online sendiri, banyak terdapat event atau
acara tententu yang sangat memungkinkan gamer untuk
melakukan perjudian antar sesama gamer. Hampir sama
halnya dengan dunia nyata, fasilitas judi online tidak
kalah sering diakses dengan tujuan sama dengan berjudi
pada tataran umum dengan kesulitan pelacakan yang rumit
membuat berjudi online sulit diberantas meskipun
melanggar hukum. Menurut Kurniawan (dalam Yayuk, 2013:14)
Perkembangan teknologi informasi khususnya komunikasi
online melalui jaringan internet selain memberi kemudahan
bagi kehidupan manusia juga memiliki dampak negatif
seperti maraknya aktivitas judi online yang umumnya
diminati generasi muda termasuk mahasiswa. Sistem
79
komputerisasi yang menyangkut segala bidang kehidupan
global seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan
ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di
seluruh dunia mendorong maraknya perjudian online.
Perkembangan teknologi internet mendorong kemajuan judi
baik jangkauan maupun jumlahnya. Berbagai rumah judi
berdiri dan melebarkan sayapnya melalui dunia maya baik
yang berskala internasional, regional atau lokal. Di
Indonesia sendiri terdapat situs judi online yang pusatnya
berada di Jakarta dan menyebar hingga ke Asia, pemilik
judi online tersebut juga berasal dari Indonesia. Judi
online menjadi dampak sosial negatif yang merupakan
bagian dari game online dan sangat sulit diberantas akibat
terlalu banyak situs judi yang berkedok game online, dan
akan mengalami adiksi judi jika tidak ditanggulangi.
Selain dampak negatif di atas, game online juga
memiliki sisi lain jika tidak dimainkan secara
berlebihan. Griffiths (2007) seorang professor dari
Universitas Nottingham menulis jurnal medis yang
menyatakan bahwa dengan bermain game online (yang tidak
berlebihan) dapat membantu anak-anak penderita attention
deficit disorder (ADD) untuk mengembangkan keterampilan sosial
bagi mereka. MMO (massivelly multiplayer online) mengajarkan
pemainnya untuk melakukan problem solving, memotivasi, dan
mengembangkan kemampuan kognitif, kebanyakan game
menantang gamer (pemain game) untuk mengatasi tantangan80
yang semakin sulit pada setiap level. Game masa kini yang
mendukung banyak pemain berinteraksi di waktu yang sama
dapat membuat gamer mengasah kemampuan komunikasi dan
bersosialisasi, terutama dalam bekerjasama secara tim.
Florence dan Chee (2013) dari Loyala University,
Chicago telah mengadakan penelitian dan menurut mereka,
game MMO dapat menumbuhkan interaksi sosial, misalnya
hubungan pertemanan, persaudaraan, organisasi,
mengahadapi konflik bersama (guild wars), memanajemen anggota
(jika menjadi guild leader), kontrol emosi, politik, dan
sebagainya. Pada permainan-permainan ini gamer dituntut
untuk mampu bekerjasama, mampu menghadapi konflik,
mengontrol emosinya, dan berlatih menjadi seorang
pemimpin. Gamer belajar berorganisasi, berinterkasi dan
mencoba memecahkan konflik-konflik sosial. Ada juga
beberapa game yang kemudian diadaptasi dan dimainkan
dalam kegiatan-kegiatan outbond.
2.1 Landasan Teori: Interaksionisme Simbolik
Beberapa orang ilmuwan punya andil utama sebagai
perintis interaksionisme simbolik, diantaranya James Mark
Baldwin, William James, Charles H. Cooley, John Dewey,
William I. Thomas, dan George Herbert Mead (Ritzer dan
Goodman, 2007:266). Akan tetapi Mead-lah yang paling
populer sebagai perintis dasar teori tersebut. Mead
mengembangkan teori interaksionisme simbolik pada tahun81
1920-an dan 1930-an ketika ia menjadi professor filsafat
di Universitas Chicago. Namun gagasan-gagasannya mengenai
interaksionisme simbolik berkembang pesat setelah para
mahasiswanya menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya,
terutama melalui buku yang menjadi rujukan utama teori
interaksi simbolik, yakni : Mind, Self , and Society (1934) yang
diterbitkan tak lama setelah Mead meninggal dunia.
Penyebaran dan pengembangan teori Mead juga berlangsung
melalui interpretasi dan penjabaran lebih lanjut yang
dilakukan para mahasiswanya, terutama Herbert Blumer.
Justru Blumer-lah yang menciptakan istilah “interaksi
simbolik” pada tahun 1937 dan mempopulerkannya di
kalangan komunitas akademis (Ritzer dan Goodman,
2007:269). Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas
yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau
pertukaran simbol yang diberi makna.
Selama awal perkembangannya, teori interaksi
simbolik seolah-olah tetap tersembunyi di belakang
dominasi teori fungsionalisme dari Talcott Parsons,
meskipun sumbangan Parsons sebagai pengikut utama Weber
terhadap pengembangan teori ini sangat besar, walaupun
tanpa pengakuan penganut teori ini (Ritzer, 2010:50).
Namun kemunduran fungsionalisme tahun 1950-an dan 1960-an
mengakibatkan interaksionisme simbolik muncul kembali ke
permukaan dan berkembang pesat hingga saat ini.
82
George Herbert Maead tidaklah secara harfiah
mengembangkan teori Weber atau bahwa teori Mead diilhami
oleh teori Weber. Hanya memang ada kemiripan dalam
pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai tindakan manusia.
Pemikiran Mead sendiri diilhami beberapa pandangan
filsafat, khususnya pragmatisme dan behaviorisme. Ada
kemiripan antara pandangan Mead dengan pandangan Schutz.
Sejumlah interaksionis memang menekankan dimensi
fenomenologis dengan mensintesiskan karya mereka dengan
gagasan Alfred Schutz dan para pengikutnya.
Interaksionisme simbolik mempelajari sifat interaksi
yang merupakan kegiatan sosial dinamis manusia. Bagi
perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif, dan
kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan
sulit diramalkan. Paham ini menolak gagasan bahwa
individu adalah organisme yang pasif yang perilakunya
ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada
diluar dirinya. Oleh karena individu terus berubah maka
masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksi
lah yang dianggap sebagai variabel penting yang
menentukan perilaku manusia bukan struktur masyarakat.
Interaksionisme simbolik Mazhab Iowa menggunakan
metode saintifik (positivistik) dalam kajian-kajiannya,
yakni untuk menemukan hukum-hukum universal mengenai
perilaku sosial yang dapat diuji secara empiris,
83
sementara Mazhab Chicago menggunakan pendekatan
humanistik. Dan Mazhab yang populer digunakan adalah
Mazhab Chicago.
Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami
perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif
ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat
sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan
mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan
ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi
mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain,
situasi, objek dan bahkan diri mereka sendirilah yang
menentukan perilaku mereka.
Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai
kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya atau tuntutan
peran. Manusia bertindak hanyalah berdasarkan definisi
atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling
mereka. Tidak mengherankan bila frase-frase “definisi
situasi”, “realitas terletak pada mata yang melihat” dan
“bila manusia mendefinisikan situasi sebagai riil,
situasi tersebut riil dalam konsekuensinya” sering
dihubungkan dengan interaksionisme simbolik.
Karya Mead yang paling terkenal ini menggaris-bawahi
tiga konsep kritis yang dibutuhkan dalam menyusun sebuah
diskusi tentang teori interaksionisme simbolik. Tiga
konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam term84
interaksionisme simbolik, yaitu pikiran manusia (mind)
dan interaksi sosial (diri/self dengan yang lain)
digunakan untuk menginterpretasikan dan memediasi
masyarakat (society) di mana kita hidup. Makna berasal dari
interaksi dan tidak dari cara yang lain. Pada saat yang
sama “pikiran” dan “diri” timbul dalam konteks sosial
masyarakat. Pengaruh timbal balik antara masyarakat,
pengalaman individu dan interaksi menjadi bahan bagi
penelahaan dalam tradisi interaksionisme simbolik (Ritzer
dan Goodman, 2007:279).
Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang
individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi
interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan
ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol
yang diberi makna. Perspektif interaksi simbolik berusaha
memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek.
Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus
dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia
membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan
mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra
interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada
orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri
yang menentukan perilaku manusia.
Mead adalah pemikir yang sangat penting dalam
sejarah interaksionisme simbolik. Interaksi simbolik
85
didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan hubungannya
dengan masyarakat. Ralph Larossa dan Donald C. Reitzes
mengatakan bahwa ada tiga tema besar yang mendasari
asumsi dalam teori interaksi simbolik:
1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
a) Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap mereka.
b) Makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia.c) Makna dimodifikasi melalui proses interpretif.
2. Pentingnya konsep mengenai diri
a) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain.
b) Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku.
3. Hubungan antara individu dan masyarakat
a) Orang dan kelompok-kelompk dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial.
b) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.
Karya tunggal Mead yang amat penting dalam hal ini
terdapat dalam bukunya yang berjudul Mind, Self dan Society.
Mead mengambil tiga konsep kritis yang diperlukan dan
saling mempengaruhi satu sama lain untuk menyusun sebuah
teori interaksionisme simbolik. Dengan demikian, pikiran
manusia (mind), dan interaksi sosial (diri/self) digunakan
untuk menginterpretasikan dan memediasi masyarakat
(society).
86
1. Pikiran (Mind)
Pikiran, yang didefinisikan oleh Mead sebagai proses
percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak
ditemukan di dalam diri individu, pikiran adalah fenomena
sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses
sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial.
Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah
produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan
secara fungsional ketimbang secara substantif.
Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan
individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak
hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas
secara keseluruhan. Itulah yang kita namakan pikiran.
Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir
tertentu, dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam
dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran. Dengan
demikian pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain
seperti konsep ingatan dalam karya Mead melalui
kemampuannya menanggapi komunitas secara menyeluruh dan
mengembangkan tanggapan terorganisir. Mead juga melihat
pikiran secara pragmatis. Yakni, pikiran melibatkan
proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah
(Ritzer dan Goodman, 2007:280).
2. Diri (Self)
87
Banyak pemikiran Mead pada umumnya, dan khususnya
tentang pikiran, melibatkan gagasannya mengenai konsep
diri. Pada dasarnya diri adalah kemampuan untuk menerima
diri sendirisebagai sebuah objek. Diri adalah kemampuan
khusus untuk menjadi subjek maupun objek. Diri
mensyaratkan proses sosial yakni komunikasi antar
manusia. Diri muncul dan berkembang melalui aktivitas dan
antara hubungan sosial. Menurut Mead adalah mustahil
membayangkan diri yang muncul dalam ketiadaan pengalaman
sosial. Tetapi, segera setelah diri berkembang, ada
kemungkinan baginya untuk terus ada tanpa kontak sosial.
Diri berhubungan secara dialektis dengan pikiran.
Artinya, di satu pihak Mead menyatakan bahwa tubuh
bukanlah diri dan baru akan menjadi diri bila pikiran
telah berkembang. Di lain pihak, diri dan refleksitas
adalah penting bagi perkembangan pikiran. Memang mustahil
untuk memisahkan pikiran dan diri karena diri adalah
proses mental. Tetapi, meskipun kita membayangkannya
sebagai proses mental, diri adalah sebuah proses sosial.
Dalam pembahasan mengenai diri, Mead menolak gagasan yang
meletakkannya dalam kesadaran dan sebaliknya
meletakkannya dalam pengalaman sosial dan proses sosial.
Dengan cara ini Mead mencoba memberikan arti
behavioristis tentang diri. Diri adalah di mana orang
memberikantanggapan terhadap apa yang ia tujukan kepada
orang lain dan dimana tanggapannya sendiri menjadi bagian88
dari tindakannya, di mana ia tidak hanya mendengarkan
dirinya sendiri, tetapi juga merespon dirinya sendiri,
berbicara dan menjawab dirinya sendiri sebagaimana orang
lain menjawab kepada dirinya, sehingga kita mempunyai
perilaku di mana individu menjadi objek untuk dirinya
sendiri. Karena itu diri adalah aspek lain dari proses
sosial menyeluruh dimana individu adalah bagiannya.
Mekanisme umum untuk mengembangkan diri adalah
refleksivitas atau kemampuan menempatkan diri secara tak
sadar ke dalam tempat orang lain dan bertindak seperti
mereka bertindak. Akibatnya, orang mampu memeriksa diri
sendiri sebagaimana orang lain memeriksa diri mereka
sendiri. Seperti dikatakan Mead :
“Dengan cara merefleksikan−dengan mengembalikanpengalaman individu pada dirinya sendiri−keseluruhanproses sosial menghasilkan pengalaman individu yangterlibat di dalamnya; dengan cara demikian, individubisa menerima sikap orang lain terhadap dirinya,individu secara sadar mampu menyesuaikan dirinya sendiriterhadap proses sosial dan mampu mengubah proses yangdihasilkan dalam tindakan sosial tertentu dilihat darisudut penyesuaian dirinya terhadap tindakan sosial itu(Mead dalam Ritzer dan Goodman, 2007:281)”
Diri juga memungkinkan orang berperan dalam
percakapan dengan orang lain. Artinya, seseorang
menyadari apa yang dikatakannya dan akibatnya mampu
menyimak apa yang sedang dikatakan dan menentukan apa
yang akan dikatakan selanjutnya.
89
Untuk mempunyai diri, individu harus mampu mencapai
keadaan “di luar dirinya sendiri” sehingga mampu
mengevaluasi diri sendiri, mampu menjadi objek bagi
dirinya sendiri. Untuk berbuat demikian, individu pada
dasarnya harus menempatkan dirinya sendiri dalam bidang
pengalaman yang sama dengan orang lain. Tiap orang adalah
bagian penting dari situasi yang dialami bersama dan tiap
orang harus memperhatikan diri sendiri agar mampu
bertindak rasional dalam situasi tertentu. Dalam
bertindak rasional ini mereka mencoba memeriksa diri
sendiri secara impersonal, objektif, dan tanpa emosi.
Tetapi, orang tidak dapat mengalami diri sendiri
secara langsung. Mereka hanya dapat melakukannya secara
tak langsungmelalui penempatan diri mereka sendiri dari
sudut pandang orang lain itu. Dari sudut pandang demikian
orang memandang dirinya sendiri dapat menjadi individu
khusus atau menjadi kelompok sosial sebagai satu
kesatuan. Seperti dikatakan Mead, hanya dengan mengambil
peran orang lainlah kita mampu kembali kediri kita
sendiri (Mead dalam Ritzer dan Goodman, 2007:282).
3. Masyarakat (Society)
Pada tingkat paling umum, Mead menggunakan istilah
masyarakat (society) yang berarti proses sosial tanpa henti
yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting
perannya dalam membentuk pikiran dan diri. Di tingkat90
lain, menurut Mead, masyarakat mencerminkan sekumpulan
tanggapan terorganisir yang diambil alih oleh individu
dalam bentuk “aku” (me). Menurut pengertian individual
ini masyarakat mempengaruhi mereka, memberi mereka
kemampuan melalui kritik diri, untuk mengendalikan diri
mereka sendiri. Sumbangan terpenting Mead tentang
masyarakat, terletak dalam pemikirannya mengenai pikiran
dan diri.
Pada tingkat kemasyarakatan yang lebih khusus, Mead
mempunyai sejumlah pemikiran tentang pranata sosial (social
institutions). Secara luas, Mead mendefinisikan pranata
sebagai “tanggapan bersama dalam komunitas” atau
“kebiasaan hidup komunitas”. Secara lebih khusus, ia
mengatakan bahwa, keseluruhan tindakan komunitas tertuju
pada individu berdasarkan keadaan tertentu menurut cara
yang sama, berdasarkan keadaan itu pula, terdapat respon
yang sama dipihak komunitas. Proses ini disebut
“pembentukan pranata”. Pendidikan adalah
prosesinternalisasi kebiasaan bersama komunitas ke dalam
diri aktor. Pendidikan adalah proses yang esensial karena
menurut pandangan Mead, aktor tidak mempunyai diri dan
belum menjadi anggota komunitas sesungguhnya sehingga
mereka tidak mampu menanggapi diri mereka sendiri seperti
yang dilakukan komunitas yang lebih luas. Untuk berbuat
demikian, aktor harus menginternalisasikan sikap bersama
komunitas. Namun, Mead dengan hati-hati mengemukakan91
bahwa pranata tak selalu menghancurkan individualitas
atau melumpuhkan kreativitas. Mead mengakui adanya
pranata sosial yang “menindas, stereotip,
ultrakonservatif” yakni, yang dengan kekakuan,
ketidaklenturan, dan ketidakprogesifannya menghancurkan
atau melenyapkan individualitas. Menurut Mead, pranata
sosial seharusnya hanya menetapkan apa yang sebaiknya
dilakukan individu dalam pengertian yang sangat luas dan
umum saja, dan seharusnya menyediakan ruang yang cukup
bagi individualitas dan kreativitas. Di sini Mead
menunjukkan konsep pranata sosial yang sangat modern,
baik sebagai pemaksa individu maupun sebagai yang
memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang kreatif
(Ritzer dan Goodman, 2007:288).
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan penelitian
92
Pada penelitian yang dilakukan pada gamer di kandang
limun Kota Bengkulu yakni mengenai fenomena kecanduan
game online pada remaja, peneliti menggunakan penelitian
dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian kualitatif pada dasarnya ialah mengamati
kegiatan manusia dalam lingkungannya, berinteraksi, serta
berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka terhadap
lingkungan sekitar, terutama lingkungan sosial mereka
(Nasution dalam Yuningsih, 2011: 25), jika bicara gamer
maka pengertian ini tentu disubstitusikan pada kelompok
sosial gamer, baik kelompok online maupun kelompok offline,
definisi tersebut linear dengan penyataan Bungin (dalam
Samri, 2013:24) yang membatasi kualitatif deskriptif
sebagai metode untuk menggambarkan serta mengangkat
situasi dan kondisi atau berbagai fenomena sosial yang
ada pada suatu masyarakat hingga menjadi objek penelitian
dan berusaha mentransformasikannya sebagai suatu karakter
atau ciri fenomena tertentu. Deskriptif artinya peneliti
diharuskan mampu untuk menggambarkan secara komprehensif
kondisi psikologis hingga kondisi sosial dalam lingkungan
gamer. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik
(menyeluruh) dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah,
artinya, peneliti mesti menggambarkan secara menyeluruh
93
tentang subjek penelitian serta situasi atau peristiwa
yang menjadi basis perilaku subjek penelitian (Moleong
dalam Wasriani, 2009:22). Dalam bukunya “metode penelitian
kualitatif”, Sugiyono (2005:3) menyatakan bahwa metode
kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam
yakni suatu data yang mengandung makna, menurutnya makna-
lah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu
nilai di balik data yang tampak oleh indera manusia,
dengan kata lain makna membutuhkan analisis kuat untuk
memperolehnya. Oleh karena itu dalam penelitian
kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi
lebih menekankan pada makna objektif, detail, dan
representatif. Menurut mardalis (dalam Samri, 2013:24),
penelitian mestilah menerapkan empat prinsip sebagai
berikut :
a. Penelitian perlu dirancang dan diarahkan untukmemecahkan suatu permasalahan tertentu dimanapada akhir penelitian, hasilnya dapat menjawabsolusi dari permasalahan yang terjadi.
b. Penelitian ditekankan untuk mengembangkangeneralisasi prinsip-prinsip, serta teori, dengandemikian hasilnya memiliki nilai deskripsi danprediksi.
c. Berangkat dari objek penelitian, prosedurpenelitian tidak dapat digunakan untuk menjawabmasalah yang tidak realistis dan tidak memilikibukti empiris.
d. Penelitian memerlukan observasi dan deskripsiyang akurat, untuk itu kecermatan menjadi sangatutama dalam menjalankan penelitian.
94
3.2 Definisi konseptual dan definisi operasional
Untuk lebih memudahkan pendeskripsian data serta
penyeragaman pengertian konsep-konsep, maka dibawah ini
dijelaskan beberapa konsep yang digunakan yang terlihat
pada tabel di halaman selanjutnya.
95
No AspekPenelitian
Definisi Konsep Definisi Operasional TeknikPengumpulanData
Sumber Informasi
1 Mahasiswagamer online(MGO)
Mahasiswa pemaingame interaktifonline dengan atautanpa konsol gametertentu
Dapat dilihat dari :Klasifikasi usia yaknigamer yang berusia 18-25Tahun, jenjang semesteryakni mahasiswa semesterI s.d XIV danjenis/genre game yangdimainkan yaitu game MMO(Massivelly Multiplayer Online)
WawancaraObservasiDokumentasi
Pecandu game (Informankunci)Gamer (informan biasa)Penjaga warnet (informanbiasa)
3 Mahasiswagamerpecandu(MGP)
MGO denganintensitas bermainyang berlebihan dandi luar kewajaranbaik itu secaraperiode waktu,kuantitas game onlineyang dimainkan dandana untuk bermain.
Dapat dilihat dari :Periode dan lama periodewaktu bermain yaitu ≥ 6Jam/Hari/Minggu,kuantitas game yangdimainkan yakni ≥ 1genre game dan danauntuk bermain ≥ Rp.200.000/Bulan
WawancaraObservasiDokumentasi
Pecandu gameGamerTeman pecandu game(informan tambahan)
4 Pendorongkecanduangame online
Berbagai hal yangberkontribusi dalammempengaruhiseorang gamer untukmemainkan game onlinesecara berlebihan
Dapat dilihat dari :Interaksi virtual didalam cyberspace: meliputiperbandingan interaksicyberspace denganinteraksi dunia nyatadalam bentuk persentase
WawancaraObservasi
Pecandu gameTeman pecandu game
96
(CI>RI); Disfungsikeluarga yang meliputiorang tua yang sibukbekerja dan pudarnyafungsi afeksi;konformitas meliputiteman sebaya dan media;dan perkembanganteknologi game dapatdilihat dari peningkatankompleksitas alur game,item, kualitas audio-visual yang dirasakangamer sehingga gamersemakin tertarikmenyelesaikan misi dalamgame online.
5 Dampaksosio-akademiskecanduangame online
Berbagai dampaksosial-akademisyang diakibatkanoleh kecanduan gameterhadap MPGO.
Dapat dilihat dari :Disfungsi peran sosialterutama fungsimahasiswa: hal ini dapatdilihat dari keaktifankuliah, IPS dan IPK,kegiatan Organisasiinternal/eksternalkampus; Social Cyberbullyingdapat dilihat dari livechat di game online yang
WawancaraObservasi
Gamer Pecandu gameKeluarga pecandu game(informan tambahan)Teman pecandu game
97
gamer pecandu mainkan,serta efeknya padakehidupan nyata MGP;Efek hikikomori dapatdilihat dari kesehariangamer dengan ukuranpersentase menyendiridengan game online yaituwaktu bangun gamer tanpainteraksi sosial didunia nyata; dan judionline dapat dilihat daritransaksi-transaksiillegal dalam gameonline dalam bentuktaruhan, dan lainsebagainya.
98
3.3 Teknik pengumpulan data
Tahap ini merupakan langkah yang paling penting
dalam suatu penelitian karena tahap ini merupakan
tujuan utama dari penelitian, yakni untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2007:22). Tanpa
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan.
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data
dilakukan pada setting alamiah atau kondisi yang tidak
dibuat-buat, sumber data primer, dan teknik pengumpulan
data lebih banyak pada pengamatan langsung, wawancara
mendalam hingga dokumentasi (Sugiyono, 2007: 63).
3.3.1 Observasi
Observasi adalah dasar seluruh ilmu pengetahuan
manusia (Nasution dalam Sugiyono, 2007:64). Para
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu
fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Observasi
adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan
diteliti.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
observasi semi partisipan, yakni peneliti ikut terlibat
dalam keseharian subjek yang sedang diamati namun tidak
secara utuh. Observasi semi partisipan adalah suatu
99
prosedur yang dengannya peneliti mengamati tingkah laku
orang lain dalam keadaan alamiah, dengan melakukan
partisipasi semu terhadap kegiatan pada lingkungan yang
diamati. Dalam observasi semi partisipan, peranan
tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang
berkenaan dengan kelompok yang diamati menjadi penting.
Walaupun bersifat semi partisipan, peneliti tidak
dapat hanya mengandalkan wawancara saja. Intensitas
pertemuan untuk pengamatan mendalam juga mesti peneliti
lakukan guna memperoleh data yang valid dan peneliti
cukup mengamati secara alamiah aktifitas gamer yang
mengalami kecanduan game. Hal ini, untuk mendapatkan
data yang akurat mengenai gamer pecandu.
3.3.2 Wawancara
Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati
informan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara
sistimatis serta berdasarkan pada tujuan penelitian.
Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan masalah yang
sedang diteliti secara lebih jelas untuk melengkapi
teknik observasi dan dilakukan beberapa kali sesuai
dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan
kejelasan masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini,
peneliti hanya hanya mempersiapkan alat perekam suara,
kamera dan alat tulis. Menurut esterberg (dalam
Sugiyono, 2007:72), wawancara adalah pertemuan dua
100
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya
jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu, sedangkan menurut susan (dalam buku
yang sama), melalui wawancara, maka peneliti akan
mengetahui hal-hal yang tidak diketahui melalui
observasi serta kualitas data yang lebih mendalam
tentang subjek dalam menggambarkan melalui gagasan
mengenai situasi dan fenomena yang sedang terjadi.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah
wawancara tak berstruktur. Dalam day in the field,
mallinowski (dalam Bungin, 2007:134) menunjukkan betapa
pentingnya wawancara tak berstruktur dalam melakukan
penelitian lapangan dibanding wawancara berstruktur
yang memiliki dua kelemahan yang diistilahkan capital
offense.5 langkah-langkah dalam melakukan wawancara tak
berstruktur adalah sebagai berikut (Bungin, 2007:134-
138) :
a. Sebelum wawancara dilakukan, jawablah pertanyaan
how do we get in?, artinya peneliti mesti
meninggalkan pakaiannya dan menyesuaikan dengan
pakaian yang dikenakan oleh informannya, dan
jadilah teman mereka, dengan begitu peneliti
akan dengan leluasa membongkar data penting yang
5 Dua hal yang dilanggar oleh pewawancara berstruktur ialah: (1)pewawancara sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari responden dan(2) pewawancara membiarkan perasaan pribadinya memengaruhi dirinya padasaat wawancara berstruktur bertujuan menangkap data yang tepat untukmenjelaskan perilaku di dalam kategori-kategori yang sudah ditetapkansebelumnya (Mallinowski dalam Bungin, 2007:134).
101
ada di dalam diri informan secara jujur tanpa
segan.
b. Peneliti harus belajar bahasa dan budaya
informan, hal ini tujuannya ialah agar informan
memahami maksud peneliti. Mengetahui kebiasaan
dan kegemaran informan juga tidak bisa
dikesampingkan, misalnya tempat favorit, waktu
senggang yang dimiliki, perilaku dan
kecenderungan topik pembicaraan, hal ini
dimaksudkan akar di antara peneliti dengan
informan terbangun trust sehingga proses wawancara
dapat berjalan dengan semestinya.
c. Perlu diperhatikan strategi-strategi nonverbal
yang kemungkinan mempengaruhi jalannya
wawancara, maksudnya ialah peneliti selain cakap
dalam berkomunikasi secara lisan ia juga
dianjurkan dapat memahami ekspresi informan
dalam aspek bahasa tubuh, mimik wajah dan
intonasi suara. Hal ini sangat penting untuk
diperhatikan, karena dalam komunikasi efektif,
bahasa nonverbal lebih besar pengaruhnya
dibanding bahasa verbal.
d. Pemilihan informan mestilah dengan kecermatan
yang tinggi. Informan merupakan unsur penting
dalam penelitian kualitatif, sebab ia menentukan
kualitas data yang akan kita dapatkan dan kita
olah terkait masalah penelitian. Kesalahan
102
memilih informan sangat berakibat fatal dengan
kualitas penelitian kita, sebab kualitatif
sangat bergantung pada kualitas data. Oleh sebab
itu, mesti ada kriteria yang jelas dan terukur
sebelum menentukan informan.
e. Ketika penelitian berlangsung, peneliti harus
menempatkan diri sesuai dengan derajat
informannya, hal ini dimaksudkan agar tidak ada
kecanggungan yang terjadi sehingga mempengaruhi
informasi yang didapatkan oleh peneliti. Kesan
yang baik sangat diutamakan, sebab kesan adalah
jembatan perasaan yang terbangun dengan sifat
membekas.
3.3.3 Dokumentasi
Dokumentasi adalah seluruh data yang berbentuk
tulisan, gambar, maupun video yang terkait dengan
penelitian yang sedang dilakukan (Moleong dalam
Wasriani, 2009:24), keseluruhan dari data dokumentasi
ialah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari
tempat dilakukannya penelitian hingga institusi
tertentu yang memiliki kaitan dengan permasalahan
penelitian. Data-data dokumentasi dapat berupa arsip-
arsip, profil geografis, demografi serta gambaran
sosial-budaya pada masyarakat setempat. Dokumentasi
juga dapat diperoleh peneliti melalui pengambilan
gambar pada saat melakukan penelitian di lapangan, hal
103
ini dilakukan guna mendukung dan memperkuat data
peneliti, selain gambar, catatan lapangan juga sangat
diperlukan sebagai alat pelengkap pengumpulan data yang
tidak bisa direpresentasikan oleh kamera.
3.4 Informan penelitian
3.4.1 Kriteria informan
Subjek penelitian yakni informan yang akan
memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama
proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini,
penentuan informan penelitian peneliti tentukan dengan
kriteria-kriteria yang dijabarkan pada halaman 24
tentang kriteria kecanduan game online menurut suler dan
halaman 28 tentang efek hokikomori, oleh karena itu
peneliti membatasi informan dalam tiga tingkatan, yaitu
:
1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengalami
secara langsung kecanduan game yang merupakan
informasi pokok dalam penelitian ini, informan
adalah mahasiswa yang sudah lama bermain game
online yaitu mahasiswa yang sudah melakukan
permainan minimal selama dua tahun ke atas, atau
sudah mulai bermain game pada tahun 2012 ke
bawah yaitu pada tahun 2011, 2010 dan
seterusnya. Informan yang dipilih juga merupakan
mahasiswa yang sudah banyak menghabiskan uang
mereka untuk kegiatan bermain game online dan
104
juga mahasiswa yang sudah sulit untuk melepaskan
diri dari permainan game online yang mereka
mainkan.
2) Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat
secara langsung dalam interaksi sosial subjek
penelitian, dalam hal ini informannya ialah
mereka yang memainkan game online namun tidak
mengalami kecanduan game dan yang sesuai dengan
fokus penelitian ini adalah teman dekat
mahasiswa yang mengalami kecanduan game online.
Teman dekat mahasiswa yang mengalami kecanduan
tersebut dijadikan informan untuk memperoleh
informasi mengenai lingkungan sosial dan
kelompok bermain (peergroup) mahasiswa yang
mengalami kecanduan game online tersebut. Teman
dekat yang dimaksud juga merupakan teman yang
sudah cukup lama mengetahui bahwa teman mereka
mengalami kecanduan game online, kemudian
informan biasa selanjutnya ialah penjaga warnet
game online yang mengetahui persis kegiatan gamer
pecandu mulai dari biaya online, transaksi, serta
lama bermain game para pecandu game online pada
periode tertentu.
3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat
memberikan informasi terkait subjek penelitian
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi
sosial yang sedang diteliti, dalam hal ini
105
peneliti menetapkan teman pecandu game yang
tidak memainkan game online sebagai informan
tambahan, keluarga pecandu game online juga
merupakan informan tambahan untuk menelusuri
dampak sosial kecanduan game dilihat dari
perubahan perilaku sosial sebelum dan sesudah
mengalami kecanduan game online.
3.4.2 Teknik penentuan informan
Teknik penentuan informan pada penelitian ini
ialah menggunakan teknik snowball. Teknik snowball
merupakan salah satu metode dalam pengambilan informan
dari suatu populasi, dalam kasus ini, populasi yang
dimaksud ialah populasi mahasiswa pemain game online di
Kelurahan Kandang limun, Kota Bengkulu. Teknik snowball
termasuk dalam teknik non-probability sampling (teknik
pengambilan sampel dengan probabilitas yang tidak
sama). Untuk metode pengambilan sampel seperti ini
khusus digunakan untuk data-data yang bersifat
komunitas dari subjektif informan, dengan kata lain
objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan
bersifat mengelompok pada suatu himpunan, artinya
snowball sampling metode pengambilan sampel dengan
secara berantai (multi level). Kelebihan dari metode
ini ialah mudah digunakan, sederhana, waktu yang
efisien, hanya membutuhkan sedikit rencana dan sedikit
tenaga kerja.
106
Sedangkan kekurangannya ialah peneliti memiliki
sedikit kontrol atas metode ini karena peneliti hanya
memilih sampel di awal, selanjutnya sampel dipilih
orang subyek-subyek yang telah dipilih sebelumnya,
kemudian keterwakilan sampel tidak terjamin karena
peneliti tidak mengetahui distribusi sampel yang akan
dipilih selanjutnya dan subyek awal cenderung untuk
mencalonkan orang-orang yang mereka kenal baik. Karena
itu, sangat mungkin bahwa subyek terdiri dari sifat dan
karakteristik yang sama, dengan demikian memungkinkan
bahwa sampel yang peneliti akan dapatkan hanya
subkelompok kecil dari seluruh populasi.
Gambar : Jenis-jenis metode snowball (Dian,
2012)
107
3.4.3 Proses penentuan informan
Pada penjabaran mengenai kriteria-kriteria
informan di atas, kita dapat mengetahui bahwa informan
pada penelitian ini memiliki standar psikologis dan
perilaku yang jelas. Adapun kriteria tersebut peneliti
sadur dari literatur-literatur yang dianggap
representatif dalam pembahasan mengenai kecanduan game
online baik dari perspektif psikologis, kesehatan
fisikal maupun sosial. Refleksi dari kriteria tersebut
sebagian besar sesuai dengan kondisi para gamer yang
bermain game online pada lokasi penelitian, ada beberapa
kriteria yang masih belum peneliti pastikan
keabsahannya pada pra-penelitian sebelumnya.
Untuk memudahkan interaksi dengan gamer pecandu,
peneliti melakukan pendekatan dengan observasi
partisipatoris semu, peneliti menyebutkan semu karena
tidak seluruh kegiatan gamer pecandu dapat peneliti
ikuti akibat terbatasnya manajemen waktu antara
peneliti dengan informan. Hal tersebut wajar mengingat
kegiatan gamer pecandu yang berkutat dengan game online
memiliki intensitas waktu yang sangat padat untuk
menyelesaikan game yang memiliki dinamika yang tinggi.
Namun kegiatan bermain game online oleh gamer pecandu
yang peneliti amati sudah sedikit menggambarkan
bagaimana perilaku gamer pecandu terhadap lingkungan
sosial gamer dan apa saja dampak sosial yang dialami
108
oleh gamer pecandu selama mengalami masa adiksi game
online tersebut, tentu hal ini perlu terus peneliti gali
hingga mendapatkan informasi yang maksimal tentang
fenomena kecanduan game online ini.
3.5 Teknik analisa data
Analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan
data yang sistematis melalui transkip wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi
menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data
merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah,
karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti
dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah
penelitian (Bogdan & Biklen dalam Yuningsih, 2011:29),
sedangkan menurut spradley (dalam buku yang sama),
analisis data merujuk pada pengujian sistematis
terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya,
hubungan di antara bagian-bagian, dan hubungan bagian-
bagian itu dengan keseluruhan. Analisis data ialah
proses menyusun data agar dapat ditafsirkan (Nasution
dalam Yuningsih, 2011:30), menyusun data berarti
mengklasifikasikan dalam pola atau tema tertentu.
Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna
terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori,
serta mencari hubungan antara berbagai konsep.
109
Dalam menganalisis data pada penelitian ini,
peneliti menggunakan model Miles dan Huberman (dalam
Sugiyono, 2005:92-99), yakni :
a. Reduksi data
Menurut Sugiyono (2007:92), mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan
demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan
mencarinya bila diperlukan.
b. Penyajian data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya
adalah mendisplaykan data. Sugiyono (2007:95)
mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan
sejenisnya. Dalam hal ini miles dan huberman (dalam
Sugiyono, 2005:95) menyatakan bahwa yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk
memahami apa yang tejadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami
tersebut.
110
c. Pengambilan kesimpulan
langkah terakhir ini disebut sebagai penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel (Miles & Huberman
dalam Sugiyono, 2005:99).
DAFTAR PUSTAKA
Aji, Chandra J, 2012, “Berburu rupiah lewat game online”,Bounabooks
Berbagi Curhat: Bullying 2014, Program Televisi, KompasTV, Jakarta, 18 Oktober pukul 13.00 WIB.
Black, A. James, dan Champion, J. Dean, 2001, Metode dan
Masalah Penelitian Sosial, PT Refika Aditama, Bandung.
111
Bungin, Burhan, 2007, “Metodologi Penelitian Kualitatif: aktualisasimetodologis ke arah ragam varian kontemporer, Rajawali Pers,Jakarta.
Cole, Helena dan Mark D. Griffiths, 2007, “SocialInteractions In Massively Multiplayer Online Role-Playing Gamers”,Jurnal Cyberpsychology And Behavior. Vol. 10(4),Halaman 575-583.
Efendi, Azwar dan T. Romi Marnelly, 2014, “DampakKecanduan Permainan Playstation (PS) Dikalangan MahasiswaUniversitas Riau”, JOM (Jurnal Online Mahasiswa) FISIPVolume 1 Nomor 2.
Fauziah, Eka R., 2013, “Pengaruh game online terhadapperubahan perilaku anak SMP Negeri 1 Samboja”, E-Journal ilmu komunikasi. Vol. 1 (3) halaman 1-16
ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id
Febrian, Andri, 2011, “Perancangan Kampanye Dampak NegatifPenggunaan Game online Yang Berlebihan”, Laporan TugasAkhir Desain Komunikasi Visual Fakultas DesainUniversitas Komputer Indonesia, Bandung.
Florence, et al, 2012, “re-mediating research ethics: end-userlicense agreements (EULAs) in online games”, Jurnal Technologyand Society. Vol. 32(6), halaman 497-506.
Maryan, Euvianry, 2012, “Kemungkinan Penerapan HukumPidana Dalam Penanggulangan Dampak Negatif Game online BagiAnak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya,Yogyakarta.
Muttaqin, Husnul n.d., Merangkai Keimanan Di DuniaCyber: Kajian Sosiologis Atas Konstruksi Model-ModelPemahaman Keagamaan Di Halaman Komunitas JaringanIslam Liberal Di Situs Jejaring Sosial Facebook,Executive Summary.
Modul, 1996, “Mengatasi Kecanduan Permainan Daring Elektronik(PDE Disorder)”. Layanan Bimbingan Sosial Bagi Siswa.
112
Piliang, Y. Amir, 2012, “Masyarakat informasi dan digital:Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial.” JurnalSosioteknologi Edisi 27 Tahun ke-11.
Poloma, Margareth, 1992, “Sosiologi kontemporer”, RajawaliPers, Jakarta.
Praditasari, Dian, 2009, “Profil Need Dan Press Pada PemainGame online.” Skripsi Fakultas psikologi UniversitasKatolik Soegijapranata, Semarang
Pratiwi, Andayani, Karyanta n.d., “Perilaku Adiksi Game-Online Ditinjau Dari Efikasi Diri Akademik Dan Keterampilan SosialPada Remaja Di Surakarta”, Fakultas KedokteranUniversitas Sebelas Maret, Surakarta.
Ritzer, George, 2010, “Sosiologi Ilmu Pengetahuan BerparadigmaGanda”, Rajawali Pers, Jakarta.
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2007, “TeoriSosiologi Modern”, Kencana, Jakarta.
Samri, K. Agus, 2013, “Cara Mabuk Baru Remaja dengan JamurLetong”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Bengkulu, Bengkulu.
Soebastian, O. Cynthia, 2010, “Dampak Psikologis NegatifKecanduan Permainan Online Pada Mahasiswa”, SkripsiFakultas psikologi Universitas Katolik Soegijapranata,Semarang.
Sugiyono, 2005, “Metode Penelitian Kualitatif,Bandung, Alfabeta
Suveraniam, G. Naiken, 2011, “Pengaruh Game online TerhadapPrestasi Akademik Pada Siswa Sma Di Kota Medan, SkripsiFakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,Medan.
113
UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 TentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Bab VIIPerbuatan yang dilarang Pasal 28.
Wasriani, 2009, “Perilaku Sosial Masyarakat Dusun III Talang PauhDalam Mengkonsumsi Air Terkait Diare Balita”, SkripsiJurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan PolitikUniversitas Bengkulu, Bengkulu.
Widyastuti, Febriana S., 2012, “Kecanduan Mahasiswa Terhadap Game online”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Yuningsih, M. Neni, 2011, “Studi Ketahanan Keluarga PadaPasangan Suami Istri TKI”, Skripsi Jurusan SosiologiFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UniversitasBengkulu, Bengkulu.
Yurita, Okti, 2014, “Perempuan Dan Kebiasaan Merokok”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Bengkulu.
Sumber Internet:APJII, 2014, Pengguna Internet 2012. http://www.apjii.co.id(di akses tanggal 8 Oktober 2014 pukul 12.01 WIB)http://bkkbn.go.id/angka_perceraian_2010http://www.Ligagame.com (di akses tanggal 9 Februari 2014pukul 09:36 WIB). http://www.networkkedblogs.com diakses tanggal 29 Februari2014 pukul 19.23 WIB).http://www.Iuc.edu/soc/florencechee.shtmlhttps://www.academia.edu/4631795/Peran_dan_Fungsi_Mahasiswahttp://kamuskesehatan.com/Kecanduanhttp://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_genres-----------------------------------/Konformitas-----------------------------------/Kecanduan_game_onlinehttp://www.lifeblog.comhttps://www.facebook.com/gan.lawliethttp://kentangtahu.blogspot.com/2012/06/snowball-sampling.html
114