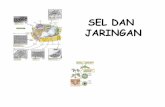REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI PELANGAN ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI PELANGAN ...
Jurnal Ilmiah
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI PELANGAN
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tugas Akhir
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1 Jurusan Teknik Sipil
Oleh :
K ARDIANSYAH
FIA 009 076
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2017
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI PELANGAN KECAMATAN SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT
(STUDI KASUS : DAERAH IRIGASI PELANGAN)
Ardiansyah1, Salehudin
2, Agustono Setiawan
2
1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 2Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mataram
INTISARI
Sesuai dengan amanat dari Kepmen PU No. 390 Tahun 2007 Tentang Penetapan
Status Daerah Irigasi yang Pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan pengelolaan
irigasi yang diatur lebih lanjut melalui Kepmen PU No 293tahun 2014 tentang penetapan status
Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari 20 Daerah Irigasi Kewenangan
kabupaten yang ada di kabupaten Lombok Barat, terdapat satu Daerah Irigasi yaitu Daerah Irigasi
Pelangan yang sampai saat ini tidak dapat berfungsi karena telah terjadi banyak kerusakan. akibat
dari tidak beroperasinya Daerah Irigasi di Pelangan maka areal Daerah Irigasi pelangan seluas 137
Ha tidak bisa mendapatkan air irigasi dan harus menggantungan air untuk pertanian dari air hujan.
Untuk melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Pelangan perlu dilakukan survey
Lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting jaringan Irigasi, kemudian menganalisis kebutuhan
air irigasi, merencanakan disain rehabilitasi jaringan Irigasi Pelangan dan menghitung Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Jaringan Irigasi di Pelangan.
Berdasarkan Survey Lapangan, Kondisi Jaringan Irigasi Pelangan seluas 137Ha rusak
pada bangunan pelengkapnya seperti, saluran, bangunan bagi, gorong-gorong, bangunan terjun dan
bangunan ukur, Berdasarkan Perhitungan, Kebutuhan air Irigasi tebesar untuk Irigasi pelangan
adalah 1,29 lt/dt/ha terjadi pada awal tanam November 1 dengan pola tanam padi-padi + palawija-
palawija dengan kapasitas pengambilan 1,17 m3/dt.Berdasarkan perhitungan saluran, dimensi
bangunan primer (b) 0,50 m, (h) 0,60 m, (w) 0,20 m, (m) 1,00 m, bangunan sekunder (b) 0,40 m,
(h) 0,52 m (w) 0,20 m, (m) 1,00 m, dan bangunan tersier (b) 0,30 m, (h) 0,44 m, (w) 0,20 m (m)
1,00 m. Sedangkan dimensi bangunan bagi sadap (b) 0,70 m (h) 0,49 m (w) 0,20, dan bangunan
gorong-gorong (b) 0,30 m, (h) 0,24 m, (w) 0,20.Total Biaya Konstruksi Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Pelangan sebesar Rp.6,926,480,000.00.
Kata kunci : Survey Lapangan, Kebutuhan Air Irigasi, Rencana Rehabilitasi, Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amanat dari Kepmen PU No.
390 Tahun 2007 Tentang Penetapan Status
Daerah Irigasi yang Pengelolaanya Menjadi
Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, kewenangan
pengelolaan irigasi yang diatur lebih lanjut
melalui Kepmen PU No 293 tahun 2014 tentang
Penetapan Status Daerah Irigasi yang
Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan
Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari 20
Daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang
terbagi dalam 3 Wilayah Kepengamatan yaitu
Pengamat Narmada, Pengamat Gunungsari dan
Pengamat Kediri.
Dari 20 Daerah irigasi Kewenangan kabupaten
yang ada di kabupaten Lombok Barat, terdapat
satu daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Pelangan
yang sampai saat ini tidak dapat berfungsi
karena telah terjadi banyak kerusakan-
kerusakan seperti, pintu pengatur hilang,
sedimentasi pada bangunan sadap di hulu/ hilir,
sedimentasi pada bangunan pembawa serta
sayap saluran dan bangunan ditumbuhi semak-
semak, kerusakan parah pada beberapa
bangunan talang dan bangunan bagi serta
banyak lagi kerusakan-kerusakan lainnya. akibat
dari tidak beroperasinya daerah Irigasi di
Pelangan maka areal daerah irigasi pelangan
seluas 108 Ha tidak bisa mendapatkan air irigasi
dan harus menggantungan air untuk pertanian
dari air hujan. Hal ini menyebabkan tingkat
produktivitas pertanian di Kecamatan Sekotong
juga menurun tajam. Melihat hal tersebut maka
dirasa perlu dan sangat dibutuhkan suatu
Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pelangan sehingga nantinya diharapkan produk
perencanaan rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pelangan ini bisa menjadi acuan dalam kegiatan
fisik rehabilitasi JaringanIrigasi Pelangan.
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari Skripsi ini
adalah :
1. Menginventarisir kondisi eksisting
sarana dan prasarana Jaringan Irigasi
di Pelangan?
2. MenghitungBerapakah kebutuhan Air
Irigasi di Pelangan ?
3. Merencanakan Detail Rehabilitasi
Jaringan Irigasi berdasarkan
persyaratan Teknis?
4. Menghitung Berapakah Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi
Jaringan Irigasi di Pelangan?
1.5 Batasan Masalah
Agar pembahasan lebih terarah maka
diperlukan batasan masalah untuk mencegah
melebarnya lingkup permasalahan. Adapun
batasan permasalahanya adalah sebagai berikut
:
1. Hanya Menginventarisir kerusakan –
kerusakan JaringanIrigasi saja.
2. Hanya merencanakan Rehabilitasi
Jaringan Irigasi seperti, Saluran,
Bangunan Bagi, Bangunan Sadap dan
bangunan pelengkap lainnya.
3. Tidak membahas masalah Bendung.
4. Menghitung Rencana Anggaran Biaya
(RAB)
2. DASAR TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Guntur (2012) melakukan penelitian
tentang menganalisis kebutuhan air di sawah
dengan ketersediaan di daerah irigasi batang
Anai serta merencanakan bangunan pelengkap
disepanjang saluran irigasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan grafik neraca
air dapat dikombinasikan : pada alternatif 1
terlihat kebutuhan bersih air di sawah
maksimum (Netto Field Requirement/ N.F.R)
sebesar 0,783 ltr/dtk/Ha, hasil dimensi
bangunan primer didapat dengan nilai (b) 1,50
m, (h) 0,80 m, (w) 0,20 m, (m) 1.50 m.
bangunan sekunder (b) 0,70 m, (h) 0,04 m, (w)
0,20 m, (m) 1 m. Bangunan Tersier (b) 0,55 m,
(h) 0,37 m, (w) 0,40 m, (m) 1 m. Sedangkan
bangunan pelengkap terdapat Sebanyak :
Bangunan bagi sadap sebanyak 1 lokasi,
bangunan sadap sebanyak 7 lokasi, bangunan
Terjun 1 Lokasi, bangunan talang 1 (satu)
lokasi, bangunan gorong-gorong 14 lokasi.
Imron (2012), melakukan penelitian
tentang kajian kebutuhan dan ketersediaan air
pada jaringan irigasi karangasem. Hasil
penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Nilai
Evapotranspirasi (Eto) terbesar bulan oktober
sebesar 5,474 mm/hari, sedangkan nilai Eto
terkecil pada bulan juni sebesar 3,392 mm/hari.
Consumtive Use (Etc) untuk tanaman padi pada
awal masa tanam (penyiapan lahan) merupakan
nilai Etc terbesar mendekat masa panen nilai
Etc akan menurun. Nilai Etc untuk tanaman padi
terbesar pada setengah bulan ke 1 dan 2 bulan
November sebesar 12,82 mm/hari sedangkan
nilai Etc untuk tanaman palawija terbesar pada
setengah bulan ke 2 bulan oktober sebesar 5,39
mm/hari. Curah hujan setengah bulanan rata-
rata terbesar pada setengah bualan 1 dan 2
bulan desember sebesar 340,00 mm/hari,
sedangkan curah hujan bulanan rata-rata
terkecil pada setengah bulan 1 dan 2 bulan
agustus sebesar 4,80 mm/hari. Kebutuhan air
total terbesar pada setengah bulan 1 dan 2
bulan November sebesar 3,14 mm/dtk,
sedangkan kebutuhan air total terkecil pada
setengah bulan ke 2 februari dan setengah
bualan ke 2 bulan juni serta setengah bulan ke 1
bulan Juli sebesar 0,00 m3/dtk. Ketersediaan
debit setengah bulanan rata-rata di intake per
bulan terbesar pada setengah bulan ke 1 bulan
februari sebesar 11,82 m3/dtk sedangkan
terkecil pada setengah bulan ke 1 pada bulan
oktober sebesar 1,51 m3/dtk. Dengan pola
tanam Padi-Padi (Varietes unggul FAO) –
Palawija ( Jagung), kebutuhan air di Daerah
Irigasi Pijenan masih dapat dilayani dengan
ketersediaan yang ada.
2.2 Landasan Teori
2.2.1 Evapotranspirasi
Peristiwa berubahnya air menjadi uap
dan bergeraknya dari permukaan tanah ke
udara disebut evaporasi (penguapan).Peristiwa
penguapan dari tanaman disebut transpirasi.Bila
kedua-duanya terjadi bersama-sama disebut
evapotranspirasi.
Jumlah kadar air yang hilang dari tanah oleh
transpirasi tergantung pada (Soemarto, 1986) :
1. Adanya persediaan air yang cukup (hujan
dan lain-lain),
2. Faktor-faktor iklim seperti suhu,
kelembaban dan lain-lain,
3. Tipe dan cara kultivasi tumbuh-
tumbuhan.
Evapotranspirasi merupakan faktor yang sangat
penting dalam studi pengembangan sumber
daya air dan sangat mempengaruhi debit
sungai, kapasitas waduk dan penggunaan
konsumtif (consumptive use) untuk tanaman.
2.2.2.1 Evapotranspirasi Terbatas
Evapotranspirasi terbatas adalah
evapotranspirasi aktual dengan
mempertimbangkan kondisi vegetasi dan
permukaan tanah serta frekuensi curah hujan.
Curah hujan (P) yang diambil yaitu curah hujan
bulanan dan jumlah hari hujan (n) = jumlah hari
hujan pada bulan yang bersangkutan.
Metode Penmann memberikan formulasi untuk
menghitung besarnya evapotranspirasi yaitu :
ETo = c [ W . Rn + (1-W). f(u). (ea-ed) ]
Dengan :
Eto : evapotranspirasi tanaman (mm/hari)
W : faktor temperatur
Rn : radiasi bersih (mm/hari)
f(u) : faktor kecepatan angin
(ea-ed): perbedaan antara tekanan uap air
pada temperatur rata-rata
dengan tekanan uap jenuh air (mbar)
c :faktor perkiraan dari kondisi musim
2.2.3 Analisis Kebutuhan Air
Dalam penentuan kebutuhan air irigasi
untuk tanaman adalah tergantung pada
penentuan pola tanam, yang dibuat dengan
beberapa alternatif dimana untuk mendapatkan
debit yang efisien juga diatur pembagian
golongan yang sesuai
Perhitungan air irigasi tiap hektar didasarkan
atas faktor-faktor yang bisa mempengaruhi
kebutuhan air tanaman di sawah, faktor tersebut
antara lain kriteria perencanaan :
a. Penyiapan lahan b. Kebutuhan air tanaman c. Perkolasi dan infiltrasi d. Hujan Efektif 2.2.3.1 Kebutuhan Air Tanaman
Untuk perhitungan kebutuhan tanamam
akan air maka pelaksanaannya adalah dengan
membuat terlebih dahulu pola tanam dan
pelaksanaan perhitungan adalah dengan sistem
tabel, adapun kebutuhan air bersih tanaman
dihitung dengan rumus :
NFR = ET crop + P - Re + WLR
DR = NFR / E
dimana :
NFR = Kebutuhan air bersih lapangan (mm/hari). NFR = NFR (l/dt/ha). DR = Kebutuhan air di tempat pengambilan
(l/dt/ha) Selanjutnya untuk mengetahui nilai Etc
tanaman tertentu maka Eto dikalikan dengan
nilai Kc yakni koefisien tanaman yang
tergantung pada jenis tanaman dan tahap
pertumbuhan . nilai Kc tersedia untuk setiap
tanaman .
Etc = Kc x Eto
Dimana:
Etc= Consumtive Use Kc= Koefisien Tanaman Eto = Evapotranspirasi
2.2.3.2 Perkolasi dan infiltrasi
Infiltrasi merupakan proses masuknya air dari
permukaan tanah ke dalam tanah (daerah tidak
jenuh), sedangkan perkolasi adalah masuknya
air dari daerah tidak jenuh ke dalam daerah
jenuh, pada proses ini air tidak dimanfaatkan
oleh tanaman. Untuk tujuan perencanaan,
tingkat perkolasi standar 2,0 mm/hari, dipakai
untuk mengestimasi kebutuhan air pada daerah
produksi padi.
2.2.4 Analisis Hidrolika Saluran Irigasi
2.2.4.1 Kriteria Perencanaan Saluran
Pasangan
2.2.4.1.1 Rumus Aliran
Rumus aliran yang digunakan untuk menghitung
dimensi saluran pasangan adalah Rumus
Manning, yaitu :
V= (1/N) R2/3
I1/2
R=P
A
A= (b+mh)h
P= b+2h 13 m
Q= v A
Dimana :
Q = Debit saluran, m3/dt
v = Kecepatan aliran, m/dt A = Luas Potongan melintang saluran, m
2
R = Jari-jari hidrolis, m P = Keliling basah, m b = Lebar dasar, m h = Tinggi air, m I = Kemiringan energi (kemiringan saluran) k = Koefisien kekasaran Strikler, m
1/3/dt
m=Kemiringan talud (1 vertikal : m horisontal)
2.2.4.1.2 Debit Saluran (Q)
Debit rencana saluran dihitung dengan
menggunakan rumus umum :
e
ANFRcQ
..
Dimana :
Q = Debit rencana, l/dt
`c = koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan
NFR= Kebutuhan bersih (netto) air di sawah, m.l/dt.ha
A = Luas daerah yang diairi, Ha e = Efisiensi irigasi secara
keseluruhan
2.2.4.1.3 Kecepatan Aliran (v)
Kecepatan maksimum untuk aliran subkritis
dianjurkan pada :
Pasangan batu : 2 m/dt
Pasangan beton : 3 m/dt 2.2.4.1.4 Jari-jari hidrolis (R)
Agar belokan saluran yang sudah dilining tidak
menimbulkan perubahan aliran air, maka
lengkung jari-jari minimum saluran harus diambil
sekurang-kurangnya 3 kali lebar muka air
rencana.
2.2.4.1.5 Koefisien kekasaranStrikler (k)
Tabel 2.2 Koefisien Kekasaran Strikler (k) untuk
Saluran Irigasi Pasangan
Jenis pasangan k
(m1/3
/dt)
Pasangan batu 60
Pasangan beton 70
Pasangan tanah 35 – 45
Sumber : KP-03 Bagian Saluran
2.2.4.1.6 Kemiringan Talud (m)
Tabel 2.3 Harga- harga Kemiringan Talud Saluran Pasangan pada bermaca m- macam dasar Tanah
2.24.1.7 T
inggi Jagaan (w)
Jenis Tanah H < 0,75
m
0,75 m < h < 1,5 m
Lempung pasiran
Tanah pasiran kohesif
1 1
Tanah pasiran lepas 1 1,25
Geluh pasiran, lempung berpori
1 1,5
Tanah gambut lunak 1,25 1,5
Gambar 2.1 Penampang Saluran
Sumber : KP-03 Bagian Saluran
Tinggi Jagaan minimum yang digunakan pada
saluran pasangan sesuai dengan debit rencana
yang dialirkan dapat dilihat pada Tabel dibawah
ini:
Tabel.2.4 Tinggi Jagaan Untuk Saluran Pasangan
Q (m
3/dt)
Tanggul (F) M
Pasangan (Fl) M
< 0,5 0,40 0,20
0,5 – 1,5 0,50 0,20
1,5 – 5,0 0,60 0,25
5,0 – 10,0 0,75 0,30
10,0 – 15,0 0,85 0,40
>15,0 1,00 0,50
Sumber : KP-03 Bagian Saluran
2.2.4.2 Tahapan Perhitungan Saluran
V = k x R2/3
x I1/2
A = (b x m x h) x h
P = b + 2 x h 12 m
R =P
A
Q = v x A
Adapun desain hidraulik untuk saluran yang
ada, secara umum dapat mengikuti tahapan-
tahapan sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data pengukuran saluran
yang ada.
2. Menentukan kemiringan saluran
memanjang (i) berdasarkan hasil ukur long
section, sedangkan lebar dasar saluran (b)
dan kemiringan bagian dalam saluran (m),
berdasarkan hasil ukur cross section.
3. Menghitung debit rencana (Q)
4. Menentukan koefisien kekasaran Strikler
5. Menentukan kecepatan maksimum yang
diijinkan
6. Menghitung (A.R2/3
) dari persamaan
maksimum Strikler dengan menggunakan
Qrencana dan kemiringan memanjang yang
ada (I).
7. Menghitung dengan cara uji coba secara
berulang untuk mendapatkan kedalaman
aliran
8. Memeriksa V > Vmaks, dari (7), jika terlalu
besar pilihlah kemiringan rencana (1) yang
lebih kecil dan diulangi langkah (6) sampai
dengan (8), dan bila diperlukan
ditambahkan bangunan terjun untuk
memperkecil kemiringan dasar saluran (i)
9. Kontrol balik besarnya Q yang didapat
dengan menggunakan rumus Q = V x A.
Jika besarnya sudah sama atau mendekati
sama dengan nilai koreksi yang mendekati
nol, maka uji coba dapat dihentikan.
10. Memilih tinggi jagaan (w) saluran yang
dibutuhkan.
2.2.4.4 Gorong-Gorong
debit pada gorong-gorong dihitung dengan
menggunakan persamaan :
Q = μ A gz2
Dimana :
Q = debit (m3/dt)
μ = koefisien debit A = luas pipa (m2) g = percepatan gravitasi (9,8 m/dt2) z = kehilangan energi (m) Harga koefisien debit dapat dilihat pada Tabel berikut :
Gambar 2.3 Gorong- gorong
Gambar 2.2 Talang
Tabel 2.5 Nilai Koefisien Debit (μ)
Tinggi dasar di bangunan sama dengan di saluran
Tinggi dasar di bangunan lebih tinggi daripada di saluran
Sisi Μ Ambang Sisi Μ
Segi empat
Bulat
0,80
0,90
Segi empat
Bulat
Bulat
Segi empat
Segi empat
Bulat
0,72
0,76
0,85
Sumber : KP-03 Bagian Saluran
2.2.4.5 Bangunan Bagi
Rumus yang digunakan untuk menghitung debit
yang dialirkan adalah :
Q = μ b x a gxz2
Dimana :
Q = debit yang dialirkan (m3/dt) μ = koefisien debit (0,80) b = lebar bukaan (m) a = tinggi bukaan (m) g = percepatan gravitasi (9,8 m/dt) z = kehilangan tinggi energi (0,5-0,10 m)
3. METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Jaringan Irigasi di
Pelangan yang secara administrasi berada di
daerah Pelangan Kecamatan Sekotong Barat
Kabupaten Lombok Barat.
3.2 Pengumpulan Data
1. Peta yang terdiri dari peta topografi dan peta
daerah Irigasi di daerah Pelangan
2. Data Skema Jaringan Irigasi Primer dan
Sekunder
3. Data Luas Lahan Iirigasi
4. Data Hidrologi
5. Data Klimatologi
6. Data Curah Hujan
Data curah hujan yang digunakan adalah data
curah hujan selama 19 tahun (1996-2014) yang
diperoleh dari BWS (Balai Wilayah Sungai)
7. Data-Data Teknis Daerah Irigasi Pelangan.
8. Laporan-Laporan terdahulu yang dapat
memberikan data dan informasi mengenani
disain awal Jaringan Irigasi Pelangan dan
riwayat perkembangan.
3.3 Analisa Data
Adapunlangkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menentukan Curah Hujan setengah bulanan
selama kurun waktu 19 tahun
2. Analisis Data Klimatologi
Evapotranspirasi merupakan salah satu unsur
hidrologi yang sangat penting dalam
keseluruhan proses hidrologi, terutama dalam
perhitungan ketersediaan air Irigasi. Besarnya
Evapotranspirasi dihitung dengan menggunakan
Gambar 3.1 Skema Jaringan Irigasi Pelangan
Gambar 2.6 Bangunan Bagi
Gambar 2.6 Bangunan Bagi
metode Penmann dengan memasukkan data-
data klimatologi yang ada.
3. Analisis Kebutuhan Air Tanaman
Analisis kebutuhan air tanaman bertujuan untuk
mengetahui banyaknya air yang dibutuhkan oleh
masing-masing tanaman.
4. Analisis Hidrolika Saluran Irigasi
Analisis hidrolika saluran bertujuan untuk
menghitung Kecepatan aliran, Debit saluran,
efisiensi irigasi, dan jari-jari hidrolis.
5. Mendisain Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
6. Gambar Rencana
7. Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)
3.4 Bagan Alir Penelitian
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Kondisi Eksisting DI Pelangan
Gambar 4.1 Skema Jaringan DI Pelangan
Hasil dari survey lapangan yang
dilakukan dapat dijelaskan mengenai
kondisi eksisting Jaringan Irigasi
Pelangan sebagai berikut :
4.2 Analisis Hidrologi Dan
Klimatologi
4.2.1 Data Hujan
4.2.2 Uji Konsistensi Data Curah
Hujan
Salah satu cara yang dilakukan untuk
mendeteksi penyimpangan data hujan
adalah dengan metode RAPS (Rescaled
Adjusted Partial Sums). Metode RAPS
merupakan pengujian konsistensi
dengan menggunakan data dari stasiun
itu sendiri yaitu pengujian dengan
komulatif penyimpangan terhadap nilai
rata-rata dibagi dengan akar komulatif
rerata penyimpangan kuadrat terhadap
nilai reratanya (Sri Harto, 1993).
Persamaan umum yang digunakan
adalah:
n nQ / nR /
90% 95% 99% 90% 95% 99%
10 20 30 40 50
100 >100
1,05 1,10 1,12 1,13 1,14 1,17 1,22
1,14 1,22 1,24 1,26 1,27 1,29 1,36
1,29 1,42 1,46 1,50 1,52 1,55 1,53
1,21 1,34 1,40 1,42 1,44 1,50 1,62
1,28 1,43 1,50 1,53 1,55 1,62 1,75
1,38 1,60 1,70 1,74 1,78 1,86 2,00
Dy2
= n
) X - X ( 2n
1 i
i k =
1,2,3, … , n
Sk* =
2
1
k
i
i XX
Sk** =
2
*Sk
Dy
dengan:
n = banyak tahun Xi = data curah hujan ke- i
X = rata-rata curah hujan Sk*, Sk**, Dy = nilai statistik Nilai Statistik ( Q )
Q = **
0k
nkSmaks
Nilai Statistik ( R )
R = **
0
**
0min k
nkk
nkSSmaks
Dengan melihat nilai statistik di atas,
maka dicari nilai Q/√n dan R/√n. Hasil
yang diperoleh kemudian dibandingkan
dengan nilai kritis. Jika hasilnya lebih
kecil dari tabel, maka data masih dalam
batasan konsisten dan data dapat
digunakan. Nilai Q dan R dapat dilihat
pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Nilai n
Q dan
n
R
Sumber: Harto (2009:41)
Hasil pengujian konsistensi data hujan
dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini.
Dari hasil pengujian konsistensi dapat
diketahui bahwa data hujan masih
dalam batasan konsisten sehingga data
tersebut dapat digunakan untuk analisis
selanjutnya.
Tabel 4.6 Uji Konsistensi Data Hujan Metode RAPS
n = 19
Dy = 23.32
Sk** maks = 2.26
Sk** min = -1.73
Q = | Sk** maks | = 2.26
R = Sk** maks - Sk** min = 3.99
Q/n 0.52 < 1.10 90% => Data Konsisten
Q/n 0.92 < 1.33 90% => Data Konsisten
Dari hasil uji konsistensi data
curah hujan dengan metode RAPS
dapat disimpulkan bahwa pos hujan
yang digunakan pada studi ini konsisten
atau memenuhi syarat berdasarkan nilai
kritis yang diijinkan untuk metode RAPS
Q/√ <Q/√ ijin 90 % serta R/√ <R/√
ijin 90% (pada Tabel 4.5).
4.2.3 AnalisisEvapotranspirasi
Besaran evapotranspirasi dihitung
memakai Metode Penman modifikasi
(FAO), dengan masukan data iklim
berikut: letak lintang, temperatur udara,
kelembaban relatif, kecepatan angin
dan lama penyinaran matahari.
Persamaan Penman dirumuskan
sebagai berikut:
ETo = c [ W . Rn + (1-W). f(u). (ea-ed)
]
dengan :
Eto : evapotranspirasi tanaman
(mm/hari)
W : faktor temperatur
Rn : radiasi bersih (mm/hari)
f(u) : faktor kecepatan angin
(ea-ed): perbedaan antara tekanan
uap air pada temperatur
rata-rata
dengan tekanan uap jenuh
air (mbar)
c :faktor perkiraan dari kondisi
musim
dengan :
W =y n
L
P0.386
L = 595 - 0.51 T
P = 1013 - 0.1055 E
= 2 (0.00738T+0.8072)T - 0.00116
Rn = Rns - Rn1
Rns = ( 1 - )Rs
Rs = ( 0.25 + 0.28 n/N ) Ra
Rn1 = f (r) f (ed) f(n/N) Ra
ed = ea Rh
ea = 33.8639 (( 0.00738 T + 0.8072
) 8 - 0.000019 (1.8 T + 48 ) +
0.001316 ))
c = 0.68 + 0.0095 Rh max +
0.018125 - 0.068 Ud + 0.013 Ur
+ 0.0097 Ud Ur + 0.43 10-4
Rh max Rs Ud
Ud =
U Ur
43.2 1 Ur
2
Ur =
Ud
Un
Analisis Evapotranspirasi metode
Penman (Modifikasi FAO) Daerah Irigasi
Pelangan untuk bulan Januari I adalah
sebagai berikut:
Diketahui : Elevasi rerata
D.Isekotong = + 361,49 m
Elevasi pos iklim
sekotong = 169 m
Suhu = 25,38˚C
Rh (%) = 97 %
= 249,76 km/hari
Tc (˚C) = T – 0,006 (361,49 –
169 = 24,23 ˚C
n/Nc (%) =
– 0,01 (361,49 –
169)
= 21,22 – 0,01 (361,49
– 169)=21 %
U2c = × ( Elv. Rerata
daerah irigasi/Elv. Sta. Klimatologi) (1/7)
= 249,76 × (169/361,49+2) (1/7)
= 223,87 km/hari
ea= ed × Rh
= 22,10 mbar
Beda tekanan uap = es-ea
=21,43- 20,87
=0,58
f (u) = 0,27 (
)
= 0,27 (
)
= 0,0010ed =Rh×ea)/100
= (97,42×22,10)/100
= 22,68 mbar
d = 2 × ( 0,00738 × Tc + 0,8072 )Tc
–
0,0016
= 2 × ( 0,00738 × 24,23++ 0,8072 )24,23
–
0,0016 = 1,47
W=d
d 0,386 1013-0,1055 10
595-0,510 Tc
=1,27
1,47 0,386 1013-0,1055 10
595-0,510 24,23
= 0,0009
f (T) = 11,25 × 1,0133Tc
= 11,25 × 1,013324,23
= 15,51
f (ea) = 0,34 – 0,044 × (ed0,5
)
= 0,34 – 0,044 × (22,680,5
)
= 0,11
f (n/N)= 0,10 + 0,90 × ( n/Nc ) / 100
= 0,10 + 0,90 × (21)/100
= 0,35
Del ( konstantan kemiringan tekanan
uap) / (del+ c)del= 1,47 jadi =>
1,47/(1,47+0,485)
= 0,75
c / (del + c) = 0,485/ (1,47 + 0,485)
=0,25
Angka Radiasi = 0,75×(328,41/58×(1-
0,25)
=3,19
Radiasi gelombang panjang netto
= 0,35×0,11 ×15,51×0,75
= 0,44
Angka perpindahan angin netto
= angka perpindahan angin ×c / (del + c)
= 0,25×0,0009
=0,0002
Jadi Eto ( mm/hari) =Angka Radiasi-
Radiasi gelombang panjang
netto+angka perpindahan angina netto
Jadi Eto ( mm/hari) = 3,19-0,44+0,0002
=2,75
Eto (mm/15 hari) = 2,75× 15
= 41,26
Dari hasil seluruh perhitungan
dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember diperoleh nilai Eto terbesar
pada bulan oktober I sebesar 4,66
mm/hari dan yang terkecil pada bulan
juni II sebesar 2.66 mm/hari. Hasil
perhitungan untuk seluruhnya dapat
dilihat pada Tabel 4.9.
4.2.4 Analisa Kebutuhan Air
Analisa Kebutuhan Airdimaksudkan
untuk menentukan besarnya kebutuhan
air untuk irigasi dan air minum
penduduk. Sehingga akan dapat
dilakukan simulasi operasional waduk
untuk dalam rangka optimasi embung.
Banyaknya air yang diperlukan oleh
tanaman pada suatu petak sawah
dinyatakan dalam persamaan berikut
(KP Irigasi, 1986) :
NFR = LP + ETc + P + WLR
– Re
dengan :
NFR =kebutuhan air di sawah (mm/hari)
LP =kebutuhan air untuk pengolahan
lahan (mm/hari)
ETc =kebutuhan air tanaman (consumptive
use), mm/hari
WLR =penggantian lapisan air (mm/hari)
P =perkolasi (mm/hari)
Re = curah hujan efektif (mm/hari)
Contoh perhitungan kebutuhan air Irigasi
awal tanam Nopember I untuk pola
tanam Padi – Padi+ Palawija-Palawija
adalah sebagai berikut:
Evapotranspirasi (Eto)
= 4,66 mm/hari
Evapotranspirasi selama penyiapan
lahan (Eo) = 1,1 × Eto
= 5,12 + 2,00
= 7,12 mm/hari
k = M × (T/S)
= 7,12 × (30/250)
= 0,85 mm/hari
Jangka waktu penyiapan lahan (T)
= 30 hari
Kebutuhan air penyiapan lahan (S)
= Penjenuhan + Lapisan Air
= 200 + 50 = 250 mm
Bilangan alam (e)
= 2,718
Penyiapan lahan (LP)
=
=
=12,41 mm/hari
Curah hujan efektif (R80) = 18,0
mm/hari
Curah hujan efektif padi (Reff)= 0,84
mm/hari
Curah hujan efektif palawija (Reff)
= 3,06 mm/hari
Penggantian lapisan air= 3,33 mm/hari
Penggantian lapisan air rerata (WLR)
= Penggantian lapisan air / 2
= 3,33 / 2
= 1,67 mm/hari
Koefisien tanaman Padi (C1)
= 1,10
Koefisien rerata Padi
=
=
= 1,10
Koefisien tanaman palawija (C2)
= 0,40
Koefisien rerata palawija
=
=
= 0,20
Penggunaan konsumtif Padi (ETC1)
(Untuk Desember I)
= 3,73 x 0,55
= 2,05 mm/hari
Penggunaan konsumtif palawija
(ETC2)(Untuk Maret II)
=Eto x Koefisien rerata plj.
=4,05x 0,81
= 3,28 mm/hari
NFR Padi = Etc + WLR + LP + P – Reff (Untuk Nopember.I) = 5,79 mm/hari NFR palawija = Etc – Reff P alawija (Untuk Mei II)
= 4,18 mm/hari
Kebutuhan air di sawah untuk padi
= NFR padi x 8,64
(Untuk nopember I)
= 0,67 lt/dt/ha
Kebutuhan air di sawah untuk palawija
= NFR palawija x 0,116
(Untuk Mei II)
= 0,14 lt/dt/ha
Kebutuhan air di intake untuk padi (DR)
=
(Untuk Nopember I)
= 1,03 lt/dt/ha
Kebutuhan air di intake untuk palawija
(DR) =
(Untuk Mei I)
= 0,74 lt/dt/ha
Dari hasil optimasi didapatkan awal
tanam terpilih yakni november 1 dengan
DR maksimum sebesar 1.29 lt/dt/ha,
luas areal irigasi 137.00 ha dengan
kapasitas pengambilan 0.18 m3/dt
1.29 lt/dt/ha
137
0.18 m3/dt
DR terpilih
Luas Areal
Kapasitas debit
4.3 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Pelangan
4.2.1 Perhitungan Rehab Saluran
Irigasi DI Pelangan
Perhitungan dimensi saluran dijelaskan
sebagai berikut:
Contoh perhitungan saluran INTAKE-
BP.1
Panjang saluran (l) : 60.50 m
Luas sawah (L) : 137.00 ha
q saluran (DR) : 1.29 lt/dt/ha
Q saluran : 0.18 m3/dt
Koef. Strikler (k) : 60.00
Kemiringan saluran (I) : 0.0005
Kemiringan talud (m) : 1
Lebar saluran : 0.50 m
Tinggi jagaan (fb) : 0.20 m
Perhitungan
Q = VA
A =(b x mh)h
A =(0.50 x 1x0.40)x0.40 = 0.362 m2
V =2
13
2
SRK
V = 60.00 x R2/3
*0.00051/2
R = A/p (p= keliling basah)= 0.362/p
P = b+2h 12 m
= 0.5+2x0.40 112 = 1.635 m
R = A/P = 0.362/1.635= 0.312 m
V =2
13
2
SRK
= 60 x 0.3122/3
*0.00051/2
= 0.491 m/det < 3.0 m/dt (Aman)
Q = VA
0.18 m3/det = 0.362 m
2 x 0.491 m/det
0.18 m3/det = 0.18 m
3/det Oke….
4.2.2 Skema Jaringan Irigasi
Skema jaringan irigasi DI Pelangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini
4.2.3 Bangunan Bagi
Perhitungan
Perhitungan dimensi bangunan bagi
dijelaskan sebagai berikut:
Contoh perhitungan Bangunan BP.1
Gambar 4.15 Skema Jaringan Irigasi Pelangan
Data:
Dimensi saluran
Q = 0.177 m3/dt
b = 0.700 m
h = 0.495 m
fb = 0.200 m
Dimensi bangunan bagi/sadap
z = 0.334 x 0.495 = 0.165 m
μ = 0.8
b = 0.500 m
h1 = 32
71.1 xb
Q
= 32
70.071.1
177.0
x =
0.279 m
a = 5.0)81.92( xhxxbx
Q
=
5.0)495.081.92(70.080.0
177.0
xxxx = 0.101 m
d = h-h1 = 0.495 – 0.279 =
0.216 m
Elv.1 = Elv.2 – fb = 13.555 – 0.200 =
13.355 m
Elv.2 = 52.00 + h + fb = 12.86 + 0.495
+ 0.20 = 13.555
Elv.3 = Elv. 1- h = 13.555 – 0.495 =
12.860 m
Elv.4 = Elv. 5 – fb = 13.190 + 0.200 =
13.390 m
Elv.5 = Elv. 1 – z = 13.355 – 0.165 =
13.190 m
Elv.6 = Elv. 3 – z = 12.860 – 0.165 =
12.695 m
Elv.7 = Elv. 3 – 0.300 = 12.860 –
0.300 = 12.560
Elv.8 = Elv. 1 – h1 = 13.355 – 0.279 =
13.076 m
Perhitungan dimensi bangunan bagi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.17 dan 4.18
4.2.5 Gorong-gorong perhitungan Data: Dimensi saluran Q = 0.057 m3/dt b = 0.30 m h = 0.24 m fb = 0.20 m Dimensi gorong-gorong K = 60.00 L = 4.00 m I = 0.0008 R = 2b+h = (2x0.30) + 0.24 = 0.84 m A = b x h = 0.30 x 0.24 = 0.07 m2
C = K (A/R)^1/6 = 60.00
(0.07/0.84)^1/6 = 39.91
V = C x (RI)^0.5 = 39.91 (0.84 x
0.0008) ^0.5 = 1.04 m/dt
67.024.081.9
04.1
gh
VFr
Q = A x V = 0.07 x 1.04 = 0.076
m3/dt
Kehilangan energy
DHf = (1.042 x 4.00)/(39.91
2 x 0.84)
= 0.0032
Dhmasuk = (0.25 x (1.04 - 1)2)/(2 x 9.8) =
0.00002
Dhkeluar = (0.50 x (1.04 - 1)2)/(2 x 9.8) =
0.00003
Perhitungan dimensi bangunan gorong-
gorong selengkapnya dapat dilihat pada
tabel 4.20
4.3 Menghitung Rencana Anggaran
Biaya (RAB)
Tabel 4.22. Rekapitulasi Rencana
Anggaran BiayaRehabilitasi
DI Pelangan
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan Survey, Kondisi
Jaringan Irigasi Pelangan seluas 137
rusak parah pada bangunan
pelengkapnya seperti, saluran,
bangunan bagi, gorong-gorong,
bangunan terjun dan bangunan ukur,
oleh karena itu dirasa sangat perlu
untuk direhabilitasi.
2. Berdasarkan Perhitungan,
Kebutuhan air Irigasi tebesar untuk
Irigasi pelangan adalah 1,29 lt/dt/ha
terjadi pada awal tanam November 1
dengan pola tanam padi-padi +
palawija-palawija dengan kapasitas
pengambilan 1,17 m3/dt. Sementara
kebutuhan air terkecil 0,21 lt/dt/ha.
3. Berdasarkan perhitungan saluran,
dimensi bangunan primer (b) 0,50 m,
(h) 0,60 m, (w) 0,20 m, (m) 1,00 m,
bangunan sekunder (b) 0,40 m, (h)
0,52 m (w) 0,20 m, (m) 1,00 m, dan
bangunan tersier (b) 0,30 m, (h) 0,44
m, (w) 0,20 m (m) 1,00 m.
Sedangkan dimensi bangunan bagi
sadap (b) 0,70 m (h) 0,49 m (w) 0,20,
dan bangunan gorong-gorong (b)
0,30 m, (h) 0,24 m, (w) 0,20.
4. Total Biaya Konstruksi Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Pelangan sebesar
Rp.6,926,480,000.00.
5.2. Saran
Selain kesimpulan yang telah dijabarkan
diatas, beberapa saran diperlukan guna
mendapatkan hasil yang lebih baik pada
perencanaan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Pelangan. Dari itu penulis
memberikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Banyak sekali kerusakan pada
Jaringan Irigasi Pelangan, maka dari itu
partisipasi masyarakat sangat
dibutuhkan terutama masyarakat
setempat untuk menjaga dan
memelihara Jaringan Irigasi pelangan.
2. Diharapkan dengan adanya
perencanaan Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Pelangan ini, dapat memberikan
masukan kepada Instansi terkait untuk
bisa ditindaklanjuti, sehingga areal
Irigasi Pelangan Dapat berfungsu
kembali.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1986 Standar Perencanaan
IrigasiKP-01, subdit
perencanaan Teknis Dirjen
Pengairan
Anonim. 1986 Standar Perencanaan
IrigasiKP-03, subdit
perencanaan Teknis Dirjen
Pengairan
Anonim. 1986 Standar Perencanaan
IrigasiKP-04, subdit
perencanaan Teknis Dirjen
Pengairan
Anonim, 2014, Undang-undang no.7
tahun 2014, Tentang Sumber
Daya Air, Sekretariat Negara,
Jakarta
Anonim, 2014 Peraturan Menteri
Republik Indonesia nomor: P.
61/Menhut II/ 2014. Tentang
Pedoman Monitoring dan
Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai.
Imror, 2012. Kajian kebutuhan dan keter
sediaan air pada Jaringan Irigas
Karang Asem.Muhammadiyah
Yogyakarta.
Mahendra, 2015.pengaruh ketersediaan
debit air terhadap pola tanam
daerah irigasi tibunangka di
kecamatan praya timur
kabupaten lombok tengah,
Universitas Mataram
Mawardi, E, 2007, Desain Hidraulik Ban
gunan Irigasi, Alfabeta,
Bandung.
Subarkah, I. 1980. Hidrolika untuk
Perencanaan Banguna Air. Idea
Dharma. Bnadung :
Triatmodjo, B., 1998, Hidrologi Terapan,
Beta Offset,Yogyakarta.
Triatmodjo, B., 1994. Hidrolika II. Beta
Offset, Yogyakarta.