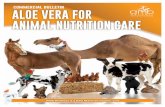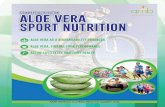pengaruh gel aloe vera terhadap jumlah cd4+ dan cd8+ pada
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of pengaruh gel aloe vera terhadap jumlah cd4+ dan cd8+ pada
PENGARUH GEL ALOE VERA TERHADAP JUMLAH CD4+ DAN CD8+ PADA
JARINGAN PERIODONTAL GIGI TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) PASCA
REPLANTASI
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Kedokteran Gigi
Oleh:
Andiani Budi Lestari
NIM: 135070400111034
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2018
vii
DAFTAR ISI
Judul ............................................................................................................... i
Halaman Persetujuan ..................................................................................... ii
Kata Pengantar ............................................................................................... iii
Abstrak ........................................................................................................... v
Daftar Isi ......................................................................................................... vii
Daftar Gambar ................................................................................................ xi
Daftar Tabel .................................................................................................... xii
Daftar Lampiran .............................................................................................. xiii
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 4
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum ..................................................................................... 4
1.3.2 Tujuan Khusus .................................................................................... 4
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis .............................................................................. 5
1.4.2 Manfaat Praktis ................................................................................... 5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Avulsi
2.1.1 Definisi ............................................................................................... 6
2.1.2 Etiologi ............................................................................................... 6
2.1.3 Pertolongan Pertama Gigi Avulsi ........................................................ 7
2.2 Replantasi
2.2.1 Definisi……………………………………………………………………….. 7
2.2.2 Tujuan Penelitian ................................................................................ 8
2.2.3 Replantasi Segera .............................................................................. 8
2.2.4 Replantasi dalam Waktu Satu Jam Setelah Avusi .............................. 9
viii
2.2.5 Replantasi Lebih dari Satu Jam Setelah Avulsi ................................... 10
2.2.6 Prognosis ........................................................................................... 11
2.3 Ligamen Periodontal ........................................................................... 12
2.4 Penyembuhan Luka ............................................................................ 12
2.4.1 Fase Penyembuhan Luka ................................................................... 13
2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka ................................ 16
2.4 Sel T CD4+ dan T CD8+ ..................................................................... 17
2.5 Inflamasi ............................................................................................. 21
2.6 Aloe Vera
2.6.1 Definisi ................................................................................................ 21
2.6.2 Jenis dan Taksonomi Aloe vera .......................................................... 22
2.6.3 Morfologi Aloe vera ............................................................................. 23
2.6.4 Kandungan Aloe vera.......................................................................... 25
2.6.4.1 Acemannan ......................................................................................... 31
2.6.5 Aloe vera sebagai Immunomodulator .................................................. 31
2.6.6 Peran Aloe vera dalam Penyembuhan Luka ....................................... 31
2.7 Anatomi Gigi Tikus .............................................................................. 34
BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Konsep ............................................................................... 35
3.2 Hipotesis Penelitian ............................................................................ 37
BAB 4 METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penilitian .......................................................................... 38
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................. 38
4.3 Sampel Penelitian
4.3.1 Kriteria Sampel ................................................................................... 39
4.3.2 Jumlah Sampel ................................................................................... 40
4.4 Variabel dan Definisi Operasional
4.4.1 Variabel Penelitian
4.4.1.1 Variabel Bebas/Independen................................................................ 41
ix
4.4.1.2 Variabel Tergantung/Dependen .......................................................... 41
4.4.1.3 Variabel Terkendali ............................................................................. 41
4.4.2 Definisi Operasional ........................................................................... 42
4.5 Alat dan Bahan Penelitian
4.5.1 Alat dan Bahan untuk pemeliharaan dan perlakuan hewan coba ........ 43
4.5.2 Alat dan Bahan untuk pembiusan hewan coba ................................... 43
4.5.3 Alat dan Bahan untuk pencabutan gigi hewan coba ............................ 43
4.5.4 Alat dan Bahan untuk perlakuan hewan coba ..................................... 43
4.5.5 Alat dan Bahan untuk pembuatan Aloe vera……………………..….... 44
4.5.6 Alat dan Bahan Pengambilan Jaringan dan Pembuatan Preparat ....... 44
4.5.7 Alat dan Bahan untuk Immunohistokimia ............................................ 45
4.6 Cara Kerja
4.6.1 Ethical Clearance ................................................................................ 45
4.6.2 Persiapan Hewan Coba ...................................................................... 45
4.6.3 Pembuatan Aloe vera …………………………………………………… 46
4.6.4 Anastesi pada Rattus norvegicus ........................................................ 47
4.6.5 Pencabutan Gigi pada Tikus ............................................................... 47
4.6.6 Prosedur Perlakuan ............................................................................ 48
4.6.7 Perawatan Tikus Pasca Pencabutan................................................... 48
4.6.8 Sacrifies pada Tikus ............................................................................ 48
4.6.9 Prosedur Pembuatan sediaan parafin blok ......................................... 49
4.6.10 Proses Deparafinisasi ......................................................................... 50
4.6.11 Immunohistokimia (IHK) ..................................................................... 50
4.7 Analisa Statistik .................................................................................. 51
4.8 Alur Penelitian ..................................................................................... 54
BAB 5 PENDAHULUAN
5.1 Hasil Penelitian ................................................................................... 55
5.2 Analisis Data ....................................................................................... 61
5.2.1 Uji Normalitas Data ............................................................................. 61
5.2.2 Uji Homogenitas Ragam ..................................................................... 62
x
5.2.3 Uji One Way Anova (Analysis of Variance) ......................................... 62
5.2.4 Uji Post-Hoc Tukey ............................................................................. 63
5.2.5 Uji Korelasi Pearson ........................................................................... 65
BAB 6 PEMBAHASAN
6 Pembahasan ....................................................................................... 68
6.1 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ pada Gigi Tikus (Rattus norvegicus) Pasca Replantasi Tanpa Pemberian Aloe vera ................ 71
6.2 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ pada Gigi Tikus (Rattus norvegicus) Pasca Replantasi Tanpa Pemberian Aloe vera ................ 72
6.3 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ Antara Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan ........................................................................... 73
BAB 7 PENUTUP
7.1 Kesimpulan ......................................................................................... 76
7.2 Saran .................................................................................................. 76
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 77
LAMPIRAN ..................................................................................................... 84
v
ABSTRAK
Lestari, Andiani Budi. 2017. Pengaruh Gel Aloe vera Terhadap Jumlah CD4+ dan CD8+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus Putih (Rattus norvegicus) Pasca Replantasi. Skripsi, Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) drg. Delvi Fitriani, M. Kes (2) drg. Yuliana R. Kumala, Sp.KG
Pada gigi avulsi terlepas dari soketnya menyebabkan terjadinya
kerusakan ligamen periodontal dan menimbulkan respon inflamasi di daerah jaringan periodontal. Perawatan yang ideal adalah replantasi. Pasca replantasi pada jaringan periodontal akan meninggalkan luka. Penggunaan gel Aloe vera dapat menjadi salah satu alternatif untuk penyembuhan luka karena kandungan antrakuinon seperti aloe emodin yang berperan sebagai antiinflamasi dengan menurunkan jumlah sel CD4+ dan CD8+. CD4+ dan CD8+ merupakan subset limfosit T yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gel Aloe vera terhadap jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi. Penelitian ini merupakan true experimental laboratory post test with control group design dengan pengamatan sebanyak 3 time series yaitu hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh. Sampel dipilih dengan teknik Simple Random Sampling kemudian dibagi menjadi kelompok perlakuan yang diberi gel Aloe vera sebelum replantasi dan kelompok kontrol yang tidak diberikan gel Aloe vera sebelum replantasi. Terdapat 24 sampel dibagi kedalam 6 kelompok. Variabel yang diteliti adalah jumlah sel CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi tikus yang diukur dengan sediaan HPA. Berdasarkan hasil uji statistik One Way ANOVA diperoleh nilai signifikansi p=0,00 (p<0,05). Uji korelasi menunjukan adanya korelasi yang kuat dengan arah korelasi negatif, sehingga semakin bertambahnya hari, maka jumlah CD4+ dan CD8+ pada gigi tikus pasca replantasi akan semakin menurun secara signifikan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Gel Aloe vera berpengaruh terhadap jumlah sel CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi.
Kata Kunci : Gel Aloe vera, CD4+, CD8+, avulsi, replantasi
vi
ABSTRACT
Lestari, Andiani Budi. 2017. Effect of Aloe vera Gel on CD4+ and CD8+ Count
on Periodontal Tissue of White Mice (Rattus norvegicus) Post Replantation. Thesis, Undergraduate Program Faculty of Dentistry Brawijaya University. Supervisor: (1) drg. Delvi Fitriani, M. Kes (2) drg. Yuliana R. Kumala, Sp.KG
When dental avulsion occurs the tooth detaches from its socket causes periodontal ligament damage and will causes an inflammatory response on the periodontal tissue. The ideal treatment is replantation. Post replantation procedure will leave some wound on the periodontal tissue. The use of Aloe vera gel can be an alternative in wound healing process because it contains anthraquinones like aloe emodin that will act as anti-inflammatory and can decrease the CD4+ and CD8+ count. This study aims to analyze the effect of Aloe vera gel on CD4+ and CD8+ count on periodontal tissues of white mice (Rattus norvegicus) post replantation. This research is true experimental laboratory post test with control group design with observation of 3 time series that is the first day, third day, and seventh day. There are 24 samples divided into 6 groups. The samples were selected by Simple Random Sampling technique and then divided into the treatment group which was given Aloe vera gel into socket before replantation, and the control group which was not given Aloe vera gel before replantation. The variables studied were the number of CD4+ and CD8+ cell count in the periodontal tissue of the mice which measured by the HPA preparats. Based on the results of One Way Anova statistical tests showed significant values p=0.00 (p <0.05). Correlation test shows there are strong bond in negative direction which shows that as the day is increasing, the CD4+ and CD8+ count in periodontal tissue of white mice post replantation will decreases significantly. The conclusions of this study were Aloe vera gel affect CD4 + and CD8+ counts in periodontal tissues of white mice (Rattus norvegicus) post replantation.
Keywords: Aloe vera gel, CD4 +, CD8 +, avulsion, replantation
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Cedera traumatik gigi didefinisikan sebagai kerusakan yang disebabkan
oleh trauma secara fisik maupun mekanik yang mengenai jaringan keras,
jaringan periodontal ataupun keduanya. Kejadian ini umum terjadi dan
perawatannya dikategorikan sebagai tindakan darurat dalam praktik dokter gigi
(Newland et al., 2007). Cedera traumatik gigi meliputi patahnya enamel gigi dan
dentin tanpa melibatkan pulpa, fraktur mahkota, fraktur akar, perubahan letak gigi
dan avulsi (Carranza, 2002). Avulsi gigi didefinisikan sebagai keluarnya seluruh
gigi dari soket akibat trauma. Gigi yang keluar dari soketnya akibat trauma
menyebabkan ligamen periodontal terputus dan suplai darah ke jaringan pulpa
terputus, sehingga pulpa gigi mengalami nekrosis dan ligamen periodontal rusak
parah (Ram & Cohenca, 2004).
Menurut Gomes (2009), perawatan yang paling ideal untuk avulsi gigi
adalah replantasi. Replantasi adalah menempatkan kembali gigi pada soketnya,
dengan tujuan mencapai pengikatan kembali bila gigi telah terlepas sama sekali
dari soketnya karena kecelakaan (McDonald et al., 2010).
Ketika gigi terlepas dari soketnya, seringkali disebabkan oleh robeknya
ligamen periodontal. Biasanya sebagian besar sel-sel ligamen periodontal akan
tertinggal di akar. Namun, karena gigi menggores soket, kerusakan kecil dan
lokal pada sementum juga terjadi. Jika ligamen periodontal yang tertinggal
menempel pada akar, permukaan tidak mengering dan akibat yang disebabkan
avulsi biasanya menjadi minimal (Trope, 2011).
2
Sel ligamen periodontal yang terhidrasi dengan baik akan
mempertahankan kelangsungan hidup mereka dan memungkinkan
penyembuhan dengan regenerasi sel ligamen periodontal saat direplantasi tanpa
menimbulkan banyak kerusakan ataupun peradangan. Selain itu, karena cidera
yang terjadi di area lokal, radang yang dirangsang oleh jaringan yang rusak akan
menjadi terbatas, artinya penyembuhan dengan penggantian sementum yang
baru kemungkinan terjadi setelah peradangan awal telah mereda. Namun,
apabila gigi avulsi tidak terhidrasi yang baik sebelum replantasi, sel ligamen
periodontal yang rusak akan menimbulkan respon inflamasi di daerah permukaan
akar yang diffuse. Berbeda dengan situasi yang dijelaskan di atas, dimana
daerah yang akan diperbaiki setelah peradangan awal responnya kecil, disini
permukaan akar yang lebih besar akan rusak sehingga harus diperbaiki oleh
jaringan baru (Trope, 2011).
Penyembuhan luka merupakan proses yang kompleks dengan melibatkan
banyak sel untuk penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak. Proses
ini terdiri dari fase inflamasi, proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi dimulai
setelah beberapa menit dan berlangsung selama sekitar 3 hari setelah cedera.
Dalam proses inflamasi terjadi perusakan, pelarutan, dan penghancuran sel atau
agen penyebab kerusakan sel (Potter & Perry, 2010). Limfosit bermigrasi
kedaerah peradangan dan mencapai jumlah yang bermakna pada hari ketiga
(Jesse, 2005). Limfosit T menghasilkan limfokin interferon-γ (IFN- γ), yang
mengaktivasi makrofag untuk mengeluarkan sitokin seperti Transforming Growth
Factor (TGF-α) yang berperan terhadap proses reepitelisasi. Makrofag
mensekresikan Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF), TNF- α dan IL-1 dan juga
bertanggung jawab atas fagositosis mikroorganisme, serta debridemen sisa
3
jaringan. Subpopulasi limfosit menunjukkan perubahan selama penyembuhan
luka: rasio limfosit T CD4+ dan CD8+ yang tinggi mencirikan stadium awal dan
saat penyembuhan berlangsung rasionya menurun. (Huttunen, 2003). Epitelial
Growth Factor (EGF), dan Insulin – like Growth Factor (IGF) bertanggung jawab
terhadap reepitelisasi dan proses proliferasi fibroblast. Platelet-Derived Growth
Factor (PDG-F), Transforming Growth Factor (TGF- ), dan Fibroblast Growth
Factor (FGF) bertanggung jawab terhadap proses proliferasi fibroblast,
angiogenesis dan reepitelisasi. Vaskular Endhotelial Growth Factor (VEGF) yang
menginduksi terjadinya angiogenesis. Peningkatan proliferasi fibroblast,
reepitelisasi dan angiogenesis akan mempercepat penyembuhan luka (Price dan
Wilson, 2006).
Aloe vera merupakan salah satu tanaman yang mempunyai daya
adaptasi tinggi. Aloe vera telah lama dijuluki sebagai tanaman obat, bahkan
master healing plant (tanaman penyembuh utama). Aloe vera memiliki manfaat
sebagai antiinflamasi, antibakteri, antijamur, peningkat aliran darah ke daerah
yang terluka dan menstimulasi fibroblas yang bertanggung jawab untuk
penyembuhan luka (Rieuwpassa, 2011). Gel Aloe vera mengandung zat fenolik
seperti antrakuinon. Kandungan aloe emodin dalam daun Aloe vera dapat
berfungsi sebagai anti inflamasi dengan menekan limfosit T sitolisis CD8+
dengan bantuan sel T supressor CD8+. Antrakuinon juga dapat menurunkan
produksi sitokin IL-2 dan TNF-α pada sel limfosit T yang teraktivasi (Rainsford et
al., 2015). Zat aktif polisakarida seperti acemannan dapat meningkatkan aktivitas
makrofag (Wiedosari, 2007).
4
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
tentang pengaruh gel Aloe vera terhadap jumlah sel CD4+ dan CD8+ pada
jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi.
1.2 Rumusan Masalah
Apakah ada pengaruh gel Aloe vera terhadap jumlah CD4+ dan CD8+
pada jaringan peridontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Mengetahui pengaruh gel Aloe vera terhadap jumlah CD4+ dan CD8+
pada jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi.
1.3.2 Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui jumlah CD4+ dan CD8+ jaringan periodontal gigi tikus
putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi yang tidak diberi gel Aloe vera
pada hari ke 1, 3 dan 7.
b. Untuk mengetahui jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi
tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi yang sudah diberi gel
Aloe vera pada hari ke 1, 3 dan 7.
c. Untuk menganalisa perbandingan jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan
periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi yang
tidak diberi gel Aloe vera pada hari ke 1, 3 dan 7.
d. Untuk menganalisa perbandingan jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan
periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi yang
sudah diberi gel Aloe vera pada hari ke 1, 3 dan 7.
5
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan data mengenai pengaruh
gel Aloe vera terhadap jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi
tikus putih (Rattus norvegicus) pasca replantasi dan dapat dikembangkan oleh
peneliti selanjutnya dalam penelitian kedokteran gigi dalam lingkup yang sama.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini untuk kedepannya dapat dijadikan informasi dalam
penanganan gigi pasca replantasi.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi mengenai pengaruh gel Aloe
vera terhadap reaksi inflamasi pasca replantasi gigi.
6
BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Avulsi
2.1.1 Definisi
Avulsi didefinisikan sebagai keluarnya seluruh gigi dari soket akibat
trauma. Secara klinik dan foto ronsen, gigi tidak ada di dalam soket (Dalimunte,
2003). Tulang alveolar, sementum, ligament periodontal, gingiva, dan pulpa akan
mengalami kerusakan pada saat gigi secara total keluar dari soketnya
(Jacobsen, 2003).
Tercabutnya gigi dari soketnya akibat trauma menyebabkan terputusnya
ligamen-ligamen periodontal dan suplai darah ke jaringan pulpa. Sebagai
akibatnya pulpa gigi mengalami nekrosis dan periodonsium rusak parah (Ram,
2004).
Gambar 2.1 Gigi anterior atas dan bawah yang mengalami avulsi (Ercan and Dalli, 2007)
2.1.2 Etiologi
Avulsi gigi akibat trauma relatif jarang terjadi dengan persentase kejadian
mulai dari 0,5% hingga 16% dari seluruh kasus trauma (Shashikiran et al., 2006).
7
Etiologi terjadinya trauma avulsi pada umumnya disebabkan oleh
kecelakaan lalu lintas, perkelahian, terjatuh, kecelakaan olahraga, kekerasan
pada anak. Avulsi yang terjadi pada usia anak sekolah seringkali terjadi pada gigi
yang masih belum mengalami maturasi secara sempurna, sehingga kerusakan
struktur gigi yang terjadi dapat menimbulkan gangguan pada pertumbuhan gigi
selanjutnya. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Quaranta et al.,
insidensi terjadinya avulsi 62% disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi di
rumah, 17% terjadi pada saat berolahraga, dan 14% terjadi di tempat lain
(Zakirulla et al., 2011).
2.1.3 Pertolongan Pertama Gigi Avulsi
Pada gigi yang avulsi prognosis terbaik didapat jika gigi segera ditanam
kembali. Jika gigi tidak dapat ditanam kembali dalam waktu 5 menit, sebaiknya
disimpan. Dalam media yang akan membantu menjaga vitalitas serat ligamen
periodontal. Tahapan yang perlu dilakukan pada saat pertolongan pertama pada
gigi avulsi adalah sebagai berikut (Walton dan Torabinejad, 2008) :
a. Bilas gigi dengan air kran mengalir yang dingin selama 10 detik
b. Jangan mengelap gigi
c. Letakkan kembali gigi dalam soketnya dengan tekanan jari yang ringan
d. Pertahankan gigi pada posisinya, bisa juga dilakukan oleh pasien sendiri
e. Cari pertolongan dokter gigi segera
2.2 Replantasi
2.2.1 Definisi
Istilah replantasi ini diartikan sebagai menempatkan kembali gigi pada
soketnya dengan tujuan mencapai pengikatan kembali bila gigi telah terlepas
sama sekali dari soketnya karena kecelakaan (Grossman, 1995).
8
2.2.2 Tujuan Perawatan
Pada gigi sulung perawatan dilakukan untuk mencegah perkembangan
cedera yang lebih lanjut pada penggantinya. Gigi sulung yang teravulsi
sebaiknya tidak ditanam kembali sebab berpotensi merusak benih gigi permanen
(Flores et al., 2007).
Sedangkan pada gigi permanen perawatan bertujuan untuk menanam
gigi sesegera mungkin dan menstabilkan gigi yang sudah di replantasi pada
lokasi anatomis yang benar untuk mengoptimalkan penyembuhan dari ligamen
periodontal dan suplai neurovaskular sambil mempertahankan integritas estetika
dan fungsional, kecuali ketika replantasi terdapat kondisi yang merupakan kontra
indikasi dari replantasi, yaitu (Flores et al., 2007) :
a. Tahap perkembangan gigi anak (risiko ankilosis dimana pertumbuhan
alveolar cukup tinggi)
b. Mengompromikan kondisi medis
c. Mengompromikan integritas gigi yang teravulsi atau jaringan pendukung.
Fleksibel splinting selama 2 minggu diindikasikan. Profilaksis tetanus dan
cakupan antibiotik harus dipertimbangkan (Flores et al., 2007). Strategi
perawatan diarahkan untuk menghindari peradangan yang mungkin terjadi
sebagai akibat kerusakan gigi dan infeksi pulpa (McIntyre et al., 2009).
2.2.3 Replantasi Segera
Jika dilakukan replantasi segera setelah avulsi, maka prognosisnya
semakin baik. Ketika pasien avulsi datang ke praktik dokter gigi dengan kondisi
giginya sudah dimasukkan kembali di tempat cedera, hendaknya dokter gigi
memeriksa baik secara klinik maupun radiologik untuk memeriksa hasil
replantasi yang dilakukannya. Selain itu, periksa juga cedera lain yang mungkin
9
terjadi pada gigi tetangga atau antagonisnya dan stabilitas serta letak gigi yang
direplantasikan tersebut (Walton dan Torabinejad, 2008).
2.2.4 Replantasi dalam Waktu Satu Jam Setelah Avulsi
Jika replantasi segera tidak bisa dilakukan, maka pasien dapat dibawa ke
klinik. Media transport terbaik yang dapat digunakan adalah salin fisiologis. Jika
salin fisiologis tidak tersedia, maka pasien dapat menggunakan susu sebagai
alternatif yang sangat baik. Selain itu, pasien juga dapat menggunakan saliva
sebagai media transportasi sementara air tidak bisa digunakan karena air tidak
bisa mempertahankan kevitalan sel permukaan akar (Walton dan Torabinejad,
2008).
Tahapan yang dilakukan ketika pasien tiba di klinik (Walton dan
Torabinejad, 2008) :
a. Gigi diletakkan pada cawan yang berisi salin fisiologis.
b. Segera lakukan rontgen pada daerah yang terkena cedera untuk melihat
apakah ada fraktur alveolus atau tidak.
c. Lokasi avulsi diperiksa dengan saksama untuk mengetahui ada-tidaknya
serpihan tulang yang harus dibuang. Jika alveolusnya telah runtuh maka
soket dikuakkan dengan instrumen.
d. Soket diirigasi dengan menggunakan salin untuk membuang koagulum
yang terkontaminasi. Lakukan dengan hati-hati.
e. Pada cawan salin, mahkota gigi diangkat dengan menggunakan tang
ekstraksi agar akarnya tidak terkena.
f. Periksa gigi apakah masih mengandung debris, jika masih ada bersihkan
dengan menggunakan kasa yang dibasahi salin.
10
g. Masukkan kembali gigi ke dalam soketnya. Setelah sebagian sudah masuk,
teruskan dengan menekannya perlahan-lahan dengan jari atau pasien
disuruh menggigit kasa sampai giginya kembali ke posisi semula.
h. Ketepatan letak gigi dalam lengkung diperiksa dan koreksi jika ada yang
mengganjal. Luka-luka di jaringan lunak dijahit, terutama di bagian servikal.
i. Gigi distabilkan selama 1 sampai 2 minggu dengan splin.
j. Dianjurkan untuk memberikan antibiotik kepada pasien dengan dosis yang
sama seperti untuk infeksi mulut yang ringan sampai moderat. Injeksi
tetanus penguatan juga dianjurkan jika pemberian tetanus terakhir
dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu.
k. Pasien diberikan perawatan penunjang. Diet lunak dan analgesik diberikan
sesuai dengan keperluan.
2.2.5 Replantasi Lebih dari Satu Jam Setelah Avulsi
Jika gigi telah berada di luar soket lebih dari satu jam dan tidak terjaga
kebasahannya dalam medium yang sesuai, maka sel dan serabut ligamen
periodontium tidak akan bertahan hidup. Oleh karena itu, dapat dilakukan
perawatan sebelum replantasi meliputi pemberian fluor pada permukaan akar
untuk mengurangi (melambatkan) proses resorpsinya (Walton dan Torabinejad,
2008).
Tahapan yang perlu dilakukan ketika pasien tiba di klinik (Walton dan
Torabinejad, 2008) :
a. Periksalah daerah avulsi dan periksa juga gambaran radiografinya untuk
melihat ada-tidaknya fraktur alveolus.
b. Bersihkan debris yang melekat pada permukaan gigi.
11
c. Celupkan gigi ke dalam larutan NaF 2,4% (diasamkan sampai pH 5,5)
selama 5-20 menit.
d. Ekstirpasi pulpa dan saluran akarnya dibersihkan, dibentuk dan diobturasi
seraya giginya dipegang memakai kasa yang dibasahi fluor.
e. Bersihkan soket alveolus dari bekuan darah dengan menyedotnya secara
hati-hati. Kemudian soketnya diirigasi dengan salin. Mungkin perlu untuk
dianestesi terlebih dahulu.
f. Replantasikan gigi dengan hati-hati ke dalam soketnya, letakkan dengan
tepat di lengkungnya dan kontaknya.
g. Pasang splin pada gigi untuk 3 sampai 6 minggu.
2.2.6 Prognosis
Prognosis pada gigi permanen bergantung pada pembentukan
perkembangan akar dan waktu kering pada ekstraoral (Flores et al., 2007). Gigi
memiliki prognosis terbaik jika segera ditanam kembali (Andreasen and
Andreasen, 2007). Jika gigi tidak dapat ditanam kembali dalam waktu 5 menit,
sebaiknya disimpan dalam media yang akan membantu menjaga vitalitas serat
ligamen periodontal (Sigalas et al., 2004). Media penyimpanan terbaik adalah
cairan fisiologis untuk gigi avulsi meliputi Viaspan™, Hank’s Balanced Salt
Solution (media kultur jaringan) dan susu dingin. Untuk media penyimpanan non-
fisiologis lainnya, seperti air liur (disimpan di vestibulum bukal), garam fisiologis,
atau air (Barrett et al., 2005). Meskipun air dapat memberikan efek yang
merugikan viabilitas sel (osmolalitas rendah) dan untuk penyimpanan jangka
panjang (yaitu lebih dari 20 menit) penyimpanan di air dapat memberikan efek
buruk pada penyembuhan ligamen periodontal. Namun hal ini tetap merupakan
pilihan yang lebih baik daripada penyimpanan kering. Risiko ankylosis meningkat
12
secara signifikan dengan waktu kering pada ekstraoral selama 20 menit
(Donaldson and Kinirons, 2005). Waktu kering ekstraoral 60 menit dianggap
sebagai titik di mana kelangsungan hidup sel periodontal akar tidak mungkin
terjadi (Trope, 2002). Pada gigi permanen yang teravulsi, terdapat resiko yang
cukup besar untuk terjadinya nekrosis pulpa, resorpsi akar, dan ankilosis (Barrett
et al., 2005).
2.3 Ligamen Periodontal
Serat periodontal atau ligamen periodontal, biasa disingkat PDL adalah
sekelompok serat jaringan ikat khusus yang pada dasarnya melekatkan gigi ke
tulang alveolar. Serat ini membantu gigi mengatasi gaya tekan alami substansial
yang terjadi selama mengunyah dan tetap tertanam dalam tulang. Fungsi dari
PDL antara lain pendukung jaringan, sensori, suplai nutrisi, homeostatis dan
erupsi (Wolf and Rateitschak, 2005).
Struktur dari PDL terdiri dari sel, dan fiber ekstraseluler. Sel nya meliputi
fibroblas, epitel, undiffrentitated mesenchymal cells, sel tulang dan sementum.
Kompartemen ekstraseluler terdiri dari serat bundel kolagen. Substansi PDL
telah diperkirakan menjadi 70% air dan diperkirakan memiliki efek yang signifikan
pada kemampuan gigi untuk menahan tekanan. PDL adalah bagian dari
periodonsium yang menyediakan lekatan dari gigi ke tulang alveolar sekitarnya.
Tampilan PDL ialah ruang periodontal 0,4-1,5 mm pada radiografi, area
radiolusen antara radiopak lamina dura dari tulang alveolar dan radiopak
sementum (Wolf and Rateitschak, 2005).
2.4 Penyembuhan Luka
Penyembuhan luka adalah respon tubuh terhadap berbagai cedera
dengan proses pemulihan yang kompleks dan dinamis yang menghasilkan
13
pemulihan anatomi dan fungsi secara terus menerus (Joyce M. Black,
2006).
2.4.1 Fase Penyembuhan Luka
Penyembuhan luka melibatkan integrasi proses fisiologis. Sifat
penyembuhan pada semua luka sama, dengan variasinya bergantung
pada lokasi, keparahan dan luasnya cedera. Kemampuan sel dan jaringan
melakukan regenerasi atau kembali struktur normal melalui pertumbuhan
sel juga mempengaruhi penyembuhan luka.
Penyembuhan terjadi dalam beberapa tahap yang terdiri dari:
a. Fase inflamasi
Fase inflamasi merupakan awal dari respon perlindungan tubuh terhadap
adanya luka. Inflamasi membatasi area luka dan menjadi barrier imun yang
melindungi tubuh dari kemungkinan infeksi yang muncul selanjutnya dan
menghalau zat asing berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh dengan
adanya fagosit dari leukosit. Ketika luka muncul tubuh merespon dengan
mensekresikan histamin yang bertujuan untuk vasodilatasi pembuluh darah dan
peningkatan permeabilitas pembuluh darah di area luka (Sinno, 2013).
Leukosit pertama yang akan muncul adalah Poli morfo nuklear
(PMN) adalah sel pertama yang menuju ke tempat terjadinya luka.
Jumlahnya meningkat cepat dan mencapai puncaknya pada 24 – 48 jam.
Fungsi utamanya adalah memfagositosis bakteri yang masuk. Aktivitas
PMN akan berubah beberapa hari kemudian setelah semua bakteri
penyebab infeksi telah difagositosis. Apoptosis akan terjadi pada PMN
setelah semua bakteri dieliminasi. Elemen imun seluler yang berikutnya
14
adalah makrofag. Sel ini turunan dari monosit yang bersirkulasi, terbentuk
karena proses kemotaksis dan migrasi. Muncul pertama 48 – 96 jam
setelah terjadi luka dan mencapai puncak pada hari ke-3. Makrofag
berumur lebih panjang dibanding dengan sel PMN dan tetap ada di dalam
luka sampai proses penyembuhan berjalan sempurna (Velnar, 2009).
Setelah itu akan muncul limfosit T dengan jumlah bermakna pada hari
ketiga setelah cedera (Jesse, 2005). Limfosit T menghasilkan limfokin
interferon-γ (IFN- γ), yang mengaktivasi makrofag untuk menghasilkan
faktor pertumbuhan seperti Transforming Growth Factor (TGF-ά) yang
berperan terhadap proses reepitelisasi. Epitelial Growth Factor (EGF),
danInsulin – like Growth Factor (IGF) yang bertanggung jawab terhadap
reepitelisasi dan proses mitogen fibroblast. Platelet-Derived Growth Factor
(PDG-F), Transforming Growth Factor (TGF- ), dan Fibroblast Growth
Factor (FGF) yang bertugas terhadap proses mitogen fibroblast,
angiogenesis dan reepitelisasi. Vaskular Endhotelial Growth Factor
(VEGF) yang menginduksi terjadinya angiogenesis. Peningkatan
proliferasi fibroblast, reepitelisasi dan angiogenesis akan mempercepat
penyembuhan luka (Robbins, 2013).
b. Fase Proliferasi (Regenerasi)
Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia, yang berlangsung
sejak akhir fase inflamasi sampai sekitar akhir minggu ketiga. Pada fase
ini, sel fibroblas berproliferasi (memperbanyak diri). Fibroblas
menghasilkan mukopolisakarida, asam amino dan prolin yang merupakan
15
bahan dasar kolagen yang akan mempersatukan tepi luka. Fase ini
dipengaruhi oleh substansi yang disebut growth factor. Pada fase ini
terjadi proses angiogenesis, yaitu proses pembentukan kapiler baru untuk
menghantarkan nutrisi dan oksigen ke daerah luka. Angiogenesis
distimulasi oleh suatu growth factor yaitu TNF-α2 (Tumor Necrosis Factor-
alpha2). Setelah itu terjadi granulasi, yaitu pembentukan jaringan
kemerahan yang mengandung kapiler pada dasar luka dengan
permukaan yang berbenjol halus (jaringan granulasi) lalu terjadi fase
Kontraksi dimana, tepi-tepi luka akan tertarik ke arah tengah luka yang
disebabkan oleh kerja miofibroblas sehingga mengurangi luas luka.
Proses ini kemungkinan dimediasi oleh TGF-β (Transforming Growth
Factor-beta), setelah fase kontraksi terjadi proses re-epitelisasi yang
merupakan proses pembentukan epitel baru pada permukaan luka. Sel-
sel epitel bermigrasi dari tepi luka mengisi permukaan luka. EGF
(Epidermal Growth Factor) berperan utama dalam proses ini (Orsted and
Keast, 2011).
c. Fase Maturasi (Remodelling)
Maturasi, yang merupakan tahap akhir proses penyembuhan luka, fase
ini berlangsung dari hari ke 7 sampai dengan 1 tahun tergantung pada
kedalaman dan keluasan luka. Fase maturasi ditandai dengan adanya
pematangan epitelisasi, pematangan angiogenesis, pembentukan jaringan
granulasi, dan deposisi kolagen. Mekanisme epitelisasi yang terjadi yaitu dengan
proliferasi sel-sel epitel di bawah luka, sel-sel epitel bermigrasi dari bawah luka
ke atas kemudian membentuk epidermis normal kembali. Neovaskularisasi
16
berguna untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen ke area luka untuk menjaga
proliferasi jaringan granulasi terjadi dengan semestinya, serta berguna untuk
memfasilitasi makrofag dan fibroblast untuk lebih mudah bergerak ke area luka.
Makrofag berfungsi untuk terus mensekresikan growth factor dan fibroblast
berfungsi untuk mensintesis, mendeposisi, dan remodeling matriks ekstraseluler
(Sinno, 2013).
Fase maturasi yang telah selesai ditandai oleh terbentuknya jaringan
parut bahkan terkadang terbentuk jaringan keloid pada bekas luka yang telah
sembuh .Hal ini terjadi karena penyembuhan luka terjadi secara repair bukan
terjadi secara regenerasi. Fase maturasi terjadi pada 14-20 hari pasca terjadinya
luka (Flanagan, 2005).
2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka
Penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks dan
dinamis karena merupakan suatu kegiatan bioseluler dan biokimia yang
terjadi saling berkesinambungan. Proses penyembuhan luka tidak hanya
terbatas pada proses regenerasi yang bersifat lokal saja pada luka,
namun dipengaruhi pula oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik
(Indonesia Enterostomal Therapy Nurse Association, 2004), yaitu :
1. Faktor Instrinsik adalah faktor dari penderita yang dapat berpengaruh dalam
proses penyembuhan meliputi: usia, status nutrisi dan hidrasi, oksigenasi
dan perfusi jaringan, status imunologi, dan penyakit penyerta (hipertensi,
DM, dan arthereosclerosis).
17
2. Faktor Ekstrinsik adalah faktor yang didapat dari luar penderita yang dapat
berpengaruh dalam proses penyembuhan luka, meliputi: pengobatan,
radiasi, stres psikologis, infeksi, iskemia dan trauma jaringan.
2.4 Sel T CD4+ dan T CD8+
Sistem yang berfungsi melindungi tubuh manusia dari unsur-unsur
patogen disebut sistem imun. Sistem imun terdiri dari komponen genetik,
molekuler dan seluler yang berinteraksi secara luas dalam merespon antigen
endogenus dan eksogenus. Salah satu jenis sel yang berfungsi dalam merespon
antigen adalah limfosit (Baratawidjaja, 2002).
Sel limfosit merupakan sel dengan inti yang besar dan bulat serta
memiliki sedikit plasma. Pada manusia diperkirakan sekitar 3.5×1010 limfosit
setiap hari masuk ke dalam sirkulasi darah. Menurut Guyton (1998), persentase
limfosit di dalam darah putih adalah sekitar 30%. Limfosit mampu bertahan hidup
selama bertahun-tahun. Menurut Alberts B et al. (2002), sel limfosit berperan
dalam sistem perlindungan tubuh dengan mensintesis dan mensekresi antibodi
atau immunoglobulin ke dalam jaringan darah sebagai respon terhadap
keberadaan benda asing. Sel limfosit selain dalam darah, terdapat pula pada
organ limfoid seperti limpa, kelenjar limfe dan timus (Baratawidjaja, 2000).
Sistem imun pada manusia terdapat dalam sel darah putih, tepatnya
pada limfosit. Di dalam limfosit terdapat sel T yang berperan penting terhadap
kekebalan selular. Sel T mampu membedakan jenis sel asing dengan
kemampuan berevolusi sepanjang waktu demi peningkatan kekebalan setiap kali
tubuh terpapar oleh sel asing. Ada beberapa jenis sel T, diantaranya adalah sel T
CD4+ dan sel T CD8+. Sel T CD4+ merupakan jenis sel T helper yang disintesis
di dalam kelenjar timus, sel ini akan terbawa oleh sirkulasi darah hingga masuk
18
ke dalam limpa dan bermigrasi ke dalam jaringan limfatik, kemudian bermigrasi
kembali ke dalam sirkulasi darah, hingga suatu saat terjadi stimulasi oleh antigen
tertentu dengan ikatan pada molekul MHC kelas II. Sedangkan sel T CD8+
merupakan sel T sitotoksik yang dapat menghancurkan sel tumor, dan sel yang
terinfeksi virus serta dapat pula menyerang sel dan jaringan yang
ditransplantasikan. Sel T CD8+ memiliki glikoprotein CD8+ pada permukaan sel
yang mengikat antigen MHC kelas I (Roitt, 2001).
Gambar 2.2 MHC Kelas I dan II yang membatasi sel T-helper dan sel T sitotoksik (Roitt, 2011)
Sel limfosit T atau sel T merupakan 65-80% dari jumlah limfosit yang ada
dalam sirkulasi darah. Dalam perkembangannya di timus, sel T mengekspresikan
berbagai macam antigen permukaan seperti CD4+ dan CD8+. Namun dalam
perkembangan selanjutnya, sebagian antigen itu menghilang dan sebagian lagi
menetap menandai subset sel T (Kresno, 2010).
Sel yang kehilangan antigen CD4+ tetapi tetap menunjukkan antigen
CD8+ akan menjadi sel T suppresor (Ts) dan sel T sitotoksik (Tc). Sedangkan sel
yang kehilangan CD8+ tetapi tetap menunjukkan CD4+ akan menjadi sel T
19
helper (Th). Berdasarkan antigen permukaannya, maka sel Ts dan Tc lebih
dikenal sebagai CD8+, sedangkan sel Th lebih dikenal sebagai CD4+ (Semba,
2008). Semua subset sel T ditandai oleh molekul protein CD3 (Roitt, 2001).
CD8+ merupakan sel Ts (T-suppresor), yaitu sel penekan, yang
mengakhiri tanggapan kekebalan atau proses inflamasi. Sel CD8+ juga
merupakan sel Tc (T sitotoksik), yaitu sel pembunuh, karena sel tersebut
membunuh sel-sel yang telah termutasi (sel kanker) dan sel-sel yang telah
terinfeksi virus (Ajani et al., 1998). Mekanisme pembunuhan sel yang terinfeksi
virus oleh sel Tc dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3 Mekanisme pembunuhan sel yang terinfeksi virus oleh sel T sitotoksik (Roitt, 2011)
Sel CD4+ dapat dibedakan dari sel CD8+ berdasarkan protein tertentu
yang ada di permukaan sel. Sel CD4+ adalah sel-T yang mempunyai protein
CD4+ pada permukaannya (Roittt, 2011). CD4+ yang merupakan penanda
permukaan sel Th adalah rantai protein glikosilat tunggal dengan berat molekul
sekitar 55-62 kDA. Ada 2 jenis sel Th yang dikelompokkan berdasarkan
fungsinya, yaitu sel Th1 yang berfungsi untuk produksi IL-2 dan IFNγ yang
berkaitan dengan fungsi sitotoksisitas (aktivasi makrofag) dan inflamasi lokal.
20
Aktivasi makrofag oleh sel Th dapat dilihat pada Gambar 6. Sel Th yang lainnya
adalah sel Th2 yang berfungsi untuk produksi IL- 4, IL-5, IL-6 dan IL-10 yang
dapat memberikan sinyal positif pada sel B sehingga sel B dapat menghasilkan
antibodi.
Gambar 2.4 Aktivasi sel Th oleh makrofag (Roitt, 2011)
CD4+ merupakan protein penanda sel Th yang dapat meningkatkan
aktivasi dan maturasi sel B dan sel T sitotoksik serta dapat mengatur reaksi
peradangan menahun yang spesifik terhadap antigen melalui stimulasi makrofag.
Molekul CD4+ membentuk ikatan tambahan dengan MHC kelas II pada antigen.
Kadar normal CD4+ dalam darah orang dewasa berkisar 500-1500 sel/mm3
darah atau sekitar 20-40% dari jumlah total limfosit. Ada juga yang menyebutkan
jumlahnya sekitar 31-61% dari jumlah total limfosit. Sedangkan kadar normal
CD8+ dalam darah orang dewasa berkisar 375-1100 sel/mm3 darah atau sekitar
18- 39% dari jumlah total limfosit (WHO, 2008). CD4+ dan CD8+ mempunyai
peran yang saling melengkapi satu sama lain. CD4+ menghasilkan sitokin yang
dapat mengaktifkan makrofag dan meningkatkan IL2 untuk mengaktifkan CD8+,
yang akhirnya dapat menghancurkan sel yang terinfeksi (Roitt, 2001).
21
2.5 Inflamasi
Inflamasi adalah respon fisiologis tubuh terhadap suatu injuri dan
gangguan oleh faktor eksternal Inflamasi terbagi menjadi dua pola dasar.
Inflamasi akut adalah radang yang berlansung relatif singkat, dari beberapa
menit sampai beberapa hari, dan ditandai dengan perubahan vaskular, eksudasi
cairan dan protein plasma serta akumulasi neutrofil yang menonjol. Inflamasi
akut dapat berkembang menjadi suatu inflamasi kronis jika agen penyebab injuri
masih tetap ada. Inflamasi kronis adalah respon proliferatif dimana terjadi
proliferasi fibroblas, endotelium vaskuler, dan infiltrasi sel mononuklear (limfosit,
sel plasma dan makrofag). Respon peradangan meliputi suatu suatu perangkat
kompleks yang mempengaruhi perubahan vaskular dan selular (Sudiono, 2003).
2.6 Aloe vera
2.6.1 Definisi
Aloe vera merupakan salah satu jenis obat-obatan popular asli Afrika,
yang termasuk golongan Liliaceae. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang ini, memperluas pemanfaatan khasiat Aloe vera.
Pemanfaatan Aloe vera kini tidak hanya terbatas pada tanaman hias saja tetapi
juga sebagai obat dan bahan baku pada industri kosmetika (Kusmawati, 2009).
Aloe vera adalah tanaman yang semua bagian tumbuhannya bermanfaat,
pelepah Aloe vera dapat dikelompokan menjadi 3 bagian yang dapat digunakan
untuk pengobatan antara lain; daun, keseluruhan daunnya dapat digunakan baik
secara langsung atau dalam bentuk ekstrak, kemudian eksudat, adalah getah
yang keluar dari dalam saat dilakukan pemotongan, eksudat ini berbentuk kental
berwarna kuning dan rasanya pahit. Kemudian gel, adalah bagian yang berlendir
yang diperoleh dengan cara menyayat bagian dalam daun. Di dalam gel Aloe
22
vera ini dipercaya mengandung berbagai zat aktif dan enzim yang sangat
berguna untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Karena kandungan zat aktif
dan enzim inilah maka sifat gel ini sangat sensitif terhadap suhu, udara dan
cahaya, serta sangat mudah teroksidasi sehingga mudah berubah warna
menjadi kuning hingga coklat (Furnawanthi, 2004).
Aloe vera telah lama dijuluki sebagai tanaman obat, bahkan master
healing plant, (tanaman penyembuh utama). Gel Aloe vera memiliki aktivitas
sebagai antibakteri, antijamur, peningkat aliran darah ke daerah yang terluka dan
penstimulasi fibroblast yang bertanggung jawab untuk penyembuhan luka.
Publikasi pada American Pediatric Medical Association menunjukan bahwa
pemberian gel Aloe vera pada hewan coba, baik dengan cara diminum ataupun
dioles pada permukaan kulit, dapat mempercepat penyembuhan luka
(Rieuwpassa, 2011).
2.6.2 Jenis dan taksonomi Aloe vera
Terdapat lebih dari 350 jenis Aloe vera yang termasuk dalam suku
liliaceae. Disamping itu tidak sedikit Aloe vera yang merupakan hasil persilangan.
Ada tiga jenis Aloe vera yang dibudidayakan secara komersial di dunia, yakni
Curacao Aloe atau Aloe vera (Aloe Berbadensis Miller), Cape Aloe atau Aloe
Ferox Miller, dan Socotrine Aloe yang salah satunya adalah Aloe Perryi Baker
(Furnawanthi, 2007). Aloe vera yang banyak dimanfaatkan adalah spesies Aloe
Barbadensis Miller yang ditemukan oleh Philip Miller, seorang pakar botani yang
berasal dari Inggris, pada tahun 1768. Aloe berbadensis Miller mempunyai
beberapa keunggulan, diantaranya tahan hama, ukurannya lebih panjang, yakni
dapat mencapai 121 cm, berat perbatangnya dapat mencapai 4 kg, dan
mengandung 75 nutrisi. Disamping itu, Aloe vera ini aman dikonsumsi, karena
23
mengandung zat polisakarida (terutama glukomannan) yang bekerja sama
dengan asam amino esensial dan sekunder serta bagian enzim. Aloe
barbadensis Miller mempunyai nama sinonim yang binomial yakni Aloe vera dan
Aloe vulgaris. Klasifikasi Aloe vera adalah sebagai berikut (Banvard dan Elaine,
2003) :
Kingdom : Plantae
Filum : Anthophyta
Kelas : Monocotyledonae
Sub kelas : Liliidae
Ordo : Liliales
Famil : Aloeaceae
Genus : Aloe
Spesies : Barbadensis
Jenis yang banyak dikembangkan di Asia termasuk Indonesia, adalah
Aloe chinensis Baker, yang berasal dari Cina, tetapi bukan tanaman asli Cina.
Jenis ini di Indonesia sudah ditanam secara komersial di Kalimantan Barat dan
lebih dikenal dengan nama lidah buaya Pontianak, yang dideskripsikan oleh
Baker pada tahun 1877 (Furnawanthi, 2007).
2.6.3 Morfologi Aloe Vera
Gambar 2.5 Aloe vera (Jatnika dan Saptoningsih, 2009)
24
a. Akar
Tanaman Aloe vera berakar serabut pendek dan tumbuh menyebar di
batang bagian bawah tanaman (tumbuh kearah samping). Akibatnya, tanaman
mudah tumbang karena akar tidak cukup kuat menahan beban daun Aloe vera
yang cukup berat. Panjang akarnya mencapai 30-40 cm (Jatnika dan
Saptoningsih, 2009).
b. Batang
Umumnya batang Aloe vera tidak terlalu besar dan relative pendek
(sekitar 10 cm). Penampakan batang tidak terlihat jelas karena tertutup oleh
pelepah daun. Jika pelepah daun Aloe vera telah dipotong (dipanen) beberapa
kali, batang akan tampak dengan jelas (Jatnika dan Saptoningsih, 2009).
c. Daun
Letak daun Aloe vera berhadap-hadapan dan mempunyai bentuk yang
sama, yakni daun tebal dengan ujung yang runcing mengarah ke atas. Daun
memiliki duri yang terletak di tepi daun. Setiap jenis Aloe vera yang satu dan
yang lain memiliki penampakan fisik daun yang berbeda (Jatnika dan
Saptoningsih, 2009).
d. Bunga
Bunga Aloe vera memiliki warna bervariasi, berkelamin dua (bisexual)
dengan ukuran panjang 50-70 mm. Bunga ini berbentuk seperti lonceng, terletak
di ujung atau suatu tangkai yang keluar dari ketiak daun dan bercabang. Panjang
tangkai 50-100 cm dan bertekstur cukup keras serta tidak mudah patah. Bunga
Aloe vera mampu bertahan 1-2 minggu. Setelah itu, bunga akan rontok dan
tangkainya mongering (Jatnika dan Saptoningsih, 2009).
25
e. Biji
Biji dihasilkan dari bunga yang telah mengalami penyerbukan.
Penyerbukan biasanya dilakukan oleh burung atau serangga lainnya. Namun,
jenis Aloe barbadensis dan Aloe chinensis tidak membentuk biji atau tidak
mengalami penyerbukan. Kegagalan ini diduga disebabkan oleh serbuk sari steril
(pollen sterility) dan ketidaksesuaian diri (self incompatibility). Karena itu, kedua
jenis tanaman ini berkembang biak secara vegetative melalui anakan (Jatnika
dan Saptoningsih, 2009).
2.6.4 Kandungan Aloe vera
Tanaman Aloe vera mengandung 99-99,5 % air, dengan pH rata-rata 4,5
yang mengandung Acemannan. Acemannan adalah fraksi karbohidrat terbanyak
di dalam gel, merupakan polimer mannose rantai panjang yang larut dalam air,
berguna untuk mempercepat penyembuhan, memodulasi fungsi imun
(mengaktivasi makrofag dan produksi sitokin), antineoplastik dan antivirus
(Wiedosari, 2007).
Kandungan dan fungsi dari zat aktif yang terdapat pada tanaman Aloe
vera menurut Fumawanthi (2004) antara lain adalah Lignin mempunyai
kemampuan penyerapan yang tinggi sehingga memudahkan peresapan gel ke
dalam kulit atau mukosa; Saponin mampu membersihkan dan bersifat antiseptik,
serta bahan pencuci yang baik; Anthraguinone sebagai bahan laksatif,
penghilang rasa sakit, mengurangi racun, dan sebagai antibiotik; Acemannan
sebagai anti virus, anti bakteri, anti jamur, dan dapat meghancurkan sel tumor,
serta meningkatkan daya tahan tubuh; Enzim Bradykinase dan Karbiksipeptidase
sebagai anti inflamasi, anti alergi, dan dapat mengurangi rasa sakit;
Glukomannan dan Mukopolysakarida memberikan efek imunomodulasi; Tannin
26
dan Aloctin A sebagai anti inflamasi; Salisilat menghilangkan rasa sakit dan anti
inflamasi; Asam Amino sebagai bahan untuk pertumbuhan dan perbaikan, serta
sebagai sumber energy. Aloe vera menyediakan 20 asam amino dari 22 asam
amino yang dibutuhkan oleh tubuh; Mineral yang memberikan ketahanan tubuh
terhadap penyakit; Vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, E dan asam folat sebagai
bahan penting untuk menjalankan fungsi tubuh secara normal dan sehat.
Tabel 2.1 Ringkasan komposisi dari Aloe vera
Kelas Komposisi Kegunaan
Antrakuinon /
anthrone
Aloe-emodin, asam-aloetic,
anthranol, barbaloin, isobarbaloin,
emodin, ester dari asam cinnamic.
Aloin dan emodin
berfungsi sebagai
analgesic, antibakteri
dan antivirus.
Karbohidrat Mannan murni, mannan
terasetilasi, glukomanan asetat,
glukan galactomannan, glukan,
galactogalacturan,
arabinogalactan, zat
pecticgalactoglucoarabinomannan,
xylan, selulosa.
Mengandung
glikoprotein dengan
sifat anti alergi, disebut
alprogen dan senyawa
anti-inflamasi.
Chromones 8-C-glusoly-(2’-O-cinnamoly)
-7-O-methylaloediol A,
8-C-glucosyl-(S)-aloesol,
8-C-glucosyl-7-O-methylaloediol A,
8-C-glucosyl-7-0-methylaloediol,
8-C-glucosyl-noreuhenin,
isoaloeresin D, isorabaichromone,
neoalosin A.
Mengandung zat anti-
inflamasi terbaru.
Enzim Alkali fosfatase, amilase,
bradikinase, Carboxypeptidase,
katalase, Siklooksidase,
siklooksigenase, lipase, oksidase,
fosfoenolpiruvat, karboksilase,
Bradikinase membantu
mengurangi inflamasi
berlebihan bila
diaplikasikan pada kulit
secara topical,
27
superoksida dismutase. sementara zat lain
membantu dalam
pemecahan gula dan
lemak.
Komposisi
inorganic
Kalsium, klorin, kromium, tembaga,
besi, magnesium, mangan, kalium,
fosfor, sodium, seng.
Zat tersebut sangat
penting dalam berbagai
sistem enzim pada jalur
metabolism yang
berbeda dan beberapa
antioksidan.
Protein Lektin dan substansi mirip lektin Juga mengandung
asam salisilat yang
memiliki anti-inflamasi
dan sifat antibakteri.
Lignin, sebagai zat
inert, ketika
dimasukkan dalam
persiapan topical,
meningkatkan efek
penetrasi bahan lain
kedalam kulit. Saponin
yang merupakan zat
sabun sekitar 3% dari
gel berfungsi sebagai
pembersih dan
antiseptik.
Vitamin Vitamin A, B12, C, E, kolim dan
asam folat
Vitamin A, C, E, berfungsi sebagai anti oksidan yang menangkal radikal bebas
Hormon Auksin dan giberelin Membantu dalam penyembuhan luka dan sebagai anti-inflamasi
(Sumber : Mogaddhasi S, Verma SK, 2011)
28
Aloe vera memiliki cairan bening seperti jeli dan cairan berwarna
kekuningan yang mengandung aloin. Cairan ini berasal dari lateks yang terdapat
di bagian luar kulit Aloe vera. Cairan yang mengandung aloin ini banyak
dimanfaatkan sebagai obat pencahar komersial. Daging Aloe vera mengandung
lebih dari 200 komponen kimia dan nutrisi alami yang secara bersinergi dan
menghasilkan khasiat tertentu. Berikut ini merupakan komponen kimia yang
terkandung dalam Aloe vera.
Tabel 2.2 Komponen kimia Aloe vera berdasarkan manfaatnya
Zat Manfaat
Lignin Memiliki kemampuan penyerapan yang
tinggi yang memudahkan peresapan gel ke
kulit sehingga mampu melindungi kulit dari
dehidrasi dan menjaga kelembapan kulit.
Saponin - Memiliki kemampuan membersihkan
(aspetik)
- Sebagai bahan pencuci yang sangat
baik
Komplek antharaquinon aloin,
barbaloin, iso-barbaloin,
anthranol, aloe emodin,
anthracene, aloetic acid, asam
sinamat, asam krisophanat,
eterat oil, dan resistanol
- Bahan laksatif
- Penghilang rasa sakit
- Mengurangi racun
- Senyawa antibakteri
- Mempunyai kandungan antibiotic
Kalium dan Natrium - Memelihara kekencangan muka dan otot
tubuh
- Regulasi dan metabolism tubuh dan
penting dalam pengaturan impuls saraf
Kalsium Membantu pembentukan dan regenerasi
tulang
Seng (Zn) Bermanfaat bagi kesehatan saluran air
kencing
29
Asam folat Bermanfaat bagi kesehatan kulit dan
rambut
Vitamin A Berfungsi untuk oksigenasi jaringan tubuh,
terutama kulit dan kuku
Vitamin B1, B2, B6, B12, C, E,
Niacinamida, dan Kolin
Berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh
secara normal dan sehat
Enzim oksidase, amylase,
katalase, lipase, dan protease
- Mengatur berbagai proses kimia dalam
tubuh
- Menyembuhkan luka dalam dan luar
Enzim protease bekerja sama
dengan glukomannan
Penghilang rasa nyeri saat luka
Asam krisofan Mendorong penyembuhan kulit yang
mengalami kerusakan
Mono dan polisakarida
(Selulosa, glukosa, mannose,
dan aldopentosa)
- Memenuhi kebutuhan metabolism tubuh
- Berfungsi untuk memproduksi
mukopolisakarida
Salisilat
Mukopolysakarida
- Anti inflamasi dan menghilangkan rasa
sakit
- Memberi efek imonomodulasi
Tennin, Aloctin A Sebagai anti inflamasi
Indometasin Mengurangi edema
Asam Amino Untuk pertumbuhan dan perbaikan serta
sebagai sumber energy. Aloe vera
menyediakan 20 dari 22 asam amino yang
dibutuhkan tubuh
Mineral Memberikan ketahanan tubuh terhadap
penyakit dan berinteraksi dengan vitamin
untuk fungsi tubuh
(Sumber : Jatnika dan Saptoningsih, 2009)
30
Tabel 2.3 Komponen bioaktif yang terkandung pada Aloe vera L.
Komponen Bioaktif Fungsionalitas
Acemannan Anti-inflammatory, wound healing, anti-kanker, anti virus, UV sunburn
Glikoprotein Anti-diabetes, anti-kanker
Aloe emodin Anti-kanker, anti-mikroba
Lectin Anti-inflammatory, wound healing, anti-kanker
Barbaloin dan komponen fenolik (Flavonoid)
Anti-mikroba
Alomicin Anti-kanker
(Sumber : Kismaryanti, 2007) 2.6.4.1 Acemannan
Aloe vera terdiri dari berbagai macam senyawa yang dapat dibagi
menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, gula kompleks
(diantaranya acemannan), berada di dalam gel daun dan memiliki kemampuan
untuk merangsang kekebalan. Kelompok kedua, antrakuinon, yang terkandung di
bagian terluar dari kulit yang dapat berfungsi sebagai pencahar yang kuat
(Bassetti A, 2005).
Aloe vera mengandung acemannan. Acemannan adalah karbohidrat
kompleks yang memiliki rantai sangat panjang. Acemannan yang terkandung
dalam Aloe vera mempunyai aktivitas antiinflamasi imunosupresi serta
antioksidan karena menghambat aktivitas mediator inflamasi yaitu bradykinin
(Yagi A., 2003).
Acemannan (acetylated mannosa) merupakan salah satu komponen
polisakarida yang memiliki aktifitas antimikroba dengan kemampuannya
menstimulasi leukosit fagositik. mampu untuk memulihkan dan meningkatkan
kekebalan tubuh dengan merangsang produksi makrofag dan meningkatkan
aktifitas limfosit T. Acemannan juga menghasilkan agen kekebalan tubuh seperti
31
interferon dan interleukin yang membantu dalam menghancurkan virus, bakteri,
dan sel-sel tumor (Kathuria, 2011).
2.6.5 Aloe vera sebagai Imunomodulator
Dari penelitian diketahui, apabila acemannan diinkubasi bersama
suspense monosit, respon limfosit T akan meningkat terhadap lektin dan akan
meningkatkan sekresi IL-1. Selanjutnya diketahui bahwa, acemannan
merupakan fraksi karbohidrat yang diisolasi dari gel daun Aloe vera dapat
menstimulasi makrofag cell line RAW 264, menyebabkan peningkatan produksi
sitokin IL-6 dan TNF-a, pelepasan nitrit oksida, ekspresi molekul permukaan dan
perubahan morfologi dari sel makrofag (Wiedosari, 2007).
Sebagai imunodulator, Aloe vera dapat meningkatkan aktivitas anti-
kanker pada pengobatan menggunakan melatonin. Acemannan meningkatkan
aktivitas makrofag dari sistem imun sistemik terutama dalam darah dan limpa
serta meningkatkan produksi NO makrofag. Fraksi karbohidrat dari gel Aloe vera
(acemannan) dapat meningkatkan produksi IL-12 dan maturasi dari sel dendritic
sehingga sel dendritic sebagai antigen presenting cell (APC) dapat meningkatkan
ekspresi molekul major histocompability complex (MHC) kelas II, dengan
demikian fungsi limfosit ThCD4++ menjadi optimal (Wiedosari, 2007).
2.6.6 Peran Aloe vera dalam Penyembuhan Luka
Aloe vera memiliki sistem penghambat yang menghalangi rasa sakit dan
peradangan serta sistem stimulasi yang meningkatkan penyembuhan luka.
Pengujian laboratorium independen tentang Aloe vera menunjukkan aktivitas
Aloe vera dalam modulasi antibodi dan kekebalan seluler. Topikal steroid
biasanya digunakan untuk memblokir peradangan akut dan kronis. Mereka
menurunkan edema dengan mengurangi permeabilitas kapiler, vasodilatasi dan
32
menstabilkan membran lisosom. Aloe vera dapat merangsang pertumbuhan
fibroblas untuk meningkatkan penyembuhan luka dan menghalangi penyebaran
infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sekitar 1% dari steroid dapat
menembus stratum korneum kulit, dan 99% terbuang. Data penelitian ini
menunjukkan bahwa Aloe vera dapat bertindak sebagai kendaraan bagi steroid
untuk meningkatkan penyerapan dan bertindak sebagai pembawa yang efisien.
Penggunaan Aloe vera adalah pertimbangan ekonomi yang signifikan.
Kompleksitas komponen Aloe vera, membuat studi penelitian tentang aktifitas
inflamasi dari Aloe vera sebagai sebuah tugas yang sulit (Davis, 2006).
Aloe vera tidak memiliki mekanisme tunggal. Aloe vera mengandung
asam amino seperti phenylalanine dan trytophane yang memiliki aktifitas anti-
inflamasi. Asam salisilat dalam Aloe vera mencegah biosintesis prostaglandin
dari asam arakidonat. Hal ini menjelaskan bagaimana tanaman ini dapat
mengurangi vasodilatasi dan mengurangi efek vaskular dari histamin, seretonin
dan mediator inflamasi lainnya. Prostaglandin memainkan peran integral dalam
mengatur baik peradangan dan reaksi kekebalan tubuh. Aloe vera dapat
mempengaruhi kedua sistem ini dengan memblokir sintesis prostaglandin. Efek
analgesik Aloe vera sinergis dengan aspirin. Aloe vera memiliki komponen
stimulasi dan penghambatan. Aloe vera dapat memodulasi baik reaksi kekebalan
maupun reaksi inflamasi. Aloe vera dapat bertindak sebagai stimulator
penyembuhan luka dan produksi antibodi. Aloe vera dapat memblokir sintesis
prostaglandin dan memodulasi produksi limfosit dan makrofag derivat mediator
(limphokinins) termasuk interleukins dan interferon. Aloe vera disamping memiliki
efek pada reaksi inflamasi dan reaksi kekebalan, juga mengurangi oksigen
radikal bebas yang dihasilkan oleh PMN. Vitamin C dalam Aloe vera
33
menghambat peradangan, mengambil radikal oksigen untuk memblokir proses
inflamasi. Vitamin E, yang dikenal sebagai anti oksidan, juga merupakan
komponen Aloe vera. Efek-efek biologis dari karya orkestra Aloe vera,
bekerjasama dengan konduktor (polisakarida) menghasilkan efek terapi yang
berharga (Davis, 2006).
Komponen yang kurang diserap stratum korneum membutuhkan
kendaraan untuk membantu mereka dalam penetrasi. Penelitian menunjukkan
bahwa Aloe vera membantu dalam penyerapan vitamin C dan menambah
aktivitas biologisnya. Aloe vera dapat melarutkan senyawa larut air serta zat larut
lipid. Selain itu dapat melalui membran sel stratum korneum untuk membantu
berbagai bahan dalam menembus kulit. Aktivitas biologis Aloe vera dapat
bertambah, bahkan bersinergi dengan banyak agen dalam meningkatkan efek
terapi (Davis, 2006).
Penelitian yang dilakukan oleh Meitha Widurini, seorang staf pengajar
Biologi Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, menggunakan
Aloe vera konsentrasi 100% yang diaplikasikan pada radang mukosa mulut
tikus, ternyata dapat menurunkan radang mukosa mulut tikus. Didapatkan hasil
bahwa Aloe vera tidak mempunyai mekanisme tunggal sebagai anti inflamasi.
Tanaman ini mengandung berbagai macam unsur dan zat yang dipercaya dapat
bertindak sebagai agen anti-inflamasi, antara lain asam salisilat vitamin,
polisakarida dan asam lemak. Disamping itu terdapat pula indometasin yang
dapat mengurangi edema, menghambat enzim siklo-oksigenase dan
menghambat motilitas dari dari leukosit poly morpho nuklear (PMN) yang bila
jumlahnya berlebihan dapat merusak jaringan. Dikatakan pula bahwa
sebenarnya daun Aloe vera yang berkhasiat sebagai pengobatan tradisional dan
34
dapat menyembuhkan penyakit atau kelainan pada tubuh adalah hasil dari
interaksi keseluruhan unsur-unsur pokok yang terkandung dalam Aloe vera dan
bila masing-masing unsur tersebut dipisahkan maka khasiat atau manfaatnya
akan berkurang (Widurini, 2003).
2.7 Anatomi Gigi Tikus
Tikus galur Wistar merupakan hewan mamalia yang sering digunakan
dalam percobaan dengan perlakuan secara konvensional. Tikus galur Wistar
dapat digunakan mewakili mamalia termasuk manusia karena mempunyai alat
pencernaan, kebutuhan nutrisi dan homestatis serupa manusia (Smith, 2000).
Tikus putih telah digunakan secara efektif sebagai hewan coba untuk
mempelajari keadaan biologi dan patologi dari jaringan rongga mulut. Spesies ini
telah berguna dalam penelitian dokter gigi untuk menjelaskan informasi biologi
yang berharga untuk membuktikan pengertian dari mekanisme dasar proses
penyakit, untuk eksperimen secara klinik dan epidemiologi yang dimaksud untuk
memberikan informasi yang dapat diaplikasikan secara langsung pada manusia
(Smith, 2007).
Insisivus adalah gigi yang berada paling depan pada mamalia. Pada
tikus, terdapat 4 buah, panjang, tajam, dua rahang atas, dan dua dirahang
bawah. Insisivus tikus memiliki fungsi untuk menggigit. Akarnya terbuka yang
berarti akan terus tumbuh selama tikus masih hidup. molar adalah gigi yang
berada dibelakang pada rongga mulut dan digunakan untuk mengahancurkan
atau menghaluskan makanan untuk ditelan. Tikus memiliki 12 molar, 6 buah
rahang atas dan bawah. Molar tidak pernah dihilangkan. Tikus hanya memiliki
satu fase gigi dalam hidupnya (monophydont) (Sharon, 2005). Tikus memiliki
35
jarak yang lebar antara gigi insisivus dan molar pada rongga mulut yang disebut
dengan diastema dikarenakan tikus tidak memiliki gigi Caninus dan Premolar.
Jumlah gigi yang berbeda pada spesies ini dapat dijelaskan dengan dentl
formula, yang ditulis dengan i n/n C n/n P n/n M n/n, dimana I, C, P, dan M
mempresentasikan gigi Insisivus, Caninus, Premolar, dan Molar serta n/n
mempresentasikan jumlah gigi pada rahang atas dan bawah pada tiap sisi
rahang. Sehingga formula untuk gigi tikus adalah I 1-1, C 0-0, P 0-0, M 3-3. Tikus
memiliki 8 gigi pada rahang atas dan bawah, totalnya 16 gigi (Hirotaka, 2007).
Gambar 2.6 Anatomi Gigi Tikus (Hirotaka, 2007)
35
BAB 3
KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN
3.1 Kerangka Konsep
IL-12
IL-2
Gigi Avulsi
Inflamasi
Replantasi
Luka pasca
replantasi
Aktivasi Limfosit
Th CD4+ ↓
Aktivasi Makrofag ↑ IFN-ɣ
Gel Aloe vera
mengandung
antrakuinon
Proliferasi
fibroblas ↑
Angiogenesis ↑
Penyembuhan luka
pasca replantasi
↑
Keterangan:
= variabel yang
diteliti
= variabel yang
tidak diteliti
= mempengaruhi
= tidak diteliti
↓ = menurun
↑ = meningkat
Gambar 3.1 Bagan Kerangka Konsep
Aktivasi Limfosit
Ts CD8+ ↓
Reepetelisasi ↑
36
Pada kasus avulsi, gigi terlepas dari soketnya dan menyebabkan
kerusakan ligamen periodontal, seringkali disebabkan oleh robeknya ligamen
periodontal dan menimbulkan inflamasi. Perawatan yang paling ideal untuk avulsi
gigi adalah replantasi. Replantasi adalah menempatkan kembali gigi pada
soketnya, dengan tujuan mencapai pengikatan kembali bila gigi telah terlepas
sama sekali dari soketnya karena kecelakaan.
Pasca prosedur replantasi pada jaringan periodontal gigi tikus akan
meninggalkan luka. Terdapat tiga fase karakteristik proses penyembuhan luka
yang berlangsung saling tumpang tindih, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan
fase remodelling. Fase inflamasi dimulai setelah beberapa menit dan
berlangsung selama sekitar 3-5 hari setelah cedera. Limfosit bermigrasi
kedaerah peradangan dan mencapai jumlah yang bermakna pada hari ketiga.
Limfosit T menghasilkan limfokin interferon-γ (IFN- γ), yang mengaktivasi
makrofag untuk mengeluarkan sitokin seperti TGF-α yang berperan terhadap
proses reepitelisasi. Makrofag mensekresikan BFGF, TNF- α dan IL-1 dan juga
bertanggung jawab atas fagositosis mikroorganisme, serta debridemen sisa
jaringan. Subpopulasi limfosit menunjukkan perubahan selama penyembuhan
luka, rasio limfosit-T CD4+ atau CD8+ yang tinggi mencirikan stadium awal dan
saat penyembuhan berlangsung, rasionya menurun. CD4+ dan CD8+
mempunyai peran yang saling melengkapi satu sama lain. CD4+ menghasilkan
sitokin yang dapat mengaktifkan makrofag dan meningkatkan IL-2 untuk
mengaktifkan CD8+, yang akhirnya dapat menghancurkan sel yang terinfeksi.
Gel Aloe vera disini berperan sebagai anti inflamasi yang disebabkan oleh
kandungan zat fenolik seperti antrakuinon. Kandungan aloe emodin dalam daun
Aloe vera dapat berfungsi sebagai anti inflamasi dengan menekan limfosit T
37
sitolisis CD8+ dengan bantuan sel T supressor CD8+. Antrakuinon juga dapat
menurunkan produksi sitokin IL-2 pada sel limfosit T yang teraktivasi. Zat aktif
polisakarida seperti acemannan dapat meningkatkan aktivitas makrofag. Gel
Aloe vera juga menstimulasi aktifitas fibroblas dan proliferasi kolagen yang
bertanggung jawab atas proses penyembuhan luka.
3.2 Hipotesis Penelitian
Gel Aloe vera dapat mempengaruhi jumlah CD4+ dan CD8+ pada
jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar pasca
replantasi.
38
BAB 4
METODE PENELITIAN
4.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian true experimental laboratory post test
with control group design secara in vivo dengan menggunakan hewan coba
Rattus novergicus dibagi kedalam 6 kelompok.
Gambar 4.1 Penentuan Sampel
Keterangan : a. Kelompok 1 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit namun tidak mendapatkan perlakuan.
Variabel diamati pada hari 1.
b. Kelompok 2 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit namun tidak mendapatkan perlakuan.
Variabel diamati pada hari 3.
c. Kelompok 3 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit namun tidak mendapatkan perlakuan.
Variabel diamati pada hari 7.
39
d. Kelompok 4 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit dan diberi gel Aloe vera dengan dosis 2
mg/ml. Variabel diamati pada hari 1
e. Kelompok 5 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit dan diberi gel Aloe vera dengan dosis 2
mg/ml. Variabel diamati pada hari 3.
f. Kelompok 6 : Tikus dilakukan ekstraksi gigi Insisif kanan atas dan direplantasi
dalam waktu 60 menit dan diberi gel Aloe vera dengan dosis 2
mg/ml. Variabel diamati pada hari 7.
4.2 Tempat dan waktu penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi, Laboratorium
Biokimia dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya,
di Malang. Penelitian dijadwalkan pada bulan Agustus - November 2017.
4.3 Sampel penelitian
4.3.1 Kriteria Sampel
Hewan coba dalam penelitian ini adalah tikus jenis Rattus norvegicus
galur wistar yang dipelihara di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran
Universitas Brawijaya Malang. Pemeliharaan dilakukan dalam kandang yang
bersih. Sampel penelitian dipilih berdasarkan ketentuan:
Kriteria Inklusi :
a. Jenis kelamin jantan (untuk menghindari efek hormonal yang lebih dominan
pada tikus betina)
b. Usia 2,5 – 3 bulan
c. Berat badan 175 – 250 gram
40
d. Sehat, ditandai dengan gerakannya yang aktif, mata jernih, dan bulu yang
tebal dan berwarna putih mengkilap
Kriteria Eksklusi :
a. Tikus yang selama penelitian tidak mau makan
b. Tikus yang pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya
c. Tikus mengalami keradangan gusi
d. Tikus dengan pertumbuhan gigi abnormal
e. Tikus yang kondisinya menurun atau mati selama penelitian berlangsung
Tikus galur Wistar dipilih sebagai sampel karena tikus merupakan hewan
coba yang tergolong jinak, mudah perawatannya dan fungsi metabolismenya
mirip dengan manusia. Lalu sampel di bagi kedalam enam kelompok dengan
teknik simple random sampling.
Gambar 4.2 Tikus jantan Rattus norvegicus galur Wistar (Estina, 2010)
4.3.2 Jumlah Sampel
Jumlah sampel yang diperlukan untuk masing-masing kelompok
perlakuan dihitung berdasarkan rumus Federer (Purawisastra, 2001), yaitu :
(n – 1) (p – 1) 15
Keterangan: n = replikasi sampel
p = banyaknya perlakuan
41
Dalam penelitian ini ada 6 jenis perlakuan sehingga berdasarkan rumus tersebut
jumlah sampel tiap kelompok adalah sebagai berikut:
(n – 1) (p – 1) 15
(n – 1) (6 – 1) 15
(n – 1) 5 15
5n – 5 15
n 4
Dari rumus tersebut diperoleh replikasi sampel sebanyak 4 ekor tikus untuk
masing-masing kelompok. Jadi penelitian ini memerlukan tikus sebanyak 24
ekor.
4.4 Variabel dan Definisi Operasional
4.4.1 Variabel Penelitian
4.4.1.1 Variabel bebas/Independen
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gel Aloe vera dengan dosis 2
mg/ml.
4.4.1.2 Variabel tergantung/Dependen
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah CD4+ dan CD8+ pada
jaringan periodontal gigi tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar pasca avulsi
pada hari ke 1, 3, dan 7.
4.4.1.3 Variabel terkendali
Variabel terkendali adalah umur, jenis kelamin dan berat badan tikus,
makanan dan minuman tikus, perawatan dan sanitasi kandang, jenis anastesi,
jumlah anastesi, waktu pemberian anastesi, lama pencabutan, alat untuk
42
mencabut, soket bekas pencabutan, dosis gel Aloe vera dan cara pemberian gel
Aloe vera.
4.4.1.4 Definisi Operasional
a. Replantasi
Pada gigi insisif rahang atas kanan tikus dilakukan dengan menggunakan
klem yang dimodifikasi khusus untuk pencabutan gigi tikus dengan cara
menggoyang gigi tersebut memakai lecron yang dimodifikasi sebagai bein.
Setelah gigi terlepas dari soketnya lalu difiksasi dengan wire dengan diameter
0,4 mm.
b. Gel Aloe vera
Merupakan cairan kental tidak berwarna yang terdapat di dalam daun
Aloe vera. Gel Aloe vera diperoleh dengan cara proses maserasi menggunakan
pelarut etanol 96% dengan asumsi konsentrasi awal adalah 100%. Ekstrak yang
telah dibuat kemudian dibuat menjadi gel menggunakan propilen glikol,
trietanolamin, dan natrium benzoat sebagai basis gel hingga terbentuk gel Aloe
vera dengan konsentrasi 20%. Sediaan daun Aloe vera diperoleh dan
diidentifikasi dari Balai Penelitian Materia Medika Batu, Jawa Timur. Diberikan
pada gigi tikus dalam dosis 2mg/ml.
b. Sel CD4+
Merupakan glikoprotein transmembran berantai tunggal yang ditemukan
pada subset sel T (helper atau inducer) yang mewakili 45% limfosit darah perifer.
Jumlah sel T CD4+ dinilai dengan skor histologi dengan pemeriksaan
imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi sel T CD4+ dengan
pewarnaan metode streptavidin-biotin pada preparat eksisi biopsi jaringan.
Penghitungan sel limfosit yang tampak ekspresi sel berbentuk bulat atau oval
43
berwarna coklat dengan inti biru dan sitoplasma coklat untuk memperoleh
ekspresi sel T CD4+.
Gambar 4.3 Sel T CD4+ pada pewarnaan Immunohistokimia dengan perbesaran 400x (Romani et al., 2017).
c. Sel CD8+
Jumlah sel T CD8+ dinilai dengan skor histologi dengan pemeriksaan
imunohistokimia menggunakan monoklonal antibodi sel T CD8+ dengan
pewarnaan metode streptavidin-biotin pada preparat eksisi biopsi jaringan.
Penghitungan sel limfosit yang tampak ekspresi sel berbentuk bulat atau oval
berwarna coklat dengan inti biru dan sitoplasma coklat sebagai nilai untuk
memperoleh ekspresi sel T CD8+.
Gambar 4.4 Sel T CD8+ pada pewarnaan Immunohistokimia dengan perbesaran 400x (Zhu et al., 2017).
44
4.5 Alat dan Bahan Penelitian
4.5.1 Alat dan Bahan untuk pemeliharaan dan perlakuan hewan coba
a. Kandang plastik ukuran 50 cm x 40 cm x 15 cm yang ditutup dengan kawat
kassa dan dialasi sekam.
b. Botol minum.
c. Timbangan untuk menimbang berat badan tikus.
4.5.2 Alat dan Bahan untuk pembiusan hewan coba
a. Dysposible syringe ukuran 1 ml sebanyak 1 buah untuk Ketalar tiap tikus
b. Ketalar dengan dosis 60 mg/kg BB
c. Diazepam dengan dosis 10 mg/kg BB
4.6.3 Alat dan Bahan untuk pencabutan gigi hewan coba
a. Klem yang telah dimodifikasi khusus untuk pencabutan gigi insisive tikus
b. Pinset kecil dengan ujung bengkok
c. Lecron yang dimodifikasi sebagai bein
d. Needle holder untuk penjahitan soket
e. Gunting.
f. Kapas dan kassa
4.5.4 Alat dan Bahan untuk perlakuan hewan coba
a. Syringe ukuran 3 ml dengan ujung jarum (ukuran 5) tumpul untuk
mengaplikasikan gel Aloe vera.
b. Syringe ukuran 1 ml tanpa jarum untuk mengambil darah tikus.
c. Cawan mortar untuk tempat mencampur gel dan darah tikus.
d. Gel Aloe vera dengan dosis 2 mg/ml
e. Wire dengan diameter 0,4 mm
4.5.5 Alat dan Bahan untuk pembuatan Gel Aloe vera
45
a. Aloe vera (Aloe barbadensis Miller)
b. Alkohol 96%
c. Kalsium hipoklorit
d. Juicer
e. Pisau
f. Kertas saring
g. Vacuum dryer
h. Tabung steril
4.5.6 Alat dan Bahan Pengambilan Jaringan dan Pembuatan Preparat
a. Scalpel no.11
b. Pinset
c. Tabung fiksasi berlabel
d. Gelas ukur
e. Object glass dan deck glass
f. Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 95%, 96%, 100%
g. Formalin 10%
h. Kapas yang diberi eter 10%
i. Xylol
j. Paraffin
k. Alat cetak paraffin
l. Dissposable syringe (1ml)
m. Rotari mikrotom
4.5.7 Alat dan Bahan untuk Immunohistokimia
a. PBS pH 7,4
b. Blocking endogenous peroksida (H2O2 3%)
c. Blocking unspesifik protein (FBS 5%)
46
d. anti TNF-
e. antibodi sekunder biotin conjugated
f. SA-HRP (Strep-Avidin Horseradis Peroxide)
g. Betazoid DAB chromogen solution (Biocare)
h. Hematoxylin
i. Mikroskop Nikon eclipse E100
4.6 Cara Kerja
4.6.1 Ethical Clearance
Penelitian ini diawali dengan pengurusan ethical clearance di Komisi Etik
Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.
4.6.2 Persiapan Hewan Coba
a. Tikus diadaptasikan dalam kandang kurang lebih selama 1 minggu pada
temperatur konstan (20-25 ºC). Tikus dipelihara dalam kandang plastik
ukuran 50 cm x 40 cm x 15 cm yang ditutup dengan kawat kassa dan dialasi
sekam yang diganti tiap minggu. Selama proses tersebut, dijaga agar
kebutuhan makan dan air minum tetap terpenuhi. Tikus diberi makan berupa
pellet dan minum ad libitum. Makanan diberikan 2 kali sehari saat pagi dan
sore hari.
b. Tikus dipuasakan selama (12-18) jam sebelum perlakuan, namun air minum
tetap diberikan (ad libitum) (Parveen et al., 2007; Rajavel et al., 2007).
c. Berat badan tiap tikus ditimbang dan dikelompokkan menjadi 6 kelompok
secara acak dengan jumlah masing-masing kelompok adalah 4 ekor.
47
4.6.3 Pembuatan Gel Aloe vera
Sebelumnya telah dilakukan penelitian pendahuluan tentang cara
pembuatan Aloe vera. Dengan demikian metode pembuatan gel Aloe vera
adalah sebagai berikut gel Aloe vera diperoleh dengan cara proses ekstraksi-
pengendapan yang merupakan cara untuk mengambil zat aktif (Acemannan)
yang terdapat dalam Aloe vera. Bahan baku yang digunakan adalah lendir Aloe
vera yang diperoleh dari tanaman Aloe vera. Selain itu ada beberapa bahan lain
yang digunakan yaitu alkohol 96% sebagai pengendap polisakarida dan kalsium
hipoklorit untuk membuat larutan pencuci Aloe vera.
Setelah Aloe vera dipotong dari tanamannya segera dicuci dengan
menggunakan larutan kalsium hipoklorit, dikupas dan dipotong kecil untuk
dimasukkan dalam juicer. Proses pencucian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menghilangkan kotoran dan bakteri yang terdapat pada permukaan Aloe vera.
Jus Aloe vera yang diperoleh diambil untuk kemudian ditambahkan dengan
alkohol 96%, dalam hal ini 50 cc jus Aloe vera ditambahkan dengan 200 cc
alkohol 96%.
Campuran jus Aloe vera dan alkohol tersebut diaduk selama 10 menit
pada suhu 30oC, kemudian didiamkan untuk proses pengendapan selama 10 jam
pada suhu 10oC. Endapan yang terbentuk dipisahkan dari larutannya dengan
menggunakan kertas saring untuk selanjutnya endapan tersebut dioven pada
vaccum (vacuum dryer) dengan suhu 50oC. Metil-paraben 0,2 gram dilarutkan
kedalam propilen-glikol 16,7 gram kemudian carbomer sebanyak 3 gram
ditambahkan pada campuran sambil terus diaduk dengan cepat hingga terbentuk
sediaan gel, lalu disimpan pada temperatur kamar selama 24 jam (Dewi, 2012).
48
4.6.4 Anestesi Pada Rattus norvegicus
Sebelum dilakukan pembiusan, tikus ditimbang terlebih untuk
menyesuaikan dosis anestesi. Malam sebelumnya tikus tidak diberi makan dan
minum. Tikus dianestesi dengan Ketalar dengan dosis 60 mg/kg BB dicampur
dengan Diazepam 10 mg/kgBB menggunakan syringe berukuran 1 ml secara
intraperitoneal. Setelah dilakukan anestesi, tikus akan menunjukkan gejala tidak
sadarkan diri yang ditandai dengan reflek kumis dan bulu mata yang menghilang
dan dilakukan asepsis pada daerah pencabutan.
4.6.5 Pencabutan Gigi pada Tikus
Anatomi gigi beberapa hewan coba berbeda, maka cara pencabutan gigi
juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Teknik pencabutan gigi pada tikus
memakai modifikasi tang dan elevator. Pada prinsipnya adalah memasukkan
modifikasi tang dan elevator di antara tulang dan gigi, berikan tekanan pada tang
serta gunakan suatu gerakan pergelangan memutar yang diarahkan menuju
apek akar ke semua sisi dan menarik gigi setelah semua ligamen periodontal
telah terpotong (Kusumawati, 2004).
Pencabutan gigi insisive rahang atas kanan tikus dilakukan dengan
menggunakan klem yang dimodifikasi khusus untuk pencabutan gigi tikus
dengan cara menggoyang gigi tersebut memakai lecron yang dimodifikasi
sebagai bein. Setelah goyang gigi dijepit dengan klem dan diekstraksi. Gigi yang
dikeluarkan harus utuh.
4.6.6 Prosedur Perlakuan
Pada kelompok perlakuan, masing-masing sampel, sebelum gigi
direplantasi, soket diberi gel Aloe vera dengan konsentrasi 2 mg/ml pada
masing-masing kelompok dengan memakai pipet khusus ke dalam soket yang
49
telah dibersihkan dengan kassa. Kemudian gigi direplantasikan dan difiksasi
dengan wire dengan diameter 0,4 mm. Pada kelompok kontrol (K) sebanyak 4
sampel, setelah pencabutan langsung dilakukan replantasi tanpa diaplikasikan
gel Aloe vera. Kemudian pada masing-masing kelompok diamati pada hari ke 1,
3, dan 7.
4.6.7 Perawatan Tikus Pasca Pencabutan
Tikus yang telah dicabut gigi insisive kanan atasnya tidak diberi makan
seperti sebelum pencabutan, akan tetapi pemberian makan dilakukan secara per
oral dengan sonde gastric untuk menghindari terganggunya jaringan
penyembuhan luka pada soket. Bahan makanan yang digunakan adalah bubur
bayi dengan komposisi gizi yang disamakan dengan komposisi gizi makanan
awal.
4.6.8 Sacrifies pada Tikus
Hewan coba dikorbankan hendaknya mengikuti syarat-syarat tertentu
yaitu tidak menimbulkan gejala yang tidak menyenangkan bagi hewan, misalnya
menimbulkan ketakutan sehingga hewan harus meronta-ronta lebih dahulu,
aman untuk peneliti dan pembantu peneliti, mudah dilakukan, sesuai dengan
umur, spesies, kesehatan dan jumlah hewan, tidak menimbulkan polusi,
irreversible, tidak menimbulkan perubahan kimiawi pada jaringan dan tidak
menimbulkan perubahan histopatologi yang akan mempengaruhi hasil penelitian.
Ruangan euthanasia dengan ether, halothane atau methoxyfluarane relative
efektif dan berperikemanusiaan (Kusumawati, 2004).
Tikus dilakukan sacrifice dengan cara dimasukkan kedalam toples yang
berisi kapasyyang mengandung eter 10%, kemudian toples ditutup. Apabila tikus
sudah mati atau tidak lagi bernafas dan bergerak, tikus didekaputasi
50
menggunakan scalpel no.11 dan mengambil rahang atas tikus yang terdapat
jaringan periodontal pada gigi yang telah dilakukan replantasi. Kemudian
direndam dalam tempat yang berisi formalin 10% selama 18-24 jam sebelum
diproses ketahap selanjutnya. Kemudian jaringan yang dibutuhkan dibuat
sediaan di Labolatorium Patologi Anatomi dan Laboratorium Biokimia dengan
menggunakan teknik Immunohistokimia.
Setelah perlakuan, tubuh tikus yang tersisa dibersihkan dan dilakukan
aseptic dengan alkohol 70%. Jasad tikus kemudian dikubur langsung kedalam
tanah dengan membuat lubang sebesar 50cm x 30cm dan kedalaman 40 cm
untuk 24 ekor tikus secara bersamaan tanpa dilapisi plastik untuk mempercepat
penguraian. Areadkerja dibersihkan dengan sabun atau disemprot dengan
alkohol 70% dan alat – alat yang digunakan dicuci dengan sabun, dikeringkan
kemudian disterilkan dengan autoklaf.
4.6.9 Prosedur Pembuatan sediaan parafin blok
Jaringan dicuci dengan PBS 3-5 x untuk membersihkan dari kontaminan.
Kemudian difiksasi pada formalin 10%. Setelah itu dilakukan dehidrasi
menggunakan alkohol bertingkat (30%, 50%, 70%, 80%, 96% dan absolut)
masing-masing 60 menit. Dilakukan Clearing menggunakan xilol 2 kali masing-
masing 60 menit. Kemudian dilakukan infiltrasi dengan parafin lunak selama 60
menit pada suhu 48oC. Kemudian dilakukan block dalam parafin keras pada
cetakan dan didiamkan selama sehari. Keesokan harinya ditempelkan pada
holder dan dilakukan pemotongan setebal 4 um dengan rotary microtome.
Dilakukan mounting pada gelas objek dengan gelatin 5%.
51
4.6.10 Proses Deparafinisasi
Gelas obyek hasil parafin block direndam dalam xilol 2 kali, masing-
masing selama 5 menit. Setelah itu dilakukan rehidrasi menggunakan alkohol
berseri (absolut, 96%, 80%, 70%, 50% dan 30%) masing-masing selama 5
menit. Kemudian dibilas dalam dH2O selama 5 menit.
4.6.11 Immunohistokimia (IHK)
Jaringan periodontal dibuat sediaan parafin blok untuk dibuat slide. Slide
jaringan difiksasi dengan metanol absolut selama 5 menit. Slide dicuci dengan
PBS pH 7,4 satu kali selama 5 menit. Blocking endogenous peroksida
menggunakan H2O2 3% selama 20 menit lalu dicuci dengan PBS pH 7,4 tiga kali,
masing-masing selama 5 menit. Blocking unspesifik protein menggunakan
FBS 5% yang mengandung 0,25% Triton X-100 dicuci menggunakan PBS pH
7,4 tiga kali, masing-masing selama 5 menit. Diinkubasi menggunakan anti TNF-
, semalaman pada suhu 40C. Slide kemudian dicuci dengan PBS, lalu
diinkubasi dengan antibodi sekunder biotin conjugated selama satu jam pada
suhu kamar. Dicuci menggunakan PBS tiga kali, masing-masing selama 5 menit.
Diinkubasi menggunakan SA-HRP (Strep-Avidin Horseradis Peroxidase) selama
40 menit. Slide dicuci lalu diinkubasi dengan Betazoid DAB chromogen solution
(Biocare) selama 3-5 menit hingga menunjukkan warna coklat yang berarti
positif. Slide kemudian dicelupkan dalam hematoxylin sebagai counterstaining,
kemudian dilakukan proses dehidrasi, clearing, dan mounting. Hasil pewarnaan
kemudian diamati di mikroskop dan dilihat ada tidaknya reaksi positif. Slide
kemudian diambil foto sebanyak 5 bidang pandang dengan perbesaran 400x
(Penkowa, et al., 2003).
52
4.7 Analisa statistik
Hasil pengukuran jumlah CD4+ dan CD8+ yang positif pada tikus kontrol
dan perlakuan dianalisa secara statistik dengan menggunakan program
komputer dengan tingkat signifikansi 0,05 (p = 0,05) dan taraf kepercayaan 95%
(α = 0,05). Langkah-langkah uji hipotesis komparatif dan korelatif adalah sebagai
berikut :
a. Uji Normalitas : bertujuan untuk menginterpretasikan apakah suatu data
memiliki sebaran atau distribusi normal atau tidak. Karena pemilihan
penyajian data dan uji hipotesis bergantung dari normal tidaknya distribusi
data. Untuk penyajian data yang berdistribusi normal digunakan mean dan
standar deviasi sebagai pasangan ukuran pemusatan dan penyebaran.
Sedangkan untuk penyajian data yang tidak terdistribusi normal
menggunakan median dan minmum-maksimum sebagai pasangan ukuran
pemusatan dan penyebaran. Untuk uji hipotesis, jika sebaran data normal,
maka digunakan uji parametrik. Sedangkan, jika sebaran data tidak normal
digunakan uji non-parametrik.
b. Uji homogenitas : bertujuan untuk menguji berlaku atau tidaknya asumsi
ANOVA, yaitu apakah data yang diperoleh dari setiap perlakuan memiliki
varian yang homogen. Uji menggunakan Levene, jika didapatkan varian
yang homogen, maka analisa selanjutnya dapat menggunakan uji ANOVA.
Uji One-way ANOVA bertujuan untuk menguji berlaku untuk
membandingkan nilai dari rata-rata dari masing-masing kelompok perlakuan
dan mengetahui bahwa minimal ada dua kelompok yang berbeda signifikan.
c. Data penelitian yang terdistribusi normal (p > 0,05), dilanjutkan dengan uji
parametrik menggunakan Oneway Anova dengan tingkat kepercayaan
53
95%(α=0,05) dan bila ada perbedaan dilanjutkan dengan uji LSD (Least
Significance Difference) dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05). Bila
data penelitian tidak terdistribusi normal dan homogen, dilakukan uji
nonparametrik dengan Kruskal-Wallis dengan tingkat kepercayaan 95%
(α=0,05) dan bila ada perbedaan nyata antara kelompok sampel, dilanjutkan
dengan uji statistik Mann-Whitney dengan derajat kemaknaan 95% dengan
nilai α=0,05 (Notoatmojo, 2002).
d. Post-Hoc Test (Uji Least Significant Difference) : bertujuan untuk mengetahui
kelompok mana yang bereda secara signifikan dari hasil tes ANOVA. Uji
POST-Hoc yang digunakan adalah uji LSD dengan tingkt signifikansi 95% (p
< 0,05).
e. Uji korelasi Pearson : untuk mengetahui besarnya perbedaan secara kualitatif
kelompok yang berbeda secara signifikan, yang telah ditentukan
sebelumnya dari hasil uji Post Hoc (LSD).
54
4.8 Alur Penelitian
Rattus novergicus
Penyesuaian 7 hari
Kelompok Kontrol K1, K2, K3
Kelompok Perlakuan P1, P2, P3
Tidak diberikan gel Aloe vera
Diberi gel Aloe vera 2 mg/ml pada soket
Hari ke-1
Hari ke-3
Hari ke-7
Hari ke-1
Hari ke-3
Hari ke-7
Pengambilan sampel jaringan
Dekalsifikasi dengan EDTA
Fiksasi, Dehidrasi, dan Clearing
Embedding dan Penyayatan Jaringan
Immunohistokimia
Pencabutan insisive kanan rahang atas
Replantasi
Penghitungan Jumlah CD4+ dan CD8+
Analisa Data
Gambar 4.5 Bagan Alur Penelitian
55
BAB 5
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA
5.1 Hasil Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan hewan coba berupa tikus putih (Rattus
norvegicus) galur wistar yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kelompok kontrol
hari ke-1 (K1), kelompok kontrol hari ke-3 (K2), kelompok kontrol hari ke-7 (K3),
kelompok perlakuan hari ke-1 (P1), kelompok perlakuan hari ke-3 (P2), kelompok
perlakuan hari ke-7 (P3). Kelompok kontrol (K) merupakan kelompok tikus yang
dilakukan pencabutan gigi dan dimasukkan kembali kedalam soketnya
(replantasi) tanpa diberikan perlakuan. Kelompok perlakuan (P) merupakan
kelompok tikus yang dilakukan pencabutan gigi kemudian diberikan gel Aloe vera
ke dalam soketnya dan gigi dimasukkan kembali kedalam soketnya (replantasi).
Tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar mula-mula dilakukan
pencabutan gigi insisive kanan rahang atas, kemudian diberikan gel Aloe vera ke
dalam soketnya, gigi dimasukkan kembali ke dalam soketnya dan difiksasi
dengan menggunakan wire. Setelah itu semua tikus dikorbankan serta diambil
sampel jaringan periodontal gigi insisive rahang atas tikus putih (Rattus
norvegicus) galur wistar yang didekaputasi pada hari ke-1, ke-3 dan ke-7 setelah
gigi dimasukkan kembali ke dalam soketnya (replantasi), kemudian dilakukan
pembuatan preparat dengan teknik Immunohistokimia, lalu dilakukan
pemeriksaan di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali pada lima
lapang pandang. Didapatkan gambaran CD4+ dan CD8+ berupa sel berbentuk
bulat atau oval dengan inti biru dan sitoplasma coklat. Hasil perhitungan jumlah
56
CD4+ dan CD8+ kelompok kontrol dan perlakuan dapat dilihat dalam tabel 5.1
dan tabel 5.2, serta gambar 5.4 dan gambar 5.5.
(a) (b)
(c) (d)
Gambar 5.1 Perbandingan Gambaran Histologi Sel CD4+ dan CD8+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus Putih (Rattus norvegicus) Kedua Kelompok pada Hari ke-1 dengan teknik Immunohistokimia dan pewarnaan Betazoid DAB chromogen solution menggunakan mikroskop Nikon eclipse E100 dengan perbesaran 400x (a) kelompok kontrol CD4+, (b) kelompok perlakuan CD4+, (c) kelompok kontrol CD8+, (d) kelompok perlakuan CD8+. Tanda = CD4+/CD8+.
Berdasarkan gambar 5.1 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisif rahang atas tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar pada kelompok
kontrol pada hari ke-1 tampak gambaran sel CD4+ memiliki jumlah yang lebih
banyak daripada kelompok perlakuan. Pada kelompok perlakuan hari ke-1
tampak gambaran sel CD4+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
Berdasarkan gambar 5.1 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisive rahang atas tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar pada
kelompok kontrol pada hari ke-1 tampak gambaran sel CD8+ memiliki jumlah
yang lebih banyak dan kelompok perlakuan pada hari ke-1 tampak gambaran sel
CD8+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
57
(a) (b)
(c) (d)
Gambar 5.2 Perbandingan Gambaran Histologi CD4+ dan CD8+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus Putih (Rattus norvegicus) Kedua Kelompok pada Hari ke-3 dengan teknik Immunohistokimia dan pewarnaan Betazoid DAB chromogen solution menggunakan mikroskop Nikon eclipse E100 dengan perbesaran 400x (a) kelompok kontrol CD4+, (b) kelompok perlakuan CD4+, (c) kelompok kontrol CD8+, (d) kelompok perlakuan CD8+. Tanda = CD4+/CD8+.
Berdasarkan gambar 5.2 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisive rahang atas tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pada kelompok
kontrol pada hari ke-3 tampak gambaran sel CD4+ memiliki jumlah yang lebih
banyak dan kelompok pada perlakuan pada hari ke-3 tampak gambaran sel
CD4+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
Berdasarkan gambar 5.2 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisive rahang atas tikus putih (Rattus norvegicus) galur wistar pada
kelompok kontrol pada hari ke-3 tampak gambaran sel CD8+ memiliki jumlah
yang lebih banyak dan kelompok perlakuan pada hari ke-3 tampak gambaran sel
CD8+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
58
(a) (b)
(c) (d)
Gambar 5.3 Perbandingan Gambaran Histologi CD4+ dan CD8+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus Putih (Rattus norvegicus) Kedua Kelompok pada Hari ke-7 dengan teknik Immunohistokimia dan pewarnaan Betazoid DAB chromogen solution menggunakan mikroskop Nikon eclipse E100 dengan perbesaran 400x ((a) kelompok kontrol CD4+, (b) kelompok perlakuan CD4+, (c) kelompok kontrol CD8+, (d) kelompok perlakuan CD8+. Tanda = CD4+/CD8+.
Berdasarkan gambar 5.3 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisive rahang atas tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pada kelompok
kontrol pada hari ke-7 tampak gambaran sel CD4+ memiliki jumlah yang lebih
banyak dan kelompok pada perlakuan pada hari ke-7 tampak gambaran sel
CD4+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
Berdasarkan gambar 5.3 diatas didapatkan bahwa jaringan periodontal
gigi insisive rahang atas tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar pada
kelompok kontrol pada hari ke-7 tampak gambaran sel CD8+ memiliki jumlah
yang lebih banyak dan kelompok perlakuan pada hari ke-7 tampak gambaran sel
CD8+ memiliki jumlah yang lebih sedikit.
Untuk analisa data hasil penghitungan CD4+ dan CD8+ ditulis dengan
format mean ± standar deviasi.
59
Tabel 5.1 Rata-rata Jumlah Sel CD4+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus (Rattus norvegicus) dengan teknik Immunohistokimia dan perbesaran mikroskop 400x sebanyak lima lapang pandang
Kelompok Hari Mean ± SD
Kontrol 1 1 13,67 ± 1,528
Kontrol 2 3 12,67 ± 2,517
Kontrol 3 7 8,67 ± 1,528
Perlakuan 1 1 3,00 ± 1,000
Perlakuan 2 3 4,33 ± 1,528
Perlakuan 3 7 3,67 ± 4,640
Gambar 5.4 Diagram Rata-rata Jumlah Sel CD4+
Gambar 5.4 menunjukkan bahwa pada hari ke-1, kelompok kontrol
memiliki rata-rata jumlah CD4+ tertinggi sebesar 13,67 ± 1,528 dan kelompok
perlakuan memiliki rata-rata jumlah CD4+ sebesar 3,00 ± 1,000. Pada hari ke-3,
kelompok kontrol memiliki rata-rata jumlah CD4+ yaitu 12,67 ± 2,517 dan
kelompok perlakuan memiliki rata-rata CD4+ tertinggi yaitu 4,33 ± 1,528. Pada
hari ke-7, kelompok kontrol memilik rata-rata CD4+ sebesar 8,67 ± 1,528 dan
kelompok perlakuan memiliki rata-rata jumlah CD4+ sebesar 3,67 ± 1,528. Selain
itu, dari diagram diatas didapatkan bahwa pada kelompok kontrol mengalami
penurunan jumlah sel CD4+ dari hari ke-1 sampai hari ke-7, sedangkan pada
13.67 12.67
8.67
3 4.33
3.67
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-7
Kontrol
Perlakuan
60
kelompok perlakuan mengalami penaikan jumlah sel CD4+ pada hari ke-1
sampai hari ke-3 lalu menurun pada hari ke-7.
Tabel 5.2 Rata-rata Jumlah Sel CD8+ pada Jaringan Periodontal Gigi Tikus (Rattus norvegicus) dengan teknik Immunohistokimia dan perbesaran mikroskop 400x sebanyak lima lapang pandang
Kelompok Hari Mean ± SD
Kontrol 1 1 6,00 ± 1,000
Kontrol 2 3 17,00 ± 1,000
Kontrol 3 7 12,00 ± 2,000
Perlakuan 1 1 4,00 ± 1,000
Perlakuan 2 3 9,33 ± 1,528
Perlakuan 3 7 3,67 ± 1,528
Gambar 5.5 Diagram Rata-rata Jumlah Sel CD8+
Gambar 5.5 menunjukkan bahwa pada hari ke-1, kelompok kontrol
memiliki rata-rata jumlah CD8+ sebesar 6,00 ± 1,000 dan kelompok perlakuan
memiliki rata-rata jumlah CD8+ sebesar 4,00 ± 1,000. Pada hari ke-3, kelompok
kontrol memiliki rata-rata jumlah CD8+ tertinggi yaitu 17,07 ± 1,000 dan begitu
juga pada kelompok perlakuan memiliki rata-rata CD8+ tertinggi yaitu 9,33 ±
1,528. Pada hari ke-7, kelompok kontrol memilik rata-rata CD8+ sebesar 12,00 ±
6
17
12
4
9.33
3.67
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-7
Kontrol
Perlakuan
61
2,000 dan kelompok perlakuan memiliki rata-rata jumlah CD8+ sebesar 3,67 ±
1,528. Selain itu, dari diagram diatas didapatkan bahwa pada kelompok kontrol
dan perlakuan mengalami penaikan jumlah sel CD8+ dari hari ke-1 sampai hari
ke-3 lalu mengalami penurunan pada hari ke-7.
5.2 Analisis Data
Data hasil penelitian berupa jumlah CD4+ dan CD8+ yang dianalisis
menggunakan metode One Way Anova. Sebelum dilakukan pengujian dengan
One Way Anova, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas ragam. Uji
normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah data kurang dari 50,
sedangkan uji homogenitas menggunakan Levene’s Test, keduanya
menggunakan tingkat kesalahan (α) 0,05.
Pada uji One Way Anova, hipotesis ditentukan melalui suatu rumusan
yaitu Ho diterima bila nilai signifikansi diperoleh p > 0,05, sedangkan Ho ditolak
bila nilai signifikansi p < 0,05. Ho dari penelitian ini adalah gel Aloe vera tidak
berpengaruh terhadap perubahan jumlah CD4+ dan CD8+ pada gigi tikus (Rattus
norvegicus) galur wistar pasca replantasi, sedangkan H1 dari penelitian ini adalah
gel Aloe vera berpengaruh terhadap perubahan jumlah CD4+ dan CD8+ pada
gigi tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pasca replantasi.
5.2.1 Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji one sample
Shapiro-Wilk karena jumlah data 24, sedangkan data yang jumlahnya lebih dari
50 menggunakan uji Kolmogorov-smirnov (lihat lampiran 3). Uji ini bertujuan
menguji apakah sebaran data yang ada dalam distribusi normal atau tidak.
62
Keluaran hasil uji adalah dengan melihat besarnya nilai signifikansi. Jika nilai
signifikansi >0,05 (α=5%), maka data dalam distribusi normal.
Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Shapiro-wilk
menunjukkan bahwa nilai signifikansi rata-rata jumlah sel CD4+ pada semua
kelompok baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan adalah 0,51 lebih
besar dari 0,05 (p>0,05), ini berarti data penelitian yang diperoleh berdistribusi
normal. Sedangkan nilai signifikansi rata-rata jumlah sel CD8+ pada semua
kelompok baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan adalah 0,145 lebih
besar dari 0,05 (p>0,05), ini berarti data penelitian yang diperoleh berdistribusi
normal.
5.2.2 Uji Homogenitas Ragam
Setelah mengetahui bahwa data berdistribusi normal selanjutnya
dilakukan pengujian homogenitas ragam dengan menggunakan Levene’s Test
(lihat lampiran 3). Uji homogenitas ragam dikatakan terpenuhi jika nilai
signifikansi hasil perhitungan lebih besar dari 0,05 (p>0,05).
Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada
perhitungan rata-rata jumlah CD4+ adalah 0,707 (p>0,05) sedangkan
perhitungan rata-rata jumlah CD8+ adalah 0,787 (p>0,05) maka dapat
disimpulkan bahwa kedua data penelitian tersebut bersifat homogen.
5.2.3 Uji One Way Anova (Analysis of Variance)
Uji One Way Anova (F) bertujuan untuk mengevaluasi perbedaan nilai
jumlah CD4+ dan CD8+ pada masing-masing kelompok. Uji ini harus
berdistribusi normal, variasi homogen dan diambil dari sampel yang acak.
Berdasarkan uji statistik ini dapat diketahui apakah terdapat perbedaan jumlah
63
CD4+ dan CD8+ yang signifikan antar kelompok. Perbedaan rata-rata sel CD4+
dan CD8+ dianggap bermakna jika nilai p<0,05 atau dengan kata lain Ho ditolak.
Pada Uji One Way Anova ini Ho yang diajukan adalah gel Aloe vera tidak
berpengaruh terhadap perubahan jumlah CD4+ dan CD8+ pada gigi tikus (Rattus
norvegicus) galur wistar pasca replantasi. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa
nilai p=0,000 (lihat lampiran 3) dan berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan
Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
dari pengaplikasian gel Aloe vera terhadap perubahan jumlah CD4+ dan CD8+
pada gigi tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pasca replantasi.
5.2.4 Uji Post-Hoc Tukey
Uji ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah CD4+ dan
CD8+ dari ketiga kelompok perlakuan. Metode Post-Hoc yang digunakan adalah
Uji HSD (lihat lampiran 3). Pada uji ini, suatu data dikatakan berbeda secara
bermakna apabila nilai signifikansi p<0,05 serta pada interval kepercayaan 95%.
Hasil perhitungan Post-Hoc Tukey adalah sebagai berikut :
Tabel 5.3 Uji Post-Hoc Tukey CD4+
K1 K2 K3 P1 P2 P3
K1 - .973 .029* .000* .000* .000*
K2 .973 - .100 .000* .001* .000*
K3 .029* .100 - .013* .067 .029*
P1 .000* .000* .013* - .916 .996
P2 .000* .001* .067 .916 - .996
P3 .000* .000* .029* .996 .996 -
64
Hasil uji Tukey HSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara kelompok K1 dengan P1, K1 dengan P2, K1 dengan P3, K2
dengan P1, K2 dengan P3, K3 dengan K1, K3 dengan P1, K3 dengan P3, P1
dengan K1, P1 dengan K2, P1 dengan K3, P2 dengan K1, P2 dengan K2, P3
dengan K1, P3 dengan K2, P3 dengan K3. Perbedaan yang signifikan
disebabkan karena nilai p<0,05.
Perbedaan yang tidak signifikan ditunjukkan oleh kelompok K1 dengan
K2, K2 dengan K1, K2 dengan K3, K3 dengan K2, K3 dengan P2, P1 dengan P2,
P1 dengan P3, P2 dengan K3, P2 dengan P1, P2 dengan P3, P3 dengan P1,
dan P3 dengan P2. Perbedaan yang tidak signifikan disebabkan karena nilai
p>0,05.
Tabel 5.4 Uji Post-Hoc Tukey CD8+
K1 K2 K3 P1 P2 P3
K1 - .000* .002* .524 .102 .372
K2 .000* - .009* .000* .000* .000*
K3 .002* .009* - .000* .250 .000*
P1 .524 .000* .000* - .005* 1.000
P2 .102 .000* .250 .005* - .003*
P3 .372 .000* .000* 1.000 .003* -
Hasil uji Tukey HSD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara kelompok K1 dengan K2, K1 dengan K3, K2 dengan K2, K2
dengan K3, K2 dengan P1, K2 dengan P2, K2 dengan P3, K3 dengan K1, K3
dengan K2, K3 dengan P1, K3 dengan P3, P1 dengan K2, P1 dengan K3, P1
dengan P2, P2 dengan K2, P2 dengan P1, P2 dengan P3, P3 dengan K2, P3
65
dengan K3, P3 dengan P2. Perbedaan yang signifikan disebabkan karena nilai
p<0,05.
Perbedaan yang tidak signifikan ditunjukkan oleh kelompok K1 dengan
P1, K1 dengan P2, K1 dengan P3, K3 dengan P2, P1 dengan K1, P1 dengan P3,
P2 dengan K1, P2 dengan K3, P3 dengan P1, dan P3 dengan P1. Perbedaan
yang tidak signifikan disebabkan karena nilai p>0,05.
Berdasarkan hasil uji Post Hoc Tukey dapat dijelaskan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
Sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian gel Aloe vera
dapat menurunkan jumlah CD4+ dan CD8+ pada gigi tikus putih (Rattus
norvegicus) galur wistar pasca replantasi.
5.2.5 Uji Korelasi Pearson
Uji Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua
variabel atau lebih yang berskala interval (parametrik). Dalam hal ini, uji korelasi
pearson digunakan untuk membuktikan korelasi antara penambahan gel Aloe
vera terhadap jumlah CD4+ dan CD8+. Agar penafsiran dilakukan sesuai dengan
ketentuan, kita perlu mempunyai kriteria yang menunjukkan kuat atau lemahnya
korelasi. Korelasi dapat bersifat positif atau negatif. Korelasi positif menunjukkan
arah yang sama hubungan antar variabel. Artinya jika variabel 1 besar maka
variabel 2 semakin besar pula. Sebaliknya korelasi negatif menunjukkan arah
yang belawanan, artinya jika variabel 1 besar maka variabel 2 menjadi kecil
(Sarwono, 2006).
Siginifikansi hubungan dua variabel dapat dianalisis dengan ketentuan,
jika probabilitas atau signifikansi p < 0.05, hubungan kedua variabel signifikan.
66
Jika probalilitas atau signifansi p > 0.05, hubungan kedua variabel tidak
signifikan. Jika output angka korelasi diberi tanda 2 bintang (**), maka signifikansi
menjadi 0,01 (Sarwono, 2006). Hasil dari perhitungan korelasi pearson terhadap
data penelitian (lihat lampiran 3) adalah sebagai berikut :
1. Kekuatan korelasi ( r ) = 0.766**, dengan demikian terdapat korelasi yang
kuat antara gel Aloe vera dengan jumlah CD4+ pada gigi tikus (Rattus
norvegicus) galur wistar pasca replantasi.
2. Arah korelasi adalah negatif, sehingga semakin bertambahnya hari, maka
jumlah CD4+ pada gigi tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pasca replantsi
akan semakin menurun secara signifikan.
3. Kekuatan korelasi ( r ) = 0.804**, dengan demikian terdapat korelasi yang
kuat antara gel Aloe vera dengan jumlah CD8+ pada gigi tikus (Rattus
norvegicus) galur wistar pasca replantasi.
4. Arah korelasi adalah negatif, sehingga semakin bertambahnya hari, maka
jumlah CD8+ pada gigi tikus (Rattus norvegicus) galur wistar pasca
replantasi akan semakin menurun secara signifikan.
68
BAB 6
PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh gel Aloe vera
terhadap jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi tikus putih
(Rattus norvegicus) pasca replantasi. Pengamatan pada penelitian ini dibagi
menjadi 3 time series, yaitu dilakukan pada hari ke-1 (K1, P1), hari ke-3 (K2, P2),
dan hari ke-7 (K3, P3) pada tiap kelompok karena limfosit muncul pada hari
ketiga lalu mencapai puncak pada hari kelima setelah itu limfosit akan mengalami
penurunan. Pengamatan dilakukan setelah semua hewan coba dilakukan
pencabutan gigi insisivus kanan maksila tikus putih (Rattus norvegicus) galur
wistar kemudian langsung dilakukan replantasi pada gigi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental murni pada hewan
coba tikus putih (Rattus norvegicus) yang dilakukan prosedur pencabutan gigi
insisif kanan atas pada tikus memakai modifikasi tang dan elevator. Pada
kelompok perlakuan, masing-masing sampel, sebelum gigi direplantasi, soket
diberi gel Aloe vera dengan konsentrasi 2 mg/ml pada masing-masing sampel
dengan memakai pipet khusus ke dalam soket yang telah dibersihkan dengan
kassa. Kemudian gigi direplantasikan dan difiksasi dengan wire dengan diameter
0,4 mm. Pada kelompok kontrol (K) sebanyak 4 sampel, setelah pencabutan
langsung dilakukan replantasi tanpa diaplikasikan gel Aloe vera. Kemudian pada
masing-masing kelompok diamati pada hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-7. Pada
penelitian ini, kelompok perlakuan (P1, P2, P3) diberi perlakuan berupa
pemberian gel Aloe vera dengan dosis tunggal berdasar pada penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sulistiawati (2011), menunjukkan bahwa
69
perbandingan dosis Aloe vera tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.
Selain itu, Aloe vera bisa menjadi salah satu obat alternatif dalam penyembuhan
luka karena mudah dalam penggunaan, memiliki efek antiinflamasi, menstimulasi
kekebalan tubuh dan membantu proses regenerasi sel (Jatnika dan
Saptoningsih, 2009).
Aloe vera memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antibakteri, antijamur,
peningkat aliran darah ke daerah yang terluka dan menstimulasi fibroblas yang
bertanggung jawab untuk penyembuhan luka (Rieuwpassa, 2011). Gel Aloe vera
mengandung zat fenolik seperti antrakuinon. Kandungan aloe emodin dalam
daun Aloe vera dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dengan menekan limfosit T.
Antrakuinon juga dapat menurunkan produksi sitokin IL-2 dan TNF-α pada sel
limfosit T yang teraktivasi (Rainsford et al., 2015). Zat aktif polisakarida seperti
acemannan dapat meningkatkan aktivitas makrofag (Wiedosari, 2007).
Subpopulasi limfosit yang menunjukkan perubahan selama penyembuhan luka:
rasio limfosit T CD4+ dan CD8+ tinggi mencirikan stadium awal dan saat
penyembuhan berlangsung rasionya menurun. (Huttunen, 2003).
Sediaan gel digunakan karena memiliki beberapa keuntungan yaitu,
mudah merata jika dioleskan pada kulit tanpa penekanan, memberi sensasi
dingin, tidak membekas di kulit, dan sangat mudah digunakan (Astuti, 2012).
Basis gel yang digunakan adalah carbomer. Carbomer mampu menjadi basis gel
tanpa mempengaruhi sifat kimia acemannan, serta tidak mempengaruhi respon
jaringan, sehingga tidak mempengaruhi efektivitas gel Aloe vera (Anggraeni et
al., 2012).
Hasil analisis data dari penelitian ini berdasarkan uji One Way Anova
yang telah dilakukan, menunjukkan rata-rata jumlah CD4+ dan CD8+ pada
70
kelompok kontrol dan kelompok perlakuan memiliki perbedaan. Pada kelompok
perlakuan, rata-rata jumlah CD4+ dan CD8+ lebih rendah dibandingkan rata-rata
jumlah CD4+ dan CD8+ pada kelompok kontrol. Hal tersebut dikarenakan pada
kelompok kontrol pasca pencabutan tidak diberi suatu bahan tertentu seperti
pada kelompok perlakuan diberi gel Aloe vera yang mengandung zat fenolik
seperti antrakuinon (Rainsford et al., 2015)
Berdasarkan uji Post Hoc yang telah dilakukan untuk mengetahui
kelompok yang berbeda secara signifikan sebagai lanjutan uji One Way Anova,
didapatkan rata-rata jumlah CD4+ dan CD8+ kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan berbeda secara signifikan. Pada hari ke-1 mulai terlihat perbedaan
yang signifikan jumlah CD4+ dan CD8+ pada kedua kelompok tersebut dan
kelompok perlakuan memiliki jumlah CD4+ dan CD8+ yang lebih rendah, hal ini
dikarenakan pemberian gel Aloe vera pada kelompok perlakuan berperan
sebagai antiinflamasi (Wiedosari, 2007). Pada hari ke-3 terdapat peningkatan
jumlah CD4+ dan CD8+ dari hari sebelumnya pada kelompok kontrol dan
kelompok perlakuan, menandakan bahwa pada tikus (Rattus norvegicus) galur
wistar yang dilakukan pencabutan gigi kemudian dilakukan replantasi akan
mengalami proses inflamasi yang mengakibatkan terjadinya peningkatan CD4+
dan CD8+ yang lebih tinggi pada daerah yang terinflamasi. Pada hari ke-7 terjadi
penurunan jumlah CD4+ dan CD8+ pada kelompok kontrol dan kelompok
perlakuan, pada kelompok perlakuan jumlah CD4+ dan CD8+ lebih sedikit
dibanding pada kelompok kontrol. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya (Yu et al., 2009) bahwa jumlah rata-rata CD4+ dan
CD8+ pada kelompok yang diberi bahan yang mengandung Aloe vera
menunjukan hasil yang signifikansi lebih rendah daripada kelompok kontrol.
71
Jumlah rata-rata CD4+ dan CD8+ kelompok perlakuan (P) yang lebih
rendah dibanding kelompok kontrol (K) disebabkan karena pengaruh zat-zat
fenolik yang terkandung dalam Aloe vera, salah satunya adalah antrakuinon.
Kandungan aloe emodin dalam daun Aloe vera dapat berfungsi sebagai
antiinflamasi dengan menekan T sitolisis CD8+ dengan bantuan sel T supressor
CD8+ (Rainsford et al., 2015). Sedangkan acemannan meningkatkan aktivitas
makrofag dilakukan melalui reseptor manosa yang terdapat dipermukaan selnya,
sedangkan terhadap sel dendritik melalui peningkatan ekspresi molekul MHC
kelas II (Wiedosari, 2007). Limfosit mulai terbentuk pada hari ketiga dan
mencapai puncak pada hari kelima lalu mulai mengalami penurunan karena
keberadaan limfosit telah digantikan oleh adanya fibroblas yang membentuk
jaringan baru (Pratiwi, 2011). Selanjutnya diketahui bahwa menurut penelitian
yang dilakukan oleh Yagi (2003), gel Aloe vera juga menstimulasi aktifitas
fibroblas dan proliferasi kolagen yang bertanggung jawab atas proses
penyembuhan luka hal ini yang menyebabkan jumlah CD4+ dan CD8+ terjadi
penurunan pada hari ke-7.
6.1 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ pada Gigi Tikus Putih (Rattus
norvegicus) Pasca Replantasi Tanpa Pemberian Gel Aloe vera
Menurut hasil penelitian dari perlakuan hari pertama, ketiga, dan ketujuh
didapatkan data bahwa rata – rata jumlah CD4+ pada kelompok K1 paling tinggi
dibandingkan kelompok K2 dan K3, sedangkan pada CD8+ kelompok K1 lebih
rendah dibandingkan kelompok K2 dan K3. Jumlah limfosit paling tinggi terdapat
pada kelompok K2 pada CD8+. Hal ini disebabkan karena pada hari pertama
72
limfosit belum terlalu berperan pada proses penyembuhan luka sehingga jumlah
CD4+ dan CD8+ yang muncul tidak terlalu besar. Yang berperan pada hari
pertama adalah sel PMN maka pada hari pertama jumlah CD4+ dan CD8+ masih
tidak terlalu banyak. Limfosit mulai terbentuk pada hari ketiga dan mencapai
puncak pada hari kelima lalu mulai mengalami penurunan karena keberadaan
limfosit telah digantikan oleh adanya fibroblas yang membentuk jaringan baru
(Pratiwi, 2011).
6.2 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ pada Tikus Putih (Rattus
norvegicus) Pasca Replantasi dengan Pemberian Gel Aloe vera
Menurut hasil penelitian dari perlakuan hari pertama, ketiga, dan ketujuh
didapatkan data bahwa rata – rata jumlah CD4+ dan CD8+ pada kelompok P1
paling rendah dibandingkan kelompok P2 dan P3. Jumlah CD4+ dan CD8+
paling tinggi terdapat pada kelompok P2. Kelompok P1 pada CD8+ signifikan
terhadap kelompok P2. Penurunan jumlah CD4+ dan CD8+ pada kelompok
perlakuan dihari ketujuh, disebabkan jumlah limfosit telah mencapai angka
puncak pada hari kelima, sehingga pada hari ketujuh jumlah limfosit terus
mengalami penurunan karena keberadaan limfosit telah digantikan oleh adanya
fibroblas yang membentuk jaringan baru. Proses penyembuhan telah masuk
pada tahap proliferasi ditandai dengan adanya penurunan jumlah sel radang
termasuk limfosit dan makrofag serta terbentuknya jaringan granulasi yaitu
fibroblas dan angiogenesis. Sehingga fase inflamasi dan proses penyembuhan
luka menjadi lebih singkat (Pratiwi, 2011). Namun hal ini juga disebabkan
perlakuan yang diberikan pada kelompok perlakuan mengandung senyawa
fenolik seperti antrakuinon yang lebih spesifiknya aloe emodin yang memiliki
73
fungsi antiinflamasi dan peningkatan aliran darah ke daerah yang terluka dan
menstimulasi fibroblas yang bertanggung jawab untuk penyembuhan luka
(Rieuwpassa, 2011). Antrakuinon mampu menekan T sitolisis CD8+ dengan
bantuan sel T supressor CD8+ dan juga dapat menurunkan produksi sitokin IL-2
pada sel limfosit T yang teraktivasi. (Rainsford et al., 2015).
6.3 Perbandingan Jumlah CD4+ dan CD8+ Antara Kelompok Kontrol
dengan Kelompok Perlakuan
Kelompok hari pertama, yaitu antara kelompok K1 dan P1 menunjukkan
perbedaan jumlah CD4+ dan CD8+ yang bermakna. Jumlah rata – rata limfosit
kelompok K1 lebih tinggi dibandingkan kelompok P1 pada CD4+ dan signifikan.
Pada CD8+ rata – rata limfosit kelompok K1 lebih tinggi dibandingkan kelompok
P1 namun nilainya tidak signifikan. Hal ini terjadi karena pada pada hari pertama
terjadi fase inflamasi yaitu tahap radang akut yang dominasi leukosit PMN dan
makrofag ke area luka untuk fagositosis, sementara limfosit sendiri baru akan
muncul di area luka pada saat keradangan berubah menjadi kronis yaitu pada
hari ke- 3 (Pratiwi, 2011).
Kelompok hari ketiga, yaitu antara kelompok K2 dan P2 menunjukkan
perbedaan jumlah CD4+ dan CD8+ yang bermakna. Jumlah rata – rata CD4+
dan CD8+ K2 lebih tinggi daripada P2 dan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa
aplikasi gel Aloe vera berpengaruh terhadap penurunan jumlah CD4+ dan CD8+
yang terbentuk yaitu paling sedikit pada kelompok perlakuan dibanding kelompok
kontrol. Berdasarkan teori, pada hari ketiga terjadi fase proliferasi dan
keradangan berubah menjadi kronis yaitu terjadi angiogenesis, proliferasi
fibroblas, penurunan PMN serta peningkatan limfosit dan makrofag (telah
74
terbentuk jaringan granulasi) (Sinno, 2013). Zat fenolik pada gel Aloe vera seperti
antrakuinon memiliki fungsi antiinflamasi dan peningkatan aliran darah ke daerah
yang terluka dan menstimulasi fibroblas yang bertanggung jawab untuk
penyembuhan luka (Rieuwpassa, 2011). Antrakuinon mampu menekan T sitolisis
CD8+ dengan bantuan sel T supressor CD8+ dan juga dapat menurunkan
produksi sitokin IL-2 pada sel limfosit T yang teraktivasi. (Rainsford et al., 2015).
Sehingga didapatkan jumlah sel CD4+ dan CD8+ pada kelompok perlakuan (P)
lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol (K). Hal tersebut sesuai
dengan penelitian (Yu et al., 2009). Subpopulasi limfosit menunjukkan perubahan
selama penyembuhan luka, rasio limfosit T CD4+ dan CD8+ yang tinggi
mencirikan stadium awal dan saat penyembuhan berlangsung, rasionya
menurun. Hal ini menunjukan bahwa limfosit supresor CD8+ memainkan bagian
dalam proses penyembuhan dan peningkatan jumlahnya selama penyembuhan
dapat mengindikasikan kebutuhan lingkungan akan sitokin antiinflamasi saat
respons inflamasi mereda (Huttunen, 2003).
Kelompok hari ketujuh, yakni antara kelompok K3 dan P3 menunjukkan
perbedaan jumlah CD4+ dan CD8+ yang bermakna. Jumlah rata – rata CD4+
dan CD8+ pada K3 lebih tinggi dibandingkan dengan P3 dan nilai yang
didapatkan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi gel Aloe vera
berpengaruh terhadap jumlah CD4+ dan CD8+ yang terbentuk. Berdasarkan
teori, pada hari ketujuh proses proliferasi telah membentuk epitel gingiva, disertai
peningkatan angiogenesis dan proliferasi fibroblas, serta mulai terjadi fase
maturasi jaringan ditandai dengan luka yang mulai menutup (Robbins, 2010).
Limfosit melepaskan limfokin interferon Ɣ (IFN-Ɣ) yang mengaktivasi
makrofag. Setelah makrofag diaktifkan oleh limfosit akan menghasilkan Nitric
75
Oxide (NO) dan Reactive Oxygen Species (ROS) yang berperan dalam
fagositosis. Makrofag juga melepaskan faktor pertumbuhan yaitu Transforming
Growth Factor (TGF-β) dan Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) yang
mengawali dan mempercepat pembentukan formasi jaringan granulasi berupa
fibroblas dan angiogenesis sehingga terjadi penyembuhan luka (Robbins, 2010)
Aloe vera memiliki manfaat sebagai antiinflamasi dan peningkat aliran
darah ke daerah yang terluka dan menstimulasi fibroblas yang bertanggung
jawab untuk penyembuhan luka (Rieuwpassa, 2011). Penelitian yang dilakukan
oleh Widurini (2003), menggunakan Aloe vera yang diaplikasikan pada radang
mulut tikus, ternyata dapat menurunkan radang mukosa rongga mulut tikus.
Didapatkan hasil ini bahwa Aloe vera tidak mempunyai mekanisme tunggal
sebagai antiinflamasi. Aloe vera mengandung berbagai macam zat yang
dipercaya dapat bertindak sebagai antiinflamasi, antara lain asam salisilat,
vitamin, polisakarida dan asam lemak. Disamping itu terdapat pula indometasin
yang dapat mengurangi edema, menghambat enzim siklooksigease dan
menghambat motilitas dari leukosit poly morphonuclear (PMN) yang bila
jumlahnya berlebihan akan merusak jaringan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikatakan
bahwa gel Aloe vera berpengaruh menurunkan jumlah CD4+ dan CD8+ serta
membantu proses penyembuhan pada jaringan periodontal gigi tikus putih
(Rattus norvegicus) pasca replantasi. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
penelitan yang telah disusun dapat diterima.
76
BAB 7
PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pemberian gel Aloe vera
mempengaruhi jumlah CD4+ dan CD8+ pada jaringan periodontal gigi tikus
(Rattus norvegicus) pasca replantasi.
7.2 Saran
Berdasarkan kekurangan yang ada pada penelitian ini, maka perlu diadakan
penelitian yang lebih lanjut sebagai berikut :
a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengamati jumlah CD4+ dan
CD8+ pada hari-3 yang mengalami peningkatan dibandingkan hari ke-1
dan ke-7.
b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek samping dan toksisitas
dalam pemberian gel Aloe vera sebagai terapi penyembuhan pasca gigi
yang replantasi.
77
DAFTAR PUSTAKA
Ajani P, Nimmagadda, Burri BJ, Neidlinger T, O’Brien WA, Goetz MB. 1998. Effect of oral β-carotene supplementation on plasma human immunodeficiency virus (HIV) RNA levels and CD4+ cell counts in HIV infected patients. Clinical Infectious Diseases (27).
Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. 2002. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science.
Andreasen JO, Bakland L, Andreasen FM. 2006. Traumatic intrusion of permanent teeth. Part 2. A clinical study of the effect of preinjury and injury factors, such as sex, age, stage of root development, tooth location, and extent of injury including number of intruded teeth on 140 intruded permanent teeth. Dental Traumatol.
Anggraeni Y, Esti H, Tuti P. 2012. Karakteristik Sediaan Dan Pelepasan Natrium Diklofenak Dalam Sistem Niosom Dengan Basis Gel Carbomer 940. Surabaya: Fakultas Farmasetika Universitas Airlangga Surabaya
Baggio Gomes. 2009. Study of storage media for avulsed teeth. Brazilian Journal of Dental Traumatology 1(2)
Banvard and Elaine. 2003. Aloe Vera (Aloe Barbadensis). http://www.earlham.edu
Baratawidjaja KG, Rengganis I. 2009. Imunologi dasar Ed ke-8. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Baratawidjaja KG. 2000. Imunologi Dasar. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Barrett E, Kenny D, Tenenbaum H, Sigal M, Johnston D. 2005. Replantation of permanent incisors in children using Emdogain®. Dental Traumatol.
Basetti A, Sala S. 2005. The Great Aloe Book. Trento: Zuccari Pty Ltd
Bassetti, A., Stefano, S. 2005. The Great Aloe Book. USA: Zuccari.
Bath-Balogh, M. dan Fehrenbach, M. J., 2006, Dental Embryology, Histology, and Anatomy 2nd edition. St. Louis: Elsevier Inc.
Carranza, F.A. 2002. Clinical Periodontology. 9th Edition. Philadelphia : W.B. Saunders Company.
Cohenca N. 2004. Treatment for avulsed permanent teeth. Therapeutic protocols for avulsed permanent teeth : review and clinical update. Pediatr Dent J.
Dalimunthe, T. 2003. Replantasi gigi depan sulung yang avulsi. Medan: Dentika Dent J.
Davis K, Philpott S, Kumar D, Mendall M. 2006. Randomised double-blind placebo-controlled trial of Aloe vera for irritable bowel syndrome. Int J Clin Pract.
78
Dewi, Galuh. 2012. Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Lidah Buaya (Aloe vera (L.) Webb) dengan Gelling Agent Hydroxyprophyl Methylcellulose (HPMC) 4000 SM dan Aktivitas Antibakterinya terhadap Staphylococcus epidermidis. Surakarta : Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Donaldson M, Kinirons M. 2005. Factors affecting the time of onset of resorption in avulsed and replanted incisor teeth in children. Dental Traumatol.
Dwi Astuti, Dhani. 2012. Formulasi Sediaan Gel Ekstrak Etanolik Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa (Scheff.) Boerl.) Dengan Basis HPMC. Surakarta: Fakultas Farmasi Universitas Muhamadiyah Surakarta
Ercan E, Dalli M. 2007. Replantation of Avulsed Teeth: A Case Report. Turkey: Atatürk Üniv Di Hek Fak Derg.
Flanagan, A.M., Bartlett, W., Skinner, J.A., Gooding. C.R., Carrington, R.W.J., Flanagan, A.M., Briggs, T.W.R., et al. 2010. Autologous chondrocyte implantation versus matrix-induced autologous chondrocyte implantation for osteochondral defects of the knee: a prospective, randomised study. J Bone Joint Surg Br. 87:640-5.
Flores M, Malmgren B, Andersson L, et al. 2007. Guidelines for the management of traumatic dental injuries. III. Primary teeth. Dental Traumatol.
Furnawanthi, I. 2004. Khasiat & Manfaat Lidah Buaya Si Tanaman Ajaib. Agro Media.
Grossman LI, Oliet S, Del Rio CE. 1995. Ilmu Endodontik dalam praktik. Alih Bahasa. Prof. drg. Rafiah Abyono. Jakarta: EGC.
Guyton AC. 1998. Human Physiology and Mechanisms of Disease, 6th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co.
Hirotaka, Sato. 2007. Proliferative Activity, Apoptosis, and Histogenesis. The early stage of rat tooth extraction wound healing. Imunology today: 348-350.
Intan Nurcahaya, Misbah. 2015. Pengaruh Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe Vera) Terhadap Peningkatan Jumlah Fibroblas Pada Proses Penyembuhan Luka Mukosa Rongga Mulut Tikus (Rattus Norvegiccus) Strain Wistar. Surakarta: Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Jacobsen I, Andreasen JO. 2003. Traumatic Injuries Examination, Diagnosis and Immediate Care. In: Koch G, Poulsen S, ed, Pediatric Dentistry – Clinical Approach. 2nd ed. Copenhagen: Blackwell Munksgaard.
Jatnika A, Saptoningsih, 2009. Meraup laba dari lidah buaya. Jakarta: Agro Media Pustaka.
Jesse A. Taylor. Blueprints Plastic Surgery, Philadelphia, 2005; 18-19.
Joyce M. Black, Jane Hokanson Hawks, 2005. Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes. Edisi 7 Volume 1. Elsevier Saunders: Universitas Michigan
79
Kathuria N, Gupta N, Manisha, Prasad R, Nikita. 2011. Biologic effects of Aloe vera gel. Internet J Microbiol.
Kismaryanti, Andiny. 2007. Aplikasi Gel Lidah Buaya (Aloe vera L.) sebagai Edible Coating pada Pengawetan Tomat. Bogor: Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Kresno SB. 2010. Imunologi: Diagnosis dan Prosedur Laboratorium. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Kuntoro. 2010. Hubungan Pemberian Ekstrak Patikan Kebo (Euphorbia hirta L.) terhadap Derajat Inflamasi Bronkus pada Mencit Balb/C Model Asma Alergi. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
Kusmawati A, Pratiwi IB. Pengambilan polisakarida acemannan dari Aloe vera menggunakan etanol sebagai pengendap. [Serial Online] 2009; [Internet] Available from http://eprints.undip.ac.id/1454/1/makalah_aloe_vera.pdf. Acessed November 2016.
Kusumawati, Diah. 2004. Bersahabat dengan Hewan Coba. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Malik Itrat, Zarnigar. 2013. Aloe Vera: A review of its clinical effectiveness. Int Res J Pharm: 4(8).
Maria Huttunen. 2003. Mast Cells in cutaneous wound healing. Finland: Kuopio University Library
Martin Trope. 2011. Avulsion of permanent teeth: theory to practice. Dental Traumatology
McDonald RE, Dean JA, Avery DR. 2010. McDonald and Avery Dentistry for the Child and Adolescent. Elsevier Health Science.
McIntyre J, Lee J, Trope M, Vann WJ. 2009. Permanent tooth replantation following avulsion: Using a decision tree to achieve the best outcome. Pediatr Dent.
Mogaddhasi S, Verma SK. 2011. Aloe vera their chemicals composition and applications: A review. International journal of biological and medical research.
Newland MC, Ellis SJ, Peters KR, Durham TM, Ullrich FA, Tinker JH. 2007. Dental injury associated with anesthesia: a report of 161,687 anesthetics given over 14 years. Journal of Clinical Anasthesia: 19(5)
Notoatmodjo, S. 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Orsted H, Keast D. (2011). Basic principles of wound healing : An understanding of the basic physiology of wound healing provides the clinician with the framework necessary to implement the basic principles of chronic wound care. Journal of Wound Care Canada, Vol : 9, No : 2.
80
Parveen, Deng, Saeed, Dai, Ahamad & Yu. 2007. Antiinflamatory And Analgesic Activities Of Thesium Chinense Turez Extracts And Its Mayor Flavonoids, Kaempferol And Kaempferol 3-O-Glucoside. Yakugaku Zasshi.
Penkowa, M., Keller, C., Keller, P.,Jauffred, S., and Pedersen, B.K. 2003. Immunohistochemical Detection of Interleukin 6 in Human Skeletal Muscle Fibers Following Exercise. Journal Faseb 17.
Pratiwi, M. 2011. Efek Ekstrak Lerak (Sapindus Rarak Dc) 0,01% Terhadap Penurunan Sel-Sel Radang pada Tikus Wistar Jantan (Penelitian In Vivo). Skripsi. Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara. Medan.
Price AS, Wilson ML. 2006. Patofisiologi Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit. Alih Bahasa: dr. Brahm U. Penerbit. Jakarta: EGC.
Potter PA, Perry AG. Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik.Edisi 4.Vol 2. Alih Bahasa : Renata Komalasari,dkk. Jakarta: EGC.2010.
Purawisastra S. 2001. Pengaruh isolat galaktomanan kelapa terhadap penurunan kadar kolesterol serum kelinci. Warta litbang kesehatan. Vol.5 (3&4). http://[email protected].
Rajavel, Sivakumar, Jagadeeswaran, dan Malliaga. 2007. Evaluation Of Analgesic And Antiinflammatory Activities Of Oscillatoria Willei In Experimental Animal Models. Journal of medicinal plant research vol 3(7).
Rainsfor KD, Powanda MC, Whitehouse MW. 2015. Novel Natural Products: Therapeutic Effects in Pain, Arthritis and Gastro-intestinal Disease. New York : Springer Basel.
Ram D, Cohenca N. 2004. Therapeutic Protocols for Avulsed Permanent Teeth: Review and Clinical Update. Pediatric Dentistry – 26:3
Rieuwpassa IE, Rahmat, Karlina. 2011. Daya hambat ekstrak Aloe vera terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus (studi in vitro). Dentofasial Jurnal kedokteran gigi 10: 65.
Robin. 2007. Granzyme B Plays a Critical Role in Cytotoxic Lymphocyte-induced Apoptosis. Imunological Review Volume 146. Issue 1.
Roitt I. 2001. Essential Immunology. Oxford: Blackwell Science Limited.
Romani B et al. 2017. Functional conservation and coherence of HIV-1 subtype A Vpu alleles. Sci Rep 7:87.
Samuel CE. 2011. The role of gamma interferon in anti-microbial immunity. Curr. Opin. Microbiol
Semba RD, Bloem MW, et al. 2008. Nutrition and Health in Developing Countries.USA: Humana Press.
Sharon, C. A. 2005. The Journal of Care Management Wound Healing, 65 (40) : 778-784.
81
Shashikiran ND, Reddy VS, Nagaveni NB. 2006. Knowledge and Attitude of 2000 Parents (Urban and Rural - 1000 each) with regards to Avulsed Permanent Incisors and their Emergency Management, in and round Davangere. India: J Indian Soc Pedod Prev Dent.
Sigalas E, Regan J, Kramer P, Witherspoon D, Opperman L. 2004. Survival of human periodontal ligament cells in media proposed for transport of avulsed teeth. Dental Traumatol.
Sinno H dan Satya Prakash. 2013. Complements and the Wound Healing Cascade: An Update Review. Hindawi Journal. Vol. 2013.
Smith JB, Mangkoe Widjoyo. 2007. Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan di Daerah Tropis. Universitas Indonesia: Jakarta. Hal 1-18.
Smith, JB. 2000. Pemeliharaan, Pembiakan, dan Penggunaan Hewan Coba di Daerah Tropis. Jakarta : UI Press.
Sudiono, J. Kurniadi, B. Hendrawan, A. Djimantoro,B. 2003. Ilmu Patologi. Editor Janti Sudiono, Lilian Yuwono-Jakarta: EGC. Hal 81-96.
Sulistiawati. 2011. Pemberian Ekstrak Daun Lidah Buaya (Aloe Vera) Konsentrasi 75% Lebih Menurunkan Jumlah Makrofag Daripada Konsentrasi 50% dan 25% Pada Radang Mukosa Mulut Tikus Putih Jantan. Denpasar: Program Studi Ilmu Biomedik Universitas Udayana
Trope M. 2002. Clinical management of the avulsed tooth: Present strategies and future directions. Dental Traumatol.
Velnar, T., T. Bailey, V. Smrkolj. 2009. The Wound Healing Process: an Overview of the Cellular and Molecular Mechanisms. The Journal of International Medical Research.
Walton RE, Torabinejad M. 2008. Prinsip dan praktik ilmu endodonsia. Alih Bahasa. Sumawinata N. Jakarta: EGC: 517-518.
Wheater, Paul R., H. George Burkitt, and Victor G. Daniels. 1979. Functional histology: a text and colour atlas. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Widurini, M. 2003. Pengaruh Daun Lidah Buaya Terhadap Peradangan Jaringan Mukosa Rongga Mulut. Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia: edisi 10: 473-477.
Wiedosari, Ening. 2007. Peranan Immunomodulator Alami (Aloe vera) dalam Sistem Imunitas Seluler dan Humoral. Wartazoa Vol. 17 No.4.
Wolf HF, Rateitschak KH, Hassel TM, 2005. Color Atlas of Dental Medicine: Periodontology. New York: Thieme Stutgart.
Yagi, A., Takeo, S. 2003. Anti inflammatory constituents, aloesin, and aloemannan in Aloe species and effects of tanshinon VI in Salvia milticctorrhiza on heart. Yakugazu Zasshi.
82
Yu ZH, Jin M, Xin M, Jianmin H. 2009. Effect of Aloe vera polysaccharides on immunity and antioxidant activities in oral ulcer animal models. Elsevier: Carbohydrate Polimer 75.
Zakirulla M, Togoo RA, Yaseen SM, Sehri DA, Ghamdi AS, Hafed SA et al. 2011. Knowledge and attitude of Saudi Arabian School Teachers with regards to emergency management of dental trauma. IJCDS.
Zhu J et al. 2017. Clinical Significance of Programmed Death Ligand-1 and Intra-Tumoral CD8+ T Lymphocytes in Ovarian Carcinosarcoma. PLoS One 12:e0170879.