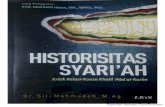masalah keagamaan dan genealogi raden fatah (1483-1518)
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of masalah keagamaan dan genealogi raden fatah (1483-1518)
MASALAH KEAGAMAAN DAN GENEALOGI RADEN FATAH (1483-1518)
Tesis
Diajukan kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Sejarah dan Peradaban Islam
Oleh:
Navida Febrina Syafaaty
21161200100055
Pembimbing:
Prof. Dr. Didin Saepudin, MA.
Konsentrasi Sejarah dan Peradaban Islam
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2021
iii
KATA PENGANTAR
حيم حمن الر بســــــــــــــــــم هللا الر
د كما صليت على سي دنا إبراهيم د وعلى آل سي دنا محم وعلى آل سي دنا اللهم صل على سي دنا محم
د كما باركت على سي دنا إبراهيم وعلى آل سي دنا محم إبراهيم و بارك على د وعلى آل سي دنا محم
سي دنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan
segala rahmat, taufik, iman, islam, ihsan, dan anugerahNya, penulis dapat
menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Masalah Keagamaan dan Genealogi
Raden Fatah (1483-1518)”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, serta berkah dari shalawat kepada
Rasulullah, dan berkah Wali-wali Allah, penulis dapat banyak kemudahan dan
keberkahan hingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini diajukan untuk
memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kajian Islam dengan konsentrasi
Sejarah dan Peradaban Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, bantuan, dan
kritikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk kedua
orang tua saya. Penelitian ini terselesaikan tentu berkat dukungan penuh baik moril
maupun materil serta doa dan sholawat dari kedua orang tua tercinta, yaitu Hj. Nana
Romadhona dan Almarhum H. Suwarno Mukti Wibowo.
Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk guru
saya, yaitu KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghoni/Abah Guru Sekumpul dan KH.
Ahmad Muzakki Kamali berkat dukungan penuh, doa, shalawat, motivasi, dan ilmu.
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Didin Saepudin,
MA selaku promotor yang telah membimbing, memberikan motivasi, mengarahkan,
dan memberikan kritik dan saran dalam penulisan penelitian ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA, dan kepada Prof. Dr. Phil.
Asep Saepudin Jahar, MA dan Arif Zamhari, M.Ag, Ph.D selaku Direktur dan Ketua
Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta serta para staf akademik yang telah banyak membantu selama
proses pembelajaran penulis tempuh.
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para penguji yang telah
menguji, memberikan kritik saran, dan ilmunya, yaitu Prof. Iik Arifin Mansurnoor,
MA, Dr. JM Muslimin, Dr. Kusmana, MA, Arif Zamhari, M.Ag, Ph.D, Dr. Abd.
Chair, MA, Prof. Dr. Dien Madjid, Dr. Hamka Hasan, MA, Prof. Dr. Jajat
Burhanuddin, MA, Prof. Dr. Budi Sulistiono, M.Hum, dan Dr. Imam Sujoko, MA.
Terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmunya, yaitu Prof. Dr.
Azyumardi Azra, MA, Prof. Dr. M. Atho Mudzar, MSPD, MA, Ph.D, Prof. Dr.
Suwito, MA, Prof. Masykuri Abdillah, MA, Prof. Abd. Ghani Abdullah, SH, MH,
iv
Prof. Dr. Said Agil Husain Al Munawwar, MA, Prof. Dr. Oman Fathurahman,
M.Hum, Fuad Djabali, MA, Ph.D, Prof. Dr. Abuddin Nata, MA, Prof. Dr. Din
Syamsuddin, Prof. Dr. Salman Harun, dan Dr. Ahmad Zubair, M.Ag dan para dosen
lainnya. Terima kasih juga kepada seluruh civitas akademika dan Perpustakaan
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga saya, yaitu nenek
Almarhumah Hj. Siti Kursiyah, paman H. Rifki Arselan, paman H. Ronnie
Muhammad Syakir, kakak Naila Chandra Qorina, adik Asrina Syafaati Arselan,
keluarga Al Banjari di Banjarmasin H. Syaifuddin Fachri, Hj. Faterah, H. Mawardi,
dan Hj. Raudatul Jannah, dan keluarga Datu Marwan Al Banjari. Terima kasih
kepada keluarga besar H. Abdullah Syukri Noor Al Banjari dan keluarga besar Mbah
Mangun Pawiro di Kulon Progo, D.I Yogyakarta atas segala doa dan dukungannya.
Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk Keluarga
Ningrat Sukapura, yaitu Raden Haji Ahmad Dimyati yang telah membimbing,
memberikan motivasi, mengarahkan, dan memberikan kritik dan saran dalam
penulisan penelitian ini, Kiai Raden Eeng Hendriyana sebagai Sesepuh Sukapura,
Raden Dicki Z Sastradikusumah, Raden Ahmad Qohar Dipanagara, Raden Agus
Wirabudiman, dan Tb. Solihin.
Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Keluarga Ningrat
Limbangan yaitu KH. Raden Amin Muhyidin sebagai Ketua Syuriah Nahdatul
Ulama (NU) Garut dan Pengasuh Pondok Pesantren Asyaadah Limbangan Garut, H.
Raden Holil Aksan Umar Zen sebagai Ketua PM Gatra, KH. Raden Usman Muhyidin
sebagai Ketua KBC Limbangan Garut, KH. Raden Husni Mubarak (Pondok
Pesantren Cikurutug Cicalengka Bandung, KH. Raden Amang Syihabuddin (Pondok
Pesantren Neglasari Limbangan), KH. Raden Jujun Junaedi (Pondok Pesantren Al
Goniyah Limbangan), dan KH. Raden Ahmad Fidadi (Pondok Pesantren Al Faruq
Cicalengka Bandung).
Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Yusuf
Bahtimi, MS, Pak M. Yunan Helmi Fakaubun, Pak Tanto, dan Pak Sinung atas segala
doa, dukungan, arahan, dan diskusi tentang sejarah.
Penulis ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat selama kuliah,
angkatan Genap 2017, kepada Ahmad Labib, Eryzka, Waki, Mas Ikfil, Taher,
Husnul, Khairani, Mbak Devy, Bang Salikin, Bang Arman, dan Bang Amirul. Terima
kasih juga kepada para sahabat dari Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dan
Sahabat Shalawat, yaitu Sarifah Dacosta Vidigal, Syela Putri Rasani, Rizky
Yulandari, dan almarhumah Herweningtyas Rakhmadani. Terima kasih kepada
Greta, Imanurul, Ardin, Rizki Banjari, Ammar, Kak Yeni, dan Mas Parman. Terima
kasih juga kepada para guru di Majelis Zikir Tawakal Depok. Terima kasih kepada
komunitas Lingkar Filologi Ciputat (LFC).
Akhir kata, tidak ada kata sempurna dalam setiap langkah dan pemikiran
manusia, demikian juga penelitian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dan
kesalahan. Maka sebagai insan akademisi, penulis mengharapkan kritik dan saran
dari semua pihak demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa yang akan datang.
v
Atas berbagai bantuan tersebut, saya mohon kepada tersayang tercinta terkasih
Allah SWT Maha Pengasih Penyayang dan Habibuna Sayyiduna Rasulullah Nabi
Muhammad SAW Sang Penghulu Yang Mulia agar membalas kepada semua pihak
yang telah membantu saya dengan balasan kebaikan lahir batin yang sempurna,
keberkahan, keselamatan dalam hidup, sukses, sehat, panjang umur, bahagia, kaya,
dan jaya dunia akhirat.
Jakarta, 12 Januari 2021
Navida Febrina Syafaaty, S.KPm, MA
vi
ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengkaji tentang Masalah Keagamaan dan Genealogi
Raden Fatah (1483-1518). Selama ini Raden Fatah ditulis sebagai penerus dari
Kerajaan Hindu Majapahit. Selain itu silsilah dan riwayat Raden Fatah ditulis sebagai
putra Raja Hindu Majapahit terdapat perbedaan dalam penulisan sejarah.
Dalam tulisan H.J De Graaf dan TH. Pigeaud, menurut cerita tradisi Mataram
Jawa Timur, Raja Demak yang pertama adalah Raden Fatah, putra Raja Majapahit
yang terakhir yang dalam legenda bernama Brawijaya. Menurut Agus Sunyoto
tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Fatah terjadi perbedaan
pendapat yaitu sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya Maharaja Majapahit yang
berkuasa pada 1447-1451 M, dan sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Maharaja
Majapahit yang berkuasa 1474-1478 M. Maka dari itu, kajian ini ingin menjelaskan
mengenai bagaimana silsilah Raden Fatah sebenarnya? dan bagaimana kedudukan
Raden Fatah dengan para Wali Penyebar Islam dan hubungan Raden Fatah terhadap
raja-raja Hindu?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
model kajian pustaka guna memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penulis
melakukan penelitian dengan 5 tahap, yaitu pemilihan topik penelitian, teknik
pengumpulan data, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Adapun dalam teknik
pengumpulan data terdapat 2 sumber yaitu primer menggunakan Suma Oriental karya
Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues
disunting oleh Armando Cortesao dan sekunder menggunakan catatan-catatan Ulama
dari Sukapura, Limbangan, dan Sumedang, kitab-kitab ulama, buku-buku para
sejarawan, dan tulisan ilmiah.
Penelitian ini menemukan bahwa 1) Kakek Raden Fatah berasal dari Gresik
dan Penguasa Cirebon, tokoh tersebut bernama Sunan Rumenggong Raja Islam Sunda
Pajajaran alias Prabu Siliwangi IV alias Prabu Brawijaya IV. Ayah Raden Fatah
adalah seorang ksatria yang bernama Prabu Cakrabuana III alias Kertabumi alias
Prabu Siliwangi V alias Prabu Brawijaya V, 2) Raden Fatah memiliki hubungan yang
erat dengan para penguasa Moor (Islam) di Jawa dan kekerabatan dengan tokoh-tokoh
Walisongo dan Raden Fatah tidak memiliki hubungan keluarga dengan Raja Hindu
Daha.
Kata Kunci: Agama Orang Tua Raden Fatah, Kiprah Raden Fatah, Silsilah dan
Riwayat Raden Fatah.
vii
ABSTRACT
This research aims to examine The Religious and Genealogy Problems of
Raden Fatah (1483-1518). During this time, Raden Fatah was written as the successor
of Majapahit Hindu Kingdom. In addition, there are differences in historical writing
about the genealogy and history of Raden Fatah written as son of King Hindu
Majapahit.
In the writings of H.J. De Graaf and TH. Pigeaud, based on the story of East
Java Mataram tradition, the first King Demak was Raden Fatah, the last son of
Majapahit King who in the legend named Brawijaya. According to Agus Sunyoto,
there are also differences opinion about who is Prabu Brawijaya that became father of
Raden Fatah. Some states telling Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit ruled in
1447-1451 AD, and some stated Kertabumi, Maharaja Majapahit ruled in 1474-1478
AD. Therefore, this research wants to explain how Raden Fatah genealogy actually is
and relationship between Raden Fatah and Wali Penyebar Islam (the scholars) and
Hindu Kings.
The method used is qualitative method with library study model to obtain the
required data. The author conducted research with 5 stages, namely the selection of
research topic, data collection technique, verification, interpretation, and writing.
There are 2 sources of data collection technique, namely the primer using Suma
Oriental by Tome Pires: Travel from The Red Sea to China and Francisco Rodrigues
book edited by Armando Cortesao and secondary using the records of Ulama from
Sukapura, Limbangan, and Sumedang, books of scholars, books of historians, and
scientific writings.
This study found that 1) Raden Fatah's grandfather came from Gresik and
King of Cirebon named Sunan Rumenggong Raja Islam Sunda Pajajaran, also known
as Prabu Siliwangi IV and/or Prabu Brawijaya IV. Raden Fatah's father was a knight
who named Prabu Cakrabuana III also known as Kertabumi and/or Prabu Siliwangi
V, and/or Prabu Brawijaya V. 2) Raden Fatah had a close relationship with the
Moorish rulers (Islam) in Java and kinship with the figures Walisongo, also Raden
Fatah did not have a relationship with the Hindu King Daha.
Keywords: Raden Fatah Parents’ Religion, Raden Fatah's Work (track record),
Genealogy and History of Raden Fatah.
viii
خالصة البحث
الدراسة تهدف لدى هذه واألنساب الدينية المشاكل فحص فتاح إلى رادين
وريث عرشحتى اآلن، تحدثت جل كتب التاريخ عن رادين فتاح بأنه (.1518- 1483)
يثير األمر هذا ووأنه من ابن ملك ماجاباهيت الهندوسي. ماجاباهيت الهندوسية،مملكة
وجهات نظر مختلفة حول الموضوع في كتب التاريخ.
جاوي، الماتارام لقصص عنوفقا ، ه.ج دي جراف و ت.ه. بيجياود كتابات في
كان رادين فتاح ، ابن آخر ملوك ماجاباهيت المسمى براويجايا ، أول ملوك ديماك. وفقا
ألجوس سونيوتو، هناك نسختان تاريخيتان تتعلقان بوالد رادين فتح. أوال ، المصدر الذي
. ثانيا، م 1451- 1447الذي حكم في وكان ملك ماجاباهيت كيرتاويجاياالملك هأنب يقول
1478-1474الذي حكم في كيرتابومي وكان ملك ماجاباهيت هأنب يقولالمصدر الذي
النسب الحقيقي لرادين فتاح ، وما هو موقف رادين تفصل لذلك، تريد هذه الدراسة أن .م
فتاح مع أولياء اإلسالم، والعالقة بين رادين فتاح وملوك الهندوس .
نموذج مراجعة األدبيات المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو أسلوب نوعي مع
من أجل الحصول على البيانات المطلوبة. ويجري المؤلف هذه الدراسة في خمس مراحل:
التفسير، والكتابة. و في مرحلة جمع البيانات، التحقيق، اختيار موضوع البحث، جمع
الذى البيانات ، استحدم المؤلف نوعان من المصادر: أساسي باستخدام سوما أورينتال
رحلة من البحر األحمر إلى الصين وكتاب فرانسيسكو رودريغيز من : الفه توما بيريس
كورتساو أرماندو أتحرير من ما . التاريخية التوثيقات باستخدام الثانوي المصدر
أخرى ذات صلة من العلماء والمؤرخين، سوكابورا و ليمبانجان و سوميدانج ، وكتب
ورسائل علمية.
( أن جد رادين فتاح من أصل جريسيك وكان حاكم 1هذه الدراسة تنتج ما يلي:
تشيريبون، وهو سونان ريمينغجونغ، وهو ملك مسلم لسوندا باجاجاران، الملقب بالملك
سيليوانجي الرابع أو الملك براويجايا الرابع. أما والد رادين فتاح فكان فارسا المشهور
الثالث أو برابو سيليوانجي الخامس باسم بانجيران تشاكرابوانا الملقب ببرابو تشاكرابوانا
الخامس. برابو براويجايا المغاربة في 2أو له عالقة وثيقة مع حكام فتاح ( أن رادين
جاوى، وكان له صلة قرابة بواليسونغو. كما أن رادين فتاح ال عالقة له بالملك الهندوسي
على اإلطالق. داها
دور رادين فتاح، نسب وتاريخ رادين فتاح : ديانة والدي رادين فتاح، الكلمات المفتاحية
ix
PEDOMAN TRANSLITERASI
Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dipedomani dalam penulisan jurnal
Al-Tahrir adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu sebagai
berikut:
Huruf
Q = ق Z = ز ’ = ء
K = ك S = س B = ب
L = ل Sh = ش T = ت
M = م {s = ص Th = ث
N = ن {d = ض J = ج
W = و {t = ط {h = ح
H = ه {z = ظ Kh = خ
Y = ي ‘ = ع D = د
Gh = غ Dh = ذ
F = ف R = ر
Ta>’ marbu>t}a tidak ditampakkan kecuali dalam susunan ida>fa, huruf tersebut
ditulis t. Misalnya: فطانة = fat}a>nah; فطانة النبي = fat}a>nat al-nabi>
Diftong dan Konsonan Rangkap
<u = او Aw = او
<i = أي Ay = أي
Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului d}amma dan
huruf ya>’ yang didahului kasra seperti tersebut dalam tabel.
xi
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME i
PERSETUJUAN HASIL UJIAN TESIS ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
viii خالصة البحث
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan 4
1. Identifikasi Masalah 4
2. Perumusan Masalah 5
3. Pembatasan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Metodelogi Penelitian 6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 7
G. Sistematika Penulisan 11
BAB II RIWAYAT RADEN FATAH MENURUT KEPUSTAKAAN
SEJARAH
12
A. Diskursus tentang Persoalan Sumber 13
1. Pendapat Sejarawan mengenai Sumber-Sumber yang terkait
Genealogi Raden Fatah
13
2. Pendapat Sejarawan mengenai Cempa dan Champa 19
B. Riwayat Raden Fatah dalam berbagai Sumber Lokal menurut
Sejarawan
23
1. Babad Tanah Jawi 23
2. Serat Kanda 27
3. Serat Pararaton 27
4. Carita Purwaka Caruban Nagari 28
5. Sadjarah Banten 28
6. Hikayat Hasanudin 30
BAB III GENEALOGI ISLAM RADEN FATAH DALAM
HISTORIOGRAFI ULAMA SUNDA
31
A. Sumber-Sumber yang digunakan 31
1. Sejarah Pencacatan Sejarah Sukapura 31
2. Babon Sukapura dan Sanad Riwayat Ulama 33
3. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan 36
a. Catatan Rukun Warga Limbangan 36
b. Catatan yang ditulis oleh KH. Atung Aunillah 37
4. Kitab Al Fatawi 37
5. Suma Oriental karya Tome Pires 39
B. Silsilah Raja-Raja Sunda Pajajaran 40
xii
1. Silsilah Pajajaran versi Kitab Al Fatawi 40
2. Silsilah Raja-Raja Pajajaran versi Babon Sukapura dan Para
Ulama Limbangan
41
a. Silsilah Pajajaran versi Babon Sukapura dan Ningrat
Limbangan
41
b. Prabu Layakusumah dan Gelar Siliwangi 45
c. Pangeran Cakrabuana 48
d. Kerajaan Sumedang Penerus Pajajaran 49
C. Silsilah Raden Fatah Sultan Demak 51
1. Hubungan Raden Fatah dengan Arya Damar 51
2. Ayah Raden Fatah adalah Ksatria 51
3. Penguasa Japura adalah Sepupu Raden Fatah 51
4. Gelar Brawijaya dan Susunan Silsilah Raden Fatah 53
5. Kakek Raden Fatah dari Gresik dan Penguasa Cirebon 58
6. Silsilah Sunan Rumenggong versi Kedua, Kakek Raden
Fatah
60
7. Pengertian Gelar Sunan versi Ulama dan Bukti Raja-Raja
Pajajaran adalah Islam
61
8. Pengertian Gelar Raden versi Ulama 62
BAB IV JARINGAN ISLAM DAN KEKUASAAN RADEN FATAH 63
A. Kerajaan Islam Pajajaran dan Kerajaan Hindu Daha 63
1. Pajajaran Barat, Pusat, dan Timur 63
a. Wilayah Kekuasaan 63
b. Nama Pajajaran 64
c. Struktur Pemerintahan Kerajaan Sunda dan Majapahit
adalah Kerajaan Sunda Timur
64
d. Bentuk Kerajaan Sunda 65
2. Penjelasan Tulisan Tome Pires mengenai Sunda 66
a. Kerajaan Sunda Pedalaman dan Kerajaan Sunda
Pajajaran
66
b. Pembahasan mengenai Polemik Riwayat antara Raden
Fatah dan Pati Unus
73
1) Nama Sabrang Lor 73
2) Raden Yunus dan Pati Unus 2 76
c. Hubungan Raja Sunda Pajajaran dengan Cina 78
B. Hubungan Raden Fatah dengan Raja Hindu Jawa dan Para Wali
Penyebar Islam
81
1. Kerajaan Hindu Daha atau Kerajaan Jawa Pedalaman 81
a. Wilayah Kekuasaan 81
b. Silsilah Raja Jawa Pedalaman atau Raja Hindu Daha 83
c. Prau Cakrabuana III dan Batara Vojyaya 86
2. Hubungan Raden Fatah dengan Para Wali Penyebar Islam 89
a. Hubungan Kekerabatan Raden Fatah dengan Para
Penguasa Pantai Utara Jawa
89
b. Hubungan Erat Raden Fatah dengan Tokoh Walisongo 92
C. Berdirinya Kesultanan Demak 93
xiii
1. Portugis merebut Malaka 93
2. Raden Fatah dimata Bangsa Portugis 94
3. Raden Fatah diangkat menjadi Sultan Demak 94
4. Pemicu terjadi Perang Malaka 95
5. Perang Malaka 1512-1513 M 97
6. Semua Tindakan Pati Unus atas Perintah dan Persetujuan
Raden Fatah
99
7. Kehancuran Kerajaan Hindu Daha 101
8. Wafat Raden Fatah 101
D. Perbandingan Silsilah dan Riwayat Raden Fatah dari berbagai
Sumber
102
BAB V PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 108
DAFTAR PUSTAKA 109
GLOSARIUM 114
INDEKS 115
BIODATA PENULIS 120
LAMPIRAN 121
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kesultanan Demak berdiri melalui proses dan kurun waktu yang cukup
panjang. Berawal dari kawasan hutan mangrove di pesisir utara Jawa Tengah. Dari
semula bernama Dukuh Kenep dan kemudian munculnya Dukuh Glagahwangi dan
kemudian akhirnya berdiri sebuah Negara bernama Kesultanan Demak Bintoro.
Semua itu tidak terlepas dari peran Walisongo dan Raden Fatah. Suatu Negara tidak
mungkin terbentuk tanpa ada yang mengawali dan mempeloporinya. Demikian juga
dengan keberadaan Kesultanan Demak Bintoro.1
Raden Fatah adalah putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Raden
Fatah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan
dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Sebagai penguasa,
negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden
Fatah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan
ajaran Islam.2
Di kawasan pesisir utara Jawa bagian tengah, Raden Fatah yang memiliki
nama kecil Raden Hasan memusatkan kegiatannya di Glagahwangi, karena daerah
tersebut direncanakan oleh para Wali sebagai pusat pemerintahan Islam di Jawa kelak.
Di Glagahwangi, Raden Fatah juga mendirikan Pondok Pesantren Glagah Arum.
Penyiaran agama dilaksanakan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.3
Pendirian Pondok Pesantren tersebut dikarenakan semakin banyak santri yang belajar
agama Islam sehingga rumah beliau tidak dapat menampung santri yang datang dan
menetap. Raden Fatah mendirikan Pondok Pesantren Glagah Arum tahun 1476 M
dengan kapasitas 2000 santri.4
Keberhasilan Raden Fatah mengembangkan Demak mengantarnya menjadi
Adipati Anom Bintoro.5 Wilayah Kesultanan Demak pada awalnya hanya sebuah
bawahan dari Kerajaan Majapahit,6 sebagai kadipaten. Asal usul wilayah Demak
Bintoro adalah kawasan hutan yang banyak terdapat rawa atau paya-paya. Pada 1466
M, Raden Fatah mulai membuka hutan mangrove di pesisir utara pulau Jawa tersebut.
Pembukaan hutan dilakukan atas perintah Sunan Ampel setelah mendapat persetujuan
Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir, ayah dari Raden Fatah.7 Menurut
1Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram (Demak:
Galang Ideapena Demak, 2015), hal 32. 2Agus Sunyoto, Atlas Walisongo (Bandung: Iiman, 2012), hal 318. 3Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 33. 4Muhammad Khafid Kasri, Sejarah Demak Matahari Terbit Di Glagah Wangi
(Demak: Syukur, 2008), hal 40. 5Umma Farida, “Islamisasi Di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-
Umara dalam Dakwah Islam di Demak,” Jurnal At Tabsyir Komunikasi Penyiaran Islam, Vol.
3 No. 2, (Desember 2015): 303. 6Soedijipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal 299. 7Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 33.
2
Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang (1975), karena hubungan
baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai
keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit.8
Raden Fatah dan Walisongo melanjutkan pembangunan Masjid Agung
Demak yang dimulai pada 1477 M.9 Masjid Agung Demak yang dikenal sebagai
masjid agung tertua karena dibangun untuk menandai Kesultanan Islam pertama di
Jawa pada abad ke 15.10 Raden Fatah awalnya ketika menetap di Demak tahun 1475
M, beliau mendirikan masjid kecil. Berdasarkan sejarah yang berkembang sejak
zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa berkembangnya masyarakat Islam dan
berdirinya Islam diawali dengan didirikannya sebuah masjid. Oleh karenanya,
berdirinya Masjid Agung Demak berawal dari berkembangnya masyarakat Islam di
Glagahwangi, selanjutnya berkembang menjadi Kadipaten dan akhirnya menjadi
Kesultanan Demak Bintoro.11 Dan juga sejarah Masjid Agung Demak erat kaitannya
dengan dakwah Walisongo. Bangunan masjid didirikan oleh Walisongo bersama-
sama.12
Walisongo membawa Islam ke Jawa menanamkan simbol-simbol kekuasaan
Jawa ke dalam struktur bangunan masjid agung untuk menjadikan Islam bagian dari
dunia Jawa. Masjid Demak bisa menyatukan antara Islam di Timur Tengah dengan
Islam di Jawa yang diekspresikan dalam bentuk dan ruang Masjid Agung Demak dan
kisah-kisah sejarah di belakang bangunan. Masjid Agung Demak mewakili kekuataan
agama Islam di Jawa.13
Sejarah Peradaban Islam menjelaskan, pengembangan agama Islam di Jawa
bersamaan dengan melemahnya posisi Raja Majapahit. Hal tersebut memberi peluang
kepada ulama-ulama Islam untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang
independen berlandaskan Islam.14 Kesultanan Demak yang didirikan dengan cara
penuh kedamaian,15 Cara berdakwah Walisongo yang dilakukan dengan cara yang arif
8Agus Sunyoto, Atlas Walisongo (Bandung: Iiman, 2012), hal 154. 9Muhammad Khafid Kasri, Sejarah Demak Matahari Terbit Di Glagah Wangi
(Demak: Syukur, 2008), hal 55. 10Abidin Kusno, “The Reality of One Which Two: Mosque Battles and Other Stories”
Notes on Architecture, Religion, and Politics in the Javanese World,” Journal of Architecture
Education, Vol. 57 No. 1 (September 2003): 59. 11Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 41. 12Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa
(Yogyakarta: Pustaka Utama, 2012), hal 39. 13Abidin Kusno, “The Reality of One Which Two: Mosque Battles and Other Stories”
Notes on Architecture, Religion, and Politics in the Javanese World,” Journal of Architecture
Education, Vol. 57 No. 1 (September 2003): 59-60.
14Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Jakarta: Rajawali
Press, 2010), hal 210. 15Tri Tunggal Dewi, Wakidi, dan Suparman Arif, “Peranan Sultan Fatah dalam
Pengembangan Agama Islam di Jawa,” Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, Vol. 5 No.
8 (2017).
3
dan bijaksana.16 Usaha dan proses islamisasi yang dilakukan para penyiar Islam terus
berlangsung. Mereka memperkenalkan Islam dengan pendekatan bijak tanpa
melawan tradisi lokal yang dianut kaum pribumi. Salah satu pesan yang ditawarkan
adalah bahwa Islam adalah agama toleransi dan persamaan derajat, tanpa unsur
penggolongan dalam masyarakat.17 Islam di Nusantara dianggap bukan Islam yang
sebenernya karena bercampur dengan budaya lokal pada intinya Islam di nusantara
berbeda dengan Islam di Timur Tengah. Kita tentu saja tidak menolak adanya
pengaruh lokal tersebut, tetapi untuk menyebut tradisi Islam di Nusantara tidak
mempunyai kaitan Islam di Timur Tengah jelas merupakan kekeliruan amat fatal.18
Sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, Kesultanan Demak sangat
berperan dalam proses islamisasi.19 Metode pelokalan budaya global untuk
melanjutkan simbolisme tradisional dengan cara yang berbeda tetapi tidak radikal.
Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan dakwah Islam bisa dipahami dengan
damai ini adalah perjuangan untuk menyebarkan agama Islam dan mempertahankan
keseimbangan antara budaya Jawa dan Islam.20 Maka dari itu, masyarakat Jawa sangat
mengenal dan menghormati para wali. Walisongo adalah ahli agama yang
memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan sekaligus sebagai
pelopor dan penggerak komunitas Islam di Demak. Dalam perkembangan selanjutnya
komunitas Islam Demak Bintoro ini menguasasi hegemoni politik dan
pemerintahan.21
Kesultanan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat
penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu
Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan.22 Disamping yang sudah ada
di Jepara, Gresik, Ampel, Cirebon, dan Banten, bahkan diberitakan sampai di
Mindanao-Filipina selatan dan Papua bagian utara.23 Kesultanan Demak adalah pusat
penyebaran Islam di Pulau Jawa dan menjadi tempat berkumpulnya para Wali. Para
16A.R Idham Kholid. “Walisongo: Eksistensi Dan Perannya Dalam Islamisasi Dan
Implikasinya Terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi Di Tanah Jawa,” Jurnal Tamaddun, Vol.4
No. 1, (Januari-Juni 2016): 1-47, hal 1. 17 Didin Saefuddin, Sejarah Politik Islam (Depok: Penerbit Serat Alam Media, 2017)
hal 343.
18Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII dan XVIII (Jakarta: Kencana, 2007), hal xix. 19M Nur Rokhman, Lia Yuliana, dan Zulkarnain, “Pengembangan Maket Pusat
Kerajaan Demak Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Di SMA,” Prosiding Seminar
Nasional, hal 385. 20Abidin Kusno, “The Reality of One Which Two: Mosque Battles and Other Stories”
Notes on Architecture, Religion, and Politics in the Javanese World,” Journal of Architecture
Education, Vol. 57 No. 1 (September 2003): 60.
21Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 13. 22Ana Ngationo, “Peranan Raden Fatah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak
Pada Tahun 1478-1518,” Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, Vol. 4 No. 1
(Juli 2018), hal 20.
23Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 13.
4
Walisongo memiliki peranan yang penting pada masa perkembangan Kesultanan
Demak dan menjadi penasehat untuk Raja-raja Demak.24
Demak memang strategis tempatnya. Letak Demak sangat menguntungkan,
baik untuk perdagangan maupun pertanian. Demak terletak di tepi selat di antara
Pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya selat itu agak lebar dan dapat dilayari
dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan pintas itu
untuk berlayar ke Rembang.25 Maka dari itu, Demak berkembang menjadi Kerajaan
Maritim. Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah di
Indonesia bagian timur dan bagian barat. Kesultanan Demak juga memiliki wilayah
di pedalaman maka Demak juga memperhatikan pertanian, sehingga beras menjadi
salah satu komoditas dagang. Selain itu, Demak juga menjual produksi andalannya
garam dan kayu jati.26
Kesultanan Demak dengan mendapat dukungan penuh, mampu tampil
sebagai Keraton Islam yang teguh, kokoh, dan berwibawa. Dalam pergaulan
antarbangsa, Kesultanan Demak merupakan juru bicara kawasan Asia Tenggara yang
sangat disegani. Hal ini disebabkan oleh kontribusi Kesultanan Demak dalam bidang
ekonomi, pelayaran, perdagangan, kerajinan, pertanian, pendidikan, dan
keagamaan.27
Kesultanan Demak Bintoro, merupakan Kesultanan Islam yang mendapat
pengaruh besar dari para ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai suatu
negara yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara, Kesultanan Demak
Bintoro memiliki suatu cerita yang heroik namun sangat beragam. Kehadiran dan
penyebaran agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa telah dibuktikan berdasarkan data
arkeologis dan sumber-sumber babad, hikayat, legenda, serta berita-berita asing.28
Menurut Graaf dan Pigeaud bahwa dalam cerita tradisi Mataram Jawa Timur,
raja Demak yang pertamma Raden Fatah adalah putra raja Majapahit yang terakhir
(dari zaman sebelumm Islam), yang dalam legenda bernama Brawijaya. Ibu Raden
Fatah konon seorang putri Cina dari keraton raja Majapahit. Waktu hamil putri itu
dihadiahkan kepada seorang anak emasnya yang menjadi gubernur di Palembang. Di
situlah Raden Fatah lahir.29 Menurut Agus Sunyoto dalam historiografi Jawa
menuturkan bahwa Raden Fatah adalah putra Prabu Brawijaya, raja Majapahit
terakhir. Tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Fatah terjadi
perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit
24Soedijipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi (Yogyakarta: Laksana, 2013), hal 324. 25Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 33. 26Soedijipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi, hal 324.
27Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 1. 28Tri Tunggal Dewi, Wakidi, dan Suparman Arif, “Peranan Sultan Fatah dalam
Pengembangan Agama Islam di Jawa,” Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, Vol. 5 No.
8 (2017). 29H.J De Graaf dan Th. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI dari judul asli De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java, Studien
Over de Staatkundige Geschiedenis van de 15 de en 16 de Eeuw diterbitkan sebagai No 69 seri
Verhandelingen van het KITLV No 029/85 (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti), hal 42.
5
yang berkuasa pada 1447-1451 M, sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Maharaja
Majapahit yang berkuasa 1474-1478 M.30
Dalam tulisan Tome Pires bahwa penguasa Cirebon merupakan kakek dari
(Pate Rodim) Raden Fatah.31 Ayah Pate Rodim adalah seorang kesatria dan bijak
dalam mengambil keputusan sedangkan kakek Pate Rodim berasal dari Gresik.32
Menurut Graaf dan Pigeaud bahwa dalam buku Pires menulis orang Gresik itu elle
veio teer a Dema, yang oleh penerbitnya berkebangsaan Portugis, Cortesao
diterjemahkan menjadi he happened to go to Demak (Dimana pun Pires tidak pernah
mmengatakan dengan tegas bahwa orang dari Grresik itu orang Islam. tetapi tepat asal
Gresik, pusat tertua agama Islam di Jawa Timur, dapat merupakan petunjuk
keislamannya).33
Berdasarkan tulisan-tulisan di atas bahwa sumber-sumber yang telah
digunakan sebagai sumber rujukkan untuk mengindentifikasikan kedudukan Raden
Fatah masih terdapat perbedaan dalam penulisan sejarah terutama dalam hal terkait
keagamaan dan genealogi orang tua Raden Fatah. Dari hal tersebut penulis
menggunakan sumber yaitu tulisan dan sanad riwayat para Ulama, tulisan-tulisan
Ulama, dan tulisan-tulisan asing. Adapun tesis ini bermaksud untuk mengkaji tentang
masalah keagamaan dan genealogi Raden Fatah (1483-1518 M).
B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas dapat diindetifikasi
masalah sebagai berikut:
a. Silsilah dan riwayat dari Raden Fatah terdapat perbedaan dalam penulisan
sejarah.
b. Penulisan nasab Raden Fatah dari sanad Ulama belum ada sejarah tersebut.
c. Penulisan kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan
hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu belum ada penjelasan yang
ilmiah.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang hendak dibahas
adalah:
1. Bagaimana silsilah Raden Fatah sebenarnya?
2. Bagaimana kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan
hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu?
30Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320.
31Armando Cortesao, Suma Oriental karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah
ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues diterjemahkan dari buku The Suma Oriental of Tome
Pires An Account of The East, From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues
edited by Armando Cortesao 2 Volume (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), hal 255.
32Tome Pires, Suma Oriental, hal 257.
33H.J De Graaf dan Th. Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 42-43.
6
3. Pembatasan Masalah
Fokus utama dalam penelitian ini adalah Masalah Keagamaan dan Genealogi
Raden Fatah, dari lahir (1483 M) sampai wafatnya Raden Fatah (1518 M). Maka dari
itu pembatasan masalah penelitian ini, yaitu: silsilah Raden Fatah sebenarnya,
kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam, dan hubungan Raden
Fatah terhadap raja-raja Hindu.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk diketahui Apakah benar Raden Fatah putra dari
raja Hindu. Hal ini akan dianalisis dalam disiplin ilmu yang penulis pelajari. Oleh
karena itu, secara khusus tujuan penulis mengangkat topik ini yaitu:
1. Menganalisis silsilah Raden Fatah sebenarnya.
2. Menganalisis kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan
hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini sebagaimana diterangkan sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi
pengembangan disiplin ilmu sejarah pada umumnya dan Sejarah Islam di
Nusantara pada khususnya, tentang penelitian Masalah Keagamaan dan
Genealogi Raden Fatah (1483-1518 M).
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi silsilah Raden Fatah,
kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan hubungan
Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu.
2. Manfaat Praktis
a. Lembaga
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan bagi pihak
lembaga-lembaga penelitian di bidang sejarah.
b. Sejarawan
Memberi kontribusi ilmiah pada kajian Sejarah Islam di Nusantara,
menambah wawasan tentang Masalah Keagamaan dan Genealogi Raden
Fatah dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi
peniliti sejarawan lainnya.
E. Metodelogi Penelitian
Dalam tujuan studi ini adalah untuk mencapai penulisan sejarah, maka upaya
merekonstruksi masa lampau dari objek yang diteliti itu ditempuh melalui metode
kualitatif dengan model kajian pustaka, yaitu menganalisis dan menjelaskan Masalah
Keagamaan dan Geneaologi Dalam Kepemimpinan Politik Raden Fatah (1483-1518
7
M). Oleh karena itu, penelitian sejarah mempunyai lima tahap34, yaitu: (1) pemilihan
topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi, (4) interpretasi, dan (5) penulisan.
1. Pemilihan Topik Penelitian
Topik penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang sejarah Raden Fatah.
Batasan penulis adalah silsilah Raden Fatah sebenarnya, kedudukan Raden Fatah
dengan para Wali penyebar Islam dan hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja
Hindu.
2. Heuristik atau teknik pengumpulan data
Dalam pengumpulan data-data untuk bahan penulisan ini, penulis melakukan
penelitian kepustakaan, wawancara, dan studi naskah. Penulis juga melakukan
penelitian ke beberapa perpustakaan dengan merujuk kepada sumber-sumber yang
berhubungan dengan tema dalam tesis ini, seperti buku-buku, tesis, disertasi, dan
jurnal.
Dalam hal ini, catatan Tome Pires tentang Raden Fatah, merupakan sebuah
sumber primer. Penulis juga akan mencari buku-buku, jurnal, tesis, dan disertasi
tentang Raden Fatah sebagai sumber sekunder.
a. Primer
Adapun data primer dari penelitian ini yaitu: dokumentasi tertulis: Suma
Oriental karya Tome Pires. 1) The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The
East, From The Red Sea To Japan, written in Malacca and India in 1512-1515 and
The Book of Francisco Rodrigues Rutter of Voyage In The Red Sea, Nautical Rules
Almanack and Maps, Written and Drawn in The East Before 1515, Translated from
the Portuguese MS in the Bibliotheque de la Chambre des Deputes, Paris and edited
by Armando Cortesao, Volume I, London printed for The Hakluyt Society 1944, 2)
Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku
Francisco Rodrigues diterjemahkan dari buku The Suma Oriental of Tome Pires An
Account of The East, From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues,
edited by Armando Cortesao, 2 volume, The Hakluyt Society, 1944, diterbitkan
pertama kali dalam Bahasa Indonesia oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI),
Yogyakarta, 2015, penyunting edisi asli oleh Armando Cortesao, penerjemah edisi
Indonesia oleh Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti.
b. Sekunder
Data sekunder diambil dari catatan-catatan Ulama, kitab-kitab Ulama, sanad
riwayat Ulama, naskah-naskah lokal, buku-buku pendukung penelitian yaitu buku-
buku para sejarawan baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Serta tulisan ilmiah
34Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal 69.
8
seperti tesis, disertasi, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dan
pembahasan penelitian ini.
3. Verifikasi
Tahapan dimana peneliti melakukan kritik sumber setelah semua sumber-
sumber yang diperlukan dalam penelitian sudah terkumpul. Tujuannya adalah untuk
menguji keabsahan tentang keaslian sumber (autentisitas) yang dilakukan melalui
kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri
melalui kritik intern.35
4. Interpretasi
Sering kali disebut juga dengan analisis sejarah, yaitu menguraikan silsilah
Raden Fatah, kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan
hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu karena data-data yang sudah
dilakukan kritik sumber biasanya masih berbeda-beda dalam isinya. Oleh karena itu
dalam teknik interpretasi ini diharapkan penulis mampu menguraikan dan
menafsirkan hal tersebut.
5. Penulisan
Tahap penulisan atau pelaporan tentang hasil penelitian. Cara penulisan,
pemaparan atau penulisan laporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.
Penulisan hasil laporan hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
proses penelitian dari fase awal hingga akhir (penarikan kesimpulan). Penyajian
penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian36, yaitu: (1) pengantar, (2)
hasil penelitian, dan (3) simpulan.
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Berdasarkan telaah kepustakaan yang telah dilakukan ditemukan beberapa
penelitian yang relevan antara lain:
Artikel yang berjudul “Islamisasi Di Demak Abad XV M: Kolaborasi
Dinamis Ulama-Umara dalam Dakwah Islam di Demak” karya Umma Farida
pada 2 Desember 2015. Penulis memfokuskan kajiannya pada peran yang dimainkan
dari kekuatan kolaboratif ulama-umara dalam Islamisasi di Demak abad XV Masehi,
dengan mengambil Sultan Fattah dan Sunan Kalijaga sebagai tokoh sentralnya.
Metode pengembangan dan penyiaran Islam yang ditempuh ulama-umara selama
proses dakwah yaitu mengedepankan hikmah kebijaksanaan, mendekatkan rakyat dan
penguasa secara langsung dengan menunjukkan kebaikan ajaran Islam. Pendirian
Masjid Agung dan Kesultanan Demak semakin memantapkan aktifitas dakwah Islam
di Demak, mengingat dua tempat penting tersebut tidak hanya berfungsi sebagai
35 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hal 77 36 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, hal 8.
9
tempat untuk mengatur strategi dan musyawarah dalam memutuskan berbagai
persoalan masyarakat. Bahkan, kolaborasi ulama-umara juga berhasil melakukan
revolusi di bidang aqidah, ibadah, pendidikan, ekonomi, militer, pemerintahan, seni,
hukum, dan sosial kemasyarakatan. Kesuksesan dakwah Islam yang dilakukan para
ulama-umara di Demak dan tanah Jawa ini tidak dapat dipandang sebelah mata.
Setidaknya ada dua faktor yang mendukung capaian kesuksesan dari kekuatan
kolaboratif tersebut. Pertama, kesadaran ulama-umara yang tinggi terhadap
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual, mampu beradaptasi
dengan masyarakat dan memobilisasi potensi sosial. Kedua, ulama-umara menduduki
posisi sebagai bangsawan. Sultan Fattah yang merupakan raja penguasa Kesultanan
Demak hingga berhasil melakukan ekspansi ke beberapa wilayah lainnya. Demikian
pula Sunan Kalijaga yang merupakan ulama mumpuni juga berasal dari kalangan
Bangsawan sejatinya Putra Adipati Tuban. Ini merupakan faktor sosiologis yang
menjadikan kekuatan kolaboratif ulama-umara ini mudah diterima dakwahnya oleh
masyarakat. Faktor internal agama Islam yang tidak membedakan antar masyarakat
dan tidak mengenal kasta menjadi daya tarik untuk menerima dakwah Islam secara
sukarela.37
Artikel yang berjudul “Transformasi Islam Kultural ke Struktural
(Studi Atas Kerajaan Demak)” karya Maryam tahun 2016. Penulis memfokuskan
kajiannya pada transformasi Islam kultural ke struktural pada Kerajaan Demak.
Perkembangan Islam di Nusantara terutama pada masa awal pembentukannya sebagai
kekuatan sosial dan budaya, berlangsung dan sejalan dengan dinamika politik internal
di wilayah tersebut, kerajaan atau juga yang disebut kesultanan dalam
perkembangannya berfungsi tidak hanya sebagai pusat politik dan ekonomi, tetapi
juga sekaligus sebagai basis bagi berlangsungnya proses islamisasi. Munculnya
kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara membuka keyakinan bagi terintegrasinya nilai-
nilai Islam kedalam sistem sosial dan politik Nusantara. Kerajaan-kerajaan itu
merupakan dari para penguasa, para pedagang, dan pengembara muslim berperan
sebagai pelaku ekonomi sekaligus juru dakwah yang memperkenankan Islam kepada
masyarakat. Peralihan struktur kekuasaan dari kerajaan yang bernapaskan Hindu ke
Islam, memiliki kaitan dengan pergeseran struktur sosial, sebagai salah satu bukti
adanya Islam kultural. Dan sejarah berdirinya Masjid Demak adalah berhubungan erat
dengan berdirinya kerajaannya. Kesultanan Demak adalah Kerajaan Islam pertama
dan terbesar di pantai utara jawa (pesisir). Menurut tradisi jawa, Demak sebelumnya
merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Islam Demak dengan
tokohnya Raden Fatah yang mendudukin sebagai Sultan pertama merupakan salah
satu data yang menunjukkan terlembaganya Islam kedalam struktur kerajaan, karena
Raden Fatah yang memiliki hubunga darah dengan Kerajaan Majapahit dan menjadi
adipati di Bintoro. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari peran dan dukungan
para Walisongo. Masuknya Islam kedalam kultur budaya masyarakat lokal sehingga
37 Umma Farida. “Islamisasi Di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-
Umara dalam Dakwah Islam di Demak,” Jurnal At Tabsyir Komunikasi Penyiaran Islam, Vol.
3 No. 2, (Desember 2015): 299-318.
10
penerimaan terhadap Islam menjadi lebih mudah dan menstruktur Islam ditandai
dengan berdirinya Kerajaan Islam pertama yaitu Kesultanan Demak.38
Artikel yang berjudul Walisongo: Eksistensi dan Perannya dalam
Islamisasi dan Implikasinya terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi di Tanah
Jawa karya A.R Idham Kholid tahun Buku yang berjudul 2016. Penulis
memfokuskan kajiannya pada eksistensi dan perannya dalam islamisasi dan implikasi
terhadap munculnya tradisi-tradisi di Tanah Jawa. Islam sebagai agama rahmatan lil
alamin sangat dipahami oleh para wali sebagai penyebar islam di tanah Jawa, sehingga
dalam menyebarkan ajaran agama Islam mereka melakukannya dengan cara yang
bijaksana dan tanpa kekerasan. Kebijakan para wali dalam menyebarkan ajaran Islam
di Jawa antaranya dapat dilihat dari bagaimana mereka tidak menghancurkan tradisi
yang telah ada bahkan justru tradisi yang telah ada tersebut disesuaikan dengan ajaran
atau syariat Islam. Realitas tersebut di atas menjadikan tanah Jawa sebagai daerah
yang sangat banyak menyimpan tradisi dengan seluruh warna-warninya dan menjaga
kelestariannya secara dinamis dalam rentang waktu cukup panjang bahkan hingga
sekarang. Islam sebagai agama yang mudah dicerna oleh masyatakat dan memiliki
ritual ibadah yang tidak memberatkan masyarakat Jawa dan tidak menempatkan
manusia pada strata atau kasta. Oleh sebab itu, Tanah Jawa sebagai salah satu daerah
penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali dan ulama yang sangat arif dan
bijaksana dimana penyebaran Islam dilakukan dengan cara mengajak dan merangkul
serta tidak menghancurkan tradisi lama tapi mengarahkan tradisi lama yang
bertentangan dengan syariat Islam menjadi sesuai dengan ajaran atau syariat Islam.
Hal tersebut menjadikan Tanah Jawa sebagai daerah yang memunyai banyak tradisi.39
Jurnal yang berjudul “Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi
Islam Maritim di Nusantara” karya Heru Arif Pianto tahun 2017. Penulis
menulis jurnal ini membahas bahwa Keraton Demak sebagai kerajaan maritim Demak
menjalankan fungsinya sebagai penghubung dan transito antara daerah penghasil
rempah-rempah di Indonesia bagian timur dan malaka sebagai pasaran Indonesia
bagian barat. Karena itulah timbul suatu inisiatif dari penguasa Demak untuk
menggantikan posisi malaka sebagai pusat perdagangan baik nasional maupun
internasional. Untuk mewujudkan kesemuanya itu, Demak Bintoro bermaksud
menduduki malaka terlebih dahulu dengan mengusir bangsa Portugis yang telah
berkuasa sejak tahun 1511 M. Usaha itu dilakukan ketika pada tahun 1511 M, Demak
di bawah pimpinan Adipati Unus mengadakan pelayaran ke malaka bersama
armadanya untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis, walaupun
tidak membuahkan hasil. Perekonomian Kerajaan Demak berkembang pesat,
khususnya dalam dunia maritim, hal ini karena di dukung oleh penghasilan di bidang
agraris yang cukup besar. Kerajaan Demak berusaha mengadakan kerjasama dengan
daerah-daerah di pantai Pulau Jawa yang telah menganut agama Islam, sehingga
38Maryam. “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan
Demak),” Jurnal Tsaqofah dan Tarikh, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni 2016): 63-76. 39A.R Idham Kholid. “Walisongo: Eksistensi Dan Perannya Dalam Islamisasi Dan
Implikasinya Terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi Di Tanah Jawa,” Jurnal Tamaddun, Vol.4
No. 1, (Januari-Juni 2016): 1-47.
11
tercipta suatu federasi atau persemakmuran dengan Demak sebagai pemimpinnya.
Dalam kerajaan, agama Islam merupakan faktor yang menjadi unsur pemersatu yang
dapat menimbulkan kekuatan besar. Selain dari unsur kehidupan ekonomi, yang
menjadikan kerajaan maritim demak ini menjadi besar adalah ajaran Islam yang sudah
di tanamkan oleh para wali. Di antara wali yang selalu aktif di Demak adalah Sunan
Kalijaga. Berkat saran beliau Demak menjadi negara theokrasi yaitu negara atas dasar
agama. Salah satu bukti sejarahnya adalah Masjid Agung Demak. Dengan melihat
kronologi Kerajaan Demak penyebab kemajuan pesat memiliki dua faktor yaitu
pertama, faktor maritim dan didukung dengan faktor agraris; kedua, faktor agama
yang telah diajarkan para wali. Para wali selain berdakwah, juga berperan sebagai
penasehat kerajaan, bidang politik, sosial ekonomi, budaya, seni, kesehatan, dan
sebagainya.40
Artikel yang berjudul “Politik Dinasti dalam Perspektif Ekonomi dari
Kerajaan Demak” karya Tundjung dan Arief Hidayat tahun 2018. Penulis
menulis jurnal ini membahas bahwa Raja Demak pertama, Raden Fatah sebagai
pendiri kerajaan berusaha untuk menguasai jalur perdagangan penting di kepulauan
Nusantara. Raden Fatah mengutus anaknya Adpati Unus untuk memimpin
penaklukan Palembang dan Malaka, tujuannya untuk menguasai kedua pelabuhan
yang ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari Asia maupun Nusantara. Raden Fatah
juga bertujuan menjaga agar pedagang-pedagang dari Asia maupun Nusantara yang
dikuasai Demak, tidak terusuk. Kepercayaan yang diberikan kepada Adipati Unus
merupakan salah satu bentuk politik dinasti, ketika Demak sedang mengembangkan
kekuasaannya. Adipati Unus sangat mendukung kekuasaan ayahnya. Sultan
Tenggrana, raja ketiga dari Kerajaan Demak, memimpin sendiri penaklukkan daerah-
daerah penting bekas wilayah Majapahit. Daerah-daerah yang sudah takluk, raja
menempatkan kerabatnya sebagai penguasa ataupun mengadakan perkawinan politik
antara keluarga raja dengan penguasa setempat. Poltik dinasti inilah yang digunakan
sebagai alat untuk menjaga terjaminnya perekonomian kerajaan. Para penguasa
daerah yang sudah terikat sebagai kerabat kerajaan akan menunjukkan loyalitas tinggi.
Sultan trenggana juga melakukan perkawinan politik dengan orang yang akan diutus
untuk menaklukkan Jawa Barat. Tujuannya untuk mendapatkan jaminan loyalitas
kepada Kerajaan Demak. Politik Dinasti dilakukan untuk mendukung perekonomian
kerajaan. Keterikatan keluarga terjadi antara kerabat Kerajaan Demak dengan
penguasa-penguasa yang berada di bawah kekuasaannya. Keterikatan itu bersifat
genealogis melalui perkawinan, yang sifatnya politik. Politik Dinasti untuk menjaga
dan menjamin keberlangsungan ekonomi kerajaan.41
G. Sistematika Penulisan
40 Heru Arif Pianto. “Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi Islam Maritim Di
Nusantara,” Jurnal LP3M, Vol. 3 No. 1, (April 2017): 18-26. 41Tundjung dan Arief Hidayat. “Politik Dinasti Dalam Perspektif Ekonomi dari
Kerajaan Demak,” Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 3 No. 1, (2018).
12
Masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, penulis membaginya
menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
Bab I merupakan Pendahuluan yang mengemukakan Latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan signifikasi
masalah, metodelogi penelitian, kajian pustaka yang relevan, dan sistematika
penulisan.
Bab II menjelaskan tentang Riwayat Raden Fatah menurut Kepustakaan
Sejarah.
Bab III menjelaskan tentang Genealogi Islam Raden Fatah dalam
Historiografi Ulama Sunda.
Bab IV menjelaskan tentang Jaringan Islam dan Kekuasaan Raden Fatah.
Bab V yang merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran.
13
BAB II
RIWAYAT RADEN FATAH MENURUT KEPUSTAKAAN SEJARAH
Islam masuk ke Nusantara berarti Islam masuk ke wilayah yang sekarang
masuk dalam negara-negara Asia Tenggara. Istilah Nusantara digunakan untuk
enyebut wilayah yang sekarang disebut kepulauan yang meliputi Indonesia, Malaysia,
Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Pada waktu itu
wilayah tersebut menyatu karena belum terbentuk negara-negara seperti sekarang ini.1
Agama Islam tersebar di Asia Tenggara dan Kepulauan Indonesia sejak abad
XII atau XIII. Sekarang di sejumlah daerah yang telah berabad-abad memeluknya,
nama mereka yang dianggap berjasa dalam menyebarkan agama itu disebut dengan
hormat dan khidmat. Masuk Islamnya berbagai suku bangsa di Kepulauan Indonesia
ini tidak berlangsung dengan jalan yang sama. Begitulah anggapan umum, legenda
mengenai orang suci dan cerita mengenai para penyebar agama Islam dan tanah asal
usul mereka sangat beragam. Belum lama berselang Dr. Drewes minta perhatian
terhadap soal-soal yang bertalian dengan Sejarah Agama Islam di Indonesia.2
Menurut Hamka bahwa pada permulaan tumbuhlah agama Islam pada abad
ke 7 Masehi, yaitu pada tahun 674-675 M telah ada utusan Raja Arab yang oleh orang
Tionghoa dibahasakan Ta Kheh datang ke Tanah Jawa meziarahi Kerajaan Kalingga.
Raja Ta Kheh itu tidak lain dari Muawiyyah, sahabat Rasulullah SAW dan saudara
dari istrinya, Ummu Habibah, dan pembangun dari Daulah Bani Umayah. Selain itu
perkuburan Fathimah binti Maimun di Desa Leran yang bertarikh 495 Hijriyah (1101
M) telah memberikan pertolongan yang sangat besar untuk membuktikkan perkiraan
itu. Orang-orang Indonesia dari Tanah Jawa sendiri pun berniaga pula ke luar negeri,
mengembara pula ke negeri orang. Di antaranya ialah Haji Purwa, abang dari Prabu
Mundingsari, Kerajaan Pajajaran. Kalau telah ada pada abad ke 11 di Jawa, niscaya
di Sumatera dan Semenanjung telah ada lebih dahulu karena letaknya lebih ke barat.
Perkuburan Maulana Malik Ibrahim di Gresik bertarikh tahun 1419 M.3
Suatu kenyataan yang sudah pasti ialah, di Sumatera Utara-di Aceh yang
sekarang ini-para penguasa di beberapa kota pelabuhan penting sejak paruh kedua
abad XIII sudah menganut Islam. Pada zaman ini hegemoni politik di Jawa Timur
masih ditangan raja-raja beragama Syiwa Buddha di Kediri dan di Singasari, di daerah
pedalaman. Besar sekali kemungkinan bahwa pada abad XIII di Jawa sudah ada orang
Islam yang menetap. Sebab, jalan perdagangan di laut, yang menyusuri pantai timur
Sumatera melalui Laut Jawa ke Indonesia bagian timur, sudah ditempuh sejak zaman
dahulu. Para pelaut itu, baik yang beragama Islam maupun yang tidak, dalam
1Didin Saefuddin, Sejarah Politik Islam, hal 325.
2H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 20. 3Hamka, Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara (Jakarta:
Gema Insani, 2016), hal 552.
14
perjalanan singgah di banyak tempat. Pusat-pusat permukiman di pantai utara Jawa
ternyata sangat cocok untuk itu.4
Di mana pun di kota-kota bandar bila telah terbentuk masyarakat Islam,
masjid niscaya segera dibangun. Itu merupakan suatu keharusan. Masjid menduduki
tempat penting dalam kehidupan masyarakat, merupakan pusat pertemuan orang
beriman dan menjadi lambang kesatuan jamaah. Wali-wali di Jawa kabarnya berpusat
di masjid keramat di Demak, masjid yang mereka dirikan bersama. Disitulah mereka
agaknya mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran tentang mistik. 5
Letak Demak sangat menguntungkan, baik untuk perdagangan maupun
pertanian. Pada zaman dahulu wilayah Demak terletak di tepi selat di antara
Pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya selat itu rupanya agak lebar dan dapat
dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalan
pintas itu untuk berlayar ke Rembang. Jepara terletak di seberang barat pegunungan
yang dahulu adalah Pulau Muria. Jepara mempunyai pelabuhan yang aman semula
dilindungi oleh tiga pulau kecil. Letak pelabuhan Jepara sangat menguntungkan bagi
kapal-kapal dagang yang lebih besar yang berlayar lewat pantai utara Jawa menuju
Maluku dan kembali ke barat. Pada abad XVI dan XVII kedua kota dwitunggal yang
perkasa.
Lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah di Demak sejak abad XVII
mendapat perhatian para pembawa cerita dan penulis Jawa.6 Maka dalam BAB ini
akan membahas tentang sumber-sumber yang terkait dengan genealogi Raden Fatah
menurut kepustakaan sejarah. Akan tetapi dari sumber-sumber yang penulis dapatkan
belum cukup memberikan informasi yang memuaskan. Hal tersebut dibuktikan
dengan terjadi perbedaan pendapat diantara para sejarawan dan naskah-naskah itu
sendiri. Sehingga menurut penulis silsilah Raden Fatah perlu adanya penelitian
kembali.
A. Diskursus tentang Persoalan Sumber
1. Pendapat Sejarawan mengenai Sumber-Sumber yang terkait Genealogi
Raden Fatah
Indonesia yang menganut agama Islam bukan hanya menciptakan kerajaan-
kerajaan tetapi juga sebuah warisan budaya yang beraneka ragam. Beberapa di
antaranya adalah warisan yang bersemangatkan Islam dan kebudayaan pra Islam.
Kebanyakan bukti dokumenter mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik berasal dari
abad XVIII atau sesudahnya, maka tidak dapat selalu merasa pasti bahwa gambaran
tentang kegiatan-kegiatan budaya sebelum abad XVIII itu lengkap atau benar-benar
4H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 20.
5H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 29-31.
6H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 38-39.
15
tepat. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan diperoleh suatu gambaran umum
mengenai kebudayaan-kebudayaan klasik itu.7
Lahirnya Kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah, di Demak, sejak abad XVII
mendapat perhatian para pembawa cerita dan penulis sejarah Jawa. Pada abad XVII
hegemoni di Jawa Tengah dan Jawa Timur jatuh ke tangan raja-raja Mataram di
pedalaman. Banten tidak pernah takluk kepada Mataram, tetapi kerajaan-kerajaan
bandar lainnya di sepanjang pantai utara Jawa selama abad XVII semuanya telah
direbut Mataram, atau terpaksa mengakui kekuasaan raja-raja Mataram. Munculnya
dan lamanya kekuasaan keluarga raja Islam kedua yang besar di Jawa Tengah
(Mataram), di daerah raja-raja Jawa Tengah (Surakarta dan Yogyakarta, de
vorstenlanden), mempengaruhi penulisan sejarah Jawa pada abad XVII dan abad-abad
berikutnya sedemikian rupa sehingga zaman sebelum Mataram dianggap kurang
penting. Cerita-cerita babad pada abad-abad sebelum munculnya Raja Mataram
pertama dipenuhi dengan legenda yang menghubungkan munculnya Kerajaan Demak
dengan runtuhnya Majapahit dari zaman pra-Islam. Raden Fatah menjadi pahlawan
besar dalam legenda ini.
Selain itu, asal usul legenda Majapahit dan Demak diolah dalam Babad
Mataram. Dan cerita tersebut terdapat dalam Serat Kanda pada abad XVII sudah
dikenal di Jawa Timur dan di pesisir.
Meskipun sifat legendaris dan kadang-kadang sifat mirip dongeng khayalan,
cerita tersebut ketara sekali, penulisan sejarah Jawa oleh orang Belanda selama abad
XIX dan lebih lama berdasarkan naskah cerita dan babad dari Jawa Timur dan Jawa
Tengah tersebut, karena tidak ada sumber lain yang lebih baik.
Baru akhir-akhir ini, karena ditemukannya Suma Oriental, terbukalah
kemungkinan menyusun sejarah Demak yang lebih dapat dipercaya. Ternyata,
pemberitaan Pires sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam buku-buku sejarah
Banten. Redaksi buku-buku itu, yang berasal dari abad XVIII, sedikit banyak
terpengaruh oleh tradisi kesusastraan Mataram, tradisi Jawa Tengah yang berkuasa.
Tetapi buku itu masih memuat unsur-unsur lama yang mengungkapkan peristiwa
sejarah lebih baik daripada legenda-legenda yang tersebar luas. 8
Menurut HJ De Graaf dan TH Pigeaud bahwa antara buku Tome Pires dan
buku-buku sejarah Jawa Barat terdapat kesesuaian dalam hal pemberitaan bahwa
Dinasti Demak dimulai dengan 3 orang raja9 yaitu:
1. Tome Pires menyebutkan:
a. Moyang, yang tidak disebutkan namanya, berasal dari Gresik
b. Pate Rodin Sr
c. Pate Rodin Jr
2. Sadjarah Banten, buku sejarah Banten yang terbesar, menyebutkan
(Djajadiningrat, Banten):
a. Patih raja Cina yang tidak disebut namanya
7M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 76.
8H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 39-40. 9H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 40-42.
16
b. Cun-Ceh, meninggal dalam usia muda dan Cu-Cu, juga disebut Arya
Sumangsang dan Prabu Anom
c. Ki Mas Palembang
3. Hikayat Hasanuddin disebut Sadjarah Banten rante-rante, buku sejarah
Banten yang lebih kecil, tetapi sangat penting, menyebutkan:
a. Cek-Ko-Po dari Manggul
b. Pangeran Wirata meninggal dunia, Pangeran Palembang Tua meninggal
muda, Cek Ban-Cun, Pangeran Palembang Anom juga disebut Molana
Arya Sumangsang
c. Molana Tranggana putra dari Pangeran Palembang Anom
4. Musafir Belanda, Cornelis de Bruin pada 1706 mengunjungi Banten, di situ
kepadanya diserahkan keterangan keturunan berikut ini (yang tampaknya
kutipan dari Hikayat Hasanudin):
a. Co-Po dari Moechoel
b. Arya Sumangsang
c. Arya Tranggana
Sebagai bahan perbandingan, di bawah ini masih disebutkan 3 orang yang
menurut legenda Mataram, bertindak sebagai raja Demak:
a. Raden Patah
b. Pangeran Sabrang Lor
c. Pangeran Tranggana
Menurut hipotesa kerja dari HJ De Graaf dan TH Pigeaud, tersusun daftar
nama penguasa pertama di Demak beserta tarikh yang dikutip dari naskah-naskah
Jawa dan Eropa10 yaitu:
1. Cikal bakal dinasti berkebangsaan asing yaitu Cina bernama Cek-Ko-Po
dalam perempat terakhir abad XV.
2. Putra Cek-Ko-Po bernama Cu-Cu alias Arya Sumangsang dan Pate Rodin Sr.
Pate Rodin Sr menurutnya campuran dari Badruddin atau Kamaruddin. Pate
Rodin Sr hidup sampai sekitar 1504 M, secara tahun masih dibawah
kekuasaan seorang penguasa yang mewakili Raja Majapahit.
3. Anak atau adik laki-laki Cu-Cu bernama Tranggana atau Ki Mas Palembang
hidup hingga 1546 M menyatakan dirinya menjadi raja Islam dan sultan yang
berdaulat. Ia memperluas wilayah Demak ke barat dan ke timur serta
menaklukkan ibu kota lama Majapahit tahun 1527 M. Ipar Tranggana yaitu
Raja Jepara yaitu Pate Unus/Yunus yang diberi gelar Pangeran Sabrang Lor.
Ia melancarkan perang laut melawan orang Portugis di Malaka, dikalahkan
1512/1513 M. Konon ia agaknya memerintah di Demak mulai kira-kira 1518
M hingga meninggalkannya pada 1521 M.
Tome Pires yang hidup sezaman, cukup tetap menguraikan peristiwa sampai
kira-kira 1515 dalam bukunya Suma Oriental. Tetapi kelanjutan sejarahnya tidak
10H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 53.
17
dialaminya. Mungkin ia terlalu banyak menyoroti pribadi Pate Unus, tokoh yang
paling banyak dihubungi orang Portugis pada waktu itu. Dalam cerita-cerita tradisi
Jawa dari abad XVII dan XVIII, baik dari Jawa Timur dan Mataram maupun dari Jawa
Barat, terjadi kekacauan antara cerita mengenai raja-raja Demak dan Jepara yang
masih ada ikatan keluarga itu dan yang hidup dalam dasawarsa-dasawarsa pertama
abad XVI. Rouffaer mengira, berdasarkan pemberitaan Portugis bahwa berkuasanya
Pate Unus dari Jepara atas Demak selama beberapa tahun itu masuk akal. Namun,
babad Jawa dari abad-abad kemudian sama sekali melupakan pejuang muda yang
gagah berani melawan kekuasaan bangsa Portugis di Malaka.11
Berdasarkan berita para penulis Portugis, Pate Unus dari Jepara adalah orang
yang penting dalam sejarah Jawa, maka Rouffaer berusaha menemukannya kembali
dalam cerita tradisi Jawa. Malahan Rouffaer berani menduga bahwa yang dimaksud
dengan Pangeran Sabrang Lor dalam cerita tradisi itu adalah raja Jepara yang oleh
orang Portugis diberi nama Pate Unus. Pigafetta seorang Italia yang bekerja sebagai
juru mudi dalam armada Magelhaens, menulis seakan-akan lawan orang Portugis di
Malaka adalah seorang raja Majapahit yang telah meninggal sebelum 1522. 12
Adapun menurut M.C. Ricklefs, bahwa negara Islam paling penting di
wilayah pantai utara Jawa pada awal abad XVI adalah Demak. Pada masa itu Demak
merupakan sebuah pelabuhan laut yang baik walaupun lumpur yang sangat banyak di
pantai pada abad-abad berikutnya telah menjadikan letak Demak dewasa ini beberapa
kilometer jauhnya dari laut. Asal usul negara ini sangat tidak jelas. Tampaknya
Demak didirikan pada perempat terakhir abad XV oleh seorang asing beragama Islam,
yang kemungkinan besar seorang Cina yang bernama Cek-Ko-Po. Putranya adalah
seorang yang oleh orang-orang Portugis disebut dengan nama Rodim yang
kemungkinan besar sama dengan Badruddin atau Kamaruddin, tampaknya dia
meninggal sekitar tahun 1504 M.13
Apa yang telah terjadi di Majapahit sejak akhir abad XV juga tidak jelas dan
apabila tidak berhasil ditemukan sumber-sumber yang baru, kemungkinan besar tidak
akan pernah diketahui secara pasti. Pada masa pengluasan militer Demak, kerajaan
Hindu Buddha di Kediri berhasil ditaklukkan sekitar tahun 1527 M. Kronik-kronik
istana Jawa sesudah masa itu melukiskan penaklukkan itu dengan berbagai cara, tetapi
kesemuanya memperlihatkan suatu kecenderungan untuk membuktikkan bahwa
Demak kini mewarisi legitimasi Majapahit. Demak digambarkan sebagai pengganti
langsung Majapahit dan Sultan Demak yang pertama yaitu Raden Fatah disebutkan
sebagai putra raja Majapahit yang terakhir dengan seorang putri berkebangsaan Cina,
Putri Cina yang telah diusir dari istana sebelum putranya lahir.
Jatuhnya Majapahit di dalam naskah-naskah seperti itu biasanya ditempatkan
pada akhir abad XIV Jawa (1400 Saka/1478-1478 M). Pergantian abad kemudian
dianggap sebagai saat biasanya terjadi pergantian wangsa atau kerajaan. Legenda-
11H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 52.
12H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 50-51.
13M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2007), hal 54.
18
legenda semacam itu hanya dapat menceritakan sedikit tentang kejadian-kejadian
yang sesungguhnya tetapi menceritakan banyak mengenai keinginan istana-istana
yang muncul belakangan untuk melihat kesinambungan dan legitimasi kerajaan
sebagai unsur-unsur yang tidak diputus oleh islamisasi.14
Kesastraan klasik Jawa berbeda dengan kesastraan Melayu, meskipun
keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Selain tradisi-tradisi dari daerah-
daerah lain ada 2 sumber pengaruh yang dapat ditemukan di kesastraan Jawa yaitu
tradisi-tradisi India melalui bahasa Jawa Kuno dan tradisi-tradisi Islam. Perbedaan
yang paling mencolok antara tradisi Melayu dengan Jawa ialah lebih kecilnya
pengaruh Islam dalam tradisi Jawa.15 Sejarah kesastraan Jawa Kuno di Jawa setelah
runtuhnya kerajaan Hindu Buddha yang terakhir sekitar tahun 1527 M. Bagaimanapun
juga sebagian besar kesastraan Jawa dapat dilihat secara langsung dipengaruhi oleh
pemikiran-pemikiran dari masa pra Islam. Bukan hanya karya-karya yang disadur
secara langsung dari bahasa Jawa Kuno itu saja yang penuh dengan pengaruh Hindu
Buddha dan kenangan akan kisah-kisah dari masa pra Islam.16
Sedangkan menurut MC Ricklefs bahwa kronik-kronik (babad) merupakan
suatu bagian yang penting dari kesastraan klasik Jawa dan tampaknya berdasarkan
inspirasi asli. Kronik-kronik yang sangat panjang dan terinci yang ditemukan dalam
bahasa Jawa Baru tidak dikenal dalam bahasa Jawa Kuno dan tidak ada tanda inspirasi
Islam. Memang masalah-masalah keagamaan hanya mendapat sedikit perhatian
dalam kronik-kronik Jawa yang pada dasarnya lebih banyak memusatkan
perhatiannya pada raja-raja, para pahlawan, pertempuran-pertempuran, dan selingan-
selingan yang romantis. Beberapa kronik merupakan karya-karya yang menyerupai
ensiklopedi yang dimulai dari Adam maupun dewa-dewa Hindu, menceritakan masa
pra Islam yang legendaris dalam sejarah Jawa dan mencapai puncaknya pada abad
XVII atau XVIII karya-karya ini biasanya disebut dengan nama yang umum yaitu
Babad Tanah Jawi yang ditulis selesai di Surakarta pada tahun 1836 merupakan
naskah yang terdiri atas 18 jilid. Kronik-kronik lain menceritakan tentang sejarah
kerajaan-kerajaan, pahlawan-pahlawan, atau kejadian-kejadian tertentu. Kronik-
kronik Jawa memang beraneka ragam.
Suatu kenyataan yang aneh dari sejarah kebudayaan Jawa bahwa walaupun
banyak kesastraan yang penting dapat ditemukan dalam ribuan naskah, namun hanya
beberapa pengarang sajalah yang dikenal namanya dari masa sebelum abad XIX.
Memang sering sulit untuk dapat dipastikan apakah karya-karya yang secara
tradisional dianggap ditulis oleh segelintir orang itu benar-benar ditulis oleh mereka.
17
Selain itu, sumber-sumber yang sering digunakan untuk penelitian
sebelumnya menggunakan karya-karya sastra18 yaitu:
14M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 55. 15M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 80. 16M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 81. 17M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 83. 18Hasan Jafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya (Depok:
Komunitas Bambu, 1978), hal 20.
19
1. Kakawin Nagarakertagama. Kakawin pujian berbahasa Jawa Kuna ini ditulis
oleh Rakawi Prapanca pada 1365 M yaitu pada masa pemerintahan Raja
Hayam Wuruk. Nama asli kakawin ini adalah Desawarnana berarti uraian
tentang desa-desa, maka sebagian besar isinya menguraikan kisah perjalanan
Raja Hayam Wuruk ke daerah-daerah di wilayah Kerajaan Majapahit.
2. Serat Pararaton. Serat Pararaton atau Katuturanira Ken Anrok ini ditulis
dalam bentuk prosa berbahasa Jawa Tengah-an yang berasal dari periode
Majapahit akhir. Isinya menguraikan kisah raja-raja Singasari dan Majapahit
mulai dari Ken Anrok sampai Bre Pandansalas. Apabila melihat bentuk serta
susunan isinya, Serat Pararaton disusun berdasarkan sumber-sumber lain
yang ada pada waktu penyusunnya. Walaupun di dalamnya terdapat uraian
dan angka tahun yang tidak cocok dengan sumber-sumber lain seperti
prasasti, dengan bantuan sumber-sumber sejarah lain sebagai pembanding.
3. Serat Babad Tanah Jawi. Serat ini berisi uraian mengenai sejarah Jawa sejak
Nabi Adam sampai tahun 1647 M. Babad Tanah Jawi merupakan sebuah hasil
historiografi tradisional Jawa dari zaman Mataram Islam. Kita memperoleh
keterangan yang penting dari Babad Tanah Jawi untuk masalah Majapahit
akhir, yakni keterangan mengenai awal pertumbuhan Kerajaan Demak dan
gambaran terakhir keadaan Kerajaan Majapahit di bawah Raja Brawijaya.
Selain itu, ada juga keterangan mengenai penaklukan Majapahit oleh Demak.
Walaupun di dalamnya banyak keterangan mengenai tokoh-tokoh dan
kejadian-kejadian dari zaman kuna yang tidak dapat diterima.
4. Serat Kanda. Serat Kanda merupakan sebuah hasil historiografi tradisional
Jawa. Uraiannya mengenai keruntuhan Kerajaan Majapahit yang hampir
serupa dengan Babad Tanah Jawi. Keterangan penting dari Serat Kanda ialah
mengenai penyerbuan ke Sengguruh oleh tentara Demak untuk menaklukkan
Raja Majapahit Brawijaya.
5. Serat Darmagandul. Isinya menceritakan sejarah penaklukan Majapahit dan
dialog antara Prabu Brawijaya dan Sabdapalon mengenai agama Buddha dan
Islam. Pada waktu Majaphit diserang Demak, Prabu Brawijaya melarikan diri
ke Bali. Akan tetapi ketika hampir menyeberang ke Pulau Bali, Prabu
Brawijaya terkejar oleh Sunan Kalijaga dan di Islamkan.
Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda, memang mendapatkan uraian genealogi
raja-raja di Jawa. Akan tetapi, tidak dapat memakai uraian genealogi tersebut untuk
menyusun genealogi raja-raja Majapahit seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan
sumber-sumber tersebut telah mencampuradukan genealogi historis dengan genealogi
yang didasarkan mitos, bahkan telah mencampuradukan genealogi dari panteon Hindu
dengan genealogi yang berdasarkan Islam.19
Bukti-bukti mengenai abad XVI terutama terdiri atas beberapa catatan orang
Portugis yang sezaman dan diantara yang paling lengkap keterangannya adalah karya
Tome Pires yang berjudul Suma Oriental. Sedangkan tradisi-tradisi sejarah Jawa dari
zaman belakangan yang merupakan campuran yang rumit antara dongeng dan sejarah.
19Hasan Jafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 104.
20
Oleh karena itulah maka banyak peristiwa penting pada masa itu tidak dapat diketahui
secara lengkap.20
Tome Pires menceritakan dalam bukunya berdasarkan cerita-cerita yang
didengarnya di Jawa pada permulaan abad XVI, pada pokoknya ialah sebagai berikut
kakek Raja Demak yang memerintah pada 1513 adalah seorang budak belian dari
Gresik. Yang dimaksud dengan budak belian ialah kawula, abdi. Orang dari Gresik
ini konon telah mengabdi kepada penguasa di Demak pada waktu itu. Apa vasal atau
kerajaan dari Maharaja Majapahit? Penguasa Demak tersebut yang mengangkatnya
menjadi capitan dan kemudian menugasinya memimpin ekspedisi melawan Cirebon
dapat direbut pada 1470 dan capitan mendapat kemenangan itu dihadiahi gelar pate
oleh tuannya. Pires banyak menyebut pate, rupanya yang dimaksud itu patih. Di
tempat lain dalam bukunya menuliskan tentang orang dari Gresik itu elle veio teer a
Dema, yang oleh penerbitannya berkebangsaan Portugis, Cortesao, diterjemahkan
menjadi he happened to go to Demak. Dimana pun Pires tidak pernah mengatakan
dengan tegas bahwa orang dari Gresik itu orang Islam. Tetapi tempat asal Gresik,
pusat tertua agama Islam di Jawa Timur, dapat merupakan petunjuk keislamannya.21
Berdasarkan beberapa berita abad XVII dan yang dari Jawa Barat, yang
jarang tetapi sangat menarik perhatian itu dapat kita simpulkan bahwa asal usul
Dinasti Demak itu dari Cina pada waktu ini dapat dipercayai. Ia sudah memeluk
agama Islam ketika menetap di daerah Demak dan setelah menjadi patihnya raja, ia
jadi terhormat. Konon, ia datang dari Jawa Timur yaitu Gresik dan menetap di Demak.
Dapat pula dipercaya bahwa selama hidup ia tidak hanya mengakui kekuasaan
penguasa setempat, gubernur atau vasal raja Majapahit. Ia sendiri konon belum
menjadi raja, melainkan orang berpengaruh yang berasal dari Cina, yang termasuk
golongan pedagang menengah yang berada. Ia hidup di Demak pada perempat
terakhir abad XV.22
Hal menarik yang perlu ditelusuri kembali yaitu siapa kakek Raden Fatah
yang berasal dari Gresik. Hingga saat ini belum terpecahkan dan menemukan titik
terang dalam Sejarah Islam di Nusantara. Pembahasan ini akan dijelaskan pada bab 3.
2. Pendapat Sejarawan mengenai Cempa dan Campa
Suatu kenyataan yang sudah pasti ialah, di Sumatera Utara di Aceh yang
sekarang ini, para penguasa di beberapa kota pelabuhan penting sejak paruh kedua
abad XIII sudah menganut Islam. Pada zaman ini hegemoni politik di Jawa Timur
masih di tangan raja-raja beragama Syiwa Buddha di Kediri dan di Singasari, di
daerah pedalaman. Besar sekali kemungkinan bahwa abad XIII di Jawa sudah ada
orang Islam yang menetap.23 Sebab jalan perdagangan di laut, yang menyusuri pantai
20M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 54.
21H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 43. 22H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 44. 23H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 20.
21
timur Sumatera melalui Laut Jawa ke Indonesia bagian timur, sudah ditempuh sejak
dahulu. Para pelaut itu, baik yang beragama Islam maupun tidak dalam perjalanan
singgah di banyak tempat. Pusat-pusat permukiman di pantai utara Jawa ternyata
sangat cocok untuk itu.
Salah seorang yang paling terkenal dan tertua di antara para Wali di Jawa
dicatat dalam semua legenda orang soleh ialah Raden Rahmat dari Ngampel Denta.
Ia diberi nama sesuai dengan nama kampung di Surabaya tempat ia dimakamkan,
mungkin ia juga pernah tinggal di sana. Menurut cerita Jawa, ia berasal dari dari
Cempa.
Tokoh terpenting dalam cerita Jawa tentang Cempa adalah Putri Cempa. Ada
dua kelompok cerita Cempa, yaitu: Kelompok pertama meliputi cerita lisan, yang
dihubung-hubungkan dengan makam Islam, yang sekarang masih dapat ditunjukkan
di suatu daerah yang dahulu merupakan ibu kota Majapahit. Makam itu bertarikh Jawa
1370 (1448 M), mungkin sekali itulah makam Putri Cempa yang menjadi permaisuri
raja terakhir Majapahit yang legendaris, yaitu Brawijaya. Menurut suatu cerita Jawa,
Serat Kandha (diterbitkan oleh Brandes), konon ia sudah kawin dengan Putri Cempa
waktu masih menjadi putra mahkota. Nama putri itu sebagai ratu yaitu Darawati atau
Andarawati. Babad Meinsma memberikan uraian panjang lebar tentang putri itu.
Sebagai maskawin konon ia membawa barang yang sangat berharga dari Cempa, yang
kelak dijadikan barang-barang perhiasan kebesaran Keraton Mataram, atau pusaka
yaitu gong yang diberi nama Kiai Sekar Delima, kereta kuda tertutup yang diberi nama
Kiai Bale Lumur, dan pedati sapi yang diberi nama Kiai Jebat Betri. Barang-barang
berharga ini diperoleh Keraton Mataram sebagai rampasan perang ketika Demak
direbut. 24
Kelompok kedua cerita tradisional Jawa yang mengisahkan Cempa
berhubungan dengan orang suci yang telah menyebarkan agama Islam di Surabaya
dan Gresik. Konon mereka berasal dari Cempa. Putri Cempa tersebut meninggalkan
saudara perempuan di tanah airnya, yang sudah kawin dengan orang Arab. Ipar putri
ini dalam satu cerita tradisional Hikayat Hasanuddin dari Banten hanya disebut
sebagai orang suci dari Tulen, keturunan Syekh Parnen. Menurut babad lain ia diberi
nama Raja Pandita, dulu namanya Sayid Kaji Mustakim. Dalam Babad Meinsma ia
disebut Makdum Ibrahim Asmara, imam dari Asmara, Maulana Ibrahim Asmara lahir
di Tanah Arab, putra Syekh Jumadil Kubro.
Orang Arab itu, yang identitasnya belum jelas, konon mendapat 2 putra dari
istrinya, Putri Cempa yaitu:
a. Yang tua namanya Raja Pandita (dalam Hikayat Hasanuddin) atau Raden
Santri (dalam Babad Meinsma) atau Sayid Ngali Murtala (dalam Sadjarah
Dalem). Menurut Hikayat Hasanuddin, Raja Pandita diangkat menjadi imam
masjid yang terletak di tanah milik Tandes (seorang kakek di Gresik) dan
menjadi tokoh penting.
b. Yang muda bernama Pangeran Ngampel Denta atau Raden Rahmat atau
Sayid Ngali Rahmat (dalam Sadjarah Dalem) Dalam Sadjarah. Menurut
Hikayat Hasanuddin, sedangkan adiknya, Raden Rahmat diangkat oleh pecat
24H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 21.
22
tandha di Terung, yang bernama Arya Sena, sebagai iman di Surabaya dan
menjadi sangat terhormat di lingkungannya.
Dari cerita-cerita Jawa itu dapat disimpulkan bahwa Gresik dan Surabaya
dianggap sebagai pusat-pusat tertua agama Islam di Jawa Timur. Tradisi tersebut
sesuai dengan kenyataan bahwa di Gresik terdapat banyak makam Islam yang tua
sekali. Pertama-tama terdapat makam Fatimah binti Maimun yang meninggal pada
tanggal 7 Rajab 475 H (1082) dan kedua makam Malik Ibrahim yang meninggal pada
tanggal 12 Rabiulawal 822 H (1419). 25
Mengenai letak Cempa dalam cerita-cerita Jawa yang menyangkut tempat
asal para penyebar agama Islam pertama di Jawa Timur, telah diajukan 2 pendapat,
yaitu:
a. Dr. Rouffaer yaitu Sumatera, berdasarkan dugaan telah mengidentifikasikan
Cempa atau Campa ini dengan Jeumpa di Aceh, di perbatasan antara
Samalangan (Simelungan) dan Pasangan. Dr. Cowan memperkuat hipotesa
ini dalam sensinya mengenai karya R.A Kern. Pendapat yang
mengidentifikasikan Cempa dengan Jeumpa di Aceh kelihatannya diperkuat
juga oleh rute perjalanan yang telah ditempuh oleh orang suci Islam lain,
seperti Syekh Ibnu Maulana, dari Tanah Arab ke Jawa yaitu Aceh, Pasai,
Campa, Johor, Cirebon. Apabila Cempa adalah Jeumpa ditukar tempatnya
dengan Pasai, maka rute perjalanannya lebih masuk akal. Dalam sebuah
petikan Kroniek van Banjarmasin tentang sejarah Jawa terdapat nama Pasai
di tempat yang seharusnya menurut orang adalah Cempa. Ini menimbulkan
dugaan bahwa Cempa atau Jeumpa dan kota Pasai yang jauh lebih terkenal
itu saling berhubungan. Mungkin tempat itu pada abad XV dan XVI lebih
penting daripada sekarang sebagai pangkalan dalam perjalanan laut menyusur
pantai timur Sumatera. Menurut ilmu bahasa, ada juga hubungan antara
Jeumpa dan Cempa.26 Menurut Hamka, ada putri Islam dari Campa pada
mulanya berat taksiran orang bahwa putri Campa itu datang dari Campa (Indo
Cina). Akan tetapi, kemudian seorang penulis menerangkan bahwa tempat
asalnya ialah Jeumpa, satu negeri di Aceh. Menikah dengan Raja Majapahit
lalu ditemukan pula tarikh wafatnya pada nisannya, bertepatan dengan tahun
1448 M.27
b. Pendapat kedua tentang letak Cempa ini diperkuat oleh sastra sejarah Melayu
dan Jawa. Cerita Sadjarah Malayu memuat riwayat singkat Kerajaan Campa.
Di situ secara khusus diberitakan bahwa penduduknya tidak makan daging
sapi dan tidak menyembelih sapi. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa
mereka beragama Hindu atau Buddha. Raja Campa bernama Pau Kubah yang
25H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 21-22. 26H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 23-24. 27Hamka, Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara , hal 553.
23
kawin dengan putri dari Lakiu. Ibu kota Campa bernama Bal dan dari sumber
lain tahun 1471 M direbut oleh orang Annam (Vietnam).28
Dengan demikian, menurut Hamka kalau benar bahwa Campa itu bukan yang
di Annam Indo Cina, tetapi di Aceh yaitu negeri Jeumpa. Maka Raden Rahmat adalah
keturunan Arab yang datang dari Aceh. Dikirimlah Raden Rahmat itu oleh kakeknya,
Raja Campa (Jeumpa), ke Tanah Jawa dan singgah dua bulan di Palembang.29
Hubungan antara Kerajaan Cempa dengan Kerajaan Majapahit berlangsung
secara harmonis. Mungkin Cempa harus dicari di tempat yang lebih jauh lagi, di
pesisir timur Indocina. Keraton Cempa secara khusus diberitakan bahwa
penduduknya tidak makan daging sapi dan tidak menyembelih sapi. Semula itu tlatah
taklukan Raja Majapahit. Cempa pada 1471 M direbut oleh orang Annam atau
Vietnam. Keraton Cempa ditaklukkan oleh raja dari Koci ketika Raden Rahmat
bermukim di Jawa. Raden Rahmat bersama saudaranya sebelum tahun 1471 M sudah
berangkat dari Cempa ke Jawa Timur.30 Hubungan darah antara Cempa dan Majapahit
nantinya akan melahirkan Raden Fatah sebagai pendiri Kerajaan Demak Bintoro.
Keraton Majapahit merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan yang sangat
maju. Sedangkan wali-wali di Jawa berpusat di Masjid Agung Demak Bintoro,
disitulah mereka mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran mengenai
keislaman.31 Kedudukan Majapahit nantinya dilanjutkan oleh Keraton Demak.32
Dalam tulisan Tome Pires tentang Pasai bahwa kerajaan Pasai menjadi
wilayah yang makmur dan kaya dengan pedagang-pedagang yang berdatangan dari
berbagai negeri Moor dan Keling. Mereka semua menjalankan perdagangan berskala
besar. Salah satu kelompok pedagang yang terpenting adalah orang-orang Bengal.
Selain mereka ada, ada pula pedagang-pedagang Rum, Turki, Arab, Persia, Gujarat,
Keling, Melayu, Jawa, dan Siam. Para pedagang yang melakukan jual beli di Pasai
merupakan orang-orang Gujarat, Keling, Bengal, pria-pria dari Pegu, Siam, pria-pria
Kedah dan Beruas dan mereka menyebar ada kelompok-kelompok yang sangat
banyak ke Pasai, Pedir dan sisanya ke Malaka.33
Dalam tulisan Tome Pires tentang Kerajaan Champa bahwa di seberang
wilayah Kamboja, di sepanjang pesisir, daerah pedalaman, terdapat Kerajaan
Champa. Negeri ini besar dan menghasilkan beras dalam jumlah besar, daging dan
bahan makanan lainnya. Negeri ini tidak memiliki pelabuhan untuk menampung jung-
jung besar. Di tempat ini terdapat sejumlah kota di sepanjang sungai. Kapal-kapal
yang bisa mencapai 1,5 depa air biasa berlayar di saar air pasang. Muara sungai akan
menjadi kering pada saat air surut. Banyak lanchara yang berlayar dari Siam hingga
28H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 24. 29Hamka, Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara , hal 553. 30Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 29. 31Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 30. 32Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 31. 33Tome Pires, Suma Oriental, hal 201-204.
24
Pahang. Raja di wilayah ini adalah seorang pagan. Ia menguasai banyak taklukkan. Ia
kaya dan mendapatkan penghasilan dari peternakan. Rakyatnya memiliki kuda.
Champa tidak menjalin hubungan dagang yang besar dengan Malaka karena Malaka
mendapatkan barang-barangnya dari Siam. Orang-orang Champa lemah di lautan.
Negeri ini membutuhkan lanchara yang bisa berlayar di perairan dangkal, karena
negerinya hanya memiliki sedikit air. Negeri ini tidak memiliki pelabuhan. Mereka
juga tidak memiliki warga Moor di kerajaan.34
B. Riwayat Raden Fatah dalam berbagai Sumber Lokal menurut Sejarawan
1. Babad Tanah Jawi
Lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa Tengah, di Demak, sejak abad XVII
mendapat perhatian para pembawa cerita dan penulis sejarah Jawa.35 Cerita-cerita
babad pada abad-abad sebelum munculnya raja Mataram pertama dipenuhi dengan
legenda yang menghubungkan munculnya Kerajaan Demak dengan runtuhnya
Majapahit dari zaman pra-Islam. Raden Fatah atau Fattah atau Victor menjadi
pahlawan besar dalam legenda ini.36
Menurut cerita tradisi Mataram Jawa Timur, raja Demak yang pertama adalah
Raden Fatah, putra raja Majapahit yang terakhir (dari zaman sebelum Islam), yang
dalam legenda bernama Brawijaya. Ibu Raden Fatah konon seorang putri Cina dari
keraton Raja Majapahit. Waktu hamil putri itu dihadiahkan kepada seorang anak
emasnya yang menjadi gubernur di Palembang. Disitulah Raden Fatah lahir.
Dari cerita yang cukup rumit ini ternyata bahwa para pembawa cerita
menganggap kesinambungan sejarah dinasti Majapahit dan Demak itu sangat penting.
Yang istimewa ialah soal keturunan Cina dan asal dari palembang sang Putri Cina. 37
Raden Fatah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Raden
Fatah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan
dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Sebagai penguasa,
negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden
Fatah berperan penting dalam mengembangkan kesenin wayang agar sesuai dengan
ajaran Islam.38 Raden Fatah saat berkuasa menggunakan gelar Senapati Jimbun
Ningrat Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama, dianggap
sebagai pendiri Kesultanan Demak. Makamnya terletak dibelakang Masjid Agung
Demak.39
Menurut Rachmad Abdullah bahwa Raden Fatah (Sultan Fattah) adalah putra
Prabu Brawijaya. Tentang siapa sebenarnya Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda
34Tome Pires, Suma Oriental, hal 156-158.
35H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 39. 36H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 40. 37H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 42. 38Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 318. 39Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 319.
25
Sultan Fattah, ternyata hingga kini belum ada titik temu sebagian menyatakan bahwa
Kertawijaya raja Majapahit yang berkuasa pada 1447-1451 M. Namun sebagian lagi
menyatakan ayah Sultan Fattah adalah Kertabhumi raja Majapahit yang berkuasa pada
1474-1478 M.40
Raden Fatah atau Sultan Fatah masa kecilnya bernama Raden Hasan atau
Raden Jinbun. Ia adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V dengan Putri
Andarawati dari Cempa (termasuk wilayah Kamboja), setelah di majapahit diberi
nama Dewi Dharawati Murdaningrum. Meskipun ia seorang putra Majapahit, namun
sejak dalam kandungan ibunya, telah diberikan kepada Raden Haryo Damar (putra
Brawijaya V dengan Dewi Sumintapura) yang menjadi adipati di Palembang. Oleh
karenanya, Raden Hasan lahir di Palembang.41
Sesampainya di Blambangan, Prabu Brawijaya yang disertai Sabdapalon dan
Nayagenggong itu menghentikan langkah. Datanglah Sunan Kalijaga kepada Prabu
Brawijaya, Sunan Kalijaga kemudian menyampaikan pesan Raden Fatah, agar raja
kembali ke istana. Prabu Brawijaya tidak bersedia. Sebaliknya Prabu Brawijaya justru
akan meminta bantuan dari Prabu Dewa Agung di Kelungkung Bali untuk menyerang
Bali untuk menyerang Raden Fatah.42
Mendengar ungkapan Prabu Brawijaya, Sunan Kalijaga mengalihkan
pembicaraan. Pembicaraan yang diarahkan Sunan Kalijaga agar Prabu Brawijaya
bersedia memeluk agama Islam. Siasat untuk mengislamkan Prabu Brawijaya
berhasil, sesudah Sunan Kalijaga melafalkan kalimat syahadat dan menguraikan
makna yang tersirat di dalamnya. Prabu Brawijaya telah memeluk agama Islam.
Namun Sabdapalon dan Nayagenggong tetap memeluk agama Buddha.43 Sunan
Kalijaga berkata sebanyak-banyaknya sampai Prabu Brawijaya berkenan pindah
agama Islam dan bersyahadat. Sang Prabu pun sudah lahir batin berkenan masuk
agama Islam.44
Menurut Agus Sunyoto dalam Historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden
Fatah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa Prabu
Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Fatah terjadi perbedaan pendapat. Sebagian
menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1447-1451
Masehi. Sebagian lagi menyatakan Kertabhumi, Maharaja Majapahit yang berkuasa
pada 1474-1478 Masehi. Namun, karena dalam banyak sumber disebutkan bahwa
Brawijaya yang menjadi ayah Raden Fatah itu menikahi Putri Champa bernama
Darawati, tidak diragukan lagi yang dimaksud Brawijaya itu adalah Sri Prabu
Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada 1447-1451 Masehi, yang
menggunakan gelar Abhiseka Wijaya Parakramawardhana, yang saat mangkat
dikebumikan di Kertawijayapura. Sejumlah silsilah yang disusun oleh keturunan Arya
40Rachmad Abdullah, Sultan Fattah: Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa
(1482-1518), hal 70. 41Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 62.
42Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, Geger Bumi Majapahit
(Yogyakarta:Araska, 2014), hal 207. 43Krisna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, Geger Bumi Majapahit, hal 208. 44Purwadi, Prabu Brawijaya Raja Agung Binathara Ambeg Adil Paramarta (Jakarta:
Oryza, 2013), hal 306.
26
Damar Adipati Palembang, tegas menyebutkan nama Prabu Kertawijaya sebagai ayah
dari Arya Damar dan sekaligus Raden Fatah.
Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Fatah lahir dari seorang perempuan Cina
yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Karena permaisuri Prabu
Brawijaya yang berasal dari Champa sangat cemburu dengan perempuan Cina yang
dikisahkan sehari bisa berganti rupa tiga kali itu, maka selir yang dalam keadaan hamil
itu dihadiahkan kepada putra sulungnya, Arya Damar, yang menjadi raja
Palembang.45
Raden Fatah adalah raja Demak yang pertama. Keraton Demak Bintoro
berdiri ditandai dengan sengkalan: geni siniraman janma atau tahun 1403 Saka atau
1478 Masehi, setelah mundurnya Sinuwun Prabu Brawijaya V dari Keraton
Majapahit. Dalam Babad Tanah Jawi dikisahkan sebagai berikuti: Sinuwun Prabu
Brawijaya V di Majapahit, memiliki istri selir seorang putri Cina, yang cantik
rupawan.46
Menurut Babad Tanah Jawi tentang silsilah raja-raja Jawa, Brawijaya V
menikahi putri Campa. Dikisahkan suatu malam dia bermimpi menikah dengan
seorang putri dari negeri Campa. Esok paginya dia memanggil Ki Patih, lalu
disuruhnya dia pergi ke Campa dengan membawa surat untuk raja Campa yang isinya
berupa lamaran. Yang lain mengatakan, dari Bhre Kertabhumi yang berdarah Jawa
dan putri berdarah Cina yang bernama Ling Ah lahirlah Sultan Fattah. Pendapat lain
menyatakan bahwa putri Campa tersebut bernama Siu Ban Cie, putri Syekh Bentong.
Dengan demikian Sultan Fattah berdarah bangsawan berdarah Jawa dan Cina.
Sultan Fattah dilahirkan pada tahun 1448 M di Palembang dan wafat pada
tahun 1518 M di Demak Bintoro pada usia 70 tahun. Nama kecilnya Jin-bun (Jimbun)
yang berarti orang yang kuat. Oleh Arya palembang (Sapu talang) beliau diberi nama
Hasan. Ibunya memberi nama Yusuf. Beliau oleh masyarakat Jawa lebih dikenal
dengan nama Raden Fatah. 47
Menurut versi Babad Tanah Jawi, nama Raden Fatah adalah Jin Bun yang
bergelar Senapati Jimbun. Dia adalah putra Brawijaya atau Bhetoro Wijoyo, raja
terakhir Majapahit dari selir keturunan China. Karena Ratu Dwarawati sang
permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa
memberikan selir China tersebut kepada putra sulungnya yang bernama Arya Damar,
bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Fatah, putri China dinikahi oleh Arya
Damar dan melahirkan Raden Kusen.48
Asal usul Raden Fatah ada dalam tradisi babad, serat, dan kronik cina. Nama
Raden Fatah terdapat dalam Babad Tanah Jawi.49 Babad disusun pada masa
pemerintahan Paku Buwono I yang menjadi Sunan Mataram hingga 1719 M. Menurut
Serat Kanda, putri Campa ini dinikahi oleh Brawijaya V ketika Brawijaya V masih
45Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320. 46Purwadi dan Maharsi, Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah Jawa,
hal 34. 47Rachmad Abdullah, Sultan Fattah: Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa
(1482-1518), hal 71. 48Rachmad Abdullah, Sultan Fattah: Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa
(1482-1518), hal 72. 49Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 62.
27
menjadi putra mahkota, belum menjadi raja Majapahit, dengan kedudukan sebagai
Pangeran Mangkubumi.
Menurut Babad Tanah Jawi, Raden Fatah bergelar Senapati Jimbun Ningrat
Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama, sedangkan menurut
Serat Pranitiradya, bergelar Sultan Syah Alam Akbar, dan dalam Hikayat Banjar
disebut Sultan Surya Alam. Namun gelar yang diberikan oleh para Wali sebagai Sultan
Demak Bintara yang pertama adalah Sultan Patah Senopati Bintoro Panembahan
Jimbuningrat Ahmad Abdur Rahman Arifin Syah Alam Akbar Kalifatullah Sayidin
Panatagama Ing Demak Bintoro.50
Raden Fatah dan prajurit Demaknya berhasil mengalahkan prajurit
Girindrawarddhana, dan bahkan berhasil membinasakannya. Kemudia sebagai
peringatan atas kemenangan Demak Bintoro terhadap Girindrawardhana Bhre Keling
tersebut diperingati dengan condrosengkolo: Sirna Hilang Kertaning Bhumi51 yang
diartikan sebagai tahun 1400 Saka atau bertepatan dengan tahun 1478 M. Sedangkan
makna dari condrosengkolo itu sendiri adalah: Hilang lenyap keburukan atau
kejahatan di bumi. Kertaning dari kata bentukkan Sukerta dan ning yang berarti
kotoran, keburukan, kejahatan.
Karena situasi dan kondisi Majapahit sudah tenang dan aman. Masyarakatpun
sudah kembali melakukan aktifitas sehari-harinya, maka Raden Fatah memohon
bantuan kepada Sunan Kalijaga supaya mencari Prabu Brawijaya V untuk diajak
pulang ke Demak Bintoro. Maka berangkatlah Sunan Kalijaga mencari Prabu
Brawijaya V ke lereng Gunung Lawu.
Sunan Kalijaga berhasil menemukan keberadaan Prabu Brawijaya V di lereng
Gunung Lawu bersama beberapa prajurit dan abdi dalam setianya yaitu Sabdo Palon
dan Naya Genggong. Beliau kemudian diajak pulang ke Ampel Denta dan bersedia
memeluk Agama Islam. Berita ini sebagaimana keterangan dari Jangka Jayabaya
Sabdo Palon-Naya Genggong.52 Setelah diislamkan oleh Sunan Kalijaga, Prabu
Brawijaya V diajak pulang ke Demak Bintoro, namun Sang Prabu tidak bersedia.
Sang Prabu Brawijaya V lebih memilih pulang ke Ampel Denta. Dalam keadaan yang
letih dalam usia tua Prabu Brawijaya V sampai juga di Ampel Denta dan disambut
dengan tangis kesedihan oleh Nyai Ageng Ampel.
Biarpun demikian Prabu Brawijaya V mengharap bahwa kisah perjalanan
hidupnya di usia lanjut ini, yang mengalami tragedi pelengseran yang tidak normatif
dan tidak susila ini tidak menjadikan kesedihan. Tentang nasib yang dialami Sang
Prabu tersebut sudah diterima dengan hati yang lapang. Setelah beberapa minggu
tingggal di Ampel Denta, Sang Prabu Brawijaya V berangsur-angsur menderita sakit,
selain karena usia sudah lanjut juga karena pukulan kejiwaan yang mendalam atas
ulah dari anak keturunannya sendiri. Sehingga menjelang wafat, beliau berpesan atau
berwasiat kepada Raden Sahid atau Sunan Kalijaga dan keluaga Ampel Denta. Isi
pesan atau wasiatnya adalah jika beliau meninggal hendaknya jasadnya tidak dibawa
ke Demak Bintoro namun dimakamkan di Sastrawulan,53 di pusat Kotanegara
50Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 63. 51Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 36. 52Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 37. 53Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 38.
28
Majapahit dan nisannya supaya dituliskan nama permaisurinya yaitu Dewi Putri
Cempa.54
Berbagai ragam ditulis dalam Babad Islam di Tanah Jawa tentang pribadi
Raja Demak yang pertama. Dikatakan bahwa baginda adalah salah seorang putra Raja
Majapahit yang penghabisan, Brawijaya. Akan tetapi, ibunya bukanlah bangsawan
jadi ia bukan putra Gahara. Ibuya ialah seorang dayang-dayang istana raja-raja besar
banyak terdapat dayang-dayang istana kiriman Tiongkok seperti terdapat juga dalam
istana sultan-sultan di Malaka. Kabarnya konon, hati Batara Brawijaya sangat
tertawan oleh kecantikan dayang itu sehingga kurang perhatiannya kepada permaisuri
sampai menimbulkan hasad dengki di istana. Ketika perempuan itu lagi hamil,
dikirimlah ia oleh raja ke negeri Palembang, ditumpangkan kepada putra baginda,
Arya Damar, yang menjadi Adipati Majapahit di Palembang.55
2. Serat Kanda
Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa bahwa asal usul Raden Fatah
sebagai putra Prabu Brawijaya dengan selir Cina itu dituturkan sebagai berikut: Arya
Damar memenuhi panggilan raja dan saat menghadap Sri Prabu bersabda wahai Arya
Damar, cepat bawalah istriku asal Cina yang lagi hamil ini ke Palembang. Jika sudah
melahirkan anakku, terserah sekehendakmu Damar. Putri Cina dikisahkan memiliki
kapal beserta isinya. Arya Damar buru-buru naik kapal bersama-sama dengan ibunya,
Ni Indhang, beserta uwanya berlayar para duruwiksa. Sudah banyak orang beragama
Buddha (Hindu-Buddha) yang masuk Islam. Banyak maulana yang datang dari
berbagai negeri, tinggal di negeri Jawa mencari penghidupan. Prabu Brawijaya tahu
bahwa istrinya yang hamil telah sampai di Palembang dan melahirkan putra yang
tampan, bercahaya seperti bintang yang dinamai Raden Fatah, yang sangat suka
kepada agama. Putri Cina itu lalu dinikahi oleh Arya Damar, melahirkan seorang putra
yang dinamai Raden Kusen.56
Versi lain menurut Serat Kanda, Sultan Fattah termasuk putra mahkota Bhre
Kertabhumi (Kung-Ta Bu Mi). Bhre Kertabhumi memiliki seorang permaisuri dari
Champa bernama Ratu Dwarawati yang beragama Islam. Dia diberi hadiah seorang
putri cantik dari China atas persetujuan permaisurinya, putri Kyai Bantong. Karena
kecantikan wajahnya dan terlalu disayang oleh Bhre Kertabhumi, membuat
Dwarawati merasa iri lalu dia memohon kepada suaminya agar dia dikembalikan ke
China. Bhre Kertabhumi akhirnya menghadiahkannya kepada Arya Damar, Adipati
Palembang.57
54Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro Pajang dan Mataram, hal 39. 55Hamka, Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian hingga Islam di Nusantara , hal 559. 56Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320. 57Rachmad Abdullah, Sultan Fattah: Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa
(1482-1518), hal 72.
29
3. Serat Pararaton
Dalam Serat Pararaton, raja di Keling, Kahuripan dengan gelar
Rajasawardana Sinagara. Bre Pamotan II alias Bre Keling II alias Bre Kahuripan V
alias Rajasanagara alias Si (nga) nagara bertahta tahun 1373 Saka dan wafat tahun
1375 Saka di makamkan di Sepang. Beliau memiliki 4 anak, yaitu Bre Kahuripan, Bre
Mataram, Bre Pamotan, dan Bre Kertabumi. Dalam 3 tahun tidak ada raja, mulai tahun
Saka 1375-1378 (1453-1456 Masehi).58
4. Carita Purwaka Caruban Nagari menurut Sejarawan
Menurut Carita Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Cina Prabu
Brawijaya adalah Siu Ban Ci. Ia putri hasil perkawinana Tan Go Hwat dengan Siu Te
Yo, penduduk muslim Cina asal Gresik. Tan Go Hwat adalah seorang saudagar dan
juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tome Pires dalam Suma
Oriental menegaskan bahwa pendiri Dinasti Demak yang bernama Pate Rodin, adalah
cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah di Gresik. Catatan Carita Purwaka
Caruban Nagari yang menyatakan bahwa ibu Raden Fatah adalah anak perempuan
Tan Go Hwat, seorang muslim Cina asal Gresik bersesuaian dengan kesaksian Tome
Pires yang datang ke Jawa pada masa kebangkitan Demak menuju kebesaran, yaitu
pada 1512-1514 ketika Adipati Unus berkuasa.
Pandangan yang menyatakan bahwa kakek Raden Fatah yang bernama Tan
Go Hwat yang mahsyur disebut Juragan Bantong sebagai orang59 dari keturunan
rendah asal Gresik, kiranya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada awal
abad ke 16 yang menempatkan penduduk pribumi sebagai orang mulia (wwang yukti)
dan sebaliknya penduduk asing dan keturunannya sebagai orang rendah sederajat
pelayan (wwang kilalan) sebagaimana tercatat pada Prasasti Sangguran. Dan jika
penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu sebagaimana tatanan sosial
kemasyarakatan era Majapahit, digolongkan sebagai kaum Mleccha, yang
kedudukannya dibawah golongan Candala, yaitu dua tingkat di bawah golongan
Sudra.
Jadi keluarga dekat Raden Fatah (Adipati Demak) memiliki kakek bernama
Tan Go Hwat menikah dengan Siu Te Yo dan melahirkan seorang putri bernama Siu
Ban Ci. Sri Prabu Kertawijaya (Brawijaya) menikah dengan Putri Champa bernama
Darawati dan Putri Cina bernama Siu Ban Ci. Raden Fatah dilahirkan dari Putri Cina,
Siu Ban Ci.60 Pendidikan awal yang diperoleh Raden Fatah dipastikan berasal dari
sang ibu yang tentunya menanamkan kaidah-kaidah dasar ajaran Islam. Selain itu
Raden Fatah juga belajar masalah agama dan ilmu pemerintahan kepada Arya
Damar.61
58R.M Mangkudimedja dan Hardjana HP, Serat Pararaton Ken Arok (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan
Daerah, 1980), hal 182-187. 59Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320. 60Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 322. 61Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 323.
30
5. Sadjarah Banten
Karya besar Sadjarah Banten memuat riwayat Jawa Barat, meskipun
kemudian bercampur dengan sisipan tradisi Jawa Timur dan Mataram. Dalam cerita
tentang Aria Damar dari Palembang dalam Sadjarah tadi, terdapat suatu fragmen
mengenai raja-raja pertama di Demak. di Cina, muncul seorang Syekh Jumadil Akbar
yang mengislamkan raja. Usaha itu tidak berhasil. Suatu gaib menyatakan bahwa raja
Cina akan tetap kafir. Konon, Jumadil Akbar kemudian berangkat ke Jawa dengan
menumpang kapal seseorang dari Gresik. Tetapi setelah Jumadil Akbar berangkat,
rupanya raja Cina itu yakin akan keunggulan agama Islam.
Konon, Syekh Jumadil Akbar menanam biji durian di alun-alun raja, yang
secara menakjubkan cepat tumbuh menjadi pohon. Raja Cina itu mengutus patihnya,
untuk mencari dan mengajak kembali syekh yang sudah berangkat itu. Patih telah
mencarinya di Siam, Samboja, Sanggora, dan Pulau Atani, hingga akhirnya sampai
juga di Gresik. Tetapi syekh itu ternyata sudah menghilang. Di Gresik konon patih
Cina bersama kedua putranya, Cun-Ceh dan Cu-Cu masuk Islam. Patih itu dan
seorang putranya Cun-Ceh meninggal di Gresik. Menurut cerita, Cu-Cu kemudian
dapat mencapai status yang tinggi.62
Ki Dilah, vasal dari Palembang, agaknya mengabaikan kewajibannya untuk
menghadap maharaja di Majapahit pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu,
maharaja Majapahit memerintahkan penguasa di Demak, Cu-Cu untuk
memperingatkan penguasa di Palembang. Usaha itu berhasil: Ki Dilah tunduk waktu
Cu-Cu muncul di Palembang dengan membawa gong Mesa Lawung, dikiranya
maharaja sendiri yang datang. Ia ikut pergi ke Majapahit. Sebagai imbalan atas jasa-
jasanya, Cu-Cu diberi gelar Aria Sumangsang. Maharaja bahkan menghadiahkan
kepadanya seorang putri Majapahit sebagai istri.
Sadjarah Banten mengabarkan lebih lanjut, konon kemudian Arya Dilah dari
Palembang membangkang lagi. Sekali lagi Cu-Cu Sumangsang dikirim oleh maharaja
untuk menghadapinya. Dan untuk kedua kalinya Cu-Cu berhasil menundukkan Ki
Dilah dengan menggunakan nyala keris pusaka “Kala Cangak”. Sebagai hadiah atas
kemenangannya yang kedua ini, Cu-Cu Sumangsang dihadiahi gelar mulia Prabu
Anom oleh maharaja Majapahit. Anaknya, yang sementara itu sudah lahir, diberi gelar
Ki Mas Palembang.
Dalam buku Sadjarah Banten cerita itu kemudian masih disusul oleh
pemberitaan bahwa Prabu Anom di Demak yang beragama Islam mencoba
mengislamkan raja. Tetapi raja yang sudah tua itu menolak. Dengan ini berakhirlah
bagian cerita tentang Cu-Cu dari Demak dalam Sadjarah Banten.
Orang Kudus dari Ngampel Denta mengutus salah seorang muridnya untuk
mendirikan permukiman Islam di Bintara (dekat Demak). permukiman ini dalam
waktu singkat berkembang menjadi kota penting. Hal ini terdengar oleh Lembu Sora,
dan dilaporkannya kepada raja Majapahit. Perintis itu oleh raja Majapahit diberi gelar
tandha di Bintara. Konon tandha di Bintara bersama para pengikutnya yang beragama
62H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 43.
31
Islam merencanakan suatu komplotan untuk melawan raja yang kafir itu. Pada suatu
malam mereka menyerang raja di istananya. Raja gugur, tetapi anaknya, Lembu
Peteng, selamat. Menurut cerita, Lembu Peteng kemudian oleh tandha di Bintara
dijadikan anak angkat.63
6. Hikayat Hasanuddin
Buku sejarah Banten lain yang penting, Hikayat Hasanuddin, tidak memuat
cerita yang panjang lebar, tetapi banyak nama dan tahun kejadian. Teks itu
menyebutkan nama moyang Cina tersebut, Cek Ko-Po dari Munggul.
Cek ini tentu kata Cina yang berarti paman menurut Klinkert. Dalam bahasa
Melayu kata itu, dalam bentuk encek masih dipergunakan sebagai kata sapaan yang
sopan: tuan, nyonya. Kata “Munggul” ini mengingatkan kita akan kata “Mongolia”.
Nama “Moechoel”, yang disebut musafir Cornelis de Bruin, mungkin salah lafal dari
kata itu juga.
Seorang Belanda lain dari abad XVII, Hendrick van der Horst, juru bahasa
VOC di Batavia menulis bahwa menurut keterangan seseorang moyang tersebut
berasal dari tanah Mogael, berbatasan dengan Arabia. Rupanya, beberapa nama
geografis yang agak mirip dikacaukan satu sama lain. 64
Hikayat Hasanuddin menandaskan bahwa penguasa kedua Demak itu dikenal
juga dengan nama Aria Sumangsang dan menyebut juga sehubungan dengan
tindakannya nama kota Palembang.65
63H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 45-46.
64H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 43.
65H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 46.
32
BAB III
GENEALOGI ISLAM RADEN FATAH
DALAM HISTORIOGRAFI ULAMA SUNDA
Selama ini tulisan dan sanad riwayat para Ulama belum dilibatkan dalam
penelitian dan penulisan sejarah khususnya dalam sejarah Raden Fatah. Dalam BAB
ini akan membahas tentang Silsilah Raden Fatah dengan menggunakan sumber-
sumber dari Babon Sukapura, Catatan Rukun Warga Limbangan, Catatan KH. Atung
Aunillah, Kitab Al Fatawi, Sanad Riwayat para Ulama, dan Suma Oriental karya
Tome Pires. Tome Pires menuliskan bahwa kakek Raden Fatah adalah Penguasa
Cirebon, sedangkan Cirebon memiliki kaitan erat dengan Pajajaran. Maka dari itu,
pentingnya mengkaji genealogi Pajajaran serta keterkaitannya dengan kerajaan-
kerajaan lain.
A. Sumber-sumber yang digunakan
1. Sejarah Pencatatan Sejarah Sukapura
Babad Tanah Jawi dan Pararaton mempengaruhi riwayat-riwayat suku Jawa
terutama trah keraton Yogyakarta dan Surakarta, tetapi juga mempengaruhi masuk ke
wilayah tatanan Sejarah Pasundan termasuk Babon Sukapura. Hal tersebut
ditunjukkan dengan adanya tulisan sebagai berikut:
“iyeu sadjarah toeren noe djoemeneng Ratoe di Djawa atawa Soenda djaman
aki djaman Dewa nepi ka para Boepati noe djoemeneng di Soekapoera jeung nganggo
ditjaritakeun heula asal oesoelna noeroet boekoe. Poestaka Radja djeung njatet tina
boekoe Adjisaka serta tina Babad Tanah Jawa noe geus ditjicatk ku Walanda.”
“demi saladjengna ka sadjarah para Boepati Soekapoera djeung sapoetre-
poetra wayahna beunang ngoempoel-ngoempoel noeroen para leluhur atawa
meunang nanya-nanya ti para soepoeh.”
Jika diartikan ke Bahasa Indonesia, yaitu:
“Sejarah ini turun temurun mengenai Ratu Jawa atau Sunda dari zaman Dewa
sampai ke para Bupati Sukapura, terlebih dahulu diceritakan asal-usul mengambil dari
buku Pustaka Raja dan dari buku Ajisaka dan juga Babad Tanah Jawi yang sudah
dicetak oleh Pemerintah Belanda.”
Sehubungan pada Buku Pustaka Raja, Ajisaka, dan Babad Tanah Jawi
banyak keganjilan maka pada uraian berikutnya terdapat kata wayahna alias terpaksa,
yaitu: “dan selanjutnya karena banyak keganjilan, Sejarah Sukapura dari Raja Jawa
sampai kepada para Bupati Sukapura, dan para putra-putranya hasil dari pengumpulan
tulisan-tulisan yang disalin dari buku-buku para leluhur atau dari hasil bertanya dari
para sepuh-sepuh Sukapura.”
Dari uraian diatas maka sesungguhnya para penulis Sejarah Sukapura secara
halus sudah menolak isi dari Babad Tanah Jawi dan babad lainnya sehingga para
sesepuh menyalin kembali dari tulisan-tulisan warisan para leluhur di zaman tersebut,
33
diantara pada zaman Raden Indrayuda maupun Kyai Raden Abdullah Saleh. Dan hasil
tulisan tersebut dibawa oleh Pemerintah Belanda.
Dalam situasi politik yang tertekan maka para sesepuh Sukapura pun menulis
sejarah yang sesuai dengan Babad Tanah Jawi yang selaras dengan Pemerintah
Belanda, yaitu: “katjacita Raden Raditja lolos ninggalkeun indungna djalanan
poendoeng toeloey ngalalana. Lawas Raden Raditja dikabarkeun djoemeneng ratoe
di nagara Gilingwesi Priangan, itoengan waris ti boeyoetna nyaeta Prabu Heserta
diganti namana Praboe Watoe Goenoeng. Sanggeus djadi ratoe pareng papanggih
djeng indoengna tegesna nama Sinta tea. Tina kalawasan heunteu papanggih, djadi
pada poho di roepa. Gantjang na indoena ditanyaan, toeloey dipake pamajikan , nepi
ka boga anak hiji lalaki dingaranan Raden Raditja djoemeneng ratoe, ngadamel
nagara galoeh nama Prabu Sindula, Ratoe Galoeh I.”
Artinya: “Raden Radiya lolos meninggalkan ibundanya terus berkelana.
Lama-kelamaan Raden Radiya dikabarkan menjadi raja di negeri Gilingwesi
Priangan, mendapat waris dari kakek buyutnya yaitu Prabu Haserta. Sesudah menjadi
raja bertemu dengan ibundanya yang bernama Sinta, sehubungan terlalu lama tidak
bertemu maka keduanya menjadi lupa satu sama lain. Secara singkat akhirnya Sinta
dilamar oleh anaknya dan menikah dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak
laki-laki yang bernama Prabu Sindula yang merupakan Raja Galuh I.”
Dari uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa Raja-raja Galuh versi Babad
Tanah Jawi yang direstui oleh Belanda adalah hasil pernikahan antara ibu dan anak.
Karena hal tersebut, para penulis Sejarah Sukapura merenkonstruksi kembali sejarah
leluhur Sukapura atau Galuh dengan mengumpulkan berupa tulisan-tulisan para
sesepuh pada zaman itu dan bertanya kepada para sesepuh yang sebagian besar para
Ulama. Sehingga tulisan Silsilah Pajajaran versi Sukapura berbeda dengan tulisan
Silsilah Pajajaran versi Wangsekerta.
Pelopor penulis Sejarah Sukapura yaitu Kyai Raden Abdullah Saleh. Beliau
adalah seorang ulama tarekat pada zamannya. Beliau menulis pada tanggal 8
September 1886 M. Tulisan beliau selain bersumber dari tulisan-tulisan para sesepuh
Sukapura yang hidup sebelum beliau, juga tentu mengambil rujukan dari Raden
Indrayuda. Raden Indrayuda adalah seorang keluarga Ningrat Sukapura, pada zaman
Tumenggung Wiradadaha VIII atau 1807-1837 M.
Namun naskah asli dari Kyai Raden Abdullah Saleh sekarang sudah tidak bisa
ditemukan lagi, yang ada hanya salinan naskah tersebut yang disalin pada tahun 1889
M. Salinannya pun sudah tidak bisa didapatkan karena pada awal November 1889 M
diambil dari keluarga Sukapura di Manonjaya oleh Belanda. Naskah tersebut sekarang
berada di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.
Satu-satunya naskah yang tidak dibawa ke Belanda adalah tulisan Raden
Indrayuda yang ditulis pada tahun 1892 M. Naskah tersebut disimpan oleh ahli waris
dari Raden Indrayuda yaitu Drs. Haji Raden Herdiana, MM selaku Ketua Umum
Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura Tasikmalaya.
Raden Idrayuda menulis naskah berupa wasiat bertepatan pada tanggal 16 Juli
1892 M. Beliau menulisnya setelah KH. Raden Abdullah Saleh menulis buku Sejarah
Sukapura. Usia Raden Indrayuda lebih tua dari pada KH. Raden Abdullah Saleh. Pada
saat menulis surat wasiat, Raden Indrayuda sudah berusia 93 tahun, berarti 1 tahun
setelah wafatnya Bupati ke 14 yaitu R.T Wiraadiningrat (1875-1901 M), dan pada
34
saat tersebut ibu kota Sukapura sudah beralih dari Sukaraja ke Manonjaya. Berarti
pada saat Surat Wasiat ditulis, KH. Raden Abdullah Saleh telah wafat tahun 1889 M.
Pada naskah Surat Wasiat yang ditulis Raden Indrayuda, dikutip dari Babon
Sukapura yang disusun oleh Raden Sulaiman Anggapraja, yaitu: “iyeu kaula Raden
Indrayuda di Sukapura, mangsa nulis umurna geus 93 tahun, lahir tahun 1805 M,
ngebatkeun carrita ti karuhun Regent Sukapura ka III, puputra 62 putra.”1
Isi wasiat tersebut diantaranya membahas tentang peninggalan keluarga-
keluarga Demak dan Pajajaran yang diterjemahkan, yaitu:
1. Pedang sintung yang berukuran panjang, pegangan Batara Karang yang
bermukim di Demak.
2. Pedang sintung yang pendek, pegangan Batara Susuk Tunggal, Parung.
3. Tombak yang besar dan panjang, Kabuyutan Batuwangi.
4. Tombak cagak besar, pegangan Kiansantang Pajajaran.
5. Tombak cagak besar, pegangan Batara Mandala.
6. Cis/keris pemberian Sultan Cirebon pada saat Sukapura bergabung dengan
Cirebon.
7. Goong Dayan Dayeuh, kepunyaaan Batara Anteg.
8. Goong Pajajaran kepunyaan Prabu Siliwangi.
Benda-benda diatas adalah benda-benda peninggalan yang terkait dengan Pajajaran
dan Demak. Selain itu peninggalan Pajajaran masih ada beberapa peninggalan lainnya
seperti dari Cirebon, Mataram, dan sebagainya.
Perlu diketahui juga berdasarkan tulisan Peter Carey bahwa masjid keluarga
Ronggo di Maospati Madiun yaitu Imam Masjid pada saat itu Kiai Nuryemengi yang
merupakan keturunan Sukapura telah dijarah. Pada saat terjadinya penjarahan
(sebelum terjadinya Perang Diponegoro) Kiai Nuryemengi bersama ke 29 muridnya
sedang pulang kampung ke Sukapura.2 Sebelum Kyai Raden Abdullah Saleh menulis
naskah Sejarah Sukapura, keluarga Sukapura mempunyai beberapa naskah yang
disusun oleh para leluhur Sukapura. Namun naskah tersebut telah dijarah dan dirusak.
Sebagian besar naskah-naskah tersebut telah dibawa ke Belanda.
2. Babon Sukapura dan Sanad Riwayat Ulama
Pada 27 September 1971 M atas inisiatif dari Raden Sulaiman Anggapraja,
beliau adalah Ketua Wargi Sukapura cabang Garut, menyusun sebuah buku yang
berjudul Sajarah Babon Luluhur Sukapura, beliau mengambil rujukan tulisan berupa
naskah yang dimiliki oleh Raden Haji Panghulu Mangunreja, beliau adalah adik dari
Kyai Raden Abdullah Saleh. Naskah tersebut ditulis dalam huruf arab. Kemudian
buku tersebut di sah kan oleh Kumpulan Wargi Sukapura Puseur dan ditandatangani
pada 1 Agustus 1977 oleh Dr. Raden Bachrum selaku Ketua KWS Pusat. Pada 15
September 1977 di sah kan oleh para Dewan Sesepuh Komisi Sejarah Sukapura yang
ditandatangani oleh Raden Muhammad Sapei dan R.O Wiradimadja.
1Sajarah Babon Leluhur Sukapura disusun Raden Sulaiman Anggapraja, hal 99. 2Peter Carey, Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di
Jawa 1785-1855 Jilid 1 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011), hal 298.
35
Selain itu pada tahun yang sama 1971 M, Tim Komisi Sejarah Sukapura yang
dipelopori oleh Raden Eeng Hendriyana menyusun buku yang berjudul Babon
Sukapura yang mengambil rujukan dari Sejarah Babon Luluhur Sukapura yang
disusun oleh Raden Sulaiman Anggapraja dan Surat Wasiat yang disusun oleh Raden
Indrayuda.
Menurut keterangan dari Raden Eeng Hendriyana, sumber rujukan dari
Babon Sukapura adalah tulisan atau riwayat para sesepuh Sukapura dan data-data
peninggalan Belanda. Babon Sukapura mengalami beberapa penyempurnaan
sehubungan narasumber yang diterima oleh tim penyusun datang secara berangsur.
Maka dari itu Babon Sukapura dicetak beberapa kali. Babon Sukapura pun terdiri dari
beberapa buku yang saling bersambung dan melengkapi.
Sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan dari Sajarah Babon Luluhur
Sukapura disusun oleh Raden Sulaiman Anggapraja dan Babon Sukapura disusun
oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura Tasikmalaya atau Tim Komisi Sejarah
Sukapura, bersumber dari tulisan para Ulama, yaitu:
1. Kyai Raden Abdullah Saleh, seorang Ulama Tarekat yang merupakan
pensiunan Wedana Galonggong Manonjaya.
2. Raden Indrayuda, penulis Surat Wasiat Sukapura.
3. Raden Haji Umar Penghulu Mangunreja, adik Kyai Raden Abdullah Saleh.
Dengan demikian pembahasan terkait Silsilah Pajajaran, mengambil rujukan
dari:
1. Terjemahan dari tulisan Raden Indrayuda berupa Wasiat ditulis 16 Juli 1892
yang sudah diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yayasan Wasiat Karuhun
Sukapura Tasikmalaya tahun 2013.
2. Sajarah Babon Luluhur Sukapura yang disusun oleh Raden Sulaiman
Anggapraja ditulis pada 27 September 1971.
3. Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura
Tasikmalaya yang dipelopori oleh Raden Eeng Hendriyana ditulis pada 1971.
4. Ringkasan Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya.
Sumber lain berasal dari kalangan para Ulama berupa tulisan dan sanad
riwayat yang bersambung kepada Silsilah Pajajaran, yaitu:
1. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah
tahun 1970 yang bersumber dari catatan KH. Raden Ahmad Zakarsyi Maolani
tahun 1890.
2. Amanat Uyut Emit 17 Maret 1867 dijadikan Catatan Rukun Warga
Limbangan yang ditandatangani Raden I. Soehaeri dan Raden H.I. Ibrahim
pada 17 Maret 1998.
3. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan disusun oleh Raden Achmad Djubaedi
tahun 2013.
4. Catatan Keluarga KH. Raden Ahmad Royani ditulis tahun 1970 yang
mengambil sanad dari KH. Ahmad Dimyati/Mama Cimasuk.
5. Sanad riwayat dari keluarga besar KH. Aceng Mu’man Mansur yang
mengambil sanad dari KH. Raden Ahmad Dimyati di Pondok Pesantren
Cimasuk, panggilan akrab beliau adalah Mama Emed Cimasuk.
36
6. Sanad riwayat dari Raden Ahmad Dimyati dari KH. Raden Amin Muchidin
tahun 1985 di Pondok Pesantren Asyaadah Limbangan Garut.
7. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Raden Husni
Mubarak bin KH. Raden Atung Aunillah tahun 2019 di Kediaman KH. Raden
Husni Mubarak.
8. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Abdul Haq
Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Subang pada tahun 2009 di
Pondok Pesantren Miftahul Huda Subang.
9. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Huban Zen
Pesantren Gelar Cianjur pada tahun 2009 di Pondok Pesantren Gelar Cianjur.
10. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati didapat pada tahun 2011 dari
KH. Amang Syihabuddin yang beliau terima dari KH. Aceng Mu’man
Mansur Cimasuk pada tahun 1990 di Kediaman KH. Raden Umar Zen di
Pondok Pesantren Kubangsari Limbangan Garut.
11. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati diterima pada tahun 1992 dari
gurunya KH. Aceng Mu’man Mansyur diterima dari ayahnya KH. Raden
Ahmad Dimyati diterima dari guru-guru beliau diantaranya KH. Raden
Muhammad Adro’i/Mama Bojong Garut, KH Raden Ahmad Satidi/Mama
Gentur Cianjur, KH. Raden Muhammad Syuja’i/Mama Gudang Tasik
diterima dari gurunya KH. Ahmad Sobari Ciwedus di Kediaman KH Aceng
Mu’man Mansyur.
12. Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari Raden Achmad Djubaedi
tahun 2013 di Kediaman Raden Haji Holil Aksan Umar Zen.
13. Sanad riwayat dari Navida Febrina Syafaaty dari Raden Haji Tiar Saiful Barri
tahun 2020 di PT Noor Abika Tours & Travel, dari KH Raden Usman
Muhyiddin dari KH Muhammad Iyad Pesantren Bunisari Tasikmalaya tahun
2017 di Pondok Pesantren Pinggirwangi Cicalengka Bandung.
14. Sanad Riwayat dari Raden Ahmad Dimyati tahun 2020 yang diterima dari
Kyai Raden Eeng Hendriyana dari kakek beliau Raden Suharma dari Raden
Sastrakusumah dari Raden Indrayuda di Kampung Sukapura Desa Sukaraja
Tasikmalaya.
15. Catatan Silsilah Pangeran Kornel yang dikeluarkan oleh Yayasan Pangeran
Sumedang.
16. Catatan Keluarga Dalem Cikundul dilihat oleh Raden Haji Ahmad Dimyati
tahun 1983 dan catatan tersebut milik Kyai Raden Abdul Karim bin KH.
Raden Toha Badruddin di Pesantren Al Badar Ciluluk, Cikancung, Bandung.
17. Catatan yang disimpan di Keluarga Pesantren Al Faruq Cicalengka Bandung.
18. Catatan Silsilah Keluarga Pangeran Raden Heru R Arya Natareja bin
Pangeran Yunus Sanusi.
19. Buku Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata Lainnya serta
Riwayat Leluhur Sumedang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden
Yeni Mulyani Sunarya, dan Raden Abdul Syukur.
20. Sanad Riwayat dari Navida Febrina Syafaaty tahun 2021 yang diterima dari
Kyai Raden Eeng Hendriyana dari kakek beliau Raden Suharma dari Raden
Sastrakusumah dari Raden Indrayuda di Kampung Sukapura Desa Sukaraja
Tasikmalaya.
37
Adapun buku Sejarah Pajajaran seperti Wangsekerta3 sebagai pembanding.
3. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
a. Catatan Rukun Warga Limbangan
Perihal: Amanat Leluhur Pantjer-Uyut Emit. Geusan Ngalaksanakeun Bebela
Nagara/Lemah Cai Dong Ngamerdekakeun Doeloer-doelur salaku- Tuturus Tina
Rassa Katut Perasaanana Dina Tatanan Achlaqulkarimah Nu Nyunda tur Islami-
Kalawan Madjadjaran Hanteu Pakia-Kia. Terjemahan: amanat leluhur pantjer Uyut
Emit demi melaksanakan bela negara/ibu pertiwi demi memerdekakan saudara-
saudara selaku ikut serta dalam tanggung jawab dalam tatanan akhlakul karimah yang
nyunda dan islami serta majajaran-sejajar tidak merasa paling tinggi.
Tulisan ini memuat silsilah dan amanat-amanat para sesepuh leleuhur Galih
Pakuan dan Galuh Pakuan (Uyut Emit) dalam upaya tahun 1850. Amanat ini
ditujukkan kepada keturunan Galih Pakuan dan Galuh Pakuan.
Uyut Emit dalam naskah tersebut mempunyai jasa yang besar juga,
mempunyai kharisma dalam upaya melaksanakan pantjer berjuang untuk
memerdekakan negara, akidah, dari sifat keserakahan diri, dari sifat-sifat yang
ditanamkan oleh negeri jiran (VOC-Belanda) sampai keturunan Galuh Pakuan tidak
tahu jati dirinya.
Uyut Emit adalah yang membuat sebuah kabuyutan (kelompok) keturunan
Galuh Pakuan. Uyut Emit adalah sosok yang ditakuti oleh negeri jiran (VOC-
Belanda). Belanda menjulukki Uyut Emit dengan sebutan Smith. Hal tersebut
diucapkan setelah Uyut Emit mengadakan serangan kepada Belanda dan juga
menyatukan saudara-saudara dari negeri Belanda sampai zamannya ditahun 1850.
Perjuangan beliau diteruskan oleh putranya bernama Haji Abdul Gofur yang
bergelar Santana dan surat wasiat dari Uyud Emit kepada Haji Abdul Gofur sebagai
berikut: Geura prak tuluykeun perjuanganrana para karuhun sirra sakabeh, dina
enggoning upaya ngamerdekakeun Nagara katut rahajat jeung sapangeusi nagarina
kungkungan Nagri Jiran VOC: engke dimana Nagara geus Merdeka, merdekakeun
Jelemana tina kasarakahan dirina anu geus didera temen pisan ku alpukah wisayana
deungeun anu ngagunakeun dulur-dulur urang keneh kalawan turun tumurun, kahade
masing imeut tur rintih bisi melengkung bekas nyalahan, sebab geus lengit sifat-sipet
anu temah wadina, ngahalalkeun sagala cara, sangkan sagala anu dicita-
citakeunana bisa tereh kahontal, rasa jeung perasaan teh geus teu dipake asal
ngeunah aing teu deungeun, malah lamun berbuat kasalahan oge bari jeung sadar
tapi embung disalahkeun. Terjemahan: segera lanjutkan perjuangan para leluhur
kalian semua dalam memperjuangkan kemerdekaan negara dan juga rakyat dan seisi
negeri dari cengkraman negeri VOC atau jiran. Setelah negara merdeka dan manusia
3Wangsakerta-Negarakertabhumi adalah kumpulan naskah yang diyakini oleh
sebagian sejarawan disusun oleh Pangeran Wangsakerta. Akan tetapi naskah tersebut masih
berpolemik secara nasab dan riwayat, maka dari itu sudah menjadi kewajiban para sejarawan
untuk meluruskan dari polemik tersebut dengan merujuk naskah-naskah yang disusun oleh
para Ulama.
38
merdeka dari keserakahan dirinya yang sudah terkena pengaruh doktrin maka harus
penyampaiannya dengan tata krama yang baik.
Amanat ini disampaikan pada peringatan Negara Kertarahayu ke 417 yang
dipimpin oleh Uyut Emit pada hari Senin, tanggal 17 Maret 1867, yang disaksikan
oleh Raden Tatang Afandi. Amanat ini dijadikan naskah Rukun Warga Limbangan
yang ditandatangani Raden. I. Soehaeri Priyatna dan Raden. H. I. Ibrahim pada 17
Maret 1998 peringatan Negara Kertarahayu ke 548.
b. Catatan yang ditulis oleh KH. Atung Aunillah
Berdasarkan keterangan dari KH. Raden Husni Mubarak, catatan silsilah yang
ditulis oleh KH. Raden Atung Aunillah sekitar tahun 1970, beliau mengutip dari
riwayat yang disampaikan oleh mertuanya yaitu KH. Raden Uding Muhyidin
Pengasuh Ponpes Wates Limbangan. Adapun KH. Raden Uding Muhyidin adalah
putra dari KH. Raden Mahfud (Mama Wates Sepuh) bin KH. Raden Ahmad Zarkasyi
Maulani (Mama Cikelepu Wetan Limbangan) bin KH. Raden Nur Muhammad bin
Raden Wergadireja bin Raden Muhammad Said bin Dalem Faqih Ibrahim bin Kyai
Raden Ahmad Mas’ud bin Dalem Arsawiguna bin Dalem Sutabangsa bin Dalem
Wirabangsa bin dalem Demang Wanakerta bin Sunan Cipucung bin Sunan
Cipancar/Prabu Wijayakusumah.
KH. Raden Uding Muhyidin selain menerima sanad riwayat juga dari tulisan
KH. Raden Ahmad Zarkasyi Maolani. KH. Raden Ahmad Zakarsyi wafat 1946,
berarti tulisan tersebut ditulis sebelum tahun 1946. Beliau lahir tahun 1826. Beliau
KH. Raden Ahmad Zakarsyi Maolani murid dari Syaikhuna Kholil Bangkalan
Madura. Dilain pihak KH. Raden Atung Aunillah pun menerima riwayat dari yaitu
KH. Raden Muhammad Sobar bin Ali Abdurahman/Mama Cukelepu Kulon bin KH.
Raden Aunillah bin Kyai Raden Muhammad Asim bin Kyai Raden Muhammad
Mufid. Secara nasab kedua jalur diatas adalah keturunan Sunan Rumenggong.
4. Kitab Al Fatawi
Penulis pertama yang membuat Kitab Al Fatawi adalah Ki Meong
Tuntu/Datuk Meong Tuntu. Ki Meong Tuntu adalah adik dari Raja Syah Khan
Mahmud Majidilah ini juga merupakan adik dari Sultan Karim Mukji dari Kesultanan
Pasai. Di dalam sejarah Aceh, Sultan Karim Mukji adalah Sultan ke 11 dari Dinasti
Batak Gayo di Kesultanan Aru Barumun. Artinya dari penjelasan ini Ki meong Tuntu
dan Raja Syah Khan Majidillah merupakan keluarga besar dari Kesultanan Aru
Barumun yang dahulunya merupakan sebuah dinasti Islam yang cukup ternama di
wilayah Pasai. Kenapa mereka yang dari Pasai bisa ada di Sunda Kelapa pada masa
itu? Sebabnya adalah pada masa itu antara Pasai, Demak, dan Cirebon sudah menjalin
hubungan komunikasi. Setelah jatuhnya Pasai oleh Malaka, maka hubungan yang
paling mudah ditempuh adalah Palembang dan Sunda Kelapa. Sultan Barumun yang
ke X yang bernama Sultan Zulkifli Majid telah melakukan hubungan silahturahmi
yang kuat dengan pihak kerajaan Sunda Kelapa. Setelah beliau wafat hubungan itu
diteruskan oleh putra penggantinya yang bernama Sultan Karim Mukji.
39
Ki Meong Tuntu adalah orang pertama yang membuat kitab sejarah dengan
memakai huruf Wesig. Penulisan yang dilakukan beliau pada masa itu sudah memakai
bahasa Melayu dicampur dengan bahasa Sunda Buhun (semacam bahasanya orang
Rawayan/Baduy di Pandeglang). Setelah Ki Meong Tuntu tidak ada, posisi dan
kedudukannya digantikan oleh Datuk Syah Syarif Fadhilah Khan dengan gelar
Kertawiweka Negara tahun 1530 Masehi. Hurufnya tetap memakai Wesig dan
bahasanya Melayu campur bahasa Karo (Melayu asli Kesultanan Aru Barumun Pasai
Samudra).
Kitab ini kemudian dikerjakan oleh Syah Fadhilah Khan sampai pada
masanya Maulana Hasanuddin yang menjadi Pangeran Ratu yang pertama di
Jayakarta. Dikarenakan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten, maka
kedudukan seorang Mushonaf (pencatat sejarah) diserahkan kepada Ki Mas Wisesa
Adimerta pada tahun 1580 M. Mushonaf Ki Mas Wisesa Adimerta belum
mempergunakan huruf Arab/Al Quran. Beliau telah memperkenalkan huruf Jawa
Kuno. Beliau tidak bisa menulis dengan huruf Wesig, maka bahasa penulisan yang
dibuat mempergunakan bahasa Jawa Mataram.
Setelah era Ki Mas Wisesa Adimerta seluruh lembaran/catatan itu telah
dikumpulkan oleh Pangeran Mertakusuma yang telah menjabat sebagai Pangeran
Adiningrat yang ke 4 di Jayakarta. Naskah-naskah itu terdiri dari:
1. Kulit kerbau, kayu, tembikar (lempengan tanah liat yang dikeringkan) yang
dibuat oleh Ki Meong Tuntu.
2. Kulit kerbau, rotan, kayu, dan tulang-tulang ikan dibuat oleh Syah Fadhilah
Khan.
3. Kulit kerbau, lontar, dan lempengan-lempengan tembaga, dibuat Ki Mas
Wisesa Adimerta.
Pengeran Mertakusuma telah disalin semuanya ke dalam satu kitab besar
yang diberi nama Kitab Al Fatawi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Syawal 1036
Hijriyah atau menurut Bapak Parada Harahap (yang telah dimintakan keterangan oleh
Ratu Bagus Abdul Majid Asmuni bin KH. Ratu Bagus Ahmad Syar’i Meertakusuma,
pada tahun 1930 an) jatuh pada tahun 1626 M. Namun Pangeran Mertakusuma tidak
menjadi Mushonif. Beliau hanya menyalin naskah lama.
Sebelumnya kedudukan pencatatan sejarah dilakukan oleh
1. Raden Suryakawisa Adimerta Jayakarta pada tahun 1611-1625 M.
2. Pada tahun 1680 M proses pencatatan Kitab Al Fatawi dilakukan Ratu Bagus
Haji Abbas Mertakusuma.
3. Pada tahun 1840 M pencatatan dilanjutkan oleh Ratu Bagus Bahsin
Mertakusuma.
4. Pada tahun 1870 M pencatatan dilanjutkan oleh Ratu Bagus Arbain
Mertakusuma.
5. Pada tahun 1890 M pencatatan dilakukan oleh Ratu Bagus Abdul Wahab
Mertakusuma.
6. Pada tahun 1910 semua naskah disalin ulang kembali oleh KH. Ratu Bagus
Ahmad Syar’i Mertakusuma setelah belajar langsung huruf khot kaligrafi
kepada Guru Mansur Sawah Lio, sekaligus Guru Mansurlah yang
menganjurkan agar semua Kitab Al Fatawi lama disusun ulang kembali
40
dengan menggunakan arab melayu. Pada tahun yang sama KH. Ahmad Syar’i
Mertakusuma juga melakukan perjalanan napak tilas para pejuang dan
mujahidin Jayakarta sekaligus kembali mengumpulkan punti punti Jayakarta
yang menyebar di Jayakarta untuk bersatu melawan penjajah.
5. Suma Oriental karya Tome Pires
Catatan Tome Pires dan Francisco Rodrigues yang telah berusia setengah
milenia ini tak pelak lagi merupakan karya yang monumental, khususnya dalam
sejarah perdagangan dan kelautan yang meliputi wilayah Timur Tengah, Nusantara,
hingga Cina. Seperti yang dikatakan Armando Cortesao, bahwa karya tersebut sudah
barang tentu merupakan catatan yang paling penting dan lengkap mengenai Timur
dibuat pada paruh awal abad XVI.
Buku yang penerbit terjemahkan dan terbitkan seizin Hakluyt Society ini edisi
aslinya terbit kali pada 1944 dalam bahasa inggris terdiri dari catatan perjalanan Tome
Pires dan Francisco Rodrigues yang disunting oleh ilmuwan dan kartografer
berkebangsaan Portugal bernama Armando Cortesao. Buku tersebut, selain memuat
kedua catatan tersebut, juga disertai dengan berbagai peta dan ilustrasi yang dibuat
oleh Francisco Rodrigues serta naskah Tome Pires dan Francisco Rodrigues versi
bahasa Portugal. Dimana naskah berbahasa Portugal tersebut kemudian sengaja
penerbit hilangkan dalam edisi bahasa indonesia ini untuk menghindari kemubaziran,
karena isinya persis sama. Adanya inkonsistensi penulisan nama tempat, tokoh,
barang dagangan dan lain-lain. Hal tersebut tidak lain karena berbagai kesalah tulisan
yang dilakukan Tome Pires, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Armando
Cortesao. Dalam proses penyuntingan, banyak kata-kata istilah dan nama tokoh yang
sengaja tidak diubah untuk mempertahankan kekhasan tulisan Tome Pires dan nuansa
Abad Pertengahan. Meskipun demikian, mayoritas nama tempat diubah dan
disesuaikan dengan nama aslinya pada zaman sekarang. Selain itu catatan kaki yang
terdapat di buku Suma Oriental ini hampir seluruhnya ditulis oleh Armando Cortesao,
baik dalam isi dan kegunaannya dalam menganalisis, mengomentari, mengoreksi,
ataupun membenarkan pernyataan Pires maupun Rodrigues.
Dalam Pendahuluan: Paris Codex, fakta bahwa dokumen yang sangat penting
bagi sejarah geografi seperti Suma Oriental karya Tome Pires yang sudah barang tentu
merupakan catatan yang paling penting dan lengkap mengenai Timur yang dibuat
pada paruh awal abad XVI, meskipun catatan ini ditulis pada 1512-1515, ini
terlupakan dan nyaris tidak diketahui hingga kini, sangatlah mengejutkan apalagi
buku ini terdapat codex yang sama seperti yang ditemukan dalam karya kontemporer
dari Francisco Rodrigues yang di dalamnya mencakup peta-peta berharga, yang
membuatnya menjadi buku terkenal di seluruh dunia pada pertengahan abad terakhir.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 buku Suma Oriental karya
Tome Pires versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yaitu 1) The Suma Oriental of
Tome Pires an acoount of the east, from the red sea to Japan, written in Malacca and
India in 1512-1515 and The Book of Francisco Rodrigues rutter of voyage in the red
sea, nautical rules almanack and maps, written and drawn in the east before 1515,
Translated from the Portuguese MS in the Bibliotheque de la Chambre des Deputes,
Paris and edited by Armando Cortesao, London printed for The Hakluyt Society 1944,
41
2) Suma Oriental Karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah ke Cina dan Buku
Francisco Rodrigues diterjemahkan dari buku The Suma Oriental of Tome Pires An
Account of The East, From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues,
edited by Armando Cortesao, 2 volume, The Hakluyt, 1944, diterbitkan pertama kali
dalam bahasa indonesia oleh Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015, penerjemah edisi
Indonesia oleh Adrian Perkasa dan Anggita Pramesti.
B. Silsilah Raja-Raja Sunda Pajajaran
1. Silsilah Pajajaran Versi Kitab Al Fatawi
Dalam Kitab Al Fatawi yang disusun oleh Raden Syar’i Mertakusuma pada
tahun 1910 M,4 tertulis Silsilah Pajajaran sebagai berikut:
1. Maharaja, berputra
2. Bumiwangi alias Bumisari, berputra
3. Niskala Wastu Kencana, berputra
4. Dewa Niskala, berputra
5. Sri Baduga Maharaja, berputra
6. Surawisesa, berputra
7. Singamanggala
Dalam Kitab Al Fatawi disebutkan Prabu Singamanggala menikah dengan
Nyai Mas Saribanar. Nyai Mas Saribanar adik dari Sayyid Fatahillah bin Hamid
Abdul Majid yang berputri Nyai Mas Jati Malabar yang menikah dengan Arya
Panangsang atau Arya Jipang.
Jika melihat keterangan di atas yang mana Singamanggala merupakan adik
ipar dari Sayyid Fatahillah, dan mengacu kepada Kitab Dirosah Finasbi Al Saadah
Bani Alawi5 maka dapat diprediksi bahwa masa hidup Prabu Bumisari sekitar abad ke
XIV atau lahir sekitar tahun 1370 M dan jika diberi angka toleransi 10 tahun maka
Prabu Bumiwangi pada tahun 1380 M.
Dari acuan tahun kelahiran Prabu Bumiwangi tersebut, maka tahun kelahiran
Sri Baduga Maharaja jatuh pada tahun 1450 M. Jika benar Sri Baduga Maharaja naik
tahta pada tahun 1482 M seperti yang ditulis pada Naskah Wangsekerta maka pada
saat beliau naik tahta berusia 32 tahun sedangkan pada saat wafat beliau berusia 71
tahun. Secara paralel dapat memprediksi Prabu Surawisesa naik tahta sekitar usia 51
tahun dan wafat di usia 65 tahun.
Dari uraian diatas bahwa Catatan Silsilah Pajajaran di Kitab Al Fatawi lebih
logis untuk bisa diterima sebagai susunan silsilah dibanding Wangsekerta, dan salah
4Kitab Al Fatawi adalah kitab yang ditulis oleh Raden Syar’i Mertakusuma tahun
1910 yang berisi tentang Silsilah Pajajaran, Riwayat Sayyid Fathahillah, Silsilah Demak dan
riwayat berdirinya kota Jakarta. 5Al Habib Assegaf bin Ali Al Kaff, Kitab Dirosah Finasbi Al Saadah Bani Alawi
Dzuriyyah Al Imam Al Muhajir Ahmad bin Isa, hal 75. Kitab Dirosah Finasbi Al Saadah Bani
Alawi Dzuriyyah Al Imam Al Muhajir Ahmad bin Isa adalah kitab yang ditulis oleh Al Habib
Assegaf bin Ali Al Kaff yang berisi tentang nasab bani alawiyyin atau ahli bait Rasulullah dan
membahas tentang tingkat generasi.
42
satu kekeliruan Wangsekerta dalam hal penempatan tokoh-tokoh seperti Sri Wastu
Kancana dan Dewa Niskala ditempatkan lebih tua dari Prabu Bumiwangi. Lebih
tepatnya Sri Wastu Kancana diidentifikasikan sebagai orang yang sama dengan Prabu
Lingga Wastu. Padahal menurut Babon Sukapura, generasi Prabu Lingga Wastu
diatas masa Prabu Wastu Kancana.6
Naskah Wangsekerta tidak membahas tentang keberadaan Prabu Bumiwangi.
Padahal dalam Catatan Silsilah Ningrat Limbangan terdapat tokoh bernama Prabu
Layaran Wangi alias Prabu Buniwangi alias Sunan Rumenggong.7 Sedangkan dalam
Kitab Al Fatawi tercatat dengan nama Prabu Siliwangi alias Prabu Cakraningrat, ayah
dari Prabu Cakrabuana. Dengan demikian secara kecocokan nama yaitu Prabu
Buniwangi alias Bumiwangi lebih sesuai dinisbatkan sebagai orang yang sama dengan
Prabu Siliwangi dibanding dengan Sri Baduga Maharaja putra dari Dewa Niskala.
2. Silsilah Raja-Raja Pajajaran Versi Babon Sukapura dan Para Ulama
Limbangan
a. Silsilah Pajajaran Versi Babon Sukapura dan Ningrat Limbangan
Dalam Babon Sukapura tertulis bahwa Prabu Siliwangi berputra Prabu
Munding Jayakawati berputra Raden Sangkan Welasan alias Batara Mandala.8
Berdasarkan penyesuaian Catatan Silsilah Ningrat Limbangan dan Catatan Museum
Sumedang bahwa Batara Mandala adalah anak dari Raden Sangkan Welasan.9
Prabu Siliwangi alias Prabu Banjaransari, berputra Prabu Munding
Jayakawati berputra Raden Sangkan Welasan berputra Batara Mandala, berputra:
1. Raden Jati Sunda di Anteg
2. Raden Bujangga Manik di Palembang
3. Raden Bujangga Malela di Mekkah
4. Raden Bujangga Lalang/Larang di Alas Peuntas
Sementara Raden Jati Sunda beristrikan Nyai Wajan Kasih, berputra:
1. Batara Galunggung
2. Batara Galuh
3. Batara Mandala
4. Nyai Nading Leuwih
5. Nyai Ijab Larang di Parung
6. Nyai Ijab Larangan di Karantenan, langkap Lancar
6Ringkasan Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya. 7Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah. 8Sajarah Babon Luluhur Sukapura yang disusun oleh Raden Sulaiman Anggapraja,
hal 111. 9Catatan Silsilah Ningrat Limbangan disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah dan
Catatan Silsilah Pangeran Kornel yang dikeluarkan oleh Yayasan Pangeran Sumedang.
43
Pada Babon Sukapura10, ditulis bahwa Ratu Sunda yang bertahta di Nusa
Jawa bernama Prabu Cakrawati, beliau Ratu Pajajaran. Prabu Cakrawati mempunyai
istri bernama Maharaja Kastori berputra Rangga Sunten alias Sunan Lingga Hyang.
Menurut analisis peneliti bahwa terdapat 2 dugaan:
1. Maharaja Kastori sebagai perempuan karena tulisan di Babon Sukapura
“Prabu Tjakrawati (Ratu Pajajaran) di Nusa Jawa kagungan garwa ka Maha
Radja Kastori” artinya Prabu Cakrawati (Ratu Pajajaran) di Nusa Jawa
mempunya istri kepada Maharaja Kastori.
2. Maharaja Kastori sebagai laki-laki, sehubungan gelar beliau adalah Maharaja
dan lazimnya Maharaja adalah seorang laki-laki.
Peneliti mengacu kepada versi pertama bahwa Prabu Cakrawati adalah laki-laki.
Rangga Sunten berputra Munding Jayakawati menikah dengan Nyai Ijab Larangan,
putri dari Raden Jati Sunda trah Mandala (ada tautan dari Majalengka), memiliki
putra:
1. Sareupeun Mandala
2. Sareupeun Sukakerta
3. Sareupeun Barangbang Parung bernama Sang Darma Siksa
4. Sareupeun Cibungur Parung
5. Sareupeun Sela Awi
Jika disusun uraian pertama, yaitu:
1. Prabu Banjaransari/Prabu Siliwangi, berputra
2. Prabu Munding Jayakawati, berputra
3. Raden Sangkan Welasan, berputra
4. Batara Mandala, berputra
5. Raden Jati Sunda
Pada uraian kedua tersusun silsilah, yaitu:
1. Prabu Cakrawati (Ratu Pajajaran) menikah dengan Maharaja Kastori,
berputra
2. Rangga Sunten alias Sunan Lingga Hyang, berputra
3. Prabu Munding Jayakawati dan memiliki istri bernama Ijab Larangan binti
Raden Jati Sunda bin Batara Mandala bin Raden Sangkan Welasan bin Prabu
Munding Jayakawati bin Prabu Siliwangi/Prabu Banjaransari. Berputra,
4. Sareupeun Sukakerta
Dari uraian diatas terdapat 2 nama Munding Jayakawati, yaitu:
1. Prabu Munding Jayakawati ayah dari Raden Sangkan Welasan, yaitu Prabu
Munding Jayakawati I.
2. Prabu Munding Jayakawati putra dari Rangga Sunten alias Sunan Lingga
Hyang, yaitu Prabu Munding Jayakawati II.
10Ringkasan Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya.
44
Garis persamaan di Sunan Sukakerta pada generasi yang paling bawah dan
Prabu Siliwangi di generasi paling atas. Pada Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
tercatat susunan Silsilah Sunan Nusakerta11, yaitu:
1. Ratu Ibu Permana Dipuntang, berputra
2. Prabu Siliwangi, berputra
3. Sunan Dayeuh Manggung, berputra
4. Sunan Darmakingkin, berputra
5. Sunan Rumenggong/Buniwangi/Jayakusumah, berputra
6. Sunan Cisorok, berputra
7. Sunan Salalangu, berputra
8. Sunan Nusakerta
Pada Silsilah Pangeran Kornel tersusun Silsilah Lembu Agung alias Sunan
Rumenggong12, yaitu:
1. Prabu Guru Dewa Haji Putih, berputra
2. Prabu Tajimalela/Prabu Tutang Buana, berputra
3. Sunan Rumenggong/Prabu Jayakusumah I/Lembu Agung, berputa
4. Prabu Jayakusumah II, berputra
5. Sunan Salalangu, berputra
6. Sunan Sukakerta
Pada Babon Sukapura tersusun Silsilah Lembu Agung13, yaitu:
1. Ratu Permana, berputra
2. Ratu Komara/Mundingsari, berputra
3. Prabu Guru Aji Putih, berputra
4. Prabu Tajimalela/Resi Cakrabuana, berputra
5. Prabu Lembu Agung
Jika disusun garis silsilah dari bawah ke atas dimulai dari Sunan Sukakerta
alias Sareupeun Sukakerta alias Sunan Nusakerta, maka terjadi penyesuaian silsilah,
yaitu:
1. Ratu Ibu Permana Dipuntang, berputra
2. Ratu Komara/Mundingsari/Prabu Siliwangi/Prabu Banjaransari, berputra
3. Prabu Guru Aji Putih/Prabu Guru Haji Putih/Munding Jayakawati I/Sunan
Dayeuh Manggung, berputra
4. Prabu Tajimalela/Resi Cakrabuana/Prabu Tutang Buana/Raden Sangkan
Welasan/Sunan Darmakingkin, berputra
5. Prabu Lembu Agung/Batara Mandala/Sunan Rumenggong/Prabu
Buniwangi/Jayakusumah I/Prabu Cakrawati, berputra
6. Prabu Jayakusumah II/Sunan Cisorok/Sunan Lingga Hyang, berputra
11Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah
pada halaman 8-15. 12Silsilah Pangeran Kornel yang dikeluarkan oleh Yayasan Pangeran Sumedang. 13Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura
Tasikmalaya yang dipelopori oleh Raden Eeng Hendriyana.
45
7. Sunan Salalangu/Munding Jayakawati II, berputra
8. Sunan Sukakerta/Sunan Nusakerta/Sareupeun Sukakerta
Pada Sajarah Babon Luluhur Sukapura, terkoreksi oleh Catatan Silsilah
Ningrat Limbangan dan Babon Sukapura terkait dengan Silsilah Lembu Agung,
bahwa “Prabu Siliwangi alias Prabu Banjaransari berputra Prabu Munding Jayakawati
I berputra Raden Sangkan Welasan berputra Batara Mandala.”
Batara Mandala alias Prabu Cakrawati (Ratu Pajajaran) di Nusa Jawa. Prabu
Cakrawati mempunyai istri kepada Maharaja Kastori dan memiliki putra bernama
Rangga Sunten alias Sunan Lingga Hyang. Sunan Lingga Hyang menikah dengan Ijab
Larangan, putri dari Raden Jati Sunda trah Mandala (ada tautan dari Majalengka)
berputra Munding Jayakawati II.
Mengacu kepada sumber Babon Sukapura, Limbangan, dan Sumedang:
1. Ratu Komara/Prabu Banjaransari/Prabu Siliwangi, berputra
2. Prabu Guru Haji Putih/Prabu Munding Jayakawati I/Sunan Dayeuh
Manggung, berputra
3. Prabu Taji Malela/Raden Sangkan Welasan/Sunan Darmakingkin, berputra
4. Batara Mandala/Prabu Cakrawati/Sunan Rumenggong/Prabu Lembu Agung,
berputra
Raden Jati Sunda Raden Lingga Hyang
Batara Galunggung Ijab Larangan x Munding Jayakawati II
Nyai Ajeng Sukakerta x Sareupeun Sukakerta
Dalem Himba
Pada Sajarah Babon Luluhur Sukapura bahwa Batara Mandala mempunyai
putra bernama Bujangga Malela yang bermukim di Mekkah,14 sementara tercatat
nama Bujangga Larang bermukim di Alas Peuntas.15 Yang dimaksud Alas Peuntas
dalam Bahasa Sunda adalah sebuah tempat yang sangat jauh di luar negara tempat
asalnya dan dapat dipastikan tempat tersebut adalah Mekkah.
14Sajarah Babon Luluhur Sukapura disusun oleh Raden Sulaiman Anggapraja, hal
111. 15Ringkasan Babon Sukapura disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya.
46
Dengan demikian Bujangga Larang adalah orang yang sama dengan
Bujangga Malela. Akan tetapi pada Surat Wasiat Sukapura menuliskan bahwa Batara
Karang bermukim di Denuh, Karang Pamijahan Tasikmalaya.16 Menurut Raden Eeng
Hendriyana bahwa Bujangga Larang adalah orang yang sama dengan Batara Karang.
Hal tersebut karena keduanya memiliki riwayat yang sama yaitu ditugaskan ke
wilayah Jawa tepatnya Demak. Setelah menyelesaikan tugasnya maka kembali ke
Denuh.17 Sedangkan yang bermukim di Demak pada Ringkasan Babon Sukapura
adalah Bujangga Malela.18 Jadi Bujangga Malela bermukim di Demak dan Mekkah.
Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Bujangga Malela alias Bujangga Larang alias
Batara Karang, yang pernah bermukim di Denuh, Mekkah, dan Demak.
Dengan demikian putra-putra Prabu Batara Mandala alias Prabu Buniwangi
alias Sunan Rumenggong dapat ditulis, yaitu:
1. Raden Jati Sunda di Anteg
2. Raden Bujangga Manik di Palembang
3. Raden Bujangga Malela/Bujangga Larang/Batara Karang pernah bermukim
di Mekkah, Demak, dan Denuh
4. Sunan Lingga Hyang
Pada Catatan Museum Sumedang dan Silsilah Pangeran Kornel, terdapat
beberapa hal yang harus dikoreksi, salah satunya dalam hal pencatatan tahun. Dalam
bagan Silsilah Pangeran Kornel ditulis bahwa Prabu Tajimalela alias Resi Cakrabuana
hidup pada tahun 980 M.19 Sementara pada Catatan Museum Sumedang bahwa Prabu
Tajimalela berkuasa pada tahun 1482-1492 M.20 Dan catatan tahun keduanya tidak
bisa diterima. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Sunan Rumenggong alias
Prabu Bumiwangi lahir pada tahun 1380 M dan jika ditarik keatas maka Prabu
Tajimalela diperkirakan lahir pada tahun antara 1340-1350 M.
Sebagaimana yang telah diuraikan pada Kitab Al Fatawi, disusunan raja-raja
terdapat nama Prabu Bumiwangi, sementara Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
yang bersesuaian dengan Catatan Babon Sukapura dan Museum Sumedang terdapat
nama tokoh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Buniwangi alias Sunan Rumenggong,
dari hal tersebut maka tokoh yang tertulis pada Kitab Al Fatawi yang bernama Prabu
Bumiwangi adalah orang yang sama dengan Sunan Rumenggong alias Prabu
Buniwangi alias Prabu Bumiwangi yang lahir pada tahun 1380 M.
16Surat Wasiat Sukapura disusun oleh Raden Indrayuda. 17Sanad riwayat dari Raden Ahmad Dimyati tahun 2020 yang diterima dari Raden
Eeng Hendriyana dari kakek beliau Raden Suharma dari Raden Sastrakusumah dari Raden
Indrayuda di Kampung Sukapura Desa Sukaraja Tasikmalaya. 18Ringkasan Babon Sukapura disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya. 19Silsilah Pangeran Kornel yang dikeluarkan oleh Yayasan Pangeran Sumedang. 20Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani Sunarya,
dan Raden Abdul Syukur, hal 17.
47
b. Prabu Layakusumah dan Gelar Siliwangi
Dalam Catatan Silsilah Ningrat Limbangan tertulis21 sebagai berikut:
1. Prabu Siliwangi Pajajaran mempunyai putra bernama Prabu Layakusumah
yang berputra Prabu Limansenjaya yang berputra Sunan Cipancar.
2. Sunan Rumenggong Buniwangi atau Prabu Jayakusumah berputra Sunan
Cisorok berputra Sunan Salalangu Salamara berputra Sunan Nusakerta.
3. Prabu Siliwangi kang medal (putra dari) Ratu Permana Dipuntang, berputra
Sunan Dayeuh Manggung berputra Sunan Darmakingkin berputra 3 yaitu:
Sunan Ranggalawe, Sunan Kajeu alias Sunan Rumenggong, dan Sunan
Patinggi.
4. Sunan Nusakerta putra dari Prabu Salalangu putra dari Prabu Mangunjaya
Cisorok putra dari Sunan Rumenggong putra dari Sunan Darmakingkin putra
dari Sunan Dayeuh Manggung putra dari Prabu Siliwangi putra dari Ratu
Permana Dipuntang.
5. Prabu Siliwangi berputra Prabu Layakusumah berputra Prabu Limasenjaya
dan Prabu Wastu Dewa bermukim di Sagaranten.
6. Prabu Siliwangi bermukim di Kuningan.
Selain Catatan Silsilah Ningrat Limbangan dan ada riwayat bersanad secara
turun menurun dari KH. Raden Husni Mubarak bin KH. Raden Atung Aunillah bin
KH. Raden Mubarak bin KH. Raden Ali Abdurahman (Mama Cikelepu Kulon) bin
KH. Raden Aunillah bin KH. Raden Muhammad Asim bin KH. Raden Muhammad
Mufid bin KH. Raden Abdullah bin Raden Dita Manggala bin Raden Jibja Manggala
bin Raden Sutamanggala bin Raden Mayasuta bin Raden Abdullah bin Dalem
Jayatingkar bin Sunan Bunikasih (Raden Emas Suryamatri) bin Sunan Bunisari bin
Sunan Rumenggong, sanad riwayat yang lain didapat dari KH. Raden Amin Muchidin
tahun 1985, dan Raden Achmad Djubaedi tahun 2013, yaitu: “Prabu Layakusumah
menikah dengan putri angkat Sunan Rumenggong yang bernama Nyai Mas
Buniwangi atau Nyai Ambetkasih, adapun Nyai Mas Buniwangi adalah putri adik
Sunan Rumenggong yaitu Sunan Patinggi.”22
Jika mengikuti alur riwayat turun menurun yang mana Prabu Layakusumah
menikah dengan putri Sunan Patinggi, hal tersebut akan menjadi sangat rancu dan
tertolak jika Prabu Layakusumah dinisbatkan sebagai putra dari Prabu Siliwangi putra
dari Ratu Ibu Permana Dipuntang, sehubungan akan terjadi pernikahan sedarah juga
pernikahan antar 2 generasi yang jauh berbeda. Dengan demikian jelas nama
“Siliwangi” bukan hanya ditunjukkan kepada 1 orang saja melainkan kepada beberapa
orang secara berurutan sebagai “gelar dari Raja-raja Pajajaran.”
Mengacu kepada Babon Sukapura bahwa tertulis Batara Mandala yang telah
disesuaikan dengan Catatan Silsilah Ningrat Limbangan dan Museum Sumedang
21Catatan Silsilah Ningrat Limbangan disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah, hal
1-22. 22Sanad riwayat dari KH. Raden Husni Mubarak tahun 2019 di Kediaman beliau,
sanad riwayat dari KH. Raden Amin Muchidin tahun 1985 di Kediaman beliau, dan Raden
Achmad Djubaedi tahun 2013 di Kediaman Raden Haji Holil Aksan Umar Zen.
48
adalah orang yang sama dengan Sunan Rumenggong, mempunyai putra bernama
Raden Jati Sunda yang menikah dengan Nyai Mas Wajankasih, nama Wajankasih
merujuk kepada orang yang sama dengan Nyai Mas Ambetkasih putri Sunan Patinggi,
Dengan demikian, Raden Jati Sunda tertujukan sebagai orang yang sama dengan
Prabu Layakusumah. Hal tersebut sesuai dengan sanad riwayat yang mahsyur di
Catatan Keluarga KH. Raden Ahmad Royani (Mama Gempol Nagreg) dan Pesantren
Cimasuk bahwa “Prabu Layakusumah adalah putra dari Sunan Rumenggong.”23
Dari uraian tersebut bahwa nama “Siliwangi” lebih menunjukkan gelar
Kerajaan yang tidak ditujukkan hanya untuk 1 orang saja. Misalkan, gelar
Hemengkubuwono pada urutan Raja-raja Yogyakarta, lalu Kusumadinata pada urutan
Raja dan Adipati Sumedang. Di lain pihak gelar Mundingsari atau Munding Surya
Agung pun adalah hal serupa sebagaimana gelar Siliwangi, sehubungan terdapat nama
tersebut pada generasi di bawah Mundingsari I alias Sri Komara misalnya pada
Catatan Silsilah Dalem Cikundul Cianjur terdapat nama Mundingsari I dan II juga
Mundingsari Leutik, Catatan KH. Raden Muhammad Zen tertulis Raden Mundingsari
berputra Prabu Rangga Mantri berputra Prabu Haur Kuning, Catatan Silsilah Dalem
Cikundul bahwa Mundingsari Leutik anak dari Mundingsari dan Mundingsari
keturunan dari Prabu Siliwangi, dari hal tersebut tersusun gelar Siliwangi dan
Mundingsari sebagai berikut:
1. Ratu Ibu Permana Dipuntang, berputra
2. Ratu Komara/Prabu Mundingsari I/Munding Surya Agung I/Prabu
Banjaransari/Prabu Siliwangi I menikah dengan Ratu Kidang Kancana binti
Prabu Ciung Wanara, berputra
3. Prabu Aji Putih/Dewa Haji Guru Putih/ Prabu Mundingsari II/Munding
Jayakawati/Sunan Dayeuh Manggung/Prabu Siliwangi II, berputra
4. Prabu Taji Malela/Prabu Tutang Buana/Prabu Mundingsari III/Resi
Cakrabuana/Sunan Darmakingkin/Prabu Siliwangi III, berputra
5. Prabu Lembu Agung/Sunan Rumenggong/Bumiwangi/Batara
Mandala/Mundingsari IV/Prabu Cakrawati/Prabu Siliwangi IV/Prabu
Jayakusumah I, berputra
6. Prabu Layakusumah/Raden Jati Sunda/Batara Karang/Bujangga
Malela/Niskala Wastu Kencana/Mundingsari V/Prabu Siliwangi V, berputra
7. Prabu Wastu Dewa/Dewa Niskala/Prabu Siliwangi VI/Mundingsari VI,
berputra
8. Sri Baduga Maharaja/Prabu Siliwangi VII/Mundingsari VII (wafat tahun
1521 M), berputra
9. Prabu Purbawisesa/Prabu Surawisesa/Mundingsari VIII/Prabu Siliwangi VIII
(wafat tahun 1535 M)
Prabu Layakusumah penerus dari Dinasti Siliwangi IV, mengacu kepada
Kitab Al Fatawi yang mana Prabu Bumiwangi berputra Niskala Wastu Kancana
berputra Dewa Niskala, sementara dalam Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang
23Catatan Keluarga KH. Raden Ahmad Royani ditulis tahun 1970.
49
tertulis bahwa Prabu Layakusumah berputra Prabu Wastu Dewa.24 Dengan demikian,
tertujukan bahwa Prabu Wastu Dewa alias Dewa Niskala sementara Prabu
Layakusumah tertujukan sebagai orang yang sama dengan Prabu Niskala Wastu
Kancana alias Raden Jati Sunda.
Dalam Catatan Silsilah Keluarga Pangeran Raden Heru R Arya Natareja bin
Pangeran Yunus Sanusi tertulis bahwa Prabu Siliwangi berputra Cakrabuana berputra
Pangeran Wastu Dewa. Sementara dalam Catatan Ningrat Limbangan bahwa Prabu
Layakusumah mempunyai putra Raden Wastu Dewa dan Raden Liman Senjaya.
Dengan demikian Cakrabuana terujukkan sebagai orang yang sama dengan Prabu
Layakusumah.
c. Pangeran Cakrabuana
Pada Kitab Al Fatawi tersusun silsilah yang terkait dengan nama Cakrabuana,
yaitu:
1. Prabu Siliwangi/Cakraningrat
2. Prabu Cakrabuana bersaudara dengan Pangeran Walangsungsang. Prabu
Cakrabuana mempunyai putra yaitu: Pangeran Sang Hyang dan Syarifah
Mudaim yang menikah dengan Syarif Abdullah Mesir.
Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa Batara Mandala alias Sunan
Rumenggong alias Prabu Siliwangi IV mempunyai putra bernama Sunan Lingga
Hyang. Dengan demikian yang dimaksud dengan Prabu Cakrabuana pada Kitab Al
Fatawi adalah Batara Mandala alias Sunan Rumenggong alias Prabu Siliwangi IV.
Maka dari itu nama Cakrabuana adalah nama gelar yang dimulai dari Prabu Taji
Malela dan pada buku Museum Sumedang bernama Resi Cakrabuana, maka tersusun
silsilah, yaitu:
1. Prabu Siliwangi III/Prabu Cakrabuana I/Resi Cakrabuana/Prabu Taji Malela,
berputra
2. Prabu Siliwangi IV/Prabu Cakrabuana II/Batara Mandala/Sunan
Rumenggong/Cakraningrat, berputra
3. Prabu Siliwangi V/Prabu Cakrabuana III/Prabu Layakusumah/Raden Jati
Sunda, bersaudara dengan Pangeran Sang Hyang/Sunan Lingga Hyang dan
Syarifah Mudaim
Taji Malela/Cakrabuana I/Siliwangi III/Resi Cakrabuana
Cakrabuana II/Siliwangi IV/Sunan Rumenggong Walasungsang
Lingga Hyang Cakrabuana III/Siliwangi V Syarifah Mudaim
24Catatan Silsilah Ningrat Limbangan disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah, hal
22.
50
Dalam Kitab Al Fatawi tertulis bahwa Prabu Walangsungsang adalah paman
dari Prabu Cakrabuana. Dalam hal ini lebih merujukkan pada Kitab Al Fatawi yaitu
Pangeran Walangsunsang adalah paman dari Prabu Cakrabuana III.
Dan sebagaimana diketahui bahwa Raden Jati Sunda memiliki saudara
bernama Sunan Lingga Hyang, sesuai dengan uraian di atas bahwa Pangeran
Cakrabuana alias Cakrabuana III memiliki saudara bernama Pangeran Sang Hyang
dan Syarifah Mudaim. Dengan demikian, Pangeran Cakrabuana alias Cakrabuana III
adalah orang yang sama dengan Raden Jati Sunda alias Prabu Layakusumah. Menurut
Catatan Keluarga Dalem Cikundul bahwa nama Pangeran Cakrabuana saudara dari
Syarifah Mudaim dan nama asli beliau adalah Syekh Abdullah Iman Lumajang
Qudrat.25 Selain itu sanad riwayat dari Raden Achmad Djubaedi bahwa Pangeran
Cakrabuana adalah Syekh Abdullah Iman.26
Nama lain dari Pangeran Cakrabuana alias Ki Cakrabumi adalah Haji
Abdullah Iman.27 Dengan adanya gelar Haji menunjukkan bahwa beliau pernah
bermukim di Mekkah. Sementara telah diuraikan bahwa Pangeran Cakrabuana alias
Raden Jati Sunda pernah bermukim di Mekkah, sedangkan yang pernah bermukim di
Mekkah menurut Babon Sukapura adalah Bujangga Malela alias Bujangga Larang
alias Batara Karang. Berarti, Pangeran Cakrabuana alias Raden Jati Sunda adalah
orang yang sama dengan Bujangga Malela, Bujangga Larang, dan Batara Karang.
d. Kerajaan Sumedang Penerus Pajajaran
Dalam Catatan Silsilah Museum Sumedang yang berjudul Mengenal Museum
Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata Lainnya serta Riwayat Leluhur Sumedang, tertulis:
Nyai Mas Ratu Inten Dewata menikah dengan seorang Pangeran Ulama Islam dari
Cirebon, Pengeran Kusumadinata putra Pangeran Pamalekaran (Dipati Teterung),
putra Arya Damar Sultan Palembang keturunan Majapahit. Sedangkan dari pihak ibu,
Ratu Martasari alias Nyi Mas Rangga Wulung keturunan Sunan Gunung Jati alias
Syarif Hidayatullah.28
Pangeran Kusumadinata pada Catatan Silsilah Museum Sumedang disebut
juga dengan Pangeran Santri. Dengan demikian Pangeran Santri adalah putra dari
Dipati Teterung, putra dari Arya Damar Palembang. Prabu Geusan Ulun memerintah
25Catatan Keluarga Dalem Cikundul dilihat oleh Raden Haji Ahmad Dimyati tahun
1983 dan catatan tersebut milik Kyai Raden Abdul Karim bin KH. Raden Toha Badruddin di
Pesantren Al Badar Ciluluk, Cikancung, Bandung. 26Sanad riwayat dari Raden Achmad Djubaedi tahun 2013 di Kediaman Raden Haji
Holil Aksan Umar Zen. 27Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 153. Pada gelar
Cakrabumi atau Cakrabuana, sebagai penyesuaian dan Sundanisasi dari Inni jailun fil ardhi
khalifah-Aku ciptakan manusia di bumi sebagai khalifah (QS 2:30). Dari nama Cakra tersebut
sebagai penerjemahan Khalifah. Sedangkan bumi tetap dengan bumi atau digantikan buana.
28Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata Lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani, dan
Raden Abdul Syukur, hal 19.
51
pada tahun 1578-1601 M dan Kerajaan Sumedang Larang pada hakikatnya sebagai
penerus dari Kerajaan Pajajaran yang hancur pada 8 Mei 1579 M.29
Pada Ringkasan Babon Sukapura tertulis bahwa susunan Prabu Geusan Ulun
sebagai berikut:
1. Arya Damar Sultan Palembang, berputra
2. Pangeran Pamakelaran, berputra
3. Pangeran Santri, berputra
4. Prabu Geusan Ulun
Sementara pada bagian lain Babon Sukapura tertulis silsilah dari Prabu Geusan Ulun,
yaitu:
1. Prabu Picuk Umum, berputra
2. Prabu Janton Dewata, berputra
3. Prabu Rangga Gading, berputra
4. Rangga Pupuk, berputra
5. Prabu Geusan Ulun
Jika dihubungkan dengan Babon Sukapura maka akan teridentifikasi nama-
nama, yaitu:
1. Prabu Picuk Umum/Pucuk Umum/Sunan Rumenggong/Batara Mandala,
berputra
2. Prabu Janton Dewata/Arya Damar/Bujangga Manik/Sultan Palembang,
berputra
3. Prabu Rangga Gading/Dipati Teterung/Pangeran Pamalekaran (menantu
Sunan Gunung Jati Cirebon), berputra
4. Rangga Pupuk/Pangeran Santri Kusumadinata, berputra
5. Prabu Geusan Ulun
Adapun dari pihak ibu dari Prabu Geusan Ulun yaitu Ratu Intan Dewata
merupakan keturunan langsung Prabu Siliwangi, dalam Babon Sukapura tertulis
bahwa beliau adalah adik dari Prabu Siliwangi. Yang dimaksud Prabu Siliwangi
adalah Prabu Siliwangi VII. Dalam hal ini silsilah Ratu Intan Dewata hanya merujuk
kepada Babon Sukapura, beliau adalah putri dari Sri Baduga Maharaja alias Prabu
Siliwangi VII.
29Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata Lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani, dan
Raden Abdul Syukur, hal 20-21.
52
Sunan Rumenggong/Pucuk Umum/Siliwangi IV
Bujangga Manik Niskala Wastu Kancana Sunan Lingga Hyang
(Arya Damar) (Siliwangi V) (Sunan Cisorok)
Dipati Teterung Dewa Niskala/Siliwangi VI Munding Jayakawati II
Sri Baduga Maharaja/Siliwangi VII/Wastu Dewa
Pangeran Santri X Intan Dewata Sekarmandapa Surawisesa/Siliwangi VIII
Prabu Geusan Ulun Jayamanggala
C. Silsilah Raden Fatah Sultan Demak
1. Hubungan Raden Fatah dengan Arya Damar
Pada Kitab Al Fatawi ditulis bahwa Arya Damar adalah paman dari Raden
Fatah. Tulisan tersebut menjadi koreksi terhadap Babad Tanah Jawi yang menuliskan
bahwa Raden Fatah saudara Arya Damar. Istri Brawijaya V saat mengandung Raden
Fatah, dihadiahkan kepada putra sulungnya yaitu Arya Damar, yang menjadi Raja
Palembang. Cerita tersebut juga dituliskan di Serat Kandaning Ringgit Purwa.30
Arya Damar orang yang sama dengan Bujangga Manik. Bujangga Manik alias
Arya Damar terujukan dari Catatan Museum Sumedang yang mana Prabu Geusan
Ulun memiliki pertalian darah dengan raja-raja Pajajaran.31 Dari hal tersebut maka
jelas Arya Damar alias Bujangga Manik adalah putra Prabu Siliwangi IV alias Sunan
Rumenggong. Dengan demikian, Raden Fatah adalah putra dari Cakrabuana III alias
Raden Jati Sunda alias Prabu Layakusumah alias Prabu Siliwangi V. Jadi, tokoh
Brawijaya V yang sering ditulis sebagai ayah dari Raden Fatah adalah orang yang
sama dengan Prabu Siliwangi V.
30Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320. 31Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani Sunarya,
dan Raden Abdul Syukur, hal 21.
53
2. Ayah Raden Fatah adalah Ksatria
Menurut tulisan Tome Pires bahwa ayah Pate Rodim alias Raden Fatah adalah
seorang kesatria dan bijak dalam mengambil keputusan.32 Raden Fatah adalah
keponakan Bujangga Manik alias Arya Damar Palembang. Ada 2 dugaan bahwa
Raden Fatah adalah: 1) anak dari Pangeran Cakrabuana alias Cakrabuana III, 2) anak
dari Sunan Lingga Hyang alias Pangeran Sang Hyang. Akan tetapi Raden Fatah
menurut beberapa naskah adalah anak dari seorang Raja. Sementara pengganti raja
setelah Sunan Rumenggong adalah Pangeran Cakrabuana alias Cakrabuana III.
Dengan demikian, Raden Fatah lebih sesuai sebagai putra dari Pangeran Cakrabuana
alias Cakrabuana III alias Prabu Siliwangi V alias Prabu Layakusumah alias Raden
Jati Sunda alias Batara Karang alias Syekh Abdullah Iman.
3. Penguasa Japura adalah Sepupu Raden Fatah
Menurut Catatan Silsilah Ningrat Sumedang bahwa Prabu Susuk Tunggal
adalah adik dari Ki Gedeng Sindangkasih.33 Sedangkan pada Catatan Silsilah Ningrat
Limbangan bahwa nama lain dari Sunan Rumenggong adalah Ki Gedeng
Sindangkasih.34 Maka, ayah Prabu Susuk Tunggal sama dengan ayah Sunan
Rumenggong yaitu anak dari Prabu Taji Malela. Lalu, mengacu pada Catatan Silsilah
Ningrat Limbangan menuliskan Prabu Susuk Tunggal adalah anak dari Prabu Lingga
Wastu.35 Dengan demikian Prabu Lingga Wastu adalah orang yang sama dengan
Prabu Taji Malela. Pada Catatan Silsilah Ningrat Sumedang bahwa Prabu Susuk
Tunggal memiliki anak bernama Amuk Murugul dan Amuk Murugul memiliki anak
Ki Ageng Japura.36 Sudah dijelaskan diatas bahwa Raden Fatah adalah anak dari
Pangeran Cakrabuna alias Cakrabuana III. Jadi, Ki Ageng Japura sebagai Penguasa
Japura adalah sepupu dari Raden Fatah. Dalam tulisan Tome Pires bahwa pate yang
berkuasa atas tempat Negeri Japura merupakan seorang ksatria, ia adalah sepupu
tertua dari Pate Rodim alias Raden Fatah.37
Menurut Tome Pires batas kekuasaan Sunda dibatasi oleh Sungai Cimanuk,38
tetapi kenyataannya dengan adanya kekerabatan antara Raden Fatah dan Ki Ageng
Japura maka kekuasaan Sunda meliputi Jawa bagian tengah dan sebagian timur.
32Tome Pires, Suma Oriental, hal 257. 33Catatan Silsilah Ningrat Sumedang yang ditulis oleh Kyai Raden Unang Abdul
Karim tahun 2013, hal 5. 34Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 35Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang ditulis oleh KH. Atung Aunillah. 36Catatan Silsilah Ningrat Sumedang yang ditulis oleh Kyai Raden Unang Abdul
Karim tahun 2013, hal 5. 37Tome Pires, Suma Oriental, hal 256. 38Tome Pires, Suma Oriental, hal 233.
54
Prabu Siliwangi
Prabu Guru Haji Putih
Prabu Taji Malela/Lingga Wastu
Sunan Rumenggong Prabu Susuk Tunggal
Prabu Cakrabuana 3 Ki Amuk Marugul
Raden Fatah Ki Ageng Japura
4. Gelar Brawijaya dan Susunan Silsilah Raden Fatah
Seperti yang diuraikan bahwa sosok Brawijaya disematkan kepada Raja-raja
Majapahit yang Hindu Buddha maka akan menimbulkan berbagai polemik yang
diantaranya dalam hal penempatan gelar Brawijaya. Berdasarkan catatan-catatan yang
tersebar sekarang ini, Raden Fatah adalah putra dari Brawijaya V. Prabu Brawijaya
disebut Brawijaya V sebagai Raja Majapahit versi naskah babad dan serat. Tokoh ini
diperkirakan sebagai tokoh yang sama dengan Bhre Kertabumi yaitu nama yang
ditemukan dalam penutupan naskah Pararaton.39 Pemberitaan Serat Pararaton tentang
raja-raja Majapahit akhir ini ternyata sangat berbelit-belit.40 Namun pendapat lain
mengatakan bahwa Brawijaya cenderung identik dengan Dyah Ranawijaya. Bre
Kertabhumi memerintah dari 1468-1478 M, sedangkan Dyah Ranawijaya
(Girindrawardhana) tahun 1474-1519 M.41 Babad Tanah Jawi menyebut nama asli
Brawijaya adalah Raden Alit. Ia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama
Prabu Bratanjung, kemudian memerintah waktu yang sangat lama, yaitu sejak putra
sulungnya yang bernama Arya Damar belum lahir, sampai akhirnya turun tahta karena
dikalahkan oleh Dyah Ranawijaya.
Serat Kanda menyebut nama asli Brawijaya adalah Angkawijaya, putra Prabu
Mertawijaya dan Ratu Kencanawungu. Mertawijaya adalah nama gelar Darmawulan
yang menjadi Raja Majapahit setelah mengalahkan Menak Jingga bupati
39Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram, hal 44. 40Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 93. 41Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal
166.
55
Blambangan. Sementara itu pendiri Kerajaan Majapahit versi babad dan serat
bernama Jaka Sesuruh, bukan Raden Wijaya. Menurut serat pranitiradya, yang
bernama Brawijaya bukan hanya raja terakhir saja, tetapi juga beberapa raja
sebelumnya. Serat ini menyebut urutan raja-raja Majapahit ialah: 1) Jaka Sesuruh, 2)
Prabu Brakumara, 3) Prabu Brawijaya I, 4) Ratu Ayu Kencawungu, 5) Prabu
Brawijaya II, 6) Prabu Brawijaya III, 7) Prabu Brawijaya IV, dan 8) Prabu Brawijaya
V. Meskipun sangat populer, nama Brawijaya ternyata tidak pernah dijumpai dalam
naskah Pararaton dan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Oleh karena
itu, perlu ditelusuri dari mana para pengarang naskah babad dan serat memperoleh
nama Brawijaya tersebut.42 Berarti, terdapat perbedaan yaitu Brawijaya versi serat dan
babad memerintah dalam waktu yang sangat lama sedangkan pemerintahan Bre
Kertabumi relatif singkat 1468-1478 M.
Sementara di naskah Purwaka Caruban Nagari menulis bahwa salah satu istri
dari Pangeran Cakrabuana adalah Nyai Retna Rasajati putri Maulana Ibrahim
Asmaraqandi. Berarti Pangeran Cakrabuana menikah dengan saudara perempuan
Sunan Ampel. Secara hitungan tahun dan kurun Cakrabuana yang dimaksud adalah
Cakrabuana I.
Berdasarkan sumber-sumber sejarah Majapahit akhir yang berupa prasasti-
prasasti diantaranya Prasasti Surodakan, Prasasti Trawulan III, Prasasti
Sendangsedati, Prasasti-prasasti Girindrawardhana (Prasasti Ptak, Prasasti
Trailokyapuri I, II, III, dan IV), dan Prasasti Pabanolan43 bahwa tidak ada raja-raja
Majapahit yang bergelar Brawijaya. Adapun gelar Brawijaya hanya muncul di Babad
Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Serat Darmagandul yang mana didalamnya banyak
keterangan mengenai tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian dari zaman kuna yang tidak
dapat diterima.44 Dari Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda memang mendapatkan
uraian genealogi raja-raja di Jawa. Akan tetapi, tidak dapat memakai genealogi
tersebut untuk menyusun genealogi raja-raja Majapahit seperti yang diharapkan. Hal
ini disebabkan sumber-sumber tersebut telah mencampuradukkan genealogi historis
dengan genealogi yang didasarkan pada mitos bahkan telah mencampuradukkan
genealogi dari panteon Hindu dengan genealogi yang berdasarkan Islam.45
Sumber-sumber tradisi seperti Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan
Darmagandul, raja terakhir di dalam sumber-sumber tradisi tersebut dikenal dengan
nama Prabu Brawijaya. Dan juga sumber-sumber tradisi tersebut tergolong ke dalam
jenis Kesastraan Babad yang jarang sekali merupakan sumber yang dapat dipercaya
sepenuhnya, tidak mustahil sumber-sumber tersebut masih menyimpan kesan-kesan
peristiwa sejarah dari masa dulu, meski sudah kabur dan kacau dikemukakan di
dalamnya.46
42Suparman, Babad Kesultanan Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram, hal 44. 43Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 9-
10. 44Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 22. 45Hasan Jafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 104. 46Hasan Jafar, Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya, hal 132.
56
Pada Catatan Silsilah Ningrat Limbangan tersusun Silsilah Ratu Kidang
Kancana,47 yaitu:
1. Ciung Wanara, berputri
2. Kidang Kancana, berputra
3. Lingga ....., berputra
4. Lingga Wesi, berputra
5. Prabu Lingga Wastu, berputra
6. Susuk Tunggal
Pada Babon Sukapura tertulis Silsilah Purbasari,48 yaitu:
1. Ciung Wanara, berputri
2. Purbasari, berputra
3. Prabu Lingga Hyang, berputra
4. Prabu Lingga Wesi, berputra
5. Lingga Wastu, berputra
6. Susuk Tunggal
Jika disusun garis silsilah dari bawah ke atas antara Catatan Silsilah Ningrat
Limbangan dan Babon Sukapura, yaitu:
1. Ciung Wanara, berputri
2. Ratu Kidang Kancana/Purbasari, berputra
3. Lingga Hyang, berputra
4. Lingga Wesi, berputra
5. Lingga Wastu, berputra
6. Susuk Tunggal
Di Silsilah Pajajaran terdapat Silsilah Kidang Kancana alias Purbasari yang
terujukkan dengan orang yang sama yaitu Ratu Ayu Kancana Wungu pada serat
pranitiradya. Pada Babon Sukapura yang disusun Raden Eeng Hendriyana terdapat
catatan Ki Gedeng Misri memiliki istri bernama Purbasari dan memiliki anak bernama
Lingga Hyang alias Lingga Buana. Namun Babon Sukapura terkoreksi dengan
Catatan Museum Sumedang bahwa tertulis Prabu Taji Malela alias Prabu Tutang
Buana49 dan merujuk pada orang yang sama dengan Lingga Buana. Prabu Tutang
Buana memiliki ayah bernama Prabu Guru Dewa Haji Putih. Dengan demikian, Prabu
Guru Dewa Haji Putih adalah orang sama dengan Lingga Hyang. Berarti mengacu
kepada Babon Sukapura50 bahwa Ki Gedeng Misri adalah Ratu Komara, ayah dari
Prabu Guru Dewa Haji Putih. Jika disusun, sebagai berikut:
47Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang disusun oleh KH. Atung Aunillah. 48Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura
Tasikmalaya yang dipelopori oleh Raden Eeng Hendriyana. 49Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani Sunarya,
dan Raden Abdul Syukur, hal 16. 50Sejarah Babon Kedaleman Sukapura dikeluarkan oleh Sukapura Ngadaunngora, hal
1.
57
1. Ki Gedeng Misri/Sri Komara/Ratu Komara menikah Kidang
Kancana/Purbasari, berputra
2. Lingga Hyang/Prabu Guru Dewa Haji Putih/Lingga Wesi, berputra
3. Lingga Buana/Prabu Tutang Buana/Prabu Taji Malela/Lingga Wastu,
berputra
4. Prabu Susuk Tunggal
Cariyosipun Redi Munggul adalah manuksrip yang dianggap oleh masyarakat
Perdikan Cahyana sebagai hasil karya historiografi tradisional. Teks kademangan
menceritakan asal usul Pangeran Jambu Karang. Tokoh leluhur itu berasal dari
Pajajaran yakni putra Prabu Brawijaya Mahesa Tandreman.51 Menurut Akhmad
Soetjipto dalam tradisi Cariyosipun Redi Munggul bahwa Pangeran Jambu Karang
atau Adipati Mendang (Mundingwangi) adalah putra Raja Pajajaran Prabu Brawijaya
Mahesa Tandreman. Tradisi Sadjarah Padjajaran Baboning Tjarios saking Adipati
Wiradhentaha Boepati Prijangan Manondjaja menyebutkan bahwa Jambu Karang
merupakan Raja Pajajaran yang bergelar Prabu Lingga Karang atau Prabu Jambudipa
Lingga Karang atau Pangeran Wali Syekh Jambukarang atau Haji Purwa.52
Menurut Catatan Silsilah Ningrat Limbangan bahwa Mundingwangi alias
Sunan Cisorok adalah anak Sunan Rumenggong. Berarti Prabu Brawijaya Mahesa
Tandreman adalah orang yang sama dengan Sunan Rumenggong. Menurut Kitab
Tarikhul Auliya bahwa Raden Fatah keturunan dari Raja Pajajaran.53
Oleh sebab itu, gelar Brawijaya lebih tepat dirujukkan kepada raja-raja Sunda.
Namun jika dimasukkan ke susunan raja-raja Majapahit akan menimbulkan polemik
dalam penempatan urutan gelar Brawijaya itu sendiri. Dengan demikian nama
Brawijaya adalah gelar Raja Sunda yang dimulai dari:
1. Sri Komara/Brawijaya I, berputra
2. Prabu Guru Dewa Haji Putih/Brawijaya II, berputra
3. Prabu Tajimalela/Brawijaya III, berputra
4. Sunan Rumenggong/Brawijaya IV, berputra
5. Prabu Cakrabuana III/Brawijaya V, berputra
6. Raden Fatah
Ada kekeliruan bahwa Lingga Karang disamakan dengan Mundingwangi,
seharusnya seorang tokoh yang berbeda. Lingga Karang adalah orang yang sama
dengan Batara Karang alias Prabu Layakusumah alias Prabu Cakrabuana III alias
Prabu Siliwangi V. Sedangkan Mundingwangi adalah orang yang sama dengan Sunan
Lingga Hyang alias Sunan Cisorok. Keduanya adalah anak dari Sunan Rumenggong.
51Sugeng Priyadi, “Perdikan Cahyana,” Jurnal Humaniora, Volume XIII, No. 1
Februari 2001 halaman 89-100, hal 92. 52Sugeng Priyadi, Perdikan Cahyana, hal 95. 53Bisri Mustofa, Kitab Tarikhul Auliya Tarikh Walisongo (Kudus: Menara Kudus,
1952), hal 5. Kitab Tarikhul Auliya Tarikh Walisongo adalah kitab yang disusun oleh KH.
Bisri Mustofa diselesaikan 12 Rabiul Awwal 1352 H/19 November 1952 berisi tentang silsilah
para Wali penyebar Islam di jawa dan membahas tentang silsilah Raden Fatah yang merupakan
keturunan Raja Pajajaran.
58
Menurut Kitab Al Fatawi, bahwa ayah Raden Fatah adalah Kertabumi alias
Brawijaya V dan ibunda Raden Fatah bernama Putri Cempa. Menurut Silsilah
Pangeran Kornel bahwa terdapat nama Kertabumi sebagai putra adik dari Sunan
Rumenggong yaitu Sunan Geusan Ulun alias Angkawijaya I.54 Sunan Geusan Ulun
memiliki anak bernama Kertabumi I, sementara dalam Catatan Museum Sumedang
bahwa Sunan Geusan Ulun menurunkan Ningrat Limbangan.55 Padahal di Catatan
Silsilah Ningrat Limbangan sendiri yang menurunkan Ningrat Limbangan adalah
Sunan Rumenggong. Dengan demikian seharusnya Sunan Geusan Ulun alias Sunan
Rumenggong. Berarti Kertabumi adalah anak Sunan Rumenggong. Uraian diatas
diperkuat oleh Catatan Silsilah Ningrat Limbangan bahwa Kertabumi adalah Raja
Galuh atau Raja Mendang.56 Haji Abdullah Iman disebut juga Ki Cakrabumi alias
Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana alias Ki Cakrabumi membangun
Cirebon Larang yang mendapat penghormatan dari Prabu Siliwangi dari Pakuan
Pajajaran.57 Adapun Prabu Siliwangi yang dimaksud merujuk ke Catatan Silsilah
Ningrat Limbangan bahwa bahwa Sunan Rumenggong pernah sebagai Penguasa
Labuan Cirebon yang berkedudukan di Sindangkasih (sekarang Majalengka).58 Maka
yang dimaksud Pangeran Cakrabuana adalah Prabu Cakrabuana III. Sebagaimana
yang telah diuraikan Silsilah Raden Fatah bahwa Cakrabuana III adalah ayah dari
Raden Fatah alias Cakrabumi, dengan demikian Cakrabumi adalah orang yang sama
dengan Kertabumi.
Sedangkan ibunda Raden Fatah adalah Putri Cempa. Letak Cempa terjadi
perbedaan pendapat diantara sejarawan. Berdasarkan Kitab Sejarah Hidup dan
Silsilah Asyaikh Kyai Muhammad Nawawi Tanara bahwa Cempa terletak di
Indonesia.59 Menurut Kyai Raden Eeng Hendriyana bahwa Cempa terletak di
Priyangan.60
Sementara berdasarkan tulisan Tome Pires mengenai Champa bahwa champa
berada di seberang wilayah Kamboja, di sepanjang pesisir daerah pedalaman. Champa
tidak memiliki pelabuhan untuk menampung jung-jung besar. Champa tidak menjalin
54Silsilah Pangeran Kornel yang dikeluarkan oleh Yayasan Pangeran Sumedang. 55Mengenal Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata lainnya serta Riwayat
Leluhur Sumedang yang disusun oleh Raden Anang Suryaman, Raden Yeni Mulyani Sunarya,
dan Raden Abdul Syukur, hal 19. 56Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 57Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 153. Pada gelar
Cakrabumi atau Cakrabuana, sebagai penyesuaian dan Sundanisasi dari Inni jailun fil ardhi
khalifah-Aku ciptakan manusia di bumi sebagai khalifah (QS 2:30). Dari nama Cakra tersebut
sebagai penerjemahan Khalifah. Sedangkan bumi tetap dengan bumi atau digantikan buana. 58Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 59Haji Rofi’uddin Arromli Tanara, Sejarah Hidup dan Silsilah Asyaikh Kyai
Muhammad Nawawi Tanara, dikumpulkan oleh Ketua Yayasan Annawawi Tanara Banten Al
Hajj Muhammad Fakhul Aslamiy, ditulis 6 April 1979 atau 3 Jumadil Akhir 1399 H, hal 12.
60Sanad Riwayat dari Navida Febrina Syafaaty tahun 2021 yang diterima dari Kyai
Raden Eeng Hendriyana dari kakek beliau Raden Suharma dari Raden Sastrakusumah dari
Raden Indrayuda di Kampung Sukapura Desa Sukaraja Tasikmalaya.
59
hubungan dagang yang besar dengan Malaka karena Malaka mendapatkan barang-
barangnya dari Siam. Orang-orang Champa lemah di lautan. Champa membutuhkan
lanchara yang bisa berlayar di perairan dangkal, karena negerinya hanya memiliki
sedikit air. Champa tidak memiliki pelabuhan dan tidak memiliki warga Moor di
kerajaan.61
Dari uraian di atas maka terkait dengan ibunda Raden Fatah yang berasal dari
Cempa. Maka Cempa yang dimaksud secara fakta tertulis lebih tepat dirujukkan
kepada Jeumpa yang terletak di Priyangan, Indonesia. Sedangkan Champa, Kamboja
tidak memiliki pelabuhan maka tidak mungkin para pedagang internasional bisa
masuk ke wilayah tersebut. Selain itu tidak memiliki warga Moor di kerajaan. Dengan
demikian, nama Cempa dan Champa adalah 2 tempat yang berbeda.
5. Kakek Raden Fatah dari Gresik dan Penguasa Cirebon
Raden Fatah adalah keponakan Bujangga Manik alias Arya Damar dari
Palembang. Arya Damar adalah anak dari Sunan Rumenggong, berarti Raden Fatah
adalah cucu Sunan Rumenggong. Tome Pires menuliskan bahwa kakek Raden Fatah
berasal dari Gresik.62 Sementara berdasarkan Catatan Keluarga KH. Raden Ahmad
Royani yang mengambil sanad riwayat dari KH. Raden Ahmad Dimyati/Mama
Cimasuk Sepuh, bahwa Sunan Rumenggong adalah keturunan dari Syekh Jumadil
Kubro.63 Syekh Jumadil Kubro berdasarkan Kitab Syamsu Al Zahiro bahwa beliau
penyebar Islam di Gresik, sebagai leluhur para Walisongo.64
Menurut sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati diterima dari
gurunya KH. Aceng Mu’man Mansyur diterima dari ayahnya KH. Raden Ahmad
Dimyati diterima dari guru-guru beliau diantaranya KH. Raden Muhammad
Adro’i/Mama Bojong Garut, KH Raden Ahmad Satidi/Mama Gentur Cianjur, KH.
Raden Muhammad Syuja’i/Mama Gudang Tasik diterima dari gurunya KH. Ahmad
Sobari Ciwedus bahwa Sunan Rumenggong adalah cucu dari Syekh Jumadil Kubro.65
Perlu diketahui KH. Ahmad Sobari/Mama Ciwedus Kuningan adalah murid utama
dari Syekh Kholil Bangkalan dan beliau ahli nasab.
Tome Pires menuliskan juga bahwa Penguasa Cirebon merupakan kakek dari
Pate Rodim alias Raden Fatah.66 Sedangkan berdasarkan tulisan dari Catatan Silsilah
Ningrat Limbangan bahwa Sunan Rumenggong pernah sebagai Penguasa Labuan
Cirebon yang berkedudukan di Sindangkasih (sekarang Majalengka).67 Menurut
Catatan Silsilah Ningrat Limbangan bahwa Sunan Rumenggong alias Prabu
61Tome Pires, Suma Oriental, hal 156-158.
62Tome Pires, Suma Oriental, hal 257. 63Catatan Keluarga dari KH. Raden Ahmad Royani ditulis tahun 1970. 64Abdurahman bin Muhammad bin Husein Al Mansyur, Kitab Syamsu Al Zahiro fi
Nasabi Ahli Al Baiti min Bani Alawi furu Fathimah Al Zahra wa Amir wa Mu’minin RA Jilid
1, Jeddah: Alam Al Marifah. Kitab berisi tentang nasab Bani Alawi dan membahas nasab
Keluarga Walisongo. 65Sanad riwayat pada tahun 1992 di Kediaman KH. Aceng Mu’man Mansyur. 66Tome Pires, Suma Oriental, hal 255. 67Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim.
60
Wijayakusuma alias Ki Gedeng Sindangkasih beliau mempunyai karisma pada status
Maha Purahita (Raja semua raja-raja penguasa labuan senusantara, nusajawa, dan
jawadwipa. Ki Gedeng Sindangakasih pernah membenahi negara Pakuan secara
bijaksana dan berakhlak. Atas jasa itu Ki Gedeng Sindangkasih, semua raja-raja setuju
mengangkat Ki Gedeng Sindangkasih menjadi Maharaja dengan gelar Sri Baduga
Maharaja Prabu Guru Dewata Purana Ratu Haji Di Pakuan Pajajaran. Prabu
Wijayakusuma mendapat kepercayaan dari raja-raja labuan di Nusantara.68
Letak ibukota Pakuan Pajajaran, menurut Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
tertulis Sunan Rumenggong adalah Raja Kertarahayu atau Raja Pakuan Pajajaran.
Letak Keraton Kertarahayu berada di Galuh Pakuan69 atau Cirebon Girang
(Limbangan sekarang).70 Pada Babon Sukapura tertulis Batara Mandala alias Sunan
Rumenggong sebagai Raja Pajajaran.71 Berdasarkan sanad riwayat dari KH. Raden
Amin Muhyidin Limbangan bahwa Sunan Rumenggong diangkat menjadi raja pada
tahun 1419 M yang berkeraton di Kertarahayu (Limbangan sekarang).72
Tome Pires menuliskan bahwa Cirebon adalah bagian wilayah kekuasaan dari
para penguasa Moor.73 Sedangkan menurut Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
bahwa kekuasaan Sunan Rumenggong meliputi Parahyangan sampai seluruh
Nusantara.74 Dengan demikian, Cirebon yang dimaksud tulisan Tome Pires adalah
Cirebon yang dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran.
Petunjuk lainnya terkait dengan Pakuan Pajajaran, yaitu:
1. Nama Pakuan Pajajaran ialah dengan menghubungkan kata pakwan dengan
paku (sejenis pohon, cycas circilanus) sedangkan pajajaran diartikan tempat
berjajar, sehingga pakuan pajajaran diartikan tempat dengan pohon paku yang
berjajar.75
2. Pada tahun 1690 M, Winkler sempat berkunjung ke tempat bekas
peninggalan Pakuan Pajajaran, ia mengatakan bahwa ibukota yang bernama
Pakuan terletak diantara dua buah sungai yang mengalir sejajar dan sama
besar.76 Maka yang dimaksud dengan pernyataan Winkler adalah ibukota
Kerajaan Sunda yang bernama Pakuan Pajajaran dan 2 sungai yang dimaksud
adalah Sungai Cimanuk yang terletak di Limbangan.
68Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 69Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 70Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati yang diterima dari KH. Raden Umar
Zen tahun 1990 di Pesantren Asyiradz Neglasari Limbangan Garut dan KH. Raden Amin
Muhyidin tahun 2018 di Pesantren Asyaadah Limbangan Garut. 71Sajarah Babon Leluhur Sukapura disusun Raden Sulaiman Anggapraja. 72Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati yang diterima dari KH. Raden Amin
Muhyidin tahun 2018 di kantor PT Noor Abika Tour Travel cabang Limbangan. 73Tome Pires, Suma Oriental, hal 255.
74Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim.
75Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid II, hal 234. 76Sartono Kartodirdjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid II, hal 231.
61
Itulah petunjuk-petunjuk terkait dengan letak Pakuan Pajajaran. Maka dari
itu, dapat memprediksi bahwa terletak di antara dua sungai maka jelas yang dimaksud
dua sungai tersebut adalah Limbangan. Dua sungai tersebut adalah Sungai Cimanuk
yeng membelah menjadi dua bagian, yaitu yang membelah kota Sumedang sampai ke
Cirebon, yang membelah kota Garut sampai ke Brebes, dan ditengah sungai tersebut
adalah Limbangan.
6. Silsilah Sunan Rumenggong versi Kedua, Kakek Raden Fatah
Versi yang kedua bahwa Cakrawati (Ratu Pajajaran) adalah perempuan dan
Maharaja Kastori adalah laki-laki. Maka dari itu, hubungan Sunan Rumenggong dan
Prabu Taji Malela adalah mertua dan menantu. Menurut sanad riwayat dari Raden
Haji Ahmad Dimyati diterima pada tahun 1992 dari gurunya KH. Aceng Mu’man
Mansyur diterima dari ayahnya KH. Raden Ahmad Dimyati diterima dari guru-guru
beliau diantaranya KH. Raden Muhammad Adro’i/Mama Bojong Garut, KH Raden
Ahmad Satidi/Mama Gentur Cianjur, KH. Raden Muhammad Syuja’i/Mama Gudang
Tasik diterima dari gurunya KH. Ahmad Sobari Ciwedus bahwa Maulana Malik
Ibrahim mempunyai 2 putra yaitu Sunan Ampel dan Sunan Santri alias Sunan
Rumenggong. Yang ditugaskan menyebarkan Islam, yaitu Sunan Ampel diutus ke
Jawa dan Sunan Rumenggong diutus ke Sunda Jawa Barat.77 Dan mengacu kepada
Catatan Keluarga KH. Ahmad Royani dari sumber KH. Raden Ahmad Dimyati/Mama
Cimasuk Sepuh bahwa Sunan Rumenggong pernah berkuasa di Cirebon.78
Dalam tulisan De Graaf dan Pigeaud bahwa terdapat cerita tradisional Jawa
yang mengisahkan Cempa berhubungan dengan orang suci yang telah menyebarkan
agama Islam di Surabaya dan Gresik. Orang Arab yang identitasnya ternyata belum
jelas, konon mendapat dua putra dari istrinya, Putri Cempa. Yang tua namanya Raja
Pandita (dalam Hikayat Hasanuddin) atau Raden Santri (dalam Babad Meinsma) dan
yang muda bernama Pangeran Ngampel Denta atau Raden Rahmat. Dari cerita-cerita
Jawa itu dapat disimpulkan bahwa Gresik dan Surabaya dianggap sebagai pusat-pusat
tertua agama Islam di Jawa Timur. Tradisi tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa
di Gresik terdapat banyak makam Islam yang tua sekali. Pertama terdapat makam
Fatimah binti Maimun wafat pada tanggal 7 Rajab 475 H (1082) dan kedua makam
Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tanggal 12 Rabiulawwal 822 H (1419).
Berdasarkan tuanya makam, Gresik lebih tua dari Surabaya sebagai pusat agama
Islam.79
Catatan yang disimpan di Keluarga Pesantren Al Faruq Cicalengka Bandung
mengenai nama Sunan Rumenggong alias Prabu Layaranwangi alias Jayakusumah
77Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati diterima pada tahun 1992 dari
gurunya KH. Aceng Mu’man Mansyur diterima dari ayahnya KH. Raden Ahmad Dimyati
diterima dari guru-guru beliau diantaranya KH. Raden Muhammad Adro’i/Mama Bojong
Garut, KH Raden Ahmad Satidi/Mama Gentur Cianjur, KH. Raden Muhammad Syuja’i/Mama
Gudang Tasik diterima dari gurunya KH. Ahmad Sobari Ciwedus di Kediaman KH Aceng
Mu’man Mansyur. 78Catatan Keluarga KH. Ahmad Royani ditulis tahun 1970.
79H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 21-23.
62
alias Syekh Muhammad. Dalam catatan di atas Syekh Muhammad alias Sunan
Rumenggong mempunyai putra bernama Sunan Bunisari.80 Sanad riwayat dari Raden
Haji Tiar Saiful Barri dari KH Raden Usman Muhyiddin dari KH Muhammad Iyad
Pesantren Bunisari Tasikmalaya tahun 2017 bahwa nama lain dari Sunan
Rumenggong adalah Sayyid Muhammad Yusuf.81 Sunan Gresik memiliki 11 orang
anak dari 4 orang istri, dan salah satu anak tersebut bernama Syekh Yusuf Al
Maghribi.82 Arti dari marga Al Maghribi adalah masih keturunan dari Sayyidina
Hasan83 dari pihak ibu.
Maka jika tulisan De Graaf dan Pigeaud disesuaikan dengan sanad riwayat
dari KH. Raden Ahmad Dimyati/Mama Cimasuk bahwa orang arab yang dimaksud
adalah Maulana Malik Ibrahim. Raden Santri yang dimaksud adalah Sunan
Rumenggong alias Sayyid Muhammad Yusuf.
Dengan demikian maka susunan Silsilah Sunan Rumenggong versi kedua
sebagai berikut:
1. Syekh Ahmad Jalaludin, berputra
2. Syekh Jamaludin Al Akbar/Syekh Jumadil Kubro, berputra
3. Barakat Zainal Alam, berputra
4. Maulana Malik Ibrahim, berputra
5. Sunan Rumenggong, berputra
6. Prabu Cakrabuana III, berputra
7. Raden Fatah
7. Pengertian Gelar Sunan versi Ulama dan Bukti Raja-Raja Pajajaran adalah
Islam
Adapun nama-nama yang didahului dengan sebutan Sunan, semuanya adalah
nama-nama julukan atau gelar Sunan yang berasal dari kata Susuhunan bermakna
Yang Mulia. Demikian Maulana yang bernama Pemimpin kita. Semua nama julukan
atau nama gelar tersebut diberikan oleh masyarakat Muslimin di Jawa pada masa
dahulu, karena ketika itu mereka belum mengenal sebutan Sayyid, Syarif, dan Habib
yang lazim digunakan menyebut nama-nama keturunan Ahli Bait Rasulullah. Pada
bagian yang lain dari buku tersebut yang dikutip oleh Sayyid Alwi Al Haddad,
dikatakan beberapa orang Arab asli yang menonjol peranannya, mempunyai pengaruh
lebih kuat dari pada pengaruh tokoh-tokoh Hindu. Mereka dikenal oleh penduduk
Jawa dengan gelar-gelar Wali, Kiai Ageng atau Sunan.84
Menurut Kitab Al Fatawi bahwa susuhunan yang diurus harta benda dan
kedudukannya sebagai Umaro. Sunan adalah Ulama Islam yang punya pangkat
80Catatan yang disimpan di Keluarga Pesantren Al Faruq Cicalengka Bandung. 81Sanad riwayat dari Raden Haji Tiar Saiful Barri dari KH Raden Usman Muhyiddin
dari KH Muhammad Ahyar Pesantren Bunisari Tasikmalaya tahun 2017 di Pondok Pesantren
Pinggirwangi Cicalengka Bandung. 82Rizem Aizid, Sejarah Islam Nusantara (Yogyakarta: Diva Press, 2016), hal 149. 83Ahmad bin Muhammad bin Umar bin Syihabuddin Al Alawi, Bayan Natijah Al
Ahshai Alladzi Qaama Bihi Maktab Ad Daimi (Jakarta: Sayyid usman Batavia Timur, 1358
H), hal 22. 84HMH Al Hamid Al Husaini, Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah, hal 710.
63
Waliyullah. Sebab itulah Sultan Raden Fattah diangkat oleh Sunan menurut sunnah
Rosulullah Muhammad SAW. Demikianlah percakapan Raden Fatah dengan
Maulanna Hasanuddin.
Sedangkan menurut Kitab Taj Al Ars bahwa kata Sunan dengan didhomahkan
huruf sin dan difatahkan huruf nun yang pertama bermana Hakim Muslim dan kata
Raden bermakna Al Amir. Maka telah selesai kalam Habib Assegaf dan kata Kanjeng
bermakna Sayyidi dan kata Kyai bermakna Asy Syekh.85
Bukti dari Catatan Silsilah Ningrat Limbangan terkait Sunan yaitu:
1. Ratu Ibu Permana Dipuntang, berputra
2. Prabu Siliwangi, berputra
3. Sunan Dayeuh Manggung, berputra
4. Sunan Darmakingkin, berputra
5. Sunan Rumenggong/Buniwangi/Jayakusumah, berputra
6. Sunan Cisorok, berputra
7. Sunan Salalangu, berputra
8. Sunan Nusakerta
8. Pengertian Gelar Raden versi Ulama
Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Abdul Haq bahwa
gelar Raden berarti Ruhuddin bermakna Ruhnya Agama.86 Selain itu, sanad riwayat
dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Huban Zen bahwa gelar Raden berarti
Rahadiyan bermakna lemah lembut dan dermawan.87 Sanad riwayat dari Raden Haji
Ahmad Dimyati didapat dari KH. Amang Syihabuddin yang beliau terima dari KH.
Aceng Mu’man Mansur Cimasuk bahwa gelar Raden berarti Sayyid dan yang bergelar
Raden itu berkerabat atau satu nasab dengan Sunan Gunung Jati.88
Jadi berarti gelar Raden, pertama secara nasab harus masuk ke jalur Sayyid,
kedua harus menjadi penghidup agama, dan ketiga harus memiliki sifat lemah lembut
dan dermawan. Menurut Kitab Al Fatawi bahwa Raden Fatah diangkat menjadi Sultan
Demak oleh Sunan Gunung Jati.
85Al Habib Ali bin Husain bin Jafar Al Atthas, Kitab Taj Al Ars ala Manaqib Al Habib
Al Qutub Solih bin Abdullah Al Atthas Jilid 2, Jeddah: Alam Al Marifah, hal 390. 86Sanad Riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Abdul Haq Pengasuh
Pondok Pesantren Miftahul Huda Subang pada tahun 2009 di Pondok Pesantren Miftahul Huda
Subang. 87Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati dari KH. Huban Zen Pesantren
Gelar Cianjur pada tahun 2009 di Pondok Pesantren Gelar Cianjur. 88Sanad riwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati didapat pada tahun 2011 dari KH.
Amang Syihabuddin yang beliau terima dari KH. Aceng Mu’man Mansur Cimasuk pada tahun
1990 di Kediaman KH. Raden Umar Zen Pondok Pesantren Kubangsari Limbangan Garut.
64
BAB IV
JARINGAN ISLAM DAN KEKUASAAN RADEN FATAH
Dalam BAB ini akan membahas tentang keterkaitan secara riwayat antara
Raden Fatah dengan Pajajaran dan keterkaitan dengan wilayah-wilayah lain yang
berhubungan dengan Demak dan Pajajaran. Dalam hal ini penulis membatasi
penelitian tentang Jaringan Islam dan Kekuasaan Raden Fatah meliputi wilayah
sebagai berikut yaitu Pajajaran, Palembang, Jambi, dan Malaka. Adapun terkait
kerajaan Sunda dimana terdapat 2 kerajaan yaitu Sunda Pedalaman dan Sunda
Pajajaran. Selain itu membahas mengenai polemik riwayat Raden Fatah dan Pati Unus
serta terdapat 3 tokoh yang bernama Yunus. Kemudian menguraikan secara fakta
hubungan ibu Raden Fatah dengan Cina, hubungan Raden Fatah dengan para Wali
Penyebar Islam, menguraikan secara fakta hubungan Raden Fatah dengan Kerajaan
Hindu Jawa, hubungan Raden Fatah dengan para penguasa pesisir pantai utara. Lalu
menjelaskan tentang kiprah dan wafatnya Raden Fatah.
A. Kerajaan Islam Pajajaran dan Kerajaan Hindu Daha
1. Pajajaran Barat, Pusat, dan Timur
a. Wilayah Kekuasaan
Ada 3 daerah yang disebut Pajajaran yaitu Pajajaran Barat, Pajajaran Tengah,
dan Pajajaran Timur. Menurut sumber-sumber tersebut Pajajaran Timur terletak di
daerah Banyumas, Pajajaran Barat terletak di daerah Banten sementara Pajajaran
Tengah terbentang antara Banten dan Banyumas. Pada buku tersebut dikemukakan
pula, pembagian penamaan Pajajaran yang terbagi 3 berasal dari sumber-sumber yang
menurut para sejarawan lebih bernilai sastra.1
Sedangkan berdasarkan Surat Wasiat Sukapura dan Babon Sukapura
sebagaimana yang telah kami bahas pada BAB III, terbukti kebenarannya. Hal
tersebut ditunjukkan dengan salah satu putra dari Batara Mandala alias Sunan
Rumenggong alias Prabu Siliwangi IV berputra Batara Karang alias Prabu
Cakrabuana III alias Prabu Siliwangi V yang bermukim di Demak. Maka dapat
disimpulkan saat masa Sunan Rumenggong, kekuasaan Pajajaran sudah meluas
sampai ke Demak dan sekitarnya, bahkan bisa jadi lebih dari itu (melampui Jawa
Tengah).
Bukti lainnya Pate yang berkuasa atas Japura merupakan seorang ksatria, ia
adalah sepupu tertua dari Pate Rodim alias Raden Fatah dan letak Japura adalah
setelah Cirebon dan sebelum Tegal.2 Sebagaimana yang telah diketahui di BAB III
bahwa Ki Ageng Japura adalah putra Ki Amuk Marugul bin Prabu Susuk Tunggal.
1Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, hal 226. 2Tome Pires, Suma Oriental, hal 256.
65
Batas wilayah timur dari Kerajaan Sunda dibatasi Sungai Cimanuk.3 Jika
memang Kerajaan Sunda dibatasi oleh Sungai Cimanuk maka menimbulkan polemik.
Salah satu contohnya menurut Tome Pires, Cirebon tidak termasuk wilayah Kerajaan
Sunda, sementara naskah-naskah Pasundan menuliskan bahwa Cirebon bagian dari
Kerajaan Sunda Pajajaran. Uraian tersebut adalah sebagai gambaran awal bahwa
Kerajaan Sunda Pajajaran mempunyai wilayah kekuasaan yang cukup luas, bahkan
tidak menutup kemungkinan Kerajaan Sunda memiliki wilayah kekuasaan yang jauh
lebih luas dari gambaran tadi.
b. Nama Pajajaran
Nama Pakuan Pajajaran mengarah kepada pengertian kota atau pusat kota
kerajaan dan bukan nama dari kerajaan itu sendiri walaupun tidak jarang nama sebuah
negara dikenal dengan nama ibukotanya. Dengan demikian, istilah Pajajaran haruslah
diartikan Kerajaan Sunda yang ibukotanya di Pakwan Pajajaran.4 Dari hal tersebut
berarti terdapat 3 wilayah yang disebut Kerajaan Sunda yaitu Kerajaan Sunda Timur,
Kerajaan Sunda Barat, dan Kerajaan Sunda Tengah. Dan setiap wilayah atau raja
Sunda baik tengah, timur, dan barat mempunyai daerah bawahan masing-masing.
c. Struktur Pemerintahan Kerajaan Sunda Pajajaran dan Majapahit adalah
Kerajaan Sunda Timur
Dalam tulisan Tome Pires tahun 1513 M bahwa Kota Dayo adalah tempat di
mana raja paling banyak menghabiskan waktunya dalam setahun. Menurut Barros,
kota utama di Kerajaan Sunda ini disebut Daio terletak agak di pedalaman. Perjalanan
ke kota ini memakan waktu 2 hari dari pelabuhan utama bernama Sunda Kelapa. 5
Kerajaan Sunda memiliki 6 pelabuhan penting, yang masing-masing
dikepalai oleh seorang syahbandar atau nahkoda. Mereka bertanggung jawab kepada
raja dan bertindak sebagai wakil raja di bandar-bandar yang mereka kuasai.6 Ke 6
pelabuhan-pelabuhan yaitu: Banten (Bantam), Pontang (Pomdag), Cigede
(Chequjde), Tangerang (Tamgara), Sunda Kelapa (Calapa), dan Cimanuk
(Chemano).7
Sementara itu, sebuah naskah yang berasal dari tahun 1518, naskah
Sanghyang Siksakanda Karesian memberikan keterangan yang dapat dipergunakan
sebagai petunjuk dari struktur pemerintahan Kerajaan Sunda yang isinya setelah
diterjemahkan sebagai berikut: inilah peringatan yang disebut sepuluh kebaktian: anak
bakti kepada bapak, istri bakti kepada suami, rakyat bakti kepada majikan (tempat
bersandar), murid bakti kepada guru, petani bakti kepada wado (pejabat rendahan),
wado bakti kepada mantri (pegawai), mantri bakti kepada nungganan, nungganan
3Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, hal 226. 4Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 233. 5Tome Pires, Suma Oriental, hal 235. 6Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 230. 7Tome Pires, Suma Oriental, hal 232.
66
bakti kepada mengkubumi, mengkubumi bakti kepada raja, raja bakti kepada dewata,
dewata bakti kepada hyang. 8
Dari kutipan diatas maka pejabat yang paling dekat hubungannya dengan
Raja adalah Mangkubumi. Ia bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi atau
dilakukan oleh yang disebut Mantri dan Wado. Maka struktur Kerajaan Sunda pada
masa tersebut di tingkat pemerintahan pusat, kekuasaan tertinggi berada ditangan
Raja.
Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Raja dibantu oleh Mangkubumi
yang membawahi beberapa orang nunggangan. Untuk mengurus daerah-daerah yang
luas, Raja dibantu oleh beberapa orang Raja Daerah. Raja-raja daerah tersebut dalam
melaksanakan tugasnya bertindak sebagai raja yang merdeka, tetapi mereka tetap
mengakui Raja Sunda yang bertahta di Pakwan Pajajaran sebagai junjungan mereka.9
Analisis terkait dengan struktur Kerajaan Sunda kurang lengkap. Sehubungan
naskah aslinya tertulis Raja berbakti kepada Dewata, Dewata berbakti kepada Hyang.
Menurut analisis, julukan Dewata dan Hyang belum tentu idektik dengan Tuhan bagi
agama Hindu. Dalam naskah tersebut menjelaskan struktur tata tertib
kewarganegaraan. Oleh sebab itu, tidak ada kaitannya dengan makna keyakinan.
Urutan tertinggi dari Raja-raja Sunda adalah sosok yang bergelar Hyang atau
Maharaja atau Maha Prabu, Batara atau Dewata (setingkat Gubernur), dan Prabu atau
Raja (setingkat Bupati). Hal tersebut sehubungan gelar-gelar Raja Pajajaran misalkan
Sunan Rumenggong bergelar Batara Mandala.
Analasis penyataan tersebut yaitu sebelum bertahta menjadi Maharaja Sunda,
Sunan Rumenggong pernah bertahta sebagai Raja Bawahan atau Batara di Mandala
atau Sindangkasih. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Kerajaan Sunda terbagi
3 yaitu Sunda wilayah timur, tengah, dan barat. Maka Demak adalah wilayah Kerajaan
Sunda yang berada di timur dengan rajanya yaitu Prabu Cakrabuana III. Pada masa
pemerintahan Sunan Rumenggong, Kerajaan Sunda Pajajaran sudah menguasai
wilayah Daha. Adapun Kerajaan Majapahit adalah sebutan dari Kerajaan Timur
Sunda, sedangkan Kerajaan Sunda Barat bernama Surosowan Banten.
d. Bentuk Kerajaan Sunda
Kerajaan Sunda mempunyai 3 wilayah kerajaan bawahan yaitu Kerajaan
Sunda Barat, Sunda Tengah (pusat), dan Sunda Timur (Majapahit). Ketiga wilayah
kerajaan tersebut mempunyai cabang wilayah kekuasaan tersendiri yang berbentuk
kerajaan kecil yang tunduk kepada Raja wilayah Kerajaan Sunda, Raja Wilayah
tunduk kepada Raja Pusat yang berkedudukan di ibukota Pakwan Pajajaran. Maka
dari itu, analisis penulis bentuk Kerajaan Sunda adalah federasi.
Semua wilayah Kerajaan Sunda misalnya Kerajaan Sunda Timur boleh
memperluas kekuasaannya sendiri dan juga boleh menentukan aturan atau hukum
tersendiri. Akan tetapi khusus untuk pergantian kekuasaan harus diketahui dan
mendapat izin dari Pakwan Pajajaran. Raja Wilayah adalah putra atau kerabat dari
Raja Pusat yang bergelar SangHyang dan harus tunduk pada pusat.
8Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 230. 9Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 230.
67
Adapaun ideologi atau agama yang dianut oleh Raja-raja Sunda, sesuai
dengan pembahasan pada BAB III adalah Islam, begitu pula Raja-raja Wilayah,
sedangkan Raja-raja Bawahan Wilayah terdapat juga raja-raja yang bukan Islam. Hal
tersebut ditunjukkan dengan buku Sejarah Nasional Indonesia jilid II bahwa khusus
di Pelabuhan Cimanuk sudah banyak berdiam orang-orang beragama Islam walaupun
syahbandarnya masih seorang yang beragama Sunda atau pagan.10
Menurut tulisan Tome Pires bahwa negeri Demak merupakan yang terluas di
antara semua tempat yang sudah disebutkan sebelumnya, mulai dari Cirebon hingga
wilayah ini. Pate Rodim adalah penguasa di negeri ini, sekaligus pate tertinggi di
Jawa. Pate-pate lain telah mengangkatnya sebagai pemimpin dari semua penguasa di
Jawa yang berada di pihaknya. Pate Rodim memiliki hubungan yang erat dengan para
penguasa di Jawa, mengingat semua putri dari ayah dan kakeknya menikah dengan
pate-pate tertinggi. Beliau sangat berkuasa sehingga mampu menaklukkan seluruh
wilayah Palembang, Jambi, Kepulauan Monomby dan banyak pulau lainnya.11 Selain
itu tulisan lainnya adalah Pati Unus berhasil menjadikan negeri Jepara sebagai negeri
yang besar, Jepara memiliki banyak jung dan meskipun Jepara berada di bawah
kekuasaan Demak. Pati Unus merupakan penguasa yang hampir sama besarnya
dengan penguasa Demak.12 Pati Unus berhasil memperluas wilayah kekuasaannya
sampai seberang laut, sampai ke Bangka dan tempat-tempat di pantai Kalimantan,
memiliki banyak kapal jung. Meskipun begitu, ia masih juga mengakui Raja Demak
sebagai atasannya.13
Maka dari itu, dalam bidang diplomasi Kesultanan Demak selalu
mengusahakan kerjasama yang baik dengan daerah-daerah di pantai utara Pulau Jawa
yang telah menganut agama Islam, sehingga tercipta semacam federasi atau
persemakmuran dengan Demak sebagai pemimpinnya. Agama Islam ini merupakan
faktor yang menjadi unsur pemersatu yang menimbulkan kekuasaan yang besar.14
2. Penjelasan Tulisan Tome Pires mengenai Sunda
a. Kerajaan Sunda Pedalaman dan Kerajaan Sunda Pajajaran
Uraian Tome Pires mengenai Raja Sunda secara sepintas bertolak belakang
dengan uraian BAB III, dimana Raja-raja Sunda adalah Sayyid yang tentu
menjalankan syariat Islam dengan taat dan patuh. Raja-raja Sunda Pajajaran juga
bergelar Sunan. Menurut Catatan Silsilah Ningrat Limbangan bahwa Sunan
Rumenggong menetapkan sebuah ajaran yang harus dijalankan oleh masyarakat
10Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 240-241. 11Tome Pires, Suma Oriental, hal 257. 12Tome Pires, Suma Oriental, hal 261. 13H.J De Graaf dan TH Piegeud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 49.
14Heru Arif Pianto, Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi Islam Maritim Di
Nusantara, hal 23.
68
mengacu kepada ajaran Islam diantaranya silih asah, asih, asuh antar sesama yaitu
yang disebut azas kesiliwangian.15
Dengan demikian jelas bahwa Pajajaran adalah Kerajaan Islam. Selain itu
berdasarkan riwayat bersanad yang diterima dari Kyai Haji Raden Umar Zen tahun
1990 di ponpes dimana beliau menyatakan jauh sebelum walisongo menyebarkan
Islam di Jawa, Cirebon Girang (Limbangan, Tasikmalaya, Ciamis atau Priangan
Timur) Islam sudah tersebar di wilayah tersebut dan sudah barang tentu yang
menyebarkan Islam di wilayah tersebut adalah keluarga Dinasti Siliwangi, bahkan
bisa jadi keluarga atau leluhur dari Prabu Ciung Wanara.16
Sedangkan uraian Tome Pires mengenai Raja Sunda dimana mereka
memegang tradisi yang jelas bukan ajaran Islam, diantaranya sebagai berikut:
1. Tradisi di Kerajaan Sunda, bahwa istri-istri raja dan para bangsawan akan
membakar diri ketika sang raja mangkat. Tradisi yang sama berlaku juga pada
kasta yang rendah. Mereka melakukan ini bukan atas dasar paksaan
melainkan atas kemauan mereka sendiri. Namun mereka yang menolak untuk
menjalankannya akan dianggap sebagai beguine (tidak harus diartikan wanita
yang mengabdikan diri kepada agama dan masyarakat tetapi pada zaman
Tome Pires wanita yang hidup dalam kemiskinan dan upaya penebusan dosa)
yang harus tinggal menyendiri dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun.
Sebagian orang menikah 3 atau 4 kali. Sebagian kecil ini menjadi orang-orang
terasing di negeri tersebut. Sang Raja memiliki dua permaisuri yang berasal
dari kerajaannya sendiri, serta lebih dari seribu selir.17
2. Kedua tradisi di atas persis dengan tradisi yang dimiliki oleh Raja-raja
Pedalaman di wilayah Jawa yang dikuasai oleh Guste Pate. Adat mengenai
kematian sudah menjadi kebiasaan di Jawa bahwa ketika sang raja mangkat,
para permaisuri dan selir-selirnya akan membakar diri hidup-hidup, begitu
juga dengan beberapa bawahannya. Hal yang sama juga dilakukan ketika ada
penguasa dan tokoh penting lain yang mati. Kebiasaan ini dilakukan oleh
kaum pagan dan bukan oleh orang-orang Jawa beragama Moor. Wanita yang
menolak untuk membakar diri akan menenggelamkan diri atas keinginan
mereka sendiri, diiringi musik dan pesta. Apabila suami yang meninggal
merupakan orang penting atau bangsawan, maka para pria dan wanita yang
ingin mengikutinya akan membunuh diri menggunakan keris, begitu juga
dengan seseorang yang ingin mati mengikuti raja. Sedangkan orang-orang
biasa akan bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di lautan atau
membakar diri.18
15Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang dikeluarkan oleh Rukun Warga
Limbangan: Raden R.I Soehari Priyatna dan R.H.I Ibrahim. 16Sanad riiwayat dari Raden Haji Ahmad Dimyati diterima dari Kyai Haji Raden
Umar Zen tahun 1990 di Kediaman KH. Raden Umar Zen Pondok Pesantren Kubangsari
Limbangan Garut. 17Tome Pires, Suma Oriental, hal 233-235. 18Tome Pires, Suma Oriental, hal 246.
69
Analisis dari tradisi tersebut yaitu kedua kerajaan tersebut dipimpin oleh
seorang pagan (Non Muslim). Dengan demikian uraian terkait dengan Kerajaan Sunda
yang ditulis oleh Tome Pires adalah Kerajaan Sunda Pedalaman sebagaimana halnya
Kerajaan Jawa yang dikuasai oleh Guste Pate. Bedanya jika di Sunda Kerajaan
Bawahan disebut Paybu (Prabu) sedangkan di Jawa disebut Pate, dan gelar Pate juga
digunakan oleh penguasa-penguasa Muslim. Dari hal tersebut bisa disimpulkan
bahwa gelar Prabu tidak bisa ditunjukkan kepada Raja-raja Pedalaman Sunda saja.
Tradisi yang dimiliki oleh kedua kerajaan tersebut sama dengan tradisi
Kerajaan Bali. Sebagaimana yang diuraikan oleh Antonio Pigafetta tentang sati di
Jawa bahwa setengah league dari Jawa Besar adalah Pulau-pulau di Bali, yang disebut
Jawa Kecil dan Madura memiliki ukuran yang sama. Mereka memberi tahu kami
bahwa di Jawa Besar itu adalah kebiasaan salah kepala suku meninggal untuk
membakar tubuhnya dan kemudian istri utamanya yang dihiasi dengan karangan
bunga telah membawa dirinya sendiri di atas kursi oleh 4 lelaki di seluruh kota dengan
wajah tenang dan tersenyum sementara mempererat hubungannya yang menderita
karena dia akan membakar dirinya dengan mayat suaminya dan mendorong mereka
untuk tidak meratap berkata kepada mereka aku akan pergi malam ini untuk makan
bersama suamiku tercinta, dan untuk tidur dengan dia malam ini. Setelah itu ketika
dekat dengan tempat pembakaran kayu dia kembali berbalik ke arah hubungan dan
sekali lagi menghibur mereka, melemparkan dirinya ke dalam api dan dibakar. Jika
dia tidak melakukan ini, dia tidak akan dipandang sebagai wanita terhormat atau
sebagai istri yang setia.19
Dalam kesusatraan epik Veda dan Sansekerta, tindakan seorang istri yang
melakukan upacara membakar diri dalam api pengorbanan untuk mendukung dan
menolong suaminya di akhirat disebut sati. Menurut Titi Pudjiastuti dalam Helen
Creese bahwa dalam teks-teks Kakawin Jawa Kuna sati dilakukan oleh para
perempuan untuk mengikuti kematian suaminya, sedangkan dalam budaya Jawa sati
dikenal dengan istilah bela pati. Dalam Ramayana Kakawin Jawa Kuna, Sita
melakukan upacara bakar diri sebanyak 2 kali, pertama, berupa sati dilakukan Sita
untuk melakukan bela pati kepada Rama ketika ia mendengar dari Rahwana bahwa
Rama sudah mati. Ketika itu, ia menyuruh Trijata untuk menyiapkan api pengorbanan
untuk menjalankan upacara sati. Namun, upacara itu batal, karena sebelum Sita masuk
ke dalam api pengorbanan Wibisana, adik Rahwana mengatakan hal yang sebenarnya
kepada Sita bahwa Rahwana berbohong demi mendapatkan Sita, karena Rama masih
hidup. Upacara bakal diri yang kedua dilakukan Sita untuk membuktikkan kesucian
dirinya kepada Rama, bahwa ia masing suci meskipun telah cukup lama menjadi
tawanan Rahwana di Alengka.20
Dalam tradisi Hindu, yang mendapat legitimasi dari agama, seorang istri
mengikuti suaminya meninggal dunia dengan membakar diri (upacara sati). Para
penganut agama Hindu memandang bahwa praktik sati (perempuan yang menikah dan
berkorban untuk menyelamatkan suami) merupakan dharma kebaikan sedangkan
19Antonio Pigafetta, The First Voyage Around The World by Magellan 1519-1522,
London: Printed for The Hakluyt Society, hal 154. 20Titi Pudjiastuti, “Sita: Perempuan Dalam Ramayana Kakawin Jawa Kuna,” Jurnal
Manuskrip Nusantara Vol 1 No 2 (2010).
70
hidup menjanda merupakan dharma keburukan. Jika sang suami meninggal, seorang
istri dihadapkan pada 2 pilihan yaitu: 1) melakukan sati, yaitu ritual kejam yang harus
dijalankan para janda dengan membakar diri di atas timbunan kayu bakar pembakar
mayat suaminya dengan predikat kemuliaan atau 2) menjadi janda dengan status
kehinaan. Masyarakat memandang perempuan sati sebagai istri yang baik, yang
mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya.21
Praktik ini dibawa ke Bali dari India melalui Jawa bersama dengan praktik
budaya dan agama Hindu lainnya. Mesatia tidak diragukan lagi telah dipraktikkan di
Bali selama berabad-abad hingga saat pulau itu dijajah oleh Belanda. Bali dijajah
secara bertahap, mesatia juga dihapuskan secara bertahap. Perempuan dikorbankan di
Bali Utara (Kerajaan Buleleng dan Jembrana) hingga pertengahan abad ke 19 di Bali
Timur (Karangasem), dan di antara penduduk Bali di Lombok hingga akhir abad ke
19 dan di Bali Tengah dan Selatan (Bangli, Tabanan, Mengwi, Gianyar, Badong, dan
Klungkung) hingga awal abad ke 20. Kasus mesatia terakhir yang didokumentasikan
terjadi pada tahun 1903 ketika 2 wanita dikorbankan dikremasi Raja Ngurah Agung
di Tabanan.22
Selain itu negeri Jawa merupakan tanah para pemain pantomim dan berbagai
macam pemain topeng, baik pria maupun wanita melakukan pekerjaan ini. Mereka
melakukan aksi pantomim, mengenakan kostum sandiwara dan kelengkapannya.
Mereka amat luwes, memainkan musik dari lonceng suara bel yang dimainkan
bersama-sama akan terdengar seperti organ. Para pemain pantomim ini memainkan
seribu gerakan luwes seperti ini tiap siang dan malam hari. Pada malam hari, mereka
mempertontonkan pertunjukkan bayangan atau wayang dalam berbagai bentuk.23
Wayang adalah salah satu jenis kebudaayan Jawa yang telah ada dan dikenal
oleh masyarakat Jawa sejak kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Kebudayaan Hindu
masuk ke Jawa membawa pengaruh pada pertunjukkan bayang-bayang, yang
kemudian dikenal dengan pertunjukkan wayang. Dalam penyebaran agama Hindu di
Pulau Jawa, para Brahmana menggunakan Kitab Mahabarata dan Ramayan selain
Kitab Weda sehingga kedua kitab ini dikenal dimasyarakat Jawa. Cerita wayang
semula menceritakan petualangan dan kepahlawanan nenek moyang kemudian
beralih ke cerita Mahabarata dan Ramayana. Pada zaman Hindu ini seni pewayangan
semakin populer terutama dengan disalinya ke dalam bahasa Jawa Kuno.24 Dimana
budaya menonton pertujukkan wayang sangat digemari dan sebagian cerita-cerita
perwayangan telah dijadikan tradisi oleh masyarakat Kerajaan Jawa Pedalaman dan
Kerajaan Sunda Pedalaman termasuk Bali. Maka dari itu, uraian Tome Pires mengenai
21Didi Suhendi, “Inferioritas Perempuan: Belenggu Jaya, Jani, dan Patni Dalam
Tradisi Agama Hindu,” Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se Indonesia, Vol 3 No
3 Agustus 2011. 22Alfons van der Kraan, “Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and
Commentary,” Cornell University Press: Southeast Asia Program Publications at Cornell
University, Indonesia No. 40 October 1985, 89-121. 23Tome Pires, Suma Oriental, hal 247 24Bayu Anggoro, “Wayang dan Seni Pertunjukkan: Kajian Sejarah Perkembangan
Seni Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukkan dan Dakwah,” Jurnal Sejarah
Peradaban Islam Vol 2 No 2 tahun 2018.
71
Kerajaan Sunda menunjukkan bahwa Sunda yang dimaksud adalah Kerajaan Sunda
Pedalaman yang mana memiliki tradisi yang sama dengan Kerajaan Jawa Pedalaman.
Selain tradisi yang sama antara Kerajaan Sunda Pedalaman dan Kerajaan
Jawa Pedalaman, hal lain yang di uraian Tome Pires mengenai Kerajaan Sunda
menunjukkan bahwa Sunda yang dimaksud adalah Sunda Pedalaman. Tome Pires
menguraikan luas wilayah Kerajaan Sunda, yaitu:
1. Sebagian orang menegaskan bahwa Kerajaan Sunda menguasai setengah
Pulau Jawa. Sebagian lainnya, yakni orang-orang yang memiliki kedudukan
dalam pemerintahan, meyakini bahwa Kerajaan Sunda menduduki sepertiga
atau seperdelapan bagian pulau. Mereka menyatakan bahwa luas lingkar
Kerajaan Sunda adalah 300 league. Batasan kerajaan ini mencapai Sungai
Cimanuk. 25
2. Terdapat 3 keterangan mengenai luas wilayah Kerajaan Sunda, yaitu: 1)
setengah dari Pulau Jawa menurut sebagian orang, 2) adapun menurut orang-
orang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan sepertiga, 3) atau
seperdelapan bagian pulau. Keterangan yang valid menurut penulis berasal
dari orang-orang yang duduk di pemerintahan. Akan tetapi terdapat 2
keterangan yaitu sepertiga atau seperdelapan dari luas Pulau Jawa.
Dalam hal ini penulis mengambil yang paling kecil yaitu seperdelapan,
sehubungan dengan Qumda (Sunda) adalah sebuah tempat yang kecil saja dimana
terdapat banyak lada.26 Jelas yang dimaksud adalah Sunda Pedalaman dengan luas
wilayah yang hanya seperdelapan dari luas Pulau Jawa dan tidak semua yang dibatasi
Sungai Cimanuk adalah wilayah kekuasaan Sunda Pedalaman.
Sebagai tambahan bukti bahwa hal tersebut adalah Sunda Pedalaman, yaitu:
1. Raja Sunda adalah seorang pagan, begitu juga dengan semua penguasa yang
berada di kerajaannya.27
2. Wilayah yang dimaksud, dibatasi oleh Sungai Cimanuk dari arah barat,
sedangkan Sungai Cimanuk jika di ambil dari hulu sungai yaitu Garut, terbagi
menjadi 2: 1) ke arah Cirebon membelah Garut, Sumedang, Majalengka
sampai ke Indramayu, dan 2) ke arah Brebes sampai ke Laut Jawa. Jika
berpatokan dimana wilayah Sunda dan Jawa hanya dibatasi Sungai Cimanuk,
maka timbul Garut Sunda-Garut Jawa, Sumedang Sunda-Sumedang Jawa,
dan hal tersebut akan menimbulkan polemik wilayah. Dengan demikian, yang
dimaksud Tome Pires adalah Kerajaan Sunda yang dibatasi oleh Sungai
Cimanuk ada di wilayah seberang Cirebon, berarti tidak semua yang
berbatasan dengan Sungai Cimanuk bisa dikategorikan sebagai wilayah
Kerajaan Sunda diuraikan oleh Tome Pires yaitu Kerajaan Sunda Pedalaman.
3. Raja Sunda ternyata hanya menguasai 1 pelabuhan yaitu Pelabuhan Cimanuk.
Hal tersebut dituliskan Tome Pires bahwa pelabuhan Cimanuk merupakan
pelabuhan keenam. Pelabuhan ini bukanlah tempat bagi jung untuk merapat,
melainkan hanya tiang pelabuhan, demikian kabar yang disampaikan oleh
25Tome Pires, Suma Oriental, hal 233. 26Sartono Kartodidjo dkk, Sejarah Nasional Indonesia, hal 227. 27Tome Pires, Suma Oriental, hal 233.
72
orang-orang, sebagian lainnya mengiyakan. Banyak orang Moor tinggal di
sini. Kaptennya adalah seorang pagan. Pelabuhan ini berada di bawah
kekuasaan Raja Sunda. Batas kerajaan berada di tempat ini (Pelabuhan
Cimanuk).28 Penjelasannya sebagai berikut:
a. Pelabuhan Cimanuk dibawah pengawasan Raja Sunda dan batas kerajaan
di pelabuhan ini. Pada pembahasannya Tome Pires memberikan
penekanan bahwa Kapten di Pelabuhan Cimanuk adalah seorang pagan,
sementara di pelabuhan-pelabuhan Sunda lainnya ia tidak memberikan
penekanan seperti terhadap Pelabuhan Cimanuk. Berarti pelabuhan-
pelabuhan Sunda selain Pelabuhan Cimanuk tidak dikuasai oleh seorang
pagan.
b. Kerajaan Sunda tidak memberi izin bagi orang-orang Moor untuk masuk
kecuali sedikit saja bagi mereka. Kerajaan Sunda takut bahwa dengan
kelicikannya, orang-orang Moor akan melakukan hal yang sama dengan
apa yang mereka lakukan di Jawa.
c. Pelabuhan ini memiliki kota yang besar dan bagus, sudah lazim ibukota
akan berdekatan dengan pusat-pusat ekonomi. Dengan demikian bisa
dipastikan kota yang disebut Dayo terletak tidak berjauhan dengan
Pelabuhan Cimanuk.
d. Perjalanan dari Cimanuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa memakan waktu
sehari semalam dengan angin yang baik. Perjalanan dari Pelabuhan Sunda
Kelapa ke kota Dayo memakan waktu 2 hari. Hal yang perlu diperhatikan
terdapat keterangan yaitu dengan angin yang baik artinya perjalanan yang
dimaksud adalah perjalanan dengan menggunakan kapal laut pada waktu
itu. Apalagi terdapat catatan lain dimana Pelabuhan Cimanuk adalah tiang
pelabuhan artinya hanya pelabuhan penunjang bukan pelabuhan utama.
Dengan demikian yang dimaksud oleh Tome Pires perjalanan 2 hari dari
Pelabuhan Sunda Kelapa ke kota Dayo, dengan memakai kapal laut
bukan lewat darat, sebab jika melewati darat biasanya Tome Pires akan
menjelaskan rute darat yang dilalui. Dengan demikian jika kota Dayo
Sunda terletak di Bogor jelas keliru karena tolak ukurnya adalah
perjalanan lewat laut dalam waktu 1 hari 1 malam atau 2 hari.
Dari ke 3 penjelasan terkait Kerajaan Sunda adalah Sunda Pedalaman. Maka
bisa diartikan bahwa ibukota Pedalaman baik di Jawa dan Sunda, disebut Dayo. Dari
hal tersebut, maka keliru jika sebutan Dayo dianalisis sebagai Pakwan Pajajaran,
sebagaimana yang ditulis oleh para sejarawan selama ini. Tome Pires tidak
menuliskan kota Dayo di Jawa sebagai ibukota Majapahit dan Dayo di Sunda tidak
dituliskan sebagai Pakwan Pajajaran.
Dapat penulis simpulkan bahwa luas Sunda Pedalaman adalah seperdelapan
dari luas Pulau Jawa atau sekitar 16.000 km persegi, hampir setengah luas Jawa Barat
sekarang, di luar Banten dan Jakarta. Jika wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda
Pedalaman memiliki luas hanya 16.000 km persegi maka sisa luas di luar wilayah
28Tome Pires, Suma Oriental, hal 241-242.
73
yang dikuasai oleh Kerajaan Sunda Pedalaman adalah milik kekuasaan Kerajaan
Sunda Pajajaran. Kesalahan analisis mengenai Sunda di Tome Pires bahwa Kerajaan
Sunda Pedalaman yang dianalisis sebagai Kerajaan Sunda Pajajaran. Sebagaimana
Kerajaan Jawa Pedalaman mengenai analisis kota Dayo di Jawa dianalisis sebagai
ibukota Majapahit. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya Hindunisasi Kerajaan
Sunda Pajajaran dan Kerajaan Majapahit.
Tome Pires dalam menjelaskan Sunda tidak sedetail seperti penjelasan
tentang Jawa, ia lebih banyak menerima kabar dari kerajaan yang ia kunjungi,
sehingga dalam menjelaskan Sunda banyak yang terputus dan bias. Selain itu, Tome
Pires mengunjungi Kerajaan Sunda pagan yang mana bisa diajak bersekutu dengan
Portugis untuk meruntuhkan Demak. Karena Tome Pires merupakan seorang
pengamat yang antusias, seorang pelajar yang giat dan selalu ingin tahu dan seorang
pencerita yang terpercaya, akurat, dan tak kenal lelah meskipun gaya literasinya
buruk.29 Tome Pires sebagai juru tulis bagi pialang dan akuntan pergi bersama armada
dan pengawas muatan.30 Pires dan ayahnya memiliki hubungan yang intim dengan
kerajaan Portugis dan mengenyam pendidikan yang lebih dibandingkan dengan
mayoritas bangsawan Portugal.31 Selain ia sebagai penulis untuk Portugis tetapi juga
sebagai mata-mata dan misionaris, tercermin dari tulisan prakatanya dalam Suma
Oriental.32 Kerajaan Sunda bukan sasaran utama Tome Pires, ia tidak menjelaskan
siapa saja Paybou atau Prabu yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang
disebut Sang Briyang (Sang Hyang).33 Jauh berbeda ketika menjelaskan Jawa sampai
menjelaskan keterkaitan darah dan geneologi keluarga Demak dan para pate yang
berkuasa di sekitar Jawa.
Tome Pires pada penjelasan Sunda hanya bersifat umum. Misalnya Tome
Pires menuliskan bahwa wilayah ini berada di tanah Jawa, wilayah yang merupakan
milik pate, penguasa, dan gubernur dan dikenal dengan nama Sunda. Sebutan pate
sebagaimana yang dituliskan bahwa di Jawa para penguasa disebut pate sedangkan
dalam bahasa Sunda mereka dikenal dengan panggilan paybou.34 Pada saat Tome
Pires datang ke Jawa, wilayah Sunda secara keseluruhan sudah berada dibawah
kekuasaan Demak. Adapun Kerajaan Sunda Pedalaman diberi hak otonomi tetapi
dilindungi keberadaannya oleh Pate Rodim sehingga Raja Sunda bisa menjalankan
tradisi mereka dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Pate Rodim telah membuat
aturan yang menjamin keselamatan dari Kerajaan Sunda Pedalaman sehingga tetap
merasa aman bahkan bisa melakukan perdagangan dengan masyarakat Kerajaan
Sunda Pajajaran.
Aturan yang dibuat tertulis pada penjelasan Pelabuhan Sunda Kelapa bahwa
komoditas dagang dari seluruh penjuru kerajaan dibawa ke Pelabuhan Sunda Kelapa.
Tempat ini dikelola dengan baik dengan adanya hakim, peradilan, dan juru tulis.
Dikabarkan bahwa peraturan di kota telah dicantumkan dalam tulisan sebagai contoh
29Tome Pires, Suma Oriental, hal XXIX. 30Tome Pires, Suma Oriental, hal XXXVII. 31Tome Pires, Suma Oriental, hal XI. 32Tome Pires, Suma Oriental, hal 1. 33Tome Pires, Suma Oriental, hal 234. 34Tome Pires, Suma Oriental, hal 232-234.
74
seseorang yang melakukan perbuatan A akan dikenakan hukuman B dan seterusnya
sesuai hukum kerajaan. Banyak jung yang merapat di Pelabuhan Sunda Kelapa.35
Tome Pires tidak menuliskan raja mana yang telah membuat peraturan, namun dengan
adanya hakim di pelabuhan tersebut telah menunjukkan bahwa ada seorang yang
berkuasa atas Sunda yaitu pate yang telah menempatkan seorang hakim. Dengan
demikian Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan yang digunakan bersama oleh 2
kerajaan yaitu Kerajaan Sunda Pajajaran dan Kerajaan Sunda Pedalaman yang berada
di wilayah Sunda. Dalam menjaga kerukunan maka Pate Rodim menempatkan hakim
yang adil. Penjelasan tersebut sesuai dengan tulisan Tome Pires bahwa Kerajaan
Sunda diperintah dengan adil oleh orang-orang yang tulus. Masyarakat yang tinggal
di pesisir pantai berhubungan baik dengan para pedagang yang ada di pedalaman.36
Yang dimaksud dengan orang-orang tulus adalah pate pemilik wilayah Sunda
secara turun-menurun. Adapun masyarakat yang berada di pesisir pantai adalah
masyarakat Sunda yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran.
Sementara para pedagang dari wilayah Kerajaan Sunda Pedalaman yang pusat
kotanya bernama Dayo.
b. Pembahasan mengenai Polemik Riwayat antara Raden Fatah dan Pati Unus
1. Nama Sabrang Lor
Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Pati Unus 2 adalah putra dari
Pati Unus 1. Berdasarkan Catatan Keluarga Ningrat Sukapura bahwa nama Pati Unus
2 adalah Syarif Ahmad Abdul Qodir. Adapun silsilah dari Pati Unus 237 yaitu:
1. Raja Utara alias Syarif Aulia Muhammad keturunan Baghdad, berputra
2. Raja Baghdad alias Syaikh Syarif Muhammad Ali Zainal Abidin alias Syaikh
Ismail Maulana Ariffin Malaka, berputra
3. Pati Unus 1 bernama Syarif Ibrahim Yunus alias Nurrudin Ibrahim, berputra
4. Pati Unus 2 adalah Syarif Ahmad Abdul Qodir
De Graaf dan Pigeaud menuliskan gelar Pangeran Sabrang Lor. Gelar tersebut
menunjukan nama sebuah tempat asal-usul yang terletak di Seberang Utara. Tepatnya
di Sebrang Utara Aceh, sehingga gelar Pati Unus 2 adalah Pangeran Sabrang Lor. 38
Riwayat tersebut adalah riwayat pertama kali pendudukan Portugis atas Malaka, tetapi
melekat dicucu Pati Unus 2. Selain itu nama Seberang Utara tetap terbawa menjadi
cerita bersanad dikeluarga keturunan Pati Unus 2. Basis orang Tashi disebut ada di
Sumatera bagian utara. Bahkan Zhao Rugua menyebut pada sumber lama awal abad
12 bahwa bagian utara Sumatera itu dahulunya adalah negeri orang Tashi artinya
pernah dipimpin oleh orang keturunan Quraisy, sekaligus dari garis keturunan
35Tome Pires, Suma Oriental, hal 241. 36Tome Pires, Suma Oriental, hal 234. 37Data-data Keluarga Ningrat Sukapura di Tasikmalaya disimpan oleh Raden Haji
Ahmad Dimyati sebagai Penyimpan sebagian data-data Ningrat Sukapura. 38H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Seajarah
Politik Abad XV dan XVI, hal 53.
75
Rosulullah SAW. Dalam Chau Ju Kua bahwa identifikasi antara Tashi dan Sumatera
ini mendorong beberapa orang untuk mengaitkan nama Aceh dari asal kota Tashi ini.
Karena lidah orang Arab akan mengucap Aceh itu ya Asyi. 39
Sebagaimana yang telah dikemukakan nama asli Pati Unus 2 adalah Syarif
Abdul Qodir. Dan juga menurut Catatan Sayyid Bahruddin Ba’alawi tentang Asyraf
di Tanah Persia ditulis pada tanggal 9 September 1979 bahwa Pati Unus 2 adalah
menantu Raden Fatah. Nama aslinya adalah Raden Abdul Qadir putra Muhammad
Yunus dari Jepara. Raden Muhammad Yunus adalah putra seorang mubaligh
pendatang dari Persia yang dikenal dengan sebutan Syekh Kholiqul Idrus. Mubaligh
dan musafir besar ini datang dari Persia ke tanah Jawa mendarat dan menetap di Jepara
pada awal 1400-an M. Silsilah syekh ini yang bernama lengkap Abdul Khaliq Al Idrus
bin Syekh Muhammad Al Aisy bin Syekh Abdul Muhyi Al Khairi bin Syekh
Muhammad Akbar Al Ansari bin Syekh Abdul Wahhab bin Syekh Yusuf Al
Mukhrawi yang merupakan keturunan cucu Nabi Muhammad generasi ke 19. Ia
memiliki ibu bernama Syarifah Ummu Banin Al Hasani (keturunan Imam Hasan bin
Fatimah binti Nabi Muhammad) dari Persia. 40 Maka Syekh Kholiqul Idrus adalah
orang yang sama dengan Syaikh Ismail Maulana Ariffin Malaka.
Keterkaitan Pati Unus 1 dengan Kerajaan Pajajaran berdasarkan bahwa ibu
dari Pati Unus 1 adalah Putri Pajajaran dari Sunan Rumenggong. Pati Unus 1 menantu
dari Prabu Cakrabuana III, beliau juga masih cucu dari Sunan Rumenggong. Oleh
sebab itu, beliau menduduki posisi yang sangat strategis dan penting di Kerajaan
Sunda Pajajaran, sehubungan beliau masih berdarah Pajajaran. Berarti, Pati Unus 1
saudara sepupu dan besan dengan Sunan Gunung Jati Cirebon.41
Hal tersebut diperkuat oleh tulisan Pigafetta. Fakta-fakta tentang keberadaan
Kerajaan Sunda Pajajaran, penulis memaparkan beberapa tulisan pada zamannya dan
juga pendapat para ahli sejarah. Buku Relazione sul Primo Viaggio Interno al Mondo
merupakan laporan perjalanan penulis Italia Antonio Pigafetta. Ia pernah mengikuti
perjalanan armada Spanyol yang dipimpin oleh Fernao Magelhaes mengelilingi dunia
pada tahun 1511-1522 M. Pada tahun 1800 M, naskah Pigafetta ini diterbitkan oleh
Amoretti dan pada 1894 M diterbitkan lagi oleh Andrea da Mosto.42 In this island of
Java are the largest towns, the principal of them is Magepaher (Majapahit), the king
of which, when he lived, was the greatest of all the kings of the neighbouring island
and he was named Raja Pati Unus Sunda. Much pepper grows there. The other towns
are Daha, Dama, Gagiamada, Minutarangam, Ciparafidain, Tuban, Gressi (Gresik),
and Cirubaya (Surabaya). Terjemahannya yaitu di pulau Jawa ini adalah kota-kota
terbesar, Raja mereka adalah Majapahit, raja yang ketika masih hidup, ia adalah raja
39Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, hal 95-96. 40Soedjipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi Terlengkap dan Terasli, hal 309-310. 41Naskah Sukapura yang ditulis oleh Raden Beben Abdullah tahun 1991, Babon
Sukapura, Catatan Silsilah Ningrat Majalengka ditulis oleh Sutirman Hadisaputra, dan Catatan
Silsilah Keluarga Kyai Raden Agus Ma’mun Cilamaya Kerawang tahun 1890. 42Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
29.
76
yang paling berkuasa dari semua raja di pulau-pulau tetangga dan dia bernama Raja
Pati Unus Sunda.43
Buku sejarah mengenai Asia ini ditulis oleh seorang penulis Portugis bernama
J. De Barros. Pada 1522-1564, buku ini baru selesai ditulis dekade I-III. Pada 1570,
De Barros meninggal sehingga buku Da Asia decade IV belum selesai ditulis. Buku
ini kemudian diteruskan oleh Lavanha berdasarakan catatan-catatan De Barros.
Selanjutnya sebagian dari decade IV sampai XII dari buku tersebut dikerjakan oleh
Diogo do Cauto. Buku De Asia ini pada tahun 1778-1788 seluruhnya dicetak kembali
di Lisabon.44 R.A. Kern telah menggunakan buku sejarah karya de Barros, Da Asia.
Di dalam Da Asia, de Barros menyebutkan Pati Unus (dari Jepara) sebagai seorang
Raja Sunda (Rey de Cunda).45 Adapun naskah yang dipakai De Barros untuk
menerangkan Pati Unus itu ialah naskah berbahasa Italia yang tersimpan di Milan.
Naskah ini dikenal sebagai naskah Amoretti.46 Diperkuat oleh tulisan Tome Pires
bahwa negeri Jepara adalah negeri Pati Unus, seorang ksatria yang banyak
dibicarakan oleh orang Jawa karena dia dikenal sebagai ksatria tangguh dan bijaksana
di Jawa.47 R.A. Kern, ia menulis bahwa Pati Unus adalah seorang Raja Sunda.48
Sedangkan menurut P.A. Tiele berpendapat bahwa Pati Unus adalah Raja Majapahit
terakhir.49 Dengan demikian, jelas berdasarkan fakta primer bahwa hubungan Demak
dengan Sunda Pajajaran memiliki keterkaitan secara nasab dan alur kekuasaan.
Adapun keterangan Tome Pires yang menyatakan kakek Pati Unus berasal
dari Kalimantan Barat.50 Sesuai dengan Catatan Keluarga Ningrat Sukapura bahwa
itu pun benar sehubungan kakek Pati Unus adalah seorang ulama penyebar Islam di
Sulu dan Kalimantan. Leluhur Pati Unus berkaitan dengan keberadaan Batu Bersurat
Terengganu yang bertarikh 702 H (sebagian pedapat tahun 711 H), dan juga Batu
Tarsilah/Prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei
Darussalam.51 Dari hal tersebut tidak mengherankan jika penulis asal Portugis, de
Barros menyebutkan Pati Unus (Pati Unus 1 dan Pati Unus 2) berpengaruh besar
berkat hubungan keluarga.52 Syekh Ismail adalah ulama keturunan Baghdad bernama
asli Ali Zainal Abidin yang merupakan leluhur Kesultanan Sulu dan Mindanau. Beliau
43Antonio Pigafetta, The First Voyage Around The World by Magellan 1519-1522,
hal 154. 44Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
30. 45R.A Kern, “Pati Unus En Sunda.” Journal Bijdragen tot de taal-, land- en
volkenkunde, 1952, Deel 108, 2de Afl. (1952) pp. 124-131, hal 126. 46Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
124. 47Tome Pires, Suma Oriental, hal 260. 48R.A Kern, Pati Unus En Sunda, hal 131. 49Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
124. 50Tome Pires, Suma Oriental, hal 260. 51Data-data Keluarga Ningrat Sukapura di Tasikmalaya disimpan oleh Raden Haji
Ahmad Dimyati sebagai Penyimpan sebagian data-data Ningrat Sukapura. 52H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 49.
77
juga adalah guru dari Walisongo dan memiliki panggilan Raja Baghdad.53 Untuk
membahas kiprah dan sejarah leluhur Pati Unus 1 perlu ada penelitian lanjutan.
2. Raden Yunus dan Pati Unus 2
Terkait dengan sosok Pangeran Sabrang Lor/Pati Unus sebenarnya ada 2 versi
yakni: dia anak Raden Fatah atau dia menantu Raden Fatah. Namun bisa jadi kedua
tokoh ini orangnya berbeda, namun nama hampir sama.54 Maka dari itu, menurut
Kitab Al Fatawi menuliskan bahwa Pati Unus adalah putra dari Raden Fatah dan
pengganti sultan setelah Raden Fatah wafat. Dalam Al Fatawi juga bahwa Pati Unus
menantu Sunan Gunung Jati wafat di Malaka dan putra dari Sultan Yunus. Menurut
Tome Pires bahwa Pati Unus menantu dari Pate Rodim alias Raden Fatah.55 Menurut
Catatan Sayyid Bahruddin Ba’alawi bahwa Pati Unus adalah menantu Raden Fatah.
Nama aslinya adalah Raden Abdul Qadir putra dari Muhammad Yunus dari Jepara.56
Maka, Pati Unus yang dimaksud Al Fatawi bukan Pati Unus 2 alias Syarif Abdul
Qodir, Raja Pati Unus Sunda Majapahit. Dengan demikian seharusnya terdapat 3
tokoh yang bernama Yunus, yaitu:
1. Syarif Ibrahim Yunus alias Muhammad Yunus alias Pati Unus 1 ayah dari
Pati Unus 2.
2. Syarif Abdul Qodir alias Pati Unus 2 menantu dari Raden Fatah dan Sunan
Gunung Jati.
3. Raden Yunus putra dari Raden Fatah dan menjadi sultan setelah Raden Fatah
wafat.
Beliau menggantikan ayahnya menjadi Adipati Jepara pada tahun 1507 M57
dan Pati Unus 2 menurut Kitab Al Fatawi wafat di lautan Malaka pada tahun 1521 M
dan dimakamkan di Pulo Besar Malaka.58 Artinya Yunus yang wafat di lautan Malaka
adalah Pati Unus 2 dan yang wafat di Demak yaitu Raden Yunus putra Raden Fatah.
Hal tersebut sesuai dengan uraian yaitu berita dari sumber Jawa, ialah sebuah
catatan pada tahun 1521 dalam Chronological Table dalam History of Java (Raffles,
History). Daftar tarikh itu berdasarkan buku Babad Sengkala. Menurut catatan itu,
konon 1521 ada tiga orang Raja Jawa yang meninggal, tetapi sayang sekali nama dan
kerajaan-kerajaannya tidak disebutkan. Mungkin sekali Pati Unus adalah salah satu
dari ketiga raja tersebut. 59
53Data-data Keluarga Ningrat Sukapura di Tasikmalaya disimpan oleh Raden Haji
Ahmad Dimyati sebagai Penyimpan sebagian data-data Ningrat Sukapura. 54Dhurorudin Mashad, Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hal 110. 55Tome Pires, Suma Oriental, hal 261. 56Soedjipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi Terlengkap dan Terasli, hal 309. 57H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 50. 58Data-data Keluarga Ningrat Sukapura di Tasikmalaya disimpan oleh Raden Haji
Ahmad Dimyati sebagai Penyimpan sebagian data-data Ningrat Sukapura. 59H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 51.
78
Jika mengacu kepada riwayat Pati Unus dan Raden Fatah yang disesuaikan
dengan uraian diatas, maka tokoh raja-raja yang wafat, yaitu :
1. Raden Fatah wafat tahun 1518 M.
2. Raden Yunus bin Raden Fatah wafat tahun 1521 M. Pada saat perang
melawan serangan Kerajaan Hindu Daha, dimakamkan di Demak.
3. Pati Unus 2 alias Syarif Abdul Qodir alias wafat tahun 1521 M. Pada saat
perang ke 2 melawan Portugis yaitu Perang Malaka, dimakamkan di Malaka.
Uraian diatas diperkuat bersumber dari Babad Cirebon60 mengenai asal-usul
sebutan Panatagama dimana gelar tersebut dikhususkan untuk jabatan
Qadhi/Penghulu Kesultanan bukan untuk raja, yaitu:
1. Raja: Arya Palembang Raden Patah Sultan ing Demak Ratu Agami
Muhammad Tazzul Ariffin
2. Patih: Patih Wanasalam
3. Penghulu (Qadhi, Penatagama): Pangeran Kudus Panatagama Qodhi Amirul
Mukminin
4. Jaksa: Ki Jaksa Yuda Bintara (mantan Jaksa Majapahit)
Pada Babad Cirebon terdapat nama Pangeran Kudus sebagai Qody dan beliau
bergelar Pangeran Kudus Amirul Mukminin. Biasanya disertai juga dengan nama
Abdurahman atau Ngabdurahman Sayyidin Panagama dan disesuaikan dengan Babon
Sukapura dimana yang bergelar Pati Kudus adalah Pati Unus, baik Pati Unus 1
maupun Pati Unus 2.61
Kesalahan penulisan sejarah yang disengaja atau tidak, serat dan babad
menulis Pati Unus 2 bahwa ia sebagai Raja Demak kedua, wafat pada tahun 1521
karena paru-parunya membengkak, yang mungkin akibat dari tusukan keris.62
Sebagaimana yang ditulis oleh De Graaf dan Pigeaud bahwa baik dalam cerita babad
di Jawa Barat maupun yang di Jawa Timur, dan Mataram, nama Pate Unus tidak
pernah disebut. Selain itu, baik Jepara maupun perang laut melawan Malaka tidak
dianggap penting dalam babad Jawa selama perempat pertama abad XVI. Tetapi
mengingat bahwa berdasarkan berita para penulis Portugis, Pate Unus dari Jepara
adalah orang penting dalam sejarah Jawa.63
Atau bahkan bagian dari pembunuhan karakter bagi keturunan Pati Unus 2
sehingga sampai saat ini keturunan Pati Unus 2 secara mayoritas banyak yang
kehilangan jejak. Tokoh Pati Unus selain masalah nama akibat dari penyamaan tokoh
Pati Unus dan Sultan Yunus sehingga terjadi kesalahan penulisan sejarah. Dan juga
terjadi ketertukaran gelar yaitu dalam Hikayat Banjar gelar Sultan Surya Alam
60Babad Cirebon, Kode 75b/PNRI, hal 86-87. 61Ringkasan Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya. 62Tundjung dan Arief Hidayat, “Politik Dinasti Dalam Perspektif Ekonomi dari
Kerajaan Demak, Jurnal LPPM UNINDRA, Vol 3 No 1 2018. 63H.J De Graaf dan TH Pigeuad, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 51.
79
dinisbatkan untuk gelar Raden Fatah,64 padahal gelar Surya Alam adalah gelar
keluarga Pati Unus.65
Selain itu menurut Babad Cirebon66 yang bergelar Khalifatul Mukminin atau
Amirul Mukminin adalah Pangeran Kudus alias Pati Unus 2 alias Panatagama alias
Sabrang Lor. Beliau juga memangku jabatan Panglima Demak yang setingkat
Perdana Menteri Kesultanan Demak Pajajaran pada waktu itu, juga memangku
jabatan Qadhy Demak atau ketua para Ulama di wilayah kekuasaan Demak atau
Pajajaran dan juga bergelar Sunan Gunung Jati II.
Adapun Raden Fatah sendiri mengacu kepada sumber yang sama dan Babon
Sukapura sejarah luluhur, beliau bergelar Sultan Tajjul Ariffin Ratu Jawa yang artinya
Mahkota Raja-Raja atau Junjungan Raja-Raja, sedangkan nama asli beliau adalah
Syaikh Sayyid Muhammad Ariffin.67 Jika dilengkapi dengan Catatan Silsilah Ningrat
Limbangan maka nama lengkap Raden Fatah adalah Syaikh Sultan Muhammad Tajjul
Arriffin Ali Akbar Al-Fattah.68
c. Hubungan Raja Sunda Pajajaran dengan Cina
Tome Pires menuliskan69 bahwa:
a. Mereka mengatakan bahwa orang Jawa pernah memiliki hubungan dekat
dengan orang Cina. Seorang Raja Cina mengirimkan salah seorang putrinya
ke Jawa untuk menikah dengan Batara Raja Cuda. Ia dikirim bersama dengan
sejumlah besar orang Cina dan uang tunai yang kini digunakan sebagai satuan
uang. Kabarnya, uang ini berjumlah sangat besar.
b. Raja tersebut merupakan bawahan, bukan taklukkan Raja Cina. Orang-orang
Jawa pun membunuh semua orang Cina yang berada di Jawa melalui
pengkhianatan. Sebagian orang lainnya mengatakan bahwa peristiwa tersebut
tidak pernah terjadi.
c. Raja Jawa dan Raja Cina tidak pernah memiliki hubungan satu sama lain.
Uang tunai yang sekarang dipakai di Jawa dibawa ke tempat ini melalui
komoditas dagang, orang-orang Cina sudah melakukan perdagangan dengan
Jawa jauh sebelum Malaka ada. Tetapi kini, sudah seratus tahun berlalu sejak
orang Cina datang ke tempat ini untuk berdagang.
Pada tulisan nomer 1 bahwa seorang Raja Cina mengirim putrinya ke Jawa
untuk menikah dengan Batara Raja Cuda. Berita tersebut dijadikan tulisan Babad
Tanah Jawi bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan Raden Fatah dimana ditulis
ibunda Raden Fatah berasal dari Cina karena Raden Fatah adalah putra Raja Jawa.
Sebagaimana menurut Agus Sunyoto bahwa Raden Fatah lahir dari seorang
perempuan Cina yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Karena
64Soedjipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi Terlengkap dan Terasli, hal 306. 65Sajarah Babon Leluhur Sukapura disusun Raden Sulaiman Anggapraja. 66Babad Cirebon Kode 75b/PNRI, hal 86-87. 67Sajarah Babon Leluhur Sukapura disusun Raden Sulaiman Anggapraja 68Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang disusun oleh KH. Raden Atung Aunillah. 69Tome Pires, Suma Oriental, hal 250.
80
permaisuri Brawijaya berasal dari Champa sangat cemburu maka selir tersebut dalam
keadaan hamil dihadiahkan kepada putra sulung Brawijaya yaitu Arya Damar yang
menjadi Raja Palembang.70
Tetapi terdapat polemik dalam penulisan tersebut, Tome Pires tidak menulis
tahun kejadiannya. Maka dari itu, kejadian tersebut tidak bisa dihubungkan dengan
sejarah orang tua Raden Fatah. Tome Pires juga tidak menuliskan bahwa Raja Cuda
memiliki hubungan dengan Raden Fatah.
Fakta bahwa Raja Cina mengirim putrinya ke Jawa untuk menikah dengan
Batara Raja Cuda, yaitu menurut Pararaton pada tahun 1376 M muncul sebuah gunung
baru, peristiwa tersebut dapat dianalisis sebagai munculnya kerajaan baru dan
menurut kronik Cina dari Dinasti Ming pada tahun 1377 M di jawa terdapat dua
kerajaan merdeka yang sama-sama mengirim duta ke Cina, Kerajaan Barat dipimpin
Wu Lao Po Wu sedangkan Kerajaan Timur dipimpin oleh Wu Lao Wang Chieh.
Menurut Pararaton Wu Lao Po Wu adalah ejaan Cina untuk Bhra Prabu yaitu nama
lain Prabu Hayam Wuruk sedangkan Wu Lao Wang Chieh adalah Bhre Wengker alias
Wijayarajasa suami dari Rajadewi. Hal tersebut perlu dikaji ulang karena tokoh raja
yang bergelar Prabu untuk gelar Raja di Sunda.
Menurut Pararaton, perang paregreg terjadi tahun 1404 M. Paregreg artinya
perang setahap demi setahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih
berganti. Kadang pertempuran dimenangkan pihak timur, kadang dimenangkan pihak
barat. Kejadian tersebut sesuai dengan berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming
(1368-1643 M). Menurut sejarah Dinasti Ming (Ming-Shih) menyebutkan bahwa
setelah Kaisar Cheng-tsu bertakhta pada 1403 M, ia mengadakan hubungan
diplomatik dengan Jawa. Ia mengirimkan utusan-utusannya kepada raja bagian barat
Tu-ma-pan dan kepada raja bagian timur Put-ling-ta-hah atau Pi-ling-da-ha. Pada
tahun 1405 M, Laksamana Cheng-Ho memimpin armada perutusan ke Jawa, ditulis
Laporan Umum Pantai Samudera (Ying-Yai-Sheng-Lan). Ma-Huan pernah mengikuti
pelayaran muhibah yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-Ho pada tahun 1413 M.
Buku yang ditulis oleh Ma-Huan diterbitkan pada tahun 1416 M, didalamnya ditulis
tentang Pulau Jawa, khususnya tentang kota-kota pelabuhan di Jawa Timur, akan
tetapi sedikit mengenai uraian Majapahit. Jadi dalam hal perutusan Cina tersebut
terjadi beberapakali kunjungan yaitu pada tahun 1405 dan 1416 M. Pada tahun 1406
M Laksamana Cheng-Ho dan para perutusan Cina menyaksikan terjadinya perang di
Jawa. Disebutkan kerajaan bagian timur mendapat kekalahan dan kerajaannya
dirusak. Berita Cina tersebut menyebutkan pada waktu terjadinya peperangan antara
dua kerajaan, para perutusan Cina sedang berada di kerajaan bagian timur.71
Pembahasan terkait dengan Perang Paregreg maka dapat disimpulkan bahwa
jika Tu-Ma-Pan diartikan Tumapel, hal tersebut menimbulkan polemik sehubungan
dalam Pararaton disebutkan bahwa Bhre Hyang Parameswara berkedudukan di
Tumapel tampil sebagai pemenang yang ditandai dengan terbunuhnya Bhre
Wirabhumi. Bhre Hyang Wisesa atau Wikramawarddhana memerintah di Majapahit
tahun 1389-1429 M.
70Agus Sunyoto, Atlas Walisongo, hal 320. 71Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 70-
71.
81
Namun catatan Cina ditafsirkan oleh sebagian sejarawan terjadi pertempuran
antara saudara di lingkungan keluarga Majapahit. Padahal pada catatan Cina jelas
menyebutkan kerajaan timur ditulis Kerajaan Daha. Dengan demikian, kerajaan barat
adalah Kerajaan Sunda Pajajaran atau kerajaan timur disebut Majapahit. Maka dapat
diartikan kerajaan barat adalah Kerajaan Sunda di wilayah timur dan Majapahit di
sebelah barat dari Kerajaan Daha. Pusat kota Kerajaan Sunda Timur saat itu di
Tumapel atau Kendal sekarang sedangkan Jepara termasuk wilayah tersebut. Sebab
jika merujuk ke Pararaton mengenai kerajaan barat akan menimbulkan polemik.
Dari uraian tersebut maka Kerajaan Hindu berdiri kembali pada tahun 1377
M, dan mereka memberontak kepada Kerajaan Islam Sunda Pajajaran sehingga
terjadilah Perang Paregreg. Dalam perang tersebut kemenangan silih berganti dan
puncaknya tahun 1468 M yaitu Bhre Kertabumi alias Prabu Cakrabuana III berhasil
merebut kembali Tumapel dengan ditandai terbunuhnya penguasa Jepara lama oleh
Pati Unus 1. Sedangkan Raja Daha yang bernama Dyah Suraprabbawa Sri
Singhawikramawardddhana pada tahun Saka 1390 (1468 M) menyingkir ke
pedalaman yaitu Daha.
Berdasarkan Prasasti-prasasti Girindrawarddhana tahun Saka 1408 (1486 M)
yaitu Prasasti Trailokyapuri I dan II menyebutkan adanya penyelenggaraan upacara
sraddha untuk memperingati 12 tahun mangkatnya Sri Paduka Bhattara rin
Dahanapura, ia adalah raja yang mangkat di Indrabhawana. Jadi raja mangkat pada
tahun Saka 1396 (1474 M) yaitu 12 tahun sebelum dibuatnya prasasti-prasasti
Girindrawarddhana pada Saka 1408. Tokoh Paduka Bhattara rin Dahanapura ini oleh
beberapa sarjana telah diidentifikasikan dengan tokoh Bhre Pandansalas Dyah
Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana. Berdasarkan keterangan dalam
prasasti-prasasti Girindrawarddhana itu, maka dapat diduga bahwa ketika Kadaton
Tumapel diserang oleh Bhre Kertabhumi, Bhre Pandansalas menyingkir ke Daha. Di
Daha, ia kemudian meneruskan pemerintahannya sebagai Raja Majapahit dan pada
Saka 1395 mengeluarkan Prasasti Pamintihan.72
Pada Prasasti Ptak tahun 1486 M, putra Sri Singhawikramawarddhana yaitu
Dyah Girindrawarddhana Ranawijaya menyatakan adanya peperangan melawan
Majapahit (yuddha lawanin Majapahit). Ditulis yuddha lawaning Majapahit dan ia
tidak menyebut dirinya sebagai seorang Raja Majapahit namun ia menamakan diirnya
Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatiktapura Jangala Kadiri.73 Dari fakta tersebut dapat
dianalisis bahwa Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya adalah musuh Kerajaan
Majapahit, dengan kata lain musuh Kerajaan Sunda Pajajaran. Namun jika hal tersebut
diartikan sebagai perang saudara didalam keluarga Majapahit maka pasti ia
menamakan dirinya sebagai seorang Raja Majapahit bukan nama raja lainnya.
Dari uraian sebelumnya maka jelas tulisan Tome Pires bahwa Raja Cina
mengirim seorang putrinya ke Jawa untuk menikah dengan Batara Raja Cuda, tidak
ada kaitannya dengan silsilah Raden Fatah dari pihak ibunya. Tulisan Tome Pires
lebih sesuai dengan kejadian jauh sebelumnya yaitu pada saat terjadinya perang antara
kerajaan barat dan kerajaan timur pada tahun 1404 M. Dalam hal ini belum
72Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 75-
76. 73Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 14.
82
menemukan petunjuk yang tepat bahwa putri yang dikirim dari Cina ke kerajaan barat
atau ke kerajaan timur. Oleh sebab itu, belum bisa dikaitkan dengan riwayat lahirnya
tokoh Raden Fatah.
Pernikahan dengan Putri Cina justru terjadi jauh sebelumnya sebagaimana
yang tertulis pada tulisan Tome Pires bahwa Xaquem Darxa (Malaka) dari
pernikahannya dikaruniai putra bernama Rajapute. Rajapute merupakan nenek
moyang dari Raja-raja Pahang. Sementara kurun waktu Xaquem Darxa sezaman
dengan Batara Tumaril yang merupakan leluhur Batara Vigjaya dari Daha. Jika diurut
secara generasi maka pernikahan antara Xaquem Darxa terjadi sekitar pertengahan
abad ke 14 berdekatan dengan Raja Jawa mengirim perutusan ke Cina. Dengan
demikian, kejadian pernikahan Raja Jawa tidak bisa ditunjukkan sebagai ayah Raden
Fatah.74
Leluhur Raden Fatah terkait dengan Cina, lebih tepat kepada tulisan Raden
Fatah nomer 3 yaitu Raja Jawa dan Raja Cina tidak memiliki hubungan satu sama
lain, artinya secara nasab/silsilah. Uang tunai yang sekarang dipakai di Jawa dibawa
ke tempat ini mellaui komoditas dagang. Orang-orang Cina sudah melakukan
perdagangan dengan Jawa jauh sebelum Malaka ada. Tetapi kini sudah seratus tahun
yang berlalu sejak orang Cina datang ke tempat ini untuk berdagang. Tome Pires
menulis halaman 237 bahwa untuk pecahan kecil mereka menggunakan uang tunai
dari Cina.75 Mereka yang dimaksud adalah orang-orang Sunda Pajajaran dan Sunda
Pedalaman.
Dari pembahasan diatas bahwa Raden Fatah tidak ada kaitan secara nasab
dengan keluarga Raja Cina. Keterkaitan mereka adalah hubungan dagang
sebagaimana yang ditulis oleh Tome Pires yang dimulai sebelum Malaka berdiri.
Fakta bantahan lain bahwa ibunda Raden Fatah terkait dengan Putri Cina yaitu
kedatangan perutusan Kaisar Cina tahun 1405/1406 M. Setidaknya saat datang ke
Pulau Jawa usia putri antara 14 sampai 16 tahun, berarti Putri Cina menikah dengan
Raja Cuda berkisar tahun 1407 M, paling lambat 1408 M. Sementara mengacu pada
hitungan Tome Pires, tahun lahir Raden Fatah jatuh pada tahun 1483 M, paling
panjang 1473 M. Berarti Putri Cina saat melahirkan Raden Fatah ia sudah berumur
sekitar 80 tahun.
B. Hubungan Raden Fatah dengan Raja Hindu Jawa dan Para Wali Penyebar
Islam
1. Kerajaan Hindu Daha atau Kerajaan Jawa Pedalaman
a. Wilayah Kekuasaan
Menurut Prof. Dr. C. C Berg melalui tulisan-tulisannya telah menyatakan
pendapat bahwa wilayah Kerajaan Majapahit hanya meliputi wilayah Jawa Timur,
Bali, dan Madura.76 Berdasarkan sumber-sumber yang ada, sejak zaman keemasannya
74Tome Pires, Suma Oriental, hal 335. 75Tome Pires, Suma Oriental, hal 237.
76Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 53.
83
mengenal 21 negara daerah yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit.77
Negara-negara daerah atau provinsi itu adalah:78
1. Daha (Kadiri)
2. Jagaraga
3. Kahuripan (Jangala, Jiwana)
4. Tanjungpura
5. Pajang
6. Kembangjenar
7. Wengker
8. Kabalan
9. Tumapel (Senguruh)
10. Singhapura
11. Matahun
12. Wirabhumi
13. Keling
14. Kalingapura
15. Pandansalas
16. Paguhan
17. Pamotan
18. Mataram
19. Lasem
20. Pekembangan
21. Pawwanawwan
Adapun yang tepat mengenai luas kekuasaan Daha, sebagaimana yang
ditulis oleh Tome Pires, yaitu:
1. Cirebon, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
2. Negeri Japura, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
3. Negeri Tegal, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
4. Negeri Semarang, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
5. Negeri Demak, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
6. Negeri Tidunan, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
7. Negeri Jepara, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
8. Negeri Rembang, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
9. Tuban, dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate
10. Negeri Sidayu, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
11. Negeri Gresik, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
12. Negeri Surabaya, dibawah kekuasaan Islam Pajajaran/Majapahit
13. Negeri Gamda, dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate
77No. 1-14 disebutkan di dalam Prasasti Warininpitu (Saka 1369); No. 1, 3, 5, 7-9,
11, 12, 16, 18, 19, dan 21 disebutkan di dalam Nagarakrtagama; No. 8-11 disebutkan di dalam
fragmen Prasasti Trawulan III (catatan pertengahan abad 15). Selain itu, satu-dua buah di
antara negara-negara daerah tersebut masih disebut-sebut di dalam beberapa prasasti
Majapahit yang lain. 78Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 56.
84
14. Negeri Canjtam, dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate
15. Panarukan, dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate
16. Pajarakan, dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate
17. Negeri Blambangan, dibawah kekuasaan Hindu daha/Guste Pate
Dari ke 17 wilayah hanya ada 6 wilayah yang dikuasai oleh Guste Pate.
Artinya tidak semua wilayah Jawa Timur dibawah kekuasaan Hindu Daha/Guste Pate.
Luas kekuasaan Hindu Daha hanya sebagian wilayah Jawa Timur ditambah Pulau
Bali. Sedangkan kekuasaan Islam Sunda Pajajaran semua wilayah Jawa Tengah dan
sebagian Jawa Timur ditambah Madura. Wilayah kekuasaan Hindu Daha memang
cukup luas dan kuat tetapi tidak sekuat dan seluas kekuasaan Islam Sunda Pajajaran
wilayah timur atau Majapahit. Berbeda dengan Kerajaan Sunda Pedalaman dimana
mereka sudah menjadi kaum minoritas sehingga mereka memilih damai dan
berlindung dibawah kekuasaan Islam Sunda Pajajaran.
b. Silsilah Raja Jawa Pedalaman atau Raja Hindu Daha
Raja Jawa Pedalaman alias Batara Vojyaya teridentifikasi sebagai orang sama
dengan Dyah Girindrawarddhana Ranawijaya adalah tokoh yang berkuasa di Daha
tahun 1474-1518 M. Berdasarkan tulisan Tome Pires bahwa silsilah Batara Vojyaya79
adalah:
1. Batara Tamarill, berputra
2. Batara Caripan, berputra
3. Batara Mataram, berputra
4. Batara Sinagara, berputra
5. Batara Mataram, berputra
6. Batara Vojyaya
Menurut tulisan Tome Pires tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa
Kertabhumi adalah putra Sang Sinagara. Berarti jika mengacu Tome Pires seharusnya
bukan Sang Sinagara yang belum diketahui asal usulnya melainkan Kertabhumi yang
namanya ada di Pararaton sebagai putra dari Sang Sinagara. Kedudukan Kertabhumi
sebagai Raja Majapahit tidak lebih dari seorang raja tandingan.80 Maksudnya
Kertabhumi sebagai raja tandingan Kerajaan Hindu Daha dan Sang Sinagara adalah
Raja Hindu Daha.
Dari pembahasan tersebut maka permulaan tulisan bahwa Raden Fatah adalah
putra seorang Raja Hindu berawal dari Pararaton yang menulis Kertabhumi sebagai
putra Sang Sinagara. Padahal sesuai pembahasan BAB III, Kertabhumi adalah putra
Sunan Rumenggong alias Prabu Siliwangi IV Raja Pajajaran. Dalam silsilah nama-
nama Raja Daha, penulis tidak mengidentifikasikan dengan isi Pararaton dan Babad
Tanah Jawi karena pada kedua naskah tersebut terjadi percampuran tokoh-tokoh Raja
Sunda Pajajaran dengan Raja-raja Hindu Daha.
79Tome Pires, Suma Oriental, hal 318. 80Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
119.
85
Setelah Jepara dan Tumapel direbut Prabu Kertabhumi namun Daha tetap
berusaha ingin merebut Tumapel dan Jepara dari Pati Unus 1. Pati Unus 1 telah
diangkat menjadi raja di wilayah Majapahit (Pajajaran Timur). Menurut salah satu
prasasti-prasasti girindrawarddhana yaitu Prasasti Ptak tahun 1486 M yaitu yudha
lawaning majapahit artinya adanya peperangan melawan Majapahit.81 Bahkan sampai
pada masa pemerintahan Pati Unus 2, Daha terus menyerang Demak dan Jepara.
Sebagaimana tulisan Tome Pires, pada saat Pate Onus, saudara tirinya datang
untuk berperang 1512 M. Ia memiliki banyak prajurit perang. Setidaknya 30.000
orang di Jawa dan 10.000 orang di Palembang. Ia terus menerus berperang dengan
Guste Pate dan penguasa Tuban.82 Adapun alasan Daha tetap berusaha merebut Jepara
menurut Tome Pires, yaitu:
1. Pelabuhan Jepara berbatasan terletak di kaki gunung yang besar dan tinggi
bernama Muria. Negara Jepara berbatasan dengan Tidunan, di satu sisi
dengan Rembang. Jepara memiliki sebuah teluk dengan pelabuhan yang
indah. Di depan pelabuhan ini terdapat 3 pulau yang tampak seperti Upeh,
kapal-kapal besar bisa masuk ke wilayah ini. Orang-orang melewati Jepara
akan bisa melihat keseluruhan kota. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan
terbaik serta terbaik, yang telah kita bahas sejauh ini. Semua orang yang
hendak pergi ke Jawa dan Maluku akan singgah ke negeri Jepara.83
2. Jepara jelas menjadi kunci dari seluruh Jawa mengingat letaknya di puncak
dan tengah Pulau Jawa. Jarak dari tempat ini ke Cirebon sama dengan jarak
ke Gresik. Tempat ini berupa pelabuhan sehingga cocok untuk berdagang,
kabarnya dari tempat inilah pedagang-pedagang mulai tersebar ke berbagai
tempat termasuk Gresik.84
Dari kedua alasan tersebut maka jelas bahwa Jepara adalah jantung semua
kota yang ada di wilayah timur Kerajaan Islam Sunda Pajajaran, karena memiliki
pelabuhan sebagai kunci untuk semua orang yang hendak ke Jawa dan Maluku harus
transit terlebih dahulu ke Jepara. Jepara terletak di sebelah barat pegunungan yang
dahulu adalah Pulau Muria. Jepara mempunyai pelabuhan yang aman yang semula
dilindungi oleh 3 pulau kecil. Letak pelabuhan Jepara sangat menguntungkan bagi
kapal-kapal dagang yang lebih besar, yang berlayar lewat pantai utara Jawa menuju
Maluku dan kembali ke barat. Ketika jalan pelayaran pintas di sebelah selatan
pegunungan ini tidak lagi dapat dilayari dengan perahu besar karena telah menjadi
dangkal oleh endapan lumpur, maka Jepara menjadi Pelabuhan Demak. Kedua kota
itu merupakan dwitunggal yang perkasa. Yang menjadi penghubung antara Demak
dan daerah pedalaman di Jawa Tengah ialah Sungai Serang yang sekarang bermuara
di Laut Jawa antara Demak dan Jepara.85
81Hasan Djafar, Masa Akhir Majaphit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 14. 82Tome Pires, Suma Oriental, hal 259. 83Tome Pires, Suma Oriental, hal 260-261. 84Tome Pires, Suma Oriental, hal 262. 85H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 38-39.
86
Maka dari itu, suatu keharusan Daha untuk merebut Jepara sebagai jantung
ekonomi Pulau Jawa dan beberapa kali melakukan penyerangan ke Jepara dan Demak.
Pelabuhan Jepara diperebutkan oleh 2 kerajaan tersebut. Menurut Thomas Stamford
Raffles didalam bukunya The History of Java bahwa Kerajaan Majapahit diruntuhkan
oleh Demak pada Saka 1400 (1478 M), pendapat itu didasarkan atas keterangan yang
terdapat dalam kitab sejarah tradisional yaitu Serat Kanda.86 Menurut Hasa Djafar
bahwa dari bukti-bukti sejarah yang ada dapat diketahui bahwa pada waktu itu
Kerajaan Majapahit ternyata masih ada bahkan masih berdiri untuk beberapa waktu
yang lama.87 Akan tetapi, dalam tulisan Tome Pires bahwa Guste Pate selalu maju
dalam perang, ia selalu berperang dengan orang Moor di pesisir pantai, terutama
dengan peguasa Demak.88 Kerajaan Hindu Daha yang berkali-kali melakukan
penyerangan ke Majapahit tepatnya di Jepara, saat itu menjadi ibukota Kerajaan Islam
Sunda Pajajaran wilayah timur.
Kerajaan Hindu Daha terletak di pedalaman yaitu selatan Pulau Jawa. Dalam
tulisan Tome Pires bahwa tempat Tuban juga menjadi pelabuhan terdekat menuju
Kota Daha (Daya), tempat dimana Guste Pate tinggal. Daya atau yang kemudian dieja
sebagai Daha. Dalam Encylopedia van Nedelandsch-Indie menyatakan bahwa Daha
merupakan ibukota dari Imperium Hindu di Jawa. Letaknya ada di suatu tempat antara
Ponorogo dan Madiun yang memiliki keterkaitan dengan sisi barat Pegunungan
Willis. Menurut Crawfurd pada bagian Daha meyakini bahwa kerajaan kuno di Jawa
ini memiliki keterkaitan dengan provinsi yang kini dikenal sebagai Kadiri, yang
terletak di sisi timur pegunungan tersebut. Menurut Campbell, mengidentifikasikan
Daha dengan Kediri. Selain itu, sebuah peta bertanggalkan 31 Desember 1889
diterbitkan oleh Verbeck memunculkan Djaha, yakni sebuah tempat di mana
ditemukan berbagai sisa bangunan dan prasasti. Letaknya 8 mil di barat laut kota
Kediri. Tuban, tentunya merupakan pelabuhan yang paling dekat dengan Kediri.
Letaknya ada di pantai utara Jawa. Pelabuhan ini terbentang 55 mil ke arah utara di
sepanjang negeri yang datar ini. Tuban berjarak 49 mil dari Daha. Hal ini
mengkonfirmasi apa yang dikatakan Pires bahwa perjalanan dari Tuban ke Daha
memakan waktu 2 hari jika segalanya lancar dengan mengendarai kereta di jalan
darat.89
Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya adalah penguasa kerajaan jawa yang
terdiri dari Jangala dan Kadiri.90 Dalam sebuah tulisan Dr. F.D.K Bosch yang berjudul
De Oorkonde van Sendang Sedati diterbitkan pada 1922, tulisan ini mengenai Prasasti
Pamintihan dari tahun Saka 1395 (1473 M). Prasasti ini dikeluarkan oleh
Sinhawikramawarddhana Dyah Suraprabhawa, di dalam prasastinya ia disebutkan
sebagai Penguasa tunggal di bumi Jawa yang terdiri dari Jangala dan Kadiri.91
86Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
126. 87Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
125. 88Tome Pires, Suma Oriental, hal 245. 89Tome Pires, Suma Oriental, hal 264. 90Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
108. 91Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 36.
87
Menurut salah satu prasasti-prasasti Girindrawarddhana yaitu Prasasti Ptak tahun
1486 M yaitu yudha lawaning majapahit artinya adanya peperangan melawan
Majapahit. Di dalam Prasasti Trailokyapuri I dan IV, Girindrawarddhana Dyah
Ranawijaya disebutkan sebagai Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatiktapura Jangala
Kadiri.92 Menurut Krom, Daha sama dengan Kediri dan Daha adalah tempat asalnya.93
Selain itu, dalam Prasasti Trailokyapuri I dan II menyebutkan adanya
penyelenggaraan upacara sraddha untuk memperingati 12 tahun mangkatnya Sri
Paduka Bhattara rin Dahanapura.94
Mengacu kepada prasasti-prasasti disesuaikan dengan uraian Tome Pires,
maka Kerajaan Batara Vojyaya dan Guste Pate adalah Kerajaan Hindu Daha bukan
Kerajaan Majapahit. Hal tersebut ditegaskan dari Prasasti Ptak bahwa
Girindrawarddhan dari Daha mengadakan peperangan melawan Majapahit.
Berdasarkan bukti-bukti yang telah dijelaskan diatas teridentifikasikan bahwa Batara
Vojyaya adalah orang yang sama dengan Girindrawarddhana yang merupakan musuh
dari Demak dan Majapahit (Pajajaran Timur).
c. Prabu Cakrabuana III dan Batara Vojyaya
Menurut Tome Pires mengenai Raja Daha yaitu Batara Vojyaya dan patihnya
Guste Pate bernama Pate Amdura, tidak memiliki keterkaitan keluarga dengan Raden
Fatah. Tome Pires menuliskan bahwa Raden Fatah alias Pate Rodim memiliki
keterkaitan dengan Pati Unus dan keluarga Walisongo di Gresik. Sebaliknya Tome
Pires menulis bahwa Raja Pedalaman sebagai musuh besar Raden Patah. Dengan
demikian, tidak bisa menyimpulkan bahwa Batara Vojyaya sebagai tokoh ayah Raden
Fatah dan disamakan dengan tokoh Brawijaya.
Raden Fatah putra Brawijaya yang Hindu mengacu kepada Serat Kanda
bahwa Demak memberontak kepada Majapahit. Senopati yang memimpin tentara
Demak adalah Sunan Kudus. Sunan Kalijaga menasehati Raden Fatah agar jangan
menggunakan kekerasan terhadap Raja Majapahit. Serbuan tentara Demak berhasil.
Prabu Brawijaya mengungsi ke Sengguruh, dalam serbuan yang kedua kalinya, Prabu
Brawijaya melarikan diri ke Bali. Peristiwa itu terjadi pada tahun Saka: sirna ilang
kertaning bumi, yakni pada tahun 1400 atau tahun 1478 M.95
Akan tetapi, sebagaimana yang telah dibahas bahwa Raden Fatah lahir tahun
1473 M. Berarti pada saat penyerangan Demak ke Majapahit versi Hindu, usia Raden
Fatah adalah 5 tahun. Pernyataan Serat Kanda tidak dapat diterima karena diusia 5
tahun Raden Fatah sudah memimpin pasukan dan diangkat menjadi Sultan Demak.
Apalagi menurut hitungan Tome Pires bahwa tahun lahir Raden Fatah yaitu 1483 M,
berarti sebelum lahir Raden Fatah sudah memimpin pasukan Demak untuk menyerang
ayahnya.
92Hasan Djafar, Masa Akhir Majaphit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 14. 93Hasan Djafar, Masa Akhir Majaphit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 107. 94Hasan Djafar, Masa Akhir Majaphit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal 19. 95Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara
Islam di Nusantara, Yogyakarta: LKIS, 2005, hal 93.
88
Pada 6 Januari 1514, Rui de Brito, Kapten Malaka menulis surat kepada Raja
Manuel dan Alfonso de Albuquerque untuk memberitahukan bahwa pada Maret 1513,
ia telah mengirimkan satu armada yang terdiri atas empat kapal ke Jawa, guna
mengumpulkan rempah-rempah. Armada ini berada di bwah komando Joao Lopes de
Akvim. Tiga diantara kapalnya (navios) adalah Sao Cristovao, Santo Andre, dan
sebuah caravel, masing-masing dipimpin oleh Francisco de Melo, Martin Guedes, dan
Joao Silveira. Tome Pires, juru tulis bagi pialang sekaligus akuntannya, pergi bersama
armada ini sebagai pialang, sekaligus pengawas muatan. Mengingat saya telah
berhasil meneliti dan menginvestigasi, menguji kebenaran fakta-fakta yang saya
ketahui dengan banyak orang-orang, kita dapat melihat bahwa Pires mengunjungi
pantai utara kepulauan tersebut setidaknya dari Cirebon ke Gresik.96 Tome Pires
menuliskan bahwa saat ini ia (Pate Rodim) berusia setidaknya 30 tahun. 97
Maka dari itu, tulisan dari babad dan serat tentang Raden Fatah menyerang
ayahnya ditahun 1478 M, tertolak. Sebagaimana pendapat J.G. de Casparis bahwa
tulisan mengenai penaklukkan Majapahit yang terjadi pada tahun 1478 M oleh Kediri
harus hilang dari catatan sejarah Majapahit. Tulisan mengenai terjadinya penyarangan
Kediri ke Majapahit tahun 1478 M bertumpu kepada salah penafsiran mengenai tokoh
Bhattara ring Dahanapura yang telah dilakukan oleh Krom.98 Krom membantah
penaklukkan Majapahit tahun 1478 M oleh pasukan Demak, menurutnya penaklukkan
Majapahit tahun 1478 M adalah Kerajaan Hindu Kediri, maka Krom tetap berasumsi
bahwa Majapahit adalah Kerajaan Hindu.99 Menurut analisis kami seharusnya tulisan
tentang penaklukkan Majapahit oleh Kediri atau Demak tahun 1478 M harus dihapus
dalam sejarah Majapahit dan Demak dari catatan sejarah Indonesia.
Menurut Tome Pires bahwa ayah Pate Rodim adalah seorang kesatria dan
bijak dalam mengambil keputusan sedangkan kakek Pate Rodim berasal dari Gresik.
Pate Rodim memiliki hubungan yang erat dengan para penguasa di Jawa, mengingat
semua putri dari ayah dan kakeknya menikah dengan pate-pate tertinggi. Beliau
sangat berkuasa sehingga mampu menaklukkan seluruh wilayah Palembang, Jambi,
Kepulauan Manomby, dan banyak pulai lainnya. Penaklukkan ini dilakukan dengan
melawan Tanjungpura dan selanjutnya, semua wilayah tersebut tunduk padanya. Pate
Rodim sangat dihormati. Beras dan bahan makanan lain yang berasal dari wilayahnya
dikirimkan ke Malaka. Dulu, ayahnya mampu mengumpulkan 40 jung dari
wilayahnya.100
Pembahasan tentang ayah Pate Rodim yang berkaitan dengan pate-pate
tertinggi di Pulau Jawa dan ayah Pate Rodim tokoh yang sangat berkuasa. Jika
dirujukkan ke tokoh Batara Vojyaya, maka tidak tepat karena tidak ada catatan yang
menuliskan bahwa Batara Vojyaya memiliki kaitan nasab atau silsilah dengan Pate
96Tome Pires, Suma Oriental, hal XXXVII. 97Tome Pires, Suma Oriental, hal 258. 98Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
109. 99Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
107. 100Tome Pires, Suma Oriental, hal 257-258.
89
Rodim. Dan juga Batara Vojyaya hanya menguasai Kerajaan Jawa Pedalaman alias
Kerajaan Hindu Daha yang hanya menguasai sebagian wilayah Jawa Timur dan Bali.
Menurut Tome Pires, ayah Pate Rodim dahulunya mengumpulkan kapal jung
sebanyak 40 buah kapal. Sedangkan Batara Vojyaya kapal jung yang ia miliki101 yaitu:
1. Pelabuhan orang-orang Moor artinya pelabuhan yang dibawah kekuasaan
Daha tetapi bisa dipakai orang-orang Moor misal Tuban, Tuban yang menjadi
wilayah kekuasaan Daria Tima de raja. Pelabuhan yang bisa kerjasama
dengan Kerajaan Pedalaman misalnya Pelabuhan Surabaya.
2. Pelabuhan orang-orang pagan, artinya pelabuhan tersebut mutlak dikuasai
oleh Kerajaan Pedalaman, misal Blambangan yang dikuasai oleh Pate Pimtor.
3. Pelabuhan milik putra Guste Pate, artinya pelabuhan tersebut mutlak
dikuasasi oleh Kerajaan Hindu Daha. Gamda sekitar Pasuruan yang dikuasai
oleh putra Guste Pate.
Dari ketiga hal tersebut tidak ada petunjuk bahwa Batara Vojyaya memiliki
banyak jung dan penguasaan pelabuhan yang banyak. Jika ayah Pate Rodim
dirujukkan kepada Raja Sunda Pedalaman bahwa di wilayah Sunda Barat dan tengah
memiliki 5 pelabuhan dan 2 di antaranya adalah pelabuhan yang sangat besar yaitu
Pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten, sedangkan pelabuhan yang dimiliki pagan
hanya Pelabuhan Cimanuk. Di wilayah Pajajaran Timur memiliki pelabuhan pusat
Pulau Jawa yaitu Pelabuhan Jepara, belum termasuk pelabuhan-pelabuhan di luar
Jawa misalnya Madura, Palembang dan lainnya.
Dengan demikian yang dimaksud ayah Pate Rodim memiliki 40 kapal jung
yang berasal dari wilayahnya, arti dari berasal dari wilayahnya ditujukkan kepada
wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Sunda Pajajaran, yang sebelumnya beribukota di
Pakwan Pajajaran. Adapun arti dari kalimat Pate Rodim mempunyai kaitan dengan
pate-pate tertinggi di Pulau Jawa bahwa Pate Jawa adalah Pate Pajajaran
sebagaimana sebutan orang-orang Sunda Pedalaman terhadap Demak dan Cirebon.
2. Hubungan Raden Fatah dengan Para Wali Penyebar Islam
a. Hubungan Kekerabatan Raden Fatah dengan Para Penguasa Pantai Utara
Jawa
Tome Pires tidak menuliskan kekerabatan antara pate-pate pagan, Batara
Vojyaya, dan Guste Pate dengan Pate Rodim alias Raden Fatah. Sedangkan tulisan
mengenai hubungan kekerabatan antara pate-pate moor dengan Pate Rodim alias
Raden Fatah begitu detail dan rinci102 yaitu:
1. Negeri Cirebon terletak di samping Sunda. Penguasanya dikenal dengan Lebe
Upa, ia merupakan bawahan Pate Rodim, tuan Negeri Demak. Berdasarkan
catatan-catatan sejarah bahwa penguasa Cirebon pada masa Raden Fatah
adalah Sunan Gunung Jati. Dengan demikian nama Lebe Upa terujukkan
sebagai tokoh yang sama dengan Sunan Gunung Jati. Selain itu, pada Babad
101Tome Pires, Suma Oriental, hal 250-251.
102Tome Pires, Suma Oriental, hal 255-271.
90
Cirebon ditulis bahwa Penguasa Upeh Malaka adalah mertua Pati Unus 2.
Maka jelas keterkaitan Sunan Gunung Jati alias Lebe Upa dengan Raden
Fatah sudah tidak dapat dibantah sebab kakak perempuan Raden Fatah,
berlainan ibu adalah salah satu istri Sunan Gunung Jati I yaitu Nyai Mas
Pakuwati binti Prabu Cakrabuana III.
2. Pate Japura yang berkuasa di tempat ini merupakan kstaria, ia adalah sepupu
Pate Rodim. Ia selalu mematuhi semua yang dititahkan oleh Pate Rodim, sang
tuan Negeri Demak. Ia sudah seperti kapten di kawasan tersebut. Penulis
sudah menjelaskan keterkaitan keluarga antara Pate Rodim alias Raden Fatah
dengan Penguasa Japura alias Ki Ageng Japura.
3. Pate Tegal ini merupakan paman dari Pati Unus, ia tunduk terhadap penguasa
Demak.
4. Pate Semarang dikenal sebagai Pate Memet. Ia merupakan ayah mertua Pate
Rodim penguasa Demak.
5. Pate Tidunan yang berkuasa di tempat ini dikenal dengan nama Pate orob. Ia
adalah paman Pati Unus, saudara laki-laki ayahnya. Pati Unus berkeinginan
untuk menyatukan segala yang tersisa dari kekayaan yang dimiliki ayahnya
dan Pate Rodim. Ia pun memutuskan untuk merebut Malaka dari tangan
rajanya pada waktu itu.
6. Pate Rembang dikenal dengan nama Pate Murob. Ia adalah paman Pati Unus.
Pati Unus adalah anak laki-laki dari saudara perempuannya.
7. Negeri Sidayu dikenal dengan nama Pate Amiza. Ia merupakan keponakan
dari Pate Murob, penguasa Rembang dan ia merupakan sepupu tertua Pati
Unus dan sepupu kedua Pate Rodim.
8. Negeri Gresik. di Gresik terdapat 2 kota yang dipisahkan oleh sungai, kota
yang satu penguasanya bernama Pate Cucuf (Pate Yusuf) yang asal usulnya
berasal dari Melayu. Sedangkan kota lainnya dipimpin oleh Pate Zeynall. Pate
Zeynall merupakan seorang kesatria dan yang tertua di antara pate-pate lain
di Jawa. Ia memiliki hubungan keluarga dengan banyak pihak. Ia merupakan
paman dari Pate Amiza dari Sidayu dan Pati Unus, rekan prajurit Pate Rodim
dan kini ia juga menjadi rekan seprajurit bagi putra Pate Rodim.
91
Maulana Malik Ibrahim
Sunan Rumenggong Sunan Ampel
Cakrabuana III Nyai Mas Aci Debaya Sunan Lamongan
Raden Fatah Pate Orob
RT Bentang X Pati Unus 1 X Halimah Pate Murob Fulan Pate Zaenal
Raden Yunus Sultan Trenggono Putri X Pati Unus 2 X Andangsari Pate Amiza Hasanudin
Abdullah Arya Athoillah Kusumadiningrat Khodijah X Mwl Yusuf
(Panembahan Agung)
Ahmad Jalaludin Kusumadiningrat Mwl. Muhammad
(Pang. Kusuma Surya Adiningrat)
M. Hasan Ainul Yaqin
(Sunan Cibuni Agung)
P. Malik Demang Raksayuda
(Entol Wiraha Adiningrat)
Raden Wirawangsa
(Tumenggung Wiradadaha 1 Sukapura)
Tome Pires menulis bahwa Pati Unus (Pati Unus 2) dengan sebutan saudara
tiri103 maka pada bagan diatas bisa terbuktikan bahwa Pati Unus 2 memiliki ibu
bernama Halimah, istri ke 2 Pati Unus 1. Sedangkan istri pertama Pati Unus 2 adalah
Nyai Mas Bentang, beliau adalah saudara perempuan dari Raden Fatah namun lain
ibu. Dengan demikian Pati Unus 1 adalah saudara ipar dari Raden Fatah. Pada
beberapa catatan sejarah Demak bahwa Raden Fatah adalah menantu dari Sunan
Ampel padahal secara generasi lebih sesuai jika Raden Fatah menikah dengan cucu
perempuan dari Sunan Ampel.104 Dengan demikian tokoh bernama Pate Memet
merupakan penguasa Semarang diduga adalah putra dari Sunan Ampel. Dari bagan 2
tadi adalah benar jika Tome Pires menuliskan bahwa Raden Fatah memiliki hubungan
yang erat dengan penguasa Jawa.105 Maka dari itu, setiap pate yang berkaitan dengan
Pati Unus 1 dan Pati Unus 2 pasti berkaitan dengan Raden Fatah juga.
Tome Pires menuliskan bahwa para pate atau penguasa bukanlah orang Jawa
asli yang berasal dari negeri ini, melainkan berdarah Cina, Persia, Keling, dan
berbagai negeri yang sudah disebutkan di atas (Arab, Gujarat, Bengal, Melayu).106
Terkait dengan hubungan yang lebih jauh, harus ada pembahasan khusus tentang
berdarah Cina tetapi bukan keturunan Cina asli sebagaimana bangsa Moor yang
bermukim di Nusantara, melainkan orang Cina pendatang dari Tarim Yaman yang
103Tome Pires, Suma Oriental, hal 258. 104Hamka, Sejarah Umat Islam Pra Kenabian hingga Islam di Nusantara, hal 560. 105Tome Pires, Suma Oriental, hal 257. 106Tome Pires, Suma Oriental, hal 254.
92
merupakan penyebar Islam di daratan Cina. Hal tersebut diuraikan oleh Ahmad Baso,
yaitu:
1. Dalam hal ini jangan kemudian ditarik lebih jauh dari sumber-sumber Cina
bahwa orang-orang Cina punya peran berlebihan dalam Islamisasi Nusantara.
Hingga menyebut para Walisongo itu hampir semua keturunan Cina hanya
karena nama-nama mereka ditulis dalam tulisan Cina dalam satu sumber
Melayu asal klenteng Semarang. Jaringan Ulama Waliyullah dimana
transmisi pengetahuan Islam mengalir di satu pihak dari para ulama-
waliyullah dari Mekkah, Baghdad, Hadramaut kepada murid-murid Indonesia
mereka.107
2. Sailan, Male (Maladewa), dan Calliana (Kali atau Ma’bar dalam sebutan
orang Arab) adalah diantara pusat sirkuit lalu lintas perdagangan global
Samudera Hindia yang menghubungkan negeri Arab hingga Cina. Sejak awal
tahun 300 M orang-orang Arab selatan sudah membangun permukiman atau
koloni-koloni di sepanjang jalur emas itu. Ketika agama Islam mulai merayap
ke segenap penjuru dunia, orang-orang Arab terutama dari Hadramaut tinggal
memanfaatkan jaringan lama ini untuk proyek Islamisasi.108
3. Posisi jaringan komunitas Al Jailani sekaligus jaringan dagang tergambar
dalam beberapa nama asal usul penghuni makam dan prasasti Arab dan
bahasa lokal (paling dini dari tahun 1171 M) di kota Guangzhou (Canton):
Yaman, Hamdan, Siraf, Shiraz, Bukhara, Khwarazm, Khurasan, Isfahan,
Tabriz, dan Gilan (Jilan). Dari jaringan kota Mekkah, Baghdad, Jailan, dan
Mirbath itulah para keluarga Alawiyyin memperoleh momentum pas karena
volume perdagangan dunia sedang meningkat pesat di Samudera Hindia dan
proses Islamisasi. Mereka memainkan peran startegis dalam menguasai jalur
ekonomi dan pengislaman.109
4. Di Benggala tokoh-tokoh agamanya di abad 13-14 berasal dari Asia Tengah
seperti dari Tabriz, negeri Arab, suku Quraisy, dan Yaman. Jaringan
Benggala menjadi pangkalan Sayyid Abdul Malik Azmatkhan di abad 13
yang menurunkan Syekh Jumadil Kubro dan para Walisongo.110
Menurut De Graaf dan Pigeaud bahwa mungkin Tome Pires yang hidup
sezaman cukup tepat menguraikan peristiwa sampai kira-kira tahun 1515 M dalam
bukunya Suma Oriental. Tetapi kelanjutan sejarahnya tidak dialaminya. Mungkin ia
terlalu banyak menyoroti pribadi Pati Unus, tokoh yang paling banyak dihubungi
orang Portugis pada waktu itu. Dalam cerita tradisi Jawa dari abad XVII dan XVIII,
baik dari Jawa Timur dan Mataram maupun dari Jawa Barat, telah terjadi kekacauan
antara cerita mengenai raja-raja Demak dan Jepara yang masih ada ikatan keluarga itu
107Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, Jakarta: Pustaka Afid, 2018, hal 45 108Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, hal 81-82. 109Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, hal 85-86. 110Ahmad Baso, Islamisasi Nusantara: Dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, hal 109.
93
dan yang hidup dalam dasawarsa-dasawarsa pertama abad XVI. Babad Jawa dari
abad-abad kemudian sama sekali melupakan pejuang muda yang gagah berani
melawan kekuasaan bangsa Portugis di Malaka. 111
b. Hubungan Erat Raden Fatah dengan Tokoh Walisongo
Dari sumber-sumber yang telah kami bahas sebelumnya, terdapat hubungan
kekerabatan yang erat antara Raden Fatah dengan beberapa tokoh Walisongo. Adapun
kekerabatan tersebut, yaitu:
1. Hubungan Raden Fatah dengan Sunan Kalijaga.
Silsilah Arya Baribin yang teridentifikasikan sebagai orang yang sama
dengan Raden Fatah. Raden Fatah alias Arya Baribin adalah putra dari Arya
Galuh alias Prabu Cakrabuana III alias Syeikh Haji Abdullah Iman.
Sedangkan pada Kitab Ahlal Musamaroh tercatat bahwa Sunan Kalijaga
adalah putra dari Arya Teja bin Arya Galuh. Maka jelas Sunan Kalijaga
adalah keponakan Raden Fatah, hanya dalam hal usia tidak berjauhan. Arya
Teja ditulis sebagai Adipati Tuban sehingga penulis sejarah
mengidentifikasikan Arya Teja112 sebagai orang yang sama dengan Pate Vira
alias Anatimao de Raja, yaitu Adipati Tuban zaman Guste Pate.113 Padahal
jika mengikuti alur riwayat dan kekerabatan, Tome Pires tidak menulis bahwa
Pate Vira memiliki kekerabatan dengan Raden Fatah. Maka menurut analisis
kami bahwa Arya Teja diangkat menjadi Adipati Tuban setelah tahun 1517
M, Tuban menjadi bawahan Demak. Berarti Arya Teja bukan orang yang
sama dengan Pate Vira. Sehubungan dengan tulisan Tome Pires bahwa
Demak terus menerus berperang dengan Guste Pate dan penguasa Tuban.114
2. Hubungan Raden Fatah dengan Sunan Gunung Jati.
Keduanya merupakan cucu dari Sunan Rumenggong, bedanya Raden Fatah
cucu dari jalur laki-laki sedangkan Sunan Gunung Jati I cucu dari jalur ibu
yang bernama Syarifah Mudaim alias Nyai Mas Rarasantang. Gelar syarifah
menunjukkan bahwa Nyai Mas Rarasantang adalah seorang syarifah.115
Itulah hubungan keluarga antara Raden Fatah dengan tokoh-tokoh Walisongo
dan sudah tentu beliau berkerabat dengan sunan-sunan lainya yaitu Sunan Giri, Sunan
Ampel, Sunan Bonang, Sunan Drajat, dan Sunan Muria putra dari Sunan Kalijaga.
111H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 52. 112Tome Pires, Suma Oriental, hal 251. 113Tome Pires, Suma Oriental, hal 263. 114Tome Pires, Suma Oriental, hal 258. 115Ringkasan Babon Sukapura yang disusun oleh Tim Yayasan Wasiat Karuhun
Tasikmalaya.
94
C. Berdirinya Kesultanan Demak
1. Portugis merebut Malaka
Eropa bukanlah kawasan yang paling maju di dunia pada awal abad ke 15 dan
juga bukan merupakan kawasan yang paling dinamis. Kekuatan besar yang sedang
berkembang di dunia adalah Islam. Pada tahun 1453 M orang-orang Turki Ottoman
menaklukkan Konstantinopel dan di ujung timur dunia Islam agama ini berkembang
di Indonesia dan Filipinan. Akan tetapi, orang-orang Eropa terutama orang-orang
Portugis mencapai kemajuan-kemajuan dibidang teknologi tertentu yang akan
meibatkan bangsa Portugis dalam salah satu petualangan mengarungi samudera yang
paling berani sepanjang zaman. Dengan bekal pengetahuan geografi dan astronomi
yang bertambah baik maka bangsa Portugis telah menjadi mualim-mualim yang
semakin mahir.116
Atas dorongan Pangeran Henry dan para pelindung lainnya, para pelaut dan
petualang Portugis memulai usaha pencarian emas, kemenangan dalam peperangan,
dan suatu jalan untuk mengepung lawan yang beragama Islam dengan menyusuri
pantai barat Afrika. Mereka juga berusaha mendapatkan rempah-rempah, yang dalam
hal ini berarti mendapatkan jalan ke Asia dengan tujuan memotong jalur pelayaran
pada pedagang Islam, yang memulai tempat penjualan mereka di Venesia di Laut
Tengah memonopoli impor rempah-rempah ke Eropa. Rempah-rempah merupakan
soal kebutuhan dan cita rasa. Pada masa itu bangsa-bangsa Eropa sangat
membutuhkan rempah-rempah dari Asia terutama Indonesia, misalnya cengkih, lada,
buah pala, dan bunga pala. Oleh karena itu, kawasan itulah yang menjadi tujuan utama
Portugis.117
Pada tahun 1487 Bartolomeu Dias mengitari Tanjung Harapan dan dengan
demikian dia telah memasuki perairan Samudra Hindia. Pada tahun 1497 Vasco da
Gama sampai di India. Pada tahun 1503 Alfonso de Albuquerque berangkat menuju
India dan pada tahun 1510 dia menaklukkan Goa di pantai barat yang kemudian
menjadi pangkalan tetap Portugis. Alfonso de Albuquerque (1459-1515) merupakan
panglima angkatan laut yang terbesar pada masa itu. Pada tahun 1510, sasaran utama
Portugis adalah menyerang ujung timur perdagangan Asia di Malaka. Pada tahun
1509 raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menjalin hubungan
persahabatan dengan penguasanya yaitu Sultan Mahmud Syah. Namun komunitas
dagang Islam Internasional yang ada di kota itu meyakinkan Mahmud bahwa Portugis
adalah ancaman berat. Maka Mahmud melawan dan menyerang empat kapal Portugis.
Pada bulan April 1511, Alfonso melakukan pelayaran dari Goa menuju Malaka. Di
Malaka terjadi peperangan sepanjang bulan Juli dan awal Agustus 1511 dan
dimenangkan oleh Portugis. Portugis kini telah menguasai Malaka tetapi tidak
menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana.118
116M.C Ricklefs, Sejarah Indonesi Modern, hal 31. 117M.C Ricklefs, Sejarah Indonesi Modern, hal 32. 118M.C Ricklefs, Sejarah Indonesi Modern, hal 33-34.
95
2. Raden Fatah dimata Bangsa Portugis
Dalam surat dari Jorge de Albuquerque Gubernur di Malaka kepada Raja
Portugis tanggal 8 Januari 1515 bahwa 3 orang dari Jawa yang membahayakan
penguasa Portugis di Malaka119 yaitu:
1. Pati Quitis, beliau Pati Unus 1 yang memiliki nama lain Qais Alaydrus
2. Pati Amoz, beliau Pati Unus 2
3. Pate Rodim, beliau Raden Fatah
Dengan adanya surat ini, jelas bahwa tokoh Pate Rodim alias Raden Fatah adalah
tokoh yang sangat diperhitungkan oleh penguasa-penguasa Portugis karena sangat
membahayakan kedudukan Portugis di Malaka dan menghambat usaha Portugis untuk
menguasai Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
Menurut Tome Pires bahwa Pate Zaenal dari Gresik, ia berkata apabila
Kapten Mayor Alfonso de Albuquerque berdamai dengan penguasa Demak, maka
semua penguasa di Jawa diharuskan untuk berdamai pula. Ia berkata bahwa penguasa
Demak mewakili seluruh penjuru Jawa.120 Dengan demikian, jika ingin menaklukkan
Jawa maka harus terlebih dahulu menaklukkan Demak yang penguasanya saat itu
adalah Pate Rodim alias Raden Fatah.
3. Raden Fatah diangkat menjadi Sultan Demak
Kesultanan Demak berdiri sekitar tahun 1500 M121 artinya bisa lebih dari
tahun tersebut. Sumber lain menulis bahwa berdiri Kesultanan Demak ditandai
dibangunnya Masjid Agung Demak. Sedangkan dalam Babon Sukapura
pembangunan masjid terjadi pada 1 Syafar tahun Saka 1428 atau 1506 M.
Dari uraian tersebut bahwa Raden Fatah merubah sistem pemerintahan
Kerajaan Islam Pajajaran menjadi bentuk Kesultanan. Ketika Kerajaan Islam
Pajajaran pemimpin tertinggi disebut Hyang sedangkan ketika menjadi kesultanan
disebut Sultan. Untuk wilayah-wilayah tertentu Raden Fatah tidak memaksakan raja
wilayah untuk mengikuti pusat. Misalnya raja bawahan Sunda Tengah yang
dahulunya disebut Pakwan Pajajaran tetap menggunakan gelar Prabu sementara
Cirebon mengubah dengan gelar Sultan.
Tatanan dalam pengambilan keputusan juga diubah yang mana ketika
Kerajaan Islam Pajajaran semua keputusan berada di raja, sedangkan setelah berubah
menjadi Kesultanan maka Raden Fatah menyerahkan keputusan kepada Dewan Wali
atau Walisongo. Semua keputusan sebelumnya dimusyawarahkan dan diputuskan
melalui hasil musyawarah.
Pemimpin para wali saat itu adalah Sunan Gunung Jati I alias Syarif
Hidayatullah dari Cirebon dan menurut Kitab Al Fatawi yang melantik Raden Fatah
menjadi sultan adalah Sunan Gunung Jati I. Dengan demikian, Raden Fatah adalah
119Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-
Negara Islam Di Nusantara, hal 117. 120Tome Pires, Suma Oriental, hal 271. 121Soedjipto Abimanyu, Babad Tanah Jawi Terlengkap dan Terasli, hal 295.
96
tokoh pertama di Nusantara sebagai pelopor dalam hal semua tatanan pemerintahan
melibatkan para alim ulama.
4. Pemicu terjadinya Perang Malaka
Pada awalnya imperialisme barat dilahirkan dari Perjanjian Tordesilas
Spanyol 7 Juni 1494 M. Suatu perjanjian yang dibuat oleh Kerajaan Katolik Portugis
dan Kerajaan Katolik Spanyol. Dipimpin oleh Paus Alexander VI, 1492-1503 M.
Dalam perjanjian ni, Paus Alexander VI memberi kewenangan kepada Kerajaan
Katolik Portugis untuk menguasai dunia belahan timur dan Kerajaan Katolik Spanyol
menguasai dunia belahan barat. Adapun tujuan dari imperialisme, yaitu Gold-emas
dengan menjajah akan memperoleh kekayaan yang dirampas dari tanah jajahan,
Gospel-pengembangan agama di tanah jajahan akan dikembangkan agama Katolik,
dan Glory-kejayaan. Praktiknya bertentangan dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan. Perbudakan, penindasan, dan pemusnahan suatu bangsa dinilai benar.122
Pada bulan April 1511 Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa Portugis
menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal.
Peperangan terjadi sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Pihak Portugis menang
dan Malaka berhasil ditaklukkan. Albuquerque tinggal di Malaka sampai bulan
November 1511. Selama di Malaka dia mempersiapkan pertahanan guna menahan
setiap serangan dan memerintahkan supaya kapal-kapal yang pertama melakukan
pelayaran mencari Kepulauan rempah-rempah.123
Portugis kini telah menguasai Malaka, tetapi segera menjadi jelas bahwa
mereka tidak menguasai perdagangan Asia. Mereka tidak pernah dapat mencukupi
kebutuhannya sendiri dan sangat tergantung pada para pedagang pamasok bahan
makan dari Asia seperti penguasa Melayu sebelumnya di Malaka. Mereka kekurangan
dana dan sumber daya manusia. Organisasi mereka ditandai dengan perintah-perintah
yang saling tumpang tindih dan membingungkan, ketidakefisienan serta korupsi. Para
pedagang bangsa Asia mengalihkan sebagian besar perdagangan mereka ke
pelabuhan-pelabuhan lain dan menghindari monopoli Portugis dengan mudah.
Pedagang-pedagang Asia mengalihkan perdagangan ke pelabuhan lain yaitu
Pelabuhan Jepara. Oleh sebab itu, di sebelah barat Nusantara dengan cepat Portugis
tidak lagi menjadi suatu kekuatan yang revolusioner. Keunggulan teknologi mereka
yang terdiri atas teknik-teknik pelayaran dan militer dengan cepat berhasil dipelajari
oleh saingan-saingan mereka dari Indonesia. Meriam Portugis dengan cepat direbut
oleh orang-orang Indonesia yang merupakan musuh mereka.124 Dampak imperialis
Portugis memasuki perairan Asia Tenggara timbullah kekacauan sistem niaga secara
damai berubah menjadi sistem perampokan.125
Segera setelah Malaka ditaklukkan, maka dikirimlah misi penyelidikan yang
pertama ke arah timur di bawah pimpinan Fancisco Serrao. Pada tahun 1512 kapalnya
mengalami kerusakan tetapi dia berhasil mencapai Hitu, Maluku (Ambon sebelah
122Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 158-159. 123M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 33. 124M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 33-34. 125Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 160.
97
utara). Para penguasa kedua pulau yang bersaing yaitu Ternate dan Tidore untuk
menjajagi kemungkinan memperoleh bantuan Portugis. Portugis disambut baik di
daerah tersebut karena mereka juga dapat membawa bahan pangan dan membeli
rempah-rempah. Akan tetapi, perdagangan Asia segera bangkit kembali, sehingga
Portugis tidak pernah dapat melakukan suatu monopoli yang efektif dalam
perdagangan rempah-rempah. Orang-orang Portugis mengadakan persekutuan
dengan Ternate dan pada tahun 1522 mulai membangun sebuah benteng disana.
Hubungan mereka dengan penguasa yang beragama Islam berubah menjadi tegang
karena mereka berusaha secara yang agak lemah untuk melakukan kristenisasi dan
perilaku orang-orang Portugis sendiri pada umumnya tidak sopan.126 Portugis juga
mengimbangi dengan mendirikan bentengnya di Sunda Kelapa, 1522 M.127
Kesultanan Demak melancarkan perlawanan bersenajata merebut kembali
Malaka, 1512 M. Demikian pula juga Kesultanan Aceh.128 Pati Unus memutuskan
untuk merebut Malaka dari tangan rajanya pada waktu itu. Ia melakukan penyerangan
setelah menghina Malaka dengan cara menolak memberikan hormat, sesuai dengan
yang diperintahkan kepada kapten kapal pada saat dia berada di Malaka. Pada saat itu
Malaka tengah dikuasai oleh Gubernur India, Alfonso de Albuquerque. Mendengar
peristiwa ini para pemuka agama dan tokoh masyarakat disana mulai memikirkan
upaya apa yang bisa diambil, selain mengambil alih kota tersebut dari Portugal.
Setelah mengambil keputusan dalam waktu 5 tahun mereka berhasil membangun
armada dengan bantuan dari Palembang, merekapun berangkat ke Malaka dengan
kurang lebih 100 kapal layar jung terkecil, mengangkut beban yang tidak kurang dari
200 ton. 129
Menurut Tome Pires bahwa Pati Unus 2 seorang kesatria yang banyak
dibicarakan oleh orang Jawa karena dia dikenal sebagai kesatria tangguh dan
bijaksana di Jawa.130 Pati Unus memboikot semua pasokan dari Jawa, semua barang
harus masuk ke Pelabuhan Jepara terlebih dahulu bahkan termasuk kapal-kapal dari
Makassar. Ia juga membuat jalur dagang sendiri ke Aceh tidak melalui Malaka, dari
Aceh langsung ke India dan Eropa.
5. Perang Malaka 1512-1513 M
Setelah Malaka jatuh tahun 1511 M, tentu sangat mengganggu jalur
perdagangan Demak, biasanya para saudagar Demak melakukan rute perdagangan
mereka dimulai dari Jepara atau Gresik langsung menuju Malaka. Akan tetapi sejak
Malaka ditaklukkan, mereka terpaksa harus menyisir ke pantai bagian barat Sumatera
yang berakibat harga dagangan Demak kalah bersaing di pasaran internasional
sehubungan biaya transportasi yang cukup tinggi. Memang pada waktu itu pelayaran
dari Jawa dan Malaya ke pulau-pulau bagian timur untuk sementara waktu berkurang,
terutama disebabkan oleh hancurnya armada Jawa di Malaka pada tahun 1511. Karena
126M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 35. 127Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 160. 128Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah Jilid Kesatu, hal 160. 129Tome Pires, Suma Oriental, hal 261. 130Tome Pires, Suma Oriental, hal 260.
98
Portugis pada dasarnya telah mengacaukan secara mendasar organisasi sistem
perdagangan Asia. Namun para pedagang bangsa Asia mengalihkan sebagian besar
perdagangan mereka ke pelabuhan-pelabuhannya terutama ke Pelabuhan Jepara dan
menghindari monopoli Portugis dengan mudah. Akan tetapi perdagangan Asia segera
bangkit kembali, sehingga Portugis tidak pernah dapat melakukan suatu monopoli
yang efektif dalam perdagangan rempah-rempah.131
Setelah Portugis menguasai Malaka, mereka berencana ingin menghancurkan
Demak dari dalam, dengan menjalin kerjasama dengan raja-raja Pedalaman baik yang
ada di Jawa dan Sunda dengan saling mengirim utusan dan hadiah. Portugis juga
memberikan bantuan senapan kepada Raja Hindu Daha untuk menambah kekuatan
tempur Daha dalam menghadapi Demak dan Jepara. Hal ini sesuai dengan tulisan
Krom bahwa kepada Guste Pate inilah Albuquerque, Gubernur Jenderal Portugis di
India, mengirimkan utusannya setelah Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada
1511. Hubungan diplomatik ini dilaporkan oleh Albuquerque dalam suratnya pada 30
November 1513 kepada Raja Portugis Dom Monoel. Kekuasaan dan peranan Guste
Pate yang sangat besar.132
Segera setelah mengadakan rapat, Raden Fatah memerintahkan para penguasa
bawahannya untuk membantu Pati Unus 2 dalam persiapan menyerang Malaka
dengan menyerahkan semua kapal jung yang dimiliki kepada Pati Unus 2. Raden
Fatah pun menyerahkan semua kapal jung yang beliau miliki kepada Pati Unus 2 dan
mengerahkan pasukan yang beliau mobilisasi dari hampir semua wilayah bekas
Kerajaan Islam Pajajaran dulu. Akan tetapi, Raden Fatah tidak secara total
mengerahkan semua kekuatannya sehubungan beliaupun harus jaga-jaga pula akan
serangan dari pihak Daha. Kekuatan dari Pasundan tidak dilibatkan untuk ikut
berperang ke Malaka, melainkan sebagian ditarik ke Demak untuk menjaga serangan
dari Daha. Pati Unus 2 pun sudah mulai mengerahkan mata-mata ke Malaka dan juga
menyimpan beberapa pasukan di Upeh untuk mengepung Malaka.
Kesultanan Demak memiliki 3 jenis kapal yaitu jung, pangajava, dan
lanchara. Sarana penunjang dalam kegiatan perniagaan adalah alat transportasi. Bagi
kerajaan-kerajaan di wilayah pantai alat transportasi yang paling utama adalah
kendaraan air. Jung adalah alat transportasi sejenis perahu dalam ukuran besar.
Mengenai para penguasa pantai yang memiliki gelar pate ada istilah yang khas
berkaitan dengan pemilikkannya atas sarana utama perdagangan, yaitu penguasa-
penguasa kapal dagang (lords of the junks). Sebutan ini tentunya dapat dianggap
sebagai petunjuk mengenai dominasi para penguasa di wilayah pantai atas kegiatan
niaga.
Jenis alat transportasi air lainnya adalah pangajava dan lanchara. Tidak ada
keterangan yang jelas mengenai perbedaan ketiga jenis alat trasnportasi air tersebut,
namun jenis jung memiliki nilai yang paling besar. Kekuatan suatu kerajaan dapat
diukur dari seberapa banyak negara tersebut memiliki jung. Jung dan pangajava
digunakan untuk memuat barang-barang dagangan yang dikirim untuk jarak jauh.
131M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 34-35. 132Hasan Djafar, Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
123.
99
Sedangkan lanchara juga perahu muatan barang dengan memuat barang sampai 150
ton.133
Kapal yang digunakan untuk mengangkut perlengkapan dan prajurit terdiri
dari beberapa jenis antara lain disebut jung, merupakan kapal layar yang berukuran
ratusan ton. Penggeraknya adalah layar yang dipasang pada tiga buah tiang, yang
mempunyai bobot antara 400–800 ton. Jenis yang lain adalah lancara, merupakan
kapal layar atau dayung hampir sama halnya dengan jenis jung. Kemudian kapal
pangajava, merupakan kapal yang dibuat khusus untuk perang dan dapat dipersenjatai
dengan meriam, tenaga penggeraknya adalah layar dan dayung.134
Setelah orang Moor Jawa menjadi kuat dan mengambil alih Palembang,
mereka mengambil alih Jambi dan mereka tidak lagi disebut raja melainkan pate.
Wilayah Jambi berada dibawah kekuasaan Raden Fatah, sang pemimpin Demak.
Negeri Palembang merupakan negeri terbaik yang dimiliki oleh Pate Rodim.135
Ekspedisi Pati Unus 2 ke Malaka pada tahun 1512 M memiliki banyak prajurit
perang setidaknya 30.000 orang di Jawa dan 10.000 orang di Palembang.136 Dalam
waktu 5 tahun mereka berhasil membangun armada dengan bantuan dari Palembang.
Mereka pun berangkat ke Malaka dengan kurang lebih 100 kapal layar, kapal yang
terkecil mengangkut beban yang tidak kurang dari 200 ton.137
Jawa mengumpulkan kekuatannya dan datang untuk melawan Malaka.
Demak membawa 100 jenis kapal yang terdiri atas 40 jung, 60 lanchara, dan 100
calaluz. Armada tersebut merupakan armada terhebat yang pernah dilihat Portugal
dan para pejabat penting di Hindia. Kemenangan ini bukan berada di tangan
Portugis.138
Pertempuran pertama tahun 1512 M di Malaka dibawah pimpinan Pati Unus
2 namun mundur, dikarenakan angin berhembus ke arah yang berlawanan dengan
Malaka dan air pasang. Dari uraian di atas, Portugis mengakui bahwa armada yang
dimiliki Demak adalah armada terhebat.
6. Semua Tindakan Pati Unus atas Perintah dan Persetujuan Raden Fatah
Tulisan Tome Pires bahwa Pati Unus berkeinginan untuk menyatukan segala
yang tersisa dari kekayaan yang dimiliki ayahnya dan Pate Rodim. Ia pun
memutuskan untuk merebut Malaka dari tangan rajanya saat itu.139 Menurut analisis
penulis bahwa Raden Fatah memberikan semua jung kepada Pati Unus 2 dalam
penyerangan tahun 1512-1513. Raden Fatah juga memerintahkan seluruh pate yag
memiliki jung untuk diberikan kepada Pati Unus 2. Dalam hal ini, sebenarnya
penyerahan jung sangat beresiko sehubungan jung sebagai alat transportasi utama
133Wiwin Djuwita Ramelan, Kota Demak Sebagai Bandar Dagang Di Jalur Sutra
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), hal 66. 134K Subroto, “Melucuti Keprajuritan Orang Jawa.” Syamina, Edisi 7 Mei 2018, hal
8. 135Tome Pires, Suma Oriental, hal 217-219. 136Tome Pires, Suma Oriental, hal 258. 137Tome Pires, Suma Oriental, hal 261. 138Tome Pires, Suma Oriental, hal 385-386. 139Tome Pires, Suma Oriental, hal 261.
100
untuk perdagangan dan militer, karena jika kehilangan jung berarti ancaman untuk
ekonomi kerajaan. Raden Fatah mencari dukungan kepada seluruh pate dan ulama
untuk mendukung Pati Unus 2 melakukan serangan ke Malaka. Maka dari itu Raden
Fatah memastikan bahwa Demak harus segera merebut Malaka.
Tulisan Ricklefs bahwa Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira
untuk menemukan Malaka, menjalin persahabatan dengan penguasanya, dan menetap
disana sebagai wakil raja Portugal di sebelah timur India. Tugas Sequiera tidak
mungkin terlaksana seluruhnya ketika dia tiba di Malaka pada tahun 1509. Pada
mulanya dia disambut dengan senang hati oleh Sultan Mahmud Syah (memerintah
1488-1528), tetapi kemudia komunitas dagang Islam Internasional yang ada di kota
itu meyakinkan Mahmud bahwa Portugis adalah suatu ancaman berat baginya.
Akhirnya dia berbalik melawan sequeira, menawan beberapa orang ana buahnya dan
membunuh beberapa diantaranya, serta mencoba menyerang 4 kapal Portugis, tetapi
telah berlayar ke laut lepas.140
Pati Unus 2 melakukan penyerangan setelah menghina Malaka dengan cara
menolak memberikan hormat, sesuai yang diperintahkan, kepada kapten kapal pada
saat ia berada di Malaka karena Malaka tengah dikuasai oleh Gubernur India, Alfonso
de Albuquerque. Mendengar peristiwa ini, para pemuka agama dam tokoh masyarakat
di sana mulai memikirkan upaya apa yang bisa diambil selain mengambil alih kota
tersebut dari Portugal.141 Penghinaan yang dimaksud itu adalah mengusir Portugis
tahun 1509 dari Malaka sebagaimana yang dituliskan oleh Ricklefs. Sedangkan
menolak memberikan hormat artinya Pati Unus 2 tidak mau berdamai dengan
Portugis, akibatnya Portugis melakukan serangan untuk taklukkan Malaka tahun
1511. Malaka kalah karena ada pertikaian antara Sultan Mahmud dan putranya
padahal Malaka telah dilengkapi secara baik dengan meriam.142
Setelah Malaka takluk 1511 maka mengadakan rapat untuk mengambil alih
kota itu dari Portugis. Namun dalam rapat tersebut lazimnya terjadi pro kontra. Raden
Fatah sebagai sultan mengukuhkan untuk melakukan penyerangan di Malaka tahun
1512 dan memerintahkan pate-pate untuk menyerahkan jung-jung kepada Pate
Rodim. Jung-jung diberikan kepada Pati Unus 2 sebagai Pemimpin Armada Maritim
Demak, dengan memiliki prajurit perang 30.000 orang di Jawa dan 10.000 orang di
Palembang.143
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Alfonso de Albuquerque, ditulis
dari Cannanore pada 22 Februari 1513, Fernao Peres de Andrade, Kapten armada
yang berhasil menaklukkan Pate Unus berkata jung milik Pate Unus adalah jung
terbesar yang pernah terlihat di wilayah ini, hingga saat ini. Jung tersebut mengangkut
ribuan prajurit. Yang mulia tidak akan mempercayai saya. Ia adalah sesuatu yang
sangat menakjubkan untuk dilihat. Saat berada di sisinya, Anunciada sama sekali tidak
tampak menyerupai kapal. Kami memborbardir kapal tersebut. Akan tetapi, peluru
yang paling besar sekalipun tidak berhasil membuat lubang di bawah garis air,
sedangkan tembakan espera (sejenis bola meriam kuno berukuran besar) dari kapal
140M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 33. 141Tome Pires, Suma Oriental, hal 261. 142M.C Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hal 33. 143Tome Pires, Suma Oriental, hal 258-259.
101
kita berhasil mengenai kapal mereka, namun tidak menembusnya. Jung tersebut
dilapisi oleh 3 pelindung yang tebal keseluruhannya melebih 1 cruzado. Ukurannya,
tentu saja, amatlah besar. Tidak seorang pun yang pernah melihat hal seperti itu.
Pembuatan jung tersebut memakan waktu 3 tahun, sebagaimana yang mungkin sudah
diketahui oleh Yang Mulia mengenai desas desus yang beredar di Malaka tentang
Sang Pate Unus orang yang membangun armada ini demi menjadi Raja Malaka.144
Maka dari itu, Pati Unus 2 diberi gelar Pangeran Atas Angin.145
Dari uraian diatas bahwa tergambarkan jung yang digunakan Pati Unus 2
dalam peperangan di Malaka. Tokoh Raden Fatah dan Pati Unus 2 adalah 2 tokoh
besar yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Pati Unus 2 mengawali karir beliau
dimulai dari seorang Imam Masjid Demak dengan gelar Panghulu Rahmatullah dari
Undung, Pandita Rabani, dan Pangeran Kudus.146 Contoh kecerdasan beliau adalah
memboikot seluruh perdagangan pelabuhan-pelabuhan harus masuk ke Pelabuhan
Jepara saat Malaka jatuh ke Portugis sedangkan keberaniannya adalah Pati Unus 2
berhasil melewati tempat yang berlawanan dengan Malaka melalui bantuan pasang
surut air karena angin di terusan telah berhembus ke arah yang berlawanan dengan
Malaka, ia berhasil mengubah keletihan menjadi angin segar dan pergi berlayar
menggunakan jung, tindakan berani ini pantas untuk dikenang.147 Semua tindakan Pati
Unus 2 seperti yang penulis uraikan di atas sudah barang tentu atas persetujuan dan
perintah Raden Fatah. Dengan demikian, Raden Fatah adalah seorang Sultan Demak
yang cerdas dalam mengambil keputusan sehubungan memilih Pati Unus 2 sebagai
patihnya. Jadi Raden Yunus meneruskan Pati Unus 2 sebagai patihnya untuk Perang
Malaka tahun 1521.
7. Kehancuran Kerajaan Hindu Daha
Tome Pires menceritakan pasca kekalahan Demak di Malaka tahun 1513 M,
Pati Unus 2 menjadi tidak aman di negerinya sendiri.148 Kondisi tersebut sudah bisa
dipastikan berkaitan dengan Daha. Melihat posisi Pati Unus 2 yang menurut mereka
lemah. Daha berkali-kali melakukan penyerangan terhadap Jepara akan tetapi ternyata
gagal, sehingga berubah haluan untuk memperlemah posisi Jepara dan Demak. Daha
mempererrat diplomatik dengan Portugis. Dengan demikian akhirnya mereka
memutuskan untuk mengerahkan kekuatan mereka berencana menyerang Demak
secara terbuka karena menurut mereka posisi Pati Unus sudah sangat lemah.
Menurut Hasan Djafar bahwa antara tahun 1518 dan 1521 yaitu pada masa
pemerintahan Adipati Unus dari Demak di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran
politik. Pergeseran politik ini adalah beralihnya penguasaan Majapahit ke tangan
penguasa Demak, Adipati Unus. Dugaan tersebut didasarkan pada pemberitaan
144Tome Pires, Suma Oriental, hal 214. 145Naskah Sukapura yang ditulis oleh Raden Beben Abdullah tahun 1991. 146H.J De Graaf dan TH Pigeaud, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah
Politik Abad XV Dan XVI, hal 55-56. 147Tome Pires, Suma Oriental, hal 214 148Tome Pires, Suma Oriental, hal 262.
102
Pigafetta tahun 1522 bahwa Raja Pati Unus adalah Raja Majapahit yang sangat
berkuasa ketika masih hidup.149
Dari tulisan tersebut analisis penulis yaitu tahun 1518 Demak dan Jepara
diserang oleh Kerajaan Hindu Daha secara besar-besaran. Perang ini dibantu oleh
Portugis. Namun Daha gagal menaklukkan Demak bahkan Batara Vojyaya dan Guste
Pate dapat dibinasakan. Maka dari itu, Daha secara politis sudah kehilangan
kedaulatan. Berarti semua bawahan Daha secara otomatis dibawah kekuasaan Demak.
Dan dugaan penulis bahwa Raden Fatah wafat saat terjadi penyerangan tersebut. Dan
sudah dijelaskan juga bahwa Pati Unus adalah penguasa Jepara, wilayah Kerajaan
Islam Sunda Pajajaran Timur atau Majapahit.
8. Wafat Raden Fatah
Berita lumpuhnya Daha sudah barang tentu diketahui oleh Portugis, sehingga
mereka secara diam-diam berbalik arah dengan mengadakan komunikasi dan
hubungan diplomatik yang lebih intensif dengan Kerajaan Sunda Pedalaman. Mereka
dikejutkan oleh kekuatan Demak, sehingga mereka selama Raden Fatah dan Sultan
Yunus berkuasa tidak berani masuk untuk mencoba menguasai Pulau Jawa.
Sementara Raden Fatah bersama Pati Unus 2 saat itu sudah mempersiapkan kembali
untuk penyerangan ke 2 dari Demak kepada Malaka. Semua tentara yang dahulunya
tentara Daha banyak yang ikut bergabung dalam persiapan penyerangan tersebut.
Dalam persiapan kali ini rupanya Raden Fatah tidak main-main, beliau mengerahkan
semua kekuatannya termasuk para kesatria dari Pasundan sudah dipersiapkan dan
kapal-kapal perang Demak sudah beliau persiapkan pula.
Akan tetapi pada saat persiapan tersebut Sang Sultan Pemberani dan
bijaksana tersebut dipanggil untuk menghadap kekasihnya yaitu Allah SWT, beliau
wafat pada saat tersebut tahun 1518 M. Beliau wafat setelah menunaikan tugas-
tugasnya dengan sangat baik, sebagai ulama maupun umaro. Beliau sebagaimana
datuknya yaitu Baginda Rasululloh SAW tidak meninggalkan harta maupun istana
megah sebagaimana biasanya seorang raja yang besar, beliau hanya meninggalkan
Masjid Demak yang dibangun bersama saudara iparnya yaitu Pati Unus 1 alias Syarif
Ibrahim Yunus dan para wali lainnya pada tahun 1506 M.
D. Perbandingan Silsilah dan Riwayat Raden Fatah dari berbagai Sumber
Sumber Silsilah Riwayat
Tulisan dari Jawa Silsilah Raden Fatah dari Babad
Tanah Jawi:
1. Prabu Brawijaya
menikah dengan selir
Putri Cina, berputra
2. Raden Fatah
Menurut Babad Tanah
Jawi, Raden Fatah lahir
dari seorang perempuan
Cina yang diangkat
menjadi selir oleh Prabu
Brawijaya. Karena
149Hasan Djafar, Masa Akhit Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya, hal
130.
103
Silsilah Raden Fatah dari Serat
Kandha:
1. Prabu Brawijaya
menikah selir Putri
Cina, berputra
2. Raden Fatah
permaisuri Prabu
Brawijaya yang berasal
dari Champa sangat
cemburu dengan
perempuan Cina yang
dikisahkan sehari bisa
berganti rupa 3 kali itu,
maka selir yang dalam
keadaan hamil itu
dihadiahkan kepada putra
sulungnya, Arya Damar,
yang menjadi raja
Palembang.
Menurut Serat Kandaning
Ringgit Purwa, asal usul
Raden Fatah sebagai
putra Prabu Brawijaya
dengan selir Cina bahwa
Prabu Brawijaya tahu
istrinya yang hamil telah
sampai di Palembang dan
melahirkan putra yang
tampan, bercahaya seperti
bintang, yang dinamai
Raden Fatah yang sangat
suka pada agama. Putri
Cina itu lalu dinikahi oleh
Arya Damar.
Menurut cerita tradisi
Mataram Jawa Timur,
raja Demak yang pertama
Raden Fatah adalah putra
raja Majapahit yang
terakhir (dari zaman
sebelum Islam), yang
dalam legenda bernama
Brawijaya. Ibu Raden
Fatah konon seorang
Putri Cina dari keraton
raja Majapahit. Waktu
hamil putri itu
dihadiahkan kepada
seorang anak emasnya
yang menjadi gubernur di
Palembang. Disitulah
Raden Fatah lahir.
104
Tulisan dari sejarah
Jawa Barat
Silsilah Raden Fatah dari
Sadjarah Banten:
1. Patih raja Cina
2. a. Cun-Ceh, meninggal
dalam usia muda
b. Cu-Cu, disebut Arya
Sumangsang dan Prabu
Anom
3. Ki Mas Palembang
Silsilah Raden Fatah dari
Hikayat Hasanuddin:
1. Cek Ko-Po dari
Munggul
2. Memiliki putra:
a. Pangeran Wirata,
meninggal muda
b. Pangeran
Palembang Tua,
meninggal muda
c. Cek Bun-Cun
d. Pangeran
Palembang Anom,
disebut Molana
Arya Sumangsang
3. Molana Tranggana,
putra dari Pangeran
Palembang Anom
Silsilah Raden Fatah dari Carita
Purwaka Caruban Nagari:
1. Sri Prabu Kertawijaya
(Brawijaya) menikah
dengan Siu Ban Ci,
putri hasil perkawinan
Tan Go Hwat dan Siu
Te Yo penduduk
muslim Cina asal
Gresik
2. Raden Fatah
Di Cina muncul seorang
Syekh Jumadilakbar yang
mengislamkan raja.
Usaha itu tidak berhasil.
Konon, Jumadilakbar
kemudian berangkat ke
Jawa dengan menumpang
kapal seorang dari Gresik.
tetapi setelah
Jumadilakbar berangkat,
rupanya raja Cina itu
yakin akan keunggulan
agama Islam. Patih telag
mencarinya di Siam,
Samboja, Sanggora, dan
Pulau Atani hingga
akhirnya sampai juga di
Gresik. tetapi syekh itu
ternyata sudah
menghilang. Di Gresik
konon patih Cina bersama
kedua putranya Cun-Ceh
dan Cu-Cu masuk Islam.
Patih dan Cun-Ceh
meninggal di Gresik.
menurut cerita, Cu-Cu
kemudiandapat mencapai
status yang tinggi.
Tulisan dari Ulama Silsilah Raden Fatah versi
pertama:
1. Sri Komara/Brawijaya
I, berputra
Raden Fatah adalah
keponakan Bujangga
Manik alias Arya Damar
dari Palembang. Arya
Damar adalah anak dari
105
2. Prabu Guru Haji
Putih/Brawijaya II,
berputra
3. Prabu
Tajimalela/Brawijaya
III, berputra
4. Sunan
Rumenggong/Brawijaya
V, berputra
5. Prabu Cakrabuana
III/Brawijaya V,
berputra
6. Raden Fatah
Silsilah Raden Fatah versi
kedua:
1. Syekh Ahmad
Jalaludin, berputra
2. Syekh Jamaludin Al
Akbar/Syekh Jumadil
Kubro, berputra
3. Barakat Zainal Alam,
berputra
4. Maulana Malik
Ibrahim, berputra
5. Sunan Rumenggong,
berputra
6. Prabu Cakrabuana III,
berputra
7. Raden Fatah
Sunan Rumenggong,
berarti Raden Fatah
adalah cucu Sunan
Rumenggong. Menurut
sanad riwayat dari Raden
Haji Ahmad Dimyati
diterima pada tahun 1992
dari gurunya KH. Aceng
Mu’man Mansyur
diterima dari ayahnya
KH. Raden Ahmad
Dimyati diterima dari
guru-guru beliau
diantaranya KH. Raden
Muhammad
Adro’i/Mama Bojong
Garut, KH Raden Ahmad
Satidi/Mama Gentur
Cianjur, KH. Raden
Muhammad
Syuja’i/Mama Gudang
Tasik diterima dari
gurunya KH. Ahmad
Sobari Ciwedus bahwa
Maulana Malik Ibrahim
mempunyai 2 putra yaitu
Sunan Ampel dan Sunan
Santri alias Sunan
Rumenggong. Yang
ditugaskan menyebarkan
Islam, yaitu Sunan Ampel
diutus ke Jawa dan Sunan
Rumenggong diutus ke
Sunda Jawa Barat.
Berdasarkan Catatan
Silsilah Ningrat
Limbangan yang
dikeluarkan oleh Rukun
Warga Limbangan bahwa
Sunan Rumenggong
pernah sebagai Penguasa
Labuan Cirebon yang
berkedudukan di
Sindangkasih
(Majalengka sekarang).
Raden Fatah adalah putra
106
dari Kertabumi alias
Prabu Cakrabuana III
alias Cakrabumi alias
Haji Abdullah Iman.
Dalam Catatan Silsilah
Ningrat Limbangan yang
dikeluarkan oleh Rukun
Warga Limbangan bahwa
Kertabumi adalah Raja
Galuh atau Raja
Mendang. Prabu Susuk
Tunggal memiliki anak
bernama Ki Amuk
Marugul dan Ki Amuk
Marugul memiliki anak
bernama Ki Ageng
Japura. Raden Fatah
adalah sepupu dari Ki
Ageng Japura/Pate
Japura.
Tome Pires Silsilah Raden Fatah menurut
Tome Pires:
1. Kakek Raden Fatah
berasal dari Gresik dan
menjadi Penguasa
Cirebon
2. Ayah Raden Fatah
adalah seorang kesatria
dan bijak dalam
mengambil keputusan
yang memiliki 40 jung
dari wilayahnya
3. Pate Rodim/Raden
Fatah
Dalam tulisan Tome Pires
bahwa Pate Rodim
(Raden Fatah) memiliki
hubungan yang erat
dengan para penguasa di
Jawa, mengingat semua
putri dari ayah dan
kakeknya menikah
dengan pate-pate
tertinggi.
Pate Japura adalah
sepupu tertua dari Pate
Rodim.
107
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Diakhir penelitian penulis akan menyajikan kesimpulan, yaitu:
1. Bagaimana silsilah Raden Fatah sebenarnya?
Setelah disesuaikan antara tulisan Tome Pires dan tulisan para Ulama bahwa
Raden Fatah adalah keponakan dari Bujangga Manik alias Arya Damar dari
Palembang. Arya Damar adalah anak dari Sunan Rumenggong, berarti Raden Fatah
cucu dari Sunan Rumenggong. Raden Fatah adalah putra dari Kertabumi alias Prabu
Cakrabuana III alias Brawijaya V alias Siliwangi V. Sunan Rumenggong adalah cucu
dari Syekh Jumadil Kubro. Sunan Rumenggong pernah sebagai Penguasa Cirebon
yang berkedudukan di Sindangkasih. Maulana Malik Ibrahim memiliki 2 putra yaitu
Sunan Ampel dan Sunan Santri alias Sunan Rumenggong. Gresik sebagai pusat agama
Islam tertua di Jawa Timur. Maulana Malik Ibrahmi bermakam di Gresik. Sunan
Rumenggong ditugaskan ke Sunda dan pernah berkuasa di Cirebon sedangkan Sunan
Ampel ditugaskan ke Jawa. Dengan demikian, susunan Silsilah Raden Fatah yaitu:
1. Syekh Ahmad Jalaludin, berputra
2. Syekh Jamaludin Al Akbar/Syekh Jumadil Kubro, berputra
3. Barakat Zainal Alam, berputra
4. Maulana Malik Ibrahim, berputra
5. Sunan Rumenggong, berputra
6. Prabu Cakrabuana III, berputra
7. Raden Fatah
Prabu Susuk Tunggal merupakan putra dari Prabu Taji Malela. Sunan Rumenggong
menantu dari Prabu Taji Malela, berarti Prabu Susuk Tunggal saudara ipar dengan
Sunan Rumenggong. Prabu Susuk Tunggal memiliki anak bernama Ki Amuk Marugul
dan Ki Amuk Marugul memiliki anak bernama Ki Ageng Japura. Dengan demikian
berdasarkan silsilah Raden Fatah versi tulisan Ulama bahwa Raden Fatah sepupu dari
Ki Ageng Japura/Pate Japura.
2. Bagaimana kedudukan Raden Fatah dengan para Wali penyebar Islam dan
hubungan Raden Fatah terhadap raja-raja Hindu?
Raden Fatah adalah penguasa di Negeri Demak dan pate tertinggi di Jawa.
Raden Fatah memiliki hubungan yang erat dengan para penguasa di Jawa, semua putri
dari ayah dan kakeknya menikah dengan pate-pate tertinggi. Raden Fatah sangat
dihormati. Mereka adalah orang-orang Moor (Islam) atau pengikut Nabi Muhammad
SAW. Jika mengacu dari Silsilah Raden Fatah yang sudah dijelaskan, sudah barang
tentu mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan tokoh-tokoh Walisongo.
Misalnya, Sunan Kalijaga adalah keponakan dari Raden Fatah, Raden Fatah dan
Sunan Gunung Jati I adalah cucu dari Sunan Rumenggong.
108
Silsilah dari Raja Daha yaitu Batara Vojyaya dan patihnya Guste Pate
bernama Pate Amdura, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Raden Fatah.
Sedangkan tulisan tentang hubungan kekerabatan antara pate-pate Moor dengan
Raden Fatah detail dan rinci. Raden Fatah memiliki keterkaitan kerabat dengan Pati
Unus dan kakeknya dari Gresik. Sebaliknya, bahwa Raja Daha Batara Vojyaya adalah
musuh dari Raden Fatah dan pihak Daha sering melalakukan penyerangan terhadap
Demak. Dengan demikian, tidak bisa menyimpulkan bahwa Batara Vojyaya sebagai
tokoh ayah Raden Fatah dan disamakan dengan tokoh Brawijaya.
Raden Fatah sangat berkuasa sehingga mampu menaklukkan seluruh wilayah
Palembang, Jambi, Kepulauan Manomby, dan banyak pulau lainnya. Ayah dari Raden
Fatah memiliki hubungan kekerabatan dengan pate-pate tertinggi di Jawa dan tokoh
yang sangat berkuasa. Sementara tidak ada catatan yang menuliskan bahwa Batara
Vojyaya memiliki kaitan nasab atau silsilah dengan Raden Fatah. Batara Vojyaya
hanya menguasai Kerajaan Jawa Pedalaman alias Kerajaan Hindu Daha yang hanya
menguasai sebagian wilayah Jawa Timur dan Bali. Ayah Raden Fatah dahulunya
mengumpulkan kapal jung sebanyak 40 buah kapal. Sedangkan Batara Vojyaya tidak
memiliki banyak jung dan penguasaan pelabuhan yang banyak.
Dengan demikian, kedudukan Raden Fatah adalah sebagai pate tertinggi di
Jawa dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan pate-pate Moor tertinggi
di Jawa. Raden Fatah tidak memiliki hubungan nasab atau silsilah dengan Raja Hindu
Daha yaitu Batara Vojyaya dan patihnya Guste Pate. Guste Pate sering melakukan
penyerangan dengan Demak.
B. Saran
Adapun saran untuk bidang Sejarah Islam di Nusantara, yaitu:
1. Untuk Sejarah Islam khususnya di Nusantara pentingnya Hukum Islam
(Fiqih) sebagai barometer dalam sebuah kebenaran tulisan sejarah silsilah dan
riwayat tentang tokoh-tokoh Islam sebagai tokoh penyebar Islam.
2. Penulisan Sejarah Islam di Nusantara masih banyak polemik sedangkan
kebesaran sebuah bangsa salah satunya tercermin dari sejarah bangsanya
dimasa lalu. Maka dari itu, menjadi tugas para sejarawan Indonesia untuk
terus mengkaji dan meneliti sejarah bangsa Indonesia karena secara fakta
bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan mandiri sejak berabad-abad
yang lalu.
109
DAFTAR PUSTAKA
Sumber-Sumber Primer
Buku Cetakan
Cortesao, Armando. Suma Oriental karya Tome Pires: Perjalanan dari Laut Merah
ke Cina dan Buku Francisco Rodrigues diterjemahkan dari buku The Suma
Oriental of Tome Pires An Account of The East, From The Sea to China and
The Book of Francisco Rodrigues edited by Armando Cortesao 2 Volume
(The Hakluyt 1944), Yogyakarta, Ombak, 2015.
Pigafetta, Antonio. The First Voyage Around The World by Magellan 1519-1522,
London, Printed for The Hakluyt Society, 1519-1522.
Sumber-Sumber Sekunder
Naskah
Abdullah, Raden Beben. Naskah Sukapura, 1991.
Anggapraja, Raden Sulaiman. Sajarah Babon Luluhur Sukapura, 1971.
Aunillah, Raden Atung. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan
Babad Cirebon, PNRI, Kode 75b
Djubaedi, Raden Achmad. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan, 2013.
Djubaedi, Raden Achmad. Sejarah Prabu Wijayakusumah atau Sunan Cipancar
Limbangan dan leluhurnya, 2013
Hendriyana, Raden Eeng dan Tim Yayasan Wasiat Karuhun Sukapura. Babon
Sukapura, 1971.
Indrayuda, Raden. Terjemahan Surat Wasiat Raden Indrayuda ditulis 16 Juli 1892,
2013.
Mertakusuma, Raden Syar’i. Kitab Al Fatawi, 1920.
Priyatna, R.I Soehari dan R.H.I Ibrahim. Catatan Silsilah Ningrat Limbangan yang
dikeluarkan oleh Rukun Warga Limbangan.
Suryaman, Radeng Anang, Raden Yeni Mulyani, dan Raden Abdul Syukur. Mengenal
Museum Prabu Geusan Ulun Obyek Wisata Lainnya serta Riwayat Leluhur
Sumedang
Tim Yayasan Wasiat Karuhun Tasikmalaya. Ringkasan Babon Sukapura
Yayasan Pangeran Sumedang. Silsilah Pangeran Kornel
Abdurahman bin Muhammad bin Al Mahsyur. Kitab Syamsu al Zahiro, fi nasabi ahli
al baiti min bani alawi furu fathimah al zahra wa amir wa muminin ra Jilid
1, Jeddah, Alam Al Marifah.
Al Fadhil Abi Al Fadhol As Senori At Tubani. Kitab Ahla Al Musamaroh fi hikayati
al auliya al asroh, Tuban, Majelis At Ta’lif wal Khotot.
Al Habib Ali bin Husain bin Jafar Al Atthas. Kitab Taj Al Ars ala manaqib al habib
al qutub solih bin abdullah al atthas jilid 1, cetakan pertama, Kudus, Menara
Kudus.
110
Al Habib Assegaf bin Ali Al Kaff. Kitab Dirosah Finasbi Al Saadah Bani Alawi
Dzuriyyah Al Imam Al Muhajir Ahmad bin Isa, tidak ada tahun.
Mustofa, Bisri. Kitab Tarikhul Auliya Tarikh Walisongo, Kudus: Menara Kudus,
1952.
Serat Pararaton Ken Arok.
Buku Cetakan
Abdullah, Rachmad. Walisongo Gelora Dakwah dan Jihad Di Tanah Jawa
(1404-1482 M), Solo, Al Wafi, 2017
Abdullah, Rachmad. Sultan Fattah Raja Islam Pertama Penakluk Tanah Jawa
(1482-1518 M), Solo, Al Wafi, 2017.
Abdullah, Rachmad. Kerajaan Islan Demak Api Revolusi Islam Di Tanah Jawa
(1518-1549 M), Solo, Al Wafi, 2017.
Abimanyu, Soedjipto. Babad Tanah Jawi, Yogjakarta, Laksana, 2013.
Adji, Krisna Bayu dan Sri Wintala Achmad. Geger Bumi Majapahit Menelanjangi
Sisi Kelam Di Balik Pesona Majapahit, Yogyakarta, Araska, 2014.
Adji, Krisna Bayu. Sejarah Runtuhnya Kerajaan-Kerajaan Di Nusantara,
Yogyakarta, Araska, 2014.
Aizid, Rizem. Sejarah Islam Nusantara, Yogyakarta, Diva Press, 2016.
Akasah, Hamid dan Aby Azyzy. Babad Tanah Jawa (Majapahit- Demak-Pajang),
Cipta Adi Grafika, Tidak ada tahun.
Akasah, Hamid. Walisongo Antara Mitos dan Sejarah Periode I Sampai V, Cipta
Adi Grafika, Tidak ada tahun.
Al Husaini, HMH Al Hamid. Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah, Bandung,
Yayasan Al Hamidy, 1997.
Al Jaziri, Abdurrahman. Kitab Al Fiqhi Ala Al Madzahib Al Arba’ah, Beirut, Dar Al
Kutub Al Ilmiyyah, 1999.
Al Zohiri, Abu Muhammad Al Qurthubi, Al Muhalla bi Al Atsar, Beirut, Dar Al Fikr.
Amar, Imron Abu. Sejarah Ringkas Kerajaan Islam Demak, Kudus, Menara
Kudus, 1996.
Atmodarminto R. Babad Demak Dalam Tafsir Sosial Politik Keislaman dan
Kebangsaan, Jakarta, Millennium Publiser, 2000.
Azyumardi, Azra. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara
Abad XVII Dan XVIII (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana, 2007.
Baso, Ahmad. Islamisasi Nusantara dari Era Khalifah Usman bin Affan hingga
Walisongo, Jakarta, Pustaka Afid, 2018.
Budiman, Amen. Babad Dipenogoro ditulis oleh Pangeran Dipanegara Sendiri Di
Tempat Pengasingannya Di Manado, Semarang, Tanjung Sari, 1980.
Djafar, Hasan. Masa Akhir Majapahit: Girindrawardhana dan Masalahnya,
Jakarta, Komunitas Bambu, 2012.
De Graaf H.J dan TH Pigeaud. De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java,
Studien Over de Staatkundige Geschiedenis van de 15 de en 16 de Eeuw,
Pustaka Utama Grafiti, Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan
Sejarah Politik Abad XV Dan XV,. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1985.
111
Hamka. Sejarah Umat Islam: Pra Kenabian hingga Islam di Nusantara, Jakarta,
Gema Insani, 2016.
Janutama, Herman Sinung. Fakta Mengejutkan Majapahit Kerajaan Islam, Jakarta,
Noura Books, 2014.
Kartodirdjo, Sartono dkk. Sejarah Nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1973.
Kasri, Muhammad Khafid. Sejarah Demak Matahari Terbit Di Glagah Wangi,
Demak, Syukur, 2008.
Khaldun, Ibnu. Mukaddimah Ibnu Khaldun, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2001.
Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2003.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 2013.
Laffan, Michael. The Makings of Indonesian Islam,. Indi Aunullah dan Rini Nurul
Badariah, Sejarah Islam Di Nusantara, Yogyakarta, Bentang Pustaka, 2015.
Lajoubert, Monique Zaini. Karya lengkap Abdullah bin Muhammad Al Misri, Depok,
Komunitas Bambu, 2008.
Mangkudimedja, R.M dan Hardjana HP, Serat Pararaton Ken Arok, Jakarta,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra
Indonesia dan Daerah, 1980.
Mashad, Dhurorudin. Muslim Bali: Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, Jakarta,
Pustaka Al Kautsar, 2014.
Muhammad, Abu Abdillah bin Muhammad Al Qurthubi. Al Jami’ li Ahkam Al
Qur’an, Qohiroh, Dar Al Kutub Al Misriyyah, 1964.
Muljana, Slamet. Menuju Puncak Kemegahan, Jakarta, Balai Pustaka, 1965.
Muljana, Slamet. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya, Jakarta, Bhratara, 1979.
Muljana, Slamet. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara
Islam Di Nusantara, Yogyakarta, LKIS, 1968.
Olthof, W.L. Babad Tanah Jawi, Yogyakarta, Narasi, 2019.
Purwadi. Prabu Brawijaya Raja Agung Binathara Ambeg Adil Paramarta,
Yogyakarta, Oryza, 2013.
Purwadi dan Maharsi. Babad Demak Sejarah Perkembangan Islam di Tanah
Jawa, Yogyakarta, Pustaka Utama, 2012.
Ricklefs M.C. A History Of Modern Indonesi,. Dharmono Hardjowidjono, Sejarah
Indonesia Modern, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007.
Ricklefs M.C, Bruce Lockhart, dkk. A New History of Southeast Asia, Komunitas
Bambu, Sejarah Asia Tenggara Dari Masa Prasejarah
SampaiKontemporer, Depok, Komunitas Bambu, 2013.
Saefuddin, Didin. Sejarah Politik Islam, Depok, Serat Alam Media, 2017.
Salam, Solichin. Sekitar Walisongo, Kudus, Menara Kudus, 1960.
Sunyoto, Agus. Atlas Walisongo, Bandung, Iiman, 2012.
Suparman. Babad Kesultanan Demak Bintoro, Pajang, dan Mataram, Demak,
Galang Ideapena Demak, 2015.
Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah I, Bandung, Surya Dinasti, 2015.
Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah II, Bandung, Surya Dinasti, 2016.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II, Jakarta, Rajawali Press,
2010.
112
Jurnal
Anggoro, Bayu. Wayang dan Seni Pertunjukkan: Kajian Sejarah Perkembangan Seni
Wayang di Tanah Jawa sebagai Seni Pertunjukkan dan Dakwah, Jurnal
Sejarah Peradaban Islam, Vol 2 No 2, 2018. (Diakses 25 Juni 2020,
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/juspi/article/view/1679)
Dewi, Tri Tunggal, Wakidi, dan Suparman Arif. “Peranan Sultan Fattah dalam
Pengembangan Agama Islam di Jawa,” Jurnal Pendidikan dan Penelitian
Sejarah, Vol. 5 No. 8 (2017). (Diakses 27 Maret 2019,
http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/14339)
Farida, Umma. “Islamisasi Di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-
Umara dalam Dakwah Islam di Demak,” Jurnal At Tabsyir Komunikasi
Penyiaran Islam, Vol. 3 No. 2, (Desember 2015): 299-318. (Diakses 20
Februari 2019, https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v3i2.1649 ) Guillot, Claude. La Necessaire Relecture de I’accord Luso-Soundanais de 1522, In
Archipel Vol 42, pp 53-76, 1991. (Di akses 25 Juni 2020,
https://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1991_num_42_1_2748 )
Hasib, Kholili. “Menelusuri Mazhab Walisongo”, Jurnal Tsaqafah Peradaban Islam,
Vol. 11 No. 1, (Mei 2015): 137-150. (Diakses 20 Februari 2019,
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/vie/257 )
Johns, Anthony H. “The Role Of Structural Organisation and Myth Javanes
Historiography,” The Journal of Asian Studies, Vol. 24 No. 1 (November
1964): 91-99. (Diakses 20 Februari 2019,
https://www.jstor.org/stable/2050416 )
Kern, RA. Pati Unus En Sunda, Jjournal Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde,
Deel 108 2 de Afl, 1952. (Di akses 8 Juli 2020,
http://www.jstor.com/stable/27859765 ) Kholid, A.R Idham. “Walisongo: Eksistensi Dan Perannya Dalam Islamisasi Dan
Implikasinya Terhadap Munculnya Tradisi-Tradisi Di Tanah Jawa,” Jurnal
Tamaddun, Vol.4 No. 1, (Januari-Juni 2016): 1-47. (Diakses 20 Februari
2019, https://doi.org/10.24235/tamaddun.v1i1.934 ) Kraan, Alfons van der. Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes, and Commentary,
Cornell University Press, Southeast Asia Program Publications at Cornell
University, Indonesia No 40, Oktober 1985. (Di akses 25 Juni 2020,
https://www.jstor.org/stable/3350877 )
Kusno, Abidin. “The Reality of One Which Two: Mosque Battles and Other Stories”
Notes on Architecture, Religion, and Politics in the Javanese World,”
Journal of Architecture Education, Vol. 57 No. 1 (September 2003): 57-67.
(Diakses 20 Februari 2019, https://www.jstor.org/stable/1425740 )
Maryam. “Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak),”
Jurnal Tsaqofah dan Tarikh, Vol. 1 No. 1, (Januari-Juni 2016): 63-76.
(Diakses 20 Februari 2019, https://doi.org/10.29300/ttjksi.v1i1.864 ) Ngationo, Ana. “Peranan Raden Fatah Dalam Mengembangkan Kerajaan Demak
Pada Tahun 1478-1518,” Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran
113
Sejarah, Vol. 4 No. 1, (Juli 2018): 17-28. (Diakses 27 Maret 2019,
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Kalpa/article/view/2445 )
Pianto, Heru Arif. “Keraton Demak Bintoro Membangun Tradisi Islam Maritim Di
Nusantara,” Jurnal Sosiohumaniora: Jurnal Imiah Ilmu Sosial dan
Humaniora, Vol. 3 No. 1, (April 2017): 18-26. (Diakses 20 Februari
2019, https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio/article/view/1521 )
Priyadi, Sugeng. Perdikan Cahyana, Jurnal Humaniora Volume XIII No 1 Februari
2001 halaman 89-100. (Di akses 16 Agustus 2020,
https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/714/560 )
Pudjiastuti, Titi. Sita: Perempuan Dalam Ramayana Kakawin Jawa Kuna, Jurnal
Manuskrip Nusantara Vol 1 No 2, 2010. (Di akses 25 Juni 2020,
https://ejournal.perpusnas.go.id/jm/article/view/00100220106/110 )
Ras J.J. “The Genesis of The Babad Tanah Jawi: Origin and Function of The Javanese
Court Chronicle,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143
2/3de Afl (1987): 343-356. (Diakses 20 Februari 2019,
https://www.jstor.org/stable/27863843 )
Rokhman, M Nur, Lia Yuliana, dan Zulkarnain. “Pengembangan Maket Pusat
Kerajaan Demak Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Di SMA, Prosiding
Seminar Nasional, Universitas Negeri Yogyakarta. (Diakses 27 Maret 2019,
https://eprints.uny.ac.id/40063/ )
Subroto, K. Melucuti Keprajuritan Orang Jawa, Syamina, Edisi 7 Mei 2018.
Suhendi, Didi. Inferiorotas Perempuan: Belenggu Jaya, Jani, dan Patni Dalam Tradisi
Agama Hindu, Jurnal Mahasiswa dan Alumni Pascasarjana se Indonesia Vol
3 No 3, Agustus 2011. (Di akses 25 Juni 2020,
https://repository.unsri.ac.id/25385/)
Tundjung dan Arief Hidayat. “Politik Dinasti Dalam Perspektif Ekonomi dari
Kerajaan Demak,” Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 3 No. 1, (2018). (Diakses
20 Februari 2019,
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/2847 )
114
GLOSARI
1. Aji Putih : Gelar raja pajajaran, Aji berarti pegangan atau
falsafah dan putih artinya suci bersih.
2. Batara : Gelar raja bawahan yang diberikan kepada
kerajaan bawahan dari kerajaan pusat.
3. Cakrabuana : Gelar raja pajajaran, cakra adalah khalifah atau
penguasa dan buana artinya dunia.
4. Darmakingkin : Gelar raja pajajaran, darma adalah melakukan
kebaikan dan kingkin adalah sungguh-sungguh.
5. Dayeuh Manggung : Gelar raja pajajaran, dayeuh adalah kota ilmu dan
manggung artinya berkibar, dikenal, dan
dakwah.
6. Dewa : Manusia yang memiliki derajat tinggi laksana
turun dari langit.
7. Hyang : Gelar raja yang memiliki arti memberi kebaikan
dan mengayomi serta memiliki kedudukan diatas
dewa.
8. Kertarahayu : Nama keraton pajajaran yang membawahi
pajajaran barat, tengah, dan timur yang memiliki
arti selamat dan sejahtera.
9. Pajajaran : Nama kerajaan islam sunda yang memiliki arti
semu sejajar jika dizaman Nabi Muhammad
SAW istilahnya sahabat, berdiri sama tinggi
duduk sama rendah.
10. Pakuan Pajajaran : Nama ibukota kerajaan islam sunda pajajaran.
11. Rumenggong : Nama raja pajajaran yang memiliki arti tokoh
yang dituakan dan ayah dari semua raja-raja.
12. Siliwangi : Gelar raja pajajaran dari kata silih dan wangi
yang memiliki makna saling memberi kebaikan.
13. Sri Komara : Gelar raja pajajaran yang memiliki arti dari sri
adalah raja dan komara adalah kependekan dari
komaruddin.
14. Taji Malela : Gelar raja pajajaran yang memiliki arti dari kata
taji adalah nama lain dari Baginda Nabi
Muhammad SAW dan Malela artinya Mulk yaitu
raja. Atau bisa diartikan Tajjul Mulk yaitu raja
diatas raja.
115
INDEKS
A
Alas Peuntas, 40, 43
Alfonso de Albuquerque, 70, 99, 110, 111,
114, 118
Antonio Pigafetta, 64, 72, 77
Anunciada, 118
Arya Baribin, 102, 103, 107
Arya Damar, 20, 21, 23, 25, 47, 48, 49, 50, 52,
89
B
babad, 6, 17, 19, 21, 28, 29, 35, 51, 52, 86,
100
Babad Tanah Jawi, 1, 3, 4, 5, 19, 21, 22, 24,
29, 30, 31, 35, 36, 49, 52, 53, 72, 84, 85,
86, 89, 101, 111, 112, 123, 124, 126
Bangka, 62, 70, 73, 111
Banten, 3, 17, 26, 27, 59, 60, 61, 67, 72, 75,
77, 78, 83, 86, 101
Barakat Zainal Alam, 58
Batara Caripan, 94, 95
Batara Galuh, 40
Batara Galunggung, 40, 43
Batara Mandala, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47, 48, 59, 61, 74, 79
Batara Mataram, 97
Batara Sinagara, 94, 95, 97
Batara Tamarill, 94, 95
Batara Vojyaya, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 115, 119
Bintoro, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 18, 20, 21, 22,
23, 51, 52, 63, 110, 124, 125
Blambangan, 20, 52, 94, 100
Brawijaya V, 1, 2, 5, 6, 16, 20, 21, 22, 24, 49,
51, 52, 55, 71, 95, 101, 102, 103, 108, 112
Bumiwangi, 34, 35, 44, 46
Buniwangi, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 57
C
Cakrabuana, 35, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 58,
60, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 90, 95, 96, 97,
102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112
Cakrabumi, 55, 96
Cakraningrat, 35, 46, 47
Cakrawati, 40, 41, 42, 46, 57
Canjtam, 94
Cempa, 5, 6, 16, 17, 18, 20, 23
Cigede, 60
Cimanuk, 51, 59, 61, 62, 66, 67, 74, 81, 101
Cirebon, 3, 5, 18, 24, 31, 37, 47, 48, 55, 58,
59, 62, 66, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84,
86, 87, 88, 92, 93, 96, 98, 100, 101, 103,
110, 112, 114, 122
Ciung Wanara, 45, 53, 88
D
Daha, 59, 61, 71, 72, 85, 90, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 110, 115,
116, 119, 120
Dayo, 60, 61, 67, 68, 69, 74
De Barros, 72
Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34,
37, 43, 49, 57, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 70,
71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 124, 125, 126
Dewa Niskala, 34, 35, 46, 49, 78
Dinasti Ming, 89, 90
Diogo do Couto, 75
Dipati Teterung, 47, 48, 49
Duerte Coelho, 76
F
Francisco de Sa, 76
116
G
Gamda, 94, 101
Girindrawarddhana, 22, 24, 71, 72, 73, 90, 91,
93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 108,
113, 115, 119
Gresik, 3, 5, 15, 17, 25, 26, 27, 30, 31, 49, 50,
56, 72, 94, 98, 99, 100, 104, 110, 111, 115
Guste Pate, 63, 64, 94, 97, 99, 101, 103, 107,
113, 115, 119
H
Haji Purwa Galuh, 81
Henrique Leme, 75
I
Indonesia, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 26, 28, 29,
30, 35, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 80, 81, 95,
100, 105, 109, 113, 114, 115, 118, 123,
124, 125, 126
Indramayu, 66, 81
Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47, 50,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 71, 74,
82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96,
97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 117,
119, 123, 124, 125
J
Japura, 50, 51, 58, 59, 80, 87, 88, 93, 96, 104
Jawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 35, 37, 40, 42, 51, 52, 56, 57, 59,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 123, 124, 125, 126
Jayakusumah, 41, 42, 44, 46, 56, 57
Jepara, 3, 27, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
81, 84, 85, 86, 90, 94, 96, 97, 98, 101, 106,
108, 110, 113, 114, 115, 119
Joao de Barros, 75
Jorge de Albuquerque, 75, 76, 111
jung, 62, 66, 69, 71, 77, 100, 101, 114, 116,
117, 118
K
Kepulauan Laue, 69
Kepulauan Monomby, 62
Kerajaan Hindu Daha, 95, 97, 99, 110
Kerajaan Jawa Pedalaman, 65, 68, 93, 100
Kerajaan Sunda Pedalaman, 63, 65, 66, 68, 69,
94, 120
Keraton Galuh Pakuan, 81
Kertabumi, 24, 51, 52, 55, 71, 90
Kesultanan Demak, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 51, 52, 62, 87, 107,
110, 112, 114, 116, 124
Ki Ageng Japura, 50, 51, 58, 59, 87, 88, 104
Ki Amuk Marugul, 51, 58, 59
Ki Gedeng Misri, 53, 54
Kidang Kancana, 45, 53, 54
Kitab Al Fatawi, 34, 35, 44, 46, 47, 49, 55, 56,
57, 75, 85, 86, 92, 96, 112, 122
Kitab Syamsu al Zahiro, 122
Kitab Taj Al Ars, 56
L
Laksamana Cheng-Ho, 90
lancaran, 117
Limbangan, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46,
50, 53, 54, 55, 56, 57, 75, 78, 79, 80, 81,
82, 87, 88, 108, 122
M
Maharaja Kastori, 40, 41, 42, 57, 88, 102
Majalengka, 40, 42, 58, 60, 66, 75, 79, 80, 88,
95, 109, 110
Majapahit, 1, 2, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 47,
51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 67, 68, 71, 72,
73, 74, 75, 82, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107,
108, 109, 113, 115, 119, 123
Maluku, 70, 87, 92, 98, 113
Mataram, 1, 2, 3, 4, 6, 17, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 28, 30, 37, 51, 52, 86, 93, 94, 95,
97, 101, 106, 110, 124
117
Maulana Malik Ibrahim, 15, 57, 58, 102, 103,
104
Mekkah, 40, 43, 105, 106
Moor, 63, 66, 67, 76, 81, 83, 88, 99, 100, 105
Munding Jayakawati, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
49, 102
Mundingsari, 15, 42, 45, 46, 78
N
Niskala Wastu Kencana, 46, 60
Nurrudin Ibrahim, 82
Nusantara, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 31, 32, 56, 63,
64, 74, 85, 99, 103, 105, 106, 111, 112,
113, 123, 124, 125
Nyai Ambetkasih, 45
Nyai Ijab Larang, 40
Nyai Mas Buniwangi, 45
Nyai Nading Leuwih, 40
P
Pajajaran, 8, 9, 14, 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 59, 60,
61, 62, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,
103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119
Pajarakan, 94
Pakwan Pajajaran, 60, 67, 81, 101, 108, 109,
112
Palembang, 3, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 27, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 62, 70, 86,
89, 97, 100, 101, 114, 116, 118
Panarukan, 94
pangajava, 71, 116, 117
Pangeran Pamakelaran, 48
Pangeran Sabrang Lor, 27, 82, 85
Pangeran Sang Hyang, 46, 47, 50
Pangeran Santri, 48
Parakanmuncang, 80
Pararaton, 24, 29, 30, 35, 51, 52, 72, 89, 90,
95, 96
Parung, 37, 40, 58, 60, 88
Pate Japura, 88
Pate Katir, 83, 84, 85
Pate Quedir, 84
Pate Rodim, 5, 50, 51, 58, 59, 62, 68, 70, 71,
75, 87, 88, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 108,
109, 111, 117, 118
Pati Quitis, 111
Pati Unus, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 96,
97, 98, 99, 103, 104, 105, 106, 108, 110,
111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125
Pelabuhan Jepara, 98, 115
pohon paku, 80
Pontang, 60
Portugis, 13, 27, 28, 30, 31, 68, 69, 72, 74, 75,
76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 106, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120
Prabu, 1, 2, 5, 6, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
27, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 68, 71,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88,
89, 90, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 122, 124
Prabu Banjaransari, 40, 41, 42, 45, 102
Prabu Geusan Ulun, 38, 44, 47, 48, 49, 54, 55,
58, 78, 122
Prabu Guru Aji Putih, 42, 80
Prabu Guru Haji Putih, 42
Prabu Janton Dewata, 48
Prabu Layakusumah, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
55, 59, 61, 71, 82
Prabu Lembu Agung, 42, 46, 79
Prabu Lingga Wesi, 53
Prabu Munding Jayakawati, 41
Prabu Picuk Umum, 48
Prabu Rangga Gading, 48
Prabu Siliwangi, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 61,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 87, 88, 95,
96, 102, 108
Prabu Surawisesa, 34, 46, 75, 76, 77
Prabu Susuk Tunggal, 50, 54, 58, 59, 60, 75,
77, 87, 88
Prabu Taji Malela, 42, 45, 46, 47, 54, 88, 102
Prabu Tajimalela, 41, 42, 43, 55
Prabu Tutang Buana, 41, 42, 45, 54
Prabu Wastu Dewa, 44, 46, 78, 112
Purbasari, 53, 54
118
R
Raden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 71, 75, 78,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 125
Raden Fatah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28,
31, 33, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
68, 71, 75, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
91, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 125
Raden Jati Sunda, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
49, 50, 58
Raden Sangkan Welasan, 39, 40, 41, 42
Raja Baghdad, 82, 92
Raja Manuel, 99
Raja Samiam, 75, 76, 77
Raja Sunda, 34, 55, 61, 63, 66, 67, 68, 73, 74,
75, 76, 77, 81, 89, 95, 101, 102
Raja Utara, 82, 103
Rangga Pupuk, 48
Rangga Sunten, 40, 41, 42
Ratu Ibu Permana Dipuntang, 41, 42, 45, 56
Ratu Komara, 42, 45, 54
Ratu Pajajaran, 40, 41, 42, 57, 102
Ratu Permana, 42, 44
Rembang, 3, 70, 94, 97, 104
Resi Cakrabuana, 42, 43, 45, 46, 47
S
Sadjarah Banten, 25, 27
Samudera Pasai, 6, 32, 82
Sang Sinagara, 95, 97
Sareupeun Sukakerta, 40, 41, 42, 43
Semarang, 3, 93, 104, 105, 123
Senguruh, 71, 93, 96
Serat Kanda, 21, 23, 29, 30, 31, 52, 53, 72, 98,
99, 107
Sidayu, 94, 104
Siliwangi, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58,
59, 77, 87, 88, 95, 111
Sindangkasih, 61, 79, 80
Sri Baduga Maharaja, 34, 35, 46, 48, 49, 76,
78, 87, 108
Sri Komara, 45, 54, 55, 88, 102
Sukapura, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43,
44, 45, 48, 50, 53, 54, 58, 59, 72, 74, 79,
82, 83, 86, 87, 88, 92, 105, 112, 122
Sultan Yunus, 83, 84, 85, 86, 104, 119, 120
Sumedang, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 54, 55, 58, 66, 68, 75, 78, 79,
81, 96, 110, 122
Sunan Ampel, 1, 6, 19, 52, 57, 104, 105, 107,
111
Sunan Baribin, 102, 103, 111
Sunan Bonang, 32, 107
Sunan Cipancar, 44, 75, 82, 122
Sunan Cisorok, 41, 42, 44, 49, 54, 55, 57
Sunan Darmakingkin, 41, 42, 44, 45, 57, 88
Sunan Dayeuh Manggung, 41, 42, 44, 45, 57,
88, 102
Sunan Drajat, 107
Sunan Geusan Ulun, 55
Sunan Giri, 2, 101, 107, 111
Sunan Kalijaga, 11, 13, 20, 22, 30, 99, 106,
107
Sunan Kudus, 99
Sunan Lingga Hyang, 40, 41, 42, 43, 46, 47,
49, 50, 55
Sunan Muria, 107
Sunan Nusakerta, 41, 42, 44, 57
Sunan Patinggi, 44, 45, 58, 88, 102
Sunan Rumenggong, 35, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 61, 81, 83, 92, 95, 102, 104, 107, 108,
109
Sunan Salalangu, 41, 42, 44, 57
Sunan Sukakerta, 41, 42
Sunda, 35, 40, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 101,
102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
114, 115, 119, 120, 125
Sunda Kelapa, 60, 61, 67, 69, 74, 75, 77, 78,
81, 101, 114
Surabaya, 1, 16, 17, 19, 72, 94, 96, 100
Syaikh Abdullah Baharudin Al-Jawi, 81
Syaikh Ismail, 82, 83, 84
Syaikh Ismail Mawlana Ariffin, 82, 84
119
Syaikh Muhammad Yusuf, 82
Syarif Ibrahim Yunus, 82
Syarif Abdul Qodir, 84, 85
Syarif Aulia Muhammad, 82
Syarifah Mudaim, 46, 47, 107
Syekh Abdullah Iman, 47, 50
Syekh Ahmad Jalaludin, 58
Syekh Jumadil Kubro, 17, 50, 58, 106
T
Tangerang, 61, 78
Tidunan, 70, 94, 97, 104
Tome Pires, 5, 10, 25, 26, 27, 30, 49, 50, 51,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 84,
87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 111,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 122
Tuban, 3, 11, 72, 94, 97, 100, 102, 107, 122
Tumapel, 71, 90, 91, 93, 96, 97, 108
U
Upeh, 70, 84, 98, 103, 116
V
Vasco de Gama, 76
W
Walangsungsang, 46, 47, 96
Walisongo, 2, 3, 6, 7, 13, 31, 33, 49, 50, 54,
89, 96, 99, 103, 105, 106, 107, 112, 123,
124, 125
Wangsakerta, 39, 50, 76, 77, 78, 79, 84, 87, 96
Wayang, 65, 124
Winkler, 80
120
BIODATA PENULIS
Navida Febrina Syafaaty, lahir di Depok, Jawa Barat, 3 Februari 1992. Ia
menamatkan sekolah menengah pertama di SMP Islam PB Sudirman Jakarta (2007),
Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta (2011) dan kuliah sarjana
di Jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi
Manusia IPB, Bogor (2015).
Penulis selama sekolah dan kuliah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi.
Ketika SMP pernah menjadi Ketua OSIS, Ketua MPK dan wartawan siswa. Lalu saat
mondok pernah menjadi Ketua Kamar 308 Arafah, Ketua CLI, bagian persidangan
Keamanan OSDN 33, dan Ketua Bagian Keamanan Pusat OSDN 34. Penulis juga
selama di pondok aktif mengikuti berbagai perlombaan. Ketika kuliah pernah menjadi
Ketua RT lorong dua, BEM TPB bagian Kajian Strategi, BEM KM IPB bagian IPB
Social Politic Center, dan IPB Political School. Penulis selama kuliah juga aktif
menjadi panitia dan peserta diberbagai acara. Penulis pernah bekerja di Alif School
tahun 2016.