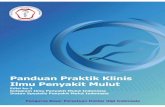Karakteristik Klinis Pasien Trauma Kelopak Mata di Instalasi ...
BUKU PANDUAN KETRAMPILAN KLINIS ( SKILLS LAB ) BLOK I HUMANIORA DAN BIOETIK
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of BUKU PANDUAN KETRAMPILAN KLINIS ( SKILLS LAB ) BLOK I HUMANIORA DAN BIOETIK
BUKU PANDUAN
KETRAMPILAN KLINIS
( SKILLS LAB )
BLOK I
HUMANIORA DAN BIOETIK
Edisi Revisi
Kode :
13130111
Kredit : 5 SKS
Semester : I
TIM
BLOK I
HUMANIORA DAN BIOETIK
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2014
A. AREA KOMPETENSI BLOK
1. Area Profesionalitas yang Luhur
a. Ber-Ketuhanan yang Maha Esa /Yang Maha Kuasa
b. Bermoral, beretika dan disiplin
c. Sadar dan taat hukum
d. Berwawasan sosial budaya
e. Berperilaku profesional
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri
a. Menerapkan mawas diri
b. Mempraktikan belajar sepanjang hayat
c. Mengembangkan pengetahuan
3. Area Komunikasi Efektif
a. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga
b. Berkomunikasi dengan mitra
c. Berkomunikasi dengan masyarakat
4. Area Pengelolaan Informasi
a. Mengakses dan menilai informasi pengetahuan
b. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan
secara efektif kepada profesional kesehatan,
pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk
peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Penjabaran Kompetensi
1. Profesionalitas yang luhur
1.1 Kompetensi Inti
Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang
profesional sesua dengan nilai dan prinsip
ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin,
hukum dan sosial budaya.
1.2 Lulusan Dokter mampu
a. Ber-Ketuhan-an ( Yang Maha Esa Yang Maha
Kuasa )
1) Bersikap dan berperilaku yang ber-Ketuhan-an
dalam praktik kedokteran
2) Bersikap bahwa yang dilakukan dalam pratik
kedokteran merupakan upaya maksimal
b. Bermoral, beretika, dan berdisiplin
1) Bersikap dan berperilaku sesua dengan
standar nilai moral yang luhur dalam praktik
kedokteran
2) Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika
kedokteran dan kode etik edokteran Indonesia
3) Mampu mengambil keputusan terhadap dilema
etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat
4) Bersikap disiplin dalam praktik kedokteran
dan bermasyarakat
c. Sadar dan Taat Hukum
1) Mengidentifikasi masalah hukum dan pelayanan
kedokteran dan memberikan saran cara
pemecahannya
2) Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum
dan ketertiban masyarakat
3) Taat terhadap perundang-undangan dan aturan
yang berlku
4) Membantu penegakkan hukum serta keadilan
d. Berwawasan sosial budaya
1) Mengenali sosial budaya ekonomi masyarakat
yang dilayani
2) Menghargai perbedaan persepsi yang
dipengaruhi oleh agama, usia, gender. Etnis,
difabilitas, dan sosial budaya ekonomi dalam
menjalankan praktik kedokteran dan
bermasyarakat
3) Menghargai dan melindungi kelompok rentan
4) Menghargai upaya kesehatan komplementer dan
alternatif yang berkembang di masyarakat
multikultural
e. Berperilaku profesional
1) Menunjukkan karakter sebagai dokteryang
profesional
2) Besikap dan berbudaya menolong
3) Mengutamakan keselamatan pasien
4) Mampu bekerja ama intra dan interprofesional
dalam tim pelayanan kesehatan demi
keselamatan pasien
5) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam
rangka sistem keehatan nasional dan global
b. Mawas Diri dan pengembanga Diri
2.1 Kompetensi inti
Mampu melakukan praktik kedokteran dengan
menyadari keterbatasan, mengatasi masalah
personal, mengembangkan diri, mengikuti
penyegaran dan peningkatan pengetahuan
secara berkesinambungan serta mengembangkan
pengetahuan demi keselamatan pasien.
2.2 Lulusan dokter mampu :
a. Menerapkan mawas diri
1) Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan
fisik, psikis, sosial dan budaya diri
sendiri
2) Tanggap terhadap tantangan profesi
3) Menyadari keterbatasan kemampuan diri dan
merujuk kepada yang lebih mampu
4) Menerima dan merespons positif umpan balik
dari pihak lain untuk pengembangan diri
b. Mempraktikan belajar sepanjang hayat
1) Menyadari kinerja profesionalitas diri dn
mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk
mengatasi kelemahan
2) Berperan aktif dlam upaya pengembangan
profesi
3) Mengembangkan pengetahuan baru
4) Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan
dengan masalah kesehatan pada individu,
keluarga, dan masyarakat serta
mendisemunasikan hasilnya
c. Komunikasi Efektif
3.1 Kompetensi inti
Mampu menggali dan bertukar informasi secara
verbal dan non verbal denan pasien pada
semua usia, anggota keluarga, masyarakat,
kolega, dan profesi lain.
3.2 Lulusan Dokter Mampu
a. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya
1) Membangun hubungan melalui komunikasi verbal
dan non verbal
2) Berempati secara verbal dan nonverbal
3)Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang
santun dan dapat dimengerti
4)Mendengarkan dengan aktif untuk menggali
permasalahan keehtan secara holistik dan
komprehensif
5)Menyampakan informasi yang terkait kesehatan
( termasuk berita buruk, informed consent )
dan melakukan konseling dengan cara yang
santun, baik dan benar
6)Menunjukkan kepekaan terhadap aspek
biopsikososiokultual dan spiritual pasien
dan keluarga
b. Berkomunikasi dengan mitra kerja ( sejawat
dan profesi lainnya )
1) Melakukan tatalaksana konsultasi dan
rujukkan yang baik dan benar
2) Membangun komunikasi interprofesional dalam
pelayanan kesehatan
3) Memberian informasi yang sebenarnya dan
relevan kepada penegak hukum, perusahaan
asuransi kesehatan, media massa dan pihak
lainnya jika diperlukan
4) Mempresentasikan informasi ilmiah seca
efekif
c. Berkomunikasi dengan masyarakat
1) Melakukan komunikasi denan masyarakat dalam
rangka mengidentifikasi masalah kesehatan
dan memecahkannya bersama-sama
2) Melakukan advokasi dengan pihak terkait
dalam rangka pemecahan masalah kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat.
d. Pengelolaan Informasi
4.1 Kompetensi inti
Mampu memanfaatkan teknologi informaasi
komunikasi dan informasi kesehatan dalam
praktik kedokteran
4.2 Lulusan Dokter mampu
a. Mengakses dan menilai informasi dan
pengetahuan
1) Mengakses dan menilai informasi komunikasi
dan informasi kesehatan untuk meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan
2) Memanfaatkan ketrampilan pengelolaan
informai kesehatan untuk dapat belajar
sepanjang hayat
b. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan
secara efektif kepada profesi kesehatan
lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait
untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Memanfaatkan ketrampilan pengelolaan
informasi untuk diseminasi informai dalam
bidang kesehatan
1. Daftar Ketrampilan
No. Komunikasi
Tingkat
Ketrampil
an
1.
Menyelenggarakan
komunikasi lisan maupun
tulisan
4A
2.
Edukasi, nasihat dan
melatih individu dan
kelompok mengenai
kesehatan (teknik dasar
)
4A
3. Komunikasi lisan dan
tulisan kepada teman
sejawat atau petugas
lainnya ( rujukan atau
4A
konsultasi )
METODE PEMBELAJARAN
1. Sesi Terbimbing
( mahasiswa akan diberikan ketrampilan kliis dipandu oleh
Instruktur)
2. Sesi belajar mandiri
( mahasiswa aktif berlatih sendiri di rumah maupun di ruang
skills lab
dengan ijin kepala skills lab )
3. Sesi Responsi
( mahasiswa akan dievaluasi kemampuan ketrampilan
SKILLS LAB I
TEKNIK KOMUNIKASI
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Mahasiswa mampu melakukan teknik komunikasi
lisan dan tulisan
B. DASAR TEORI
Komunikasi adalah proses penyampaian
dan penerimaan pesan dari seseorang yang
dibagi kepada orang lain. Berkomunikasi
berarti membantu menyampaikan pesan untuk
kemudian diketahui dan pahami bersama. Pesan
dalam komunikasi digunakan dalam memilih dan
pengambilan keputusan.( Ariyanto )
Komunikasi melibatkan hubungan antar manusia
dan mengharuskan memiliki
peserta komunikasi dan persamaan pemahaman.
Persamaan bahasa dan gerak tubuh adalah
sarana utama yang orang mempengaruhi orang
lain. Dalam komunikasi antarpribadi proses
komunikasi yang berlangsung secara dinamis
dan transaksional demikian hal komunikasi
massa diperlukan untuk menyampaikan pesan
kepada publik yang lebih luas untuk mencapai
khalayak luas.
Seperti semua jenis komunikasi
antar manusia, komunikasi kesehatan dapat
mengambil berbagai bentuk dan terjadi dalam
konteks yang berbeda. Perbedaan dasar dalam
semua komunikasi antara manusia seperti,
komunikasi verbal (bahasabased) dan non-verbal.
Masing-masing dapat terjadi di sejumlah
tingkatan kontekskomunikasi yang berbeda.
Komunikasi verbal, proses berkomunikasi
berlangsung dalam konteks tingkatan diri-
sendiri (komunikasi intrapersonal) atau
dengan orang.
Indonesian patients still feel reluctant to
be actively involved in a communication with
health professional; which will lead to
ineffective and inefficient communication
session, (Kim YM, et al, 2002)
Komunikasi kesehatan melibatkan
dokter, pasien, dan keluarga adalah
komunikasi. Seorang pasien yang datang
berobat memiliki harapan akan kesembuha
penyakitnya, yang tidak dapat dihindari
dalam kegiatan kesehatan atau klinikal.
Pasien datang merobat menyampaikan
keluhannya, didengar, dan ditanggapi oleh
dokter sebagai respon dari keluhan tersebut
sedangkan seorang dokter mempunyai kewajiban
memberikan pengobatan sebaik mungkin.
Komunikasi dalam lingkup kesehatan begitu
penting. Hasil konferensi tentang komunikasi
kesehatan yang berlangsung di Toronto
menghasilkan ‘Toronto Consensus”,
menghasilkan 8 (delapan) point pernyataan
hubungan antara praktek komunikasi dan
kesehatan sebagai berikut :
1. Communication problems in medical practice are
important and common.
2. Patient anxiety and dissatisfaction are related to
uncertainty and lack of information, explanation and
feedback.
3. Doctors often misperceive the amount and type of
information that patients want to receive.
4. Improved quality of clinical communication is related to
positive health outcomes.
5. Explaining and understanding patient concerns, even
when they cannot be resolved, results in a fall in anxiety.
6. Greater participation by the patient in the encounter
improves satisfaction, compliance and treatment outcomes.
7. The level of psychological distress in patients with serious
illness is less when they perceive themselves to have received
adequate information.
8. Beneficial clinical communication is routinely possible in
clinical practice and can be achieved during normal clinical
encounters, without unduly prolonging them, provided that
the clinician has learned the relevant techniques. (Dianne
Berry, 2007:31)
Aplikasi definisi komunikasi dalam
interaksi antara dokter dan pasien di tempat
praktik diartikan tercapainya pengertian dan
kesepakatan yang dibangun dokter bersama
pasien pada setiap langkah penyelesaian
masalah pasien. Untuk sampai pada tahap
tersebut, diperlukan berbagai pemahaman
seperti pemanfaatan jenis komunikasi (lisan,
tulisan/verbal, non-verbal), menjadi
pendengar yang baik (active listener),
adanya penghambat proses komunikasi (noise),
pemilihan alat penyampai pikiran atau
informasi yang tepat (channel), dan mengenal
mengekspresikan perasaan dan emosi.
Selanjutnya definisi tersebut menjadi
dasar model proses komunikasi yang berfokus
pada pengirim pikiran-pikiran atau informasi
(sender/source), saluran yang dipakai
(channel) untuk menyampaikan pikiran-pikiran
atau informasi, dan penerima pikiran-pikiran
atau informasi (receiver). Model tersebut
juga akan adanya penghambat pikiran-pikiran
atau informasi sampai ke penerima (noise),
dan umpan balik (feedback) yang
memfasilitasi kelancaran komunikasi itu
sendiri.
tercapainya pengertian dan kesepakatan yang
dibangun dokter bersama pasien pada setiap
langkah penyelesaian masalah pasien.
Diperlukan pemahaman :
- jenis komunikasi (lisan, tulisan/verbal,
non-verbal),
- menjadi pendengar yang baik (active
listener),
- penghambat proses komunikasi (noise),
- pemilihan channel yang tepat
- mengenal mengekspresikan perasaan dan
emosi.
KOMUNIKASI LISAN/ VERBAL
Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis
simbol yang menggunakan satu kata atau
lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai
sistem kode verbal (Deddy Mulyana, 2005).
Bahasa dapat didefinisikan sebagai
seperangkat simbol, dengan aturan untuk
mengkombinasikan simbol-simbol tersebut,
yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.
Bahasa mempunyai tiga fungsi: penamaan
(naming atau labeling), interaksi, dan
transmisi informasi.
1. Penamaan atau penjulukan merujuk pada
usaha mengidentifikasikan objek, tindakan,
atau orang dengan menyebut namanya sehingga
dapat dirujuk dalam komunikasi.
2. Fungsi interaksi menekankan berbagi
gagasan dan emosi, yang dapat mengundang
simpati dan pengertian atau kemarahan dan
kebingungan.
3. Melalui bahasa, informasi dapat
disampaikan kepada orang lain, inilah yang
disebut fungsi transmisi dari bahasa.
Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi
informasi yang lintas-waktu, dengan
menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa
depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan
tradisi kita.
Cansandra L. Book (1980), dalam Human
Communication: Principles, Contexts, and
Skills, mengemukakan agar komunikasi kita
berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi
tiga fungsi, yaitu:
1. Mengenal dunia di sekitar kita.
Melalui bahasa kita mempelajari apa saja
yang menarik minat kita, mulai dari sejarah
suatu bangsa yang hidup pada masa lalu
sampai pada kemajuan teknologi saat ini.
2. Berhubungan dengan orang lain.
Bahasa memungkinkan kita bergaul dengan
orang lain untuk kesenangan kita, dan atau
mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan
kita. Melalui bahasa kita dapat
mengendalikan lingkungan kita, termasuk
orang-orang di sekitar kita.
3. Untuk menciptakan koherensi dalam
kehidupan kita. Bahasa memungkinkan kita
untuk lebih teratur, saling memahami
mengenal diri kita, kepercayaan-kepercayaan
kita, dan tujuan-tujuan kita.
Keterbatasan Bahasa:
1. Keterbatasan jumlah kata yang
tersedia untuk mewakili objek.
2. Kata-kata adalah kategori-kategori
untuk merujuk pada objek tertentu: orang,
benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan
sebagainya. Tidak semua kata tersedia untuk
merujuk pada objek. Suatu kata hanya
mewakili realitas, tetapi buka realitas itu
sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada
dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan
sesuatu secara eksak.
3. Kata-kata sifat dalam bahasa
cenderung bersifat dikotomis, misalnya baik-
buruk, kaya-miskin, pintar-bodoh, dsb.
4. Kata-kata bersifat ambigu dan
kontekstual.
5. Kata-kata bersifat ambigu, karena
kata-kata merepresentasikan persepsi dan
interpretasi orang-orang yang berbeda, yang
menganut latar belakang sosial budaya yang
berbeda pula. Kata berat, yang mempunyai
makna yang nuansanya beraneka ragam*.
Misalnya: tubuh orang itu berat; kepala
sayaberat; ujian itu berat; dosen itu
memberikan sanksi yang berat kepada
mahasiswanya yang nyontek.
6. Kata-kata mengandung bias budaya.
7. Bahasa terikat konteks budaya. Oleh
karena di dunia ini terdapat berbagai
kelompok manusia dengan budaya dan subbudaya
yang berbeda, tidak mengherankan bila
terdapat kata-kata yang (kebetulan) sama
atau hampir sama tetapi dimaknai secara
berbeda, atau kata-kata yang berbeda namun
dimaknai secara sama.
8. Konsekuensinya, dua orang yang
berasal dari budaya yang berbeda boleh jadi
mengalami kesalahpahaman ketiaka mereka
menggunakan kata yang sama. Misalnya
kata awak untuk orang Minang
adalah saya atau kita, sedangkan dalam
bahasa Melayu (di Palembang dan Malaysia)
berarti kamu.
9. Komunikasi sering dihubungkan
dengan kata Latin communis yang artinya
sama. Komunikasi hanya terjadi bila kita
memiliki makna yang sama. Pada gilirannya,
makna yang sama hanya terbentuk bila kita
memiliki pengalaman yang sama. Kesamaan
makna karena kesamaan pengalaman masa lalu
atau kesamaan struktur kognitif
disebut isomorfisme.Isomorfisme terjadi bila
komunikan-komunikan berasal dari budaya yang
sama, status sosial yang sama, pendidikan
yang sama, ideologi yang sama; pendeknya
mempunyai sejumlah maksimal pengalaman yang
sama. Pada kenyataannya tidak
ada isomorfisme total.
10. Percampuranadukkan fakta,
penafsiran, dan penilaian.Dalam berbahasa
kita sering mencampuradukkan fakta (uraian),
penafsiran (dugaan), dan penilaian. Masalah
ini berkaitan dengan dengan kekeliruan
persepsi. Contoh: apa yang ada dalam pikiran
kita ketika melihat seorang pria dewasa
sedang membelah kayu pada hari kerja pukul
10.00 pagi? Kebanyakan dari kita akan
menyebut orang itu sedang bekerja. Akan
tetapi, jawaban sesungguhnya bergantung
pada: Pertama, apa yang dimaksudbekerja?
Kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk
mencari nafkah? …. Bila yang
dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan
tetap untuk mencari nafkah, maka orang itu
memang sedang bekerja. Akan tetapi, bila
pekerjaan tetap orang itu adalah sebagai
dosen, yang pekerjaannya adalah membaca,
berbicara, menulis, maka membelah kayu bakar
dapat kita anggap bersantai baginya, sebagai
selingan di antara jam-jam kerjanya.
(dwiuwiq, 2012 )
Komunikasi Lisan dibagi tiga tahap :
4. Komunikasi personal
Hilangkan ambiguitas, bertanya untuk
memastikan, catat point-point penting,
gunakan alat bantu, sampaikan rangkuman
5. Presentasi atau beretorika
Persiapan yang matang, pembukaan yang
menarik, memberikan penekanan pada point-
point yang penting, gunakan fakta, gunakan
alat bantu, perhatikan bahasa tubuh dan
intonasi, kontak mata, libatkan audiensi.
6. Diskusi grup
KOMUNIKASI NON VERBAL
Komunikasi non verbal dokter yaitu kinesik
berupa ekspresi wajah dan kontak mata,
haptik contoh berupa sentuhan dan mengelus-
ngelus kepala anak/ bayi atau memegang
anggota tubuh pasien, proksemik berupa
proksemik jarak, proksemik ruang, dan
proksemik waktu, paralinguistik berupa cara
berbicara, dan artifak yang ditunjukkan
berupa pakaian yang dikenakan oleh dokter.
Hambatan yang terjadi ketika dokter
berkomunikasi dengan pasien adalah hambatan
psikologis karena kondisi atau keadaan
pasien, seperti rewel, cengeng, dalam
keadaan sakit dan perasaan takut pasien.
Hambatan ekologis disebabkan oleh gangguan
lingkungan dalam proses berlangsungnya
komunikasi. Hambatan tersebut adalah
lingkungan fisik yang berupa kondisi ruangan
dan suasana ruangan yang kurang memadai.
(Pratiwi dkk , 2010 )
MENDENGAR AKTIF
Hal mendengar aktif adalah salah
satu unsur penting dalam proses komunikasi
terutama proses konseling. Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam mendengar aktif
adalah :
1. Perhatian
Adalah suatu usaha yang serius dan kerja
keras , tidak hanya mendengarkan tetapi
mengkomunikasikan keterlibatan yang aktif.
Sehingga dapat memahami yang dialami pasien,
menunjukkan rasa hormat, dan terus terpusat
pada satu atau dua perhatian tertentu.Karena
ketiga hal tersebut dapat menolong pasien
dalm memahami masalah dan keluhannya.
Cara memperhatikan secara efektif yaiutu :
a. Menjaga kontak mata. Kontak mata menunjukka
anda sedang mendengarkan apa yang dikatakan
pasien dan membuat kita dapat dipercaya.
Perhatikan kapan pasien membuang
pandangannya , maka kitan akan mengetahu apa
yang membuat dia malu, terancam dan mencuri
perhatiannya.
b. Gunakan bahasa tubuh dengan fasih. Untuk
menunjukkan keterlibatan kita,dengan
menghadapkan badan ke arah kita. Pakailah
gerakan yang mengekspresikan semangat.
c. Iktilah apa yang dikatakan pasien, dengan
demikian ia melihat kita tertaik dan memberi
perhatian terhadap perkataanya. Jangan
pernah memotong pembicaraan pasien atau
melompat dari satu pokok ke pokok yang
lainnya dan jangan menceritakan pribadi dan
pengalaman endiri
2. Respon-respon selanjutnya
Setelah mendengarkan pasien, berikan espon
yng mendorong pasien untuk terus
menceritakan keluhannya. Respon tersebut
seperti “ O,ya?” , “ Hmmm” , “Lalu”, “Oke
saya mengerti. Dan bijak dalam
menggunakannya.
3. Menyatakan kembal
Setelah pasien menceritakan keluhannya, ada
baiknya mengulangi apa yang dibicarakannya.
Dengan demikian pasien bisa mengulangi
maksud penjelasan/ ceritanya, dan merupakan
sarana yang baik untuk meminta informasi
yang lebih banyak, sambil tetap tinggal pada
poko yang sama seperti yang dikemukkan
pasien.
4. Waktu Diam
Dalam satu komunikasi pembicaraan, jika satu
pihak diam, maka pihak yang lain akan
bicara. Apabila keduanya diam, maka suasana
akan tegang, dalam situasi seperti ini
jangan langsung memberikn pertanyaan,
menawarkan jaminan atau memberikan usulan
solusi. Coba untuk memandang saat idam itu
dari sudut pandang pasien. Bisa jadi pasien
sedang merenungkan kembali apa yang telah
diceritakannya kepada pemeriksa. Ketika kita
memberikan jeda untuk bicara ini adalah
langkah positif , bawa pemeriksa menghormati
pasien dan memberikan wakt kepadanya untuk
memikirkan masalahnya. Tetapi jangan berlama
karena pasien akan menanti reaksi pemeriksa
setelah mendengarkan keluhannya. Dan
gunakanlah saat diam inipada waktu awal-awal
pasien mengungkapkan isi hatinya dan bukan
pada perakapan selanjutnya. Hindari
konfrontasi yag tidak berguna, jika pasien
tidak tahu harus berkata apa maka berikanlah
nasehat atau edukasi diluar waktu diam.
Tetapi kembalilah kepada pokok yang menjadi
perhatian pasien.
5. Fokus
Pendengar yang aktif akan mempengaruhi apa
yang akan dibicarakan lawan bicaranya.
Respon pemeriksa terhadap suatu pernyataan
akan membuat respon pasien terfokus pada
pemeriksa. Kita memiliki kekuatan yang luar
biasa untuk mengarahkan pembicaraan, bahkan
hanya dengan jawaban-jawaban yang singkat
sekalipun. Pemeriksa sebainya memberikan
beberpa pandangan pada pasien. Akan tetapi
jangan berusaha menolong pasien jika
ternyata pasien kembali tidak fokus dan
seperti menolak pandangan pemeriksa.
6. Pertanyaan
Pertanyaan bertujuan menfokuskan pasien
supaya pemeriksa mampu menggali berbagai
informasi dari pasien. Ada cara agar
pertanyaan kita efektif yaitu :
a. Jangan menggunakan dua puluh pertanyaan,
artinya jangan mengubah proses edukasi atau
konseling menjadi tanya jawab yang hanya
menjawab ya dan tidak. Pertanyaan yang
panjang juga akan membantu untuk memahami
kasus yang dihadapi dengan lebih baik.
b. Mintalah jawaban satu persatu. Sehingga
tidak membuat pasien bingung.
c. Hindari pertanyaan yang memberikan pilihan
terbatas, pertanyaan ini akan membuat sikap
defensif
d. Berhemat dengan pertanyaan yang memakai kata
mengapa. Pertanyaan mengapa akan membuat
orang merasa tertakan dan akan bersikap
defensif
e. Berfikirlah sebelum bertanya, usahakan
membuat percakapan yang nyaman, dan pasien
mau memberi informasi serta sukarela, bukan
seperti menginterogasi terdakwa.
f. Pencerminan isi. Pemeriksa harus menyaring
informasi yang diperolehnya dari pasien dan
menyampaikan kembali apa yang dipahaminya
dengan bahasa sendiri. Hal ini berbeda
dengan menyatakan kembali isi cerita. Jika
pencerminan ini dilakukan dengan tepat dan
peka akan membuat lancar percakapan dan
menunjukkan pemeriksa terlibt akktif dalam
mendengarkan masalah pasien dan menolongnya
menjalankan masalah-masalahnya.
Konsep Lasswell yang menggambarkan
komunikasi secara sederhana menjawab
pertanyaan” Siapa mengatakan ApaSaluran Apa
kepada Siapa Dengan pengaruh Bagaimana?”
berikut :
Who ( sender )
Say what ( massage )
In what Channel ( channel)
To whom ( receiver )
With what effect ( effect )
Komunikasi tertulis
Komunikasi Tertulis adalah komunikasi yang
dilaksanakan dalam bentuk surat dan
dipergunakan untuk menyampaikan berita yang
sifatnya singkat, jelas tetapi dipandang
perlu untuk ditulis dengan maksud-maksud
tertentu. Contoh- contoh komunikasi tertulis
ini antara lain:
1.naskah, yang biasanya dipergunakan untuk
menyampaikan berita yang bersifat komplek.
2.blangko-blangko, yang dipergunakan untuk
mengirimkan berita dalam suatu daftar.
3.gambar clan foto, karena tidak dapat
dilukiskan dengan kata-kata atau kalimat.
4.spanduk, yang biasa dipergunakan untuk
menyampaikan informasi kepada banyak orang.
Dalam berkomunikasi secara tertulis,
sebaiknya dipertimbangkan maksud dan tujuan
komunikasi itu dilaksanakan. Disamping itu
perlu juga resiko dari komunikasi tertulis
tersebut, misalnya aman, mudah dimengerti dan
menimbulkan pengertian yang berbeda dari yang
dimaksud. ( Fauzi M.R, 2011)
Kelebihan komunikasi tulis
Secara historis, komunikasi tertulis
memiliki arti penting bagi sejarah peradaban
manusia. Tulisan merupakan titik awal sejarah
manusia. Dengan kata lain, manusia dapat
dikatakan memasuki zaman sejarah ketika
mereka telah mengenal tulisan. Selain itu,
komunikasi tertulis memiliki fungsi
dokumentasi dan transformasi budaya.
Dibandingkan dengan komunikasi lisan,
komunikasi tertulis memiliki beberapa
kelebihan. Pertama, komunikasi tertulis lebih
tahan lama. Artinya, komunikasi tertulis
memiliki bentuk fisik baik berupa kertas,
kulit binatang maupun prasasti batu.
Sedangkan komunikasi lisan tidak memiliki
bentuk fisik. Kita tidak tahu kemana perginya
kata atau kalimat setelah diucapkan.
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa
komunikasi tertulis memiliki fungsi
dokumentasi. Sehingga pesan atau informasi
yang terkandung di dalamnya bisa tersampaikan
meski pemberi pesan sendiri sudah meninggal.
Sebagai contoh, pemikiran-pemikiran Plato,
Aristoteles dan filsuf lainnya hingga kini
masih bisa kita terima karena mereka
memahatkan ajaran mereka pada lempengan-
lempengan batu. Meski jasad Karl Marx,
Darwin, Max Weber sudah hancur dalam tanah,
kita dan generasi sesudah kita masih bisa
menerima informasi tentang pemikiran mereka
selama perpustakaan menyimpan buku-buku karya
mereka. Bukti lain yang tak kalah penting
adalah bahwa kita masih bisa meneruskan
tradisi dan ajaran agama karena adanya kitab-
kitab suci. Semua agama besar di dunia pasti
memiliki kitab suci. Di sini kita bisa
melihat bahwa kitab suci agama merupakan
sarana komunikasi tertulis yang memuat
seperangkat aturan, cerita masa lalu,
ancaman, kabar gembira tentang masa depan
yang semuanya bertujuan melestarikan dan
mempertahankan tradisi (Suseno, 1997:17).
Kedua, komunikasi tertulis berlangsung
secara massive dan dinamis. Berkat jasa
Gutenberg, informasi dapat diproduksi secara
massal dengan biaya yang lebih murah.
Sehingga informasi dapat tersebar dengan
cepat dan mudah. Suseno (1997:27) menyebutkan
bahwa keberhasilan Reformasi Gereja Martin
Luther di Jerman salah satunya dengan
menggunakan sarana pencetakan. Mereka
melemparkan gagasan dan argumen melalui
selebaran yang mereka sebar. Dikatakan pula
bahwa jika sebelumnya pikiran orang hanya
dapat dipengaruhi melalui orasi (yang
terbatas pada beberapa ratus orang dan
diucapkan sekali saja serta dengan mudah
dikontrol), kini pikiran orang dapat
dipengaruhi melalui leaflet, buku dan media cetak
lain yang dapat dibaca dan didiskusikan
berulang-ulang dengan angota masyarakat lain.
Ketiga, komunikasi tertulis relatif
lebih terstruktur dan terencana. Sebagai
sebuah tindakan strategis (Littlejohn,
2002:13), komunikasi lebih bisa direncanakan
dan disusun ketika disampaikan melalui media
tulisan. Komunikator dapat menyusun pesan,
menggunakan kata-kata pilihan, memilih topik
tertentu dan memperkirakan respon dari
audience. Sehingga proses komunikasi bisa
dievaluasi dan dikembangkan.
Keempat, ketika kita tidak memahami
sesuatu hal dari apa yang kita baca atau kita
menemui kata asing, kita bisa mengulangi
beberapa paragraf sebelumnya, menggunakan
kamus atau bertanya kepada seseorang untuk
memahaminya. Berbeda dengan komunikasi lisan
yang berlangsung hanya sekali, kita tentu tak
bisa serta merta meminta pembicara untuk
mengulangi kalimat yang tidak kita pahami.
Kelemahan komunikasi tertulis
Sebagai bagian dari komunikasi verbal,
komunikasi tertulis tak bisa lepas dari
penggunaan bahasa sebagai sarana bertukar
makna. Oleh karena itu, kelemahan unsur
kebahasaan dalam proses komunikasi tentunya
menjadi kelemahan dari komunikasi tertulis.
Larry L. Barker sebagaimana dikutip Dedy
Mulyana dalam Pengantar Ilmu Komunikasi
menyebutkan tiga fungsi bahasa: penamaan
(labeling), interaksi dan transmisi informasi.
Penamaan merupakan usaha manusia untuk
mengidentifikasi objek, tindakan dan perasaan
yang berbeda dengan memberi nama pada objek,
tindakan dan perasaan tersebut.
Meski bahasa merupakan unsur yang sering
kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari,
bahasa memiliki sejumlah keterbatasan.
Mulyana (2002:245-255) menguraikan
keterbatasan bahasa sebagai sarana
komunikasi. Pertama, keterbatasan jumlah kata
yang tersedia untuk mewakili objek atau
perasaan. Tidak semua benda, peristiwa,
perasaan dapat diwakili oleh kata yang
berbeda. Suatu kata hanya mewakili realitas,
tetapi bukan merupakan realitas itu sendiri.
Kata hanya bisa mewakili sebagian dari
realitas, bukan keseluruhan realitas.
Keterbatasan bahasa dalam mewakili realitas
tampak pada penggunaan kata sifat. Kata sifat
cenderung dikotomis, maksudnya membagi
sesuatu hanya dalam dua kategori, semisal
kaya-miskin, bahagia-sengsara, pandai-bodoh,
baik-buruk dan lain sebagainya. Namun perlu
disadari bahwa realitas sesungguhnya tidaklah
sekaku itu. Kita tidak bisa memvonis bahwa
kalau tidak hitam berarti putih atau
sebaliknya. Antara warna hitam dan putih
terdapat puluhan bahkan ratusan warna abu-abu
yang pasti beda. Seringkali agar kata yang
kita ungkapkan lebih tepat, kita menggunakan
tambahan ‘agak’ atau ‘sangat’.
Untuk mengukur makna yang lebih akurat,
Charles E. Osgood, George Suci dan Percy
Tannenbaum merancang suatu instrumen yang
disebut Semantic Differential. Mereka mengukur
makna suatu konsep dalam skala 1 sampai 7.
dalam hal ini 1 menunjukkan kecenderungan
negative sedang angka 7 menunjukkan
kecenderungan positif (Mulyana,2002:246).
Kedua, kata bersifat ambigu dan
kontekstual. Setiap kata (meskipun sama)
berpotensi untuk dimaknai secara berbeda oleh
orang yang berbeda. Perbedaan makna tersebut
dipengaruhi oleh latar belakang tiap orang
yang tentunya berbeda. Pemaknaan kata juga
perlu memperhatikan konteks kalimatnya.
Ketiga, kata-kata mengandung bias
budaya. Budaya sangat mempengaruhi bahasa.
Menurut hipotesis Sapir-Whorf (Griffin,
2003:30) menyatakan bahwa struktur bahasa
suatu budaya membentuk persepsi dan perilaku
manusia. Dengan kata lain, struktur bahasa
menunjukkan budaya suatu masyarakat.
Misalnya, penggunaan tenses yang
memperhitungkan waktu dalam struktur bahasa
masyarakat Eropa menunjukkan penghargaan
mereka atas waktu. Penggunaan bahasa yang
bertingkat dalam budaya Jawa menunjukkan
sistem sosial masyarakat yang terbagi dalam
kelas-kelas tertentu. Oleh sebab itu, sangat
mungkin terjadi kita tidak menemukan padanan
yang tepat untuk kata tertentu dalam bahasa
asing.
Disamping kelemahan-kelemahan bahasa dalam
komunikasi tertulis tersebut, Beebe and Beebe
(1997:257) menyebutkan kelemahan dari
komunikasi tertulis adalah hubungan
antarpartisipan komunikasi berjarak.
Komunikator tidak bisa merinteraksi dengan
audien secara langsung, melihat perubahan
sikap yang terjadi atau merespon sikap
audien. Sehingga feedback dalam proses
komunikasi tersebut bersifat tidak langsung
dan tertunda (no immediate interaction). Sedang
dalam komunikasi lisan, hubungan pembicara
dengan audien berlangsung akrab, hangat dan
lebih personal.
Komunikasi tertulis bersifat lebih formal
daripada komunikasi lisan. Dalam komunikasi
tertulis kita terikat dengan konsep atau
aturan ejaan tertentu untuk memenuhi syarat
sebagai komunikasi tertulis yang baik. Kita
harus memperhatikan struktur kalimat yang
njelimet agar bisa dipahami oleh pembaca.
Sedangkan dalam komunikasi lisan pembicara
bisa memakai kalimat-kalimat pendek tanpa
harus mematuhi aturan kalimat yang baik
dengan alasan efisien.
(Maulinni’am MA , 2008)
C. ALAT DAN BAHAN
1. Meja dan kursi
2. Check List
3. Bolpoint
D. PRASYARAT :
1.Pemakaian Bahasa Indonesia yang baik dan
benar
2. Memakai Jas Skills lab dengan rapi
3. Mematuhi tata tertib dan aturan bagian
laboratorium ketrampilan klinis
4. Mahasiswa wajib membawa alat tulis sendiri
E. PROSEDUR PELAKSANAAN
1. Mahasiswa mempersilahkan pasien masuk ,
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
2. Mahasiswa mengucapkan :
a. Basmallah
“Bismillahirrahmanirrahiim”
b. salam “ assalamu’alaikum” dan
menjabat tangan pasien ( Islam :
menjabat tangan pasien yang sama
jenis kelaminnya/ orangtua) ,
c. menyapa pasien “ Selamat
pagi/siang/sore”,
d. Mempersilahkan pasien duduk
e. Menjaga kontak mata, senyum dan
tenang
3. Mahasiswa memperkenalkan diri : nama “
dr....” dan menanyakan identitas pasien
dan menuliskan pada lembar medis pasien:
a. Nama
b. Umur
c. Alamat
d. Pekerjaan
e. No telp yang bisa dihubungi
f. Pendidikan terakhir
4. Mahasiswa menanyakan maksud kedatangan
pasien
a. Keluhan utama : ingin konsultasi
b. Keluhan tambahan : sesuai skenario
5. Mendengar aktif ketika pasien
mengungkapkan keluhannya
“ skenario : seorang Ibu umur 34 tahun,
bekerja sebagai ibu rumah tangga, datang
ke dokter Fahmi untuk berkonsultasi,
merasa lelah, jantung selalu berdetak,
nafas seperti tertahan, kencing terus
jika minumnya banyak sudah sejak tiga
hari yang lalu setelah anaknya mengalami
kecelakan lalu lintas dan harus dirawat
di Rumah sakit “
Keluhan tambahan : susah tidur,
memikirkan anaknya apakah akan sebuh atau
cacat
6. Mahasiswa sebagi dokter menjaga kontak
mata, sesekali mengangguk, atau
menegaskan dengan kata ya atau baiklah
ketika pasien selesai menceritakan
keluhannya
7. Mahasiswa yang berperan sebagi Dokter
menanyakan kesedian nya untuk diperiksa,
hasil pemeriksaan normal ( tidak
memeriksa fisik )
8. Dokter mengumpulkan informasi :
Cemasnya datang pada saat apa
saja ? ( pasien menjawab : tidur )
Cemas berkurang pada saat apa?
( pasien menjawab : saat aktivitas
atau kegiatan , atau tidak sedang
sendirian )
Apakah anaknya sudah pulang ?
jawabnya sudah
Apakah anaknya sudah berangkat
sekolah? Belum, masih bengkak
kakinya, dokter berpesan jangan
untuk jalan terlalu lama.
Apakah ananya dioperasi atau di
gips? Jawabnya tidak
9. Mahasiswa sebagai Dokter mengulang
kembali dan menegaskan apa yang didapat
saat mengumpulkan informasi dengan
membuat ringkasan
Ringkasan dalam bentuk tulisan
dilembar medis pasien
10. Mahasiswa sebagai dokter menanyakan
kembali apakah ada yang terlewat?
11. Mahasiswa sebagai dokter memberikan
edukasi / saran kepada pasien
Bahwa pasien sehat
Pasien hanya diharapkan lebih
tenang dan ikhlas dalam menghadapi
kejadiannya yang menimpa anaknya
Pasien disarankan tidak berfikir
yang belum terjadi , misal anaknya
pasti nanti jalannya jadi pincang,
karena dokter yang memeriksa tidak
melakukan tindakan diarea kaki
anaknya
Dokter menegaska kembali pasien
sehat dan tidak perlu diberikan
resep obat.
12. Mengakhiri dengan :
Mengucapkan Hamdallah
Mengucapkan salam
Menjabat tangan pasien
Mengantar dan membukakan pintu
Penilaian Ketrampilan Klinis “ Teknik
Komunikasi”
No
.
Ketrampilan Bob
ot
Skor Tot
al
Nil
ai3 0 1 2 3
1 Mahasiswa mempersilahkan
pasien masuk , dengan
menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan
benar2 Mahasiswa mengucapkan :
a.Basmallah
“Bismillahirrahmanirrahii
3
m”
b.salam “
assalamu’alaikum” dan
menjabat tangan pasien
( Islam : menjabat tangan
pasien yang sama jenis
kelaminnya/ orangtua) ,
c.menyapa pasien “
Selamat pagi/siang/sore”,
d.Mempersilahkan pasien
duduk
e,Menjaga kontak mata,
senyum dan tenang
3 Mahasiswa memperkenalkan
diri dan menanyakan
kesediaan utuk wawancara:
nama “ dr....” dan
menanyakan identitas
pasien dan menuliskan
3
pada lembar medis pasien:
a.Nama
b.Umur
c.Alamat
dPekerjaan
e.No telp yang bisa
dihubungi
f.Pendidikan terakhir
4 Mahasiswa menanyakan
maksud kedatangan
pasien
a.Keluhan utama : ingin
konsultasi
b.Keluhan tambahan :
sesuai skenario
5 Mendengar aktif ketika
pasien mengungkapkan
keluhannya
6 Mahasiswa sebagi dokter
menjaga kontak mata,
sesekali mengangguk, atau
menegaskan dengan kata ya
atau baiklah ketika
pasien selesai
menceritakan keluhannya
7 Mahasiswa yang berperan
sebagi Dokter menanyakan
kesedian nya untuk
diperiksa, hasil
pemeriksaan normal
( tidak memeriksa fisik )
3
8 Dokter mengumpulkan
informasi :
Cemasnya datang pada
saat apa saja ? ( pasien
menjawab : tidur )
Cemas berkurang pada
saat apa? ( pasien
menjawab : saat
aktivitas atau
kegiatan , atau tidak
sedang sendirian )
Apakah anaknya sudah
pulang ? jawabnya sudah
Apakah anaknya sudah
berangkat sekolah?
Belum, masih bengkak
kakinya, dokter
berpesan jangan untuk
jalan terlalu lama.
Apakah ananya
dioperasi atau di
gips? Jawabnya tidak
9 Mahasiswa sebagai Dokter
mengulang kembali dan
menegaskan apa yang
didapat saat mengumpulkan
informasi dengan membuat
ringkasan
Ringkasan dalam bentuk
tulisan dilembar medis
pasien
10 Mahasiswa sebagai dokter
menanyakan kembali
apakah ada yang
terlewat?11 Mahasiswa sebagai dokter
memberikan edukasi /
saran kepada pasien
Bahwa pasien sehat
Pasien hanya
diharapkan lebih
tenang dan ikhlas
dalam menghadapi
kejadiannya yang
menimpa anaknya
Pasien disarankan tidak
berfikir yang belum
terjadi , misal
anaknya pasti nanti
jalannya jadi pincang,
karena dokter yang
memeriksa tidak
melakukan tindakan
diarea kaki anaknya
Dokter menegaska kembali
pasien sehat dan tidak
perlu diberikan resep
obat.
12 Mengakhiri dengan :
Mengucapkan
Hamdallah
Mengucapkan
3
salam
Menjabat
tangan pasien
Mengantar dan
membukakan
pintu
Penilaian : Total nilai x100%
50
dr..........................................
....................................