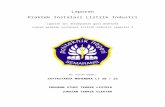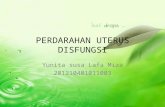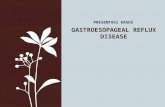Yunita
-
Upload
frans-elya-cohen-manalu -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
Transcript of Yunita

Systemic Lupus Eritematosus
Yunita
102010152
19 Maret 2012
Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana
Jl. Arjuna Utara No 6, Jakarta
Telp. (021) 5605140 E-mail : [email protected]
Pendahuluan
Lupus Eritematosus Sistemik (SLE) adalah penyakit rematik autoimun yang ditandai
adanya inflamasi tersebar luas, yang mempengaruhi setiap organ atau sistem dalam tubuh.
Penyakit ini berhubungan dengan deposisi autoantibodi dan kompleks imun sehingga
mengakibatkan kerusakan jaringan. SLE melibatkan berbagai sistem organ dengan manifestasi
klinik dan imunologik yang sangat bervariasi. Gejala umum seperti nyeri sendi, demam, lelah,
malaise atau penurunan berat badan sering ditemukan. Keluhan utama yang terbanyak adalah
gejala muskuloskeletal seperti artralgia, arthritis, mialgia dan kelemahan otot. Diperkirakan
bahwa faktor genetik, non genetic, hormonal dan imunologik turut mendukung terjadinya SLE.1
Anamnesis
Jenis anamnesis yang dapat dilakukan adalah autoanamnesis dan alloanamnesis.
Autoanamnesis dapat dilakukan jika pasien masih berada dalam keadaan sadar. Sedangkan bila
pasien tidak sadar, maka dapat dilakukan alloanamnesis yang menyertakan kerabat terdekatnya
yang mengikuti perjalanan penyakitnya.2
1. Identitas Pasien
Menanyakan kepada pasien/ orang tua dari anak : Nama lengkap pasien, umur
pasien ,tanggal lahir, jenis kelamin,agama, alamat, umur (orang tua), pendidikan dan
pekerjaan (orang tua) ,suku bangsa.2
2. Keluhan Utama : 2
1

Menanyakan keluhan utama pasien yaitu : badan terasa lemah, nyeri pada jari-jari kedua
tangan pada pagi hari, rambut banyak yang rontok, wajah mudah memerah bila terkena
sinar matahari, badan terasa hangat hilang timbul.
3. Riwayat Penyakit Sekarang3
Menanyakan kepada pasien/orang tua sebagai wali :
- Kapan pasien merasa tubuhnya lemah ?
- Nyeri sendi: lokasi nyeri
- Apakah ada komplikasi dan gejala klinis lain yang dirasakan ?
- Apakah pasien sudah melakukan tindakan pengobatan seperti berobat ke dokter lain,
atau sudah meminum obat ?
- Apakah setelah minum obat pasien bertambah baik atau semakin memburuk ?
4. Riwayat Penyakit Dahulu3
- Apakah pasien pernah terkena penyakit sendi sebelumnya ?
5. Riwayat Penyakit Dalam Keluarga3
- Apakah ada riwayat penyakit persendian atau penyakit autoimun dalam keluarga pasien ?
Jika data-data dari pasien sudah lengkap untuk anamnesis, maka dapat dilakukan pemeriksaan
fisik untuk menunjang anamnesis tadi.
Pemeriksaan Fisik
Inspeksi :
- Keadaan umum pasien : tampak sakit ringan
- Kesadaran pasien : - Kompos mentis (sadar sepenuhnya), apatis (pasien tampak
segan, acuh tak acuh terhadap lingkunganya), delirium (penurunan kesadaran
disertai kekacauan motorik, dan siklus tidur bangun yang terganggu), somnolen
(keadaan mengantuk yang masih dapat pulih penuh bila dirangsang, tetapi bila
rangsang berhenti, pasien akan tertidur lagi), sopor/stupor (keadaan mengantuk yang
dalam, pasien masih dapat dibangunkan tetapi dengan rangsangan yang kuat,
rangsang nyeri, tetapi pasien tidak terbangun sempurna dan tidak dapat memberikan
jawaban verbal yang baik).3
- Pemeriksaan kulit: dilihat apakah ada perubahan warna dan lipatan kulit abnormal.
2

- Adanya bengkak atau benjolan.
Palpasi :
Mencari dan memperlihatkan nyeri tekan, pembengkakan yang disebabkan oleh cairan
atau peradangan jaringan lunak, perubahan warna dan suhu kulit. Perubahan anatomi tulang atau
jaringan lunak, deformitas, kelemahan. Pemeriksaan fisik meliputi inspeksi dan palpasi.
Pemeriksaan fisik harus lengkap, tetapi dengan pertimbangan khusus adanya :3
Ruam
Demam
Anemia
Alopesia/ kebotakan
Limfadenopati
Ulkus mulut
Bengkak sendi : efusi dan nyeri tekan.
Takipnea : pertimbangkan hipertensi pulmonal, emboli paru, gagal ginjal disertai
kelebihan cairan, efusi pleura dan fibrosis paru.
Tekanan darah : periksa adanya hipertensi.
Edema pergelangan kaki
Neuropati
Defisit neurologis, termasuk defisit fokal dan gangguan kognitif.
Gangguan psikiatrik, khususnya psikosis.
Pemeriksaan Penunjang
Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien adalah
pemeriksaan hitung darah lengkap dan pemeriksaan kelainan imunologis ditemukan
sel LE, antibodi antinuclear, komplemen serum menurun, faktor rheumatoid dan uji terhadap
VDRL yang positif palsu. Tes antibodi anti-Ro positif pada 25% penderita lupus.
Tes komplemen serum, bila rendah menunjukkan penyakit lupus sedang
aktif biasanya disertai penyakit ginjal. Hasil pemeriksaan darah dapat
menunjukkan adanya anemia hemolitik, trombositopeni, limfopenia, atau
leukopenia; erythrocyte sedimentation rate (ESR) meningkat selama
3

penyakit aktif, test Coombs mungkin positif, level IgG mungkin tinggi, ratio
albumin-globulin terbalik, serum globulin meningkat, albumin dan sel darah
merah juga sering ditemukan pada urin.4
1. Adanya ANA
Hasil ini ditemukan pada 95% pasien SLE. Pola yang paling lazim adalah
homogen dan difus (pola yang menghasilkan sel LE). Antigen anti-DNA untai ganda dan
anti-Smith hanya ditemukan pada SLE, sedangkan antibodi lain seperti anti-DNA untai
tunggal bisa juga ditemukan pada penyakit lain. Antibodi lainnya misalnya anti-Ro dan
anti-La juga dapat ditemukan. Pada pasien dengan rematoid artritis serta para pasien
dengan penyakit autoimun yang relatif sehat dapat memiliki ANA positif. ANA positif
juga bisa karena faktor usia, infeksi virus tertentu.4
.
2. Tes faktor rheumatoid
Hasilnya positif pada 80% rheumatoid artritis dan 20-30% pasien SLE. Faktor
rheumatoid yang tinggi dan ANA yang rendah menunjukkan bahwa diagnosis rematoid
artritis. Antibodi anti cyclic citrullinated peptide (CCP), jika ada, cukup spesifik untuk
rematoid artritis dan hanya terlihat 5% pada SLE.4
3. Kelainan hematologik
Anemia normokromik normositik terdapat pada 40% pasien. Bisa ditemukan
tanda-tanda anemia hemolitik antara lain peningkatan haptoglobin serum.
Trombositopenia ditemukan pada 25% pasien. Kadar LED mungkin meningkat tetapi
tidak berhubungan dengan aktivitas penyakit.4
4. Antikoagulan lupus
Ditandai dengan adanya antikoagulan dalam sirkulasi dengan peningkatan PTT
atau antifosfolipid dalam sirkulasi (50% pasien dengan lupus) / antibody kardiolipin
terkait dengan thrombosis vena atau arterial.4
4

5. Pasien SLE dapat memiliki uji VDRL positif palsu. Namun antibodi Treponemal
fluoresen (FTA) akan negatif.4
6. Hipokomplementia (CH50, C3, C4) bisa ditemukan dan berhubungan dengan aktivitas
penyakit.4
7. Uji laboratorium yang kadang masih dipakai sampai sekarang adalah uji faktor LE. Sel
LE dapat juga ditemukan pada gangguan sistemik lain dari penyakit golongan reumatik
yang juga diperantarai oleh imunitas. Urin diperiksa untuk mengetahui adanya protein,
leukosit, eritrosit, dan silinder. Uji ini dilakukan untuk menentukan adanya kompliksi
ginjal dan untuk pemantauan perkembangan penyakit.4
Diagnosis
Dari data-data yang sudah didapat dari pasien. Maka ada beberapa kemungkinan bahwa
si pasien mengidap penyakit SLE (Sistemik Lupus Erithematosus), remathoid artritis,
osteoarthritis, dan artritis gout akut.
Working Diagnosis
Lupus Eritematosus Sistemik (LES)
Lupus erithematosus adalah suatu kondisi inflamasi yang berhubungan dengan sistem
imunologis yang menyebabkan kerusakan multi organ. Lupus eritematosus didefinisikan sebagai
gangguan autoimun, dimana sistem tubuh menyerang jaringannya sendiri. LES dapat disebabkan
oleh 3 hal yaitu reaksi hipersensitivitas, imunodefisiensi dan autoimun. Reaksi hipersensitivitas
merupakan reaksi imun tubuh yang bersifat terlalu sensitif/aktif. Reaksi hipersensitivitas tipe 3
yang menjadi dalang penyebab LES. Reaksi hipersensitivitas tipe III adalah reaksi yang terjadi
akibat pembentukan kompleks imun (kumpulan kompleks Ag-Ab). Imunodefisiensi adalah
lemahnya sistem imun tubuh dalam kerjanya sebagai sistem pertahanan tubuh. Lemahnya sistem
imun memudahkan tubuh terkena penyakit karena benteng patologis runtuh. Autoimun adalah
respon imun terhadap self-antigen karena hilangnya toleransi imun terhadap self-antigen
tersebut. Ketiga hal di atas menyebakan terbentuknya kompleks imun. Kompleks imun yang
5

terbentuk bisa mengendap. Kompleks imun dapat merangsang aktivasi komplemen dan
inflamasi untuk mengeliminasinya.5
Gejala-gejala
LES bersifat sistemik, artinya menyerang seluruh bagian tubuh. Gejala umunya berupa
kelelahan, pucat, anemia, demam dan berat badan menurun akibat nafsu makan menurun. Gejala
sistemik mulai dirasakan bila kompleks imun mengendap pada salah satu organ dan kemudian
organ lain. Organ yang paling utama diserang adalah dermatomuskuloskeletal (kulit dan
organ pergerakan). Pada penderita LES akan ditemukan ruam malar pada pipi yang berbentuk
kupu-kupu. Selain itu penderita sering mengalami rematik (nyeri otot, nyeri sendi). Alopecia
areata (kebotakan) juga akan telihat akibat pengecilan folikel rambut. Kompleks imun juga dapat
mengendap padaorgan vital seperti jantung, saraf, paru-paru, gastrointetinal, hati dan bahkan
organ lain.5
Diagnosis SLE dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinik dan laboratorium.
American College of Rheumatology (ACR) pada tahun 1982 mengajukan 11 kriteria untuk
klasifikasi SLE, dimana bila didapatkan 4 kriteria maka diagnosis SLE dapat ditegakkan. Kriteria
tersebut adalah :6
1. Ruam (rash) di daerah malar
Ruam berupa eritema terbatas, rata atau meninggi letaknya di daerah malar ,biasanya
tidak mengenai lipat nasolabialis.
2. Lesi diskoid
Lesi ini berupa bercak eritematosa yang meninggi dengan sisisk keratin yang melekat
disertai penyumbatan folikel . Pada lesi yang lama mungkin terbentuk sikatriks.
3. Fotosensitivitas
Terjadi lesi kulit sebagai akibat reaksi abnormal terhadap cahaya matahari. Hal ini
diketahui anamnesis atau melalui pengamatan dokter.
4. Alopecia atau kebotakan
Pada pasien SLE dapat timbul kerontokan rambut yang kadang-kadang dapat menjadi
berat hingga terjadi kebotakan (alopecia).
5. Ulserasi mulut
6

Ulserasi di mulut atau nasofaring biasanya tidak nyeri, diketahui melalui pemeriksaan
dokter .
6. Artritis
Artritis non-erosif yang mengenai 2 sendi perifer ditandai oleh nyeri, bengkak atau efusi.
7. Serositis.
a. Pleuritis : Adanya riwayat nyeri pleural atau terdengarnya bunyi gesekan pleura oleh
dokter atau adanya efusi pleura.
b. Perikarditis : Diperoleh dari gambaran EKG atau terdengarnya bunyi gesekan
perikard atau adanya efusi perikard
8. Kelainan ginjal
Proteinuria yang selalu >0,5 g/hari atau > 3+ atau
Ditemukan silinder sel, mungkin eritrosit, hemoglubulin granular, tubular atau
campuran.
9. Kelainan neurologis
a. Kejang yang timbul spontan tanpa adanya obat-obat yang dapat menyebabkan atau
kelainan metabollik seperti uremia, ketosidosis dan gangguan keseimbangan
elektrolit.
b. Psikosis yang timbul spontan tanpa adanya obat-obat yang dapat menyebabkan atau
kelainan metabollik seperti uremia, ketosidosis dan gangguan keseimbangan elektrolit
10. Kelainan hematologik
a. Anemia hemolotik dengan retikulositosis.
b. Leukopenia, kurang dari 4000/mm³ pada 2 kali pemeriksaan atau lebih .
c. Limfopenia, kurang dari 1500/mm³ pada 2 kali pemeriksaan atau lebih.
d. Trombositopenia, kurang dari 100.000/mm³ ,tanpa adanya obat yang mungkin
menyebabkannya.
11. Kelainan Imunologi
a. Adanya sel LE.
b. Anti DNA : antibodi terhadap native DNA (anti –dsDNA) dengan titer abnormal.6
7

Gambar 1. Ruam malar pada penderita SLE
Etiologi
Tiga faktor etiologi yang dianggap berperan dalam timbulnya penyakit ini adalah :1
Genetik : Faktor ini dibuktikan perannya melalui adanya fakta dimana kejadian penyakit
serupa pada kembar monozigotik sebanyak kira-kira 20% dibandingkan dengan pada
kembar dizigotik yang hanya 3%. Kemudian juga ditemukan fakta bahwa anggota keluarga
yang tidak manifest secara klinik, ternyata menunjukan adanya autoantibodi di serum.
Fenomena terakhir ini juga merupakan indikasi bahwa manifestasi klinik penyakit
autoimun ditentukan juga oleh factor pencetus lainnya misalnya factor lingkungan atau
non-genetik . Selanjutnya jenis HLA tertentu yang dulu dianggap merupakan predisposisi
terhadap penyakit autoimun ternyata berkaitan dengan pembentukan autoantibodi tertentu
seperti anti ds- DNA ,anti Sm dan antifosfolipid.1
Faktor genetic memegang peran penting dalam kerentanan serta ekspresi
penyakit. Sekitar 10%-20% pasien SLE mempunyai kerabat dekat (first-degree relative)
yang juga menderita SLE. Angka terdapatnya SLE pada saudara kembar identik pasien
SLE (24-69%) lebih tinggi daripada saudara kembar non-identik (2-9%). Penelitian-
penelitian terakhir menunjukan bahwa banyak gen yang berperan terutama gen yang
mengkode unsur-unsur system imun. Kaitan dengan haplotip MHC tertentu, terutama
HLA-DR₂ dan HLA-DR₃ serta dengan komponen komplemen yang berperan pada pada
fase awal reaksi ikat komponen (yaitu C₁Q -C₁R- C₁S ,C₄ dan C₂) telah terbukti. Gen-
gen lain yang mulai terlihat ikut berperan adalah gen yang mengkode reseptor sel T,
imunoglobin dan sitokin.6
8

Non-Genetik : Ada sejumlah obat yang dapat menginduksi penyakit SLE pada orang-
orang yang peka, suatu sindrom yang menyerupai SLE. Sindrom ini memiliki hampir
semua gejala SLE termasuk uji ANA yang positif, tetapi jarang menyerang ginjal dan SSP.
Gejala-gejala SLE yang timbul akan menghilang dalam waktu beberapa minggu setelah
obat yang menyebabkannya dihentikan. Hasil pemeriksaan ANA akan kembali menjadi
negatif dalam waktu beberapa bulan kemudian. Hidralazin dan prokainamid adalah dua
dari kelompok obat-obatan yang paling sering menimbulkan gangguan ini. Selain itu ada
juga beberapa obat yang mampu menimbulkan ANA positif, misalnya penisilamin,
isoniazid dan obat anti konvulsan seperti barbiturat, fenitoin, etosuksimid, metsuksimid dan
primidon. Beberapa obat dapat menyebabkan elsasernaso SLE pada pasien yang
sebelumnya berada dalam keadaan remisi. Kelompok ini mencakup sulfonamid,
penisilamin dan kontraseptif oral.1
Imunologik : Kelainan fungsi system imun diduga mendasari proses terjadinya lupus .
Letak kelainan masih kontroversial, semula diduga akibat sel B yang hiperaktif pada
perangsangan poliklonal, namun belakangan ini ditemukan indikasi bahwa letak kelainan
adalah pada sel T-helper. Mekanisme imunologik yang mendasari kerusakan jaringan pada
umumnya adalah hipersensitifitas tipe 3.1
Faktor Hormonal : SLE adalah penyakit yang lebih banyak menyerang perempuan.
Serangan pertama kali SLE jarang terjadi pada usia prepubertas dan setelah menopouse.
Metabolisme estrogen yang abnormal telah ditunjukkan pada kedua jenis kelamin, dimana
peningkatan hidroksilasi 16a dari estrone mengakibatkan peningkatan yang bermakna
konsentrasi 16a hidroksiestron. Metabolit 16a lebih kuat dan merupakan feminishing
estrogen. Perempuan dengan SLE juga mempunyai konsentrasi androgen plasma yang
rendah, ternasuk testoteron, dehidrotestoteron, dehidroepiandosteron (DHEA), dan DHEA
sulfat. Abnormalitas ini mungkin disebabkan oleh peningkatan oksidasi testoteron pada C-
17 atau peningkatan aktivitas aromatase jaringan.Konsentrasi testoteron plasma yang
rendah dan meningkaynya konsentrasi LH ditemukan pada beberapa penderita SLE laki-
laki maupun perempuan, jadi estrogen yang berlebihan dengan aktivitas hormon androgen
yang tidak adekuat pada laki-laki maupun perempuan mungkin bertanggung jawab
9

terhadap perubahan respon imun. konsentrasi progesteron didapatkan lebih rendah pada
penderita SLE perempuan dibandingkan dengan kontrol sehat.6
Hormon dari sel lemak diduga terlibat dalam patogenesis SLE adalah leptin.
Penelitian konsentrasi leptin serum pada penderita SLE perempuan yang dilakukan oleh
Garcia Gonzales dkk., mendapatkan kadar leptin pada penderita SLE tinggi dibanding
dengan kontrol sehat.6
Epidemiologi
Dalam 30 tahun terakhir, SLE telah menjadi salah satu penyakit reumatik utama di dunia.
SLE ditemukan lebih banyak pada wanita keturunan ras Afrika-Amerika, Asia,
Hispanik, dan dipengaruhi faktor sosioekonomi. Sebuah penelitian
epidemiologi melaporkan insidensi rata-rata pada pria ras kaukasia yaitu 0,3-
0,9 (per 100.000 orang per tahun); 0,7-2,5 pada pria keturunan ras Afrika-
Amerika; 2,5-3,9 pada wanita ras Kaukasia; 8,1-11,4 pada wanita keturunan
ras Afrika-Amerika. Penyakit ini dapat ditemukan pada semua usia, tetapi paling banyak
pada usia 15-40 tahun (masa reproduksi). Insidens SLE 1 dari 2500 orang dalam beberapa
populasi yang umum, rasio perempuan dibanding laki-laki adalah 9 : 1. Pada lupus eritematosus
yang disebabkan obat (drug induced LE) rasionya lebih rendah yaitu 3:2. Beberapa data yang ada
di Indonesia diperoleh dari pasien yang dirawat dari rumah sakit. Kejadiannya 90% pada wanita,
seringkali mengenai wanita pada usia produktif (15-40 tahun) akibat fluktuasinaik esterogen.6
Dari 3 peneliti dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UI/ RS Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta yang melakukan penelitian pada periode yang berbeda diperoleh data
sebagai berikut : antara tahun 1969-1970 ditemukan 5 kasus SLE, selama tahun 1972-1976
ditemukan 1 kasus SLE dari setiap 666 kasus yang dirawat (insidens sebesar 15 per 10.000
perawatan), antara tahun 1988-1990 insidensi rata-rata ialah sebesar 37,7 per 10.000 perawatan.6
Patogenesis
Adanya satu atau beberapa faktor pemicu yang tepat pada individu yang mempunyai
predisposisi genetik akan menghasilkan tenaga pendorong abnormal terhadap sel T CD₄⁺,
mengakibatkan hilangnya toleransi sel T terhadap self-antigen. Sebagai akibatnya munculah sel
T autoreaktif yang akan menyebabkan induksi serta ekspansi sel B, yang memproduksi
10

autoantibodi maupun yang berupa sel memori. Wujud pemicu ini masih belum jelas. Sebagian
dari yang diduga termasuk didalamnya ialah hormon seks, sinar ultraviolet dan berbagai macam
infeksi.6
Pada SLE ,autoantibodi yang terbentuk ditujukan terhadap antigen yang terutama
terhadap nukleoplasma. Antigen sasaran ini meliputi DNA ,protein histon dan non-histon.
Kebanyakan diantaranya dalam keadaan alamiah terdapat dalam bentuk agregat protein dan atau
kompleks protein –RNA yang disebut partikel ribonukleoprotein (RNA). Ciri khas autoantigen
ini ialah bahwa mereka tidak tissue-spesific dan merupakan komponen integral semua jenis sel.6
Antibodi ini secara bersama-sama disebut ANA (anti-nuclear antibody). Dengan
antigennya yang spesifik, ANA membentuk kompleks imun yang beredar dalam sirkulasi. Telah
ditunjukan bahwa penanganan kompleks imun pada SLE terganggu. Dapat berupa gangguan
klirens kompleks imun besar yang larut, gangguan pemrosesan komplek imun dalam hati, dan
penurunan uptake kompleks imun pada limpa. Gangguan-gangguan ini memungkinkan
terbentuknya deposit kompleks imun di luar sistem fagosit mononuclear. Kompleks imun ini
akan mengendap pada berbagai macam organ dengan akibat terjadinya fiksasi komplemen pada
organ tersebut. Peristiwa ini menyebabkan aktivasi komplemen yang menghasilkan substansi
penyebab timbulnya reaksi radang. Reaksi radang inilah yang menyebabkan timbulnya
keluhan/gejala pada organ atau tempat yang bersangkutan seperti ginjal, sendi, pleura, pleksus
koroideus, kulit dan sebagainya. Bagian yang penting dalam patogenesis ini ialah terganggunya
mekanisme regulasi yang dalam keadaan normal mencegah autoimunitas patologis pada individu
yang resisten.6
Manifestasi Klinis
Gejala Muskuloskeletal
Gejala yang sering pada SLE ialah gejala musculoskeletal berupa artritis atau artralgia
(93%) dan seringkali mendahului gejala-gejala lainnya, yang paling sering terkena ialah sendi
interfalangeal proksimal diikuti lutut, pergelangan tangan, metakarpophalangeal, siku dan
pergelangan kaki. Selain pembengkakan kaki dan nyeri mungkin juga terdapat efusi sendi yang
biasanya termasuk kelas I (non-inflamasi). Kaku pagi hari jarang ditemukan. Mungkin juga
terdapat nyeri otot dan miositis. Artritis biasanya simetris, tanpa menyebabkan deformitas,
11

kontraktur atau ankilosis. Adakalanya dapat terjadi pada berbagai tempat dan terutama
ditemukan pada pasien yang mendapat pengobatan dengan steroid dosis tinggi. Tempat yang
paling sering terkena ialah kaput femoris.6
Gejala Mukokutan.
Kelainan kulit,rambut atau selaput lendir ditemukan pada 85% kasus SLE. Lesi kulit
yang paling sering ditemukan pada SLE ialah lesi kulit akut, subakut, diskoid dan livido
retikularis. Ruam kulit yang dianggap khas dan banyak menolong dalam mengarahkan diagnosis
SLE ialah ruam kulit berbentuk kupu-kupu (butterfly-rash) berupa eritema yang agak edematus
pada hidung dan kedua pipi. Dengan pengobatan yang tepat, kelainan ini dapat sembuh tanpa
bekas. Pada bagian tubuh yang terkena sinar matahari dapat timbul ruam kulit yang terjadi
karena hipersensitivitas (photo-hypersensitivity). Lesi ini termasuk lesi kulit akut. Lesi kulit
subakut yang khasi berbentuk anular. Lesi diskoid yang berkembang melalui 3 tahap yaitu
eritema, hyperkeratosis dan atrofi. Biasanya tampak sebagai bercak eritematosa yang
meninggi, ,tertutup oleh sisik keratin disertai adanya penyumbatan folikel. Kalau sudah
berlangsung lama akan berbentuk sikatriks.6
Kadang-kadang terdapat urtikaria yang tidak berperan terhadap kortikosteroid dan
antihistamin. Biasanya menghilang perlahan-lahan beberapa bulan setelah penyakit tenang secara
klinis dan serologis. Alopesia dapat pulih kembali jika penyakit mengalami remisi. Ulserasi
selaput lendir paling sering pada palatum durum dan biasanya tidak nyeri. Terjadi perbaikan
spontan kalau penyakit mengalami remisi. Fenomen Raynaud pada sebagian pasien tidak
mempunyai korelasi dengan aktivitas penyakit ,Sedangkan pada sebagian lagi akan membaik jika
penyakit mereda.6
Ginjal.
Kelainan ginjal ditemukan pada 68% kasus SLE. Manifestasi paling sering ialah
proteinuria dan atau hematuria. Hipertensi, sindrom nefrotik dan kegagalan ginjal jarang terjadi
hanya terdapat 25% kasus SLE yang urinnya menunjukan kelainan.6
Ada 2 macam kelainan patologis pada ginjal yaitu nefritis lupus difus dan nefritis lupus
membranosa. Nefritis lupus difus merupakan kelainan yang paling berat. Klinis biasanya tampak
12

sebagai sindrom nefrotik,hipertensi serta gangguan fungsi ginjal sedang sampai berat. Nefritis
lupus membranosa lebih jarang ditemukan. Ditandai dengan sindrom nefrotik, gangguan fungsi
ginjal ringan serta perjalanan penyakit yang mungkin berlangsung cepat atau lambat tapi
progresif.6
Kelainan ginjal lain yang mungkin ditemukan pada SLE ialah pielonefritis
kronik,tuberkolosis ginjal dan sebagainnya. Gagal ginjal merupakan salah satu penyebab
kematian SLE kronik.6
Kardiovaskular
Kelainan jantung dapat berupa perikarditis ringan sampai berat (efusi perikard), iskemia
miokard dan endokarditis verukosa (Libman Sacks).6
Paru
Efusi pleura unilateral ringan lebih sering terjadi daripada yang bilateral. Mungkin
ditemukan pada sel LE dalam cairan pleura.Biasanya efusi menghilang dengan pemberian terapi
yang adekuat. Diagnosis pneumonitis lupus baru dapat ditegakkan jika faktor-faktor lain seperti
infeksi virus, jamur, tuberkolosis dan sebagianya telah disingkirkan.6
Saluran Pencernaan
Nyeri abdomen terdapat pada 25% kasus SLE, mungkin disertai mual (muntah jarang)
dan diare. Gejala menghilang dengan cepat jika gangguan sistemiknya terdapat pengobatan
adekuat. Nyeri yang timbul mungkin disebabkan oleh peritonitis steril atau arteritis pembuluh
darah kecil mesenterium dan usus yang mengakibatkan ulserasi usus. Alteritis dapat juga
menimbulkan pankreatitis.6
Kelenjar getah bening & kelenjar parotis
Pembesaran pada kelenjar getah bening sering ditemukan (50%). Biasanya berupa
limfadenopati difus dan lebih sering pada anak-anak. Limfadenopati difus ini kadang-kadang
disangka sebagai limfoma. Kelenjar parotis membesar pada 6% kasus SLE.6
Susunan saraf tepi
13

Neuropati perifer yang terjadi berupa gangguan sensorik dan motorik. Biasanya bersifat
sementara.6
Susunan saraf pusat
Gangguan saraf pusat terdiri dari 2 kelainan utama yaitu psikosis organik dan kejang-
kejang. Penyakit otak organik biasanya ditemukan bersamaan dengan gejala aktif SLE pada
sistem-sistem lainnya. Pasien menunjukan gejala delusi/halusinasi disamping gejala khas
kelainan organik otak seperti disorientasi.6
Differential Diagnosis
Arthritis Rheumatoid (RA)
Artritis rematoid merupakan suatu penyakit peradangan kronis sistemik yang menyerang
berbagai jaringan. Pada artritis rematoid sering terjadi sinovitis poliferatif nonsupuratif yang
sering kali berkembang menjadi kehancuran tulang rawan sendi dan tulang di bawahnya.dan
menimbulkan kecacatan akibat arthritis. Patogenesis dari penyakit ini adalah hipersensifitas tipe
IV yang dimediasi sel T. Faktor pencetus dari penyakit ini belum diketahui secara pasti dimana
limfosit menginfiltrasi daerah perivaskular dan terjadi poliferasi sel endotel, dan terjadilah reaksi
inflamasi yang ditimbulkan oleh limfosit. Terjadi juga pertumbuhan yang iregular pada jaringan
sinovial yang mengalami inflamasi sehingga membentuk jaringan pannus. Gejala RA adalah
terjadi peradangan pada sendi, terasa hangat di bagian sendi, bengkak, kemerahan dan sangat
sakit. Biasanya pada banyak sendi, simetris, sendi terasa kaku di pagi hari. Selain itu, gejala
lainnya adalah demam, nafsu makan menurun, berat badan menurun, lemah, dan anemia.7
Gejala dari arthritis rematoid ini dapat dibedakan dengan gout dengan anamnesis ataupun
dengan pemeriksaan lainnya. Pada arthritis rematoid ini onset dari penyakit tersebut sebagian
besar secara perlahan, tetapi dalam jumlah yang sedikit onsetnya timbul dengan cepat. Pada
arthritis rematoid ditemukan artritis yang simetris berbeda dibandingkan dengan gout yang tidak
simetris. Pada stadium awal dari penyakit ini juga dapat diketemukan polyarthritis permanen.
Pada pemeriksaan lab terjadi peningkatan faktor reumatoid, inilah yang menjadi salah satu
pembeda dengan gout. Yang menjadi persamaan dengan gout adalah adanya kenaikan LED dan
14

CRP. Kenaikan ini juga mekanismenya hampir sama dengan gout karena disebabkan oleh reaksi
inflamasi.7
Pada arthritis rematoid stadium lanjut proses inflamasi tidak lagi menimbulkan bengkak
yang berwarna merah walaupun terjadi reaksi peradangan yang nyeri. Gejala arthritis rematoid
lain pada stadium lanjut ditemukan sebuah panus. Panus ini terbentuk oleh sel epitel sinovial
yang berpoliferasi dan bercampur dengan sel radang, jaringan granulasi, dan jaringan ikat
fibrosa. Panus ini juga lah yang akan menyebabkan keraguan apabila dibandingkan dengan topus
yang relatif sama. Pada pasien yang sudah kronis, biasanya akan diikuti deformitas sendi dan
sudah tidak dapat dikoreksi lagi. Ketidakdapatan dikoreksinya ini terutama disebabkan karena
sudah hilangnya lapaisan tulang rawan, bahkan dapat juga terjadi penyatuan tulang, sehingga
kemampuan sendi tersebut tidak dapat digerakan sama sekali. Deformitas yang sering terjadi
adalah membentuk leher angsa. Dimana telapak tangan akan bergerak ke arah ulna dan jari-jari
akan bergerak ke arah radius. 7
Pada gambaran radiologi konvensional baik pada fase akut ataupun pada fase kronis akan
ditemukan pembengkakan jaringan lunak osteopenia juxta articular, erosi tulang dan hilangnya
tulang rawan. Foto polos sendi yang juga penting yaitu pergelangan tangan dan pergelangan kali
untuk data dasar, sebagai pembanding dalam penelitian selanjutnya. Untuk foto MRI mampu
mendeteksi adanya erosi sendi lebih awal dibandingkan dengan foto polos, sehingga tampilan
sendinya akan lebih rinci. Pada foto rontgen polos yang paling dapat dibedakan dengan gout
adalah adanya pembengkakan jaringan lunak dan terdapat erosi tulang sekitar dari sendi yang
terkena tersebut. Gout sendiri jarang bersama-sama dengan Artritis reumatoid, bila dicurigai
adanya gout maka pemeriksaan cairan sendi perlu dilakukan. Apabila pemeriksaan cairan sendi
didapatkan kristal urat maka dapat dipasitkan terjadi gout.7
Artritis Pirai (Gout)
Gout ditandai oleh meningkatnya kadar asam urat plasma dengan serangan artritis
berulang. Kelainan ini disebabkan oleh kelainan metabolisme bawaan dan secara dominan
menyerang laki-laki.7
Secara umum, gejala penyakit gout adalah sendi yang membengkak dan nyeri biasanya
pada sendi metatarsofalang (MTP) pertama dan hiperurisemia asimptomatik. Perubahan
15

radiologi terjadi setelah bertahun-tahun timbulnya gejala. Terdapat predileksi pada sendi MTP
pertama, walaupun pergelangan kaki, lutut, suku, dan sendi lainnya juga terlibat. Film polos
dapat memperlihatkan efusi dan pembengkakan sendi; erosi yang cenderung menimbulkan
penampakan punched out yang berada terpisah dari permukaan artikular; densitas tulang tidak
mengalami perubahan; dan ditemukan tofi yang mengandung natrium urat dan terdeposit pada
tulang, jaringan lunak, dan sekitar sendi. Gout dapat merusak ginjal sehingga dapat ditemukan
batu ginjal pada pemeriksaan radiologi.7
Secara umum, gejala-gejala penyakit gout ialah : 7
Nyeri hebat yang dirasakan pada satu atau beberapa sendi, seringkali pada malam hari.
Sendi membengkak dan kulit di atas sendi yang terkena tampak memerah atau keunguan,
kencang dan licin, serta teraba hangat. Jika disentuh menimbulkan nyeri yang luar biasa.
Sering mengenai sendi di pangkal ibu jari kaki, tetapi juga menyerang sendi pergelangan
kaki, lutut, pergelangan tangan dan sikut.
Demam, menggigil, tidak enak badan, denyut jantung cepat.
Pemeriksaan LED meningkat.
Cairan sendi mengandung kristal monosodium urat.
Osteoartritis (OA)
Osteoarthritis merupakan penyakit arthritis yang paling sering terjadi. Sering disebut juga
degeneratif osteoarthritis atau hipertropic OA. OA merupakan radang sendi yang bersifat kronis
dan progresif disertai kerusakan tulang rawan sendi berupa integrasi (pecah) dan perlunakan
progresif permukaan sendi dengan pertumbuhan tulang rawan sendi ( osteofit) di tepi tulang.7
Pada umumnya penderita OA mengatakan bahwa keluhannya sudah berlangsung lama
tetapi berkembang secara perlahan-lahan. Penderita OA biasanya mengeluh pada sendi yang
terkena yang bertambah dengan gerakan atau waktu melakukan aktivitas dan berkurang dengan
istirahat. Selain itu juga terdapat kaku sendi dan krepitus, bentuk sendi berubah dan gangguan
fungsi sendi. Pada derajat yang lebih berat, nyeri dapat dirasakan terus menerus sehingga sangat
mengganggu mobilitas penderita.7
OA sendi lutut ditandai oleh nyeri pada pergerakan yang hilang bila istirahat, kaku sendi
terutama setelah istirahat lama atau bangun tidur, krepitasi sewaktu pergerakan dan dapat disertai
16

sinovitis dengan atau tanpa efusi cairan sendi. Nyeri akan bertambah jika melakukan kegiatan
yang membebani lutut seperti berjalan, naik turun tangga, berdiri lama. Gangguan tersebut mulai
dari yang paling ringan sampai yang paling berat sehingga penderita tidak bisa berjalan.7
OA sendi lutut merupakan kelainan sendi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan
sehari-hari penderitanya. Walaupun belum ada pengobatan medis yang dapat menyembuhkan
dan menghentikan progresifitas OA, banyak hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan nyeri,
menjaga mobilitas dan meminimalkan disabilitas.7
Penatalaksanaan
Penyuluhan dan intervensi psikososial sangat penting diperhatikan dalam
penatalaksanaan penderita SLE terutama pada penderita yang baru terdiagnosis. Pasien diberi
penjelasan mengenai penyakit yang dideritanya (perjalanan penyakit, komplikasi, prognosis dan
sebagainya) sehingga dapat bersikap positif terhadap penanggulangan penyakit ini.6
Pada umumnya, penderita SLE mengalami fotosensitifitas, sehingga penderita harus
selalu diingatkan untuk tidak terlalu banyak terpapar oleh sinar matahari. DNA yang terkena
sinar ultraviolet secara normal akan bersifat antigenik dan hal ini akan menimbulkan serangan
setelah terkena sinar. Mereka dinasehatkan untuk selalu menggunakan krim pelindung sinar
matahari, baju lengan panjang, topi atau payung bila akan berjalan di siang hari. Pekerja kantor
juga harus dilindungi terhadap sinar matahari dari jendela.8
Karena infeksi sering terjadi pada penderita SLE, maka penderita harus selalu diingatkan
bila mengalami demam yang tidak jelas penyebabnya, terutama pada penderita yang memperoleh
kortikosteroid dosis tinggi.8
Terapi dengan obat bagi pasien SLE mencakup pemberian obat-obat anti inflamasi non-
steroid (OAINS), kortikosteroid, antimalaria dan agen penekan imun. Pemilihan obat yang sesuai
bergantung pada organ-organ yang terserang oleh penyakit ini. OAINS dipakai untuk mengatasi
arthritis dan artralgia.9
Beberapa prinsip dasar tindakan pencegahan pada SLE :6
Monitoring yang teratur untuk menghindari adanya infeksi pada pasien.
17

Penghematan energi
Pada kebanyakan pasien kelelahan merupakan keluhan yang menonjol. Diperlukan waktu
istirahat yang terjadwal setiap hari dan perlu ditekankan pentingnya tidur yang cukup.
Fotoproteksi
Kontak dengan sinar matahari atau sinar ultraviolet harus dikurangi atau
dihindarkan .Dapat juga dipakai lotion tertentu (sunscreener lotion) untuk mengurangi
kontak dengan sinar matahari.
Mengatasi infeksi
Pasien SLE rentan terhadap infeksi. Jika ada demam yang tak jelas sebabnya, pasien
harus segera memeriksakan diri. Diperlukan terapi pencegahan dengan antibiotik pada
operasi gigi, traktus urinarius atau prosedur bedah invasif lain.
Pengobatan simptomatik
Pengobatan yang diberikan bersifat simptomatik sesuai dengan gejala yang diderita.6
Artritis/artralgia, mialgia dan demam diberikan salisilat atau preparat lain seperti
indometasin (3 x 25mg/hari), asetaminofen (6 x 650mg/hari) dan ibuprofen (4 x 300-
400mg/hari) dan harus disertai istirahat yang cukup. Metotreksat dosis rendah (7,5-15
mg/minggu) juga dapat dipertimbangkan untuk mengatasi arthritis pada penderita SLE.
Eritema. Terapi local dngan krim atau salep kortikosteroid.
Ulserasi mulut dan nasofaring diberikan terapi lokal.
Obat antimalaria
Sering memberikan hasil yang baik dalam mengatasi kelainan kulit. Kadang-kadang juga
terdapat adenopati hilus serta kelainan paru ringan dan artralgia ringan. Preparat yang sering
dipakai adalah klorokuin atau hidroksiklorokuin dengan dosis 200-500 mg/hari. Selama
pemakaian obat ini penderita harus control ke ahli mata setiap 3-6 bulan karena adanya efek
toksis berupa degenerasi macula. Klorokuin mengikat DNA sehingga tidak dapat bereaksi
dengan anti-DNA.6
Kortikosteroid
18

Kortikosteroid diberikan jika kelainan kulit memburuk dan tidak responsive terhadap
pengobatan konservatif. Dalam keadaan ini biasanya diperlukan dosis rendah sampai sedang.
Keadaan lain dimana diperlukan kortikosteroid adalah gejala adanya gangguan susunan saraf
pusat, perikarditis, miokarditis, pleuritis, miositis berat, anemia hemolitik, leucopenia, gangguan
pembekuan darah, nefritis lupus dan demam tinggi. Pada fase akut biasanya diberikan prednison
dengan dosis 0,5 mg/kgBB/hari. Pada keadaan yang berat, terutama pada SSP dengan kejang-
kejang dan psikosis, diberikan prednison atau prednisolon dosis 1-1,5 mg/kgBB/hari. Setelah
keadaan klinis menjadi tenang, dosis kortikosteroid diturunkan (tapering off) dimulai dengan 5-
10% setiap minggu bila tidak timbul eksaserbasi akut.6
Jika terdapat kelainan ginjal, perlu dilakukan dulu biopsy ginjal untuk memastikan jenis
kerusakan ginjal. Glomerulonefritis lupus fokal memberikan respon yang baik terhadap
pengobatan. Biasanya diberikan prednisone 40-60 mg/hari selama beberapa minggu sampai
gejala klinis menghilang, sedimen urin membaik dan komplemen kembali normal.6
Obat imunosupresif
Biasanya obat imunosupresif diberikan bersamaan dengan kortikosteroid. Penggunaan
obat imunosupresif sebenarnya masih diperdebatkan. Umumnya hanya dianjurkan pada kasus
gawat atau lesi difus dan membranous di ginjal yang tidak memberikan respon baik terhadap
kortikosteroid. Yang paling sering dipakai adalah azatioprin dan siklofosfamid. Siklofosfamid
diberikan per oral 50-150 mg per hari. Setelah pemberian siklofosfamid, jumlah leukosit darah
harus dipantau. Bila jumlah leukosit mencapai 1500/ml maka dosis siklofosfamid berikutnya
diturunkan 25%. Siklofosfamid diberikan selama 6 bulan dengan interval 1 bulan, kemudian tiap
3 bulan selama 2 tahun. Selama pemberian siklofosfamid, dosis steroid diturunkan secara
bertahap dengan memperhatikan aktifitas lupusnya.6
Obat sitotoksik lain yang toksisita dan efektifitasnya lebih rendah dari siklofosfamid
adalah azatioprin. Azatioprin diberikan secara peroral dengan dosis 1-3 mg/kgBB/hari.
Imunosupresan lain yang dapat digunakan untuk pengobatan SLE adalah siklosporin-A dosis
rendah (3-6 mg/kgBB/hari) dan mofetil mikofenolat.6
19

Komplikasi
Komplikasi yang paling sering terjadi adalah infeksi sekunder. Pada sistem
kardiopulmoner mungkin timbul gagal jantung karena miokarditis, efusi pleura dan perikard
sampai tamponade jantung yang memerlukan perikardiektomi. Kelainan ginjal dapat berupa
kegagalan gagal ginjal ringan sampai berat. Dalam keadaan ini dipertimbangkan pemberian
diuretic, obat anti hipertensi dan mungkin juga dilakukan dialisis serta transplantasi ginjal.
Pemberian koagulan juga dianjurkan. Heparin diberikan dalam dosis antikoagulasi, kemudian
dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 250 mg/hari subkutan. Terhadap kejang-kejang yang
timbul akibat gangguan susunan saraf pusat diberikan obat antikonvulsi. 6
Prognosis
Angka harapan hidup 5 tahun secara keseluruhan adalah 85-88% dan 10 tahun 76-87%.
Penyebab utama kematian pada SLE adalah infeksi, nefritis lupus, konsekuensi gagal ginjal
(termasuk akibat terapi), penyakit kardiovaskuler dan lupus SSP. Penyakit ginjal merupakan
indikator prognosis yang paling buruk pada SLE dan oleh karenanya titer antibodi pengikat
DNA positif dan/ atau meningkat, yang berkaitan dengan keterlibatan ginjal , dikaitkan dengan
prognosis yang lebih buruk.1 Sebelum tahun 1950, SLE merupakan penyakit yang fatal.
Pemakaian preparat kortikosteroid merupakan pengobatan pertama yang memberikan hasil baik
pada penyakit ini. Pemakaian kortikosteroid yang lebih teratur dan terencana, pemakaian obat
imunosupresif dan penggunaan antibiotik, antihipertensi, dialisis serta transplantasi ginjal lebih
memperpanjang survival rate lagi. Survival rate sebesar 50% pada tahun 1954, menjadi 85%
pada tahun 1976. Beberapa tahun terakhir ini prognosis penderita lupus semakin membaik.
Angka harapan hidup 10 tahun meningkat sampai 85%.6
Prognosis buruk dijumpai pada penderita lupus nefritis kronik dan penyakit saraf, yaitu
harapan hidup hanya berkisar 2 tahun. Prognosis yang baik yaitu harapan hidup bisa mencapai
20 tahun maupun lebih dengan penatalaksaan yang tepat yang ditunjang dengan ilmu kedokteran
yang semakin modern dan berkembang.6
20

Kesimpulan
Dengan memperhatikan gejala-gejala yang dialami pasien berusia 22 tahun ini, dapat
disimpulkan bahwa ia menderita SLE karena ia mempunyai beberapa gejala klinis yang tampak
seperti mudah lemah, nyeri pada jari-jari kedua tangan, kaku pada pagi hari, rambut rontok,
wajah memerah walau sebentar terkena matahari, badan hangat hilang timbul, demam dan
terdapat anemia.
Daftar Pustaka
1. Pringgoutomo S, Himawan S, Tjarta A. Buku ajar patologi 1 (umum). Edisi ke-1. Jakarta:
Sagung Seto;2006.h.262-4.
2. Willms JL, Schneiderman. Buku saku diagnosis fisik. Jakarta: EGC;2005.h.5-17.
3. Gleadle J. At a glance anamnesis. Jakarta: Erlangga;2005.h.115-6.
4. Graber MA, Toth PP, Herting RL. Buku saku dokter keluarga. Edisi ke-3. Jakarta:
EGC;2006.h.288-293.
5. Cotran RS, Kumar V, Robbins SL. Buku ajar patologi robbins. Jakarta :
EGC;2007.h.144-7.
6. Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, et al. Buku ajar ilmu penyakit dalam. Edisi ke-5.
Jakarta: Interna Pubslishing;2009.h.2565-76.
7. Mitchell, Kumar, Abbas, Fausto. Buku saku dasar patologis penyakit. Jakarta:
EGC;2009.h.742-8.
8. Davey P. At a glance medicine. Jakarta: Erlangga;2006.h.395-6.
9. Price SA. Patofisiologi: konsep klinis proses-proses penyakit. Edisi ke-6. Jakarta:
EGC;2006.h.1392-5.
21