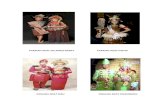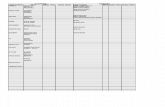wabm
description
Transcript of wabm

Nama : Sinar Desi PratiwiNim : H311 15 007
Bugis–Makassar Seamanship And Reproduction Of Maritime CulturalValues In Indonesia
(Ilmu Pelayaran Bugis-Makassar dan Reproduksi dari Nilai Budaya Maritim di Indonesia)
Munse Lampe dengan jurnalnya yang berjudul “Bugis–Makassar Seamanship And Reproduction Of Maritime Cultural Values In Indonesia”, membahas mengenai betapa pentingnya pembangunan nasional dalam pengembangan peradaban maritim, baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas. Yang dimana Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara kepulauan dengan karakteristik alami, demografi sosial dan ekonomi, dan budaya maritim yang mencolok.
Alasan yang melandasi Munse Lampe dalam mempelajari etos maritime dan nilai-nilai budaya maritime bermula dari pendapat anggota senior LSM di Indonesia dan juga penasihat di Coral Reef Rehabilitation dan Program manajemen (COREMAP) Sulawesi Selatan pada tahun 1996/1997 yang meyatakan bahwa pelaut Bugis-Makassar sangat tangguh berlayar pada masa lampau dan saat ini. Kemudian Edward Poelinggomang (2002), sebuah Sejarawan di ilmu pelayaran Bugis-Makassar, menyatakan bahwa pembentukan kepulauan ini menjadi bangsa diterima karena persahabatan dan persaudaraan melalui jaringan navigasi dan maritim perdagangan mengakibatkan toleransi dan simpati antara kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang memiliki share yang signifikan, menurut Poelinggomang, adalah pelaut Bugis-Makassar dan pedagang dari Sulawesi Selatan.
Pengidentifikasian yang sulit mengenai nilai-nilai budaya maritim Bugis-Makassar disebabkan karena pendekatan teoritis tidak berhubungan dengan fenomena mental yang dipahami sebagai hasil dari kekuatan pelayaran yang sangat panjang namun sebuah pelajaran yang berfokus atau yang sesuai pendekatan antropologis dikembangkan dalam studi maritim nilai-nilai budaya adalah untuk melihat atau mengerti maritim etos disposisi reproduksi pengalaman navigasi yang panjang.
Sebagai sikap dan nilai-nilai budaya maritim yang penting, dimana Prins beranggapan perlunya unsur-unsur maritim etos disposisi seperti pragmatisme, instrumentalisme, adaptivism, sikap yang ketat, disiplin, struktur longgar, keberanian mengambil resiko, kemauan yang kuat, kelonggaran, dan kompetitif, dll. Terlepas dari kelemahannya asumsi reproduksi etos maritim disposisi dievaluasi untuk menjadi cukup tajam untuk memberikan inspirasi dan membuka jalan bagi saya untuk memperluas fokus penelitian pada maritim budaya lainnya nilai-nilai yang dapat dijelaskan secara empiris dari beberapa disposisi etos maritim diajukan oleh Prins.
Indonesia dalam catatan sejarah, itu adalah diketahui sebagai negara yang kaya budaya maritim. Dimana terdapat enam kelompok etnis sebagai pelopor komunitas maritim di Indonesia, yaitu Bajos, Bugis, Makassar, Mandar, Buton dan Madura.
Penyebab jatuhnya kegiatan navigasi pelaut Bugis-Makassar ke kekuasaan VOC karena salah satu syarat dalam kebijakan VOC di bawah Speelman untuk melarang kapal asli membawa rempah-rempah dan ekspor utama komoditas lainnya. serta tidak sejalan dengan kebijakan politik Sultan Alauddin sebagai Raja Gowa dalam menolak aplikasi VOC yang membuat hubungan dengan lainnya Negara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Inggris. Pernyataan kebijakan politik ini sangat diperjelas oleh Sultan Alauddin yang menyatakan, “Allah telah menciptakan darat dan

laut, tanah dibagi antara manusia dan laut untuk semua manusia. Hal ini tidak pernah mendengar bahwa seseorang dilarang untuk berlayar di laut. Jika Anda melakukannya, itu berarti anda telah merampas makanan (roti) dari mulut kita. Aku seorang raja miskin”.
Hubungan yang baik terjalin antara pelaut dan pedagang daerah Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Diantaranya mereka mampu menjaga janji yang mereka dan bersedia menolong siapapun yang diperlakukan tidak adil. Ini seperti pernyataan penyair Belanda, “ayam jantan yang penuh kasih dari Timur (de hantjes van het Osten)”.
Tidak dapat dipungkiri peran koloni Belanda terhadap daerah Republik Indonesia yang dulunya berada dibawa tapi tetap didukung oleh toleransi sikap dan simpati dari kelompok etnis yang telah membuat persahabatan dan persaudaraan melalui navigasi maritim dan jaringan perdagangan yang pelaut dan pedagang dari Bugis-Makassar dimainkan peran besar.
Setelah kemerdekaan Indonesia, tradisi navigasi produktif lagi karena pelaut Bugis-Makassar sebagai ahli waris dari budaya nenek moyang 'yang ada selama waktu kolonial dan luar. Dimana saat era kemerdekaan melalui informasi dan pengalaman yang panjang, Bugis-Makassar menemukan konsep baru dimana perairan dan pulau yang telah diarungi diintegrasikan menjadi satu negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaut Makassar dengan penduduk pesisir pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Pengalamannya dalam berlayar dan pengetahuan laut dan pulau-pulau membuatnya mungkin untuk berlayar luar negeri tiga kali, yaitu Darwin, Australia dua kali, dan sekali ke Tokyo, Jepang untuk berlayar tradisional perahu dipesan dari Bira, Bulukumba untuk museum nasional di kedua negara. Pertama dan navigasi kedua Darwin. Karir puncaknya dicapai ketika ia ditunjuk Kapten pada tahun 1990 dan dipercaya untuk kapten kapal pesiar milik pariwisata industri di Bali.
Dengan demikian, perjalanan maritim Bugis-Makassar yang pertama adalah pada dasarnya nilai-nilai budaya maritim para pelaut Bugis-Makassar terpaku pada reproduksi dari pengalaman pelayaran panjang mereka dan juga interaksi mereka pada dengan dunia social di Indonesia. Dan yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai budaya maritim serta konsep perairan pelaut Bugis-Makassar diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Pengalaman langsung ialah hal paling penting bagi mereka. Ketiga ialah nilai utama diantaranya harga diri dan kepercayaan diri direproduksi oleh pengalaman berlayar menjadi sikap keras dan kebiasaan berpetualang, etos kerja, kompetitif, sikap terbuka dan lain-lain. Keempat adalah dengan memiliki kesadaran dan pengakuan akan etnik lain rasa persatuan akan negara dan bahasa. Kelima adalah hubungan yang kuat dalam integrasi dan harmoni sosial antar etnik serta perkembangan masyarakat maritime dibutuhkan melalui pelaksanaan pendidikan niali-nilai budaya maritim.

Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negeri kepulauan terbesar yang memiliki karakteristik alami, demografi social dan ekonomi dan budaya maritimnya yang mencolok serta menurut Asahitaro Nishimura, maritimnya mengacu pada komponen berlayar, pengiriman, dan item sistem kognitif pengetahuan, ide, nilai, norma, keyakinan yang berkaitan dengan kegiatan maritim. Dimana karakter alami dapat dilihat dari ukuran pulau besar kecil dengan panjag pantai total 81.000 Km, luas lahan dan wilayah lautnya, dan juga letaknya yang diapit oleh dua benua dan dua samudera.
Demografis sosialnya dapat dilihat dari banyaknya pendudukan yang menempati sepanjang pantai dan pulau-pulau kecil, kurang lebih 40.000.000 orang. Mereka yang menempati daerah tersebut berhubungan langsung dengan sector ekonomi perikanan transformasi dan perdagangan laut.. Karakter budayanya dapat dililhat dari peradaban maritim terdiri aspek kebijakan pemerintah, keamanan dan pertahanan, industri perahu kayu, arsitektur, astrologi, transportasi dan perdagangan, dan port digunakan untuk mengembangkan di pusat maritim Kerajaan Allah "tradisi besar maritim" di Mukhlis Jangka Paeni ini.
Program pembangunan nasional harus memiliki prioritas pertama dalam pengembangan maritim peradaban. Sehubungan dengan itu, studi ilmiah tentang tradisi dan budaya maritim proses dinamis perlu ditingkatkan di Indonesia, baik kualitas dan kuantitas, yang sebenarnya ada banyak studi di antropologi dan sosiologi tapi tentu saja masih ada banyak fenomena penting yang belum pernah diteliti dengan menggunakan asumsi dan phenomena terntentu.
Alasan yang melandasi “ “ dalam mempelajari etos maritime dan nilai-nilai budaya maritime bermula dari pendapat anggota senior LSM di Indonesia dan juga penasihat di Coral Reef Rehabilitation dan Program manajemen (COREMAP) Sulawesi Selatan pada tahun 1996/1997 yang meyatakan bahwa pelaut Bugis-Makassar sangat tangguh berlayar pada masa lampau dan saat ini. Kemudian Edward Poelinggomang (2002), sebuah Sejarawan di ilmu pelayaran Bugis-Makassar, menyatakan bahwa pembentukan kepulauan ini menjadi bangsa diterima karena persahabatan dan persaudaraan melalui jaringan navigasi dan maritim perdagangan mengakibatkan toleransi dan simpati antara kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang memiliki share yang signifikan, menurut Poelinggomang, adalah pelaut Bugis-Makassar dan pedagang dari Sulawesi Selatan
Pengantarpern
Manfaat dari studi maritim nilai-nilai sistem budaya seperti ini di Indonesia adalah bagi pengembangan masyarakat maritim sebagai perekat bangsa yang majemuk dan multikultural yang rawan konflik horisontal dan vertikal. Kesulitan mengindentifikasi dan menjelaskan nilai-nilai budaya maritime termasuk budaya maritim Bugis-Makassardikarenakan konsep atau pendekatan yang digunakan oleh antropolog sejauh telah dipinjam dari manusia ekologi perspektif / antropologi ekologi dan sosiologi. Materialisme budaya yang dijelaskan oleh Marvin Harris (1986) ialah institusi atau tabu berdasarkan costbenefit pertimbangan dalam hubungannya dengan manajemen penggunaan sumber daya alam.

PENGANTARIndonesia dikenal sebagai salah satu yang terbesar kepulauan negara di dunia dengan yang alami karakteristik, demografi sosial dan ekonomi, dan budaya maritim mencolok yang – menurut untuk Asahitaro Nishimura (1973), yang maritim jangka mengacu pada komponen berlayar, pengiriman, dan item sistem kognitif pengetahuan, ide, nilai, norma, keyakinan yang berkaitan dengan kegiatan maritim. Karakteristik alam termasuk 17.508 besardan pulau-pulau kecil dengan panjang pantai total 81.000 Km, luas lahan 2.027.087 Km2, 5,8 Km2 wilayah laut (terdiri dari 3.166.163 Km2 Nusantara dan perairan teritorial dan 2.500.000 Km2 ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kondisi -yang sebelumnya Timor Timur bebas dari Negara Kesatuan Indonesia. Perairan memiliki terbarukan alami sumber daya (perikanan, terumbu karang, rumput laut, dan bakau) dan berlimpah dan tak ternilai yang tak terbarukan (minyak dan gas, mineral, zat besi, harta). Indonesia juga terletak di antara dua benua: Asia dan Australia dan di antara dua samudera besar: Samudra Hindia dan Pasifik Laut (BPP Teknologi dan Wanhankamnas, 1996).
n jn n mxn jnjncdj chndujdicuhDemografis sosial dan ekonomi karakteristik menunjukkan bahwa daerah sepanjangpantai dan pulau-pulau kecil yang membentang dari Sabang ke Merauke dihuni oleh lebih dari 40.000.000 orang. Mereka tinggal langsung atau tidak langsung dari sektor ekonomi perikanan, transportasi, dan perdagangan laut. Kedua transportasi dan perikanan adalah sektor ekonomi yang paling tertua orang dari daerah pesisir menangani dalam hal ini Nusantara.
Karakteristik budaya masyarakat di Indonesia penuh dengan peradaban maritim terdiri aspek kebijakan pemerintah, keamanan dan pertahanan, industri perahu kayu, arsitektur, astrologi, transportasi dan perdagangan, dan port digunakan untuk mengembangkan di pusat maritim Kerajaan Allah "tradisi besar maritim" di Mukhlis Jangka Paeni ini (1985). Adapun tradisi maritim budaya seperti memancing dilakukan dan didukung oleh miskin komunitas-pantai "sedikit maritim Tradisi "di jangka Mukhlis Paeni ini (1985).
Dari alam, demografi sosial, ekonomi, dan karakteristik budaya dan yang strategis posisi geografis dalam konteks internasional, Program pembangunan nasional harus memiliki prioritas pertama dalam pengembangan maritim peradaban. Sehubungan dengan itu, studi ilmiah tentang tradisi dan budaya maritim proses dinamisperlu ditingkatkan di Indonesia, baik kualitas dan kuantitas.Sebenarnya ada banyak studi di antropologi dan sosiologi pada sosioekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan pulau di Indonesia, tapi tentu saja masih ada banyak

fenomena penting yang belum pernah diteliti dengan menggunakan asumsi tertentu dan Pendekatan. Penelitian sebelumnya pada nelayan sistem sosial ekonomi (Lampe, 1986; Lampe et al.1996 / 1997; Lampe et al, 1997/1998.; Lampe et al., 2000), pelaut dan nelayan sosial ekonomi lembaga (Lampe, 1995; 2010), peoplesea interaksi (Lampe, 1989; 2006) dll fokus lebih pada permukaan atau perangkat keras budaya maritimdari pada etos maritim dan kelautan budaya nilai dipahami sebagai hasil dari ilmu pelayaran panjang pengalaman.Minat saya dalam mempelajari etos maritim dan nilai-nilai budaya maritim dimulai dari saya diskusi dengan Kristen Linda, diakui anggota senior sebuah LSM di Indonesia dan juga penasihat di Coral Reef Rehabilitation danProgram manajemen (COREMAP) South Sulawesi pada tahun 1996/1997 dan 1997/1998, dalam ruang seminar yang diselenggarakan di provinsi Sulawesi Selatanpada tahun 1997. Dia menyatakan bahwa pelaut Bugis-Makassar memiliki keberanian untuk berlayar perairan Indonesia di masa lalu dan saat ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki konsep kepulauan dan nasionalisme yang tinggi semangat. Kemudian Edward Poelinggomang (2002), sebuah Sejarawan di ilmu pelayaran Bugis-Makassar, menyatakan bahwa pembentukan kepulauan ini menjadi bangsa diterima karena persahabatan dan persaudaraan melalui jaringan navigasi dan maritim perdagangan mengakibatkan toleransi dan simpati antara kelompok masyarakat. Salah satu kelompok yang memiliki share yang signifikan, menurut Poelinggomang, adalah pelaut Bugis-Makassar dan pedagang dari Sulawesi Selatan.
PENGANTARPernyataan-pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran dan kebaikan pelaut Bugis-Makassar dalam pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Sebaliknya, itu adalah upaya ilmiah untuk mengidentifikasi sikap dan nilai-nilai budaya maritim dan menjelaskannya secara empiris dalam konteks panjang sejarah ilmu pelayaran. Pertanyaannya adalah: dapatkah unsur mental seperti keberanian petualang, nasionalisme semangat, persahabatan dan persaudaraan, toleransi dan simpati, dll dipahami sebagai nilai-nilai budaya maritim? Jika ya, maka bagaimana adalah pembentukan nilai-nilai budaya maritim? Apakah itu bagian peradaban etnis Bugis-Makassar yang dikembangkan di darat atau itu hasil dari proses panjang Pengalaman ilmu pelayaran? Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi maritim nilai-nilai budaya pelaut Bugis-Makassar dan menjelaskan secara empiris dalam konteks maritim dan ilmu pelayaran di Indonesia-dalam konteks studi budaya maritim, etnis Bugis-Makassar adalah hanya satu dalam menulis, ini adalah karena kedua etnis memiliki unsur-unsur budaya maritim yang relatif sama terutama di sektor navigasi dan perikanan.
Di Indonesia studi maritim nilai-nilai budaya Sistem seperti ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan antropologi maritim yang memiliki pernah statis sejauh ini, tapi juga bermanfaat bagi pengembangan masyarakat maritim sebagai perekat bangsa yang majemuk dan multikultural yang rawan konflik horisontal dan vertikal. Sulit untuk mengidentifikasi dan menjelaskan maritim nilai-nilai budaya termasuk maritim Bugis-Makassar budaya karena konsep atau pendekatan yang digunakan oleh antropolog sejauh telah dipinjam dari manusia ekologi perspektif / antropologi ekologi dan sosiologi. Sebagai contoh, pendekatan strategi adaptif oleh Bernett (di McCay, 1978; Acheson, 1981) melihat masalah lingkungan (fisik, sosial ekonomi, politik, teknologi, demografi, pasar) dan respon pola yang digunakan oleh

manusia dalam menggunakan sumber daya lingkungan dan mengatasi menekan masalah yang dihadapi oleh manusia.Pendekatan Eco-sistemik oleh Rappaport (1968) dan Vayda dan Rappaport (1968) lembaga pandangan atau Upacara sebagai mekanisme untuk mempertahankan Kondisi keseimbangan sumber daya lingkungan. Materialisme budaya oleh Marvin Harris (1986) menjelaskan institusi atau tabu berdasarkan costbenefit pertimbangan dalam hubungannya dengan manajemen penggunaan sumber daya alam. Perspektif konstruksionis (Pallsson, 1999) views hubungan paradigmatik antara manusia danlingkungan dalam tiga paradigma: komunalisme (antar hubungan subjektif antara manusia dan lingkungan), orientalisme (pria mengendalikan alam / lingkungan), paternalisme (manusia bertanggung jawab untuk melindungi kondisi alam berdaya).
Symbolicmetaphoric perspektif yang dikembangkan oleh Ossewijer(2001) menggambarkan interaksi manusia dengan lingkungan metaforis dan simbolis. The sistem dunia teori dengan Wallerstain diterapkan olehEstelle Smith (1977) memandang perubahan strategi usaha nelayan dan berbagai sosial ekonomi konsekuensi dan lingkungan dalam konteks pengembangan pasar ekspor dunia. The Pendekatan lembaga sosial yang dominan memandang hidup tertutup dan homogen dari kelompok pelaut (pelaut dan nelayan) sepenuhnya dibatasi oleh kapal atau lembaga perahu (Aubert V. di Lette, 1985). Dari review untuk aplikasi masing-masing Pendekatan teoritis disebutkan sebelumnya, itu adalah diketahui bahwa studi yang bukan tentang jiwa fenomena (konsep, nilai, norma, keyakinan, moral, dan sikap) yang dipahami sebagai akibat dari dan atau diperkuat dengan perjalanan panjang.
Sebuah pelajaranfokus atau yang sesuai pendekatan antropologisdikembangkan dalam studi maritim nilai-nilai budayaadalah untuk melihat atau mengerti maritim etos disposisireproduksi pengalaman navigasi yang panjang(Prins, 1985).NAVIGASI DAN REPRODUKSI PENGALAMANOF MARITIME BUDAYANILAI: FOKUS BARU DI STUDIBUDAYA MARITIMKetika budaya maritim dipahami sebagaifenomena mental / kognitif (konsep, nilai,norma, keyakinan, moral dan sikap) sebagai akibat daridan atau diperkuat oleh pengalaman navigasi,etos maritim disposisi pendekatan oleh Prinsdievaluasi untuk menjadi lebih tepat untuk mengembangkan distudi nilai-nilai budaya maritim di Indonesiadari yang lain. Sebagai Prins (1985) menunjukkan,pembuatan perahu, navigasi dan perdagangan, dan memancingadalah cara untuk memahami budaya maritim darimasyarakat lokal yang unik dan kompleks yangmaritim disposisi etos.Prins mengasumsikan bahwa interaksi manusia(pelaut dan nelayan) dengan lingkungan laut

menggunakan perahu / kapal, navigasi, dan aktivitas memancingsecara bertahap mereproduksi maritim yang kompleks dan uniketos disposisi. Menurut Prins, unsur-unsurmaritim etos disposisi seperti pragmatisme,instrumentalisme, adaptivism, sikap yang ketat,disiplin, struktur longgar, keberanian mengambil resiko,kemauan yang kuat, kelonggaran, dan kompetitif, dll Dariasumsi, jelas bahwa konsepmaritimeness etos disposisi oleh Prins diwujudkansebagai sikap dan nilai-nilai budaya maritim penting.Pertanyaan yang tersisa dari asumsi Prins 'adalah yang maritim etos disposisi dipahamireproduksi interaksi manusia (pelaut)dengan laut lingkungan fisik, dan mana yangreproduksi interaksi manusia dengan-Nyadunia sosial eksternal? Dalam penelitian ini diasumsikanbahwa meskipun dua kategori pengalamanInteraksi biasanya mereproduksi sikap dannilai-nilai budaya maritim, hasil atau yangreproduksi relatif berbeda. Semacam inianalisis belum dilakukan oleh Prins.Terlepas dari kelemahan, yangasumsi reproduksi etos maritimdisposisi dievaluasi untuk menjadi cukup tajam untukmemberikan inspirasi dan membuka jalan bagi saya untuk memperluasfokus penelitian pada maritim budaya lainnyanilai-nilai yang dapat dijelaskan secara empiris daribeberapa disposisi etos maritim diajukanoleh Prins. Misalnya, unsur-unsur mental sepertikeberanian petualang, sikap yang ketat, taat kepadanorma, toleransi dan loyalitas, kolektivitas, keterbukaan,menghormati perbedaan etnis, nasionalisme, dll bisadipahami sebagai nilai-nilai budaya maritimkarena dapat dijelaskan secara empiris dalamkonteks navigasi panjang, pengaruh internal yang(sosial-budaya pelaut) dan pengaruh eksternal(situasi pasar, kebijakan pemerintah, dll).MENELUSURI THE BUGIS-MAKASSAR BahariDI INDONESIAIndonesia dalam catatan sejarah, itu adalah diketahuisebagai negara yang kaya budaya maritim. Tentu sajatidak semua masyarakat berada di bawah kerajaan maritimdi Indonesia di masa lalu sampai Indonesiaera kemerdekaan menjadi sebuah komunitas maritim.Menurut Adrian Horridge, dari banyak kelompoknelayan dan pelaut, ada enam etniskelompok sebagai pelopor komunitas maritim diIndonesia, yaitu Bajos (nomaden laut), Bugis(Teluk Bone), Makassar (Galesong, Tallo),

Mandar (Sulawesi Barat), Buton (TenggaraSulawesi), dan Madura (Jawa Timur). Mereka adalahahli waris budaya maritim (pembuat perahu dan terampilpelaut) dari bahasa Melayu-Polinesia ras dan pelopordan dai budaya maritim di TenggaraAsia sejak ribuan tahun yang lalu (Horridge, 1986).Dari tersebar luas, menurut Horridge, adamuncul kelompok etnis lainnya seperti nelayanmasyarakat dari Bawean pulau, Masalembo,dan Sapudi (Jawa), pedagang dari Bonerate danPolu'e pulau di Laut Flores, pemburu paus dariLamalera (Lomblen di Lurus Timor, Luangorang di barat daya), dan beberapa Bugiskoloni di Indonesia (antara lain Flores,Bima, Riau, Lampung) mengendalikan perdagangan lebarjaringan untuk berbagai jenis ekspor dan imporkomoditas.Sebuah penjelasan rinci tentang navigasi perdaganganpetualangan masyarakat Sulawesi Selatan adalahditemukan dalam catatan Cornelis Speelman ditulis setelahPerang Makassar tahun 1670 (lihat Poelinggomang,2002). Poelinggomang mencatat bahwa perdaganganhubungan dilakukan dengan Bugis-Makassar dari SelatanSulawesi sampai penaklukan Kerajaan Gowaoleh VOC yang berlangsung dari dan ke Manggarai, Timor,Tanimbar, Alor, Bima, Buton, Tomboku, Seram,Mindanao, Sambuangan, Macao, Manila, Cebu,Kamboja, Siam, Patani, Bali, pelabuhan Jawa Utara,Batavia, Banten, Palembang, Jambi, Johor,Malaka, Aceh, Banjarmasin, Sukadana, Pasir,Kutai, Berau, dan perdagangan kota di Sulawesi danMaluku. Komoditas yang dijual, menurutdicatat dari Cornelis Speelman pada tahun 1670 (dalam J.Noorduyn, 1983) adalah rempah-rempah, cendana,budak, produk tekstil India: dragam (sejenisdua kain berwarna dari Gujarat), touria Godia (ajenis kain katun berwarna dari India Muka),bethilles (semacam kain katun berwarna dariPortugal), dll .; Produk China seperti porselen,sutra, benang sutra, emas, perhiasan, gong, dll .; rumahproduk industri (parang, pedang, kapak, Selayarkain, Bima kain, dll); dan hasil lautsisik terutama penyu dan mutiara.Ketika Makassar jatuh ke kekuasaan VOC,kegiatan navigasi Bugis-Makassarpelaut yang berhenti di bagian timurIndonesia. Hal ini disebabkan salah satu syaratdalam kebijakan VOC di bawah Speelman untuk melarang kapal aslimembawa rempah-rempah dan ekspor utama lainnya

komoditas. Itulah sebabnya setelah PerangMakassar (1666-1667; 1668-1669) pelautSulawesi Selatan berubah arah mereka danrute perdagangan dengan melakukan eksodus ke banyak port perdagangandi bagian barat Indonesia sepertiKalimantan dan pulau-pulau Sumatera, dan MelayuPeninsula. Mereka diperdagangkan ke pelabuhan lain sepertiJailolo (Sulu), Banjarmasin, Palembang, Johor,Pahang, dan Aceh. Perahu perdagangan yang dikunjungiJailolo berasal dari port yang berbeda seperti Kutai,Pasir, dan Samarinda (Kalimantan Timur), Ternate,Banda (Maluku), Pantai bagian dari Papua Barat, danMandar, Kaili, Bone, Gorontalo, Menado, danKema (Sulawesi) (Warren, 1981). Mereka inginberdagang ke pelabuhan di bawah kendali Belandapemerintah dan tidak dilarang oleh portPemerintah Belanda juga komoditas yang diperdagangkandimonopoli oleh pemerintah seperti rempah-rempah.Daerah navigasi mereka (untuk mendapatkan produksi untukpemasaran untuk perdagangan port) berada Nusa Tenggara,Maluku Tenggara (Aru dan Kepulauan Tanimbar)sampai pantai utara Benua Australia.Pertempuran semangat pelaut Bugis-Makassarpetualangan ke seluruh wilayah Indonesia tidak pudarmeskipun Makassar telah jatuh di bawah tanganVOC. Hal ini disebabkan pengaruh perdagangan bebaskebijakan atau kebijakan pintu terbuka yang dilakukan oleh Gowa Raja,Sultan Alauddin, ketika dia menolak aplikasiVOC tidak membuat hubungan dengan lainnyaNegara-negara Eropa seperti Portugal, Spanyol, danInggris. Kebijakan ini sangat jelas di SultanPernyataan Alauddin yang mengatakan:"Allah telah menciptakan darat dan laut; tanahdibagi antara manusia dan laut untuk semuamanusia. Hal ini tidak pernah mendengar bahwa seseorangdilarang untuk berlayar di laut. Jika Anda melakukannya, itu berarti Andaambil jauh makanan (roti) dari mulut kita. Akuseorang raja miskin "(Stapel, 1922).Hubungan baik antara pelaut danpedagang Sulawesi Selatan dan daerah memilikipernah dikunjungi, menurut Poelinggomang (2002),disebabkan beberapa faktor. Pertama, mereka mengatakanmenjadi sangat pintar untuk memberikan hadiah kepada otoritasdan ulama (ulama Islam) di tempat yang dikunjungi.Kedua, mereka dikatakan selalu menjaga merekajanji. Ketiga, mereka dikatakan selalu bersediauntuk membantu siapa pun diperlakukan tidak adil. Hal ini didasarkan padapenyair Belanda menyatakan bahwa pelaut dan pedagang dariSulawesi Selatan adalah seperti "ayam jantan yang penuh kasih dari

Timur (de hantjes van het Osten) (Poelinggomang,2002).Jejak untuk navigasi maritim dan perdaganganpetualangan Bugis-Makassar (dan Buton) adalahdimaksudkan untuk menunjukkan fakta ekonomi, sosial, danhubungan politik dan menjadi dasar bagipembentukan integrasi bangsa di kemudianpembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwaRepublik Indonesia daerah dulunya di bawahBelanda koloni, tapi ini didukung oleh toleransisikap dan simpati dari kelompok etnis yangtelah membuat persahabatan dan persaudaraan melaluinavigasi maritim dan jaringan perdagangan yangpelaut dan pedagang dari Bugis-Makassar dimainkanperan besar.MENJAGA TRADISI navigasiDAN PERTUMBUHAN MARINE KONSEPINDONESIA kepulauanSetelah kemerdekaan Indonesia,Tradisi navigasi produktif lagi karenaPelaut Bugis-Makassar sebagai ahli waris daribudaya nenek moyang 'yang ada selama waktu kolonial danluar. Belajar dari proses sejarah yang panjangkegiatan politik mengenai daerah Indonesia,kelompok pelaut Bugis-Makassar dapatmengubah konsep perairan dan lahan dariIndonesia dari zaman kolonial dan di luar untukera kemerdekaan. Generasi pelaut tuatelah mendapat pengalaman masa lalu bahwa perairan di Indonesiadan sejumlah pulau-pulau berada di bawah klaimkerajaan maritim yang berkuasa yang telah membuathubungan politik dan perdagangan.Selama era kemerdekaan melaluiinformasi dan pengalaman panjang, Bugis-Pelaut Makassar mendapat konsep baru yang menyiramdaerah dan Kepulauan Indonesia yangberlayar dan mengunjungi telah terintegrasi ke satubangsa, yaitu Negara Kesatuan Indonesia. Theperubahan konsep memungkinkan untukpenyebaran jaringan navigasi antar pulaudan transaksi ekonomi menjadi lebihintensif dan komunikatif antara Bugis-Pelaut Makassar dengan penduduk pesisirpulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.Berkenaan dengan pengalaman dan konsepBugis-Makasasr pelaut di perairan daerah danpulau di barat dan timur wilayah Indonesia,beberapa contoh kasus navigasi rute yangdisajikan dengan menunjukkan mengalami Bugis-

Kapten Makassar kapal. Mereka sayainforman berpengalaman dalam melakukan StranasProyek penelitian 2010.H. Andi Murtala dari Bira, Bulukumba (75tahun, mantan kapten, Bugis). Dia mulai sebagai kapalKapten pada tahun 1957. Kapal pertama kapten adalah pinisi(jenis perahu) dengan kapasitas 500-600 ton GT. TheKapal memiliki 10 sampai 15 kru dan mulai berlayar dariApril atau Mei sampai Desember. The kargo terdiridari berbagai jenis produk pertanian, misalnya, minyak kelapa,kayu, semen, ikan, garam, dll tergantung daripedagang yang menggunakan perahu. Di luar SelatanSulawesi, daerah penunjukan H. AndiPerahu Murtala ini adalah port dari Lombok, Sumbawa,Surabaya, Pasuruan, Semarang, Jakarta,Pontianak, Jambi, Palembang, dan Lampung. Dibagian timur Indonesia yang rute yangKendari, Ambon, dan Timika. Rute dibagian barat Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.H. Mustadjab dari Bira, Bulukumba (65tahun, mantan kapten, Bugis). Pada tahun 1958 H. Mustadjabmemulai karirnya sebagai kru. Pada awalnya ia adalah seorang juru masakselama 5 tahun. Setelah itu ia menjadi kru dan menjadiKapten kapal pada tahun 1974 dengan menavigasi pinisi BungaHarapan. Sama seperti kapal lain, Bunga Harapanjuga mulai berlayar dari April atau Mei sampai Desember.Di timur dan barat wilayah Indonesia, ruteadalah port dari Wengapu, Labuan Bala, Badas(Sumbawa), Ampena Lombok, Gresik, KalimasSurabaya, Jakarta, Bangka Belitung danSamarinda. Komoditas perdagangan yang semen,ubin, produk pertanian, produk campuran, pasir (materialuntuk industri kaca), dan kayu. Rute H.Mustadjab di bagian barat Indonesia dapatterlihat pada Gambar. 2H. Puang Ambo dari Paotere , MakassarKota ( 52 tahun , Kapten , Makassar ) . Dia memulaiberlayar pada tahun 1964. Kota-kota yang telahnavigasikan yang Kolaka , Buton , Bima , Kupang ,Ambon, Sorong , Biak , Surabaya , Denpasar ,Sumbawa , Lombok , Balikpapan , Samarinda danPotianak . Perahunya penuh dengan berbagai jenisproduk pertanian dan bahan bangunan terutamasemen, kayu , campuran komoditas , cengkeh , dankakao . Kedua cengkeh dan kakao diangkutdari Ambon . Rute kapal H. Puang Ambo inidapat dilihat pada Gbr.3 .H.Masruddin dari Bira, Bulukumba (60tahun, Kapten, Bugis). H. Masruddin mulai

berlayar pada tahun 1962 sebagai kru. Jenis pinisi perahukapten oleh H. Andi Murtala. Adapun pelaut lainnyadari Bira, status H. Masruddin sebagai kru memiliki jugamengunjungi banyak port Di Indonesia kedua timur danbagian barat Indonesia. Karena nyaprestasi, ia diangkat sebagai Mualim II (WakilKapten) yang menyertai H. Andi Murtala pada tahun 1972.Pengalamannya dalam berlayar dan pengetahuanlaut dan pulau-pulau membuatnya mungkin untuk berlayarluar negeri tiga kali, yaitu Darwin, Australiadua kali, dan sekali ke Tokyo, Jepang untuk berlayar tradisionalperahu dipesan dari Bira, Bulukumba untukmuseum nasional di kedua negara. Pertamadan navigasi kedua Darwin, Australia mengambildua jenis kapal "HATI Marege" dan "PinisiNUSANTARA ", dan ke Jepang untuk berlayar perahu dari"DAMAR SAGARA '. Karir puncaknya dicapaiketika ia ditunjuk Kapten pada tahun 1990 dandipercaya untuk kapten kapal pesiar milik pariwisataindustri di Bali. Rute dari "HATI Marege" untukDarwin, Australia Pelabuhan tahun 1984 dapat dilihat padaGbr.4.Dari diskusi dengan empat Bugis-Makassar mantan kapten dan pelaut dari Bira,Bulukumba dan Paotere, Kota Makassar, beberapainformasi tentang navigasi tradisional danpertumbuhan konsep kesatuan daerah Indonesiayang diperoleh. H. Andi Murtala mengatakan dengan bangga nyaPengalaman navigasi selama sekitar 40 tahun. Diabersyukur kepada Tuhan karena ia menjadi salah satupelaut yang bisa melanjutkan profesi dariGenerasi tua dari Bira Bugis yang telah pernahmenjadi kemenangan di era sebelumnya, terutama sebelumEra Kolonial Belanda di Nusantara. H. AndiMurtala mengatakan navigasi nya tanyapengalaman dan pengetahuan tentang Indonesiaruang air besar, termasuk pulau-pulau dan pelabuhanyang menjadi rute navigasi nya dibagian barat Indonesia. Terakhir namun tidak sedikit diaberhasil mendidik beberapa pelaut sampai merekaakhirnya menjadi kapten.Semirip H. Andi Murtala, H. Mustadjabjuga pelaut Bugis dari Bira yang statusnyaadalah kapten kapal pinisi (prototipePerahu perdagangan Bugis). Pada awalnya ia adalah seorangGbr.4. Navigasi Route Petaawak perahu H. Andi Murtala ini yang berlayar banyakkali di bagian barat Indonesia. Karenaia digunakan untuk perdagangan di wilayah itu, ia terus

dipertahankan rute navigasi dan port tuadi bagian barat Indonesia, terutamaSumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Jawapulau sebagai tempat tujuan perdagangan. Selamawawancara, ia antusias menceritakan nyanavigasi dan pengalaman maritim, dan nyapreferensi untuk asosiasi dan perdagangan dengan lokalorang. Ia bersyukur pada Allah karena dia adalah salah satu daripelaut profesional yang sukses yang lamagenerasi di Bira.Kapten lain saya diwawancarai adalah H. PuangAmbo yang memberitahu navigasi perdagangantradisi yang mengambil rute dan tujuan daerahdi bagian timur Indonesia. Ia mengakuibahwa ia adalah salah satu kapten dari Makassargenerasi muda yang masih dipertahankan untuk berlayar beberapapelabuhan di pulau-pulau di bagian timurIndonesia. Port di era sebelumKemerdekaan Indonesia, menurut dia, adalahdi bawah pemerintahan kerajaan maritim kecildi bagian timur Nusantara yang diperdagangkandengan Goa-Makassar Maritime Kingdomsterpusat di Somba Opu. Untuk membandingkan dengan Birasebagai tempat utama Bugis pelaut di Bulukumba,Paotere yang terletak di Makassar adalahpemukiman pusat dan pelabuhan Makassar yangselalu memendam oleh pinisi sejak BelandaEra kolonial.H. Masruddin, kapten lain, menginformasikan bahwaia tidak hanya berlayar di perairan laut Indonesia,tetapi juga di beberapa negara tetangga, sepertisebagai, Australia, Thailand, Filipina, dan Jepang.H. Masruddin juga mulai karirnya sebagai krudi bawah kepemimpinan Kapten H. AndiMurtala. Selama 10 tahun pertama, ketika diamasih dalam status awak, dia tahu laut besarperairan dan nama-nama pulau dan pelabuhan dibagian barat Indonesia yang menjadi nyadaerah tujuan. Karena prestation, iadiangkat sebagai kapten untuk menavigasi pinisidua kali untuk Darwin dan sekali ke Thailand, dan berlayarterus ke Jepang melalui Filipina. Diapengalaman navigasi telah mengembangkan idenyaAsia Tenggara dan dunia maritim Australia. Sebagai
KESIMPULANDari ilustrasi dan penjelasandisebutkan sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat

ditarik. Pertama, pada dasarnya maritim budayanilai-nilai pelaut Bugis-Makassar yangreproduksi pengalaman navigasi panjang mereka(persepsi manusia pada kondisi perairan, ruang,dan pulau-pulau) dan interaksi maritim (interaksipelaut dengan dunia sosial eksternal mereka diIndonesia). Kedua, nilai-nilai budaya maritimdan konsep air laut dari Bugis-Makassarpelaut di Indonesia kepulauan diwariskandari generasi ke generasi. Bagi mereka, langsungPengalaman adalah faktor yang paling menentukan untukpembentukan dan pengayaan maritimnilai-nilai budaya dan konsep air nusantara.Ketiga, nilai-nilai utama yang diambil dari lahanantara lain harga diri dan percaya bawaan yangdireproduksi oleh pengalaman navigasi menjadisikap yang ketat dan perilaku petualang, pekerjaanetos, daya saing, secara terbuka sikap, dllDemikian pandangan agama kemutlakan yangtakdir direproduksi dalam kemutlakanbisnis / kerja keras dan doa, dll Keempat,kelompok pelaut, terutama Bugis-Makassarpelaut, yang memiliki kesadaran danpengakuan untuk etnis yang berbeda diIndonesia, mencintai negara, kesatuan bahasa, danpersatuan nasional memiliki peran sebagai perekat pluralistikdan bangsa multikultural di kepulauan inipulau. Kelima, dalam kaitannya dengan penguatanintegrasi dan harmoni sosial etnik antarpengembangan masyarakat maritim adalahdiperlukan melalui pelaksanaan yangpendidikan nilai-nilai budaya maritim