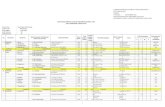Usaha tani kelompok
-
Upload
nabilussalam-saifullah-masum -
Category
Documents
-
view
3.348 -
download
8
Transcript of Usaha tani kelompok

BAB I
PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian di Indonesia mensyaratkan paradigma baru dari para
pengambil kebijakan. Sektor pertanian dalam paradigma baru perlu dilihat sebagai suatu
sistem yang integral. Seluruh komponen sistem idealnya harus diuntungkan dan berkembang
secara proporsional. Kondisi ini belum terjadi di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan
reformasi kebijakan pembangunan pertanian yang mengacu konsep pertanian berkelanjutan.
Sebelum reformasi itu digulirkan, pemerintah masih harus membenahi masalah besar yang
belum terjawab diera orde baru, yaitu ketidakseimbangan antara faktor-faktor produksi :
tanah, tenaga kerja, dan modal. Pembenahan ini perlu karena usaha tani berkelanjutan
biasanya menempuh strategi diversifikasi usaha tani dan padat karya.
Agar usaha tani tersebut layak secara ekonomis, dibutuhkan tingkat pemilikan modal
dan tanah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dibidang pertanahan dan
permodalan agar petani memperoleh kemudahan dan akses memperoleh modal. Faktor lain
yang perlu disiapkan untuk memdukung sistem pertanian berkelanjutan adalah kesiapan
petani. Hal mendasar yang dibutuhkan petani adalah suatu model pendidikan yang memicu
kesadaran kritis mereka. Hal ini penting agar para petani dapat mengambil sikap terhadap
pilihan-pilihan yang diberikan kepada mereka, misalnya dalam hal teknologi . Sistem
pertanian berkelanjutan juga mensyaratkan informasi yang utuh, terpercaya, dan dapat
diakses dengan mudah oleh petani. Dari pihak pemerintah, dituntut kemauan pilitiknya untuk
mereformasi kebijakan, pendekatan, serta metodologi pembangunannya selama ini. Misalnya
untuk mengurangi segala macam peraturan (regulasi) dan pengendalian yang cenderung
berlebihan serta membelenggu kebebasan dan mengingkari hak-hak petani. Dukungan
berupa insentif seperti asuransi juga perlu untuk dipertimbangkan diberikan kepada petani.
Kelembagaan petani juga perlu diperkuat dengan jalan memberikan akses kepada
petani seluas luasnya untuk mengorganisir diri dan memperkuat posisi mereka tanpa
intervensi dan pembatasan oleh pemerintah. Perlu disadari bahwa agenda pertanian
berkelanjutan hanyalah merupakan salah satu dari sekianbanyak agenda refoemasi sektor
pertanian yang perlu terus diperjuangkan. Masih banyak lagi masalah-masalah petani yang
sampai sekarang belum teratasi. Semua itu disebabkan oleh kebijakan pembangunan
pertanian selama ini masih belum berpihak kepada para petani. Petani umumnya dibiarkan
berjuang sendiri untuk memperjuangkan hak-haknya. Aksi-aksi menuntut reformasi yang

marak sekarang ini perlu digunakan sebagai momentum untuk membangun jaringan aliansi
yang lebih luas sambil terus menerus memperjuangkan kebijakan alternatif sistem pertanian
berkelanjutan di Indonesia. Semua itu tentu dalam kerangka merekonstruksi kebijakan
pembangunan pertanian masa lalu yang belum berpihak kepada petani.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 REVOLUSI HIJAU
Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan
perubahan fundamental dalam pemakaian teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada
tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Hasil yang
nyata adalah tercapainya swasembada (kecukupan penyediaan) sejumlah bahan pangan di
beberapa negara yang sebelumnya selalu kekurangan persediaan pangan (pokok), seperti
India, Bangladesh, Tiongkok, Vietnam, Thailand, serta Indonesia, untuk menyebut beberapa
negara. Norman Borlaug, penerima penghargaan Nobel Perdamaian 1970, adalah orang yang
dipandang sebagai konseptor utama gerakan ini.
Revolusi hijau mendasarkan diri pada empat pilar penting: penyediaan air melalui
sistem irigasi, pemakaian pupuk kimia secara optimal, penerapan pestisida sesuai dengan
tingkat serangan organisme pengganggu, dan penggunaan varietas unggul sebagai bahan
tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadi peningkatan hasil
tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman tiga kali dalam setahun untuk
padi pada tempat-tempat tertentu, suatu hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi.
Revolusi hijau mendapat kritik sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan
kelestarian lingkungan karena mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Oleh para
pendukungnya, kerusakan dipandang bukan karena Revolusi Hijau tetapi karena ekses dalam
penggunaan teknologi yang tidak memandang kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Kritik
lain yang muncul adalah bahwa Revolusi Hijau tidak dapat menjangkau seluruh strata negara
berkembang karena ia tidak memberi dampak nyata di Afrika.
Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara – negara berkembang dan
Indonesia dijalankan sejak rejim Orde Baru berkuasa. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana
telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi
sebuah negara yang berswasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu
lima tahun, yakni antara tahun 1984 – 1989. Disamping itu, Revolusi Hijau juga telah
menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial pedesaan karena ternyata Revolusi
Hijau hanyalah menguntungkan petani yang memiliki tanah lebih dari setengah hektar, dan
petani kaya di pedesaan, serta penyelenggara negara di tingkat pedesaan. Sebab sebelum

Revolusi Hijau dilaksanakan, keadaan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia sudah
timpang, akibat dari gagalnya pelaksanaan Pembaruan Agraria yang telah mulai dilaksanakan
pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1965. Pertanian revolusi hijau juga dapat disebut
sebagai kegagalan karena produknya sarat kandungan residu pestisida dan sangat merusak
ekosistem lingkungan dan kesuburan tanah.
Penggunaan pestisida juga menyebabkan terjadinya peledakan hama suatu keadaan
yang kontradiktif dengan tujuan pembuatan pestisida karena pestisida dalam dosis berlebihan
menyebabkan hama kebal dan mengakibatkan kematian musuh alami hama yang
bersangkutan.Namun, mitos obat mujarab pemberantas hama tetap melekat di sebagian
petani. Mereka tidak paham akan bahaya pestisida. Hal ini disebabkan karena informasi yang
sampai kepada mereka adalah ‘jika ada hama, pakailah pestisida merek A’. para petani juga
dibanjiri impian tentang produksi yang melimpah-ruah jika mereka menggunakan pupuk
kimia. Para penyuluh pertanian adalah ‘antek-antek’ pedagang yang mempromosikan
keajaiban teknologi modern ini. Penyuluh pertanian tidak pernah menyampaikan informasi
secara utuh bahwa pupuk kimia sebenarnya tidak dapat memperbaiki sifat-sifat fisika tanah,
sehingga tanah menghadapi bahaya erosi. Penggunaan pupuk buatan secara terus-menerus
juga akan mempercepat habisnya zat-zat organik, merusak keseimbangan zat-zat makanan di
dalam tanah, sehingga menimbulkan berbagai penyakit tanaman. Akibatnya, kesuburan tanah
di lahan-lahan yang menggunakan pupuk buatan dari tahun ke tahun terus menurun.
Di Indonesia, penggunaan pupuk dan pestisida kimia merupakan bagian dari Revolusi
Hijau, sebuah proyek ambisius Orde Baru untuk memacu hasil produksi pertanian dengan
menggunakan teknologi modern, yang dimulai sejak tahun 1970an. Memang Revolusi Hijau
telah menjawab satu tantangan ketersediaan kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat.
Namun keberhasilan itu bukan tanpa dampak dan efek samping yang jika tanpa pengendalian,
dalam jangka panjang justru mengancam kehidupan dunia pertanian. Gerakan revolusi hijau
di Indonesia memang terlihat pada dekade 1980an. Saat itu, pemerintah mengkomando
penanaman padi, pemaksaan pemakaian bibit impor, pupuk kimia, pestisida, dan lain-lainnya.
Hasilnya, Indonesia sempat menikmati swasembada beras. Namun pada dekade 1990an,
petani mulai kuwalahan menghadapi serangan hama, kesuburan tanah merosot,
ketergantungan pemakaian pupuk yang semakin meningkat dan pestisida tidak manjur lagi,
dan harga gabah dikontrol pemerintah. Bahan kimia sintetik yang digunakan dalam pertanian,
pupuk misalnya telah merusak struktur, kimia dan biologi tanah. Bahan pestisida diyakini
telah merusak ekosistem dan habitat beberapa binatang yang justru menguntungkan petani

sebagai predator hama tertentu. Disamping itu pestisida telah menyebabkan imunitas pada
beberapa hama. Lebih lanjut resiko kerusakan ekologi menjadi tak terhindarkan dan
terjadinya penurunan produksi membuat ongkos produksi pertanian cenderung meningkat.
Akhirnya terjadi inefisensi produksi dan melemahkan kegairahan bertani. Revolusi hijau
memang pernah meningkatkan produksi gabah.
A. STUDI KASUS
MEMACU PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH MELALUI INOVASI
TEKNOLOGI
BUDI DAYA SPESIFIK LOKASI DALAM ERA REVOLUSI HIJAU LESTARI
Upaya peningkatan produksi pangan terutama beras telah lama menjadi sebuah
kebijakan nasional. Mulai Pelita I, teknik budi daya padi sawah di lahan irigasi menggunakan
“panca usaha tani” yang mencakup: penggunaan benih unggul, cara bercocok tanam yang
baik,pengaturan air irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama dan penyakit. Awalnya
program ini menggunakan berbagai varietas yang sudah dilepas, di antaranya varietas
Bengawan, Sigadis, Remaja, Sinta, dan Arimbi. Panca usaha tani yang mendasari program
Bimas dimulai pada tahun 1969 dengan menggunakan varietas introduksi dari IRRI yaitu IR8
yang merupakan varietas unggul baru (VUB) hasil persilangan padi Peta dari Indonesia
dengan Dee-geo-woo-gen dari Taiwan dengan postur tanaman sedikit lebih pendek dan
potensi hasil 4,5 t/ha (De Datta 1981).
Kebijakan intensifikasi pertanian melalui Bimas pada era tersebut mengatur
penerapan paket teknologi secara sentralistis dan sistematis yang memiliki kekuatan politik
dan ekonomi yang sangat kuat dengan sistem komando. Program Bimas diikuti oleh Insus
pada tahun 1980 dengan menerapkan teknologi sapta usaha tani yang merupakan
penyempurnaan dari panca usaha tani. Pengalaman menunjukkan, implementasi program
intensifikasi yang didukung oleh inovasi teknologi dan penyuluhan serta perbaikan
infrastruktur pertanian telah mampu meningkatkan produksi padi nasional secara
meyakinkan, sekaligus merupakan implementasi dari revolusi hijau. Puncaknya adalah
terwujudnya swasembada beras pada tahun 1984.
Supra Insus yang pendekatannya lebih holistik dicanangkan pada tahun 1987 dengan
10 jurus teknologi paket D. Program Supra Insus didukung berbagai VUB yang lebih tahan
hama dan penyakit, terutama IR64, sehingga mampu kembali meningkatkan produksi padi
sampai menembus 50 juta ton pada tahun 1996, namun dengan laju kenaikan produksi
pertahun lebih rendah dari sebelumnya. Situasi perberasan nasional berada pada keadaan

kritis sejak 1997 akibat dari krisis moneter, disertai oleh kemarau panjang. Untuk memacu
laju kenaikan produksi padi, dicanangkan Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Padi,
Kedelai dan Jagung (Gema Palagung).
Upaya ini belum terlalu efektif karena laju kenaikan produksi padi, jagung, dan
kedelai masih lebih rendah dari laju kenaikan permintaan. Produktivitas dari total faktor
produksi juga turun, yang menandakan bahwa untuk memperoleh tingkat produksi yang sama
diperlukan input lebih besar atau penambahan input tidak proporsional dengan kenaikan
hasil. Dengan kata lain, efisiensi produksi menurun. Untuk kembali meningkatkan efisiensi
produksi, Badan Litbang Pertanian membuat beberapa pilot percontohan Sistem Usaha Tani
Padi Berwawasan Agribisnis (SUTPA) tahun 1995-1997 di 14 provinsi. Teknologi yang
diintroduksi meliputi VUB Memberamo dan Cibodas serta teknologi hemat tenaga kerja
melalui sistem tanam benih langsung, pemupukan spesifik lokasi, dan penggunaan alat tanam
benih langsung (Fagi dan Zaini 1996; Adnyana 1997).