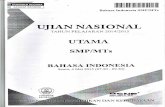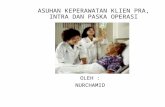Ujian Pak Syukriy
-
Upload
glen-purba -
Category
Documents
-
view
8 -
download
1
description
Transcript of Ujian Pak Syukriy
No. 2 Pengertian Belanja ModalBelanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar.Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa bangunan yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Sebagai contoh adalah belanja modal untuk pembangunan kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau inspektorat daerah. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa belanja modal adalah belanja publik, atau sebaliknya, belanja publik adalah belanja modal. Pengaktegorian ke dalam belanja publik dan belanja aparatur mengandung bias dari aspek penggunaan makna fungsi (outcome) belanja.Penganggaran Belanja ModalPada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan.Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja modal di pemerintah daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi atau pencarian rente (rent-seeking) oleh para pembuat keputusan anggaran (budget actors). Setiap tahapan dalam penganggaran memang memiliki ruang untuk korupsi (Isaksen, 2005), namun korupsi dalam pengadaan aset tetap atau barang modal, terutama yang memiliki spesifikasi khusus, termasuk yang paling sering terjadi (Tanzi, 2001).Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja modal adalah belanja ikutan setelah aset tetap diperoleh, yakni belanja operasional dan pemeliharaannya aset tetap bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat agar nantinya tidak membebani anggaran berupa pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang/sektor lain (trade-off). Dalam ilmu ekonomi, trade-off yang besar akan menghasilkan kebijakan yang tidak optimal.
No 1. Perubahan Anggaran Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPDPerubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama merngapa perubahan APBD dilakukan.Perubahan atas pendapatan, terutama PAD bisa saja berlatarbelakang perilaku oportunisme para pembuat keputusan, khususnya birokrasai di SKPD dan SKPKD. Namun, tak jarang perubahan APBD juga memuat preferensi politik para politisi di parlemen daerah (DPRD). Anggaran pendapatan akan direvisi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan karena beberapa sebab, diantaranya karena (a) tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, (b) perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah, dan (c) penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini.Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, di antaranya:1. Target pendapatan dalam APBD underestimated (dianggarkan terlalu rendah). Jika sebuah angkat untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang diperintahkan oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah.2. Alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktikmoral hazardyang dilakukanagency yang dalam konteks pendapatan adalahsebagaibudget minimizer.Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuatbudget slackkarena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD.3. Jikadalam APBD murni target PAD underestimated, maka dapat dinaikkan dalam APBD Perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD-P. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas keberhasilan belanja modal dalam mengungkit (leveraging) PAD, khususnyayang terealiasai dan tercapai outcome-nya pada tahun anggaran sebelumnya.Perubahan atas alokasi anggaran belanjamerupakan bagian terpenting dalam perubahan, khususnya pada kelompok belanja langsung. Beberapa bentuk perubahan alokasi untuk belanja modal berrdasarkan penyebabnya adalah:1. Perubahan karena adanya varian SiLPA. Perubahan harus dilakukan apabila prediksi atas SiLPA tidak akurat, yang bersumber dari adanya perbedaan antara SILPA 201a definitif setelah diaudit oleh BPK dengan SiLPA 201b.2. Perubahan karena adanya pergeseran anggaran (virement). Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu SKPD, meskipun total alokasi untuk SKPD yang bersangkutan tidak berubah.3. Perubahan karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Dari perspektif agency theory, pada saat penyusunan APBD murni, eksekutif (dan mungkin juga dengan sepengetahuan dan/atau persetujuan legislatif) target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukanadjustmentpada saat dilakukan perubahan APBD.Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisi dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran ayng ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).SiLPA tahun berjalan merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK RI belum menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.Selisih (variance) antara SiLPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.-Pergeseran AnggaranPeruahan anggaran sejatinya akan mengubah posisi, proporsi, dan komposisi rekening-rekening dalam APBD. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ada beberapa aturan tertulis yang harus dipahami, yakni (Copas dari Note Gunawan Widiatmoko: https://www.facebook.com/notes/gunawan-widiatmoko/pergeseran-anggaran/199265540537):1. PERMENDAGRI 13/2006BAB VIIIPERUBAHAN APBDBagian PertamaDasar Perubahan APBDPasal 154(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;d. keadaan darurat; dane. keadaan luar biasa.Bagian KetigaPergeseran AnggaranPasal 160(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.(7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah.2. PP58/2005Bagian KeduaPerubahan APBDPasal 81(1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;d. keadaan darurat; dane. keadaan luar biasa.3. UU32/2004Paragraf KedelapanPerubahan APBDPasal 183(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; danc. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahunanggaran berjalan.(2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.(3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pergeseran anggaran adalah dasar dari perubahan APBD.Tags: ags: anggaran daerah, apbd, belanja, budget variances, bupati, dprd, Gubernur, P-APBD, pembiayaan, pendapatan, SILPA, varian, walikoNo. 5Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah? Atau,Mengapa?Oktober 19, 2008tags: anggaran, apbd, APBN, Bawasda, BPK, BPKP, inspektorat daerah, inspektorat jenderal, internal audit, internal control, kode etik, pemda, PP 41 2007, pp 60-2008, PP No.60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SPIP, UU No.1/2004, UU No.15/2004by syukriy Pendahuluan. Isu tentang sistem pengendalian iternal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji kekuatan SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian iternal pemerintahan. Diskusi hangat muncul ke permukaan berkaitan dengan penerbitan PP ini. Beberapa topik utama diskusi berkaitan dengan: Urgensi penerbitan PP ini di saat konsistensi peraturan perundangan yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak Daerah yang belum melaksanakan peraturan perundangan yang sangat mendasar secara utuh, misalnya PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan. Costs-benefits bagi daerah. Daerah bertanya-tanya: apa manfaat PP ini bagi daerah? Jangan-jangan hanya menambah pekerjaan baru saja! Apakah memang PP ini bisa menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemda melalui SKPD-SKPD yang ada akan efektif, efisien, dan akuntabel? Jangan-jangan ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam penerbitan PP ini. Hampir semua kalangan paham bahwa PP ini berkaitan dengan upaya untuk memperkuat posisi BPKP sebagai auditor internal Presiden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di daerah.Substansi PP No.60/2008PP No. 60/2008 ini terdiri dari empat bab dan 61 pasal. Keempat bab tsb adalah Bab 1: Ketentuan Umum, Bab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bab 3: Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; dan Bab 4: Ketentuan Penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.Pasal 60 dan 61 berbunyi:Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Perturan Pemerintah ini.Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Dalam penjelasan PP No.60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur urusan internal Pemerintah dan Pemda ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU No.15/2004 disebutkan bahwaDalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. (Pasal 11 UU No.15/2004)Pada bagian lain UU tsb dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. (Pasal 9 UU No.15/2004).Penjelasan PP No.60/2008undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintahsecara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi: Lingkungan pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harusmenciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhanorganisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukungterhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yangdihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahanpimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatanpengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikandalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.Download PP No.60/2008: Lewat situs BPKP atau Rapidshare.