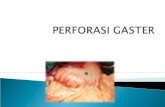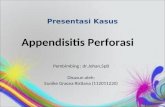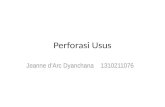tifoid perforasi
description
Transcript of tifoid perforasi
BAB II
DEMAM TIFOID PERFORASI
Definisi
Demam potensial yang fatal yang dapat mengenai berbagai sistem tubuh, yang disebabkan oleh bakteri salmonella typhi dan salmonella para typhi.
Epidemiologi
Pada beberapa dekade terakhir demam tifoid sudah jarang terjadi di Negara negara industri, namun tetap menjadi masalah kesehatan yang serius di sebagian wilayah dunia, seperti bekas negara Uni Soviet, anak benua India, Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Afrika. Menurut WHO, diperkirakan terjadi 16 juta kasus per tahun dan 600 ribu diantaranya berakhir dengan kematian. Sekitar 70 % dari seluruh kasus kematian itu menimpa penderita demam tifoid di Asia.
Demam tifoid merupakan masalah global terutama di negara dengan hygiene buruk. Etiologi utama di Indonesia adalah Salmonella enterika subspesies enterika serovar Typhi (S.Typhi) dan Salmonella enterika subspesies enterika serovar Paratyphi A (S. Paratyphi A). CDC Indonesia melaporkan prevalensi demam tifoid mencapai 358- 810/100.000 populasi pada tahun 2007 dengan 64% penyakit ditemukan pada usia 3-19 tahun, dan angka mortalitas bervariasiantara 3,1 10,4 % pada pasien rawat inap.
Etiologi
tifoid disebabkan oleh Salmonella typhi (S. typhi), basil gram negatif, berflagel, dan tidak
berspora. S. typhi memiliki 3 macam antigen yaitu antigen O (somatik berupa kompleks polisakarida), antigen H (flagel), dan antigen Vi. Dalam serum penderita demam tifoid akan terbentuk antibodi terhadap ketiga macam antigen tersebut.
Pathogenesis
Infeksi S.typhi terjadi pada saluran pencernaan. Basil diserap di usus halus kemudian
melalui pembuluh limfe masuk ke peredaran darah sampai di organ-organ terutama hati dan limpa. Basil yang tidak dihancurkan berkembang biak dalam hati dan limpa sehingga organ-organ tersebut akan membesar disertai nyeri pada perabaan. Kemudian basil masuk kembali ke
dalam darah (bakteremia) dan menyebar ke seluruh tubuh terutama ke dalam kelenjar limfoid usus halus, menimbulkan tukak pada mukosa diatas plaque peyeri. Tukak tersebut dapat mengakibatkan perdarahan dan perforasi usus. Gejala demam disebabkan oleh endotoksin yang dieksresikan oleh basil S.typhi sedangkan gejala pada saluran pencernaan disebabkan oleh kelainan pada usus
Gejala Klinis
Masa inkubasi Demam tifoid 10-14 hari, rata rata 2 minggu. Gejala timbul tiba tiba atau berangsur angsur. Penderita Demam tifoid merasa cepat lelah, malaise, anoreksia, sakit kepala, rasa tak enak di perut dan nyeri seluruh tubuh. Minggu ! : demam (suhu berkisar 39-400C), nyeri kepala, pusing, nteri otot, anoreksia, mual muntah, konstipasi, diare, perasaan tidak enak di perut, batuk dan epiktasis. Minggu 2 : demam, bradikardi, lidah khas berwarna putih, hepatomegali, splenomegali, gangguan kesadaran.
Demam pada tifoid umumnya berangsur angsur naik selama minggu pertama, demam terutama pada sore hari dan malam hari (bersifat febris reminent). Pada minggu kedua dan ketiga demam terus menerus tinggi (febris kontinua). Kemudian turun secara lisis. Demam ini tidak hilang dengan pemberian antipiretik, tidak ada menggigil dan tidak berkeringat. Kadang kadang disertai epiktasis. Gangguan gastrointestinal : bibir kering dan pecah pecah, lidah kotor, berselaput putih dan pinggirnya hiperemis. Perut agak kembung dan mungkin nyeri tekan. Limpa membesar dan lunak dan nyeri pada penekanan. Pada permulaan penyakit umumnya terjadi diare, kemudian menjadi obstipasi.
Pemeriksaan Penunjang
1. Hematologi
Kadar hemoglobin dapat normal atau menurun bila terjadi penyulit perdarahan usus atau perforasi.Hitung leukosit sering rendah (leukopenia), tetapi dapat pula normal atau tinggi. Hitung jenis leukosit: sering neutropenia dengan limfositosis relatif.LED ( Laju Endap Darah ) : Meningkat
Jumlah trombosit normal atau menurun (trombositopenia). 2. Urinalis
Protein: bervariasi dari negatif sampai positif (akibat demam)
Leukosit dan eritrosit normal; bila meningkat kemungkinan terjadi penyulit. 3. Kimia KlinikEnzim hati (SGOT, SGPT) sering meningkat dengan gambaran peradangan sampai hepatitis Akut.4. Imunologi
Widal
Elisa Salmonella typhi/ paratyphi lgG dan lgM 5. MikrobiologiKultur (Gall culture/ Biakan empedu) 6. Biologi molekular.PCR (Polymerase Chain Reaction) 7. Foto polos abdomenUdara bebas pada rongga peritoneum atau subdiafragma kanan
Diagnosis
Diagnosis pasti ditegakkan dengan cara menguji sampel feses atau darah untuk
mendeteksi adanya bakteri Salmonella spp dalam darah penderita, dengan membiakkan darah pada 14 hari pertama setelah terinfeksi.
Selain itu tes widal (O dah H agglutinin) mulai positif pada hari kesepuluh dan titer akan
semakin meningkat sampai berakhirnya penyakit. Pengulangan tes widal selang 2 hari menunjukkan peningkatan progresif dari titer agglutinin (diatas 1:200) menunjukkkan diagnosis positif dari infeksi aktif demam tifoid8. Biakan tinja dilakukan pada minggu kedua dan ketiga serta biakan urin pada minggu ketiga dan keempat dapat mendukung diagnosis dengan ditemukannya Salmonella8.
Gambaran darah juga dapat membantu menentukan diagnosis. Jika terdapat leukopeni
polimorfonuklear dengan limfositosis yang relatif pada hari kesepuluh dari demam, maka arah demam tifoid menjadi jelas. Sebaliknya jika terjadi lekositosis polimorfonuklear, maka berarti terdapat infeksi sekunder bakteri di dalam lesi usus. Peningkatan yang cepat dari lekositosis polimorfonuklear ini mengharuskan kita waspada akan terjadinya perforasi dari usus penderita.
Tidak selalu mudah mendiagnosis karena gejala yang ditimbulkan oleh penyakit itu tidak selalu khas seperti di atas. Bisa ditemukan gejala- gejala yang tidak khas. Ada orang yang setelah terpapar dengan kuman S.typhi, hanya mengalami demam sedikit kemudian sembuh tanpa diberi obat. Hal itu bisa terjadi karena tidak semua penderita yang secara tidak sengaja menelan kuman ini langsung menjadi sakit. Tergantung banyaknya jumlah kuman dan tingkat kekebalan seseorang dan daya tahannya, termasuk apakah sudah imun atau kebal. Bila jumlah kuman hanya sedikit yang masuk ke saluran cerna, bisa saja langsung dimatikan oleh sistem pelindung tubuh manusia.
Perforasi usus Terjadi pada sekitar 3% dari penderita yang dirawat. Biasanya timbul pada
minggu ketiga namun dapat pula terjadi pada minggu pertama. Selain gejala umum demam tifoid yang biasa terjadi maka penderita demam tifoid dengan perforasi mengeluh nyeri perut yang hebat terutama di daerah kuadran kanan bawah yang kemudian menyebar ke seluruh perut dan disertai dengan tanda-tanda ileus. Bising usus melemah pada 50% penderita dan pekak hati terkadang tidak ditemukan karena adanya udara bebas diabdomen. Tanda-tanda perforasi lainnya adalah nadi cepat, tekanan darah turun, dan bahkan dapat syok. Leukositosis dengan pergeseran ke kiri dapat menyokong adanya perforasi
Terapi
1. Terapi antibiotic
Pemberian antimikroba dengan tujuan menghentikan dan mencegah penyebaran kuman.
2. Terapi bedah
a) Indikasi : Perforasi ususPendarahan intestinal yang tidak dapat diatasi dengan konservatif b) Tindakan :Penutupan primer
Reseksi, end to end anastomose Reseksi ileostomi Hemikolektomi kanan