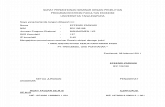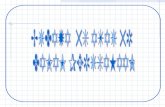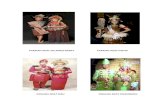septri.doc
Transcript of septri.doc
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaikan proposal yang berjudul: Analisis Perubahan Pola Tanam dan Indek Pertanaman Padi Sawah Akibat Perubahan Iklim di Daerah Irigasi Koto Tuo. Proposal ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian.
Dalam menyelesaikan proposal ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : Bapak Dr. Ir Feri Arlius, MSc selaku pembimbing I dan Bapak Dr.Ir. Eri Gas Ekaputra, MS selaku Pembimbing II yang bersedia menggantikan Ibu Ir. Asmiwarti. Selanjutnya kepada dosen-dosen Teknik Pertanian serta rekan-rekan BP 2010 seperjuangan dan junior Teknik Pertanian.
Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak luput dari kesalahan, kekeliruan maupun kekurangan yang berada diluar jangkauan penulis, untuk itu diharapkan semua pihak memberikan arahan dan masukan guna penyempurnaan proposal ini. Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini bermanfaat bagi pembaca dan berguna dalam upaya pengembangan Teknologi Pertanian.Padang, Juni 2014
S.PDAFTAR ISIHalamaniKATA PENGANTAR
iiDAFTAR ISI
ivDAFTAR TABEL
vDAFTAR GAMBAR
1I. PENDAHULUAN
11.1 Latar Belakang
21.2 Tujuan
21.3 Manfaat
3II. TINJAUAN PUSTAKA
32.1 Perubahan Iiklim
42.2 Perubahan Iklim Indonesia
42.2.1 Perubahan Pola Curah Hujan
52.2.2 Kejadian Iklim Ekstrim
62.2.3 Perubahan Iklim di Pantai Barat Sumatera Barat
62.3 Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air
82.4 Ketersediaan Air
82.4.1 Air Permukaan
92.4.2 Neraca Air
92.4.3 Kebutuhan air konsumtif (Etc)
132.5 Analisis neraca ketersediaan kebutuhan
142.6 Pola Tanam dan Indek Pertanaman
16III. METODE PENELITIAN
163.1 Waktu dan Tempat
163.2 Alat dan Bahan Penelitian
163.2.1 Alat
163.2.2 Bahan
163.3 Metode Penelitian
173.4 Prosedur Penelitian
173.4.1 Pengumpulan Data
173.4.2 Pengolahan Data
183.4.3 Analisis Potensi Indek Pertanaman
193.4.4 Analisis Perubahan Indek Pertanaman Akibat Perubahan Iklim
193.5 Output
21DAFTAR PUSTAKA
22LAMPIRAN
DAFTAR TABELTabelHalaman2.1 Tren perubahan kondisi curah hujan bulanan dan tahunan di sepanjang pantai barat Sumatera Barat6
2.2 Koefisien Tanaman Padi102.3 Hubungan antara T, ea, w dan f(t)112.4 Angka Angot (Ra) (mm/hari) (Untuk Daerah Indonesia, antara 50 LU sampai 100 LS)122.5 Angka Koreksi ( c ) Bulanan Untuk Rumus Penman133.1. Kriteria status ketersediaan air berdasarkan defisit neraca ketersediaan kebutuhan air lahan19DAFTAR GAMBARGambarHalaman2.1. Keragaman iklim Indonesia32.2 Gambar tren perubahan curah hujan musiman pada periode bulan: Des- Jan - Feb (DJF; atas) dan Jun Jul - Agu (JJA; bawah)5
3.1 Diagram Alir Analisa Potensi Indek Tanam dan Pola Tanam20I. PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang
Akhir - akhir ini dibeberapa tempat di Indonesia telah mulai merasakan terjadinya perubahan iklim sebagai implikasi dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca. Salah satu ciri perubahan iklim yang dirasakan seperti terjadinya, perubahan atau pergeseran pola curah hujan dan pergeseran musim.Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di daerah khatulistiwa sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ditinjau rerata tren perubahan kondisi curah hujan di pantai Barat Sumatera Barat telah mengalami perubahan hingga saat ini, hal ini dilihat dengan penurunan curah hujan disetiap bulan yaitu pada probabilitas 66 % atau kemungkinan terjadinya penurunan curah hujan sebesar 66 % . Sedangkan pada bulan Maret, April, Mei secara berturut - turut di seluruh stasiun di pantai barat Sumatera Barat mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan dengan nilai probabilitas 90 % (Ekaputra et al, 2013).Pertanian lahan sawah merupakan salah satu usaha tani yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Dalam pengembangan pertanian lahan sawah, masalah utama yang sering dihadapi adalah ketersediaan air. Air yang merupakan faktor utama dalam menentukan tingkat produksi, intensitas tanam, dan luas tanam potensial. Kondisi ini membuat ketersediaan air sangat menjadi faktor pembatas, dalam usaha tani lahan sawah. Ketersediaan air harus sesuai dengan kebutuhan air yang diperlukan, sehingga budidaya tanaman padi di lahan sawah tersebut tidak mengalami kekurangan air dalam proses budidayanya.
Pada proses budidaya tanaman padi sawah ini terdapat beberapa fase dimana setiap fase tersebut sangat membutuhkan air yang bervariasi yaitu dari fase penanaman, perkembangan vegetatif, pembungaan, dan fase pembentukan biji. Kekurangan air pada fase - fase tersebut dapat mempengaruhi produksi tanaman padi sawah dan berakibat pada indek pertanaman di lahan tersebut dalam setahun.Hal yang sama juga mungkin dialami pada daerah irigasi Koto Tuo yang merupakan salah satu jaringan irigasi semi teknis yang terdapat di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, didirikan pada tahun 1978 yang memiliki luas baku 1.088 ha. Daerah irigasi Koto Tuo terdiri dari dua bagian yaitu Daerah Irigasi Koto Tuo Kanan dengan luas lahan sekitar 709,3 ha dan daerah irigasi Koto Tuo kiri seluas 378,7 ha. Daerah irigasi tersebut merupakan salah satu lahan pemasok beras kota Padang. Dengan adanya perubahan iklim ini maka proses budidaya tanaman padi di lahan ini juga di pengaruhinya.Berdasarkan ulasan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perubahan Pola Tanam dan Indek Pertanaman Padi Sawah Akibat Perubahan Iklim di Daerah Irigasi Koto Tuo
1.2 TujuanTujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perubahan pola tanam dan potensi indek pertanaman lahan pertanian sawah yang diakibatkan oleh perubahan iklim disepanjang pantai barat provinsi Sumatera Barat.
1.3 Manfaat
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pola tanam dan indek pertanaman berdasarkan neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah di Daerah Irigasi Koto Tuo.II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Perubahan IiklimIklim merupakan sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya (World Climate Conference, 1979). Konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur -unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Glenn T. Trewartha, 1980). Peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Gibbs, 1987).Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2001). Perubahan fisik ini tidak terjadi hanya sesaat tetapi dalam kurun waktu yang panjang. LAPAN (2002) mendefinisikan perubahan iklim adalah perubahan rata-rata salah satu atau lebih elemen cuaca pada suatu daerah tertentu. Sedangkan istilah perubahan iklim skala global adalah perubahan iklim dengan acuan wilayah bumi secara keseluruhan. IPCC (2001) menyatakan, bahwa perubahan iklim merujuk pada variasi rata-rata kondisi iklim suatu tempat atau pada variabilitasnya yang nyata secara statistik untuk jangka waktu yang panjang (biasanya dekade atau lebih). Selain itu juga diperjelas bahwa perubahan iklim mungkin karena proses alam internal maupun ada kekuatan eksternal, atau ulah manusia yang terus menerus merubah komposisi atmosfer dan tata guna lahan. Gambar keragaman iklim Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Keragaman iklim IndonesiaSumber : Hales et al., tanpa tahun
2.2 Perubahan Iklim Indonesia
2.2.1 Perubahan Pola Curah HujanPerubahan pola hujan sudah terjadi sejak beberapa dekade terakhir dibeberapa wilayah di Indonesia, seperti pergeseran awal musim hujan dan perubahan pola curah hujan. Selain itu terjadi kecenderungan perubahan intensitas curah hujan bulanan dengan keragaman dan deviasi yang semakin tinggi serta peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, terutama curah hujan, angin, dan banjir rob.
Beberapa ahli menemukan dan memprediksi arah perubahan pola hujan di Bagian Barat Indonesia, terutama di Bagian Utara Sumatera dan Kalimantan, dimana intensitas curah hujan cenderung lebih rendah, tetapi dengan periode yang lebih panjang. Sebaliknya, di Wilayah Selatan Jawa dan Bali intensitas curah hujan cenderung meningkat tetapi dengan periode yang lebih singkat (Naylor, 2007). Secara nasional, Boer et al. (2009) mengungkapkan tren perubahan secara spasial, dimana curah hujan pada musim hujan lebih bervariasi dibandingkan dengan musim kemarau.Perubahan iklim juga berdampak terhadap peningkatan hujan musiman Desember, Januari, Februari (DJF) secara signifikan di sebagian besar wilayah di Jawa, Kawasan Timur Indonesia, dan Sulawesi. Sebaliknya, perubahan iklim berdampak terhadap penurunan hujan musiman Juni, Juli, Agustus (JJA) secara signifikan disebagian besar wilayah Jawa, Papua, Bagian Barat Sumatera, dan Bagian Timur Selatan Kalimantan. Perubahan iklim mengakibatkan musim kemarau memanjang disebagian besar wilayah Jawa, Bagian Selatan Sumatera, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Gambar tren perubahan curah hujan musiman dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2. Gambar tren perubahan curah hujan musiman pada periode bulan: Des-Jan-Feb (DJF; atas) dan Jun Jul - Agu (JJA; bawah)Sumber: KLH, 20102.2.2 Kejadian Iklim Ekstrim
Keragaman iklim antar - musim dan tahunan, terutama yang menyebabkan munculnya iklim ekstrim akibat fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) dan Osilasi Atlantik atau Osilasi Pasifik, juga semakin meningkat dan menguat. Menurut Timmerman et al. (1999) dari Max Planck Institute dan Hansen et al. (2006), pemanasan global cenderung meningkatkan frekuensi El-Nino dan menguatkan fenomena La-Nina. Peningkatan siklus ENSO dari 3 - 7 tahun sekali menjadi 2 - 5 tahun sekali (Ratag, 2001). Telah terjadi peningkatan peluang curah hujan ekstrem harian disebagian wilayah Indonesia, kecuali beberapa wilayah di Maluku, dalam kurun waktu kurang lebih selama 10 tahun selama 1998 2008. El-Nino adalah gejala gangguan iklim yang diakibatkan oleh naiknya suhu permukaan laut Samudera Pasifik sekitar khatulistiwa bagian tengah dan timur. Naiknya suhu di Samudera Pasifik ini mengakibatkan perubahan pola angin dan curah hujan yang ada di atasnya. Pada saat normal hujan banyak turun di Australia dan Indonesia, namun akibat El-Nino ini hujan banyak turun di Samudera Pasifik sedangkan di Australia dan Indonesia menjadi kering.2.2.3 Perubahan Iklim di Pantai Barat Sumatera BaratHasil analisis dengan menggunakan Uji Mann-Kendall, dihasilkan tren curah hujan di sepanjang pantai sumatera barat mengalami penurunan curah hujan disetiap bulan dengan tingkat probabilitasnya 66 %, dengan demikian walaupun perubahannya tidak begitu signifikan namun perlu dilakukan antisipasi dari dampak perubahan kondisi curah hujan yang terjadi di sepanjang kawasan pantai barat Provinsi Sumatera Barat. Seperti pada bulan Maret, April, Mei secara berturut turut di seluruh stasiun mengalami penurunan curah hujan yang sangat signifikan dengan nilai probabilitas di atas 90% (Ekaputra et al. 2013). Tren perubahan kondisi curah hujan tahunan dan bulanan di sepanjang pantai barat Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.1.Tabel 2.1 Tren perubahan kondisi curah hujan bulanan dan tahunan di sepanjang pantai barat Sumatera Barat
BulanTrendProbabilitas
JanuariExpansion66%
FebruariExpansion66%
MaretDecreasing81%
AprilDecreasing94%
MaiDecreasing77%
JuniStable/No Trend66%
JuliDecreasing66%
AgustusStable/No Trend66%
SeptemberDecreasing66%
OktoberExpansion67%
NovemberStable/No Trend66%
DesemberStable/No Trend66%
AnnualDecreasing66%
2.3 Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air
Secara umum, perubahan iklim akan berdampak terhadap penciutan dan degradasi (penurunan fungsi) sumberdaya lahan, air dan infrastruktur terutama irigasi, yang menyebabkan terjadinya ancaman kekeringan atau banjir. Ancaman banjir dan kekeringan akan diperparah oleh perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrim.
Selain itu, tingkat kerusakan jaringan irigasi juga cukup tinggi. Diperkirakan saat ini jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik mencapai 70 %, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan air (Ditjen PLA, 2007). Perubahan pola curah hujan menyebabkan penurunan ketersediaan air pada waduk, terutama di Jawa. Sebagai contoh, selama 10 tahun rata-rata volume aliran air dari DAS Citarum yang masuk ke waduk menurun dari 5,7 milyar m3 menjadi 4,9 milyar m3 per tahun (Bappenas, 2009). Kondisi tersebut berimplikasi terhadap turunnya kemampuan waduk Jatiluhur mengairi sawah di Pantura Jawa. Kondisi yang sama ditemui pada waduk lain di Jawa, seperti Gajahmungkur dan Kedung Ombo akibat perubahan iklim.Ancaman banjir yang semakin sering terjadi pada lahan sawah juga merupakan salah satu dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Hal ini menyebabkan berkurangnya luas areal panen dan produksi padi. Peningkatan intensitas banjir secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi karena meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman. Peningkatan frekuensi banjir dapat menimbulkan masalah berupa serangan hama keong mas pada tanaman padi. Di samping itu, juga ada indikasi bahwa lahan sawah yang terkena banjir pada musim sebelumnya berpeluang lebih besar mengalami ledakan serangan hama wereng coklat.
Kebutuhan air di dalam negeri pada tahun 1990 adalah 3.169 x 106 m3, sedangkan angka proyeksi pada tahun 2000 dan 2015 berturut - turut sebesar 6.114 x 106 m3 dan 8.903 x 106 m3. Berarti peningkatan kebutuhan air berkisar antara 10 % per tahun dalam periode 1990 - 2000 dan 6,67 % per tahun dalam periode 2000 - 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup, 2002). Berdasarkan perhitungan kebutuhan air oleh Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, maka Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mengalami defisit air, terutama pada musim kemarau. Defisit air akan bertambah parah di masa yang akan datang akibat pertambahan penduduk, meningkatnya kegiatan ekonomi, dan perubahan iklim.2.4 Ketersediaan Air
Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air pada dasarnya berasal dari air hujan (atmosferik), air permukaan dan air tanah. Hujan yang jatuh di atas permukaan pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Wilayah Sungai (WS) sebagian akan menguap kembali sesuai dengan proses iklimnya, sebagian akan mengalir melalui permukaan dan sub permukaan masuk ke dalam saluran, sungai atau danau dan sebagian lagi akan meresap jatuh ke tanah sebagai pengisian kembali (recharge) pada kandungan air tanah yang ada (Anonim, 2006).Secara keseluruhan jumlah air di planet bumi ini relatif tetap dari masa ke masa (Suripin, 2002). Ketersediaan air yang merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (spatial variability) dan variabilitas waktu (temporal variability) yang sangat tinggi. Konsep siklus hidrologi adalah bahwa jumlah air disuatu luasan tertentu di hamparan bumi dipengaruhi oleh masukan (input) dan keluaran (output) yang terjadi.2.4.1 Air Permukaan
Air permukaan adalah air yang mengalir secara berkesinambungan atau dengan terputus-putus dalam alur sungai atau saluran dari sumbernya yang tertentu, dimana semua ini merupakan bagian dari sistem sungai yang menyeluruh. Yang termasuk air permukaan meliputiair sungai (rivers), saluran (stream), sumber (springs), danau dan waduk. Jumlah air permukaan diperkirakan hanya 0,35 Juta km atau hanya sekitar 1 % dari air tawar yang ada di bumi (Suripin, 2002). Aliran yang terukur di sungai atau saluran maupun danau merupakan ketersediaan debit air permukaan, begitu halnya dengan air yang mengalir ke dalam tanah, kandungan air yang tersimpan dalam tanah merupakan ketersediaan debit air tanah. Dari ketiga sumber air tersebut di atas, yang mempunyai ketersediaan paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai, saluran, danau, waduk dan lainnya. Penggunaan air tanah sangat membantu pemenuhan kebutuhan air baku maupun air irigasi pada daerah yang sulit mendapatkan air permukaan, namun pemanfaatan air tanah membutuhkan biaya operasional pompa yang sangat mahal (Anis et al, 1980).2.4.2 Neraca Air
Penyusunan neraca air di suatu tempat dan pada suatu tempat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah netto dari air yang diperoleh sehingga dapat diupayakan pemanfaatannya sebaik mungkin (Gede, 2009).
Menurut Mather (1978) istilah neraca air mempunyai beberapa arti yang berbeda tergantung dari skala ruang dan waktu :a. Skala makro : neraca air dapat digunakan dalam pengertian yang sama seperti siklus hidrologi, neraca global tahunan dari air di lautan, atmosfer dan bumi pada semua fase;
b. Skala meso : neraca air dari suatu wilayah atau suatu drainase basin utama;
c. Skala mikro : neraca air yang diselidiki dari lapangan bervegetasi, tegakan hutan atau kejadian individu pohon. Neraca air merupakan perimbangan antara masukan (input) dan keluaran (output) air di suatu tempat pada suatu saat atau periode tertentu. Dalam perhitungan digunakan satuan tinggi air (mm, atau cm). Satuan waktu yang digunakan dapat dipilih satuan harian, mingguan, dekad (10 harian), bulanan ataupun tahunan sesuai dengan keperluan (Gede, 2009).
2.4.3 Kebutuhan air konsumtif (Etc)
Doorenbos dan Pruitt (1977) mendefinisikan kebutuhan air konsumtif sebagai jumlah air yang disediakan untuk mengimbangi air yang hilang akibat evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan proses penguapan dari permukaan tanah atau evaporasi dan penguapan dari daun tanaman atau transpirasi. Besarnya kebutuhan air konsumtif ini adalah jumlah air yang hilang akibat proses evapotranspirasi dikalikan dengan koefisien tanaman. Menurut Direktorat Jenderal Pengairan (1986) kebutuhan air konsumtif dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:
Etc = kc Eto ..............................................................................(2.1)Keterangan :
Etc= Kebutuhan air konsumtif (mm/hari),
Eto= Evapotranspirasi potensial (mm/hari),
kc = Koefisien tanaman Besarnya koefisien tanaman setiap jenis tanaman berbeda-beda dan berubah setiap periode pertumbuhan tanaman. Evapotranspirasi potensial dihitung dengan metode Penman Modifikasi yang telah disesuaikan dengan keadaan daerah Indonesia dan nilai Kc untuk berbagai jenis tanaman yang ditanam disajikan harga - harga koefisien tanaman padi dengan varietas unggul dan varietas biasa menurut Nedeco atau Prosida dan FAO (Direktorat Jenderal Pengairan, 1986). Tabel Koefisien Tanaman Padi dapat dilihat pada table 2.2.Tabel 2.2 Koefisien Tanaman Padi
BulanNedeco/Prosida FAO
Varietas BiasaVarietas UnggulVarietas BiasaVarietas Unggul
0.51.21.21.11.1
11.21.271.11.1
1.51.321.331.11.05
21.41.31.11.05
2.51.351.151.10.95
31.2401.050
3.5 1.12 0.95
4 0 0
Sumber: Direktorat Jenderal Pengairan (1986)
Varietas padi biasa adalah varietas padi yang masa tumbuhnya lama. Varietas unggul adalah varietas padi yang jangka waktu tumbuhnya pendek. Selama setengah bulan terakhir pemberian air irigasi ke sawah dihentikan, kemudian koefisien tanaman diambil "nol" dan padi akan menjadi masak dengan air yang tersedia.Menurut Linsley dan Franzini (1996), untuk mengetahui nilai evapotranspirasi potensial, maka metode yang paling sering digunakan adalah metode Penman Modifikasi. Rumus Penman Modifikasi yaitu:
ETo = c x ET *.....(2.2)
ET* = w (0.75 Rs Rn1) + (1-w) f (u) (ea-ed) .......(2.3)dimana:
w=Faktor yang berhubungan dengan temperatur (T) dan elevasi daerah. Untuk daerah Indonesia dengan elevasi antara 0 - 500 m, hubungan harga T dan w seperti pada Tabel 2.3Rs=Radiasi gelombang pendek dalam satuan evaporasi (mm/hari)
=(0,25 + 0,54 n/N) Ran/N= Penyinaran matahari (mm/hari)
Ra=Radiasi gelombang pendek yang memenuhi batas luar atmosfir (angka angot) yang dipengaruhi oleh letak lintang daerah. Harga Ra seperti (Tabel 2.4)Rn1=Radiasi bersih gelombang panjang (mm/hari)
=f(t) . f(ed) . f(n/N)
f(t)=Fungsi suhu (Tabel 2.3)
f(ed)=Fungsi tekanan uap
=0,34 - 0,044 . ((ed)
f(n/N)=Fungsi kecerahan
=0,1 + 0,9 n/N
f(u)=Fungsi dari kecepatan angin pada ketinggian 2 m dalam satuan (m/dt)
=0,27 (1 + 0,864 u)
U=Kecepatan angin (m/dt)
(ea-ed)=Perbedaan tekanan uap jenuh dengan tekanan uap yang sebenarnya
ed=ea . Rh
RH=Kelembaban udara relatif (%)
ea=Tekanan uap jenuh (mbar) (Tabel 2.3).
ed=Tekanan uap sebenarnya (mbar)
c=Angka koreksi Penman yang memasukkan harga perbedaan kondisi cuaca siang dan malam. Harga C dapat dilihat pada Tabel 2.5.Tabel 2.3 Hubungan antara T, ea, w dan f(t)
T( 0 C)Ea (Mbar)WF(t)
24.0029.500.73515.40
25.0031.690.74515.65
26.0033.620.75515.90
27.0035.660.76516.10
28.0037.810.77516.30
28.6039.140.78116.42
29.0040.060.78516.50
Sumber: Irigasi dan Bangunan Air (1997)Tabel 2.4 Angka Angot (Ra) (mm/hari) (Untuk Daerah Indonesia, antara 50 LU sampai 100 LS)
BulanLintang UtaraLintang Selatan
5420246810
Januari13.014.314.715.015.315.515.816.116.1
Pebruari14.015.015.315.515.715.816.016.116.0
Maret15.015.515.615.715.715.615.615.515.3
April15.115.515.315.315.114.914.714.414.0
Mei15.314.914.614.414.113.813.413.112.6
Juni15.014.414.213.913.513.212.812.412.6
Juli15.114.614.314.113.713.413.112.711.8
Agustus15.315.114.914.814.514.314.013.712.2
September15.115.315.315.315.215.115.014.913.3
Oktober15.715.115.315.415.515.615.715.814.6
Nopember14.814.514.815.115.315.515.816.015.6
Desember14.614.114.414.815.115.415.716.016.0
Sumber : Irigasi dan Bangunan Air (1997)Tabel 2.5 Angka Koreksi ( c ) Bulanan Untuk Rumus PenmanBulanCBulanC
Januari1.04Juli0.90
Peruari1.05Agustus1.00
Maret1.06September1.10
April0.90Oktober1.10
Mei0.90Nopember1.10
Juni0.90Desember1.10
Sumber: Irigasi dan Bangunan Air (1997)2.5 Analisis neraca ketersediaan kebutuhanAnalisis neraca ketersediaan kebutuhan air lahan sawah yang dikembangkan oleh Kartiwa (2010). Neraca ketersedian kebutuhan air lahan sawah dihitung berdasarkan neraca antara ketersediaan air di bendung irigasi serta curah hujan dan kebutuhan irigasinya. Kebutuhan irigasi terdiri dari kebutuhan tanaman, kebutuhan air untuk pengolahan tanah, dan kehilangan air karena perkolasi. Analisis kebutuhan tanaman dilakukan berdasarkan menurut metode FAO (Doorenbos.J. dan A.H Kassam, 1979)
Kebutuhan air tanaman dihitung berdasarkan persamaan berikut :
ETtan = Kc ET(2.4)Keterangan :
ETtan = Evapotranspirasi tanaman
ETo = Evapotranspirasi Referensi
Kc = Koefisien Tanaman
Kebutuhan air untuk pengolahan dan penggenangan lahan dihitung berdasarkan rekomendasi PU sedangkan perkolasi telah ditetapkan berdasarkan survei lapangan .
Untuk menghitung kebutuhan irigasi lahan sawah dihitung berdasarkan ketetapan sebagai berikut (Kartiwa, 2010):1. Irigasi diberikan apabila tinggi genangan di lahan sawah lebih rendah dari batas ketinggian yang diperbolehkan.Gi > GminGi = Gi-1 Perci ETCi + CHi(2.5)Keterangan :
Gi = Tinggi genangan air sawah pada hari ke-i
Gmin = Tinggi genangan air lahan sawah minimum
2. Irigasi dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :
Ir = Gmax (Gi-1 Perci ETCi + CHi)(2.6)Keterangan :
Ir = Kebutuhan air irigasi pada hari ke-i (mm)
Gmax= Tinggi genangan air lahan sawah maxsimum (mm)
Gi-1= Tinggi genangan air lahan sawah pada hari ke-(i-1) (mm)
Perc = Perkolasi
ETCi= Evapotranspirasi tanaman pada hari ke-i (mm)
CHi= Curah Hujan pada hari ke-i (mm)2.6 Pola Tanam dan Indek Pertanaman
Perencanaan pola tanam merupakan bagian dari tahapan dalam upaya pengaturan (Perencanaan) budi daya tanaman pangan untuk meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber daya iklim secara efisien. Setyanata (1983) dalam Hermayani Barus (2001) mengemukakan pola tanam pada sebidang lahan dengan mengatur pola pertanaman, sedangkan pola pertanaman adalah suatu susunan tata letak dan tata urutan tanaman pada sebidang lahan selama periode tertentu, termasuk didalamnya pengolahan lahan dan bera. Pola tanam dalam arti memilih jenis tanaman yang dapat ditanam dalam setahun (Nasir dan Effendy, 1999)
Indek Pertanaman (IP) Merupakan salah satu cara potensial untuk meningkatkan produksi. Peningkatan produksi dengan peningkatan intensitas pertanaman sangat potensial dan memberikan dampak yang lebih cepat ( Las et al. 199) dalam Hermayani Basur (2001). Angka IP menunjukkan intensitas pertanaman dalam tiga kali musim tanam selama setahun. Apabila seluruh lahan ditanami 3 kali dalam setahun maka IPnya adalah 3. Untuk menunjukkan jumlah persentase lahan yang ditanami angka tersebut dibuat dalam bentuk persen, misalnya untuk IP 3 ditulis IP 300.
Berdasarkan potensi dan ketersediaan sumber daya air, potensi dan peluang peningkatan IP baik untuk pada maupun palawija pada beberapa daerah masih cukup besar (Balitbang Deptan, 1998) dalam Hermayani Basur (2001). Khusus untuk potensi perluasan palawija perlu mempertimbangkan beberapa aspek sosial ekonomi masing-masing komoditas pada setiap daerah. Untuk keberhasilan peningkatan IP sebaiknya diikuti dengan identifikasi lokasi dan analisis potensi serta pola ketersediaan air disertai pola tanam.III. METODE PENELITIAN3.1 Waktu dan Tempat
Penelitian untuk menganalisis perubahan potensi pola tanam dan indek pertanaman padi sawah akibat perubahan iklim berdasarkan neraca ketersediaan dan kebutuhan air akan di laksanakan pada tanggal 30 Mei - 30 Juni 2014 bertempat di Daerah Irigasi Koto Tuo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pengolahan dan penganalisaan datanya akan dilakukan di Laboratorium Teknik Sumberdaya Lahan dan Air Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknik Pertanian Universitas Andalas.3.2 Alat dan Bahan Penelitian3.2.1 Alat
Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah :
1. Seperangkat komputer untuk menjalankan Microsoft Excel2. Current Meter yang digunakan untuk mengukur debit air yang masuk pada bangunan sadap dan debit air yang sampai di lahan sawah3. Rambu Ukur digunakan untuk mengukur tinggi muka air4. Meteran digunakan untuk mengukur luas penampang saluran5. Alat tulis untuk mencatat data3.2.2 Bahan
Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah :
1. Data curah hujan harian 10 tahun terakhir dari tahun 2002 sampai 2012.
2. Data debit bendung irigasi harian 10 tahun terakhir dari tahun 2002 sampai 2012.
3. Data iklim harian 10 tahun terakhir dari tahun 2002 sampai 2012.3.3 Metode Penelitian
Untuk mengetahui perubahan pola tanam dan indek pertanaman akibat perubahan iklim ini dilakukan analisis neraca ketersediaan air dan kebutuhan air lahan sawah per 10 harian dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2002 sampai 2012 dengan skenario pola tanam dan indek pertanaman padi, padi, padi, yang masa tanam sesuai dengan yang telah dilakukan selama ini. Setelah neraca ketersediaan dan kebutuhan air didapatkan, maka ditentukan potensi indek pertanaman pertahunnya berdasarkan jumlah defisit neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah. Data sepuluh tahun terakhir digunakan untuk menentukan potensi indek pertanaman setiap tahunnya. Setelah potensi indek pertanaman setiap tahunnya didapatkan maka dibandingkan kondisi existing dengan hasil neraca ini apakah terjadi perubahan indek pertanaman selama sepuluh tahun tersebut, hasil ini akan dikaitkan dengan perubahan iklim.3.4 Prosedur Penelitian3.4.1 Pengumpulan Dataa. Data curah hujan harian akan diperoleh dari stasiun klimatologi yang berada di daerah irigasi Koto Tuo yang merekam curah hujan yang terjadi setiap hari di irigasi Koto Tuo.
b. Data debit bendung irigasi akan diperoleh dari stasiun yang merekam debit bendung irigasi yang ada di daerah irigasi Koto Tuo. c. Data Iklim diperoleh dari stasiun klimatologi yang ada di daerah irigasi Koto Tuo.
d. Data efisiensi saluran di peroleh dari data debit air yang masuk ke jaringan irigasi dan debit yang sampai ke lahan sawah yang diukur langsung di lapangan menggunakan current meter. e. Data luas lahan sawah atau luas daerah irigasi Koto Tuo diperoleh dari data PU3.4.2 Pengolahan Dataa. Efisiensi saluran Irigasi
Untuk data efisiensi saluran di peroleh dari perhitungan berikut :
Efisiensi saluran = Qout 100%(3.1)
QinKeterangan: Qin= Debit yang masuk pada hulu saluran
Qout= Debit yang sampai ke hilir saluranQ1 dan Q2 diperoleh dengan rumus
Q = A V(3.2)Keterangan :A = Luas Penampang Basah
V = Kecepatan Aliran Air
Untuk efisiensi saluran irigasi dihitung dengan rumus berikut :EI = ep es et(3.3)Keterangan:EI = Efisiensi Irigasi
ep = Efisiensi saluran primer
es = Efisiensi saluran skunder
et = Efisiensi saluran tersierb. Evapotranspirasi
Ada empat variabel iklim yang digunakan dalam alokasi dan distribusi air ini yaitu suhu, kelembaban, lama penyinaran, dan kecepatan angin. Data iklim tersebut digunakan untuk menghitung nilai evapotranspirasi potensial menggunakan metode Penman Modifikasi. Untuk menghitung evapotranspirasi potensial dapat digunakan persamaan 2.2.c. Analisa Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Air
Data curah hujan harian, debit harian, evapotranpirasi harian, luas daerah irigasi, serta data efisiensi saluran akan di input kedalam perhitungan neraca ketersediaan - kebutuhan air lahan sawah untuk menganalisa neraca ketersediaan - kebutuhan airnya. Perhitungan analisis neraca ketersediaan - kebutuhan air lahan sawah menggunakan perhitungan analisis neraca ketersediaan- kebutuhan air lahan sawah menurut Kartiwa, (2010). Perhitungan disusun dalam Microsoft Excel dengan data input yang diperlukan dalam perhitungan analisis neraca ketersediaan kebutuhan air lahan sawah tersebut adalah data curah hujan harian, data debit air sungai atau debit bendung irigasi harian, data evapotranspirasi harian, efisiensi saluran, dan luas lahan sawah.3.4.3 Analisis Potensi Indek Pertanaman
Dari perhitungan neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah akan diperoleh jumlah defisit dan surplus air. Potensi indek pertanaman dan pola tanam ditentukan berdasarkan jumlah defisit neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah, yaitu jumlah hari yang mengalami kekurangan air dalam satu tahun, yang telah di bagi menjadi sepuluh harian sehingga terdapat 36 DAS harian dalam setahun. Kreteria status ketersedian air berdasarkan defisit neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Kriteria status ketersediaan air berdasarkan defisit neraca ketersediaan kebutuhan air lahan sawahGolonganIP actualDefisit neraca ketersediaan - kebutuhan air lahan sawah
110013-24
22004-12
33000-3
Sumber : Kartiwa, Buletin Hasil Penelitian Agroklimat dan Hidrologi (2010)3.4.4 Analisis Perubahan Indek Pertanaman Akibat Perubahan Iklim
Setelah indek pertanaman dan pola tanam setiap tahun didapatkan yaitu dari tahun 2002 sampai 2012 maka akan dilihat apakah terjadi perubahan indek pertanaman dan pola tanam atau tidak selama sepuluh tahun tersebut, hasil ini akan dikaitkan dengan perubahan iklim dan kondisi existing (aktual) di lapangan.3.5 OutputOutput dari penelitian ini adalah mendapatkan neraca ketersediaan dan kebutuhan air lahan sawah daerah irigasi Koto Tuo, kemudian akan di dapatkan perubahan indek pertanaman dan pola tanam akibat Perubahan Iklim yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2012. Diagram alir analisis potensi indek tanam dapat dilihat pada Gambar 3.1
tidak
iya
Gambar 3.1. Diagram Alir Analisa Potensi Indek Tanam dan Pola TanamDAFTAR PUSTAKABalitklimat dan PJT II. 2004. Penyusunan Decision Support System Untuk Produksi Air Berkelanjutan di SWS Citarum . Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi dan Perum Jasa Tirta II.Balitklimat. 2012. Buletin Hasil Penelitian Agroklimat dan Hidrologi. Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.
Indra Kusuma Sari, dkk. Analisa KetersediaanKebutuhan Air Pada DAS Sampean.Allen. G Richard. Luis s. Pereira. Dirk Raes and Martin Smith. 1998. Crop Evapotranpiration Guidelines For computing crop water requitments. Irigation and Drainage paper 56. FAO. Rome. 301 p.Doorenbos. J. And A. H. Kassam. 1979. Yield Respon To Waater. FAO Irigation and Drainage Paper no. 33. 193p.
Hermayani Barus. 2001. Potensi Peningkatan Indeks Pertanaman Berdasarkan Pola Ketersediaan Air Irigasi Di Sumatra Bagia Utara.
Wirawan. 1991. Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi. Dalam Irigasi di Indonesia. LP3ES. Jakarta.Ekaputra, Eri Gas. 2013. Peningkatan Peranan Irigasi Dalam Upaya Adaptasi Perubahan Iklim Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Di Sumatera Barat. KNI-ICID Komda Sumatera Barat.LAPAN (2002): Laporan Perubahan Iklim, LAPAN BandungIPCC,2001 : Emission Scenarios: Special Report On Emission Scenarios. Cambridge University Press.
Boer, R., A. Bouno, Sumaryanto, E. Surmaini, A. Rakhman, W. Estiningtyas, K.Kartikasari, and Fitriyani. 20009. Agriculture Sector. Technical Report on Vulnerability and Adaptation Assessment to Climate Change for Indonesia Second National Communication. LAMPIRANLampiran 1. Skema Jaringan Irigasi Koto Tuo Kanan
BKT : Bangunan Koto Tuo
PROPINSISUMATERA BARAT
KOTAPADANG
KECAMATANKOTO TANGAH
KELURAHANBatipuh Panjang, Koto Pulai, Balai Gadang dan Batang Kabung Ganting
LUAS BAKU10.000 HA
LUAS AREAL SAWAH709,30 HA
BPB : Bangunan Parak Buruk
BTA : Bangunan Tanjung Aur
BBS : Bangunan Basuang
BP : Bangunan Pulai
Mulai
Identifikasi dan kondisi existing
pola tanam dan indek pertanaman existing
Input data, curah hujan, debit irigasi dan evapotranspirasi 10 harian dalam 10 tahun
Hitung Kebutuhan air tanaman per 10 harian dalam 10 tahun
Skenario pola tanam dan indek pertanaman
Neraca Air
Pola tanam dan IP
Pola tanam dan IP yang disarankan
Selesai