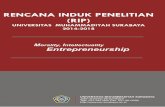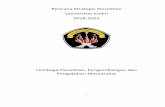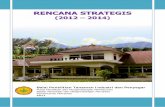RENCANA PENELITIAN
description
Transcript of RENCANA PENELITIAN

1
BAB IPENDAHULUAN
Demam tipoid pada masyarakat dengan standar hidup dan
kebersihan rendah, cenderung meningkat dan terjadi secara endemis.
Biasanya angka kejadian tinggi pada daerah tropik dibandingkan daerah
berhawa dingin. Sumber penularan penyakit demam tipoid adalah penderita
yang aktif, penderita dalam fase konvalesen, dan kronik karier. Demam tipoid
juga dikenali dengan nama lain yaitu Typhus Abdominalis,Tipoid fever atau
Enteric fever (Anonim, 2008)
Gejala demam tipoid sangat bervariasi, dari yang ringan, sehingga
tidak terdiagnosa, sampai gambaran penyakit yang khas dengan komplikasi,
bahkan menyebabkan kematian. Tapi pada umumnya keluhan dan gejala
penyakit ini adalah demam, biasanya lebih dari 1 minggu dan dapat
mencapai 39–40◦C, di malam hari, demam lebih tinggi dibanding malam hari.
Kemudian pada pemeriksaan laboratorium mungkin terjadi penurunan
leukosit (sel darah putih), dan kemudian pada tes Widal, akan terjadi
peningkatan titer antibodi terhadap kuman Salmonella thyposa. Biasanya
leukosit yang normal itu antara 5000 – 10,000/ul. Sedangkan titer antibodi,
dikatakan positif jika antibodi tipe O, mencapai 1/320.
Dalam menentukan penyakit atau diagnosis, membantu diagnosis,
mengendalikan penyakit dan memonitor pengobatan atau memantau
1

2
jalannya penyakit, maka dokter memerlukan suatu pemeriksaan laboratorium
sebagai penunjangnya yang sampelnya diambil dari penderita atau pasien
dan diperiksa dilaboratorium (Hardjoeno, 2003).
Fungsi utama sel lekosit adalah sebagai sistem imun tubuh terhadap
eksogen atau endogen yang dikenali oleh tubuh sebagai antigen. Fungsi
utama granulosit netrofil segmen sebagai sel fagosit terhadap bakteri dalam
jaringan radang sistem vaskuler. Eosinofil untuk pertahanan terhadap parasit
atau cacing yang dapat menimbulkan efek sitotoksik langsung, dan sebagai
regulasi dalam pengendalian reaksi anafilaksis pengendali kerja basofil.
Basofil dan sel mast berhubungan erat dengan pelepasan senyawa pengatur
sirkulasi (histamin, serotinin dan heparin) meningkatkan permiabilitas
vaskuler pada tempat aktivitas antigen lokal, sehingga mengatur aliran masuk
sel-sel radang (Baratawidjaja K, 2004., Kresno BS,2001).
Pada berbagai keadaan klinik, dapat terjadi kelainan jumlah pada
masing-masing jumlah dan jenis lekosit, baik berupa peninggian atau
penurunan dari nilai normal lekosit. Peninggian jumlah jenis lekosit dapat
disertai atau tanpa peninggian jumlah lekosit keseluruhan. Peninggian relatif
lekosit adalah apabila peninggian jumlah suatu jenis lekosit secara
keseluruhan, sedang absolut diikuti peninggian total lekosit (Anonim, 2005).
Rujukan untuk jumlah total lekosit adalah 4.500 sampai 10.500/mm3.
Nilai normal jenis lekosit, eosinofil 1% sampai 3%, basofil 0 samapi 1%,

3
netrofil batang 2% sampai 6%, netrofil segmen 50% sampai 70%, dan limfosit
20% sampai 40%, serta monosit 2% sampai 8%. (Hamurwono, 2003).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang timbul
adalah bagaimana penurunan jumlah lekosit pada penderita demam Tipoid
pasca pemberian antibiotik yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kolaka. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui jumlah
lekosit pada penderita demam Tipoid pasca pemberian antibiotik.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perubahan jumlah lekosit pada pasien penderita demam tipoid pasca
pemberian antibiotik di rumah sakit umum Daerah Kabupaten Kolaka.

4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Demam Tipoid
1. Definisi
Demam tipoid dan demam paratipoid adalah penyakit infeksi
akut usus halus. Demam paratipoid biasanya lebih ringan dan
menunjukkan manifestasi klinis yang sama atau menyebabkan
enteritis akut.
2. Etiologi
Etiologi demam tipoid dan demam paratipoid adalah
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B,
dan Salmonella paratyphi C.
3. Epidemiologi
Demam tipoid dan demam paratipoid endemik di Indonesia.
Penyakit ini termasuk penyakit menular yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1962. tentang wabah. Kelompok
penyakit menular ini merupakan penyakit-penyakit yang mudah
menular dan dapat menyerang banyak orang, sehingga dapat
menimbulkan wabah.
Di Indonesia demam tipoid jarang dijumpai secara epidemik,
tetapi lebih sering bersifat sporadis, terpencar-pencar di suatu
4

5
daerah, dan jarang menimbulkan lebih dari satu kasus pada orang-
orang serumah. Penyebab demam tipoid adalah Salmonella typhi
dengan dua cara penularan, yaitu dari pasien dengan demam tipoid
dan yang carrier. Penderita demam tipoid mengekskresikan 109
sampai 1011 bakteri per gram tinja. Di daerah endemik transmisi
terjadi melalui air yang tercemar.
Makanan yang tercemaroleh carrier merupakan sumber
penularan yang paling sering di daerah nonendemik. Carrier adalah
orang yang sembuh dari demam tipoid dan masih terus
mengekskresikan Salmonella typhi dalam tinja dan air kemih selama
lebih dari satu tahun. Disfungsi kandung empedu merupakan
predisposisi untuk terjadinya carrier. Bakteri Salmonella typhi berada
di dalam batu empedu atau dalam dinding kantung empedu yang
mengandung jaringan ikat, akibat radang menahun.
4. Patogenesis dan Patofisiologi
Kuman Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh manusia
melalui mulut dengan makanan dan air yang tercemar. Sebagian
kuman dimusnahkan oleh asam lambung, sedangkan sebagian lagi
masuk ke usus halus dan mencapai jaringan limfoid plaque Peyeri di
ileum terminalis yang mengalami hipertrofi. Ditempat ini komplikasi
perdarahan dan perforasi intestinal dapat terjadi. Bakteri Salmonella
typhi kemudian menembus lamina propia, masuk aliran limfe, dan

6
mencapai kelenjar limfe mesenterial yang juga mengalami hipertrofi.
Setelah melewati kelenjar-kelenjar limfe ini, bakteri masuk ke aliran
darah melalui ductus thoracicus. Bakteri Salmonella typhi lain
mencapai hati melalui sirkulasi portal dari usus. Salmonella typhi
bersarang di plaque Peyeri., limpa, hati, dan bagian-bagian lain
sistem retikuloendotelial.
Semula disangka demam dan gejala toksemia pada
demamtipoid disebabkan oleh endotoksemia. Akan tetapi kemudian
berdasarkan penelitian eksperimental disimpulkan bahwa
endotoksemia bukan merupakan penyebab utama deman dan gejala-
gejala toksemia pada demam tipoid. Endotoksin Salmonella typhi
berperan pada patogenesis demam tipoid karena membantu
terjadinya proses inflamasi lokal pada jaringan tempat bakteri ini
berkembang biak. Demam tipoid disebabkan karena Salmonella typhi
dan endotoksinnya merangsang sintesis dan pelepasan zat pirogen
oleh leukosit pada jaringan yang meradang.
5. Manifestasi Klinis
Masa inkubasi demam tipoid berlangsung antara 10 sampai 14
hari. Gejala-gejala yang timbul amat bervariasi. Perbedaan ini tidak
saja antara berbagai belahan dunia, tetapi juga di daerah yang sama
dari waktu ke waktu. Selain itu, gambaran penyakit bervariasi dari
penyakit ringan yang tidak terdiagnosis, sampai gambaran penyakit

7
yang khas dengan komplikasi dan kematian. Hal ini menyebabkan
bahwa seorang ahli yang sudah sangat berpengalaman pun dapat
mengalami kesulitan untuk membuat diagnosis klinis demam tipoid.
Pada minggu pertama, keluhan dan gejala serupa dengan
gejala infeksi akut pada umumnya, yaitu demam, nyari kepala,
pusing, nyeri otot, anorteksia, mual, muntah, obstipasi atau diare,
perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Pada
pemeriksaan fisis hanya didapatkan suhu badan meningkat. Pada
minggu kedua, gejala-gejala menjadi lebih jelas berupa demam
bradikardia relatif, lidah yang khas (kotor di tengah, tepi dan ujung
merah dan tremor), hepatomegali, splenomegali, meteroismus,
gangguan mental berupa somnolen, stupor, koma, delirium, atau
psikosis.
6. Biakan Darah
Biakan darah positif memastikan demam tipoid, tetapi biakan
darah negatif tidak menyingkirkan demam tipoid. Hal ini disebabkan
karena hasil biakan darah tergantung pada beberapa faktor, antara
lain:
a. Teknik pemeriksaan laboratorium
Hasil pemeriksaan satu laboratorium berbeda dengan
yang lain, terkadang hasil satu laboratorium bisa berbeda dari
waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh perbedaan teknik dan

8
media biakan yang digunakan. Karena jumlah bakteri yang berada
dalam darah hanya sedikit, yaitu kurang dari 10 kuman/mL darah,
maka untuk keperluan pembiakan, pada pasien dewasa diambil 5-
10 mL darah dan pada anak-anak 2-5 mL. Bila darah yang
dibiakan terlalu sedikit, hasil biakan bisa negatif, terutama pada
orang yang sudah mendapat pengobatan spesifik. Selain itu, darah
tersebut harus langsung ditanam pada media biakan sewaktu
berada di sisi pasien dan langsung dikirim ke laboratorium. Waktu
pengambilan darah paing baik adalah saat demam tinggi pada
waktu bakteriemia berlangsung.
b. Saat pemeriksaan selama perjalanan penyakit
Pada demam tipoid, biakan darah terhadap Salmonella
typhi positif pada minggu pertama penyakit dan berkurang pada
minggu-minggu berikutnya. Pada waktu kambuh biakan bisa
positif.
c. Vaksinasi di masa lampau
Vaksinasi terhadap demam tipoid di masa lampau
menimbulkan antibodi dalam darah pasien. Antibodi ini dapat
menekan bakteriemia, sehingga biakan darah kemungkinan
negatif.

9
d. Pengobatan dengan antimikroba
Bila pasien sebelum pembiakan darah sudah mendapat
obat antimikroba, pertumbuhan kuman dalam media biakan
terhambat dan hasil biakan mungkin akan negatif.
7. Penyebab
Demam tipoid timbul akibat dari infeksi oleh bakteri golongan
Salmonella yang memasuki tubuh penderita melalui saluran
pencernaan. Sumber utama yang terinfeksi adalah manusia yang
selalu mengeluarkan mikroorganisme penyebab penyakit,baik ketika
ia sedang sakit atau sedang dalam masa penyembuhan. Pada masa
penyembuhan, penderita pada masih mengandung Salmonella sp
didalam kandung empedu atau di dalam ginjal.
Sebanyak 5% penderita demam tipoid kelak akan menjadi
karier sementara, sedang 2 % yang lain akan menjadi karier yang
menahun.Sebagian besar dari karier tersebut merupakan karier
intestinal (intestinal type) sedang yang lain termasuk urinary type.
Kekambuhan yang yang ringan pada karier demam tipoid,terutama
pada karier jenis intestinal,sukar diketahui karena gejala dan
keluhannya tidak jelas.

10
B. Tinjauan Umum Salmonella
1. Pengertian
Salmonella adalah kuman pathogen bagi manusia yang masuk
melalui mulut bersama makanan atau minuman yang telah
terkontaminasi. Sebagai port d’ entry adalah kelenjar getah dari usus
halus terjadi ulcus sehingga dapat terjadi perforasi dan pendarahan
usus (Noegroho, 1989).
Salmonella juga merupakan penyebab demam typhoid,
bakteremia dan entrekolitis karena keracunan makanan. (Chatim
Aidilfiet, 1991).
2. Klasifikasi
Salmonella diklasifikasi dalam 3 spesies yang merupakan genus
dan enterobaktericeae yaitu Salmonella choleraesuis, Salmonella
typhi, Salmonella entretidis. (Haidil, 2006).
3. Morfologi dan Sifat-sifat Salmonella
Kuman berbentuk batang pendek dengan diameter 0,5-0,8
mikron dan panjang 1-3 mikron. Tidak berspora pada pewarnaan
gram bersifat negatif gram. Bergerak karena memiliki flagella peritrika
tidak berselubung (Noegroho, 1989).
Kuman tumbuh pada suasana aerob dan fakultatif anaerob
pada suhu 370C dan tumbuh pada media dengan pH 6-8. Memiliki
sifat-sifat : gerak positif, reaksi fermentasi terhadap manitol dan

11
sorbitol positif. Semua spesies Salmonella tidak merugikan laktosa
dan sukrosa. Pada media cair membentuk kekeruhan yang merata
(Noegroho, 1989).
4. Struktur Antigen
a. Antigen O
Disebut juga Ag Somatik, berasal dari bagian dinding sel
terdiri dari lipopolisakarida, bersifat termostabil (1000C), tahan
asam alkhohol. Bersifat endotoksin dan mempunyai efek
menimbulkan panas, toksis, dan antibody spesifik IgM.
b. Antigen H
Disebut juga Ag flagel, bersifat termolabil (> 600C), tidak
tahan asam, alcohol dan fenol, antibody yang dibentuk bersifat
endotoksin dan mempunyai efek menimbulkan panas, toksis dan
antibody spesifik IgM.
c. Antigen Vi
Disebut juga Ag kapsul, berasal dari lapisan pembungkus
kuman, protektif melindungi kuman terhadap fagositosis dan efek
zat anti dari komplemen. Bersifat termolabil (600C, 1 jam), tidak
tahan asam dan fenol serta cenderung lebih virulen (Mursalim A,
2002).

12
5. Resistensi
Kuman mati pada pemanasan 60 0C selama 20 menit, juga
dengan desinfektan. Dalam air bisa bertahan selama 4 minggu. Hidup
subur pada medium yang mengandung garam empedu, tahan
terhadap zat warna hijau brilian dan senyawa Natrium tetrationat serta
Natrium deoksikholat (Noegroho, 1989).
6. Patogenesis
Keganasan bakteri typus didasarkan atas kemampuan kuman
untuk bertahan hidup dan berkembangbiak terus menerus secara
intraseluler, adanya endotoksin, ditemukannya mikrokapsul pada
badan bakteri terhadap lisis dari gen yang dimiliki (MursalimA, 2002).
Kuman Salmonellosis yang disebabkan yaitu demam enteric,
bakteremia, dan enterokolitis(Chatim, 1991).
a. Demam Enterik (Demam typhoid)
Adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh kuman
S. typhoid, serta S. eteridis bioserotip paratyphi A dan Salmonella.
Seseorang bisa menjadi sakit bila menelan organisme ini
sebanyak 107 kuman, dosis dibawah 105 tidak menimbulkan
penyakit. Organism yang tertelan masuk kedalam lambung untuk
mencapai usus halus bagian proksimal, melakukan penetrasi
kedalam lapisan epitel mukosa, bila S, typhi sampai dikelenjar

13
getah bening regional akan terjadi bakteremia kemudian kuman
sampai di hati, limfa, juga sumsum tulang dan ginjal.
Setelah periode multiplikasi intraseluler, organisasi
dilepaskan lagi kealiran darah, dan dapat menimbulkan reaksi
radang atau nekrosis jaringan yang secara klinis ditandai dengan
kholestitis nekrotikan dan pendarahan usus.
Masa inkubasi demam typhoid umumnya 1-2 minggu, gejala
klasik penyakit ini adalah demam tinggi, anoreksia, nyeri otot,
sakit kepala, pembesaran hati dan limpa, serta bintik rose pada
sekitar umbilicus.
b. Bakteremia
Dapat ditemukan pada demam typhoid dan infeksi
Salmonella non – typhi lainnya. Gejala yang menonjol adalah
panas dan bakteremia intermiten. Adanya Salmonella sp didalam
darah merupakan resiko tinggi terjadinya infeksi atau abses
metastatic. Penyebab tersering adalah S. typhimurium, selain S.
enteridis dan S. Cholevaesuis.
c. Enterokolitis
Penyebab Enterokolitis yang paling sering adalah S. enteridis
dan S. typhimurium. Kuman penyebab dapat diisolasi dari tinja
penderita dalam beberapa minggu. Masa inkubasi berkisar antara
12-48 jam atau lebih. Gejala yang timbul pertama kali adalah mual

14
dan muntah diikuti nyeri abdomen, pada kasus yang berat terjadi
diare yang bercampur darah. Penderita seringkali sembuh dengan
sendirinya tetapi kadang-kadang menjadi berat bila terjadi
gangguan keseimbangan elektrolit dan dehidrasi (Mursalim A,
2002).
7. Epidemiologi
Demam typhoid terjadi disemua bagian dunia tapi jarang
terjangkit di tempat-tempat yang sanitasinya baik, yaitu bila
pembuangan sampah biologisnya dan pemurnian air dilakukan
dengan baik. Namun sumber utama infeksi oleh Salmonella typhi ialah
penderita penyakit atau pembawa organism tersebut (penular) karena
demam typhoid secara khusus merupakan penyakit manusia. Air atau
makanan yang tercemari tinja manusia baik secara langsung maupun
tidak langsung merupakan sumber infeksi. Salmonella dapat bertahan
selama berminggu-minggu didalam air, debu, es dan bahkan limbah
yang sudah dikeringkan dan bila organism masuk kedalam lingkungan
yang cocok akan berkembangbiak mencapai dosis infektif (Pelczar
dkk, 1988).
8. Identifikasi Salmonella
Diagnosis yang pasti bagi penyakit ini bergantung pada
terisolasinya bakteri dari tinja. Penggunaan media yang selektif atau
differensial merupakan prosedur rutin. Identifikasi mikrobanya

15
kemudian dilakukan dengan metode-metode biokimia dan serology
(Pelczar dkk, 1988).
a. Media Pemupuk
Sampel ditanam pada media selenite broth dan tetrathionate
broth, dimana keduanya menghambat pertumbuhan bakteri
saluran usus normal tetapi mempercepat pertumbuhan
Salmonella. Sesudah inkubasi 18-24 jam, bakteri ditanam pada
media differensial dan madia selektif.
b. Media differensial
Media differensial adalah media yang dipakai untuk
indentifikasi bakteri menurut sifat-sifat biokimia bakteri yang
bersangkutan. Media yang dipakai dalam pembenihan bakteri
adalah Mac Concey, media ini mengandung laktosa dan merah
netral sebagai indikator, sehingga bakteri yang meragikan laktosa
tumbuh dengan koloni berwarna merah dan dapat dibedakan
dengan bakteri yang tidak meragikan laktosa karena tumbuh
sebagai koloni yang tidak berwarna. Salmonella akan tumbuh
dengan koloni yang tidak berwarna, cembung, tepi rata,
permukaan rata dengan diameter < 2 mm, waktu inkubasi 18-24
jam.

16
c. Media Selektif
Media selektif adalah media yang ditumbuhi bakteri tertentu
karena mengandung penghambat pertumbuhan lain. Media
selektif untuk isolasi salmonella adalah Shigella Agar, yang
hanya menumbuhkan Salmonella dan Shigella. Media ini
mengandung garam empedu dan Brilliant green sebagai bahan
penghambat bakteri gram positif dan menekan pertumbuhan basil
patogen non enteric. Koloni spesies menghasilkan warna hitam
dibagian tengahnya, bentuk koloni cembung, tepi rata dengan
diameter < 2 mm, waktu inkubasi 18-24 jam.
d. Identifikasi Akhir
Koloni yang diduga dari perbenihan padat diidentifikasi
dengan tes biokimia. Diantara tes biokimia yaitu :
1) Peragian karbonat (Glukosa, Lactose, Sucrose, Maltose)
Sejumlah kuman dapat meragikan gula-gula
(karbohidrat) dengan atau tanpa pembentukan gas, dan ada
yang tidak meragikan glukosa sama sekali. Hasil peragian ini
sebagian besar berupa asam organik yang dapat ditunjukkan
dengan indikator pH, seperti ungu brom kresol (Chatim
Aidilfet, 1991).

17
2) Tes KIA (Kliger’s Iron Agar)
Digunakan untuk mengetahui pertumbuhan jenis
kuman tertentu, dengan melihat kemampuan bakteri
memfermentasi glucose, lactose serta terbentuknya gas H2S.
Salmonella pada medium ini akan membentuk reaksi alkali
(merah) pada permukaan agar, reaksi asam (kuning) pada
dasar dan mungkin terbentuk gas pada bagian bawah tabung,
serta mungkin tebentuk H2S yang ditandai timbulnya warna
hitam. Reaksi alkali pada permukaan menunjukkan bahwa
lactose tidak difermentasi dan Salmonella, reaksi asam pada
dasar tabung menunjukkan terjadinya fermentasi glucose
(Supardi dkk, 1999; Gani A, 2003).
3) Triple Sugar Iron Agar (TSIA)
Media ini mengandung 3 jenis karbohidrat yaitu :
Glukosa, Laktosa dan Sukrosa dan ferrisulfat untuk
mendeteksi H2S, protein dan indikator fenol red. Salmonella
bersifat alkali acid, alkali terbentuk karena adanya proses
oksidasi dekarboksilasi protein membentuk amina yang
bersifat alkali, dengan adanya fenol red. Maka terbentuk
warna merah. Adanya warna kuning disebabkan karena
Salmonella memfermentasi glukosa yang bersifat asam
(Jawet, 2001).

18
4) Sulfur Indol Motility (SIM)
Media ini merupakan perbenihan semisolid yang
digunakan untuk mengetahui Motility (gerakan), Indol dengan
penambahan reagens kovac dan pembentukan H2S.
Salmonella tidak membentuk Indol dan Motility positif. Semua
jenis Salmonella menghasilkan H2S kecuali Salmonella
paratyphi A, dan menghasilkan gas, kecuali Salmonella typhi.
5) Citrat
Pada media ini bakteri akan menghasilkan natrium
karbonat yang bersifat alkali yang berwarna biru dengan
adanya indikator Brom thymol blue. Media ini digunakan
sebagai sumber karbon bagi bakteri. Namun, Salmonella tidak
memanfaatkan citrate sehingga pada penanaman media ini
hasilnya negative.
6) Urea
Pada media ini bakteri yang dapat menghidrolisis urea
dan menghasilkan amoniak ditandai dengan terbentuknya
warna merah karena adanya indikator Fenol red. Salmonella
pada media ini memberikan hasil negatif.
7) Methyl Red
Media ini digunakan untuk mengetahui bakteri yang
mampu memproduksi asam kuat sebagai hasil fermentasi

19
glukosa dalam media ini, yang dapat ditunjukkan dengan
penambahan larutan methyl red. Salmonella pada
penambahan methyil red membentuk warna merah.
8) Vogas Proskauer
Bakteri tertentu dapat menghasilkan acetyl methyl
carbinol dari fermentasi glukosa yang dapat diketahui dengan
penambahan larutan Voges Proskauer dan Kalium Hidroksida
(KOH) 40%. Pada media ini Salmonella memberikan hasil
negatif.
9. Pencegahan
Pada taraf masyarakat luas, pencegahan terbaik terhadap
demam typhoid ialah sanitasi yang baik. Mencegah kontaminasi
makanan dan minuman dari kuman Salmonella. Penularan harus
dikenali dan dicegah agar tidak mencemari pengolahan dan
penanganan pangan. Bagi perorangan, vaksin typhoid efektif untuk
menurunkan kemungkinan timbulnya penyakit. (Pelczar dkk, 1988).
C. Pengobatan demam tipoid
Obat-obat antimikroba yang sering dipergunakan dalam
pengobatan demam tipoid adalah:
1. Kloramfenikol
Di Indonesia, kloramfenikol masih merupakan obat pilihan
utama untuk demam tipoid. Belum ada obat antimikroba lain yang

20
dapat menurunkan demam lebih cepat dibandingkan kloramfenikol.
Dosis untuk orang dewasa 4 kali 500 mg sehari oral atau intravena
sampai 7 hari setelah bebas demam. Penyuntikan kloramfenikol
suksinat intramuskular tidak dianjurkan karena hidrolisis ester ini tidak
dapat diramalkan dan tempat suntikan terasa nyeri. Dengan
penggunaan kloramfenikol, demam pada demam tipoid turun rata-rata
setelah 5 hari.
2. Tiamfenikol
Dosis dan efektivitas tiamfenikol pada demam tipoid sama
dengan kloramfenikol. Komplikasi hematologis pada penggunaan
tiamfenikol lebih jarang daripada kloramfenikol. Dengan penggunaan
tiamfenikol , demam pada demam tipoid turun rata- rata setelah 5-6
hari.
3. Kotrimoksazol (Kombinasi Trimetoprim dan Sulfametoksazol)
Efektivitas kotrimoksazol kurang lebih sama dengan
kloramfenikol. Dosis untuk orang dewasa, 2 kali 2 tablet sehari,
digunakan sampai 7 hari setelah bebas demam (1 tablet mengandung
80 mg trimetoprim dan 400 mg sulfametoksazol). Dengan
kotrimoksazol, demam pada demam tipoid turun rata-rata setelah 5-6
hari.

21
4. Ampisilin dan Amoksisilin
Dalam hal kemampuannya untuk menurunkan demam,
efektivitas ampisilin dan amoksisislin lebih kecil dibandingkan dengan
kloramfenikol. Indikasi mutlak penggunaannya adalah pasien demam
tipoid dengan leukopenia. Dosis yang dianjurkan. Dosis yang
dianjurkan berlisar antara 75-150 mg/Kg berat badan sehari,
digunakan sampai 7 hari setelah bebas demam. Dengan ampisilin atau
amoksisilin demam pada demam tipoid turun rata-rata setelah 7-9 hari.
5. Sefalosporin Generasi Ketiga
Beberapa ui klinis menunjukkan bahwa sefalosporin generasi
ketiga antara lain sefoperazon, seftriakson, dan sefotaksim efektif
untuk demam tipoid, tetapi dosis dan lama pemberian yang optimal
belum diketahui dengan pasti.
6. Fluorokinolon
Fluorokinolon efektif untuk demam tipoid, tetapi dosis dan
lama pemberian yang optimal belum diketahui dengan pasti .
D. Tinjauan Umum Lekosit
Lekosit yang diproduksi dalam sumsum tulang akan masuk ke
pembuluh darah dan meninggalkan sirkulasi masuk kejaringan. Sel
lekosit adalah kelompok sel-sel berinti, terdiri atas granulosit, limfosit dan
monosit.

22
Terdapat tiga (3) jenis granulosit yaitu: Netrofil, Eosinofil, dan
Basophil. Dalam keadaan normal, granulosit hanya berasal dari sumsum
tulang, sejumlah kecil limfosit dibentuk disumsum tulang, sebagian besar
berasal dari jaringan limfe dan thymus. Monosit dari retikuloendhotelial
system, khususnya di limfa. Jumlah normal lekosit yang beredar dalam
darah, jauh lebih sedikit dari eritrosit. Pada orang dewasa sehat, terdapat
4.000 – 10.000 lekosit per mm3 darah. Lekosit masa hidupnya lebih
pendek dibandingkan eritrosit, granulosit,hidup sekitar 3-5 hari
(Hamurwono GB, 2003).
Ada beberapa jenis sel darah putih (lekosit)
Tipe Gambar Diagram% dalam tubuh manusia
Keterangan
Neutrofil 65%
Neutrofil berhubungan dengan pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri serta proses peradangan kecil lainnya, serta biasanya juga yang memberikan tanggapan pertama terhadap infeksi bakteri; aktivitas dan matinya neutrofil dalam jumlah yang banyak menyebabkan adanya nanah.
Eosinofil 4%Eosinofil terutama berhubungan dengan infeksi parasit, dengan demikian meningkatnya eosinofil menandakan banyaknya parasit.

23
Basofil <1%
Basofil terutama bertanggung jawab untuk memberi reaksi alergi dan antigen dengan jalan mengeluarkan histamin kimia yang menyebabkan peradangan.
Limfosit 25%Limfosit lebih umum dalam sistem limfa. Darah mempunyai tiga jenis limfosit: Sel B, Sel T, Sel natural killer:
Monosit 6%
Monosit membagi fungsi "pembersih vakum" (fagositosis) dari neutrofil, tetapi lebih jauh dia hidup dengan tugas tambahan: memberikan potongan patogen kepada sel T sehingga patogen tersebut dapat dihafal dan dibunuh, atau dapat membuat tanggapan antibodi untuk menjaga.
Makrofag
(lihat di atas)
Monosit dikenal juga sebagai makrofag setelah dia meninggalkan aliran darah serta masuk ke dalam jaringan.
1. Fungsi Lekosit
Fungsi utama sel lekosit adalah sebagai sistem imun tubuh
terhadap eksogen atau endogen yang dikenali oleh tubuh sebagai
antigen. Fungsi utama garanulosit netrofil segmen sebagai sel
fagosit terhadap bakteri dalam jaringan radang sistem vaskuler.
Eosinofil untuk pertahanan terhadap parasit atau cacing yang dapat
menimbulkan efek sitotoksik langsung, dan sebagai regulasi dalam
pengendalian reaksi anafilaksis pengendali kerja basofil. Basofil dan

24
sel mast berhubungan erat dengan pelepasan senyawa pengatur
sirkulasi (histamin, serotinin dan heparin) meningkatkan permiabilitas
vaskuler pada tempat aktivitas antigen lokal, sehingga mengatur
aliran masuk sel-sel radang.
Fungsi utama sel agranulosit monosit melawan bakteri
fagositosis, dan pembersih sisa sel yang tua. Limfosit berperan
sebagai kunci terhadap aktifitas imunologik dengan sub-set dari
limfosit yaitu imfosit-T, limfosit-B (Baratawidjaja K, 2004., Kresno
BS,2001).
2. Kelainan Jumlah dan Jenis Lekosit
Pada berbagai keadaan klinik, dapat terjadi kelainan jumlah pada
masing-masing jumlah dan jenis lekosit, baik berupa peninggian atau
penurunan dari nilai normal lekosit. Peninggian jumlah jenis lekosit
dapat disertai atau tanpa peninggian jumlah lekosit keseluruhan.
Peninggian relatif lekosit adalah apabila peninggian jumlah suatu jenis
lekosit secara keseluruhan, sedang absolut diikuti peninggian total
lekosit (Anonim, 2005).
Rujukan untuk jumlah total lekosit adalah 4.500 sampai 10.500
mm3. Nilai normal jenis lekosit, eosinofil 1% sampai 3%, basofil 0
samapi 1%, netrofil batang / stab 2% sampai 6%, netrofil segmen 50%
sampai 70%, dan limfosit 20% sampai 40%, serta monosit 2% sampai
8%.

25
3. Hitung Jumlah Lekosit
Terdapat dua cara untuk menghitung leukosit dalam darah tepi
Yaitu :
a. Cara pertama adalah cara manual dengan memakai pipet leukosit,
kamar hitung dan mikroskop.
b. Cara kedua adalah cara semi automatik dengan memakai alat
elektronik. Cara kedua ini lebih unggul dari cara pertama karena
tekniknya lebih mudah, waktu yang diperlukan lebih singkat dan
kesalahannya lebih kecil yaitu ± 2%, sedang pada cara pertama
kesalahannya sampai ± 10%. Keburukan cara kedua adalah harga
alat mahal dan sulit untuk memperoleh reagen karena belum
banyak laboratorium di Indonesia yang memakai alat ini.
Jumlah leukosit dipengaruhi oleh umur, penyimpangan dari
keadaan basal dan lain-lain.
Pada bayi baru lahir jumlah leukosit tinggi, sekitar 10.000 -
30.000/µl. Jumlah leukosit tertinggi pada bayi umur 12 jam yaitu
antara 13.000 - 38.000 /µl. Setelah itu jumlah leukosit turun secara
bertahap dan pada umur 21 tahun jumlah leukosit berkisar antara
4500 - 11.000/µl. Pada keadaan basal jumlah leukosit pada orang
dewasa berkisar antara 5000 - 10.0004/µ1. Jumlah leukosit
meningkat setelah melakukan aktifitas fisik yang sedang, tetapi
jarang lebih dari 11.000/µl.

26
Bila jumlah leukosit lebih dari nilai rujukan, maka keadaan
tersebut disebut leukositosis. Leukositosis dapat terjadi secara
fisiologik maupun patologik. Leukositosis yang fisiologik dijumpai
pada kerja fisik yang berat, gangguan emosi, kejang, takhikardi
paroksismal, partus dan haid.
Leukositosis yang terjadi sebagai akibat peningkatan yang
seimbang dari masing-masing jenis sel, disebut balanced
leokocytosis. Keadaan ini jarang terjadi dan dapat dijumpai pada
hemokonsentrasi. Yang lebih sering dijumpai adalah leukositosis
yang disebabkan peningkatan dari salah satu jenis leukosit
sehingga timbul istilah neutrophilic leukocytosis atau netrofilia,
lymphocytic leukocytosis atau limfositosis, eosinofilia dan basofilia.
Leukositosis yang patologik selalu diikuti oleh peningkatan absolut
dari salah satu atau lebih jenis leukosit.
Leukopenia adalah keadaan dimana jumlah leukosit kurang dari
5000/0 darah. Karena pada hitung jenis leukosit, netrofil adalah sel
yang paling tinggi persentasinya hampir selalu leukopenia
disebabkan oleh netropenia.

27
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriftif analitik, yakni untuk
mengetahui seberapa besar jumlah lekosit pada penderita Demam tipoid
yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
B. Populasi, Sampel, dan Besar Sampel.
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah penderita demam tipoid
yang telah melakukan tes jumlah lekosit di laboratorium Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
2. Sampel
Data hasil hitung jumlah lekosit pasien penderita demam tipoid.
3. Besar Sampel
Dalam penelitian ini akan diambil 10 sampel data
laboratorium dari penderita demam tipoid yang telah melakukan
hitung jumlah lekosit.
C. Definisi Operasional
Hitung Jumlah Lekosit adalah cara menghitung jumlah lekosit yang
diencerkan dalam tabung reaksi dan dilanjutkan perhitungan jumlah
dalam kamar hitung.
27

28
Penderita demam tipoid adalah individu yang mengalami
karakteritik demam, sakit kepala dan ketidakenakan abdomen
berlangsung lebih kurang 3 minggu yang juga disertai gejala-gejala perut
pembesaran limpa dan erupsi kulit.
D. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Kolaka khususnya bagian laboratorium pada bulan Januari 2009.
E. Hasil Penelitian
Data diperoleh dari hasil pengamatan hasil perhitungan jumlah
lekosit penderita demam tipoid yang dirawat di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kolaka.
F. Analisa Data
Data hasil hitung jumlah lekosit sebelum dan sesudah
pengobatan yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, kemudian
dilakukan analisis data dengan uji t’ (uji dua pihak) untuk menentukan
perbedaan nilai lekosit pada penderita Demam Tipoid. Dengan kriteria
pemeriksaan atau penolakan itu adalah sebagai berikut :
X1 - X2
t’ =
√(S 21 / n1) + (S 2
2 / n2)Keterangan :

29
X1 = Rata-rata hasil nilai lekosit pada penderita Demam tipoid
sebelum pengobatan.
X2 = Rata-rata hasil nilai lekosit pada penderita Demam tipoid setelah
pengobatan.
S1 = Standar deviasi nilai lekosit pada penderita Demam tipoid
sebelum pengobatan.
S2 = Standar deviasi nilai lekosit pada penderita Demam tipoid
setelah pengobatan.
n1 = Jumlah sampel Demam tipoid sebelum pengobatan
n2 = Jumlah sampel demam tipoid setelah pengobatan.
.

30
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil penelitian
Tabel 1. Hasil pemeriksaan laboratorium hitung jumlah lekosit pada penderita demam tipoid sebelum dan sesudah pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
Kode sampel Diagnosa Jumlah lekosit sebelum pengobatan
Jumlah lekosit setelah
pengobatan1 + 3500/mm3 8500/mm3
2 + 3560/mm3 8560/mm3
3 + 3200/mm3 7500/mm3
4 + 3300/mm3 6500/mm3
5 + 3510/mm3 8230/mm3
6 + 3350/mm3 7550/mm3
7 + 3160/mm3 6500/mm3
8 + 3740/mm3 6400/mm3
9 + 3500/mm3 7450/mm3
10 + 3460/mm3 8100/mm3
11 + 3460/mm3 8210/mm3
12 + 3500/mm3 7500/mm3
13 + 3350/mm3 7650/mm3
14 + 3780/mm3 6750/mm3
15 + 3800/mm3 6800/mm3
16 + 3760/mm3 7600/mm3
17 + 3100/mm3 7500/mm3
18 + 3700/mm3 8500/mm3
19 + 3300/mm3 8800/mm3
20 + 3600/mm3 8900/mm3
∑ 69630 153500
X 3481,5 7675
Sumber : Data sekunder 2009
Keterangan : Nilai rujukan normal lekosit 4000 – 10500/mm3
(Sumber : Instalasi laboratorium)
B. Pembahasan

31
Demam tipoid timbul akibat dari infeksi oleh bakteri golongan
Salmonella yang memasuki tubuh penderita melalui saluran pencernaan.
Sumber utama yang terinfeksi adalah manusia yang selalu mengeluarkan
mikroorganisme penyebab penyakit,baik ketika ia sedang sakit atau
sedang dalam masa penyembuhan. Pada masa penyembuhan, penderita
pada masih mengandung Salmonella sp didalam kandung empedu atau
di dalam ginjal.
Gejala demam tipoid sangat bervariasi, dari yang ringan,
sehingga tidak terdiagnosa, sampai gambaran penyakit yang khas
dengan komplikasi, bahkan menyebabkan kematian. Tapi pada
umumnya keluhan dan gejala penyakit ini adalah demam, biasanya lebih
dari 1 minggu dan dapat mencapai 39–40◦C, di malam hari, demam
lebih tinggi dibanding malam hari. Kemudian pada pemeriksaan
laboratorium mungkin terjadi penurunan leukosit (sel darah putih), dan
kemudian pada tes Widal, akan terjadi peningkatan titer antibody
terhadap kuman salmonella thyposa. Biasanya leukosit yang normal itu
antara 5000 – 10,000/ul
Fungsi utama sel lekosit adalah sebagai sistem imun tubuh
terhadap eksogen atau endogen yang dikenali oleh tubuh sebagai
antigen. Pada berbagai keadaan klinik, dapat terjadi kelainan jumlah
pada masing-masing jumlah dan jenis lekosit, baik berupa peninggian
atau penurunan dari nilai normal lekosit. Peninggian jumlah jenis lekosit

32
dapat disertai atau tanpa peninggian jumlah lekosit keseluruhan.
Peninggian relatif lekosit adalah apabila peninggian jumlah suatu jenis
lekosit secara keseluruhan, sedang absolut diikuti peninggian total
lekosit (Anonim, 2005).
Rujukan untuk jumlah total lekosit adalah 4.500 sampai 10.500
mm3. Nilai normal jenis lekosit, eosinofil 1% sampai 3%, basofil 0
samapi 1%, netrofil batang / stab 2% sampai 6%, netrofil segmen 50%
sampai 70%, dan limfosit 20% sampai 40%, serta monosit 2% sampai
8%.
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap studi jumlah
lekosit pada penderita demam tipoid yang dirawat dan berobat di Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian yang dilakukan
terhadap 20 sampel yang terdiagnosa demam tipoid dan melakukan uji
laboratorium setelah melakukan pengobatan menunjukkan jumlah
lekosit mengalami peningkatan dan masih dalam batas normal dimana
jumlah hitung lekosit berkisar antara 4.000 sampai 10.000 / mm3.
Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa pada taraf
kemaknaan 0,05 dan daftar kepercayaan (DK) 18 (n1 + n2 - 2), (1-α/2)
pada jumlah lekosit di dapat thitung = 3,1078 > ttabel =2,23, artinya Ha
diterima. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan bermakna antara hasil
jumlah lekosit sebelum dan sesudah pengobatan pada penderita

33
Demam Tipoid yang berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Kolaka.
Sedangkan obat-obat yang sering diberikan kepada penderita
antara lain Chloramex, parasetamol Klorampenikol, Cefotaxine, inbost
force. Pemberian kloramfenikol dan tyampenicol masih merupakan obat
pilihan utama untuk demam tipoid. Belum ada obat antimikroba lain
yang dapat menurunkan demam lebih cepat dibandingkan
kloramfenikol. Dosis untuk orang dewasa 4 kali 500 mg sehari oral atau
intravena sampai 7 hari setelah bebas demam. Dengan penggunaan
kloramfenikol, demam pada demam tipoid turun rata-rata setelah 5 hari.

34
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 20 pasien
penderita demam tipoid yang mendapat pemeriksaan laboratorium di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.dapat disimpulkan
yaitu :
1. Hasil penelitian menunjukkan jumlah lekosit mengalami
peningkatan setelah menjalani pengobatan.
2. Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pada taraf
kemaknaan 0,05 dan daftar kepercayaan (DK) 18 (n1 + n2 - 2), (1-
α/2) pada jumlah lekosit di dapat thitung = 3,1078 > ttabel =2,23, artinya
Ha diterima. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan bermakna antara
hasil jumlah lekosit sebelum dan sesudah pengobatan pada
penderita Demam Tipoid yang berobat di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Obat-obat yang sering diberikan kepada penderita demam tipoid
antara lain Chloramex, parasetamol Klorampenikol, Cefotaxine,
inbost force.
34

35
B. Saran
Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti tentang pola
pennggunaan obat demam tipoid.

36
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2008, http://manglufti.wordpress.com/2008/03/05/demam-Tipoid/, diakses tanggal 1 Januari 2009
Anonim, 2008, http://www.jevuska.com/2008/05/10/demam-tipoid-typhoid-fever/. Diakses tanggal 1 Januari 2009
Anonim, 2008, http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid. Diakses tanggal 29 Desember 2008
Anonim, 1994, “Petunjuk Pemeriksaan Hematologi, Departemen Kesehatan RI Pusat Laboratorium Kesehatan
Gandasubrata R, 2004, Penuntun Laboratorium Klinik, Jakarta, Dian Rakyat.
Hardjoeno, 2000, Interpretasi Hasil Test Laboratorium Diagnostik, Edisi Khusus 2000, Makassar, UNHAS Press
Hardjoeno, 2003, Interpretasi Hasil Test Laboratorium Diagnostik, Edisi 3, Makassar, LPI UNHAS.
Hamurwono. GB.H, 2003, Pelbagai Komponen dan Fungsi Darah Dalam Buku Pedoman Pelayanan Transfusi Darah, Serologi Golongan Darah, Jakarta, WHO, JBIC, Dep.Kes.
Hoffbrand A.V. Pettit J.E, Moss.P.A.H, 2005, Kapita Selekta Hematologi, Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
Juliani. S, Aprianti. S, Arif Mansyur, 2003 Hematopoiesis, Dalam Makalah Kulia Bag. Patologi Klinik, FK- UNHAS/RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar
Sacher Ronal A, McPherson Richard A, 2004, Metode Hematologi, Dalam Tinjauan Klinik Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Edisi II.
Sylvia A. Price dan Lorraine M. Wilson. 1995, „Patofisiologi“, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta hal 753-763
Wirawan R, 1988, Pemeriksaan Laboratorium Hematologi Sederhana, Jakarta, FK UI – RSCM

37
Gambar 1. Skema Kerja Studi Jumlah Lekosit Terhadap Penderita Demam Tipoid Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka
Universitas Indonesia Timur( UIT )
Pemerintah Daerah Kota KolakaPropinsi Sulawesi Tenggara
Dinas Kesehatan Kota Kolaka
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka
Pengumpulan Data
Analisa Data
Pembahasan
Kesimpulan

38
Lampiran 1. Hasil pemeriksaan nilai jumlah lekosit pada penderita demam tipoid di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.
Kode sampel Diagnosa Jumlah lekosit sebelum pengobatan
Jumlah lekosit setelah
pengobatan1 + 3500/mm3 8500/mm3
2 + 3560/mm3 8560/mm3
3 + 3200/mm3 7500/mm3
4 + 3300/mm3 6500/mm3
5 + 3510/mm3 8230/mm3
6 + 3350/mm3 7550/mm3
7 + 3160/mm3 6500/mm3
8 + 3740/mm3 6400/mm3
9 + 3500/mm3 7450/mm3
10 + 3460/mm3 8100/mm3
11 + 3460/mm3 8210/mm3
12 + 3500/mm3 7500/mm3
13 + 3350/mm3 7650/mm3
14 + 3780/mm3 6750/mm3
15 + 3800/mm3 6800/mm3
16 + 3760/mm3 7600/mm3
17 + 3100/mm3 7500/mm3
18 + 3700/mm3 8500/mm3
19 + 3300/mm3 8800/mm3
20 + 3600/mm3 8900/mm3
∑ 69630 153500
X 3481,5 7675
Tabel 3. Pengolahan data hasil tes jumlah lekosit Pada Penderita Demam Tipoid sebelum dan sesudah pengobatan.
Jumlah lekosit sebelum (X – X1) (X – X1)2
Jumlah lekosit setelah (X –X2) (X – X1)2

39
NomorSampel
pengobatan pengobatan
123456789
1011121314151617181920
35003560320033003510335031603740350034603460350033503780380037603100370033003600
1,230,231,13-7,27-1,87-0,173,135,031,83-3,270,250,65-0,02-1,030,150,150,060,390,15-0,77
1,51290,05291,2769
52,85293,49690,02899,7969
25,30093,3489
10,69290,06500,42906,25001,07120,02400,02404,22500,15600,02400,6006
85008560750065008230755065006400745081008210750076506750680076007500850088008900
-1,3-0,42,21,00,3-1,7-1,11,01,4-1,5-0,370,120,190,39-0,27-0,23-0,300,060,18-0,02
1,690,164,841,000,092,891,211,001,962,250,130,010,030,150,070,050,094,480,035,29
Jumlah 69630 - 170,964 153500 - 1083,615
x1 = 69630 x2 = 153500
(x – x1)2 = 170,964 (x – x2)2 = 1083,615
x1 x2
x1 = n n
69630 153500= =
20 20
= 3,481 = 7,675
(x – x1)2 (x – x2)2 S1 = S2 = n – 1 n - 1

40
170,964 1083,615S1 = S2 = 19 19
= 2,99 = 7,55
X1 - X2
t’ =
√(S 21 / n1) + (S 2
2 / n2) 7,675, – 3,841
t’ =
√(2,992 / 20) + (7,552 / 20)
3,834t’ =
√(0,44 ) + (2,85) 3,834
t’ =
√ 3,23
26,61t’ = 1,813835
= 14,6705
Tabel 4. Hasil analisis pemeriksaan jumlah lekosit pada penderita Demam Tipoid sebelum dan sesudah pengobatan.

41
Variabel n DK thitung ttabel
Hematokrit 20 18 3,1078 2,23
Tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa pada taraf kemaknaan
0,05 dan daftar kepercayaan (DK) 18 (n1 + n2 - 2), (1-α/2) pada jumlah
lekosit di dapat thitung = 3,1078 > ttabel =2,23, artinya Ha diterima. Hal ini
berarti bahwa ada perbedaan bermakna antara hasil jumlah lekosit
sebelum dan sesudah pengobatan pada penderita Demam Tipoid yang
berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka.