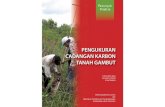Permukaan Tanah Gambut
Click here to load reader
Transcript of Permukaan Tanah Gambut

MAKALAH MATA KULIAH TANAMAN KARBOHIDRAT NON BIJI DAN PEMANIS (AGH 344)
PERMUKAAN TANAH GAMBUT
Disusun Oleh :
Galvan Yudistira (A24070040)
DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
201

Gambut
Kata gambut diambil dari nama suatu desa, yaitu desa Gambut (kini kecamatan Gambut), yang terletak sekitar 10 km di sebelah timur kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana untuk pertama kalinya padi telah berhasil dibudidayakan pada pesawahan tanah gambut (Subagjo, 2002 dalam Wahyunto, 2006). Tanah Gambut adalah tanah-tanah jenuh air, terbentuk dari endapan yang berasal dari penumpukan sisa-sisa jaringan tumbuhan masa lampau yang melapuk dengan ketebalan lebih dari 50 cm.
Tanah gambut kurang subur, sehingga hasil tanaman rendah. Di samping tanahnya asam, air tanahnya juga asam. Jika pirit dalam lapisan tanah mineral dibawah gambut terkena udara, aka air dapat dengan menjadi asam lagi.
Air bisa mengalir dengan mudah di dalam gambut, bahkan bisa bocor ke luar melalui tanggul sehingga petakan sawah cepat menjadi kering bila tidak terairi secara teratur. Sulit membuat lapisan olah untuk menahan air di dalam petak sawah.
Gambut yang selalu basah biasanya masih “mentah” sehingga zat-zat yang dibutuhkan tanaman tidak tersedia. Untuk itu gambut ini perlu dimatangkan agar lebih bermanfaat untuk tanaman (Adhi, W. et al, 1997)
Lahan gambut adalah lahan yang memiliki lapisan tanah kaya bahan organik (C-organik > 18%) dengan ketebalan 50 cm atau lebih. Bahan organik penyusun tanah gambut terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sempurna karena kondisi lingkungan jenuh air dan miskin hara. Oleh karena itu lahan gambut banyak dijumpai di daerah rawa belakang atau daerah sekungan yang drainasenya buruk (Agus, 2008).
Pakar pertanian di Indonesia menggunakan batasan minimal ketebalan 50 cm, dan kandungan bahan organik > 18% sebagai batas antara tanah gambut dan tanah mineral.
Beberapa ahli memperkirakan bahwa hutan gambut mulai berkembang pada saat kenaikan permukaan air laut eustatik, yang terjadi pada pasca zaman glacial telah stabil. Ketika itu sungai-sungai banyak mengendapkan lapisan berliat/berlumpur sehingga terbentuk tanggul-tanggul dan dataran banjir. Rawa-rawa kemudian berkembang di belakang tanggul. Semakin tinggi deposit bahan debu dan liat yang terjadi, semakin berkurang pula kadar garam pada rawa-rawa itu, sehingga vegetasi bakau yang ada tergantikan oleh tumbuhan daratan. Karena kondisi lingkungan yang

relatif masih payaum kandunga sulfida tinggi, dan selalu tergenang air, maka proses dekomposisi terhambat. Sebagai akibatnya, terjadi penumpukan serasah yang semakin tebal sehingga membentuk tanah gambut. Ambut yang terbentuk dengan proses ini disebut gambut ombrogen. Tanah gambut yang terbentuk tidak lagi dipengaruhi oleh air pasang surut dan tidak mendapat pasokan air sungai biasanya miskin unsur hara (oligotrofik) dan bersifat masam.
Gambut dapat pula terbentuk pad daerah cekungan yang drainasenya buruk atau jelek. Karena akumulasi gambut berjalan relatif lambat, maka lapisan yang terbentuk relatif tipis (kurang dari satu meter). Tipe ini disebut gambut topogen dan umumnya terbentuk di bagian pedalaman dataran pantai, namun dapat juga terbentuk di daerah yang terkena pengeruh pasang surut. Rawa gambut topogen biasanya masih mendapat pasokan air dari aliran permukaan, sehingga memiliki unsur hara yang relatif tinggi dibanding gambut ombrogen. (Wahyunto, 2006)
Lahan Rawa gambut di Indonesia cukup luas, sekitar 20,6 juta ha, atau sekitar 10,8 % dari luas daratan Indonesia. Lahan rawa tersebut sebagaian besar terdapat di empat pulau besar yaitu Sumatera 35 %, Kalimantan 32 %, Sulawesi 3% dan Papua 30% (Wibowo dan Suranto, 1998 dalam Asril, 2009).
Sifat dan karateristik fisik lahan gambut ditentukan oleh dekomposisi bahan itu sendiri. Kerapatan lindak atau bobot isi (bulk density : BD) gambut umumnya berkisar antara 0.05 sampai 0.4 gram/cm3 . Nilai kerapatan lindak ini sangat ditentukan oleh tingkat pelapukan/dekomposisi bahan organik, dan kandungan mineralnya (Kyuma, 1987 dalam Asril, 2009). Hasil kajian Kyuma (1987) dalam Asril (2009) tentang porositas gambut yag dihitung berdasarkan kerapatan induk damn bobot jenis adalah berkisar antara 75-95%. Dalam taksonomi Tanah (Soil Survei Staff, 1999 dalam Asril , 2009), tanah gambut atau Histosol diklasifikasikan kedalam 4 (empat) subordo berdasarkan tingkat dekomposisinya yaitu : Folits-bahan organik belum terdekomposisi di atas batu-batuan, Fibritis- bahan organik fibrik dengan BD < 0,1-0,2 gram/cm3 dan Saprists – Baan organik saprik dengan BD > 0,2 gram/cm3.
Lahan Gambut
Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang die tuk oleh adanya penimbunan/akumulasi bahan organik di lantai hutan yang berasal dari reruntuhan vegetasi di atasnya dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena

lambatnyalaju dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah/tergenang tersebut (Najiyati et al, 2005 dalam Asril, 2009).
Di Indonesia, lahan gambut terdapat di daerah pantai rendah Kalimantan, Sumatra dan Papua Barat. Sebagian besar berada pada daerah rendah dan tempat yang masih terpengaruhi dengn kondisinya, berada di daratan sampai jarak 100 km sepanjang aliran sungai dan daerah tergenang. Lahan gambut menutupi lebih dari 26 juta hektar (69 % dari seluruh lahan gambut tropis) pada ketinggian sekitar 50 mdpl (Rieley, 2007 dalam Asril, 2009).
Sebagai catatan, hingga kini luas lahan gambut di Indonesia belum dibakukan, kaena itu data luasan yang dapat digunakan masih dalam kisaran 13,5-26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Dari berbagai laporan, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia atau setengah dari luas lahan gambut tropis dunia berada di Indonesia (Najiyati et al, 2005 dalam Asril, 2009).


Daftar Pustaka
Adhi IPGW, NPS Ratmini IW Swastika. 1997. Pengelolaan Tanah dan Air di Lahan Pasang Surut. Proyek Penelitian Pengembangan Pertanian Rawa Terpadu - ISDP. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Agus, F dan IG Made Subiksa. 2008. Lahan Gambut: Potensi untuk Pertanian dan Aspek Lingkungan. Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian.Bogor.
Asril. 2009. Pendugaan Cadangan Karbon di Atas Permukaan Tanah Rawa Gambut di Stasiun Penelitian Suaq Balimbing Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara. Medan. 90 hal.
Wahyunto, Suprapto, Bambang H., dan Hasyim Bhekti. 2006. Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Cadangan Karbon Bawah Permukaan di Papua. Proyek Climate Change, Forest and Petlands in Indonesia. Wetland International - Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor.