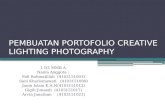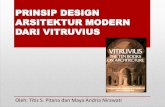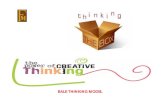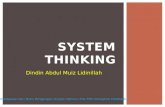Penerapan Design Thinking Dalam Arsitektur
-
Upload
azsep-kurniawan -
Category
Documents
-
view
62 -
download
0
Transcript of Penerapan Design Thinking Dalam Arsitektur

!"#$%&$'()(#*+$,)#!-".-()$/+!0")#!-*#$1)!#-"+$2"-)*$
3"4!+*)$5*#!6+*7$8$9"+(:($,)#!-".-()$;")<4=*-!$
3()*;*>*?$%@&$9"!$ABCA$
&BD$
Penerapan Design Thinking dalam Inovasi Pembelajaran Desain dan
Arsitektur
Filipus Priyo Suprobo 1
Abstrak
Design thinking sebagai pola pikir, metode, dan perangkat kerja telah memberi warna dalam
pembelajaran desain dan arsitektur dengan menerapkan 5 (lima) tahapannya yang terdiri atas discovery,
interpretation, ideation, experiment, dan evolution.
Hal ini juga telah memberikan tingkat keberhasilan tinggi melalui pengukuran self!efficacy atau dorongan
diri para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Dari sepuluh variabel, semuanya menunjukkan
skala antara 3 (hampir tinggi) sampai dengan 4 (sangat tinggi). Analisis menggunakan pendekatan non parametrik
dengan instrumen GSE Scale (General Self!Efficacy). Analisis menunjukkan bahwa data diambil dari populasi yang
acak (asymp. Sig > 0.05), sehingga hasil statistik deskriptifnya dianggap mewakili.
Kata Kunci: Design thinking, Pembelajaran arsitektur, Self!efficacy
Pendahuluan
Banyak pemikir metode desain selalu menyampaikan isu bahwa strategi novasi yang dilakukan
oleh suatu konsultan desain, akademisi, dan peneliti ilmiah adalah berbeda (Simons, Gupta, Buchanan,
2011). Di sisi lain Simons dan kawan!kawan setuju bahwa saat ini sedang berjalan fenomena menarik
yang memberi pengaruh dalam proses pekerjaan kreatif di berbagai bidang, termasuk di dunia
pendidikan atau pembelajaran, yakni design thinking.
Design thinking adalah pola pikir yang sekarang menjadi fenomena di banyak negara dan di
berbagai bidang. Pink (2005) mengungkapkan bahwa di era kreativitas, keterampilan yang berbeda
dari era sebelumnya diperlukan. Salah satu kemampuan penting adalah kemampuan desain. Avital dan
Boland (2008) menyebut kemampuan ini sebagai design attitude.
Apakah design thinking itu? Tim Brown (2008, 2009) merumuskan design thinking sebagai
sebuah metode untuk menciptakan nilai bagi calon pengguna dan peluang pasar secara keseluruhan,
1 Staf Pengajar dan Peneliti di Program Studi Arsitektur ! Universitas Widya Kartika Surabaya, email.

3(=)6;6?$EF$2F
&CB$
bukan hanya berdasarkan penampilan dan fungsi saja. Seluruh sistem didasarkan pada korespondensi
antara keinginan, kelayakan teknologi dan kelangsungan hidup strategi bisnis. Kegiatannya adalah untuk
menerjemahkan hasil observasi menjadi inspirasi yang mendorong ke dalam penciptaan produk, jasa,
proses dan bahkan strategi untuk kualitas hidup yang lebih baik.
Ada beberapa perluasan penerapannya di beberapa bidang seperti untuk desain organisasi,
perencanaan strategis wilayah/ sektor publik, praktek manajemen, penciptaan bisnis baru, inovasi
pendidikan dan bahkan sosial bagi pembangunan masyarakat (Brown, 2008; Wyatt, 2010).
Berdasarkan fenomena dan kebutuhan inovasi di berbagai bidang, maka penelitian ini berfokus
kepada pertanyaan tentang bagaimana jika design thinking ini diterapkan untuk pembenahan di bidang
inovasi pendidikan desain dan arsitektur. Dengan demikian, pendekatan design thinking ini diharapkan
dapat (1) memberikan warna alternatif dalam sistim pembelajaran desain dan arsitektur yang berbasis
solusi , (2) memberikan deskripsi bagaimana implementasi design thinking yang tepat dalam suatu
pembelajaran desain dan arsitektur, (3) memberikan deskripsi keberhasilan melalui pengukuran kinerja
diri siswa dalam pembelajaran desain dan arsitektur.
Telaah Pustaka
Design Thinking
Fenomena gerakan pemikiran kreatif melalui pemikiran desain sudah diprediksi oleh beberapa
ahli. Dr Edward de Bono, salah satu pakar terkemuka pada kreativitas dan cara berpikir, telah
menyarankan bahwa desain sebenarnya berakar pada kemampuan berpikir yang berbeda yang disebut
"design thinking". Cara berpikir tradisional kita terutama didasarkan pada pengenalan pola (misalnya
analisis, penilaian, dan logika). Sementara itu, berbeda dalam kemampuan berpikir desain yang
didasarkan pada pola baru penciptaan. Pola berpikir kreatif (creative thinking) sebagai komponen
penting design thinking sudah seharusnya dilihat untuk menjadi bagian penting pengajaran di semua
sektor seperti halnya critical thinking dan jangan dipandang sebagai pemberian mistik yang tidak dapat
diajarkan De Bono (2000).
Hal inilah yang membedakan bagaimana pola creative thinking atau design thinking selalu
mendasarkan pada persepsi, posibilitis, dan praktek, sementara di critical thinking selalu mendasarkan
pada analisis, fakta temuan, dan justifikasi. Critical thinking adalah cara kerja linier yang kita kenal
sekarang sebagai suatu metode ilmiah, sehingga tidak dipungkiri bahwa hasilnya cenderung bersifat
improvement (perbaikan), bukan inovasi.

3"4!+*)$5*#!6+*7$8$9"+(:($,)#!-".-()$;")<4=*-!$
&CC$
Penerapan Design Thinking dalam Pendidikan
Berdasarkan fenomena ini, ditemukan pentingnya pemikiran desain di segala bidang, termasuk
pendidikan. IDEO (2011), sebuah perusahaan desain dunia secara khusus juga telah
mengimplementasikannya, walaupun di tingkat pendidikan dasar. Dalam pendidikan teknik, cara
berpikir kritis telah lama dikenal tetapi dengan mempelajari pergerakan fenomena yang terjadi, ada
beberapa institusi pendidikan yang menjalankan pembelajaran berbasis pemikiran kreatif (Awang &
Ramly, 2008). Awang dan Ramly (2008) menemukan perbedaan yang signifikan antara metode
pembelajaran berbasis masalah dengan berpikir kreatif dan pendekatan konvensional di kelas
rekayasa.
Awang dan Ramly mengatakan bahwa dalam pendekatan berpikir kreatif melalui pembelajaran
berbasis masalah, siswa belajar untuk bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan kognitif untuk
memecahkan masalah dalam PBL masih cukup efektif diantara pendekatan lainnya (Abadi, Jahan, &
Shoorcheh, 2011). Karena sifat berpikir kreatif lebih fleksibel, kondisi ini tak lepas dari otonomi pelajar,
regulasi diri, dan metakognisi (Cubukcu, 2009). Disisi lain, Lawanto (2010) menemukan bahwa orientasi
tujuan yang tinggi pada siswa terkait dengan efikasi diri mereka atau kemampuan diri sendiri dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan. Ditemukan koefisien korelasi kuat antara intrinsik mahasiswa dan
efikasi dirinya daripada ekstrinsik dan efikasi dirinya. Pada studi Lawanto (2009) dalam hal perubahan
metakognisi ditemukan perbedaan signifikan dalam mahasiswa teknik yang melakukan metode
pendekatan yang berfokus pada solusi. Hal ini didukung oleh studi Case & Gunstone (2002) yang
menyatakan bahwa pendekatan belajar berbasis algorithmic (metode solusi) akan lebih menunjukkan
perubahan metakognisi siswa dibandingkan pendekatan berbasis konsep ataupun informasi.
Studi tentang Awang & Ramly (2008) dan Lawanto (2009, 2010) memberikan rekomendasi
bahwa siswa yang belajar berpikir kreatif atau dengan design thinking dalam memecahkan masalah
harus memiliki regulasi diri yang tinggi, sehingga dapat berdampak pada perubahan metakognisi tinggi.
Metode
a. Partisipan
Penelitian ini melibatkan 6 (enam) tim atau proyek yang terdiri atas 14 mahasiswa di program
studi desain dan arsitektur dari 2 (dua) institusi, yakni Institut Informatika Indonesia dan Universitas
Widya Kartika. Dalam tuntutan metode yang bersifat kolaboratif, maka para mahasiswa ini diminta
untuk bekerja sama secara tim dengan masing!masing tim diminta untuk menyelesaikan sebuah
tantangan desain.

3(=)6;6?$EF$2F
&CA$
b. Instrumen Penelitian
Dengan keterbatasan partisipan yang tidak bersesuaian dengan riset Lawanto (2010), maka
untuk instrumen dalam penelitian ini diserahkan kepada General Self!Efficacy (GSE) Scale oleh Aristi
Born, Ralf Schwarzer & Matthias Jerusalem (1995). Instrumen ini telah memiliki kehandalan yang tinggi
dalam mengukur motivasi diri atas suatu tugas, dari sejak diciptakan pada tahun 1979 hingga saat ini
dengan 10 item pernyataan dan berskala 4 (empat) poin.
c. Pengumpulan Data dan Analisis
Prosedur penelitian dimulai dengan penerapan tahap demi tahap design thinking sampai
dengan solusi proyek dihasilkan. Pengukuran kinerja motivasi diri (self!regulation) dilakukan setelah
para mahasiswa menyelesaikan proyek mereka. Untuk hasil pengukuran dilakukan analisis non
parametrik dengan menggunakan paket statistik SPSS yang digunakan dengan tujuan untuk (1)
memberikan hasil statistik deskriptif dalam menggambarkan hasil temuan empiris dan (2) memberikan
hasil statistik inferensial dalam membuktikan bahwa hasil perhitungan bersesuaian dengan populasinya.
Penerapan Design Thinking
IDEO (2011) mengembangkan tahapan design thinking dalam rumusan langkah Discovery,
Interpretation, Ideation, Experiment, dan Evolution. Dalam penelitian ini, 5 (lima) langkah inilah yang
akan dijalankan dan dapat dilaporkan secara sistematis di bawah ini.
Gambar 1. Tahap Discovery untuk
penetapan masalah.
Sumber: dokumentasi peneliti
Gambar 2. Tahap Discovery dalam
kegiatan observasi menggali inspirasi.
Sumber: dokumentasi peneliti

3"4!+*)$5*#!6+*7$8$9"+(:($,)#!-".-()$;")<4=*-!$
&CG$
a. Tahap Discovery
Dalam tahap ini, tim melakukan proses penetapan masalah, penetapan partisipan yang terlibat
untuk diwawancarai dalam penggalian inspirasi, perencanaan riset dari mulai pembagian kerja, daftar
pertanyaan, rencana tempat, peralatan serta alokasi waktu. Membenamkan diri di dalam konteks/
lingkungan permasalahan, baik saat wawancara maupun observasi selalu dilakukan dengan menanyakan
“bagaimana jika atau bagaimana seandainya?”. Jadi apa yang menjadi temuan adalah sebuah wawasan/
persepsi baru yang akan menjadi inspirasi. dan sebaiknya tercatat sebagai kata kunci yang ringkas dan
jelas, dimana satu kata kunci dicatat di satu post!it.
b. Tahap Interpretation
Inspirasi yang diperoleh selama wawancara dan observasi ini diceritakan di forum “story telling”
yang kemudian ditangkap oleh forum dalam persepsi masing!masing. Dengan demikian, persepsi itu
menjadi inspirasi yang semakin berbuah lebih banyak untuk setiap proyek.
Setelah semua inspirasi tersebut terkumpul, saatnya bagi tim untuk melakukan pengelompokan dan
kategorisasi berdasarkan kesamaan tema/ topik. Pengkajian yang lebih mendalam atas tema!tema yang
ada menjadikan hubungan antar tema menjadi lebih jelas dan menghasilkan suatu kerangka aksi dan
peluang.
Gambar 3. Tahap Interpretation yang
memunculkan Kerangka Aksi dan
Peluang berdasar hubungan antar
tema inspirasi
Sumber: dokumentasi peneliti
Gambar 4. Tahap Ideation dan
Eksperimen yang dilakukan dengan
memunculkan banyak possibilitas
tanpa justifikasi
Sumber: dokumentasi peneliti

3(=)6;6?$EF$2F
&C%$
c. Tahap Ideation dan Experiment
Dalam tahap menghasilkan ide berdasarkan rencana aksi dan peluang ini, tim akan berfokus
pada kuantitas ide dan berpotensi untuk selalu menambahkan ide yang dihasilkan sebelumnya.
Prosesnya juga dapat berbarengan sambil menghasilkan prototipe yang bisa diujicobakan. Pemanfaatan
material seadanya dan menangkap perwujudan ide melalui model skenario, video ataupun roll play
dapat mewakili prototipe juga.
d. Tahap Evolution
Dalam tahap ini, tim memperoleh respon dari para calon penggunanya atas uji coba prototipe
yang dilakukan. Umpan balik ini ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan desain. Tim
mendokumentasikan semua proses dan prototipe karyanya dalam berbagai paket multimedia untuk siap
diwujudkan atau dikembangkan bersama investor.
Analisis dan Pembahasan
Proses pengukuran tingkat keberhasilan penerapan design thinking atas 6 (enam) proyek atau
tim yang melibatkan 14 mahasiswa dilakukan di akhir proyek. Pengukuran mendasarkan pada General
Self!Efficacy (GSE) para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. GSE sendiri ditetapkan
ada 10 variabel dengan 4 (empat) skala poin. Tabel 1 menunjukkan hasil olahan paket statistik SPPS dari
hasil pengumpulan data GSE yang disajikan untuk kebutuhan deskriptif dan analisis inferensialnya.
Tabel 1. Hasil analisis deskriptif & inferensial General Self!Efficacy (GSE)
Variabel Self!Efficacy/ Self!Regulation Skala
rata2
Makna P!value
RUN Test
Pemecahan soal!soal yang sulit dalam proyek ini
selalu berhasil bagi saya, kalau saya berusaha. 4
Sangat
Tinggi 0,715
Jika seseorang menghambat tujuan saya, saya
telah dapat mencari cara dan jalan keluar 3
Hampir
Tinggi 1,000
Saya tidak mempunyai kesulitan untuk
melaksanakan niat dan tujuan saya dalam proyek 3
Hampir
Tinggi 0,239
Dalam situasi yang tidak terduga, saya tahu
bagaimana saya harus bertingkah laku/ bertindak. 3
Hampir
Tinggi 1,000
Kalau saya akan berkonfrontasi dengan sesuatu
yang baru, saya sudah tahu bagaimana saya dapat
menanggulanginya.
3 Hampir
Tinggi 0,965
Untuk setiap problem, saya pasti mempunyai
pemecahannya. 3.5
Mendekati
Sangat
Tinggi
0,164

3"4!+*)$5*#!6+*7$8$9"+(:($,)#!-".-()$;")<4=*-!$
&C&$
Variabel Self!Efficacy/ Self!Regulation Skala
rata2 Makna
P!value
RUN Test
Saya dapat menghadapi kesulitan dengan tenang,
karena saya mampu mengandalkan kemampuan
saya.
3.5
Mendekati
Sangat
Tinggi
0,781
Kalau saya menghadapi kesulitan, saya sudah
terbiasa mempunyai banyak ide untuk
mengatasinya.
3 Hampir
Tinggi 0,571
Juga dalam kejadian yang tidak terduga, saya
mampu menangani kejadian dengan baik. 3
Hampir
Tinggi 0,585
Apapun yang terjadi dalam proyek ini, saya sudah
siap menanganinya. 4
Sangat
Tinggi 0,350
Dalam hal analisis inferensial untuk mengetahui apakah hasil deskriptif skala rata!rata dan
makna tersebut dapat digunakan untuk mewakili populasi, digunakan uji runs yang menunjukkan hasil
bahwa hampir semua variabel memberikan nilai Asymp. Sig. adalah > 0.05 (nilai probabilitas error/p!
value) . Dengan demikian hipotesis awal untuk suatu uji runs, yang menunjukkan bahwa data yang
diperoleh bersifat random (acak), dapat diterima. Dengan demikian, hasil sajian deskriptif dari GSE ini
dapat digunakan untuk mewakili populasi.
Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa design thinking ternyata
memberikan tingkat motivasi atau dorongan diri yang besar bagi para mahasiswa partisipan dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan temuan ini berarti mendukung temuan hasil penelitian Awang
& Ramly (2008) dan Lawanto (2009, 2010), sehingga dapat dikembangkan bahwa design thinking ini juga
akan menghasilkan perubahan metakognisi yang tinggi.
Kesimpulan dan Diskusi
Design thinking sebagai pola pikir, metode, dan perangkat kerja telah memberi warna dalam
pembelajaran desain dan arsitektur dengan menerapkan 5 (lima) tahapannya yang terdiri atas discovery,
interpretation, ideation, experiment, dan evolution. Hal ini juga telah memberikan tingkat
keberhasilannya yang tinggi melalui pengukuran self!efficacy atau dorongan diri para mahasiswa dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan.
Menjadi diskusi yang menarik untuk mengembangkan riset ini lebih dalam, terutama dalam
kajiannya untuk mendukung perubahan metakognisi atau kemampuan berpikir para mahasiswa.
Sedangkan yang kedua dalam tataran konsep mengapa para mahasiswa memberikan apresiasi yang

3(=)6;6?$EF$2F
&CH$
tinggi pada design thinking dan bukan pada pendekatan lainnya, khususnya di bidang pendidikan desain
dan arsitektur.
Daftar Pustaka
Abadi, Bahramali AGH., Abadi, Mustafa B., Jahan, Zahra VJ. & Soorcheh, RM., (2011), Comparison of the
Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group
Therapies on Improving Problem!Solving Skill, Psychology, 2, No.4, p.307!311. Scientific
Research.
Awang, H. & Ramly, Ishak., (2008), Creative Thinking Skill Approach Through Problem!Based Learning:
Pedagogy and Practice in the Engineering Classroom, International Journal of Human and Social
Sciences, 3, No.1, p.18!23.
Avital, M. & Boland, RJ., (2008), Managing as Designing with a Positive Lens, Advanced in Appreciative
Inquiry Volume 2: Designing Information and Organizations with a Positive Lens. Elsevier Ltd.
Brown, T. & Wyatt, J., (2010), Design Thinking for Social Innovation. Stanford Social Innovation Review,
winter 2010, Leland Stanford Jr. University.
Brown, T., (2009), Change by Design, New York, Harper Collins
Brown, T., (2008), Design Thinking,Harvard Business Review, June 2008, p. 84 – 92.
Cubukcu, Feryal, (2009), Learner Autonomy, Self Regulation, and Metacognition. International Electronic
Journal of Elementary Education, 2, Issue 1, p.53!64
Case, J., & Gunstone, R., (2002). Metacognitive Development as a Shift in Approach to Learning: an in!
depth study. Studies in Higher Education, 27(4), 459!470.
De Bono, Edward, (2000), New Thinking for the New Millennium, CA, New Millennium Entertainment
IDEO, (2011), Design Thinking for Educators version one, April 2011.
Lawanto, Oenardi, (2010), Understanding the Correlation between Goal Orientation and Self!Efficacy for
Learning and Performance in an Engineering Design Activity in Grade 9!12. Proceedings of the
2010 American Society for Engineering Education Zone IV Conference, p.355!362
Lawanto, Oenardi, (2009), Metacognition Changes during an Engineering Design Project, 39th
ASEE/IEEE
Frontiers in Education Conference T2F!1. Oct 18!21, 2009, San Antonio, TX.
Pink, D.H., (2005), A Whole New Mind: berpindah dari jaman informasi menuju jaman konseptual,
Jakarta, Penerbit Dinastindo

3"4!+*)$5*#!6+*7$8$9"+(:($,)#!-".-()$;")<4=*-!$
&CI$
Simons, T., Gupta, A. & Buchanan, M., (2011), Innovation in R&D: Using design thinking to develop new
models of inventiveness, productivity and collaboration. Journal of Commercial Biotechnology,
17, No. 4, p.301!307.
Schwarzer, R., & Jerusalem, M., (1995), Generalized Self!Efficacy scale. In J. Weinman, S. Wright, & M.
Johnston, Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35!
37). Windsor, UK: NFER!NELSON.
Wang, AY. (2011). Contexts of Creative Thinking: A Comparison on Creative Performance of Student
Teachers in Taiwan and the United States. Journal of International and Cross!Cultural Studies, 2,
Issue 1, p.1!14.