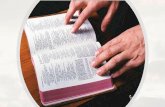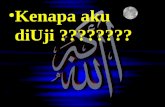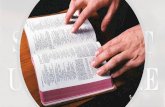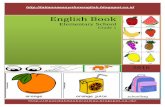PENELITIAN AKU
-
Upload
komet-budi -
Category
Documents
-
view
29 -
download
1
description
Transcript of PENELITIAN AKU

POTENSI ANTIJAMUR MINYAK DAUN CENGKEH DAN MINYAK LENGKUAS DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN
JAMUR PERUSAK SALAK PONDOH (Salacca edulis) SELAMA PENYIMPANAN
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajad Sarjana S-2
Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Jurusan Ilmu-ilmu Pertanian
Diajukan Oleh :
YOANITA ASTRID NOVIANTI (07/259471/PTP/890)
Kepada
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA 2009

ii

PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
Yogyakarta, Juni 2009
Yoanita Astrid Novianti
iii

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya serta kemudahan untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul “Potensi
Antijamur Minyak Daun Cengkeh dan Minyak Lengkuas dalam Menghambat
Pertumbuhan Jamur Perusak Salak Pondoh (Salacca edulis) Selama
Penyimpanan.
Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar
Magister S-2 pada jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Gadjah Mada.
Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dukungan
dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Departemen Pertanian melalui Program Kerja Sama Kemitraan Penelitian
dengan Perguruan Tinggi (KKP3T) yang telah mendanai penelitian ini,
2. Dr.Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. selaku dekan Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Gadjah Mada,
3. Dr.Ir. Pudji Hastuti, MS selaku Ketua Program Ilmu dan Teknologi Pangan
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada,
4. Dr.Ir. Supriyadi, MSc dan Dr.Ir. Sardjono, MS selaku dosen pembimbing
yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan
Tesis ini,
5. Dr.Ir. Suparmo, MSc. dan Dr.Ir. Retno Indrati, MSc. selaku dosen penguji
yang telah memberikan banyak saran dan masukan sehingga Tesis ini dapat
menjadi lebih baik,
6. Segenap staff dan bagian pengajaran S-2 Fakultas Teknologi Pertanian,
7. Segenap teknisi Lab. Bioteknologi dan Lab. Rekayasa Fakultas Teknologi
Pertanian,
8. Ibu, bapak, Didit, dan Mas untuk semua doa dan dukungannya,
9. Teman-teman ITP 07 dan teman-teman Humaniora,
iv

10. Serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu
terselesaikannya Tesis ini.
Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun
demikian semoga tulisan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kritik dan saran akan penulis terima untuk
penyempurnaan Tesis ini
25 Juni 2009 Penulis
v

DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul.................................................................................................. i Halaman Pengesahan ....................................................................................... ii Halaman Pernyataan......................................................................................... iii Kata Pengantar ................................................................................................. iv Daftar Isi .......................................................................................................... vi Daftar Tabel ..................................................................................................... vii Daftar Gambar.................................................................................................. viii Daftar Lampiran............................................................................................... ix Intisari .............................................................................................................. x Abstract ............................................................................................................ xi
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1 1.2. Tujuan Penelitian ............................................................................... 4
II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Salak Pondoh ..................................................................................... 5 2.2. Kerusakan Pasca Panen Salak Pondoh oleh Infeksi Mikoflora ......... 7 2.3. Agensia Antijamur ............................................................................. 14 2.4. Minyak Daun Cengkeh dan Minyak Lengkuas sebagai Antifungal Alami.................................................................................................. 16 2.5. Hipotesis ............................................................................................ 21
III. METODE PENELITIAN 3.1. Bahan ................................................................................................. 22 3.2. Alat..................................................................................................... 22 3.3. Jalannya Penelitian............................................................................. 22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Isolasi dan Identifikasi Jamur Perusak Salak Pondoh........................ 30 4.2. Uji Potensi Antijamur Minyak Daun Cengkeh pada Medium Sintetis 33 4.3. Uji Potensi Minyak Lengkuas pada Medium Sintetis........................ 36 4.4. Aplikasi Minyak Daun Cengkeh dan Minyak Lengkuas pada Salak 43 4.5. Hasil Analisis Komposisi Minyak Daun Cengkeh & Lengkuas........ 46
V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ........................................................................................ 47 5.2. Saran .................................................................................................. 48
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 49 LAMPIRAN
vi

Daftar Tabel
Halaman
Tabel 1. Komposisi Kimia Daging Buah Salak Pondoh........................... ....... 7 Tabel 2. Komposisi Media Uji......................................................................... 25 Tabel 3. Hasil Isolasi dan Identifikasi Jamur Perusak Salak Pondoh .............. 31 Tabel 4. Indeks Antijamur Minyak Daun Cengkeh dan Minyak Lengkuas terhadap empat isolat uji pada hari ke 7 ........................ 38 Tabel 5. Awal Pertumbuhan Jamur pada Salak Pondoh yang Diberi Perlakuan Pencelupan dalam Minyak Daun Cengkeh dan Lengkuas................. 36
vii

Daftar Gambar
Halaman
Gambar 1. Skema tahap isolasi dan identifikasi jamur................................. 24 Gambar 2. Skema uji penghambatan laju pertumbuhan miselia jamur ........ 26 Gambar 3. Skema kerja aplikasi minyak daun cengkeh dan minyak lengkuas pada salak pondoh....................................................................... 28 Gambar 4. Pertumbuhan jamur Fusarium sp. pada berbagai konsentrasi minyak daun cengkeh.................................................................. 33 Gambar 5. Pertumbuhan jamur tak teridentifikasi isolat CII1 pada berbagai konsentrasi minyak daun cengkeh........................... 34 Gambar 6. Pertumbuhan jamur Aspergillus sp. isolat CII4 pada berbagai konsentrasi minyak daun cengkeh............................ 35 Gambar 7. Pertumbuhan jamur Fusarium sp. pada berbagai konsentrasi minyak lengkuas. ........................................................................ 36 Gambar 8. Pertumbuhan jamur isolat CII1 pada berbagai konsentrasi minyak lengkuas ......................................................................... 37 Gambar 9. Pertumbuhan jamur Aspergillus sp. isolat CII4 pada berbagai konsentrasi minyak lengkuas ..................................................... 37 Gambar 10. Uji penghambatan jamur Aspergillus sp. isolat CII4 oleh minyak daun cengkeh pada medium uji................................................... 42 Gambar 11. Kondisi salak yang diinfeksi spora jamur Fusarium isolat CI4 selama penyimpanan 6 hari......................................................... 45
viii

Daftar Lampiran
Lampiran 1. Kromatogram minyak daun cengkeh dan minyak lengkuas
Lampiran 2. Hasil enumerasi jamur perusak salak pondoh
Lampiran 3. Uji potensi antijamur minyak daun cengkeh pada media PDA agar
Lampiran 4. Uji potensi antijamur minyak lengkuas pada media PDA agar Lampiran 5. Perhitungan Indeks Antijamur Minyak Daun Cengkeh dan Minyak
Lengkuas terhadap Isolat yang Diuji pada Hari ke-7
ix

POTENSI ANTIJAMUR MINYAK DAUN CENGKEH DAN MINYAK LENGKUAS DALAM MENGHAMBAT PERTUMBUHAN
JAMUR PERUSAK SALAK PONDOH (Salacca edulis) SELAMA PENYIMPANAN
(Antifungal Capacity of Clove Leaf- and Galangal-Oil on Reducing The
Growth of Spoilage Fungi during Storage of Salak Pondoh (Salacca edulis)
Yoanita Astrid Novianti
07/259471/PTP/890
Intisari
Potensi antijamur minyak daun cengkeh dan minyak lengkuas terhadap jamur perusak salak pondoh diuji menggunakan media sintetis dan aplikasi langsung pada salak. Isolasi jamur perusak dilakukan dengan metode direct plating. Isolat dominan diinokulasikan ke dalam media PDA yang mengandung minyak dengan konsentrasi 500-2000 ppm dengan metode giant colony. Pertumbuhan jamur diamati tiap hari dengan mengukur diameter koloni serta mengamati pembentukan konidianya secara visual. Kemampuan kedua minyak dalam menghambat pertumbuhan jamur dinyatakan dengan nilai indeks antijamur, yaitu rasio ukuran diameter koloni jamur yang ditumbuhkan pada media uji dan media kontrol (0 ppm minyak). Untuk aplikasi, buah yang telah dicelup dalam minyak diinokulasi dengan jamur perusak, disimpan pada wadah dengan RH 90% dan diamati pertumbuhan jamurnya.
Jamur perusak dominan pada salak pondoh berasal dari genera Fusarium mencapai 78% sampel yang diuji. Jamur yang paling resisten terhadap minyak daun cengkeh adalah Fusarium sp. isolat CII6 dengan indeks antijamur berturut-turut adalah 32,35; 41,67; 67,40; 86,76; dan 100 pada konsentrasi 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm dan 2000 ppm. Untuk minyak lengkuas, jamur yang paling resisten adalah Aspergillus sp. isolat CII4 dengan indeks antijamur berturut-turut adalah 13,03; 39,51; 44,17; 100; 100 pada konsentrasi 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm. Adapun jamur yang paling peka terhadap kedua minyak adalah isolat CII1 (tak teridentifikasi). Konsentrasi 500 ppm minyak menghasilkan indeks antijamur 23,18 untuk minyak daun cengkeh dan 100 untuk minyak lengkuas. Penggunaan minyak daun cengkeh sebesar 2000 ppm, mengakibatkan jamur tidak mampu tumbuh, sedangkan untuk minyak lengkuas cukup dengan konsentrasi 1500 ppm. Salak yang dicelup minyak lengkuas dan minyak daun cengkeh ditumbuhi jamur pada hari ke 6 dan hari ke 8, sedangkan salak yang tidak dicelup minyak ditumbuhi jamur pada hari ke 4.
Kata kunci : Fusarium, indeks antijamur, pertumbuhan jamur, salak pondoh
x

xi
ANTIFUNGAL CAPACITY OF CLOVE LEAF- AND GALANGAL-OIL ON REDUCING THE GROWTH OF SPOILAGE FUNGI
DURING STORAGE OF SALAK PONDOH (Salacca edulis)
(Potensi Antijamur Minyak Daun Cengkeh dan Minyak Lengkuas dalam Menghambat Pertumbuhan Jamur Perusak Salak Pondoh (Salacca edulis)
selama Penyimpanan)
ABSTRACT
The antifungal capacity of clove leaf- and galangal oil against salak Pondoh’s spoilage fungi were evaluated using synthetic media and direct application. The isolation of spoilage fungi was done by direct plating method. Dominant isolates were inoculated to PDA medium containing oils ranging from 500 to 2000 ppm using “giant colony” method. The growth of fungi was observed everyday by measuring the diameter of the colony and formation of conidia visually. The ability of both oil in preventing growth of fungi was determined as an antifungal index, which is ratio of the diameter colony grown on test media compared to one grown on control media. For applications, salak was soaked into oils for definite time followed by dipping in fungal spore suspension, and stored in the vessel with 90% humidity. The growth of spoilage fungi was observed visually.
The result indicated that spoilage fungi consist of genera Fusarium, Aspergillus, Trichoderma, and Mucor, with the genera of Fusarium was the dominant, reaching 78% of the sample. The most resistant fungi against clove leaf oil is a Fusarium sp. isolate CII6 with antifungal index 32,35; 41,67; 67,40; 86,76; and 100 for the concentration of 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, and 2000 ppm respectively. For galangal oil, the most resistant fungi is Aspergillus sp. isolate CII4 with antifungal index 13,03; 39,51; 44,17; 100; and 100 for the concentration of 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, and 2000 ppm respectively. The most sensitive fungi to the both oil is unidentified isolat CII1. The minimum inhibitory concentration for clove leaf oil was 2000 ppm, while galangal oil was 1500 ppm. The aplication of galangal- and clove leaf-oil able to keep salak until 6 and 8 days respectively, while the Salak without dipping was spoilage on the day 4.
Keywords: Antifungal index, Clove leaf oil, Galangal oil, Salak Pondoh

1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salak (Salacca edulis) merupakan salah satu buah eksotik Indonesia yang
mempunyai rasa khas dan bentuk yang unik. Salah satu varietas salak yang saat
ini banyak dibudidayakan di Indonesia adalah salak pondoh. Buah ini mempunyai
potensi yang besar untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Salak pondoh yang kini menjadi komoditas unggulan perkebunan Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah mampu menembus pasar
China. Ekspor salak pondoh ke China sudah dimulai sejak September 2008.
Hingga April 2009 sudah dilakukan 57 kali dengan total 194 ton salak pondoh.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Petanian, pada 2008 jumlah rumpun
produktif salak pondoh sebanyak 4.565.793 rumpun di lahan seluas 2.000 hektare
dengan produksi sekitar 12,80 kg per rumpun atau sekitar 58.176,8 ton per tahun.
Salak termasuk buah yang bersifat perishable/mudah rusak. Tranggono
(1992) mengatakan bahwa salak pondoh yang telah dipetik dan disimpan pada
suhu kamar, pada hari ke 10 sudah menunjukkan tanda-tanda kebusukan dan tidak
layak dikonsumsi. Pangkal buah salak yang berbentuk meruncing sangat peka
terhadap beban mekanik yang menimpanya. Kerusakan fisik pada salak menjadi
titik awal infasi jamur perusak yang sudah mengkontaminasi buah sejak di
lapangan. Pertumbuhan dan kegiatan fisiologik jamur akan meningkatkan suhu
dalam tumpukan buah. Peningkatan suhu, memar pada buah dan serangan jamur,
akan mempercepat terjadinya kemunduran dan kerusakan buah. Kusumo dkk

2
(1995) menyatakan bahwa pembusukan buah salak disebabkan oleh tiga jenis
jamur yaitu Ceratocystis paradoxa, Fusarium sp., dan Aspergilus sp.
Upaya pengendalian penyakit pada buah yang disebabkan oleh jamur
selama pasca panen umumnya dilakukan menggunakan fungisida (Pantastico,
1975). Penanganan menggunakan bahan kimia masih dipandang sebagai metode
yang paling efektif dan murah dalam menghambat penyakit pasca panen.
Senyawa-senyawa seperti thiabendazole, imazilil, sodium ortho-phenylphenate
adalah komponen-komponen aktif dalam fungisida yang sering digunakan.
Namun demikian, penggunaan senyawa-senyawa ini secara terus-menerus
ternyata justru menyebabkan resistensi beberapa jenis jamur perusak terrhadap
fungisida ini (El-Goorani et al., 1984; Chapeland et al., 1999; Dave et al., 1989).
Peningkatan kesadaran masyarakat akan efek samping penggunaan fungisida
terhadap lingkungan maupun kesehatan karena residu toksisitasnya (Paster &
Bullerman, 1988) juga mendorong dilakukannya pengembangan senyawa-
senyawa antijamur yang aman dan ramah lingkungan (natural fungisida).
Potensi beberapa ekstrak tanaman telah diteliti mampu mengendalikan
banyak jamur patogen. Beberapa di antaranya menunjukkan potensi yang sangat
besar. Ekstrak tanaman ini dapat menghambat perkecambahan spora, menghambat
pertumbuhan dan multiplikasi patogen, ataupun mematikan patogen (Hay &
Waterman, 1993). Banyak minyak esensial telah diuji aktivitas antijamurnya
(Northover & Scheider, 1993). Beberapa minyak esensial yang diperoleh dari
tanaman dilaporkan mampu menghambat jamur perusak seperti Penicillium sp.
(Caccioni & Guizzardi, 1994; Smid et al., 1995), Botrytis cinerea, dan Monilinia

3
fructicola (Wilson et al., 1987). Bahan-bahan alami seperti cengkeh dan lengkuas
telah lama dikenal mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang bersifat
antimikrobia. Penelitian yang dihimpun menunjukkan bahwa kandungan minyak
atsiri kuncup bunga cengkeh dapat menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus
flavus penyebab penyakit kulit dengan uji secara in vivo. Penelitian yang
dilakukan Amiri et al., (2008) menunjukkan bahwa minyak eugenol dari cengkeh
mempunyai sifat fungistatik terhadap jamur pathogen pada buah apel. Neri et al.,
(2006) melaporkan bahwa volatil eugenol pada konsentrasi 74 dan 984 µL/L
mampu menghambat pertumbuhan miselia dan germinasi spora pada Penicillium
expansum. Minyak esensial dari rimpang lengkuas juga dilaporkan mempunyai
aktivitas antimikrobia dalam menghambat bakteri, jamur, yeast dan parasit
(Farnsworth & Bunyapraphatsara, 1992). Menurut Janssen (1985), komponen
lengkuas yang bersifat antijamur adalah 1’ acetoxychavicol acetate (ACA) dan
(E)-8β, 17-epoxyblad-12-ene-15, 16 dial (Haraguchi, 1995). Selain kedua
senyawa di atas, senyawa α-pinene, β-pinene, limonene, 1,8-cinole, α-terpineol,
dan terpin-4-ol dapat menghambat bakteri gram +, yeast dan jamur (Janssen,
1985).
Hingga saat ini informasi mengenai penggunaan antifungal alami untuk
menghambat infeksi mikoflora pada salak pondoh belum dijumpai. Penelitian-
penelitian yang telah dilakukan lebih banyak membahas mengenai usaha-usaha
memperpanjang umur simpan salak dengan berbagai metode pengemasan. Oleh
karena itu, pada panelitian ini dikaji potensi minyak atisri daun cengkeh dan

4
minyak atsiri lengkuas untuk menghambat pertumbuhan jamur perusak salak
pondoh.
1.2. Tujuan Penelitian
1. Mengisolasi dan mengidentifikasi jamur perusak salak pondoh hingga
tingkat genera
2. Menguji potensi antijamur dari minyak daun cengkeh dan minyak
lengkuas pada media sintetis
3. Aplikasi minyak langsung pada salak pondoh dengan dasar penelitian
tahap 2

5
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Salak pondoh
Tanaman salak (Salacca edulis) termasuk ke dalam family Palmae yang
tumbuh berumpun dengan tinggi 4,5-7 meter (Kusumo dkk, 1999). Salak
merupakan tanaman asli daerah Asia Tenggara yang banyak dibudidayakan di
Indonesia. Buah salak termasuk buah non klimakterik sehingga hanya dapat
dipanen jika benar-benar telah masak di pohon, yang ditandai dengan sisik yang
telah jarang, warna kulit buah merah kehitaman atau kuning tua, bulu-bulu di kulit
telah hilang, bila dipetik mudah terlepas dari tangkai dan beraroma salak. Buah
salak yang masih muda umumnya mempunyai rasa sepet yang sangat menonjol.
Pada tingkat ketuaan optimum rasa sepetnya akan hilang dan berubah menjadi
manis dengan sedikit rasa asam serta mengeluarkan aroma yang harum (Anonim,
2002).
Salak pondoh merupakan salah satu varietas salak yang banyak
dibudidayakan di daerah Sleman, Yogyakarta. Tanaman salak pondoh mempunyai
batang pendek, berumah dua, berduri banyak, tumbuh tegak dengan ketinggian 3-
7 meter dari atas permukaan tanah, batang beruas banyak, perakaran dangkal dan
kuat, daun majemuk menyirip dengan ujung anak daun lebih lebar (Santosa,
1990). Salak pondoh mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan dan
dipasarkan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salak pondoh mulai
dikembangkan sekitar tahun 1980. Pada tahun 1999, produksi salak pondoh di
Yogyakarta mencapai 28.666 ton meningkat 100% dalam lima tahun. Salak

6
pondoh kini menjadi komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) dan telah mampu menembus pasar China. Ekspor
salak pondoh ke China sudah dimulai sejak September 2008. Hingga April 2009
dah dilakukan 57 kali dengan total 194 ton salak pondoh Berdasarkan data yang
disampaikan Dinas Petanian, pada 2008 jumlah rumpun produktif salak pondoh
sebanyak 4.565.793 rumpun di lahan seluas 2.000 hektare dengan produksi sekitar
12,80 kg per rumpun atau sekitar 58.176,8 ton per tahun.
Buah salak pondoh pada umumnya lebih kecil daripada buah salak jenis
lain. Namun dewasa ini dikenal jenis salak pondoh ekspor yang ukurannya normal
seperti buah salak biasa. Warna kulit salak pondoh bervariasi mulai dari coklat
kehitaman, coklat kemrahan, kuning kemerahan, coklat kekuningan dan merah
gelap keitaman dengan rasa buahnya yang manis (Santosa, 1990).
Buah salak pondoh terdiri dari tiga bagian yaitu kulit buah, daging buah
yang dilapisi selaput tipis dan biji. Tiap butir salak dapat memiliki 1-3 biji yang
keras dan berwarna coklat kehitaman. Pada umumnya setiap butir salak tediri atas
2-3 juring yang saling menempel dan dipisahkan oleh selapur tipis. Ketebalan
lapisan daging buah pada setiap juring tidak sama. Semakin besar ukuran salak,
semakin besar juga bagian yang bisa dimakan (Subari, 1982). Salak pondoh
memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh salak varietas lain yaitu telah
manis ketika buah masih muda. Namun kelemahan dari buah ini adalah umur
simpannya setelah panen sangat singkat. Menurut Tranggono (1992), buah salak
pondoh yang telah dipetik dan disimpan pada suhu kamar, pada hari ke 10 sudah
menunjukkan tanda-tanda kebusukan dan tidak layak dikonsumsi.

Adapun komposisi kimia dari daging buah salak pondoh dalam setiap
100g dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi kimia daging buah salak pondoh
Sumber : Hartanto (1998); *Suhardi, dkk (1997)
Komposisi Kadar Energi (Kkal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) Serat kasar (g) Kadar abu (g) Kalsium (mg) Fosfor (mg) Besi (mg) Vitamin A (IU) Vitamin B1 (mg) Vitamin C (mg) Air (g) Tanin (g) Pektin (g) Asam sitrat (g) Asam malat (g)
77 0,40 (0,94*) 0,00 20,90 - 0,67 (0,63*) 28,00 18,00 4,2 0,00 0,04 2,00 (2,43*) 78,00 (82,81) 0,58 (0,63*) 0,94* 0,62* 2,04*
2.2. Kerusakan pasca panen salak pondoh oleh infeksi mikoflora
Di daerah tropis, kehilangan pasca panen pada buah dan sayuran segar
sangat besar. Kerusakan oleh mikrobia dianggap faktor utamanya (Eckert, 1978).
Infeksi oleh mikrobia yang terjadi melalui luka pada saat panen atau sesudahnya
merupakan kerugian utama yang menyebabkan pembusukan buah. Penyakit pasca
panen buah dan sayur dapat terjadi karena infeksi selama pertumbuhan dan
perkembangan buah di pohon, melalui luka mekanis selama dipanen atau melalui
kerusakan fisologis yang disebabkan kondisi lingkungan yang tidak
menguntungkan. Perkembangan selanjutnya setelah terjadi infeksi bergantung
pada kemampuan enzimatis patogen dan kondisi fisiologis jaringan inang yang 7

8
meliputi kelembaban, kemudahan untuk diserang patogen, dan ketahanan jaringan
inang sebelum proses infeksi sempurna.
Serangan penyakit di kebun atau setelah panen menimbulkan kerugian
yang sangat berarti, yaitu berupa penurunan hasil serta penurunan kualitas buah
pada saat dipasarkan. Penyakit pasca panen seringkali merupakan kelanjutan dari
penyakit yang terjadi ketika buah masih di pohon / di kebun. Infeksi yang terjadi
di pohon seringkali tidak terlihat nyata pada saat penen tetapi kerusakan akan
berkembang cepat setelah buah dipanen.
Kebanyakan buah mempunyai pH yang rendah (<4,5). Ini berarti
kerusakan mikrobiologis yang mungkin timbul disebabkan oleh jamur perusak
pangan, karena pada pH rendah bakteri sulit tumbuh pada bahan pangan.
Berdasarkan daya perusaknya maka jamur perusak pangan dapat dikelompokkan
menjadi 2 yaitu, jamur yang merusak tanaman sebelum panen dan jamur yang
menyerang komoditas setelah panen. Sifat pertumbuhan yang khas dari jamur
adalah berbentuk kapas dan biasanya terlihat pada buah-buahan yang membusuk.
Pertumbuhannya dapat berwarna hitam, putih, atau berbagai macam warna. Jamur
bersifat aktif karena merupakan organisme saprofitik. Organisme seperti ini dapat
memecah bahan-bahan organik kompleks menjadi yang lebih sederhana. Beberapa
jamur dapat bersifat patogenik dan menyebabkan penyakit pada tanaman, seperti
penyakit pada ruas batang dan biji padi oleh Pyricularia oryzea, busuk daun, lanas
pada tembakau dll. Beberapa jenis lain selama proses pembusukan pangan atau
pertumbuhannya dalam bahan pangan dapat memproduksi racun yang dikenal
sebagai mikotoksin (Buckle et al., 1978). Jamur umumya mampu menghasilkan

9
enzim pektinolitik yang melunakkan dan merusak jaringan tanaman karena enzim
tersebut mendegradasi pektin pada jaringan tanaman sehingga menyebabkan
strukturnya rusak/lunak. Adanya jamur pada buah atau sayuran dapat
menimbulkan kerusakan yang sangat hebat hingga merusak jaringan tanaman
hingga menyerupai bubur (Hayes, 1995).
Pola pertumbuhan jamur dimulai dari proses germinasi yang diawali
dengan munculnya germtube dari permukaan spora (Robinson, 1978). Germ akan
tumbuh terus membentuk filamen yang panjang dan bercabang yang disebut hifa.
Hifa akan terus tumbuh menjadi panjang dan bertambah banyak membentuk
massa hifa yang disebut miselium (Fardiaz, 1992). Jamur berfilamen tumbuh
dengan membentuk filamen atau hifa yang memanjang dan membentuk koloni.
Bila koloni jamur tumbuh pada medium, maka hifa akan tumbuh dengan bentuk
radial dari inokulum dan koloni yang dihasilkan pada umumnya memiliki garis
tepi luar yang sirkular atau berbentuk ligkaran Ketika koloni menyebar di atas
medium padat, pertumbuhan akan tergantung dari bagian apikal hifa utama
(leader hyphae), subapikal dan cabang-cabang lateral (Robinson, 1978).
Laju pertumbuhan hifa berbeda-beda untuk jenis atau spesies yang berbeda
pula. Laju pertumbuhan hifa yang diukur menggunakan waktu versus
pertumbuhan, dalam keadaan normal akan konstan. Pengukuran pertumbuhan
jamur tidak bisa dihitung dengan metode enumerasi biasa seperti plate count atau
viable count. Enumerasi terhadap jamur benang lebih tepat dilakukan dengan
pengukuran biomassa. Meski tahap untuk mengukur pertumbuhan jamur tidak
dapat dilakukan dengan metode enumerasi biasa, namun jamur tetap memiliki unit