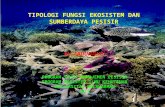Pemanfaatan SD Pesisir
-
Upload
muhammad-jafar-ibrahim -
Category
Documents
-
view
55 -
download
0
description
Transcript of Pemanfaatan SD Pesisir
RENCANA PENATAAN KAWASAN PANTAI KABUPATEN PATI
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN
(Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat)
Makalah disampaikan pada :
Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan
Oleh :
Subiyanto
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro
Semarang
4 - 9 Maret 2002
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA
PESISIR DAN LAUTAN
(Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat)
1. PENGERTIAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR.
Maksud dari pengelolaan wilayah pesisir ini adalah kegiatan manusia baik pemerintah maupun masyarakat di wilayah tersebut di dalam mengelola sumberdaya, ruang di wilayah pesisir dan sekaligus cara pemanfatannya. Di dalam pengelolan ini perlu dipertimbangkan hubungan antara setiap sumberdaya di setiap ekosistem dan diarahkan kepada pemanfaatan yang berkesinambungan (sustainable) (Bappenas, 1999). Walaupun terminologi dari pengelolaan ini bermacam-macam, akan tetapi tujuan dari pengelolaannya sama.
Beberapa terminologi tersebut antara lain, ialah Coastal Management (CM), Coastal Resources Management (CRM), Integrated Coastal Management (ICM), Integrated Coastal Zone Management (ICZM) dan lain sebagainya (Dahuri, 1996 ; Cicin-Sain dan Knecht, 1998). Selanjutnya oleh Dahuri (1996) dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan ICZM adalah pengelolaaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penelitian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya.
2. DESKRIPSI WILAYAH PESISIR
Berbicara mengenai definisi wilayah pesisir, maka sampai dengan saat ini belum ada suatu definisi yang baku tentang batas-batas wilayah pesisir. Akan tetapi telah disepakati bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara daratan dan lautan. Oleh karena itu, menurut Soegiarto (1976) batasan wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih mendapat pengaruh sifat -sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti pengundulan hutan dan pencemaran. Sedangkan menurut kesepakatan Internasional, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut dan ke arah darat meliputi daerah paparan benua atau continental shelf ( Beatley et al. 1994 dalam Dahuri et al. 1996 ).
Berdasarkan uraian diatas, maka sangatlah sukar untuk menentukan garis batas wilayah pesisir suatu daerah secara permanen, mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi wilayah tersebut selalu berubah menurut ruang dan waktu. Misalnya dalam menentukan batas wilayah pesisir ke arah daratan, dimana pengaruh pasang surut setiap saat selalu berubah, maka wilayah daratan yang terkena pengaruh pasang surut tersebut akan selalu berpindah pula.
Mengingat tidak adanya kepastian batas wilayah pesisir, maka guna keperluan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir batas fisik suatu wilayah menjadi kurang penting, akan tetapi batas-batas wilayah tersebut lebih ditekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan atau pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem pesisir beserta segenap sumberdaya yang ada didalamnya serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri (Dahuri et al. 1996).3.SUMBERDAYA DI WILAYAH PESISIR DAN PEMANFAATANNYA
Secara ekologis wilayah pesisir merupakan suatu wilayah yang sangat kompleks, dimana terjadi suatu interaksi antara ekosistem yang ada di darat dan laut. Dengan lingkungan yang spesifik, baik daratan maupun perairan yang bersifat alami seperti hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, padang lamun estuaria, pantai pasir dan lain sebagainya, maupun lingkungan buatan seperti pertambakan, kawasan pemukiman, kawasan pariwisata, kawasan industri, wilayah ini mempunyai nilai sumberdaya yang sangat tinggi. Adapun sumberdaya dapat dikategorikan sumberdaya yang bisa bersifat dapat pulih kembali, seperti sumberdaya perikanan yang terdiri dari ikan, krustasea, moluska, plankton, rumput laut, lamun, pohon bakau dan lain sebagainya, dan sumberdaya yang bersifat tidak dapat pulih kembali, seperti minyak dan gas, pasir, biji besi dan mineral lainnya. Selain itu hal penting yang perlu diketahui beberapa jenis dari sumberdaya perikanan juga memanfaatkan ekosistem di kawasan tersebut sebagai tempat asuhan (nursery ground), mencari makan (feeding ground) serta tempat untuk memijah (spawning ground).
Dengan kondisi seperti tersebut diatas serta adanya berbagai kepentingan disana, maka bisa mengakibatkan pemanfaatan sumberdaya maupun penggunaan kawasan pesisir menjadi tumpang tindih, dan cenderung menurunkan mutu bahkan merusak lingkungan beserta sumberdaya yang ada. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan yang didasari oleh kepentingan sektoral untuk memenuhi kebutuhan tertentu tanpa melihat kepentingan sektor lain atau pengguna lainnya.
4.DAMPAK PEMANFAATAN SUMBERDAYA DI WILAYAH PESISIR
Disadari atau tidak, suatu kegiatan pemanfaatan sumberdaya bisa berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan pemanfaatan lainnya, apabila kepentingan sepihak didahulukan, dan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi. Perlu diingat bahwa ekosistem di wilayah pesisir merupakan interaksi antar ekosistem yang ada di daerah tersebut, seperti ekosistem mangrove, karang, padang lamun dan ekosistem lainnya. Sehingga dengan turunnya daya dukung atau rusaknya salah satu ekosistem akan memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lainnya, serta bisa mengancam kelestarian sumberdaya di kawasan tersebut.
Selain dampak negatif secara langsung terhadap ekosistem dan sumberdaya, permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah timbulnya masalah sosial dengan munculnya konflik sosial antar pengguna kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lain adanya pemanfaatan ganda dari beberapa pengguna, pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan karena ketidaktahuan atau bahkan secara sadar melakukan pengrusakan terhadap lingkungan dan sumberdaya yang ada.
Sering kita dengar terjadinya konflik antara nelayan yang memanfaatkan sumberdaya perikanan didaerah pantai dengan alat tangkap yang berbeda, pengambilan terumbu karang, penebangan pohon bakau, pencemaran yang terjadi didaerah pesisir dan lain sebagainya.
Dengan keadaan seperti ini sudah barang tentu perlu dipikirkan suatu cara pengelolaan yang memperhatikan ekosistem tersebut secara menyeluruh dan dengan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan dengan wilayah pesisir secara terpadu.
5. PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
a. Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Akhir- akhir ini pengelolaan berbasis masyarakat sering kita dengar, dan menjadi perhatian pemerintah maupun orgasnisasi non pemerintah. Dari istilah tersebut bisa disimpulkan bahwa didalam pemanfaatan sumberdaya ini, masyarakat di wilayah tersebut mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dengan sumberdayanya dan bahwa pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumberdaya terletak ditangan masyarakat didaerah tersebut, sehingga masyarakat merupakan kunci utama dari keberhasilan pengelolaan model ini. Dikatakan oleh Nikijuluw (1994) dalam Zamani dan Darmawan (2000) pengelolaan dengan model ini didasari oleh suatu pendekatan yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya, dengan basis budaya dan kepercayaan (religion). Di Indonesia, cara pengelolaan sumberdaya seperti ini telah dilaksanakan dibeberapa daerah, misalnya Sasi di Maluku dan Panglima Laut di Aceh.
Dari ilustrasi tersebut diatas, maka masyarakat pengguna dengan berbagai macam kegiatannya merupakan faktor penting didalam menentukan nasib lingkungan dengan segala sumberdaya yang ada. Oleh karena itu kemudian munculah suatu model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (PBM atau CBM).
Menurut Carter (1996) dalam Zamani dan Darmawan (2000), definisi dari PBM adalah suatu strategi untuk pencapaian pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut. Dilihat secara sepintas model pengelolaan ini akan memberikan hasil yang dianggap baik bagi masyarakat setempat, mengingat aspirasi mereka terpenuhi didalam merencanakan pengelolaan didaerahnya. Akan tetapi seiring dengan kompleksitas permasalahan didaerah pesisir akibat semakin meningkatnya laju pembangunan dari berbagai sektor dan keterbatasan kemampuan sumberdaya di daerah tersebut, maka model seperti ini banyak mengalami kendala.
b.Pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu
Jauh sebelum munculnya Pengelolaan suatu wilayah pesisir berbasis masyarakat, peran pemerintah sangat kuat di dalam menangani segala persoalan yang ada wilayah tersebut, dimana pengelolaannya juga masih bersifat sektoral tanpa mempertimbangkan kepentingan sektor lainnya, misalnya sektor Perikanan. Sudah barang tentu model pengelolaan seperti ini akan menimbulkan permasalahan di sektor lainnya, atau sektor yang satu akan mendapatkan dampak dari sektor lainnya.
Dikatakan oleh Cincin-Sain and Knecht (1998) bahwa pada awalnya, pengelolaan kawasan pantai dimulai dari bagian daratan dan difokuskan pada isu-isu yang terdapat di batas antara daratan dan laut, seperti kasus abrasi pantai, proteksi dari rawa pantai dan lain sebagainya, dimana pengelolaan ini cenderung ditangani oleh pemerintah daerah ditingkat propinsi dan tingkat dibawahnya, yang kadang-kadang ada intervensi dari pemerintah pusat. Akan tetapi dengan semakin meningkat pemanfaatan kawasan daratan maupun laut, yang menimbulkan dampak negatif baik di daratan maupun lautnya, maka muncul model pengelolaan terpadu antar sektor, yang lebih dikenal dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu atau Integrated Coastal Management (ICM).
Untuk Indonesia, sesuai Undang-Undang yang berlaku haruslah disesuaikan dengan tingkat kewenangan untuk antar kabupaten/kota di koordinasi oleh provinsi dikoordinasi oleh Pemerintah Pusat. Demikian pula Brown ( 1997) mengatakan bahwa sehubungan dengan semakin kompleknya permasalahan di daerah pantai, manajemen secara sektoral tidaklah efektif lagi.
Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menurut Dahuri (1996) adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Lebih lanjut dikatakan pula bahwa keterpaduan disini meliputi tiga demensi yaitu keterpaduan sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan sektoral disini diartikan sebagai suatu koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat tertentu (horizontal integration), dan antar tingkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat (vertical integration) yang dijalankan secara terpadu. Sedangkan keterpaduan keilmuan merupakan sudut pandang dari pengelolaan yang dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu, yang melibatkan berbagai bidang ilmu seperti, ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lain bidang ilmu yang relevan. Tetapi aktivitas masyarakat di wilayah tersebut mempunyai hubungan dengan kedua lingkungan baik darat maupun lautnya.
Oleh Chua (1993) dalam Brown (1998) dikatakan bahwa wilayah dimana interaksi antara kedua jenis lingkungan dan kegiatan manusia tersebut berada merupakan wilayah pesisir yang didalamnya terdapat sistem sumberdaya wilayah pesisir, seperti terlihat pada ilustrasi 1.
Kita ketahui bahwa di wilayah pesisir dengan berbagai macam sumberdaya terdapat berbagai aktivitas masyarakat dari berbagai kepentingan yang memanfaatkan sumberdaya yang ada serta membentuk suatu hubungan yang sangat komplek antara fungsi dari lingkungan, sumberdaya dan aktivitas pengguna, sehingga terjadi saling ketergantungan antara demensi tersebut (Ilustrasi 2.)
Dari ilustrasi tersebut diatas, maka untuk mengurangi permasalahan didaerah pesisir yang antara lain kemungkinan terjadinya perubahan proses dan fungsi dari lingkungan, menurunnya sumberdaya serta kemungkinan terjadinya konflik diantara penggguna, maka dibutuhkan suatu kerjasama antara pengguna baik masyarakat, swasta, dan pemerintah didalam melakukan upaya pengelolaan wilayah pesisir beserta sumberdayanya dalam menuju tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dalam bentuk hubungan kemitraan yang kooperatif dan komunikatif.
Konsep keterpaduan antara pemerintah dan pengguna yang mampu menampung semua aspirasi dan kepentingan semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pengguna lainnya merupakan konsep Cooperative Management (Co-Management), yang menurut Pomeroy and Williams (1994) dalam Zamani dan Darmawan (2000) didefinisikan sebagai pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna sumberdaya alam lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hendaknya konsep ini jangan dipandang sebagai strategi tunggal untuk pemecahan problem yang ada, tetapi lebih dipandang sebagai alternatif pengelolaan, mengingat situasi dan kondisi masing-masing daerah berbeda-beda
c. Upaya Memperkuat Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Mayarakat.
Seperti telah dijelaskan didepan, bahwa konsep Co-Management ini merupakan suatu kerjasama pengelolaan suatu kawasan antara pemerintah dan masyarakat yang menjurus kearah kemitraan, dimana masyarakat di sini merupakan kunci kesuksesan dari pengelolaan tersebut. Namun demikian konsep ini masih dirasakan adanya suatu kekurangan, khususnya di dalam merencanakan strategi perencanaannya. Hal ini bisa dimaklumi, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang merupakan unsur pelaksana pengelolaan di masing-masing daerah sangat beragam.
Oleh Purwaka (1995) disarankan bahwa untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya pantai melibatkan para ahli (experts) dalam berbagai bidang yang terkait, dan pengelola diharapkan mampu memilih para ahli dan melibatkannya dalam perencanaan. Hal ini mengingat bahwa dalam pengelolaan suatu kawasan tidak lepas dari aspek ekonomi sosio-kultural, ekologis, hukum, teknik dan lain sebagainya. Hal ini dikatakan juga oleh Zamani dan Darmawan (2000) bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat dalam konsep PSPT-BM atau Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat yang dikeluarkan oleh PKSPL-IPB, adalah segenap komponen yang terlibat baik secara langsung maupuntidak langsung dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya, diantaranya ialah LSM, Perguruan Tinggi, kalangan Peneliti lain, dan Swasta.
Adapun maksud dari keterlibatan pihak luar sepert LSM,PT dan yang lainnya ialah memberikan informasi hasil penelitian atau kajian sebagai inputan, ikut terlibat dalam memecahkan permasalahan sekaligus pendampingan disamping berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat (ilustrasi 3).
Disamping keterlibatan pihak luar tadi, beberapa hal penting yang menjadi prioritas didalam pengelolaan pesisir antara lain ialah; batas wilayah yang akan dikelola harus jelas, pengakuan secara legal terhadap pengelola serta ada pendelegasian tanggung jawab dari pemerintah, kerjasama antar pengguna, serta perlu adanya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan kepedulian terhadap lingkungannya. Dengan keterlibatan pihak luar ini, dan diperhatikannya hal-hal tersebut diatas, diharapkan kemungkinan kegagalan pengelolaan menjadi semakin kecil.
Daftar PustakaBappenas. 1999. Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir Indonesia. Bappenas. Jakarta
Brown, B. 1997. Integrated Coastal Management South Asia. Dept. of Marine Sience and Coastal Management. Univ. of New Castle. Upon Tyne. United Kingdom.
Cincin-sam, B. and Knecht, R.W. 1998. Integrated Coastal and Ocean Management. Concepts and Practices. Island Press. Washington.
Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P. dan Sitepu,M.J. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta.
Purwaka, T.H. 1995. Policy on Marine and Coastal Resource Development Planning. Center for Archipelago, Law, and Development Studies. Bandung.
Soegiarto, A. 1976. Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir. Lembaga Oseanologi Nasional. Jakarta.
Zamani, N.P. dan Darmawan. 2000. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Dalam : Bengen, D.G. (editor). Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. PKSPL - IPB.Terestrial Environment
Coastal zone
Coastal resourse system
Ilustrasi 1. Relationship between the coastal zone and the coastal resource system (after Chua 1993, in Brown, 1998).
Human Activities
Marine Environment
ENVIRONMENTAL PROCESSES
FUNCTIONS
GOODS
USERS
HYDROLOGY
MATERIAL FLOWS
NUTRIENT FLOWS
ENERGY
Ilustrasi 2. The complex relationships between environmental processes, coastal ecosystems, their functions, the goods generated and their users (after Burbridge 1994, in Brrown, 1998).
dibantu oleh PT, LSM, Konsultan dan Lembaga Penelitian
Ilustrasi 3. Model Pendekatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu berbasis Masyarakat
Bottom Up
Top Down
Diterima
Sosialisasi rencana / public hearing
STOP
Model Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Sumber pendanaan
Swadana
Mampu
Tidak
Mampukah komunitas masyarakat melakukan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu (RPWPT) berbasis masyarakat
EVALUASI
MONITORING
IMPLEMENTASI
Masuk ke dalam proses penentuan program pembangunan
Penyusunan RPWPT oleh lembaga pemerintah terkait
Penyusunan RPWPT berbasis masyarakat
Penguatan kelembagaan kebijakan dan peraturan
Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat
Studi Awal
secara Partisipatif
START
LOCAL LEVEL SDM, SDA dan Sumberdaya Buatan Strategi Propinsi
NAS LEVEL
GBHN, Konsep Nasional tentang CRM Propinsi, Strategi Perencanaan CRM
PAGE 4