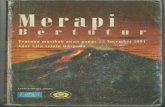Novel Riang Merapi
-
Upload
rhiez-mike -
Category
Documents
-
view
988 -
download
28
Transcript of Novel Riang Merapi
2
BISIKAN
Kebanyakan orang mengalami intimidasi dari lingkungan saat ia pindah keyakinan
yang dipeluk turun menurun oleh trahnya. Si Dwi seorang teman SMA Riang di Jogja sempat
tidak mendapat kiriman uang selama dua tahun karena pindah keyakinan dari agama Hindu
ke Kristen. Teman Riang yang satunya lagi, yang namanya Maimoon pernah kepergok akibat
salah perhitungan. Disangkanya orang tua dia sudah pergi arisan hingga bisa leluasa tunaikan
sholat. Eh, baru sujud rakaat pertama dilakukan, bunyi ceklik terdengar di kamar. Pintu
terbuka dan gelombang suara bariton serta alto mencapai empat oktaf sampai ke telinga, “O
YESUS!” Mama Maimoon histeris menangis dan dengan semangat inkuisisi abad keimanan
Eropa, bapak anak itu kalap! Dalam posisi sujud pantat anaknya menjadi samsak.
Ditendanglah satu-satunya buah percampuran antara zygoth dan sperma mereka pas di
bokong! Meclenglah membentur sudut lemari. Ubun-ubun si anak benjol sebesar telur
merpati. Tak beres di sana si bapak menggampar Maimoon menggunakan tulang carpals
Plak! Plak! Plak! sembari menunjuk tangan ke pintu rumah dan berkata “Aku tak sudi punya
anak seperti kamu! Memalukan keluarga. Durhaka! Hina! Are you understand! Are you
understand? Pergi!” Dan semua bala yang membuat asmanya teman Riang kambuh itu
terjadi karena dia pindah tempat ngetem, pindah dari agama Katolik ke Islam.
Biar kejadiannya menyeramkan, setidaknya si Maimoon itu lebih beruntung
ketimbang si Dwi karena cuma setahun dia diintimidasi: dikutuk, diancam mau dibunuh dan
dipreteli mendekati mutlisi. Namun, setahun kemudian semuanya wassalam. Mamanya
datang ke kosan. “Mama rindu kamu Delilah,” katanya sembari membujuk anak
perempuannya yang murtad. ”Kembalilah ke rumah!”
Karena si Maimoon yang dulu memang bernama Delilah itu bersikukuh, Papanya pun
mengiming-imingi: Delilah bakal disekolahkan ke negeri kiwi, tepatnya ke Port Moresby
New Zealand.
BAGI KELUARGA RIANG konflik perpindahan tempat ngetem macam itu tak
pernah berlaku. Sudah berapa kali entah dia pindah-pindah keyakinan: dari Hindu ke Islam
pernah ia lakukan. Itu pun cuma satu semester. Dipikirnya –pada saat itu-- bapak dia bakal
murka, ternyata tidak. Sewaktu bapak tahu beliau cuma sendawa. “Terserah situ. Yang
terpenting jangan dibuat macam-macam. Dibuat sampai kamu berani mencak-mencak!
Sampai kamu datang ke depan Ibu dan Bapak cuma untuk ngomong, KAFIR! KAFIR!
Seenak dengkulmu. Kalau kau seperti itu nantinya … kalau kau begitu juntrungannya bapak
3
cuma bisa berpesan. Tolong diingat siapa yang susah payah melahirkan kamu. Siapa yang
susah payah ngurus dan netekin kamu? Ibumu toh?!”
Setelah itu tak ada letupan. Monggo silahkan pindah. Tidak ada efek. Adem ayem
saja. Damai sejahtera. Aman sentausa seperti Indonesia yang benar-benar raya. Marilah kita
dentangkan sebuah lagu keramat yang sering dinyanyikan siswa sewaktu upacara bendera.
Coba yang di sana tolong di genjrang-genjrengkan gitarnya. Awali dengan kunci C. mulai…
Indonesia tanah air beta
Pujaan abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala, slalu dipuja-puja bangsa
Di sanaaaaa…..tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bundaaaa
Tempat…(lupa) hari tua
Tempat (lupa) menutup mata.
MERBABU TEGAK membentengi desa dari risauan angin. Baik pagi, siang,
terlebih malam, suasananya sejuk. Di pagi dan senja, horison benteng alam setinggi lebih dari
tiga ribu meter itu berubah menjadi warna beludru. Bersamanya lautan aura mistis
mengambang di angkasa, bersinar-sinar memberitahu bahwa cahaya alam adalah perlambang
keajaiban.
Di sini, di tempat Riang berada ini kegelapan dan cahaya dapat bersatu menjadi
sebuah lukisan surealis yang indah. Saat awan berbondong-bondong datang, angin
membentuknya menjadi kuda berkepala harimau; cabikan daging manusia yang digilas
kereta; atau bulatan-bulatan misterius seperti lukisan psikotik si bohemian kuping rebing Van
Gogh.
Desa Riang berada di kangkangan gunung itu, menyempil di lekuk lembah, di sisi
belantara dan hutan yang sedikit pepohonan besarnya. Lerengnya ditumbuhi kol yang apabila
tua warna daun juga bonggolnya menjadi hijau pekat dan yang muda berwarna hijau pastel,
sementara di sisi lainnya, umbi wortel berwarna oranye menghunjami lahan pertanian dan
daun-daun bawang menyucuk-nyucuk angkasa mengeluarkan aroma menyengat yang nikmat.
Ya, kisah ini berawal dari desa di lereng Merbabu yang indah. Kisah ini berawal
ketika rintik air melayang dibawa kabut, ketika --untuk pertama kalinya-- Riang melihat dua
lelaki berjalan seperti kalkun, mengaso di pos penjagaan lokasi wisata Kopeng.
4
Saat itu Riang memberi mereka sedikit perhatian. Hanya senyum yang dilampirkan.
Ia yakin jika kedua lelaki itu bakal bertemu dengannya dalam tempo yang sesingkat-
singkatnya, secepat-cepatnya.
Setengah jam kemudian kedua lelaki itu sampai di tepi halaman rumah Riang. Salah
seorang di antara mereka membuka tas, mengendurkan otot dan menggerakkan jemari tangan
sambil melirik jam saat lelaki satunya mengetuk pintu rumah.
Bapak menyambut selagi Riang mengintip dari balik jendela. Percakapan terdengar.
Kedua orang itu menuju ruang sebelah, ruang yang khusus didirikan bagi para pendaki
sebelum mereka tancap gas melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di dalam ruangan yang
bisa menampung hingga empat puluh pendaki tu tidak terdapat tempat tidur konvensional.
Keluarga Riang sebatas menyediakan panggung sederhana agar para pendaki tidak tidur di
lantai. Kondisi itu pun sudah lebih dari cukup sebab, mereka nemang sudah terbiasa tidur
beralas tanah dan berselimut ponco, bahkan sebagian kecilnya sudah terbiasa tidur dan
melamun di samping jenazah.
Setelah cukup lama berada di dalam rumah, Riang keluar mengantar teh panas,
hendak mengundang kedua pendaki itu mengikuti ‘syukuran kecil’ atas panen berlimpah
yang keluarga Riang nikmati tahun ini. Masuk ke dalam, ruangan kosong melompong. Riang
tidak dapat menemukan mereka. Ia menyimpan baki teh panas di atas panggung kayu. Angin
dingin masuk, pintu lantas ditutup. Riang termenung. Sesuatu mengganggunya. Sewaktu
berjalan melewati gerbang pekuburan, ia berpapasan dengan beberapa lelaki. Sekilas Riang
merasa pernah melihat salah seorang di antara mereka, tapi hingga saat ini ia belum dapat
menyimpulkannya.
Riang pun keluar, dan di bawah pohon beringin dekat rumah ia menjumpai Oerip.
Tetangganya yang baru menikah itu tidak melihat pendaki yang Riang maksud. Setelah
memberitahu Oerip bahwa penjualan panen tahunan bisa diambil di rumahnya, Riang lantas
pergi menyusuri jalan batu. Ia berpikir kedua pria itu hendak membeli Djarum Coklat, rokok
yang konon paling mantap jika dihisap di ketinggian, sembari melengkapi kekurangan bahan
makanan.
Sesampainya di warung Riang menemukan Simbok Rahayu tengah menyeduh mie
instant rasa rawon untuk anaknya, Parman.
”Hari ini ndak ada pendaki yang ke sini, Mbok?” tanya Riang.
”Ada juga yang beli batu baterai, Yang,” jawab Simbok.
“Dua orang?!”
”Bukan, sendiri Yang.”
5
Riang menduga. ”Lelaki berewok, yang pakai kupluk, yang lehernya dililit kain
merah?” tanyanya.
Simbok mengiyakan sambil mengetuk mangkuk mie hingga menimbulkan bunyi ting
berkali-kali.
“Orangnya sendirian Mbok?”
“Memangnya kenapa Yang?”
”Di gerbang pekuburan aku melihatnya tidak sendirian.” Riang meminta penegasan,
”Benar dia sendirian, Mbok?”
Simbok sewot “Sudah dibilang sendirian, ya sendirian!”
Riang tertawa. Ia mencomot pisang goreng lalu pergi menuju lahan di mana leluhur
desa Thekelan dikuburkan.
Menuruni jalan batu yang menyimpan dingin, sunyi menjadokan ketukan langkah
kaki Riang terdengar. Di kuburan itu tak ada tanah merah yang baru. Semuanya menua.
Batu-batu nisan terlihat jompo, gerbang pekuburan lembab dan tampak kehilangan vitalitas
dimakan usia. Jangkrik mengerik. Kerosak pohon kemboja yang disiurkan angin
menciptakan suasana yang mencekam. Bayang-bayang hitam pohonnya bergerak-gerak
melambai. Sunyi kembali datang dan sebuah bisikan tiba-tiba terdengar:
R
i
a
n
g
K e m a r i
R
i
a
n
g
A y o k e s i n i
R
i
a
6
n
g
A k u i n i
M
b
a
h
m
u
J a n g a n
T
a
k
u
t
Sesuatu di luar akal tiba-tiba menyebut nama Riang berulang-ulang Mendengar
bisikan itu tubuh Riang mendadak dijalari dingin yang menjalar seperti ubi jalar.. Bulu kuduk
Riang meremang menancapi udara. Ia ingin berlari tetapi takut jika sesuatu yang membisiki
telinganya itu memiliki persamaan dengan tingkah laku anjing. Anjing yang semakin garang,
yang semakin kurang ajar apabila yang digonggongi mengeluarkan ilmu mustika alias ilmu
musti kabur, angkat kaki dan berlari.
Saat pinus hutan menjadikan bayangan bukit di sebelah barat Merbabu terlihat seperti
pucuk senjata tajam, Riang berbalik. Sesampainya di halaman rumah ia melihat halaman
pintu ruangan di samping terbuka lebar. Kedua orang yang dicarinya sudah kembali. Riang
masuk ke dalam rumah menghangatkan badan. Tak terpikirkan lagi olehnya berbincang.
Yang kini mengisi tempurung kepala Riang hanya bisikan yang masih menyisakan rasa heran
bercampur kekhawatiran.
Riang menyegerakan masuk ke kamar. Orang tuannya menganggap biasa. Mereka
pikir anaknya tengah membutuhkan waktu menyendiri, melakukan semedhi. Mereka tidak
tahu jika hati anaknya kebat-kebit seperti hati perawan yang baru saja dinodai dan dirogol
kokolnya satpam.
7
Sekeping merah tersisa di angkasa. Bintang-bintang menyala, menggantikan matahari
yang meredup di batas cakrawala. Usai selamatan Riang tertidur dan keesokan harinya ia
sudah bisa memulai kehidupan seperti biasa.
TESIS VI
8
D u m!
Du m!
Du m!
Dentum Merapi menghamparkan permadani ketakutan. Suaranya mengkelebat di
seluruh penjuru mata angin. Echonya menggelegarkan desa hingga keraton Yogyakarta.
Dentum pertama menyebabkan ketuban seorang Ibu pecah. Tak lama berselang lelaki itu
lahir ke dunia berbekal nama Riang sebagai lokomotifnya dan Merapi sebagai gerbongnya.
Riang Merapi demikian gagah perwira namanya. Beruntunglah dia yang memiliki
nama sedemikian wow-nya sebab dalam setiap perkenalan pertama yang hangat, hampir
setiap orang merenungi dan sejenak mengomentarinya, --dan itulah-- sebab, mayoritas orang-
orang yang baru mendengar nama Riang pasti membayangkan perawakan yang tegap,
membayangkan keberadaan lelaki yang bugar berotot selang, berkulit plat kuningan,
berambut gimbal dengan karakter khas Merapi yang meledak-ledak.
Benar kulit Riang berwarna coklat. Benar jika dia cukup kuat mengangkat beban
yang dua kali lipat dari massa tubuhnya, tapi jika awak dia dikatakan tegap seperti anggota
angkatan bersenjata Timor Leste, atau kalau dibayangkan rambutnya didreadlocks seperti
rambut penyembah kaisar Ethiophia Hailie Selasie, pada kenyataannya tidak. Nehi nehi nehi.
Penampakan Riang bisa dikatakan biasa-biasa saja.
Setiap nama adalah cangkang yang memiliki kisah menarik dibaliknya, demikian pula
dengan nama Riang. Dia sang pemilik nama yang menggetarkan itu tidak begitu saja
mengetahui asal muasal penamaan dirinya setelah plop keluar dari cervix ibunya. Riang baru
memahami makna keramat yang disematkan kepadanya, itu pun setelah usia dia sama dengan
pertambahan usia planet biru sewaktu mengorbit matahari selama 1826 hari dengan
kecepatan rata-rata 107 ribu km/jam.
“Le kemari. Duduk di sini. Bapak mau cerita,” bujuk Bapak mengajak Riang bicara.
Riang meletakan pengki yang sedari tadi ia buat mainan. Riang duduk bersandar di
dada bapak sambil memandangi puncak Merapi yang mengepulkan asap. “Cerita apa Pak’e?”
tanyanya.
“Mau tahu kenapa bapak menamakanmu Riang?”
Kepala Riang mendongak ke arah dagu bapak.“Mau Pak’e.”
“Kamu tahu Riang artinya apa?”
“Ndak Pak’e”
“Nama Riang artinya bahagia. Bapak bahagia dikaruniai anak lelaki sepertimu.”
“Kalau bukan anak lelaki, apa Bapak tidak bahagia?” tanya Riang menyela.
9
Bapak tersenyum. “Ya bahagia.” Beliau mengusap bulir keringat di cambang Riang.
Pertanyaan anaknya kadang memang merepotkan. “Kalau nanti Kau sudah besar” kata Bapak
melanjutan. ”Le, kalau nanti kamu sudah menikah, punya anak lelaki atau perempuan, Kamu
akan memandang sama untuk anak pertama”
“Lntas kalau sama, kenapa Pak’e bahagia?”
“Ya bahagia. Ya … ya …” Bapak bingung memikirkan pertanyaan Riang. Di kepala
bapak ada banyak kata yang dibolak-baliknya. Kalau anak perempuan tidak sama berarti
tidak bahagia. Hm, kalau sama berarti bahagia. Bukannya sama-sama yang justru sama
bahagianya. “Ya… ya …honocorokodotosowolo …” ujar bapak berusaha menepiskan
pertanyaan yang membingungkan itu, tapi Riang malah terus menerus bertanya.
“Kenapa honocoroko Pak’e?”
Bapak tertawa. Ia tak mau ikut mencampur pikiran anaknya yang kompleks.
Dihisapnya rokok klobot.
“Begini Nak …” Bapak menghisap rokok klobotnya, “namamu itu dulu bukan Riang
pada awalnya. Bapakmu ini ndak tahu harus menamakan kamu apa, padahal ... waktu ibu mu
itu hamil tua, bapak suka menghina,” bapak tertawa. ”Nama yang dulu ibumu berikan jelek
semua,” katanya.
“Kenapa dihina? Kan menghina kan dosa Pak’e?”
Bapak seperti dipentung. “Ya … ya, ya tapi bagaimana?” Bapak gagap. Lidahnya
seperti dipentung. Ia menyerah. ”Memang dosa ... memang dosa, tapi nama yang ibumu beri
itu kurang Le’ …”
“Kurang apa Pak’e?”
“Ya kurang sreg poko’e.”
“Tapi kan dosa Pak’e?”
“Iya! Tapi ... tapi apa Kamu mau dikasih nama Pitono?” Bapak membuat muslihat:
mengalihkan pertanyaan Riang. ”Lha kamu lahirnya kapan saja belum ada yang tahu! Aneh
ibumu itu!”
“Pitono artinya apa Pak’e?”
“Jam pitu wes ono! Kamu mau dikasih nama itu?!”
Riang meraba-raba. “Ya ndak Pak e’!” Nama yang diberikan ibu memang kurang
menjanjikan dibandingkan namanya sekarang.
“Nah,” sambung bapak, ”Kamu saja ndak mau dinamai Pitono apa lagi aku!” Bapak
menjentikkan abu rokok lalu menghisap dalam-dalam dan menjadikan hisapannya itu sebagai
ancang-ancang. “Dulu ... namamu bukan Riang. Waktu bapak mentertawakan nama Pitono
10
itu ibumu marah. Ya sudah! Kata ibumu. Cari nama yang sampean mau! Akhirnya Bapak
jadi kelimpungan Le’.”
“Kenapa bisa kelimpungan Pak’e?”
“Soalnya sampai kandungan ibumu tua, Pak’e belum menemukan nama yang
kedengaran enak, kedengaran nikmaaaaaaaaat.”
”Lalu, lalu Pak’e?”
”Pas Merapi meledak, Kamu lahir!”
Ya! saat dentum Merapi terdengar, sewaktu letus pertamanya menjungkir balikkan
bebatuan, memuntah dan melelehkan agar-agar bersuhu ribuan derajat yang mengkilat, serta
merta saat itu juga bapak Riang melunjak gembira. Nama yang sedari dulu pusing dipikirkan
tiba-tiba meng-eureka dari balik gumpal otaknya.
Baspak memberi anak pertama yang keluar dari rahim istrinya itu nama Gembira.
Penamaan awal itu merupakan ungkapan yang jujur melompat dari hati seorang bapak yang
baru mendapat jagoan pertama –yang juga bakal selamanya. Kebahagiaan yang luar biasa itu
pula yang menyebabkan bapak meletakkan nama Merapi sebagai tetangga nama Gembira.
Namun, karena tidak enak dalam mengucapkannya, maka di hari kedua, nama Gembira
bukan saja diusir tapi disemayamkan seperti ari-ari yang tak boleh dipungut kembali:
Gembira diganti Riang, yang hingga kini masihlah Riang. Mengenai nama Merapi
bagaimana ceritanya?
Ah Ari Tulang! Kau jangan berpura-pura bodohlah! (logat Batak Mandailing bah!)
CAHAYA MATAHARI sampai di desa Thekelan setelah melakukan perjalanan
yang cukup lama. Cahayanya mendandani wajah angkasa, mengelus lekukan lereng Merbabu
yang sedikit mirip pinggul janda. Cahayanya yang eksotis berbisik agar ‘janda raksasa’ itu
menyiapkan tubuh semloheinya untuk menyambut pada pendaki yang –pada saatnya nanti—
akan berteriak kelojotan ketika mengagumi keindahan belukar dan gundukan karangnya.
Pagi itu di Thekelan, kayu pagar dan rerumputan yang menyempil di bebatuan
jalanan, berembun. Suara burung memantul di dinding lembah. Ada yang bersuara seperti
tekukur, adapula yang melengking. Riang bangun. Ia membuka pintu rumah, merasakan
udara dingin menyapu wajahnya
Setiap subuh kerjaan dia ya begini. Keluar dari kamar, membuka pintu, melamun,
memegang pokok pagar dan mengharapkan sapu yang digenggamnya tiba-tiba beraksi
membersihkan halaman sendiri. Setiap pagi seperti inilah, Riang memandangi lanskap,
11
mensyukuri betapa hidup dia dipenuhi berkah meski migrasi keluarganya menuju Thekelan
tidak dilakukan atas dasar pilihan.
Dulu, Riang memiliki keluarga besar yang tinggal di bawah Merapi di dekat kali
Boyong, tetapi itu dulu pada tahun 1995 sebelum aliran awan panas memangsa enampuluh
empat nyawa. Kakek, nenek, bibi, paman, ponakan dan sepupu dari pihak bapak serta ibu
Riang lebih baik nasibnya, dibandingkan dengan nasib penuduk yang menjadi arang. Bagi
keluarga besar Riang, tak ada istilah manusia panggang bagi mereka, sebab tak ada yang
tersisa. Alakazam, sim salabim, abracadabra ibra azhari! Keluarga Riang hilang. Amblas
dikremasi wedhus gembel gunung Merapi. Dari tanah liat menjadi debu.
Riang mengingat apa yang ia lakukan sewaktu awan panas menimbulkan suara
daging yang mendesis dan tulang penduduk desa yang mengkeretak. Saat itu Riang dan
ibunya tengah memasukkan rumput ke dalam karung goni di lereng barat gunung Merapi.
Riang masih mengingat bagaimana dengkur mengerikan terdengar dari kejauhan, awan hitam
gerak cepat menyelancari angin. Semakin awan itu mendekat, suhu bertambah panas dan
cuaca menjadi semakin kelam, dan burung-burung menjadi seperti buah masak yang
berjatuhan.
Riang menatap langit. Menyaksikan awan hitam yang memberik kiriman guntur
menakutkan, Riang segera membuang sabit yang menggantung di celana pendeknya. Ia
melemparkan ranting kayu yang berada di punggung ibunya.
Kedua anak beranak itu berlari menuruni jalan setapak, menerjang bebatuan dan
onak, terpontang panting dalam kebingungan dan ketakutan. Lima puluh meter dari tubuh
mereka gugusan cemara terbakar. Suasana mencekam. Dan ketika manusia sudah tak mampu
lagi melihat harapan, ketika manusia sudah harus ikhlas melepaskan diri dari usaha yang
dilakukan, selaris angin yang puitis datang menjinakkan aliran awan panas.
Ibu Riang menoleh. Ia menyaksikan keajaiban datang menyelamatkan. Aliran awan
panas itu mendadak belok kiri, grak angkat kaki. Entah bagaimana kejadiannya, anggota
keluarga kecil Riang selamat. Kawasan penambangan tempat bapak biasa menambang pasir
tidak dilalui aliran awan jahanam. Dan kalau pun awan itu tetap bersikukuh keluarga nuklir
Riang tetap bakal selamat sebab –kebetulan—di hari yang naas itu bapak mengirim dua truk
pasir ke Bantul.
Jadi begitulah, hanya keluarga Riang yang disisakan bencana, hanya keluarga Riang
yang menjadi penerus trah keluarga.
12
Usai kejadian tak ada yang tersisa kecuali petak peninggalan kakek di Thekelan yang
tanpa bukti surat tanah, kecuali patok dan beberapa penanda yang apabila di bawa ke
pengadilan tidak bisa dijadikan bukti kepemilikan. Keluarga Riang benar-benar harus
merangkak dari awal, namun hidup harus tetap berjalan. Bapak segera mendirikan rumah
kecil di bawah gunung Merbabu.
Saat itu tidak ada orang Thekelan yang memanfaatkan pengetahuan hilangnya surat
tanah keluarga Riang. Mereka bersimpati. Semuanya berbudi kecuali satu orang yang
hidupnya senantiasa disarati keburukan hingga feses, hingga ampas kotoran. Lelaki yang di
paru-parunya dijamuri syakwasangka itu biasa membuat masalah sepele menjadi alat
berkelahi.
Lelaki itu Kardi. Lelaki yang hatinya di siasati purbasangka itu pernah memukul
kakek Oerip dengan bata merah karena ia merasa diperhatikan. Kardi, yang tidak ketulungan
itu tidak pernah menganggap perlu menghormati orang lain. Mau kepala pamong praja, mau
anak gorila, mau turunan siluman ular sanca dia tidak peduli. Bagaimana dengan keluarga
Riang yang baru menetap di Thekelan?
Semula keluarga Riang tidak tahu menahu (siapa Kardi), hingga lelaki liar itu datang
tanpa spada tanpa kulonuwun. Dalam syukuran pendirian rumah keluarga Riang itu Kardi
memasuki ruang tengah tanpa melepaskan sandal. Di luar, lima orang temannya berjaga.
Lengan kaus mereka dilinting. Beragam corak tato dari yang cabul macam lukisan di bak
truk, tulisan norak seperti i love you Ratna hingga yang seram-seram semisal tato
kalajengking dan kepala macan kumbang sengaja mereka perlihatkan.
Suasana rumah saat itu berubah. Muka penduduk pias. Suasana canda mendadak
berhenti karna sodoran mukanya. Kardi berkacak pinggang. Seperti periskop kapal selam
kepala dia berputar.
“Namaku Kardi.” Satu persatu dilihatnya wajah penduduk desa. “Orang-orang ini
tahu siapa aku!” ia menunjuk dan mengultimatum ”Jadi … Kalian keluarga baru di desa ini
harus tahu siapa penguasa di sini! Kalian harus tahu siapa aku!”
Riang menatap wajahnya.
“Kau! Sini!” Kardi berteriak. Ia marah.
Riang diam. Ia menatap bukan karena keberanian. Riang yang masih empat belas
tahun diam ketakutan.
Merasa perintahnya Riang elakkan, mata Kardi langsung membelalak. Bola matanya
membesar dua kali lipat. Ia menggoyang golok pada sabuknya. Semua mata mengarah ke
pinggang Kardi. Kehawatiran membuat kupu-kupu berada di perut semua orang. Beberapa
13
orang penduduk desa mulai kesemutan namun rasa yang diindera Riang berbeda. Ketakutan
menimbulkan gempa berskala dua richter mengguncang tubuhnya. Riang mengingat
ketakutan yang sama seperti saat ia berlari menyelamatkan diri dari awan panas Merapi.
Gelas kopi yang Riang pegang tumpah.
Kardi cuma menggertak. Lelaki bau ikan asin itu menyarungkan golok lalu
melanjutkan koakannya di ruang tengah. “Aku begini supaya kalian, koak koak! … Sekarang
kumpulkan sumbangan (inilah intinya). Penduduk desa merogoh kantung, seribu per kepala.
Koak-koak! Jangan sampai koak-koak! Dan ”siapa saja yang memberi informasi ke polisi
maka akan ku koak-koak!”
Setelah kedatangan yang tak jelas titik komanya itu, Kardi pulang membawa belasan
bungkus rokok yang dimasukan ibu ke dalam gelas hadiah cat Avian. Ia tidak sadar
punggungnya ditusuk-tusuk kebencian. Ia tidak sadar jika mata penduduk desa
membicarakan kutukan.
Kardi? Siapa dia? Musuh nomor satu masyarakat Thekelan itu anak Samsu, ustad tua
yang di masa mudanya gemar membantu apa saja: membetulkan genting mbok Sumi oke,
menggebah ayam mbah Karjo yang rabun tidak mengapa, mengajar ngaji, masya Allah ... tak
perlu meminta karna itu hobinya.
Lantas, apa yang salah dengan Samsu hingga anaknya jadi begajul macam begitu?
Tidak ada yang salah dengan kehidupan masa muda sang ustad, kecuali keinginannya
menikahi Marmi seorang perempuan dipanggil Marmut --sejenis tikus tetapi bukan tikus--,
sebagai panggilan kesayangan mantan pacarnya yang tewas dipukuli di atas motor RX King.
Seperti biasa, pernikahan antara Samsu dan Marmut diawali dengan persamaan kehidupan
masa pernikahan pasangan muda yang bahagia di tahun pertama. Namun, semakin masa-
masa yang asoy --menurut lagak Jakartanya-- itu menjauh, semakinlah tampaklah tabiat
Marmut.
Wanita cantik macam si cantik Marmut memang seperti mobil mewah yang
membutuhkan pelumas super perusahaan trans nasional; membutuhkan bensin yang bukan
saja tidak bersubsidi tetapi pertamax; belum lagi asuransi bodi dan cat dempul. Dipikir-pikir
Samsu keadaan seperti ini harus dibendung. Kondisi semacam ini berbahaya: bisa membuat
celaka dunia akhirat. Dan ayat-ayat serta hadist pun Samsu keluarkan menjelang malam usai
bikin peluh.
Anehnya, semenjak ayat-ayat dikeluarkan permintaan barang bukannya mereda. Dan
ketika tuntutan tuntutan Marmot bertambah banyak dan kebanyakannya tidak masuk akal,
14
Samsu mulai menimbang untuk menjatuhkan adzab: Marmut harus ditalak. Tetapi, hingga
sampai saat ini Marmut tak pernah ia ceraikan. Hati Samsu tak sampai.
Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci Tuhan. Samsu
mengetahui itu, dan ia pun mulai berpikir dan merenung: mengapa kerja keras dan kebaikan
yang telah ia tebar di Thekelan tidak menjadikan hidupnya berkecukupan.
Samsu mendapat pencerahan. Ia menyadarai, kadang, kebaikan di dunia hanya
menggembungkan tabungan di akhirat sana. Lantas, Samsu pun turun gunung dengan niat
mulia menyelamatkan perahu cadik (bahtera) rumah tangganya. Samsu berkerja menjadi kuli
penggulung jala di pelabuhan. Tak kuat menahan anyir laut ia banting setir menjadi kuli batu.
Keberuntungan datang saat Samsu mendapat kenalan yang melempangkan jalan: Tauke yang
di kabari kecanggihan kerja dan keuletan Samsu, mengajaknya jualan di dekat Tanah
Genting Malaysia. Samsu menerima lalu ia mulai berpindah-pindahlah dia dari satu daerah
ke daerah di wilayah persemakmuran salah satu negara di Eropa dan hal inilah yang tidak ia
sangka menjadi salah satu masalah utamanya:
Selama banting tulang demi keluarga, Samsu tidak pernah bertemu Kardi kecuali dua
kali setahun di saat Lebaran Haji dan Idul Fitri tiba, maka, Wajar jika Samsu merasa dilistriki
usai sebuah surat memberitahukan dia bahwa anaknya yang dulu fitrah kini berubah menjadi
anak jin tomang, keponakannya setan.
Kabar itu benar, bukan kabar burung melainkan kabar dari pemilik sangkar burung.
Kabar dari orang Thekelan ia buktikan langsung melalui mata kepalanya. Samsu memergoki
anaknya makan sambel terong di bulan Ramadhan. Hati yang sudah hancur menjadi lebur.
Anak yang dulu dulu ia timang-diambing-ambing malah mendelikan mata saat dinasehati dan
diingatkan.
Ketika liburannya berakhir, Samsu pun membawa kesedihan sewaktu ia balik ke
Malaysia. Dan, belum hilang kesedihannya, sebuah kabar dikirim oleh Oerip, anak muda
yang dulu pernah ia ajari ngaji: Kardi berteman berbagai jenis orang jahat, katanya.
Melalui sebuah hadis kullu mauluudin yuuladu alal fitrah, setiap manusia lahir dalam
keadaan fitrah, Samsu diingatkan bahwa lingkunganlah yang membentuk perilaku sesat
anaknya.
Tak ada yang meleset, sesuai dengan perkiraannya: di perguruan tinggi jalanan Kardi
terlibat praktik kerja nyata pengutilan pemukulan dan aneka macam kenakalan. Di
sekolahnya, bukan saja Kardi melakukan kenakalan pada temannya bahkan ia pernah
mempermak wajah Kepsek yang putih berubah menjadi hijau kebiruan seolah keracunan
15
Waktu itu Kepsek shock! Knalpot Datsunnya meleduk. Esok harinya Kepsek
memanggil Kardi yang sore sebelumnya dipergoki penjaga sekolah tengah memasukan ketela
pohon pada knalpot mobilnya.
Selaku seorang pemimpin yang wajib beri momongan Kepsek sabar. Ia menasehati
anak itu, tapi karena Kardi bebal, nasihatnya tak mempan. Di titik inilah temperatur Kepsek
mendadak naik. Ia marah dan tak sadar jika gigi palsunya lepas.
“Stop! Stop!” Kepsek menjaga wibawa. Ia membentak.
Bukannya berhenti Kardi malah makin ngakak gak gak tertawa melihat gigi Kepsek
melompat seperti kodok.
Tingkah laku tuna etika dan peradaban macam begini membuat Kepsek murka!
Telapak tangannya terbang dan landing di jidat Kardi. Ia mengusir anak itu dari kantornya.
Dan untuk yang terakhirkalinya, keesokan hari Kardi merancang ulah. Sewaktu Kepsek
tengah men-starter vespa karyawan kontrak tata usaha, sebuah jitakan maut tiba-tiba mampir
pada batok kepala yang tidak pernah Kepsek programi reboisasi.
Kepsek mendapati si anak sialan itu tengah cengar-cengir dan bacagi yang
merupakan amalan taekwondo –yang Kepesek peragakan setiap latihan-- ia berikan di
pundak Kardi si anak tersayang: ia menendang Kardi dari sekolah untuk selamanya, dalam
artian literal dan kontekstual.
NAH, karena ingin memperbaiki arah keluarga yang melenceng dari ajaran agama
itu, atau setidaknya meminimalisir pancaran tulang sulbinya dari pengaruh lingkungan,
Samsu menguatkan tekad untuk pulang. Sayangnya kehadiran Samsu, tidak berarti apa-apa.
Mendengar bapaknya datang, si anak bukannya pulang. Ia malah melanjutkan aksinya.
Kardi yang berubah menjadi kriminal mengundang polisi untuk terus menerus
mendatangi Thekelan, menjadikan Samsu stress dan putus asa menghadapi kenyataan das
sein yang tidak sesuai dengan realitas das sollen.
Samsu menjadi gagu dan Marmut pun kemudian menggantikan posisinya dalam
memberikan penjelasan di hadapan aparat keamanan.
”Dari SMA anak saya tidak pernah kemari!” Jelas Marmut, padahal semua orang
Thekelan mahfum: sejak naik pangkat jadi residivis perampok toko emas, bersama sembilan
orang temannya Kardi datang ke Thekelan. Tanpa diketahui Samsu ia mampir ke rumah
membawa bekal dan alat pertukangan menuju Merbabu.
Entah karena yakin, berani atau dungu, Kardi dan gerombolan residivis lainnya
bernyanyi saat –di malam hari-- mereka pergi menuju Merbabu. Suara sumbang itu sampai
16
membuat ayam berkotek bangun, sampai sapi-sapi melenguh dan anjing yang dipelihara
untuk memperingati kedatangan celeng, menggonggong riuh. Auuuu!
Tak ada yang sanggup menegur rombongan itu. Warga yang kebetulan berpas-pasan-
an dengan mereka segera menyingkir. Jalan batu menuju Merbabu itu ibaratnya jalan aspal
bagi pemilik Harley Davidson. Tuan besar Kardi datang! Sirine dimainkan! Yang ada di
dalam rumah segera mematikan lampu, lalu mengintip dari balik horden.
Beberapa hari kemudian polisi mendatangi Thekelan. Tak ada satu pun penduduk
yang berani melaporkan Karena sebelumnya beredar desas-desus, warga desa tetangga yang
didodet Kardi karena memberi tahu ke arah mana gerombolan mereka lari. Kardi tak
terjamah, hingga saat ini ia dan gerombolannya masih berada di belantara Merbabu untuk
mendirikan hidup sembari berteduh di sebuah gubug.
Tiga tahun yang lalu ketika tengah mengumpulkan kayu dan jamur--, Riang pernah
melihat gubug itu. Dindingnya terbuat dari kayu pohon pinus yang menghujam setengah
meter ke dalam tanah. Atapnya dilapisi plastik hitam yang biasa dijadikan pot tanaman oleh
penduduk Thekelan. Riang bimbang. Di satu sisi takut ia jika gubug tersebut benar menjadi
sarang gerombolan Kardi, tetapi di sisi lain ia tergoda oleh keberadaan jamur sebesar piring
yang berada di dekatnya.
Riang tak kuasa menolak. Ia menyembunyikan keranjang lalu beringsut perlahan.
Baru beberapa meter merangkak Riang mendapati seorang penghuni gubug keluar sambil
menggaruk-garuk punggung menggunakan tangan kanan sementara tangan kirinya membuka
risleting. Lelaki brewok itu membuat pancuran di sela pepohonan sambil berteriak
menanyakan keberadaan Kardi.
Balasan mengudara. Seseorang dari dalam gubug bilang: Kardi tengah mengincar
ayam jantan di dekat wihara lalu lelaki brewok itu pun pergi sambil mengancingkan celana.
Riang segera menyisihkan ranting. Ia tak ingin patahannya menimbulkan bunyi lalu
mendatangkan bahaya. Riang merangkak. Dan jamur raksasa itu pun tercerabut dari tanah.
Tak menyiakan waktunya, Riang segera mengambil keranjang. Sayang, beberapa meter
sebelum balik menuju jalan setapak, terlihat dari kejauhan. Riang tak sempat sembunyi. Ia
tak bisa berlari karena beban di punggung mempersulit dirinya.
Saat Kardi mendekat, nafas Riang mulai tak beraturan. Riang tak mampu berpikir. Ia
hanya teringat kejadian tatkala Kardi memasuki ruang tengah rumahnya. Riang gemetar. Ia
takut namun saat melihat Percik, ayam jantannya ditangkapi, Riang memaki: Itu ayam
jantanku! O cecunguk! O badjingan! (Tentu saja hanya di dalam hati)
17
Kardi tahu ayam yang dibawanya milik anak lelaki yang beberapa tahun lalu pernah
ia bentak, karenanya ia hanya berkata. “Sekarang ayam mu jadi hak milikku!”
Sinting.
Kardi menerka raut wajah Riang. “Situ kesal?!”
Riang malah diam. Unjuk rasa yang kentara itu membuat Kardi emosi.
Ditendangnya perut Riang menggunakan lutut.
Karena tengah menggendong keranjang Riang tak mampu mengontrol keseimbangan.
Ia sempoyongan, lalu jattuh.
“Diajak ngomong baik-baik malah bisu! Tuna wicara atau Situ mau digorok, hah!”
Membayangkan bagaimana sakitnya digorok, Riang bergidik. “Ndak Mas! Jangan
Mas!” Riang menguik-uik.
“Begitu kalau ditanya,” kata Kardi Puas. ”Mau apa ke sini?! Mau menjadi mata-mata,
hah?!”
Riang ampun-ampunan. ” “Ndak, ... tengah mencari jamur Mas. “ Riang menyorong
kantung yang menyelempang di tubuhnya
Kardi menengok ke dalam keranjang. Ia mengeluarkan pisau. ”Seenaknya Kau ambil
jamur di halaman rumahku! Jamur ini sudah lama kupelihara tahu!”
Riang hampir mampret kalau Kardi tidak menjambak. Riang bersyukur, karena Kardi
hanya berniat memutuskan tali keranjangnya. “Sekarang pulang!” bentak Kardi sambil
mendorong badan Riang sampai doyong. ”Situ jangan buka mulut kalau ada yang tanya!”
Kardi berbalik arah. Ia tidak takut jika Riang bakal menikamnya dari belakang. Kardi
yakin seratus persen, anak yang ada belakang tubuhnya tidak akan membuat dirinya celaka.
Dari sejak itu hingga sekarang, tidak ada lagi polisi yang datang ke Thekelan.
Penyebabnya sudah barang tentu bukan karena Riang. Aparat keamanan letih dengan
pencarian yang tak pernah didukungan penduduk Thekelan. Kini, --mesti penduduk desa
yakin jika gerombolan Kardi masih ada di sekitar Merbabu—mereka tak lagi bisa
memastikan apa Kardi dan gerombolannya masih berada di dalam gubugnya.
Gerombolan itu bukannya pensiun. Mereka memperluas wilayah pencurian melalui
perpindahan tempat ala orang purba, dan karena beberapa bulan lalu Riang sering menerima
laporan dari para pendaki yang kehilangan ransel dan barang, Riang pun menduga, pencurian
itu dilakukan di pertigaan jalan setapak, antara puncak Syarif 3119 m dan Kenteng Songo
3142 m. Pelakunya, siapa lagi.
18
SEMALAMAN Riang memikirkan bisikan-bisikan yang mengaku Simbah. Tapi pagi
ini ia berusaha mengesampingkan bisikan yang ia dengar di gerbang kuburan. Ada hal yang
yang lebih penting harus ia tuntaskan. Pagi itu Riang mengambil kesimpulan pertama: lelaki
brewok yang berpapasan dengannya di gerbang kuburan adalah lelaki yang pernah ia pergoki
--tiga tahun yang lalu—tengah kencing sebelum Riang dipergoki Kardi. Kesimpulan ke dua:
orang itu hendak berbuat jahat. Riang kemudian teringat dua orang lelaki yang hendak
mendaki Merbabu pagi ini. Kesimpulan ketiga ditariknya. Ya! Gerombolan Kardi mencuri
atau bahkan merampok mereka.
Setelah menyimpulkan apa yang harus dilakukan, apa lantas Riang harus
memberitahu ke dua orang itu agar tidak mendaki pagi ini? Sebaiknya begitu. Namun,
pikiran sederhana Riang berkerja untuk mencari alternatif lain agar kedua orang itu tidak
merasa rugi ketika Merbabu telah nampak di depan mata mereka!
Sepilon-pilonnya Riang dalam mengambil kesimpulan, setidaknya anak pegunungan
ini berbeda dari kebanyakan ahli filsafat yang hanya memikirkan kondisi dunia namun tidak
ikut serta merubahnya, maka melalui tesis ke IV Riang pun memutuskan untuk mengantar
kedua lelaki itu hingga selamat sampai di puncak.
Riang mungkin mengigau ingin menyelamatkan dunia tapi bukankah kitab moralitas
berkata menyelamatkan satu nyawa ibarat menyelamatkan seluruh umat manusia? Tesis ke
IV inilah yang menjadikan wajah Riang berpendar cerah.
Di pagi hari itu salah seorang pendaki memergokinya: mendapati Riang tengah
tersenyum memperhatikan dinding Merbabu, menggenggam sapu sambil menyaksikan
matahari yang tengah mengoplos warna-warna di angkasa menggunakan cahayanya yang
indah
“Sudah lama melamun?” tanya seorang pendaki sambil menyisir rambutnya
menggunakan jemari tangan.
“Sudah setengah jam yang lalu.” Riang tersenyum.
Lelaki itu pendendam. Ia merasa harus membalas senyuman Riang. “Namaku Pepei,”
katanya, mengulurkan tangan.
Tangan yang dingin berjabatan dengan tangan yang hangat.
“Kemarin sore Mas mencari kami ya?!” tanyanya tiba-tiba.
Bagaimana lelaki ini bisa tahu? Riang bingung.
”Dari mas Oerip,” Pepei menjelaskan.
”O”
Mereka diam
19
Pepei mengalihkan pembicaraan. “Dini hari begini Masnya sudah keluar rumah?”
“Iya.”
Pembicaraan kemudian berlanjut dengan dengan huruf o dan gabungan y dan a: ya.
O ya, o ya, o dan ya.
O dan ya yang keluar dari mulut Riang membuat bosan. Pepei memilih pergi usai
meminjam sendal. Ia balik ke dalam, mengambil sikat gigi yang diimbuhi pasta, kemudian
pergi menuju bak penampungan air di dekat wihara. Di sana ia menjumpai sahabat karib
yang bahunya bergetar menahan dingin. Ia mencium wangi pasta gigi dan pembersih di
wajahnya. Rambutnya lelaki bernama Fidel itu klimis.
Sekembalinya dari bak penampungan Pepei mendapati sahabatnya tengah bicara
dengan orang yang sebelumnya berkata o ya o ya menyebalkan. Pepei kemudian masuk ke
dalam ruangan, kemudian keluar membawa sebungkus rokok. Dimasukkan sampah plastik ke
dalam kantung celana. Disodorkannya bungkus rokok untuk Riang. Riang menjentik sisa
rokok kreteknya, ia mengambilnya sebatang. Pepei memantikkan geretan untuknya. Api
menyerobot keluar dari dalam lubang geretan. Asap pun mengepul.
Riang kini leluasa bicara. “Hendak mendaki jam berapa?” tanyanya. Riang merasa
ujub dan bangga dengan bau mulutnya.
“Jam tujuhan.” Pepei memasukan batang rokok ke dalam mulut. Badan yang
sebelumnya bergetar hebat bergerak beraturan. Hisapan rokok membantu kinerja paru-
parunya. “Tidak berangkat bertani?” tanya dia kepada Riang.
“Tidak, Mas. Paling-paling nanti pagi mencari kayu. Seminggu yang lalu bapak,
melihat pohon besar tumbang di jalan setapak dekat Pereng Putih. Dari pada busuk,
sebaiknya pohon itu dimanfaatkan.”
“Penduduk yang lainnya ndak tahu?”
“Ndak tahu apa?”
“Pohon yang tumbang?”
“O… Kayunya pasti masih teronggok di jalan. Saya belum melihat penduduk
Thekelan membawa lempengan kayu sejak seminggu yang lalu.”
Fidel yang berada di samping mereka, tersisih. Ia membiarkan kedua orang itu
berbincang sementara dirinya memandangi dinding Merbabu yang setiap pertambahan
detiknya mengingatkan dia pada keajaiban teknologi yang membuat foto hitam putih menjadi
berwarna.
“Mas baru pertama kali naik Merbabu, ya?” kali ini Riang yang ganti bertanya.
20
“Ya? Tapi, orang yang di samping Mas Riang pernah,” Pepei menunjuk ketika Riang
melirik Fidel.
“Masnya pernah lewat mana?” tanya Riang pada Fidel.
Fidel lupa, tetapi ia yakin selama ini ia belum pernah melewati jalur Kopeng.
Jawaban inilah yang menimbulkan ilham di dalam diri Riang. Ia lantas menjelaskan
beberapa jalur yang ada namun ia menekankan bahwa jalur yang pemandangannya paling
menarik, jalur yang paling indah yang pernah ia lalui adalah jalur Kopeng. ”Start awalnya, ya
dari desa ini!” ujarnya bangga. “Dan, kalau seandainya masih menginginkan pemandangan
yang lebih indah lagi, Mas-Masnnya harus berbelok ke arah Tenggara dari jalur yang biasa
pendaki tempuh.” Riang terkekeh, ”trek rahasia Mas! Karena jarang ada pendaki yang
mengetahui, jalurnya sudah lama tidak dilalui.”
Kedua orang itu mulai terpengaruh oleh kekehan Riang yang bernada misteri itu
Fidel yang sedari tadi tenang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya,
“Petanya bisa dibuatkan?” pintanya pada Riang.
Aha, inilah saatnya.
“Sulit Mas! Sukar!” Riang pura-pura berpikir. ” Begini saja ... bagaimana kalau
kalian aku antar saja?”
Berpandang-pandanglah mereka. Dan pada jam tujuh lewat dua menit, Fidel serta
Pepei melakukan packing, sementara sang gembala mempersiapkan semuanya: Riang
menukar uang dengan sendal capit baru. Ia memasukan pakaian, bahan makanan berupa
beras dan beberapa bungkus mie. Ia mengambil geretan yang tergeletak di perapian dan
memasukan golok ke dalam sarung lalu ia selipkan ke pinggang sewaktu ibu tengah
membungkus nasi dan sayuran untuk bekal di perjalanan.
Beberapa belas menit kemudian, --di depan rumah-- Pepei mengeluarkan dua lembar
poto kopi KTP dari dompetnya. Ia memberikannya secara estafet kepada Fidel, lalu Fidel
menyerahkan lembaran dengan tambahan beberapa helai uang pada Bapak sebagai balas jasa
penginapan (Bapak menolak).
Mereka pun berangkat. Wajah Fidel dan Pepei tampak jelas bahagia. Mereka tak
sadar jika kebahagiaan menjadikan alpa: jam tangan Fidel ketinggalan di Thekelan. Kedua
orang itu begitu bahagia hingga tidak mengetahui jika hati orang yang mengantarkan mereka
mulai dirawani kerusuhan.
21
SIULAN BATU
Riang tak mau terus terang. Tetap ia tak mau. Ia memasukan kekhawatiran ke dalam
peti dan menggemboknya di dasar hati. Apa yang sebenarnya bakal Riang lakukan, apa yang
hendak Riang rencanakan jika gerombolan Kardi memergokinya? Tidak ada. Memang tiga
tahun merupakan waktu yang lama untuk mempupuk keberanian. Tapi tak semua lelaki
telaten memupuk keberaniannya hingga tanaman dia berubah menjadi pohon keberanian
yang rindang.
Perihal keberanian Riang memang ada kemajuan. Buktinya ia memilih untuk
mengantar dan menyimpangkan Fidel dan Pepei dari jalur protokol yang biasa dilewati,
tetapi sebatas itu -- tetap saja-- tak cukup. Pikiran Riang terlampau sederhana.
ANGKASA BIRU diarsir ujung pohon pinus yang tajam. Awan melayang perlahan
menuju tenggara. Angin mengajak bercanda penduduk Thekelan yang beranjak dari
peraduan, hendak menuntaskan panenan. Angin bersiul memainkan simfoni ketenangan
22
yang dalam. Satu persatu penduduk Thekelan menyimpang dari jalan batu menuju lahan
garapan. Menuju gundukan yang ditutupi plastik pupuk terlihat dari jalan batu.
Gundukan itu berisi tumpukkan wortel, kol, bawang, dan kentang yang kemarin
siang tak sempat petani bawa. Beberapa orang menyelinapkan tangan di bawah plastik hitam,
lantas melemparkan beberapa ikat hasil pertanian ke arah Riang. Ia menerima sayuran segar
yang bisa ia jadikan sup ke dalam tas gendongnya.
Memasuki hutan habislah iring-iringan penduduk. Tinggallah mereka bertiga di jalan
setapak yang ditutup helai dedaunan pinus mati. Buah pinus yang berbentuk lonjong dan
berbuku berserakan. Beberapa pohon terlihat cedera. Pada batangnya terdapat goresan
beralur spiral berupa jalan bagi lendir terpentin, menuju wadah yang terbuat dari batok
kelapa.
Pepei menyepak kebekuan saat perjalanan mendekati dua jam. Riang tak mendengar
suara sumbang keluar dari lubang penciumannya. Nafas Pepei teratur. Sambil berjalan ia
berkata.
“Jalan setapak, udara segar, potongan kayu, semuanya merupakan partikel-partikel
pembentuk alam. Mereka mampu mengolah dan memanfaatkan unsur-unsur yang terkandung
di dalam diri, untuk meningkatkan kehidupan manusia, meningkatkan taraf peradaban yang
sudah dikembangkan semenjak manusia ada. Pernahkan setiap manusia berpikir bahwa hidup
memiliki awal dan akhir, bahwa pada akhirnya manusia akan mati dan melebur menjadi
bagian dalam keagungan semesta. Adakah manusia yang akan mati, berakhir setelah
memiliki guna?”
Pepei tidak menujukan perkataannya pada Riang mau pun pada sahabatnya. Riang
menengok Fidel. Ia tengah menggigit pangkal bolpoint. Orang yang dimintainya pendapat
angkat bahu –tersenyum. Fidel menjawab tanda tanya yang ada di muka Riang dengan
memiringkan telunjuk di keningnya.
Belum selesai Riang membalikan badan, Pepei kembali berkata-kata.
“Manusia. …manusia,
Ah manusia. Bagaimana seandainya jika kau tidak ada?
Kalau manusia tidak ada, mengapa kita ada?.
Mengapa kita merasa.
Lantas apa yang dimaksud rasa?
Duhai gila.
Mengapa kita ada?.
Dengan maksud apa k i ta a a a a a ada?”
23
Riang memikirkan apa yang Pepei lontarkan.
“Mengapa aku harus ada?” Parau, Pepei menekankan kata-kata.
“O, mengapa aku harus ada!”
Rintang memutar badannya. Fidel kembali memiringkan telunjuknya.
“O, seandainya tuhan ada,
mengapa Tuhan tak memberi tahu
tujuan penciptaan manusia dan semesta?
O, siapa yang mengetahui tujuan keberadaan kita?
Manusia manakah yang mengetahuinya?
Pendetakah?
filosofkan?
ilmuwankah?
petapakah?
O, haruskan hidupku terombang-ambing seperti ini?
O’ haruskan Tuhan ada?”
Riang membalikan badannya. Seperti mimpi yang datang berulang, ia menemukan
Fidel tengah memiringkan telunjuk di keningnya.
Tiba-tiba Pepei berhenti.
“Di depan tampak sebatang pohon menghalangi jalan,
Ini merupakan tanda bahwa keberakhiran. Akhir kepastian.
Tak mungkin dihindari, tak mungkin ditepis.
Batu kelamaan akan menghilang digerus angin.
Manusia,
binatang dan tumbuhan …
tinggal menunggu waktu, menanti tanggal mainnya.
Mati adalah kepastian.
O’, lantas apa yang akan kita hadapi
setelah kematian?”
24
Riang mulai terganggu. Ia melihat berkeliling, berusaha matikan ucapan Pepei Tebing
batu warna putih keabu-abuan memanjang di sebelah kanan. Seekor elang melayang.
Rimbunan tanaman perdu menempel. Ada tetesan air yang masuk ke dalam rimbunan
tanaman perintis itu.
“Kita sampai di pereng putih. Ini pohon mati yang kemarin aku ceritakan.” Kali ini
Riang yang ganti bicara.
Sambil mendengarkan penjelasan, Pepei memegang pohon yang tumbang. “Biasanya
pohon tumbang dijadikan apa oleh penduduk desa?” Pepei membelai batang pohon.
Wajahnya diselimuti kasih sayang.
“Tergantung kebutuhan”, jawab Riang. Ia bersyukur berhasil menimbulkan penasaran
yang mengalihkan kegilaan Pepei. “Kalau butuh lemari pakaian,” lanjut Riang, ”ya, dibuat
lemari. Kalau butuh perluasan kandang ya dijadikan kandang. Kalau dinding rumah lapuk,
ya, dijadikan dinding.”
Pepei mengangguk, terantuk-antuk.
Beberapa saat kemudian sesal mendatangi Riang. Penjelasan Riang Pepei gunakan
untuk mengganggu Riang dari pangkal, hingga menghunjam ke akar eksistensinya.
“Pohon seperti ini. Pohon yang terlihat tak memiliki daya di hadapan manusia ini …
pohon yang sering manusia tebang sekedar dijadikan penunjuk arah … pohon yang sering
ditendangi pendaki hanya untuk perlihatkan lelucon barbarnya … ternyata … O ... O ...
dalam kematiannya masih memberikan bakti untuk kita. Untuk manusia. Bakti untuk apa?”
Pepei bertanya dan menjawabnya sendiri pula. “Baktinya untuk menjadi, menjadi tempat
menyimpan pakaian, baktinya untuk dijadikan pelindung bagi hewan peliharaan dari
terkaman binatang liar, bakti diri dibakar, agar tubuh kita memperoleh kehangatan.“
Pepei menetesi kepala Riang dengan kata-kata seperti penyair gila,
“O, pohon ini memberi makna
untuk
Kehidupan manusia,
O’, sudahkan manusia berikan makna
Untuk alam semesta?
O, sudahkah kita?
Jika di dunia, manusia hanya hidup untuk dirinya,
hanya untuk kepuasannya dan kesombonganya saja …
lantas mengapa manusia dianggap sebagai mahkluk
25
yang paling mulia melebihi kemuliaan emas, topaz ... O
intan.
Sementara, sementara ... tumbuhan pada kenyataannya
lebih mulia jika dibandingkan dengan manusia.”
Riang meminta pertolongan. Ia mengais penjelasan yang tak mampu ia temukan. Sial!
Jawaban Fidel idem, sama, menduplikasi layaknya amuba!
Hati Riang kacau. Benarkah tindakannya menemani mereka menuju puncak
Merbabu? Haruskah ia mendampingi orang-orang yang di setiap pertambahan langkahnya
semakin membuat ia ragu?
Ah bukan ragu! Riang ketakutan! Ia ingin berlari meninggalkan mereka.
Berada di tengah orang gila adalah pilihan yang gila pula. Riang masih sehat. Ia tak
mau terular. Ia harus pergi berlari tetapi pikiran untuk meninggalkan mereka tertimbun pasir.
Bagaimana dengan keselamatan dua orang ini? Bagaimana? Riang terdampar pada dua
pilihan. Ia termenung di atas pohon yang telah mati. Hatinya bimbang. Sangat-sangat
bimbang! Ia tak sadar jika tetesan kata-kata Pepei mulai merembes di dalam pikirannya.
”Pepohonan selalu memberikan bakti pada manusia,
apakah manusia lebih mulia
bila tak pernah memberikan baktinya?”
Racauan itu menelusup, menembus masuk ke dalam tulang tengkorak. Ucapan itu
membuat Riang –seakan— mandi di pancuran. Suhu tubuhnya sontak sejuk, pikirannya
terbuka seluas cakrawala, pikirannya hampir tak bertapal hampir tak berbatas.
Aku harus menolong mereka. Kegelisahan ini tidak sebanding dengan keselamatan
mereka. Aku harus berkorban seperti pohon yang tumbang. Berbakti! Aku harus berbakti
seperti pohon yang tumbang itu!... Tak kan, tak akan kubiarkan mereka menjadi arwah!
Dan mereka pun beranjak.
Setengah jam perjalanan dari pohon mati Pepei tidak lagi berbicara. Ia hanya bersiul-
siul. Tanda-tanda yang menjadi penghalang jalan setapak rahasia mulai tampak. Rerumputan
nampak mengembang di kanan kirinya. Jalan rahasia itu terhalang batu dan longsoran tanah
yang terjadi setahun lalu.
Sebelum menyimpang dari jalan protokol Riang menyuruh Fidel dan Pepei istirahat.
Riang memeriksa keadaan. Lima menit kemudian ia kembali, menyerahkan buah arbei yang
memenuhi kantung bajunya. Setelahnya Riang berjalan melawan arah dari jalan yang tadi
telah ditempuhnya.
”Apa yang kau lakukan?” Tanya Pepei sebelum Riang menjauh.
26
Riang menjawab asal. Mencari jamur, katanya.
Empat menit kemudian Riang kembali.
Tak ada yang ditenteng, oleh tangan Riang, sebab alasan sebenarnya bukan itu. Riang
menyelidik, ia memastikan mereka aman dari kuntitan gerombolan Kardi. Fidel memasukan
arbei ke dalam kantung plastik transparan dan mengaitkannya di pinggang. Sebelum rute
baru dimulai Riang mengatakan bahwa monyet dan kucing hutan bersarang di sepanjang
jalan yang akan mereka lewati. Pepei berhenti bersiul. Itu yang diharapkan. Riang khawatir
jika rombongan Kardi mendengar siulannya.
Riang kemudian mengitari longsoran. Ia lantas memasuki jalan setapak yang tertutup
semak-semak. Duapuluh meter kemudian ia keluarkan golok. Ranting pohon yang
menghambat dibabat. Mereka berjalan dalam diam. Hening diganti kepak sayap belalang.
Pekik monyet terdengar. Jalan semakin curam, menurun. Hingga ...
Suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt!!!! (bunyi melengki ng terdengar panjang)
”Suara apa itu?” tanya Fidel.
”Suara angin di Watu Gubug.” Jawab Riang sambil membersihkan wajahnya yang
gatal.
Beberapa langkah kemudian ketiga orang itu sampai di kali kecil yang bening. Riang
turun mengisi air. Pepei dan Fidel mencuci mukanya. Aliran kali kecil mengalir hingga ke
penampungan Thekelan.
Fidel mengeetatkan tali ransel, saat perjalanan kembali dilakukan. Adalah hal yang
wajar, sebab mereka menghadapi tanjakan curam selama setengah jam ke depan.
Sesampainya di puncak lembah, Pereng Putih tampak. Dua ekor elang terlihat melanglang di
atasnya. Pemandangan itu membuat Pepei dan Fidel menggelengkan kepalanya.
Desa Thekelan terlihat jelas di bawah. Atap wihara berwarna merah cerah. Petak-
petak sayuran terhampar bagai permadani yang dibentangkan raksasa Kilau-kilau air pada
bak penampungan menyilaukan mata. Pemandangan menakjubkan itu melukis kegembiraan
di wajah Pepei dan Fidel. Hal itu Riang syukuri benar. Kegembiraan Riang memupuskan
kekhawatiran di dalam dirinya hingga kemudian sepi pun datang dan ...
Suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiit!! (bunyi melengking kembali terdengar panjang)
Perjalanan dilanjutkan hingga sampai di batu berkumpul yang –kumpulannya--
mengesankan persekutuan. Batu-batu itu memanjang hingga menuju ujung Watu Gubug.
Bebatuan itu tersusun rapi, seolah ada yang menatanya.
27
Tepat jam dua siang mereka berhenti di depan batu besar yang masyur. Batu memiliki
bolong besar tepat di tengah.
Suiiiiiit! (bunyi menjadi pendek)
Pepei dan Fidel masuk ke dalam batu hingga otot-otot mereka menjadi lemas. Mereka
mengantuk ...
Lantas, kemana bunyi suit?
Hilang?!
OBROLAN YANG TAK JELAS
Sirkulasi yang baik membuat mereka tidur pulas selama tiga jam dan si penunjuk
jalan baru bangun saat matahari tenggelam. Riang keluar dari bolongan batu. Fidel
menyodorkan cangkir dan roti saat melihat Riang telah berada di sampingnya. Roti
tenggelam di dalam cangkir. Perut Riang kenyang. Ia mengmpulkan ranting-ranting kayu
untuk menghangatkan badan. Dimasukannnya kayu ke dalam batu yang dapat bersiul.
Dinding bolongan di dalam batu itu dibercaki butiran kaca. Ruangannya mampu
memuat lima orang dewasa, tingginya sekitar satu meter, memiliki dua lubang, yakni lubang
yang mereka tempati sementara lubang lainnya yang sebesar roda mobil bisa mereka jadikan
perapian mini.
Riang memperhitungkan agar api tidak terlihat dari gubuk gerombolan Kardi. Ia
membuat rangka menggunakan ranting yang tersisa. Atap rangkanya ia lapisi kertas koran
dan rerumputan. Selesai mengerjakan Riang merasakan angin menderas di buhulnya. Ia
masuk ke dalam bolongan dan mengeluarkan sayuran.
Tanggap oleh kesibukan Riang Fidel masuk ke dalam dan memasang kompor parafin
di dekat lubang perapian. Matras digelar, tak lama berselang, sup jadi. Mereka makan. Dua
kali perut Riang kenyang. Setelahnya, Rokok putih dinyalakan. Riang menolak tawaran
Pepei. Rokok kretek yang diselipkan di dalam dompetnya dimainkan. Busss...Buss...Buss!
Dalam sekejap ruangan menjadi pekat.
28
Di saat saat seperti ini cerita pun mengalunlah. Batu yang mereka tempati biasa di
beri makan oleh penduduk desa dan pendaki yang percaya. Makanan batu ini adalah
sebungkus rokok kretek dan klobot, dua genggam bunga mawar melati, cerutu menyan,
bunga kemboja, satu kendi besar berisi air, ditambah nasi dan ayam bakar camani merupakan
persyaratan dasar pemberian sesaji. Semuanya dimasukkan ke anyaman besar dan ditujukan
untuk mencari jodoh, menebak toto gelap, memohon arwah leluhur memerangi hama, agar
lelembut Merbabu tidak lagi menjahili pendaki.
Untuk keperluan yang terakhir tadi Riang pernah menyaksikan dua kepala kerbau
disajikan diatas nampan, dimasukan ke dalam bolongan batu setelah belasan pendaki hilang.
Pepei dan Fidel berusaha memahami. Mereka serius mendengar apa yang Riang tak
paparkan dan –mereka-- tak mengeluarkan satu komentar apapun pun, hingga ketika Riang
mengemukakan keraguannya akan pengaruh mahluk gaib yang bisa mencelakakan atau
membuat manusia bahagia, penuturan pun dimulai.
”Sejak zaman purba manusia memiliki ketertarikan terhadap keajaiban yang berada di
luar dirinya.” Tutur Pepei. ”Manusia, kita, mengagumi gumpalan awan dan berkah hujan.
Manusia, kita, berdecak-decak atas kemampuan hujan menyulap tanaman untuk tumbuh
dengan cantik dan baik. Manusia terkagum-kagum menyaksikan hasil bercocok tanam yang
semarak, manusia terkagum-kagum tasa melimpahnya hasil perburuan, besarnya gelombang
di samudera, tiupan angin yang mampu membawa bahtera berlayar dari satu pulau ke pulau
lainnya. Manusia pun terbelalak manakala menyaksikan kekuatan negatif alam berupa
gempa, kekuatan air bah, kekuatan taufan di kepulauan tropis! Manusia heran, kita super
heran. Hal ini menjadi semacam rahasia dan untuk medapatkan jawaban atas rahasia yang
membuat heran itu, segala peristiwa kemudian manusia sangkutpautkan dengan kekuatan
gaib yang manusia anggap berada di balik seluruh kejadian. Manusia berkhayal, fenomena
alam nan dahsyat mereka kaitkan dengan kebahagiaan dan amarah mahluk kasat mata yang
tak mampu manusia indera ...”
Pepei coba menyederhanakan. ”Kalau melihat ibu Masnya murka, apa yang akan Mas
lakukan?”
Apa maksudnya ia bertanya? Mau mengetes Riang? Bukankah tidak semua orang
bisa ditanya seenaknya, --namun-- bukannya balas bertanya, Riang malah terburu-buru untuk
menjawab apa yang Pepei tanyakan.
”Melakukan sesuatu yang beliau mau.” Tanggap Riang.
”Seperti halnya Mas, jika alam tampak menakutkan, manusia zaman purba
melakukan tindakan yang --manusia anggap—akan disenangi mahluk kasat mata. Manusia
29
memberi sesaji, mereka mengabulkan pesanan yang dianggap keinginan mahluk kasat mata
yang menguasai alam. Mereka melakukan berbagai macam hal agar pertanian, perburuan,
dan segala hal yang mereka usahakan tidak dikenai bala.”
”Dulu ...” Pepei panjang bercerita, ”bangsa Teotihuakan memiliki ritual agar dewa
musim semi Xipo Totec tidak menurunkan murka. Imam-imam yang dianggap paling
mengerti keinginan dewa menyeleksi wanita terpilih untuk mereka tikam dengan belati batu
lalu jantung wanita-wanita terpilih yang masih segar, yang masih berdenyut itu diambil
hidup-hidup. Para Imam dan pengikut agama Teotihuakan menganggap apa yang mereka
lakukan sebagai simbol penyambutan bergantinya musim dingin menuju semi. Tak selesai
sampai di sana, mereka menganggap para dewa membutuhkan simbolisasi yang sempurna,
lantas kulit wanita-wanita pilihan itu mereka kelupas untuk dikenakan para imam selagi
merapal mantra dan menari-nari sembari mengelilingi altar.”
Riang mengatakan cerita itu seram sekali.
Ohoi bangsa bangsa Toltec lebih seram lagi, sanggah Pepei. Apa yang dilakukan
bangsa Toltec lebih memuakan lagi, apa yang mereka lakukan lebih menakutkan dari bangsa
Teotihuakan. Datangnya musim semi –adalah-- berarti pengurbanan besar. Tentara Toltec
kemudian mencari kurban dengan menculik atau memerangi suku-suku kecil yang tersebar
mengelilingi kota besar mereka. Suku-suku itu diburu, di matikan dan kurbannya bukan
hanya ratusan. Dalam satu hari tumpukkan mayat bergelimpangan di dekat altar. Oh, Riang
tak bisa membayangkan bila pengurbanan manusia masih berlaku di abad ini. Ia tidak
sanggup membayangkan jika imam abad kontemporer ini adalah Kardi.
Riang bersyukur ketika Pepei mengisahkan bahwa manusia sudah mampu
memperkiraan alam, manusia sudah mampu mempelajari gejala, sudah mampu
mengendalikan bahkan memanfaatkan alam untuk kehidupan. Semakin abad bertambah
kemampuan manusia makin baik. Jika dulu manusia mengetahui musim yang baik untuk
bercocok tanam melalui rasi bintang tapi manusia tidak mempu mendatangkan hujan, kini
manusia sudah bisa membuat tempat bercocok tanam yang tak terpengaruh musim.
“Tidak berhenti di sana kita yang semula hanya menunggu hujan terbang ke awan,
membawa berkarung-karung bubuk garam, ammonium nitrat dan bahan kimia lain untuk
ditebarkan di atas awan: untuk memaksa awan menurunkan hujan.”
“Dari yang percaya, menyerahkan nasib serta memberi sesaji pada pada penguasa alam,
manusia mulai beralih mempercayai dirinya sendiri, pada kekuatan dirinya, tidak pada yang
lain! Hanya kepada dirinya manusia percaya! Menyandarkan segala!”
“Maksudnya?” tanya Riang kepada Pepei.
30
“Jangan menyandarkan diri pada kegaiban, masukilah dirimu sendiri, temukanlah
kekuatan untuk mengelola kehidupan. Temukanlah kekuatan ilmiahmu sendiri!”
“Maksudnya?”
Setelah–di rumahnya-- Riang mengatakan o dan ya, o dan ya, kini pertanyaan
‘maksudnya-maksudnya’ yang bertubi ia sampaikan, membuat Riang tampak seperti anggota
sekte yang tidak memiliki kreatifitas. Padahal, --di dunia tertentu—perkataan Pepei masih
standar. Pemaparan tersebut belum merambah perkataan bapak atom Democritus hingga
Menheim, dari Durkheim, si kere Marx hingga pemikiran Deridda yang licin berlendir
seperti belut.
Beberapa hal yang Pepei paparkan memang masih terlalu cepat untuk Riang cerna,
tetapi pada kenyataannya Riang memang tidak bodoh bodoh amat. Yang ia perlukan saat ini
hanyalah duduk manis dan tidak terburu-buru mempertanyakan hal-hal yang mendesak di
kepalanya. Selanjutnya, Riang tak mengetahui kelanjutan arah pembicaraan ketika Fidel
menggertak Pepei dan mengejeknya. Untuk sementara keikutsertaan Riang dalam
pembicaraan berakhir. Ia merasa belum mampu masuk ke dalamnya. Pembicaraan itu masih
terlalu cepat.
Riang hanya menyimak, menyaksikan bagaimana Fidel menyangkal bahwa tidak
semua manusia yang percaya pada Yang Maha Mengendalikan alam menjauhi pemikiran
ilmiah. Newton, Pascal dan Einstein adalah bukti. Yang lainnya pun tidak hanya berdoa agar
taufan reda. Manusia beriman menerbangkan kamera kecil super canggih untuk mengetahui,
untuk menggali penyebab, untuk mengendalikan kebuasan alam, tetapi mereka tetap
menyadari bahwa tidak semua hal bisa di laboratoriumkan, dan tidak semua hal yang tidak
bisa dilaboratoriumkan bukan merupakan sesuatu nyata.
Siapa yang buas? Jawabannya, tentu alam, tetapi pikiran Riang jauh melampaui. Buas
dalam metafora Riang adalah bab serudukan badak dan cakaran singa.
“Kita tahu di dunia ini ada banyak paham,” Fidel menyambung, “keyakinan akan
keberadaan Tuhan ataupun penafikan terhadap-Nya, tidak ada sangkut pautnya dengan upaya
manusia menjelajah, mengeksplorasi alam semesta. Di alam ini ada manusia beriman tapi
pemalas, ada pula manusia yang tak percaya tetapi juga pemalas yang sama. Yang satunya
menyandarkan semua hal dengan jawaban sederhana: “ya itu karena Tuhan” sementara yang
satunya lagi mengatakan, “tidak ada tuhan, yang terjadi di alam semesta hanyalah hukum
alam. Lalu mereka diam membatu dan berlumut di dalam dunia filsafat yang pasif.”
Pepei menyepak Fidel “Kebenaran itu relatif!” kataya, “Tetapi, di antara kebenaran
yang relatif itu hanya pemahamankulah yang benar,” Pepei bercanda.
31
“Gneuti Seuton! Pahamilah kaplingmu sendiri!” Fidel menyalak.
“Sialan! Obrolan kita tak pernah berakhir. Sudah berapa kali kita bicara dan Kau tak
lantas meyakinkanku!”
“Justru argumentasimu yang tak meyakinkan!”
Mereka saling membantah.
Pepei meninju lengan Fidel, sahabatnya yang telah lama dipisahkan oleh bus antar kota
dan provinsi. Pepei merindukan Fidel. Dan di atas bolongan batu itu,s langit yang
menggantung menyerupai atap tenda yang melengkung. Atmosfer seakan kantung plastik
yang melindungi kemah bumi dari canon ball angkasa yang tajam laksana belati. Bintang-
bintang silih berganti berpijar.
Ketiga lelaki itu pun tertidur hingga matahari datang menyepuh pagi.
BEBERAPA RATUS METER dari bolongan seorang lelaki memaki-maki dengan
kata-kata kasar sambil menendang batang pohon, menjatuhkan dua ekor tentara semut yang
tengah menggendong larva anggota koloninya. Sementara itu, belasan orang lelaki yang
mengelilinginya menadah tetesan anggur murahan yang masih menempel di pohon sembari
memainkan kartu remi porno, untuk membunuh rasa bosan.
32
SESAT
Api padam sejak subuh. Bakaran rantingnya menjadi karbon. Pagi, ini ada begitu
banyak energi yang terkumpul. Riang keluar dari batu. Ia menuju ujung atas Watu Gubug,
mencermati adakah jejak kaki gerombolan Kardi di dalam kompleks di mana batu bersiul
berada.
Riang tak menemukan jejak apa pun. Ia lantas berbalik dan mendapati Fidel tengah
menggulung sleeeping bag bulu angsa, memasukan matras dan sebuah tabung hitam,
sementara Pepei tengah sibuk memasak telur. Setelah sarapan, perjalanan mereka lanjutkan
Sekitar satu jam ke depan mereka sudah mulai meniti jalan menanjak yang berujung di
kompleks pemancar. Tanjakan yang membuat pening tersebut membuat ketiga orang itu
kehausan.
Sampai di pemancar air habis. Di tempat ini pendaki yang masuk di luar jalur Kopeng
biasa mencari air di dekat kawah kecil, --mereka tak tahu—padahal, di dalam kompleks
pemancar itu, di balik kawat berduri terdapat tong berisi air bersih.
Riang segera membuka tas. Ia mengambil celana jeans untuk ia jadikan pembalut.
Riang tak rela jika tangannya berdarah saat memanjat. Hap! Riang sampai di kawat tertinggi.
Hap! Tubuhnya mendarat di tanah. Mimiknya melambangkan kejayaan. Riang pun berjalan
dipenuh kebanggan hingga --kebanggaan itu pupus—saat ia menemukan Fidel dan Pepei
tengah mengisi beberapa botol plastik tanpa rasa bersalah. Kedua orang itu masuk ke dalam
kompleks pemancar melalui sebuah celah. Maka di hadapan tong itulah kejayaan Riang pun
hancur menjadi puing.
33
Selepas menara pemancar, rerumputan di lembah dan puncak bukit terlihat serapih
karpet lapangan futsal. Kicauan burung terdengar. Saat itu matahari yang berada di posisi
seperempat kubah langit belum mampu menerangi lembah dengan cahaya. Fidel mengambil
sudut yang pantas diabadikan (semuanya pantas. Tak ada yang tidak). Dari tempat ini
perjalanan menuju puncak masih lama. Masih harus lewati bukit-bukit dan tebing yang
indah.
Mereka melanjutkan perjalanan meniti Kenteng Songo –sebuah jalur selebar satu meter
dengan jurang yang dalam dengan bebatuannya yang mudah runtuh. Kerikil menggelinding
menuju jurang. Debu dan pasir menghalangi pandangan. Kawah Condro Dimuko terlihat
samar. Inilah jalan terberat di Merbabu yang mewajibkan para pendaki untuk menghemat
nafas.
Tiga orang lelaki itu tak banyak bicara, mereka menekuni jalan. Sepi menyebabkan
suara keresek ransel, serta langkah kaki terdengar jelas. Di saat-saat letih dan sunyi seperti
ini, tak mungkin, ada satu pun pekerja yang masih memikirkan kantornya. Di saat seperti ini,
--bahkan-- seorang penakut yang berjalan di tengah malam, tidak akan lagi memiliki
kesempatan untuk berpikit tentang setan. Yang menguasai tempat ini hanya adalah
ketenangan yang membuat tentram.
Akhirnya, setelah meniti tanjakan itu selama setengah jam mereka sampai di tanah
datar yang bagi para pendaki berarti surga. Mereka istirahat. Ketiga orang itu berada di
puncak dua tanduk: puncak Syarif dan Kenteng Songo.
“Inilah tanjakan setan.” Riang memberikan informasi.
“Kalau disebut tanjakan setan, ... yang meniti tanjakannya disebut apa?!” Pepei
melempar botol mineral lalu Fidel menyerahkan botol air mineral pada Riang.
“Yang menaikinya berarti setan!” Riang asal bicara sambil memuaskan dahaga.
“Berarti ada tiga setan di tempat ini!” kata Pepei tertawa.
Setelah mengatakan itu angin tiba-tiba datang. Bunyi lengkingan terdengar jelas.
Suiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiit!!
Dari kejauhan rombongan orang terlihat berjalan beriringan. Kilatan-kilatan besi
memantul. Riang tak tahu siapa mereka tapi dari kecepatan langkah kaki nya ... Firasat
datang ... sepertinya ... sepertinya ... ya Tuhan, mudah-mudahan jangan! Riang berdoa.
Wajahnya seputih bedak. Jemarinya pucat, kakinya bergetar hebat.
Menyaksikan perubahan itu, Pepei segera membuka ransel. Ia mengambil teropong dan
memberikannya pada Riang. Melalui lensa Riang melihat beberapa orang memegang parang.
34
Riang tidak mengenal orang-orang itu tetapi beberada detik kemudian, --dari patahan setapak
dekat pemanca-- sesosok lelaki brewok yang ditemuinya di gerbang kuburan muncul. Orang
kelima belas sang empunya gerombolan, tampak!
Hati Riang diboyong huru-hara.
Fidel dan Pepei menatap Riang meminta penjelasan. Namun Riang tak sempat
memberi keterangan secara detail. Ia meringkas.
“Kita harus berangkat, mereka begal!”
“Begal apa?” Fidel meneropong barisan itu.
“Aku tak bisa menjelaskan! Satu jam lagi mereka sampai di tempat ini! Kita harus
segera pergi menuju puncak, sekarang!” Riang beranggapan ke dua orang di samping dia
merupakan tanggung jawabnya. “Kalian harus selamat sampai di Jogja!” katanya terdengar
hebat.
Fidel menepuk bahu Riang. Ia berjalan lebih dulu, namun langkahnya terhenti.
“Del?!” tegur Pepei mengingatkan.
“Ya!?”
“Foto! Siapa tahu ini hari terakhir kita di dunia,” Pepei tertawa.
Setelah menghabiskan sepuluh buah jepretan mereka berjalan seperti dikejar setan!
Riang tak habis pikir mengapa gerombolan Kardi bisa mengetahui keberadaan mereka.
Ia tak mengerti apa yang terjadi, namun mendadak, angin besar mengiibarkan rambut Pepei
yang panjang. Suara siulan terdengar.
Aaaaaaaah, bolongan batu di Watu Gubug tidak bersiul tadi malam. Bagaimana
mungkin gerombolan iblis itu tidak berfikir ke sana. Sial! Riang mengutuk. Ia memukuli
kepalanya. Pepei segera menenangkan Riang dengan sebatang rokok yang terbakar. Mereka
kemudian menyusul Fidel yang tengah meniti tebing curam.
Beberapa saat kemudian, batu besar berwarna hitam menghadang perjalanan mereka.
Sepintas tak ada jalan, namun di samping batu itu terdapat setapak kecil selebar setengah
meter. Ketiga orang itu kemudian meretas jalan dan menemukan gundukan eidelweis.
Setelah tebing curam terlewati, ketiga orang itu pun sampai di puncak tertinggi.
Sebuah letusan menyambut. Merapi terlihat kokoh berdiri. Tubuhnya kelabu. Bagi
Pepei dan Fidel gunung itu tampak menakjubkan, tetapi bagi Riang, tidak! Bentuk
mengkerucut itu menandakan angkuhnya kekuatan alam. Merapi –baginya—merupakan
lambang kejahatan.
35
Merapi memang tak memiliki jiwa dan keinginan, Riang memahami itu tetapi
ketidaksukaannya tetap sukar untuk dihilangkan. Di atas puncak tertinggi Merbabu itu ia
lebih suka melayangkan pandangannya menuju arah barat tempat Sindoro dan Sumbing: dua
buah gunung yang kini sebagian hutannya telah habis dibabat.
Riang mengingatkan, tak ada waktu untuk mengaso di puncak Merbabu. Pepei segera
membuang air di botol, meringankan beban. Kini langkah kakinya tidak lagi tersendat. Ia
bahkan mampu berlari menuruni bukit yang jalur setapaknya sambung menyambung dengan
Merapi.
Fidel yang lebih dulu berangkat, tersusul. Semakin cepat berlari, semakin jauh
gerombolan Kardi berada di belakang mereka. Saat ketiga orang itu memasuki padang
eidelweis udara menjadi dingin. Sengatan matahari menjadi tak terasa di kulit. Kabut pun
datang menyandung perjalanan.
Fidel dan Pepei segera menyalakan senter, lalu mengenakannya di kepala sementara
Riang yang tak membawa alat penyinaran mereka tempatkan di tengah. Perjalanan
menembus kabut tebal dilanjutkan hingga dua ratus meter ke depan. Setelahnya senter tak
bisa lagi diandalkan.
“Berhenti di sini dulu,” Fidel mengusulkan, namun dalam kebingungan Riang
merasakan gerombolan Kardi masih tetap menghantuinya. Riang ketakutan. Ia memaksa
Fidel dan Pepei untuk terus melangkah.
“Mereka tidak akan diam diri!” kata Riang tercekat. “Gerombolan itu mengetahui seluk
beluk Merbabu! Kita harus pergi... kita harus pergi!”
Fidel dan Pepei tak sampai hati mendengar suara itu. Mereka langsung melanjutkan
perjalanan, hingga akhirnya buah ketakutan Riang menjadi penyebab hilangnya arah
perjalanan mereka menuju Selo. Riang menyesal. Mereka tersesat!
36
DANAU MISTIS
Menembus kabut tebal memang merupakan perbuatan terkutuk. Riang tahu itu tapi
terkadang ketakutan membuat seseorang hilang akal. Ia tidak lagi mengenal kawasan yang
saat ini dipijaknya.
Kabut hilang beberapa jam yang lalu. Hutan seperti labirin yang diciptakan untuk
menyesatkan. Riang tak dapat lagi melihat matahari untuk mengetahui kepastian waktu.
Matahari terhalang pepohonan tinggi. Fidel segera mengambil inisiatif setelah Riang
berulang kali menggelengkan kepalanya saat ditanya mengenai posisi mereka. Fidel
langsung naik ke atas pohon. Sampi di dahan pertama ia meminta Pepei untuk melempar
tabung berwarna hitam.
Fidel menggantungkannya di leher. Ia merayap lincah setangkas cicak di batang dan
dahan pohon. Cara memanjat Fidel tidak tampak seperti gerakan penyadap terpentin yang
kaku.Keahlian memanjat tebing membantunya mengurangi pijakan kaki dan genggaman jari
yang memboroskan energi.
Dalam sekejap pohon setinggi lima belas meter ia taklukan hingga batang yang paling
ujung. Fidel mengeluarkan teropong dari balik bajunya. Ia memandangi seluruh kawasan
hutan, lalu membuka tabung berisi selembar peta. Fidel menerpong, melihat peta, matanya
berkeliling, mulutnya mengguman: Merapi, Merbabu. Ia mencari tanda untuk menentukan
arah utara kemudian merogoh kompas. Ia membidik puncak Merapi dan Merbabu, lantas
mengeluarkan bolpoint dan menuliskan angka-angka di balik peta.
Usai menghitung, Fidel menggulung dan menjatuhkan peta bersamaan dengan tabung
hitam. Saat peta jatuh ke tanah, Riang melihatnya (peta itu) mirip dengan peta selalu di bawa
37
tim SAR. Peta itu dilengkapi dengan garis-garis kontur, garis imajinasi yang menyerupai
sidik jari manusia.
“Ini aliran air yang kita lewati saat menuju Watu Gubug. Ini puncak Merapi dan
Merbabu! Kita berada di sini, di pinggir jurang ini,” Fidel menjelaskan sembari menunjuk
garis kontur yang rapat bersinggungan antara satu garis dengan garis lainnya.
Pepei berjalan menyelidik. Ia menembus pepohonan. “Di sini jurang curam,” Pepei
berteriak, memastikan.
“Sebelum potong kompas sebaiknya kita melipiri jurang lebih dulu,” ujar Fidel sambil
memandang Riang.
“Bagaimana kalau kita kembali mencari jalan menuju Selo?” Riang mengusulkan.
“Kita sudah jauh tersesat. Kalau pun menemukan jalur menuju Selo, kemungkinan
besar gerombolan itu berada di depan kita. Aku khawatir mereka membagi diri menjadi dua
kelompok. Jika bersikukuh, kita akan terjebak di antara dua kelompok itu!” katanya.
Riang faham, terjebak berarti berbahaya. Ia menghela nafas, menghela beban
perasaan bersalah, menghela kekesalan terhadap dirinya sendiri karena kedua orang itu untuk
melanjutkan perjalanan karena alasan yang ia buat.
“Se...se... sebenarnya...” Riang gugup, “sebenarnya, gerombolan Kardi mengincar
kalian sejak di Thekelan,” ia mengaku.
Siapa Kardi tentulah Pepei dan Fidel mana tahu. Riang pun mengkisahkan gubug
tempat Kardi bersembunyi hingga menceritakan keberadaan lelaki berewok yang ia temui di
dekat gerbang kuburan.
“Seandainya aku berfikir sedikit ... kejadiannya tidak akan sesulit ini! Maafkan aku ...,”
Riang memohon.
Pepei tersenyum. “Berfikir sedikit itu yang seperti apa?” Ia malah mempertanyakan hal
yang tidak penting.
“Harusnya aku berpikir nyawa lebih penting ketimbang antarkan kalian,” jawab Riang
yang tak menyadari jika ia tengah dialihkan.
“Jadi harusnya Kau menyelamatkan dirimu sendiri?!” Pepei menaikan tempernya.
“Bukan! Bukan Mas!” Riang terdesak. “Aku seharusnya memberitahu kalian sejak di
Thekelan. A-ak- aku ... aku tidak berpikir sampai ke sana. Aku berpikir kepalang ... kepalang
kalian jauh-jauh datang... sayang apabila perjalanan ke puncak Merbabu tidak kalian
lanjutkan.”
Pepei dan Fidel tertawa.
38
“Seandainya siulan batu Watu Gubug kuperhitungkan,” lanjut Riang, “kejadiannya
mungkin tidak akan begini.”
“Apa hubungan gerombolan Kardi dengan siulan di Watu Gubug?” tanya Fidel.
“Kalau ada angin dan di dalam batu tidak ada orang, batu itu akan terus menerus
bersiul. Hilangnya siulan di sore hingga subuh hari menandakan adanya beberapa orang yang
tengah berkumpul di dalam bolongan batu. Melalui ketiadaan siulan batu, gerombolan Kardi
mengetahui: ada orang yang melewati jalur pendakian yang sudah lama tidak biasa dipakai
pendaki. Aku sungguh menyesal!” ucap Riang.
Pepei bosan. Ia mengingatkan. “Mas?!” tanyanya.
“Ya,” jawab Riang.
“Tak ada yang harus disalahkan,” kata Pepei. “Setidaknya kami bisa lebih mengenal
Masnya.” Pepei melirik Fidel yang tengah tersenyum.
“Nyawa memang harus dipikirkan,” kata Fidel menyambung, “Tetapi jika mati, matilah
karena ajal memang sudah tiba. Kalau kami mati kelaparan, mati kekurangan air, terkena
hipotermia atau mati dimakan binatang buas, tak ada yang perlu dikhawatirkan karena itulah
hidup.”
“Asal jangan mati sewaktu kami buang air besar!” celetuk Pepei tertawa.
“Memang mati buang air besar dosa?!”
“Tidak, tapi malu.” ” Fidel menyanggah Riang,
Senyum Riang muncul untuk yang pertama kalinya di pagi ini.
“Mas Riang...” Fidel mengingatkan. “Jangan menjerumuskan diri dengan menyalahkan
terlalu berlebih. Tak usahlah terlalu dipikirkan! Yang penting Mas Riang sudah berani
menentukan hidup! Berani menantang!”
“Berani menentukan hidup, keberanian menantang?”
“Ya! Keberanian menantang hidup! Keberanian untuk menantang ego, keberanian
untuk tidak mendekam saat kami tengah diincar bahaya.”
Mendengar sanjungan itu wajah Riang mendadak merah.
“Riang sudah berani memilih! Berani mengganti ego dengan sikap altruis. Riang sudah
berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang.”
“Ah Mas ini. Bukankah itu...e...sikap apa tadi?” Rasa berdosa Riang hampir hilang.
“Sikap altruis: mau mengorbankan diri.”
“Bukannya lebih baik aku memberikan informasi mengenai gerombolan Kardi, pada
saat ketika kita masih berada di Thekelan, ketimbang dekati bahaya seperti ini? Bukankah
sikap yang aku miliki ini sikap yang bodoh .... Ini bukan, .... sifat apa tadi, ... Mas ...?”
39
“Altruis!”
“Ini bukan sifat altruis yang pintar Mas. Ini altruis yang bodoh!”
Fidel menunjuk dada. “Riang .... Jangan pernah menyesali apa yang pernah Kau
perbuat! Jangan pernah mengandai-andai, mengulur angan-angan mengenai suatu kesalahan
di masa lampau! Penyesalan tidak akan berfungsi jika tidak menjadikan peristiwa masa lalu
sebagai pembelajaran! Penyesalan hanya untuk sekali! Setelahnya tatap masa depan! Jangan
pernah melihat ke belakang!”
Riang merasa senang di angkat-angkat, di puja puji. Ia menggunakan cara-cara
merendahkan untuk mendengarkan bujukan dan sanjungan berkali-kali.
“Tapi, sikapku tetap bukan altruis yang pintar. Aku tetap bodoh,” ujar Riang
membantah.
Fidel memangkas. Ia bukannya tak tahu apa yang tak sadar Riang lakukan. Fidel hanya
menjawab. “Perihal bodoh atau tidaknya, terserahlah ...”
Pepei tertawa.
Tawa itu bukan untuk merajam Riang. Tawa itu merupakan pertolongan pertama agar
Riang mau melepaskan dirinya dari rasa bersalah.
Tak lama setelah berbincang, ransel pun sudah berada di punggung masing-masing
orang. Mereka beranjak menempuh jurang yang dibentuk oleh bebatuan kapur. Dalam
perjalanan itu lumut-lumut terlihat menyediakan tempat bagi tanaman kecil di tebing untuk
tumbuh. Lumut gemuk tersebut meneteskan air bening yang steril. Dari jurang ini ketiga
orang itu menyaksikan pinus pegunungan tumbang. Suaranya terdengar berderak
menakutkan. Sampai di bawah, Riang memandang ke atas. Tebing terjal itu –setidaknya--
memiliki ketinggian lebih dari duapuluh meter.
Matahari terlihat jelas dari bawah. Bolanya tampak condong ke arah barat. Tanah yang
mereka pijak tidak memperlihatkan tanda-tanda kalau pernah dilewati manusia. Beberapa
meter ke depan kaki ketiga orang itu mulai menginjak rawa-rawa. Setelah berputar-putar
sekian lama di tanah yang basah, mereka menemukan sebuah danau mungil. Fidel dan Pepei
bersiul girang.
Riang menyapu pandangan. Mengapa danau ini tidak pernah diceritakan orang? Aneh.
Di tengah danau, asap tipis terlihat membumbung, melayang-layang lalu diam seperti
sesosok mahluk yang seram. Ikan-ikan putih dan abu-abu sebesar telapak tangan
berseliweran di dalam danau. Di pinggirnya, lumpur coklat bergerak-gerak: ada beberapa
40
kepiting yang lezat untuk disantap. Seekor belibis terbang di ujung danau paling jauh lalu
masuk ke dalam semak dan berkoak.
“Tempat apa ini?” tanya Pepei mendahului pertanyaan Fidel
Riang menggeleng. Tak berapa lama kemudian, --setelah menyibak tanaman--, Fidel
menemukan lahan yang dipenuhi bantalan lumut. Riang tak mampu menutupi kegirangan
saat ia memperhatikan tempat yang nyaman bagi mereka untuk bermalam.
Tenda dibuka sementara Fidel menggelar peta. “Daerah ini tidak terpetakan,” Fidel
tenggelam. “Danau ini mungkin tidak pernah disinggahi para pendaki.”
“Danau mistis!” komentar Pepei.
“Bukan mistis. Hanya suram,” jelas Fidel menyamarkan.
Riang terganggu saat Pepei mengucapkan kata-kata mistis. Mistis? Danau ini misterius!
Bayang-bayang kejadian di gerbang kuburan menziarahi Riang lagi.
Riang bergidik.
Pepei merasakan getaran itu. “Ada apa?” tanyanya berusaha menenangkan.
“Tidak apa-apa.”
Hati Riang mulai diselipi rasa tidak aman.
TENDA DOOM BERSIH seperti baru. Warnanya didominasi merah marun, sisanya
kuning. Rangka yang terbuat dari serat fiber melengkung di luar. Setelah selesai mendirikan
tenda Pepei mengambil benang pancing dan kail di antara gulungan tali rapia. Ia masuk ke
dalam tenda, mengambil parang dan roti. Ia mengitari danau, mencari ranting yang cukup
kuat untuk menahan tarikan ikan. Tak menemukan, kemudian Pepei naik ke atas pohon,
mengayunkan parang yang menimbulkan suara erangan.
“Apa alam memiliki jiwa?” Riang bertanya pada Fidel. “Apa pepohonan memiliki
nyawa?”
“Nyawa?” Fidel kebingungan dengan pertanyaan serius yang datang tanpa lampu sen.
“Jika yang dimaksud nyawa seperti jiwa manusia, aku mana tahu? Tetapi, jika yang
dimaksud nyawa adalah kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, mungkin pohon
memilikinya.”
“Mungkin?”
“Mungkin artinya aku tak dapat memastikan jawabanku tepat atau tidak.”
Fidel menatap Riang. Ia meminta penjelasan: pertanyaan yang datangnya tiba-tiba itu.
“Suara pohon yang Mas Pepei tebang, terdengar sedih. Pohon itu mengerang!s”
41
Fidel merenung. “Aku merasakan keanehan yang Kau rasakan. Kupikir yang dirasakan
Pepei pun demikian.” Hati-hati Fidel bertanya, “Maaf ... agamamu apa Yang?”
Riang menggelengkan kepalanya.
“Tidak tahu agamamu apa?” Suara Fidel datar, tak berteriak, tak berkecipak.
“Aku tidak tahu.”
“Percaya Tuhan?”
“Tentu.”
Fidel menghela nafas. Nampaknya penjelasannya akan panjang. Ia mengetahui benar
jika lelaki di hadapannya takut setan. “Ini pemahamanku. Ini kepercayaanku.” Fidel memilih
kata-kata dan memulainya. “Aku sangsi mahkluk halus dapat dilihat di bumi. Aku belum
bertemu mereka. Banyak orang yang mempercayai wujud halus seperti palasik, pocong yang
–yang tubuhnya dibelit kain kafan; genderuwo yang seram; atau tuyul yang dianggap sebagai
penyebab raibnya uang, tapi, aku ... seumur hidupku belum pernah melihat mereka, belum
begitu mempercaya jika mahluk-mahluk itu mampu menampakkan diri. Aku hanya
mempercayai hal-hal yang gaib, tanpa embel-embel penggambaran bentuknya seperti
apa,” Saat mengatakan itu wajah Fidel mengesankan ketenangan yang sulit dicapai.
“Mengenai keanehan yang kita rasakan, saat ini, adalah hal yang wajar. Keanehan adalah
sesuatu yang alami.” Fidel berusaha meraba kondisi orang yang ada di sampingnya. “Riang?”
Fidel bertanya.
“Ya?”
“Waktu pertama kali melihat kota yang baru Kau lihat, apa yang Kau rasakan?”
“Bingung,” jawab Riang singkat.
“Dulu kau bingung dengan kota yang dipadati orang, sekarang kejadiannya sama! Siapa
yang bakal merasa nyaman berada di tempat yang tak tercetak di dalam peta. Siapa yang
langsung merasa nyaman saat tersesat tiba-tiba menemukan danau yang airnya berwarna
hijau pekat, danau yang seolah dihuni mahkluk hijau menyeramkan. Riang ... merasa aneh
tidak merupakan sebuah masalah. Merasakan keanehan pada saat ini merupakan sesuatu
sikap yang wajar.”
Fidel membiarkan Riang mengendapkan apa yang ia katakan. Setelah agak lama,
barulah ia melanjutkan.
“Riang pernah melihat mahkluk halus?”
“Tidak,” jawab Riang. “Tapi teman-temanku pernah melihatnya. Mas Oerip pernah
menjumpai lelembut Merbabu. Rambutnya panjang, wajahnya cantik tapi pucat,” Riang
sedikit bersemangat, seolah peristiwa itu ia sendiri yang mengalami..
42
“Apa Mas Oerip melihat lelembut dengan mata kepaalanya sendiri? Menyetuh dengan
tangannya sendiri?” Tanya Fidel.
Riang tak yakin. Ia tak menjawab.
“Bagaimana jika kuusulkan saja, ... Kau bisa mempercayai penggambaran mahluk
yang menyeramkan seandainya Kau melihat atau menyentuh mahluk itu dengan tanganmu
sendiri.”
Pertanyaan cerdas keluar dari mulut Riang, “Apa untuk meyakini, kita harus menyentuh
dan melihat terlebih dulu?”
“Meski tidak mutlak seperti itu, tapi untuk kasus ini, ya! Demi menjaga dirimu dari
ketakutan yang berlebih, dari hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan kontrol diri. Ya!
Kau harus melihat dan menyentuhnya dulu sebelum mempercayai penggambaran yang
dikatakan orang. Yang ...” kata Fidel menekankan, “manusia terkadang melakukan dusta.”
“Aku tidak mengerti?” Riang berusaha mencecar. “Mas tidak mempercayai hantu?”
“Aku mempercayai jika mahkluk halus itu ada, tetapi aku belum mempercayai jika
mahluk-mahluk itu dapat mengganggu manusia dengan penampakannya. Ingat ... pe nam pa
kan nya,” Fidel mengeja, “sebab bagaimana mau percaya, bagaimana dikatakan
menggangguku jika bertemu sekali seumur hidup pun, aku tak pernah. Kadang, aku baru bisa
meyakini sesuatu setelah melihat atau menyentuhnya, tapi itu kadang-kadang, ... dan teknik
ini ternyata berhasil membebaskanku dari rasa takut yang menjijikan.”
Riang tidak mencecar dengan pertanyaan ‘maksudnya?’ ia mengerti sebagian dan tak
mengerti sebagian yang lainnya. Ia cuma bilang, “Kata-kata Mas membuatku pusing.”
Fidel tak perlu melanjutkan toh tujuan awal dia untuk mengurangi ketakutan pada diri
Riang berhasil dilakukan.
Fidel tersenyum. Riang membalas. O begitu banyak senyum.
Rupanya senyum dapat membuat orang yang kalut menjadi tenang. Yang suram
menjadi bahagia.
SEMENTARA ITU itu di bagian danau lainnya, tak satupun bibir ikan yang jontor
dikait kail Pepei. Riang kemudian menyampaikan kornet yang diberkani Fidel. Pepei
kemudian kembali membuat bulatan umpan. Tak lama berselang, benang pancingnya diseret
ikan yang bernasib sial. Sebuah tarikan lantas melayangkan ikan ke udara. Ikan itu
membentur pohon. Satu ikan besar memar. Mulutnya sobek mengeluarkan darah.
43
Riang dan Pepei membawa dua ekor ikan menuju tenda. Sebelum di masak, Riang
membedah dua ekor ikan di pinggiran danau, sendirian. Saat itulah keganjilan kembali
mendatanginya. Sebuah suara memanggilnya.
R
i
a
n
g
K e m a r i
R
i
a
n
g
A y o k e s i n i
R
i
a
n
g
A k u i n i
M
b
a
h
m
u
J a n g a n
44
T
a
k
u
t
Riang menepis bisikan itu. Tapi suara yang sama semakin jelas di telinganya. Bulu
kuduk Riang tegap. Ia tergopoh-gopoh, menyelesaikan pekerjaannya lalu menghilang di
pintu tenda. Bersamaan dengan itu lenyap pulalah pembicaraan antara dirinya dengan Fidel.
Hitam mulai mengepung. Malam menjadikan danau segelap kubangan aspal. Bulan tak
sanggup mengintip yang dilakukan ketiga orang itu menggunakan permukaan danaunya. Di
luar tenda onggokan kayu kering tampak berdiri menyerupai piramida: kayu terbakar tetapi
hutan yang lebat memborgol api. Cahaya api tidak mungkin melarikan diri untuk
menyampaikan pesan pada gerombolan Kardi.
MALAM ITU, karena terlalu banyak ganggang, Pepei membawa air di dalam wadah
ke dekat perapian. Genangan air yang dari jauh terlihat pekat, dari dekat kini terlihat hijau
kekuningan. Ia kemudian menampung air di dalam peples besi dan panci kecil: menunggu
ganggang dan tanah mengendap. Tak mau tinggal diam, Riang lantas membantu Pepei
membuat penampungan air hujan, sembari berharap agar hujan segera datang hingga mereka
tak lagi kerepotan menunggu mengendapkan tanah dan ganggang hingga keesokan harinya.
Tak jauh dari ke dua orang itu, Fidel berhasil mengubah kayu menjadi abu yang panas.
Ikan segera ia masukan ke dalam perapian. Tak beberapa lama kemudian ketiga orang itu
sudah bersantap sambil berbincang ringan. Ketiga orang itu kemudian masuk ke dalam tenda,
mengistirahatkan badan. Tak berapa lama kemudian hujan pun turun deras dan ketika –di
pertengahan malam-- hujan mereda, sebuah suara kembali datang menyapa Riang.
R
i
a
n
g
K e m a r i
45
R
i
a
n
g
A y o k e s i n i
R
i
a
n
g
A k u i n i
M
b
a
h
m
u
J a n g a n
T
a
k
u
t
A y o k e m a r i d a l a m p e l u k a n M b a h.
M a s u k ke d a l a m k e d a m a i a n.
R i a n g ... D a m a i Riang!
46
Mendengar suara misterius itu, Riang langsung menempelkan badannya di tubuh Fidel.
Fidel bangun, ia menebarkan kantung tidurnya. Lelaki itu menyangka jika Riang hampir mati
kedinginan. Ia tak menyadari jika tubuh Riang bergetar karena ketakutan yang sangat.
PLASTIK PENAMPUNGAN diluberi air hujan. Seekor semut dan sebuah daun
kering mengambang di atas genangannya. Fidel menuangkan genangan air itu ke dalam
botol. Sisa genangannya ia manfaatkan untuk memasak air teh dan merebus mie, sementara
air endapan danau ia gunakan untuk menanak nasi.
Pagi itu Riang kembali bangun kesiangan. Ia tak sempat melakukan apapun pagi ini.
Sekedar untuk cuci muka atau buang air pun belum. Riang mengingat kembali suara yang
mampir di telinganya tadi malam. Acapkali ia mengigat suara itu, acapkali pula ia tersesat di
dalam pikirannya: mengapa suara yang mengaku sebagai simbah itu kini manambahkan kata
damai? Riang berusaha menggodam pertanyaan itu hingga serpih remah-remah. Tetapi, tidak
bisa. Riang membutuhkan pertolongan. Ia segera membuka tenda dome. “Mas?” sahutnya
pada Fidel. Mulut tenda terbuka lebar.
Fidel melirik. “Badanmu segar?” tanyanya sambil menyodorkan gelas.
Riang menghirup air.
“Ada apa Yang?” tanya Fidel setelah menyaksikan kesadaran Riang bertambah.
“Sore kemarin kita membicarakan keberadaan mahluk halus ...”
“Kemarin kita bicara tentang keberadaan dan penggambarannya, lantas?” Fidel
menatap Riang. Tak ada satu orang pun yang pernah ia kenal langsung membicarakan topik
yang berat seperti itu setelah bangun tidur.
“Bagaimana Mas mempercayai keberadaan mahkluk halus, sedang Mas sendiri
belum pernah melihat, meraba atau mengajaknya bicara?”
Fidel memperhatikan rongga mata Riang. Hitam. Tidurnya tak nyenyak.
“Apa yang terjadi tadi malam?” Fidel curiga. Ia berusaha menyelidikinya.
“Tidak apa,” Riang mengelak.
Fidel tahu. Ia membiarkan Riang. Manusia tidak bisa dipaksa. Kalau Riang bersedia,
ia pasti akan membeberkan semuanya.
“Mempercayai keberadaan berbeda dengan mengetahui wujudnya.” Jelas Fidel
sambil menambahkan air teh pada gelas yang dipegang Riang. “Ada, belum tentu dapat
diketahui wujudnya...”
Keriut di wajah di Riang kurang lebih menanyakan: apa pula ini?!
47
“Mempercayai keberadaan berarti mempercayai adanya sesuatu di alam semesta,
tetapi mempercayai tidak otomatis mengetahui langsung wujudnya: Riang mendengar aku
bersuara, tetapi bagaimana wujud suaraku?”
“Tidak tahu”
“Bukankah suara itu ada? Bagaimana wujudnya?” Fidel tak memaksa Riang
menjawab. Ia melanjutkan. “ Karena tiupan angin, aku merasakan dingin sewaktu mencuci
muka di bak penampungan wihara dekat rumahmu, tetapi bagaimana bentuk angin itu?
Seperti apa bentuk dingin itu? Aku tidak tahu tetapi aku yakin angin ada. Ketika dikejar-kejar
gerombolan Kardi, kita cemas. Kita tahu bahwa kita cemas, tetapi seperti apa bentuk rasa
cemas itu? Kita tidak tahu tetapi kita mengetahui bahwa cemas itu ada. Keberadaan suara,
angin, perasaan cemas itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya. Tidak terlihat itu
bukan berarti tidak ada.”
“Rasanya aku mulai paham.”
“Kau merasa paham lantas seperti apa bentuk rasa faham?” Fidel menguji.
Riang tertawa. “Sudah! Sudah!” katanya. Dan dengan itu ketakutannya sedikit reda.
Fidel berusaha mengkoreksi pengertian Riang mengenai perbedaan antara
keberadaan dan wujud. Ia memahami bahwa yang dimaksud keberadaan dalam
pertanyaan: “Bagaimana mempercayai keberadaan mahkluk halus sedang Mas sendiri
belum pernah melihat, meraba atau mengajaknya bicara?” Adalah pertanyaan mengenai
wujud.
Riang cerdas. Ia mengkonfrontir pekataan Fidel kemarin sore bahwa untuk
mempercayai wujud atau penggambaran mahluk halus seperti yang dikatakan orang-orang,
ia diharuskan untuk menyentuh atau setidaknya melihat lebih dulu apa yang dikatakan orang
sebelum ia mempercayainya. Riang pikir Fidel tidak konsisten dengan ucapannya kemarin.
Salah sangka itu terjadi karena Riang belum bisa membedakan makna kata: mempercayai
keberadaan, dengan mempercayai wujud atau penggambaran (khusus) mahluk halus yang
diberitakan orang, semacam Oerip.
“Jadi, apa menurutmu, aku mempercayai keberadaan mahluk halus atau tidak?” Fidel
kembali bertanya, untuk memastikan.
“Percaya! Seperti kepercayan adanya angin dan perasaan cemas.”
“Aku mempercayai keberadaan mahluk halus bukan karena menyandarkan pada
analogi atau perumpamaan suara, angin dan perasaan. Itu cuma untuk membedakan
pengertian kata keberadaan dan wujud,” Fidel tertawa.
Riang tidak. Otaknya keriut.
48
“Jika kebanyakan orang mempercayai keberadaan mahluk halus dikarenakan
merasakannya, sedangkan aku tidak,” Fidel meluruskan penangkapan Riang. “Aku
mempercayai keberadaan mahluk halus karena menyandarkan kepercayaan dari informasi
yang disampaikan Tuhan melalui kitab suci.”
“Lantas, orang lain mempercayai mahluk halus dari mana?”
“Bisa dari informasi yang diberikan oleh sesuatu yang ia percaya: bisa dukun bisa
manusia.”
“Bisa juga ia benar-benar melihatnya,” sanggah Riang.
“Bisa iya melihatnya, dan bisa juga tidak, tetapi untukku .... aku tetap tidak
mempercayai penggambaran mahluk halus sebelum benar-benar melihat dan
membuktikannya sendiri, karena terkadang ketika orang mengatakan melihat wujudnya,
padahal terkadang wujudnya memang tidak ada.”
Pembicaraan ini semakin sulit bagi Riang.
“Orang sering kali menyimpulkan wujud mahluk halus padahal bisa jadi ia salah
menganalisa fakta. Kita sering melihat atau mendengar orang lari terbirit-birit karena
menurut penuturannya, mereka melihat hantu hitam, melihat sosok mahluk menyeramkan
yang dikepalanya menggeliat-geliat ular, padahal setelah diselidiki ternyata bukan mahluk
halus atau hantu. Apa yang mereka lihat adalah bayangan pohon kering yang disinari cahaya
bulan.”
“Lantas dari mana Mas mempercayai keberadaan mahluk halus?”
“Kan sudah kubilang mempercayainya dari kitab suci. Mengenai wujudnya seperti
apa aku tidak tahu, sebab aku belum menemukannya. Aku akan mempercayai wujud atau
penggambaran mahluk halus bila aku menemukan wujud, melihat dan membuktikannya
langsung, atau menemukan informasi penggambaran mahluk halus dari kitab suci dan
informasi yang kitab suci menyuruhku untuk mempercayainya. Aku belum merasa perlu
mempercayai penggambaran wujud mahluk halus dari dukun atau manusia di sekitar kita
karena manusia itu selalu alpa.”
“Lantas kita harus mempercayai dari siapa?”
“Dari firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci.”
“Bagaimana kita percaya pada informasi yang diberikan Tuhan?” Pertanyaan Riang
naik jabatan. Ia maju selangkah.
“Bagaimana kita bisa tidak mempercayai Tuhan Pencipta Semesta Alam jika kita telah
membuktikan-Nya? Bagaimana kita bisa tidak mempercayai informasi yang disampaikan-
Nya, jika kita telah membuktikan keberadaan Tuhan sementara kita tidak mempercayai
49
informasi yang diberikan-Nya? Lalu kepada siapa lagi kita menaruh kepercayaan?” jawab
Fidel. “Apa Riang pernah disuntik?” tanyanya.
Riang tidak melihat adanya keterkaitanan antara suntik menyuntik dengan
kepercayaan terhadap Tuhan, namun ia berusaha mengikuti alur pembicaraan.
“Pernah.”
“Di mana?”
“Di tangan.”
“Berapa kali?”.
“Di tangan sekali, di pantat berkali-kali! Aku tidak menghitungnya. Sebegitu
pentingkah?”
“Sebegitu pentingkah pantat, maksudmu begitu?”
“Ya bukan to Mas!”
“Maksudmu, sebegitu pentingkah keterkaitan antara disuntik dengan kepercayaan
terhadap informasi yang diberikan Tuhan?”
Riang lega, orang yang ia pikir kehilangan fokus pembicaaraan ternyata mengerti
sepenuhnya apa yang akan dibicarakan.
“Kau akan mengerti kaitannya, tetapi sebelumnya mari kita sistematikakan dulu.”
pandu Fidel. “ Tetap di lanjutkan?” tanyanya.
“Ya.”
“Sehabis disuntik pernahkah Riang bertanya mengenai racikan bahan kimia apa yang
dimasukkan dokter ke dalam tubuh Riang?”
“Tidak. Untuk apa bertanya?”
“Bukan untuk apa, tetapi mengapa, mengapa tidak menanyakannya?!”
“Sebab aku percaya penuh pada dokter.”
“Mengapa harus percaya penuh, padahal banyak dokter yang melakukan praktik ilegal,
praktik gelap. Padahal, banyak dokter yang menyuntik cairan kimia yang salah dan membuat
penyakit seseorang bertambah parah.”
“Dokter di desaku pintar dan baik,” sergah Riang. “Tidak pernah satu orang pun yang
bertambah parah setelah diobati olehnya!”
Fidel tersenyum, “Riang mempercayai dokter, karenanya Riang menganggap tidak
perlu untuk bertanya: mengenai bahan kimia apa yang dimasukkan dokter ke dalam pantat?”
“Ya”.
“Nah, sekarang kembali ke pokok permasalahan yang kita bicarakan: mengapa Riang
tidak mempercayai sesuatu yang di sampaikan Pencipta manusia, mengenai suatu hal
50
sementara Riang malah lebih mempercayai yang diciptakan-Nya?”
“Mempercayai yang diciptakan-Nya? Mempercayai siapa?”
“Orang-orang yang membicarakan wujud mahluk halus ciptaan Tuhan?”
Riang diam.
“Apa mungkin kita menuduh Tuhan berbohong berkenaan dengan informasi yang
disampaikan-Nya, sementara kita mengakui bahwa dia Pencipta manusia?”
Riang menggaruk kepala, “Oh iya, tapi ...”
“Tapi apa?”
“Bagaimana kalau kita tidak mengakui adanya Pencipta manusia?”
“Kalau tidak mengakui adanya Pencipta, wajar jika dia tidak mempercayai informasi
yang diberikan Tuhan. Karena baginya Tuhan tidak ada.”
“Berarti dia tidak mempercayai keberadaan dan wujud mahluk halus?”
“Itu wajar. Bagaimana mau mempercayai keberadaan mahluk halus terlebih
wujudnya sementara mempercayai Tuhan yang menciptakan mahluk --termasuk diantaranya
mahluk halus-- saja tidak?"
Riang berpikir lama. “Lantas,” tanyanya, “informasi dari Tuhan mana yang dapat
kupercaya.”
Fidel menganggap pertanyaan itu sebagai sebuah kejutan. Riang cerdas.
“Banyak orang yang mengatakan bahwa kitab yang dipegangnya adalah kitab
informasi yang paling terpercaya. Artinya kitab yang di pegangnya dianggap sebagai
sebenar-benarnya kitab suci ciptaan Tuhan untuk mengatur dan memberikan informasi gaib,
termasuk mahluk halus pada manusia. Maka, ketika ada banyak orang yang mengatakan
kitab suciku adalah kitab suci ciptaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan?”
“Aku tidak tahu.”
“Membandingkan!”
“Membandingkan?”
“Ya! Membandingkan, meneliti kitab suci yang mana yang sesungguhnya ciptaan
Tuhan atau malah reka-rekaan manusia belaka,” Fidel memperhatikan wajah Riang yang
bersinar.
Riang mendapat pencerahan.
“Kau memahami bagaimana manusia menemukan alur untuk mempercayai
keberadaan sesuatu yang gaib, bukan saja mengenai mahluk gaib, tetapi juga mengenai
surga, neraka bahkan awal penciptaan manusia dari mana?”
Riang berpikir hingga semenit. Fidel membiarkan.
51
“Aku memahaminya,” ucap Riang tiba-tiba.
“Dan kau memahami alur fikiran manusia yang tidak mempercayai hal gaib?”
“Setidaknya faham sedikit Mas.”
“Sedikit juga tidak apa!”
Riang kembali menghirup teh yang sedari tadi ia biarkanmenganggur.
“Mas?”
“Apa?”
“Saat kita percaya keberadaan mahkluk halus melalui informasi yang disampaikan
kitab suci-Nya, lalu bagaimana cara kita mempercayai keberadaan Tuhan? Kepercayaan
terhadap Tuhan disandarkan pada apa?”
“Disandarkan pada alam semesta menggunakan kekuatan akal kita,” jawab Fidel
gembira. Pertanyaan Riang mengejutkannya lagi.
“Mengapa untuk mengetahui keberadaan Tuhan kita harus menyandarkan pada alam
semesta menggunakan kekuatan akal? Mengapa bukannya dengan panca indera?”
“Mengetahui keberadaan alam semesta menggunakan apa?” tanya Fidel tersenyum
memahami.
“Menggunakan Indera?”
“Benar! Menggunakan telinga, penciuman, penglihatan. Dan salah satu syarat untuk
menjalankan akal dengan baik ialah menggunakan hal hal tadi, menggunakan perangkat
indera. Kamu mempercaya Tuhan?”
“Aku mempercayainya!”
“Lantas Kau mempercayai keberadaan Tuhan dengan apa?” Fidel menguji.
“Aku tidak tahu! Tetapi yang kutahu alam semesta itu teratur. Dan apa pun alasannya
keteraturan selalu ada yang menciptakan.”
“Alam semesta memang teratur sehingga terkesan mustahil jika terjadi dan muncul dari
sebuah kebetulan. Sebagai contoh, ada beberapa angka yang dianggap membuktikan
penciptaan yang tak mungkin kebetulan. Dan ini harus diuji.” Ujar Fidel. “Contoh ini sedikit
klasik.”
Fidel mengambil penggaris pita di dalam tabung hitam. Ia meminta Riang berdiri.
Riang mengikuti arahannya. Ia mengambil penggaris untuk mengukur tinggi badan,
kemudian membagi dengan jarak pusar ke telapak kaki; mengukur pinggang ke kaki dan
membagi dengan panjang lutut sampai kaki; membagi panjang jari dan membagi dengan
lekuk jari; yang terakhir, membagi panjang pundak ke ujung kaki dan membaginya dengan
siku ke ujung jari.
52
“Hasilnya: selalu 1,618: phi” ucap Fidel.
Riang terperanjat amat sangat. “Menakjubkan!” teriaknya. “Mengapa bisa seperti
ini?”
“Mengapa? The golden number of human life Fibonaci jawabannya. The golden
number of human life, merupakan bukti keberadan Arsitek Agung penciptaan. Semua
manusia kalau diukur seperti itu hasilnya, sama.”
“Mungkin Tuhan menggunakan penggaris saat menciptakan manusia?”
Fidel tertawa. “Dan menggunakan millimeter blok untuk menggambar cetakan wanita
cantik,” sambutnya.
Riang menggelengkan kepala berulang-ulang. “Menakjubkan! Me-m-menakjubkan!”
“Jangan dulu bahagia!” Fidel kembali mengetes Riang. “Latas, bagaimana dengan
manusia cacat yang tak memiliki jemari tangan dan kaki untuk membuktikan adanya angka
fibonacci? Apa mereka tak menakjubkan juga?”
Riang tak dapat menjawab. Penemuan yang membahagiakan itu dihantam palu.
Kebahagiaannya melesak hingga ke dasar bumi.
Fidel tidak mau membiarkan Riang kebingungan. Ia segera mengangkatnya kembali.
“Riang ...” ujar Fidel. “Manusia tak begitu memerlukan angka fibonaci untuk
membuktikan keseriusan penciptaan. Susunan saraf yang ada di dalam tubuh orang cacat, di
dalam aliran darah, di degup jantung mereka membuktikan betapa rumitnya proses
penciptaan. Alam semesta, termasuk manusia di dalamnya, tidaklah terjadi secara kebetulan
seperti saat kita mendapat lotre”.
Riang merasa lega, namun ada lagi yang hendak ia pertanyakan. ” ”Mas?”
”Ya?”
”Maaf ...” Riang bertanya hati-hati. ”Agama yang Mas Fidel anut, apa?”
”Memangnya kenapa?”
”Hanya ingin tahu saja.”
Fidel mengatur nafas. ”Menurut bahasa, agamaku bermakna damai. Islam berarti
damai.”
Mendengar kata damai Riang tiba-tiba terkena setrum! Bukankah suara yang
menghantuinya itu menambahkan perkataan:
M a s u k ke d a l a m k e d a m a i a n.
R i a n g ... D a m a i Riang!
M a s u k d a l a m k e d a m a i a n.
R i a n g ... D a m a i Riang!
53
Sesuai dengan apa yang Fidel sampaikan. Riang tenggelam di dalam arus deras
pikirannya. Ia tak begitu memperhatikan lagi apa yang Fidel sampaikan. Kata damai terus
menerus mengiang-ngiang di telinganya. Memompa jantungnya, mempercepat aliran darah
di aortanya dan membangkitkan perasaan yang tak menentu. Mata Riang melompong!
Pandangannya kosong!
KEMARIN SORE Kardi masih berharap bisa menyusul sasarannya, tetapi ketika
kabut datang menyandung harapannya menjadi pupus. Kabut mengaburkan semua benda.
Jangankan menemukan kedua pendaki, untuk pulang pun mereka kesulitan. Sore datang dan
kabut tak jua hilang. Malam datang dan kabut menghilang. Ketiadaan senter memaksa
gerombolan itu menginap. Mereka menebasi ranting pepohonan, mengumpulkan dedaunan
untuk mereka jadikan atap bivak.
Pagi harinya, kekesalan memuncak! Malam dingin yang memaksa Kardi untuk tidur
bertumpuk-tumpuk bersama anak buahnya membuat Kardi mengutuk. Ia menghabiskan
seluruh perbendaharaan makian. “Asu!” teriaknya.
Kardi membangunkan beberapa orang anggota gerombolan yang mendengkur. Dalam
perjalanan pulang, pepohonan menjadi sasaran goloknya. Kardi membacok mereka. Sampai
di kaki gunung, penduduk kampung menjadi pelampiasan kemarahannya.
Gerombolan Kardi membuat onar.
54
PULANG
Setelah mendengar kata damai yang dikatakan Fidel, Riang berjibaku menghilangkan
sejuta macam pertanyaan yang mengganjal pikirannya. Ia bingung: mengapa di kepalanya
antri pertanyaan yang ingin keluar dari loketnya? Mengapa sejak kenal mereka pertanyaan-
pertanyaan yang dulu ia penjarakan kabur melarikan diri dan menemukan kebebasannya?
Jeruji dibobol. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah maling yang merongrong kenyamanan
hidup Riang.
Sejak Riang menyelesaikan sekolah menengah atas, sejak ia pulang dari Yogya ke
Thekelan pertanyaan-pertanyaan menghilang untuk sementara tetapi ketika Pepei meracau di
jalan setapak, di dekat pohon mati, pertanyaan-pertanyaan itu kembali mengendap-endap
seperti copet. Pertanyaan-pertanyaan itu tengah menunggu Riang lengah. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut menyerupai gerilyawan Siera Maestra saat menjatuhkan rezim Batista.
RIANG MASIH MELAMUN saat Pepei menyerahkan dua ekor ikan pada Fidel.
Riang merasa tidak nyaman. Ia bangkit, membantu Fidel memasak satu ikan lagi. Usai
sarapan mereka berkemas..
Meninggalkan danau, Riang tidak mendengar suara aneh sekedar untuk mengucapan
selamat jalan. Danau yang Riang lihat untuk pertama dan terakhir kalinya itu menghilang.
Hanya ceritanya saja yang hidup dari mulut ke mulut, dari kicau ke kicau: menjadi obrolan
para pendaki dan setiap penduduk desa. Ketiga orang itu berjalan perlahan menembus
belantara. Parang berpindah tangan saat seorang di antara mereka kelelahan, karenanya, yang
memimpin jalan pun bergantian.
Tantangan terberat selama tersesat hanya pada saat mereka melipiri jurang yang
dalam. Selanjutnya tak ada masalah kecuali sepatu karet Riang yang menyebabkan kakinya
koyak. Kaki Riang lengket mengeluarkan bau tak sedap. Pepei mengambil tindakan. Ia
mempelester kaki Riang dan melapisinya dengan kain katun dan wol. Riang merasa
langkahnya menjadi nyaman, rasa sakitnya berkurang.
Beberapa jam kemudian, ketiga orang itu sudah melewati vegetasi khas pegunungan.
Ketika sebuah semak duri berbuah warna warni mereka sibak, perjalanan pulang menemui
55
titik terang. Jalan setapak yang semula Riang kira jalan air, memandu ketiga orang itu
menuju arah perkampungan. Semua keletihan dan ketidak pastian musnah saat mereka
melihat genting warna hitam terpanggang matahari. Di tempat itu kumpulan ternak mulai
tampak sebesar potongan lidi. Pemandangan ini membuat orang yang tersesat kembali
merasa berbudaya. Pemandangan itu membuat mereka tentram. Dan dari bukit terakhir pun,
suara sungai kecil terdengar berdenyar. Sampai di sana mereka berleha-leha di alirannya.
Ketiga orang itu memakan biskuit, meminum air hujan dan mencampurnya dengan sirup.
Usai rehat cukup lama, mereka kembali berjalan. Sore harinya ketiga orang itu sudah sampai
di perkampungan.
Riang tak mengenali perkampungan yang ia lewati, sebab memang perkampungan itu
jarang dilewati pendaki. Penduduknyapun merasa janggal melihat tiga orang tiba-tiba
berjalan beriringan. Biasanya iring-iringan yang mereka lihat adalah iring-iringan tukang
panggul kantung mayat.
Di gerbang kampung, energi mereka isi. Ketiga orang itu melahap nasi dan lauk pauk
sederhana, namun –nasi dan lauk pauk itu-- mereka rasakan paling nikmat sedunia. Dan di
warung itulah desas desus mengenai munculnya gerombolan residivis yang mengacau desa
Selo terdengar siaranya. Sekitar jam sembilan tadi, berita di radio menginformasikan bahwa
ketika gerombolan membuat kekacauan, tak ada yang melawan sebab saat itu ketika
gerombolan –yang diberitakan radio berjumlah puluhan orang datang-- hampir seluruh lelaki
dewasa tengah berada di lahan pertanian. Berita di radio diulang-ulang hingga menjadi topik
pembicaraan yang paling hangat hari ini.
“Iki lho! Iki lho beritane, ini lho. Ini lho beritanya!” pemilik Radio berteriak antusias
sewaktu duri ikan pindang selip di geraham Riang.
Jumlah orang-orang yang mengacau kampung terdengar terlalu berlebihan. Jumlah
gerombolan hanya belasan orang.
Keresek ... keresek... keresek
“Mboten jelas Pak! volumene di agengaken. Kurang jelas Pak! Volumenya
diperbesar!” pinta Riang.
Keresek ... keresek ... Volume radio diperbesar.
Sejak tadi siang aparat kepolisian bergerak. Dalam investigasinya, radio menyiarkan
langsung komentar korban. “Dasar mucikari!” kata seorang perawan kampung yang diisengi
perabotannya. Wanita lain yang mengaku rambutnya dijambak dan seorang ibu yang
ditendang, memaki-maki. “Polisi harus segera menangkap bajingan-bajingan itu!” kata dua
orang pemilik warung yang tabungannya dibobol.
56
Berita selesai. Penyiar menjanjikan kabar terbaru beberapa saat ke depan dan di saat
berita beralih menuju berita harga kol dan jantung pisang, dahi Pepei tiba-tiba mengkerut.
Bukan, bukan dikarenakan pemberitaan radio. Sesuatu yang menjalar di pangkal paha Pepei
membuatnya gatal. Seekor binatang –menyerupai lintah—menempel di sana. Pepei mencabut
lalu meletakkan binatang itu di tanah. Ia meminta satu kantung plastik air panas pada pemilik
warung. Pepei meletakannya di kantung celana untuk merredakan gatal. Setelahnya barulah
mereka turun dari perkampungan menuju jalan aspal.
Dalam perjalanan itu Riang membujuk Pepei dan Fidel agar tidak mengantar dirinya.
Ia mengkhawatirkan keselamatan dua orang, yang sebenarnya lebih banyak menyelamatkan
dirinya. “Mengenai jam yang ketinggalan, biar kuantar,” ucap Riang membujuk. Tetapi,
kedua orang itu tetap bersikukuh.
“Ini bukan tentang jam,” elak Fidel “Jika gerombolan Kardi mencegat, apa yang
akan Riang lakukan jika sendiri melawan lima belas orang? Jika bertiga, setidaknya
gerombolan itu akan berfikir dua kali untuk menyerang?”
Tentu saja. Pepei menambahkan.
“Mungkin, kita tidak sanggup melawan mereka semua, tapi semakin banyak jumlah
orang yang melawan, semakin banyak pula waktu yang bisa kita ulur?”
“Mengulur apa?” tanya Riang.
“Memberi kesempatan agar penduduk Thekelan memberi pertolongan.”
Tak ada lagi yang bisa Riang lakukan. Ia tahu pernyataan mereka tak mungkin bisa
digubrisnya. Pernyataan kedua orang itu merupakan keputusan yang fix.
Riang segera menghentikan bus yang melaju di jalan aspal. Mereka berada di
dalamnya hingga dua jam perjalanan. Ketika sampai di pasar Kopeng bus berhenti. Ketiga
orang itu turun lalu berjalan melewati gerbang wisata. Mendung di lokasi wisata Kopeng
menyebabkan suasana menjadi suram. Riang menemui penjaga. Ia yang sudah Riang kenal
bertahun-tahun tidak tahu menahu mengenai peristiwa yang terjadi di Selo tadi pagi. Penjaga
yang dahulu pernah tinggal di Thekelan tidak melihat gerombolan Kardi memasuki lokasi
wisata tempatnya bertugas.
Ketiga orang itu berjalan lagi, naiki tangga tanah sambil sesekali menyapu pandangan
ke segala arah. Tak ada yang mencurigakan namun Riang belum yakin selamat hingga ia
melewati gerbang kuburan. Kabar baik dari penjaga Kopeng tidak menyurutkan
kekhawatirannya. Riang bukan saja khawatir akan keberadaan gerombolan Kardi. Gerbang
kuburan yang nanti akan mereka lewati mengingatkan dia pada bisikan yang membuatnya
sulit pejamkan mata.
57
Gerbang kuburan semakin dekat, ratusan nisan tampak kusam dan mengerak Angin
mendorong pohon-pohon sampai doyong. Suara krak yang ditimbulkan mengingatkan Riang
pada tulang yang patah.
Di tempat itu segalanya tampak mencurigakan dan ... sebuah suara pekak tiba-tiba
menjadi sangsakala yang seolah menggulung tulang ekor Riang. Seorang lelaki yang
dikenalnya muncul dari balik semak.
“Setan alas!” mata Kardi terbelalak, melalap. “Rupanya anak setan ini yang membuat
semua kacau! Asu!”
Seorang lelaki mengelus brewoknya, anggota gerombolan yang lainnya melompat
keluar dari semak-semak di pinggir jalan setapak. Lima belas orang mengepung. Empat
orang lelaki memegang pentungan kayu, lima lainnya memegang golok, senjata sisanya
kepalan tangan.
Riang merasa tulangnya dipresto. Tulang punggungnya tiba-tiba rapuh, kekurangan
zat kapur.
“Kalau tidak mau mati, jangan melawan!” Kardi memperingatkan. “Serahkan barang-
barang Kalian!” Kardi berteriak mengancam Pepei dan Fidel, lalu menunjuk Riang. “Untuk
Asu yang satu itu!” Goloknya ia mainkan. “Aku akan memberinya pelajaran yang tak
mungkin dilupakan! Kau akan mengisi sisa hidupmu dengan penyesalan!”
Kardi hendak membuat cacat.
Ancaman itu membuat Riang tak mampu gerakkan badan. Ancaman adalah sirap. Tak
terpetik keinginan Riang untuk melawan. Ia mendadak mencium bau kemboja. Riang merasa,
dirinya tengah dimasukan ke dalam keranda. Riang hanya bisa menaruh harapan. Ia hanya
bisa memandang, meminta tolong dan menatap. Tetapi apa yang Riang harap? Ia tak melihat
adanya indikasi Pepei dan Fidel akana bergerak. Kedua orang itu malah meletakan ranselnya
di tanah.
Lelaki yang perkataannya tentang mahluk halus demikian meyakinkan, kini Riang
saksikan --dengan mata kepalanya—sendiri, gemetar. Lutut kaki Fidel tampak bergerak
secepat jarum mesin jahit. Yang lebih tak bisa dipercayai, lelaki lain yang sok-sokkan
bersabda tentang kegunaan pohon tumbang, yang belagak bicara kematian: o kematian
adalah kepastian, o apa yang akan kita hadapi setelah kematian, o dan o berlagak seolah jalan
setapak adalah panggung teater itu, membuat Riang ingin hoek sor! Yang berarti muntah.
Pepei sok-sok-an itu kencing di celana.
Gerombolan Kardi tertawa.
“Badan dan muka boleh keren, tapi kelakuan? Kayak banci!” Teriak Kardi mengejek.
58
Riang kecewa. Mengapa bisa seperti itu? Dimanakah janji mengulur waktu, sebelum
penduduk desa datang membantu? Kepercayaan Riang akan keberanian ke dua orang itu
wafat. Riang ingin menangis, namun ... tiba-tiba ... di detik-detik yang tak mungkin ia duga,
sebuah senter terbang dan menghantam! Bersamaan dengan itu, ketika Pepei melempar
ranselnya, sebuah tas kecil berwarna coklat terjatuh. Pepei segera mengeluarkan parang dan
mengayunkannya menuju bahu lelaki bertubuh paling besar. Lelaki itu mengelak lalu
membuat sabetan ke arah kepala.
Pepei menghindar. Ujung golok tipis membeset wajah. Ia tak merasakan apa-apa,
luka itu terlampau ringan. Dan jeda waktu antara sabetan dan tarikan tangan itu lantas Pepei
manfaatkan. Ia menyerang balik dan “Krak!” Bunyi tulang terdengar patah. Tak ada darah
yang memancar. Pepei belum mengeluarkan parang dari sarungnya, namun dua orang sudah
terkapar.
Di sisi lainnya, senter yang sebelumnya Fidel lempar membuat anak buah Kardi
terhempas di tanah. Di tangannya alat penerang itu menjadi senjata yang berbahaya. Usai
menghantam satu kepala lagi, senter yang ada di tangan Fidel hancur berkeping. Tak ada lagi
senjata, namun Fidel tak mau memberi kesempatan bernafas. Ia meringsek dan memukul satu
lelaki lain dengan tangkas! Ia bergulat di tanah dengan seorang yang –tubuhnya—lebih kecil
darinya. Beberapa pitingan dan bogem ke arah dagu membuat penjahat bertubuh kecil
pingsan.
Di tengah-tengah kejadian yang begitu cepat, Riang tersulut. Ia kalap. Ketakutan
membuatnya nekat. Ia menyabet pinggang anak buah Kardi yang bertubuh tambun. Usus
yang terburai membuat lelaki itu kelojotan hampir mati.
Lelaki brewok yang Riang temui di gerbang kuburan ia kejar. Ia menebas golok di
lambung. Lelaki brewok berkelit cepat. Parang Riang menggombang angin.
Peristiwa yang begitu cepat terjadi membuat gerombolan Kardi mundur dan tak lagi
mengelilingi mereka rapat. Lima orang telah terkapar di jalan, dan semak-semak. Keraguan
mulai mengganggu gerombolan yang tersisa. Mereka tak mau lagi bertindak gegabah.
Mereka mulai menaksir kekuatan lawan, dan saat taksir menaksir itu terjadi, akal Riang yang
beku mulai mencair.
“Tolong! Toloooooooong, begal! Ada begaaaaaaall!!” pita suara Riang bergetar
hebat. Teriakan pertama mengantarkan dua orang petani yang melengkapi dirinya dengan
pacul dari lokasi wisata Kopeng. Teriakan kedua membawa seorang ibu penggarap lahan
kentang. Clurit berada di genggamannya.
Kardi bimbang. Ia dan gerombolannya kebingungan.
59
Riang terus teriak. “Begaaaaall! Toloooooooooooong! Ada begal!” Teriakan Riang
yang terakhir disambut kentongan dari arah Thekelan.
Keputusan diambil.
Gerombolan Kardi surut. Kardi menyuruh anak buahnya berlari masuk ke dalam
hutan. Lelaki berewok segera memungut tas coklat yang terjatuh saat Pepei melemparkan
ranselnya. Bersama Kardi, ia menyusul sisa gerombolan. Kedua orang itu memotong lahan
pertanian bersama delapan orang lainnya. Dari kejauhan Kardi berhenti. Ia berteriak
mengancam. “Riang!! Lusa Kau pasti mampus di tanganku!”
Kemeja planel Kardi berkibar sebelum tubuhnya menghilang.
DARI ARAH THEKELAN kerumunan orang lari membawa macam senjata. Sisa
anak buah Kardi yang terkapar menjadi bulanan penduduk desa. Beberapa orang hampir mati
setelah kepalanya diadu dengan batu. Polisi kemudian datang memisahkan.
Mereka langsung menggiring lima pesakitan menuju bak mobil di pintu wisata
Kopeng. Di tempat itu mereka menyusun siasat: memobilisasi masyarakat untuk mengadakan
penyisiran.
Hingga beberapa hari kemudian, penyisiran tak menghasilkan apa pun juga, namun
kini, peristiwa dikalahkannya gerombolan menyehatkan kepercayaan diri penduduk
Thekelan. Jika gerombolan Kardi dibekuk oleh tiga orang, bagaimana hal nya jika orang-
orang satu desa bersatu meringkus mereka?
SORE SETIBANYA di rumah, bapak memeluk Riang erat-erat. Di ruang tengah
ibu menggamit langannya. Pada wajah Riang ibu meletakkan pipinya yang dicucuri air mata.
“Ndak kurang apa pun Bu... ndak kurang apa pun...” sahut Riang menenangkan. Di luar
rumah, ia melihat Fidel dan Pepei diinterogasi tentang ihwal kejadian oleh aparat kepolisian.
Mereka dikelilingi penduduk desa yang mengharap datangnya kisah perkelahian yang hebat.
Kedua lelaki itu berusaha meminimalisir peran yang mereka lakukan. Dan hal ini membuat
banyak penduduk desa kecewa.
Malam hari itu, sebenarnya Riang ingin mendengar kembali, ia ingin mengulangi
lagi kejadian yang telah mereka alami bersama. Tetapi sehabis makan ikan yang mereka
dapatkan di danau Merbabu, kedua orang itu tidak membicarakan hal yang Riang inginkan.
Mereka tertidur begitu saja, seolah-seolah mengalami hal yang biasa terjadi.
Esok hari, tepat jam delapan pagi Fidel dan Pepei memutuskan pergi. Riang
kemudian menyerahkan jam tangan Fidel yang tertinggal. Di gerbang kawasan wisata
60
Kopeng, mereka berpisah. Kedua orang sahabat itu Riang dekap erat. Mereka membalasnya
dengan peluk erat dan genggaman tangan yang rekat.
“Sampai jumpa lagi Mas!” ujar Riang. “Suatu saat nanti, mungkin aku akan
mengunjungi Mas di Yogja.” Lalu Riang beralih ke arah Fidel. “Mudah-mudahan Mas Fidel
senantiasa sehat dan bisa lekas kembali ke Thekelan!” katanya.
Fidel tersenyum dan entah mengapa Riang tiba-tiba tertawa. “Lain waktu bukan aku
yang ke Thekelan. Lain waktu Riang yang akan ke tempatku?”
Mobil kemudian berjalan perlahan. Sesekali klaksonnya terdengar. Dari kejauhan
Riang melihat tangan Pepei keluar dari jendela angkutan. Lelaki itu membuang kantung
plastik transparan ke dalam bak sampah. Terulang dalam ingatan Riang, kilasan peristiwa
saat Pepei memasukkan air panas ke dalam kantung celana untuk meredakan gatalnya.
Riang tertegun. Ia tak sadar menepukkan tangan di jidatnya! Riang menginsyapi.
Riang bersyukur. Lelaki itu ... Pepei, mengetahui benar, betapa pentingnya fungsi toilet
umum.
Riang sungguh-sungguh bersyukur.
MITOS
Sejak Fidel dan Pepei meninggalkan Thekelan etos kerja penduduk desa meningkat.
Keberanian membuat aura desa benderang, akibatnya banyak yang berubah. Thekelan yang
61
semula sepi menjadi ramai. Wartawan radio dan surat kabar Yogyakarta, berbondong datang
meminta penjelasan rinci perihal perubahan itu. Mereka mencoba menggali peristiwa
perkelahian yang terjadi di gerbang kuburan juga di danau Merbabu, Dan dari sekian banyak
informasi yang diberitakan, tentu ada salah satu yang menyimpang dari kebiasaan. Wartawan
yang seharusnya menerakan fakta di dalam surat kabarnya malah memuat head line “Seorang
Penduduk Thekelan Menemukan Ikan Purba.” Head line surat kabar lokal itu menampilkan
kerangka ikan.
Seingat Riang, tulang ikan danau Merbabu yang ibu masak untuk syukuran
dibuangnya di bak sampah. Riang tidak tahu keesokan harinya wartawan yang
mewawancarainya meminta Oerip mengubek tempat sampah. Tulang ikan yang Oerip
dapatkan itu lah yang dicetak surat kabar sebagai penguat judul headline.
Riang Merapi, bukan saja menemukan ikan purba. Riang Merapi berhasil menemukan
danau gaib, danau misteri dengan kekuatan supranaturalnya. Ia memiliki ilmu suci, ilmu
alam akhirat guna menerawang objek kasat mata.
Pemberitaan bombastis tersebut menggembol imbas psikologis yang tak disangka.
Thekelan mendadak diluberi ratusan peziarah dan paranormal dari ujung barat hingga ujung
timur pulau Jawa. Penjual mie pangsit, es campur, air keramat, pakaian, mainan anak dan
batu akik, tumplek di sana, di sekitar rumah Riang. Akibatnya banyak peristiwa membuat
Riang kerepotan. Pemilik warung yang dulu Pepei mintai seplastik air panas untuk redakan
gatal datang memintanya meridloi penjualan plastik berisi air berkah di halaman depan
rumahnya. Riang mempersilahkan tetapi tentu saja tidak di halaman depan rumahnya yang
sesak.
Seperti halnya entrepreneur kawakan, pemilik warung tak patah arang mendapat
penolakan. Ia berusaha, datang saban minggu terus menerus membawa sebungkus rokok,
kopi sebagai sesaji agar Riang bukan saja meridloi tetapi merestui. Pucuk dicinta ulam pun
tiba, setelah lima kali bolak balik Riang tetap bersikukuh. Lelaki itu harus merelakan diri
menjual air plastik bermerek Air Keramat Danau Merbabu di depan Wihara.
Usaha pencarian danau keramat terus menerus di lakukan. Bersamaan dengannya
mitos baru muncul. Di dasar danau Merbabu bersemayam azimat Majapahit yang akan
membangkitkan kharisma menyerupai kharisma presiden dan wakil presiden NKRI yang
utama: Soekarno – Hatta. Azimat akan mengucurkan karomah gamelan yang bernama Kyai
Pinurbo Joko hanya untuk penemunya seorang! Azimat adalah khadam pengganti doberman:
tak akan ada lagi wadam yang mengganggu kenyamanan hidup dengan bas betotnya. Tak ada
lagi penjaja serbuk abate! Tak ada lagi godaan duda dan baby sitter nakal yang tidurkan anak
62
majikan dengan ctm! Sirna sudah loyo! Hilang bala dan marabahaya! Hidup keharmonisan
keluarga!
Penjual batu akik pun mendompleng berkata-kata, berkhutbah di atas bukit, ajarkan
moralitas terkutuk. Ini bukan khurafat! Batu akik dilirik! Ini sejalan dengan ajaran sunan Kali
Jaga! Batu akik dibeli! Ini serpihan sisa batu hitam hajar aswad! Batu akik laris mensugesti
peziarah hingga ke alam akhirat. Batu akik adalah radar, lampaui endusan terwelu dan
musang! Adalah penuntun yang mempermalukan gprs! Inilah batu yang akan menuntun
kalian wahai saudara! Wahai umat! Duhai pengikut arwah Nyai Blorong dan bung-bung
penganut ajaran setia Murba Tan Malaka!
Sampai berbusa-busa, sepercaya apa pun orang terhadap tuah, tak seorang pun
berhasil menemukan azimat. Penjual batu akik yang ahli memanipulasi psikologi masa
akhirnya ditimpa sial. Dari arah Merbabu, seorang bapak bercelana sontog turun
bersemangat. Ia yang membeli batu akik berkali kali, tanpa cang tanpa cing dan cong
langsung melayangkan jotosan yang membuat ketupat di dalam perut remek. Penjual batu
akik kelenger, pingsan setelah mental setengah meter. Ia segera di larikan menuju klinik
pengobatan terdekat.
Penjual batu akik yang naas hilang, namun busa busa dan kecapnya masih bisa
Riang rasakan. Satu minggu kemudian sebuah mercedes benz hijau metalik berhenti tepat di
depan halaman rumah.
Seorang lelaki tegap keluar dari pintu depan, tergopoh-gopoh keluar, menuntun
seorang ibu turun dari pintu belakang. Wangi parfum si ibu tercium hingga kediaman
Hamengkubuono lima.
“Rumah Mas Riang Merapi dimana?” Tanya lelaki tegap.
Menggunakan jempol penjual nangka menunjuk. “Di atas Pak.” katanya.
Mengetahui ada yang mencarinya, Riang bergegas masuk ke dalam.
Beberapa detik kemudian suara dehem merayap di ruangan tengah.
“Ehem! Pemisi ... kulonuwon!”
“Monggo.” Riang melihat wanita setengah baya melihat-lihat keadaan.
“Benar, ini rumahnya Mas Riang Merapi?” Tanya lelaki itu tersenyum melihat
cecak di atap rumah.
“Bukan! Di sini bukan rumahnya Riang Merapi!”
“O, saya sangka...” lelaki itu membetulkan kerah jas. “Maaf kalau begitu.” Ia
berbalik namun sang ibu gerakan kepala memberi kode.
“Adik kenal Mas Riang Merapi?” Sang ajudan menghadap Riang kembali.
63
“Kenal.”
“Rumah beliau dimana ya?”
“Ya disini.” Riang geli dipanggil beliau.
Kalau di desa ini, tentu tahu, tapi kediaman pasnya beliau saya ndak tahu. Adik bisa
tunjukkan rumah beliau?” tanya sang ajudan sopan.
“Ya di sini!”
“Disini dimana?” Si ibu hilang kesabaran.
“Ya di sini! Saya Riang Merapi.”
“Oladalah ini Mas Riang?” Sang ajudan terkejut. “Lagi berkunjung ke rumah
teman?” Tanyanya.
“Ini rumah orang tua, saya belum punya rumah.” Jawab Riang.
Sang ibu melepas kacamata hitam, mengeluarkan tangan kanan menggenggam
tangan Riang erat.
Riang mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Si ibu menolaknya. Ia datang
hanya ingin memastikan karena tak memiliki waktu panjang. Tapi hukum evolusi mana pun
selalu mengatakan, orang yang membutuhkan akan tunduk pada yang dibutuhkan. Sang ibu
bersama ajudan masuk ke dalam ruang tamu.
Setelah berbasa-basi sedikit Riang langsung menuju pokok permasalahan.
“Ada apa perlu apa, sampai Ibu jauh-jauh datang ke sini?”
“Begini ...” Si ibu membuat jeda. “Sebelum langsung ke tujuannya saya harus
bertanya dahulu.”
Riang membuka telapak tangannya.
“Benar, Mas Riang pernah sampai di danau keramat Merbabu?”
“Bukan saja aku! Dua orang teman ku ikut serta!” Jawab Riang nakal.
“Langsung dengan mata kepala sendiri?!” Ibu itu memastikan.
“Bukan hanya dengan mata, mancing ikan! Saya mancing ikan Bu!” Riang terkekeh
seperti kakek-kakek.
“Bagaimana gambaran danaunya?”
Maka diceritakanlah detail keadaan danaunya.
Usai selesai menceritakan, mendadak sang Ibu menjentikkan jari. “Ctak!” Bunyinya
nyaring sekali.
“Tepat seperti yang dikatakan paranormal Jaka Edan” Katanya bergairah.
“Memang apa katanya?” Riang penasaran.
64
“Beliau bilang di dasar lumpur danau Merbabu tersimpan azimat Majapahit...” bla,
bla bla”
Artinya sang ibu ingin membantu suaminya mendapat azimat untuk membantu
promosi kenaikan jabatan suaminya.
Mendengar itu Riang tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya.
“Uedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!” teriak dia.
Wajah ibu pejabat berubah. Ia mengira Riang menghina diri dan suaminya. Riang
faham, salah sangka dapat berakibat buruk padanya. Ia memutar cara menghilangkan
kesalahpahaman.
“Apa kulit Jaka Edan berwarna coklat Bu?”
Wanita itu tidak tahu arah pertanyaan Riang, tetapi ia menjawab, “Benar!”
“Sudah berapa kali Jaka Edan datangi rumah Ibu?”
Wanita itu menelengkan mata pada sang ajudan.“Sekitar tiga kali ya?”
“Lebih dari itu...” Sang ajudan mengkoreksi. “Kalo ndak salah lebih dari lima kali.”
“Apa selama datang ke sana Mbah Jaka Edan mengenakan blangkon hitam?”
“Ya!” jawab si Ibu.
“Selalu hitam?”
“Cermat!”
“Apa janggutnya dilinting? Pakai baju orang yang sering ke masjid?”
“Baju koko maksudnya?”
“Tidak tahu! Pokoknya warna hitam. Baju yang sering dipake ke masjid?”
“Tepat!”
“Apa cengkoknya seperti logat orang Tegal?”
“Pas!” Sang Ibu sumringah.
“Walah gawat!”
Wajah sang Ibu mulai di warnai kekhawatiran.
“Bagaimana bisa gawat?!”
“Kalau memang Jaka Edan ciri-cirinya begitu! Berarti... berarti ...”
Si ibu mendesak. “Berarti apa!?”.
“Berarti Ibu kena tepu! Ibu ditepuuu!” Riang menahan tawa. “Jaka Edan itu
pedagang batu akik!”
Si ibu stress mendengarnya, apalagi ketika Jaka Edan dipukuli. Wajah si Ibu
merah. Kata-kata kasar tumpah dari mulutnya. ”Ealah. Wueddan! Wewe gombel! Nasi
65
goreng basi! Jus tai kuda! Meses tai cicak! Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah kiamat! Kiamat
aku!”
Mendengar makian-makian aneh yang seumur hidup baru ditemuiya Riang tak bisa
menahan tawa. Mati-matian ia berusaha mengentikan. Ia butuh pengalihan.
“Memang kenapa Bu?” Riang bertanya.
“Uangku ludes buat beli batu akik!” keringat dingin si Ibu bercucuran. Dan kata-
kata makian yang lebih aneh dari semburan yang pertama keluar. “Mas Riang punya
kedigjayaan?” Tanya si Ibu sebelum pingsan.
Riang kebingungan. Apa maksudnya?
“Mas punya keahlian? Atau mungkin punya benda yang mumpuni menambah
kharisma? Tolong suami saya ... tolong” Ibu itu mengemis.
Riang tidak mau berbohong. “Tidak Bu! Aku bukan paranormal seperti ... seperti ...
seperti ... JAKA EDAN!”
Jaka Edan adalah supersonik! Nama itu membuat telinga si Ibu menggelegar. Ia tak
kuat menahannya. Sang Ibu pingsan selama satu jam. Bangunnya ia menangis, bertaubat,
menyesali amblasnya uang duapuluh juta untuk membeli batu akik, bukan! Bukan hanya batu
akik! Tapi batu akik super tuah milik murid terbaik Sunan Bonang.
Mendengarnya, Riang malah dungu bertanya. “Bu ... kalau boleh tahu ... murid
Sunan Bonang itu siapa?”
Si ibu gelengkan kepala. Dan ia pun pingsan untuk yang kedua kalinya selama tiga
puluh menit. Lelaki sopan yang menjadi ajudannya merasa tidak enak, ia tidak mau
merepotkan. Diangkatnya tubuh sang majikan.
Di halaman depan rumah Riang, tiba-tiba sang ajudan mengingat masa-masa ketika
ia masih menjadi buruh angkut pelabuhan. Ia mengingat bagaimana sulitnya mengangkut
karung beras merah di punggungnya.
Riang salut. Jaka Edan istiqomah dengah profesi yang dijalankannya.
Heibat!
MACAM-MACAM KEANEHAN dan kejadian gila yang dialaminya membuat
Riang mengkait-kaitkan kejadian yang ia alami. Informasi bisa mengangkat orang biasa
setinggi-tingginya! Jika pemberitaan membuatnya tenar, pastilah kemahaberanian,
kemahaganasan gerombolan Kardi disebabkan obrolan penduduk yang terlalu berlebihan.
Obrolan itu membuat mereka makin ditakuti, padahal ketakutan yang berawal dari diri
66
sendiri membuat semua lemah terpecah. Jika obrolan dihentikan dan penduduk bersatu
mungkin sejak dulu desa Thekelan akan menjadi aman. Pikiran Riang selalu jauh.
Bisikan Simbah yang membuat kantong kemihnya bocor, entah mengapa tak pernah
mendatangi Riang kembali. Tetapi Riang tak meninggalkan ajakan “simbah” Ia terus
menerus memikirkan maksud dan penyebab hadirnya bisikan tersebut. Ia tak menemukan
jawabannya, hingga ibu menceritakan hal yang memaksanya untuk mengingat kembali.
Di atas kayu yang terbuat dari robohan pohon di dekat Pereng Putih, ibu
membicarakan masa muda Simbah yang ia habiskan dalam pengembaraan. Beliau gemar
mencari tempat menyepi, tempat bersemedi, kata ibu. Tapi simbah berbeda dengan temannya
kebanyakan. Dia orangnya penasaran. Selalu ingin membuktikan apa yang diceritakan
teman-temannya mengenai penampakan.
Teman-teman simbah sempat kesal, sebab setiap mereka menceritakan sebuah
keanehan, simbah yang langsung mencari tempat itu selalu bilang bohong, bohong, bohong.
Teman simbah tidak punya alat untuk menyangkal, tetapi ada waktunya ketika mereka pun
bersorak dan berhuray manakala simbah bertemu Kanjeng Ratu Kidul setelah melakukan
semadhi selama tujuh hari di Parang Tritis.
Sebelum bertemu Kanjeng Ratu Kidul, kata teman teman Simbah bangga, dari laut
terdengar suara-suara gemerincing. Orang-orang berteiak Lampor! Suara kentungan dipukul
keras-keras. Segala macam benda yang berbunyi ditabuh, agar mahkluk halus pengiring
kereta kuda Kanjeng Ratu Kidul tidak merasuki badan. Suasana sepi. Simbah tak peduli, ia
melanjutkan semedi, tapi baru sebentar menutup mata, simbah merasa pahanya ditepuk. Ia
membuka mata dan melihat wanita cantik datang menyerahkan kembennya. Waktu
kembennya Simbah ambil, wanita cantik itu hilang! Begitu pula dengan kembennya.
Pertemuan seseorang dengan Kanjeng Ratu Kidul di mata teman-teman Simbah
merupakan kejadian langka. Sangat-sangat langka. Mereka yang bertahun-tahun mendahului
Simbah dalam melakukan semadhi pun, belum pernah bertemu Kanjeng Ratu Kidul. Meski
pun ingin berjumpa dengan sosok yang diidam-idamkan, mereka tak pernah mendapatkan
barang sekali, atau setengah kali, bahkan seperempat kali pun.
Pertemuan dengan Kanjeng Ratu Kidul akhirnya menjadi perantara antara simbah
dengan seorang pemimpin paguyuban mistis ternama. Adik jadi simpatisan paguyuban kami
saja, katanya. Simbah tidak tahu, dari mana, orang-orang paguyuban tahu ia pernah bertemu
Kanjeng Kidul. Simbah tak begitu peduli. Ia melanjutkan semedhinya sendiri.
Tak tahu lah apa yang didapat dari semedhi Simbah selanjutnya namun teman-
temannya berusaha menerka, menyangka-nyangka.
67
“Waktu kemarin dia baru kembennya, bagaimana kalau dapat yang lainnya?” kata
Mbah Jamus yang menyangka Simbah terkena sirep.
Biar teman-teman Simbah lainnya hampir berpikiran sama, mereka berusaha
mengusir jauh-jauh pikiran semacam itu. “Husy!” kata mereka. “Ojo ngomong koyok ngunu.
Ora ilo. Ngkuk ditekani! (Jangan ngomong kayak gitu. Pamali. Nanti didatangi)”
Teman yang lain yang suka ikut nimbrung tetapi tidak percaya kejadian macam
begitu malah terangsang. “Kalau didatangi. Alhamdulillah, ya tak ajak!”
“Ngajak nyapo?”
“Ngajak iku!”
“Iku opo!?”
...
Tentulah, bincang macam itu berlanjut ke hal-hal yang tak baik buat perkembangan
psikologi anak yang kak Seto kembangkan. Sudahlah. Kekotoran pikiran semacam itu harus
dihentikan. Simbah bersih. Jika pikirannya macam pikiran teman-temannya tentu Simbah
akan mencari tempat semedhi yang penunggunya putri-putri cantik macam Nyi Rambut
Kasih atau Banowati. Simbah tidak berpikir urusan fisik sederhana. Peristiwa di pantai
selatan malah membuatnya ingin menemukan Kanjeng Sunan Gunung Lawu yang selalu
dibicarakan. Tentunya Riang tidak boleh bertanya pada ibu apa simbah punya kelainan? Jika
Simbah punya kelainan, mungkin itu lain soal tetapi kenyataannya setelah ia semedhi dan tak
menemukan sang Sunan, Simbah beranjak menuju sebelah utara hutan Krendawahana. Ia
ingin membuktikan keberadaan raksasa bernama Sang Hyang Pamoni.
Sulit membayangkan ke-dajjal-an dan ke-syaitonirrajim-an Simbah, jika ia bukan
saja bergairah dengan sesama lelaki tetapi bergairah pula sama raksasa.
Riang mati-matian menghapus segala kemungkinan. Ia menolak akalnya bisikan-
bisikan lain yang membicarakan hubungan antara simbah Dengan Buto Cakil.
Tak adala lagi yang terjadi. Tak ada lagi mahkluk halus semenjak pemberian
kemben di pantai selatan membulatkan Simbah untuk mengentikan pengembaraannya.
Teman-teman yang menganggap simbah memiliki potensi tentu tak setuju, mereka
memalangi ketika simbah mulai mencoba menjalani hidupnya yang sehat. Simbah mencari
kerja di Kraton.
“Sebabnya apa?” tanya Riang sewaktu ibu katakan beliau berhenti mengabdi pada
sultan setelah tiga tahun berkerja, kemudian Simbah pergi dan menetap di desanya sendiri, di
bawah kaki Merapi.
68
Ibu tidak tahu penyebabnya, tetapi beliau menyangka karna simbah jatuh cinta sama
nenek Riang. Semua orang termasuk ibu hanya bisa berspekulasi. Yang tahu penyebabnya
hanya Simbah dan Sultan.
Dan di kemudian hari, di kaki Merapi lahirlah ibu Riang meramaikan dunia
Simbah. Setelah cukup dewasa ibu kemudian menikah, bercocok tanam dengan lelaki desa
hingga menghasilkan tanaman yang dalam kelahirannya diharapkan jam tujuh sudah ada
(jam pitu wes ono).
Semua manusia pastilah mengingat waktu yang merupakan pertanda bagi proses
perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Demkianlah dengan kelahiran yang menjadi
penanda. Simbah menganggap kelahiran Riang sebagai sebuah perubahan drastis dalam
hidupnya. Bukan saja ia makin sayang pada keluarga, bukan pula ia jadi sering bolak-balik
ke Yogyakarta sekedar untuk membeli makanan dan pakaian buat cucunya. Sejak Riang
lahir, Simbah menjadi semakin bijak.
Menurut penuturan teman-teman yang masih berharap simbah kembali ke dunia
perkembenan, seorang lelaki berambut kriwil, seorang lelaki yang sering Simbah temui di
Yogyakarta lah yang mempengaruhi cara pikirnya.
Ibu lupa nama lelaki itu. Beliau memutar gelas, berharap putaran itu dapat
mengembalikan ingatannya.
“Siapa Bu?” Riang terus memaksa.
“Sebentar...sebentar” Ibu berpikir keras. “Sebentar lagi dapat.”
“Emha Ainun Najib Bu!?”
“Ndak pasti itu. Tapi eeee....” Ia seperti mengingatnya.
Riang mendesak, “Emha Bu?! Emha?! Simbah pernah bicara dengan Emha?!”
“Ya ndak pasti ...belum tentu! Tapi sepertinya ...”
“Yang benar Bu?!”
Ibu berdiri, masuk ke dalam kamar menemui Bapak.
“Pak..Pak! Yang dahulu meng-islam-kan Simbah siapa?”
“Emha Ainun Nadjib!” Teriak Bapak agar Riang mendengarnya.
“Haaaaaaaaaaaaa!!” Riang melongo. “Emha Ainun Nadjib mengislamkan Simbah?”
Kepala Riang jadi berat seberat-beratnya. Emha pernah mengislamkan Simbah?
Lagi-lagi, suara itu mencor kepalanya.
R
i
a
69
n
g
K e m a r i
R
i
a
n
g
A y o k e s i n i
R
i
a
n
g
A k u i n i
M
b
a
h
m
u
J a n g a n
T
a
k
u
70
t
A y o k e m a r i d a l a m p e l u k a n M b a h.
M a s u k d a l a m k e d a m a i a n.
R i a n g ... D a m a i Riang!
“Kenapa melamun Nak?” Ibu menepuk paha Riang. Riang tergagap.
“Bagaimana kelanjutannya Bu?” Ia menjawab sekenanya.
“Bagaimana bagaimana? Setelah masuk Islam simbah mu ya jadi seperti orang Islam!
Sering shalat. Puasa di bulan ramadhan!” Ibu melihat Riang. “Jangan melamun hei!”
Riang mengusap wajah, mengucek matanya.“Terus bagaimana lagi Bu?”
“Bagaimana, bagaimana?! Yang bagaimana itu kamu Nak!” Ibu suruh Riang ke air.
“Kalau melamun bisa kesurupan!” Ia mengingatkan.
Riang cuci muka ibu melanjutkan cerita. Sampai di bab kepunahan keluarganya cerita
berhenti. Ibu menangis. Riang memeluk tubuhnya. Ia merasa tulang pundak ibu menusuk
dadanya. Ibu semakin kurus. Setelah tangisan reda, ibu melanjutkan cerita, menguak teka teki
mengenai suara misterius yang dulu pernah memanggil manggilnya.
“Sukanya Simbah, sukanya simbah ...” Ibu tertawa geli, “jilati kupingmu Nak setiap
jam delapan pagi.” Tapi, Riang haramkan ikut-ikutan tertawa apalagi ketika mendapat
informasi jika beliau suka membisik-bisikan sesuatu dikupingnya. Sesuatu seperti yang ia
dengan di gerbang kuburan dan danau Merbabu.
Riang bergumul dengan pikirannya. Saat itu, tentunya ia tak mungkin berpikir
tentang teori Freud mengenai alam bawah sadar. Ia tak mungkin menganalisa bisikan itu
mengambang di permukaan kesadaran saat kondisi mentalnya sedang jatuh. Riang cuma
berkata. “O, rupanya itu! Rupanya penyebabnya begitu!”
Apa yang ibu utarakan menjadi bahan perenungan baginya. Inilah yang membedakan
Riang dengan teman-teman sebayanya. Inilah yang menyebabkan Riang acapkali terlihat
bimbang dari segi keyakinan: bingung saat pikirkan alasan mengapa ia harus beragama.
Riang bimbang mendapati fakta.
Untuk apa agama? Sementara, orang-orang yang melakukan kekacauan di dunia,
adalah orang-orang yang menganut agama! Untuk apa agama, sementara, yang
menumpahkan darah di dunia, yang berperilaku amoral adalah orang-orang yang mengaku
memiliki agama! Untuk apa aku memeluk agama jika pemukanya ... jika seorang guru ngaji
mushola dekat sekolahnya digebuk ramai-ramai waktu kepergok menjilat payudara santrinya.
Untuk apa memeluk agama yang pemuka agamanya yang kata Delilah, temannya SMA,
71
pernah bilang, bahwa ada pastur yang kepergok menikmati anal seks dengan biarawati di
gerejanya!
Gila! Mereka yang beragama seharusnya memberi contoh! Riang yakin bahwa agama
tidak bisa mengkontrol manusia! Dan ia terus menerus menghabiskan energi,
mempertanyakan kenapa dirinya harus beragama? Harus melakukan ritual padahal tidak
shalat, puasa, pergi ke gereja, melakukan misa, bersemedi atau ritual macam apa pun juga
manusia bisa hidup. Ia masih bisa bernafas, masih bisa makan minum, dan masih bisa
berhubungan baik dengan sesamanya, teman-temannya.
Perenungan-perenungan itu tidak bersumber dari buku-buku yang ajarkan
epistemologi, tidak pula berdasar penelaahan hermeuneutika yang rumit dan kadang tak bisa
digunakan. Perenungan itu disamaknya dari kehidupan sehari-hari di Yogyakarta dan
mengendur ketika Riang menyelesaikan sekolahnya.
Sewaktu kedua orang itu datang, sewaktu Fidel dan Pepei datang, pertanyaan yang
ada di kepalanya menghantui Riang kembali. Ia merasa harus mempetanyakan, harus
merenungi semuanya. Ia merasa aneh, mengapa Fidel beragama? Mengapa dia meyakini
agama –yang di negeri ini—pengikutnya paling banyak menempati penjara? Mengapa agama
kakekku serupa dengan agama yang dianut Fidel?
Sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala, ketika tak ada
seorang pun yang bisa diajak Riang bicara, berbagi cerita.
Mengapa Riang tidak membicarakan hal ini dengan orang tuanya? Apakah Riang
merendahkan mereka. Tentu tidak, Riang hormat, meninggikan ke dua orang tua di atas
segalanya. Ia sangat mencintai mereka. Cintanya bahkan bisa dikatakan seperti orang-orang
norak kekurangan sumber bacaan yang kemudian mengatakan pada kekasihnya, “Cintaku se
dalam samudera.” Atau cinta kita melebihi tingginya langit.” Lebih kreatif jika mengatakan
cintaku setinggi pohon mahoni, cintaku hingga astana giri bangun (maksudnya hingga
dikubur masih cinta) atau cinta kita sedalam dompet seperti tulisan yang tertera di bak truk
menuju Blora.
Akan tetapi, sesuatu yang norak adakalanya benar. Cinta Riang pada orang tua,
begitulah kenyataannya. Meski dia mencintai mereka, dalam masalah tertentu seseorang
tidak mungkin berbagi. Di keluarganya Riang tidak terbiasa membicarakan hal-hal yang bisa
mengeluarkan keringat darah dan munculkan bintang-bintang di kening. Riang memilih
menyimpan pertanyaan dan perenungan di kepalanya sendiri.
72
Riang keluar mencari udara segar, setelah ia mengkhatamkan pembicaraan dengan
ibu. Ia merokok, memandangi dinding Merbabu yang berkilat seakan dipernis. Di halaman
itu Riang serasa dibisiki.
Mengapa tidak kudatangi Emha, sekalian datangi Pepei saja?
Bisikan itu tidak muncul dari alam bawah sadarnya.
Riang memang harus menyegerakan diri memecahkan krisis eksistensi ini, sebab jika
tidak, sebab jika terus dipendam, bisa-bisa pikiran-pikirannya menjadi humus yang
membusuk di batok kepala. Jika tidak Riang bisa gila. Riang segera habiskan rokoknya.
Masuk ke dalam kamar ia menghitung uang yang di simpannya di kaleng biskuit Marie.
Jumlahnya yang beberapa puluh ribu cukup untuk membiayai hidupnya selama seminggu.
Malam hari, setelah orang tuanya memberi izin, Riang mengemas baju. Bapak
memberi Riang uang panen yang tersisa. Total uang yang ada di dompetnya ternyata cukup
banyak. Cukup untuk berpetualang menuju arah Barat pulau Jawa.
Riang teringat kembali janjinya pada Fidel.
Apa janji itu harus ia tepati?
NURANI
Kardi marah atas kejadian di gerbang kuburan. Lima anak buahnya habis, tinggal
sembilan yang tersisa. Saat mengetahui kabar penyisiran yang dilakukan penduduk desa dan
aparat kepolisian, ia mangkel. “Apa kita ini kutu sampai harus di sisir!” Baskom yang
malang, baskom yang digunakan sebagai wadah sementara tangan dan kaki menjadi mesin
cuci retak ditendang, retak pada hantaman ke dua dan ambrol sepenuhnya pada hantaman ke
lima. Busa cucian terbang, airnya tumpah. Kardi tak mempedulikan. Ia pilin planel dan
celana jeansnya yang kotor oleh tanah. Air mengucur. Ia menjemurnya di bentangan tali
73
rapia. Setelah cuciannya di keringkan oleh angin, Kardi bersama gerombolan yang tersisa
mengungsi dari pegunungan.
Melarikan diri dari penyisiran, mereka berpencar sejak batas akhir hutan. Mereka
menunggu malam untuk sampai di perkampungan, mengendap-endap menuju jalan raya
naiki bison, bis kecil menuju Solo atau menghentikan truk masuk ke dalam bak kayu, menuju
habitatnya semula di Yogyakarta.
Di Yogyakarta, untuk beberapa saat Kardi dan lelaki brewok menghindari pasar
tempat mereka dulu mencari nafkah. Kedua orang ini cukup cerdas. Mereka mengira aparat
kepolisian masih akan melakukan pencarian di tempat-tempat yang mereka pernah singgahi.
Kedua orang itu pun bersembunyi dari satu kontrakan ke kontrakan teman teman lainnya
yang satu aliran. Mereka baru melakukan aktivitas seperti biasa setelah pemberitaan media
massa reda. Keduanya menuju pasar, menumpang bersama preman yang Kardi kenal semasa
SMA. Mereka melakukan aktivitas menjemukan yang dulu pernah dilakukan: menarik uang
parkir sepeda motor, pajak keamanan yang sudah dilakukan belasan tahun oleh preman
sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya kehidupan kedua orang itu berubah setelah seorang
lelaki dari organisasi kepemudaan mendekati mereka.
LANTAS SIAPAKAH LELAKI BREWOK yang selalu dampingi Kardi, siapakah
dia yang seolah-olah berprofesi sebagai asistennya seandainya Kardi adalah direktur PT.
Gunung Harta yang bergerak dalam usaha minyak curah. Dialah Sekarmadji, seorang yang
bertampang seram, kejam, tetapi sesungguhnya hati dia tidak sekeras intan. Di hari ke dua
ketika penyisiran berlangsung, Sekarmadji menemukan tas coklat yang di pungutnya saat
peristiwa gerbang kuburan. Tas yang sebelumnya ia berikan pada Kardi itu menggantung di
antara dahan pintu.
Sekarmadji naiki pohon. Setelah mendapatkannya ia tidak menyegerakan diri menuju
gubug. Ia bersandar di batang pohonnya, membaca buku catatan yang ada di dalam tas. Buku
itu menyedot kesadarannya. Sekarmadji linglung. Hatinya menjadi berat.
Aneh jika perasaan berkecambah, tumbuh dengan sendirinya. Di masa lalu
sesungguhnya Sekarmadji bukanlah orang yang tak beradab. Di kota kecilnya dulu ia pernah
mengalami hidup berkecukupan. Awal kejatuhan kenyamanan hidupya berawal dari
komplikasi penyakit bapaknya.
Sekarmadji masih mengingat bentuk Othang baik-baik. Masih tergambar jelas di
benaknya, sisiran rambut Othang yang klimis. Ia masih mengingat bagaimana lelaki itu
memilin-milin janggut khas orang-orang shalih dan menggunakan atraksi berbahasa yang
74
santun untuk mengajak bapaknya bisnis lobster serta madu dari hutan di pinggiran pantai
selatan.
“Kenapa tidak mencoba pinjam uang di bank?” tanya Bapaknya, ketika Othang
ajukan proposal peminjaman uang. Othang tersenyum bijak atas pertanyaan itu. Ia lantas
menjelaska perbedaan antara riba dengan sistem sirkah mudarabah, yakni sistem bagi hasil
yang tidak libatkan rente di dalam pengerjaannya.
Bapak Sekarmadji yang sebetulnya memahami keharaman riba, tertawa. Ia percaya
dengan Othang, sebab bukan satu kali dua kali ia melihat pemuda itu shalat berjamaah di
masjid desanya. Perilaku Othang ia anggap jaminan mutu.
Dana pensiun cair karena garansi, tetapi tak ada angin tak ada hujan beberapa hari
setelah uang pinjaman di berikan, Othang diketahui raib pada hari Jumat! Ia yang ibadahnya
diketahui jagoan, tidak masuk ke dalam gua menuju dan shalat menuju Masjidil Haram di
Makkah. Bapak Sekarmadji tidak mempercayai kemampuan seperti macam wali seperti itu.
Ia mulai berpikir pemuda yang sudah ia beri kepercayaan dengan derajat kepercayaan seratus
prosen itu meruntuhkan kepercayaannya.
Bapak Sekarmadji depresi. Ia tidak tahu jika pemuda Othang bukan orang yang
lidahnya ringan dipergunakan untuk urusan kibul mengkibul seperti kebanyakan orang yang
dengan mudahnya menggunakan sumpah atas nama Allah, demi Allah’. Othang tak seperti
yang dibayangkan orang-orang. Raibnya Othang dikarenakan ketentuan yang berasal dari
luar kekuasaan dia.
Othang tidak disembunyikan jin untuk di sunat, --apa yang mau disunat?—Othang
tidak terkait dengan mistisme timur macam itu. Jika dirunut, cerita hilangnya Othang berawal
saat dia melakukan survei sarang lebah kayu di dalam hutan pinggiran pantai selatan. Saat
menemukan sebuah sarang lebah yang gemuk, ponakan dia yang setengah waras setengah
dungu, melempar sarang lebah kayu itu. Otomatis lebah marah. Mereka mengejar ke dua
orang itu. Kejadian yang seharusnya dipandang horror menjadi sesuatu yang
menggembirakan bagi ponakan Othang. Sambil lari ia tertawa, sementara di sampingnya
adrenalin Othang melonjak membuat larinya menjadi semakin cepat. Ia lari, terus lari
menyelamatkan diri, tak sadar jika di hadapannya terdapat jurang limapuluh meter. Othang
terjun bebas. Di udara ia berusaha membuat gerakan agar ketika jatuh posisi tubuhnya
vertikal menembus permukaan laut. Namun lelaki malang itu tak sempat melakukannya.
Othang mendarat keras di permukaan laut. Ia merasa tubuhnya dihantam dinding raksasa.
Othang pingsan dan tenggelam.
75
Di atas jurang, ponakan Othang di hadapkan pada dua pilihan: menolong pamannya
atau berlari memutar. Si idiot masih memiliki tanggung jawab. Ia loncat dari ketinggian,
masuk ke dalam laut dengan posisi sempurna. Saat tubuh pamannya ia dapatkan, ponakan
Othang tak mampu mengangkat. Nafasnya sesak. Pada akhirnya dua orang itu menjadi
teman-teman cumi dan ikan kakap. Jasad mereka terseret arus liar bawah laut, masuk ke
dalam gua dan mendekam hilang untuk selamanya.
Peristiwa macam ini memang sangat sulit dipercaya, tetapi adakalanya dalam satu
tahun kita membaca atau mendengar sebuah peristiwa yang sama sekali tidak pernah terpikir
akan menimpa manusia: di Jakarta seorang seorang ibu melahirkan di bawah pohon yang
tumbuh di kompleks rumah sakit bersalin; di negeri gajah putih, seorang pilot di skor karena
sempat-sempatnya menurunkan helikopter dalam latihan tempur hanya untuk mencari jamur
yang di pesan ibunya; ada lagi kumpulan warga Kamboja yang memakan mayat teman-
temannya karena cadangan makanan di perahu pengungsian habis. Atau peristiwa
pembakaran diri Yan Pallach seorang mahasiswa Praha yang menjadikan dirinya sebagai
obor peringatan bagi tentara beruang dari Rusia. Di hadapan peristiwa yang benar-benar
terjadi itu apa yang terjadi pada Othang dan ponakannya tampak kecil.
Bapak Sekarmadji tidak tahu musibah tersebut, karenanya cukup manusiawi jika
buruk sangka membuat beliau depresi, membuat ia digerogoti penyakit lamanya. Bapak yang
semula bugar dan sehat menjadi kurus. Sisa uang pensiunan dan tabungannya amblas
terkuras membiayai perawatan di rumah sakit. Ia berbaring tanpa daya di tempat tidurnya dan
tanggung jawab pun beralih pada anaknya yang tertua.
Seperti sinetron rumah produksi Raam Punjabi yang gampang di tebak, bantuan entah
dari keluarga atau tetangganya yang berkecukupan tidak juga datang. Tidak ada yang bisa
atau lebih tepatnya tidak ada yang mau membantunya membuat Sekarmadji patah arang.
Dengan teramat sederhana, kebencian mulai tubuh di hatinya. Ia memutuskan pergi dari desa
kelahirnya, menetap dari satu kota ke kota lain.
Tingkat pendidikan Sekarmadji yang di zaman ini sulit digunakan membuatnya putus
asa. Bergabung dengan Kardi merupakan cara pintas. Di Yogyakarta pertambahan waktu
selanjutnya menjadikan Kardi sebagai kawan dekat yang mendangkalkan nurani Sekarmadji.
Sekarang buku itu ada di tangannya. Apa yang harus ia lakukan ketika nurani
memanggil-manggil, menagih-nagih hak yang harus ditunaikan pemiliknya. Nurani berusaha
menguasai kontrol dirinya, namun itu belum cukup, hingga suatu kejadian datang dan
mengingatkan Sekarmadji akan kesalahan jalan yang sudah cukup lama ditempuhnya.
76
PENGAKUAN
Agustus. Sudah setahun Riang tak menyambangi. Yogyakarta tidak begitu banyak
yang berubah. Hampir sama seperti dulu. Di jalan, motor-motor susul menyusul. Helm catok
yang fungsinya –sebatas— supaya tidak ditilang polisi –bukan sebagai pelindung kepala--,
menempel di sebagian besar pengendara. Warung-warung berjejer di pinggir jalan. Di balik
kaca penghalang debu jalanan, goreng lele yang renyah, pecel sayuran, tempe bacem,
sambal, sayur asam, tahu, rempeyek dan ikan teri putih sebesar kelingking, membuat lidah
Riang menggeliat. Riang harus bertahan, harus bersabar, mutlak musti bertekad! Tarif makan
warung pinggir jalan itu mahal. Ia yang biasa hidup sederhana harus berhemat. Manusia yang
belum kaya, jangan terlalu dihamba bisikan selera!
77
Yogyakarta, kini terasa panas bagi Riang. Perubahan suhu yang drastis berakibat pada
kesehatan tubuhnya. Baru sebentar berada di kota ini, temperatur badannya naik.
Menggunakan lengan baju, ia seka keringat. Nodanya coklat. Minyak yang ada di mukanya
jadi penyaring debu dan karbon monoksida. Di setopan ia bertemu dengan wanita manis
berwajah gulali. Badannya harum, tetapi sayang-disayang bulu ketiaknya tidak dicukur.
Wanita itu bilang, tujuan Riang masih jauh, masih harus menggunakan bus.
Dibilang jauh, Taryan ketawa. Ia memilih jalan. Jauhnya orang kota tentu tidak
sebanding dengan jauhnya orang desa, apalagi yang bilang jauh itu wanita. Riang melewati
beberapa lampu merah, melewati bangunan universitas megah yang halamannya luas. Ia
ingin masuk tapi rasanya segan. Lagipula tujuannya ke Yogyakarta bukan untuk jalan-jalan
melainkan bertemu Emha, bertemu budayawan berikut menyambangi dan bertanya mengenai
banyak hal yang mengganggunya pada Pepei.
Dari jalan besar Riang belok ke arah kiri, menuju gang berhias gapura tujuh belasan
bergambar tentara menggenggam senjata otomat zaman Westerling, bren! Mulut tentara itu
menganga, kakinya nyeker. Tiang lain pada gapura menggambarkan extrimis republiken
tengah menikam dua tentara Dai Nipon yang berteriak Akh! Sementara tentara satunya lagi
mengumpat, Bagero!. Di atas gapura, kain merah putih terbentang. Di tengah-tengahnya
tergantung triplek putih bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke sekian, tak lupa
diembel-embeli pekik meredeka! Dengan huruf kapital tentunya!
Sekitar seratus meter dari gapura jalan menurun. Alamat rumah Pepei akhirnya Riang
temukan. Rumah itu bercat hijau. Halamannya ditanam rambutan. Di depannya terdapat
lapangan bulu tangkis yang berhimpitan dengan wartel dan warung keperluan sehari-hari.
Ktuk! ktuk! ktuk! Riang mengetuk pintu rumah, “Permisi!”
Seekor ayam yang asyik tidur, terusik. Ayam itu terperanjat, terbang keluar dari balik
pagar. Minibus yang tengah melaju, meninjunya. Tubuh si jago yang gagah msenghantam
pohon asam! Rem tangan di tarik. Krek! Minibus berhenti ditanjakan. Pengemudi turun.
Wajahnya pias.
”Siapa pemilik ayam ini Mas?” Pengemudi bertanya pada Riang, wajahnya pias.
”Mana ku tahu? Baru pertama ke sini Mas.” jawab Riang singkat.
Pengemudi bingung. Di belakang minibus antrian mobil membunyikan klakson tan
tin tan tin ketika mengetahui bahwa yang sekarat bukan manusia.
Pengemudi minimbus segera pinggirkan kendaraan tepat di atas tanjakan. Orang-
orang berkerumun. “Lekas panggil Paijo!” Teriak seseorang pada anak yang tubuhnya
78
terlihat paling kecil di kerumunan. Anak itu berlari dibayang-bayangi gigitan tato laba-laba
pada bahu pemuda yang baru saja memberinya perintah.
Tak lama berselang, orang yang dicari si anak datang. Ia menatap ayamnya, nanar.
Paijo mengelus sambil memandang mata pengemudi minibus. Pengemudi minibus lekas
minta maaf. Beberapa orang berkhayal, polisi yang nantinya datang terlambat akan
menggunakan kapur tulis seperti yang digunakan polisi bule saat memberi tanda tempat
kejadian perkara di film action yang sering mereka tonton.
Tak ada film action karena Paijo memaafkannya. Pengemudi minibus bernafas lega.
Ia serahkan uang tapi Paijo menepis nya. “Tidak usah Mas! Saya yakin Mas tidak berniat
menubruk ayam saya! Ini kecelakaan! Setiap kejadian adalah qudrat dan iradat-Nya.”
Pengemudi minibus tak begitu saja percaya. Ia sodorkan uang, membungkuk-bungkuk,
namun segigihnya orang, pastilah menyerah jika sudah berhadapan dengan manusia
berkeyakinan cadas. Setelah sebelumnya mengatakan ’maaf’ yang Riang hitung sudah
diucapkan lebih dari duapuluh empat kali, pengemudi mini bus berlalu.
Konsentrasi Paijo kini terfokus pada ayam sekarat yang didekapnya. Ia menarus ayam
yang malang itu di samping net bulu tangkis. Ia berlari menuju tempat Riang berdiri. Riang
khawatir, benar-benar khawatir! Jangan-jangan Paijo tahu kalau dirinya yang membuat ayam
terbang. Tidak! Paijo melewatinya begitu saja. Di Yogya Riang bersyukur untuk yang
pertama kali dan yang kedua kalinya saat Paijo mengetuk pintu, dan berteriak “Masssssssss!
Mas Pepei!”
Tak ada jawaban dari dalam. Paijo membuka pintu, masuk ke dalam dan kembali
berteriak. Tak lama kemudian ia keluar membawa pisau dapur. Paijo belari menderu-deru,
menuju lapangan bulu tangkis. Sebelum piaraannya mati, ia menyembelih ayamnya,
“Alhamdulillah masih sempat!” katanya.
Dalam pada itu seseorang yang datang dari belakang mengejutkan Riang “Ada apa?”
Tanyanya. Lelaki yang bertanya melihat ayam yang menggelepar, “O kusangka ...” lalu ia
menoleh pada Riang dan berteriak. “Ya ampuuuuun! Bandoooo… ya ampun Bando …
Riang! Sejak kapan ada di depan!”
Riang latah ikut-ikutan. “Ya ampunnnnn Mas Pepei. Ya ampuuuun!” sambil
menempelkan kedua tangan di pipi seperti Meisyi saat membawakan acara Bando di salah
satu stasiun televisi swasta.
“Masuk-masuk!” Pepei membawa Riang ke dalam. “Silahkan duduk!” Katanya.
Saat Riang duduk tanpa memberitahu akan kemana, Pepei meninggalkannya. Ia
keluar dari pintu belakang.Riang duduk diatas ubin yang sudah dialasi tikar.
79
Di ruangan itu Riang tidak melihat tempat duduk. Majalah lawas berserakan.
Lembaran-lembarannya lepas. Ada hektar yang di paku pada meja kayu. Sebuah jam
sederhana tergantung di tembok. Sebuah televisi tua dimatikan. Di sampingnya pesawat
telepon dialasi tatak rotan menclok.
Beberapa menit kemudian Pepei kembali dari pintu depan. Ia membawa makanan
ringan, kacang-kacangan, wafer dan es jeruk.
”Sejak kapan di Yogya?” Sambil menuang air yang maha segar itu, Pepei memulai
perbincangan.
”Baru saja sampai.” Jawab Riang datar.
”Kabar orangtuamu bagaimana?”
”Baik-baik saja.”
Jika sudah lama tidak bersua membuat atmosfer sebuah perjumpaan akan menjadi
hambar. Pepei membiarkan Riang makan dan membiasakan diri terlebih dulu. Pepei
menjerang air di dapur dan membawa dua gelas air hitam. Wangi air itu sampai di hidung
Riang.
”Ayo diminum!”
”Baik Mas.”
”Jadi kayak robot!?” Pepei tertawa memandang Riang. Ia berusaha memecah
kekakuan.
”Siapa ?” Tanya Riang sambil menghirup kopi.
”Ya kamu!”
Riang tidak begitu ahli dalam permainan psikologi perbincangan semacam ini, maka
ia alihkan obrolan. ”Mas membaca koran beberapa bulan lalu?”
”Tentang apa?”
”Tentang kita, tentang danau keramat di Merbabu, tentang perkelahian yang waktu
itu...”
”Bagaimana bisa?” Pepei menatap langit-langit yang sempit, ”...menemukan ikan
purba?!” Saat tertawa, amandel Pepei kelihatan. ”Ada-ada saja! Seminggu berturut-turut
Thekelan dimuat di koran, diberitakan di radio, setelah itu apa yang terjadi di sana?”
”Yang terjadi bagaimana?” Riang kebingungan.
”Ada yang berubah?”
”Apa?”
”Ya apa?!” Pepei pura-pura kesal. ”Apa yang berubah di Thekelan?” Tanyanya.
80
”O itu,” Riang melongo. ”Sekarang banyak orang yang ziarah ke Thekelan Mas...”
Dan ia pun menceritakan semuanya. Mendengar cerita Riang tentang ibu pejabat yang
semaput, air kopi nyembur mengenai baju Riang.
”Yang!?” Tanya Pepei setelah meminta maaf.
”Iya Mas?”
”Tadi kau ceritakan perubahan di Thekelan, sekarang, kau mengalami perubahan
macam apa?”
Yang berubah tentangku?” Riang menunjuk dirinya.
”Iya, yang tentangmu!” Pepei hampir-hampir menggelengkan kepala. ”Sekarang
kamu terkenal di mana-mana, diberitakan di media massa, barangkali kamu banyak ditaksir
wanita?”
Riang hilang keseimbangan, mendengar pertanyaan itu. ”Ah mas ini! Sungguh
Maaaas! Ndak ada niat pacaran! Repot kalau harus membiayainya.”
”Siapa yang bertanya tentang pacaran. Aneh, aku kan Cuma bertanya, apa kamu
sudah ditaksir wanita, lagipula, memangnya kalau pacaran harus membiayai. Aturan dari
mana itu? Membiayai itu kalau sudah kawin. Ini kan belum.”
”Orang pacaran butuh uang. Masak pacaran di tempat menanam sayur?”
”Lha! Di tempat wisata Kopeng, kan gratis?!”
”Gratis iya tapi makannya?”
”Bawa dari rumah!”
Riang cengangas cengigis. ”Oh iya .... oh iya .... benar Mas!”
”Oh iya-oh iya! Kalau gitu siapa pacarmu sekarang?”
Riang membungkuk-bungkuk. ”Ampunnnnn sungguh tak punya ... malu aku Mas...
sudah!”
Pepei menahan tawa.
Obrolan terhenti. Riang berpikir.
”Kalau Masnya sendiri bagaimana?”
”Apanya yang bagaimana?”
”Pacar lho Mas. Pacar!” Mata riang berkedap kedip.
”Simbahmu!!! Malas aku omongin itu!”
Lelaki yang ada dihadapan Riang lumayan licik, tapi ia tidak begitu
mempermasalahkanya.
Beberapa detik keduanya diam lagi.
”Omong-omong ada perlu apa di Yogyakarta Yang?” Tanya Pepei tak berbasa-basi.
81
”Mau temui Emha Mas!” Riang bangga, wajahnya ceria. ”Mas tau rumahnya?”
”Emha? Emha mana?! Kalau Paijo Emha yang ayamnya kamu kageti itu, ya tahu!”
Mendengar Paijo Emha, mendengar ayam membuat darah di muka Riang seakan
disedot selang. Ia merasa membutuhkan waktu yang lama untuk menjawabnya. Leher Riag
dingin.
Pepei tertawa melihat raut wajah Riang yang kebingungan harus mengutarakan apa.
Pepei memberi kesempatan, bagi Riang untuk bernafas. ”Mukamu belel,” katanya. ”Lebih
baik kau bersihkan badan dulu sebelum ketemu lelaki itu sore ini”
”Ketemu siapa Mas?”
Hampir-hampir Pepei berteriak! ”Katanya mau ketemu Emha?!”
”O ya ya...Benar Mas? Mas tahu tempatnya?!”
Pepei malas menjelaskan. Ia memberikan instruksi. ”Setelah kamu makan kita
berangkat ke sana!”
Karena rahasianya dipegang, Riang manut saja. Banyak hal membuat Riang terlihat
dongo dan itu wajar karena manusia memang begitu, memang mudah kehilangan kecepatan
berpikir, kehilangan kemampuan mengolah kata di beberapa suasana termasuk ketika
bertemu dengan teman yang sudah lama tak ia jumpai atau ketika rahasia yang ia simpan
ternyata terbongkar dalam tempo yang sangat singkat. Hanya orang hebatlah yang bisa
mengatasinya dengan cepat.
DI DALAM KAKUS yang panjang kali lebarnya satu kali satu meter, Riang
membakar rokok. Ia berusaha santai agar bayang-bayang ayam Paijo menghilang. Tapi tak
bisa. Oh mengapa Mama, Oh mengapa Papa. Kalau saja warga tidak berkerumun
mengelilingi ayam itu, Riang akan mengakui perbuatannya. Di zaman yang Ronggowarsito
tidak akan kuat menempatinya ini, di zaman yang edan begini, Riang takut jika ia di hakimi
beramai-ramai atas kesalahan yang tak ia sengaja.
Dari kakus yang sepi, Riang mendengar suara air dituang dari dalam sumur. Suara
lain datang. Langkah kakinya terdengar.
“Mas Pepei di mana Dikau?”
“Di belakang!” Jawab Pepei, “lagi nimba!”
”Mau mandi Mas?!”
”Ndak! Buat sodaraku dari Tepus!”
“Walah, dari Tepus?! Simas yang guanteng tadi itu dari Tepus? Sekarang dia ada
dimana?”
82
“Di kamar mandi!”
Volume suara berkurang. Paijo berbisik, “Nama teman Mas siapa?.”
“Kalau mau tau namanya, tanya aja sendiri.”
“Masak nanya orang di kamar mandi? Ya ndak sopan?”
“Ya nanti kalau dia sudah selesai mandi.” Jawab Pepei tertawa.
Mendengar suara Paijo, Riang langsung gemetar. Ia mempetajam pendengarannya.
Katel digeser dari tempatnya semula. Ada gelas yang beradu dengan asbak. Langkah kaki
mendekat ke kamar mandi. Suara besi beradu dengan porselein. “Pisaunya sudah dicuci. Aku
taruh ditempat semula!” Teriak Paijo. Langkah kaki menghilang. Degup jantung Riang tak
lagi kencang.
Konsentrasinya Riang beralih dari ayam menuju konsentrasi yang seculum:
konsentrasi di sini dan saat ini. Ia mulai memperhatikan penghuni kakus, mengikuti gerak
beberapa buah kecoak yang kegeeran dikejar-kejar cecak. Ia mulai memikirkan hal yang
aneh-aneh, Kalau di bawah kloset ini ada kerajaan kecoak, jumlah anggotanya ada berapa
ya? Beratus-ratus? Rajanya sebesar apa ya? Ratunya cantik atau tidak?
Byur! Byur! Byur!
Riang selesaikan mandinya. Kulitnya sudah tak terasa lengket.
"Bagaimana segar?” Tanya Pepei sambil memberikan handuk dari atas pintu seng.
”Segar!” Riang membuka pintu.
”Memangnya sirup!?”
”Mas ini ...” Riang memperlihatkan gigi, tertawa, ”Tadi, mas Paijo datang untuk apa
Mas?”
”Menyelidik?”
Riang gelagapan.
”Tadi dia cuma mau kembalikan pisau!” Jawab Pepei menenangkan. ”Mas Paijo itu
warga RT yang paling disenangi di rumah ini.” Pepei melirik Riang yang wajahnya semakin
memperlihatkan rasa khawatir. ”Tenang, rahasia akan tetap menjadi rahasia!” Pepei
tersenyum jahil. ”Kita bakal makan besar malam ini!” Ujarnya menutup pembicaraan.
Pepei merasa tak harus menjelaskan maksud perkataannya. Setelah cerita ke sana
kemari ia mengajak Riang makan di warung yang dikatakannya termurah di Yogya.
Diambilnya kunci motor teronggok di samping telepon. Dinaikinya motor yang Pepei
namakan Jolly Jomper, kuda seorang cowboy yang tembakannya melebihi kecepatan
bayangan. Jika dalam komik si Jolly bisa diandalkan, sayang, dalam kenyataan si Jolly
berbeda dengan yang ada dalam khayalan. Motor Honda warna merah tahun enam puluh
83
sembilan itu selambat siput. Melampaui beberapa buah warung, satu siskamling dan dua
tanjakan, si Jolly terengah-engah. Sesampainya di warung si Jolly istirahat sembarangan.
Lempengan kayu kayu bernomor terlihat bertumpukan di samping warung yang
suasananya gelap seperti gua. Seorang lelaki tua langsung mengambil dua centong nasi dari
bakul.
”Lauknya apa nak Pepei?”
”Ayam!”
”Dada atau paha?”
”Telurnya saja Mbah!”
”Bisa kualat kamu!” Simbah mengancam. Mulutnya tampak ompong.
Pepei meminta Simbah menambahkan sayur dan kerupuk di menu makan siangnya, ia
kemudian menggeser posisinya.
”Ini siapa?” wajah keriput Simbah mendekati wajah Riang.
Sebelum Riang menjawab, Pepei mendahului ”Ini Riang Mbah. Dari Tepus!”
”Tepus?”
Riang hendak membantah apa yang dikatakan tapi ia memilih diam karena tiba-tiba
tangan Simbah bergerak cepat menempatkan tiga centong nasi padanya.
Riang mengambil tempe.
Wajah Simbah terlihat sedih. ”Ayo ... ayo makan apa saja! Pilih yang lain Nak!”
Riang mengambil tahu.
”Masya Allah Nak ... Jangan begitu! Ayo yang lainnya. Ambil saja!”
Riang bingung. Baru kali ini ia bertemu pemilik warung yang memaksa calon
pelanggan apa yang harus dimakan. ”Tahu tempe juga tidak apa-apa.” Jawab Riang, tapi
Simbah malah mengambil sepotong hati sapi untuknya. Riang tak mungkin mengembalikan.
Dari meja panjang Pepei berteriak. ”Mbah ... maaf, aku pesan es teh dua.”
Simbah mengadu-aduk nasi menahan emosi. ”Ndak usah maaf-maafan” katanya, ”...
sebentar!”
Ruang makan itu lumayan besar jika dibandingkan dengan ruangan tempat Simbah
duduk. Besarnya empat kali empat meter. Ditengah-tengahnya terdapat meja dan sesisir
pisang raja. Dan di temboknya terdapat bercak-cercak minyak.
Bunyi kelintingan gelas beradu dengan sendok. Bunyinya terdengar nyaring.
Dentingnya terdengar kemana-mana menguatkan kesan ruangan tersebut seperti gua.
”Mas?” Riang dekatkan mulutnya pada telinga Pepei.
”Ya?”
84
”Kenapa Mas ngapusi, bohongi Simbah dan mas Paijo?”
”Ngapusi apa?”
”Kalau aku dari Tepus!” Riang masih berbisik.
”Apa guyon ndak boleh?”
Riang tak berani bilang tak boleh.
Dalam beberapa tahun ini guyonan atau lelucon berkenaan dengan Tepus sedang in.
Tepus, daerah yang sangat jauh dari Yogya itu, tanah retak-retak. Konon hanya ketela pohon
yang mampu bertahan di tanahnya yang gersang. Kemiskinan dan keterbelakangan lahan
daerah itulah yang menjadikan Tepus menjadi objek hiburan, objek guyonan, meski di
beberapa orang tujuannya bukan untuk memperolok-olokan. Jika mau disamakan, mungkin
guyonan semacam ini mirip dengan guyonan mengenai desa Samin yang kejujuran
penduduknya dianggap sebagai keluguan.
Sambil makan, dan memikirkan Tepus, tak sengaja Riang memperhatikan Pepei
cukup lama. Lalaki itu memilki rahang yang kokoh persegi. Rambutnya yang dahulu
panjang, kini dipangkas pendek, rapi. Dagunya ditumbuhi bulu-bulu tipis berwarna
kecoklatan. Kelopak matanya besar. Tatapan matanya simpatik. Hidungnya mancung,
semancung mancungnya. Pada pipinya melintang garis luka. Dipikir Riang wajahnya seperti
wajah peranakan Eropa. Hanya kulit coklatnya yang mengindentifikasi kalau ia orang Asia
dan tentunya dari wilayah tenggara. Riang hanya mampu mengidentifikasi Pepei dari
penampakkan luar. Ia belum terlatih. Ia hanya merasa wajah lelaki yang ada di hadapannya
membuat nyaman.
Riang mengelus-elus perut. Lambungnya membutuhkan sedikit ruangan untuk
sirkulasi udara. Pada saat seperti itulah Pepei menanyakan keperluan Riang untuk bertemu
Emha. Riang lantas menceritakan awal masuknya Simbah ke dalam Islam, tak lupa pula ia
menjelaskan kaitan antara suara yang muncul di danau Merbabu, di gerbang kuburan dengan
bisikan-bisikan Simbah waktu Riang masih kecil.
”Kamu tertarik agama Simbahmu?” Pepei menghabiskan es tehnya.
Riang mengangguk. ”Kalau bisa, kalau tak keberatan, aku minta diajari Islam sama
Mas?”
Segaris senyum muncul di wajah. “Kalau begitu kita cari Emha!” Pepei tidak
mengiyakan. Ia menuju Simbah
“Disatukan harganya Mbah.”
Sembunyi-sembunyi Simbah menunjuk “Untuk Mas itu, gratis Nak!”
”Kenapa harus gratis?”
85
”Kan kasihan dari Tepus.”
Kebaikan Simbah membuat Pepei tak nyaman. Ia ingin mengatakan kalau yang ia
bilang cuma guyonan, tapi ia mengurungkannya. Pepei tidak enak. Dan sejak saat itu, meski
hanya guyon ia tak mau lagi mengatakan pada orang lain kalau Riang berasal dari Tepus.
Riang menggunakan helm catok!
Jolly Jumper meringkik!
Ketepak…ketepak…ketepak!
Gas ditekan pol!
Ketepak…ketepak…ketepak!
Lajunya tidak seperti siput lagi. Ya sedikit cepat! Seperti jalan putri keraton!
Dari kejauhan suara gamelan terdengar. Mulut Riang menguap! Lebar.
LEWATI BENTENG VREDEBERG dekat pusat wisata kota (Malioboro) mereka
menyusuri tempat orang-orang yang dahaga akan ilmu mencari pemuasan: Shoping. Buku-
buku bertebaran, bertumpuk-tumpuk menggoda. Bagi laki-laki sang pencinta, buku
merupakan wahana onani intelektual. Bagi wanitanya, ya tentu saja vibratornya!
Sesampainya di tempat yang mereka tuju kekecewaan datang. Hari ini tak ada itu yang
namanya Emha. Mereka tak mungkin menemukannya selama satu atau dua bulan ke depan.
Menurut pamflet --yang ditempelkan di gerbang beberapa perguruan tinggi dan dinding-
dinding jalanan--, Emha tengah berkeliling di berbagai kota, melakukan konser dengan
sekumpulan orang yang tergabung dalam sebuah kelompok kesenian religius. Tujuannya,
membangkitkan kerinduan manusia pada Tuhannya.
Mendapati kata rindu, Riang jadi teringat oleh pengalamannya beberapa tahun silam
tatkala mendatangi sebuah mushala yang karpet kuning golkarnya bau pesing. Ia
menyengajakan diri datang kesana, demi mendengar penuturan seorang ustad mengenai
kecintaannya pada Tuhan.
Tak tuntas hanya menjadi pendengar di antara puluhan pendengar lainnya, sehabis
khutbah ia menuju ruangan di balik mimbar. Ia datangi Ustad dan duduk bersila. Riang yang
saat itu sedang naiki kadar spiritualnya ingin mengetahui bagaimana pengalaman ketika sang
ustad mendekatkan diri kepada Tuhan, maka, pada Sang Ustad, Riang pun mengungkapkan
bahwa ia benar-benar rindu untuk berasyik-mahsyuk dengan Tuhan. Ia mengakui bahwa
dirinya sudah sejak lama melupakan ’hubungan intim’ dengan Pemilik Semesta.
Riang fikir kejujurannya dalam hal itu bakal membuat sang ustad berkopeah haji
simpati. Praktik ilmu komunikasi yang secara tidak langsung dijalankan, bahwa seseorang
86
akan terbuka seandainya orang yang memulai bicara lebih dahulu membuka diri,
kenyataannya gatot alias gagal total!
Riang melihat ada yang menyala di tubuh sang ustad berkopeah. Dada dan bahunya
naik turun seperti tangga eskalator.
“Tuhan ingin berhubungan intim?!” Ludah sang ustad muncrat.
Riang kaget bukan kepalang. “Tarik perkataanmu!” bentak sang ustad, ”Jika tidak ...
KAFIR KAU!”
Badan Riang doyong ke belakang, manakala sang ustad menambah semburannya.
Riang tidak tahu jika ia tengah berhadapan dengan pengkhutbah yang tak mau
mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Ia tengah berhadapan dengan tipe ustad yang
menguasai pengadilan kehidupan. Manusia yang asal memvonis orang tanpa berusaha
mengetahui latar belakang mengapa. Riang tidak tahu jika ia berhadapan dengan manusia
penebar fitnah, penebar detonator kebencian untuk diledakan agar orang-orang yang
dianggapnya kafir mati kutu ketakutan! Riang tidak tahu, sungguh tidak menahu mengenai
hal itu. Riang hanya tahu jik dirinya tengah dilecehkan.
Seperti halnya tawon yang hanya akan mengganggu jika diganggu, Riang pun
menyengat!
“Memang ada apa dengan kafir, hah! Memang kenapa kalau aku KAFIR! Apa Tuhan
tak mengajari sopan santun pada orang KAFIR hah!”
Mendapat perlawanan dari lelaki yang dianggapnya masih bau minyak telon, sang
ustad meradang “Astagfirullah! ... SETAN!”
Riang tak mau kalah. Ia berdiri di pintu geser musholla, ”Yang setan itu Sampeyan!”
cemooh Riang. ”Dasar ustad gila!” Bentaknya sambil berteriak, berlari menutup perdebatan
yang tak sehat.
Sebenarnya pemuda yang dikatakan bau minyak telon oleh sang ustad adalah lelaki
yang tahan terhadap makian, tapi seperti umumnya manusia, ketika kegelisahan datang
menggeser titik ekuilibrium mental, maka emosilah yang mengkontrol kendali atas dirinya.
Riang pun demikian. Ia hampir tidak pernah bisa tahan dengan orang yang malang dirundung
syak wasangka. Apa salah, kalau dia ingin bercumbu dengan sesuatu yang dianggapnya
transedental? Apa salah? Memang ketika mengatakan itu birahi Riang tengah tinggi-
tingginya, sampai-sampai, manusia, setan, babi, pepohonan, dan jin sudah tak bisa
menampung horny purbanya!? Apa Riang pengen berzigi-zig-zag sampai pelumasnya habis
di hisap spon vagina Tuhan?
87
Kecintaan mendalam terkadang hanya bisa diungkapkan dengan bahasa bersayap.
Bahasa sastra. Dan mengenai hal ini, orang-orang, banyak yang tidak tahu ditidak-tahunya.
Mereka pura-pura tahu atas sesuatu yang tidak-mereka ketahui sehingga wajar jika benturan
fisik yang dibenci Tuhan seringkali meletus. Dor!
DOR! Sebuah paku besar menembus kaki motor. Pepei tidak menghentikan laju
motor yang didorongnya meski sudah berada di samping tambal ban. Ia tetap menuntun si
Jolly tanpa melirik ke arah tukang tambal ban yang sempat menyapanya. Setelah melewati
beberapa kelokan ke depan, barulah si Jolly diperban. Setelah sembuh, ia meringkik!
Keteplak! keteplok! Pulanglah mereka.
Sampai di rumah, rasanya tubuh Riang letih sekali! Ia ingin merebahkan diri, tapi tak
jadi. Menunggu malam tiba, ia menimba air, kemudian mengambil handuk dari dalam tas.
Kegelapan datang. Di balik pohon waru, cahaya merah pudarkan biru angkasa. Kepak ayam-
ayam jago terdengar dari kejauhan. Malam melingkupi seluruh Yogjakarta. Lampu-lampu
neon dan bohlam menggantikan matahari. Matahari diganti listrik, yang diperangkapkan
manusia dalam bentuk bulatan dan tabung gas. Manusia yang semula dikuasai alam, yang
tergantung pada alam, kini berbalik menguasai dan memanfaatkan unsur alam untuk
membuat nyaman kehidupannya.
Setelah tubuh Riang wangi. Setelah asam keringatnya hilang, ia melunglai. Setelah
maghrib, Riang menutup mata, untuk sementara.
DI ATAS KASUR RIANG MENGGELIAT laksana ular sanca. Jarang tidurnya
senyaman ini. Tidur yang sempurna membuat aliran darahnya terasa. Di kamar ini sebuah
cermin besar menempel di dinding. Pada bagian lain, lemari plastik tersudut. Beberapa
sisinya robek. Jika pemilik kamar malas memasang perangkap sudah bisa dipastikan tikus
nikmat beranak di dalam robekannya. Di kamar ini tak ada yang menarik, kecuali rak buku
yang menempel di dinding. Buku-buku berjejer rapih dari bawah lantai sampai menyentuh
plafon. Riang khwatir jika raknya rubuh. Ia melihat paku-paku yang menyambungkan antar
sudutnya berkarat. Pembuatan raknya tak mengikuti peraturan pembuatan rak yang layak.
Riang berniat memberitahukan hal ini pada Pepei.
Riang bangun, mengucek mata, membuka pintu kamar ... pas keluar ...
Krompyang!
Ia menumbuk seseorang.
88
Piring seng meloncat ke atas. Sebuah benda kecoklatan membentur tembok. Riang
menangkapnya. Benarlah apa yang dikatakan Pepei mengenai ’makan besar’. Ayam malang
itu berada dalam cangkup tangannya. Ayam yang tadi siang sayapnya masih gagah
berkepak-kepak itu kini mengepulkan uap panas dari badannya.
Paijo memaafkan Riang. Ia memberikan ayam panggang pada Riang setelah
meletakan ayam itu kembali di atas piring seng. Paijo pergi setelah mengetahui orang yang
ditemui tidak mengetahui keberadaan Pepei.
Tak beberapa lama setelah Paijo pergi, lelaki yang dicari membawa nasi bungkus
tanpa lauk. Pepei meyakini ramalannya mengenai makan besar bakal terlaksana benar.
Santap malam pun berlangsung. Di suapan pertama, Riang merasa tak nyaman memakan
ayam yang mati karena ulahnya, tapi rasa dibunuhnya menggunakan pikiran. Suapan pertama
dan kedua memang sedikit sulit menelan, selanjutnya, demi penghematan, rasa bersalah
sebaiknya harus dihilangkan.
”Ada apa?” Tanya Pepei ketika Riang memperhatikan wajahnya.
”Luka di wajah Mas tidak bisa hilang ya?”
Pepei meraba bekas luka goresan di gerbang kuburan. ”Mafia Italia wajahnya kan
kayak gini.”
”Mafia Italia?”
Riang tidak tahu Sisilia, God Father dan Don Corleon, Pepei mengerti. ”Kalau
dioperasi, pasti bisa dihilangkan,” katanya. ” Tapi, kalau dilihat-lihat wajahku jadi makin
bagus kalau begini ...”
”Mas?”
”Ya?”
”Bagaimana caranya supaya kita berani berkelahi,” tanya Riang tiba-tiba, ”supaya
bisa menjaga diri seperti waktu dulu Mas beraksi.”
”Beraksi? Memangnya Sarimin, pakai beraksi segala.” Pepei berusaha alihkan
pembicaraan.
”Mas?”
Pepei malas menjawab. Ia hanya mendehem.
”Apa rahasia supaya aku bisa berani seperti Mas?”
Riang kebelet menjadi pemberani. ”Besok aku beritahu rahasianya,” Pepei
menjanjikan, ”tapi Kau jangan bertanya lagi tentang hal ini.”
Riang mengangguk. Ia mengigit tulang rawan paha ayam.
Tak lama kemudian, pertanyaan dengan topik yang berbeda diajukannya.
89
“Mas?”
”Iya?”
”Pernah mengalami pusing karena tidak tahu tujuan hidup Mas apa?”
Mendengar pertanyaan berbobot tiga ribu kilogram yang berbeda dengan pertanyaan
tiga ons sebelumnya, Pepei hampir memuntahkan nasi. ”Tak ada lampu sen!”
“Lampu sen? Maksudnya apa?”
“Pertanyaan seberat itu kamu mulai tanpa awalan!”
“Pertanyaan berat?”
“Saking beratnya hanya sedikit orang yang mau bertanya dan serius
memecahkannya!” Pepei melancarkan tenggorokannya. ”Akhir-akhir ini kamu tengah
mengalami kegelisahan?”
”Mas bisa tahu?”
Riang mengangguk.
”Bukannya tahu. Aku hanya meraba. Jika ada orang yang bertanya mengenai tujuan
hidup, biasanya ia tengah alami kegelisahan. Saat ini kau berada di persimpangan
jalan!Hidupmu akan berubah cepat!”
“Masak Mas?”
Pepei tertawa, “Masak kangkung. Masak telor ceplok. Mangga masak he … he …he.”
Ia mencungkili daging ayam yang menyelip di giginya.
“Masak mas?”
“Apa karena aku bicara sambil tertawa jadi nggak percaya?”
“Aku tidak mengerti maksud persimpangan jalan yang Mas katakan!?”
“Tak usahlah itu difikirkan” sahutnya. ”Nanti kau bakal menemukan maksud
perkataanku seperti apa, dan bagaimana. Perlahan saja, tidak usah terburu-buru. ...Yang?”
“Apa?” Sebenarnya Riang masih mengolah kata-kata Pepei mengenai persimpangan
jalan tetapi ia berusaha mendengarkan.
“Ayam ini sudah mati! Kalau mati seperti yang Kau makan ini, Riang bakal
kemana?”
Riang belum memahami kaitan antara ayam dengan pertanyaannya mengenai tujuan
hidup. Tapi pertanyaan yang disodorkan Pepei membutuhkan jawaban. Ia hendak menjawab
pertanyaan yang dianggapnya mudah, namun pertanyaan itu membuat jiwanya
bergemerincing dan pikirannya seakan dicantoli beban berat. Ia merasa kesulitan.
Pepei mengulangi pertanyaanya.
90
“Kalau mati kamu bakal kemana Yang? Bakal menjadi tanah? Jadi materi kembali?
Coba lihat ayam ini … Awalnya, ia materi yang hidup kemudian ditubruk mobil. Disembelih
mas Paijo, di goreng, dan sekarang ini sudah masuk ke dalam perut kita! Setelah diolah usus,
ia bakal keluar menjadi pupuk! Tubuh ayam ini akan bersatu kembali dengan materi asalnya:
tanah! Setelah mati, ayam ini tak mungkin bertamasya kemana-mana! Tempat akhir
kehidupan adalah tanah. Menuju tanah.”
“Manusia mati akan kedua tempat Mas. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka.” Kuduk
Riang merinding.
“Itu menurut pendapatmu. Tapi orang atheis berbeda paham denganmu.” Pepei
mengambil dua gelas. Ia menuangkan air ke dalamnya. Diminumnya dalam satu tegukan. Ia
kemudian membungkus kertas nasi dan memasukannya ke dalam kantung plastik. Sendok
yang kotor tergeletak di lantai.
“Menurut mereka, menurut orang atheis, surga dan neraka sebenarnya tidak ada.
Surga itu karangan nenek moyang saja. Surga dan neraka itu rekayasa, dan Kamu pun bisa
membuat karangan yang serupa.” Pepei mengambil jeda, ”Yang? Bagaimana mau masuk di
akal, keberadaan hidup dialam baka, sementara, di dalam kehidupan ini, tidak pernah ada
orang yang menelepon dari surga: kalau dia sedang asyik-asyiknya adu kelamin dengan
bidadari; kalau dia sedang makan dari piring emas dan mandi di telaga kolesterum? Padahal,
sekali lagi Yang, sekali lagi ..., tak ada satu orang pun yang pernah memberi telegram dari
neraka, memberi kabar melalui sandi morse dan mengatakan bahwa dubur dia tengah dicolok
tusukan sate sampai tembus ke mulut. Tak pernah ada satu orang pun yang memberi kabar
peringatan, bahwa setelah malaikat, sang eksekutor puas colok mencolok dubur seseorang
menggunakan tusukan sate, ia berkacak pinggang sambil tertawa, ”Ha…ha…ha itulah
akibatnya, Kalau di dunia ini, manusia pernah bersetubuh dengan kambing tetangga....
hahaha itu balasan kelalaian, bagi orang yang menyebabkan ayam tetangga mati ditabrak
colt!”
Hal itu terlalu berbahaya bagi Riang. Lidah Pepei, menghantam akalnya,
Akal Riang membenarkan
Akalnya menafikan!
Seperti yang dijelaskan Fidel di danau, Pencipta pasti ada! Pencipta
tidak mungkin tidak ada. Bukti yang diungkap Fidel mengenai angka-
angka fibonacci demikian mengagumkan, tapi di dalam hati Riang
muncul riot, meruyak kerusuhan!
“Masih mau dilanjutkan?”
91
Riang tak mau mengatakan ya, tetapi tak mampu pula mengatakan jangan.
Riang t e r p a h a t di dinding,
menjadi a r c a,
menjelma …
menjadi p a t u n g yang tak memiliki
kehendak.
Pepei masuk ke dalam kamar Saat orang yang diajaknya berbicara membisu, dan
balik sambil membawa buku berwarna biru.
“Ada pertanyaan yang menarik di dalamnya. Coba baca dan renungkan.”
Riang membuka halaman yang ditunjukan Pepei. Saat membaca kalimat yang tertera
di dalamnya, jemari Riang bergetar seolah tengah memegang gergaji mesin. Riang
melepaskan buku itu. Rasanya dunia berputar lebih cepat.
“Bagaimana?”
Tuhan itu maha Kuasa, maha Pencipta. Bisakah Tuhan yang maha Kuasa dan
Pencipta itu menciptakan suatu benda yang sangat besar … sehingga Tuhan tidak mampu
untuk mengangkatnya?
Tatapan Pepei tajam menguliti muka, masuk ke dalam kornea mata, menembus
daging … masuk kedalam pemikiran dan perasaan Riang. Ia terguncang. O’ sungguh
mengerikan.
Pepei mengerti apa yang dialami Riang. Ia berhenti mendesaknya, berhenti
memberikan ancaman --yang secara tidak langsung— membuatnya mengkeret ketakutan.
“Sudahlah nanti saja kita teruskan.” Pepei memegang lembut bahu Riang. Ia berdiri
menuju kamar mandi.
Ditinggalkan Riang di dalam alam kebingungan yang menakutkan. Sudah berapa
belas tahun, Riang meyakini bahwa Tuhan ada, tetapi di hadapan pertanyaan itu ia merasa
tidak mampu untuk membuktikan-Nya. Apa yang pernah diutarakan Fidel sepertinya sirna
begitu saja. Kesadarannya akan keberadaan Tuhan menjadi sebesar atom. Ia dikalahkan oleh
pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak! O’ Riang belum kalah. Ia bertekad untuk menjatuhkan
pertanyaanya.
Riang tak bisa tidur. Ia mengalami kegelisahan sepanjang malam. Matanya pejam tapi
pikiranku tidak! Ia melayang -layang seperti burung di dalam alam fikiran. Ia berpindah-
pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa sayap Dari satu pohon pertanyaan-ke pohon
pertanyaaan yang tak juga terselesaikan. Pertanyaan yang membuat tidurnya tak nyenyak
terus menerus mengganda, beranak pinak pertanyaan-pertanyaan yang baru. Ia putuskan
92
untuk berhenti memikirkannya lebih lanjut, namun pikirannya yang kacau membuat Riang
tidak bisa menikmati tidur di atas kasur yang empuk!
Kasur empuk, fasilitas yang nyaman dan memikat memang bukan jaminan
kebahagiaan. Letak kebahagiaan kemungkinan besar … ada di dalam fikiran.
MATAHARI SUDAH SEPENGGALAN, sinarnya cukup kuat untuk mengeringkan
pakaian yang basah. Riang tak menemukan Pepei di sampingnya. Ia bangun dari tidurnya,
kongkok di kasur ia memperhatikan jejeran buku yang ada. Itu barang-barang yang
mengerikan! Buku biru yang membuatnya bingung mengintip di antara himpitan
ensiklopedia. Riang begidik. Satu buku memusingkan, bagaimana dengan buku yang lain. Ini
buku-buku yang membuat kacau pemikiran orang!
Kamar menjadi lorong sepi. Lorong yang menakutkan! Lorong yang dihiasi barang-
barang mengerikan! Bagaimana mungkin kekacauan terjadi padaku? Kenapa kekacauan tidak
terjadi pada Pepei. Dia punya pertanyaan aneh, tapi kenapa pertanyaan itu tidak membuat dia
memiliki beban berat? Apa yang menyebabkannya? Riang mual. Ia masuk ke dalam kamar
mandi. Sekeluarnya dari sana ia mencari Pepei di ruang tamu, di kamar mandi sebelah, di
sumur dan halaman depan, hasilnya nihil. Ia tak menemukannya di mana-mana.
Dalam pada itu, ia mulai menemukan keanehan, mengapa rumah yang besar ini,
penghuninya hanya Pepei? Kemana yang lain? Apa dia memang sendiri di rumah ini?
Pepei sebenarnya hanyalah bagian dari tujuh orang yang tinggal di rumah ini. Rumah
ini sebenarnya merupakan tempat kumpul, base camp, atau semacam shelter, bagi orang-
orang yang berkumpul dalam jaringan yang Pepei buat bagi orang-orang yang membutuhkan
tempat barang sehari, dua hari atau sebulan sebelum menemukan tempat yang cocok untuk
dijadikan sebagai tempat tinggalnya. Sehari-hari tempat ini selalu diisi diskusi, dan tempat
bedah dan nonton film. Hari-hari yang sepi ini lebih dikarenakan orang-orang yang tinggal di
sana tengah mengadakan pendampingan selama beberapa minggu terhadap sebuah kasus
penyerobotan tanah di sebuah desa, di pinggiran Yogyakarta.
Pepei tidak ikut serta, karena perkerjaannya sebagai kepala perpustakan di sebuah
lembaga penelitian membutuhkan tenaga dan fikiran ekstra. Hari sabtu minggu dan hari-hari
besar lain adalah hari perayaan dia, hari liburan untuk menyegarkan diri kembali dari
rutinitas kerja. Beruntunglah orang yang tidak mengetahui hari kerja Pepei, datang ke tempat
itu tanpa perencanaan dan bertemu dengannya.
Kebingungan, setelah mencari Pepei ke sana ke mari, membuat Riang memutuskan
untuk duduk di ruang tengah, melihat tumpukan majalah. Bosan, ia mencari-cari remote
93
control. Tidak menemukan alat itu, ia nyalakan televisi yang mati. Itu hanya sebentar.
Setelah menekan-nekan tombol salurannya cukup lama, ia bosan. Televisi dimatikan.
Riang kembali gelisah. Saat ini ia tidak tahan dengan kesendirian. Pandangan
matanya beralih dari satu titik ke titik lain. Ia berdiri mondar-mandir. Masuk ke dalam
kamar, melihat kembali jejeran buku, merasakan kembali bagaimana tangannya maju mundur
utuk memegang buku biru yang membuatnya ragu.
Sepi itu tak berlangsung lama. Azan dzuhur berkumandang. Sebuah ketukan
terdengar dari luar. Seseorang masuk begitu saja. Riang terkejut!
”Mau bertemu dengan siapa?” Tegur Riang.
Bukannya menjawab lelaki itu malah balik bertanya.”Lha, kamu siapa?!”
”Aku Mahdi! Apa urusan kamu di sini?”
Riang menyodorkan nama sebagai ketebelence”Aku teman Mas Pepei...”
”Ooooh” Senyum sinis muncul di sisi kanan bibir Mahdi.
”Mas salah satu penghuni rumah ini?”
”Bukan... maen-maen aja ke sini!” Mahdi masuk ke dalam dapur. Ia menyeduh kopi
kemudian datang kembali, menyalakan rokok.
”Dzuhur!” Ia seolah mengingatka Riang.
”Ya?”
”Sudah Dzuhur, nggak shalat?”
“Nggak Mas, nanti aja…”
Tahun ini, Riang hanya shalat dua kali. Itu pun shalat sunah, Iedul Adha dan Iedul
Fitri.
”Kamu muslim?”
”KTP sih iya tapi kalau ditanya agamanya apa aku tak tahu harus jawab apa.”
”Kok aneh! Kalau di KTP mu muslim, Kamu jangan setengah-setengah. Kalau
muslim Kamu harus jalankan tetek bengek ibadah!” sekali lagi Mahdi bilang: jangan
setengah-setengah!
Riang tidak suka caranya berbicara. Alarm dirinya berbunyi. Tetek bengek?
Memangnya ibadah itu tetek? Sembarangan bicara orang ini!
Mahdi tersenyum mendapati Riang terdiam.
”Aku juga dulu seperti Kamu ...” Mahdi senyum sinis lagi. Ia meralat ucapannya,
”Maksudku, dulu aku lebih dari Kamu. Agamaku juga Islam...” Mahdi memikirkan siapa
nama orang yang tadi berkenalan dengannya...”Siapa namamu ... sori?”
”Riang!”
94
”Ya, agamaku juga Islam tapi ... lain soal ketika aku bertemu dengan seseorang ...”
Mahdi menunggu Riang bertanya tapi Riang tetap diam seperti sediakala.
”Di Parang Tritis, di pantai berpasir hitam itu pada satu waktu aku ketemu seorang
lelaki yang tengah memandang laut. Aku ajak dia untuk bicara tentang apa saja. Apa saja
yang pokok ujungnya bakalan kubelokan pada ajakan untuk beribadah pada Tuhan. Tapi
Kamu tahu? Ternyata orang yang akan aku ajak itu tak bertuhan! Edan ... aku baru pertama
kali ketemu orang yang gak percaya Tuhan! Hari itu adalah kesempatan. Aku ajak dia bicara
tentang ketuhanan, ia meladeni. Aku ajak dia untuk buktikan pencipta di balik ciptaan, dan
lelaki itu malah bilang ketiadaan pencipta di balik ciptaan! Aku tidak bisa mematahkan
logikanya. Aku bingung. Aku tidak bisa membungkam mulutnya. Karena kesal, aku pura-
pura pulang dan pas orang itu lengah, aku ambil cangkang kerang besar! Dari belakang aku
hantam kepalanya! Orang itu kejang-kejang! Mampus orang kafir tak bertuhan! Aku ludahi
mukanya. Aku pergi selagi lelaki itu mengerang-erang, tapi setelahnya, ... setelahnya, Kamu
tau apa yang terjadi?”
”Tidak.” jawab Riang mulai tertarik dengan obrolannya.
”Aku pulang ke masjid tempatku menjadi takmir. Tempatnya di pinggir pantai Parang
Tritis... aku pikir aku menang melawan orang kafir, tapi dalam perjalanan pulang mataku
tidak fokus memperhatikan lingkungan. Pandangan mata ku mendadak kosong. Hatiku
mengajak bicara...
Benarkah?
Jangan-jangan?
Kalau begitu ...
Ah masak? bermain dikepalaku!
Aku berusaha menghalau yang diungkap orang atheis yang
baru ku hantam!
Tiba di masjid, kata-kata tak bisa lagi kubendung lagi! Kata-kata itu mengalir...
semakin malam dan siang berganti pertanyaan itu mampat dan membludak! Aku tak bisa
membendungnya! Makin dipikir makin sesak, makin pekat menutup kesadaran! Aku jadi si
peragu... keraguan itu semakin rindang, sampai akhirnya aku terlambat mengetahui, jika aku
jadi ...” Mahdi mengajak Riang masuk ke dalam ceritanya.
”Jadi apa?”
”Jadi edan! ... kata orang-orang, aku jadi sering berteriak-teriak tengah malam, dan
mengaku sebagai Imam Mahdi pada orang-orang yang datang di sore dan malam hari untuk
mengaji. Aku imam penyelamat zaman!”
95
”Bagaimana Mas bisa sembuh?”
”Itulah... aku ditemui orang yang aku pukul kepalanya pakai kerang dari belakang!
Semula orang itu mau menyelesaikan masalah, tapi saat melihat diriku seperti itu, dia merasa
kasihan... lelaki itu malah ajak aku bicara... dan gilaku sembuh! Aku sadar!”
Mahdi sadar dalam versinya. Orang yang kepalanya dihantam, yang semula
mendatangi Mahdi untuk membuat perhitungan, memahami bahwa orang yang tengah
ditemuinya mengalami kerusakan mental yang berawal dari penyangkalan argumentasi
terhadap sebuah keyakinan. Di satu sisi Mahdi tak mau melepaskan keimanan yang lalu, di
sisi lain, fikiran membisikan bahwa perkataan orang yang ditemuinya di Parang Tritis adalah
kebenaran.
Lelaki itu mengajak Mahdi membuka pikiran. Lelaki itu menuntunnya hingga Mahdi
mengetahui permasalahan apa yang dihadapinya benar. Ia mengajaknya menuju ujung
sebuah keyakinan.Ujung di mana keyakinan berawal. Mahdi ditemani agar ia mau bersikap
jujur terhadap pikirannya sendiri. Dan ketika Mahdi memilih untuk jujur, ia pun sembuh
perlahan-lahan. Gilanya hilang.
”Bisa nebak orang itu siapa?”
Riang menggeleng kepala.
”Orang itu Pepei!”
”Hah, Mas Pepei?!”
”Iya si Pepei!”
”Hebat ...” Riang tersenyum.
Tapi Mahdi menyanggahnya, ”Itu dulu... maksudku, hebatnya dulu. Kalau sekarang,
... pekerjaan yang buat dia diam di dalam ruangan ber-AC buat pemikirannya mandul!
Kenikmatan hidup buat dia jadi lemah! Jadi tidak seberapi-api dulu! Hilang sudah
konsistensinya terhadap perubahan! Dialektikanya mandek! Ia jadi mahluk yang ditinggalkan
evolusi! Purba! Ya ... jadi manusia purba yang hampir-hampir tak memiliki guna....Orang
yang mengkhianati rakyat sebaiknya minggir!”
Riang tidak mengerti atas dasar apa orang ini menjelek-jelekkan Pepei setelah
mengangkatnya. Seharusnya ia menghargai Pepei yang telah menuntun kesadarannya.
Lagipula, seenaknya saja menuduh Pepei tak mempercayai Tuhan.
”Apa urusanmu dengan si Pepei?” Mahdi kembali mengajak Riang bicara.
”Untuk ketemu Emha!”
”Emha Ainun Nadjib?”
”Benar.”
96
”Untuk apa temui itu orang?”
”Aku mau belajar Islam.”
”Agama Islam? Alaaaah .... memangnya agama benar-benar berasal dari Tuhan?
Agama itu kebudayaan! Hasil cipta rasa dan karsa! Agama manusia yang buat! Tuhan itu
hanya ada di kepala manusia! Materi selalu mendahului essensi! Tuhan itu dusta yang dibuat
manusia! Aku tidak mempercayai keberadaannya! Tuhan telah kubunuh! Lehernya sidah
kugorok sampai darahnya terpancar-pancar!”
Riang tidak mau menimpali perkataannya. Ia hanya diam, mencoba melarikan
pandangannya dari tatapan Mahdi. Ia berusaha lari dari sergapan pemikiran Mahdi, namun
lelaki itu terus mengejarnya. Dia berusaha memasukan pemikirannya pada pemikiran Riang.
Kuping Riang terbuka namun pemikirannya tertutup dari apa yang dibicarakan.
Cukup sudah!
Tapi Mahdi tak mau berhenti. Ia terus menerus bicara tentang Tuhan itu tidak ada!
Tuhan diciptakan manusia karena ketidakberdayaannya!
”Yang, agama Tuhan hanyalah perkakas yang digunakan manusia jahat untuk
melindungi kejahatannya. Agama itu bangkai! Tai!”
Riang ingin memukulnya, bukan karena apa yang diutarakan Mahdi. Ia membenci
bombardirnya yang memuakan. Setan! Seharusnya ia melihat orang yang diajaknya bicara
tengah melakukan apa. Kalau dia bilang menjadi sadar karena tidak mempercayai Tuhan, tapi
apa dia tidak memikirkan kalau perkataannya berangasan itu pertanda... pertanda kalau dia
kesurupan! Kesurupan itu tidak sadar!
Bukan main Riang kesal padanya. Tanpa memperdulikan perasaan Mahdi, toh Mahdi
sendiri tidakmemperdulikan perasaannya, maka Riang masuk ke dalam kamar.
Setan dia datang lagi!
Mahdi masuk ke kamar. Awalnya ia berpura-pura melihat-lihat buku, kemudian
bersandar di dekat Riang. Dan kembalilah Mahdi meracau.
”Boleh aku tanya? ... Boleh kan?”
”Terserah Kau!” Riang menatapnya garang! Ia menggelar tubuhnya di kasur.
”Coba perhatikan pertanyaan ini Bung”
Bang bung bang bung!
”Aku ada oleh karena itu Riang ada... Riang ada karena itu aku ada.... alam semesta
itu ada oleh karena kita ada.... kita ada oleh karena itu Tuhan ada.... seandainya kita berpikir
bahwa Tuhan tidak ada berarti Tuhan memang tidak ada! Tuhan itu cuma ada di dalam
pikiran manusia Yang!”
97
Perkataan itu memaksa Riang untuk menundukkan kepala. Bangsat! Riang melamun.
Kata-kata itu mengorek hati dan mencemari kesadarannya. Di tengah kebingungan, Pepei
masuk ke ruang tengah, menggosok-gosok rambutnya yang basah. Ia yang bertelanjang dada
membuat Mahdi terkejut.
Sedari tadi, setelah membeli makan siang untuk Riang, Pepei berada di sumur.
Obrolan Mahdi yang meledak-ledak didengarnya. Ia tidak menyegerakan diri masuk ke ruang
tengah demi mendengar mendengar perkataan Mahdi dari luar. Dijelek-jelekan sedemikian
rupa, Pepei tetapi ia cukup mampu menahan emosinya. Baginya, meski tidak bisa
dibenarkan, usaha jelek menjelekkan itu biasa terjadi di dalam dunia ide. Dan saat ini ketika
memasuki ruang tengah, ia melihat seolah-olah mata Riang meminta tolong padanya.
” Jangan terlalu difikirkan. Itu cuma permainan kata-kata!” Pepei tanggap.
Riang melihat wajah Mahdi sekilas. Wajahnya berubah. Mahdi serasa di martil! Ia
menerka-nerka apakah Pepei mendengar perkataannya. Keringat dingin mulai mengucur!
”Mari kita ulangi perkataan Mahdi,” ajak Pepei. ”Jika Mahdi ada maka Riang ada?...
hm ... Di... umurmu berapa?”
Mahdi berusaha mempertahankan harga dirinya. Ia memaksa menjawab dan melihat
Pepei sinis. ”Dua puluh empat!” katanya.
Pepei berpaling ”Umurmu?!”
Riang menjawab, ” ...”
Nah, sewaktu Mahdi ada, Riang belum ada kan? ... Berarti jika aku ada belum tentu
kamu ada! Jika Mahdi ada belum tentu kamu juga ada!”
Pepei melirik ke arah Mahdi.
”Nah yang kedua, ... alam semesta ada oleh karena kamu ada, karena kita ada!
Benarkah begitu? Tidak mesti! Sewaktu kita ada .... sewaktu kita belum dilahirkan, alam
semesta sudah ada! .... ” Pepei kembali melirik ke arah Mahdi. Ia menanti respon orang yang
telah menjelek-jelekkan dirinya.
”Yang ketiga .... ketika Mahdi mengatakan seandainya kita tidak ada maka berarti
Tuhan pun tidak ada, kemudian aku membakar Mahdi ... aku membakar Riang ... maka
Tuhan akan tetap ada! Alam semesta akan tetap nyata! Itulah jawaban orang yang menyakini
agamanya! Tuhan tetap ada! Apa yang Mahdi utarakan hanya akrobatik kata! Permainan
bekel semata!”
Riang merasa tenang oleh jawaban yang Pepei sampaikan. Uh, Mahdi memfitnah
Pepei, tak mempercayai Tuhan! Keterlaluan! Riang geram! Ia menganggap Pepei
membelanya, pada kenyataanya tidak juga. Nanti segalanya akan terbuka.
98
Mahdi berkeringat, kausnya basah di ketiak. Tak berucap, ia mendengus! Tanpa
berkata-kata ia meninggalkan mereka lalu menuju sumur. Lelaki itu membutuhkan air untuk
meredakan emosinya.Selepas apa yang mereka bicarakan di ruangan tengah, Pepei menyusul
Mahdi menuju sumur. Riang mendengar perdebatan yang berusaha di tahan namun mereka
tak mampu menyembunyikan.
”Apa yang kau lakukan?! Memangnya segampang itu berpindah keyakinan?!” Pepei
susah payah menekan suaranya.
”Apa salahku? Memang faktanya demikian! Mas sekarang jadi hilang keberanian!
Hilang keradikalan!”
”Apa kau fikir keradikalan, keberanian harus ditampakkan dengan sampah doktrinasi
semacam itu?! Gunakan adab dalam bicara ... Tak peduli keyakinannya apa, orang harus
memiliki etika!”
”Indoktrinasi apa?! Ini kebenaran!”
”Memang Kau sudah lama mengenalnya? Kalau sudah, tidak terlalu
dipermasalahkan! Ini ...! Baru kenal saat itu, Kau sudah langsung menset semena-mena
pikiran Riang, mengindoktrinasinya!”
”Mas ... sudah tekena racun humanisme universil!” Riang mendengar Mahdi tertawa.
”Aku tak peduli humanisme! Aku tak ambil pusing dengan bermacam isme! Yang
aku peduli: manusia apa pun keyakinannya, tidak berhak melakukan doktrinasi dalam
melakukan penyebaran keyakinannya!”
Brak! ... Duk! Duk! Duk! Riang mendengar bunyi ember jatuh, dan mendengar
ancaman.
”Kalau berani jangan dengan benda mati! Kalau kau memang yang sejati, lawan aku!
Jangan seperti waktu dulu saat Kau menghantamku dari belakang!!!”
Riang tegang mendengarkannya. Ia berandai-andai, bagaimana kalau tantangan itu
diterima Mahdi?
Perkelahian tak bersambut.
Mahdi tahu, ia tak mungkin mengalahkan Pepei. Ia meninggalkan Pepei melewati ruang
tengah tanpa melihat Riang. Ia membanting pintu! Keras-keras!
Adanya pertengkaran itu menjadikan Riang tak kerasan. Kedatangannya
mengakibatkn kedua orang itu terlibat perseteruan. Ia pun memutuskan untuk pulang
sebelum Ashar tiba. Seribu satu alasan dipikirkannya, dan ia menemukan bahwa Bapak
membutuhkannya di Thekelan, untuk mengurusi lomba panjat pinang tujuh belasan.
99
Pepei tak berusaha menahan kepergiannya Riang. Ia sendiri tidak merasa nyaman
dengan apa yang terjadi. Usai mengantar pada sebuah lokasi, menuntaskan janji pembicaraan
mengenai keberanian, Pepei antar Riang hingga terminal. Dimasukinya bus yang akan
membawa Riang menuju Kopeng.
Dia atas bus itu Pepei meminta maaf atas segala sesuatu yang membuat pikiran Riang
tidak beres. Ia menambahkan kalimat bergharga yang ternyata merupakan pertemuan
penghabisan dengannya.
”Yang ... kamu bisa berlari dan boleh berlari dari pertanyaan mendasar mengenai
tujuan hidup yang terus menerus datang menuntutmu! Namun ... pertanyaan itu akan terus
menerus mengejarmu dikala sibuk, mau pun disaat kamu sendiri.”
”Tak ada yang bisa bersembunyi darinya Yang! Kamu harus menemukan jawaban
pertanyaan yang pernah kamu pertanyakan ... Jika tidak Kamu akan terus menerus
mengalami kegelisahan! Jika tidak menuntaskannya, Kamu bakal menjadi manusia yang
hidupnya setengah-setengah! Manusia yang tidak mengetahui tujuan hidupnya di dunia untuk
apa!”
”Ingat! Tak ada satu pun manusia yang bisa bersembunyi dari bisikan hatinya. ...tak
ada satu manusia pun... ”
Riang meresapi kedalamannya. Kata-katanya yang sejuk menjalari hati. Kata-kata
yang Pepei ucapkan direkamnnya di dalam memori.
”Terimakasih atas segalanya Mas!”
Mesin bus menyala. Supir bus meloncat dan duduk dibelakang setir.
Sebelum Pepei turun, Riang mempertanyakan sebuah pertanyaan yang akan
mempengaruhi penerimaannnya terhadap warna warni keyakinan.
”Maaf kalau boleh tahu agama Mas Islam ya?”
Pepei tak lekas menjawabnya. Ia menghirup nafas dalam. Pandangannya kokoh,
senyumnya menyapa Riang dengan kedamaian.
”Apa hubungan kita bakal terpengaruh hanya karena kita memiliki perbedaan
keyakinan!?”
Riang menggeleng.
”Kalau aku tidak beragama bagaimana?”
”Tidak beragama?”
”Agamaku bukan Islam seperti yang Kakekmu, Emha, dan yang sahabatku Fidel anut.
Aku tidak mempercayai satu agama pun Yang.”
”Bagaimana mungkin?”
100
”Mungkin saja, realitanya berdiri di hadapanmu.”
”Mas tak mempercayai Tuhan?”
”Ya.” Pengakuannya demikian tenang. Ketenangan itu mempengaruhi penerimaan
Riang terhadap keyakinannya.
”Setidaknya aku tidak penasaran,” desah Riang. Ia kemudian tersenyum,
mengulurkan tangan. Mereka berjabatan.
Pepei turun turun dari bus yang mulai berjalan perlahan.
SORE INI ADA KESEGARAN di udara ketika Riang berhadapan dengan atheis
yang santun. Atheis yang sangat baik padanya dan Riang yakin, ia baik pula terhadap orang
lain. Riang bersyukur sempat mengenali dirinya. Mengenal sesosok lelaki tegar, yang
konsisten menjalani keyakinan akan ketidakpercayaan terhadap Tuhan, namun memiliki
kebaikan hati yang berbanding terbalik dengan informasi, yang dulu sering disampaikan
melalui pendidikan moral guru-guru di sekolahnya. Seandainya banyak orang seperti Pepei,
tentu … bumi ini bakal awet selama-lamanya.
101
KONSPIRASI
Di sebuah jalan, di bawah tiang listrik mati tiga orang pria berkumpul. Yang satu
tampak tenang namun kata-katanya tajam dan kejam. Yang lainnya tinggal dijerang
menunggu titik didih pembicaraan untuk meluapkan kemarahan.
”Coba kita permak dia, tidak usah di matikan. Ini sebatas pelajaran! Siapa yang
mengkhianati ... siapa yang membangkang, siapa yang menghalangi jalannya partai maka ia
harus dihentikan! Kita harus membuatnya kapok!”
”Apa kau yakin dia bakal takut oleh ancaman kita?! Kau sendiri yang bilang, kalau
dia tidak pernah memperlihatkan rasa takutnya pada orang!”
”Dia memang tidak pernah memperlihatkan rasa takutnya, tapi apakah manusia tidak
memiliki rasa takut? Dia memilikinya hanya tidak memperlihatkan pada siapa-siapa.”
”Siapa yang akan menjalankan rencananya? Siapa yang berani berhadapan
dengannya!? Apa kau tidak pernah berpikir, kedepannya, bagaimana kalau dia tau dan dia
memperpanjang urusan dengan kita?”
”Aah, terlalu banyak pertimbangan, bisa-bisa mandek urusannya! yang harus kita
pikirkan, dia ..., itu menghalang-halangi pergerakan partai secara tidak langsung, dia
menggerogoti dari dalam, menjadikan kader-kader muda sebagai pembangkang. Maksudku,
itu cukup untuk dijadikan alasan untuk menggunakan kekerasan padanya!
”Bukannya jalan partai kita sepenuhnya pemikiran, tidak menggunakan kekerasan?!”
”Siapa bilang begitu. Jika sekarang tidak mungkin lain kali ya! Kau pikir Stalin, si
tangan besi dulunya melakukan apa? Dia dibesarkan Lenin dan dibiarkan melakukan segala
tindak kekerasan untuk mendukung partai! Melakukan sabotase, intimidasi terhadap gerakan
lain dan kawan yang tak sehaluan dengan kinerja partai! Ini wajar dalam pergerakan ide.
Sebuah ide harus selalu dikawal kekuatan otot! Lagipula, apa yang orang katakan tentang
lelaki itu, apa yang kau dan kita bayangkan tentangnya terlalu berlebihan. Kalau kau takut
berhadapan dengannya, kau memiliki kawan yang saling menguatkan. Kawan-kawan satu
jaringan, satu ide, satu radikalisme dalam pemikiran ini. Kau pikir mereka tidak akan tinggal
diam jika salah seorang diantara kita digebuki oleh seorang pengkhianat! Yang perlu Bung
tahu, dia itu sendiri meski banyak orang yang memiliki ke dekatan personal dengannya, dia
102
selalu sendiri... Dalam pengamatanku dia tidak mau melibatkan orang lain dengan masalah
yang dihadapinya. Apalagi jika masalah pribadi.”
”Apa yang kau maksud di cukup jantan?” Pria itu mendengus.
”Dia tidak pernah mengajak orang lain berkelahi untuknya. Ini kelebihan dia tetapi
sekaligus kekurangannya. Kita akan manfaatkan itu!”
”Bukankah kita jadi terlihat seperti pecundang? Melawan seorang menggunakan
banyak orang? Kalau begini, rasanya pun tidak membenarkannya.” Seorang pria membantah.
”Nurani lagi nurani lagi! Nurani itu bukan alat berpikir. Alat berpikir itu otak!
Sekarang yang harus dipikirkan adalah partai dan tujuannya. Siapapun yang menggembosi,
yang mempreteli dari dalam, dia harus dihancurkan! Caranya tak masalah dengan apa saja!
Materi di hadapan materi sama saja!”
Orang yang diajak bicara mengulangi kalimat terakhirnya, seolah membenarkan,
”Hmmm materi di hadapan materi sama saja! Oke kalau begitu, tapi siapa yang
melaksanakannya?”
”Kau saja!”
”Kenapa mesti aku?”
”Kau kan punya lingkaran pertemanan dengan preman!?”
Pria yang dilimpahi tanggung jawab menatap sinis. ”Memang kau tak memiliki teman
preman apa?!”
”Bukan begitu. Baiklah ... kalau aku yang kalian tunjuk untuk membereskan, tidak
masalah, tapi ...” ia berpikir tapi tidak menemukan jawaban. ”sebaiknya jangan ... aku ... aku
... tahu aku tidak bisa mengalahkannya!”
”Memangnya aku bisa?!”
”Pukul saja dari belakang! Seperti yang kau ceritakan dulu pernah memukulya dari
belakang!”
”Aku memang pernah sukses, tapi tidak untuk yang ini, tidak untuk sekarang!”
”Pecundang! Bilang saja kau takut padanya!”
Orang yang dikata-katai meranggas, ia marah!
”Apa Kau bilang?!” lelaki itu mengangkat kerah pria yang mengata-ngatainya, tetapi
salah satu yang sedari tadi paling sedikit melibatkan diri melerai.
”Sudah ... untuk apa gunanya bertengkar! Aku punya seorang kenalan. Saat ini dia
sedang kudekati. pikirannya hampir berubah total sama dengan pemikiran kita! Kalian tahu
sendiri bagaimana radikalnya orang yang baru berubah. Dia yang akan kita gunakan untuk
103
memberi pelajaran ... tak usahlah kita menggunakan tangan sendiri untuk membersihkan
kotoran!”
Dengan leraian dan penjelasan itu, selesailah permasalahan. Tapi apakah orang yang
mereka limpahkan harapan mau melakukannya?
JEEP BERJALAN PERLAHAN menuju warung tempat Suwito biasa nongkrong.
Jeep berhenti. Pintu terbuka. Ada enam pria di dalamnya. Lima pria bertubuh keka,
menggunakan jaket dan emblem sebuah organisasi pemuda turun dari pintu Jeep, mendatangi
warung. Satu pria lainnya yang berwajah paling bersih, berambut paling klimis menggerak-
gerakan leher dan tangannya. Sepatu boots, berbunyi ketepak-ketepok di jalan. Sampai di
warung, ia mengeluarkan pak sigaret dari kantung celana jeansnya. Pria itu menggerakan
roda kecil pada kota berlabel Zippo. Cur! Api menyembur.
“Di mana Suwito?!” Tanyanya menekan orang-orang yang berada di dalam warung.
Orang-orang itu memiliki naluri yang peka seperti binatang. Mereka diam. Solidaritas
membuat mereka bungkam.
“Sekali lagi aku tanya, di mana Suwito?! Mana yang namanya Suwito?!”
Bahasa tubuh beberapa orang beriak. Sekilas mata mereka menunjuk Suwito yang
saat itu sedang merokok santai di bawah pohon, di dekat warung.
Lelaki itu faham. Pria itu mendatanginya.
“Kau yang namanya Suwito!?”
Orang yang ditanya menghembuskan asap, ke samping “Aku Suwito! Kenapa?!”
Pria itu menghisap dalam-dalam rokoknya. Lalu, “Pfuuuuuuh!” ia menghembuskan
asap menuju wajah orang yang sedari tadi dicari. Ia berpaling pada empat lelaki yang
mengikutnya. “Ini orangnya!” lelaki itu memberi instruksi. ”Pukuli dia! Kalian kuandalkan,”
ia memfokuskan perintahnya, ”terutama Kau yang harus membuktikan!”
Kardi menarik kerah baju. Suwito berontak! Dua orang lainnya tanggap, mereka
memberangus tangan Suwito dari belakang. Saat tubuh Suwito dipaksa mendekati tubuh
lelaki yang memberi instruksi, tensi amarah Suwito drop. Emblem nama yang di jaket lelaki
itu menggetarkan jiwanya. Minus yang diderita matanya, membuat Suwito menyesal. Ia tak
mungkin menentang. Dua orang pria mendorong tubuhnya. Suwito diseret ke selokan dekat
bangunan kosong. Ia mulai ketakutan. Wajahnya seperti baru dikucek pemutih oleh laundry!
Mereka berhenti di samping selokan. Suwito merunduk-runduk mengingat kematian.
Lelaki yang memerintah masuk ke dalam Jeepnya. Kardi lantas melompat. Kepalanya
menyundul hidung Suwito sampai berdarah. Ia diseret ke arah bangunan kosong. Lutut
104
Suwito ditendang, kepalanya diadu dengan tembok. Ia melenguh. “Uh, uh, uh!” Ulu hatinya,
disodok boots. Suwito meringis.
Pria yang memberi perintah surut. Ia memberi isyarat pada pria lainnya untuk
mempermak Suwito. Tubuhnya jadi gebok pisang. Ia ditendang, dibogem, disiku, dipiting. Ia
ingin melawan tapi informasi yang beredar tentang nama seorang pemimpin organisasi
kepemudaan membuatnya tak berani. Suwito mengiba.
”Om Toto! Ampun Om. Sakit! Nyeri! Uh, uh, uh” Ia meringis dan memohon ampun,
tetapi lelaki yang dipanggil om Toto olehnya malah menghisap sigaretnya dalam-dalam.
Suwito tak tahu lagi siapa yang harus dimintai pertolongan Benaknya berkejap-kejap
ingatan akan kampung halaman di Ambon. Ia teringat akan perlindungan dan kasih sayang
yang senantiasa di berikan ayahnya. Ia melolong “Papaaaaa....! Tolong anakmu
Papaaaaaaaa!”
Mendengar teriakan menyedihkan itu, Sekarmadji, salah seorang di antara pria itu
terpengaruh. Ia mengendurkan cengkraman tangannya. Suwito merasakan. Di tengah situasi
yang mencekam ia melihat kesempatan. Dengan hentakan yang cepat Suwito melepaskan
cengkraman tangan pria satunya. Suwito lepas, ia berlari mengerahkan kemampuannya yang
terbaik. Kardi berusaha mencegahnya. Suwito berlari seakan larinya merupakan pertaruhan
hidup dan mati.
Tapi itu untuk sementara. Suwito salah menentukan arah larinya. Ia melewati Jeep.
Brak! Pintu Jeep terbuka. Wajah Suwito yang sudah tak karuan membentur kaca yang tebal.
Tubuhnya meluruh ke bawah. Beramai-ramai lelaki yang semula memburu mengangkat
tubuhnya, membawa dia ke pinggir solokan, lalu melemparkannya.
Tubuh Suwito melayang! Tulang punggungnya lebih dulu membentur dasar selokan!
Tak henti di sana, Kardi meloncat ke dalam selokan, menginjak Suwito! Histeria Suwito
berteriak, ia melolong ketakutan, menggeliat di dalam selokan.
Ia meratap, “Mamaaaaaaaaaa, tolong beta! Mamaaaaaaaaaaaaa …” Tolong betaaaaa!
............. Tolong Mama! Anakmu mau dimatikan Mamaaaaa! Tolooooong!”
Hanya sebentar Suwito berteriak, karena balok pajang yang gemuknya sebesar
kepalan membuatnya diam. Suwito koma. Ditinggalkan begitu saja di selokan.
SORE HARI, setelah kejadian di selokan, di sekretariat organisasi kepemudaan,
Mahdi bertemu dengan Toto. Ia menceritakan segalanya tentang lelaki itu. Mahdi
105
menambah-nambahi garam dan ketumbar obrolannya. Hampir di akhir pembicaraan, Mahdi
berpesan, supaya tidak ada yang dihabisi. ”Cukup di beri pelajaran!” ujarnya.
”Don ...!?” Toto melirik pada pemuda yang sudah duapuluh tahun dipeliharanya.
”Menurutmu siapa yang pantas melakukan ini?!”
”Aku pantas!” sahut Gendon.
”Ya, ya ... aku tak meragukanmu, tapi kalau mau membunuh lalat yang digunakan
bukan meriam.” Toto terkekeh.
Gendon tersanjung.
”Tapi lelaki itu pintar berkelahi!” Mahdi memotong.
”Comberan! Kau ... yang tak mengetahui apa-apa, tak perlu bicara!” Toto yang tak
bisa diinterupsi, menghardik. ”Kalau dua orang baru itu tidak mampu membereskan, akan
kupertimbangkan orang lain untuk menembakknya!”
Kelenjar keringat Mahdi mengendut. Membunuh itu bukan memberi pelajaran. Mahdi
ingin mengutarakan pemikirannya, namun pria di sampingnya memberi tanda agar ia tak
kembali bicara.
”Mas Toto, maaf ...” Obrolan beralih kendali, teman Mahdi yang ganti bicara, ”saya
rasa terlalu besar resikonya jika harus membunuh lelaki itu. Bagaimana kalau aparat
kepolisian mengkaitkan pembunuhan itu dengan gerakan? Habislah semua. Sia-sialah apa
yang sudah dibangun demikian lama.”
”Oke kita akan beri dia sedikit pelajaran saja.” Toto sedikit simpati pada teman
Mahdi, ia tersenyum” Bagaimana Don?”
Gendon mengangguk, ”Oke! Paling lambat lusa, aku beritahukan dua orang baru itu
untuk menyelesaikan masalah ini.”
Mahdi pun pulang. Ia menganggap hubungan yang selama ini ia jalin dengan
tokoh kepemudaan itu menghasilkan sesuatu. Mahdi tak tahu, jika Toto tak mau tahu apa
yang dilakukan Mahdi dan gerakannya. Toto tak memperdulikan klaim keadilan sosial yang
diungkap dalam setiap pembicaraan. Ia ia tak mau soalan konsep penyamarataan, ia
menganggap tai kucing semua organisasi dan orang-orang yang berbusa bicara tentang
penindasan. Apa yang ia lakukan merupakan perencanaan matang hasil timbang
menimbang.Yang Toto ingin hanya kepatuhan buta dan pengembalian atas uluran tangan
yang harus dikembalikan jika satu saat ia meminta.
SEBELUM GENDON MEMBERI TAHU tugas Sekarmadji dan Kardi yang baru,
tanpa bisa diperkirakan, situasi menjadi buruk. Tanpa sengaja Sekarmadji merasa mengenal
106
lelaki yang tengah berjalan di stasiun. Sebuah kejadian membuat wajah lelaki itu tersimpan
baik di dalam memorinya.
Di dekat penjual es balok, lelaki itu berpandangan dengan Sekarmadji, tetapi seperti
kebanyakan penumpang lain, pandangan itu hanya sekilas, tidak menambat. Lelaki itu tidak
sadar jika sapuanpandangnya itu mendekatkan dirinya pada bahaya hanya dalam hitungan
beberapa menit ke depan.
Tak sadar atas apa yang dilakukannya, Sekarmadji berlari. Ia mencari Kardi dan
menemukannya tengah berbincang dengan seorang juru parkir. Mendengar penuturan
Sekarmdji, Kardi langsung meloncat dari bangku panjang yang ia duduki. Mereka berjalan
cepat, khawatir penumpang kereta api yang menghanyutkan lelaki yang mereka cari. Pada
lorong yang dindingnya ditulisi exit mereka menanti. Dua lelaki itu memperhatikan satu
persatu kerumunan orang-orang, hingga lorong itu hampir menjadi lengang.
“Dia memakai baju apa?” Kardi tak sabar.
“Kaus putih, celana jeans hitam!”
Perburuan itu membuat mereka terengah. Ada semacam ketegangan dalam setiap
pertambahan langkah Sekarmadji. Ia tak yakin atas apa yang dilakukannya. Mereka terus
mencari, berputar dan memperhatikan kerumunan remaja beransel, melihat seorang bapak
yang membujuk anaknya menggunakan bonus mainan yang terdapat dalam bungkus
makanan ringan, juga ibu-ibu, dan tante-tante yang menggeret koper plastiknya menuju
bagasi taksi.
“Itu orangnya!” Sekarmadji berteriak, melihat punggung lelaki yang mereka cari.
Dan langkah kaki pun berderap-derap, setengah berlari. Sekarmadji melihat Kardi
memasukan tangan kanannya ke pinggang. Dalam ketergesaan itu segalanya menjadi cepat.
Ketegangan mulai menguasai. Ia kemudian teringat sesuatu, tetapi apa yang ia ingat tak akan
membantu menghentikan takdir yang akan terjadi.
Sekarmdji tiba-tiba merasakan bumi menjadi sedemikian malas berotasi. Waktu
melambat saat ia melihat tangan Kardi keluar dari pinggangnya. Sekarmadji berteriak
“Jangaaaaan!” namun Kardi tidak mendengar. Ia tak mau mendengarnya sebab dirinya telah
dikuasai keinginan babi yang buta!
Di samping penjual es balok , seorang lelaki jatuh terlentang oleh tusukan yang
sempurna. Belati menancap di tepian jantungnya. Hembus nafasnya melemah. Ia merasa
sakit, hanya dalam beberapa detik. Setelahnya ... lelaki itu kehilangan segalanya. Menjelang
dibunuhnya cahaya sore oleh malam ... di stasiun kota tua itu, seorang lelaki terkapar menjadi
bangkai.
107
KE BARAT
Alam selalu menuai kehendaknya kapan saja. Tak bisa dimutlakkan. Manusia yang
merupakan salah satu unsur di dalamnya, pun demikian, bahkan bisa jadi manusia merupakan
unsur alam yang paling rumit untuk diprediksi.
108
Sejak meninggalkan Yogya, semua menjadi sepi. Tak ada kabar yang Pepei beri
untuknya. Surat-surat Riang tak jua dibalas. Pepei melupakan lelaki dari udik. Lelaki yang
letak rumahnya hampir masuk ke dalam hutan rimba.
Riang merasa disepelekan tapi ia tidak gegabah untuk memvonis sebuah keadaan
sementara ia tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Riang seharusnya beriman pada
Pepei. Aku mempercayainya, ujar Riang, tapi apa memang demikian. Jangan jangan
kepercayan hanyalah pelarian untuk mempercayai bahwa aku tidak diinginkan.
Riang menginginkan pertanyaan itu lewat tanpa melihat lampu penyebrangan. Lewat
begitu saja tak usah dihiraukan, tetapi kesepian justru menstimulasi pertanyaan lainnya
mengenai keimanan: jangan-jangan keimanan hanyalah pelarian yang menenangkan?
Gumamnya, lantas apakah seorang yang tak beriman tidak akan mendapat ketenangan?
Astaga!
Riang terkejut. Ada ruh yang terus menerus mengajaknya berdialog. Ruh sialan itu
menuntutnya untuk menguak kabut pertanyaan yang selama ini ia represi. Riang kembali
gelisah. Pencariannya terhadap Emha di Yogyakarta yang salah sasaran, semakin
membuatnya kebingungan. Emha yang diucapkan ibu, yang informasinya beliau dapatkan
dari bapak ternyata bukan Emha yang ada dalam bayangannya.
Bapak hanya asal bicara. Emha yang mengislamkan Simbah, ternyata Emha antah
berantah. Emha yang sangat sulit ditelusuri dimana keberadaan dan kediamannya. Teka-teki
semakin sulit untuk dipecahkan.
Riang makin sering diam di berbagai kesempatan. ”Riang di rasuki penghuni
Merbabu,” kata seorang penduduk Thekelan. Sungguh, otak Riang tak kosong! Mereka
semua salah! Pemikiran Riang tak melompong! Dalam diamnya ia berfikir! Otaknya berjalan
seperti mesin. Otaknya turbo! Otaknya bergerak cepat, melompat-lompat seperti kuda-kuda
yang biasa dipacu untuk mengantar sayuran --hasil lahan pertaniannya-- menuju Tumpang.
Riang tak peduli orang lain bakal membicarakan dia seperti apa. Kegelisahan
membuat repot dengan dirinya sendiri. Tak ada waktu luang untuk memikirkan anggapan
orang karna kekacauan pikirannya begitu hitam dan menakutkan! Semakin ia diam dan
berusaha mengasingkan diri, semakin sering pula ucapan Pepei sowan di kepalanya.
“Manusia. …manusia,
Ah manusia. Bagaimana seandainya jika kau tidak ada?
Kalau manusia tidak ada, mengapa kita ada?.
Mengapa kita merasa.
Lantas apa yang dimaksud rasa?
109
Duhai gila.
Mengapa kita ada?.
Dengan maksud apa k i ta a a a a a ada?”
Riang memikirkan lontarkan perkataan Pepei di Merbabu.
“Mengapa aku harus ada?” Parau, Pepei menekankan kata-kata.
“O, mengapa aku harus ada!”
Riang mengingat bagaimana ia memutar badannya dan Fidel kembali
memiringkan telunjuknya.
“O, seandainya tuhan ada,
mengapa Tuhan tak memberi tahu
tujuan penciptaan manusia dan semesta?
O, siapa yang mengetahui tujuan keberadaan kita?
Manusia manakah yang mengetahuinya?
Pendetakah?
filosofkan?
ilmuwankah?
petapakah?
O, haruskan hidupku terombang-ambing seperti ini?
O’ haruskan Tuhan ada?”
“Di depan sebatang pohon halangi jalan,
Ini merupakan tanda bahwa keberakhiran. Akhir kepastian.
Tak mungkin dihindari, tak mungkin ditepis.
Batu kelamaan akan menghilang digerus angin.
Manusia,
binatang dan tumbuhan …
tinggal menunggu waktu, menanti tanggal mainnya.
Mati adalah kepastian.
O’, lantas apa yang akan kita hadapi
setelah kematian?”
110
Semakin ia berdiam dan berusaha mengasingkan diri semakin sering bisikan Simbah
silaturahmi di kepalanya.
R
i
a
n
g
K e m a r i
R
i
a
n
g
A y o k e s i n i
R
i
a
n
g
A k u i n i
M
b
a
h
m
u
J a n g a n
111
T
a
k
u
t
A y o k e m a r i d a l a m p e l u k a n M b a h.
M a s u k d a l a m k e d a m a i a n.
R i a n g ... D a m a i Riang!
Riang semakin masuk ke dalam. Terjerumus ke dalam lubang hitam. Ia tengah
melintasi padang kekacauan. Inikah yang dirasakan Mahdi. Bukankah yang kualami kini
sama dengan yang dialaminya? Mataku tidak lagi fokus terhadap lingkungan. Di dalam
hatiku muncul dialog-dialog yang berpangkal pada pertanyaan
Benarkah?
Jangan-jangan?
Kalau begitu
Ah masak? bermain dikepalanya
Bukankah ini yang dirasakan Mahdi dalam pertarungan keyakinannya?
Anarki memukul-mukul kepala Riang.
Di gubug yang berdiri di tengah lahan yang tengah ia garap Riang meringkuk,
menangis dan tertawa sendiri. Ia merasa aneh dengan eksistensinya. Riang belum berkarat. Ia
masih mampu melewati semua kegelisahan ini. Masih ada waktu untuk menuntaskan
pencarian jawaban atas teka-teki yang membingungkan. Masih ada harapan baginya untuk
membuat sebuah pondasi keimanan.
Riang akan terus mencari Tuhan! Ia akan menyembah-Nya! Atau sebaliknya menjadi
seperti Mahdi ....mengangkat batu di atas kepala dan mengkeprak kepala Tuhan sampai
Tuhan menguik-nguik seperti anjing budugan yang buang air besar karena ketakutan! Ia tidak
akan mengkasihani Tuhan!
Riang berani untuk menjadi!
Perjalan hidupnya masih panjang.
WAKTU BERLANJUT ...
di sekitar lokasi wisata Kopeng ... bola yang sudah berjuta tahun memberi
penghidupan pada bumi menjadi katarak di mata! Hujan turun perlahan! Rintihan-rintihannya
112
menjulur terputus-putus, membasahi baju. Hujan yang tercurah terasa hangat sehangat air
kencing. Apakah mungkin di atas langit ribuan malaikat tengah membuka risleting? Cur!
Cur! Mereka merasa bosan, menanti perintah Tuhan untuk mengurusi manusia. Saking
sebalnya mereka tidak tahan! Melawan Tuhan tidak mampu maka pelampiasannya
dikencingilah manusia!? Riang tertawa.
Usai turunkan hasil pertanian di pasar terdekat menggunakan mobil carteran,
punggung Riang bebas merdeka. Ia menembus gerimis menuju pos Kopeng. Selama satu jam
lebih, di pos Kopeng itu, ia menanti. Hujan pun berhenti. Ia menjentik puntung rokok ke
dalam bak. Selarik angin memutarkan sampah di hadapannya. Sisa air hujan mengalir
mengikuti hukum alam, menuju tempat yang rendah.
Angin datang memacu, mengibas tubuh orang-orang, yang mulai berani berhamburan
menuju jalanan. Beberapa orang menahan topi dengan kedua tangannya. Kertas koran yang
diremas-remas, menggelinding, mencocol air seperti roti yang dicocol pada gelas kopi.
Robekan kertas koran lainnya yang ada di sebuah kios, ditiup angin, terbang membumbung,
lalu meliuk.
Riang berjalan cepat, melewati apa saja. Ia khawatir hujan susulan datang sementara
ia tak menyadari jika selembar kertas koran melayang hanya beberapa jengkal di atas
kepalanya. Tiupan angin nampak bersemangat. Kertas koran dengan iklan sepenuh halaman
itu menyusul, melewati tubuhnya. Di jembatan kecil, hembus angin tertahan oleh
pepohonan. Kertas koran kehilangan daya, turun ke bawah, dua kali bergoyang ke kanan ke
kiri lalu menubruk dan menutupi wajah.
Riang berhenti sejenak, memperhatikan koran yang berisi iklan mobil dengan latar
belakang pegunungan dan pesawahan subak yang berundak. Ia lipat kertas koran di
kantungnya sambil berjalan pulang menuju rumahnya. Ia tidak tidak menyentuh kertas koran
itu bahkan hingga ia menggantung baju di belakang pintu rumahnya. Riang tidak mengetahui
bahwa di balik iklan sepenuh halaman itu sebuah berita genting menanti untuk dibaca.
Subuh hari, usai menyapu halaman ia memasukan pakaian kotor yang terbengkalai
beberapa hari ke dalam ember. Sewaktu mengeluarkan barang-barang yang ada di saku
celana dan bajunya, sebuah warta ia temukan dari kantung baju yang kemarin ia kenakan.
Warta yang berasal dari kertas koran di balik separuh iklan itu membuat Riang mengambang
seakan berada di pertengahan dunia nyata dan khayalan.
Seorang lelaki ditusuk sampai mati di stasiun Tugu. Aparat kepolisian mendapati
bahwa korban penusukan adalah lelaki yang beberapa bulan lalu pernah mengagalkan usaha
pembegalan di Thekelan. Dari sana polisi mengembangkan kemungkinan kejadian bermotif
113
dendam, tidak ada satu barang berharga pun yang hilang dari tubuh korban. Informan yang
tak mau disebutkan identitasnya memberitahu ciri-ciri pelaku. Dari ciri-ciri fisiknya, Riang
menarik kesimpulan bahwa mereka adalah lelaki yang pernah mencegatnya di gerbang
kuburan, dan lelaki yang diberitakan tewas dalam kejadian adalah lelaki yang sangat
dikenalnya.
Tepat pada jam yang sama sewaktu Riang menunggu hujan yang seolah diciptakan
untuk memberi kabaran: empat bulan yang lalu Pepei mati di tikam, di dapan sebuah stastiun.
RIANG TAK BEGITU MENGERTI mengenai keberanian bangsa Aria saat
meruntuhkan imperium besar Romawi. Riang tak begitu mengerti mengenai arti keberanian.
Tetapi, keberanian itu muncul ketika ia teringat akan obrolan antara dirinya dengan Pepei, di
sebuah masjid besar berkubah menjelang kepulangannya menuju Thekelan.
Amarah mendorong keberanian Riang hingga ke puncak! Ia pun berkemas dan
hengkang dari desa Thekelan. Menuju bagian barat pulau Jawa.
TARYAN
Sementara itu, saat Riang tengah menimbang nimbang untuk pergi dari desanya, di
dekat barongan. seorang lelaki bertubuh kurus memisahkan diri. Ia berlari, dari massa yang
mengacungkan senjata. Ia mengeluarkan segenap tenaga demi menyelamatkan saudaranya.
Di kali kecil, dipotongnya kali, di kuburan cina, diseberanginya kuburan cina. Ia terjang
onak, ia tendang kerikil. Beberapa kali terjatuh ia pantang mengeluh. Ia tak mau berhenti
meski darah merembes di sela-sela bulu matanya. Ia berlari, berlari dan terus berlari karena
tak rela saudaranya dibakar hidup-hidup di hadapan orang-orang yang dicintai dan
mencintainya.
Di sebuah rumah yang bisa dianggap megah penduduk desa, Taryan duduk dikelilingi
orangtua, mertua, istrinya Radia dan anaknya Chaidir. Mereka berharap kabar yang datang
114
mampu melemaskan syaraf ketegangan. Bukannya ketegangan itu hilang, kedatangan yang
diharapkan malah membawa mereka menuju puncak kecemasan. Setio, lelaki kurus itu
datang mengabarkan dan Taryan harus diungsikan. Ia harus diselamatkan sampai
permasalahan terselesaikan.
Mertua Taryan masuk ke dalam kamar. Dari laci lemari, ia mengambil uang simpanan
dan memasukan beberapa helai baju hangat ke dalam tas. Taryan melihat air mata istrinya
mengalir deras. Ia memandang anak tirinya, ”Jaga ibumu baik-baik Nak!?” Chaidir tak
menangis, ia menganggukan kepala. Pintu belakang dibuka. Diiringi tangisan Radia yang
memecah hati, Taryan berjanji ia akan segera kembali setelah keadaan terkendali. Ia
menghilang di batas antara cahaya dan kegelapan.
Ketika senja menjadi pertanda dibunuhnya cahaya matahari oleh malam, Taryan
berangkat dari Magelang.
MENGGUNAKAN BUS ANTAR PROVINSI Taryan sampai di Jakarta. Dalam
perjalanan panjangnya yang pertama, ia renungi kejadian yang seumur hidupnya baru ia
rasakan. Tak habis fikir, mengapa di dunia ini ada orang sejahat Hatta? Mengapa sedemikian
gampangnya penduduk desa mempercayai berita busuk yang mengatakan bahwa dirinya
memuja babi, mengapa karena menikahi Radia ia harus dihabisi.
Turun dari tangga bus, sandal swallow mendarat di aspal yang tergenang air berwarna
coklat kekuningan. Ia tak mempedulikan. Ia hampa. Matanya menerawang kosong. Kejadian
yang dialaminya beberapa jam lalu membuat shock. Ia tak mampu merespon keadaan di
sekelilingnya. Ia tak merasa jika sebuah mata berongga memperhatikan dari kejauhan dan
mengikutinya dalam diam.
Di bangku plastik berwarna biru Taryan menjatuhkan diri. Ia lihat gelandangan tidur
di balik pilar-pilar beralas koran dan kardus. Lagu dangdut disetel mengoyak telinga.
Beberapa lelaki mengerumun di bawah warung tenda. Mereka bermain judi ceki-ceki
menggunakan kartu gaple. Suara-suara cekakak gemuruh memecah keheningan. Bising
mesin bis yang baru datang dari Garut, Kuningan, Banjar atau kota-kota di jawa Timur
membuat pekak. Dua orang sundal tertawa liar. Panas! Bibir mereka merah darah; matanya
bercelak hitam; pipinya retak-retak karena ramuan bedak yang tak rata karena mercuri.
Ingat dirinya berada di kota besar Taryan membuka tas, mengambil alamat yang
disematkan mertuanya ke dalam dompet. Mata berongga yang sedari tadi memperhatikan
bergerak mendekat. Di dekat tiang listrik yang dicahayai lampu, pemilik mata itu
115
menampakkan wujud. Ia berjalan perlahan mendatangi Taryan sembari mengambil sebatang
rokok dari saku bajunya.
”Kau punya api?” lelaki itu menyatukan jari, membentuk kepalan, sambil
menggerakan jempolnya di hadapan Taryan.
Taryan merogoh korek api john koping tanderstickor dari kantung celana bahan.
Bungkus korek api yang lembab oleh keringat mengharuskan lelaki itu menggesek bungkus
korek api selama beberapa kali. Korek api menyala namun setiap kali itu pula angin meredup
dan mematikannya.
Lelaki itu membenamkan kepalanya ke dalam kemeja. Ada noda berwarna merah
menyala di sana. Asap keluar dari kerah baju. Rokok terbakar.
Taryan terhibur oleh lelaki itu menyalakan rokok dan mengeluarkan kepalanya
seperti kura-kura.
”Kau mau ke mana?”
”Mau ke Jakarta!” Jawab Taryan.
”Ini Jakarta! ... mau kemana di Jakartanya? Payah Kau ini!”
Taryan tergeragap, ia tanggap, ”O Anu Mas! Saya mau ke Tanjung Priok. Mau
ketemu saudara.”
“Tanjung Priok daerah mana?”
“Ndak tau juga, tapi sebentar...” Taryan membuka risleting dompetnya, mengeluarkan
kertas, memberikannya.
”Mas tau alamatnya?”
Lelaki itu mengambil kertas yang disodorkan.
”Mas tahu?” Taryan mendesak.
Lelaki itu berteriak. ”Mana mungkin aku tak tahu! Daerah ini dekat dengan rumah
sahabat karibku, si Mangunsong! Nah ... coba Kau cari angkutan kota di luar terminal sana!”
Tiba-tiba lelaki bertubuh tambun itu memperhatikan tubuh Taryan, ”... Kau orang udik dari
mana sampai tak tahu ibukota kita!?” Ia tertawa.
”Saya dari Magelang, Masnya sendiri?”
”Ya sendirilah tentu! Ada-ada saja Kau ini!”
”Maksud saya, Mas sendiri dari mana? Saya dari Magelang.”
”Oh... ya ... ya ... aku tanggap ... aku tanggap!” ia tertawa. ”Asalku, Sumatera Utara!”
”Jauh sekali rumahnya! Nama saya Taryan! Mas sendiri!?”
116
Lelaki itu berpikir sejenak. Ia hampir salah lagi mengartikan pertanyaan Taryan.”Aku
tanggap ... aku tanggap! Namaku Leonard!” Lelaki tambun itu tertawa. Disangkanya dari
perkenalan itu obrolan akan berpanjang putar. Tak tahunya,
”Kalau begitu ... terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ... saya kesana
Mas?”
”Santai lah...”
”Tapi saya harus pergi.”
”Hai...hai ... Aku tidak bisa memaksa! Tapi, biar Kau aku antar sebab di sini kalau
jalan sendiri bahaya! Kemarin ada orang Garut mati! Ditusuk! Dari pada ada apa-apa dan
apa-apa dari pada, biar aku antar Kau saja!”
Taryan menyetujui. Ia membungkuk, memasukan dompet ke dalam tas dan risleting
ditutupnya rapat-rapat. Angin meniup kain-kain spanduk dan botol aqua. Bungkus gorengan
dan karcis peron yang remek, menggelosor mengikuti tiupan angin. Suara hingat bingar
dangdut koplo berderit. Taryan tak tahu, di luar terminal di sebuah pohon rindang yang
membuat suram apa saja yang ada di bawahnnya, empat orang menunggu kedatangannya.
Tak lama berselang, mereka sampai di pohon itu. Taryan dan Leonard memasuki
bayangan yang suram. Empat orang yang berada di balik pohon mengepung. Tanpa basa-basi
keempat orang itu serempak menyerang. Sebuah pukulan mencium wajah Taryan. Pukulan
lainnya datang menyusul!
Menerima serangan mendadak Taryan kebingungan setengah mati. ”Ada apa ini?!”
Salah seorang berusaha menyarang pukulan lagi di muka Taryan. Si korban menangkis.
Taryan balas melawan. Dijerembabkan satu orang. Kakinya melayang, namun sebelum
kakinya sampai, seseorang memukul Taryan dari belakang. Ia hilang keseimbangan. Ia
kelimpungan. Ia berharap Leonard membantunya. Dan ... betapa terkejut Taryan memergoki
Leonard yang tengah berusaha menendang rusuknya.
Taryan berkelit namun sebuah hempasan kaki kering mengenai pinggangnya. Suara
buk terdengar nyaring! Ia terpojok! Tangannya dipasung. Taryan tak bisa membela diri.
Wajahnya berdarah! Dengkulnya jatuh di aspal. Dalam hujan pukulan dan tendangan ia
ngap-ngapan. Taryan hilang kesadaran saat Leonard menjadikan wajahnya asbak rokok.
SETENGAH JAM KEMUDIAN... jemari Taryan bergerak. Kukunya menggores
pasir yang menggendap. Ia pegangi kepala. Pusing tersisa. Pandangannya masih berpendar-
pendar saat azan subuh singgah di telinga. Ia mengikuti seruan ”mari meraih kemenangan!”
Taryan merasa membutuhkan Tuhan. Dimasukinya gang-gang kecil. Sebuah mesjid kecil
117
menyambutnya dalam keremangan. Ia menuju tempat wudu; memutar keran air; membilas
noda-noda merah pada muka dan bajunya. Ia hadapi cermin dan terpana saat menyaksikan
gigi depannya tanggal.
Hilangnya satu gigi, wajahnya mendadak berubah total. Wibawanya tanggal. Taryan
meringis. Gusi yang mulai dirasakan perih, mengalihkan perhatian, ia bersuci, masuk ke
dalam masjid dan mengikuti shalat subuh yang baru saja dimulai.
Seusai shalat, --ketika-- orang-orang berhamburan keluar, Taryan jongkok di atas
karpet hijau yang lembab dan koyak. Dalam keadaan seperti ini ia tak tahu melarikan diri ke
mana. Ia menjadi individu lemah yang perlu mencurahkan keluh kesah pada sesuatu yang tak
pernah dilihatnya. Setamat memanjatkan doa Taryan mendapati dirinya hanya berdua
bersama seorang lelaki tua.
”Asalamualaikum!”
Orangtua itu membalikan badan ”Apa ane pernah ketemu ente sebelumnya?”
Taryan menggeleng.
”Ada perlu?!”
”Saya Taryan Pak. Baru pagi tadi saya sampai di Jakarta. Saya dari Jawa, sampai di
sini karena ... hop … hop… hop.” (ia ceritakan kejadian di kampung hingga perihal
Leonard), ”Saya butuh pertolongan, uang saya habis”
Lelaki tua itu memandang. ” KTP Ente?”
”KTPnya ada di dompet. Dompet saya diambil Leonard Pak”
Lelaki tua tak percaya,
”Ada perlu apa di mari?!”
”Di mari?”
”Ente perlu apa di Jakarta?!”
”Ketemu paman istri saya Pak ...”
”Ketemuan di mana?!”
”Ndak tahu di mananya.”
”Ente ini bigimana? Ke Jakarta nggak tau tujuan! Sedeng apa sedeng?!”
“Kalau ndak salah Priok nama daerahnya!”
“Tanjung Priok di mana?!”
Taryan gelengkan kepala. ”Mertua saya yang nyimpan alamat keluarga di dalam
dompet. Sekarang dompetnya di tangan Leonard. Sungguh tidak hapal alamatnya! Sungguh
Pak!”
118
“Alesan! Orang kayak Ente bejibun! Minggu kemaren ampir sama! Kagak jauh-jauh
alesannya! Eh sore arinya, ntu orang gua liat maen judi di terminal! Tiga hari yang lalu, hari
kemaren kejadiannya kayak gini juga! Pelakunya aja nyang beda ...kalo dulu laki, nyang ini
ibu-ibu. Datang ke masjid pake nangis-nangis. Alesannya sama ama yang kemaren ...
kecopetan! Terus sekarang Ente!!! Ane udah kagak pecaye!” Lelaki tua itu menantang. Ia
tidak takut badan kerempeng Taryan.
”Mending Ente cari kerja nyang bener dah! Jangan jadi tukang tipu!!! Ente masih
muda. Jangan nyiain idup. Jangan ampe nyesel pas tua nanti!” Lelaki tua berdiri dan
meninggalkan suara sendalnya yang berat.
Taryan melemaskan kakinya di teras masjid. Tubuhnya rebah. Air matanya menitik.
Ia merasa lelah hingga tak sadar, selama beberapa jam Taryan tertidur di atas sajadah, hingga
matahari yang memanggang atap seng, membangunkannya, mengaktifkan kembali otaknya.
Ia lihat jam di atas mimbar kayu bertulis kaligrafi Allah dan Muhammad. Ia merangkai ide.
Jam bingkai emas berbentuk masjid berdetak. Suaranya menyamai detak jantung Taryan.Ia
berjingkat, memisahkan jam dengan paku yang menancap di dinding. Ia masukan jam itu ke
dalam baju.
Jam terlalu besar, Taryan mengurungkan niat. Kepala kembali berputar. Di ujung
kanan kiri dekat pintu, didapatinya dua buah sarung, satu buah mukena. Taryan
menimbangnya. Usai berkalkulasi ia mengurungkan niat kemudian memasuki mimbar yang
terdiri dari tiga tingkat. Ia dapati mix pada tingkat ke tiga; ia dapati lima buah Al Quran pada
tingkat ke dua; dan sebuah kotak kayu, keropak masjid pada tingkat pertama. Ia intip. Di
dalamnya gelap. Taryan ambil besi penyangga mix. Ia pukulkan besi ke arah kunci gembok
berkali-kali.
Gembok terbuka. Suaranya terdengar merdu di telinga. Ia tumpahkan seluruh isinya
ke lantai. Uang yang ada di dalam keropak berisi dua keping receh seratusan, dua lembar
uang lima ratus, tiga lembar lima ribu dan 11 lembar uang seribuan. Jika seluruhnya
ditambahkan maka berjumlah Rp 27200. Taryan mengeruk seluruh uang, memasukannya ke
dalam kantung celana bahan. Taryan beranjak keluar mushalla. Dalam perjalanan kembali
menuju terminal ia diganggu perasaan berdosa, maka diniatkannyalah untuk mengembalikan
uang akhirat itu. Direalisasikannya entah kapan, setidaknya niat itu membuat Taryan cukup
ringan.
Taryan terus berjalan menuju terminal. Sampai di sana ia melakukan gerak cepat. Di
belinya satu botol Aqua serta dua sobek roti seharga dua ribu rupiah. Ia setop bus yang
menurut aparat DLAJR menuju Tanjung Priok. Naik ke atas bus, melalui jendela kusam
119
dilihatnya lokasi di mana Leonard memukulnya habis-habisan. Bus berjalan. Kernet turunkan
Taryan di terminal karena tak tahu tujuan. Turun dari bus ia berjalan menuju sebuah gang
dekat terminal. Ia ingin bertanya pada kumpulan orang yang ada di depan gang, namun
diurungkan karena kebanyakannya bermuka seram tak bercahaya. Pengalaman mengajarkan
Taryan memilah wajah mana yang bisa dipercaya. Ia terus berjalan hingga seorang anak
muda bermata sipit membuatnya merasa harus bertanya. Taryan mendekati meski ia tahu
kemungkinan pemuda itu mengenal paman Radia sangat kecil. Tapi Taryan tak punya pilihan
lain. Tak punya tujuan lain sebab seluruh keluarga di pihak orangtua kandungnya berada di
perbatasan desanya dengan desa Radia. Artinya percuma saja jika ia lari ke sana. Ia
membuka mulutnya setengah. Sebelum suaranya keluar sempurna, pemuda sipit yang
menggunakan menggunakan topi Chicago Bulls, celana jeans Keller ngatung dan singlet
merek Swan itu menanggapi.
“Kayak pusing. Nyari siapa Mas?”
Taryan perlihatkan giginya yang bolong. “Nyari keluarga Dik.”
“Siapa?”
”Paman istri saya.”
Anak muda sipit menggaruk pantat. “Paman istri Mas pasti punya nama dong?!”
“Kalau ndak salah e, ... Joko ... ee, namanya Joko Suseno!”
Tubuhnya anak muda itu tersentak kebelakang, “Siapa? Joko Suseeeeenooooo!?”
Taryan hampir berjingkrak
“Joko Suseno yang mana!? Jangan dulu kayak gitu ...”
“Walah ... wong belum pernah ketemu”
”Alamatnya?”
”Ilang!”
”Mas orang baru di sini?”
”Iya!”
”Kalo gini susah Mas. Tapi siapa tau orang yang Mas cari, cocok ma Joko Suseno
yang gue kenal. Orangnya kumisan? Badannya tinggi besar?”
Taryan tidak tahu wajah paman Radia seperti apa namun dipikirnya, Masak di dunia
ini ada orang bernama sama?
”Ya ..! ya!” sahut Taryan.
Anak muda itu berdiri dari kursi kayu panjang. Ia masuk ke dalam warung dan
kembali sambil mengigit batang korek api. Tanpa bicara apapun pada Taryan, anak muda itu
120
masuk ke dalam gang. Taryan ragu untuk mengikuti dan anak muda itu baru menyadari
setelah jarak 10 meter berlalu. Ia menegok ke belakang, melambaikan tangan.
“Katanya mau ketemu Joko!? Sini gua anter!”
Taryan kuatkan hati. Ia masuki gang kumuh. Kertas nasi bungkus, karet gelang dan
plastik berserakan di sisi kanan gang itu. Semakin ke dalam, semakin becek tanahnya.
Seorang perempuan tua mengenakan kutang hitam menjemur kain diatas genting; seorang
anak peerempuan berumur belasan tahun membetulkan antena televisi. Musik dangdut
meraja, membisingi udara. Udara sepak! Banyak panci gosong digantungkan. Sabut kelapa
untuk mencuci gelas dan piring tergeletak. Baskom berisi air dan piring kotor ditinggalkan
pemiliknya. Ayam kejar mengejar. Ada yang berkelahi menggunakan taji. Ada yang
melindungi anaknya. Ada seonggok bangkai kucing dimakan tikus.
Tidak seperti rumah-rumah di desa Taryan, keadaan di gang ini memprihatinkan.
Rumah-rumah satu petak didirikan di atas tanah yang sempit. Dempet. Tak ada celah untuk
bernafas. Lorong-lorongnya terlalu gelap dan bercabang. Taryan tak mungkin kembali ke
gerbang tempatnya bertanya.
Delapan belas menit berlalu. Anak muda itu berhenti di sebuah rumah tingkat
berbahan triplek. Taryan masuk ke dalam setelah anak muda itu mengisyaratkan untuk
mengikutinya.Di dalam ruangan yang –ternyata—kosong itu, Taryan melihat ke atas. Ia
temukan banyak sekali sarang labah-labah. Atapnya bolong. Sinar matahari menerobos dari
celah-celahnya.. Keraguan muncul.
“Ini rumah bapak Joko Suseno!?”
Anak muda itu berbalik. Ia tatap Taryan sambil mengeluarkan suara yang nyaring
seakan mulutnya menyimpan pengeras suara, ”Ctok!” Beberapa detik setelah suara ctok
menjalar di dinding, tiga pemuda keluar. Umur mereka terlihat lebih tua ketimbang anak
muda yang mengantarkan Taryan. Ia merasa dalam bahaya. Benar, baru saja merasa, ketiga
orang itu memamerkan pisau yang diselipkan di ikat pinggang. Melihat banyaknya bilah
pisau keberanian Taryan amblas. Ia pasrahkan nasibnya.
Anak muda bermata sipit yang tadi mengantar, tidak ikut menggeledah. Ia
memerintah. Menyuruh anak buahnya membuka baju dan celana. Taryan patuh, lain halnya
ketika ia diperintah membuka celana dalam. Untuk urusan yang satu ini ia memohon. Ketiga
pemuda tak pedulikan. Taryan menelanjangi diri dan mereka mendapatkan alat kelamin dan
perlengkapannya, juga geretan serta uang sebesar 22.200,- rupiah. Ke tiga pemuda murka
atas ketidak terus terangan Taryan. Salah seorang di antara mereka maju mencabut pisau.
121
Sebelum pisau berkata, anak muda bermata sipit yang memberi isyarat. Taryan bersyukur tak
jadi berdarah.
Anak muda sipir menyuruh Taryan membalikan badan. Dan sebuah tendangan
sampai. Badan Taryan menghantam pintu triplek. Pintu jatuh.
“Pergi Luh!” Anak muda sipit melempari Taryan dengan pakaian dan celananya
Tak ada orang yang menaruh iba. Taryan menggunakan baju dan celana di tempat
terbuka.Seluruh kekayaan habis. Taryan berjalan gontai tak tentu arah, mencari jalan keluar
dari gang setan. Keinginan mencari Joko Suseno sirna. Kini ia hanya berfikir bagaimana
melakukan survival di tengah lingkungan predator kota Jakarta.
Dua hari setelah kejadian. Dua hari setelah bosan makan nasi buangan, Taryan
mengemis, meminta belas kasihan orang. Dengannya ia membeli makanan yang layak dan
menabung. Di hari ketujuh uang dikantungnya mencapai 10.000,- rupiah. Di hari ketujuh
yang keramat itulah, Taryan sampai di sebuah bangunan yang dikerumuni pedagang kaki
lima. Ia sampai di stasiun kereta yang menghubungkan kota Jakarta dan Surabaya. Ia
berkehendak pulang. Tekadnya bulat, meski uangnya tak mencukupi. Ia siap hadapi resiko. Ia
sudah tak tahan hidup seperti itu dan keinginan yang ditumbuhkan derita menjadi obor
pembakar. Taryan segera mendekati restoran cepat saji di sekitar stasiun. Ia tunggu makanan
yang dilempar ke bak sampah. Ia kumpulkan makanan sisa untuk bekalnya di perjalanan.
Sebuah botol plastik dibuang pemiliknya. Sebuah kaleng biskuit teronggok Makanan dari bak
sampah yang sekiranya awet, ia masukan ke dalam kaleng lalu ia isi kentang goreng serta
beberapa potong biskuit yang ditinggalkan penumpang kereta.
Merasa cukup dengan bekal mengkerenyitkan, ia menyodok tangannya menuju
celana dalam. Ia ambil lembaran kertas kusam yang nilai instrinsiknya tidak sesuai dengan
nilai exstrinsik. Dengan lembaran itulah ia membeli dua sachet shampo anti ketombe. Taryan
masuk ke dalam stasiun. Menunggu antrian kamar mandi yang dindingnya ditulisankan, gent.
Di dalam kamar yang keramiknya berair itu, ia membuka pakaian yang lengket. Ia siram air
di kepala. Air berjalan di dada, paha dan kelingking kakinya. Dirobeknya shampo. Disisik
rambutnya. Di bersihkan leher, muka, ketiak, hingga telapak kakinya yang kapalan. Segar
menjalar. Baru kali ini ia rasakan mandi menjadi salah satu anugerah terbesar. Perasaan
nikmat membuat matanya berkaca-kaca. Mandi menyegarkan kesadaran, mengembalikan
ingatan Taryan pada keluarga, pada Chaidir, pada saat ia mendekap Radia di malam-malam
yang sesak. Ia terkenang akan panas tubuh Radia. Taryan teramat sangat rindu. Di
kepengapan kamar mandi yang airnya kuning berbau besi, ia ambil busa-busa Tatkala satu
gelembungn terbang dan pecah di lantai, Taryan terisak. Ia merintih. Ia menangis
122
Tangisan adalah ledakan.
Beban yang menghimpit kehidupannya hancur berkeping, keping.
Tangisan
memusnahkan kekalutan.
Tangisan
mensucikan amarahnya pada Tuhan.
Hajatnya tuntas. Tubuh Taryan melandai di bak kamar mandi.
Keluar dari sana, Ia melangkah, bersiul-siul. Kali ini ia harus meredakan debaran
jantungnya sembari mencari jalur kereta ekonomi. Gerbong ditemukan. Tak begitu lama
menunggu, gerbongnya datang. Taryan masuk, dan menemukan satu-satunya tempat yang
difikirnya aman bersembunyi hanyalah di kamar mandi. Di antara sambungan gerbong ia
menikmati aroma kemenangan yang keluar dari kelamin jutaan penumpang kereta. Taryan
tak peduli jenis kelaminnya apa. Gerbong kereta pun bergerak. Suaranya derak-menderak.
MENGGELANDANG
Waktu seperti trenggiling, berguling-guling di tanah menindas semut yang menjadi
sisa makanannya. Demikian pula dengan Riang. Ia digulung waktu. Rencananya semula
memburam tidak seenak mie ayam.
Selepas berangkat dari Thekelan menuju Yogya, Taryan tak menemukan lelaki yang
dicari meski seluruh terminal Yogyakarta sudah ia hampiri. Ia semakin yakin Simbok Marmi
atau Marmut, menipu dirinya. Seburuk-buruknya anak, --meski mengetahui anaknya
melakukan kesalahan besar-- orang tua tetap akan bepikir berpuluh kali untuk memberikan
informasi yang akan membahayakan anaknya. Peribahasa itu khusus untuk orang tua yang
akal dan perilakunya pertengahan antara waras dan tidak. Peribahasa itu, tentunya tak berlaku
untuk Mbok Marmi, duga Riang.
Riang tak putus asa. Ia terus menekuni apa yang dicarinya. Dan sebuah pribahasa lain
dari negeri kita mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai buang gas akhirnya terendus
123
juga, terbukti dalam kehidupan Riang. Informasi mengenai keberadaan Kardi, ia dengar
melalui perbincangan di warung kopi.
”Nyeberang ke Kalimantan!” seorang tukang becak menerka.
” Genduruwo itu kabur ke Bandung!” yang lainnya menyanggah.
”Biar hidup wong gendheng itu tidak tenang! Biar modiar sekalian!” timpal penjual
soto Lamongan
Informasi itu simpang siur di jalanan. Di bicarakan diam-diam namun dipenuhi
dendam. Kebencian Riang adalah kebencian orang-orang itu juga dan informasi yang tak
memiliki akurasi tersebut memancingnya untuk terus mengejar Kardi.
“Lain waktu bukan aku yang ke Thekelan. Lain waktu Riang yang akan ke
tempatku.”
Keyakinan Fidel akan ucapan yang di sampaikannya di Kopeng, membuat Riang tak
ragu pergi menuju kota pelarian itu. Sesampainya di Bandung kenyataan segera
menghampiri. Ia menemukan kontrakan yang kosong.
”Fidel mangkat ka nu tebih,” jawab induk semangnya.
Mojang Priangan yang orisinil cantik itu menterjemahkan perkataan indungna,
ibunya. ”Fidel pergi ke tempat yang jauh Kang.”
Mengenai jauhnya berapa kilometer, letaknya di mana, induk semang dan anaknya
tak dapat menunjukkan. Mereka hanya menjawab, ”Fahan, fahan ... naon nya, apa ya, di
tempat Sadam Husein sigana mah, sepertinya.”
”Irak?” Jawab Riang.
”Sigana! Mungkin!”
”Sugan We, bisa saja di Iran, nggak tahu lah, Kang.” Anaknya yang cantik
memungkas.
Kedua orang itu tak dapat meyakinkan Riang. Harapan bertemu Fidel menjadi ampas.
Tak ada tempat berteduh bagi Riang tetapi ia tak peduli jika harus menggelandang. Ia tak
peduli meski harus menjalani hidup di jalan.
PAGI BUTA. Dingin akhir musim kemarau menjeruji kaki. Cahaya lampu hotel dan
rumah mewah Dipati-Ukur memantul dari steinles stell pagar yang cerlang. Bintang pagi
meremang. Subuh datang membuka hari. Bergulirlah kembali. Malam digilir pagi dan pagi
digilir malam. Terus seperti itu hingga seisi semesta gulung tikar.
Berada ruang besar yang disanggah hukum alam, Riang meringkuk, berselimut kertas
koran alas shalat jumat kemarin siang. Ia diami ghetto di bawah semesta nan rindang. Tempat
124
kediaman itu ia dibuatnya menggunakan peti buah, spanduk curian dan terpal sobek yang ia
jahit. Terpal dan spanduk ia jadikan sebagai atap sementara kayu peti buah yang di ikat tali
rapia ia jadikan rangka. Tempat kediaman itu tak pantas disebut kediaman, sedikit lebih
pantas jika disejajarkan dengan kandang.
Jam delapan. Toet-toet knalpot, ketepok ladam kuda dan tapak kaki sepasang manula
memopor kesadarannya. Riang membuka mata. Lendir yang halangi pandangan,
membuatnya berpikir tentang lendir yang bisa dijadikan lem perangko atau pengganti garam
perangsang nafsu makan. Riang melihat ke kanan dan ke kirinya. Ia tak menemukan orang
yang selama ini menemaninya di jalanan. Riang hany melihat seorang perempuan berambut
kusut tengah jongkok tak jauh dari tempatnya, tertawa di dalam bak sampah.. Rambut kusut
perempuan itu mengingatkan dia akan keadaan dirinya.
Baju Riang lusuh. Mulutnya bau septictank. Di kupingnya dedak kuning menumpuk.
Di rongga hidungnya lendir hijau mulai mengerak. Rasa jijik pada diri sendiri membuatnya
merasa bersalah.
Riang berniat mandi. Ia bangun dari conblock dan baru menyadari jika perempuan itu
memperhatikannya. Perutnya perempuan itu bengkak. Riang tiba-tiba teringat kisah yang
beberapa waktu lalu dianggapnya dongeng belaka.
”Ada seorang betina gila. Betina gila yang dicokok dari jalanan,” demikianlah
Aplatun mengawali ceritanya. ”Betina gila itu di ambil sekelompok preman menggunakan
mobil bak!” Pemilik warung indomie itu mulai mendesis. Ia mulai mendramatisir. ”Lalu, lalu
perempuan gila itu dibawa ke sebuah tempat, sebuah tempat yang jumlah manusianya dalam
satu kilometer hanya sejumlah rokok di dalam satu bos! Di tempat sepi itu, si perempuan
gila di masukan ke dalam kali. Perempuan gila yang kulitnya bau kesemek busuk itu diberi
sabun!” Aplatun mencermati benar wajah Riang dan Taryan. ”Orang gila mana ngerti yang
namanya kebersihan.” Aplatun meringkik senyaring ringkikan kuda. ”Bukannya bersihin
badan, eh ... eh dia malah nyipratin air orang-orang yang nunggu tontonan streaptease gratis
di pinggir kali!”
”Streaptease apa Ton?” tanya Taryan antusias.
”Nari bugil, gaya ular kobra,” Aplatun mendongak, tertawa.
”Terus, terus?”
”Preman-preman itu gak sabar.”
”Sebabnya?”
”Perempuan gila itu ngulangin kegiatannya.”
”Ngulangin apa?”
125
”Nyiprat air!” Riang mencemooh kesal. ”Lanjut Ton!” ia tak sabar.
”Waktu si perempuan gila itu ’ngulang-ngulang kegiatannya’ preman-preman pada
buat undian. Yang kalah harus mandiin, harus nyampoin perempuan gila itu di kali!”
”Yang undian siapa?”
”PREMAN!!” Riang membentak Taryan sebelum Aplatun menjawabnya.
Ada kemenangan yang muncul diketiak saat Taryan berhasil menjahili Riang. Ia
tertawa.
”Setelah di mandiin gimana Ton?”
”Ya tentulah!”
”Tentulah apa?” Tanya Riang penasaran.
”Lelaki yang sudah mimpi basah harusnya bisa nebak!” Taryan balas berteriak
membuat pekak. ”Disetrum Yang ... Disetrum!”
”Dan setelah disetrum, perempuan gila itu menjadi-jadi!” Aplatun menggambarkan
seolah ia menggambarkan kebahagiaan Socrates dalam Phaedo sebelum filsuf Athena itu
menenggak hemlok, racun.
”Menjadi apa?” Riang keracunan.
”Haus seks!” Aplatun tertawa penuh kebahagiaan.
Di sanalah cerita berakhir. Di sana pulalah Riang menganggap cerita Aplatun
berlebihan. Terlalu banyak dramatisasi. Tetapi, lain soal ketika Riang perut perempuan gila
di hadapannya melendung. Perempuan gila itu pertanda. Ia mulai memperhatikan perempuan
gila yang tengah jongkok dan makan sepuasnya di dalam bak sampah. Dilihatnya mata
perempuan itu berkeliling seperti komedi putar. Perempuan gila itu melihat makanan.
Berkeliling melihat segala macam lalu melihat makanan. Lalu melihat Riang. Melihat
makanan. Melihat Riang. Melihat makanan. Melihat Riang.
Perempuan gila cengar-cengir. Ia lempar makanan basi yang ada ditangannya.
Badannya ngesot dan... horas bah! ... dimasukannya jari yang masih ditempeli nasi ke dalam
kemaluan. Astaganaga bung Rhoma! Dia masturbasi! Hawa tubuh Riang mencapai titik
panasnya! Riang gemetar! Baru sekali ia melihat kejadian live macam gini.
Riang palingkan pandangan. Di balik kaca belakang angkutan kota, anak-anak SMA
tertawa. Orang-orang melihat ke arah Riang, lalu melihat si perempuan gila. Riang dan dia.
Dia dan Riang. Uh malu! Riang lekas menjauh. Ia benar-benar insyap.
Semua rencana yang dipikirkannya pagi itu buyar. Ia bergegas menjumpai Taryan.
”Cerita Aplatun benar!”
126
Lalu peristiwa penting melebihi perang Paregreg bahkan perang tiga tahun di
Stalingard itu membuat kedua lelaki aneh itu rela berjalan selama seperempat jam, tergopoh-
gopoh menuju warung sekaligus pemilik radio penyebar informasi amatir.
Aplatun yang tengah menabur merica di atas telur setengah matang melihat ke dua
orang ini berjalan ke arahnya, masuk ke dalam warungnya, terengah-engah menceritakan apa
yang dialami Riang pagi itu.
”Orang gila yang Kamu lihat itu korban kejadian sebelumnya.” Komentar Aplatun
santai. Ia malah menjerumuskan ke dua orang aneh di hadapannya pada cerita lain yang tak
kalah menjijikan.
Riang dan Taryan menukar pandangan. ”Sebelumnya berarti ada yang ...”
”Tidak, tidak!” Aplatun memang jago menimbulkan pertanyaan dan angan-angan
yang kebablasan. ”Tidak ada perempuan gila lagi dalam ceritaku! Cerita ini lebih keren lagi.”
Katanya.
”Ayo Ton... Ayo Ton!” Riang dan Taryan menyemangati.
Lantas diceritakannyalah, ditanamnya belati di dalam dubur aki-aki, kakek-kakek.
”Dan tahukah kalian?”
”Apa wahai begawan?” Riang tertawa.
”Belati yang ditanam di dubur adalah hasil cocok tanam ’belati tumpul’ si aki waktu
muda!”
Di neraka dunia tempat Riang menjebloskan diri, sudah tak terhitung preman
menanam belati tumpul di dubur anak jalanan. Kalau anak-anak malang berteriak kesakitan
”Wuah! Akh! Ampun!” si preman malah teriak. ”O Yeah! Yeah,” kerasukan setan
kenikmatan. Kebiasaan umat nabi Luth itu dilakukan hingga si anak jadi terbiasa dan karna
terbiasa, kejadian ini menjadi siklus. Anak-anak kecil yang dulu di tanam balik balas
menanam di dubur anak kecil yang tak berani melawan. Tapi tidak semuanya begitu.
Ada seorang anak yang tidak malang melintang di dunia sodom dan gomoroh. Setelah
disodom, ia menunggu kesempatan. Ia memendam amarahnya. Ia tunggu perhitungan dengan
orang yang pernah menyodomnya. Setelah dewasa. Setelah menjadi penguasa lahan parkir di
Cileunyi dubur aki-aki yang di masa lalu pernah mempraktikan kesesatan itu ditikamnya.
Lalu, munculah pertaubatan besar akhir zaman. Jalanan sepi kasus penyodoman. Preman-
preman dewasa mulai mencari jalan aman penyalur kebutuhan biologisnya. WTS dan orang
gilalah yang terkena getahnya. Perempuan gila yang Riang temui, salah satunya.
127
Taryan gelengkan kepala. Riang tidak. Ia hanya menggeleng setengah. Riang teringat
danau Merbabu. Ia teringat bagaimana cara Pepei dan Fidel membangun sebuah kepercayaan
dalam dirinya. Ia ragu lagi pada Aplatun. Cerita dia tidak pernah Riang lihat dengan matanya
sendiri. Keberadaan perempuan gila memang bisa menjadi bukti, tetapi bisa jadi bukan.
Cerita penanaman belati yang terrlalu ekstrim itu membuat Riang merasa perlu
menambahkan melihat perempuan gila disetubuhi. Dipikirnya lagi Aplatun bisa saja
mengarang bebas.
”Cerita itu berasal dari mana? Dari siapa?”
Mata Aplatun yang sipit makin menyipit. Senyumnya yang melar membuatnya
nampak misterius. Senyum Aplatun msenimbulkan spekulasi. Bisa jadi anaknya! Yang ada di
dalam perut perempuan gila itu anaknya! Aplatun tega khianati keluarganya! Tapi masa?
Riang yang bertanya, dan Riang pun yang membantah, Lha berkeluarga itu bisa saja
karangan dia. Aslinya Aplatun jangan-jangan! Jangan-jangan?
Riang meragukan Aplatun. Ia mulai mengingat, mengkaitkan segala sesuatunya,
termasuk tawaran bertubi agar ia dan temannya tidur di warung Indomie milik Aplatun.
Riang mulai terjangkiti. Ia mulai khawatir jika sebilah belati tumpul ditanam di lubang
belakangnya.
Untuk sementara kekhawatiran mengidap di dalam diri Riang. Tak lama keraguan itu
hilang sebab niatan Aplatun memang tulus. Di luar apa yang dikhawatirkan Riang,
sesungguhnya rasa curiga yang dimiliki Riang tatkala hidup dijalan sudahlah benar. Jalanan
itu keras seperti kehidupan zaman purba saat tyranosaurus jadi raja. Asal punya power,
punya kekuatan, semua seakan sah jadi kanibal. Sah --diangkat tanpa surat pengangkatan--
jadi tukang kadal, tukang bunuh, tukang sodom. Di jalananlah awal mula seleksi alam
manusia terjadi. Karenanya jika mau survive seseorang harus benar-benar mempercayai
setelah melewati proses mencurigai.
MENCURIGAI adalah sesuatu yang tidak dijadikan bekal oleh teman Riang.
Beberapa bulan lalu, teman yang sudah pernah ’mimpi basah dan disetrum juga menyetrum’
itu menderita di Jakarta. Penderitaan tak tertanggunglah yang membuatnya memutuskan
pulang ke desa.Ia berharap permasalahannya di desa sudah diselesaikan keluarganya melalui
pihak yang berwajib.
Duduk di depan ruangan, di mana jutaan penumpang mengeluarkan air seni. Manusia
perlu udara bersih. Lelaki itu pun demikian. Sialnya keinginan yang wajar namun tak tepat
128
waktu, menghentikan perjalanannya. Petugas memergoki lelaki itu tengah berjalan di
gerbong kereta. Karena tak punya karcis dan yang paling fatal tidak memiliki uang untuk
ditempel lalu disalam-salam, lelaki itu dimaki dan diturunkan secara paksa, diusir. Ia berjalan
sambil berpikir apa salah emak mengandungnya? Tentu emaknya tidak salah karena yang
salah adalah orang yang menyalahkan emaknya. Lelaki itu berjalan tak tentu arah.
Kecapaian. Ia lelap di dekat bengkel sepeda. Bangunnya ia masuk angin.
Riang tengah menyeduh genangan terakhir bubur kacang hijau, saat lelaki itu bersin.
Dilihatnya lelaki itu tengah menyeka mulut menggunakan kerah baju. Lelaki itu merasa
diperhatikan. Tidak seperti perempuan gila, lelaki itu menundukkan pandangan lalu berdiri.
Jalannya menyorong-nyorong. Ia pegang bak sampah lantas jatuh. Orang-orang di trotoar
mengambil jalan memutar, menghindar. Yang kepalang lewat menyalip dengan cepat. Kalau
diibaratkan tekanan gas kendaraan bermotor, mungkin kecepatan salipnya mencapai 20
km/jam.
Riang kasihan melihatnya tengkurap di jalan. Ia hampiri, ia bangunkan, ia silangkan
lengan lelaki itu di bahunya. Riang bawa lelaki itu menuju warung tempatnya makan. Lelaki
itu diberi pemilik warung Indomie segelas teh panas. Lelaki itu terharu. Ia meminta maaf
sekonteiner banyaknya.
Saat teguk teh terakhir melorot di kerongkongan, sejak saat itu pula, Riang mendapat
dua kebahagiaan. Ia mendapat dua orang teman: Aplatun, si pemilik warung indomie dan
seorang lelaki asal Magelang. Namanya tentu saja Taryan!
Sebagai teman, Aplatun memiliki perbedaan dengan teman Riang yang lamanya dia
di tempat orang buang air seni itu ternyata tidak membuat apresiasi seninya semakin tinggi.
Jika Aplatun selalu memberi mereka makan, Taryan sebaliknya. Ia menyusahkan. Ini beban
untuk Riang. Buruk-buruknya ia pernah menganggap pertolongannya akan menjadi
’asuransi’ apabila ia ditimpa kecelakaan di masa mendatang dan tentu, apa yang
dilakukannya ia anggap sebagai konsekuensi hubungan pertemanan.
Waktulah yang menguji hubungan mereka. Di saat Riang sudah lama menghapus
asuransi yang di tanamnya sejak lama, hal yang tak di duga-duga datang ketika Taryan yang
di pagi harinya ia tahu tidak memiliki uang sepeser pun tiba-tiba datang membawa dua bos
rokok, dua bungkus pecel lele. Jangankan Riang, Taryan sendiri tidak menduga karena
setelah mengemis dari ujung jalan ke ujung jalan lainnya, di wilayah institut ternama, ia
terjongkang di bawah pohon besar yang berjajar. Ia tak dapat uang. Di bawah pohon Taryan
memohon pada Tuhan dikasih nasi bungkus untuk dimakan. Permohonan itu di rendahkan
tingkatannya. Ia mohon untuk tega matikan kucing. Untuk tega makan cecurut bakar.
129
Permohonan itu tak pernah terkabul, namun apakah perbuatan Tuhan waktu Taryan
menemukan dompet abu di genangan air, di samping pohon tempatnya bersandar? Taryan
menganggapnya ya. Ia menahan senyum melihat banyaknya uang di dalam dompet.
Tak seperti pertama kali kala ia merasa dosa mengambil uang keropak kemudian
berniat mengembalikannya, kali ini Taryan membuang hatinya. Alasan kepepet memuaskan
isi kepalanya. Dompet berikut kartu pengenal yang ada di dalam dompet ia buang. Taryan
menggulung uang yang ada di dalam dompet menggunakan karet gelang. Di belinya nasi
bungkus dan bahan untuk ngelepus
Riang curiga karena Taryan lain dari biasanya.
”Dapat uang dari mana?” Riang menginterogasi.
Taryan tidak ubris pertanyaan Riang. Ia malah menyuruh Riang kembali makan.
”Laper kan?” katanya.
Ya jelas Riang lapar, tapi kadang orang lapar pun butuh kejelasan terlebih jika si
pemberi adalah orang yang selama ini hidupnya di bawah pas-pasan.
”Situ nyuri ya?!”
Taryan tidak tersinggung. Ia angkat kakinya yang mirip pipa.
”Tanya- tanya segala! Makan saja nanti mengik!”
Riang mengumpat, namun ia sadari, bagi gelandangan, makan tentu lebih utama dari
rasa penasaran, maka secepat burung kasuari mematuk sagu yang menempel di rambut bocah
Irian, secepat itu pula Riang makan. Perutnya kembung.
”Enak?” Taryan mengelus perut Riang.
”Enak tapi Kurang!” Riang tertawa.
Dan diberinya Riang uang limaribuan.
Itu cuma permulaan. Esok harinya, Taryan bawakan makanan yang enak-enak. Ia
belikan temannya karedok, masakan padang, tahu gejrot, pempek palembang, dan yang luar
biasanya ia ngomong begini: ”Mau disetrum atau nyetrum Yang?” Taryan memasang
tampang serius.
Taryan lagak. Riang tahu, temannya itu tidak punya keberanian. Sepengetahuannya
shalat pun masih jalan. Malahan kalau tidak tahu besoknya makan apa, Taryan mengemis
sambil puasa. Keganjilan itu membuat pikiran Riang habis.
Seperti yang sudah pernah di singgung --beberapa waktu lalu-- oleh sebuah
peribahasa (namun kali ini lebih mahsyur) bahwa: selama-lamanya kentut dipendam akhirnya
perepet juga maka rahasia uang yang dimiliki Taryan pun terkuak. Bengep-bengep di wajah
dan noda darah di kepala Taryan mengawali terbongkarnya rahasia kekayaan dia. Uang
130
Taryan beralih ke tangan preman. Cerita selanjutnya tidak perlu dikisahkan. Apapun yang
terjadi, bagi Riang, Taryan telah menunjukkan bagaimana hubungan pertemanan mereka
berjalan Sejak itu hitung-hitungan asuransi di kepala Riang benar benar hilang. Teman
adalah teman.
HARI ITU, ketika Riang bertemu perempuan gila, semua jerih payah dan pemberian
Bapaknya habis. Taryan pun tak bisa mengharap uang bercucuran dari upaya dia mengemis,
pasalnya kemudaan diri dia membuat orang sudi najis memberi uang padanya. Kalau pun ada
yang memberi, itu lebih dikarenakan mencari aman.. Satu-satunya yang bisa diharapkan
hanyalah Aplatun.
Mereka tidak bertepuk sebelah tangan dengan tangan monyet. Aplatun adalah
manusia yang menghargai hubungan pertemanan. Dia bukan binatang. Selamatlah mereka.
Makanan yang diberi Aplatun di hari ini membuat Riang dan Taryan semangat mencari uang.
Mereka berpencar. Di sebuah lokasi pembangunan Riang menemukan kerumunan. Kasak-
kusuk terdengar: dua orang pekerja ketiban batu yang jatuh dari ketinggian. Tiga kepal batu
jatuh disenggol buruh yang tengah memperbaiki tiang penyangga. Batu pertama jatuh
merobek spanduk asuransi kerja, dua batu lainnya membentur helm dua orang pekerja
pemanggul pipa. Karena jatuhnya dari tempat tinggi, helm yang mereka kenakan tidak begitu
berfungsi. Dua buruh bangunan pingsan. Bukan sulap bukan sihir, celah sempit yang
melebihi sempitnya titian rambut dibagi tujuh itu dimasuki Riang. Ia meliuk di antara
kerumunan. Ia bertanya untuk mengetahui siapa mandor bangunan. Satu jam kemudian,
mandor tidak saja ditemui olehnya. Dengan sedikit kemampuan bicara yang lebih tinggi dari
kemampuan kaum buruh dan tani, Riang meyakinkan mandor untuk memperkerjakan dia.
Mandor memutuskan. Riang dipekerjakan lataran sang mandor diburu atasan, dan atasan
mandor diburu atasan lainnya untuk tuntaskan kerjaan.
Riang pun semangat berlari, usai menyelesaikan draft kontrak kerja, demi
memberitahu kebahagiaan itu pada Taryan. Ada informasi perkerjaan yang juga bisa Taryan
dapatkan namun pada akhirnya keinginan Riang tak kesampaian. Mandor memang butuh
pekerja, akan tetapi akal sehat menuntut dia untuk mempekerjakan orang yang memiliki
selembar kartu sebagai jaminan. Dalam pekerjaan sekecil apa pun, identitas diri menjadi
sangat diperlukan. Mandor tidak mungkin meluluskan keinginan setiap orang.
Taryan kecewa. Riang mengerti. Ia tak mau membahas segala hal menyangkut
pekerjaan barunya, termasuk ketika mandor mengharuskan Riang tidur di bedeng. Ia bingung
siapa yang nanti temani Taryan.
131
“Kenapa nggak di ajak kerja? Kan bisa sama-sama tidur di bedeng.”
”Sudah ku ajak Ton.” jawab Riang pada Aplatun yang panggilan kecilnya Ton.
”Kalau mandor percaya padamu, kan lain soal?”
”Percaya sama orang baru? Sudah dijelaskan, tetap tak percaya.”
“Jadi hanya karna KTP?”
”Pasti karena itu!”
“Kalau tidak pernah mencoba, Kau tidak akan pernah tahu.”
“Ampun Ton! Aku sudah bawa Taryan tapi mandor menolak!”
“Sekarang apa yang dia perbuat?”
”Taryan?”
”Ya.”
“Dia tidak bilang waktu tadi pergi.” Riang mengembungkan paru-parunya. Ia
mengela nafas. ”Aku kasihan padanya....”
Aplatun merasakan kesedihan itu.
”Karena pekerjaan ini, aku terpaksa tidur di bedeng Ton!”
Aplatun menerka macam kesulitan yang ada dalam pernyataan Riang.
”Yang, Yang! Kau ini! Dari dulu sudah ku bilang, kalau mau tidur itu sepele! Tidur di
sini saja! Nggak usah di jalan! Kau pikir tawaran itu untuk mu saja? Untuk Taryan juga!
Demi solidaritas antar teman yang kukatakan pasti benar!”
Lepaslah satu beban. Riang merasa ringan saat melihat Taryan mendatanginya sambil
menjinjing kantung kresek yang dipenuhi segepok gajih kambing.
”Menjijikan yang Kau bawa!”
”Pinjami aku uang, Ton.” Taryan cengegesan.
“Untuk apa?” Aplatun memencet hidungnya.
“Beli obat merah.”
Aplatun membuka laci harta karunn. Ia memberikan beberapa lembar uang berwarna
merah.
”Besok ku ganti Ton.”
”Tak usah! Amal!”
Aplatun tahu apa yang akan dilakukan Taryan. Gaji kambing itu akan membantunya
mengemis. Sejak saat itu Taryan menjadikan ngemis sebagai profesi. Setiap hari, puluhan
uang receh masuk berdenting-denting ke dalam plastik biru deterjen miliknya. Selang dua
hari kemudian, profesi inilah yang akan menyelamatkan Riang dari kelaparan. Selang dua
132
hari ke depan, Taryan kembali membuktikan eratnya siklus simbiosis parasitisme dan
mutualisme antara dirinya dengan mahluk biologis yang satunya, kawannya yang tak ada
dua: Riang.
TAKDIR MEMPERTEMUKAN
Mencurigai adalah sesuatu yang tidak dijadikan bekal oleh teman Riang. Beberapa
bulan lalu, teman yang sudah pernah ’mimpi basah dan disetrum juga menyetrum’ itu
menderita di Jakarta. Penderitaan tak tertanggunglah yang membuatnya memutuskan pulang
ke desa. Lelaki itu tahu bahwa permasalahan yang tidak dapat dipastikan kesudahannya, bisa
membuat dia masuk ke lubang yang sama berbahaya dengan kehidupan di Jakarta.
Ia berharap permasalahannya di desa sudah diselesaikan keluarganya melalui pihak
yang berwajib. Naiklah ia di kereta kelas kambing. Ia duduk di depan ruangan, di mana
jutaan penumpang mengeluarkan seni. Belama-lama di dekat tempat sebau itu, tentu tidak
membuat apresiasi seni si lelaki makin tinggi. Manusia perlu udara bersih. Lelaki itu pun
demikian. Sialnya keinginan yang wajar namun tak tepat waktu itu menghentikan
perjalanannya.
Petugas memergoki lelaki itu tengah berjalan di gerbong kereta. Karena tak punya
karcis dan yang paling fatal tidak memiliki uang untuk ditempel, lalu disalam-salam, lelaki
itu dimaki dan diturunkan secara paksa, diusir.
Ia berjalan sambil berpikir apa salah emak mengandungnya? Tentu emaknya tidak
salah, karena yang salah adalah orang yang menyalahkan emaknya. Lelaki itu berjalan tak
tentu arah. Kecapaian. Ia lelap di dekat bengkel sepeda. Bangunnya ia masuk angin.
Riang tengah menyeduh genangan terakhir bubur kacang hijau, saat lelaki itu bersin.
Dilihatnya lelaki itu tengah menyeka mulut menggunakan kerah baju. Lelaki itu merasa
diperhatikan. Tidak seperti perempuan gila, lelaki itu menundukkan pandangan lalu berdiri.
Jalannya menyorong-nyorong. Ia pegang bak sampah lantas jatuh.
133
Orang-orang di trotoar mengambil jalan memutar, menghindar. Yang kepalang lewat
menyalip dengan cepat. Kalau diibaratkan tekanan gas kendaraan bermotor, mungkin
kecepatan salipnya mencapai 20 km/jam. Riang kasihan melihatnya tengkurap di jalan. Ia
hampiri, ia bangunkan, ia silangkan lengan lelaki itu di bahunya. Riang bawa lelaki itu
menuju warung tempatnya makan. Lelaki itu diberi pemilik warung indomie segelas teh
panas. Lelaki itu terharu. Ia meminta maaf sekonteiner banyaknya.
Saat teguk teh terakhir melorot di kerongkongan lelaki itu, sejak saat itu pula, Riang
mendapat dua kebahagiaan. Ia mendapat dua orang teman: Antoni, si pemilik warung
indomie dan seorang lelaki asal Magelang. Namanya tentu saja Taryan.
Sebagai teman, Antoni memiliki perbedaan dengan Taryan. Jika Antoni selalu
memberi mereka makan, Taryan sebaliknya. Ia menyusahkan. Ini beban untuk Riang, Buruk-
buruknya ia pernah menganggap pertolongannya akan menjadi ’asuransi’ apabila ia ditimpa
kecelakaan di masa mendatang. Ini tidak berlangsung lama. Apa yang dilakukannya untuk
Taryan dianggapnya sebagai konsekuensi hubungan pertemanan.
Waktulah yang menguji hubungan pertemanan mereka. Di saat Riang benar-benar tak
memiliki uang, ’asurani’ yang sudah dihapus dari pikirannya datang. Hal ini pun tak
disangka sebab ia tahu jika hari yang lalu itu, Taryan tidak dapat uang sepeser setelah
mengemis. Yang ia tahu tiba-tiba Taryan datang membawa dua bos rokok, dua bungkus
pecel lele.
Kejadian macam begini pun jauh dari dugaan Taryan, karena lapar setelah mengemis
dari ujung jalan ke ujung jalan lainnya, di wilayah institut ternama, Taryan terjongkang di
bawah pohon besar yang berjajar. Ia tak dapat uang. Di bawah pohon, Taryan mohon pada
Tuhan dikasih makan. Ia mohon untuk tega matikan kucing. Untuk tega makan curut bakar.
Permohonan itu tak pernah terkabul. Tuhan tak pernah menawar –sekedar—nasi bungkus
untuk dimakan. Namun, apakah perbuatan Tuhan waktu Taryan menemukan dompet abu, di
genangan air, di samping pohon tempatnya bersandar? Taryan menganggapnya ya.
Taryan bersorak, berhuray ada uang banyak di dalamnya. Tak seperti kali pertama
kala ia merasa dosa mengambil uang keropak, dan berniat mengembalikannya. Kali ini
Taryan membuang hatinya. Alasan kepepet ia punya di kepalanya. Dompet berikut kartu
pengenal yang ada di dalam dompet Taryan buang. Uangnya ia masukan ke dalam celana
setelah di gulung menggunakan karet gelang.
Riang curiga karena Taryan lain dari biasanya.
”Dapat uang dari mana?” tanyanya.
134
Taryan tidak ubris pertanyaan Riang. Ia malah menyuruh Riang kembali makan.
”Laper kan?” katanya.
Ya jelas, Riang lapar, tapi kadang orang lapar pun butuh kejelasan terlebih jika si
pemberi adalah orang yang selama ini hidupnya di bawah standar pas-pasan.
”Situ nyuri ya?!”
Taryan tidak tersinggung. Ia angkat kakinya yang mirip pipa.
”Tanya- tanya segala! Mending makan aja. Nanti mengik!”
Riang mengumpat, namun segera ia insyapi. Sebab, bagi gelandangan, makan tentu
lebih utama dari penasaran.
Secepat burung kasuari mematuk sagu yang menempel di rambut bocah Irian, secepat
itu pula Riang makan. Perutnya kembung.
Taryan menepuk perut Riang.
”Enak?”
”Enak tapi Kurang!” Riang tertawa.
Dan diberinya Riang uang limaribuan.
Itu cuma permulaan. Esok harinya, Taryan bawakan makanan yang enak-enak. Ia
belikan temannya karedok, masakan padang, tahu gejrot, pempek palembang, dan yang luar
biasanya ia tawarkan cewek.
”Mau disetrum atau nyetrum Yang?”
Taryan llagak. Riang tahu, Taryan tidak punya keberanian untuk itu.
Sepengetahuannya shalat pun masih jalan. Malahan kalau tidak tahu makan apa, besoknya
Taryan mengemis sambil puasa. Keganjilan itu membuat Riang kehabisan pikir.
Seperti yang sudah pernah di singgung --beberapa waktu lalu-- oleh sebuah
peribahasa (namun kali ini lebih mahsyur) bahwa: selama-lamanya kentut dipendam akhirnya
perepet juga, maka rahasia uang yang dimiliki Taryan terkuak. Bengep-bengep di wajah dan
noda darah di kepala Taryan mengawali terbongkarnya rahasia kekayaan dia.
Riang mengetahui asal muasal uang temannya dan mengetahui pula kemana uang itu
amblas. Uang Taryan beralih ke tangan preman. Apapun yang terjadi, bagi Riang, Taryan
telah menunjukkan bagaimana hubungan pertemanan mereka berjalan Sejak itu tak ada lagi
hitung-hitungan asuransi di kepalanya. Teman adalah teman.
Setelah dua orang itu kehabisan uang, lantas apa yang terjadi?
Taryan tak bisa mengharapkan dari hasil mengemis, pasalnya kemudaan diri dia
membuat orang, sudi najis memberi uang padanya. Kalau pun ada yang memberi, itu lebih
dikarenakan mencari aman. Uang simpanan Riang pun ludes. Semua jerih payah dan
135
pemberian Bapaknya habis. Satu-satunya yang bisa diharapkan hanyalah Antoni. Tangan
mereka tak bertepuk sebelah tangan dengan tangan monyet. Antoni adalah manusia yang
menghargai hubungan pertemanan. Dia bukan binatang. Selamatlah mereka.
Diberi makan, Riang dan Taryan semangat mencari uang. Mereka berpencar mencari
peluang. Peluang pertama menjumpai Riang saat sebuah kecelakaan terjadi. Riang melihat
kerumunan. Kasak-kusuk terdengar: dua orang pekerja ketiban batu yang jatuh dari
ketinggian. Katanya tiga kepal batu jatuh disenggol buruh yang tengah memperbaiki tiang
penyangga.
Batu pertama jatuh merobek spanduk asuransi kerja, dua batu lainnya membentur
helm dua orang pekerja pememanggul pipa Karena jatuhnya dari tempat tinggi, helm yang
mereka kenakan jadi tidak begitu berfungsi apalagi fungsi menyelamatkan kerja mereka.
Dua buruh bangunan pingsan. Segera celah sempit yang melebihi sempitnya celah
Keiber itu dimasuki sang pencari peluang. Riang meliuk-liuk di antara kerumunan. Ia
bertanya untuk mengetahui siapa mandor bangunan.
Satu jam kemudian, dengan sedikit kemampuan bicara yang lebih tinggi dari
kemampuan buruh bangunan, Riang meyakinkan mandor untuk memperkerjakannya. Dalam
keadaan biasa, siapa yang bakal percaya, dan mau memperkerjakan orang yang datang tiba-
tiba? Tapi bukankan keadaan di dunia, tidak selamanya merupakan keadaan biasa? Mandor
memutuskan. Riang dipekerjakan.
Takar-menakar di kepala mandor yang akhirnya menghasilkan keputusan itu lataran
ia diburu atasan, dan atasan mandor diburu atasan lainnya untuk tuntaskan kerjaan.
Selesai menyepakati draft kontrak, Riang semangat lari demi memberitahu Taryan.
Pikirnya ada pekerjaan kasar yang bisa Taryan lakukan. Sayang, keinginan Riang tak
kesampaian.
Dalam pekerjaan sekecil apa pun, identitas diri menjadi sangat diperlukan. Memang,
mandor butuh pekerja, akan tetapi akal sehatnya menuntut dia untuk mempekerjakan orang
yang memiliki selembar kartu sebagai jaminan. Mandor tidak mungkin meluluskan keinginan
Taryan
Taryan kecewa. Riang mengerti. Ia tak mau membahas segala hal menyangkut
pekerjaan barunya, termasuk ketika mandor mengharuskan Riang tidur di bedeng. Siapa
yang nanti temani Taryan?, pikirnya. Riang perlu jalan keluar.
“Kenapa nggak di ajak kerja? Kan bisa sama-sama tidur di bedeng.”
”Sudah ku ajak Ton.”
”Tidak bisa? ”Kalau mandor percaya padamu, kan lain soal?”
136
”Percaya sama orang baru? Sudah dijelaskan, tetap tak percaya.”
“Jadi hanya karna KTP?”
”Pasti karena itu!”
“Kalau tidak pernah mencoba, Kau tidak akan pernah tahu.”
“Ampun Ton! Aku sudah bawa Taryan, tapi mandor nolak!”
“Sekarang apa yang dia perbuat?”
”Taryan?”
”Ya.”
“Tidak tahu! Dia tidak bilang waktu tadi pergi. Aku kasihan padanya....”
Antoni merasakan kesedihan itu.
”Karena pekerjaan ini, aku terpaksa tidur di bedeng Ton!”
Antoni menerka macam kesulitan yang ada dalam pernyataan Riang.
”Yang, Yang! Kau ini! Dari dulu sudah ku bilang, kalau Kau mau tidur, tidur di sini
saja! Nggak usah di jalan! Kau pikir tawaran itu untuk mu saja? Demi solidaritas antar teman
yang kukatakan pasti benar!”
Lepaslah beban Riang. Ia tidak merasa dosa saat Taryan menemuinya di warung
indomie.
Taryan menjinjing kantung kresek. Isinya segepok gajih kambing.
”Apa yang kau bawa?” tanya Antoni.
”Nanti kau tahu. Ton ... sekarang pinjami aku uang.” Taryan cengegesan.
“Untuk apa?”
“Beli obat merah.”
Antoni membuka laci harta karunnya. Diberikannya beberapa lembar uang berwarna
merah.
”Besok ku ganti Ton.”
”Tak usah! Amal!”
Antoni tahu apa yang dilakukannya. Gaji kambing itu digunakan Taryan
membantunya mengemis. Alhasil, setiap hari, puluhan uang receh masuk berdenting-denting
ke dalam plastik biru deterjen milik Taryan..
Sejak saat itu Taryan menjadikan ngemis sebagai profesi. Tak lama lagi, profesi
inilah yang akan menyelamatkan Riang dari kelaparan. Selang dua hari, Taryan kembali
membuktikan eratnya hubungan timbal balik antar mereka.
137
MABUK
Sore hari, usai lempar ratusan batu-bata, bahu dan pergelangan tangan Riang terasa
pegal. Dua kuli bangunan yang sejak awal jadi teman Riang bekerja mengajaknya pulihkan
stamina.
”Kita minum Big Boss Yang.”
”Cape pegel ilang, badan jadi hangat. Ada lagi khasiat yang utama.” teman Riang
sesama buruh bangunan tersenyum genit.
”Minuman apa itu?” tanya Riang, ”bagaimana dengan khasiatnya?”
”Bisa membuat lelaki seperti kita jadi banteng!”
”Ngamuk diranjang!” seru kuli yang satunya.
“Bukan cuma ngamuk, Yang. Nanduk-nanduk!”
“Kelojotan!”
Mereka tertawa dan Riang percaya. Maka setelah dua orang kuli itu shalat Isya,
dibawanyalah Riang menuju penjual jamu. Sampai di sana salah seorang teman kerja Riang
berteriak. “Biasa!” dan tersedialah tiga cangkir minuman bening warna kuning.
Riang membaui Big Boss. Ia curiga. “Akohol!?” tanyanya sambil mendelikan mata.
Dua kuli berpandangan. ”Emang pernah minum AO Yang?!”
“AO?!”
“Anggur Cap Orang Tua! Masak gak tau?”
“Ndak tahu itu!”
“Udah minum Topi Miring?”
Riang mengangkat bahu.
“Minuman beralkohol!” jelas kuli yang satunya, menengak seseloki air jeruk yang
menemani Big Boss.
“Ndak pernah tapi waktu di SMA pernah hampir minum.”
Penjelasan ”hampir” menjadi bahan cemoohan.
“Eu maneh mah. Alah! Kamu itu! Nanya-nanya minuman alkohol, tapi teu nyaho, tapi
nggak tau Topi Miring jeung sama AO!”
138
Ketidaktahuan merupakan kelemahan. Riang pun dibombardir oleh dua orang kuli
mengenai khasiat Big Bos yang menggemparkan dan anak kemarin sore ini, akhirnya tertarik
juga.
”Pahit!” Desis Riang saat mencoba.
”Pan, kan jamu!”
”Jamu kuat Yang!”
Ludeslah Big Boss yang ada tangan Riang. Minuman ditambah. Dua kuli menyoraki.
Memberi semangat supaya Riang minum untuk yang keduakalinya. Satu menit setelah
meletakan gelas ke dua, Riang merasa tubuhnya diayun. Badannya digoyang ke kiri ke
kanan. Ia bakal hilang kesadaran. Ia tak kuat. Dunia yang lambat membuat tubuhnya terasa
dicanteli gandulan besi. Untuk pertama kali dalam seumur hidupnya Riang mabuk berat.
Dua kuli bangunan tak menyangka, jika efek Big Boss sedemikian kuat untuk teman
barunya itu. Usai habiskan minum mereka membawa Riang pulang menuju bedeng. Namun
apa yang bisa diharapkan dari dua orang pemabuk? Keduanya putus asa. Setelah membopong
cukup lama, Riang ditinggalkan di samping monumen Pancasila yang sakti mandraguna.
Pagi hari menjelang kembalinya matahari, Riang bangun. Ia mengingat-ingat apa
yang telah terjadi. Ia menemukan. Riang mengumpat meski diakuinya benar khasiat Big Boss
membuatnya bugar. Riang mulai merasa khawatir. Ia harus memastikan berada pada jam
berapa hari ini, di dunia ini.
Ketegangan menyedot seperempat stamina tubuhnya.
”Sekarang jam berapa Mbak?” Ia bertanya pada seorang wanita.
Simbak yang seharusnya dipanggil teteh tak mendengar. Riang mengulang
”Maaf ... Mbak. Sekarang jam berapa?!”
Muka si Mbak pucat! Bulu -bulu halus di sekitar lehernya berdiri. si Mbak menarik
kemeja birunya cepat-cepat.
”... jam 8.30.”
Jam 8.30 ... jam 8.30!!!
Plak! Riang menghantam jidat. Ia berteriak
”Mati aku!”
Mendengar kata mati, si teteh geulis gumelis terkejut. Ia lari, melolong-lolong.
”Toloooooooooooooooooooooong!” Sebuah angkutan kota yang bunyi knalpotnya
menyerupai kentut berhenti menyelamatkannya.
Seharusnya Riang tertawa menyaksikan akibat yang ia perbuat. Kehawatiran
membuat sense of humornya hilang. Menyadari dirinya terlambat, Riang terpekur. Ia mulai
139
berpikir buruk mengenai nasibnya ke depan. Riang tak mau jadi pengemis seperti Taryan. Ia
tidak mau menadahkan tangan sambil tidur-tiduran seperti binatang dabba, seakan reptil
yang melata! Riang tidak mau. Ia lebih memilih jadi kuli karena tahu, menjadi pengemis itu
susah menahan gengsi.
Tubuh Riang lemas, perutnya sakit! Cahaya matahari tak lagi terasa hangat. Muncul
dingin di perutnya! Pengaruh cairan kekuningan Big Bos mengaduk perutnya. ”Sialan!
Sialan!” Umpat Riang berulang-ulang.
Kata sialan tak pernah bisa merubah keadaan. Riang pun memberanikan diri menemui
mandor di tempat kerjanya. Jujur ia jelaskan semua kejadan bahkan yang seharusnya tak ia
ceritakan.
Mandor tak ambil pusing. Ia tak butuh alasan, terlebih jika alasan itu tak ia sukai.
Bagi mandir mabuk merupakan perkara berat. Riang langsung divonis. Ia tidak bisa
mengajukan banding. Keputusan telah di buat. Ia dipecat!
Dengan wajah yang lesu ia menuju warung Aplatun.
”Taryan kemana Ton?”
Antoni angkat bahu, bibirnya bergelayut. ”Mana kutahu. Malam tadi kusuruh tidur di
sini. Dia tak mau.”
”Kenapa tak kerja?!”
Riang tak menjawab. Big Bos lebih dulu mencuri perhatiannya. Mengaduk-aduk
perutnya. Perut Riang merilit. Ia menuju kamar mandi. ”Ikut buang air Ton!” Riang berlari,
berteriak.
Antoni tidak bilang jika air PAM di warung tak mengalir deras. Riang keluar. Ia lari
terbirit menuju WC perguruan tinggi. Riang mengejan cukup lama di sana. Ia merasa sakit
perutnya merupaka siksaan terberat untuk umat manusia. Ia tak mengetahui bagaimana
sakitnya seorang wanita saat melahirkan, pinggulnya serasa dijebol! Riang tak akan pernah
mengetahui.
Selesai menuntaskan hajat, Riang berjalan menuju kediamannya semulanya yang
berupa tenda darurat beratap terpal itu. Di jalan ia mengantungi kerikil sebagai berhala
penangkal. Ia tak mau kapacirit, buang air di celana, di jalan raya.
140
DR NURLAILA
Taryan tertawa kebablasan. Cerita mengenai bujukan maut dua kuli bangunan dan
Big boss membuatnya jatuh. Hilangnya pekerjaan Riang tak jua menyurutkan tawanya.
Riang kesal. Dari pada berakhir menjadi pertengkaran ia pejamkan mata. Lima menit
kemudian ia tak mengingat apa-apa. Selang dua jam ia mimpi buang air besar. Ia bangun dan
merasa seekor alien ada di dalam perutnya. Riang melesat menuju kamar mandi masjid jami.
Balik dari sana ia lanjutkan tidur. Setengah jam kemudian ia bangun dalam keadaan tegang,
merasa tertekan, mengalami perasaan terancam. Ia lari lagi. Malam itu, bulak baliknya Riang
ke kamar mandi melebihi jumlah bulak-baliknya Adam dan Hawa dari Shafa menuju Marwa.
Ketika tak ada lagi yang bisa dikeluarkan perutnya, Riang tertidur. Bangunnya ia
temukan dua pil pereda sakit perut, juga nasi hangat dan lauk-pauknya. Lebih dari itu, ia
menemukan uang receh di sakunya. Riang bersyukur sebab sisa upahnya kemarin, hanya
cukup untuk sekali makan. Hari ini Riang habiskan waktunya di dalam tenda.
SORE HARI. Taryan datang dari balik tikungan. Ia bawakan Riang satu lembar
celana panjang dan jaket tentara. Acuh-tak acuh ia lempar celana dan jaket berpenutup kepala
itu ke arah sahabatnya.
“Pake!” Taryan melempar. ”Persediaan celanamu habis. Untuk sementara pakai dulu
yang kubeli!”
”Maaf nyusahin situ!” Hati Riang serasa di gosok batu. Ia terharu.
Taryan menghela nafas, “Yang? ... kau ingat waktu pertama kali kita bertemu?”
Riang anggukan kepala.
“Sekarang saatnya aku balas kebaikanmu!”
Mereka diam.
”Yang?”
Riang masih diam.
“Kita akan saling menjaga!”
Mata Riang buram. Ia mengangguk pelan. Ia sandarkan badan dan limpangkan jaket
di dengkulnya. Taryan merasa canggung melihat Riang seperti itu. Menggunakan alasan:
belum shalat ashar, ia pergi, tetapi baru beberapa langkah berjalan Taryan tertawa kemudian
141
berbalik.
“Nih seadanya!” Ia melemparkan sebuah kantung plastik lagi. Taryan melangkah
kembali menuju masjid.
Riang membuka bungkusan yang dilemparkan. Ia menemukan kerupuk lepek dan
sebungkus nasi di dalamnya. Meski tanpa lauk-pauk Riang merasa nikmat. Air yang
memburami matanya merembes, mengalir melewati hidung, menetes dan menjadi kuah yang
menggarami nasi bungkusnya.
Satu jam setelah makan berselang, sakit Riang bertambah parah. Riang berak di
celana. Ia pikir Taryan berniat membunuhnya.
TARYAN YANG DATANG saat udara magrib diisi kesejukan, terkejut saat
menemukan Riang yang tengah kelojotan. Kalau terus menerus begini temannya bisa mati.
Maka di bawanya Riang menuju warung Aplatun.
”Sebaiknya kau bawa Riang ke dokter Nurlaila.” Aplatun memberi saran.
”Tak punya uang Ton!” Mendengar kata dokter Taryan ketakutan.
”Coba kamu ke sana!Dia bukan dokter matre!”
Bukan dokter matre berarti menjadi idola di kalangan tak berpunya. Menjadi idola di
kalangan tak berpunya berarti sang dokter tidak memberi tarif gila, seperti dokter yang
kerasukan mengejar setoran. Menjadi idola di kalangan tak punya adalah jaminan bahwa si
dokter tidak akan mempengaruhi pasiennya untuk membeli obat mahal yang ditawarkan
salesman pabrik farmasi, agar ia bisa pergi dua kali ke luar negeri setahun sekali.
Berbekal alamat dan teh pahit buatan Aplatun, Riang dan Taryan berjalan hingga
terminal Kebun Kelapa. Di sana orang-orang berteriak menjual baju, menjual celana bekas
dan baru. Tukang stiker menyingkir, menutup barang dagangannya dengan terpal biru.
Tukang martabak dan gorengan dibanjiri cahaya neon. Suara minyak panci penggorengan
mendesis-desis. Penjual buku memasukan buku pelajaran, tuntunan praktis bercocok tanam,
komik sampai majalah porno ke dalam gerobak.
Dekat penjual kaset yang memakai anting di bibir, Riang dan Taryan masuk ke dalam
angkutan kota yang gelap. Calo meminta jatah. Uang berpindah dan roda berputar beratus
ribu kali hingga mereka sampai di pusat kota: Dago. Di sana orang-orang keluar seperti
gerombolan kelelawar. Anak remaja pria dan wanita bergandengan tangan. Mereka masih
muda. Masih murni, belum bau tanah. Selang-seling manusia berkerumun, masuk ke dalam
pertokoan atau sekedar duduk-duduk di cafe. Cahaya benderang. Mesin mobil-mobil mewah
hampir menempel di tanah. Suara bas menendang-nendang. Lampu merah menyala. Mobil
142
berhenti. Bunga mawar putih yang dilapisi plastik transparan dijajakan Beberapa orang
membeli tanpa meminta kembalian. Lampu hijau menyala, derum memekakan telinga.
Beberapa mobil melesat cepat. Angkutan yang mereka tumpangi berjalan lambat, mengedut-
ngendut.
Lampu merah lagi. Anak kecil memakai topi berwarna hijau dekil, masuk ke dalam.
Tingginya kira-kira sedada Riang. Kakinya kanannya menjejak angkutan kota. Yang kiri,
menjejak aspal. Ia memakai sendal jepit yang mereknya sama dengan yang Riang pakai.
Swallow. Jemarinya kusam. Dari mulutnya yang bau, suara cericit keluar. Ia menyanyi.
Suaranya sumbang.
Azan telah mengumandang (Tangannya berbunyi)
Di puncak menara tinggi.
Memanggil kaum muslimin dan muslimat, bergegas untuk bersembahyang.
Panggilan Tuhan yang Esa,
jangaaaanlah engkau abaikan. Lima kali sehari semalam,
la ... la ... la la ... (Ia lupa).
Anak itu membuka topi. Kepalanya plontos. Dijulurkannya topi itu ke arah Riang dan
Taryan. Mereka memberi senyum pada si anak. Seorang wanita belia memasukan dua ratus
rupiah. Anak kecil berbaju necis memberikan uangnya. Penjual suara bertubuh kecil turun
dari angkutan kota. Dan lampu hijau pun menyala.
”Sampai di Simpang Dago,” Taryan bersuara. “Aku biasa mangkal di sana Yang!” Ia
menunjuk warung buah-buahan yang ramai oleh warna. Ada jeruk --yang warna oranyenya
bikin perut Riang melilit. Ada apel merah. Ada anggur yang membuat liur Taryan terbit dari
kerongkongan.
“Di bawah triplek itu,” Taryan menujuk papan bertuliskan Jus Ngeunah ”aku
meniipu mahasiswa ITB yang katanya pintar-pintar itu.”
“Orang yang pandai berakting, harusnya jadi bintang film.” Riang berkomentar
lemas.
Taryan memukuli dadanya seperti kingkong.
Angkutan kota berhenti di depan sekolah bertingkat dua, saat Taryan berteriak ”Kiri”.
Mereka menatap plang-plang, dan masuk ke dalam gang.
143
Dr. Umum Nurlaila
Praktik Dari Hari Senin – Sabtu
Pukul 17.30-21.00
Pas! Mereka masuk ke dalam ruang praktik. Warna cream dinding membuat mereka
silau. Sebuah buku tulis terbuka di atas meja bertaplak putih. Seorang wanita muda
tersenyum. Lampu membuat rambutnya yang panjang terlihat merah. Riang dan Taryan
membalas senyumnya.
“Baru kesini?” Tanya wanita itu ramah
“Iya. Nganter teman!” Taryan antarkan Riang menuju sofa. ”Sebentar ya Mbak.”
“Namanya siapa?”
“Saya Taryan!”
Wanita itu tidak memakai lipstik tapi warna bibirnya merah jambu mengkilat ditimpa
cahaya lampu. Ia keluarkan karton hijau bergaris.
”Akang, sakit apa?”
Taryan menunjuk. “Yang sakit bukan saya. Itu ...”
“Jadi yang sakit bukan Akangnya.” Wanita itu mengambil tip ex. “Nama teman Mas
siapa?”
“Riang?”
Taryan kebingungan. Wanita itu melihat ke arah Riang, meminta nama panjangnya.
“Riang Merapi!” Riang menyahut dari tempat duduknya, kemudian mengenakan
penutup kepala, memperhatikan wanita itu, namanya Milea. Ia mengingat baik-baik huruf
yang menempel di dada wanita itu. Melihat Milea membuat sakit perutnya berkurang. Selesai
menulis nama, Milea masuk ke dalam sebuah ruangan. Tak lama, pintu dibuka. Pasien wanita
berpakaian seronok muncul. Mukanya lesu. Sekarang, giliran Riang dan Taryan masuk ke
dalam.
Seorang wanita tua berwajah keibuan duduk di sana. Umur nya sekitar 50 tahunan. Ia
persilahkan si pasien duduk dan menceritakan keluhan. Setelahnya Riang berbaring di
ranjang.
Dokter menekan perutnya. “Sakit atau tidak?”
“Sakit!”
“Asal dari mana?” Dokter Nurlaela memasang stetoskop.
“Thekelan Jawa Tengah Bu.”
“Disini kerja?”
144
“Jadi kuli bangunan di Kebun Kelapa.” Riang berbohong. Ia malu mengakui
statusnya sekarang.
“Di Bandung ada keluarga?”
“Ndak ada!”
Pemeriksaan selesai. Ada tanda tanya di wajah dokter. Riang memakai baju dan
jaketnya.
“Terakhir mengkonsumsi apa?” tanya dokter sembari mencuci tangan di keran.
Hampir saja Riang bilang Big Boss. Kerudung yang dikenakan dokter Nurlaila
membuatnya tak tega berterus terang.
”Tongkol” yang terucap dari mulut Riang.
”Untuk sementara makan bubur saja.” Dokter mengambil kertas. ” Selama dua hari
ini, jangan makan yang keras-keras.”
Riang menyenggol dengkul Taryan.
Taryan memasukan tangan ke dalam kantung celana. “Biayanya berapa Bu?”
“Sebentar,” Dokter menulis resep di kertas. “Apotik ada di samping.” Katanya.
Taryan mengulang pertanyaan, “Maaf Bu ... berapa biaya berobatnya?”
“Tidak usah.”
“Jangan!” Teriak Riang dan Taryan hampir bersamaan.
“Tak apa. Uangnya dibelikan obat saja”.
”Jangan Bu!”
Dokter Nurlaila tersenyum melihat bolong di gigi Taryan. Tak perlu lagi ada
percakapan mengenai biaya, sebab keputusannya sudah final.
Riang dan Taryan pamit berdiri. Taryan mengambil tangan dokter Nurlaila. Dahinya
ia letakan di atas lengannya. Dokter kebingungan. Mereka pun keluar. Saat pintu hampir
tertutup, dokter keluar dari ruangannya. Kali ini suaranya terdengar hangat. “Lekas sembuh
ya Nak!” Hari ini hati kedua orang itu dipenuhi bunga. Dokter Nurlaila membuat bahagia.
Mereka memetik pelajaran bahwa tak selamanya orang yang kelihatan dingin tak mempunyai
kepedulian.
Malam itu di bawah temaramnya bintang Taryan bermimpi bertemu mertuanya.
Riang lain lagi. Ia bermimpi bertemu Milea. Dalam mimpinya, Milea mencoreng morengi
wajah Riang dengan arang. Dalam tidurnya Riang tertawa. Subuh harinya, ia sudah bisa
kentuti wajah Taryan.
KETERTARIKAN
145
Satu minggu setelah berobat, seorang pria memperhatikan tenda darurat Riang.
Wajahnya bolong-bolong bekas cacar. Ia menyembunyikan rambut keritingnya di balik topi
bergambar Iwan Fals. Rahangnya yang tegas bertentangan dengan kedua lesung pipitnya.
Kausnya berwarna putih. Ada tulisan Djarum Coklat berwarna merah di dadanya. Ia
menggunakan jeans abu-abu yang serat-seratnya terlihat di bagian dengkul. Pria itu
menggendong gitar. Ia memergoki Riang yang tengah memperhatikan kalender lama
bergambar wanita yang lagi nungging. Pria itu kemudian mencocokan wajah Riang dengan
photo yang ada di tangannya. Riang tak tahu. Ia dicari sejak lama.
Sebelum hampiri Riang, pria itu meminjam korek api dari pejalan kaki. Korek api
lembab. Matanya berkeliling mencari pedagang asongan. Ia tak menemukan. Pria itu
kemudian berjalan, sampai di tenda darurat yang menyerupai kandang ia lantas jongkok,
menggerakkan tangan dan memberi isyarat pada Riang bahwa ia ingin meracuni paru-
parunya. Tanpa melihat wajahnya lebih dahulu, refleks Riang sibuk mencari geretan. Di balik
onggokan baju, ia menemukan geretan kuning yang sudah beberapa hari tidak ia digunakan.
Pria itu mengulurkan tangan. Riang tengadah. Ia terkejut melihat tingkat kerusakan wajah
lelaki yang ada di hadapannya. Pria itu biasa dengan respon pertama yang biasa dia dapatkan.
Ia mengembalian geretan lalu menawarkan jabatan tangan.
Riang tak tahu rencana yang ada di balik kepala pria yang ada di hadapannya. Tak
terasa obrolan sudah berlangsung lebih dari lima belas menit. Riang merasa nyaman
dengannya. Nama panggilan pria itu, Awas Bentar. Namanya aslinya tenggelam karena
sebuah kejadian.
”Suatu saat, waktu aku tengah ngamen di Jakarta hujan lebat datang tiba-tiba! Petir
menyambar pohon paling tinggi di daerah UKI. Semua orang nunduk. Semua orang takut.
Seram! Kejadian itu menyeramkan! Aku melihat langit. Cahaya seperti akar muncul di
angkasa. Sebelum suara menggelegar muncul, aku teriak! Aku mengkhawatirkan teman-
temanku. Aku berteriak .... AWAS BENTAR!!! dan sejak saat itulah nama Awas Bentar jadi
panggilan untukku. Resmi!” Ia mengepulkan asap rokoknya.
”Jadi yang ganti nama aslimu, Aep Ahmadi itu, teman-temanmu?”
Pertanyaan tak berbobot itu dijawab Bentar dengan senyuman. Ia masukan abu rokok
ke dalam bolongan gitar.
”Siang begini tidak bekerja?”
Karena Riang tidak berhadapan dengan seorang wanita seperti Milea, ia tak ragu
untuk mengatakan terus terang. ”Pengangguran.” katanya, berharap menemukan peluang.
146
”Pengangguran banyak rizki?”
Riang tertawa.
”Bisa main gitar?”
”Sedikit.”
”Mau ikut ngamen?”
Ia menimbang-nimbang tanpa tahu apa yang harus ditimbang. ”Kalau bisanya cuma
kunci standar, tidak apa-apa?” tanya Riang.
”Tidak masalah. Kunci lainnya nanti ku beri contoh.”
”Kapan mulai?”
”Sekarang.”
Riang berbinar. Ia berjalan di samping teman barunya. Bentar mengajaknya menuju
daerah kost-kosan mahasiswa, di Simpang Dago, Dipati-Ukur dan daerah tugu Pancasila.
Mereka menaiki angkot Kebun Kelapa menuju Kimia Farma, lantas turun dan menunggu
DAMRI pulang dari terminal Leuwi Panjang.
” Itu dia!” Bentar berteriak. Bus reot datang.
Kedua orang gelantungan seperti monyet padahal ruang bus cukup leluasa. Untuk
Bentar gelantungan itu berarti gaya sedang untuk Riang mengikuti saja.
Di dalam bus orang-orang duduk beraturan. Hanya dua orang lelaki yang berdiri.
Kaca jendela digeser setengah. Angin masuk. Suasana sumpek hilang. Leher-leher beraneka
warna putih, kuning, dan coklat menantang. Dari pintu belakang, Bentar melangkah ke
depan. Ia memegang besi di langit-langit. Gas DAMRI yang tak stabil membuat jalannya
seperti Kwei Cheng Kein. Di tengah-tengah bus, Bentar berteriak lantang. “Kalau Anda
menyangka bahwa Anda tidak akan bertemu lagi, tidak mungkin menjumpai lagi pengamen
jalanan maka .... Anda semua … SALAH BESAR! ........ Selamat Siang! Salam pembebasan
untuk teman-teman yang sedang menikmati pendidikan! Untuk yang lain, saya ucapkan
semoga bisnis hari ini berjalan lancar.”
Tak duk, tak duk, suara gitar di tepuk.
”Maaf jika saya mengganggu!”
Gonjreng… gonjreng!.
Bentar bernyanyi diiringi pantun.
”Dari manakah datangnya lintah,
darilah sawah terus turun ke kali.
Perut mual serasa mau muntah,
147
padahal nyium perek cuma sekali!
(Dia berhenti nyanyi, memainkan gitar,
kemudian diselingi kembali pantun)
Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar,
titiplah saya sekilo kentang.
Sungguh mati lutut suka gemetar,
kalau liat cewe tidur telentang!
Ke kamar mandi aku tak masuk mandi,
tapi untuk mencuci tempat menggoreng.
Pada nona aku tak Bermaksud berjanji,
tapi hanya sekedar tularin Koreng.
Ada roda dijalan tanjakan,
tertimpa dahan si pohon jengkol.
Ada janda menjerit kesakitan,
gak taunya lagi dikerjain banpol
Tinggilah tinggi air pancuran,
terdengar kicau si burung pipit.
Padahal satu bulan baru pacaran,
badan kurus habis dijepit!
Jalan-jalan ke kampung,
pacaran menjadi kadal di dalam gua.
Mati juga aku tak penasaran,
kalau sudah gamparin mertua!
Terbanglah tinggi kapal-kapalan,
jatuh ke ember ada airnya.
Sungguhlah cantik itu perawan,
waktu ditelanjangin banyak kutilnya!
148
Nenek2 ompong makan bengkuang,
tukang kredit datang menagih.
Nenek-nenek ditindihin anak bujang,
dasar genit … besoknya minta lagi
Ada seorang bapa datang merinding,
gak tahan ingin kencing.
Rasanya diri ini mau mati,
waktu mimpi pantat digerogotin kucing!
Tentara jepang gagah tegak berdiri,
tapi kalau perang dia takut sendiri.
Ke anak orang sayang kaya ke anak sendiri.
Kalo liat bini orang lupa bini
sendiri eeeh, dasar laki-laki!”
Lagu berhenti.
Orang-orang di dalam bus tertawa. Ada yang nangis. Ada yang memegang perut. Ada
yang senyum simpul mendengar lagu yang pernah dibawakan Doel Sumbang.
Bentar mohon pamit. “Terima kasih. Mudah-mudahan tidak tersinggung! Kalau
tersinggung Saya mohon maaf.” Ia senteri orang-orang dengan senyum. Orang-orang
membalas dengan senter yang sinarannya lebih kuat. Mereka terhibur.
Bentar mengambil kantung permen. Didatanginya penumpang satu persatu.
Kebanyakan orang memberi dua ratus rupiah. Orang yang terbahak sampai keluar air mata
memberinya uang seribuan. Uang mengalirlah. Bunyinya sampai di kuping Riang. Cring-
cring!
Bus sampai di tempat ngetem. Orang-orang berhamburan. Gencet-gencetan.
Kondektur marah. “Sabar! Sabar!” bentaknya. Seorang penumpang, nyeletuk. ”Sabar! Yang
sabar di sayang kucing!” Orang-orang tak pedulikan. Kondektur hampir murka. Ia tahan
untuk mengucapkan sumpah serapah tak senonoh. Dari mulutnya akhirnya keluar rapal
istighfar. Ia cuma takut penumpangnya tergilas. Riang dan Bentar tinggalkan kerumunan,
meloncat paling awal. Mereka berjalan menuju warung tegal.
149
Suara mix masjid keresekan. Azan mengudara. Suaranya timbul tenggelam.
Gelombangnya terhalang rimbun pohon flamboyan, suara kendaraan dan teriakan calo-calo
angkutan. Masuki ke dalam warteg, dangdut remix meradang mengombang-ambing.
Syairnya mengenai derita wanita yang menjadi janda.
Botol-botol kecap dan saus kosong tergeletak di pipiran kedai. Jam dinding gambar
balita gelengkan kepala. Segelas kopi panas disajikan. Tukang ojek keluarkan gulungan uang
yang diikat karet.
“Minum apa?” Bentar memecah perhatian Riang.
“Air putih!”
Bentar tersenyum sinis. ”Kamu pikir uang yang aku dapat bakal di bawa mati?”
Ucapan itu mengartikan: pesanlah apa saja! Masalah bayar kutanggung sampai tujuh
turunan! Tapi, Riang tak mengerti.
“Es jeruk dua Bu!” Bentar acungkan dua jari.
Ibu berambut kusam, jalan ke arah cerek. Ia ciduk air menggunakan gayung panjang.
Ia masukan isinya ke dalam termos bunga. Di ambilnya dua buah gelas besar. Diperasnya
dua buah jeruk nipis, dibubuhkannya dua sendok gula pasir. Sendok yang diputar berpuluh
kali timbulkan orkes. Balok es ditusuk besi tajam sekurus lidi. Bongkah es tambah isi gelas.
“Tertarik ngamen?” Bentar bertanya.
“Daripada ngemis, ngamen lebih terpandang, lebih cepat datang uang.”
“Kapan mau mulai?”
“Mulai?” Riang pura-pura.
”Ya! Kapan mulai makan?”
Oh, Riang kecewa.
”Ya, mulai ngamen lah!”
Bukan menjawab waktu kesiapan dia kapan, Riang malah semangat bilang, ”Mau!”
“Kalau begitu, datang kerumahku dulu saja.” Bentar pinjam pulpen. Ia sobek kertas
rokok. Dituliskannya alamat dibalik kertas alumunium emas. ”Podok Liliput. Dago elos 62.”
“Kamu bisa main gitar kan?” Bentar memastikan.
“Cuma kunci standar.”
“Bagus! Itu dasar!” Bentar angkat jari. “Bu pesan nasi satu pake perkedel, tambah
kangkung,” ia menoleh. “Kamu makan apa?”
Riang menjawab masih kenyang padahal perutnya keroncongan.
”Jangan basa-basi ah!” Bentar angkat alis. “Bu satu lagi. Sama!”
Siang itu perut Riang membuntal. Usai bicara tak tentu arah, Riang ucap terima kasih
150
waktu Bentar tengah mencongkel biji cabai. Mereka berpisah.
Riang teringat Taryan. Ia berjalan menuju simpang Dago. Menurut taksirannya,
tempat Taryan mangkal tak kurang satu kilometer jauhnya. Selama sepuluh menit ia lewati
bermacam hal. Mahasiswa-mahasiswi seliwer berlawanan atau berjalan searah dengannya.
Kebanyakan dari mereka memakai baju seragam hitam putih.
Melewati kedai kedai kopi, ia melihat mahasiswi berambut sebahu datang ke arah
penjual rujak. Wanita itu mengambil semangka, duduk di bangku panjang bersama seorang
lelaki kekar. Wanita lainnya bertubuh mungil, rambutnya dihias bandana corak bunga,
bersandar di mesin fotokopi bermerek Xerox. Lampu mesin fotocopy yang seterang petir itu
mengelus jerawatnya. Wanita itu tersenyum. Seorang lelaki tua menyekop debu dan sampah
plastik yang terserak. Dimasukannya sampah itu ke dalam tong bekas cat.
Riang sampai di perempatan Dago. Ia tak temukan Taryan di samping kios buah, di
bawah triplek Jus Ngeunah yang beberapa waktu lalu ditunjuknya. Riang melangkah lebih
jauh melewati warung masakan padang. Ia menemukan sahabatnya tengah duduk dekat
etalase kacamata. Setelah menukar uang seribu dengan sebungkus keripik singkong, Riang
menepuk pundak Taryan.
“Lha kok di sini!?” Taryan terkejut.
Riang tak lekas menjawab. Ia sibuk mengunyah. Taryan merebutnya. Tak berapa
lama kemudian cerita pun mengalir.
“Mau ngamen tapi tak punya gitar?” Taryan berikan tanggapan sinis, setelah Riang
menyelesaikan ceritanya.
Riang nyengir.
Taryan mendesak.
“Ngamen pake apa? Pakai kecrekan?! Tepuk-tepuk tangan?! Ndak pantas! Yang
pantas pake kecrekan itu anak kecil!”
“Lha orang dia punya dua. Dia mau meminjamkan gitarnya!”
”Baru pertama ketemu sudah berani pinjamkan gitar,” Taryan geleng kepala. Sewa?”
“Gratis!”
“Wah… wah! Baru pertama kali sudah baik gitu. Situ ditipu! Si Bentar itu orang
mana dia?! Batak?!”
Riang menggoda. ”Bukan! Dia tinggal di Kampung Rambutan!”
“Orang kampung Rambutan? Tuh! Kamu ditipu Yang!” Taryan menunjuk mukanya.
“ Mau gigi depanmu hilang hah?!”
”Dia asli Garut!”
151
”Sama saja!” Taryan sebal. Dia diam. Mereka diam.
Lima menit kemudian Riang menyerah. Ia memberi Taryan pengertian.
”Yan.... aku tak punya pilihan. Kamu tau sendiri kalau uangku habis. Lagipula, kalau
Bentar memang seperti yang kau pikirkan, ia tak bakal dapat apa-apa dariku. Dia bakal rugi
habiskan waktu denganku!”
Taryan tak beri komentar. Malam harinya tawaran Bentar memeriahkan mimpi Riang.
SOLIDARITAS
Taryan belum bisa membujuk Riang. Selogis apapun alasan yang Riang beri, ia tetap
tak setuju atas keputusan Riang. Kampung Rambutan, masa lalunya di Jakarta merupakan
salah satu pengalaman terbaik bagi Taryan. Pengalaman yang membuat giginya tanggal,
uang di kancut, serta Leonard dan anak muda sipit yang menurut kajian ilmu antropologi
tidak menyiratkan ciri-ciri fisiknya berasal dari tanah Tuanku Rao dan Sisingamangaraja itu,
menanamkan sikap skeptis padanya. Pagi ini, sebelum sore hari mereka menemui Bentar di
Dago elos, Taryan terus berpikir, mencari cara agar Riang mau mengikuti sarannya.
152
Warung Aplatun tampak di depan mata. Dari kejauhan mereka melihat tangan
pemilik warung melambai. Aplatun butuh receh. Ia tahu kepada siapa uang besar harus
dipecah.
Kantung Taryan tak lagi memberatkannya, uang logam di ganti uang kertas yang
ringan, yang semua ekonom mengetahui bahwa nilai yang tertera di permukaannya hanyalah
dusta, Aplatun mulai menggosip: mengenai IP pelanggannya tadi yang turun, tentang wajah
drop outnya, tentang kuliahnya di sastra jurusan basket karena kuliahnya dihabiskan di
lapangan basket.
Aplatun melucu. Riang, Taryan dan seorang pelanggan lain tak ingin humor Aplatun
disia-siakan. Mereka pun memberi Aplatun tawa kemanusiaan.
”Sekarang anak itu malah kecanduan game.” Aplatun memulai lagi. ”Tak tahulah apa
jadinya! Tak ada urusan!”
Pelanggan yang sebelumnya ikut tertawa bersama Riang dan Taryan menyelesaikan
makannya. Ia memberikan uang pas lalu melenggang keluar dan menyalakan mesin
motornya yang berplat merah.
”Kalau dia,” Aplatun menunjuk keluar, ”anak yang barusan tadi kuliahnya di jurusan
peternakan gigi!”
”Jurusan apa itu?” Taryan kebingungan.
”Lha giginya maju!”Aplatun tertawa. Riang diam tak timpali. Biar dia dari desa, dari
udik Riang tetap tidak suka gurauan tak berperadaban semacam itu. Aplatun merasa tidak
nyaman. Merasa salah dengan ucapannya, larilah si bujang mencuci mangkuk dan gelas yang
sudah menumpuk, meninggalkan Riang dan Taryan yang tengah menikmati sarapan paginya.
Di sana Taryan kembali membujuk Riang. Ia terus menerus membicarakan perihal
yang haram di bicarakan karena mengandung bahasan SARA. Riang tak peduli. Sejak
bertemu Bentar dan memperhatikan betul wajah serta kepribadiannya, ia sudah memutuskan.
Kekeraskepalaan Riang membuat Taryan yang kesal, meminta bantuan. ”Ton,” Taryan
berteriak, menyindir, ”... masa dia mau percaya sama orang yang baru dikenal!”
Orang yang dimintai bantuan sadar diri. Aplatun baru saja keluar, menghindari
perang dinginnya dengan Riang. Ia belum mau mengomentari. Ia menunggu apa yang bakal
Riang katakan.
”Yan, mungkin situ ada benarnya,” Riang berniat membalikan, ”tapi kalau pikiranku
begitu terus, mencurigai setiap orang terus, apa situ pikir kita bakal bertemu, menjadi
teman?”
Taryan butuh waktu untuk mencerna, menggambarkan bagaimana dulu Riang
153
membopongnya sewaktu tengkurap di jalan. Membopong dirinya, orang yang sama sekali
tidak Riang kenal.
”Tapi, waktu itu situ yang nolong aku, bukan orang lain.” Taryan bersikukuh.
Riang mengambil nafas. ”Banyak orang jahat, tapi tidak semua orang jahat kan?”
Tanya Riang.
Taryan kalah telak. Ia tahu Riang benar, bahkan sejak alasan awal alasan bahwa
dirinya tak punya uang. Riang pun tahu, apa yang dilakukan sahabatnya --berusaha
membalikan pikirannya-- adalah sebentuk solidaritas serupa dengan pengorbanan Taryan
untuk tetap bersamanya di jalan, meski ia tahu uang yang dimiliki Taryan dari mengemis,
sebenarnya bisa digunakan untuk membeli tiket kereta. Alasan mengapa Taryan tidak
melakukannya adalah sebentuk rahasia. Riang malas menanyakannya. Ia hanya menanam
keyakinan, bahwa suatu saat nanti Taryan bakalan pulang. Riang berusaha berpikir jernih
bahwa yang dilakukan sahabatnya adalah –pula-- sedikit dari usaha dia untuk melindunginya.
Sampai di titik itu, Riang menyesal mengungkit kebaikan yang pernah ia lakukan, untuk
membalikan keadaan.
Aplatun masuk ke dalam warung membawa gelas dan mangkuk yang masih
bercucuran. Dari luar terdengar desis pipa PAM yang bocor. Ia mengambil plastik dan tali
yang terbuat dari karet ban. Aplatun kembali keluar.
”Situ harusnya ambil pelajaran!”
Taryan yang sudah tidak bisa menggunakan pikirannya. Taryan membuat Riang
bosan. Ia tidak mungkin mempan. Ia biarkan Taryan mengulang-ulang membicarakan
pengalamannya. Taryan hanya tidak ingin kehilangan harga diri usai argumentasinya
dikalahkan.
”Situ dengar ndak aku bicara? Situ dengar Yang?! Jangan sampai Situ nyesel! Orang
batak yang kutemui, si Leonard itu itu gila! Yang di Kampung Rambutan awalnya baik! Sok-
sokan baik! Orang yang satunya lagi yang aku kira benar ternyata begajul juga! Apalagi
orang kemarin kutemui di dekat BIP, orang yang pernah buat aku babak belur, yang ampil
dompet temuan itu... sama juga!”
Riang teringat ketika Taryan menawarinya main cewek dan membelikannya makanan
usai menemukan sebuah dompet.
”Hah!” Riang tak sadar jika ia berdiri.
Taryan hentikan kicauannya. Ia tertegun.
154
”Di mana tadi!? Di BIP kau bilang?!” Riang memaksa.
Suasana tiba-tiba berbalik. Taryan bingung. Marahnya padam. Ia tidak menemukan
kata untuk menjelaskan.
”Di mana?” Riang menekan. ”Di BIP?!” Ia memastikan.
Taryan tidak punya maksud mengungkit sial yang pernah orang lain timpakkan, tetapi
ia kadung bicara.
“Yang, aku sudah ndak mikirin itu.” Taryan berubah dingin. Panas lima puluh
sembilan derajat yang beberapa detik lalu dicapainya, berubah menjadi dua derajat selsius.
“Yan!?”
”Sudah. Aku malas bahas itu.” Taryan reflek meminum es teh sisa pelanggan yang
masih teronggok di meja.
”Kalau malas, kenapa Situ bilang lihat preman yang buat Situ bengep?!”
“Kalau tahu sikapmu bakal begini, mustahil aku cerita.” Jawab Riang asal. ”Aku
cerita bukan supaya Situ ngamuk.”
”Siapa yang ngamuk!?”
”Situ! Lha, aku cerita supaya situ jangan percayai ... siapa itu namanya ... siapa?!”
Riang tak menjawab pertanyaan Taryan.
”Ceritaku bukan untuk balas dendam.” Taryan mematenkan.
Riang berpikir cepat. “Ini bukan masalah balas dendam!” Keahliannya yang
terpendam ia gunakan, ia keluarkan ”Ini masalah mengingatkan! Kalau preman itu didiamkan
apa yang terjadi?”
Taryan tak peduli. Ia menerawang ke depan. Tangannya, mengetuk-etuk gelas.
“Yan, ... bagaimana mereka mau sadar kalau ndak ada yang mengingatkan? Mereka
bakal terus jahati orang! Nodong orang! Nakutin orang! Bener kan?!”
Riang haluskan suaranya. ”Yan ... kalau semua orang kayak Situ, di dunia ini tidak
bakal ada nabi!”
Taryan menjauhi mata Riang namun ia mulai tertarik karena Riang menyebut-nyebut
nabi.
”Kamu fikir nabi Musa diturunkan untuk apa?!”
“Untuk umatnya.”
“Sungguh tepat untuk umatnya! Tapi bukan itu maksudku! Musa diturunkan untuk
mengingatkan! ... Isa diturunkan untuk apa?”
“Untuk mengingatkan seperti mau mu itu!”
“Bukan mauku! Situ cinta Muhammad ndak!?”
155
Taryan diam.
Riang menemukan celah.
“Muhammad diturunkan untuk apa?”
“Mengingatkan!.”
“Benar!” Taryan didesaknya hingga ke pojok. ”Sekarang, agamamu apa?”
“Dari dulu juga Situ tahu!”
“… Kalau agamamu Islam, Kamu ndak mau mengiikuti nabimu? Apa Situ
tidak mau peringatkan orang lain supaya tidak kembali melakukan kejahatan lagi?”
Taryan gamang. Disaat itulah Aplatun masuk. Teriakan Taryan di awal-awal
pembicaraan membangkitkan naluri alaminya Wajahnya merah padam. Ia seakan menahan
benda besar yang hendak keluar dari tubuhnya.
”Aku dengar sedari tadi! Siapa mau kelahi?!” Aplatun meminta penjelasan yang
sebenarnya sudah jelas baginya.
Mulut Riang terbuka, hendak menjelaskan semuanya, namun mendadak Taryan
mennyalipnya untuk menyederhanakan permasalahan. Penyederhanaan ini malah
memanjang. Kepanjangan inilah yang justru membuka selubung pengunci mahluk yang
bersemayam di tubuh Aplatun.
“KAMPANG!” Hidung Aplatun mendadak kembang kempis Ia marah. Nafasnya
menghembus-hembus! ”Orang Batak itu suaranya saja yang besar!!! Kalau ditantang kelahi
pakai pisau, kabur semua!!! KAMPANG!!! Biar ku tujah mereka! Biar! Biar mereka tahu
kalau berurusan dengan temannya siapa!!!”
Ghuarg! Awan tabrakan. Suara petirnya melabrak rongga pendengaran. Suara
Aplatun sungguh menakutkan! Tidak cukup, Ia gebrak triplek putih. Gelas yang ada di
atasnya berajojing meloncat setengah senti.
“Aku ikut kelahi dengan kalian!!!” Blar! Petir ganas menyambar! “Kurus-kurus
begini, aku pernah jadi pemimpin bajing luncat!” Dan mengucur deraslah cerita menakutkan
dari keran mulut Aplatun.
Diceritakan bagaimana dulu, ia menyengajakan diri menumpang bis eksekutif menuju
Bengkulu. Manakala bus sampai di Jerambah Kawat, manakala orang masih terlelap, Aplatun
menyiram lantai bus pakai bensin. Aplatun teriak, menggertak! Suaranya bangunkan semua
penumpang! Diperintahnya orang-orang preteli hiasan dan dompet. Di perintahnya supir bus
berhenti injak pedal gas. Kalau tidak, Aplatun ancam: bus itu bakal dia bakar!
Bus berhenti. Teman-teman --yang memang sudah menunggu di Jerambah Kawat--,
naik. Tidak ada satu penumpang pun yang berani melawan, kecuali satu orang lelaki yang
156
perawakannya mirip tentara. Aplatun kalap. “Kau mau jadi pahlawan hah!?” Ia teriak! Maka
di bacoknya kepala orang itu sampai mati! Wanita yang ada di dalam bis ringsut. Tak ada
yang teriak kecuali seorang lelaki yang dandan ala banci.
Penumpang bus sadar. Mereka tidak bisa melawan. Maka, beberapa wanita menjadi
sukarelawan: mempreteli anting-anting, gelang, tusuk konde emas, cicin tunangan, walkman
dan dompet milik sendiri, untuk dimasukan ke dalam karung goni.
Aplatun, merasa harus yakinkan Riang dan Taryan. Cerita yang tak kalah seram
ditambahkan.“Dulu, aku pernah masuk Angkatan Darat di Palembang. Di sana aku ketemu
komandan brengsek, yang kalau aku salah sedikit dia selalu ngancam kalau aku bakal
dipecat! Kerjanya maen perintah seolah aku ini hewan! Aku melawan! Komandanku marah!
Aku digamparnya! Maka aku matikan saja dia!”
Bukannya si komandan yang memecat, malah Aplatun yang memecat sang komandan
dari kehidupan di dunia. Si komandan dipersonanongratakan dari alam manusia menuju alam
baka! Perbuatan ini sebabkan Aplatun masuk berita koran-koran besar. Akibatnya lahan
hidup dia di Palembang menyempit. Aplatun lari ke Jakarta. Di waktu-waktu ke depannya, ia
jadi tangan kanan preman nomor satu di Kampung Rambutan.
Riang dan Taryan tak habis pikir. Dia ... Aplatun yang kerempeng itu... Aplatun yang
banyak omong itu ... punya masa yang kelam, punya cerita seram yang bisa buat manusia
biasa keriput.
Dukungan Aplatun, dengan skill tersendiri yang seharusnya membuat Riang bahagia.
Cerita masa lalu Aplatun tidak membuatnya senang. Ia malah berpikir: bagaimana jika
preman itu dipecat Aplatun dari nikmatnya kehidupan di dunia?
Pemukulan dan perampasan harus di balas dengan balasan yang setimpal. Akan tetapi
balasan yang setimpal itu bukan dibunuh!
Di antara waktu jeda, Riang berpikir..
“Aku senang kau punya itikad baik. Siapa yang tidak senang Ton ... tapi maaf, kali ini
jangan!” Ia temukan alasan.
“Jadi kau …?!” Ada kata-kata yang tak mampu kelur dari mulut Aplatun.
Riang khawatir Aplatun merasa disepelekan. “Bukan! Bukan aku sangsi
keberanianmu, tapi sekarang ini Kau sudah hidup tenang. Sudah hidup baik-baik! Kalau ikut
kami, tusuk sana tusuk ini, apa yang terjadi?”
“Tak peduli! Aku tak peduli. Pantang kata kutarik lagi. Pantang! Tak mungkin takut.
Nenek moyang ini tak pernah takuti apa! Aku bunuh orang-orang itu!”
“Bukan! Bukan begitu … ,” Riang rendahkan suaranya, “Aku tahu kau tidak takut
157
kecuali takut pada Tuhan,” Riang sengaja sebut nama Tuhan. Nama Tuhan biasanya mujarab
redakan marah. “Aku tahu Ton… aku tahu… tapi masalah tidak semudah yang dibayangkan.
Kalau kau menujah, yang ditujah mati, apa selesai? Tidak. Kau bakal dicari, bukan cuma
dicari segelintir orang Batak. Bakal orang-orang Batak se-Bandung!”
“Kalau semua uber aku, tidak takut aku! Nenek moyang ini, sejak kemerdekaan
berjuang demi tegaknya UUD 45! Aku tahu, biar mereka bajingan tapi bajingan untuk
Belanda! Nenek moyangku, kakekku, arwah kakekku Mat Kancil bakal malu kalau lihat
keturunannya, aku Aplatun tidak turun tangan! Ikut bela kawan! Tidak perlu satu! Seribu
orang Batak, aku lawan mereka! Sepulau Samosir, aku tujah satu persatu!”
Riang berusaha kesankan dirinya berani. Kesankan kalau ia dan Taryan bisa
selesaikan masalah sendiri, “Demi Tuhan Ton ... jangan dipotong dulu perkataanku ... Ton …
kalau aku dan Taryan ndak apa–apa tujah sana-sini Habis beri pelajaran, habis bunuh itu
preman, bisa pergi semau kita. Bagaimana dengan mu? Kau pasti rugi. Mau dikemanakan
warung yang kau bangun? Mau kau bawa? Warung tak mungkin digendong. Membangun
warung baru butuh modal, butuh uang, perlu biaya dan masalah tidak mungkin selesai di situ
saja! Kalau warung Kau tutup, bagaimana nasib istrimu?”
Kehidupan istri, keluarga yang disayang, adalah salah satu cobaan terberat sepanjang
sejarah manusia. Wajar jika Aplatun goyah. “Tapi!... Tapi!...,” Aplatun masih berusaha
menyangkal, namun pikiran menghambatnya. Pengaruh Riang sampai di kepalanya. Sebelum
Aplatun mendapat celah, Riang menyudahi.
“ ... Terimakasih! Aku dan Taryan hargai keberanianmu. Solidaritas sudah cukup.
Lebih dari cukup! Aku bangga punya teman sepertimu! Aku gembira, di zaman seperti ini
tersisa manusia yang pentingkan orang lain ketimbang dirinya. Inilah yang dinamakan altruis
Kamu preman shalih Ton. Kau pemberani. Kau tak usah libatkan diri. Aku janji, bilang
padamu, kalau temui masalah. Aku yakin, ini bisa diselesaikan,” Riang menyikut perut
Taryan.
Aplatun tak bicara lagi. Ia masuk ke dalam sekat triplek, mengambil golok panjang
berkarat. Diberikannya benda berbahaya itu, ”Buat jaga-jaga,” katanya. Riang tak menolak.
Untuk sementara golok itu akan disimpannya ditempat yang aman. Serah terima berlangsung
baik, aman dan terkendali. Untuk Taryan, Aplatun mengambil garpu. Ia bengkokan hingga
gagangnya dapat dikepal. Dua ruas tengah garpu tajam dibengkokkan menggunakan jempol.
Dua ruas itu bisa dijadikan senjata, menusuk orang. Suk!
158
SEPATU ROMBENG
Setelah mandi di masjid Agung, tubuh Riang dan Taryan bersih dan suci. Mereka
duduk di bawah terpal, Taryan berniat membincangkan cerita mengenai kehebatan dan
kedigjayaan Aplatun, namun orang di sampingnya tak mereken, tak memperdulikan. Riang
masih melayang-layang memikirkan kehebatan dirinya, memikirkan bakat terpendamnya
ketika mempengaruhi dua orang dalam satu hari. Riang tak habis pikir bisa mengeluarkan
kata-kata beracun semacam itu. Kata-kata yang bisa pengaruhi orang, kata-kata yang bisa
buat orang beringas jadi tenang, kata-kata yang bisa membolak-balik, mengaduk-aduk
pikiran orang. Ia hampir takabur. Senyum sendiri, mesem sendiri.
Apa yang Taryan katakan, ia dengar selewat. Riang dalam keadaan mabuk. Dalam
kondisi kepayang. Penyesalannya saat memaksa Taryan mengingat pertolongan yang ia
berikan hilang. Pertolongan yang pernah dilakukannya malah membuat Riang berkhayal dan
mengasosiasikannya dengan kata-kata altruis yang canggih. Riang mengulang kembali kata
yang pernah didengarnya. Altruis, altruis, altruis. Dalam pada itu, kejapan kata yang
membuatnya bahagia mengingatkan dia akan dua orang pria: Fidel entah di mana, dan Pepei
159
... O, Riang sedih. Riang berusaha melupakan. Hari itu waktu mereka menghabiskan waktu
dengan menggosipi apa saja yang menyangkut diri Aplatun, tentunya kisah perempuan gila
yang Riang temui di jalanan, tak luput dari perhatian.
Pada akhirnya acara gosip itu membuat Riang dan Taryan akur. Perseteruan tak perlu
dilanjutkan. Riang memilih waktu baik --yang entah kapan--, untuk membicarakan perihal
balas dendam.
Di bawah atas kulit bumi, dibawah terpal, mereka bersila damai, padahal di sebuah
ruangan, seorang pria gagah memberi instruksi. Orang-orang berseragam yang mengitari
tubuhnya mengangguk-angguk, memperhitungkan jam yang tepat untuk melakukan
gebrakan.
MALAM ITU, dalam diam Riang dan Taryan perhatikan keadaan sekeliling:
voltase tak stabil membuat lampu masjid agung redup berkedip, seorang ibu mengarahkan
pancuran air pipis balitanya menuju dinding tong sampah, seorang nenek memilih menyetop
kuda ketimbang angkutan kota, di samping tenda darurat penjudi goblok tenggak minuman
keras. Penjudi plus pemabuk itu kalah. Kalau sudah begini, malam dibuatnya menjadi
berisik, membuat Riang dan Taryan kesulitan memejamkan mata. Kata-kata kasar yang
dikeluarkan mulut pemabuk itu tak lucu. Hal ini berbeda dengan kawan-kawannya satu kubu
kemaksiatan.
Riang dan Taryan hapal benar binatang apa yang paling sering penjud-penjudi itu
teriakan sebagai umpatan, sebagai lakaran. Riang dan Taryan pasti rindukan lakaran itu.
Merindukan kehadiran Bapak yang di kepalanya selalu bertengger kopeah haji. Bapak yang
tak pernah langgar absensi di areal perjudian itu tentu bukan dalam rangka khutbah
ittaqullah! Bertaqwalah kepada Allah, melainkan untuk menyemangati dan membandari judi
kartu gaple dan remi.
Taryan yang suka shalat di masjid Agung tahu kalau bapak itu rajin shalat, meski
gerakannya secepat pelatuk Woody Wood Packer. Taryan tahu bapak itu dzikirnya berabad,
dan seharusnya ia sebal atas sikap munafik yang dipraktikan olehnya, namun tingkah laku
dan kata-kata si bapak membuat Taryan merasa harus mengecualikan. Se-preman-
premannya, sebejat-bejatnya, orang Sunda, mereka masih bisa menjadi Kabayan --dan
tentunya—masih memiliki kesempatan mempersunting ’Nyai Iteung’ yang cantik jelita.
”Kumaha mun tarohanana iman Islam!? Gimana kalo tarohannya iman Islam” Kata
si Bapak pada suatu waktu. “Mun tarohannana agama mah bosen! ’kalau taruhan agama sih
160
bosen’ Ayeuna, anu tarohanana leuwih keren mah, sekarang taruhan yang paling mutakhir di
antara yang mutakhir sih ... MATA SIA DICOLOK!!! MATA LU GUA COLOK! Wani teu!
Berani gak!’”
Riang dan Taryan yang sedikitnya sudah paham bahasa Sunda tertawa hampir habis
tenaga. Bapak itu memang edisi khusus yang tidak ada dua. Kalau kebanyakan penjudi
ucapkan, ”ANYING! ’Anjing!’ di setiap kekalahan dan kemenangan yang didapatkan, si
bapak yang acapkali dipanggil bos itu punya gaya beda. Kalau dia kalah yang pertama
dilakukan nyanyi lagu bung Rhoma:
Judi!
(Judi! Teot!)
menjanjikan kemenangan
Judi!
(Judi! Teot!)
menjanjikan kekayaan
Bohong! Bohong!
(kata bohong sengaja ia teriakan
di kuping orang yang paling dekat dengannya)
Kalaupun kau menang,
itu awal dari kekalahan.
Bohong! Bohong!
Kalaupun kau kaya,
itu awal dari kemiskinan
Judi!
(Judi! Teot!)
meracuni kehidupan.
Judi!
(Judi! Teot!)
meracuni keimanan
Pasti! Pasti!
karna perjudian,
161
orang malas dibuai harapan
...
Apapun namanya bentuk judi
itu perbuatan Keji!
…
Selesai nyanyi si Bos selalu ingatkan, ”UANG JUDI NAJIS! TIADA BERKAH!
APAPUN NAMANYA BENTUK JUDI!!” tidak puas di sana. Ia kemudian bercerita tentang
penjudi-penjudi yang bakal digosongkan menggunakan setrika sebesar traktor di neraka
Saqor!
Cerita tidak buat penjudi lainnya takut. Mereka tak peduli dengan neraka dan cerita
seseram apapun mengenainya. Mereka tak kuat tahan tawa. Riang bahkan pernah melihat
buih keluar dari mulut mereka.
Si Bos berkopeah haji itu memang hebat. Ia bukan saja mampu teriak, berkata
melainkan juga bernyanyi demi kepentingannya. Kalau ia menang di putarbalikannya lirik
bung Rhoma. Ia bernyanyi: "Uang judi memang penuh berkah! Itulah berkahnya judi! ... Judi
teot! ... dan seterusnya.
Riang dan Taryan boleh tertawa oleh perilaku sesat itu, tetapi seorang ustad muda di
masjid jami tidak! Ustad muda itu kesal. Ia tak sanggup melihat munculnya manusia yang
mainkan kesakralan surga dan neraka, memainkannya seolah tempat yang indah dan seram
itu tidak ada! Wajar jika pada satu waktu, usai shalat Isya, ustad muda itu menziarahi, dengan
niat menasehati para penjudi.
Bukannya sadar mereka malah balas khotbah sang ustad dengan olokan. Apa mau di
kata, maksud baik sang ustad muda dimutilasi oleh si Bos penjudi-penjudi gila. “Maneh teh
lemet keneh. Nyaho naon heh!? ’Lu tuh masih ingusan heh! Tau apa kamu tentang
kehidupan?!’ Mun maneh geus boga kaluarga, karak nyaho!, Kalau Lu dah punya keluarga,
baru tau!”
“Heeuh! ’Iya, benar!’” Penjudi yang mengelilingi si Bos kompak bersuara.
Lantas apa yang menjadi bantahan sang ustad muda?
“HARAM!!! Ini dosa benar! Sekali dosa besar tetap dosa besar!!” ia berkacak
pinggang.
Di hadapan anak buah, si Bos pantang mengalah.
“He … he … Dosa?! Ku aing di sunat siah! ’Hei hei, dosa?! Gua sunat luh! Sia kudu
nyaho kana kaayaan beul! ’Elu harus tau keadaan, bebal!’ Mun sia jadi aing, mun anak sia
di imah congor na ngangap-ngangap menta kadaharan, istri gering rek ngajuru, maneh
162
ngaharap ti mana?!m Kalau Elu jadi gua, kalau anak Elu di rumah, mulutnya ngangap-
ngangap minta makan, istri sakit mau melahirkan, mau ngeharap dari mana?’ Pamarentah?!
Cuiih! Pemerintah?! Cih!” Ia meludah. “Ti iraha pamarentah ngurusan aing sakaluarga?!
’Sejak kapan pemerintah ngurus keluarga gua?! Anak aing paeh ge teu paduli. Cuih! Anak
gua modar aja nggak peduli. Cuih!”
Ustad muda diam, lalu balik pulang. Dan perjudian pun berlanjutlah. Namun
keesokan malamnya, di jam-jam ketika perjudian tengah ramai, sang ustad datang bawa batu
sekepal tangan. Ia lempar batu itu! Melayang ...! Kopeah haji tersambar! Si bos jungkal
sekaligus dengan badan! Pingsan! Dari kepala si bos keluar darah. Arena judi kacau balau!
Penjudi-penjudi marah! Kartu remi dan gaple mereka lempar ke tanah. Mereka berdiri,
mengambil ancang-ancang. Mereka kejar itu ustad.
Ustad lari karena jumlah yang mengejar dirinya terlampau banyak. Bukan main!
Larinya cepat sekali! Dia berkelat-kelit, meliak-liuk gesit. Sayang! batu yang ia lempar
datangkan sial. Batu itu dilempar balik, menyerempet muka si ustad sampai pipinya codet!
Ustad terhuyung-huyung! Dan habislah badan dia dipukuli sampai sekarat.
Taryan dan Riang ingin membantu. Namun keinginan mereka hanya sampai bab niat.
Mereka hanya bisa doakan agar sang ustad tidak mati. Kalaupun mati mudah-mudahan
matinya syahid. Masuk surga!
Setelah para penjudi puas memukuli si ustad, barulah Riang dan Taryan mendatangi
got tempat ustad malang itu njompret. Ajal belum datang. Nafas sang ustad masih ada. Itulah
mengapa, sejak kejadian tragis itu tak ada satu orang pun yang mau menjadi martir. Perjudian
tak mungkin bubar hingga sebuah kejadian melakukannya.
MALAM ITU UDARA MENGHANGAT. Sebentar lagi hujan. Riang lupa ia ia
harus pergi ke rumah Bentar. Gosip mengenai Aplatun membuat dirinya hilang ingatan.
Menjelang tengah malam, Riang mulai merasa tidak enak dengan Bentar. Ia jadi takut
membayangkan Bentar menolak kedatangannya. Ia teringat atas apa yang dilakukan mandor
terhadapnya. Riang dipecat karena terlambat, karena bangun kesiangan. Ia takut
kesempatannya kali ini pupus akibat alpa.
Berulang kali Riang melihat Taryan yang tengah tidur pulas. Melihat lelaki yang
tidak ia ketahui merasa senang karena berhasil mengalihkan pikirannya ke arah Bentar.
Taryan terlihat letih. Belakangan ini, temannya itu acapkali bangun malam. Taryan
merahasiakan apa yang dilakukannya. Yang Riang tahu, Taryan selalu menggoyang kakinya,
163
pura-pura bertanya, “Sudah tidur Yang?,” Kalau Riang mengguman ia merebahkan badannya
kembali. Kalau Riang tak keluarkan reaksi, Taryan menyegerakan diri berjingkat keluar.
Riang sempat berpikir kalau sahabatnya tak punya pertahanan diri. Ia tidak tahan
karena dipikirnya Taryan sudah pernah ’mencoba’ dan dari obrolan masa remajanya, Riang
mendengar bahwa orang yang sudah ‘mencoba’ suka kecanduan. Pikiran buruk berusaha
Riang tepiskan, toh, setiap Taryan pulang, Riang tidak pernah mencium parfum perempuan
bergincu tebal yang sering berpapasan dengan Riang di jalanan. Hingga saat ini, kelakuan
Taryan masih menjadi misteri baginya.
Riang ikut rebahkan diri. Kesadarannya melarut. Tidurnya satu manusia lagi, mebuat
bumi semakin sepi. Deru mobil sesekali terdengar. Para penjudi sudah ditinggalkan begitu
banyak keramaian. Hanya tinggal mereka yang tersisa.
Tak jauh dari tempat itu, orang-orang berseragam yang di waktu sore mengangguk,
telah tentukan siasat dan jam. Beberapa puluh orang mereka datangkan dari suatu tempat
untuk lakukan penggarukan. Di malam yang gerah itu, suara sirine merayap di udara.
Suaranya belum sampai ke tempat Riang dan Taryan. Orang-orang berlari.
Desas-desus menyebar mengembang di udara. Penjudi kasak-kusuk. Puluhan orang
berseragam datang dari arah Dago. Mereka sampai di belakang masjid besar alun-alun. Suara
sirine mulai terdengar. Sayup. Orang berlarian dari arah masjid. Suara teriakan terdengar.
”Aparat! Aparat!”
Suara hingar bingar. Serombongan orang datang membawa kayu, membawa
pentungan! Mereka ’garuk’ warung dan gelandangan yang membuat Pemkot ’geli’. Penjudi-
penjudi di samping tenda bukannya malah melarikan diri. Mereka yang mabuk lempari
petugas Kamtibmas menggunakan botol dan gelas. ”Prang! Prang!” Beling pecah membentur
aspal. Tak satu pun petugas yang cedera.
Petugas masygul! Mereka mendatangi kumpulan penjudi. Pentungan membuat para
penjudi, akhirnya kocar-kacir melarikan diri. Beberapa orang yang tertangkap, dipukuli, lalu
dilempar ke dalam truk, sementara itu otak judi –si bos berkopeah haji selamat, sebab waktu
kejadian berlangsung si bos itulah yang lebih dulu melarikan diri.
Riang bangun. Keriuhan terdengar. Ia tak melihat Taryan di sampingnya. Riang
keluar. Ia melongo, menggaruk kepalanya menyaksikan Kamtibmas melancarkan operasi
penggarukan. Dari kejauhan, dari balik pengkolan seseorang berlari seperti orang liar. ”Yang
kabur! Kabur,” katanya. Riang sadar. Ia ambil harta yang tersisa. Ke dua orang itu tak sempat
mempreteli bahan bangunan rongsok yang mereka curi dan temukan. Riang dan Taryan terus
berlari, menyembunyikan diri. Di balik kegelapan mereka menyaksikan terpal, spanduk dan
164
kayu-kayu penyangga tenda darurat diterjang. Satu-satunya tempat kediaman bagi mereka
dirubuhkan. Sedih mendatangi seperti ubi jalar. Sedih membuat mereka tersesak. Tak ada
yang bisa dilakukan. Kedua orang ini gontai, berjalan meninggalkan kenangan.
Malam menua. Hujan tak jadi datang. Tak ada bulan dan bintang. Yang ada hanya
cahaya buatan manusia sinari jalan. Dari jendela angkutan kota, pohon-pohong, dinding
bangunan dan tiang-tiang berlari. Semua yang usang harus ditinggalkan. Malam ini ...
kehidupan layaknya sepatu rombeng!
UNTUKMU EMAK
Sementara itu
Kardi tengah bersembunyi di gundukan tanah. Seorang petani kentang meninggalkan
lahannya, berdendang pupuh kinanti. Kardi beringsut-ingsut lalu berdiri dari gundukan tanah
setelah meyakini si petani itu tak mungkin kembali hingga keesokan hari. Kardi pun melihat
Sekarmadji tengah tertawa, menggosok-gosok tangan, meludah-ludahi telapak seolah-olah
dengannya ia hendak melakukan sebuah pekerjaan berat yang membutuhkan persiapan.
Dalam sekejap beberapa puluh kentang tercerabut dari tanah, dikeruk oleh tangan dua orang
pelarian yang kelaparan.
Sekarmadji memilih kentang yang besar dan kelihatan matang ketimbang yang
lainnya. Kentang itu akan mereka rebus sebelum di makan. Lauk pauknya bakal mereka
dapatkan di sebuh kandang ayam dekat jembatan. Mereka meninggalkan lubang galian.
Sekarmadji bersiul-siul menanggung kebahagiaan. Dalam perjalanan menuju kandang ayam
kedua orang itu mendengar suara motor di tanjakan, mereka melihat motor trail melompat di
atas gundukan. Kardi sembunyi di balik batu. Sekarmadji mengikutinya.
Bising mendekat. Kopling berpindah saat motor trail menginjak batas bawah tanjakan
curam. Sesosok lelaki berbadan besar memainkan keseimbangan di atas jok. Beberapa meter
mendekati akhir tanjakan motor melambat. Karung goni dan karung plastik beras membebani
165
si pengendara. Ketika kopling kembali di tekan dan gigi satu dimasukkan, motor menggerung
keras, melewati akhir tanjakan, Kardi tiba-tiba melompat. Ia menendang motor hingga
pemiliknya terjungkal berguling-guling di tanah. Motor terpisah. Lelaki itu terpuruk. Ban
motor tertahan di celah bebatuan. Saat Kardi kesulitan mengambil motor, lelaki berbadan
tegap mendadak bangkit, memberikan kejutan.
“Awas!” Sekarmadji mengingatkan, namun ia terlambat. Lelaki itu lebih dulu
menempatkan kepalan di leher Kardi. Ban motor yang hampir lepas dari himpitan batu,
masuk kembali. Kardi jatuh tak sadarkan diri.
Tak bisa melihat temannya diperlakukan semena-mena, Sekarmadji melempar lelaki
itu menggunakan kentang. Hanya beberapa yang mengenai, itu pun tak terasa. Badan lelaki
itu terlampau besar. Orang dihadapinya memiliki postur tubuh paling tinggi yang pernah ia
hadapi. Pengalaman Sekarmadji memaksanya untuk menafikan perbedaan tinggi lawan
hingga tak menjadikannya persoalan. Pada kenyataannya, hanya dengan dua pukulan di
rusuk dan ulu hati, Sekarmadji pun jatuh bermesraan dengan tanah.
Lelaki itu menanggalkan dua begundal, lalu ia meninggalkan mereka begitu saja.
SEKARMADJI bangunkan Kardi. Mereka lantas memunguti kentang yang
berserakan, lalu melanjutkan perjalanan. Peristiwa yang baru mereka alami membuat rencana
mencuri ayam terlupakan. Mereka terus berjalan hingga mendekati rumah kediaman masa
kecil Sekarmadji.
Memasuki pekarangan rumah, Sekarmadji mendapati pekarangan itu dihiasi pucuk-
pucuk tanaman dan sayur mayur dan kandang ayam berwarna biru muda. Ia masuk
memandangi emak-nya yang tengah pulas, tidur di bale-bale. Bale-bale berderak. Sekarmadji
memeluk wanita tua itu. Sebuah drama tercipta.
“Siapa yang menanam sayur di depan rumah Mak? Othang atau Nenden Mak?”
Sekarmadji bertanya usai isak dan haru reda.
Lelaki dengan ciri fisik diucapkan Emak.
Sekarmadji enggan menerima.
“Lelaki yang mengendarai motor trail? Yang tubuhnya tinggi itu, bangunkan kandang
ayam juga, Mak?!”
Emak mengiyakan.
Sekarmadji merahasiakan apa yang terjadi, namun, di desa yang sepi, ketika jarang
ada orang yang datang meramaikan, siapa kira-kira yang bakal di curigai ketika penduduk
desa bertambah dua? Siapa yang bakal menjadi tersangka sementara seorang lelaki yang
166
dikenal penduduk desa akan kebaikan hatinya, memberitahu keberadaan dua orang begundal
di dekat gundukan tanah tak jauh dari lahan kentang.
Sekarmadji tak berani berkelit. Ia tak memiliki energi untuk berbohong ketika Emak
mendengar kejadian itu dari orang di desa.
“Kau masih shalat nak?” Emak bertanya sambil mengelus-elus rambut Sekarmadji.
Sekarmadji teringat kata dan makna dosa.
“Dosa yang tersangkut paut dengan manusia, teu tiasa, tidak bisa diselesaikan dengan
penyesalan. Kau mengetahuinya.” Sekarmadji ditangisi seolah dirinya sudah menjadi mayit.
“Lekas datangi lelaki itu. Kalau kau masih shalat, minta maaflah nak.”
Sekarmadji menunduk.
“Jangan kemana-mana setelah kau menemuinya. Kembalilah ke desa. Teu kudu tebih-
tebih milarian artos, tidak perlu mencari uang jauh-jauh jika hasilnya tidak membawa
berkah. Bantu Emak di sini nak. Bantu Emak mengurusi adik-adikmu!”
Sekarmadji berangkat menuju kota yang memang, sebelumnya harus mereka tuju.
Sampai di Bandung, bukan alamat lelaki tegap yang lebih dulu mereka cari. Kardi malah
mengajaknya menemukan orang yang dititipi Gendon untuk mengurusi mereka.
Tempat singgah di sebuah terminal ditemukan dan hingga pagi berlipat ganda
menjadi dua, Sekarmadji tak tunaikan janji. Esok datang, kembali berulang dan Sekarmadji
pun menghentikan janjinya. Ia mengganti janjinya dengan kalimat “Jika sudah siap, pasti
kutemui lelaki itu!”
Ketika hari itu telah mantap, waktu tak berpihak padanya.
167
PONDOKAN
(Sejak saat itu…kehidupan berjalan sangat singkat.)
Kayu pinus digantung. Permukaannya yang tertera tulisan pondok Liliput
dininabobokan angin. Kayu warna orangenya mengantuk. Kasian kayu itu. Dia belum pernah
mencicipi kopi dari daerah Lintang Empat Lawang. Lampu sepuluh watt di tempat itu
menjadikan bayang-bayang tembok batu bata tampak suram. Halaman depan pondok
ditanami kaktus. Bunga-bunga mekar ditempa sinar purnama, mengeluarkan sulur-sulur dari
batang yang ditanggalkan. Beberapa bunga jatuh.
Pagi itu dua orang yang di babak beluri kemalangan sambangi pondokan.
"Dik Riang kemari,” Riang menghayal datangnya respon Bentar, ”mari aku jambaki
rambutmu agar peningmu itu tak membuatmu semaput! Jambakkan tanganku akan membuat
migrain yang diakibatkan penderitaanmu sedikit hilang!”
Pagi itu ada percik kembang api di perut mereka tatkala menduga reaksi yang bakal
mereka terima. Riang khawatir Bentar tidak membuka telapak tangan lebar-lebar,
menyambutnya. Riang sadar diri, sore kemarin ia tak penuhi janji dan kali ini pun, ia datang
tak membawa kemaluan: mendatangi pondokan pagi-pagi buta saat semua orang terjongkang
di peraduan. Riang mengeraskan hati, menguatkannya hingga tak sadar cemas membuat
Riang meremas pantat temannya, membuat Taryan hampir berteriak. Bagaimanapun juga
cerca tak akan membuat orang mati. Benarlah apa yang di katakan si juling Sartre ketika
mengatakan lebih baik kita difitnah dari pada di bunuh!
168
Tok! tok! toroktok! Riang mengetuk pintu. Kalaulah ia tepati janji datang kemarin,
sore, mungkin Riang bakal mengetuk pintu dengan nada yang lebih ceria, lebih berbobot dan
menyeni. Seni yang akan mengiingatkan orang-orang pada rampak beduk yang di takol
bertalu-talu ketika ramadhan hampir hilang di penghujung bulan. Bunyi ketukannya tok!
torok tok dug! toroktok duk! tak dug tak dug!
Tak ada jawaban dari dalam, tetapi lamat-lamat mereka mendengar suara telapak kaki
mendatangi. Suaranya semakin jelas. Pintu berbunyi. Lingga kunci beradu dengan yoni
bolongan pintu. Pintu terbuka. Seorang lelaki berdiri di baliknya. Riang mengenalnya. Pria
itu melawan kantuk. Bentar tak memaki. Ia hanya berkata, “masuk.” sederhana sekali.
Kedua orang itu masuk ke dalam ruang tamu pondokan, lantas Bentar menuju ke
kamar, mengambil dua buah bantal dan menyerahkan pada Riang dan Taryan. Di saat itulah
sikut tajam Taryan memberi kode menusuk pinggang Riang.
”Bilang padanya ...” Taryan mengancam.
Bentar keriutkan dahi.
”Ikut ke kamar mandi mas?” Jawab Riang.
”Apa?”
”Mau ikut kebelakang. Kebelet!”
Bentar lihat Taryan. Ia berusaha menahan sesuatu. ”Beol! Ee?!”
Riang mengangguk mewakili Taryan.
“Disini nggak ada kamar mandi. Kamu kebelakang saja.”
Riang lihat senyum kecil Bentar,Taryan tidak.
Bentar kembali ke kamar lalu membawa dua buah sentar. Ia memberikan senter yang
satunya pada Taryan.
Pintu dibuka. Taryan mengikuti. Riang rebah di sofa. Ia beradaptasi dengan ruang
gelap. Ia melihat gundukan yang tak bisa dipastikan. Riang berpikir untuk menjelaskan
penyebab ia dan Taryan datang ke tempatnya, tetapi setelah mengantar Taryan, Riang
melihat kantuk Bentar tak tersisa. Ia terlihat menahan tawa. Pagi ini, lelaki itu terlihat tak
membutuhkan penjelasan. Konsentrasinya seakan pecah. Ia lebih memfokuskan diri dalam
usahanya menahan tawa. Klimaks pun datang sewaktu Bentar melihat Taryan balik ke dalam
pondokan. Tawa Bentar tiba-tiba memberondong, meledak-ledak, menghambur dan terasa
separti tambur yang di pukul. Tawanya seperti bola bekel, memantul ke mana-mana.
Bentar berusaha menahan diri tapi siapa yang bisa menahan tawa jika rasa geli sudah
menjalar di otak bagian kanan? Bentar tak bisa. Ia kesulitan menyudahinya apalagi ketika
memperhatikan tubuh lelaki dihadapannya basah. Bentar kembali ke dalam kamar ketika ia
169
merasa tawanya berlebihan. Di dalam kamar lantas terdengar suara wanita, yang juga ikut-
ikutan tertawa. Suara tawa dan tangis silih berganti, bersahut-sahutan, saling timpal
menimpal seperti acapela.
Sepi tiba-tiba ... dan tawa itu datang kembali. Lalu berhenti dan berkobar-kobar lagi,
bergelombang lagi meninggi seperti tsunami menghantam jejeran pohon kelapa yang menjadi
di gerogoti kelomang, kumang. Tawa itu terus menerus, hampir nonstop, sampai Riang dan
Taryan hampir tak bisa tidur karenanya.
SUBUH DATANG. Dari jendela besar terlihat beberapa orang melewati pondokan.
Jendela besar itu seolah sengaja di persembahkan pemilik pondokan untuk pejalan kaki
mematut-matut diri bergaya. "Hm, saya sudah ganteng belum ya? Hm ... pantat saya kok
tetap tepos padahal saya sudah latihan mejen selama sebulan." Atau, "nah loh rambut gue
makin polem ajah. Keren akh!" Apa itu polem? Polem itu poni lempar!
Riang bangun saat gundukan berisi tiga orang anak lelaki bergerak. Seorang wanita
mendatangi tempat Riang, membawakannya teh dan surabi. Riang segera mengusik
temannya. Taryan terbangun dari tidurnya, tergeragap, mengetahui seorang wanita duduk
didekatnya dengan megah. Ia memperbaiki sikapnya. Trayan, –sewajarnya lelaki— setiap
saat selalu ingin terlihat elegan di hadapan wanita. Sayang disayang, “prepeeeeeeeeeeet!
Brewek! Dut!. Dut!. Berewek!” Knalpot Taryan mengacaukan performanya. Kepalang
kehilang muka, Taryan berdiri hampir berlari. Tak berbasa-basi ia berlari menuju pintu,
seakan larinya itu merupakan lari penghabisan.
Wanita itu melarang, “Buang airnya di dalam saja!”
Taryan dan Riang kebingungan. Seperti ada piloxan tanda tanya di jidat mereka.
”Di sana!” wanita itu menunjuk, ”kamar mandi ada di dalam!”
Sementara Taryan menghilang, Riang bertanya, keheranan. “Di rumah ini ada kamar
mandi?”
Wanita itu tak langsung menjawab. “Kang Bentar,” katanya, ”begitu pekerjaannya.
Jahilnya tak pernah hilang. Hampir setiap orang yang pertama kali datang ke pondokan
mendapat perlakuan yang sama. Setiap orang di sini tahu penyakitnya.”
Riang bingung atas sikap Bentar, namun ia bersyukur sebab meski ia pertama kali
datang, Taryan justru –secara tak sengaja—membantu menyelamatkan mukanya. Terima
kasih kawan. Ia bersyukur, karena menemukan anggapan lama, yang mengatakan bahwa
tawa merupakan tanda jika tuan rumah senang dengan tamunya. Demikianlah.
170
Wanita yang kini berbicara dengan Riang tampak cantik, namun menurutnya, wanita
yang ada di dokter Nurlaila jauh lebih cantik, bahkan Taryan bukan saja mengatakan,
”ceuwantik!” --sebuah kekhasan Jawa ketika menambahkan kekaguman atau kelebihan
sesuatu-- lebih dari itu, ia merasa perlu menambahkan huruf Qaf. ”Pakai qalqalah Qubro!”
katanya. “Qo, Qo, Qo!” Tenggorokannya cekok-cekok. “Bukan kaf!. Bukan qalqolah sugro
tapi Qubro!" "Kiamat Sugra itu kecil!, tetapi kiamat Qubra itu kiamat yang besar! Cantik
betul itu bukan cantik tapi: CantiQ! Pake Qo! CantiQ! CantiQ!”
Riang tak mengerti, tapi, terserah dialah! Lantas, mengapa Riang masih berpikir
tentang wanita yang ada di Dr. Nurlaila? Ia tak memahaminya. Melihat Eva, wanita yang ada
di depannya, bayangan wanita yang pernah ditemui di Dr. Nurlaila tiba-tiba melintas.
Taryan kembali dari kamar mandi. Ada endemik ganja di pondokan ini. Anak-anak
yang baru bangun ikut tertawa. Ada yang edarkan jamur tahi sapi di ruangan ini. Eva
memperlihatkan gusinya, Bentar tergelak sampai lehernya hampir keseleo, sementara
sebatang bulu di hidung Riang, putus, tak sanggup menahan gempa tektonik diseluruh
anggota tubuhnya.
Taryan memohon belas kasihan. Perutnya membutuhkan perhatian lebih dari sekedar
tawa. Ia pun tak bisa marah. Masih untung di jahili buang air di kali, bagaimana jika disuruh
menggali tanah.
Tawa pun bubar ketika masing-masing orang memisahkan diri agar tak tertular
Bentar keluar dari kamarnya setelah berhasil mengendalikan diri. Ia melihat Taryan yang
tengah menyeruput teh dan menyobek surabi pemberian Eva di meja. Untuk sementara
Bentar tidak mau melihat wajah Taryan. Ia mengalihkannya pada anak-anak.
“Nggak mandi dulu?” Tanya Bentar.
“Tanggung.” seorang anak mewakili jawaban teman yang lainnya.
” Ayo! Biar seger, cuci muka!”
Anak-anak menuruti perkataan Bentar. Mereka masuk ke dalam kamar mandi. Bentar
memandang jauh ke luar halaman. Menghirup oksigen perlahan. Setelah merasa yakin
mampu mengendalikan dirinya, Bentar duduk di ruang tengah, mengajak Riang dan Taryan
berbincang.
Anak-anak yang disuruhnya cuci muka, keluar dari pintu belakang, lalu berkaca pada
sebuah jendela besar.
”Berangkat dulu Kang!”
Bentar keluar, mewanti-wanti.
“Nggak saya mah, tapi kalo si Agus, nggak tau Kang!” Seorang anak membela diri.
171
Agus meninju temannya,
“Teu Kang! Nteu dedeuieun deui. Tidak Kang, tidak lagi."
Bentar tersenyum. “Kalau kalian ngelem yang rugi bukan akan, tapi kalian!”
"Dunia akherat nya Kang?!" Agus nyeletuk.
Bentar tertawa. Ketiga anak berjalan, saling tendang. Agus ditendang teman yang
menuduhnya. Yang menuduh tendang yang satunya. Mereka pergi.
Riang dan Taryan pernah mengalami hal itu. Mereka mengetahui bagaimana berada
di jalanan saat melihat kekasaran orang dewasa mempengaruhi anak-anak kecil seusia
mereka.
Riang terkejut. Ia membiarkan bentar berbicara.
"Tak ada yang tanggung jawab. Anak-anak itu masih terlalu kecil!”
"Tanggung jawab orang tua?" Tanya Taryan.
"Pemerintah, orangtua, keluarga mereka."
“Pernah dengar pepatah singa tidak mungkin terkam anaknya, apalagi manusia?”
tanya Bentar.
Riang dan Taryan menyimak.
”Kadang di dunia nyata ini, pepatah tak berlaku. Anak-anak itu lari dari orang tuanya.
Mereka takut pulang. Takut dipukuli tanpa sebab.” Bentar memegang kuping cangkir tehnya.
”Kamu suka ngelem? Mau ceritakan tentang dirimu Yang?”
Riang terkejut. Tidak! Bukan karena perkataan Bentar, melainkan karena lelaki yang
ada di hadapannya masih mengingat namanya. Riang tidak tahu, Bentar mengetahui dirinya
lebih dalam dari yang ia sangka.
"Yang?" Bentar membangunkan Riang.
Untuk apa Riang menceritakan dirinya? Atas kepentingan apa? Riang malas cerita
namun ia butuh pertolongan Bentar. Jika ada yang ingin di dapat maka ada yang harus
dilepaskan, maka dirangkumlah cerita mengenai hal-hal yang tak perlu disembunyikan. Tak
lupa Riang mengenalkan Taryan untuk melanjutkan cerita. Selesai bercerita, terbukalah
penerimaan yang memang Riang dan Taryan harapkan.
“Kalian bisa tinggal di pondokkan,” sahut Bentar. "Tak perlu bayar iuran! Aku hanya
ingin kalian baik-baik di sini."
Itu artinya Riang dan Taryan dilarang macam-macam.
"Kalau Kalian buat satu kali macam saja, aku bisa maafkan. Kalau diulangi, kalian
harus tahu diri. Faham konsekuensinya.” Bentar mencari jeda, ” ... sampai saat ini aku tidak
pernah mengusir satu orang pun dari pondokan... jadi kalian harus paham konsekuensinya.”
172
”Berbuat macam-macam itu apa?” tanya Riang.
Bentar tertawa, karena lupa menjelaskan.
Syarat ’jangan macam-macam’ itu bukan sesuatu yang memberatkan. Bentar hanya
mensyaratkan: mereka tidak mabuk dan membuat onar di dalam pondokan. Persyaratan itu
ingatkan Riang pada Bos Besar alias Big Bos, dan inti dari semua syarat yang dikemukakan
Bentar, sebenarnya –bagi Riang dan Taryan—merupakan syarat tanpa syarat, bagaimana
tidak, selama ini kedua orang itu tidak pernah menghabiskan umurnya dengan melakukan
kegiatan ’macam-macam’. Kalau pun pernah, itu pun berarti jarang. Tak ada yang berat.
Persyaratan yang bentar kemukakan mereka anggap seringan kapas guling dan bantal.
Sejak saat itulah, sejak diperbolehkannya mereka menetap, hidup mereka terasa
berjalan singkat, karena sebenarnya, pondokan hanyalah sebuah jembatan. Jembatan yang
meriah.
173
JEMBATAN INI
Berada di sebuah tempat, tanpa memiliki penghasilan, tanpa miliki sesuatu untuk
dibarter atau ditukar adalah sifat parasit yang berusaha Riang jauhi. Ia tidak berdiam diri.
Riang tidak mau jadi manusia yang kerjanya hanya makan, buang air, main dan melamun. Ia
punya harga diri tinggi. Teramat tinggi, tak tersentuh.
Selama menjalani hidupnya di pondokan bersama Taryan, ia membantu apa yang bisa
dibantu: memapas rumput, mengikuti piket membersihkan lantai, membenahi atap yang
bocor, membantu Eva beli sayur atau belanja untuk pondokan. Di samping itu, tentu, Riang
belajar mengamen yang benar, mengamen tidak asal mengeluarkan bunyi sembarang.
”Keluarkan dari mulutmu, lidahmu, pita suaramu!” Bentar menuntun. ”Jika suaramu
tidak bagus, tidak sama dengan kunci dan nada, yaknilah, sumber suaramu itu bukan berasal
dari mulut tapi dari tembolok! Kau harus bedakan suaramu dengan suara ayam!” ketus
Bentar pada Riang.
Di belakang pondokan terdapat sanggar yang dihubungkan jembatan bambu --yang
pernah Taryan jadikan pijakan buang air besar--, di sanalah Riang belajar padukan nada dan
suara bersama macam orang yang kadang pergi laksana kelabang, kadang kembali, kadang
menetap sekian lama lalu hilang begitu saja. Di sanalah Riang ditempa. Di sebuah sanggar
yang mirip tempat penampungan. Sebuah sanggar yang cukup luas untuk dijadikan tempat
bagi anak anak untuk koprol dan berguling, atau jika perlu, bisa dijadikan tempat senam bagi
ibu-ibu PKK.
Sanggar itu di kelilingi tempat duduk sederhana terbuat dari batang kelapa. Setiap
malam minggu orang-orang berbondong menyaksikan pentas seni dan pembacaan puisi.
Menyaksikan orang-orang multi talenta membawa ’paku’, memaku penduduk, memaku
pengunjung hingga membuat mereka terpaku di batang-batang kelapa. Yang tidak kebagian
tempat merelakan dirinya bersila seperti anak kecil yang keranjingan mendapat kisah dan
musik yang menakjubkan.
Di sini Riang berkenalan dengan musisi jalanan yang keahliannya membuat Riang
174
tercengang. Musisi yang kemahirannya melolong dan uikkan gitar, meggempur perkusi dan
menggesek biola membuat Riang iri, menjadikannya merasa tercampak bukan karena sakit
campak. Tidak. Biar orang desa, orang tuanya Riang mengetahui manfaat imuniasi. Ia merasa
tercampak karena skill nya yang tak ada setai kuku dari keahlian mereka.
Riang sukai benar alat musik yang disebutkan terakhir. Biola. Alat mungil yang
gesekannya membuat perasaan Riang memuncak. Suara yang keluar seakan menjelma
menghubungkan antar waktu. Gesekannya menjadi knop pembuka sebuah tempat yang jauh-
jauh hari Riang tinggalkan. Lengkingannya menggambarkan erangan keluarga besar Riang
saat terpanggang disapu awan panas Merapi. Gesekan biola dewa itu tak hanya membawa
Riang pada kesedihan. Gesekan yang syahdu membuatnya dialiri kesegaran dan ketenangan.
Seandainya energi yang dikeluarkan biola adalah makanan nyata yang terbuat dari materi
yang sama seperti masakan ibunya, lidah Riang tentu akan menjulur, menangkapi ’makanan’
seperti lidah cecak saat menangkap lalat hijau. Hap hap hap! Demikianlah. Iri positif
kembangkan keinginan dan keahlian Riang. Iri positif mendorong Riang untuk menguasai
alat musik yang menjadi alat utama sumber penghasilannya.
Riang tak hanya selalu mengikuti Bentar mengamen dengan suara seadanya. Riang
tak mau sampai di situ. Ia ingin terus berubah, ia hampir mati dan sekarat berusaha hingga
orang-orang mampu menikmati lagu yang ia bawakan. Itulah mengapa, kemampuannya yang
berkembang dari hari ke hari membuat uang dikantung Riang semakin banyak, hingga
sebagian uangnya dirasa cukup untuk ia belikan gitar yang Bentar tawarkan. Riang mencicil
hingga gitar itu jadi miliknya.
Lain dengan Riang, lain pula dengan Taryan. Karena tidak memiliki kemampuan
dasar di bidang seni, Bentar berpikir keras untuk mencari jalan pada saat Taryan mengeluhka
mata pencahariannya (mengemis). Melalui kenalannya, Bentar mendapat pemecahan. Taryan
diberi kesempatan berkerja sebagai pembersih water closed sebuah perguruan tinggi.
”Aku ndak punya KTP!” Sahut Taryan mengaku.
”Yan,” Bentar bersikap kebapakan, ”kalau keinginanmu bersumber dari keinginan
memuliakan diri, biar diriku yang kau jadikan jaminan! Tidak perlu KTP-KTP an!” Tanpa
hitam di atas putih, tanpa lem dan materai, hanya bermodal kepercayaan yang andalannya
adalah kejujuran, Taryan pun berkerjalah.
Penerimaan itu membuat Taryan bangga. Ia berteriak bahagia saat hari pertamanya
tiba. Bagai mesin yang sudah lama tidak dinyalakan, ia begitu bersemangat. Taryan meminta
Riang mencukur rambutnya yang tak pernah dicukur semenjak mangkat dari kampungnya.
Ia terlihat rapi jali. Taryan begitu tinggi berdiri di atas altocumulus, ia demikian gembira
175
hingga terus bersiul-siul di dalam kamar mandi. Di hadapan cermin, rambutnya ia polesi
Brisk. Tubuhnya ia semproti minyak colongan yang biasa Eva gunakan sebagai pewangi
ruangan, dan setelah penampilan serta performanya dirasa tak ada bandingannya, beberapa
butir debu jatuh dari para-para disenggol tokek kecil. Debu itu melayang, masuk menggelitik
hidung Taryan. ”Hua hua huatsyi! Hua hua huatsyi!” Muka Taryan yang merupakan
pencapaian paripurna sekota Bandung hari itu, kembali pengok seperti sedia kala. Mandinya
jadi tak berguna. Ah, bagaimana pun keadaannya, Taryan tetap ceria baik saat pergi atau pun
baliknya. Aha!
Hidup seperti inilah yang membuat waktu terasa berjalan singkat bagi Riang dan
Taryan. Hidup yang singkat adalah hidup yang dipenuhi makna. Hidup penuh makna adalah
kehidupan dimana orang yang menjalaninya tidak merasa bahwa waktu berjalan apa adanya.
Bumi berputar sama cepatnya dengan aktivitas mereka. Benar, waktu tidaklah berubah. Yang
berubah hanyalah pemaknaan manusia terhadap kejadian yang ada di hadapannya. Semakin
manusia bahagia, semakin cepat pula keberlangsungan hidupnya.
Riang dan Taryan merasakan itu karena kebahagiaan merupakan bagian dari hidup
mereka di pondokan. Berada di pondokan seperti berada di sebuah universitas alam, berada
di sebuah institusi non formal yang memberi kebebasan dengan pembatasan yang luas.
Pondokan bukan saja merupakan tempat berteduh. Pondokan adalah tempat dimana pasangan
Eva dan Bentar berbagi dengan sesamanya. Mereka dan sahabat lainnya mengajarkan banyak
orang keahlian merajut, memasak, menghitung, mengaji, memainkan alat musik dan --sedikit
demi sedikit berusaha—memahamkan bahwa ‘bentuk’ dunia bisa diubah andai manusia mau
berusaha.
Di pondokan, mereka yang berkecimpung dan mengkecimpungkan diri di dalamnya,
tidak di fokuskan untuk menghadapi masa depan material, meski secara tidak langsung yang
dipelajari dalam pondokan mendukung usaha kearah sana. Fokus utama pembelajaran di
pondokan itu adalah pembentukan manusia yang mau bertanggung jawab terhadap diri dan
pilihannya. Menjadi manusia yang eksis! Ujar Iqbal dan kalangan philosof of reason lainnya
macam Kierkegard, Tolstoi dan Nietzche. Menjadi manusia ayam jago! ujar Bentar
menambahkan. Menjadi manusia yang memiliki taji untuk berhadapan dengan kerasanya
kehidupan! Untuk memperjuangkan hidup hingga batasan akhirnya!
Inilah pondokan revolusioner tanpa senjata. Inilah pondokan pendobrak. Pondokan
yang diisi oleh kolektivisme yang memuja penuh pada semangat persamaan, egalitarian. Di
sinilah guru dalam artian formal dinihilkan. Guru yang berkecap-kecap di depan kelas yang
menjadikan muridnya adukan semen di perabukan. Guru yang menuntut penghambaan
176
muridnya untuk patuh, dihadiahi kentut di pondokan ini. Mereka diajarkan untuk berdiri satu
derajat.
“Tak ada hierarki yang batasi manusia! Aku hanyalah pencari mutiara. Pencari
mutiara yang tersemat di dalam dalam hati, di dalam akal budi, dan itu ada di setiap diri
manusia yang kutemui. Termasuk di dalam diri kalian semua!” ujar Bentar saat seseorang
sematkan pujian.
Seseorang acungkan tangan ”Hierarki itu apa?”
”Hierarki itu tingkatan ...”
Dan beberapa orang mendapat perbendaharaan kata-kata baru.
”Ya .. ketiadaan hierarki, ketiadaan tingkatan di pondokan ini, di tempat kita duduk
bersama ini akan membentuk kita untuk percaya terhadap diri. Hierarki dalam pengajaran
akan timbulkan hamba, timbulkan ketidak beranian bertanggung jawab!”
Mata Bentar berkeliling, ”Mungkin, kita memang berbeda dari segi pemahaman.
Berbeda adalah wajar, asal perbedaan itu tidak mensahkan manusia untuk membuat
tingkatan! Bagiku guru adalah kita semua! Guru adalah kehidupan sehari-hari, adalah
pengalaman mengenai keberadaan kita di tengah semesta!”
Banyak yang mengerti, banyak pula yang tidak mengerti perkataan Bentar. Kalau
sudah begitu kesabaran untuk menjelaskan pun dipraktikkan.
”Kehidupan sehari-hari, pengalaman yang ada di dalamnya adalah guru! Semua hal
adalah guru, tak peduli bernyawa atau tidak! Tidak dipertimbangkan apakah yang
menyampaikannya masih kecil atau sudah berkepala tiga, atau bahkan medusa,” Bentar
melirik. Eva tertawa, menyadari penggunaan medusa akan membuat orang-orang tambah tak
mengerti.
Bentar tak usai di situ, ia memulai start untuk mempraktikkan, dan membuktikan
bahwa semua hal adalah guru.
”Anak yang ada di sampingmu itu guru kita...” Bentar melirik ke arah Taryan.
”Anak kecil itu!?! Anak sekecil itu!?” Taryan menunjuk Agus yang mulai berlagak,
berdiri dan membusungkan dada. Tingkah laku Agus membuat orang di sekitar tertawa.
Taryan seperti tak mau percaya.
”Anak yang menurutmu kecil itu guru kita!”
Orang-orang yang sudah lama tinggal di pondokkan, memahami apa yang akan
terjadi. Mereka tersenyum. Mereka melakukan konspirasi. "Bogem dia Gus!” Bentar
meninju tangannya sendiri.
Agus menerima bendera perang yang diserahkan padanya. Agus menjentikkan
177
matanya. ”Kang Taryan!” Agus mulai genit, ”kang Taryan!”
Orang yang dipanggil membentak. ”Apa!?”
”Kang Taryan, katanya, kata kang Riang, kang Taryan kaya?”
Taryan melirik ke arah Riang. Riang tidak mengaku! Ia menggelengkan kepala
seakan mengatakan ’apa untungnya aku bilang ke Agus kalau Situ kaya!?"
Taryan alihkan pandangan. Ia terbayang Ahmad dan Radia. Ia terbayang puluhan
ekor kambing, lahan pertanian yang makmur, pondasi rumah yang terbuat dari beton. Ia
melayang pada ingatan kala ia gemar membeli tiket bioskop menggunakan sepeda motor
yang kecepatannya kalahkan kuda paling gagah di Magelang untuk boyong Radia dan
Ahmad menonton film-film Onky Alexander atau Kevin Kostner, Van Dame, dan Michael
Dudikov. Taryan terbayang. Sebelum kenangan itu hambai dirinya, sayup-sayup ia
mendengar Agus mengulang,
”Kang Taryan, kang Taryan kaya!”
Semua yang ada di pondokan diam menanti respon.
”Tau dari mana aku kaya?!” Taryan melecehkan.
”Tau! Agus tahu kalau kang Taryan kaya!”
”Apa buktinya kalau aku kaya?” Taryan mulai terkena racun yang membuat
kepalanya besar. Ia mulai kegeeran. ”Memangnya Agus pernah ke Magelang?”
Agus memberi jeda...
”Agus tidak pernah ke rumah Akang, tapi Agus tau kalau Akang kaya! Akang kaya ...
karna Akang punya mata untuk lihat matahari. Akang kaya ... karna Akang punya kuping
untuk dengar suara burung setiap pagi! Akang punya kaki untuk berjalan, punya tangan
untuk bekerja ... Akang kaya! Beneran ... Akang kaya!”
Mendengar perkataan itu Taryan diam. Ia ambruk di hadapan Agus. Agus menjewer
kupingnya. O’, tidak, tidak! Agus juga menjewer kuping temannya yang tak habis pikir,
duduk melongo. Dia menjewer kuping Riang. Taryan lekas memeluk Agus. Saat anak itu
berteriak. ”Kang ... eungaaaaaaaap! Kang sesak nafas!” Pelukan Taryan melonggar.
Drama itu merogoh hati dan pikiran Riang.
”Siapa yang ajari?!”
Bentar tersenyum. ”Tidak ada!” sahutnya. ”Sejak datang kesini ia sudah punya
konsep kekayaan seperti itu!”
”Inikah yang dimaksud semua orang adalah guru?!” tanya Riang.
”Bukan hanya semua orang!" Bentar meluruskan. ”Semua hal, semua bisa dijadikan
sarana belajar! Belajar setiap hari! Belajar setiap saat!”
178
”Tidak capai belajar terus?! Apa tidak sulit?!”
”Ya sulit, ya cape!"
"Lantas bagaimana?"
Untuk pertahankan kesadaran memang sulit! Aku sendiri kadang lupa, hingga aku
tidak mendapatkan pembelajaran setiap hari, tapi setidaknya aku berusaha, setidaknya aku
terus mencari intisari hidup yang aku jalani.”
”Intisari nekad!” Agus berteriak.
”Husy!” Eva menggebahnya. Teman-teman Agus menjitakinya. Semua orang yang
berkumpul di pondokan tertawa.
”Semua orang yang melakukan pembelajaran itu sama,” lanjut Bentar, ”Ya,
semuanya sama,
sama,
sama,” kata itu diulang karena penting.
“Karenanya... karena manusia sama, maka tidak patut kita merendahkan diri dan
rendahkan orang lain! Kita harus belajar sederajat …belajar berdiri di antara manusia dengan
perasaan sama dan berbangga sebagai manusia yang setara!”
Itulah periode kebangkitan. Kata-kata itu, ucapan itu menimbulkan efek yang luar
biasa. Inilah lingkungan terbaik. Lingkungan yang ajarkan Riang untuk kembali lakukan
pencarian. Bukan! Bukan pencarian terhadap Kardi dan Sekarmadji, melainkan pencarian
terhadap diri sendiri. Pencarian terhadap kemanusiaan. Pencarian terhadap kekhasan dan
keunikan karakter diri manusia, dirinya! Pencarian terhadap tujuan hidupnya! Tak heran,
keberadaan Riang di pondokan ingatkan dia akan pertanyaan yang dulu senantiasa
mengganggunya. Riang benar-benar ingin mengetahui, mengapa tiba-tiba ia berada di dunia?
Pertanyaan itu datang mengorek kesadaran Riang.
Akan kemana aku setelah mati?....
Mau apa aku ini?
Riang kembali didatangi kegelisahan.
Batinnya terus meringsek pemikiran.
Adakah di balik perjalanan ini, aku menemukan akhir?
Apakah kehidupan ini seperti halnya pemberentian akhir bus DAMRI?
Seperti apakah pemberhentian akhir?
Apakah pangkalan akhir adalah kematian,
lalu apa yang akan terjadi?
179
Diri ini hilang begitu saja?
Sesederhana itukah hidup?
Ataukah setelah mati aku akan berjalan di padang abadi?
Meyakini keberadaan Jannah, seperti yang orang Islam yakini?
Nirwana?
Surga bagi orang Kristen?
Mau dibawa kemana hidupku ini?
Adakah Neraka?
Adakah Surga?
Adakah hari pembalasan?
Riang ingin mencari sebuah kunci. Ia tidak ingin dirasuki kegelisahan terus.
Keimanan yang pernah ia dapat terguncang-guncang! Keimanannya bagai kumpulan kartu
remi yang dijajarkan, menunggu runtuh hanya dengan satu tiupan!
Riang tak beriman.
Tidak! Ia masih beriman.
Beriman, bahwa dirinya tak beriman.
Riang kembali didatangi kekalutan. Tubuhnya mengigil, memikirkan pertanyaan yang
mulai mecereweti lagi hidupnya.
O’ berat. O’ beban. O’ sesal.
Andai ia bisa memilih, ia lebih memilih, seperti yang dibisikkan seorang filsuf
Delphi, Riang sungguh memilih untuk tidak dilahiran. Ia tidak ingin dibebani. Ia memilih
untuk ditiadakan semenjak awal. Selagi muasal. Namun, berandai-andai dan menyesal
sungguh tak miliki guna, karena Riang sudah berada di dunia. Sesal bukan jawaban baginya.
Penyesalan adalah kepengecutan yang tak bersandar pada relita bahwa: "AKU TELAH
ADA!" Jawaban bagi kegelisahan adalah pencarian! Usaha Riang untuk temukan jawaban:
“mengapa aku ada?” merupakan keberanian yang tidak disadari banyak orang!
180
SUP NOT BOMB
Kesibukan tak bisa dijadikan alasan bagi manusia untuk mengesampingkan
pertanyaan-pertanyaan terkait eksistensi diri Riang. Kesibukan adalah perbuatan pragmatis
yang mutlak dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan jasadinya. Tetapi pertanyaan
mengenai eksistensi, mengenai darimana aku berasal, akan kemana setelah aku mati dan mau
di bawa kemana hidup ini aku bawa, harus senantiasa dicari, harus senantiasa ditemukan.
Jika dengan alasan sibuk, manusia menyiakan 18, 25 atau bahkan 80 tahun usianya tanpa
menyempatkan diri merenung, mencari jawaban atas teka-teki yang mau tak mau harus
dijawab rasanya manusia itu gila. Dan Riang memilih untuk tidak menjadi gila. Bahkan
sebelum organ reproduksinya matang, Riang sudah memulai perjalanan dirinya ke dalam. Ia
menelusuri jiwa dan pikirannya. Ia jatuh bangun dalam melakukan penelusuran ini. Jatuh
oleh kebingungan, terbangun oleh kegelisahan. Terus menerus seperti itu. Jatuh oleh
kebingungan, bangun kembali untuk melakukan pencarian. Kedua sahabat yang pernah ia
temani di Merbabu: Pepei dan Fidel lah yang membangunkan dirinya setelah lama terjatuh,
hampir tak bangun. Kedatangan mereka menjadikan keran pertanyaan yang ada di kepalanya
mulai menetes kembali, kemudian menderas, memancar-mancar, lalu kehidupan berjalan dan
pertanyaan itu di sumbat kesibukan di jalanan saat ia dan Taryan mengambil peran setengah
gembel.
Kesibukan pertahankan diri, hanya pertahankan diri, hampir menyumbat
perenungannya. Namun kini di pondokan, waktu luang dan minimnya kekhawatiran akan
nafkah kehidupan membuat Riang kembali pikirkan eksistensi mengapa adanya. Hal ini tidak
sungguh-sungguh berlangsung sewaktu ia masih berada di jalan. Meski pikiran, meski
pertanyaan itu sempat melintas, namun dengan mudahnya pertanyaan itu ditindas. Kebutuhan
akan makan, pekerjaan, jaminan akan hidup keesokan harinya adalah bos yang
memerintahkan Riang untuk meminggirkan pertanyaan yang ada di alam pikirannya.
Berada di Pondokan menjadikan semuanya berbeda. Suplai makanan terus mengalir.
”Dari mana asalnya?” Di beri marsupilami? Tidak mungkin. Marsupilami hanya memberi
makan anaknya. Marsupilami tidak bisa memberi makan manusia. Manusialah yang bisa
memberi makan marsupilami. Bolak balik memikirkan marsupilami tentu tidak menjawab
pertanyaan dan Sup Not Bombs (SNB) yang mengawali jawabannya.
Promotor SNB lah yang mengalirkan kebutuhan pokok, di samping –memang--,
pengurus pondokan memiliki kantung cadangan untuk menghidupi orang-orang yang
181
kebetulan tinggal di sana. Pagi itu, Riang dan Taryan melihat langsung bagaimana SNB
dilaksanakan.
Suara motor trail terdengar dari kejauhan. Seiring berhentinya dua buah mesin motor
di depan pondokan, kukuruyuk ayam menelusup hingga ke sanggar. Dua orang lelaki yang
seminggu lalu Riang saksikan perseteruannya, mengangkat ayam-ayam yang terikat. Satu
karung wortel, kentang, kol, berapa ikat seledri, serta daun bawang dijatuhkan dari pangkuan.
”Bruk!” Suara itu menjadi peresmian kegiatan yang akan dilakukan. Kuali-kuali besar di
keluarkan dari pondokan. Eva mengambil baskom untuk mencuci sayuran. Bentar menguliti
kentang dan wortel. Riang dan Taryan membantunya. Mereka semua bersuka cita atas apa
yang akan mereka kerjakan.
Sup Not Bombs adalah duplikasi dari gerakan internasional yang lebih memilih
menyumbangkan makanan ketimbang perang. Gerakan yang dinamakan Food Not Bombs
(FNB) ini lahir di Cambridge, Massachusetts pada tahun 1980 oleh aktivis anti nuklir. Di
kemudian hari gerakan ini memeriahkan dunia bersama gerakan anti globalisasi yang
setidaknya tercatat di awali oleh gerakan Laskar Pelangi, Green Peace.
FNB merupakan gerakan otonom yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.
Menjadi salah satu jaringan yang manivestonyanya selalu di bacakan ibarat mantra yang
melingkupi sanggar saat kegiatan SNB di adakan.
Food Not Bombs!
Karena makanan adalah hak semua orang,
bukan hak istimewa segelintir orang saja!
Karena ada cukup makanan untuk semua orang d imana-mana!
Karena kekurangan bahan makanan pokok adalah bohong!
Karena disaat kita lapar atau kedinginan,
kita punya hak untuk mendapatkan,
apa yang kita inginkan dengan cara meminta, mengamen, atau menempati
bangunan-bangunan kosong!
Karena kapitalisme menjadikan makanan sebagai sumber keuntungan,
bukan sebagai sumber nutrisi!
Karena makanan tumbuh pada tanaman!
Karena kita butuh lingkungan bukan kendali!
Karena kita butuh rumah bukan penjara!
182
Karena kita butuh makanan bukan bom!
Sepertinya kekanak-kanakkan saat kita terus menerus mendengar manivesto tersebut
dibacakan seolah mulut pesertanya berasal dari alat perekam, namun mereka yang datang ke
sanggar bersungguh-sungguh untuk itu. Lagipula bagaimana bisa mengejek mereka jika
Bentar mengucapkan perkataan seperti ini:
”Sup not Bomb bukanlah kegiatan amal! Bukan sekedar kegiatan yang memberi
makanan tanpa menjelaskan mengapa seseorang tidak bisa makan! Bukan kegiatan amal
yang membuat seseorang tertidur dan kenyang, bukan kegiatan yang rentan dimanfaatkan
Kapitalisme untuk melanggengkan kekuasaannya!”
”Kegiatan kami tidak untuk diikuti orang-orang yang moto hidupnya, kalau lapar
galak tapi kalau kenyang bego! Kami berbeda! Kolektif ini berdiri agar kita semakin keras
berteriak! Makanan yang kita konsumsi harus menjadi suplai energi! Teriakan yang semula
lemah harus menjelma menjadi makian! Dari makian menjelma menjadi kebencian! Menjadi
kemarahan yang akan membakar bangunan besar Kapitalisme! Menghancurkan kontrol
kapitalisme terhadap makanan!”
SNB justru mengesankan sebaliknya. Mengesankan pembangkangan yang dibentuk
oleh individu-individu otonom, yang memahami bahwa hidup harus senantiasa di rayakan
dan semua manusia berhak untuk melakukannya.
ADALAH WALUH, seorang vegan, vegetarian radikal, anggota Food Not Bombs,
yang memberi inspirasi mengenai pendirian dupilikat gerakan internasional tersebut. Lelaki
yang tengah menurunkan sayuran dari motor trailnya itu, membenci jika binatang
diperlakuan semena-mena. Binatang memiliki hak yang sama untuk hidup seperti manusia.
Bagaimana mungkin seorang vegan berkawan dengan Fred, lelaki yang memanggul
beberapa ekor ayam di sampingnya. Lelaki yang dalam kegiatan tersebut memilih tugas
sebagai tukang menyembelih ayam?
Perkawanan bukan tanpa cobaan. Perkawanan mereka diawali perseteruan. Di pantiki
sebuah pertengkaran logika yang mengendurkan sikap keduanya.
“Kalau anak-anak vegan konsisten dengan hak hidup, seharusnya vegan tidak makan
sayur. Kalau binatang memiliki hak hidup yang sama dengan manusia, kenapa sayur tidak
memiliki hak hidup pula. Kenapa Kau memakan kol, membuat wortel menjadi jus, kacang
kedelai kau tenggelamkan di baskom, kemudian kau peras hingga cairan tubuhnya mengalir
hanya untuk dijadikan susu sebagai pengganti susu sapi?” tanya Fred menguji.
183
Waluh tak siap dengan pertanyaan itu. Seperti petualang yang terperangah
menemukan peninggalan purbakala sebuah pemikiran, seperti itulah yang Waluh rasakan.
”Untuk menjamin hak hidup kenapa kita tidak membuat kesepakatan tidak makan
saja?” desak Fred.
”Lantas apa yang manusia makan?" Tanya Waluh. "Bagaimana manusia bisa
bertahan?"
”Kita bukan bicara apa yang manusia makan! Kita bicarakan hak hidup seperti yang
sering kau propagandakan! Jika bicara hak hidup, makan sajalah batu, namun sebelumnya
kau harus berpikir panjang lebih dulu, apakah batu memiliki jiwa atau tidak. Jangan-jangan
batu memilikinya.”
”Jangan berandai-andai!”
”Siapa yang lebih dulu?! Kau sendiri dulu yang berandai-andai bahwa binatang pun
memohon belas kasihan ketika disembelih untuk dijadikan makanan! Kau yang bertanya
bagaimana jadinya jika alien menangkap manusia di gurun Nevada kemudian manusia
mengui-uik sebelum disembelih meminta belas kasihan! Kau bilang Alien tak mengerti
permohonan belas kasih manusia, dan hal itu sama saja dengan rengekan kambing saat akan
disembelih. Sebenarnya binatang mengajak manusia berkomunikasi sebelum disembelih.
Kita hanya tidak mengerti bahasa mereka, bukankah seperti itu yang Kau katakan?”
”Tapi!”
”Kalau berandai-andai tak usahlah makan sayur! Kasihan sayuran!”
Waluh tersentak dengan pembalikan pengandaian dari binatang menuju sayuran. Ia
berusaha melawan ego di dalam dirinya. Ia bimbang dan mulai berpikir tentang apa yang ia
bicarakan pada orang-orang selama ini. Ia mulai berpikir untuk berdamai membiarkan
keyakinan orang namun ia tetap melaksanakan keyakinannya sediri.
Bimbang tertanam, lantas bertunas menjadi aktivitas. Waluh berubah tetapi ia tetap
tidak mau mentolerir kebengisan terhadap binatang. Dia memang tak memiliki devinisi dan
standarisasi kebengisan. Makna kebengisan dalam pemikirannya bukan undang-undang yang
bisa diketatkan aturannya, akan tetapi kebengisan itu bisa ia rasakan ketika tingkah laku Fred
terhadap binatang sudah sangat keterlaluan.
Beberapa waktu setelah ucapan Fred menetralkan agresifitasnya sebagai seorang
vegan, Waluh melihat anak-anak pondokan mengelilingi Fred. Dilihatnya, lelaki itu
mengambil salah satu ayam jantan, lalu menekan dengkul ayam tersebut dan meminta Agus
untuk memegang lehernya. Darah mengalir! Ayam jantan menggelepar, lehernya lunglai. Ia
yang disembelih, Fred lemparkan ke dalam kebun singkong.
184
Agus dan teman-temannya jongkok. Sesuatu yang mengerikan terjadi! Ayam jantan
yang sebelumnya menggelepar berdiri dengan kepala yang hampir putus! Ayam jantan
engambil ancang ancang. Ia yang mati berlari, berkeliling tak tentu arah karena matanya
tidak bisa digunakan. Ayam itu terbang membentur tembok setelah menerobos semak-semak.
Sepuluh menit berlalu! Ayam jantan yang malang tak juga mati! Fred tertawa. Ketiga
anak pondokkan tidak. Mereka ketakutan. Agus tak tahan. Ia menangkap ayam yang malang,
mencengkram badannya dan memasukan ayam itu ke dalam bak sampah yang baru saja di
bakar Eva.
”Kenapa dimasukan ke sana?!” Fred tertawa. ”Manggangnya bukan sekarang, nanti
malam!”
Ayam malang jumpalitan di udara. Ia kehabisan tenaga. Terbakar. ”Kasian Kang!”
Fred berlari menyelamatkan makanannya. Lantas, Waluh bergerak cepat menyaingi
laju kaki Fred. Pukulan mendarat di kening. Kaki Fred terbongkar dari tanah. Ia terjerembab
oleh sebuah pukulan yang mantap.
“Anjing!” Waluh meraung. ”Matikan saja! Tapi jangan Kau permainkan mahluk
bernyawa!" Diambilnya kerah Fred. ”Setan! Ini yang kau ajarkan pada anak pondokan!”
Fred terangkat. Waluh memakukan tatapannya. ”Jangan menyiksa binatang apa pun
di hadapanku!” gertaknya.
”Menyiksa apa?!”
”Kau tahu itu! Kau menyiksa mahluk bernyawa!”
Keributan membuat pemilik pondokan keluar. Bentar melihat ayam jantan
menggelepar dan terbakar sia-sia di dalam bak sampah. Ia melihat ada amarah yang meluap
dan tumpah! Ia melerai.
Fred hanya ingin memperlihatkan pada anak-anak, bahwa menekan dengkul ayam
sebelum menyembelihnya, entah bagaimana akan membuat ayam yang disembelih mampu
bertahan lama sebelum ayam itu mati. Di luar perkiraannya, kejadian itu berubah
menyeramkan saat Agus memasukan si ayam ke dalam bak sampah yang terbakar.
Fred berusaha memahami apa yang dilakukan Waluh, namun ia tetap tak bisa
menerima, bagaimana mungkin darah seekor ayam demikian berharga ketimbang darah yang
meleleh di hidungnya?
Kekesalan Fred hampir menyerupai dendam. Ia me-meti-es-kan kekesalannya untuk
ia buka pada waktu yang tidak tepat. Ia tak sadar jika serangannya di kemudian hari ibarat
membuka kotak pandora, ibarat mengundang taufan Katrina.
Pelampiasan kekesalan Fred pada Waluh terjadi pada saat Waluh tengah memaparkan
185
apa yang ia yakini benar mengenai tindakan kembali ke alam yang meliputi penggunaan
pupuk menggunakan kompos atau kotoran hewan di hadapan petani di sekitar pondokan dan
sanggar.
Saat Waluh mulai bicara mengenai penyelamatan burung, sebagai imbas penggunaan
pupuk alami, pada momentum itulah Fred menyela.
“Bicara menyelamatkan bumi? Bukannya kerjaanmu cuma ngasi makan burung?!
Yang penting itu bukan menyelamatkan burung tapi menyelamatkan manusia. Manusia
adalah pusatnya semesta!”
Fred sebenarnya faham sindiran tajamnya salah alamat, namun emosi yang
ditabungnya sejak perselisihannya dengan Waluh, membuat dia kehilangan kontrol.
Sindirannya merambah pada sesuatu yang seharusnya tak di rambah. Waluh tak
mengomentari, ia membiarkan Bentar untuk menjawabnya. Ia memilih untuk diam.
Usai forum, saat Riang tengah malas-malasan karena kecapaian, taufan itu pun
datang.
“Kalau kau bilang organisasi penyelamatan burung tak ada kerjaan, kalau Kau bilang
mengurusi burung tidak ada manfaatya, kalau Kau anggap kami naif karena Kau tidak
melihat organisasi penyelamatan burung mengurusi gepeng, mematikan koruptor yang buat
negara ini bangkrut, sudah seharusnya Kau berpikir sistematis! Coba berpikir sistemik,
anjing!”
”Setiap orang punya bidang garapannya masing-masing. Semua orang punya peran.
Semua orang seharusnya saling menghargai. Petakanlah masalah, jadilah burung di langit,
terbang melihat keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya!”
”Bergabung dengan organisasi pecinta burung, memberi pakan, menjaga burung—
burung langka, mengembangbiakan untuk dilepas ke hutan tidak sesederhana seperti yang
Kau liat! Berpikirlah sistematis, anjing! Burung habitatnya hutan! Belantara saat ini
digergaji, dijadikan penyokong industri furnitur raksasa. Di tebangi untuk digantikan dengan
rumah peristirahatan, villa, lapangan golf beratus hektar! Membela hak burung sama dengan
menggalang isu untuk membongkar” rayap hutan” dan tikus birokrasi! Bersama isu
perlindungan burung kami menyatakan perang terhadap illegal loging, pembabatan hutan
yang bukan hanya sebabkan burung kehilangan tempat tinggal, tapi manusia pun juga! Suku-
suku pedalaman yang terancam punah! Bersama isu penyelamatan burung terkait
penggalangan suara untuk melawan pemerintah yang tidak ambil pelajaran dan bebal dalam
permasalahan ini! Bersama isu penyelamatan burung, terkait juga isu penangkalan banjir!”
”Kau bisa lihat apa yang terjadi jika hutan dibabat, ruang hijau didesak mall dan
186
pabrik! Banjir dibilang pemerintah karena sampah! Padahal hutan mereka bunuh! Liat
Punclut! Lihat Dago Pakar! Malapetaka semua! Banjir di sukarno Hatta karena tak ada
hutan! Tak ada tempat hidup untuk burung! Malapetaka untuk burung, malapetaka untuk
manusia! Berpikir sistematis, anjing!”
Cobalah hitung makian anjing yang ditujukan Waluh untuk Fred. Kotak pandora itu
telah terbuka. Badai Katrina itu telah datang terbangkan pepohonan, jamban tempat Taryan
buang air di tengah malam, membuat Riang bergidik. Tak ada perlawanan yang dilakukan
oleh Fred. Bersamaan datangnya badai yang mengerikan itu, terbang pula kesombongan di
hati Fred.
Adakalanya kekerasan hati perlu dibenturkan dengan kekerasan bicara yang
mengandung kekayaan argumentasi dan logika. Tidak semua manusia sama. Kekerasan bisa
menjadi obat yang mujarab bagi manusia berbeda. Salah satu manusia itu adalah Fred.
Saat diam dipergilirkan, pikiran Fred bermetamorfosa menjadi ayakan logika.
Perenungan datang. Ia memilah barang berharga miliknya yang dilemparkan badai ke udara.
Ia berlari ke sana kemari, memunguti harta yang pernah dipendamnya: nuraninya.
Orang seperti inilah yang bisa diharapkan berpihak pada kebenaran. Fred bertanggung jawab
atas apa yang diperbuatnya. Ia fair merubah persepsi, dan tindakkannya. Dan tahukah apa
yang terjadi dengan Riang?
Ia mengigil! Ada sesuatu yang mempesonanya. Waktu seolah break dance, jalan
patah dan merangkak di pikirannya. Ada kekaguman yang membuat wajahnya yang semula
tegang menjadi tenang. Ada sesuatu yang Riang pulungi dari keporak-porandaan yang
dilihatnya.
Riang menambah kepekaannya, memperkaya afeksinya, mengubah alam bawah
sadarnya dan mempercepat respon dua untuk melakukan tindakan di sebuah taman yang
dinamakan orang Jurrasic Park. Sore menjadi saksi saat Riang memergoki empat orang
anak SD mengendap-endap, mendekati tempatnya berada. Mereka menunjuk-nunjuk,
memandang ke atas pohon.
Riang mengikuti arah pandang keempat anak itu. Ia melihat seekor burung kuning
kecil bertengger di salah satu dahannya. Ia melihat dua di antara anak SD itu memungut
kerikil. Mereka mengluarkan ketapel. Karet merah melar. Riang segera mengambil pasir
yang ada di dekat jalan. Di lemparkannya pasir itu di antara rimbun dedaunan. Burung kecil
terkejut. Dilentingkannya dahan kecil menjadi alas penerbangan. Burung melesat cepat.
“Yaaaaaaaah!” Anak-anak itu melihat ke arah Riang. Mereka kecewa.
Riang meminta maaf. Ia lantas, berkisah tentang tentang burung-burung kecil di
187
Merbabu. Ia menyederhanakan kata, bagaimana burung-burung akan memiliki guna lebih
bagi alam apabila dibiarkan terbang bebas di angkasa. Dijelaskannya pula keterkaitan dengan
hutan dan bunga, bagaimana dengan bantuan paruh dan kakinya, putik sari tersebar dan
perkawinan antar bunga terjadi. Dengan bantuan burung dunia kita menjadi indah, menjadi
berwarna. ”Burung kecil itu salah satunya,” jelas Riang.
”Yang membuat dunia dipenuhi bunga?” tanya seorang anak.
Riang mengangguk. Si anak yang bertanya mengucapkan terima kasih. Tak berapa
lama berselang ketiga anak lainnya serempak mengucapkan kata yang sama.
”Terima kasih om!”
Aduh! Aduh! Mendengarnya hidung Riang meler-meler. Aduh aduh wajahnya
menjadi merah. Empat anak itu mengerjap-erjap. Kekecewaan mereka punah hanya dalam
sekejap.
PRIIIIT! Suara peluit terdengar. Kini saatnya Riang bertugas. Ia harus memastikan
agar wortel, daging, kentang, dan bahan-bahan lain yang sedang berenang di dalam sup
matang merata. Tak lama Riang berteriak, ”Sup mataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang!”
Sup yang masih mendidih di dalam kuali besar, diangkut ke atas pick up. Kompor
minyak tanah dimasukan bersama dengan tikar, terpal dan meja. Pukul enam lewat beberapa
menit, belasan orang bersuka cita. Mobil bergerak. Dua motor trail milik Fred dan Waluh
berjalan mesra, beriringan.
APLATUN ITU BINATANG APA?
Biar tak punya kaki, langkah SNB untuk yang kesekian kalinya berjalan lancar.
Panci-panci yang pada ujungnya menempel lemak kini melompong. Air panas di dalam
jerigen menjadi dingin dan menggenang. Sayur-sayur yang berceceran, dan remah-remah
nasi dibersihkan. Pick up yang diparkir di belakang monumen menggerung. SNB bulan ini
selesai.
Riang menjinjing kantung plastik transparan sementara Taryan membawa sebungkus
nasi dalam genggaman. Mereka tak membawa kantung hitam untuk menyamarkan pemberian
yang ingin mereka persembahkan pada Aplatun. Mereka berjalan setelah menemukan cukup
alasan.
188
Dari kejauhan warung Aplatun kini tampak terlihat segar. Catnya yang mengelotok
ditimpa cahaya kuning matahari, berpendar menyilaukan. Warung itu tampak sehat dan
segar.
”Ada sesuatu yang berubah...” Kata-kata Riang lebih dimaksudkan bukan secara fisik,
melainkan secara spiritual. Secara spiritual warung Aplatun berubah. Ada sesuatu yang
membuatnya bersinar.
Taryan tak mengerti. Ia hanya mengerti bahwa kenyataannya warung itu memang
telah berubah.
”Ton.... Ton!?” Tanpa basa-basi dan lupa mengucapkan salam, kedua orang itu
berteriak riuh rendah.
Tak ada jawaban, seorang wanita terlihat tergopoh-gopoh berlari dari pinggir jalan.
Wanita itu membenahi rambut yang menyempil dari kerudungnya.
”Aplatun ada?” Riang dan Taryan curiga.
Wanita itu memperhatikan wajah Riang dan Taryan. Ia mengingat ciri-ciri wajah
seperti yang pernah diceritakan. Ia berpikir lambat. Lima detik kemudian jarum ingatan yang
sedari tadi dicari dalam tumpukan jerami pikiran ditemukan. ”Mas Riang?” jempolnya
menunjuk. Lengan bajunya bergeser Pergelangan tangannya terlihat putih, bersih.
Riang dan Taryan belum bisa menerima kenyataan jika di warung Aplatun terdapat
seorang wanita berwajah sopan dan mengembirakan. Mereka kebingungan.
”Bang Aplatun selalu membicarakan kalian,” wanita itu menjelaskan. Air panas
dituang. Keretak gelas tipis terdengar. Bubuk hitam dibubuhkan ke dalamnya. Harum
mendatangi hidung Riang dan Taryan.
”Mas Masnya sudah lama tidak datang ke warung ini?” Wanita itu menuntut. ”Bang
Aplatun selalu menunggu setiap malam. Bang Aplatun selalu bilang, di Bandung cuma kalian
temannya.”
Riang dan Taryan tidak menjawab.
”Maaf ... teteh jangan marah,” ujar Riang.
”Marah untuk apa?”
”Teteh siapanya Aplatun?”
Wanita itu tesenyum. ”Menurut Mas Mas, saya siapanya bang Ap?”.
Riang berharap dia adiknya, tapi mulutnya malah menjawab, ”Jangan-jangan
istrinya?”
Wanita itu tersenyum anggun. Jawaban itu mengambang. Wanita itu masih tampak
bagaikan misteri.
189
”Beberapa minggu yang lalu, bang Ap, muter-muter di terminal, mencari Mas-
Masnya. Ia bertemu pedagang asongan yang bilang kalau kalian sudah tidak di Kebun
Kelapa. Bang Aplatun pikir, Mas Mas nya sudah kembali, ternyata masih di sini. Bang Ap
pasti gembira. Alhamdulillah!”
”Sekarang orang yang akan bergembira ada di mana?” Tanya Riang tertawa.
”Jualan kaus di belakang gedung sate. Pulangnya sehabis Dzuhur. Mas Masnya
tunggu di sini saja.”
Wanita itu menyajikan kopi. Dibenahinya mangkuk dan gelas yang membuat warung
berantakan. Ia meminta izin ke belakang.
Riang dan Taryan mencecap, merasakan kopi itu istimewa, padahal, sesungguhnya
ramuan yang dibuat istri Aplatun tak ada beda. Riang dan Taryan lalu membicarakan hal
yang tak berguna. Agak lama di warung Aplatun membuat dua orang itu merasa bosan.
”Mba?” Riang merogoh uang.
Wanita itu masuk tergopoh-gopoh. Riang dan Taryan melihat sekilas keanehan pada
perutnya. Ada kehidupan di dalam rahim dia. Riang dan Taryan saling menukar pandang.
Taryan tiba-tiba mengucapkan, ”amin!”
”Amin?” istri Aplatun mencari jawaban.
Taryan yang reflek mengatakan mengucap amin, mengelak. ”Ya amin!” jawabnya tak
nyambung. Lalu mereka pun berpamitan dan menitipkan pesan. Aplatun tak usah khawarir,
tempat tinggal Riang dan Taryan, kini jauh baik ketimbang tempat tinggalnya dulu. Mereka
lalu memberikan sup sisa SNB, meletakan uang pembayaran.
Istri Aplatun tidak menolak sup dan nasi yang diberikan, namun ia menolak bayaran
atas apa yang ia ikhlaskan.
Dengan itu tak ada lagi hal unik yang bisa diceritakan tentang Aplatun dan istrinya.
Riang dan Taryan tak ingin mengganggu kehidupan mereka. Riang mengingat bagaimana
Aplatun memberinya golok dan garpu. Ia tak tega melihat kebahagiaan wanita itu sebab
Riang berfirasat yang bukan-bukan. Ia takut jika sewaktu-waktu keberadaan dirinya dan
Taryan akan menyeret Aplatun kembali menuju kehidupan masa lalunya. Riang kasihan pada
keluarga dan bakal anak mereka. Mereka hanya akan datang ke tempat itu, sekali-kali untuk
silaturahmi.
Beberapa meter setelah keluar dari warung, suara muntah terdengar.
”Amin!” Taryan mengusap wajahnya.
”Lho, amin apa?”
“Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.”
190
”Amin sebelumnya apa?”
”Sama.”
Riang tersenyum. Ia membetulkan celana.
”Yan?”
”Ya?”
”Kalau seandainya istri Aplatun pawang binatang, yang dipawanginya binatang apa?”
Karena pola pikir Taryan seperti lensa konvergen, jawabannya tentu yang biasa.
Taryab menjawab macam binatang yang sering diinderanya. Riang lain, ia berpikir jauh,
membanding-bandingkan Aplatun dengan ikan tenggiri, babi rusa, kecebong, hingga ikan
paus. Riang tak menemukan banyak persamaan antara Aplatun dengan binatang-binatang
yang dipikirkannya, hingga akhirnya ia memutuskan jawaban yang paling benar. Baginya,
Aplatun adalah manusia.
Ia dan Taryan pun manusia.
Binatang yang sama.
Mamalia yang radik!
BUKAN ORANG BATAK
Kehidupan berjalan apa adanya. Taryan merasa nyaman. Di kampus tempatnya
bekerja, secara rutin atasan dia menularkan harga diri raja diraja pada manusia siapa pun
juga.
”Asal kau profesional, pekerjaan apa pun tak perlu menjadikanmu seperti dubuk yang
hobi mengangguk-angguk, menunduk-nunduk!”
Di antara anak buahnya ada yang tak mengetahui dubuk itu apa, tetapi si atasan tetap
mengoceh mengenai harga diri yang tak ketulungan.
”Manusia itu sendiri yang tentukan harga dirinya.” Atasan Riang yang nyentrik ini
benar-benar mempraktikkan apa yang ia omongkan. Si Junaedi, yang bertanggung jawab
terhadap kebersihan langit pernah ia pergoki bersikap seperti dubuk.
”Jangan kayak gitu dong,” kata atasan Taryan menggunakan logat Jakarta. ”Kamu itu
kerja! Bukan jadi budak! Tunduk-tunduk di hadapan orang udah nggak zaman. Kalau gitu di
191
keraton atau di depan kiai mu, masih mungkin, tapi kamu di sini berkerja bukan untuk
menjadi budak!
Junaedi diam, atasan melanjutkan. ”Kita nyari makan. Mereka yang kamu tunduk-
tunduki itu nggak pernah kasi kita makan. Jangan malu! Jangan pernah merendahkan diri!
Hargai diri!” katanya. ”Kalau kamu sendiri nggak ngehargain, siapa yang mau ngehargain?!”
Dibangunkannya harga diri si Junaedi hingga bangunan harga dirinya yang reot
berubah menjadi bangunan kepercayaan yang gagah. Kepercayaan diri si pekerja bertambah,
berlipat-lipat. Perlahan-lahan badan teman-teman Taryan tegap jika berhadapan dengan
orang, dan mungkin juga jika mereka harus dihadapkan pada orang keraton atau pun kiai,
karena yang dimaksud ’kiai dan keraton’ oleh atasannya, sebenarnya hanya sekedar pemanis
kata-kata belaka. Situasi kerja seperti ini memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan
mental Taryan.
Situasi yang khas itu memang merupakan sebuah situasi yang tidak tiba-tiba terjadi.
Jaringan pertemanan, solidaritas satu pemikiran membentangkan hubungan yang luas antara
pondokkan dengan sahabat-sahabat di luar. Salah satunya adalah atasan Taryan. Jaringan itu
terajut kuat, menyebar hingga batas-batas yang sukar untuk diperkirakan.
Di luar itu, perkerjaan dan kehidupan Taryan yang mulai ’mapan’ di pondokkan,
akhirnya mendorong dia untuk menyurati Radia. Taryan tak lagi memiliki halangan
psikologis untuk memberitahu kabar dirinya kepada sang istri. Ia bahkan menjelaskan
panjang lebar bagaimana perjalananannya yang merana sebelum sampai di pondokkan.
Surat-surat menyurat dengan kertas cap Harvest atau kertas-kertas warna norak berisi rayuan
gombal di sertai bubuhan cap listik membombardir pondokan.
Bagi Riang surat Radia, mengisyaratkan kepulangan Taryan. Ia berusaha menjauhkan
kekhawatiran itu dari pikirannya. Sejak saat itu ia mulai memupuk kesiapannya, berjuang
untuk melepaskan Taryan jika saatnya tiba.
Semua orang butuh bahagia. Setiap manusia punya alur dan cara hidup yang berbeda.
Riang percaya. Ia berjuang untuk itu, maka untuk melempangkan jalan sahabatnya, sekalipun
Riang tidak pernah mengungkit kembali perihal pembalasan dendam yang pernah
menjadikan Aplatun kalap.
Berbagai kejadian silih berganti mendatangi, seolah tidak memiliki keterkaitan
dengan tujuan awal keberangkatan Riang. Apa yang Riang inginkan belum kesampaian.
Ihwal pembalasan dendam atas kematian Pepei, ihwal kesokheroikannya Riang pun terpaksa
diredam, namun, hal ini tidak untuk selamanya berlangsung, karena sebuah kejadian lain
menyambungkannya kembali di saat libur hari keagamaan datang.
192
SAAT ITU TAK ADA YANG MEMULAI hari dengan cara tak wajar, kecuali
pertanyaan seorang bapak berumur lima puluh tahunan yang diarahkan pada Bentar.
“Aya teu Kang, pernah ada tidak Kang, orang yang pernah kemasukan Allah?”
Mendengar pertanyaan itu semua orang hampir mengeluarkan liur, tertawa.
Bentar tak bisa menjawabnya. Tak ada yang bisa menjawabnya. Pertanyaan itu
mengarungi kekosongan. Si Bapak ikut tertawa. Ia yang bertanya sebenarnya tidak benar-
benar ingin menemukan jawaban. Dia hanya ingin meramaikan. Dia merasa puas jika orang-
orang disekelilingnya tertawa. Di dalam dirinya tidak ada guncangan pemikiran. Tidak ada
yang menggoyahkan keimanan. Pertanyaan itu berlalu begitu saja.
Semula Riang tertarik dengan pertanyaan si Bapak, namun ketertarikannya tersedot
oleh tingkah laku seorang lelaki yang berdiam diri tatkala orang lain tertawa. Lelaki aneh itu
menggunakan topi hijau berlambang perhutani. Topinya dimiringkan, --hingga-- lidah
topinya membuat bayangan hitam yang menyebabkan wajah orang itu tersamarkan.
Sedari awal Riang memperhatikan ia meyudut di pinggiran. Gerak-gerik tubuhnya
mencurigakan. Di kepala Riang menari-nari godaan untuk menuduhnya maling sandal hingga
tukang kutil kutang. Inti dari semua buruk sangka itu, Riang tidak menyukai gerak-gerik
lelaki tersebut. Bagaimana tidak curiga, ketika orang tertawa lelaki itu malah diam. Ketika
orang lain diam, ia malah menambah kadar diamnya. Ketika Waluh mempersilahkan lelaki
itu bicara, ia menunduk, kemudian menyodorkan tangan dan mempersilahkan orang lain
untuk bicara. Kecurigaan Riang bertambah. Setiap Riang menatap matanya, setiap kali pula
lelaki itu menunduk. Mata lelaki itu seolah berlari sprint menjauhi palang papan berbentuk
mata Riang.
Di pertengahan obrolan, Riang melihat orang itu menjalin komunikasi dengan Fred
yang ada di sampingnya. Setiap kali mereka bicara Fred selalu melihat ke arah Riang.
Riang berpikir, mungkin ia kenalan Fred dan Fred seperti berpikir sebaliknya, seperti
halnya dua orang pengantin yang tengah mereka-reka tamu asing yang hadir dalam resepsi
pernikahan mereka.
Riang gelisah. Ia ingin memastikan. Ketika pembicaraan selesai, Riang berusaha
menghampirinya. Aneh! Semakin dekat jarak Riang dengannya, semakin ekstrim lelaki itu
membenamkan wajah menggunakan topi yang ia kenakan. Saat Riang hampir menyentuhnya,
lelaki itu berdiri, lalu mundur beberapa langkah dan berhenti karena tubuhnya membentur
tembok. Lelaki itu segera berbalik arah, berjalan cepat, seolah baru saja bertemu dedemit.
Riang membiarkankannya melangkah hati-hati melewati jembatan. Ia mulai merasa
193
tak nyaman atas perbuatannya.
”Teman?” Fred datang memegang bahu Riang meminta penjelasan.
Mendengar pertanyaan itu, Riang langsung berlari. Ia memanggil. Lelaki itu tak mau
menoleh. Langkahnya dipergegas. Semakin cepat… semakin cepat! Ia berlari kecil. Dari
kejauhan lelaki itu menoleh ke belakang, melihat Riang membuntutinya. Ia menyiapkan
ancang-ancang! Lelaki itu melesat!
“Hei jangan lari… mau kemana?!” Riang mengejar sekuat tenaga sambil berteriak.
Penduduk sekitar sanggar dan beberapa orang yang entah dari mana, menganggap
lelaki itu melakukan kejahatan. Kini ia diuber banyak orang. Waluh ikut berlari. Larinya
cepat. Ia menyusul Riang.
”Berhenti!” Waluh ikut memperingatkan.
Lelaki itu tak mau, ia terus berlari hingga beberapa detik kemudian kausnya berada
dalam cengkraman. Bunyi kaus sobek terdengar dari kejauhan! Lelaki itu terus berusaha
melepaskan diri, terus berusaha berlari, namun kekuatan Waluh menjadikan tenaga dan laju
kakinya tak berarti. Waluh tak melakukan apa pun. Ia tidak memukul atau menendang. Ia
hanya menangkap dan memeluk lelaki itu kuat. Waluh sepenuhnya sadar, tubuh dan
tangannya yang liat adalah penjara bagi siapa pun yang berada di dalamnya. Waluh menjadi
kantung semar dan lelaki itu menjadi lalat.
Gerakan perlawanan menjadi sekedar guncangan yang justru membuat topi terjatuh.
Saat topi lelaki itu lepas, pengalaman pahit tentang diri Riang di rewind. Tanjakan setan,
parang-parang yang berkilauan, berita di radio, pekuburan, ancaman matanya, sahabatnya
yang mati ditusuk berbayang-bayang di benak Riang. Tapi … mengapa lelaki itu merungkut
selemah rumput Mengapa tubuhnya sedemikian kurus. Astaga, matanya nampak cekung,
mukanya tampak ketakutan menawarkan gencatan, memohon perdamaian. Riang sungguh
tak tahu apa yang harus dilakukan hingga orang-orang berdatangan.
Penduduk yang berlari dari sanggar sampai di lokasi kejadian. Beberapa orang
berteriak-teriak menanyakan keberadaan maling, namun setelah mendekat, mereka malah
diam dan menyelinap mundur di balik punggung orang-orang yang datang kemudian.
Beberapa orang balik ke sanggar. Beberapa yang lainnya menyaksikan bagaimana
keberadaan Riang mengintimidasi lelaki yang penduduk ingin gebuki sampai rubuh
berkalang tanah.
Masih berada di kantung semar lelaki itu menyembah Riang. O’ dimana lelaki
brewok yang dulu berkuasa? Dimana kegarangan dirinya? Riang tak sampai hati. Ia mulai
mengasihaninya. Riang melihat siksa yang menjadi deterjen pembilas dosa di matanya.
194
Riang melihat kemurnian lelaki itu. Ia merasakan batin yang meraung-raung dilindas
penyesalan. Ia merasa iba melihat tubuh lelaki itu menyusut/
”Sudah sudah!” bujuk Riang saat melihat lelaki itu mencucurkan air mata.
Tangis lelaki itu tidak juga mau berhenti. Ia malah bersujud. Ia menghamba
sahayakan diri, mengikhlaskan tubuhnya didera hukuman.
“Sudahlah …. Jangan mempermalukan diri mu seperti itu!” Riang mengambil bahu
dan lelaki itu malah menyungkurkan diri, memeluk kakinya.
Melihat peristiwa yang menggoncangkan itu, Waluh beranggapan bahwa lelaki lelaki
yang saat itu telah ia lepaskan, memiliki sangkut paut pribadi dengan Riang. Ia tak mau ikut
campur, padahal, sesungguhnya lelaki itu pernah berurusan dengan dirinya. Waluh tak tahu,
karenanya, ia pun pergi meninggalkan pondokan menggunakan motor trailnya.
Riang membutuhkan ketenangan untuk membicarakan banyak hal dengan lelaki itu.
Ia merasa membutuhkan tempat yang aman dari pendengaran banyak orang. Eva memberi
tempat yang lapang, di sebuah kebun, tepat di belakang podokan. Taryan dibiarkan
mengikutinya. Mereka pun duduk di bangku yang terbuat dari akar tanaman teh.
“Sampeyan bukan orang Batak?” Taryan yang duduk di belakang punggung Riang
tiba-tiba bertanya.
Lelaki itu menunduk. Taryan terus memperhatikan.
“Sampeyan pernah kepruk kepala orang pakai bata?!”
Lelaki itu mengangkat kepala. Ia sering melakukannya, namun di kota ini, yang
pernah melakukan itu hanya temannya.
Taryan meneliti wajah lelaki itu benar-benar. Usai perampasan --dompet yang
sebelumnya Taryan temukan-- terjadi, ia mem-pelat-i wajah orang-orang yang pernah
membuat kepalanya berdarah. Taryan merasa terang. Penglihatannya terasa benderang.
“Sampeyan yang waktu itu ambil uang di dompetku! Sampeyan temannya preman
yang mukul kepalaku! Ayo ngaku!”
Lelaki itu terpojok. “Yang mana?! Preman yang mana?!”
Ada ruang kosong, hanya antara Riang dan Taryan sementara lelaki itu kembali
bergulat di dalam ruangannya sendiri.
“Di kota ini, beberapa bulan lalu, temanmu pernah rampas uang orang! Dan kau ada
di sampingnya.” Riang terinfeksi perkataan Taryan untuk menginterogasinya.
Lelaki itu lemas. Ia mengaku.
Taryan memandangnya. Dilihat tubuh lelaki itu kuyu di-shower-i ketakutan. Lelaki
itu terpecah belah. Ia lunglai tak bisa memaknai keberadaan dirinya. Jiwanya seolah
195
dicerabut paksa oleh tang yang kasat mata. Ia makin merunduk, terus merunduk, melingakar
seperti keong yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Lelaki itu meminta ampun, meminta
maaf, meminta penyucian.
Taryan belum pernah mengalami kejadian semacam ini. Ia tersedak, tak mampu, tak
tahu harus melakukan apa. Ia hanya bisa menggelengkan kepala.
Lelaki itu terus berulang-ulang meminta maaf seakan dirinya didesain seperti sebuah
program yang salah copy. Lelaki itu terus meminta maaf, meminta Riang untuk
memasukannya ke dalam purgatory. Ia tak lagi mampu mengingat dosanya di masa lalu.
Ketakutannya membuat dia histeria, menjadikannya bimbang menyerupakan gila.
“Ampuni! Ampuni! Ampuni aku!” lelaki itu mengerang.
Siapa yang tahan dengan erangan itu. Tidak Riang. Tidak pula Taryan, yang segera
memutuskan untuk melupakan benar, sesuatu yang sesungguhnya memang ingin ia lupakan
dan pernah ia sarankan pada Riang. Taryan tidak ingin menuntut pembalasan, ia malah ingin
menyelamatkan. Dosa lelaki itu harus ditimbun.
“Sudahlah…” sebatas itu yang bisa Taryan ucapkan. Rengkuhan pada bahu lelaki
tersebut mewakili seluruh permufakatan untuk memaafkan.
Riang terharu dengan perbuatan Taryan, namun masih ada satu lagi yang
menahannya. Ia harus membereskan persoalan, ada yang masih harus dituntaskan, di
khatamkan.
“Siapa yang membunuh sahabatku?!” tanya Riang.
Lelaki itu mengangkat lehernya. “Bu… bu… bukan aku Mas! Aku hanya
memberitahu!” Ia takut, semakin takut. “Yang melakukan itu bukan aku! ... Aku … aku
hanya memberitahu. Kardi! … Kardi Mas!” Lelaki itu tergeragap. Lututnya lemas. Ia terisak.
Semakin lama, isakannya makin kentara. Ia menangis.
Riang merasa kelu. Lelaki yang kini bersimpuh di hadapannya adalah lelaki yang
sama, yang dulu dipergokinya memancurkan air seninya di sela-sela pepohonan, sambil
berteriak menanyakan Kardi yang tengah mengincar ayam jantannya, si Percik di Thekelan.
Lelaki yang kini terpekur seperti burung yang disiram air panas di hadapannya itu
adalah lelaki berewokan yang menyergapnya saat turun dari Merbabu bersama Fidel dan
Pepei. Lelaki itu Sekarmadji, seorang yang bertampang seram, kejam, tetapi sungguh hatinya
tidak sekeras intan sejak dirinya memungut tas coklat Pepei yang membuatnya bimbang.
Riang merasa digulati perasaan kelu. Ia mendesahkan nafasnya, seolah-olah hari ini
adalah hari terakhir dia menghirup oksigen di dunia. Kebencian Riang kini tak terbagi.
Dendamnya Riang, kini hanya untuk Kardi.
196
Di sela-sela tangisannya Sekarmadji menggapai-gapai. Suaranya terputus.
“Tas mas, … tas…tas…”
Riang ia teringat akan tas Pepei yang dibawa Kardi sewaktu melarikan diri,
menghindari keroyokan penduduk desa Thekelan.
“Tasnya aku simpan di rumah,” jelas Sekarmadji. “Tak ada sesuatu pun di sana
kecuali dua buah buku dan alat tulis. Di dalamnya hanya terdapat uang lima puluh ribu
rupiah. Sungguh …aku tak mengambil apa pun darinya. Sungguh aku tidak berbohong!”
“Untuk sementara,” Sekarmadji membuka dompet,” ini uangnya teman Mas.”
“Tasnya dan isinya menyusul,” tambahnya.
Riang menolak.
Sekarmadji berkaca-kaca,
“Ada yang lebih penting dari sekedar uang dan tas!”
Sekarmadji tak memberi respon. Ia menunduk.
“Mas jangan menyembunyikan! …. di mana Kardi?!”
Wajah Riang panas. Degup jantungnya berubah mendentum seperti meriam setelah
Sekarmadji memberinya informasi. Riang hampir tak percaya. Kardi tak jauh dengan
pondokkan. Riang muskil untuk percaya, ia masih butuh untuk memastikan. “Di terminal
Dago?!”
Berulang untuk memastikan. Dan berulang-ulang pula Sekarmadji mengatakan ‘ya’.
Pembunuhan yang dilakukan Kardi di stasiun Yogyakarta memaksa mereka
menyembunyikan diri. Toto yang meminta Gendon mengutus Sekarmadji dan Kardi untuk
mencederai Pepei tak mengetahui urusan yang sebelumnya terjadi antara Pepei dan Kardi di
kuburan Thekelan. Ia hanya mengetahui bahwa Kardi dan Sekarmadji bisa menjadi anjing
yang buas terhadap orang lain namun berprilaku ramah terhadap manjikan jika mereka
memeliharanya.
Pembunuhan yang dilakukan Kardi merupakan semacam teskes. Apa yang terjadi
melebihi sesuatu yang ia harapkan. Menyadari itu, setelah kejadian Toto segera meminta
Gendon untuk menghubungi rekannya di Bandung,
“Sebelum sampai di Bandung, Kardi lebih dahulu pergi menuju kediamanku …”
Sekarmadji ragu-ragu mengaku. Ia melihat berkeliling, mencari lelaki yang sebelumnya
membekuk setelah mengulati dirinya. Sekarmadji tidak melihat Waluh di sekitar pondokkan,
namun ia memilih untuk tak melanjutkan. Sekarmadji memilih untuk memutuskan
kalimatnya.
Riang tak menangkap keraguan itu. Fokusnya hanya pada Kardi. Ia tak mau tahu
197
siapa yang disebut Gendon dan Toto oleh Sekarmadji.
“O, mas…” Riang menyaksikan Sekarmadji merintih lagi.
“O Apa yang harus kulakukan untuk menebus dosa ini?!” Sekarmadji menangis.
“Apa yang harus kulakukan?! Aku malu di hadapan Alloh! Aku tak memiliki harga lagi di
hadapan-Nya! Oh, dengan apa aku harus menebus dosaku?! Ya Alloh…”
Riang merasa kasihan, tetapi tangisan dan keluh pertaubatan yang terus berulang itu,
akhirnya membuat Riang risih.
“Mas pulang saja,” bujuk Riang.
Sekarmadji sengguk. Ia tak habis pikir. Apa yang dikatakan Riang keluar dari
prakiraan cuaca pikirannya.
“Tapi … Mas… Oo…”
Riang memotong, sebelum Sekarmadji meneruskan rintihannya.
“Sudahlah… Mas tutupi lembaran lalu! Jalani yang ada di depan, dan Mas haramkan
untuk menengok ke belakang! Mas jangan pernah tenggelam dalam penyesalan! Terus
melaju! Buka lembaran baru!”
“Tapi dosa ini …” Sekarmadji merintih lagi.
Taryan mengehela nafasnya/ “Kalau pun teringat kesalahan, jadikan saja kesalahan
itu sebagai pelajaran, tapi, Mas tetap jangan pernah tenggelam dalam penyesalan! Semua
manusia pasti pernah melakukan dosa! Dan semua manusia diberi waktu untuk memperbaiki
diri! Mas memiliki kesempatan itu…”
”Syarat utamanya dimulai dari satu: mulailah mengampuni diri dan jangan melakukan
perbuatan jahat lagi! Jangan pernah melakukan perbuatan yang pernah Mas timpakan pada
kami ke orang lain!”
Sekarmadji ragu.
Entah bagaimana Riang bisa se-agung itu. Kata-kata Pepei dan Fidel saat Riang
menyesatkan kedua orang itu di Merbabu, membantunya.
“Sebaiknya Mas pulang,” bujuk Riang.
Sekarmadji tak tahu harus berkata apa. Ia berdiri. Menunduk, lalu memeluk pemuda
di hadapannya, rekat. Riang membiarkan pundaknya basah.
Sekarmadji berpamitan. Ia berjalan semakin cepat, semakin cepat. Ia alpa bahwa
tujuannya semula adalah untuk meminta maaf pada orang yang membekuknya sewaktu
melarikan diri dari kejaran Riang. Ia datang untuk mencari Waluh, lelaki yang membuatkan
kandang ayam, membantu menanam sayuran di pekarangan rumah keluarganya. Terkadang
emosi menjadikan seseorang hilang ingatan.
198
Sebelum tubuh Sekarmadji menghilang, ia membalikan badan, mengelap pipi
menggunakan punggung lengannya. “Mas orang baik … terima kasih!”.
Bertepatan dengan teriakan singkat Sekarmadji, Eva keluar membawa segelas susu
yang dikirim Fred untuk pondokkan.
Hilangnya Sekarmadji, tentu membuat wanita itu kecewa.
DUA MINGGU SETELAH MABUK tangisan dan senggukan, buku harian Pepei
sampai di pondokkan. Tas berisi buku catatan perenungan Pepei itulah yang merubah
kehidupan Sekarmadji. Riang tersenyum membacanya. Ia teringat kembali akan kesegaran
udara sewaktu dirinya berhadapan dengan atheis yang santun. Atheis yang sangat baik
padanya --dan Riang yakin, ia baik pula terhadap orang lain.
Riang bersyukur sempat mengenali Pepei, sempat mengenal sesosok lelaki tegar
yang konsisten menjalani keyakinan akan ketidakpercayaan terhadap Tuhan, namun memiliki
kebaikan hati yang berbanding terbalik dengan informasi yang sering disampaikan guru-guru
melalui pendidikan moral di sekolanya.
”Seandainya banyak orang seperti Pepei, tentu bumi ini bakal awet selama-lamanya.”
Riang kembali melontarkan kata-kata yang sama saat bus Yogya menderum hendak
berangkat menuju Thekelan.
Buku harian yang ditulis Pepei --sebelum menjadi atheis--, menggoyang hidup
Sekarmadji hingga ke sendi-sendi. Riang tersenyum kala menyadari seorang atheis mampu
mengantarkan seorang durjana untuk mengingat kematian dan juga mengimani kembali, hari
pembalasan.
Riang menangis.
199
BALAS DENDAM
Ingatan mengenai Kubah
Kartu atm di telan mesin. Antrian memanjang di belakang pintu transparan saat
penyangga sepeda motor Pepei di turunkan. Helm membuat rambut Riang kusut. Pagi tidak
terasa dingin karena tempat itu tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketinggian
Thekelan. Kedua orang itu membersihkan tangan dan kaki dialiran air keran.
Masuk ke dalam, suasana lengan. Ada kedamaian seperti yang biasa ditemukan di
tempat peribadatan. Angin masuk dari bawah tangga, menjadikan ruangan segar, membuat
lantai ruangan besar diseraki orang-orang yang terlelap istirahat. Ada yang memejamkan
mata, ada yang baru saja bangun dan menguap.
Pepei mengajak Riang menuju tengah ruangan. Kubah masjid yang mereka jejak
demikian besar, mungkin sebesar Aya Sophia, sebuah gereja yang dirubah menjadi masjid
akibat pertempuran yang berlangsung lama di Konstantinopel.
“Lihatlah ke atas!” tunjuk Pepei.
Riang duduk. Ia berada di bawah lampu raksasa. Tepat berada di titik tengah, sesuatu
menguasainya. Bukan mistis. Sesuatu yang dapat dirasionalkan, merambati perasaannya.
“Apa pendapatmu?” Pepei berbaring, tersenyum.
“Sukar untuk di katakan, aku merasa … aku merasa kecil...” Kesulitan menjabarkan
lantas membuat Riang diam.
“Kau berada tepat di bawah kubah. Kau merasa kecil, merasa demikian mungil di
bawah lingkaran yang kau pandang. Ada perasaan mengagungkan. Ada keindahan,
ketakjuban, keinginan untuk tenggelam. Kau berhadapan dengan keagungan yang di buat
oleh manusia.”
Riang tak mengerti penuh namun ia membenarkan. Riang takzim.
200
“Akal budi! Seni arsitektur kubah!” Pepei berbisik. Rombongan orang lewat, berhenti
lalub berbaris dua saf, “membuat manusia yang berada di bawahnya merasa kecil. Melebur
bersama semesta keagungan! Bentuk kubah di dalam bangunan-bangunan yang dianggap
suci didesain: untuk mengingatkan manusia bahwa dirinya merupakan bagian kecil dari alam
semesta dan keagungan yang indah dan tak terbatas! Kubah merupakan lambang
ketertundukan!”
Kedua orang itu melangkah keluar dari bangunan megah tersebut. Burung-burung
mendarat di terpal, menyerbu kacang-kacangan yang jatuh tercecer dari sebuah kantung
kertas yang bocor. Tangga masjid licin oleh tetesan air sisa wudlu. Di sisi belakang yang sepi
dinding masjid terkelupas.
“Keberanian serupa dengan kubah!” ujar Pepei. Ia mengelap kaca motor yang kusam.
“Ketakutan memang alamiah, tetapi jika ketakutan bisa dikemudikan, seorang lelaki bertubuh
kecil bisa menjelma jadi raksasa di hadapan orang yang memiliki kaki, tangan dan tubuh
yang kokoh! Jiwalah yang menjadi penentu keberanian! Kau tak akan bisa menakut-nakuti,
Kau tak akan bisa membuat orang lain segan, Kau tak akan bisa menjadikan lawanmu
berpikir belasan kali, jika jiwamu Kau kerdilkan! Letak keberanian ada di sana.” Jarinya
menunjuk ke arah kepala Taryan.
“Di kepala?”
“Di otakmu! Di akal pikiranmu! Dengannya Kau dapat menundukkan serigala!
Menundukkan macan! Gunakan akalmu!”
Motor oleng ke arah kanan. Satu mesin berputar, menggerakan mesin yang lainnya.
Ratusan kerja mekanik membuat besi beroda itu menjauhi masjid. Nomor serial sebuah
rahasia terbuka. Memori memuatnya. Otak Riang menyimpannya.
KEBERANIAN PASANG DAN SURUT. Keberanian ada di otak manusia.
Kekhawatiran yang datang Riang lemahkan. Keragu-raguan ia tikam. Diingatnya kembali
situasi gerbang kuburan ketika Kardi dan gerombolannya berbalik arah menuju hutan
Merbabu kala api keberanian penduduk Thekelan tumbuh menyatu. Diingatnya kembali
mitos yang ia tebarkan.
Kepalan Riang menggebrak lantai kayu pondokkan yang sepi.
“Akan kuciptakan kubah!” Teriak Riang gegap gempita. Ketika otak memunculkan
eureka dan aha elebernis, segala sesuatu menjadi jernih seperti wahyu yang baru saja turun.
“Kubah?!” Taryan melongo. Dianggapnya Riang kesurupan arwah kuli bangunan.
“Mari menanam!”
201
Terbayang bercocok tanam dalam pikiran Taryan.
“Mari menabur!”
Anak itu gila! Kawannya kemasukan setan kuburan!
Riang kemasukan, tapi bukan kemasukan setan. Di dalam otaknya bergentayangan
informasi. Ingatan silih ganti, bertumbukkan, saling berciuman. Diendapkannya,
diheningkannya. Riang menemukan sistematika mengenai awalan berperang yang jauh
dimulai sebelum era Sun Tzu.
Riang meneliti informasi mengenai Kardi agar pembalasan dendamnya terlaksana
serapih gerakan Janitsar Otsmani mengangkut gelondongan kayu yang diperintahkan Al
Fatih demi menyulap bukit menjadi bahtera untuk menggempur dinding Byzantium. Riang
merahasiakan apa yang akan diperbuat. Ia tak ingin apa yang nanti dilakukan menjadi getah
yang menempel di tubuh penghuni pondok. Ia tak ingin menyusahkan dan membawa
persoalan yang memungkinkan pondokkan diporandakkan.
Semula Riang ingin menanggung semuanya sendiri, tetapi Taryan adalah teman
senasib. Ia bersumpah untuk membantu Riang. Tak ada rencana yang berubah ketika Taryan
membantu. Semua berjalan dengan semestinya. Sembah sujudnya Sekarmadji mereka awali
sebagai modal. Bapak yang bertanya mengenai kerasukan Allah, yang menjadikan gunjingan
sebagai sifat yang menyimpang, menyebarkan informasi kemaha besaran Riang secara
sukarela tanpa perlu diminta, tanpa perlu diberitahukan rencananya apa. Inilah perang urat
syaraf dan pemanfaatan yang dipelajari ahli strategi di Pentagon sana.
Cerita-cerita heroik di bakar. Kemenyannya merebak ke mana-mana. Asap, asap
dusta menelusup ke pelipiran, dibicarakan anak-anak, disebarluaskan si Ongki anaknya kang
Nurdin pada pamannya, ujang Eboh yang tengah mencuci sandal. Ibu-ibu tak luput terkena
godaan. Mulut-mulut saling tular menular hingga sampai di kuping pemuda-pemuda
pengangguran yang punya keahlian orisinil menerbangkan burung merpati. Mulut klub
Japati, klub yang memiliki puluhan burung merpati pos, menerbangkan informasi itu pada
nenek enam orang anak yang makin membuat kisah Riang semakin seru. Makin berkepul-
kepul cerita, makin dahsyat ilmu kibul mengkibul yang diperantarai Hermes bernama
Taryan.
Minggu pertama itu Riang diceritakan menjadi perambah hutan. Gergaji mesin yang
pertama kali ia pergunakan bukan untuk menebang kayu tetapi membelah kaki Jagawana.
Saat peluru Jagawana meleset memecahkan sebongkah batu, Riang mengambil kesempatan.
Suara mengerikan kemudian mendominasi seluruh suara di hutan melebihi auman macan.
Groah! Akh!
202
Riang lari ke perbatasan Malaysia lantas membantu menyelundupkan batu bara. Tak
betah di sana, ia pergi ke Jawa menuju stasiun Senen. Baru beberapa bulan bergaul dengan
lingkungan keras Jakarta, Riang sudah berbuat onar, menjadi penyebab huru-hara antara
orang Batak dan Palembang. Riang yang berada di pihak jemo Palembang menusuk seorang
preman sampai mati; satu di leher; lima di dada. Kerusuhan terjadi selama tiga hari. Polisi
datang bertruk-truk. Riang si pemain baru dalam dunia kriminal--, dinobatkan sebagai
buronan. Ia disebut-sebut dengan nama mat Kater. Sebuah julukan yang berawal dari
perbuatannya menusukkan pisau cutter lalu mematahkan pisaunya di dalam tubuh korban.
Riang kabur, hidupnya dari todong sana-todong sini, hampir perkosa tapi tak tega, ia
hantamkan balok jati pada pinggang tukang sate Madura, ia ambil cincin emas anak orang
China. Ia lakukan apa saja untuk bertahan. Ia terus mengembara hingga dalam perjalanan itu
ia bertemu abah Sharun pensiunan perbaikan tower PLN yang profesinya setinggi ilmu
agamanya.
Babak ke dua, pada minggu selanjutnya, cerita mengenai kekebalan tubuh Riang dari
proyektil dan tusukan mengepul. Mengetahui Riang melakukan tindakan dianggap lebih
buruk dari merampok, Abah Sharun mengingatkan, “Cabut susukmu Riang! Sirik itu
mengerikan!”
Riang ingin taubat sempurna, tetapi ia tak bisa mencabutnya bahkan hingga saat ini.
Ilmu nomor satu yang ditanam tanam di tubuh Riang menjadikan hanya sedikit orang pintar
yang memiliki kemampuan menetralisirnya. Susuk itu tidur di dalam tubuh Riang. Susuk itu
seperti kekuatan yang bersemayan di dalam tubuh mahluk hijau Hulk. Kekuatan
mengerikannya bisa muncul apabila pemiliknya membutuhkan.
Berita tersebar dari mulut ke telinga. Riang berharap preman tanggung di sekeliling
Kardi akan berpikir dua kali jika waktu pembalasan dendam yang direncanakan tiba.
Merdu nyanyian dan tebar kibulan itu memang dirasakan Riang. Saat ia jalan di bibir
gang, beberapa pemuda pengangguran menegurnya sopan.
“Kamana ’Aa? Mau kemana Kak?” sapa mereka. Padahal sebelumnya mereka tidak
pernah begitu. Atau, pas Riang mencari geretan, seseorang pengamen yang juga berprofesi
sebagai preman tiba-tiba menawarkan bantuan. “Bade ngisep ’Aa! Mau merokok Mas?”
Dahsyat! Hebat! Durga! Sensasi kelas tinggi! Riang makin yakin manusia dapat
dipengaruhi informasi. Segala persiapan kemudian diselesaikan. Untuk mempertahankan diri,
tak mungkin Riang meminjam lagi golok Aplatun. Ia mengeluarkan uang membeli pisau di
pasar. Riang berusaha menjauhkan Riang, memisahkan temannya agar Taryan tak mengikuti
langkah terakhir yang akan Riang lakukan.
203
Taryan menolak. Ia tak mau hanya menanti. Ia ingin ikut menikmati benih informasi
yang ia bantu tanam sebelumnya. Taryan menyadari konsekuensinya. Taryan ingin melihat
orang yang pernah mengkepruk kepalanya, meski ia yakin tak bakalan tega membalas
perlakuannya dengan kadar yang sama.
Menjelang H-1 pembalasan tiba, Taryan mendatangi terminal Dago. Ia ingin
mengetahui sejauh mana mitos mengembang. Ia ingin memastikan siapa yang mereka incar.
Juru parkir memberi telunjuk, memberi tahu wajah Kardi. Taryan terkesima. Lelaki yang
menjadi musuh kawannya adalah benar, lelaki yang juga pernah membuat kepalanya ternoda
oleh darah.
Taryan mengenalinya baik. Lelaki itu yang membuat ia tidak dapat pulang menemui
Radia. Lelaki itu yang membuatnya tidak bisa membawakan lagi makanan enak untuk Riang.
Pulang ke pondokkan, kepercayaan diri Taryan menjadi bulat. Tekadnya menjadi kuat!
MALAM JUMAT yang keramat.
Tak satupun, harapan yang mampir di benak Riang dan Taryan selain menyelesaikan
urusan. Mungkin, ini malam terakhir mereka di Bandung dan pondokan. Sebuah surat sudah
mereka persiapkan.Terimakasih dan permintaan maaf terkait kepergian yang tiba-tiba mereka
tumpahkan. Riang dan Taryan memilih menghilang begitu saja. Menjadi ingatan yang tak
ada satu orang pun mampu memastikan realitanya. Biarlah semua berlalu seperti bakaran
kapas, menjadi serat-serat rapuh dalam penghabisan, diterbangkan angin hingga tak tersisa.
Riang dan Taryan memperhatikan sanggar yang menyenangkan. Merekam baik-baik
keadaan serta pegalaman yang membuat sel-sel otak mereka berdenyar lancar. Mata mereka
kuyu, sayu. Mereka menghormati Bentar dan Eva. Mereka mengharap kedua orang itu
sanggup memaafkan apa yang mereka lakukan. Pondokan akan tinggal kenangan.
Melalui jalan potong, mereka menuju terminal, menyibak alang-alang yang runcing
dan melewati beberapa buah pancuran. Jalan raya di depan. Riang dan Taryan tak lagi bicara.
Keadaan menjadi tegang. Tak ada keraguan. Jika kalah, kalahlah! Mati-matilah! Sekarat-
sekaratlah! Riang tak peduli. Ia hanya ingin menuntaskan siksa dan kutukan. Ia berniat habis-
habisan. Dendam tak akan membuatnya bersikap fair. Ada dibelakang atau dihadapan Kardi,
ia akan tetap menikamnya sampai mati! Ia tak musti adil! Jahannam itu yang lebih dulu tidak
fair terhadap Pepei! Ini adalah pembalasan dendam bukan usaha untuk menjadi jagoan dan
pahlawan!
Terminal. Kijang-kijang angkutan kota dan colt berwarna hijau berbaris sesuai
dengan jurusannya. Ada oli yang berceceran, puntung rokok bergeletakan beberapa di
204
antaranya masih terbakar Sampah-sampah terserak meski tongnya baru terisi setengah.
Sebuah truk diparkir di depan sebuah toko beras yang tutup. Dahak truk yang batuk pada
knalpotnya mencemari paru-paru bayi berumur satu bulan yang lengket di pelukan ibunya.
Gambar lelaki berkumis ala Hitler menghias kios mie ayam. Lelaki berkumis itu berkata,
Ojolali! sambil mengacungkan jempol yang lebih besar dari kepalanya. Seorang pengendara
motor masuk ke dalam terminal. Selempang yang terjulur ke bawah dagu menyelimuti mulut
dan hidungnya. Masih banyak orang-orang yang berteriak. Masih ada yang sekedar
menggerutu. Bising mengintervensi.
Riang bertanya pada calo angkutan kemudian menuju ke belakang terminal tempat
Kardi mangkal. Saat kritis itu tiba. Tak ada gelembung ketakutan. Bulatan-bulatan yang
semula menganggu pecah. Jika Edison menemukan lampu dan membuat manusia tak lari lagi
dari monster kegelapan, Riang menemukan bahwa dendam telah membuka terangnya jalan
yang menihilkan rasa takutnya. Ia menemukan penyanggah yang Pepei sampaikan mengenai
Kubah. Ia beriman pada informasi yang Taryan sebarkan.
Di bawah lapak yang siang hari tadi menjadi depot es, beberapa bilah kayu di pasang
menjadi dipan yang nyaman untuk istirahat. Ada bantal yang mengesankan Kardi dan teman-
temannya sudah menganggap terminal ini sebagai tempat kediaman. Lima orang tampak
duduk-duduk dan melemparkan jejaring pandangan. Mereka bisu. Riang memperbaiki
langkahnya. Ia masuk ke dalam bayangan atap. Taryan yang berada di sampingnya gemetar.
Tak ada suara. Hanya tatapan dan aura yang pesing yang mengganggu kenyamanan!
Lima pria bangkit. Kutub negative dan kutub negatif lainnya akan bertumbukan! Resonansi!
Seakan tujuh ekor cupang, pertempuran antar mata terjadi. Ada pertempuran di dalam
kegelapan!
Ke lima orang itu tak terpengaruh! Riang mulai khawatir akan keberhasilan informasi
yang diceritakan Taryan. Dengan kecerdasan yang melintas Taryan menyalakan rokok yang
terselip di mulut Riang. Muka Riang jelas terlihat, benderang, meredup, lalu menghilang.
Wajah Riang terekam dengan baik meski hanya beberapa detik.
Alarm berbunyi! Hoy! inilah mitos itu. Inilah wajah lelaki yang memiliki wajah dua
dimensi. Wajah kegelapan dan cahaya. Seperti Ahura Mazda. Akulah pemberi surga dan
neraka! Akulah api yang menggado laron menjadi lalapan!
“Eh, … tos timana ‘Aa? Dari mana Mas?”
Awalan yang baik.
205
Awalan yang baik. Rasa nyaman tercipta. Pemuda yang tadi bertanya menyalakan
korek api tepat di wajahnya. Pria itu membakar korek api untuk yang kedua kalinya. “Di,
pang meulikeun lilin, belikan lilin!” ujarnya.
Orang yang disuruh, tergopoh membusanakan kakinya yang telanjang menggunakan
sandal. Ia berlari. Meloncat-loncat dan balik lagi membawa sebuah lilin. Dinyalakannya lilin
itu.
Satu persatu senyum berkelap-kelip memperhatikan wajah Riang.
“Bade milarian saha Aa? Mencari siapa Mas?”
“Main,” jawab Riang singkat.
“Meuni kitu si A’a mah. Kalo maen mah mending ka Gasibu, pan keur aya nu
manggung, dangdutan. Suka begitu si Mas ini. Kalau mau main mending ke Gasibu. Kan
sekarang ada yang manggung, dangdutan.”
“Kardi kemana? Aku ada perlu dengannya.” Riang mengalihkan pertanyaan.
“Abdi tos lami teu pependak. Sudah lama nggak ketemu.” Pria itu berpikir. ”Kardi
teh rerencanganana Akang? Kardi temennya Mas?!”
Aha edan! Dia mengetahui nama Riang. Managemen mitos Riang berhasil. Iklan!
Taryan piawai membuat iklan! Ia pantas diikutsertakan dalam tim sukses Pilkada!
”Kardi teh babaturan akang zamen bareto. Zaman aki-aki disunatan pake tambang,
zaman nini-nini di tumpakan kuda, sanes? Sekarmadji itu temennya Mas Riang zaman dulu?
Zaman pas kakek-kakek di sunatin pake tambang, pas nenek-nenek ditunggangi kuda,
bukan?” Pria itu tertawa. Ia berusaha melucu.
Dehidrasi. Ia sadar Riang tak suka. Pria itu memperbaiki sikapnya.
“Kehuelanya ’Aa. (sebentar ya Mas).” Ia bertanya pada pemuda yang tadi
membawakan lilin. Pemuda itu berlari lagi, lalu balik membawa seseorang yang
menyengajakan diri untuk menyampaikan informasi mengenai Kardi.
Saat klimaks datang, tiba-tiba takdir berbelok begitu saja. Kardi hilang dijemput Jeep
berwarna merah. Lelaki sialan itu hilang, menguap! Riang kecewa! Harus sampai kapan ia
berada di kota ini?
Nasib manusia benar-benar tidak dapat diprediksi. Nasib Riang seperti dipimpongkan
entah oleh siapa. Ping di lambungkan … pong … di smash sintir dan menukik. Pong yang
mengecewakan pada waktunya akan menjadi ping kebahagiaan hanya dalam hitungan hari.
KEJUTAN
206
Setelah kepergian mereka ke terminal, Riang dan Taryan kembali kepondokan.
Mereka mengubur rapat apa yang telah mereka lakukan beberapa minggu yang lalu. Kedua
orang itu menganggap penghuni pondokan tak mengetahui apa pun mengenai apa yang
terjadi. Riang dan Taryan tidak mengetahui, keluasan jangkauan indera penghuni pondokan
melebihi perkiraan yang mereka sangka.
DI ATAS PUNUK BUKIT, langlang burung pipit sibakan awan ikal layaknya bulu
domba. Pipit itu membumbung tinggi di jalur bebas tanpa hambatan. Dari angkasa terlihat
bebukitan yang berseni di arsir angin. Sebuah kotak terletak di tengah ruang hijau terbuka.
Jauh dari kotak yang merupakan kompleks pondokan dan sanggar itu seliris garis putih yang
merupakan air terjun tampak berasap.
Pagi ini Riang dan Taryan akan meniti bebukitan, memotong susunan karang,
melewati air terjun tersebut.
Ransum yang dimasukan Riang ke dalam tas terlau banyak. “Tidak usah terlalu
banyak,” tegur Bentar. “Di sana banyak ikan, lagipula malam ini kita pulang.” Bentar
menunjuk pepohonan yang bergerombol.“Di sana hutan kopi! Jangan dulu masuk ke
dalamnya. Tunggu aku tepat di depan hutan kopi itu.”
Taryan masih mencari cacing di tanah gembur dekat sanggar, saat Riang menuruni
tangga bata. Melihat Riang melangkah semakin jauh, ia segera mengikat daun talas
menggunakan serat bambu. Geliat cacing yang berada di dalam lipatan daun membuat
tangannya geli. Taryan berlari. Ia bersiul menikmati pagi yang bergizi.
Kawasan di luar pagar sanggar merupakan kawasan gelap, sebuah wilayah tera
incognita bagi mereka yang tak pernah berjalan jauh semenjak hidup di pondokan. Matahari
membuat pori-pori kedua orang itu hangat. Keringat bermunculan sekecil titik lalu membesar
menjadi jentik-jentik dan menggembung sebesar biji jagung. Saat keringat di pori-pori
meleleh Riang dan Taryan sampai di hutan kopi. Cuit, cuit suara burung dan kepak sayapnya
terdengar jelas. Ada gemericik air. Suaranya tak begitu jauh. Riang istirahat di atas rumput,
sementara Taryan lebih tertarik melihat aliran sungai. Ia menghilang.
Baru saja Riang menguap, sebuah teriakan histeris terdengar “Masya Allah Riang!
Masya Allah!”
Riang melupakan kantuknya. Ia berlari searah dengan tempat menghilangnya Taryan.
Ia melihat aliran sungai. Merah bertebaran di mana-mana. Taryan tergeletak, di dahan pohon.
Riang memungut ranting. “Sialan!” umpatnya. Ia melemparkan ranting di tangannya kuat-
207
kuat. Taryan mengikik. Ia membalasnya lemparan itu menggunakan jambu air yang
menggunduk di dalam genggaman tangannya.
Pohon jambu air berbuah lebat. Buah-buahnya berjatuhan ke tanah. Ada yang busuk,
namun sebagiannya yang masih segar membuat liur menetes. Riang tergoda untuk memanjat.
Ada saja jambu yang jatuh ke sungai setiap Riang menggoyang dahannya. Kedua orang itu
mengantungi dan memakan jambu air liar sampai puas.
Fred tiba lebih dulu di pelipiran hutan kopi. Ia berteriak. Teriakannya disambut Riang
dan Taryan lalu ketiga orang itu menghabiskan hampir sebagian jambu air matang yang
tumbuh di pohon. Setengah jam kemudian, Bentar dan Eva sampai di tepian hutan. Taryan
menyambut mereka dengan tingkah laku monyet, menyorongkan jambu air yang ia masukan
ke dalam serokan.
Memasuki hutan kopi perubahan terasa. Hawa menjadi segar. Hutan kopi yang
mereka masuki adalah refrigerator alami. Pepohonan rapi berjejer. Tak ada biji-bijian yang
menempel di dahannya. Hutan ini mandul, menopause, tak produktif lagi. Pohon kopi terlihat
diselang selingi tepus, semacam obat alami pereda panas. Di tengah jalan, Riang yang berada
di depan rombongan menemukan onggokan arang. Ada tiga batu mengepung kayu yang
sudah mengitam. beberapa jam yang lalu beberapa orang melanjutkan mematikan bakaran,
mematikannya dan meninggalkan hutan kopi. Mereka terus berjalan. Cahaya semakin terang
di depan. Aliran air, --yang semenjak pertengahan hutan menghilang- -, terdengar kembali
suaranya. Rombongan itu keluar dari hutan.
“Ini kebun, bukan hutan!” protes Riang. Wilayah itu hanyalah kebun kopi yang
menyendiri memisahkan diri.
Bentar yang saat itu tengah mencabut tanaman rheumason tak mau ambil pusing.
Didekatkanya akar tanaman pada Eva. Hidung perempuan itu blong. Suara guruh terdengar.
Tebing batu basah. Percikan air tanah merayap di dinding lalu jatuh. Tebing batu itu
ditumbuhi lumut dan didominasi tanaman yang lumrah dijadikan tanaman pagar yang
merambat seperti jenggot. Tanaman itu tampak subur menutupi dinding selebar lima puluh
meter. Tinggi tebing batu yang mereka lewati sulit diprediksi ketinggiannya.
Memasuki jalan batu yang licin berair, beberapa tanaman, merunduk menahan
terpaan air. Pepohonan yang membusuk, tumbang di samping jalan. Tanaman-tanaman tropis
bergoyang-goyang oleh angin deras yang menghempas dari arah selatan. Ada gemuruh dalam
kesunyian, terkadang menjedar-jedar menakutkan.
Keluar dari tebing mereka masuk ke dalam ruangan terbuka. Ada raksasa di tempat
itu. Sebuah air terjun yang megah tampak di hadapan. Air liurnya yang putih, menimpa
208
bebatuan mengukir salah satu batu membentuk cincin-cincin besar. Di hadapan Raksasa
putih mereka istirahat sementara Eva bergerak menaiki puing-puing bebatuan, menyeberangi
aliran air, menuju sebuah pondok kayu. Bentar menyusulnya.
Air terjun itu pasti sudah ada sejak zaman purba, mungkin pernah dijadikan tempat
minum stego dan tyranosaurus, menjadi tempat menggembleng kesaktian pendekar zaman
dulu, dan pernah dibalikan oleh satu pukulan, seperti yang dilakukan Ryu dalam Saint Saiya
yang sering Riang tonton di Yogya saat SMA. Air terjun itu memiliki panorama yang indah.
Akar-akar yang kokoh dan pohon-pohon raksasa yang bergerombol mengelilingi air terju itu
mengesankan penjara alam yang indah. Di beberapa sisi tebing, akar-akar yang kokoh,
menjadikan bebatuan menjadi bongkahan. Di pertengahan tebing kiri, sebuah akar sebesar
diameter phyton tiba-tiba bergerak, menjulur ke bawah. Seorang lelaki turun menggunakan
akarnya. Baju lelaki itu berkibar. Sampai di bawah, lelaki itu masuk ke dalam kolam yang
dingin. Badannya ditempa curahan air dari ketinggian puluhan meter. Riang tahu rasanya
tubuh ditimpa air dari ketinggian belasan meter. Ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya.
Wajahnya serasa ditampar sandal jepit. Riang melihat tubuh lelaki itu memerah, tetapi ia tak
mendengar erang atau goyangan tubuh yang mengesankan lelaki itu kesakitan.
Riang tidak sadar, saat dirinya melihat lelaki itu wajah Fred mendadak berubah.
Lelaki itu mencemari udara di sekitar dengan tatapan yang memangsa. Fred beringsut
perlahan, mencari kesempatan. Suaranya mengalahkan deru air.
“Tahu tidak?” Fred mencolek tulang iga Riang, kasar.
Riang berpaling.
“Eva,” Fred menunjuk, “wanita itu tengah membuat feature mengenai keyakinan
tradisional setempat untuk majalah luar. Kau tahu fokus tema yang diangkat dalam tulisan
Eva?”
Riang tidak tahu.
“Mengenai pertemuan antara Adam dan Hawa.” Fidel mendekatkan mulutnya. “Kau
tahu di mana nenek moyang manusia itu bertemu?”
Pertanyaan itu terlalu tiba-tiba. Muncul di saat yang tidak tepat. Riang ragu
menjawabnya.
“Di Batu Jajar?” jawab Fred.
Adam bertemu Hawa di Arafah. Guru agama Riang yang mengatakannya.
“Kau tahu, Yang?” Fred menyoodorkan bibirnya yang berubah membentuk corong.
Riang mana tahu.
“Adam turun ke dunia tidak pakai kolor. Tidak pakai cangcut!”
209
Seperti seks, prostitusi, kondom, dan kelamin, maka cangcut dan kolor adalah sebuah
kode. Menyebut salah satu di antaranya akan membukakan kolektif ingatan yang diterpakan
koran kuning yang memiliki kelainan dan Chomsky menyebut cara yang sudah dipraktikan di
Timur Tengah mengenai term terorisme dan radikalisme sebagai American Ideological
system. Riang tidak seideologis itu. Pikirannya Riang merah jambu. Cabul Ideological
system Riang berdering-dering. Ia berkhayal, jika Adam tidak menggunakan cawat
bagaimana dengan Hawa?
“Kau tahu Yang?!” Fred mengejutkannya lagi. “Kolor Adam terbuat dari daun talas!
Adam menggunakan kolor daun talas! Kau tahu?!”
Riang mengikik. Cabul ideological systemnya masih berbunyi. “Gatel dong!”
katanya.
“Ya jelas! Bagian vitalnya Adam beruntusan.” Fred tertawa. “Tahu sendiri, pohon
talas zaman purba sebesar apa. Getahnya ratusan kali lebih gatal ketimbang pohon tales
zaman sekarang!”
Fred sorongkan mulutnya di daun telinga Riang. “Kau tahu siapa yang membuat anu
Adam gatal?”
Dalam permasalahan seperti ini, Riang tangkas. “Daun talas!” katanya bahagia.
“Euhhh!” Fred kecewa. “Kan aku bilang siapa, bukan apa.”
Riang tampak harus kembali ke zaman SMA.
“Kau tahu siapa?!”
“Siapa?!”
“Yang…” Fred berahasia. “Yang buat titit Adam gatal-gatal itu Tuhan! Tuhan
sekalian alam!”
Fred jadi tampak menakutkan. Ia terlihat berubah. Riang melihat giginya yang kuning
bertambah. Kerongkongannya seolah berubah menjadi gua Selarong.
“Lu tahu Allah buat Adam pakai apa?” Fred menteror.
Riang yang masih terkejut, belum bisa menerima perubahan itu menjawab lurus.
“Pake kun fayakun.” Riang teringat kembali guru SMA-nya. Ia belum sanggup menahan
pertanyaan yang datang. Ia masih merasa pertanyaan itu seolah tak pernah ditanyakan. Ia
merasa dirinya bermimpi.
“Salah! Mana ada kun fayakun! Adam diciptakan… ya… ya…” Fred meminta Riang
untuk mendekatinya, “sini…sini Aku bisikin lagi!”
Riang memberikan kupingnya.
“Adam diciptakan dari sperma tuhan! AIR MANI ALLAH!”
210
Riang mental sepuluh meter. Membentur bongkahan batu besar. Ia seakan merasakan
lelaki yang berada di bawah air terjun mencabut akar tumbuhan dan menggunakan akar itu
untuk mencambuknya.
Riang step (lumpuh).
Dalam kondisi itu, Fred mengetahui pada saat seperti itu siapa pun sukar untuk
memulihkan diri. Kesempatan itu ia gunakan benar. Fred mendongeng. “Waktu zaman
Pleistosen dulu, tuhan sendiri. Setelah sekian tahun, ia tak tahan. Tuhan tak bisa menahan
libido-nya! Ia menggesekkan kemaluannya ke batu karang. Digeseknya sampai bucat!
Sperma-Nya muncrat! Dia puas. Tuhan puas! Ia yang maha mengetahui terbang ke angkasa.
Di tengah-tengah perjalanan tuha pulang ke surga, seekor biawak betina datang. Si biawak
ngaso di batu tempat sperma Tuhan keluar. Si biawak tidak sadar, jika sperma tuhan
merangkak mendekati kelaminnya yang mangap-mangap! Biawak itu hamil! Tiba-tiba
………… seperti katanya penciptaan dunia, biawak itu hamil! Dan kau tahu siapa yang ada
di perutnya?! Kau tahu siapa?! …. ADAM Yang!!! Cangkokan sperma tuhan itu berwujud
Adam!” Fred tersenyum mengerikan. Ia mengambil kesimpulan. “Jadi… kalau ada yang
bilang Adam datang dan tercipta tiba-tiba begitu saja turun ke dunia, itu salah! Salah total!
Salah hu akbar! Bagaimana bisa Adam lahir dengan sendirinya?! Ibunya Adam itu
biawak!!!”
Perkataan Fred membuat Riang ingin bunuh diri. Marah dan rasa tidak percaya jika
Fred yang mengatakan itu, membuat Riang tak bisa berbuat apa-apa. Riang menggapai-gapai,
melarikan pandangannya, dari pandangan yang memangsa.
Fred terus tancapkan keraguan di pikiran Riang.
Seperti halnya menghadapi gempuran perkataan Mahdi di Yogyakarta, Riang
menutupi pendengarannya, tapi gempuran itu tidak serta merta hilang. Gempuran itu
membekas di dalam pikiran.
Riang memaksa diri melihat Bentar dan Eva turun dari pondok kayu. Kedua orang itu
mendekati lelaki di bawah air terjun tanpa mengganggu. Bentar membuka payung untuk
menjaga lensa kamera dan Eva menembaknya. Mereka berjalan, menuju samping air terjun,
menaiki akar lalu menggunakan isyarat tangan.
Riang melompat. Ia berjalan tak mempedulikan Fred. Sekitar sepuluh meter
menjalari akar, Eva dan Bentar menghilang di telan bebatuan. Kedua orang itu masuk ke
dalam lorong hijau dihiasi dedaunan dan bunga-bunga terompet berwarna ungu. Lorong yang
cukup panjang dengan kemiringan tigapuluh derajat itu memudahkan seseorang untuk
sampai di atas air terjun raksasa.
211
Riang menyusul Bentar dan Eva, ia tak menyadari jika Taryan meneriakinya. Riang
terus melangkah. Sampai di lorong hijau, menuju ujungnya, lalu berbelok ke kanan dan
menyibak dedaunan yang menutupi jalan. Riang menemukan Bentar dan Eva istirahat di
sebuah kebun teh tua yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya..
“Di sekitar wilayah ini,” papar Eva, “ada sebuah masyarakat yang mengakulturasikan
kepercayaannya dengan kekuatan alam.” Eva tersenyum pada Riang. “Kau melihat orang
yang turun memanfaatkan akar Yang?”
Riang diam. Ia menyeka wajahnya.
“Butuh tenaga besar untuk turun dari sana. Apalagi jika harus menaikinya,” ujar Eva.
“Lorong yang kita masuki tadi tersambung hingga ke atas air terjun. Di atasnya kita bisa
menemukan sebuah arca yang dililiti akar pohon yang menjulur hingga ke dasar air terjun.
Naik dan turunnya lelaki yang kau lihat di air tejun tadi adalah ritual peribadatan.” Eva
sedikit bingung. Riang tidak memberinya respon.
Bentar melirik. Ia melanjutkan penjelasan. “Masyarakat yang bisa kita temui satu kilo
ke arah tenggara dari tempat ini Yang … masyarakat di sana percaya, di bawah air tejun yang
kita lewati tadi Adam dan Hawa bertemu!”
Dar! Mendengar pertemuan Adam dan Hawa halilintar menyambar! Pantat Riang
hangus! Ke dua orang itu melihat hentakan tubuh Riang. Riang tak bisa ditanya. Ia
mengasingkan dirinya dalam perjalanan. Ia diam. Perjalanan yang panjang jadi tak terasa saat
konsentrasi pecah. Jalan setapak terus menanjak, menanjak dan menanjak hingga akhirnya
Riang menyadari kakinya menginjak hamparan rumput Jepang. Tampak sejajar dengan
matanya rumah mungil bergaya arsitektur Jepang berdiri. Jendela-jendela kotak
mendominasi. Genting rumah terbuat dari rumbia hitam. Tak ada pagar, hanya rumput yang
menandakan batasnya.
Di samping rumah mungil itu, ratusan mentimun mengintip siap petik. Bunga kol
merekah, warnanya hijau tua. Ada kolam air deras pinggir lahannya. Pada muara kolam itu
ditaruh roda besar. Bunyi gerakannya memecah hening. Sebuah kabel disambungkan ke
dalam rumah. Roda itu dijadikan pembangkit liistrik oleh pemiliknya. Rombongan orang dari
pondokan berjalan menuju pintu utama rumah. Tiga buah kursi, satu meja dan sebuah kursi
malas, bergoyang-goyang. Seseorang baru saja duduk di atasnya.
Bentar mengenal baik rumah kayu ini. Ia mengetuk pintu. Tak ada sahutan. Tiga kali
ia rasakan cukup. Bentar masuk ke dalam dan tidak menemukan seorang pun di sana. Tak
berapa lama kemudian suara gebrakan terdengar. Dua buah keranjang yang dipenuhi wortel
dan beberapa tomat jatuh di atas papan kayu.
212
Seorang berbadan besar menunduk, wajahnya ditutupi caping. Sebilah clurit
tergantung di pinggangnya. Ia mengangkat kepala. Waluh! Lelaki gagah itu terkapar di atas
lantai. Ia lagsung mengambil air pada botol yang terletak di tengah tubuh Taryan dan Eva,
tanpa meminta izin.
“Lelaki itu itu di mana?” Tanpa basa-basi Bentar langsung bertanya padanya.
“Masih di kolam!” jawab Bentar padat.
“Di hulu sungai?”
“Kemarin air meluap. Ada kemungkinan bendungan di hulu roboh. Dia pulang jika
bendungan sudah dibenahi.”
Bentar tersenyum. “Mudah-mudahan anak ini bahagia!”
Anak ini? Siapa yang dimaksud anak ini?
Obrolan berakhir. Maknanya hanya diketahui beberapa orang. Waluh lantas
mengambil beberapa buah wortel. Ia mencucinya di dalam kolam. Eva masuk ke dalam
rumah kayu menyiapkan makanan, sementara Riang dan Taryan mengitari kolam dan
halaman luas yang digunakan Waluh mensupport Sup Not Bomb. Jika tanah ini tidak
menghasilkan ia mendatangkan bahan makanan dari lahan lainnya di Lembang atau
Pangalengan. Waluh mengelola lahan, mengkomersilkan ke swalayan untuk mensubsidi
pasokan bahan makanan dan kegiatan dan membuat jaringan antar pemilik lahan. Jaringan itu
ia gunakan untuk menjamin distribusi makanan dari pemilik lahan bagi yang membutuhkan.
“Satu kilo ke arah tenggara ada lahan seluas tiga hektar milik Sup not Bomb. Jika
kalian jalan lagi sekitar dua kilo kalian akan menemukan lahan pertanian yang luasnya enam
kali lapangan bola.” Tunjuk Bentar pada Taryan dan Riang. “Pemilik lahan itu petani tua
dari Jakarta. Dia pendukung berat SNB. Coba lihat titik cahaya di bawah sana,” Bentar
menunjuk ke arah lembah, “itu cahaya rumah petani miskin yang juga mendermakan hasil
pertanian yang tak seberapa untuk panjangkan usia saudara kita.”
KETIKA SORE JEMBATANI MALAM Riang sudah membenahi denyut nadinya.
Ia menjauhi Fred untuk sementara. Setelah maghrib lewat beberapa orang memasuki rumah.
Tiga orang wanita seusia Eva. Sisanya laki-laki semua.
Beberapa saat kemudian, anggota kumpulan itu bertambah. Seorang lelaki jangkung
datang. Dari perawakan, rambut, wajah, dan bola matanya, jelas ia bukan berasal dari ras
yang sama dengan orang-orang yang berkumpul sebelumnya. Ada sesuatu yang menyatukan
mereka di sini.
213
Lelaki jangkung itu memperkenalkan diri. Dia datang sembunyi-sembunyi,
menggunakan paspor untuk wisata ke Bali, menyeberang dan akhirnya sampai ke tempat ini.
Eve menterjemahkan. Chris berharap kedatangannya bisa diterima.
“Di Inggris saya bertemu dengan Eva. Saya sempat berdiskusi mengenai keadaan
politik Indonesia. Saya di sini bukan ingin ikut campur. Saya datang, hanya ingin berbagi.
Saya yakin Your’e experiences beyond mine, pengalaman kalian jauh melampaui pengalaman
saya. In this spot kita bisa saling memahami, berbincang, mengisi.” Chris diam merumuskan
apa yang hendak ia sampaikan. “Kita sama-sama memahami, saat ini politik Indonesia
tengah memanas. Suasana di negeri ini keruh. Eva bilang, pemerintah akan menindak siapa
pun, yang dianggap berusaha menggulingkan pemerintahan .... maaf… di mana pun saya
berkunjung, aparat pemerintah dunia ketiga selalu menjadi antek kapitalisme global.
Perusahaan transnasional yang dibangun pemilik modal dunia, melakukan kerjasama dengan
pemerintah negara ketiga. Mereka adalah penguasa yang sesungguhnya.”
”Mengatas namakan stabilitas penanaman modal, mereka membuat kebijakan yang
menghantam gerakan-gerakan bawah tanah. Mereka takut pada jaringan-jaringan kecil yang
satu saat nanti akan membesar menjadi rival yang menakutkan. Jaringan-jaringan itu mereka
putus menggunakan cara yang halus hingga represi. Entah sudah berapa ribu anak muda
hilang karenanya…”
“Saya mendengar, saya ikut bersimpati. Kita kehilangan kontak akibat kehilangan
terlalu banyak pemuda-pemuda yang memahami kekuatan informasi. Komunikasi harus
kembali di bangun. Teman-teman di luar berusaha membantu. Di Filipina, Australia,
Singapura, Malaysia, Amerika, mereka mensupport kegiatan yang kalian lakukan. Saya
hanya ingin mengatakan bahwa kalian tidak sendiri saat ini.”
Seseorang menjelaskan keadaan. Bahasa Inggrisnya terpatah-patah.
“Gerakan-gerakan Leninis mencuri start. Organisasi-organisasi underbow mereka
lebih dulu turun. Gerakan-gerakan pembangkangan yang di organisir secara terselubung,
mulai bergerak. Kita mendengar di Garut, di Cianjur selatan, Sukabumi, di Tapos, muncul
demonstrasi-demonstrasi kecil. Mahasiswa-mahasiswa pun, sudah mendesas-desuskan
munculnya revolusi di Jakarta. Mereka percaya, rekayasa sosial berawal dari kerjasama antar
gerakan, yang meski memiliki landasan berbeda tapi untuk saat ini memiliki tujuan yang
sama. Gerakan mahasiswa dan gerakan Marxis memiliki common enemy yang sama:
tumbangkan rezim yang telah lama berkuasa. Apa kita masih harus tinggal diam?”
“Kita tidak akan bergabung dengan mereka!” Tegas yang lainnya.
214
Chris tak mau mendominasi pembicaraan. Ia menyadari, disini, ia tidak datang untuk
menyetir apa yang seharusnya dilakukan. Ia hanya seorang tamu saja. Tak lebih dari itu.
“Untuk saat ini, kita tidak akan bergabung dengan mereka.” Kali ini Waluh yang
bicara.“Kawan-kawan mahasiswa dan gerakan Stalinis belum memiliki dasar yang kuat
untuk menggantikan sistem. Terlalu cepat jika revolusi sistemik terjadi.”
“Jika bersikukuh, yang nanti terjadi, revolusi prematur seperti peristiwa Prambanan.
Revolusi seperti itu mudah dimatikan antek-antek kapitalis. Revolusi terlalu dini akan
tumpas. Pikiran masyarakat belum berpihak secara sadar mendukung revolusi. Mereka hanya
faham kalau mereka disusahkan. Tak lebih dari itu. Masyarakat hanya memamah
propaganda.” Waluh melirik,” bagaiman telaah kolektif anarki di tempatmu?”
“ In England our movement running by methodology of education. Tak ada
propaganda, jika propaganda itu hanya dilakukan sekedar membakar amarah. Rakyat akan
bersimpati dan tidak akan balik menyerang, suatu saat kami yakin masyarakat akan bergerak
atas pemahaman, bukan propaganda. Proses pendidikan harus dijalankan. Kami menganggap
satu-satunya cara berubah adalah pendidikan. Revolusi dan propaganda, cara pintas
pendidikan jalanan, tidak akan menggantikan apa pun selain kekacauan. Kami tidak
bergabung dengan gerakan seperti itu. Kami anarki pasifis.”
“Tak ada yang dikhwatirkan,” seseorang menambahkan, “lagipula yang hanya
mereka siapkan hanya atap bukan bangunan berpikir yang kokoh. Mereka masih lemah. Tak
ada yang perlu ditakutkan. Kekuatan mereka bahkan belum samai kekuatan, kala mereka
menyetir Soekarno.”
“Kita tidak akan bergabung dengan mereka kan?” Seorang wanita memastikan.
“Untuk apa?” Waluh mengambil ancang-ancang, “hanya sekedar untuk memamerkan
dan berkata bahwa kita bergerak? Tidak, kita tidak akan tercebur dalam kolam kejatuhan
yang sama. Dulu, dalam Revolusi Jerman 1918, ide-ide anti-negara telah diletakkan ke dalam
praktiknya. Berbagai anarkosindikalisme didirikan dan dideklarasikan, bahwa mereka
independen dan memiliki otonomi penuh. Tapi kemudian otonomi ini dihancurkan aliansi
pemerintah komunis bersama milisi-milisi fasis yang pro negara dan kaum sayap kanan.
Semua bersatu menghancurkan anarkosindikailis.”
“Pada tahun 1921 ketika pelaut Petrograd bersama kaum buruh menduduki kota
Kronstad, kita dibantai habis-habisan oleh Tentara Merah Bolshevijk dan Trotsky dengan
angkuhnya berkata, pada akhirnya pemerintah Soviet, dengan tangan besi, telah membawa
Russia lepas dari anarkisme! Padahal, dulu, seolah-olah mereka mendukung kita dalam
tuntutan-tuntutan revolusinya. Saat ini kita memahami yang terjadi. Tetap di tempatnya. Kita
215
tetap melakukan hal yang biasa kita lakukan! Kita tak akan melakukan kekerasan, sebab
kekerasan adalah sebuah bentuk penguasaan dan pemaksaan! Kekerasan pun hanya akan
menyebabkan perbudakan,” Waluh mulai mempersuasi. “Mungkin diantara kita ada yang
memiliki prinsip yang berbeda. Tapi tolong, kita harus stigma yang telah di bakukan
Kapitalisme terhadap Anarkisme!”
Ada kemelompongan di dalam. Eva kemudian mengajak mereka semua untuk
mendengarkan Chris kembali. Lelaki itu menceritakan secara detail bagaimana kegiatan-
kegiatan yang dia lakukan bersama gerakannya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Ia
mengambarkan bagaimana langkah yang dilakukan teman-teman di Inggris untuk
memperkuat masyarakat dan komunitas menggunakan konsep anarkisme. Untuk
menciptakan sebuah dunia dimana orang-orang datang bersama-sama membentuk tatanan
masyarakat baru, yang bebas. maka kita harus melakukan hal-hal yang alamiah. Anarki
adalah kegiatan membangun diri dalam bentuk paling sederhana: menolong tetangga
disekitar, menanam sendiri makanan, mendukung aksi-aksi pemogokan, hingga demonstrasi
di dimana pun juga sebagai upaya penentangan terhadap konfrensi WTO; sebagai tanggapan
atas diberlakukannya kebijakan-kebijakan pasar bebas, menolong menjagakan anak,
menjawab apabila ditanya, hingga tidak menjadi tipikal seseorang yang diharapkan oleh
sistem. Anarki adalah kerjasama yang saling menguntungkan, ko-operasi dan tidak
menyerahkan hidupmu pada orang lain untuk mengaturnya.
“We trying to keep our tradition. Do it yur self. D. I. Y.” ujar Chris. “Saya berbangga
ketika melihat teman-teman berhasil melakukan hal kecil seperti SNB tetapi berarti besar
atau seperti yang dilakukan petani-petani di Brazil. Ratusan dari ribuan petani yang
mengorganisir diri dalam MST (organisasi gerakan para petani hamba) menduduki lahan-
lahan pertanian untuk kemudian mengolah Lahan secara kolektif. Tahun 1994 lalu, kaum
Zapatista memapankan zona otonomi di berbagai desa di daerah Chiapas, Meksiko. Kami
berpikir, untuk terus tularkan tradisi resistensi dan perlawanan. Mereka mengangkat senjata.
Kita mungkin berbeda pemahaman dalam mengartikan anarkisme tetapi kolektif Chiapas
menjalankan tradisi pendidikan dan mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Saya pikir kita
semua faham bagaimana anarkisme diwujudkan.”
Riang dan Taryan tak bisa ikuti perbincangan itu. Keterbatasan berbahasa dan
kurangnya informasi menjadikan mereka seperti selada yang kesepian teronggok di pasar
swalayan. Mereka tak perlu berharap mengerti sebab inti kedatangan mereka bukan untuk
mendengarkan Chris, si bule anglosaxon itu membicarakan ideologi otonomi. Kedua orang
216
itu merasa tak berguna. Ingin keluar dari ruangan rasanya tidak nyaman karena harus
meminta izin memotong pembicaraan.
Taryan melihat kegelapan yang ada di balik jendela. Angin dingin masuk ke dalam
ruangan melalui pintu. Riang mencuri-curi pandang memperhatikan Fred yang seolah-olah
tengah merekam seisi ruangan dengan matanya.
Saat perbincangan mulai melonggar, dari kejauhan suara motor trail terdengar
memecah konsentrasi. Situasi yang semula hangat berubah menjadi tegang. Hanya Bentar
Eva dan Waluh yang tidak terganggu. Mereka mengenal suara knallpot motor trail itu. Mesin
motor berhenti. Langkah sepatu boots beradu dengan tanah. Beban jatuh di lantai.
Langkahnya terdengar berat. Pintu dibuka. Cahaya lampu menegur wajahnya kala lelaki itu
memasuki rumah kayu.
“Hai Chris,” sapanya. “Di sini terlalu gerah ya,” lelaki itu tersenyum, memandang
persatu. “Bagaimana kalau kita santap malam di luar.” Ia membujuk. Dan wajah lelaki itu
tiba-tiba menukik. Tatap matanya menyambar ke arah Riang.
“Riang Merapi … Lama tak bersua. Selamat datang di gubug kecilku kawan!”
sambutnya ramah. Bahagia mengerjap di matanya.
Suara itu hanya dikeluarkannya sekali, tetapi resonansinya terasa lambat bagi Riang.
“Riang Merapi … Lama tak bersua. Selamat datang di gubug kecilku kawan!”
“Riang Merapi … Lama tak bersua,
Selamat datang di gubug kecilku kawan!.”
“Riang Merapi … lama tak bersua,
Selamat datang di gubug kecilku kawan!.
Suara itu?
Suara itu?!
…
…
…
…
..
.
“Fidel!”
Riang bangun dari duduknya. Ia setengah berlari. Sebelum menubruknya, Fidel
mengulurkan tangannya yang hangat di bahu Riang. Dipeluknya rekat. Riang tak kuasa
menahan haru. Ia menangis. “Mas Fidel ada disini?”
217
Fidel melepaskan pelukan, ”ceritanya panjang” Ia meminta izin keluar rumah. Riang
mengikutinya. Taryan menyusul berjingkat jingkat padahal tak semestinya ia begitu sebab
orang-orang ikut berhamburan keluar, mengambil gelembung plastik dan arang yang ada di
gudang belakang.
Bentar menghampiri. Ia meninju pangkal lengan Fidel.
“Hai Petir,” sapa Fidel “Bandrek pesananmu ada di dalam tasku!”
Keakraban itu menimbulkan kecurigaan. “Mas kenal Kang Bentar?!” Tanya Riang.
“Menurutmu?”
Riang diam.
“Lebih dari sekedar kenal,” Fidel menjelaskan. “Dia teman baikku.”
“Kalau Mas kenal, kalau begitu, be…berarti Mas tahu aku ada di Bandung?”
“Sabar,” Fidel tertawa. “Episode kita masih panjang Mas!”
“Panggil aku Riang saja, Mas.”
“Begitu halnya denganku!” Perkataan Riang di makannya. “Jangan panggil aku Mas.
Panggil seperti teman-teman biasa memanggilku.”
“Oh ya … Mas … eh Del … eh Mas saja ya?”
Fidel terseyum. “Terserahlah mau panggil aku apa.”
Riang senggol Taryan. “Ini temanku!”
“Mas ini siapanya Riang?” sederhana sekali Taryan bertanya.
Riang sebal dengan pertanyaan itu, tapi siapakah Fidel baginya? Ia hanya bertemu
dengannya sekali tetapi pengalamannya bersama Fidel seakan pengalaman seseorang yang
hidup dan berteman selama bertahun-tahun. Riang tak bisa menjelaskan. Fidel pun kesusahan
dibuatnya.
“Saya? Siapanya Riang?”
Sulit untuk menjawabnya.
Waktu di sandera. Over hang selama beberapa detik.
Riang memutuskan. “Ia penyelamatku di Merbabu. Sudah berapa kali kita bicarakan
ini. Kau lupa?!.”
“Temennya Mas Pepei itu?”
“Tepat! Riang itu …” Fidel masih sulit mendevinisikan. “Ya, Riang-ku!” Fidel
sedikit lega.
Usai menyeduh minuman hangat, Bentar datang menggoda. Uap bandrek dam kopi
membuat orang-orang melupakan tua. Bentar menarik kursi malasnya. “Fidel itu sepupuku.”
Ia mengakuinya santai.
218
“Fidel yang memberitahukan keberadaan dirimu di kota ini.” Bentar pasang tampang
tak bersalah. “Sebelum ia pergi ke Isfahan, aku di wajibkannya mencarimu. Taruhannya,
nyawa.” Katanya serius. “Kalau aku tak menemukan dirimu…” ia menunjuk Riang, “bisa-
bisa aku digergaji olehnya!”
Fidel tertawa.
“Kenapa tak memberitahu kalau mas Bentar kenal mas Fidel sejak lama?” Riang
menuntut.
“Itu asyiknya!”
“Asyik darimana!?”
“Asyik pikirkan cara supaya Kau betah di pondokan! Supaya tak balik ke jalan! Aku
khawatir kau akan pulang ke Thekelan. Kau hanya akan ke pondokan, seandainya Fidel
pulang.”
“Dari mana mas mengetahui wajahku?”
“Memangnya tidak ada kamera foto apa? Waktu kau antar Fidel dan Pepei di
Merbabu kau kan di foto!”
Penjelasan itu masuk akal, tapi Riang tetap merasa janggal. “Mas tahu dari siapa aku
di Bandung?” Riang menuntut memperkarakan Fidel. Dalam pikiran dia, tak mungkin orang
tahu segalanya.
“Aku bertemu orang tuamu di Thekelan.” Fidel menjawab.
“Bertemu orang tuaku?”
“Bukan hanya itu. Aku bertemu bapaknya Kardi.”
“Sekarmadji pernah datang ke pondokan, Mas tahu juga tentang itu?”
“Bentar yang menceritakannya padaku. Itu kebetulan yang luar biasa.”
Bentar menegur. “Yang!”
Riang bingung dengan setelan suara Bentar.
“Maksudmu menyebarkan desas-desus di sekitar pondokan itu, apa?!”
Riang tak siap menjawab. Ia tak memahami, mengapa hampir seluruh perbuatannya
diketahui dua orang yang ada dihadapannya. Riang bingung. Wajahnya matang.
Bla…blap…blup, Bentar menjelaskan detail peristiwa yang terjadi pada sepupunya.
Fidel tertawa. Ia pun menceritakan bagaimana mitos Merbabu mendongkrak pandangan
orang terhadap pemuda yang ada di hadapan mereka.
“Ia membuka hijab informasi!” Fidel menjelaskan pada Bentar. “Ia berhasil
memanfaatkan informasi!”
219
Bentar bersandiwara. Ia marah pada Riang. “Jadi pembelajaran yang kau dapatkan
digunakan untuk menipu penduduk di sekitar pondokan?! Jahat kau, Yang!”
Riang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Ia tertawa, dan Taryan, selaku
asisten dalam persekongkolan di terminal Dago berusaha membelanya.
“Jahat tapi hebat!” ucap Taryan bersemangat.
Riang bengkak. Wajahnya yang sudah matang dipepes menjadi merah dan kalau
sudah gede rasa sebaiknya diam.
Eva dan dua orang wanita lainnya memotong perbincangan. Mereka membawa
mangkuk-mangkuk kecap berikut racikan jahe beberapa siung bawang merah dan tomat.
Chris ikut menebas daun pisang, melemaskannya menggunakan api bersama yang lainnya.
Suasana gembira tiba. Nasi bercampur bumbu-bumbu ikan baker dihidangkan. Chris diberi
kesempatan pertama untuk mencicipi ikan bakar. Nasi dan lauk yang dihidangkan itu
menyatukan ras. Rasa menghubungkan bangsa. Inilah persaudaraan yang terjalin karena
makanan.
DINI HARI, Chris dan beberapa kawan-kawan yang lainnya pulang. Taryan, tak
sanggup lagi melanjutkan obrolan. Ia mendengkur pelan sewaktu Riang melanjutka
pembicaraannya dengan Fidel.
Riang menumpahkan isi hatinya.
“Aku hampir gila mas,” jelasnya. “Sejak Mas dan Mas Pepei datang ke desa, aku jadi
seperti ini…”
Fidel tersenyum. “Kau hendak menuntutku karena itu?”
Riang tiba-tiba mengingat ucapan Fred. “Aku gelisah!” ucapnya.
Fidel mengetahui kegelisahan macam apa yang ada di kepala Riang. Ia hanya
menjawab.“Kau sedang mengandung, Yang!” Senyumnya mencair lagi. “Kelahiranmu sudah
dekat! Kau akan melompat, melompat jauh ke depan!”
“Apa yang saat ini kau fikirkan menunjukkan eksistensimu! Bahwa kau manusia yang
sedang berfikir, manusia yang tengah berusaha menggali makna kehidupannya sendiri!”
“Ada keputusasaan di kala Kau merasa tak mampu menyelesaikannya, ada
kegelisahan yang harus ditebus karenanya. Kau tahu Yang … kegelisahan itu ibarat sebuah
canopy trail, ibarat sebuah jembatan yang menguatkan arah hidup manusia. Kegelisahan
adalah jembatan. Dan jembatan --seperti yang kita ketahui-- bukan tempat kediaman yang
nyaman … Tempat kediaman yang nyaman adalah tempat akhir, di mana kita tak perlu lagi
menanyakan apa tujuan penciptaan manusia”
220
“Tapi kegelisahanku?” Riang merajuk. Wajahnya memerah.
“Tidak boleh tidak …” Fidel menunjuk, “manusia, aku, kamu, kita haru melewati
jembatan tersebut! Hanya dengan melaluinya kita dapat mencapai tingkatan demi tingkatan
di dalam kehidupan! Ketika manusia ingin mendaki tingkatan itu, ia akan menghadapi
bermacam ujian! Jika seseorang yang ingin naik tingkat dalam beladiri, ia diharuskan
bertanding, menahan pukulan, mengelitkan tendangan. Ia memerlukan kecemasan untuk
sampai pada tingkatan, pada sabuk selanjutnya! Jika ujian itu diselesaikan dengan baik, naik
tingkatlah ia. Tetapi jika tidak, ia akan terus menerus berada di tempat yang sama! Inilah
hakikat dari ujian. Hakikat dari kecemasan dan kegelisahan yang kau alami!”
Fidel menghirup sepertiga udara yang mampu ia tampung. Menghisap dan
melepaskannya dengan santai.
“Kegelisahan adalah jembatan menuju kesempurnaan dirimu sebagai manusia…
Percayalah Yang! Kau akan melompat jauh! Tinggal menunggu momentum, Kau akan
terbang meninggalkan orang-orang disekelilingmu! Kau memiliki potensi yang besar untuk
itu! Kau wajib meyakininya! Yakini dalam hatimu! Yakini itu di dalam! Jangan ragukan!”
Ucapan itu membuat Riang adem. Rasanya pas.
“Mas tidak takut gila? Pernahkah mengalaminya?”
Fidel tersenyum.
“Mas ngin terlihat misterius ya?”
Fidel tertawa. Pertanyaan itu tepat sasaran. Fidel menerawang “Ya … aku pernah
mengalami ketakutan. Aku tahu rasanya saat kita sudah tidak bisa lagi mengkontrol
pemikiran kita sendiri. Aku mengerti bagaimana kecemasan itu membuat pikiran terlalu
berdenyar hingga kita merasa direpotkan, bagaimana mencicipi kekhawatiran yang
berdentang-dentang, kala kita berada di atas tempat tidur, kala mata kita tertutup… merasa
tersiksa dan kita mengharapkan tak akan bangun keesokan harinya …Kadang kita berandai-
andai bahwa kehidupan adalah stop kontak yang tinggal kita tekan tombol off. … clik … jika
ingin mematikannya, gelaplah semua! Tapi, adakalanya di saat-saat seperti itu kita menjadi
takut menghadapi pertanyaan: adakah kehidupan setelah kematian, akankah kita mati dan
mati saja menghilang karena tak ada kehidupan lain selain di dunia. Kita tak yakin! Kita
merasa tak mampu meyelesaikannya! Kita merasa menyesal dan merasa harus mengutuki diri
kita sendiri! …. Inilah …inilah titik kritis. Inilah ambang batas saat kita akan menjadi gila!
Tinggal satu langkah. Dan saat ini Riang mungkin sedang berada di ambang batas itu!”
Benderang sekali. Kenyamanan akan terasa jika seseorang mengetahui bahwa dirinya
dipahami.
221
“Yang kau alami itu memang berat Yang… dan semakin diperberat sewaktu
lingkungan menvonis kamu! Memvonis bahwa kau tidak memiliki keimanan! … Kau di
hakimi! Kau dibeliungi! Kau dipermalukan di hadapan orang lain dan dirimu sendiri!
…Mereka jahat! Mereka belum pernah mengalami kegelisahan, tetapi mereka menjatuhkan
persangsian pada kita! Mereka bukan mengobati. Mereka tak sadar, jika apa yang mereka
lakukan membuat seseorang yang membutuhkan jawaban, menjadi pendiam, menjadi malas
untuk membincangkan apa yang ada di dalam kepala karena khawatir orang-orang yang akan
kita temui, bakal menghantam kita kembali, menyakiti kita kembali! … Semakin dalam
kegelisahan itu datang, semakin tak ada teman untuk berbagi, maka tahukah Kamu apa yang
terjadi ketika hal itu terjadi pada orang yang mengalami kegelisahan?!”
Riang menggelengkan kepala. Ia masih inginkan terang.
“Gelisah akan mengeruhi pikiran, menumbuhkan prasangka, saat orang menyalahkan!
Betapa menyakitkan saat mendengar mereka menghakimimu, membeliungimu, mengeratmu
hingga serpih! Mereka adalah orang yang belum pernah mengalami essensi keimanan yang
harus dilalui melalui pergulatan pemikiran! Mereka masih S.D. Dan –mungkin-- selamanya
akan menjadi anak S.D.”
Fidel memandang Riang dengan tatapan sayang.
“Kau berbeda! Kau adalah manusia yang berani menjalani kegelisahan itu! Kelasmu
tidak akan mentok di sekolah dasar saja. Teruslah naik kelas, sampai ijazah kematian di
lekatkan waktu untuk dirimu!”
Fidel tiba-tiba mentertawakan dirinya sendiri. Secangkir kopi tumpah. Apa yang ia
katakan terlalu panjang. Penjelasannya terlalu meluber. Terlalu semangat, membuat dia
merasakan terlalu berlebihan.
“Mas mengerti diriku.” Riang tak peduli, ia terkesima.
Fidel bernafas lega. “Hanya manusia yang pernah mengalami keggilaaanlah yang
mengerti bagaimana rasanya menjadi gila! Dan hanya orang yang pernah gilalah, yang
mengetahui siapa yang memiliki potensi menjadi gila!” Fidel berderai.
“Mudah-mudahan kita tidak, ya Mas?”
“Tidak ada yang tidak mungkin di dunia.” Fidel bersikukuh.
“Ya … ya! Mas benar!” Riang sok tahu. “Tidak ada yang tidak mungkin di dunia
karena Adam pun ada dari ketidakmungkinan, dari ketiadaan!”
“Kau mulai berfilsafat?” Fidel berpikir, “Yang?!”
“Ya?”
“Duluan telur … duluan ayam?”
222
“Kok jadi main teka-teki?” protesnya.
“Jawab dulu saja.”
”Nyerah Mas!”
“Kok langsung nyerah?”
“Aku tidak menemukan jawabannya. Sudah kupikirkan dari dulu.” Riang ganti
bertanya, “kalau begitu jawabannya apa?”
Tanpa rasa bersalah, Fidel mengatakan tidak tahu.
“Masak yang mengajak main tidak tahu jawabannya?!” Riang menuntut.
“Kapan aturannya kalau yang mengajak teka-teki harus tahu jawaban?”
Rian diam. Dia kehabisan ucapan.
“Kukatakan tidak tahu, karena saat itu, saat ayam pertama muncul di dunia, aku
belum ada.” Fidel menjelaskan. “Aku tidak menemukan informasi berkenaan dengan siapa
yang lebih dulu, ayam atau telur dulu kah, dari sumber informasi yang aku percayai.” Fidel
mengungkit sebuah peristiwa. “Kau masih mengingat sumber informasi yang dulu pernah
kita bicarakan?”
“Yang kita bicarakan di danau Merbabu lalu?” Riang menggali ingatannya. Tapi ia
tidak bisa mengkaitkannya.
“Dalam masalah telur dan ayam aku tidak menemukan sumber informasi yang
kupercayai.”
“Masa teka-teki jawabannya seperti itu! Tidak seru!” Riang mencela.
Fidel tertawa. “Kalau mau ramai bolehlah aku berspekulasi. Kemungkinan besar …
ayam ada lebih dulu sebelum telur.”
“Mengapa?”
“Adam pengulu manusia berawal dari seorang anak. Begitu halnya dengan ayam.
Seperti halnya Adam, nenek moyang ayam bukanlah telur. Tetapi ayam itu sendiri?! Bener!”
“Aku ndak ngerti!”
“Sudahlah.”
Suasana sepi. Trilunan bintang mengkerlip di atas sana. Tiba-tiba langit membuka
diri.
Riang menunjuk. “Mas ada meteor…!”
Sambil melihat angkasa ia Fidel berkata.“Sebentar lagi hijabmu akan terbuka!”
Riang melirik ke arahnya. Fidel terus menyenteri angkasa.
Meteor berjatuhan.
Tidak satu.
223
Banyak sekali.
Ini hujan meteor!
Sebuah kejadian langka.
“Mas … aku ingin menjadi meteor!”
“Bercahaya sebelum meredup. Menjadi seperti mereka!”
“Dalam sekali ucapan Mas.”
“Ya, inilah bahasa batin antar orang gila. Tak perlu lagi penjelasan. Satu kata akan
menjelaskan yang menyamudera.”
“Aku mengerti. Aku memahami!.”
“Aku tak meragukan kemampuanmu. Tak usah Kaukatakan itu!”
“Mas?”
“Apa?.”
….
“Apa?.”
“Ndak ...”
“Sudahlah … tidur sana.”
“Aku belum mengantuk.”
“Ya sudah …” Fidel berjalan meninggalkannya.
“Mas … mau kemana?”
“Aku harus memeriksa generator!”
“Aku ikut.”
“Kau tidur saja. Hari-hari kita masih panjang.”
KATA-KATANYA ADALAH HARAPAN. Riang berdiri untuk mengakhiri. Ia
ingin berkata bahwa ia senang bertemu dengannya. Bahwa Fidel adalah anugerah. Bahwa
dialah yang merupakan satu-satunya harapan. Riang ingin mengucapkan terimakasih
padanya. Entah mengapa, Riang ingin mengatakan ia sangat menyayanginya, tetapi hal itu
urung dilakukan. Mengatakan rasa sayang pada seorang lelaki memang mengerikan!
Pertengahan malam itu hati Riang meluas … tak bertapal batas … Pikirannya menjadi
fluida, meleleh. Tubuhnya menjadi ringan, bersatu dengan alam. Ia merasa ingin terbang.
224
PERPISAHAN
Kertas-kertas yang semalam berserakan rapih kembali. Rumah kayu menjadi bersih
seperti sedia kala. Beberapa orang yang berdiskusi tadi malam, pulang. Beberapa lainnya
berangkat memancing.
Riang tidur terlampau nyenyak. Ia seperti di-anastesi. Bentar dan rombongan
pondokan –termasuk Taryan—telah lama pulang. Sarapan mie yang disediakan Eva telah
berubah menjadi dingin. Riang bangun setelah lampu mulai berkelap-kelip seperti arklilik.
meredup, nyala, meredup, nyala selama beberapa detik hingga Riang yang tengah berbaring
di bawahnya khawatir terkena ledakan bohlam.
Fidel masuk ke dalam rumah menyaksikan pekerjaannya lalu kembali membenahi
peralatan.
“Taryan pulang dini hari.” Jelasnya sambil mematikan saklar. Fidel mengajak Riang
sarapan. Mereka menyelesaikannya lalu keluar rumah, jalan-jalan, bertawaf mengitari lahan
pertanian.
“Tanah ini luasnya hampit dua hektar.” Fidel menunjuk batu. “Dari ujung sana …”
ia mengalihkan telunjuknya menuju pohon cemara bercabang dua, “Bentar yang mengajakku
mengelola tanah ini. Baru sepetak yang kami tanami sayuran.” Fidel menoleh. “Kau mau
membantu mengelolanya? Kami, aku dan Bentar tak sanggup melakukannya.”
“Mengelola tanah ini Mas?”
225
“Iya.”
“Taryan bagaimana?”
“Dia boleh ikut.”
“Asyik! Asyeeiiik!” Diliputi kesenangan tingkat tinggi karena mengetahui bahwa
dirinya akan kembali bekerja seperti halnya seorang pemuda Thekelan bekerja, Riang berlari
ke sana-kemari seolah lahan itu merupakan pekarangan taman bermain anak-anak. Riang
terus berlari, hingga suruk di rawa-rawa, membuat baju dan celana dia satu-satunya kotor
terendam lumpur.
Siang harinya Riang menuju kepondokkan. Ia mengambil pakaian tanpa diantar,
menemui Taryan dan membujuknya.
“Bantu aku Yan!”
“Bagaimana dengan kerjaanku?” Taryan diam.
“Aku yang bilang ke Bentar!” Riang pasang badan.
“Bukan itu,” Taryan tertawa. “Apa Situ ndak kasihan sama Bentar kalau aku harus
keluar kerja? Ini masalah kepercayaan. Kalau aku keluar akhir bulan ini, bagaiman nasib
orang baru di pondokan, orang baru yang nantinya butuh pekerjaan? Apa Situ ndak mikir?
Nanti atasanku bakalan ndak percaya sama Bentar karena orang seperti aku ini, seenak
udelnya keluar karena alasan sepele. Alasan bisa di buat tapi aku pantang berbohong.
Lagipula …” Taryan menghela nafas, “mertuaku sudah kirimi aku kabar mengenai keadaan
di Magelang.”
Riang tahu apa yang akan dibicarakan. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya
pura-pura tertawa. Riang merasakan sesak.
“Yang?” tanya Taryan tampak ragu-ragu. “Awal bulan depan aku pulang. Uang
simpananku sudah lebih dari cukup untuk membiayai perjalanan pulang.” Taryan tahu Riang
lemas.
“Bagaimana dengan penduduk Desa dan Karno?” Riang memaksa bertanya.
“Keadaan di desa aman. Beberapa bulan sejak kepergianku Karno ditangkap. Ia
kembali berbuat onar.”
“Karno pasti kapok membuatmu begini.” Riang tak memiliki harapan. Ia menepiskan
kekecewaan,
Taryan tersenyum. “Ya, Karno pasti malu padaku.”
“Kau akan membalas perlakuan orang-orang di desa, Yan?”
226
Taryan melambungkan pandangannya, “Untuk apa? Katanya. “Semua hal yang
kualami sudah ada ketentuannya. Semua sudah digariskan. Dia berkehendak agar aku keluar
dari desa, menemui orang-orang di sini, menemui Situ. Hidup seperti ini memberiku banyak
hal. Banyak yang kudapatkan.”
“Pasti banyak sekali!” Riang tersenyum. Ia mulai mengikhlaskan kehendak Taryan.
“Pokoknya, kalau Situ pulang, jangan lupa memberitahu! Jangan membuatku marah seperti
pagi tadi!”
“Tadi pagi apa?!” Taryan mengelak.
“Kau tinggalkan aku di rumah Fidel!”
“Lha, aku sudah membangunkanmu!”
Riang murung.
Nafas Taryan terhempas. Ia mengatur pernafasan. “Aku pasti bilang Yang,” angguk
Taryan dalam. “Yang … terimakasih untuk segalanya,” nada suara Taryan tertekan.
“Terima kasih untuk apa?”
“Untuk perhatianmu ketika aku sakit … atas perhatianmu … atas segalanya,
semuanya! Terima kasih atas kesetiakawananmu … atas bimbinganmu!”
“Sudah-sudah tak perlu begitu! Kalau mau pergi, pergilah sana!” humor kuli Riang
keluar. “Pergi Kau! PERGI SANA!”
Retina mata kedua orang itu bocor. Ada air yang mengucur, meninggalkan bekas
yang hangat di hati, membuat siapapun yang tidak pernah merasakan panasnya api
persahabatan cemberut.
RIANG LUPA pesan Fidel untuk membawakan buku harian Pepei. Sore itu fokusnya
hanya berkemas, melupakan buku yang juga penting bagi Fidel. Ia memasukan seluruh
barang yang dimilikinya. Keesokan paginya, Riang kembali ke rumah kayu Fidel. Pemilik
pondokan tidak mengantarnya hingga pagar. Mereka tahu, sesekali, Riang masih akan
menginap di pondokan.
Beberapa hari kemudian Riang kembali ke pondokan. Tidak ada satu orang pun di
sana. Taryan masih bekerja. Bentar mengantar Eva yang sedang mengikuti tes. Bosan
menunggu, Riang menemani Fidel belanja persediaan makananan. Setelahnya, di tengah
jalan pulang menuju pondokan, ia melihat Taryan menyetop angkutan. Dipikirnya, Taryan
yang akan lebih dulu sampai di pondokkan. Ternyata tidak. Sejam kemudian wajah
sahabatnya yang tengil itu tampak. Taryan menjinjing empat buah kantung hitam besar.
227
Taryan menghempaskan tubuhnya. Ia memberikan satu kantung untuk Bentar dan
Eva, dan meminta maaf karena tak bisa membalas budi baik keduanya
“Maaf! Maaf! Lebaran masih lama!”
Komentar Bentar usai mereka mengatakan terimakasih membuat Taryan tertawa. Ia
kemudian mengambil sebuah kantung hitam lainnya. “Ini untukmu!” katanya. Ia
menghadiahi Riang sebuah buku tulis tebal bergembok. Kantung lainnya berisi makanan
untuk orang-orang yang berkumpul di pondokan.
“Lainnya lagi?” Agus mendesak. Anak itu melihat beberapa kantung yang belum
jelas pemiliknya. Taryan tersipu ketika Eva menegur anak kecil itu. Barang-barang di dalam
kantung-kantung yang tersisa itu untuk Radia anak dan keluarga Taryan di Magelang.
Malam ini menjadi malam penghabisan antara Riang dan Taryan. Orang-orang yang
mengenalnya bermain habis-habisan. Suara biola Bentar dan gitar yang bermantra
mempertemukan kegembiraan yang ada di dalam hati dan mencuatkannya. Masing-masing
berusaha memberikan kemahiran, memaksimalkan apa yang mereka miliki untuk membuat
Taryan gembira.
Malam itu Riang tidak mengatakan sesuatu yang berharga untuk Taryan, namun
Riang meyakini adanya keberadaan ikatan yang sulit dipahami kecuali oleh orang yang
mengerti. Jika bahasa lisan tidak selalu mewakili keadaan yang sebenarnya untuk apa
seseorang melisankan. Riang tidak mau memaksakan dirinya, ia tak mungkin bisa, karena
bahasa yang agung iu tak bisa diwakilkan keluasannya oleh lidah manusia yang terbatas.
Riang diam dan membiarkan simbol bahasa yang menyemesta berjalan alami apa adanya.
Ke dua orang ini pun tidur saat pertengahan malam menjelang. Wajah mereka terlihat
teduh tanpa tekanan, minim beban seperti bayi pada sebuah mobil yang melaju kencang di
sebuah jalur bebas hambatan.
Saat saat yang tak Riang harapkan itu datang. Derit—derit roda besi yang memasuki
stasiun, menunggu ribuan orang sebelum gerbongnya beranjak menuju arah tempat terbitnya
matahari di ufuk timur. Riang berharap, jalur yang Taryan tempuh bersama kereta itu akan
membawanya kepada kebenderangan, menuju arah kebahagiaan.
“Yan?!” Riang berusaha menutupi kesedihannya.
“Apa?”
“Situ ndak layak lagi dihina. Kalau situ bertemu dengan petugas yang dulu
menendangmu perlihatkan seluruh kekayaanmu! Sombongkanlah tiketmu! Pelihatkan uang
kertas yang kau kumpulkan itu! Biar dia tahu Yan!... Biar mereka tahu.”
228
Taryan yakin tidak akan bertemu dengan petugas sialan yang pernah ia ceritakan pada
hampir semua penghuni pondokan. Di balik jendela kereta, Taryan menunduk. Wajahnya
muram.
“Yan!” Riang membentak. “Jangan seperti itu!” ia menegurnya. “Ayo ketawa
Yan!.Ayo ketawa! Sama-sama ketawa!
Riang tertawa seperti terpaksa. Ia mengeluarkan tangannya dari jendela.Fidel, Bentar,
dan Eva memahami permainan emosi saat mereka mengantar Taryan pergi.
“Hua...ha...ha...ha!.”
“Hua...ha...ha...ha!.”
“Teruslah tertawa Yan!...teruslah tertawa! Jangan pernah berhenti mentertawakan
dunia! Jangan pernah bersedih! Terus tertawa! Jangan berhenti!”
Taryan terbahak-bahak! Ia tak tahu apa yang harus ditertawakan tetapi mulutnya
terbuka. “Hua… ha… ha… orang gila! Orang gila!”
Riang tertawa diejek Taryan. Ia berteriak ketika roda kereta berputar pelan. “Aku
selalu mendoakan! Kau senantiasa kudoakan!”
Riang terseguk.
Selamat jalan kawan! Berkah kepulanganmu itu... adalah milikmu. Kali ini, jangan
biarkan orang lain merampasnya! Rebutlah kebahagiaan bersama Radia dan anakmu,
....bersama keluarga besarmu ...
Doa Riang Merapi menyertai langkah panjangmu!
Kereta menjauh lalu hilang ditelan kelokan.
229
METEOR
Fidel mengetahui bagaima posisi Taryan di mata Riang. Ia mengetahui bagaimana
kekosongan yang dialami, ketika seseorang yang lama mengisi hidup kita tiba-tiba hilang.
Ada kekosongan yang membuat kenyataan seperti soda pada sebuah kaleng minuman. Fidel
memikirkan apa yang harus ia lakukan untuk membantu Riang --secara alami-- cepat keluar
dari situasi yang membuatnya selambat moluska.
Saat membaca buku catatan Pepei, Fidel melihat Riang tengah memperhatikan ikan di
tepian kolam. Fidel memanggilnya. “Ada yang ingin kuberitahu,” ujar Fidel usai memberi
batasan pada buku yang baru saja ia tutup.
Fidel keluar dari rumah dan mengambil banyak langkah. Riang mengikutinya. Di
dekat bukit suara jangkrik makin berisik. Krik krik krik! Membuat kuping terasa berdenyit.
Fidel masuk ke dalam hutan. Tak begitu jauh dari batas hutan dan lahan pertanian, ia berhenti
di depan sebatang pohon yang dikelilingi semak-semak. Fidel menerobos. Riang mengikuti
jejaknya di atas semak lebat yang terkuak. Gundukan semak-semak hampir kembali pada
posisinya saat ketika Fidel jongkok, meraba-raba sesuatu di kakinya. “Mundur,” Fidel
memberi perintah. Suara penghalang terdengar. Ada sesuatu yang terlepas. Sebuah pintu
kecil besi yang menempel di tanah terbuka.
Riang tegang Tempat apa ini. Fidel menuruni tangga. Riang mengintip di luar.
Fidel memberi isyarat pada Riang untuk terus mengikutinya. “Tutup pintunya!” Riang
mengambil gagang pintu, menutup pintu karatan itu dari tangga yang kemudian ia jejak. Ia
terus turun ke bawah, masuk ke tanah.
230
Bertemu lorong yang datar Riang melihat sebuah ruangan kecil yang nyaman. Udara
di ruangan itu terasa dingin tetapi tidak terasa lembab. Sebuah lorong rahasia –lainnya--
tempat angin bertukar sapa sebelum keluar masuk membersihkan udara, membuat tempat itu
sehat. Di sudut ruangan sebuah meja tertancap di lantai tanah. Tangga berulir yang terbuat
batu bata tak disemen menjadi penghubung ruang yang ada di atas. Sebuah ranjang besi,
termos dan gelas kosong tertata rapi. Rak-rak buku berjejer melebihi koleksi yang pernah
Riang lihat di tempat Pepei.
“Ini, untuk membuka pintu besi yang tadi kita lewati.” Fidel memberikan duplikat
kunci pada Riang yang terperangah. “dan ini,” lanut Fidel, “untuk jalan masuk yang
satunya.” Fidel melemparkan satu duplikat lagi. Riang menangkapnya.
“Habiskanlah waktumu di sini. Tapi jangan ingkar. Kau tidak boleh memberitahu
siapa pun mengenai ruangan ini.”
Fidel membuka pintu diatas kepalanya, keluar dari ruang bawah tanah. Naiki tangga
yang sama, Riang masih mendengar langkah orang di atasnya, namun setelah kakinya
menjejak lantai atas, ia tak mendengar langkahnya bergema, menandakan ada ruangan
kosong di bawahnya. Riang mendapati dinding dapur mengepung dirinya. Riang berdecak.
Riang kembali ke bawa, matanya terpaku pada rak-rak yang terkesan tua namun bersih, tidak
tampak kusam. Di dalam ruangan bawah tanah ini, Riang menemukan kesenangan
mengakses ilmu pengetahuan yang dipenjarakan ke dalam onggokan kertas. Riang
menjelajahi rawa, ngarai, gurun pasir, pasir hidup, atmosphere, ia meniti jalan menuju
mercusuar pemikiran. Ia melewati batas-batas negeri tanpa harus membeli visa dan paspor,
masuk ke dalam situasi genting dunia, mengintip tragedi, menyaksikan ironi, beringsut
menuju pemakaman cerdik cendikia dan mempelajari satire dunia. Ia merasa lingkungannya
yang dulu mengecil. Semakin lama ia berada di ruangan ini, ia semakin merasa mungil
melebihi kecilnya proton dan neutron. Riang menganggap dirinya disterilisasi, di bakar api
spirtus yang menjadikan kesadarannya gerah berkobar-kobar.
RUMAH KAYU FIDEL berada di tengah lahan di antara puncak bukit berbentuk
seperti laguna. Dengan halaman depan yang menantang matahari, rumahnya disinari cahaya
matahari sampai jam 10.00 pagi. Setelahnya, tak beda dengan cuaca di Thekelan. Tempat itu
menjadi dingin. Jika sore datang hampir semua benda-benda di sana jadi berbayang.
Fidel mebersihkan tangan, dan kakinya di aliran air yang mengucur deras ke dalam
kolam. Ia mengelap muka dengan handuk putih. Riang menunggunya, melihat rumah-rumah
231
dan jalan tol yang memanjang seperti sungai. Pabrik-pabrik yang mengeluarkan asap setiap
hari membuat nafas orang-orang menjadi sesak.
“Apa yang Kau pikirkan?” Fidel datang setelah menyelesaikan ibadahnya.
Riang menanti Fidel untuk membicarakan ruang bawah tanah yang beberapa jam lalu
ia masuki. Riang memberi Fidel air putih yang hangat, menanti. Ia tak mendengar penjelasan
apa pun. Fidel tidak menganggap apa yang ia tunjukkan sebagai suatu keanehan. Hingga
malam tiba Riang merasa Fidel tak akan membicarakan hal itu. Ia pun berusaha menganggap
ruang bawah tanah sebagai sesuatu yang biasa.
Malam ini Riang merasa tubuhnya letih, usai mengolah lahan pertanian, tetapi ia
masih menyempatkan diri mengambil setumpuk buku dari ruang bawah tanah. Lelah tidak
membuat keingintahuan Riang lenyap. Ia menekuni lembaran demi lembaran ensiklopedia di
tangannya. Di sampingnya Fidel diam tak bicara. Ia memandangi tulisan tangan Pepei
sahabatnya. Setelah agak lama, ia menutup buku catatan itu. Di samping Fidel terdapat
sebuah radio transistor.
“Apa arti Pepei untukmu?” tanyanya tiba-tiba.
Riang memandangi Fidel. “Mas tahu Emha?” Ia melantur. Ia tak mendengar
pertanyaan itu. Fidel membiarkan Riang untuk sementara. Ia melantur tanpa dosa.
“Di Yogyakarta kami mencari Emha. Aku meminta tolong mas Pepei membantuku
mencarikannya.”
“Emha Ainun Nadjib?”
“Sebenarnya bukan Emha yang itu.” Riang menceritakan kesalah pahaman yang
diakibat jawaban ngasal bapaknya. “Emha lain yang mengajari kakekku untuk mengenal
lebih dalam tentang Islam.”
“Tapi, akhirnya Kau bertemu Emha?”
Riang tertawa. “Tidak, akhirnya ya hanya numpang tidur di tempat mas Pepei. Mas
…” tanya Riang hati-hati seolah di tempat itu ada orang lain selain mereka.
”Aku bertemu orang aneh di sana!”
“Orang aneh?”
“Mas kenal Mahdi?.”
Fidel tak menjawab. Wajah Fidel sedikit berubah. “Apa yang ia katakan?” tanyanya
“Aku diajak Mahdi membunuh Tuhan!” jawab Riang tanpa tendeng aling.
Fidel tersenyum. Ia memainkan tombol on transistor yang dekat dengan tangan
kanannya. Sebuah lagu terdengar lamat..
232
“Aku tak suka Mahdi mendesak-desakku, Mas. Dia seperti orang kerasukan! Mahdi
atheis!” ” Riang mengadu.
“Waktu itu ada Pepei di sampingmu?”
“Tidak ada, tapi Mas Pepei mendengar apa yang diucapkan Mahdi. Aneh,” ungkap
Riang. “Mas Pepei justru membelaku.”
“Di mana letak keanehan itu?” tanya Fidel.
“Waktu antar aku pulang, Mas Pepei juga begitu.”
“Begitu bagaimana?.”
“Ia tak percaya Tuhan. Dia atheis,”
“Anehnya di mana?”
“Kenapa dia malah membelaku?”
“Bukannya membela Mahdi maksudmu?” tanya Fidel
Riang memberi isyarat setuju. Nafas Fidel lembab. “Ada konsep keadilan di
kepalanya … Pepei fair.” Jawab Fidel. “Ia mempercayai manusia tidak bisa dipaksa untuk
mengambil sebuah keyakinan. Keyakinan adalah kesadaran, bukan proses pemerkosaan,
bukan pengagahan kesadaran.” Fidel menghirup air hangat di tangannya. “Pepei atheis yang
shalih … atheis yang santun,” sahutnya.
“Mereka sama-sama tak percaya Tuhan, mengapa mereka saling berseteru?!” tanya
Riang.
“Dia …” nafas Fidel tak berarturan, tak beritme. Ia merindukan sahabatnya. “Pepei,
satu diantara lelaki yang paling fair yang pernah kutemui. Ia akan mengatakan benar
seandainya benar. Ia akan mengungkapkan salah seandainya salah. Ia membela siapa saja
tanpa memperdulikan keyakinan seseorang itu apa. Ia menganggap apa yang Mahdi lakukan
bukan saja keliru tetapi salah”
“Mengapa Mahdi harus membenci Mas Pepei separah itu?”
Fidel berusaha berkelit. “Tak baik membicarakan orang,” katanya, namun kemudian
ia berpikir, “tapi, okelah, ... maaf,” Fidel menimbang, “Mahdi itu salah didik. Pikirannya
yang sudah terbuka ia hamba sahayakan pada mentornya yang batu. Atheis kepala batu
merusak Mahdi, menghilangkan kemanusiaannya. Mereka memecah belah hubungan
persahabatan antara Mahdi dengan Pepei. Mereka menanamkan kebencian pada diri Mahdi
untuk membalas pikiran Pepei yang tidak sesuai dengan maksud yang mereka inginkan.
Mereka menjadikan Mahdi manusia liar. Mahdi dididik untuk menganggap orang lain
sebagai sahayanya. Mahdi dididik beranggapan bebas untuk memperlakukan orang lain di
luar keyakinan dia sekehendak hatinya.”
233
“Mereka siapa?!” tanya Riang sok-sok menyelidiki. “Siapa orang atheis batu yang
Mas bilang itu, apa aku mengenalnya?”
“Tak perlu tahu sedetil itu,” senyum Fidel terlihat samar. “Aku malas bergosip,” kata
Fidel singkat.
“Yang masih sulit kupahami,” sambung Riang, “mengapa orang yang tak
mempercayai Tuhan bisa berseteru, padahal keyakinan mereka sama?”
“Aku sudah menjawabnya, Yang?” Fidel tertawa memikirkan jawaban yang baru
saja ia sampaikan kurang tepat sasaran.
“Yang mana…?”
“Sssst…sst…” bisiknya. Nada piano yang dikenal Fidel, tiba-tiba mengalun.
“Dengarkan ini.” Transistornya bernyanyi
“Imagine there’s no heaven
It easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine theres no country
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion to
Imagine all the people
living life and peace
you may say i am dreamer
but iam not the only one
I hope someday you will join us
And the world will lives as one.
Riang memperhatikan Fidel. Wajahnya menuntut jawaban. Apa maksudnya?
“Jhon Lenon!” pekik Fidel.
“Masa jawabannya Jhon Lenon?”
Tawa Fidel pasang. Usai tawanya surut ia menjelaskan. “Yang menyebabkan
manusia saling berseteru bukan hanya karena satu hal. Banyak faktor Yang! Manusia itu
bukan benda! Manusia itu memiliki jiwa dan jiwa bisa dipengaruhi beragam hal! Dendam!
Kebencian yang mengakar! Kecemburuan! Banyak hal! Atheis dengan atheis bisa saling
234
menghantam! Agnostik dengan agnostik bisa saling berseteru, yang beragama dengan yang
beragama bisa saling memutilasi karena persoalan sepele! Manusia itu tidak sepenuhnya
berjalan dengan nilai yang diyakini, karena manusia adalah manusia .. Banyak faktor yang
mempengaruhi tingkah lakunya. Sumber kericuhan di dunia ini, bukan serta merta karena
agama atau anti agama, tetapi terkadang, karena manusia itu sendiri.”
Perkataan Fidel mengganggu kesimpulan Riang tentang agama. Dulu ia berpikir
untuk apa beragama? Ia tak mau agama yang timbulkan kekacauan. Ia tak mau beragama
karena beragama pun bisa menimbulkan konflik.
“Apa mas Pepei tidak pernah menimbulkan kericuhan, tidak pernah menjadi
penyebab konflik?!”
“Bukannya tidak suka, tetapi sangat jarang,” jawab Fidel. “Konflik hanya jika
dibutuhkan. Apa yang terjadi di gerbang kuburan Thekelan itu, perlawanan yang kita lakukan
adalah konflik. Di pihak kita, dan pihak siapa pun juga yang masih memiliki akal yang
jernih, sesuatu yang gerombolan Kardi lakukan merupakan kesalahan, dan karena Pepei
memiliki keberanian, dan karena kamu juga memiliki keberanian, kita melawan mereka.
Konflik yang Pepei lakukan tidak muncul karena dengki, iri hati. Bukan karena permasalahan
sepele, bukan karena ingin merampas hak, menindas orang lain hingga menimbulkan
kekacauan. Pepei jarang menimbulkan kericuhan.”
“Mengapa jarang?” Riang masih tidak puas.
Fidel hanya menjawab. “Karena almarhum adalah manusia!”
“Apa mereka yang berseteru bukan manusia?”
“Manusia! Mereka manusia …” ” untuk pertama kalinya, Riang melihat Fidel
menggaruk kepala. “Sulit aku memaparkan…”ujarnya. “Suatu saat, suatu masa, kau akan
mengerti, kau akan memahaminya, bahkan hingga tulang ekor.” Fidel tersenyum.
“Tulang ekor?”
“Tulang sulbi maksudnya.”
“Tulang sulbi? Aku tak mengerti.”
“Sudahlah!” Fidel kesal.
“Tak bisa sekarang?”
Fidel Head banger, ekstrim goyangkan kepala.
“Kok bisa-bisanya Mas berteman dengan mas Pepei? Apa karena kalian manusia?”
Fidel tersenyum. “Kami bukan manusia! Kami primata sejenis anoa!”
“Anoa bukan primata Mas.” Riang membantah. “Anoa itu mamalia!”
235
Fidel menggelengkan kepalanya, Penjelasan Riang hampir patahkan lehernya. Susah
juga berbicara dengan pemilik ilmu biologi sekaliber Riang. Bagaimana jika dihadapannya
adalah ahli biologi molekul, bagaimana dengan kimia biologi? Apa yang harus Fidel
sampaikan jika Riang adalah profesional dalam kajian biologi moral versus biologi
prostitusi? Fidel menyerah.
“Sejak dahulu kami bersahabat,” kata Fidel. “Segala hal yang paling buruk dan yang
paling baik pernah kami lalui bersama. Aku mengetahui sejak kapan ia berubah dan
sebaliknya pun demikian. Kami sadar, setiap manusia memang harus berubah. Semua orang
harus mencari jati dirinya sendiri. Semua punya pilihan, tapi, untuk persahabatan … aku
menerima Pepei apa adanya seperti saat pertama kali aku mengenal dia. Aku menghargai
prinsip Pepei. Aku memaklumi atas pilihan yang dilakukannya. Jalan orang memang
berbeda, tetapi perbedaan keyakinan itu tidak akan membuat persahabatan kami hancur.”
”Tidak seru kalau tidak ada musuh-musuhan!”
“Kami pura-pura musuhan.” Fidel meyakinkan. “Biar terkesan membiarkan,
meskipun terkesan tak saling memperdulikan keyakinan masing-masing, sebenarnya proses
alami melalui diskusi tengah kami jalani. Tidak ada doktrinasi. Kami saling menyayangi,
lagipula apakah Pepei memang pantas dimusuhi?”
Kata-kata Fidel menghunjam.
“Mas?”
“Ya?”
“Aku ingin segera melewati kegelisahanku!”
“Kenapa harus dilewati?” Fidel mengetes Riang.
“Karena kegelisahan adalah jembatan!” jawab Riang menduplikasi perkataan Fidel
beberapa hari yang lalu.
Fidel protes. “Itu perkataanku, bukan perkataanmu!”
”Terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa ku selesaikan,” Riang memberengut.
“Terlalu banyak pertanyaan yang membuatku tidak waras!”
Suara panggilan tiba-tiba terdengar.
“Sudah maghrib,” Fidel mengingatkan. Waktu berbincang sudah habis. “Mudah-
mudahan aku memiliki kunci agar Kau mampu membatasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa
membuat hidupmu tak nyaman.”
Riang mengerti. Ia berdoa agar kuncinya pas.
Fidel menggulung celana. “Jadi…”
“Jadi apa Mas?.”
236
“Jadi … apa arti Pepei untukmu?”
Riang tak menemukan kata yang tepat. Ia tidak bisa memastikan adonan pada loyang
yang pas. Riang hanya mengungkapkan perasaannya pas-pasan. “Mesti sekejap, bagiku …
Mas Pepei demikian berarti.”
Mata Fidel berair. “Seperti meteor!” ucapnya lirih.
Riang tak berani melihat Fidel. Ia mengalihkan pandangan ke atas bukit yang sepi.
Malam ini Riang tak mau menganggunya. Ia membiarkan Fidel menyepi … menggali sunyi.
237
TUHAN
Riang memandangi album foto. Seperti kebiasaan orang, ia memandangi wajahnya
sebelum melihat wajah dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Merapi terlihat tampak kukuh
seperti raksasa rahwana: sombong dan culas, selain itu tampak kibaran bendera, tawa Pepei
dan keseriusan Fidel, bolongan batu serta tebing-tebing yang gagah. Riang mematung. Ada
jutaan kesan, yang menumpuk di kepalanya Ia mengetahui sekuat apa desir angin di sana, ia
masih menangkap kesan ketakutan yang ditampakkan wajahnya saat suasana genting terjadi
manakala gerombolan Kardi memburu mereka. Riang teringat Pepei. Rasanya kejadian itu
baru saja berlalu sementara di rumah kayu Fidel ia sudah menjalani hidupnya selama enam
bulan.
Riang memasukan album kenangan itu kembali. Ia melihat jajaran rak buku.
Diambilnya buku yang belum ia selesaikan. Halaman terakhir yang ia baca dinodai tanah
lahan pertanian yang kemarin ia olah. Buku itu menjadi salah satu bukti bagaimana pemuda
itu membaca buku sekenanya di mana saja: di tepian kolam, di air terjun, di bangku teras
rumah, di kamar mandi, di ruang bawah tanah. Di mana-mana Riang membawanya, mengejar
sesuatu yang ia anggap tertinggal.
Ia pernah ditegur Fidel karena menaruh buku di atas batu. Kalau tak hujan sebenarnya
tak apa, Fidel tak akan menegurnya, tetapi buku yang ia tinggal sembarangan itu menjadi tak
karuan bentuknya, menjadi lepek. Antar antar halaman menjadi rekat tak bisa dibaca kecuali
setelah Riang menjemurnya hingga menjadi kering. Kecerobohan Riang itu terjadi untuk
yang kedua kalinya, setelah secara tak sengaja pula ia mengubur ensiklopedia ke dalam
lubang yang akan Waluh jadikan lubang percobaan biogas.
Membaca membawa perubahan berarti pada Riang. Ia membaca, kemudian bertanya,
dan membahas hal-hal yang tidak bisa dijangkau pikiran, atau membahas pertanyaan yang
senantiasa menziarahi dirinya. Saat membaca folklore Riang membandingkannya dengan
pencatatan yang merupakan salah satu teknik pendokumentasian ilmiah. Menyadari
kelebihan dan kekurangan metode itu Riang menjadi terobsesi untk melakukan pencatatan.
Buku yang diberikan Taryan menjadi hadiah yang berguna baginya. Apa pun yang ingin ia
tanyakan, yang ingin ia hafal dan yang ingin ia kembangkan ia tulis di dalam bukunya.
238
Ketika membaca perikehidupan dan kronik peradaban serta biografi tokoh yang ada di
dalamnya, Riang digugah oleh birahi keingintahuan akan kebangkitan dan keruntuhan
bangsa-bangsa. Tatkala ia melakukan korespondensi antar alam pikiran, ia merasa menjadi
pelari marathon yang tertatih-tatih kehabisan nafas.. Manakala eksplorasinya menerabas alam
eksakta, ia mengakui kelemahan dirinya. O betapa mulianya ilmuwan yang membantu
kehidupan material manusia. Ah Riang bukan saja menjadi pelari marathon. Ia melakukan
thriathlon. Ia memasifkan kerja otak yang diimbangi dengan kerja fisiknya di lahan
pertanian. Riang merasa segar. Fase ini ia rasakan seperti meminum jus bianglala melalui
cangkir piala. Ini fase carpe diem, fase mimesis, momentumnya berdansa tango, menjadi
swingger, bergoyang dombret sambil memainkan kolintang. Ini fase teriakan parau Sid
Vicious pada lirik pertama Anarki in U.K menuju lengkingan lulusan les musik Sebastian
Bach dalam lirik “good by to blues-nya” Yngwy Malmsteen.
Riang kesurupan! Kemasukan bukan dalam kegelisahan, tetapi gila dalam melakukan
pencarian, menapaki kebijaksanaan. Riang merapihkan folder pikirannya. Ia satu langkah
menuju pemikiran yang mapan. Ia berada di bawah alam kedewasan untuk memilah dan
memilih madzhab pemikiran. Tempatnya berteduh kini memberi banyak makna. Semua yang
pernah ia alami: asuhan orang tua, kehidupan masa SMA, pendakian yang mempertemukan
dirinya dengan Fidel dan Pepei, jalanan, pondokan Bentar, rumah kayu, SNB dan bermacam
peristiwa lain ia rasakan manisnya karena ia dapat menarik hikmah di balik kejadian yang
telah ia lewati..
Riang mengembalikan kembali buku yang rusak oleh hujan. Sebelum keluar dari ruangan
bawah tanah dan menaiki tangga, tiba-tiba Riang merasa ragu mengunci pintu besi. Ia
mengambil senter dan berjalan hingga ke ujung lorong. Pintu sudah terkunci namun ia malah
membukanya kembali. Suara jangkrik terdengar. Ia menyibak dan berjalan merebahkan
semak-semak, menuju sebuah pekarangan luas di pinggiran hutan yang secara alamiah
rumputnya lembut dan tumbuh sejajar, sama rata. Sampai di tempat itu ia duduk
mencangklong.
Petak yang terbuka menghadapi lembah. Angin menyisir rambut Riang. Lahan datar
yang Riang olah di bawah petak tanah --yang saat ini tengah ia duduki-- tinggal menunggu
panen. Bulan menyirami lahan itu dengan sinarnya. Lampu jauh hotel berbintang lima
menyorot ke angkasa . Riang teringat. Di awal kedatangannya ia merasa tidak bisa
membatasi gondola pertanyaan yang berlayar di sungai pikirannya. Ia teringat bagaimana
Fidel menjanjikannya kunci pembuka agar ia tak terlalu kewalahan menghadapi aliran
239
pertanyaan yang mengendap di kepalanya. Ia mengingat bagaimana Fidel meletakan
punggungnya lalu bersandar di batu.
“Pohon tumbang yang menghalangi jalan kita di Merbabu dulu pun dikeroposi
waktu.” Fidel memulai pembicaraan menggunakan bahasan siklus kehidupan. “Matahari
yang merajai angkasa pun memiliki durasi. Umur! Setiap mahluk memiliki umur sendiri!
Manusia adalah mahluk, yang juga akan mengalami akhir yang sama dengan mahluk lainnya.
Manusia berada dalam kungkungan waktu dan dikeroposi oleh waktu secara alamiah. Kita
lahir sebagai bayi, beranjak dewasa, merenta, kehilangan energi, lalu mati! Kesadaran akan
keberakhiran ini akan melahirkan pertanyaan mengenai awal dan bagaimana menjalani
kehidupan. Ini masalah klasik dari awalan manusia ada hingga saat ini saat.”
Masih terbayang di pikiran Riang, suatu masa ketika Pepei berkata dalam pertemuan
penghabisan dengannya. ” ... kau bisa berlari dan boleh berlari dari pertanyaan mendasar
mengenai tujuan hidup yang terus menerus menuntutmu!”
“Aku tidak mau hidup setengah-setengah Mas.” Kata Riang. “Aku harus
menuntaskan pertanyaan yang memusingkan ini.” Riang mengeluh, “aku … aku, lelah
dengan ketidakstabilan ini! Aku tidak ingin bersembunyi. Aku tidak ingin terus alami
ketidakpastian! Aku ingin memecahkannya!”
“Ya, Kau akan memecahkan!” ujar Fidel memberi sugesti pada Riang, “Kau akan
menstrukturkan, mensistematikakan pertanyaan juga pikiranmu!”
“Bagaimana agar bisa, bagaimana caranya?”
“Awalilah dengan mempercayai Tuhan, atau menafikannya, bahkan malah tidak
memperdulikan keberadaan atau ketidakberadaan-Nya sekalian!”
Kepala kopong. Riang tak paham.
“Theis: percaya Tuhan, atheis: menafikannya, agnostik: tidak mempedulikan ada atau
tidaknya.” Fidel memaksa. “Kau harus memilihnya!”
“Aku tak bisa memilih, aku tak tahu harus memilih apa!”
Riang tersenyum.
“Yang membuat kita kelimpungan, yang membuat kita gelisah dicereweti begitu
banyak pertanyaan dikarenakan banyak hal. Bisa jadi karena kita belum menemukan untuk
apa tujuan hidup di dunia, belum bisa menjawab dari mana kita berasal, dan akan kemana
setelah tubuh kita ini habis fungsi, mati. Bisa pula, karena kita tidak mengetahui sejauh mana
kinerja akal kita berkerja, seluas apa cakrawalanya, selebar apa jangkauannya.”
“Orang yang telah mendapat jawaban asal muasal sert tujuan akhir yang dicapai
setelah kematian, biasanya akan mengetahui tujuan hidup dia yang sebenarnya. Kehalauan,
240
kegelisahan akan mudah ia atasi. Hidupnya akan di warnai makna, dan lebih dari itu, ketika
ia telah mengetahui sampai di mana batasan berpikir, maka ia akan dengan mudah
mengumpulkan, mengorganisasikan pertanyaan mana yang benar-benar harus ia pikir dan
cari jawabannya dan mana pertanyaan yang sekedar ia jadikan tamasya di alam pikirannya.”
Tentu, Riang tak memahami utuh apa yang diungkap Fidel, namun ia menangkap
substansinya..
“Tamasya? Sepertinya asyik,” Riang membayangkan.
“Jika Kau sudah memiliki struktur berpikir dan mengetahui batasan-batasan yang tak
mungkin Kau jangkau dengan kekuatan akalmu, maka pertanyaan yang dulu Kau anggap
menyeramkan, menakutkan, mendirikan bulu kuduk akan Kau anggap sebagai hiburan. Jika
Kau memahami tamasya pikiran, kau akan mengetahui mana pertanyaan yang mengalihkan,
yang mengombang-ambingkan dan Kau hanya akan menganggap pertanyaan itu sekedar
pengasah otak, sekedar hiburan di taman ria.”
Fidel tahu, seseorang tak mudah mengerti apa yang ia ungkap. Ia berusaha
mencairkan kepekatan. “Sebelum kau bertamasya, kita harus mengetahui lebih dulu makna
mengenai struktur pemikiran.” Fidel mengetahui perjalanan pemahaman Riang masih jauh
dan panjang.
STRUKTUR. FIDEL MENGAMBIL KERIKIL dan melemparkannya.
“Coba kau raup bebatuan yang ada di bawah kakimu!” Fidel berteriak. “Anggaplah
bebatuan itu kelereng berjumlah seribu. Lemparkan kelereng itu sekuat tenaga! Lempar!”
Riang meraup dan melemparkannya. Saat batu jatuh ke tanah. Fidel bertanya.
“Berapa kemungkinannya kumpulan kelereng itu membentuk bulat, bujur sangkar,
persegi panjang atau membentuk sebuah garis lurus vertikal ke atas?”.
“Mana mungkin,”.jawab Riang.
“Apa!? Tak dengar!”
“Mana mungkin!”
“Teriak yang!”
“Mana mungkin!!!” Gema pantul kemana-mana. “Kin…kin…kin!”
“Kemungkinan kelereng yang jatuh ke tanah kemudian membentuk formasi bulat,
bujur sangkar, persegi panjang atau membentuk sebuah garis lurus vertikal ke atas adalah:
0,0000000000000000000000000. Tidak ada ujung pangkalnya! Mustahil! Lantas bagaimana
dengan bintang yang ada disana?! Bagaimana dengan planet-planet di luar bumi manusia!
Bagaimana keberadaan Bima Sakti yg terdiri dari bilyunan bintang! Bagaimana galaksi
241
lainnya! Bagaimana degan semua planet dan bintang yang ada dan memiliki garis edarnya
masing-masing?!”
“Mereka tak saling berbenturan kecuali pada masa tertentu! Mereka memiliki
keteraturan garis edar! Rumit! Keteraturan itu lebih rumit dari sudut-sudut pada bujur
sangkar dan trapesium!”
“Bumi melayang dalam sebuah ruangan kosong! Begitu pula Matahari, Mars dan
lainnya! Mana penyangganya? Mana tiang beton cakar ayamnya? Mungkinkah itu terjadi
karena kebetulan sementara sesuatu yang sederhana, sepatu, gelang, diciptakan pengrajinnya,
gedung dan kendaraan yang berlalu lalang di jalanan, kita yakini diciptakan manusia. Kita
pahami tidak ada dengan sendirinya.”
“Jika ada yang mengatakan alam terbuat dari materi, apa yang harus kusangkal. Aku
mengakui bahwa alam terbuat dari materi. Tidak masalah untuk meyakini itu, tetapi siapa
yang menciptakan awal pembentukan alam semesta dari materi yang setitik itu? Materi itu
sendiri? Apa materi yang setitik itu dapat mengatur rotasi planet dan bintang pada porosnya?
Apakah titik kecil (materi) itu yang melakukan penjagaan, agar bumi dan bulan menyepakati
garis edarnya masing-masing hingga tidak saling bertumbukkan?”
“Mungkinkah seonggok materi, mengatur Pluto, Jupiter atau Sedna agar mereka, agar
planet tersebut melayang di sebuah ruangan besar yang kosong? Mungkinkah itu semua?
Mungkinkah kemunculan hukum alam, hukum peredaran bintang, hukum planet dan bintang
yang menggantung di ruangan kosong terjadi dan ada dengan sendirinya?”
Riang berpikir. Ia membisu.
“Bahkan bukti penciptaan bisa kau lihat di sana.” Fidel menunjuk.
Riang meraba alisnya.
“Setelah kau dewasa, pendek rambut di atas matamu hampir pasti selalu seperti itu.
Mengapa rambut alis tidak tumbuh seperti rambut yang menempel di kepalamu?”
Riang membayangkan alisnya, memanjang seperti rambutnya yang lama tak
dipangkas. Ia membayangkan bulu matanya menempel di makanan, menyapu jalanan,
alisnya menjadi rumbai-rumbai seperti tirai dan surai keledai membuat mata dan kepalanya
menjadi berat. Riang bahkan terlalu jauh berpikir. Pikirannya beranak pinak. Riang berkhayal
hidup sejahtera karena dirinyalah yang pertama membuka salon pangkas alis dan bulu mata
dalam sejarah. Ia bahkan telah menyiapkan pengembangan usaha creambath bulu idung dan
rebonding ketiak.
Khayalan yang jika dibiarkan akan mengalahkan khayalan J.K. Rowling serta
Danarto itu dimatikan oleh perkataan Fidel. “Bukti penciptaan ada di salah satu inderamu
242
juga!” Fidel menunjuk mata Riang. “Pernahkan berpikir mengapa mata kita memiliki
keterbatasan? Mengapa kita tidak bisa melihat benda yang super kecil seperti virus bakteri
dan amuba? Mengapa telinga kita tidak bisa mendengar suara yang jauh? Bukankah asyik
jika kita memiliki ketidakterbatasan jangkauan indera. Kita bisa menjadi sekuat Clark Kent,
bisa berubah seperti mimikri, digjaya seakan Wisanggeni, dan kalau kau wanita kau bisa
menjadi Mantili dalam serial cantik Brama Kumbara, menjadi wanita Amazon yang hebat,
menjadi manusia super di antara manusia super lainnya.”
Riang berpikir.
“Semua ada aturannya.” Papar Fidel. “Penciptaan tidak dibuat ibarat sirkus
ketangkasan. Penciptaan bukanlah sesuatu yang dibuat main-main. Jika kita memiliki
kekuatan: kemampuan melihat benda super kecil, memperhatikan detail, memperhatikan
lipatan-lipatan kecil maka kita tidak akan menyukai wanita secantik apa pun parasnya.
Dalam detail wajah si cantik akan berubah menjadi mengerikan. Kulit wajahnya bolong-
bolong oleh pori-pori. Jerawat kecil akan menjadi kawah. Lemak yang menyumbatnya akan
kita lihat seakan nanah yang menjijikan dan menakutkan. Kita akan melihat seribu satu
macam ancaman karena mata kita melihat ribuan hewan mikroskopis yang bentuknya
berbuku-buku, berlendir, berbulu tajam dan mengerikan di permukaan wajah kita bukan
hanya wajah kita tentunya. Wanita cantik yang kita bicarakan tadi akan menampakan diri
seperti siluman!”
“Bukan hanya mata, jika telingamu peka, Kau akan kesulitan menikmati tidur.
Kecoak yang merayap di pipa akan terdengar seperti suara garukan gabus pada dinding yang
kasar. Obrolan-obrolan yang puluhan meter dari tempatmu berbaring akan terasa nyata
berada hanya beberapa senti dari kupingmu. Derum mobil, suara motor satu kilometer dari
tempatmu, buah yang jatuh, penyewan game, dingdong, tangisan anak, akan membuatmu
depresi. Suara akan menjadi terror, melemahkan mental, membuatmu gila!”
“Jika kita mau melihat tubuh kita sendiri kita akan melihat beragam keagungan,
melihat keteraturan. Kulit yang kita kenakan ini, tidak sembarangan melekat. Kulit
merupakan benteng agar tubuh tidak mudah cedera ataupun mudah terkena organisme yang
membahayakan kesehatan tubuh, kulit menjaga agar tubuh kita stabil suhunya dan tidak
kering. Kerangka manusia berfungsi untuk menahan guncangan, menjadi penopang daging,
otot serta organ bagian dalam tubuh kita. Otot menjadi semacam kabel yang menarik tulang
untuk menimbulkan gerakan. Peredaran darah yang bergeraknya satu arah. Peredaran yang
memiliki panjang sekitar sembilan puluh enam ribu kilometer yang di pompa oleh jantung
yang hanya sekepalan, kemudian berputar di dalam tubuh kita, yang dalam sekali putarannya
243
hanya memakan waktu kurang dari satu menit. Dan kegiatan yang rumit serta menakjubkan
itu terjadi tanpa membutuhkan istrirahat, terus berkerja sepanjang hidup kita. Belum lagi
kalau kita berbicara otak manusia, berbicara tentang organ tubuh lainnya.”
“Yang …” ucap Fidel lembut. “Kau, aku, manusia, alam semesta, tidak ada karena
permainan. Manusia tidak muncul tiba-tiba. Desain diri kita dan mahluk lainnya, terlampau
sempurna untuk dikatakan muncul dari kebetulan atau ketidaksengajaan yang tidak bisa
dideskripsikan.”
Riang tiba-tiba mengingat sesuatu “Tapi,” Ia menyanggah, “jika memang Pencipta itu
ada, bisakah Pencipta yang maha kuasa itu menciptakan batu besar, batu yang super besar,
hingga Ia tidak bisa mengangkatnya?”
Fidel tertawa. “Kau dapat dari mana pertanyaan itu?”
Riang mengaku. “Buku yang diperlihatkan mas Pepei!” lugas.
“Itu pertanyaan yang mengalihkan.” Fidel menegaskan. “Ada banyak pertanyaan
yang mengalihkan keyakinan kita untuk mempercayai Tuhan. Yang kau utarakan salah satu
diantaranya. Atau yang lain, misalnya: untuk apa kita menyembah Tuhan yang tak berkuasa
atas iblis? Bukankah dia yang maha kuasa seharusnya mencegah iblis yang telah
meneebarkan wabah kejahatan di dunia? Seharusnya Tuhan menjadikan iblis baik, atau kisah
tentang anak taman kanak-kanak yang diminta berdoa agar Tuhan memberinya gulali dan
sekantung permen.”
Riang teringat kembali akan pertanyaan Mahdi di Yogyakarta. Ia teringat kembali
pernyataan sperma tuhan dan biawak. Tak sadar ia menggumam. “Sperma tuhan
mengalihkan?!”
“Apa.” Fidel memastikan.
“Tidak Mas.” Riang mengelak. Tadi ia mengeluarkan pernyataan yang ditujukan bagi
dirinya.
“Mas… untuk apa kita menyembah Tuhan, apa guna kita bersujud pada-Nya, untuk
apa kita mempercayai-Nya, toh manusia tidak akan mati kalau tidak mempercayai Dia?”
Fidel mengulum senyumnya. “Itu termasuk yang mengalihkan,” katanya.
Riang diajak untuk kembali menata pikiran.
“Mempercayai Tuhan tidak agar kita mati karena mau percaya pada Tuhan atau tidak
manusia akan mati juga. Mempercayai Tuhan, menyembahnya merupakan beragam tanda:
tanda penyerahan kita atas rahasia yang tidak bisa kita singkap, tanda terimakasih manusia,
tanda penghambaan, tanda-tanda lainnya.”
“Jika Tuhan maha kuasa mengapa Dia tidak menjadikan iblis memiliki kebajikan?”
244
“Tebak apa yang kupikirkan?” tanya Fidel tiba-tiba.
“Aku tidak tahu,” Riang menjawab spontan.
Kau tidak bisa menebak pikiranku, apalagi pikiran Tuhan yang dahsyat,” Fidel
tertawa. “Tuhan memberi pilihan agar mahluknya memilih yang baik dan yang salah, agar
mahluknya memilih konsekuensi perbuatan yang telah ia kerjakan dan Iblis telah
memilihnya. Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu penuh kebaikan, nanti akan ada pula
manusia yang bertanya … kalau begitu Tuhan Maha tidak Demokratis. Kata manusia,
seharusnya setiap mahluk diberikan pilihan. Serba salah. Apa yang kau tanyakan, kenapa
iblis tidak diciptakan saja penuh kebaikan seperti malaikat merupakan salah satu rahasia
kehidupan terbesar. Yang paling penting dari semua yang kita bicarakan ini, apakah hanya
dengan pertanyaanmu itu, apakah dengan pertanyaan lain yang terlontar lantas Tuhan
menjadi tak?”
“Ini rahasia mas…” Riang berbisik meski hanya ada dua manusia yang berada di
lahan itu. “Fred pernah mengatakan di pondokan, bahwa mahluk Tuhan yang paling beriman
itu Iblis.” Riang mengadu.
“Fred?” Fidel merasa aneh. Dahinya berkerenyit.
Riang melanjutkan. “Iblis tidak mau bersujud pada manusia sebab iblis tahu yang
patut di sembah itu bukan Adam, melainkan Tuhan, Allah.”
“Ya,” Fidel mengakui. “Kisah tidak mau sujudnya iblis itu ada di injil dan Quran…”
Riang memotong, “lantas untuk apa Tuhan menghukum Iblis atas kesalahan yang
tidak terbukti? Kalau pun Iblis memang salah, kesalahannya kecil. Tidak ada bandingannya
dengan dosa yang dibuat manusia. Manusia membunuh ribuan orang dalam perang,
memperkosa, menyiksa manusia lainnya, sementara salah iblis hanya tidak mau bersujud
pada Adam. Dimana kesalahan besarnya?”
“Mengutip Fred lagi?” Fidel curiga.
Riang mengangguk.
“Aku tak tahu penjelasan sahabat-sahabat Kristianiku mengenai hal ini tapi dalam
pandang keyakinanku, perintah sujud Tuhan pada iblis bukan perintah penghambaan, bukan
perintah agar Adam menjadi majikannya, menjadi sembahan-nya. Sujud dalam kitab-ku
memiliki banyak pengertian, dua diantaranya: sujud penghambaan seperti halnya ketika aku
shalat dan sujud penghormatan layaknya yang malaikat lakukan terhadap Adam. Tuhan
meminta Iblis bersujud kepada Adam bukan untuk menghamba tetapi menghormati mahluk
yang memiliki pengetahuan. Iblis membangkang melakukan penghormatan, ia menolaknya
karena di dalam diri dia ada kesombongan, padahal iblis mengetahui yang memerintah dia
245
bukan manusia, bukan malaikat, tetapi pemilik alam semesta. Iblis mengetahui bahwa yang
memerintahkan adalah Zat yang menciptakan dirinya, maka pembangkangan macam apa
yang terbesar ketimbng pembangkangan mahluk yang sudah mengetahui Penciptanya, yang
sudah berhadapan langsung dengan pembuatnya?”
“Bukankah Adam membangkang juga? Bukankah Adam memakan buah larangan?”
“Adam membangkang, tetapi ia menangis setelah melakukan kesalahan, ia bertaubat.
Ini berbeda dengan iblis. Dia malah mengancam Tuhan untuk terus menggoda manusia untuk
menjadi temannya di Neraka.”
Riang sedikit lega. Seolah tak percaya.
“Ada banyak pertanyaan, ada banyak hal tentang kisah Tuhan, tentang Iblis dan
manusia.” Fidel melebarkan. “Ada yang mengatakan bahwa diturunkannya Adam ke bumi
dikarenakan Tuhan cemburu. Tuhan takut akan kekuatan manusia setelah memakan buah
Khuldi. Kata mereka, Tuhan takut jika manusia menyainginya. Mereka katakan juga bahwa
sesungguhnya Iblis bukanlah penjahat. Iblis adalah penolong manusia untuk mencapai
kekuatan, merebut keabadian. Persepsi ini berusaha disamakan dengan kisah Yunani
mengenai Promoteus yang mencuri api keabadian dari Zeus untuk ia berikan pada manusia.
Api keabadian merupakan kekuatan dan Zeus dalam mitologi itu diidentikkan dengan Tuhan.
Padahal, satu kisah lain dengan kisah lainnya tidak bisa disamakan, dipaksakn untuk
dicocokkan, karena sumbernya pun berbeda. Mengenai buah khuldi, , dalam pandangan
pemikiran keagamaan Islam, buah tersebut banyak di terjemahkan sebagai buah kejahatan
kemanusiaan. Adam dihukum karena tidak menggunakan akal pikirannya untuk menjauhi
kejahatan. Penafsiran lainnya mengenai diturunkanya Adam oleh Tuhan, bukan dikarenakan
hukuman memakan buah khuldi, melainkan karena memang perencanaan Tuhan bagi
manusia untuk mengolah planet biru ini, untuk mengolah bumi … lagipula kalau yang
dituduhkan oleh mereka bahwa Tuhan ketakutan jika Adam mengalami keabadian dan
mendapatkan pengetahuan setelah memakan khuldi, apa yang perlu ditakutkan, jika Ia
memang Tuhan? Sejak kapan Tuhan yang menciptakan takut pada yang diciptakan? Apa
magma yang bergejolak di bawah bumi itu tidak bisa Ia gunakan untuk membinasakan
manusia? Apa kehancuran bintang-bintang oleh kekuatan alam yang Ia pegang tidak cukup
untuk membuat manusia menjadi ampas abu? Dialah pemegang kekuatan, mengapa dia takut
kepada ciptaan yang besarnya cuma sepertrilyun dari besaran bumi yang diciptakan oleh-
Nya?”
“Tuhan maha gagah!” ucap Riang. Kesehatannya pulih.
246
“Jika kau memahami struktur keimanan, kau akan mengetahui mana pertanyaan
dan ungkapan yang mengalihkan. Manusia boleh kesulitan untuk memberi jawaban
mengenai pertanyaan ketuhanan. Orang boleh membuat bingung manusia lainnya tentang
keberadaan Tuhan dengan aneka pertanyaan, tetapi apakah hanya dengan pertanyaan itu,
dengan akrobatik kata itu Tuhan lantas jadi tak ada sementara bukti penciptaan-Nya, bukti
keberadaan-Nya merentang di keajaiban dan keagungan alam semesta, di tubuh kita.”
“Lantas siapa yang menciptakan Tuhan?” Riang tak yakin dengan pertanyaan yang ia
ucapkan.
“Kalau Tuhan ada yang menciptakan,” Fidel tersenyum, “apakah kita akan tetap
menafikan keberadaan Pencipta manusia? Apakah pertanyaan itu menghapus keberadaan
Pencipta kita di dalam semesta yang teramat nyata?”
“Maksudku bukan itu…” Riang berusaha menjabarkan tetapi ia tak menemukan.
Fidel menolongnya, berusaha mengerti pikirannya. “Sebenarnya, kalau Tuhan
diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Kalau kejadianku dibentuk hukum alam, katakanlah
yang orang lain katakan sebagai tuhan adalah hukum alam, maka dalam kepercayaan yang
menjadi sandaranku, dalam keyakinanku: Tuhan adalah tempat segala sesuatu berawal.
Termasuk tempat bersandar hukum alam yang membentuk kejadian diriku.”
“Tapi menurut Mas sesuatu yang menakjubkan itu diciptakan. Tuhan itu
menakjubkan, berarti dia diciptakan. Siapa yang menciptakan diri-Nya?” Riang gemetar. Ia
merasa takut dengan pertanyaannya sendiri.
Fidel menyentuh tubuh Riang, ia menenangkannya. “Kalau tuhan di ciptakan, berarti
dia bukan tuhan. Pertanyaan lanjutan dari pertanyaan tersebut adalah … siapa yang
menciptakan yang tidak bisa diciptakan? Ini pertanyaan yang membingungkan, dan
selamanya akan membingungkan bukan hanya untukmu saja, tapi untuk orang yang mau
berpikir dan bertanya sejauh itu dan sedalam itu.”
Fidel memandang Riang. “Coba jawab pertanyaanku. Apa dengan pertanyaan itu
Tuhan menjadi tidak ada?” Fidel melepaskan tatapannya. “Pertanyaan itu hanya untuk
mengalihkan.” Fidel mengingatkan. “Keteraturan semesta merupakan jawaban yang
memuaskan mengenai eksistensi Pencipta. Keteraturan alam merupakan jawaban yang logis
ketimbang menihilkan, menolkan, menafikan ketiadaan Pencipta di balik segala macam
keteraturan yang dahsyat yang melingkupi seluruh alam. Bagaimanapun juga, ada Sesuatu
yang menciptakan diri kita. Kita diciptakan dan dibentuk mungkin oleh pembantu-Nya
Tuhan, mungkin malaikat yang memegang hukum alam atau entah oleh siapa yang kita tidak
mengetahuinya, namun pada hakikatnya kita tidak bisa menyangkal bahwa kita diciptakan.”
247
“Lantas siapa yang ciptakan Tuhan.” Riang tahu ia mengulangi pertanyaan. Ia merasa
tegang.
“Hm,” Fidel mendesah. “Di sanalah batas berpikir manusia. Di sanalah tapal
batasnya. Bukan hanya kau dan aku, bukan hanya kita, seluruh manusia tidak bisa melampaui
hal itu. Di sanalah keterbatasan manusia sebagai mahluk yang serba bisa. Di sanalah
kegelapan yang tidak mungkin bisa kita sibak. Sampai di sini tamasya pikiran kita berhenti.
Di luar itu batas berpikir manusia, kita memerlukan sandaran dan jika memaksakan maka
kita berkhayal.”
Riang berpikir, ia menciptakan sebuah sistem berpikir di kepalanya untuk
memecahkan pertanyaan siapa yang menciptakan tuhan. Ia tak menemukan. Ia merasa
gamang.
Fidel menepuk Riang. “Kehampaanlah yang akan kita peroleh jika berusaha
mengungkit sesuatu yang tak mampu kita pikirkan. Kehampaanlah yang akan kita dapatkan
jika berusaha melampaui batas kemampuan berpikir kita, melewati tamasya pikiran manusia.
Jika terlarut dalam pikiran seperti itu, Kita akan merasa sia-sia, lebih jauh lagi, merasa bahwa
hidup yang kita jalani ini serasa begitu mengerikan. Ketidak tahuan akan rahasia tersebut
membuat pikiran kita kacau, galau. Sesal akan datang. Kita menyesal dilahirkan. Kesal ada
dan menjalani kehidupan di dunia, lantas, apa penyesalan tersebut dapat menjadikan kita
musnah, menjadi tidak dilahirkan? Tidak. Kita telah ada di dunia. Hidup adalah untuk
berjuang. Hidup tidak untuk disesali. Kita ada untuk memperjuangkan sesuatu yang kita
yakini. Manusia yang dikepung kebingungan, kegelisahan, dan tidak mampu menyingkap
rahasia yang teramat gelap seharusnya menjadikan dirinya sadar bahwa ia memerlukan
sandaran dan seharusnya sandaran itu merupakan sesuatu yang berkuasa terhadap dirinya.
Kita menyebutnya Tuhan.”
“Kalau Tuhan ada, mengapa tak bisa kita lihat, tak bisa kita raba?”
“Memang bentuk Tuhan untuk saat ini tak bisa dilihat. Tapi, keberadaanya dapat
manusia rasakan melalui perasaan dan dibuktikan keberadaan-Nya melalui pikiran. Kita tidak
melihat pesawat, tetapi kita mendengar suaranya. Pesawat terbangnya jenis apa, kita tak tahu,
tapi kita tahu pesawat itu ada. Tuhan itu nyata, namun bentuk dan wujud Zatnya seperti apa
kita tak tahu. Dan suatu saat, mungkin, kita akan melihat-Nya.
“Kalau begitu Tuhan ada.”
“Keteraturan adalah bukti keagungan sebuah desain penciptaan. Kagungan desain
penciptaan adalah pikiran yang masuk akal ketimbang menafikan Tuhan tetapi tidak
248
memiliki bukti selain asumsi mengenai aneka macam kejadian yang dianggap sebagai
kebetulan.”
“Untukku, keberadaan Tuhan itu masuk akal,” ungkap Riang.
“Terserahmulah,” ujar Fidel tertawa.
Riang mengingat betul apa yang terjadi setelah perbincangan itu. “Jangan gampang
teralihkan dengan pertanyaan yang mengalihkan. Jadilah api yang tak terpadamkan!” kata
Fidel mentransfer energi. “Buku-buku di ruang bawah tanah itu adalah salah satu bahan
bakarnya.”
Dengan tekun, satu persatu buku-buku Riang baca dan Riang pelajari. Ia melalap-
lalap, membakarnya satu persatu, hingga satu persatu buku-buku gosong menjadi abu. Ketika
Riang menemukan sesuatu yang membingungkan, ia mendiskusikan segala sesuatunya
hingga apa yang ia pelajari menjadi kobaran api yang semakin besar nyalanya, semakin
panas tariannya, semakin haus, semakin ritmis geliatnya.
MORALITAS
Riang masih berada di lahan yang tak jauh dari ruang bawah tanah. Ia masih
memandang ke belakang.
“Tuhan, adalah awalan, dan Tuhan adalah akhir tempat manusia kembali,” ungkap
Fidel mengawali. “Jika sudah menjawab dari mana kita berasal dan akan menuju kemana
setelah kita mati, maka apa yang seharusnya manusia lakukan untuk mengisi kehidupan?”
Riang menyimak.
249
“Ada beberapa pandangan mengenai hal ini. Satu kalangan menyatakan bahwa Tuhan
adalah pembuat jam. Usai membuat jam Tuhan tidak ikut dalam pengaturan kehidupan
manusia. Manusialah yang menentukan moralitas mana yang terbaik bagi dirinya. Kata satu
kubu yang lainnya, tidak mungkin! Tidak mungkin yang menciptakan tidak memberikan
petunjuk moralitas bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Televisi dan mobil pun ada
pabriknya. Kalau rusak, memperbaikinya harus mengikuti aturan pabrik. Manusia pun
demikian.”
“Tuhan yang mana yang harus diikuti aturan-Nya?”tanya Riang.
“Itu pertanyaan yang bagus. Tapi apa sebaiknya kita tidak membandingkan dulu
logika antara satu kubu dengan kubu lainnya.”
“Apa kaitannya?”
“Jawaban mengenai Tuhan yang mana yang harus diikuti aturan-Nya seperti yang kau
tanyakan tadi akan menjadikan kita memilih moralitas yang diungkap dalam agama-agama,
sementara saat ini kita tidak akan membandingkan antar agama lebih dulu, tetapi membicara
sesuatu yang lebih mengakar dari padanya, yakni benarkah Tuhan membuat aturan moralitas
untuk ditaati, ataukah Tuhan malah membiarkan manusia untuk mencari aturan moralnya
sendiri?”
Fidel membiarkan Riang berpikir lama.
“Aku sedikit kesulitan untuk mempermudah permasalah moralitas ini,” ungkap Fidel
jujur. “Tapi, begini saja.” Fidel merangkai. “Apa menurutmu korupsi itu kejahatan?”
“Tentu saja! Setiap manusia mempercayai korupsi adalah kejahatan!”
“Pemerkosaan, pembunuhan bayi menggunakan gergaji mesin, mencopet dompet
nenek-nenek, menembaki sembarang orang karena tak memiliki uang untuk latihan menjadi
cowboy, apakah itu salah?”
“Salah! Luar biasa salahnya!”
“Mengapa salah?”
“Karna semua agama, mengatakan itu salah.”
“Itu kalau kau sudah percaya agama.” Fidel tersenyum. “Kita kan tidak sedang
memperbincangkan agama. Yang kita bicarakan, apakah aturan moralitas dari Tuhan itu
benar-benar ada?”
“Aku tak tahu mas. Aku bingung.”
“Semua contoh yang kusampaikan dianggap kejahatan, karena perilaku itu merampas
hak orang!”
250
“Kalau tidak merampas hak orang lain, apa suatu perbuatan tidak dikatakan sebagai
kejahatan?”
“Tergantung dari cara kita memandang. Aturan moralitas agama-agama, setidaknya
agama yang besar, mengatakan contoh yang kuberikan adalah kejahatan, tetapi karena agama
memiliki definisi hak sendiri, maka terkadang perbuatan yang “tidak mengambil hak orang
lain” dianggapnya sebagai perbuatan tercela. Kehidupan seks bebas, bersetubuh tanpa ikatan
agama salah satu contohnya.”
“Jika memang tidak melanggar hak manusia lainnya, mengapa agama melarang?”
Tanya Riang.
“Karena agama memiliki definisi haknya sendiri. Seks bebas melanggar hak Tuhan
mengenai pengaturan kehidupan seks, dalam aturan agama.”
“Sepertinya tidak masuk hitungan?”
“Masuk hitungan logikamu?” Fidel tertawa.
“Iya.”
“Itu wajar, tetapi mengerti aturan moralitas agama tidak bisa dilihat sekilas dari sisi
itu saja. Kita harus masuk ke hal-hal yang lebih dalam lagi.” Fidel berpikir, “Aku sukar
menjabarkan. Aku berikan pertanyaan saja.”
Riang menanti.
“Apakah hubungan seks antara anak dan ibunya, antara bapak dengan anaknya, bisa
dibenarkan oleh moralitas kepalamu?”
“Ampun bunda!” Riang mengembik. “Memikirkannya saja tak berani!
Memikirkannya saja merupakan sesuatu yang memalukan!”
“Bukankah jika suka sama suka tidak apa-apa? Asal tidak merampas hak orang tidak
mengapa? Kalau kau, ibu, bapakmu ikhlas sukarela kan tidak menjadi masalah?”
Riang kehabisan nafas.
Fidel membuatnya sesak. “Bersetubuh dengan orang tua kita, dengan nenek atau
kakek kita tidak menjadi masalah asal kita sama-sama ikhlas. Asal tidak sama-sama
dirugikan. Semuanya sama-sama nikmat, selesai masalah.”
“Jadi… jadi,” Riang tak sanggup melanjutkan. Ia ketakutan. Lelaki di sampingnya
punya kelainan! Sinting! Riang merasa dipancangkan untuk menyetujui statement Fidel.
Lebih dari itu, ia merasa dijerumuskan Bentar dan Eva untuk mengenal Fidel.
“Jadi Mas… jadi…”
“Aku hanya bertanya,” Fidel paham Riang mengkeret. “Itu bukan pemahamanku.
Ambil nafas. Tenangkan dirimu.” Fidel tersenyum. “Aku hanya menanyakan konsistensimu.
251
Jika moralitas yang baik dilandaskan “asal tidak merampas hak orang” maka mau tak mau
kau harus menyetujui apa yang dilakukan keluarga yang mengikhlaskan incest atau
hubungan seks antar anggota keluarganya.”
Fidel menuang kopi. “Kita sudahi dulu. Tenangkan dirimu.”
“Tak usah mas. Aku minum dulu saja.”
Fidel berdiri. Ia menggerakan badannya. Tak berapa lama isyarat itu datang. Riang
terlihat lebih jernih parasnya. “Lanjutkan Mas,” pinta Riang.
“Siapkan dirimu. Kita melakukan petualangan yang lebih ekstrim lagi. Kita tamasya
sejauh yang kita bisa. Kendalikan nafasmu.”
Riang menarik nafas. Ia merasa lebih sigap. Lebih siap.
“Jika landasan perbuatan adalah tidak saling merugikan, tidak saling merampas,
lantas siapakah yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa tindakan yang dilandaskan
pemahaman tidak saling merugikan adalah sebuah kebenaran?”
“Otoritas?” Jenis barang macam apa itu, mata Riang meminta penjelasan,
“Siapa yang memiliki hak untuk menentukan mana yang benar dan yang salah.”
Riang mengerti. “Akal manusia. Yang berhak menentukan adalah akal manusia!”
“Mengapa mengambil paksa hak orang tidak diperbolehkan, mengapa aku harus
mengikuti akal orang jika kepalaku mengatakan tidak apa-apa bila aku membunuh orang lain
yang tidak kusukai. Bukankah hidup du dunia ini merupakan perjuangan. Yang lemah
dimakan, yang kuatlah yang akan menjadi pemenang! Itu alamiah! Membunuh itu alamiah!
Memakan manusia hal yang biasa, binatang pun kadang melakukannya. Memperkosa tidak
mejadi persoalan besar. Balas memperkosa saja kalau kita diperkosa!”
Riang ngos-ngosan. Pertanyaan-pertanyaan dan perkataan itu tak tertangguhkan. Tak
tertahankan, terlampau mengerikan. Ia membisu.
Fidel meraba ketidaksiapan mental itu. Ia membenamkan ketakutan Riang, dengan
mengganti caranya menjelaskan.
“Orang mungkin akan mengatakan itu tidak manusiawi. Perkosaan, kanibalisme
dalam kehidupan adalah hal yang mengerikan, yang dilakukan untuk mengambil paksa hak
orang lain, tetapi siapakah yang berhak menentukan hal ini mengerikan, dan hal itu tidak
mengerikan, sementara tidak ada satu otoritas pun yang mengatakan bahwa perbuatan itu
benar. Kemudian, manusia berharap pada otoritas akalnya. Tapi apakah otoritas akal itu?
Samakah satu otoritas akal dengan otoritas lainnya? Jika sama, mengapa ada pembunuhan
atas nama Teotihuakan yang dulu kita bicarakan di danau Merbabu. Kau masih
mengingatnya?” tanya Fidel.
252
Riang memberi tanda. Ia masih mengingat apa yang mereka bicarakan di danau
Merbabu.
“Jika antara satu otoritas dengan otoritas lain memiliki kesamaa, mengapa di dunia ini
masih ada klan kanibal di Amerika tengah atau suku kanibal lainnya yang masih hidup di
belantara Irian sana?”
Riang merangkak. ”Tidak boleh memperkosa, tidak boleh memakan manusia,
diperlukan manusia untuk menjaga perdamaian.”
Fidel tersenyum. Jika senyum itu terbit, Riang mulai faham, Fidel akan dengan
mudahnya membuat senyum itu tenggelam.
”Aku tahu itu,” ucap Fidel, ”tapi kita bukan membicarakan perdamaian. Kita
membicarakan hal yang lebih radikal lagi. Jika Kau mengetengahkan perdamaian untuk
memenangkan pendapatmu, maka Kau sudah menganggap perdamaian adalah kebaikan.
Maka, atas otoritas siapa perdamaian dikatakan sebagai sebuah kebenaran, sementara
kekacauan adalah kekeliruan? Siapa yang berhak mengatasnamakan perdamaian? Siapa yang
menentukan perdamaian adalah kebaikan? Kenapa pembunuhan dan pemerkosaan dikatakan
kejahatan? Siapa yang menentukan?”
Riang diam.
”Jika sama-sama fair, tidak melibatkan moralitas apa pun, maka tidak ada satu pun
manusia yang berhak mengklaim kebenaran kerangka moralitas. Pembunuhan, pemerkosaan
tidak sama baiknya dengan menjaga perdamaian.”
”Di alam ini tidak ada klaim yang mutlak. Dan ketika ketiadaan klaim yang mutlak
itulah yang akan menimbulkan kekacauan, meski dalam pikiran yang teramat ekstrim
kekacauan itu pun bukanlah sesuatu yang salah karena tidak ada klaim yang memiliki
otoritas untuk mengatakan kekacauan itu benar atau salah.”
Riang berusaha keras memahami. Ia tak sampai-sampai. Ia menggapai-gapai.
”Yang, ... di titik inilah manusia mengalami kebingungan, mengalami kekalutan.
Disinilah banyak manusia masuk ke dalam labirin. Manusia masuk ke dalam ruangan berisi
jalan yang dipenuhi jutaan kelokan. Yang gila tak bisa keluar darinya. Dan pada satu titik
kekalutan dan kebingungan yang tak bergaris finish, para filsuf non agama mencari cara
singkat menjebol dinding labirin. Mereka keluar dengan menjadikan konsensus peraturan:
manusia tidak boleh saling memakan, tidak boleh memperkosa, tidak boleh mermpas hak
manusia lainnya, yang ditetapkan bersama untuk menjaga apa yang dinamakan keharmonisan
kehidupan, untuk mengatasnamakan perdamaian.”
253
”Para filsuf berusaha menjadikan peraturan itu universal. Padahal, mereka tidak yakin
dengan keuniversalan itu, sebab tak ada satupun otoritas yang bisa mengatakan bahwa
moralitas a atau b adalah kebenaran mutlak. Standar kebenaran ini kemudian disebarluaskan,
di globalisasikan, meringsek nilai nilai lokal dan kegamaan.”
”Agama perlahan digeser, dan hak asasi manusia (HAM) perlahan dijadikan sebagai
agama baru. HAM dimutlakkan sebagai kebenaran dan pemikir agama perlahan-lahan
menstandarkan nilai moralitas agama yang mereka miliki untuk distandarkan dengan HAM.
Yang tidak sesuai dengan HAM dinafikan, diinterpretasi ulang sesuai dengan nilai kebenaran
para filsuf yang semula kebingungan menentukan siapa yang berhak menentukan otoritas
moral. Tetapi, di kalangan pemikir keagamaan lainnya, kebingungan untuk menentukan siapa
yang berhak menentukan otoritas kebenaran moral, justru semakin menguatkan kepercayaan,
bahwa hanya Tuhanlah yang berhak menentukan apa yang layak dan tidak bagi manusia!”
“Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa penyandaran moralitas kepada
‘otoritas’ Tuhan yang disimpulkan pemikir keagamaan sebagai sebuah kemalasan berpikir,
dan tindakan orang-orang dungu yang putus asa. Padahal, kembali lagi …jika mau fair,
bukankah konsensus bersama mengenai HAM pun dilahirkan dari keputusasaan, dilahirkan
dari kebingungan juga kemalasan ketika manusia masuk ke dalam dan ingin keluar dari
labirin moralitas yang membingungkan.”
“Pemikir agama yang radikal tidak bisa dikatakan malas berpikir dalam penentuan
standar moralitas sebab mereka pernah mencapai kondisi yang sama. Mereka pernah masuk,
bertamasya ke dalam labirin, berpikir mendalam, hingga pikiran yang mendalam itu justru
menjadi landasan bagi mereka untuk tunduk pada aturan moralitas yang bersumber dari
ajaran moralitas keagamaan. Tuhanlah tempat manusia bersandar! Tuhanlah tempatku
bersandar!”
“Aku?” Riang mempertanyakan pengakuan Fidel.
“Ya tempatku bersandar,” jawab Fidel.
Riang sumringah. Ia yang belum siap berhadapan dengan pemikir radikal atheis,
agnostic, atau berhadapan dengan pemikir yang percaya tuhan tetapi tidak percaya
keberadaan aturan moralitas Tuhan itu, merasa tenang di hadapan orang yang meyakini
moralitas yang bersumber dari otoritas yang disebutnya berasal dari Tuhan.
Ketenangan memeluk Riang. Beban di kepalanya hilang.
“Jadi mas tidak setuju pemerkosaan?”
Fidel tertawa.
“Termasuk tidak bolehnya makan daging manusia?”
254
“Juga tidak bolehnya bersetubuh dengan orangtuaku!” Ujar Fidel menambah untuk
lebih meyakinkan.
Riang lega.
“Orang memang tidak boleh merampas hak orang lain. Tetapi, devinisi tidak boleh
merampas hak orang atau bahkan merampas hak diri kita sendiri pun, seharusnya tidak kita
sandarkan pada otoritas moralitas manusia yang tidak memiliki kekuatan klaim! Devinisi
rampas merampas hak itu, kuserahkan pada pemilik diriku, pemilik dan pengatur alam
semesta. Kuserahkan pada Tuhan yang menurunkan aturan! Pada agama!”
“Agama kan banyak Mas?”
“Itu pertanyaan yang pas di waktu yang tepat.” Fidel melihat jamnya. “Tapi, waktu
membatasi. Istirahatlah!”
“Aku belum mengantuk,” Riang menantang.
“Kalau aku sudah.” Fidel pura-pura menguap.
“Ya sudah, kalau mengantuk istirahat saja.” Riang pura-pura kecewa.
“Aku tahu kau berpura-pura!” tegur Fidel.
Riang tertawa. “Jadi, apakah berusaha menggali sejauh mana kemampuan kita dalam
menentukan akar moralitas adalah tamasya berpikir juga?”
Fidel terhenyak. Dalam persangkaannya Riang masih membutuhkan waktu lama
untuk mengendapkan apa yang telah ia paparkan.
“Jadi itu tamasya juga Mas?”Riang menegur.
“Bagi orang yang memiliki struktur pemikiran penggalian yang kita lakukan adalah
tamasya pikiran. Tamasya ya hanya tamasya, bukan tempat pemberhentian. Tamasya
hanyalah sekedar relaksasi pikiran, aktivitas olahraga untuk mengasah sejauh mana
kemampuan akal kita menjangkau sebuah permasalahan. Tamasya bukanlah tempat kita
diam. Tamasya hanyalah hiburan. Bukan sesuatu yang bisa menjadi sumber keyakinan orang
yang memiliki struktur pemikiran.” Fidel mengalihkan pandangannya. “Yang?”
“Ya Mas?”
“Bukan hanya dalam ilmu, tetapi dalam keyakinan, dalam hal keimanan pemahaman
terstruktur itu luar biasa penting!
Hm … Bukan hanya dalam ilmu,
dalam keyakinan pun,
pemahaman terstruktur itu penting!
Pemahaman itu benar-benar mengikat, seakan kaus kutang yang ketat.
255
Riang menyalin ingatannya ke dalam buku. Desir angin lembah menerpa tak
berkesudahan. Karena merasa dingin ia berbalik arah. Pintu besi ditutup. Hewan yang
memiliki kualitas kecerdasan tingkat tinggi itu, kembali sarangnya.
CERMIN
Dalam pembicaraannya mengenai pencarian, pergulatan manusia dengan keyakinan,
Fidel tidak menyertakan figure pembela eksistensi Tuhan paling mutakhir dan figur
penyangkal Tuhan terbesar, Dawkins dengan teori mengenai meme, virus akal budi yang
mendapat pencerahan dari bapak evolusi, Darwin.
Riang hanya dipahamkan mengenai sebuah fondasi. Ia hanya diberikan pemahaman
mengenai tiang pancang keimanan dan dijelaskan kembali mengenai sandaran informasi
yang pernah Fidel sampaikan saat mereka menginap di danau Merbabu. Bahwa, setelah
manusia meyakini keberadaan Tuhan, setelah seseorang menyimpulkan adanya informasi
256
yang diberikan Tuhan untuk mengelola kehidupan, maka ia akan berhadapan dengan
berbagai klaim keagamaan bahwa kitab inilah, atau kitab itulah yang merupakan wahyu
Tuhan untuk manusia.
Dalam taraf seperti ini manusia akan melakukan serangkaian pengujian mengenai
otentisitas kitab termasuk di dalamnya mengenai penelitian bahasa atau salah satu cara yang
paling sederhana dan bukan yang paling canggih ialah dengan meneliti sejarah bagaimana
kitab suci itu di bukukan: apakah pencatatan kitab suci tersebut dilakukan ketika Nabi --yang
dianggap pembawa kabar ayat-ayat Tuhan-- masih hidup, dalam artian, pencatatannya
langsung dilakukan ketika nabi mendapatkan wahyu atau penulisan kitab suci itu dilakukan
jauh-jauh hari setelah sang nabi wafat? Hal ini perlu dipertimbangkan karena perbedaan
waktu antara pencatat dengan orang yang dicatat ucapannya, akan mempengaruhi tinggi atau
rendahnya distorsi informasi yang disampaikan Tuhan pada sang nabi.
Mencari kitab yang tidak terdistorsi, atau yang paling rendah tingkat distorsinya akan
menunjukan bahwa manusia tersebut adalah manusia yang serius melakukan pencarian. Ia
tidak dengan mudahnya meyakini seluruh keyakinan itu benar atau bahkan semua agama
salah, sebelum ia melakukan penelaahan yang dalam bukan hanya penelaahan terhadap
kesamaan imbauan moral atau beberapa tuntunan etika yang tertera di dalam kitab kitab yang
berserakan di dunia, tetapi penelaahan yang lebih dari sekedar itu. Dan penelahan yang
sistematis seperti itu tentu membutuhkan waktu yang panjang melebihi panjang coki-coki
atau bahkan tubuh ular boa.
Riang akan menjalani tahapan untuk memahaminya, akan tetapi –setidaknya--, saat
ini Riang sudah memahami sistematika sederhana mengenai pencarian keimanan terhadap
sumber informasi.
TAK ADA JAM yang bisa memastikan posisi matahari di angkasa. Riang tertdur
tanpa ada yang membangunkan. Malam kemarin, usai merenung ia kembali menuju ruang
bawah tanah. Riang tak berniat tidur di atas sebab Fidel tidak ada semenjak sore kemarin di
rumah kayunya. Riang bangun, menuju ke atas ruang bawah tanah. Ia membersihkan dirinya
di kamar mandi, menghangatkan sarapan dan memastikan tidak ada kerjaan yang harus ia
lakukan di lahan. Riang lantas kembali lagi ke ruang bawah tanah.
Riang membaringkan tubuhnya di ranjang. Ia mengambil novel yang Fidel sarankan.
Baru beberapa belas halaman ia membaca dari atas terdengar suara aneh yang mencurigakan.
Konsentrasi Riang terpecah. Suara langkah kaki terdengar berketuk-ketuk. Ada seseorang
257
yang berjalan bolak balik di atas sana. Langkah kaki itu lalu menjauh, hilang perlahan. Sunyi
kembali datang. Lalu langkah kaki itu kembali datang.
Riang menunggu yang terjadi, ia tak mengenal bunyi langkah kaki itu. Sesorang
berhenti tepat di pintu masuk ruang bawah tanah. Suara gerendel pintu terdengar di buka
paksa. Suara itu terdengar kasar. Riang melihat berkeliling. Ia khawatir. Tak ada alat. Tak
ada yang bisa ia jadikan senjata. Ruangan ini hanya berisi buku. Riang membalikan ranjang.
Alas ranjang terbuat dari kawat, ia tak menemukan kayu di baliknya. Mata Riang kembali
berputar. Ia mengeluarkan buku yang paling besar dan tebal dari rak buku. Riang menanti.
Suara paksaan terdengar lagi. Riang tak ragu. Tak mesti ragu. Yang di atas bukan
Fidel. Keringat turun mengelap dadanya. Ia menanti. Suara gerendel pintu tiba-tiba berhenti.
Langkah kaki menjauh lagi. Lalu hilang sama sekali. Orang itu pergi.
Riang menunggu cukup lama. Ia menenangkan diri lalu naik ke atas, membuka pintu
perlahan. Ia menyamarkan langkahnya, memeriksa seluruh ruangan.
Tak ada orang. Riang melihat keluar melalui jendela. Di bukanya pintu. Ia tak
menemukan siapa pun di sana. Ia menuju ruang tengah, duduk dan membiarkan besi panjang
yang ia temukan menemaninya.
Di ruang tengah itu cuaca terlihat mendung. Riang lalu beranjak menekan saklar,
menyalakan lampu. Lampu berkedip-kedip lantas mati. Ada yang salah dengan kincir air di
dekat air terjun. Riang menutup jendela dan mengambil peralatan lalu mengunci pintu dan
memeriksanya hingga ia merasa yakin.
Riang menuju kincir air. Ia melihat air sungai luber. Ada kemungkinan banjir di hulu.
Riang mengecek pandangannya. Mendung di ujung. Ia berlomba dengan awan hitam. Air
terasa semakin deras. Kincir air yang tampak dari kejauhan, berhenti berputar. Ada sesuatu
yang membuatnya tersendat. Tak hanya itu saja, Riang melihat seorang wanita melompati
batu menuju hulu.
“Hei! Jangan ke atas. Banjir bandang!” Riang berteriak berkali-kali tetapi suara air
meredam teriakannya. Ia menyusul. Wanita itu hilang.
Sampai di kincir air Riang melihat bongkahan batu besar yang menghambat
putarannya. Ia mencari kayu, menjadikannya pengungkit. Batu terlempar. Kincir kembali
berputar perlahan lalu bertambah cepat hingga kecepatan yang Riang lihat tidak seperti
biasanya. Riang segera menyusul wanita itu.
Setelah terpeleset dua kali, ia sampai di hulu sungai. Di danau yang dingin tempat
curahan air terjun ditampung, debit air bertambah tinggi. Riang melihat wanita itu berada di
atas batu. Riang merasa mengenal raut wajahnya. Ia melihat wanita itu diam untuk sementara
258
lalu mengembangkan tangannya dan melompat seolah kedua tangannya adalah sayap. Tubuh
wanita itu meluncur deras. Air berbusa dan Riang berharap sayap itu membuatnya
mengambang di atas air.
Riang mulai berpikir tentang kematian. Ia berlari, melompat-lompat di atas batu dan
keseimbangannya muncul paripurna. Sampai di tepian danau Riang menajamkan matanya
dan di dalam danau yang berwarna hijau remang itu ia melihat tubuh wanita bergerak liar
jauh di kedalaman. Ia melihat tubuh wanita itu menggeliat lalu berhenti. Nafasnya habis.
Riang langsung meluncur. Ia masuk ke dalam danau dan berusaha keras mengayuh
tangannya hingga berhasil menyentuh tubuh wanita itu. Dipeluknya pinggang wanita itu lalu
ia membawanya ke atas dan membiarkan kepala wanita itu tepat berada di atas permukaan.
Dalam pada itu Riang tiba-tiba merasa sesak. Ia tak bisa bernafas. Ketika mengangkat tubuh
wanita itu, Riang masih memeluk pinggangnya. Ia menggunakan teknik bodoh: membawa
kepala wanita kepermukaan tetapi kepala dia sendiri masih berada di dalam air dengan posisi
lengan berada di pinggang wanita yang ingin ia tolong. Riang tak bisa bernafas. Untung, air
yang yang bergerak ke tepian mempercepat masa kritis itu.
Saat kakinya menjejak batu di pinggiran danau Riang langsung menyembur keluar.
Nafasnya terengah-terengah. Ia menyeret wanita itu ketepian pada sebuah batu besar yang
datar. Ia mengenalnya, benar-benar mengenalnya. Wanita itu pernah ia temui di Dr. Nurlaila
Wanita itu Milea.
Riang merasa khawatir. Tak ada tanda kehidupan dari tubuhnya. Riang terpaksa
menekan dada Milea dan memberinya nafas bantuan. Matanya terbuka. “Ka..” Milea
menggumam. Kesadarannya hilang tetapi ia selamat. Detak nafasnya mulai teratur.
Riang lantas menyalipkan tangan, mengangkat paha dan melingkarkan kaki MIlea di
pinggangnya. Riang melompati batu, setengah berlari sembari menggendongnya. “Turunkan
aku.” Kata Milea saat mereka melewati kincir air.
Riang tak percaya Milea dapat menyanggah tubuhnya. Benar saja, baru beberapa
detik berkata, kesadaran Milea hilang. Sesampainya di rumah kayu. Riang segera
membaringkannya di sofa. Ia tak tahu harus melakukan apa: untuk mengganti bajunya, Riang
tak merasa mampu. Riang hanya memandangi Milea lalu suara dengung motor trail terdengar
jelas dan Riang mulai merasa tenang.
Fidel datang. Ada Waluh tepat berada di belakang tubuhnya.
“Ia hampir tenggelam,” Riang menjelaskan.
Fidel mengecek urat nadi di leher Milea. Ia mengambil selimut untuk menghangatkan
tubunya dan hati Riang tiba-tiba bergetar saat Fidel memandang lembut wajah Milea.
259
Minuman hangat datang. Waluh memberikan cangkir pada Riang sementara cangkir
yang satunya ia letakan di meja.
“Kasihan anak ini.” Ujar Waluh saat mereka menunggu Milea siuman.
Fidel diam. Ia tak memberi komentar. Ia masuk ke dalam kamarnya lalu
mengeluarkan alat tulis dan kaca. Ia meminta Riang untuk mengambar. Riang menolak
namun Fidel memaksanya. Riang tak mengerti maksud kegiatan yang harus ia lakukan.
Tak berapa lama, wanita itu pun siuman dan melihat dua orang di antara tiga orang
yang ada di hadapannya tersenyum. Fidel memberikan cermin padanya. Milea terperangah.
Mulutnya tiba-tiba menjadi lebar, senyumnya semakin lapang, dan hampir saja rumah kayu
itu rubuh diguncang tawa yang meledak-ledak. Milea bangkit, lalu memukuli Fidel.
“Bukan aku!” Fidel spontan menunjuk Riang. “Dia!”
Entah, setan dari mana yang lewat hingga Riang menuruti saja apa yang
diperintahkan Fidel saat Milea tak sadarkan diri. Mulut Milea ia gambari kumis, patil ikan
lele yang biasa tumbuh di dagu sesepuh kuntau film-film China. Riang menambahkan tahi
lalat berbulu di bawah bibir Milea, tak ketinggalan bulatan merah di pipinya. Hasilnya
mujarab! Riang tak bisa berkelit. Milea tak mau tahu. Ia mengarahkan kepalannya sekuat
tenaga di tubuh Riang. Fidel dan Waluh langsung menghambur keluar rumah. Mereka
mendahului Riang berlari.
“Kau ...kau!” Milea terus menyalahkan Riang.
“Apa salahku?!” Riang membela diri.
Milea memukul punggung Riang.
“Apa salahku?!” Riang berlari.
“Kau... kau... betapa teganya!” Milea jauh tertinggal di belakang. Ia hanya bisa
mengancam lalu duduk di tanah. Fidel yang berada di dekat Milea masih mencoba
menjahilinya. Ia mendatangi Milea, membawa kaca. Milea melirik dan lagi-lagi kaca itu
hampir pecah karena tawanya! Milea mengatur nafasnya, namun beberapa detik kemudian,
tawanya yang tertahan keluar lagi dari mulutnya. Milea kuatkan diri, lalu ia berdiri dan
kembali mengejar Fidel.
Fidel terus saja menjahili Milea. Ia memperlambat langkah kakinya, namun dua meter
sebelum tangan Milea menyentuh bajunya, Fidel kembali berlari seolah kerasukan. Fidel
mengulanginya hingga dua kali, sampai menjadikan Milea kehabisan nafas. Milea menyerah.
Fisiknya yang lemah memaksany untuk mengatur nafas dan duduk di samping ladang
sayuran. Fidel merasa salah. Ia lantas duduk di dekatnya..
“Terima kasih,” ucap Milea lirih. Ia menangis.
260
Riang dan Waluh tidak tahu harus melakukan apa. Mereka membisu.
“Peluk aku … ” pinta Milea tiba-tiba.
Medengar permintaan itu, dunia Riang seolah berhenti berputar. Ia bersyukur melihat
Fidel hanya menepuk bahu wanita itu.. Fidel tak bisa melakukan lebih. Ia hanya bisa
memandang dan menghangatkan Milea menggunakan matanya.
MENJELANG MAGRIB saat matahari tenggelam tubuh Milea sudah terbungkus
kain wol yang hangat. Hujan sudah berhenti sejak sejam yang lalu. Motor trail Waluh
menggerung
“Sudah malam.” Fidel memberi isyarat padanya.
Milea cemberut. “Aku tak akan melakukan itu lagi,” janjinya pada semua.
Fidel menggulung koran, memukul kepalanya. “Ya, ya, ya, jangan melakukan
tindakan bodoh lagi!”
Milea sebal. Figur wanita dewasa yang Riang lihat di tempat praktet Dr. Nurlaila
hilang. Di mata Riang, Milea kini tampak seperti seorang adik yang ingin ia lindungi. Milea
seperti adik bungsu yang manja, padahal pada kenyataannya Riang tak pernah dan tak akan
memiliki adik. Maghrib itu Riang benar-benar sok tahu.
MANUSIA PLANET NAMEC
261
KEMARIN RIANG merasakan khasiat Big-Bos kembali. Tubuhnya menjadi ringan,
tak berbobot.
“Kamu Riang! Riang Merapi!” Milea mengingat namanya.
Bagaimana mungkin, o opium dan segala macam jenis mirasantika, Riang tengah
mabuk kepayang. Ia tak bisa mengendalikan perasaannya.
Milea tertawa menyaksikan perubahan wajah Riang yang kentara.
“Fidel yang memberitahu namamu,” terang Milea.
“Kapan?!” Riang mencurigainya. “bahkan tahu sejak aku sakit perut itu?” tebak
Riang.
Senyum Milea bernada rahasia.
“Kenapa tidak memberitahuku?!” kata-kata Riang terdengar seperti pendakwa ruang
pengadilan.
Milea tak merasa bersalah. Fidel menyuruhnya mengambil bagian dalam rencana. Riang
teringat perkataan Bentar kala ia menuntut penjelasan yang sama di hadapan Fidel. Ada
begitu banyak rahasia yang tidak ia ketahui. Riang membatalkan tuntutannya. Biarlah hal itu
menjadi hiburan baginya.
Semenjak Pepei –kakaknya-- wafat, hidup Milea menjadi jarang berwarna. Hidupnya
seolah hasil cetak operator yang hanya memberikan pilihan foto hitam putih atau B/W. Tidak
ada warna pelangi. Warna hidup Milea meluntur.
“Aku tak tahu rasanya kehilangan keluarga,” ujar Fidel. “Aku tak pernah
mengalaminya. Aku tak bisa membayangkan ketika satu-satunya keluarga yang tertinggal
tidak lagi dapat aku pandangi. Tindakan putus asa, untuk mengakhiri hidup adalah tindakan
yang salah, tetapi apa yang Milea lakukan adalah sesuatu yang manusiawi.”
Kehilangan itu merupakan gempuran terparah yang dilakukan nasib terhadap Milea.
Riang memikirkan betapa nelangsa-nya Milea. Ia pernah kehilangan keluarga, tetapi ia masih
memiliki orang tua. Rahang Riang menggeretak. Pembunuhan Pepei berdampak besar pada
penderitaan yang melebar. Kardi adalah komet besar yang membuat dunia Milea hancur
berantakan. Ia merupakan meteor kepunahan! Kardi adalah vacuum cleaner penghisap
kebahagiaan.
Riang sudah sampai pada titik yang ia tidak sadari. Seperti tua bangka berkedok ingin
melindungi seorang anak SMA padahal ia menyukainya, Riang tak sadar jika hatinya sama.
Keinginan standar jagoan-jagoan untuk melindungi yang dicintainya mulai tumbuh. Ia tak
262
sadar, sikapnya justru membuat Milea ketergantungan. Pertolongan yang ia lakukan di danau
merupakan awalan. Milea berterimakasih dan berharap lebih padanya.
Sisi getir kehidupan adalah kekecewaan. Jika tak ingin kecewa maka hidup tak perlu
di gantung. Milea memang harus cepat dilepaskan. Ia harus segera dimandirikan.
PAGI ITU Riang berkemas. Kemarin sore, sebelum membawa pulang Milea, Waluh,
meninggalkan pesan. Balasan surat dari Thekelan sudah sampai di pondokkan. Bentar yang
menyimpannya, kata Waluh. Sampai di pondokkan Riang membuka surat bapak yang isinya
sederhana. Kedua orang tua Riang menanyakan kapan pulang.
Riang tersedu. Apa yang ingin ia dapatkan di kota ini? Pencarian keparat Kardi
tampaknya usai. Tak ada lagi yang dapat Riang telusuri. Pertanyaan-pertanyaan yang
membuatnya pusing pun telah mereda seiring pemahamannya tentang tamasya, keimanan
dan kaus kutang.
Riang saat ini adalah Riang yang berbeda dengan Riang di masa lalunya, dan ia
meyakini bahwa Riang di masa yang akan datang akan menjadi Riang yang lebih baik
ketimbang Riang di masa ini. Riang di masa kini tak takut menghadapi perubahan. Ia yang
pernah mengalami fase kegelisahan yang mendekati kegilaan. Riang mengetahui dan mampu
menjabarkan bahwa kegelisahan merupakan sesuatu yang berat dan kegilaan adalah sesuatu
yang kita tak tahu harus bagaimana, ketika kita tak bisa membuka jalan ke depan atau balik
lagi ke belakang. Fase yang membuat manusia berjalan di tempatnya. Ia telah melewati fase
itu. Kegelisahan yang berdentam adalah suatu fase yang apabila terlewati akan
menjadikannya kuat.
Kalaulah boleh membuat pembagian manusia berdasarkan kegelisahan yang
dialaminya, maka di dunia ini terdapat manusia yang tidak mau melakukan pertaruhan untuk
meningkatkan kapasitas intelektualnya; Ada pula manusia yang mengikuti kehidupan
layaknya alunan air. Dia melaju dengan ketenangannya, mendapatkan pembelajaran tanpa
mengalami proses yang berat. Dia mencicil sedikit demi sedikit kemampuan intelektualnya
dan manusia seperti ini jarang mengalami kompleksitas kedahsyatan pergulatan pemikiran.
Bagi mereka kemungkinan menjadi gila itu kecil karena pembelajaran yang mereka lakukan
bersifat alamiah. Dua sifat itu tidak dimiliki Riang. Dan Fidel mengatakan “Itu bukan kita!”
Riang adalah manusia yang seperti Fidel jabarkan. Riang adalah manusia planet
Namec!
“Kau mengingat Bezita?!” tanya Fidel pada suatu waktu.
Riang mengangguk.
263
“Bezita manusia planet Namec. Ia manusia yang sama dengan Son Go Ku. Jika kau
perhatikan, orang planet Namec memiliki sifat ambisius yang alamiah! Mereka
mempertaruhkan apa saja untuk menjadi kuat. Mereka meningkatkan kekuatannya dengan
melakukan latihan dan pertempuran yang mendekati ambang kematian. Bezita mengetahui
itu. Ia mengalami peningkatan kekuatan yang pesat. Ia mempertaruhkan kematian untuk
mendapatkan kekuatan dan kita pun sama! Kita adalah orang-orang yang baik secara sadar
atau tidak, mau mempertaruhkan keyakinan yang ada di dalam diri kita. Kita meyakini
kosekuensi pertaruhan keyakinan adalah datangnya kegelisahan dan mengalami kegilaan.
Kegelisahan dan kegilaan adalah konsekuensi negatif pencarian makna yang kita lakukan,
tetapi, jika kita berbicara tentang konsekuensi positif kegelisahan maka kita akan
mendapatkan segarnya saripati kehidupan. Kita mengalami peningkatan-peningkatan yang
signifikan! Karena itulah kita mau dan berani mempertaruhkan keimanan!”
Mahdi pun manusia planet yang sama. Ia melakukan pertaruhan yang berbahaya. Ia
pernah gila karena ketika akal menyangkal keyakinan yang dulu dianutnya, hati Mahdi
menolak. Argumentasi yang ditemuinya di Parang Tritis ternyata lebih baik dari
argumentasinya tentang ketuhanan. Di dalam jiwa Mahdi muncul pergulatan. Ia tidak
sanggup menerima kehebatan argumentasi Pepei, tetapi ia tidak bisa meninggalkan
keyakinannya yang dulu dan pertemuannya dengan Pepei untuk yang keduakalinya,
membuat Mahdi terbebas dari keterpecah kepribadian.
Riang memang sebal pada Mahdi tetapi ia mulai bersimpati pada manusia yang
mengalami banyak hal yang sama dengannya.
“Proses yang Mahdi alami adalah lukisan perjalanan hidupnya. Lukisan itu tidak akan
selesai hingga ia mati… Lukisan kita pun belum selesai,” ungkap Fidel. “Kita tidak tahu
kedepannya akan menjadi apa. Masa depan bukan milik kita! Entah aku akan memiliki
keyakinan yang kuat atau murtad, aku tidak tahu! Kita tengah berproses dan orang yang
menjalani proses pencarian --yang sama-- adalah orang yang memiliki kedekatan spiritual
dengan kita. Kita tidak berhak melecehkan mereka! Melecehkan orang atheis, melecehkan
agama agama lain diluar agama kita, melecehkan agnostis selama mereka menyadari dan
menjalani proses pencarian kebenaran dalam kehidupannya. Kita tidak berhak melecehkan
karena masa depan selalu terbuka untuk di jalani, karena masa depan itu gelap, meskipun kita
berusaha menentukan, dan menjalani sebab akibatnya. Waktu merupakan kanvas dan
kematian merupakan tetesan terakhir warna pada kuas kehidupan. Kita tidak mengetahui
akhir hidup kita. Berusahalah dan teruslah berdoa.” Kata Fidel.
264
Riang kini sudah berani mengatakan, kakinya telah menjejak tanah planet Namec dan
itu berarti bahwa ia masih harus mencari jembatan-jembatan kegelisahan untuk ia lalui demi
meraih derajat kesempurnaan sebagai manusia yang selalu ingin berkembang.
Saat memikirkan hal tersebut kedamaian datang seperti saat Riang duduk di bawah
pohon yang mengeluarkan banyak O2. Suplai oksigen menderas masuk ke dalam paru-
parunya. Seakan pasien tuberkolosis yang tengah menikmati terapi, Riang mengantuk. Ia
merasa hidup tanpa beban, seolah sampai dalam keadaan puncak, ketika ia baru dilahirkan.
Kata-kata, ungkapan dan keindahan ucapan sahabatnya membuat Riang ingin mengerat lidah
Fidel menggunakan silet.
SURAT DARI ORANG TUA Riang yang menanyakan kepastian dirinya untuk
pulang membuat Riang merasa tidak nyaman. Masih di pondokkan, ia menuliskan jawaban
dan langsung memposkannya.
Riang masih harus di uji. Kegelisahan, dan pertanyaan-pertanyaan di masa lalunya –
memang—kini tidak menjadi beban, tetapi apakah manusia hanya mengalami kegelisahan
ketika melakukan pencarian terhadap keyakinan.
Riang masih merasa harus berada di tempat ini karena dirinya mulai dijangkiti rasa
hampa yang ia sendiri sulit untuk menjabarkannya. Riang ingin tahu tapi tak mengetahui
harus memulai darimana. Ada yang mendesak. Ada yang berontak di dalam dirinya. Ia tak
mengerti. Ia melamun.
Fidel melihat diri Riang hilang. “Jujurlah…” masih di pondokan Fidel menodongnya.
Riang ragu. Ia tak tahu. Ia tak mengerti.
“Bicaralah… bicarakan apa saja,” ujar Fidel.
“Aku merasa ada yang mengganjal. Selama ini aku mendapatkan begitu banyak
pelajaran berharga dari Mas. Aku mendapatkan pencerahan pemikiran, mendapat beribu
macam manfaat darinya. Aku bingung. Aku merasa diri tak berguna. Mas memberi banyak
hal, tapi aku tak pernah…” Riang khawatir atas apa yang ia ucapkan, lalu ia berusaha
menjaga perasaan mas Fidel. “Bukan … bukan memberi materi pada mas, tapi sesuatu yang
berharga di atasnya.. Maaf … aku merasa …”.
Jantung Riang berdetak.
“Kau merasa tidak memiliki harga?” Fidel tergelak.
Pertanyaan itu membuat pintu hati Riang terbuka. Ada yang mengalir. Deras. “Aku
merasa tak berguna. Hidupku seakan sia-sia. Aku tidak bisa memberi. Tidak bisa berbagi!
265
Aku merasa terasing! Merasa terkucilkan. Hal ini sukar kujelaskan.” Riang menunduk. “Aku
orang yang aneh ya mas?”
Fidel menggeleng. “Sudah berapa lama kita hidup di dalam rumah yang sama?”.
“Berbulan-bulan,” jawab Riang.
“Itu waktu yang cukup lama.”
Riang mengangguk
“Yang, kalau kukatakan bahwa kau berguna, bahwa kau berharga, bahwa belajar itu
tidak mutlak mendengarkan sebuah perkataan, melainkan –juga-- upaya mempelajari
aktivitas seseorang, apa Kau akan merasa tenang jika aku mengatakan, bahwa Riang pun
memberikan banyak hal melalui apa yang Riang lakukan, bukan yang Riang katakan?” Fidel
bernafas tenang. “Jujurlah apa adanya. Jangan dipendam.”
“Aku sendiri jadi bingung,” Riang menggaruk kepalanya. Perasaan Riang terlalu
dalam. Ia sulit untuk mengungkapkannya.
Supaya Riang lebih mudah mengungkapkan apa yang ia rasakan, sekali lagi Fidel
bertanya, “apa yang membuat Riang merasa tidak berharga dan berguna di hadapanku?”.
Riang berfikir lama. Diam tak bicara. Ia tak menemukan juga.
Fidel tersenyum. Rasa-rasanya ia mengetahui apa yang terjadi dengan diri Riang.
“Yang … saat ini kau sedang mengalami puncak-puncaknya pembelajaran. Kuperhatikan kau
sudah banyak membaca? Kau meningkat di segala hal. Kau haus akan segala macam hal
yang tersangkut paut dengan pengetahuan dan jika kini kau menginginkan sesuatu yang lebih
dari itu, mungkin ini adalah kesadaran yang tak bisa Kau ungkap bahwa kau memerlukan
eksistensi, bahwa Kau memerlukan pengakuan?”
Ucapan Fidel terasa vulgar.
“Jika saat ini hal itu terjadi pada dirimu, biar kukatakan bahwa mendapat pengakuan,
merasa ingin dihargai adalah sesuatu yang wajar. Penghargaan memang seharusnya tidak
menjadi tujuan manusia, tetapi penghargaan adalah sesuatu yang wajar. Kau memerlukan
eksistensi untuk ketenangan spiritualmu. Peningkatan pengetahuan memang harus disertai
potensi lainnya. Manusia yang mendapatkan banyak input mutlak memerlukan output. Ketika
manusia terlalu banyak pemasukan tetapi di satu sisi ia tidak memiliki saluran untuk
mengeluarkannya, maka manusia akan merasa sakit. Bukankah makan tak buang air itu
sakit?”
“Ah, mas ini!”
“Aku sungguh-sungguh!” ucap Fidel. “Manusia akan menderita jika ia terus menerus
minum tetapi tidak memiliki system saluran pembuangan air di dalam tubuhnya. Hal ini sama
266
dengan dengan pengetahuan. Jika Kau terlalu banyak memasukan pengetahuan tetapi tidak
memiliki medium untuk menyalurkannya kau akan merasakan sakit!”
“Sakit jiwa maksudnya?” Riang tertawa. Riang tahu Fidel benar.
“Ya sakit jiwa! Sedeng! Kurang lima menit! Gelo siah!” Fidel membentak.
Riang tertawa.
“Ada pemasukan ada pengeluaran. Itu hukum alam. Jika Kau tidak melakukan
ekskresi, apabila Kau tidak mengeluarkan pengetahuanmu maka akan terjadi sesuatu. Jika
saat ini Kau merasakan ganjalan yang demikian memberatkan, kupikir itu wajar, karena
mungkin, karena di tempat ini, Kau …”. Fidel berfikir keras untuk mengunyah kata-katanya,
menjadikannya lembut. “Salahkah anggapanku ini …?”
Anggapan apa Mas?”.
“Kau terlalu menghormatiku, sehingga Kau tidak berani berpendapat banyak saat aku
ada?”.
Riang tunawicara. Ia menjadi seperti pengantin yang baru saja naik ranjang.
Muka Riang merah.
“Yang … jika memang seperti itu. Jika memang eksistensiku, keberadaanku
membuatmu ragu-ragu, menjadikan dirimu merasa tidak nyaman untuk mengeluarkan
pemikiran pribadimu, maka sudah selayaknya aku tidak menjadi sahabat bagimu!”
“Aku menghormati Mas!” Riang memprotes.
"Apa penghormatan mengharuskan seseorang bungkam?! Kufikir kau bukannya tidak
bisa memberi jika memberi itu berargumentasi atau bertukar fikiran denganku! Kau hanya
tidak berani!” Fidel mengetahui perkataan yang ia susun berdasarkan anggapannya semula –
mengenai eksistensi-- tepat sasaran. “Yang …” Fidel melanjutkan,
”penghormatan adalah sesuatu yang baik karena penghormatan adalah tindakan yang bisa
mengantarkan kita pada pengertian, mengantarkan kita pada keselarasan! Tetapi, jika
penghormatan itu justru membuat seseorang, membuat Kau menjadi kacung pemikiranku
rasanya lebih baik Kau tidak menghormatiku lagi!”
“Menghormati bukan berarti merendahkan diri! Menghormati bukan berarti
membungkam isi hati! Pengutaraan isi hatimu, penyuaraan pendapatmu, orisinalitas
pemikiranmu justru sebuah penghormatan yang besar bagi ku! Betapa bangganya aku jika
bisa melihat dirimu seperti itu!”
Riang mengangguk lesu. Perkataan Fidel tepat menggambarkan keadaan hatinya.
Riang merasa lesu, merasa berdosa karena menganggap dirinya memaksakan kehendak, agar
Fidel mengakui eksistensi dirinya.
267
Riang salah menyangka. Pada wajah Fidel tidak terlukiskan gurat-gurat penyesalan
dan kekecewaan. Fidel adalah edisi khusus. Ia adalah manusia pilihan yang telah diciptakan.
Fidel telah siap dengan apa yang terjadi, bahkan sejak saat ia menempatkan Riang di rumah
kayunya, sejak ia memperkenalkan sahabat-sahabatnya. Ia telah menyadari bahwa sejak kata-
kata dalam perbincangan ini keluar dari mulutnya, sebuah babakan baru dalam hubungannya
dengan Riang telah ia ramalkan.
“Kau akan menjadi raksasa suatu saat nanti...” ujar Fidel dan ia melihat Riang ingin
membantah kata-katanya. “Tidak, jangan Kau hentikan dulu! Aku tidak bermaksud
mematikanmu lebih awal dengan memuji! Aku mengetahui benar potensi yang Kau miliki!
Keberanianmu, ketekunanmu, kehausanmu! Sejak dulu aku tidak pernah menganggapmu
sebagai ladang yang hendak ku garap. Di alam persahabatan ini semua sahabat adalah sama!
Sejak dulu aku tidak pernah membiarkanmu berada di belakang tubuhku karena Kau bukan
budakku! Kau ada di sampingku, Kau sahabatku!”
Tenggorokan Riang serak. “Dulu aku tak menyadarinya.”
“Dan Sekarang Kau baru sadar?!” Fidel menonjok hati Riang.
Ingus Riang meleleh. Ia bersyukur bertemu dengan orang mampu memahami
pendalaman dirinya. “Aku mencintai Mas!” Kata-kata itu mengalir begitu saja.
“Dan aku tak akan mengatakan cintaku padamu.” Fidel tidak menampiknya.
Beberapa saat kemudian kedua orang itu terdiam.
Apa yang mereka bicarakan menjadi ngambang. Lalu apa yang harus Riang lakukan
jika ia telah mengetahui apa yang ia inginkan?
“Mengapa tidak Kau buat zine saja?!”
Dan penemuan yang dilontarkan Fidel abad ini pun tercipta.
268
MANUSIA PLANET NAMEC YANG SETARA
“Aku tak tahu rasanya. Tak pernah aku mengalaminya. Kupikir apa yang dilakukan
Milea manusiawi.” Ujar Fidel mengomentari.
“Ayah ibu ku pernah kehilangan keluarga, tapi ia masih memiliki satu sama lainnya.
Mereka masih memiliki diriku.” Riang memikirkan betapa nelangsa-nya Milea.
“Lintang …” Fidel menerawang. “Dia paling tahu memanjakan adiknya. Ia paling
mengerti memperlakukan Milea, menyayanginya hingga melebihi apa yang ia sayangi di
dunia. Rasa sayang timbulkan ketergantungan. Bayangkan, apa yang kau rasakan ketika satu-
satunya keluarga yang tertinggal, kakakmu tidak lagi dapat kau pandangi wajahnya. Apa
yang berkemul di hatimu saat kakak yang kau kagumi tidak lagi tampakkan keagungannya di
hadapanmu? Ketika matamu terbuka. Segalanya sirna. Kehilangan itu merupakan gempuran
terparah yang dilakukan nasib terhadap Milea.”
Riang menggeretak. Kardi adalah komet besar yang membuat dunia Milea hancur
berantakan. Ia merupakan meteor kepunahan! Pembunuhan hanyalah starting point sebuah
penderitaan. Pembunuhan Lintang berdampak besar pada penderitaan yang melebar.
Riang paham Milea harus di pisahkan dari ketergantungan. Riang paham itu, namun
kenyataannya ia tidak bisa menggelakkan Milea dari dirinya. Apa yang dilakukannya di
danau, pertolongannya, tidak sadar menjadikan Milea berterimakasih dan berharap lebih
padanya. Wanita itu memang harus dilepaskan. Sisi getir kehidupan adalah kekecewaan. Jika
tak ingin kecewa maka hidup tak perlu di gantung.
SEBELUM MEMBAWA PULANG Milea, Waluh, meninggalkan pesan. Balasan
surat Riang sudah sampai di pondokkan.
“Bentar yang menyimpannya. Kau sampaikan saja pada Riang,” ujarnya pada Fidel.
269
Maka, pagi-pagi benar Riang berkemas. Sampai di pondokkan ia segera membaca
surat bapaknya. Isinya sederhana, menanyakan kapan pulang. Riang tersedu. Apa yang ingin
ia dapatkan di kota ini? Pencarian keparat Kardi pun tampaknya usai. Tak ada yang dapat
ditelusuri. Pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya pusing mereda, seiring pemahamannya
tentang tamasya, keimanan dan kaus kutang.
Ia mensyukuri dipertemukan dengan orang yang memahami dirinya. Riang saat ini
adalah Riang yang berbeda dengan Riang di masa lalunya, dan ia yakin Riang di masa yang
akan datang akan menjadi Riang yang lebih baik ketimbang Riang di masa ini.
Riang tak takut akan perubahan. Menjadi gila, kegelisahan yang berdentam adalah
sesuatu yang jika dilewati akan membuatnya kuat. Ia teringat akan penjabaran Fidel
mengenai dirinya sendiri, mengenai fase yang sama yang pernah ia lalui.
“Aku tak menyesal, alami fase-fase kegilaan,” ujar Fidel pada suatu waktu.
“Awalnya, terasa berat, karena kegilaan adalah ketika kita tidak tahu lagi harus bagaimana.
Ketika kita tidak bisa membuka jalan ke depan atau balik lagi ke belakang. Kita berjalan di
tempat!”
“Aku merasakannya, aku pernah mencobainya,” ungkap Riang.
“Di dunia ini, setidaknya manusia yang tidak mau melakukan pertaruhan untuk
mengalami peningkatan kapasitas intelektualnya. Ada pula manusia yang mengikuti
kehidupan layaknya alunan air. Dia melaju dengan ketenangannya. Mendapatkan
pembelajaran tanpa mengalami proses yang berat. Dia mencicil sedikit demi sedikit
kemampuan intelektualnya. Orang seperti ini jarang mengalami kompleksitas kedahsyatan
pergulatan pemikiran. Bagi mereka, kemungkinan menjadi gila itu kecil karena pembelajaran
yang mereka lakukan bersifat alamiah.”
“Itu bukan kita.”
“Benar.” Riang tersenyum. “Sudah kau selesaikan komik Dragon Ballz?”
“Belum semua.”
“Sudah sampai pada kemunculan Bezita?”.
“Sudah.”
“Bezita manusia planet Namec. Ia manusia yang sama dengan Son Go Ku. Orang.
Orang planet Namec ambisius! Mereka pertaruhkan apa saja untuk menjadi kuat. Mereka
tingkatkan kekuatannya dengan mendekati ambang kematian. Mereka tahu, seandainya
melatih diri dengan cara-cara yang menyiksa, hingga hampir mati, mereka akan mengalami
peningkatan kekuatan yang pesat. Mereka pertaruhkan kematian untuk mendapatkan
kekuatan! Kita pun sama! Kita adalah orang-orang yang baik secara sadar atau tidak, mau
270
pertaruhkan keyakinan yang ada di dalam diri! Kita meyakini kosekuensi pertaruhan itu
adalah kegelisahan dan mengalami kegilaan. Kegelisahan dan kegilaan adalah konsekuensi
negatife pencarian makna yang kita lakukan. Tapi, jika kita berbicara tentang konsekuensi
positif maka kita akan mendapatkan segarnya saripati kehidupan. Kita mengalami
peningkatan-peningkatan yang signifikan. Karena itulah kita mau mempertaruhkan keimanan
kita”.
Riang teringat Mahdi. “Mengapa dia seperti itu?” tanyanya. “Apa Mahdi alami hal
yang sama dengan diri kita?”
“Jelas! Mahdi melakukan pertaruhan yang berbahaya. Ia gila karena ketika akal
menyangkal keyakinan yang dulu dianutnya, hati Mahdi menolak. Argumentasi Lintang yang
ditemuinya di Parang Tritis lebih baik dari argumentasinya tentang ketuhanan. Di dalam
jiwanya terjadi dua pergulatan. Ia tidak sanggup menerima kehebatan argumentasi Lintang,
tetapi ia tidak bisa tinggalkan keyakinannya yang dulu. Kepribadiannya terpeleset.”.
“Ya, Mahdi memang pernah alami hal yang sama dengan yang kualami.” Riang
insyaf. “Pertemuannya dengan Lintang, untuk yang keduakalinya, membuatnya bebas dari
pecahnya kepribadian. Apa pun keyakinannya, kupikir Mahdi hebat! Proses yang dialaminya
menakjubkan!”
“Kau pernah sebal ke Mahdi Yang?”.
“Dia patut disebali kok. Tapi, aku mulai menaruh simpati!”
“Itu, karena kau dan dia mengalami proses yang hampir sama.”
“Mungkin ya... aku tidak tahu.”
“Proses yang Mahdi alami adalah lukisan perjalanan hidupnya. Lukisan itu tidak akan
selesai hingga ia mati… Lukisan kita pun belum selesai Yang. Kita tidak tahu kedepannya
akan jadi apa. Masa depan bukan milik kita! Entah kedepannya, aku akan memiliki
keyakinan yang kuat atau murtad. Aku tidak tahu! Kita tengah berproses dan orang yang
menjalani proses pencarian --yang sama--, adalah orang yang memiliki kedekatan spiritual
dengan kita. Kita tidak berhak lecehkan mereka! Melecehkan orang atheis, melecehkan
agama agama lain diluar agama kita, melecehkan agnostis selama mereka menyadari dan
menjalani peroses pencarian kebenaran dalam kehidupannya. Kita tidak berhak melecehkan,
karena masa depan selalu terbuka untuk di jalani, karena masa depan adalah sebuah kanvas
besar kehidupan yang bisa dilukis oleh macam keyakinan apapun”.
Kata-kata Fidel, ungkapannya, keindahan ucapannya… Riang ingin mengerat lidah
Fidel menggunakan silet.
271
“Sebelum aku menjadi gila,” terang Riang. “Tolong katakana pada orang bahwa
kegilaan ini karena aku berusaha menggenggam keyakinanku yang purba ketimbang
menggantinya dengan yang baru! Kalau saya gila tolong jelaskan hal itu ke orang-orang yang
saya cintai!”
“Aku berdoa agar tidak memberitahukan itu ke orang-orang.”
“Dan saya pun berdoa untuk Mas!” Riang tertawa.
Jembatan kegelisahan telah Riang lalui, meski masih terlalu dini dan harus diuji. Jika
ia sudah berani mengatakan, bahwa kini kakinya menjejak di tanah planet Namec bezita,
maka ia harus mencari jembatan-jembatan kegelisahan untuk ia lalui. Agar ia meraih derajat
kesempurnaan, sebagai manusia yang selalu ingin berkembang.
Saat memikirkan itu, kedamaian datang seperti saat ia duduk di bawah pohon yang
mengeluarkan banyak O2. Suplai oksigen menderas masuk ke dalam paru-parunya.
Seakan pasien tuberkolosis yang menikmati terapi oksigen. Riang mengantuk. Ia
merasa hidup tanpa beban, seolah sampai dalam keadaan puncak, ketika baru dilahirkan.
Tapi itu beberapa waktu lalu.
“Kapan pulang?” membuatnya tidak nyaman. Masih di pondokkan, ia tuliskan
jawaban dan langsung memposkannya. Ia masih merasa harus di tempat ini, karena ia mulai
dijangkiti kembali rasa hampa.
RIANG TAK MENEMUKAN JAWABANNYA. Ia ingin tahu tapi tak tahu
memulai darimana agar ia tahu. Ia duduk di hadapan Fidel kembali. Bagaimana memulainya?
Hampa, ia ingin sesuatu. Ada yang mendesak. Ada yang berontak di dalam dirinya. Ia tak
mengerti.
“Aku melihat dirimu hilang. Aku merabanya. Jujurlah…” Todong Fidel padanya.
“Aku tak tahu… aku tak mengerti akan diriku, Mas.”
“Bicaralah… bicarakan apa saja.”
“Aku merasa ada yang mengganjal. Selama ini aku mendapatkan begitu banyak
pelajaran berharga dari Mas. Aku mendapatkan pencerahan pemikiran, mendapat beribu
macam manfaat darinya. Mas tahu benar bagaimana perkembanganku saat ini.”
“Aku mendengarkan Yang, aku mendengarkanmu.”
“Aku merasa diri tak berguna.”
“Apa yang membuatnya?”
“Mas memberi banyak hal, tapi aku tak pernah…” Baru saja Fidel akan berbicara,
Riang memotongnya. “Bukan … bukan memberi materi pada mas, tapi sesuatu yang
272
berharga di arasnya. Aku … Aku tidak bisa memberi pengetahuanku pada mas Fidel
mengenai apa yang kuketahui. Maaf … aku merasa …”.
Jantung Riang berdetak.
“Di hadapanku, kau merasa tidak memiliki harga?”
Pertanyaan itu membuat pintu hati Riang terbuka. Ada yang mengalir. Deras. “Aku
merasa tak berguna. Hidupku seakan sia-sia. Aku tidak bisa memberi. Tidak bisa berbagi!
Aku merasa terasing! Merasa terkucilkan. Hal ini sukar kujelaskan.” Riang menunduk. “Aku
orang yang aneh ya mas?”
Fidel menggeleng. “Sudah berapa lama kita hidup di dalam rumah yang sama?”.
“Berbulan-bulan.”
“Sudah cukup lama.”
Riang mengangguk
“Yang, kalau kukatakan bahwa kau berguna, bahwa kau berharga. Bahwa belajar itu
tidak mutlak mendengarkan sebuah perkataan, melainkan –juga-- upaya mempelajari
aktivitas seseorang. Apa Riang akan merasa tenang, jika aku mengatakan, bahwa Riang pun
memberikan banyak hal melalui apa yang Riang lakukan, bukan yang Riang katakan?”
“Dengan mengatakan itu, apa Riang merasa nyaman?” Fidel bernafas tenang.
“Jujurlah apa adanya. Jangan dipendam.”
“Terus terang belum. Aku sendiri jadi bingung,” Riang menggaruk kepalanya.
“Perasaan ini terlalu dalam hingga sulit untuk kuungkapkan.”
“Supaya lebih gampang lagi, aku tanya: apa yang membuat Riang merasa tidak
berharga dan berguna di hadapanku?”.
Riang berfikir lama. Diam tak bicara. Ia tak menemukan juga.
Fidel tersenyum. “Yang … saat ini kau sedang mengalami puncak-puncaknya
pembelajaran. Kau haus akan segala macam hal yang tersangkut paut dengan pengetahuan!
Kau inginkan sesuatu lebih dari itu! Ada kesadaran yang tak bisa kau ungkap bahwa kau
memerlukan eksistensi! Kau memerlukan pengakuan. Manusia memang begitu. Ini wajar.
Manusia adalah mahluk yang perlu dihargai dan ingin dihargai.”
“Kuperhatikan kau sudah banyak membaca? Kau meningkat di segala hal. Disaat
itulah kau memerlukan eksistensi diri untuk ketenangan spiritualmu. Peningkatan
pengetahuan seseorang memang harus disertai perluasan potensi lainnya.”
“Kau banyak mendapatkan input dan kau memerlukan output. Manusia ingin berbagi
dan kau pun ingin berbagi. Hanya saja kau bingung caranya”.
273
Riang renungi kata-katanya. Benar. Ia sudah mendapat input yang demikian banyak.
Ia mendapatkan banyak pengetahuan melalui pembacaan pembacaan literature yang
bertumpuk begitu banyaknya di ruang bawah tanah. Ia mendapat begitu banyak masukan dari
orang yang ada di hadapannya.
“Apa yang terjadi jika sesuatu digembungkan terus menerus tetapi tidak ada
penyusutan?” Tanya Fidel. “Ketika terlalu banyak masukan dan manusia tidak memiliki
saluran untuk mengeluarkannya, maka manusia akan merasa sakit. Bukankah makan tak
buang air itu sakit?”
“Ah, mas ini!”
“Aku sungguh-sungguh! Apa banyak minun, tetapi tidak pipis tidak akan membuat
manusia menderita.”
“Menderita.” Jawab Riang menyerah.
“Demikian dengan pengetahuan. Jika kau terlalu banyak memasukan pengetahuan,
tanpa mengeluarkannya, membaginya kau bisa sakit.”
“Sakit jiwa maksudnya?” Riang tertawa. Ia tahu Fidel benar.
“Ya sakit jiwa! Sedeng! Kurang lima menit! Gelo siah!” bentak Fidel
Riang tertawa.
Fidel memeriksa jidat Riang, “Masa? Kau tidak demam? Ambienmu tidak kambuh!?”
“Mas ini!”
“Ada pemasukan ada pengeluaran. Itu hukum alam. Jika kau tidak melakukan
ekskresi, mengeluarkan pengetahuanmu maka akan terjadi sesuatu. Jika kau merasakan
ganjalan yang demikian memberatkan, kufikir wajar, karena mungkin, karena kau …”. Fidel
berfikir keras untuk mengunyah kata-katanya, menjadikannya lembut. “Salahkah anggapanku
ini …?”
Anggapan apa Mas?”.
“Kau terlalu menghormatiku, sehingga kau tidak berani berpendapat banyak saat aku
ada?”.
Riang diam lagi.
“Kau seperti pengantin yang baru naik ranjang!”
Muka Riang merah.
“Yang … jika memang seperti itu. Jika memang eksistensiku, keberadaanku membuat
Riang tak mengeluarkan pemikiran pribadi yang orisinil, sudah selayaknya aku tidak menjadi
sahabat bagimu!”
“Aku menghormati Mas!”
274
"Apa penghormatan mengharuskan seseorang bungkam? Kufikir kau bukannya tidak
bisa memberi, jika memberi itu berargumentasi atau bertukar fikiran denganku! Kau tidak
berani!”
“Yang … penghormatan adalah sesuatu yang baik karena penghormatan adalah
tindakan yang bisa mengantarkan pada pengertian. Mengantarkan pada keselarasan!. Tapi,
jika penghormatan justru membuat kau menjadi kacung pemikiranku, rasanya lebih baik kau
tidak hormat padaku!”
“Menghormati bukan berarti merendahkan diri! Menghormati bukan berarti
membungkam isi hati! Pengutaraan isi hatimu, penyuaraan pendapatmu, orisinalitas
pemikiranmu justru sebuah penghormatan yang besar bagi ku! Betapa bangganya aku jika
bisa melihat dirimu seperti itu!”
Riang mengangguk lesu. Perkataan Fidel tepat menggambarkan keadaan hatinya.
Riang merasa lesu, merasa berdosa karena menganggap dirinya memaksakan kehendak, agar
Fidel mengakui eksistensi dirinya.
Tetapi bukankah Fidel adalah edisi khusus? Manusia pilihan yang telah diciptakan?
Di wajahnya tidak terlukiskan gurat-gurat penyesalan dan kekecewaan. Fidel siap dengan apa
yang terjadi, sejak saat ia menempatkan Riang di rumah ini. Sejak ia memperkenalkan
teman-temannya dengan Riang.
Ini babakan baru dalam hubungan Riang dengannya. Apa yang akan terjadi
selanjutnya?
“Kau akan menjadi raksasa suatu saat nanti...” Fidel mulai meracau.
“Ah mas ini.” Riang gilani.
“Tidak! Jangan-jangan kau hentikan dulu! Aku tidak bermaksud mematikanmu lebih
awal dengan memuji! Aku mengetahui benar potensi yang kau miliki! Keberanianmu,
ketekunanmu, hausmu!”
“Terus hargai otakmu yang punya kapasitas jutaan giga itu! Manfaatkan! Hingga kau
tak mampu lagi memanfaatkannya! Dunia ini teramat ramai! Suatu saat kau akan
meredakannya! Dunia ini teramat sunyi dan kamu akan menyorak-nyorakinya!”
“Percayai dan hargai dirimu! Manusia itu sama di mata Tuhannya! Sejak dulu aku
tidak pernah menganggapmu sebagai lading yang hendak ku garap. Di alam persahabatan,
semua sahabat adalah sama!”
“Sejak dulu aku tidak membiarkan Riang berada di belakang tubuhku, karena Riang
bukan budak ku! Kau ada di sampingku, kau sahabatku!”
Tenggorokan Riang serak. “Dulu aku tak menyadarinya.”
275
“Dan Sekarang kau baru sadar.”
Ingus Riang meleleh.
Fidel membentak. “Sadarlah wahai manusia! Taubatlah wahai invertebrata!”
“Sadarlah unggas unggas dan minyak jelantah!” Riang tertawa.
“Terima kasih atas pelajaran yang kau berikan. Atas proses perubahan yang tekun kau
lakukan!”
Riang tak mau kalah. “Terimakasih pula atas pelajaran betapa pentingnya makna
sebuah persahabatan.”
“Terima kasih!”.
“Aku mencintai mas!” Kata-kata itu mengalir begitu saja.
“Dan aku tak akan mengatakan cintaku padamu.” Fidel tidak menampiknya.
Ah, persahabatan kadang tidak mutlak diawali dari kesetaraan. Riang tahu diri, meski
sejak dulu Fidel telah menerima dirinya, ia tetap merasa tidak setara. Riang sadar, kesetaraan
yang didapatkannya, pun, melalui pertolongan Fidel. Kesetaraan baginya bukanlah
kesetaraan dari berbagai sudut pandang. Baginya Fidel lebih dari segalanya. Semua itu hanya
dapat ditandingi oleh Lintang. Mereka setara. Layaknya mur dan baut mereka saling
melengkapi satu sama lainnya.
Mereka tak berbahasa. Diam.
“Mengapa tidak kau buat zine saja?!”
Lalu penemuan yang dilontarkan Fidel abad ini pun tercipta.
ZINE
276
“Dengan nama Tuhanmu! Mabuklah!” Waluh memberi Riang setumpuk zine.
Milea tertawa. Ia mengeluarkan setumpuk zine lain dari ranselnya.
“Banyak sekali!” Riang mencicit minta ampun. Ia membalik-balikan tumpukkan zine
itu hingga lecek. Prisca Pricilia, Kontaminasi Kapitalis, No Compromise, HC, Openmind,
Tiga Martil, Brigade Lawan Arus, Apocalypse hanyalah beberapa zine yang Riang pegang
ditangannya.
Bundelan kertas yang dipegangnya adakalanya sarkas namun full logika. Di penuhi
makian yang berseni, sinisme, kritisme, skeptisisme. Ada yang memadukannya dengan data,
ada pula yang sembarang nyablak mengenai kehidupan sehari-hari yang dipenuhi kesegaran
caci maki. Zine-zine adalah tempat pembuangan.
“Tempat modol, beol!”
“Jangan bicara kotor! Ada anak-anak di sini!” Eva mengingatkan.
Riang mengerti. Bukankah ekskresi adalah membuang sesuatu. Fred tidak berlebihan.
Membuat zine pada hakikatnya seperti yang pernah dikatakan Fidel dan dikuatkan Fred,
adalah juga membuang kesakitan. Jadi, kata Waluh jika Kau ingin membuatnya, jangan
pernah terbebani berpikir mengenai apa tulisanmu berguna atau tidak, bagus atau jelek. Zine
adalah tempat berbagi. Zine adalah tempat pelepasan, yang isinya tidak seperti yang Riang
dapatkan di media massa atau majalah-majalah yang dikatakan Waluh, majalah mainstream.
Zine-zine itu bernyawa! Memiliki jiwa-jiwa! Uh… uh Riang tertantang untuk mencipta!
“Bagaimana dengan desainnya? Bagaimana dengan izinnya!?”
“Memang syarat membuat zine harus ada izin dari pemerintah? Memang pemerintah
bisa mengatur seluruh kehidupan kita?” Waluh tergelak. “D.I.Y do it your self! Semangat
zine ada di sana! D.I.Y adalah pengambilan alihan kontrol yang dilakukan negara dan
menggantikannya dengan kontrol individu! Zine itu otonom! Buat sendiri, tulis sendiri!
Kalau kau tidak bisa menulis, curi tulisan orang! Pembajakan untuk pengetahuan adalah sah!
Untuk masalah desain-mendesain, gampang! Yang penting saat ini, selesaikan saja dulu
tulisanmu!”
Riang pun mengalihkan seluruh tulisannya pada buku catatan ke atas selembar kertas
kuarto. Setelah memodifikasi bahasa dan ia merasa kontennya sudah cukup. Riang pun
melapor. “Sudah selesai!” katanya.
“Tambahkan ini!” Fidel mengambil puisi-puisinya.
“Muat juga terjemahanku ini!” Waluh mengeluarkan print out mengenai biografi
Zapata.
277
“Lha desainnya bagaimana?” tanya Riang.
Milea membawakan majalah bekas yang menumpuk di gudang.
“Gunting topi tentara itu” Fidel menunjuk foto topi tentara pada sebuah majalah.
“Gunting semua. Preteli. Gambar apa saja. Ban, pisau dapur, pistol, gelas mineral, obeng,
gambar kerbau, apa saja yang Kau anggap cocok dengan karakter tulisan yang akan Kau
muat di dalam zinemu!” Fidel tahu Riang bingung. “Gunting saja!” sahutnya. “Tak usah
bertanya!”
Fidel meminta Milea untuk membantu Riang menggunting paragrap tulisannya.
Setelah gunting menggunting selesai. Fidel mengambil kertas kosong, yang segera ia penuhi
dengan guntingan paragrap tulisan yang terkumpul. Kertas menjadi penuh warna setelah
dihiasi gambar-gambar yang terkesan tak beraturan.
“Tunggu sebentar!” Waluh membawa lembaran kertas-kertas itu. “Jangan kemana-
mana,” teriaknya pada Riang.
Riang menunggu. Bagaimana jadinya, majalah tanpa izin itu? Bagaimana bentuk
majalah aneh yang dikerjakan dengan kepercayaan diri di luar batas itu?
Dua jam kemudian, suara knalot yang menyejarah sampai di pondokan. “Aku
memfoto copi 200 eksemplar. Ini!” Suar bruk! zine yang diikat tali rapia terdengar keras.
Riang membukanya. Oladalah! Megaphone nama zine-nya! Namanya tertera jelas,
teramat sederhana namun Riang melihatnya menyala, deemikian meriah! Uah! Cup! Cup
muah! Segala macam bentuk sukacita! Semua suka cita! Tak ada bir tak ada psikotropika
yang membuat huru hara! Semua gembira! Derit kereta uap Christopher Morley! Terima
kasih untukmu duhai dewi penggandaan masal! Duhai kekasih para nabi dan mesin foto
kopi!
Zine Megaphone membuat Riang bangga! Bagaimana bisa? Aku yang membuatnya?
Oh tidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak! Riang berteriak dalam hati. Kepalanya benar-benar
iritasi! Riang tersenyum gembira seolah hari itu adalah hari di mana amalan baik diterima
menggunakan tangan kanannya.
“Kita distribusikan siang ini!”
“Mengapa tidak?!” Riang menjawab tantangan Bentar.
“Tapi uangnya mana?!”
“Uang apa?”
“Ini masalah sensitif Bung!” Bentar menghentikan kegembiraan Riang. “Kau pikir
foto kopi dua ratus eksemplar menggunakan daun?! Dua ratus eksemplar itu menggunakan
uangku!”
278
Riang terpojok.
“Uang simpananmu! Uang simpananmu!” Bentar seperti satuan pamong Kemarikan!
Kamarikan!”
Riang menghabiskan uang di dompetnya.
“Segini sih cuma dua puluh lima eksemplar!” ejek Bentar.
Fidel tertawa. “Kubayar lima puluh eksemplar untuknya!”
Milea ikut serta. “Aku tujuh puluh lima!”
“Lima puluh eksemplar yang lainnya mana?!” wajah Bentar mulai tampak seperti
anggota asosiasi penagih hutang.
Tak ada lagi yang relakan uangnya.
“Ngutang Mas,” Riang memelas. “Ngutang ya Mas?”
Fred memperagakan tangannya. “Om, om minta uang om. Om kasihan Om!”
“Yah, kalau begitu aku talangi saja!” Bentar pura-pura kecewa.
“Ashik! Asyek!” Riang berhula-hula! Ia tahu semua orang bermain sandiwara.
DALAM ETHOS D.I.Y, seseorang tak mungkin mengetahui berapa eksemplar zine
yang sudah ia sebarluaskan. Di luar kopian yang dikeluarkan pembuatnya, zine dapat
menggandakan diri tanpa bisa dikontrol. Pembajakan atas suatu karya seni, suatu perbuatan
yang di dalam dunianya dilakukan tanpa izin tetapi tetap dengan mencantumkan nama
penciptanya sebagai bentuk penghormatan. Gairah membajak inilah yang mampu
menjadikan sebuah zine yang hanya dicetak 100 eksemplar, menggandakan dirinya hingga
menjadi 5000 eksemplar.
Pembajakan adalah perlawanan! Adalah salah satu keyakinan utama bahwa ilmu
pengetahuan harus dikembangkan tanpa batas. Melalui distro-distro, dan Peniti Merah
Jambu, sebuah jaringan informasi penerbitan zine, Megaphone masuk ke daftar zine baru
yang dicari.
Riang tak tahu jika Megaphone-nya ditenteng orang di sebuah beberapa gigs (konser)
Skin Head di Jakarta, dibicarakan wanita yang cuping hidungnya dihiasi tindikan. Ia tak
mengetahui jika potokopian Zine-nya dibarter dengan uang dan zine luar kota yang berbeda,
ditukar dengan kaset, ditukar dengan kaus, ditukar dengan keikhlasan.
Megaphone mengganda tersebar hingga ke Malang, sebuah kota yang ethos D.I.Y
kolektif underground-nya nya tak perlu di ragukan kembali. Respon yang tak terduga pun
berdatangan. Satu bulan semenjak pendistribusian zine Megaphone, enam buah surat sampai
279
di pondokkan. Riang tak menanggapi surat-surat itu. Ia bukannya besar kepala. Uang Riang
tidak mencukupi untuk membalas surat-surat yang entah dari mana itu.
“Kita cantumkan e-mail di edisi Megaphone selanjutnya,” Milea menyarankan.
Mengenai, email itu barang apa, Riang tak tahu. Ia mau belajar. Ia rela menjadi anak
bawang. Milea mengajari Riang, sesuatu yang di abad informatika ini merupakan sesuatu
yang sangat sederhana. Diajaknya Riang ke warung internet. Di sederhanakannya
pengetahuan teknologi komunikasi untuk Riang. Keduanya tak sadar. Riang dan Milea, tak
memahami jika hubungan mereka menjadi hangat. Zine semakin menautkan hubungan
mereka.
Semenjak dibukanya alamat surat elektronik Megaphone, korespondensi pun
berlangsung dengan baik selama dua edisi ke depan. Saat edisi ke lima tengah di siapkan dua
buah subjek melaut di dunia elektrik dan sampai di geladak maya perahu Riang. Dari
seseorang yang mengakui kera Ngalam, arek Malang, seorang wanita --yang sejak edisi ke
dua Megaphone dilepaskan-- memberi tanggapan. Ia mengajak Riang bertemu, sementara
dari Jakarta sebuah attachment meminta Riang menjadi salah satu pengisi obrolan santai
mengenai Zine dan ideologi contra cultura
Menerima surat yang terakhir itu liver Riang jadi tak seimbang. Ia berdebar. Aku
yang anak desa ini? Aku … Aku …tulisanku di baca mahasiswa yang sebentar lagi sarjana?
Oh Atlas menduduki bola bumi! Dunia terbalik! Oh, Riang masih ingin hidup seribu tahun
lagi!
“Datangilah Jakarta!” dukung Fidel. Ia bersemangat saat mengetahui berita itu.
Percaya diri Riang masih setengah. Riang berharap Fidel menemaninya. Semisal
purwaceng dan ginseng, Fidel adalah suplemen yang berkhasiat, buat Riang. Fidel tak
menampiknya.
SABTU SUBUH mereka berkemas menuju stasiun. Jam sembilan pagi kereta
memasuki stasiun Gambir Jakarta. Di stasiun itu nyala emas terlihat membeku di kejauhan.
Monas berdiri sendiri di tengah lahan gersang paving block. Kereta ekonomi oranye datang.
Perjalanan mereka lanjutkan hingga Pondok Cina.
Saat kereta singgah di Pondok Cinta, dari jendela kereta seseorang wanita membawa
nama Riang pada selembar karton. Mereka turun.
Seorang mahasiswi menyalami Fidel. “Mas Riang,” terkanya.
“Bukan.” Fidel menunjuk orang di sampingnya.
280
Riang keteteran. Apa wajahnya tidak tampak intelek? Apa performa dirinya tidak
meyakinkan? Riang tidak menggunakan stavolt. Kepercayaan dirinya naik turun saat itu.
Wanita yang mengaku bernama Nizar itu tidak merasa nyaman dengan
kesoktahuannya. Ia menyogok Riang dan Fidel menuju kantin. Di areal kantin, Nizar
memesan makan pagi lalu menyerahkan kertas biodata. Riang merasa lega. Nizar tidak
mempermasalahkan jenjang pendidikannya dan beban Riang hilang setengah ketika Nizar
mengatakan, “Terserah Mas, membahas apa asal yang nanti disampaikan terkait dengan tema
yang diketengahkan.”
Usai makan, tak jauh dari kantin, Riang kemudian dipertemukan dengan seorang
pembuat zine Lelaki pembuat zine Arvatar yang Nizar perkenalkan mengaku menggunakan
nama pena Illuminat dalam zinenya, namun nama aslinya Joned. Nama yang sedikit aneh di
kuping orang Jawa Tengah itu membuat Riang sukar menyembunyikan tawanya. Di kepala
Riang sepertinya ada speaker yang terus menerus mengumandangkan nama Joned. Illuminati.
Joned. Illuminati… Jauh sekali zine dengan nama pembuatnya, pikir Riang. Di hadapan
lelaki yang rambutnya gimbal dan kakinya dibalut boots tinggi itu Riang mati-matian
menahan tawa. Riang tidak mau dihabisi lelaki botak menyeramkan itu. Bagaimana ia
sanggup melawan jika kausnya saja bertuliskan: sendiri melawan sistem. Luar binasa!
Masuk ke dalam auditorium Fidel memisahkan diri. Riang dan Joned menunggu tepat
di hadapan meja panjang. Tak beberapa lama kemudian acara di mulai. Seorang pria lainnya
bergabung Ia mengenakan planel. Rambutnya cepak. Bibirnya di tindik.
“Bleeding Balerina zine.” Demikian ia memperkenalkan produknya.
“Riang. Dari Megaphone zine.”
Lelaki itu tertawa karena lupa menyebut nama. “Namaku Sama!” ucapnya.
“Nama mas Riang?” Riang tak percaya.
“Namaku Sama!”
Riang ragu. “Nama mas sama dengan namaku?”
Lelaki itu menunjuk mukanya. “Namaku Sama! Bukan Riang!”
Riang berpikir keras. “Sama… Riang?”
Lelaki itu kesal. “Nama aku Sama! Sama! Sama! Bukan Riang!”
Riang mencerna cukup lama. Tak merasa nyaman. Ia tak menanyakan lagi
kebingungannya pada lelaki yang kemudian moderator memanggilnya Sama. Obrolan aneh
yang tak bertahan lama itu terjadi di tengah suasana ramai. Riang merasa dipandangi
mahasiswi cantik. Riang grogi. Ia merasa terbebani. Bagaimana jika tak bisa bicara?
Bagaimana jika ia menjadi tuna rungu? Keringat mendadak bermunculan di sela jemarinya.
281
Riang gemetar. Di dadanya ada tambur. Lidahnya berubah menjadi sekering savana. Dua
kali ia mengosongkan gelas mineral, dan tindakannya itu membuat kandung kemihnya
kembung. Riang kebelet kencing.Ya Tuhan. Bagaimana ini. Kantungi batu! Riang teringat
petuah masa-masa remajanya, namun di mana ia harus memungutnya? Carilah yang berat-
berat, bisikan nenek moyangnya datang. Mikropon? Tidak mungkin! Boots Joned? Uh itu
akan mendatangkan perang etnis Rwanda. Keringat Riang sampai di bagian belakang
lehernya. Ini masa kritis.
“Mbak … mbak!” Riang tak menyadari jika didekatnya tergeletak mike. Sound system
yang dipancangkan di setiap rangka bangunan merekam dan mempidatokan suaranya. Panitia
yang tengah membagikan kopi-an zine bereaksi.
“Mau apa?!” Sama menawarkan pertolongan.
“Pengen pipis. Ndak tahan!” Riang tak sadar jika ia memegang senjata
pamungkasnya.
Sama yang penampilannya berbanding terbalik dengan kebaikan hati segera merebut
mike, lalu menekan tombolnya. Mike mati, tetapi suara seseorang yang tengah menggenggam
biological future weapon itu terlanjur didengar seisi ruangan. Riang sadar ia ditertawakan. Ia
merasa malu, tetapi pipis adalah prioritas utama dan pertama. Tak ada yang lebih penting
darinya. Riang langsung berjalan cepat setelah panitia memberi Riang kode untuk
mengantarnya.
Saat misi terselesaikan dan prioritas utama telah Riang tunaikan yang tertinggal
dalam diri Riang adalah rasa malu. Riang malu. Ia mencuci wajahnya keras. Kini, gardu
listrik kepercayaan dirinya bukan saja tanpa stavolt. Kepercayaan diri Riang hilang.
Fidel mengetahui tentang hal itu. Ia keluar dari tempat duduknya kemudian meminta
panitia yang tengah menunggu Riang untuk kembali ke ruangan. Fidel menungguinya cukup
lama dan menyaksikan bagaimana ketika pintu kamar mandi wajah yang lepek, seolah-olah
wajah itu merupakan makanan basi swalayan yang dikomplain beberapa pelanggan melalui
surat pembaca Kompas.
Fidel berusaha membantu Riang untuk bersikap biasa. Ia memasang mimik tak
memiliki ingatan. Ia memasang sikap biasa hingga menjadikan Riang merasa aneh dengan
sikapnya. Ia tak sadar jika Fidel mengambil inisiatif, mengalihkan perhatiannya. Fidel
membicarakan beberapa arahan tanpa sekalipun mengetengahkan subjek yang menjadi bahan
ketakutan Riang. Dan sekembali Riang ke dalam auditorium, kepercayaan diri Riang tumbuh
kembali.
282
Riang mendapat kesempatan terakhir bicara dalam obrolan santai itu. Joned dan Sama
mengawalinya. Dua orang itu terbiasa bicara di hadapan orang. Dengan analogi yang
menyentil, pemaaparan mereka menjadi renyah. Ketika giliran Riang tiba, Riang merasa
kandung kemihnya serasa mau bocor. Tak percaya diri datang membuatnya kembali kalut. Ia
melihat Fidel. Riang membutuhkan bantuannya. Di sudut kiri atas auditorium Fidel pun
berdiri memberi energi. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencontohkan agar Riang
mengikutinya. Rasa nyaman menjalar, membuat Riang merasa ringan saat Fidel
mengacungkan jempol.
Genggaman pada mike Riang perkuat..
“Ehm… selamat siang. Siang-siang selamatan!”
Orang-orang terhibur. Ada senyum yang ditebar dan saat suasana hangat di ruangan
itu menyebar, dengan cerdasnya Riang mengambil kesempatan, mulai berkicau. Ia tidak
membicarakan mengenai counter hegemoni dan contra cultura terhadap kapitalisasi yang di
musuhi kebanyakan pembuat zine. Ia hanya membicarakan hal yang sederhana bagaimana
zine bisa membuatnya merasa lega. Merasa berharga. Merasa bulat, menjadi utuh dan penuh.
Tentu, pembicaraan yang begini, tidak sepenuhnya sesuai dengan tema panitia yang
bombastis. Riang tidak menangkap efek negatifnya kekecewaan panitia, tetapi ia tak
membutuhkan waktu lama untuk mengobati kekecewaan mereka. Riang membayarnya!
Kontan tanpa bon!
Dalam sesi berikutnya, beberapa orang kemudian mengutarakan pendapatnya
mengenai materi ketiga zine. Ada diantara komentator yang memuji artikel mengenai
perjuangan Zapatista bersama suku asli di Chiapas Mexico dan memberi apresiasi mengenai
essay konsepsi ideologi yang diuraikan zine Megaphone. Mereka tidak tahu jika tulisan itu
bukan Riang yang membuatnya. Riang berharap, Fidel mau membicarakan hal tersebut,
tetapi dari kejauhan ia hanya melihat Fidel memberi tanda, bahwa dirinya menyerahkan
sepenuhnya pembahasan pada Riang.
Riang memberikan jawaban tuntas, lalu dari tengah-tengah peserta tiba-tiba seseorang
pria meminta panitia untuk memberikan mike. Ia sudah memendam apa yang ingin ia
utarakan sedari tadi. Di sesi pertama, pria itu sudah mengangkat tangannya berkali-kali tetapi
moderator tak memberinya kesempatan. Lelaki itu mengambil mike. Wajahnya terlihat biasa
tetapi mulutnya luar biasa. “Zine ini sampah total,” katanya. Pria itu memasukan tangannya,
ke saku celana dengan gaya yang hampir menyerupai tolak pinggang. “Apalagi ketika zine
ini membicara ideology,” lelaki itu melanjutkan. “Ideologi itu mencret. Mencret monyet.
Karena ideology perang muncul.
283
Antara manusia berjibaku, perang! Saling berseteru! Ideologi tak memiliki fungsi selain
melakukan dekonstruksi! Melakukan penghancuran total manusia, apalagi ideologi agama.
Nah, yang kau tulis dalam zine mu ini lucu. Kukatakan sekali lagi, ideologi yang kau
sampaikan itu mencret. Seharusnya dunia tak memiliki ideologi, yang penting bagi manusia
bukan ideologi tapi rasa saling menghormati.” Kata mencret berulang-ulang dikatakannya
dengan santai, hampir tidak mengeluarkan emosi. “Apa pula ini?” Pria itu lalu mengewer-
ewer zine Riang seolah jijik. “Zine ini seolah-olah memberitakan sesuatu, tetapi yang di muat
di dalamnya bukan contoh berita. Bahasa dan kata-katanya tidak sesuai dengan kaidah
jurnalistik. Di sini banyak sekali ketidak seimbangan. Orang yang membuatnya tidak intelek,
selalu merasa paling benar. Cobalah berada di tengah, jangan membuat berita yang
berpihak.”
Moderator yang kurang jam terbang mulai mengingatkan, tetapi dengan gaya sok-nya
Riang mengatakan tidak apa-apa. “Biar ramai.” Katanya.
Moderator berpikir cepat. Ia yang bertanggung jawab mengendalikan forum, tetapi ia
dituntut pula untuk membuat suasana menjadi hangat. Ia tergoda oleh tawaran “biar ramai”-
nya Riang. Ia memberi Riang jatah bicara.
“Yang penting rasa saling menghormati,” Riang memulai, “tapi komentarmu tidak
sesuai dengan apa yang Kau katakan. Ibarat kecelakaan, ucapanmu ibarat tabrakan beruntun
truk tronton di jalan! Kau mengajarkan orang untuk saling menghormati, tapi Kau sendiri
tidak memulai untuk menghormati keyakinan orang mengenai ideologi! Banyak hal yang
juga harus di pertanyakan mengenai omonganmu tadi: apakah benar yang paling penting di
dunia adalah saling menghormati. Apa bentuk saling menghormati itu? Apa saling
menghormati akan menyelesaikan seluruh permasalahan manusia? Hidup di dunia lebih
rumit dari itu. Negeri ini kaya. Bagimana agar kita dapat menikmati sumber daya alam yang
sama? Bagaimana mendistribusikannya secara merata? Apa dengan saling menghormati
masalah-masalah itu akan terselesaikan? Di sanalah salah satu arti pentingnya ideologi.
Distribusi adalah salah satu unsur kecil yang diatur ideologi.” Riang tak merasa jika ia
berbicara cepat. Nada bicaranya memperlihatkan emosinya naik. Hal itu menguntungkan
sebab Riang menjadi lupa segalanya. Ia hanya terfokus pada apa yang ingin ia sampaikan.
Fidel terkejut dengan yang di sampaikan Riang. Ia tidak tahu hingga sejauh dan
secepat itu nalar Riang terasah. Ia tak mengira. Fidel tak menyangka. Fidel yang semula
bertopang dagu. Duduk siaga, menanti ungkapan-ungkapan macam apa yang diungkapkan
anak desa Thekelan tersebut.
284
“Mungkin majalahku, zine yang kubuat itu tidak sesuai dengan harapanmu. Tidak
apa. Aku tidak menganggapnya sebagai masalah, sebab sejak awal membuat zine Aku hanya
ingin berbagi. Apalagi, jika bicarakan kaidah kata dan bahasa. Apa itu?” Riang mengangkat
tangan dan bahunya. “Aku tak tahu. Apa aku harus memahami kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar dulu sebelum membuat zine? Kalau seperti itu kapan buatnya? Kalau seperti
itu buat saja koran. Aku tidak mu terbebani. Biar saja orang mengatakan apa. Aku tak
memerlukan tetek bengek peraturan berbahasa, tih peraturan itu manusia yang membuatnya.
Aku juga bisa membuat aturan berbahasa. Aturan yang tidak memiliki aturan. Kenyataannya
apa yang kutuliskan ini bukan untuk dijadikan koran harian. Zine adalah zine. Terserah yang
membuatnya. Kalau yang membuatnya mau bicara tentang menghayal menjadi kambing, apa
salahnya? Kalau zine bicara tentang mengupil yang enak memangnya kenapa? Kalau yang
buatnya tidak menafikan keberpihakan, toh, kamu yang mungkin menganggap diri berada di
tengah-tengah berpihak juga! Kalau Kau tetap merasa ini sebagai sebuah masalah, buat saja
zine sendiri. Jangan dibuat susah!”
Bantahan Riang seperti setrika. Lelaki itu panas. “Bisa saja ngeles! Orang yang anut
ideologi kebanyakannya memang kepala batu macam ini!” Ia yang santai menjadi deras.
“Itulah kenapa –seperti yang kukatakan—ideologi membuat manusia saling berperang,
terutama ideologi agama yang membuat manusia menjadi ganas. Agama itu virus akal budi!”
Riang tertawa. Tawanya semakin membuat panas. “Memang aku jagoannya! Aku
jagoan ngeles!” Riang menyombong. Dalam benak Riang tergambar jelas bayangan masa
lalu dia mengenai agama. Tergambar jelas bagaima cara Fidel menggambarkan kesalahan
pengambilan kesimpulan yang pernah ia lakukan.
“Inilah ciri-ciri fundamentalis agama!” Pria itu menyimpulkan jawaban Riang ketus.
Riang langsung menggunting perkataannya. “Apa yang salah dengan
fundamentalis?! Kamu pun fundamentalis! Fundamentalis tengah-tengah! Kalau Kamu
mengatakan aku radikal maka Kau pun radikal! Kau pikir ada gunanya? Bahkan orang yang
menulis artikel tentang ideologi di zine-ku jauh lebih baik ketimbang dirimu!” Riang melihat
Fidel, tetapi Fidel menunggu. Ia membiarkan Riang. Ia mempercayakan padanya.
“Lihat di sana!” Riang menunjuk Fidel. Tak etis memang, tetapi Fidel melazimkan.
“Dia, lelaki itu tidak pernah menyepelekan orang! Dia faham bagaimana berhubungan
dengan manusia! Dia paham, seseorang berhak memilih jalan hidupnya, tetapi setiap orang
pun berhak meninjau keyakinan yang lain. Yang dia lakukan dalam zine-ku hanya
berkomunikasi. Caranya pun santun, berbeda dengan caraku! Dia tidak sok-sokkan seperti
lagakmu! Dia yang menghormati orang lain biasa saja dengan mulutnya! Kamu! Kamu yang
285
bilang ke sana kemari bahwa dirimu bukan fundamentalis, pada kenyataannya malah
memperlihatkan bahwa pemahaman dirimulah yang paling benar!”
“Ah!” Pria itu membantah. Ia menunjukan artikel dalam zine Riang. “Sistem yang
Kau propagandakan dalam zine mu itu sistem kuno! Ideologi purba yang tak berhak hidup di
zaman modern ini!”
Moderator mencari artikel yang dimaksud lelaki itu. Ia berusaha masuk ke dalam
perdebatan. “Di zine mas Riang ada pemahaman mengenai ideologi dan sistem yang tadi
disebut purba,” moderator bertanya “bagaimana menjelaskannya?”
Riang sudah marah. “Bisa jadi yang diyakini Mas itu lebih purba ketimbang
keyakinan sahabatku!” jelasnya pada moderator. Riang bukannya memaparkan pertanyaan.
Ia malah kembali menyasar pria itu. “Purba dan tidak purba hanya propaganda! Propaganda
tidak perlu dibicarakan karena propaganda bahasa tidak perlu di perbincangkan oleh pencari
kebenaran!”
Pria itu membantah. “Tetap saja! Sesuatu yang purba tidak mungkin diterapkan lagi,
di sini dan saat ini!” Pria itu bertahan. “Yang diperlukan manusia bukan formalisasi! Yang
diperlukan manusia kesejahteraan, keadilan! Dasar muslim kepala batu!”
Riang sampai pada puncaknya. “Aku bukan muslim! Aku tak beragama!!” Wajahnya
terlihat merah. Pria itu salah melakukan diagosa. Ia meminum racun. Auditorium benar-benar
menjadi sepi! Moderator mulai berpikir untuk mengakhiri forum. Ia berusaha mencari jeda
bernafas untuk memutus perdebatan, tetapi nafas Riang terlalu panjang. Seakan hutan
belukar, jeda bernafas sukar moderator temukan.
“Keadilan! Kesejahteraaan!” sambung Riang. “Macam apa keadilan dan
kesejahteraan itu? Keduanya filosofi kehidupan!” Riang marah. “Setiap manusia mudah saja
membicarakan keadilan dan kesejahteraan! Camat, walikota tak ubahnya sama dengan
tukang becak, tak jauh beda dengan gelandangan jika sudah membicarakan keadilan dan
kesejahteraan! Keadilan dan kesejahteraan itu filosofi yang harus dibumikan! Apa yang
dibicarakan temanku dalam tulisannya sudah jauh meninggalkan tetek bengek yang Kau
koarkan! Ia sudah bicara bagaimana membumikan keadilan dan kesejahteraan dalam
pengaturan sistem, dalam perangkat ideologi, dalam tataran yang bahkan bersifat matematis!
Kau ku ajak berbisnis! Mari bisnis warung internet! Kita sama-sama menginginkan
keadilan! Tapi keadilan yang bagaimana! Pembagian untukku sekian, sebagai pemilik modal,
dan Kau sebagai pengelola warnet sekian! Hak kamu begini! Hak aku begitu! Dalam bisnis,
dalam distribusi pengelolaan sumber daya alam, dalam pengelolaan harta warisan, dalam
peperangan, dalam pengumpulan harta untuk distribusi kesejahteraan semua konsep harus
286
dibumikan. Sekarang … keadilan dan kesejahteraan macam apa yang Kau inginkan itu!
Bagaimana membumikannya! Mari kita membandingkan!”
Mendengar tantangan Riang, pria itu keracunan arsenik. Ia tercekik. Riang memberi
tiger upper cut macam pukulan Guild Street Fighter dalam permainan ding-dong. Pria itu
membisu. Ia terkena mantra, tak bisa bergerak. Pria itu beku seperti ditenung! Sunyi
mengurung auditorium seakan karamba.
Di atas sana, tiba-tiba Fidel berdiri. Cahaya lampu ruang yang dibiaskan kaca-kaca
bergoyang. Mata Fidel berkaca-kaca. Ia menepukan tangannya di udara. Fidel bangga!
Gemuruh menjelma. Tepuk tangan di mana-mana, menggema! Untuk pertama kalinya, Riang
dimuliakan. Tepuk tangan menjebol pertahanan jiwanya. Riang tak kuat menahan haru.
Bukan karena kemenangan tetapi karena rasa kasihan. Pria yang dipukulinya habis pergi
meninggalkan forum yang bukan lagi miliknya. Ia mundur perlahan. Riang memandangnya
dengan penyesalan. Kemanusiaannya bermain. Lelaki itu hanya orang biasa, sama seperti
dirinya. Ia manusia yang butuh dihargai bahkan setelah ia dikalahkan. Pria itu menghilang di
balik kerumunan.
Moderator bernafas lega. Acara yang ia pandu berakhir klimaks. Ia mengakhiri
tanggungjawabnya.
“Tatum valet auctoritas quantum valet argumentatio! Aforisma bahasa Latin
mengatakan bahwa nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya. Mengutip terjemahan
bebas sebuah ayat: silahkan sekolah yang tinggi-tinggi! Silahkan! Tetapi jika sekolah yang
tinggi itu tidak membawa karya untuk manusia, maka sejarah dan masyarakat akan lupakan
dan tinggalkan kita semua! Demikian perkataan Pram! Terima kasih! Dan … mari kita beri
applause untuk mas Riang Merapi!”
Tepuk tangan menggema. Lebih meriah dari yang pertama. Dan hal itu justru
membuat Riang bertambah sedih.
DEBAT YANG MENYIMPANG dari Zinee dan ideology contra cultura tentu tidak
menjadikan orang-orang yang hadir berubah drastis pemikirannya. Perubahan paham tak
semudah mengangkat tangan lebih tinggi dari kepala agar burung unta tidak menyerang
manusia.
“Kadang manusia tidak bisa mengatakan seluruh isi kepalanya. Mungkin lelaki itu
memiliki sejuta macam argumentasi untuk membalikan argumentasimu, argumentasi di
dalam tulisanku,” kata Fidel. “Kadang, ketika emosi menyisihkan ketenangan dan peranan
akal, argumentasi di dalam kepala yang semula luas, menjadi sempit. Mungkin karena
287
kondisi psikologi yang kurang baik pada saat itu, lelaki yang ada di forum tadi tidak bisa
mengeluarkan argumentasi dengan jernih. Bisa jadi Kau mengalami hal yang sama. Dalam
kondisi normal Kau merasa mudah mematahkan pendapat-pendapat tertentu, tetapi dalam
forum yang disesaki banyak orang, dalam forum yang di hadiri orang-orang yang sering kita
lihat di televisi dan kita baca pendapatnya di media massa, ada kalanya kita merasa tertekan.
Tekanan itulah yang akan menghambat manusia dalam mengungkapkan seluruh isi
pikirannya.”
“Yang…” Fidel memalingkan padangannya. “Tak ada manusia yang kalah dalam
diskusi.”
“Lantas yang kalah siapa?” tanya Riang.
“Yang kalah, adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya salah. Yang kalah adalah
orang yang hatinya sudah mengatakan bahwa argumentasinya tidak bisa dipertanggung
jawabkan tetapi ia terus menerus melakukan pembenaran.”
Roda besi mulai mengayuh. Pluit panjang merusakkan gendang telinga masinis. Fidel
tumbang saat mencium jok kereta yang tengik. Di saat yang sama, lelaki di sampingnya
melamunkan banyak hal dan tentu saja: melamunkan Milea.
LIBURAN YANG TAK MUNGKIN TIBA
Begadang membuat tubuh Fred limbung. Tidur hanya dua jam membuat jalannya,
seperti orang yang baru menenggak minuman keras. Fred kecapaian menyusun laporan yang
dipesan. Laporan itu seharusnya ia kerjakan bertahap, ia cicil sedikit demi sedikit, tapi
kebiasaan menjadikan laporan itu menumpuk.
Sampai di sebuah rumah, Fred menekan bel dua kali. Seorang berseragam biru,
kamera cctv mengintipnya dari atas gerbang. “Mari masuk Mas.” Lelaki berseragam biru,
288
mengenal Fred baik “Bapak ada di dalam,” katanya.
Gerbang terbuka. Fred masuk. Ia diantar pemuda berseragam biru berbadan tegap. Ia
melewati pintu yang dipasang alat deteksi. Fred kemudian berjalan di ruangan besar yang
menyerupai lobi hotel bebintang lima. Dua tangga mengulir sementara lidah karpetnya
menjulur berwarna hijau. Sampai di lantai, lidah itu menyebar memenuhi seluruh ruangan.
Lukisan-lukisan menempel pada dinding ruangan. Guci yang berasal dari perahu penjelajah
China yang karam di abad 12 terlihat terawat. Kamera menggantung hampir di setiap sudut
ruang.
Fred merasa tak nyaman saat mendengar salakan anjing. Di masa kecilnya kuping
kanan dia pernah digigit anjing. Setengah kuping yang tersisa itu mewajibkan Fred untuk
memanjangkan rambutnya. Fred terus berjalan mendekati suara yang membuatnya tak
nyaman. Saat ia melihat dua ekor anjing berada dalam jeruji pagar yang memisahkan rumah
dan lahan tempat latihan, Fred memberanikan diri keluar rumah. Lelaki yang disebut bapak
oleh penjaga meminta dia untuk menemuinya di tepi luar pagar.
Di bawah payung rumbia, lelaki paruh baya yang akan Fred temui terlihat santai.
Kaus kutang tidak mampu menekan gelambir lemak pada perutnya
“Kemari!” bapak berkacamata hitam, yang mulutnya di penuhi cerutu yang gemuk itu
memanggil.
Fred ragu. Seekor anjing memandangnya lekat. Kekuatan tenaga ke dua anjing itu
diekspresikan oleh dua kaki depan yang terangkat hingga tigapuluh centimeter dari tanah.
Garis lekukan otot dua anjing tersebut tampak di sekujur badannya. Di kepalanya, otot pipi
terlihat kencang dan kuat. Otot kepala sekitar telinga dan kepala bagian atas tampak rata,
sementara otot pada paha belakang, kaki depan serta kepala ke dua anjing itu terlihat besar.
Ekor kedua anjing itu mengibas liar.
Fred mengetahui anjing jenis apa yang menggonggonginya. Gigi kedua anjing itu
setajam belati. Cengkraman taringnya tidak bisa dibuka, selain menggunakan pengungkit.
Taringnya bahkan mampu membuat ban motor besar pecah. Kedua anjing pitbull itu mampu
mematahkan leher seekor sapi, mematikan herder, membunuh babi hutan dan manusia
dengan kondisi yang menggenaskan. Yang paling menakutkan adalah, anjing pitbull itu
memiliki kemampuan melompati pagar setinggi setengah meter tanpa ancang-ancang yang
berarti.
Fred memang berhak khawatir. Ia orang baru bagi si anjing. Ia tak bisa
membayangkan jika kedua anjing itu berlari melompati pagar lalu membuat kuping kirinya
289
rebing. Fred bukan saja tak mau kehilangan kuping. Fred tak mau mati tersia karena lehernya
di pitek rahang anjing.
Sang majikan memberi kode pada penjaga untuk menenangkan kedua pitbull. Penjaga
lelaki yang jauh-jauh hari Riang cari itu segera menggiring pitbull masuk ke dalam kandang.
Kedua anjing itu menyalak ke arah Fred kemudian pergi mengibaskan otot ekornya yang liat.
SEJAK berada di terminal Dago, Kardi menunggu cukup lama. Kepergiannya dari
terminal Dago ia anggap sebagai sebuah anugerah. Dalam pikirannya semula, menjadi
penjaga anjing bukan sesuatu yang ia angankan, dan tak dapat ia banggakan. Tetapi, anjing
yang mana, dan anjing yang seperti apa? Jika menjadi penjaga anjing nenek-nenek atau
menjadi pengantar anjing tante-tante genit macam cihuahua, atau menjaga anjing yang jika
dilempar sepatu hak tinggi sudah mengkeret, menguik-uik macam pudle, mungkin Kardi
boleh kecewa.
Di tempat ini ia memperoleh kepercayaan menjaga anjing yang semula ia recehkan.
Dua pitbull itu benar-benar membuatnya bangga. Kardi merasa dipercaya.
Saat ini, Kardi, mulai menyadari posisinya. Ia hanyalah preman biasa. Seorang
pengacau liar yang hanya dianggap sebelah mata. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang benar
sebenar-benarnya dapat ia temukan pada diri sang Bapak. Otak, kekayaan, kemampuan
mengorganisasi orang-orang, dan tentu saja kelihaian sang Bapak dalam berpolitik yang licik
merupakan syarat tinggi dalam meraih kekuasaan.
Kardi mulai berkaca. Keinginan itu membuatnya merelakan diri untuk mengabdi.
Kardi ingin yang lebih tinggi. Ia ingin yang membukit, menggunung, ia ingin memancang
hingga ke langit-langit. Berjalan perlahan pun tak apa. Menjaga serta melatih pitbull
merupakan awalan yang sempurna. Kardi cukup puas dan bangga.
DUA PITBUL yang kembali ke dalam kandang menjadikan Fred merasa aman untuk
menyerahkan catatannya. Ia melihat kertas yang malam kemarin ia kerjakan dengan susah
payah, dilihat si Bapak pun tidak. Lelaki paruh baya itu malah meminta Fred untuk mencoba
cerutunya. Fred tak terbiasa, tapi ia mengambilnya.
“Kau kelihatan capai?!” Sang Bapak membujuknya. “Liburlah.” Cerutu terbakar.
Pipi yang gemuk kempong.
Fred tak terbiasa menghisap cerutu. Ketebalan dan harga cerutu tak pernah
membuatnya cocok. Fred mencoba tertawa, “Entah sejak kapan, aku tak berlibur,” katanya
sambil terbatuk.
290
“Itulah…” Batuk Fred ia jadikan pembenaran, “kerjaan seperti yang Kau lakukan ini
bisa membuat orang menjadi gila,” ia menunjuk kertas yang Fred serahkan padanya. “Kau
terlalu stress! Nikmatilah hidup… berliburlah …”
Fred hanya tersenyum.
Lelaki paruh baya itu mengetahui maknanya. “Kau berhak melupakan kerjaanmu.
Kau perlu memulihkan diri… berliburlah!” Lelaki itu faham. Memata-matai bukanlah
perkerjaan yang mudah. Menjadi mimikri membuat mental Fred ringsek. “Mainlah ke
Sengigi,” bujuknya, “Tenangkan dirimu, seminggu dua minggu di sana. Jangan menolak
tawaranku. Istirahatlah di sana.”
Catatan yang tersusun rapi dibawa masuk ke dalam ruangan. Catatan itu berisi siapa
yang menggerakkan ratusan orang kolektif bawah tanah saat mereka menuntuk hak
masyarakat Punclut atas air. Catatan itu menjabarkan dengan detail mengenai kegiatan seni
di pondokan, rapat-rapat terorganisir yang diadakan di rumah kayu Fidel, kondisi tempat
rapat hingga kebiasaan orang-orang yang aktif dan simpatisan lain yang ikut memfasilitasi
aneka macam kegiatan.
Sejak aksi yang menyebabkan amuk massa di Punclut, rencana pendirian perusahaan
air mineral yang dimiliki lelaki setengah baya itu terbengkalai. Tanah perusahaan airnya
menjadi sengketa, terlantar dikeroposi masa.
Kerugian harus segera di tambal. Catatan Fred membantu lelaki setengah baya itu
melengkapi dan menjabarkan apa saja yang harus dibutuhkan saat ia memerintahkan orang-
orang suruhannya untuk melakukan eksekusi.
Kesimpulan sudah di dapat. “Terima kasih.” ujar Fred. Ia mengatakan akan berlibur
setelah memastikan semuanya selesai. Fred masih berusaha menunjukan harga dirinya yang
tersisa.
Fred membuka pintu taksi. Tak ada yang dipikirkanya selain ingin membalas dendam
atas waktu yang ia habiskan selama beberapa malam di hadapan komputernya. Ia ingin
segera menghilang di peraduan. Fred ingin tidur, melupakan segalanya. Melupakan
pengkhianatan pada orang-orang yang sudah menghargainya. Ia hanya ingin tidur. Tidur
sehat yang dipikirnya akan membuat dia terbebas dari rasa bersalah.
291
RAA
Milea. Milea.
Payah. Riang terlalu meninggikan peranan Milea di dalam zine-nya. Itulah mengapa,
sejak tidur di jok kereta, nama Milea terus menerus mengiang di telinganya. Riang tersesat
dalam reaksi kimia. Riang engah jatuh cinta. Ia berharap Milea ada di pondokan.
Sesampainya ia di sana, Riang berencana untuk menceritakan apa yang dialaminya di
Jakarta. Tetapi, rencana tinggal rencana lain padang lain belalang, lain seprai lain tumbila
dan lain kepala, lain pula kutu pemikiran.
292
Milea yang ditemuinya di pondokan memasang tampak tidak peduli. Riang merasa
hutan hijaunya mendadak luruh disiram agen oranye. Ia tak tahu kesalahan apa yang telah
diperbuatnya. Dua hari tiga hari ke depan, wajah Milea tetap demikian. Perubahan tidak
pernah datang. Riang merasa tak diberkati. Ada apa? Haruskah ia bertanya pada rumput yang
bergoyang? Mestikah ia berkiblat pada petuah Ebiet yang sudah menjadi standar.operasional
script writer yang kehilangan kreatifitas? Pada siapa Riang harus bertanya? Pada cacing
kremi yang ngendon di usus dua belas jarinya, pada Oma-Opa yang sering ia lihat latihan tai
chi di lapangan Gasibu? Pada siapa? Mungkin pada zine-nya.
Riang melarikan diri ke warung internet. Ia membuka e-mail dan menemukan
beberapa surat. Sebuah surat yang datangnya dari Malang terbuka. Riang tak merasa pernah
membukanya. Hanya ia dan Milea yang mengetahui kata sandinya. Riang menerka, tetapi
ketertarikan malah membuatnya perhatiannya pada Milea mengendur. Bujuk rayu di saat
seseorang naik daun memang mengerikan.
Kau tak membalas suratku? Sekarang .. Raa ada di Bandung.
Kapan kita bertemu? Raa di sini hanya sampai hari minggu.
Datanglah ke Holiday inn.
Raa menyertakan emoticon yang membuat Riang kelu.
Surat itu dikirim dua hari yang lalu. Esok hari Sabbath. Ini hari Jumat. Di dua hari
yang keramat itu Riang masih berharap bisa bertemu Raa.
Aku kesana. Esok aku ke sana. 8.00. Balasnya singkat.
SABTU. 7.45 Riang sudah berada di atas angkutan kota Dago-Kelapa. Riang melihat
Holiday Inn seperti ketika orang Yahudi melihat tanah Zionis yang dijanjikan. Ia
menyeberangi ruas jalan yang dibelah dua. Hotel itu terlihat megah, perkasa. Dua buah
patung singa hitam yang diletakkan di lahan parkir memandang mobil bermerk kijang seolah
buruannya sementara yang bermerek panther seakan tampak sebagai kawannya.
Mobil-mobil hilir mudik menurunkan nona, tante, dan om. Di depan pintu utama
hotel, dua orang muda-mudi membuka kaca millimeter. Senyumnya santun, hanya untuk
yang mulia seorang ratu dan raja dalam semalam. Tamu masuk bergiliran. Riang lulus dari
cegatan satpam, melewati senyum pemikat muda-mudi bell boy yang andalan. Ia masuk ke
293
dalam ruangan besar dan segar. Wangi parfum dan roti yang membuat noni dan meneer
Belanda malas berkerja, merebak di udara. Ada beberapa lukisan menggantung. Di samping
sebuah tangga, Cepot, sebuah patung salah satu maskot humorologi Sunda tersenyum
memperlihatkan giginya yang ompong tinggal dua. Bar dan tumpukan minuman keras
tampak berikut koran-koran nasional yang diletakkan dengan posisi handuk yang tengah
dijemur. Riang bingung.
“Ada yang bisa di bantu,” tanya office boy.
Riang menyebut nama. Lelaki itu meminta Riang duduk di sofa putih tempat
bercengkrama. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Layanan naik turun tak mengeluarkan keringat
itu menteleportasikan seorang nenek renta dan cucunya. Seorang lelaki keluar menjinjing
laptop. Pintu lift tertutup, lalu terbuka lagi dan membawa seorang bapak gendut yang tengah
memandangi wanita muda di sampingnya. Bapak gendut itu mengantungi cerutu di saku
baju. Wanita muda tertawa penuh gairah menyadari jika dirinya diperhatikan. Wanita itu
meninggalkan bapak gendut yang masih menatapnya dengan pandangan lapar. Wanita itu
melangkah membawa tumpukkan majalah.
Raa kah dia? Rambutnya terlihat sehat bercahaya dan tubuhnya berdiri tegak
sempurna. Ia menyapu seluruh ruangan. Matanya adalah kuas dan pandangannya adalah
warna. Ia melangkah ke depan, menemukan seorang diantara banyak lelaki yang
memandangnya.
“Riang Merapi!” tanyanya serta merta.
Riang angkat tangannya. Riang mengangguk. Ia di serbu oleh seribu satu kehormatan.
“Raa?” tanya Riang, sambil berdiri sok-sok-an bersahaja.
“Sudah lama menunggu?” Raa tersenyum behel menyerupai bintang muncul di
giginya.
Riang canggung. Ia tak bisa memulai.
“Sudah sarapan Yang?” Raa langsung mengambil inisiatif yang malah membuat
mulut Riang mangap. Wajah Riang merah. Ia tak sanggup. Riang tak kuat dengan panggilan
‘Yang’ yang ia khayalkan sayang itu. Sayang… O yayang! Mengapa Kau tidak membawa
setangkai bunga? Tanya Raa. Untuk apa bunga? Jawab Riang, itu terlampau old school dan
teramat tradisional. Akan lebih baik jika Aku membawakannmu kemocheng! Riang
mengidap neurosis. Alangkah lebih baik jika ia mengaji falaq bin nas.
Saat Riang tengah melamun itu, Raa menggamit lengannya tiba-tiba. Sembarangan.
Tindakan itu benar-benar sukar di maafkan. Listrik mengalir dari tangan Raa. Ia berusaha
menangkal segala macam goda. Hati Riang berontak. Ingatannya akan membuat aliran listrik
294
dari tangan Raa melemah. Riang merasa berdosa. Seraut wajah membayang. Riang tak mau
meyakiti Milea.
Riang tak sadar jika Raa telah menuntunnya hingga memasuki ruang makan. Ada
belasan senyum ditebarkan pelayan. Di ruangan itu tercium wangi mentega. Aneka macam
selai dan buah-buahan, tumpukkan roti, butiran gula dan coklat dihidangkan di satu meja.
Meja lainnya di penuhi makanan pembuka, sementara di sampingnya di hidangkan makanan
penutup. Riang tak tahu aturan tutup buka macam risleting celana atau macam tutup buka
lajur puncak pada hari sabtu dan minggu. Bagi Riang makan adalah makan. Lezat hanyalah
tambahan. Yang penting kenyang.
Kursi di geser. Raa duduk dengan adab puluhan tahun, sementara adab Riang adalah
adab karbitan. Riang tidak terbiasa.
Pelayan datang memasang sehelai serbet. “Kopi atau teh?” tanyanya.
Tujuan Riang ke hotel ini bukan untuk minum kopi dan makan. Tujuannya hanyalah
bertemu dengan Raa.
“Suka kopi atau cenderung teh?” Tanya Raa menegaskan tawaran pelayan. Ia
memperhatikan betul wajah lelaki di hadapannya.
Di saku Riang hanya ada lima ribu. “Tidak usah, terima kasih,” katanya.
“Kenapa?” tanya Raa sambil menuangkan cairan hitam di gelas Riang.
Riang menghentikan nafas. Riang mendadak menjadi tua dan beruban karena
memikirka uang, tetapi Riang mulai berfilsafat. Pikirnya, yang terjadi maka terjadilah!
Raa tiba-tiba tersenyum. Ia melihat lelaki gendut yang berada satu lift dengannya kini
tepat berada di belakang Riang.
“Ini pacarmu?” Suaranya terasa berat dan tangannya terasa lebar di bahu Riang.
Riang mencium bau tembakau yang keras.
“Dia, papaku!” ujar Raa setelah menghabiskan waktu seper sepuluh detik untuk
berpikir.
Riang mencoba mempercayai lelaki yang bersama Raa di lift adalah ayahnya.
“Ini Riang Pa,” ujar Raa memecahkan perhatian.
Riang mengulurkan tangan. Ia memperkenalkan diri. Lelaki itu menyambut uluran
tangan Riang.
“Tak baik aku ganggu kalian,” lelaki itu tertawa. “Papa pergi dulu,” ucapnya pada
Raa sambil mengedipkan mata. “Semua sudah papa bayar. Ajak Mas mu ini,” katanya.
“Ajak apa Pa?” tanya Raa,
“Jangan keterlaluan!” katanya pura-pura marah. “Makan!”
295
Papa pergi. Raa tertawa dan Riang merasa lega. Ia tidak harus memikirkan uangnya
yang tinggal lima ribu itu.
“Mengapa anaknya tak seputih papanya?” tanya Riang bercanda.
“Tak ada manusia yang bisa memilih warna asal kulitnya. Termasuk memilih ibu atau
ayahku,” jawab Raa tegas.
Riang merasa tidak nyaman ketika menyinggung permasalahan warna. Riang tak
meneruskan. Raa kemudian beranjak dari tempat duduknya dan mengambil sebuah roti
berlapis coklat dan mentega diatasanya.
“Ini croissant?” Riang menebak-nebak.
Raa tertawa. Riang tak peduli. Ia begitu bahagia. “Seumur hidup aku baru
memakannya.” Pikiran Riang dibawa croissant menuju perang Salib. Ia teringat bagaimana
penduduk Eropa wilayah tertentu membuat roti berbentuk bulan sabit yang digunakan orang
Saracen sebagai lambang pada benderanya. Memakan croissant yang berawal dari crecent
dan Saracen ibarat memakan megapolitan Islam di Cordova.
Sesuatu yang lazim kemudian dibicarakan oleh dua orang yang dipertemukan karena
kesukaan yang sama. Raa menyetir Riang hingga batas-batas yang seharusnya tidak diterabas
ia anggap lazim. Raa memang cerdas, Riang tidak menyadarinya.
Setelah obrolan dan makanan berat di habiskan mereka pun berpisah untuk
selamanya.
Tugas Raa selesai. Ia kembali ke lantai tiga. Masuk ke dalam kamarnya dan
dikejutkan oleh lelaki yang beberapa waktu lalu ia panggil papa.
“Riang tak tahu apa-apa,” Raa menjelaskan sambil membuka sendalnya di peraduan.
Lelaki paruh baya itu mendadak hilang ingatan. Tubuh Raa yang memerah
menjadikan permasalahan mengenai rekaman peristiwa penganiayaan warga Punclut terpaksa
ia kesampingkan. Ia meyakini, catatan Fred akan memberikan jalan.
MANAKALA CHAOS di mulai dari peraduan, melalui sebuah jendela kaca yang
besar dan berkeringat, sebuah mobil hitam terlihat berhenti di pelipiran jalan. Di dalam mobil
fiat hitam itu, seorang wanita memperhatikan Riang menjinjing kaus dan tumpukan zine
melalui kaca spion. Wanita itu teringat akan e-mail yang ia buka beberapa hari yang lalu.
Wanita itu merasa sakit. Ia tak berani memikirkan apa yang telah terjadi antara Riang dan
Raa di dalam hotel itu.
296
PLAK!
MILEA HILANG. Sudah beberapa hari ini ia meminta izin tak masuk kerja. Dr
Nurlaila tak mengetahuinya. Seisi pondokkan tak tahu apa yang terjadi. Riang takut. Seisi
pondokkan takut. Rumah Milea sepi. Tetangganya pun tak bisa memberikan informasi. Fidel
mengecek air terjun. Milea tak ada di sana. Seluruh pondokkan khawatir. Hampir semua
orang dewasa di pondokan tahu, bahwa sejak kematian orangtuanya ia terperangkap dalam
tubuh orang dewasa dan kematian Pepei menjadikan keadaan ini bertambah sulit.
Ada kemungkinan lain. Fidel mengemas tenda dan sleeping bag, menyerahkannya
pada Riang. “Pergilah ke Ranca Upas,” kata Fidel. “Esok kami menyusulmu.”
Fidel tidak bisa meninggalkan aksi yang menjadi tanggungjawabnya. Hari ini seluruh
anggota SNB dan beberapa veteran bentrokan berdarah kasus air Punclut berkumpul di
pondokan. Informasi sudah tersebar. Mereka bermaksud menampakkan reaksi yang lebih
keras. Ini berarti bahwa patok-patok tanah harus di cabut dan mereka berharap aksi ini
menjadi aksi terakhir hingga pemerintah dan media massa mau mengangkat masalah
penyerobotan sumber air yang disertai intimidasi fisik menjadi masalah nasional.
Riang tidak pernah diikutsertakan aksi sebelum dan setelah aksi pemukulan di
Punclut. Beberapa orang, terutama Fidel dan orang di pondokan memiliki pertimbangan
sendiri mengapa Riang tidak ikut disertakan dalam aksi. Karenanya, mereka tidak
menganggap Riang kehilangan solidaritas terlebih dalam aksi ini Riang dibebankan tugas
untuk mencari Milea. Riang pun melenggang ketika suasana pondokkan mulai tampak hiruk
pikuk..
SEPANJANG PERJALANAN sejak terminal terakhir hingga Kawah Putih dan
pemandian air panas, pepohonan meranggas. Batangnya berwarna hitam. Ujung-ujung dahan
yang paling tinggi kecoklatan. Daun-daunnya luruh terserak seperti peminta-minta berbaju
kumal di pinggir jalan. Tanda-tanda kebakaran reda di penangkaran rusa Ranca Upas. Usai
297
Riang membayar tiket masuk petugas jagawana menunjukkan lokasi mobil fiat hitam yang
menurutnya sudah berada di tempat parkir sejak dua hari yang lalu. “Pemiliknya, tadi pagi
memberi makan rusa,” ungkap jagawana. Riang cukup lega mendapatkan kepastian itu. Ia
pun beranjak masuk. Sekitar satu kilometer dari pos penjagaan ia menemukan fiat hitam
Milea.
Milea tidak ada di mobilnya. Ia kemudian menaiki tempat pengamatan di mana
wisatawan leluasa melihat penangkaran hingga batas pagarnya yang paling jauh. Puluhan
gelondongan kayu, menjadi tempat berpijak. Atap tempat pengamatan rusa ini terbuat dari
ijuk hitam yang lembab ditumbuhi lumut. Terlihat dari sana, pagar penangkaran dan
kumpulanan rusa yang bertingkah malas. Tak satu pun dari puluhan rusa itu yang meloncat-
loncat seperti dalam bayangan anak-anak. Mereka berdesak-desakan saling menghangatkan.
Di sana Riang tak melihat tanda-tanda keberadaan Milea. Ia turun dari tempat
pengamatan, menyinggahi warung satu persatu. Milea tetap tak dia temukan. Riang
menunggu cukup lama. Ia mulai khawatir.
Menjelang sore, udara di tempat itu mendadak menjadi dingin. Atap bumi
mengisyaratkan mendung. Kekhawatiran Riang bertambah. Mendung meng-arang. Cahaya
benderang keluar dari balik awan. Beberapa detik kemudian suara halilintar terdengar.
Milea…Milea… dengung Riang.
mendung memblok senja. Cuaca kelam dan warna menghitam.
Pletak! …
Pletak! …
Pletak! …
Riang mengaduh. Bongkahan es terjun dari lngit. Bunyi suara keras teredam dempul.
Kap dan atap fiat hitam Milea terlihat penyok dari kejauhan.
Milea… berilah pertanda.
Riang berlari ke tempat pengamatan. Ia memastikan. Ia berteriak. Tak ada jawaban.
Gema di telan cuaca buruk. Suara di makan gemuruh batu. Riang merasa hilang sandaran. Ia
membutuhkan sesuatu.
Ya Tuhan lindungilah Milea… Ya Tuhan….Riang bersujud.
Ya Tuhan berilah aku kesempatan menyembahmu…. Berilah keajaiban agar hatiku
tidak kotor menafikann-Mu. Ya Tuhan penguasa alam, penguasa amarah dan badai, penguasa
kebaikan dan murka, lindungilah Milea dari badaimu.
298
Riang bersujud. Ia tak mempedulikan bongkahan batu es yang mendarat di
punggungnya. Riang terus bersujud di hamparan rumput.
Lelaki tua penjaga warung melihatnya dari kejauhan. Ia mengambil payung lalu
belari dan menyeret Riang. “Setelah hujan es reda, Abah bantu mencari kawanmu Nak!”
lelaki tua itu membujuknya.
Tetapi, kapan hujan es ini akan berhenti? Setengah jam berlalu. Empat puluh lima
menit…satu jam… satu setengah jam… dua jam…. Hujan tak juga reda.
Riang harus berusaha. Tak ada doa yang tak diiringi kerja. Ia harus berusaha. Pak tua
meminjaminya ponco, senter dan payungnya. Riang menerobos hujan, namun baru beberapa
langkah ia berjalan Riang mendengar sayup teriakan.
“Tunggu Nak, aku ikut!”
Riang berbalik arah, mengambil bilah kayu bernomor yang biasa digunakan Pak Tuan
untuk menutup warung. Pak tua mencegah. “Tak perlu, teu nanaon, tidak apa-apa.” katanya.
“Kudu buburu, harus cepat-cepat.” Ucapan pak tua mengisyaratkan keyakinan yang kuat.
“Lekas pergi Nak! Adikmu tak bisa menunggu!”
Riang berbohong saat Pak Tua menanyakan status Milea. Mereka kemudian berjalan
menembus hujan dan angin kencang, mengelilingi pagar penangkaran.
Setengah jam kemudian hujan es hilang berganti hujan yang mencopot tulang.
Mereka memasuki rawa. Kaki kedua orang itu semakin sulit digerakan. Setiap melangkah
setiap itu pula Riang memforsir tenaga keluarkan kakinya dari benaman Lumpur. Tak berapa
lama kemudian sandal Riang putus, amblas ke dalam lumpur. Bersusah payah mereka keluar
dari rawa. Hujan dan lumpur tak lagi menyulitkan namun berjalan di dalam hutan bukannya
tanpa halangan. Jalan setapak berubah menjadi jalan air. Beberapa kali kaki mereka
tergelincir.
Di dalam hutan Riang mulai merasa lelah. Sudah tiga jam berlalu. Langkah adalah
doa yang berjalan. Riang tak mau kalah. Tetapi, tanda-tanda tak juga tampak. Pak tua
memandangnya. Riang merasa kasihan. Ia mengerti. Mereka membutuhkan tambahan
bantuan. Kedua orang itu pun beranjak menuruni bukit.
Saat-saat menuju pos jagawana itu, hujan menembus dedaunan. Riang tak bisa
membayangkan bagaimana hujan berlangsung di tempat terbuka. Hutan lebat ini tak mampu
meredam serbuan air. Malam kemudian datang dan menjadikan jarak pandang berkurang,
sementara senter yang mereka pegang tidak bisa menembus jarak lebih dari dua meter. Di
luar itu kegelapan paripurna meraja. Adakah kegelapan merupakan perlambang? Riang
mengingat perjalanannya di Kopeng saat menemukan kertas koran yang memberitakan
299
kematian Pepei. Kejadian buruk itu menjadikan pikiran Riang tak karuan. Apakah ini
pertanda? Riang mengusir jauh-jauh pikiran negative dalam benaknya. Ia membuang pikiran
bangsat itu menuju pinggiran jalan setapak, membuangnya ke dalam semak-semak. Riang
terus berjalan dan …….. bruk!............... Pak tua ambruk. Sebuah benda mengait kedua
kakinya. Riang mengarahkan senter ke bawah, dan ia pun … berteriak.
“Pak … adikku…!”
Posisi tubuh Milea telungkup. Riang mengambil tubuh itu, dam membersihkan
wajahnya.
“Milea…..?” Riang berbisik.
Detak jantung Milea melemah. Badannya membiru.
Riang mengenali gejala itu. Milea terkena hipotermia.
Keadaan darurat tak membutuhkan banyak tanya. Pak tua mengerti. Ia segera
membantu menempatkan Milea ke punggung Riang. Pak tua melangkah cepat, tetapi Riang
tak bisa mengikuti. Jalan setapak terlalu licin. Mereka melewati jembatan. Air kali terlihat
mengepul. Melewati jembatan Riang memantapkan langkahnya. Ia berlari melawan waktu.
Seratus meter dari jembatan sebuah telaga tampak. Bau belerang tercium di sela hujan.
“Telaga air panas?!” Riang berteriak.
Pak tua mengangguk.
“Ada pemandiaannya?”
Hujan masih mengucur deras. Riang mengulangi beberapa kali pertanyaannya. Pak
Tua mengerti. Ia berlari menuju sebuah bangunan. Pintu pemandian terkunci. Kaki Pak Tua
melayang. Pintu pun dobrak berderak. Di dalam pemandian tak ada penerangan. Cahaya
senter menyoroti bak yang kusam dan dinding yang berwarna kuning. Riang langsung
menceburkan diri. Ia memangku badan Milea, dan memeluknya erat.
Riang meminta tolong pada Pak Tua untuk melanjutkan perjalanan ke pos jawagana.
Mereka membutuhkan bantuan. Riang kembali berpikir cepat. Riang memberi instruksi “Di
tas saya ada tenda! Tolong Bapak dirikan tenda itu di dalam warung dan sediakan minuman
serta makanan hangat! Jangan lupa ambil kantung plastik besar yang bisa Bapak bawa! Air di
sini harus dimasukan ke dalam tenda!” katanya.
Pak Tua tak tersinggung, “Itu saja?” jawaban yang keluar dari mulutnya.
“Ya!”
Ketika Pak Tua pergi, Riang menyenteri wajah Milea, kemudian menyandarkan
tubuhnya pada dinding bak. Riang meletakan wajah Milea di dadanya. Tanah yang melekat
di dahi Milea, ia seka. Pipi yang semula membiru, mulai terlihat merah. Rambut Milea yang
300
panjang mengambang di petmukaan air. Ya Tuhan! Riang benar-benar takut kehilangannya.
Ia menciumi pipi Milea. Mencium hidungnya, mata, bibirnya. Riang takut kehilangan Milea.
Ya Tuhan, dengan nyala-Mu, hangatkanlah tubuh Milea.
Ya Tuhan. Hanya pada-Mu aku menggantungkan harapan.
Ya Tuhan buatlah Milea siuman.
Bibir Milea yang semula mengatup terbuka. Merekah. Indah.
“Kaa… ka Pepei…” Milea mendesah.
Berbahagialah Pepei yang sedemikian dirindukan, yang sedemikian diharapkan.
Berbahagiah Pepei.
Milea terus menerus mengerang.
HUJAN PERLAHAN REDA. Dari kejauhan kecipak langkah Pak Tua terdengar.
Tak ada langkah lain yang menyertainya.
“Tak ada jagawana, Nak! Mereka pergi!” jelas Pak tua terengah.
Di saat-saat genting Riang dilatih agar tak merasa butuh terhadap penyesalan. Ia
melakukan apa yang bisa ia lakukan.
“Kantung plastiknya ada Pak?” tanyanya.
“Hanya ada tiga. Hendak diapakan, Nak!?”
“Masukkan air panas kedalamnya,” Riang menunjuk pancuran.
Derasnya aliran air membuat ketiga kantung plastik besar itu cepat terisi. Pak tua
mengikat dan membawa satu kantung menuju warung, sementara Riang keluar dari bak, dan
segera memfokuskan diri pada nafas serta langkah kakinya. Riang berlari.
Memasuki warung Riang merasa sesak, “Di mana tendanya?” tanya Riang.
“Ada di kamar.”
Tenda masih teronggok di lantai. Pak tua meminta maaf. Ia tidak mengerti cara
mendirikannya.
Luna lantas dibaringkan di atas papan. Riang segera membuka ikatan dan menepiskan
rangka tenda. Dengan satu gerakan, tenda tiba-tiba berdiri membentuk doom secara ajaib,
membuat Pak Tua takjub. Riang langsung menghamparkan kantung tidur di dalamnya. Ia
meminta Pak Tua untuk memasukan plastik berisi air panas ke dalam tenda.
Riang membopong Milea. Saat membuka bajunya, Pak tua paham apa yang
dikerjakan Riang. Ia mundur, mengambil kantung air yang tersisa.
301
Riang menutup tenda. Nadinya berdenyar hebat. Desing jantungnya melebihi rentetan
AK-47 senjata khas pejuang Afghanistan. Ia lantas mengangkat kaus Milea yang basah,
menahan nafas.
Ya Tuhan jangan Kau biarkan kejahatan menguasai diriku. Riang membuka kaus
dalam Milea. Riang silap. Untuk pertama kalinya ia melihat dada wanita. Pikiran-pikiran
aneh melintas.
Tuhan, ampuni diriku. Jauhkanlah kejahatan. Jauhkanlah.
Riang mempercepat apa yang memang harus dilakukan. Ia tak mau menghayati tubuh
Milea. Ia menolak dan menganggapnya menggarap patung.
Milea adalah patung. Patung adalah Milea. Riang utarakan mantra.
Saat membuka kancing celana jeans Milea, Riang mengalihkan pandangannya. Ia
mempercepat apa yang ia lakukan lalu menjalani tahapan pertolongan selanjutnya:
memasukan Milea ke dalam kantung tidur. Riang merebahkan diri di samping Milea sembari
merangkul pinggangnya. Dua tubuh merapat. Rekat.
Tak berapa lama, satu kantung plastik berisi air panas lainnya sampai. Saat Pak Tua
hendak kembali berlari, Riang tiba-tiba mengingat mobil Milea. Ia berteriak. “Pak… tolong
carikan kunci mobil di celana jeans adik saya.”
Pak Tua tak menemukan kunci yang diminta. Ia kembali mengambil plastik berisi air
panas yang terakhir. Setelah menyelesaikan apa yang Riang pinta, Pak Tua keluar dari
warungnya. Ia menanti mobil untuk memberi pertolongan. Hingga tengah malam tiba tak ada
satupun derum mobil yang terdengar sampai di warung.
Hanya ada dua orang di warung malam itu. Riang menyaksikan bagaimana Milea
masih memanggil Pepei dalam igauannya. Setiap kali Milea mengigau saat itu pula Riang
mendekapnya. Igauan Milea baru hilang ketika subuh datang.
Jantung Milea mulai berdetak seperti biasa. Fase kritis mereka lewati. Riang merasa
lega. Ia pun mengantuk, tertidur dan bermimpi: tubuhnya terperosok ke dalam jurang tak
berdasar. Perasaan tegang mengganggunya. Riang terbangun, dan terkejut merasakan geliat
yang luar biasa di tubuhnya.
Milea siuman. Ia melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan siapa yang tengah
menghimpit tubuhnya. Tangan Riang lantas menyusup. Ia meraba-raba kantung tidur, lalu
membuka risletingnya pada bagian dalamnya. Milea sadar apa yang terjadi. Ia tiba-tiba
berteriak tertahan. Milea bangkit dan berbalik. Ia tak sadar jika tubuhnya polos, tak terhalang
oleh sehelai benang pun.
302
Wajah Milea terlihat pias menyaksikan tubuh telanjang di hadapannya. Riang malu!
Ia segera menutup tubuhnya menggunakan kantung tidur..
Milea tak percaya. Ia marah dan hempasan itu pun datang.
Plak!!!
Milea menutup wajahnya..
“Aku tak menyangka!” Ia terisak.
Riang mengambil celananya. Ia mengambil tangan Milea.
Milea menepiskan tangan Riang, kasar, “Mana pakaianku!?” teriaknya histeris.
Riang menunjuk.
Milea mengenakan baju dan celana yang basah.
“Masih basah. Nanti Kau sakit,” Riang membujuk. “Gunakan saja baju dan
celanaku,” katanya.
Milea hilang keseimbangan. “K-K-Kau…Kau…”Emosinya tertahan.
“Aku menemukanmu tak sadarkan,” jelas Riang.
“Kau memanfaatkan keadaan!!!” suara Milea terdengar serak.
“Dengar dulu! Tolong Milea… tolong dengar penjelasanku!”
“Tidak! Tidak ada yang perlu di jelaskan!” Amarahnya di telan tangisan. Dengan
tubuh yang lemas, Milea berjalan ke pintu …dan
Bruk!!!
“Milea kau salah sangka.” Lirih Riang.
Milea tak mendengar penjelasan Riang. Ia pingsan.
Riang kembali membaringkan Milea di dalam tenda. Kening wanita itu panas. Milea
panas. Ia harus dilarikan ke rumah sakit. Riang segera keluar dari warung. Ia tak menemukan
Pak Tua. Riang kembali masuk ke dalam warung, menuju dapur, mengambil dua bungkus
mie, menggoreng dua buah telur untuk sarapan.
Hingga makanan itu dingin Milea tak menjamahnya. Wanita itu masih tak sadarkan
diri.
Situasi ini berbahaya. Riang lantas meninggalkan Milea, mencari kunci ke dalam
hutan, menuju tempat Milea rubuh. Ia tak menemukan. Kunci teronggok di dalam bak
pemandian air panas. Riang menemukannya tak berapa lama kemudian, lalu berlari kencang
mecari Pak Tua hingga pos jagawana.
Riang menemukan Pak Tua terkantuk-kantuk di pinggir jalan, tak jauh dari pos
jagawana. “Bapak bisa mengendarai mobil?” tanya Riang.
303
“Bisa juga motor, Nak!”
“Mana motornya?”
“Tidak punya, Nak.” Pak Tua tak hendak melucu. Ia hanya menjawab.
Hingga pagi ini ia belum menemukan satu mobil pun yang melintas sejak kemarin
malam. “Sebentar lagi penjaga pos datang,” ujar Pak Tua berusaha menenangkan Riang.
Ada kepastian yang membuat hati Riang tenang. Riang berbalik ke warung. Dalam
perjalanan itu ia mendengar bunyi motor trail yang ia kenal. Riang bersyukur. Waluh datang
pada saat yang diperlukan.
JAM SEMBILAN SIANG ITU, Milea sudah mendapat perawatan. Waluh kembali
ke Ranca Upas mengambil motornya yang tertinggal. Riang bersikeras untuk mengucapkan
terima kasih pada Pak Tua, tetapi Waluh menolaknya, “Biar kusampaikan saja!” ujarnya
tegas.
Waluh kemudian mengingatkan Riang pada situasi tak menentu yang ia ceritakan
dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ia bukan saja menyarankan, tetapi memerintahkan
Riang untuk menjauhi pondokkan.
“Pergilah ke rumah kayu Fidel,” katanya. “Istirahatlah dulu! Siang ini, aku, Bentar
dan Eva menyusul.”
Riang tiba-tiba teringat Fidel.
Bukankah Fidel berjanji akan menjemputnya di Ranca Upas?
304
MOBILISASI YANG MENIPU
Mundur ke belakang. Keluarga Sekarmadji merupakan salah satu warga desa yang
dirugikan semenjak pendirian hatchery (lahan pembibitan udang) di Cianjur Selatan, sejak
kuwu Daryo mengumumkan “Lahan ini bukan punya kita! Sudah ada kuitansinya! Punya
orang luar!
Warga desa mengerti fungsi kuitansi tetapi pada siapa orang luar membeli tanah yang
sudah mereka garap sejak tahun 1970-an.
Tak pernah ada yang memiliki tanah di pinggiran samudera Hindia itu. Mungkin
VOC pernah mengklaim kepemilikannya, tapi VOC sudah lama hengkang, bahkan sejak
kedudukannya di ganti Belanda yang kemudian pergi diusir Jepang, lalu Jepang terkena
karma diusir sekutu, kemudian warga sekitar dan solidaritas kemanusiaan antar ummat
manusia berjuang menggunakan senjata dan --melalui-- perundingan internasional demi
mengusir agresi yang dilakukan tentara dari negeri Holand.
Perjalanan sejarah desa Cibenda itulah yang menjelaskan mengapa karuhun-karuhun
desa yang usianya sudah melebihi delapan puluhan bersyahadat bahwa tidak ada tanah untuk
hatchery. Mereka bersaksi bahwa tanah di Cibenda adalah tanah tak bertuan salian tanah
milik Allah, kecuali tanah milik Allah!
Tanah kosong itu memang miliki Allah tetapi beberapa tahun setelah merdeka tanah
itu menjadi milik negara yang kemudian oleh penduduk desa ditanami pandan laut: untuk
305
disamak, ditanami padi: tentu saja untuk di makan, di tanami ketela dan ribuan pohon
penghasil santan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian..
Lalu, setelah berpuluh-puluh tahun penduduk desa melakukan usaha mandiri atas
tanah milik negara –yang tidak diurus negara itu—tiba-tiba tanah-tanah di patok. Tanah itu
bukan lagi dimiliki negara. Tanah menjadi milik swasta. Menjadi milik perorangan melalui
kongkalingkong badan pertanahan tanpa bincang-bincan persetujuan dengan penduduk desa.
Penduduk desa tidak tahu, sebenarnya status tanah di Cibenda itu telah diselesaikan di
kota hanya dalam hitungan hari, di saat yang bersamaan ketika mereka melihat sebuah papan
pengumuman: tanah sengketa berdiri di tengah-tengah lahan pencaharian mereka. Itulah
mengapa, ketika kuwu Daryo dan aparat desa yang juga ditunjuk menjadi fasilitator ganti
rugi hektaran tanah mengizinkan truk-truk tronton datang, penduduk desa terperangah.
Truk yang bagi warga desa besarnya termasuk aujubillah itu membawa kayu,
potongan besi penyangga dan semen. Seorang supir truk yang bersahabat dengan penduduk
desa memberi bocoran, tempat itu akan dibangun apa. “Pabrik pengalenga udang!” katanya,
tetapi buruh lain yang wajahnya sukar untuk dipercaya mengatakan, untuk pabrik terasi juga.
Ketika cor-coran beton ditumpahkan, warga Cibenda bertambah bingung “Yang di
sana untuk untuk resort!” jelas Kuwu. “Itu bagus, bahkan nanti di daerah kita akan ada
bianglala seperti di Ancol!” kata Kuwu berbelit-belit.
Mau biang lala atau gula biang, tak satupun warga desa yang peduli. Mereka tak
memerlukan apa pun selain tanah yang sudah mereka garap turun temurun selama berpuluh
tahun itu menjadi tempat garapan seperti semula, atau kalaupun tidak, penduduk desa
Cibenda mendapatkan hak untuk diikutsertakan dalam perundingan nasib tanah di wilayah
mereka.
Perundingan tak pernah dilakukan. Hal inilah yang membuat tensi darah penduduk
desa naik.
“Aing geus teu tahan! saya sudah tidak tahan! Kumaha aing bisa hirup mun kieu!
Bagaimana saya mau hidup kalau begini! Paeh geus aya nu nentukeun, mati sudah ada yang
menentukan” cerocos Mang Uple siap berperang.
Keesokan harinya, Mang Uple yang sebelumnya tak begitu dianggap warga,
memasuki areal pembangunan yang konon hendak dijadikan pabrik pengalengan. Golok di
tangan kanannya, menjadikan Mang Uple yang bertubuh kecil menjadi besar menakutkan.
Mang Uple mengetahui, Mang Uple sadar jika hanya dengan golok di tangannya,
pembangunan pabrik pengalengan tidak akan berhenti. Golok yang menghantam pondasi
306
beton hingga beberapa kali menjadikan goloknya roheng dan tumpul, namun Mang Uple
tidak kehilangan akal. Di dekat generator ia menancapkan goloknya pada batang pisang.
Mata Mang Uple menyala-nyala. Jerigen solar ia lemparkan! “Kaluar maraneh!
Kaluar! Keluar semua! Keluar semua!” ia mengusir buruh bangunan.
Solar menempel di bedeng. Golok di cabut. Korek api menyala. Bedeng terbakar.
Buruh-buruh bangunan yang semula hanya memperhatikan mendadak marah. Mereka
kemudian berlari mengejar Mang Uple hingga sampai batas pagar pembangunan.
Mang Uple berhasil meloloskan diri. Tanggung jawab Mang Uple saat ia sendiri
menyerahkan diri ke kator polisi, menaikan posisinya di hadapan warga desa dan juga
menaikan daya tawar warga dihadapan pengelola hatchery. Dan karena Mang Uple pula,
kasus kasus penyerobotan tanah di desa Cibenda lolos dan di dengar hingga kemana-mana
meski media masa ragu-ragu memberitahukannya. Di Cibenda, Mang Uple kini menjadi ikon
yang melebihi Ernesto Che Guvara, karena ikon ini terdiri dari darah dan daging yang hidup
di tengah-tengah warga desa.
Suasana panas yang mengasyikan itulah yang mengundang beberapa orang untuk
mendatangi desa yang juga merupakan tempat kelahiran Sekarmadji. Kasus yang terjadi di
desa Cibenda sebenarnya hanya satu kasus dari kasus lainnya yang bertebaran namun
dipencilkan. Waluh segera menggali informasi di Cibenda kemudian bersama beberapa orang
lainnya mengorganisasikan kasus-kasus di desa-desa lainnya, termasuk yang terjadi di
wilayah Punclut.
Membela bagi orang semisal Waluh dan yang lainnya memang merupakan kengerian
yang mengasyikan. Kegemaran mendekati bahaya memang ‘penyakit kejiwaan’, namun tak
apalah jika penyakit kejiwaan tersebut di salurkan pada hal-hal yang berguna bagi
kemanusiaan.
“Jangan sinis begitu!” kata seorang pejabat. ”Pemanfaatan lahan tidur di Punclut
bukan anti kemanusiaan!” katanya.
”Benar,” Waluh memotong, ”pemanfaatan itu tidak anti kemanusiaan, tetapi jika
pemanfaatannya melibatkan warga yang sudah menggarap turun temurun di sana,” ujar
Waluh tenang.
”Pengelolaan air terjun oleh pihak swasta akan menghasilkan apa yang kita kenal
sebagai trickle down effect!” pejabat mantan lulusan Fakultas Ekonomi Unversitas Indonesia,
mengaum menggunakan salah satu komponen di dalam teori ekonomi pasar bebas. “Lihatlah
villa-villa yang bertebaran di sekitar air terjun,” kata dia. ”Penduduk mendapat rezeki dari
kerja menjaga villa-villa di sana, pikirlah yang sehat, belum lagi ...”
307
”Ya!” Fidel memotong ucapan si pejabat dengan sinis. ”Trickle down effect adalah
upah yang didapat penjaga villa di kawasan Punclut dari kapitalis pemilik tambang! Ya!
Trickle down effect adalah secuil upah yang di dapat penduduk setempat, usai memperbaiki
pipa sumber air, usai pemodal di Jakarta memprivatisasi kepemilikan sumber air Punclut
demi pendirian pabrik air mineral, yang akan mematikan akses penduduk untuk
mengkonsumsi air langsung dari mata airnya! Ya! Trickle down effect adalah upah minimum
regional yang didapat jutaan buruh setelah bekerja habis-habisan, sementara dari memerkosa
sumber daya alam pemilik, pejabat dan kroninya terbiasa menghabiskan beratus kali lipat
upah minimum regional per/bulan hanya untuk membeli Virtue! Ya! Trickle down effect
merupakan alat pembenaran keserakahan yang dilegalisasikan oleh negara! Trickle down
effect adalah pembayaran atas tindakan amoral terhadap minyak, lng, batubara, air terjun,
mata air, dan segala sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan jika
trickle down effect dianggap sebagai upah, maka penjaga, buruh bangunan, buruh tani adalah
gadis yang dilacurkan, sementara kaum kapitalis dan sistem yang menaungi sistem tersebut
adalah mucikarinya!”
Di mana-mana aktivis bertaruh di meja judi. Nyawa ditaruhkan dengan pembebasan
tanah ala Mao di iringi lagu this song of freedom Redemption Song dan untuk pertaruhan ini,
Riang tidak pernah dilibatkan. Anak gunung Merbabu itu benar-benar dilokalisir dari
koordinasi yang sejak kedatangan aktivis-aktivis straight edge, skin head, kolektif anarki,
mahasiswa yang mengadvokasi tanah warga, dan beberapa kolektif lainnya yang tergabung
dalam gerakan bawah tanah Bandung di rumah kayu Fidel.
Riang mungkin menganggap dianaktirikan, tetapi Fidel dan kawan-kawannya tidak
menganggap demikian. Semua ada perencanaannya. Dan jika saat itu tiba, seseorang bahkan
tak mungkin membendung kecenderungannya untuk bersikap heroik atas tuntutan yang
dilandasi pertanggungjawaban seseorang pada Pemilik tongkat bisbol hari pembalasan.
Riang teringat betul apa yang pernah dikatakan Fidel padanya, bahwa “Perenungan
teologis yang tidak membawa pada pergerakan akan membuat seseorang lumpuh!” dam
dalam perjalanan mengantar Milea menuju rumah sakit itu, Riang cemburu atas aksi kedua
yang dilakukan Fidel dan kawan-kawannya di Punclut. Aksi mereka merupakan
pengejawantahan direct action yang pernah Fidel ucapkan.
Cerita Waluh mengenai aksi yang tidak Riang ikuti justru tidak menjadikan Riang
untuk berhati-hati. Semangatnya justru malah menderu-deru. Ia ingin berada di tengah-
tengah kaum yang mengidentifikasi dirinya dengan pembangkangan massal terhadap WTO
pada tahun 1992 di Seatle. Ia ingin melawan trinitas WTO, IMF, World Bank yang ia belum
308
mengetahui sepenuhnya apa. Ia ingin bersama Fidel yang bergerak karena keyakinannya
teologisnya.. Ia ingin m\empraktikkan direct action: melakukan aneka pencurian yang
sebenarnya merupakan tuntutan keadilan, menghancurkan bangunan dan instalasi yang
dipersiapkan pengembang mata air Punclut dengan kunci Inggris, pipa besi yang ditemukan
di lokasi keributan, atau melemparkan molotov setelah memastikan buruh pembangunan
aman dikondisikan.
Riang mengingat benar apa yang Fidel ucapkan ketika membicarakan direct action
dihadapan anak-anak muda yang setiap minggunya berkumpul di pondokan.
“Jika kalian sudah melampirkan berkali-kali surat pemberitahuan tetapi birokrasi tidak
meresponnya, maka kalian berhak mengobrak-abrik lapak minuman keras, pelacuran dan judi
yang berlangsung di hadapan kalian! Jika pemerintah hanya memberikan vonis empat tahun
bagi koruptor yang memakan uang masyarakat ratusan, milyaran bahkan trilyunan rupiah
maka kalian berhak menusuknya di pengadilan lalu menyeret koruptor itu untuk dibunuh di
hadapan pengadilan rakyat! Jika kalian merasa kecamatan telah berlaku tidak adil meminta
administrasi KTP hingga ratusan ribu rupiah, maka kalian berhak mencuri uang dengan
jumlah yang sama di kantor kecamatan itu! Jika majikan kalian tidak mau membayar gaji
yang telah menjadi hakmu, maka curi computer yang ada di kantormu!
“Apa yang kita bicarakan ini mengerikan,” seorang pemuda baik hati
mengungkapkan. “Jangan-jangan nanti kalian mensahkan pemboman terhadap orang sipil tak
berdosa untuk meraih tujuan!?”
“Tidak!” jawab Fidel. “Jika hal itu dilakukan maka itu merupakan tindakan yang
salah kaprah! Keyakinanku menentang tegas hal itu! Tak satu agama pun yang membenarkan
tindakan barbarian tersebut!”
“Tapi itu tindakan melawan hukum. Itu tindakan anarkis!”
“Aku hanya akan melawan hukum yang sudah terbeli! Ini bukan tindak anarkis dalam
pengertian kamus. Direct action adalah sebuah kontrol individu yang hanya segelintir orang
yang bisa melakukannya. Direct action buka tindakan chaotic! Direct action bukan tindakan
mensahkan bangsat, keculasan, kejahilan orang-orang yang dijiwanya hanya terdapat
keinginan mau menang sendiri, merasa benar di kepala sendiri! Ini adalah tindakan mata di
balas mata yang tidak popular di kalangan kalangan Ghandiisme, atau pasifisme! Ini hanya
tindakan pengambilan hak yang sudah dicuri individu, komunitas, bahkan penindasan yang
dilakukan oleh aparatur negara! ”
“Tapi cara damai harus dilakukan!”
309
“Sudah kami lakukan!” tegas Fidel setelah mengutip kasus Punclut, Cibenda Cianjur
Selatan, Ciamis dan lainnya. “Kami sudah melakukan cara yang disebut baik-baik itu! Media
cetak sudah kami bombardir dengan surat pembaca! Kami sudah melayangkan surat
pemberitahuan ke berbagai instansi untuk menyelesaikan penembakkan dua orang warga
Punclut, intimidasi dan kebangsatan lain yang terjadi di sana! Tapi tidak ada tindakan! Kami
sudah bosan! Kami tahu jika tindakan ini tidak mutlak membuat bangsat sadar, tapi direct
action akan memberi efek jera, karena tindakan ini bukanlah cara pertama dan satu-satunya
melainkan sebuah alternative cara yang bisa dilancarkan apabila tindakan pesuasif
dipentalkan oleh kebebalan! Kami bukan pengikut Ghandiisme, kami bukan Pasifis!” dan
jawaban yang disampaikan Fidel menjadi pembeda antara direct action dengan aksi teroris.
Direct action hanyalah tindakan pengambilan hak ketika birokrasi, hukum dan negara
menjelma telah menjadi zombie.
Riang membayangkan bagaimana Fidel mengancam ruang dewan ketika hal-hal yang
baik dalam pengertian formal sudah tidak digubris. Riang membayangkan bagaimana Fidel
dan kawan-kawannya mengancam dewan dengan konsep direct action, mengancam dewan
dengan tindakan yang sebenarnya tak jauh dengan budaya vendetta dan ia, si anak gunung
Merbabu itu menyadari betapa mengerikannya jika ia tidak melibatkan diri karena ia yakin
pada suatu hari akan berhadapan dengan dengan Pemilik tongkat bisbol.
Riang kini sadar, ia tumbuh di dalam lingkungan yang didirikan bukan untuk
bermain-main. Cerita Waluh terhadap peristiwa penghancuran penyerobotan tanah untuk
instalasi air menyadarkannya bahwa Fidel tidak hanya membicarakan apa yang diyakininya,
tetapi melaksanakannya dengan perencanaan yang matang.
KISAH PENGAMBILALIHAN hak atas air dan tanah untuk kepentingan warga
Punclut yang diceritakan Waluh dalam perjalanan menuju rumah sakit pun tidak bisa
digolongkan ke dalam sebuah tindakan sporadis minim strategi. Pada saat peristiwa Punclut
terjadi, petani penggarap, warga desa beberapa daerah lain yang lahannya diserobot
menggunakan puluhan truk datang berbondong.
Aparat keamanan yang dipusatkan di gedung dewan tak menyadari jika Fidel dan
kawan-kawannya bergerak menjauhi pusat keramaian. Mereka menyerbu Punclut dan
berhasil melakukan tindakan keras tanpa ceceran darah di tanah.
310
Fidel dan kawan-kawannya membumihancurkan super struktur pembuatan instalasi
air. Inilah tindakan balasan setelah penembakkan dilancaran pihak pengelola dalam aksi
Punclut yang pertama dan inilah yang membuat Riang malah makin tergila-gila.
Riang terlalu platonis. Riang ingin diceburkan ke dalam dunia yang berwarna itu. Ia
tak sabar, namun saat ini ia masih membutuhkan rehat. Bagaimana pun juga, mengingat-
ingat tamparan Milea membuat metal Riang lemah. Tamparan itu benar-benar memarut
fisiknya.
TEGAP MENANTANG
Riang yang diharuskan untuk mengambil jalan lain melewati pondokan, tidak
mengetahui jika pondokkan yang berada dibelakang tubuhnya sudah diobrak-abrik orang
suruhan sang Bapak. Lima belas menit di depan Riang, Fred menjauhi Kardi yang tengah
menggiring seekor pitbull, diantara puluhan tukang onar yang membawa dua jerigen bensin
dan beberapa orang yang mempersenjatai diri mereka dengan pistol dan senjata tajam.
Riang terus berjalan. Rasa letih membuat pikirannya tak fokus. Langkahnya
semerawut. Usai mengambil jalan potong melewati pondokkan, Riang membayangkan
betapa jauhnya perjalanan. Ia masih harus memasuki hutan kopi, melewati air terjun beserta
lorong-lorongnya lalu melewati perkebunan teh dan lahan pertanian yang luas.
Riang hampir-hampir putus asa. Ia benar-benar tak sanggup jika harus sampai saat ini
juga. Fisiknya yang diforsir kemarin malam, memaksa dia mengistirahatkan dirinya di depan
hutan kopi, tepat di bawah pohon tempat ia dan Taryan pernah mengumpulkan jambu.
Kericik air membuat istirahat yang diniatkan sebentar membuatnya menjadi lama.
Angin membantu menghela kesadarannya. Riang tertidur. Pada awalnya ia tak memimpikan
apa pun jua, namun di akhir-akhir tidurnya, ia terkenang kembali sahabat-sahabatnya.
Taryan, Fidel, Bentar dan Eva, Antoni, bahkan Agus menyapanya. Informasi mengenai aksi,
perihal kemungkinan pembalasan yang dilakukan penanam modal di Punclut, larangan
beristirahat di pondokkan dan segala kemungkinan buruk lain yang diceritakan Waluh
membuat alam pikirannya bergerak. Dalam mimpi bola mata Riang mengendut-endut cepat.
Ia mimpi yang bukan-bukan.
Riang bangun. Mimpi buruk menjadikan pengisian energi tubuhnya tidak berlangsung
baik. Tidur siang satu jam tidak mengaruniakan kebugaran sempurna. Ia baru merasa segar
setelah air terjun memijat punggungnya. Setelah air terjun ia lewati Riang memasuki
311
kawasan kebun teh, lalu menyaksikan menyaksikan bagaimana angkasa dicoreng morengi
asap hitam.
Was-was melanda. Ia berjalan cepat seolah ikuti lomba. Tak jauh dari hamparan
rumput Jepang, ia melihat rumah kayu Fidel terbakar api. Atap rumbianya sebagian habis
menjadi abu lalu dihembuskan angin. Riang bersembunyi. Di lahan mentimun, ia melihat
orang-orang menampakkan wajah tegang.
Orang-orang itu mencari rekaman tindak penembakan yang mereka lakukan dalam
aksi warga Punclut yang pertama. Fred merasa dongkol rekaman yang ia informasikan
kepada sang Bapak tidak ditemukan, baik di pondokan dan di rumah kayu Fidel.
Rencana lain harus dilaksanakan. Lelaki bertubuh atletis yang berada di luar rumah
memberi isyarat. Ia berteriak agar Fred keluar. Bensin diguyur pada dinding rumah. Lelaki
itu memerintahkan pria lainnya untuk mengelilingi rumah, memastikan tidak ada satu pun
orang yang bisa keluar lalu menyebar informasi pembakaran rumah kayu dan –menyebarkan
informasi— mengenai usaha melenyapkan barang bukti penembakan di Punclut.
Botol bensin dilemparkan ke atap rumah. Sebuah letusan terdengar. Botol bensin
pecah diserempet peluru. Gesekan yang ditimbulkannya menyalakan api. Api muncrat turun
di berbagai sisi atap rumbia. Api berlari cepat menuju dinding. Berlari mengagumkan
mengelilingi tiang-tiang, jendela dan pintu lalu menggabungkan diri pada satu titik. Asap
hitam mulai muncul, lalu di sapu angin. Api bertambah besar.
Lelaki bertubuh tegap bak perenang pekan olahraga nasional itu berteriak lagi. Ia
memastikan agar Fred keluar rumah. Ia tak mengetahui jika di dalam rumah itu Fidel
mengintai dari celah pintu bawah tanah. Fidel merangkak setelah mengetahui rumah kayu
menjadi panas oleh api. Secepat gerilyawan pembebasan Fidel merangkak. Ia mengambil
mulut Fred lalu membantingnya.
“Apa yang kau cari?!” bisik Fidel mengancam.
Fred diam.
“Apa yang kau cari itu memusnahkan nuranimu sendiri?!” Fidel mengingatkan.
Tapi Fred tetap diam. Ia lebih memilih memfokuskan konsentrasi untuk
membebaskan diri. Fred bukan bukan orang sembarang. Ia mengetahui beberapa teknik
keluar dari kuncian. Fred bukan orang biasa yang pernah dikalahkan Waluh usai
mempraktikkan kekejian pada seekor ayam.
Keluar dari pitingan itu Fred segera menghantam kepala Fidel menggunakan tulang
belakang tengkorak kepalanya. Beberapa kali daerah di wajah dihantam membuat hidung
Fidel patah. Darah membuat mulutnya terasa asin. Alis Fidel koyak. Fred langsung berdiri,
312
menendang tulang rusuk Fidel, tetapi tangan Fidel yang bergerak cepat membuat tubuh Fred
kembali tidak seimbang.
Fred terjatuh. Ia dikurung oleh tubuh Fidel. Ia menggapai-gapai kaki kursi. Tangan
Fred segera membentuk benteng pertahanan seperti yang dilakukan Chris Jhon sang petinju.
Kursi mental ke samping, melenceng keluar jendela. Tak ada satu orang pun yang berani
masuk ke dalam. Api semakin besar. Asapnya membuat sesak. Waktu semakin sempit. Fidel
menubruk Fred. Kepalanya meleset menuju ulu hati, tetapi lengannya melingkar di kepala
Fred. Setelah Fidel memastikan posisi tangannya, kakinya langsung menyambar perut Fidel
menggunakan dengkul dan menghentak, membalikkan tubuh Fred sekuat tenaga menuju
lantai. Punggung Fred membentur tiang. Tulang lehernya retak. Nyerinya tak terkira. Asap
semakin tebal. Paru-paru ke dua lelaki itu sudah sampai pada batas yang tak dapat ditolerir.
Dengan sisa kekuatan Fidel meninggalkan Fred yang tergolek tak memiliki
kemampuan. Fidel merayap menggunakan lengan dan dengkulnya. Ia membuka pintu bawah
tanah lalu terjatuh. Pintu tertutup. Asap menyusup ke dalam. Fidel merangkak, menjauhi
asap. Di tiga perempat lorong bawah tanah ia pingsan.
Di atas ruang bawah tanah, Fred menggelepar seperti ayam yang dulu pernah disiksa
olehnya. Tangan Fred terlihat dari luar jendela, diubari api, menjadi gosong. Api mengamuk
membuat atap rumah ambruk. Palang penyangga terjun bebas mengakhiri rasa sakit yang
menjalar di tubuh lelaki itu.
Di lahan mentimun, Riang yang sudah bisa menguasai dirinya mengendap-endap,
memutar. Ia memiliki harapan, menuruni lereng bukit lalu berlari menuju tempat Fidel biasa
membincangkan segala hal dengannya. Dalam keadaan itu ia tak mengingat jika sesuatu
terjadi di luar kesadaran. Jemari tangannya menancap di tanah. Di lereng bukit itu ia
merangkak cepat seperti binatang berkuku tajam. Bukit itu dengan mudah ia daki.
Riang menuju semak-semak. Asap terlihat meleleh dari pintu yang tersembunyi. Ia
bergegas masuk ke dalam. Asap membuat Riang terganggu. Ia membuka baju dan
menggunakannya untuk menyaring asap.
Lorong gelap. Lampu padam. Riang tak bisa menyaksikan apa-apa. Ia ragu untuk
melanjutkan. Beberapa meter ke depan Riang memutuskan untuk berhenti, tetapi beberapa
langkah kemudian ia sudah tidak tahan. Nafasnya serasa tercekik. Ia berbalik dan … sebuah
tangan tiba-tiba memegang pergelangan kakinya. Riang jongkok meraba. Instingnya
bermain. Ia menarik tangan Fidel, menyeret tubuhnya. Di tangga ia memanggul tubuh Fidel
ke atas.
313
Saat pintu lorong terbuka ia merasa lega. Udara segar yang meski masih bercampur
asap menolongnya. Riang membanting pintu dan melemparkan tubuh Fidel ke luar, namun
… belum selesai ia mengatur nafasnya, sebuah laras senapan menempel di kepalanya.
“Di sini Bang!” seseorang berteriak antara tegang dan senang.
Pitbul menyalak. Riang mendengar langkah kaki mendekatinya. Ia mengangkat
tangan tak memiliki kesempatan melawan. Riang diikat. Ia melihat wajah sahabatnya
berjelaga, namun ia bersyukur masih bisa melihat gerakan halus di dada. Jantung Fidel masih
memompa darahnya. Perutnya masih berdenyut konstan.
Riang bersyukur sahabatnya masih bisa bernafas. Kini, yang ia khawatirkan hanya
dirinya. Orang-orang berkumpul mengelilingi Riang. Riang tak mampu menatap wajah
mereka. Ia memilih berdamai. Lalu ketika salakan anjing terdengar didekatnya, Riang
merasakan wajahnya berputar. Tulang pipinya berguncang disepak. Dalam pening ia melihat
seseorang mengayunkan kembali kakinya. Orang itu hilang akal. Kaki mendarat di tubuh dan
wajah Riang. Darah bertebaran di tanah. Lidah Riang tergigit. Gigi gerahamnya terasa nyeri.
“Siapa suruh menghabisi dia, goblog!” Lelaki bertubuh atletis memaki. Kardi yang
memukuli Riang sampai habis disergap, sementara anjing yang ada di tangannya di alihkan.
Sebelum kesadaran Riang pupus, ia melihat mulut yang benar-benar dikenalnya meludah.
Ludahnya bau pasaran, bau mayat!
Setelah amukan api reda, beberapa lelaki diperintahkan untuk menuruni tangga,
memasuki lorong bawah tanah. Berbekal senter mereka memeriksa buku-buku yang
berwarna kecoklatan lalu membalikan risbang. Mereka tak menemukan rekaman yang
dibicarakan Fred. Mereka hanya berharap pada dua orang yang tertangkap. Puluhan orang itu
kemudian berjalan. Mereka bergantian menjinjing Fidel dan Riang seakan klan kanibal yang
tengah menjinjing hewan buruan.
MALAM HARINYA, Waluh, Bentar dan Eva sampai di rumah kayu. Mereka hanya
melihat reruntuhan. Diantara reruntuhan itu tercium bau daging matang. Ketiga orang itu
mengais-ais arang. Ketakutan akan takdir seorang sahabat membuat mereka ketakutan.
Sebuah tangan mereka temukan terlihat hitam kaku dan meregang, di balik
reruntuhan. Bentar dan Waluh membuka sisa bakaran perlahan dan memastikan bahwa
mereka tidak mengenal tubuh yang hangus itu. Tinggi tubuh mayat tersebut lebih pendek
ketimbang tubuh, Fidel sahabat mereka. Bentar kemudian mencari-cari pintu ruang bawah
tanah. Ia menemukan dan membukanya, menyalakan senter lalu masuk memeriksa dan tak
menemukan seorang pun juga di sana.
314
Ketiga orang itu segerameninggalkan rumah kayu dengan perasaan yang berkecamuk.
Sampai di tempat seorang kawan mereka bergerak cepat, mengumpulkan teman yang tersisa.
Tak ada yang hilang kecuali Fidel dan Riang. Dan pada saat seseorang memberitahukan Fred
hilang, bulu kuduk ketiga orang yang telah menyaksikan jasad yang gosong terbakar itu
meremang.
Orang-orang segera menyusun rencana. Draft kronologis peristiwa Punclut dan
kemungkinan keterkaitan antara dirusaknya pondokkan dan dibakarnya rumah kayu serta
penemuan mayat tak dikenal mereka susun. Jam sepuluh pagi draft digandakan lalu
dibagikan pada beberapa lembaga advokasi yang mereka percaya dan media massa lainnya.
Aksi lanjutan disusun. Informasi berantai di tangkap seluruh jaringan gerakan sub
culture di Bandung serta beberapa organisasi lainnya. Jam satu siang hari itu, Riuh rendah
orang-orang menyemut, berkumpul di gedung sate Bandung.
Jalan di samping kiri gedung pemerintahan yang bersambung dengan Bandung Indah
Plaza segera diriuh rendahi pekikan. Klakson digonggongkan. Kendaraan pribadi dan
angkutan menyingkir. Yel-yel membakar. Dari arah Jatinangor ratusan orang berdatangan
mengeluarkan bunyi begemuruh. Arus massa terbelah menjadi dua, saat bus kuning
membelah jalan. Penumpang bus itu sesak. Di atasnya berdiri lima orang. Tiga menggunakan
slayer dan ikat kepala yang lainya memegang megaphone. Di jalanan patroli polisi tampak
terkejut. Empat orang polisi yang saat itu tengah istirahat belari memastikan pagar gedung
dewan terkunci. Tak ada barikade berduri.
Surat yang baru disampaikan setengah jam lalu membuat aparat tak siap. Mereka
membutuhkan waktu untuk mengkoordinasikan anggotanya di lapangan. Waktu jeda itu
dimanfaatkan oleh rombongan lain yang berjumlah seratusan. Rombongan ini menentang
arah ratusan orang yang berjalan menuju gedung pemerintahan. Mereka anak-anak muda
pakaiannya di dominasi warna hitam. Rambut beberapa orang diantaranya ditegakkan lem
uhu melawan grafitasi. Warna-warna menyala. Beberapa orang melilitkan rantai anjing di
saku celana, beberapa lainnya mengenakan rantai di leher.
Wartawan terpilah menjadi dua. Mereka ragu-ragu untuk tetap bertahan di gedung
pemerintahan atau mengikuti aksi lainnya. Beberapa wartawan yang akurasi informasinya
bisa dipertanggungjawabkan mengambil sepeda motor, beberapa di antaranya berlari menuju
RRI.
Rombongan seratusan orang ini menemukan gerbang RRI yang sudah ditutup satpam.
Penjaga keamanan tampak kebingungan. Bentar yang berada di dalam rombongan
melakukan negoisasi. Jumlah orang yang ada di belakangnya memuluskan jalan.
315
Auman! Pekikkan! Kemarahan menyala-nyala di udara. Mereka masuk, menduduki
ruangan, dan beberapa orang lainnya menuju ruang siaran. Waluh dan Bentar mengambil
mike. Beberapa orang kawan mencari operator radio, meminta mereka untuk menyiarkan apa
yang ingin mereka sampaikan, on air!
Seorang operator menolak. “Bisanya hanya siaran tunda!” kata dia. Tetapi dari ruang
siaran seorang teman berteriak. Ia mendapatkan operator yang bisa mengacak program RRI
nasional. “Siang ini berita bisa kita bajak!” teriaknya.
Operator itu segera di paksa masuk ke dalam ruang siaran. Di bawah tekanan operator
muda itu hanya memakan waktu hampir setengah jam untuk mengacak siaran pusat. On air!
Saat siaran baru berjalan beberapa menit, seorang kawan lain masuk. Ia berteriak
membuat kaca ruang siaran berembun. “Situasi kacau! Polisi sebentar lagi datang! cepat!
Teman-teman berusaha mempertahakan!”
Bentar mengambil inisiatif. “Masukkan wartawan!” ujarnya. “Biar mereka menjadi
saksi penangkapan kita.” Setelah berkata demikian ia mempercepat apa yang ingin di
sampaikannya.
WTO, IMF, World Bank, serta imbas penanaman modal asing dan dibukanya
pengelolaan hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam selain oleh Negara ia jabarkan.
Bentar sampai di puncak kemarahannya ketika membeberkan penyerobotan tanah di berbagai
daerah. Ia menceritakan kronologis Punclut. Seluruh keterkaitan yang masih menjadi dugaan
ia jabarkan. Hilangnya Fidel dan Riang penemuan mayat membuatnya berang. Makian di
selipkan … puisi-puisi… pekikan kaum bercaping…kesadaran akan emansipasi … pestisida
korupsi… anjing… anjing dan anjing dilontarkan. dan …
Dar! Dar! Dua buah letusan letusan tiba-tiba terdengar.
Seorang wartawan yang terkena gas air mata mengingatkan. “Polisi menyerbu!”
Suaranya hingga ke dalam. Pintu ruangan didobrak! Kaca pecah! Lampu kilat berkejaran.
Wartawan yang ada di dalam ruangan merekam kejadian yang tak mungkin terulang.
Selasa menjelang Ashar itu, Waluh, Bentar dan kawan-kawanya digelandang polisi
menuju truk bak terbuka. Mereka tak melawan. Pembajakan yang mereka lakukan tak sia-sia.
Peristiwa pembajakan kantor dan pembajakan berita resmi RRI itu menjadi kisah yang
gaungnya tak mungkin hilang di masa yang akan datang.
MANAKALA PEMBAJAKAN RRI BERAKHIR di sisi terluar kota itu, Riang
merasakan tubuhnya mengalami banyak guncangan. Kelokan, jalan berbatu yang telanjang
tanpa aspal membuat seluruh isi truk terguncang. Tak jauh dari tubuhnya, Fidel berbaring,
316
mempertahankan posisinya, berpura-pura pingsan sambil mencerna keadaan. Truk berhenti.
Lelaki yang ada ada di dalam truk menyeret tubuh Fidel dan Riang.
Suara jangkrik terdengar. Riang dan Fidel tak melihat apa-apa. Mata mereka ditutup
kain semenjak mereka di lemparkan ke dalam truk. Tubuh Fidel di gotong, sementara Riang
diperintahkan berjalan jongkok. Seseorang lelaki mendekati Riang.
“Sudah kuingatkan di Merbabu!!”
Riang berusaha menerka dalam diam.
Kardi tertawa dingin. “Aku setanmu!” ujarnya. “Tak aku sangka kita akan bertemu
lagi!” ia kemudian duduk dan berbisik. “Kali ini kau akan mati! Mati! Mati ditanganku!”
Ancaman itu membuat Riang ketir. Ia tak terlatih mengelola emosinya menghadapi
penculikan. Dalam kepalanya muncul gambaran-gambaran penyiksaan. Gambaran itu makin
rindang, berbuah lebat. Sebelum ngeri yang sesungguhnya mendatangi, Riang dihancurkan
oleh kemungkinan-kemungkinan negatif yang di sodorkan pikirannya. Riang strees. Ia mual.
Malam itu Riang dimasukan ke dalam sebuah ruangan tak berwarna selain hitam.
Lampu dimatikan. Tak ada makanan. Organ tubuhnya mulai berkerja mengambil cadangan
lemak. Makanan masih bisa ditangguhkan, tetapi air. Riang kehausan. Di hari ke dua,
matahari menyerobot masuk. Riang di gelandang keluar, diperintahkan jongkok untuk
memakan makanan anjing. Ia mendengar suara riuh dari kejauhan. Riang menyaksikan Fidel
dikalungi tali. Ia bersyukur masih bisa melihat lelaki itu. Riang terharu. Ia tak melihat
ketakutan di wajah Fidel.
Fidel demikian tenang saat ia dibawa ke dekat Riang. Fidel ditelanjangi hingga hanya
menggunakan cawat. Ia di guyur air dingin dari dalam tong. Tubuhnya memar-memar di
beberapa bagian. Warna merah sisa darah masih menempel. Fidel mengigil. Ikatan pada
tubuhnya di perketat lalu Fidel dimasukan ke dalam tong berisi air. Fidel dipukuli, dipaksa
masuk ke dalam airnya. Tong ditutup. Beberapa puluh detik kemudian tong bergetar lalu
rubuh. Air mancur keluar, Fidel mengap-mengap. Wajah tenangnya terlihat merah padam.
“Di mana video itu!?” lelaki bertubuh atletis membentak.
Fidel menatap. “Terbakar bersama kawanmu!” ungkapnya.
Lelaki itu marah. Ia tak percaya, Fidel pastilah berdusta. Lelaki itu ingin mengetahui
batas kekuatan yang dimiliki Fidel. Ia memasukan Fidel lagi ke dalam tong lainnya yang
berisi sedikit air. Batu kerikil di masukan ke dalam tong. Kali ini bukan hanya dikeram. Lima
orang mementungi tong itu dengan kayu dan sepatu, lalu tong digelindingkan di turunan.
Tong berlari hingga menyimpang dari jalannya lalu berhenti setelah membentur pohon. Fidel
317
dalam keadaan tak sadarkan diri saat tong di buka. Ia ditarik ke atas oleh seutas tambang. Di
dekat Riang, Fidel dipaksa siuman.
Lelaki bertubuh gempal yang ingin terlihat garang lantas mengambil tusuk gigi. Ia
menginjak lengan Fidel lalu tusuk gigi itu ia masukan ke dalam kuku Fidel. Fidel menahan
sakit. Mulutnya mengatup, merapal-rapal sesuatu yang tak asing bagi orang yang
menyiksanya. Fidel terus merapal. Rapalan itu tak mengalihkan rasa sakit yang tak tertahan
tak terbayangkan. Jeritan terdengar ketika tusuk gigi yang ketiga membongkar kuku jari
tengah. Fidel merintih di hadapan Riang. Fidel yang biasa terlihat gagah berusaha melawan
rasa sakitnya.
Betapa menyakitkan melihat orang yang Riang kagumi dihinakan. Riang meneteskan
air mata menyaksikan peragaan kejahatan yang belum sampai batasnya. Riang tak hendak
memperdulikan keadaannya. Dalam suasana sempit Riang teringat kembali atas apa yang
telah Fidel lakukan padanya. Ia teringat masa-masa ketika dirinya masih teronggok dalam
bentuk bebatuan dan Fidel ulet memahatnya. Riang berubah menjadi karya seni yang indah.
Riang teringat ketika Fidel mengatakan, akan selalu ada hari esok. Akan selalu ada hari
kemenangan. Kejarlah kemenanganmu di masa ini. Cintailah hidup, akan tetapi jika takdir
sudah menentukan dan kemenangan tidak berada di tangan maka kemenangan itu akan tiba
bagi orang yang mempercayai kehidupan sesudah kematian.
Apakah tidak ada kemenangan Riang di dunia? Riang masih ingin menikmati sari pati
kehidupan. Ia ingin keluar dari celah sempit ini. Tidak sendirian. Ia ingin bersama Fidel.
Riang memperhatikan wajah Fidel yang kuyu di hadapannya mulai bercahaya.
Matanya yang bengkak mulai terbuka. Entah mengapa Fidel tersenyum padanya. Riang tahu,
dalam kondisi hidup mati seperti ini, adalah manusiawi untuk memperlihatkan ketakutan,
tapi Fidel mulai tersenyum. Ia berusaha menenangkan Riang dengan senyumannya seolah
mengatakan, santai … Ini hanya kepingan. Atau, menguatkan Riang bahwa pengalaman
seperti ini sudah seringku alami. Kita akan baik-baik saja.
Fidel memberi energi positif. Ia berusaha menguatkan Riang. Berada di dekatnya
ibarat mendekati sebuah adaptor. Ibarat mempersilahkan diri ditranfer energi besar yang
disalurkan secara alami.
Riang tak sadar, ketika ia tengah memperhatikan Fidel, lelaki bertubuh atletis
berbisik. “Mungkin kau kuat, tapi apa kau kuat melihat temanmu kami siksa?!” Lalu lelaki
bertubuh atletis memberi tanda pada lelaki berbadan gempal untuk berhenti menyiksa Fidel.
Lelaki berbadan gempal itu mengganti posisi. Ada kesenangan psikotik di matanya.
Ia menuju Riang, lalu mengikat lengan Riang pada sebatang pohon. Orang-orang berkumpul
318
lalu membantunya mebogemi tubuh Riang. Ulu hati Riang mulai kempis, ekspresi wajahnya
kacau, tubuhnya dihantam sampai ringsek. Riang bersujud di tanah. Ia hampir tak kuat
menahan sakitnya. Lalu generator dinyalakan. Percikan api yang muncrat membuat Riang
ketakutan.
Fidel terus tersenyum, tetapi senyum itu malah menimbulkan dengki. Lelaki bertubuh
gempal memergoki. Ia kesal lantas, tas! tas! Percikan api muntas. Tas! Tas! Tas! Tubuh
Riang di sengat. Peredaran darahnya beku. Matanya mebeliak merah Riang kejang-kejang
hingga membuat dahan pohon bergoyang.
Fidel menyadari, memfokuskan diri pada penyiksaan di hadapannya justru akan
memperlambat upaya dia membebaskan diri. Fidel bergegas. Patahan-patahan tusuk gigi
yang sebelumnya dipergunakan untuk menyiksa, ia gunakan untuk memutuskan serabut tali
rami yang mengikat tangannya. Ketika tusuk gigi sudah tak berfungsi, ia meraba-raba dan
menemukan ceceran kerikil yang membuatnya pingsan di dalam tong. Gesekan batu kerikil
ia percepat pada tali rami. Dan ketika ketajaman batu kerikil itu berkurang, tali rami putus.
Fidel memperhatikan keadaan seksama. Ia melihat orang-orang menyaksikan
penyiksaan itu dari jarak yang bisa Fidel taksir. Ia melakukan kalkulasi lalu melihat letak
senjata. Senjata yang paling dekat adalah yang tersemat di pinggang lelaki gempal yang
tengah menyetrum Riang. Belati itu terselip di pinggang, disarungi kulit sapi. Fidel telah
menentukan momentum.
Jerita Riang kembali terdengar. Beberapa lelaki yang menyaksikan penyiksaan sudah
merasa tak kuat, akan tetapi mereka berpura-pura menguatkan diri. Sama halnya ketika tusuk
gigi membongkar kuku Fidel, orang-orang itu menganggap kekejaman yang lelaki gempal
praktikan sudah keterlaluan. Ada sikap manusia yang tersisa di dalam diri mereka tetapi
lelaki bertubuh gempal itu tidak. Ia binatang, melebihi binatang ternak.
Riang terus menjerit. Tubuhnya meronta lidahnya terasa kering, air liurnya mencelat
kemana-mana dan ketika jeritan terkeras itu menihilkan suara generator, Fidel segera berdiri
dan berlari menubruk. Ia Menghantam iga dan merampas pisau. Seseorang mencabut pistol..
Fidel menjadikan tubuh lelaki bertubuh gempal sebagai tameng.
“Buka!” Fidel memerintahkan mereka untuk membuka ikatan di tubuh Riang.
Tak ada yang bergerak. Mereka menanti reaksi lelaki bertubuh atletis.
“Kepung dia!”
Fidel dikelilingi. Ia tak mungkin memiliki kesempatan. Ia memilih mempertaruhkan
kemungkinan yang belum terpikirkan oleh gerombolan orang ini. Fidel menikam pelan di
punggung belakang lelaki bertubuh gempal. Lelaki itu berontak, memaksa diri berbalik dan
319
tikaman ke dua merobek pipinya. Lelaki itu terhuyung, meminta bantuan. Tangannya
mendompleng bumi, jemarinya meremas tanah.
Fidel berlari zig-zag ketika letusan terdengar. Peluru menembus pohon pisang, dan
masuk ke dalam tanah. Fidel terus berlari. Pisau digengaman tangannya mulai menembus
bahu seorang lelaki. Ia mencabut pisaunya lalu berlari mencari sasaran lain. Darah muncrat
dari leher. Usus dicungkil, menjulur keluar. Gerombolan itu kalang kabut. Lelaki bertubuh
atletis memerintahkan mundur, menjaga jarak. Fidel terus berputar.
“Kardi!” Lelaki bertubuh atletis berteriak.
Kandang di buka. Salakan anjing terdengar. Fidel gentar. Sebelum pitbul sampai di
tempat itu ia berharap bisa membebaskan Riang. Fidel terus menerus berlari dan memangsa
orang-orang dengan pisau yang ada di genggamannya. Seseorang yang menguatkan diri
memungut pipa. Pisau dan besi berbenturan. Di saat itulah Kardi datang dan melepaskan tali
kekang.
Pitbul menyerang, ia melompat terjang. Mengigit paha. Fidel tak mau merasakan rasa
sakit itu. Ia tusukkan pisau di kepala pitbul. Anjing itu mati di tempat. Tertatih Fidel
mendekati Kardi. Pitbul ke dua dilepaskan, memutar mencari kesempatan. Ketika pisau
merobek baju Kardi, pitbul melompat mencengkramkan pisau email yang menempel di
rahangnya pada tengkuk Fidel.
Ini pertarungan penghabisan. Pistol menyalak. Lengan kiri Fidel tertembus peluru.
Dalam sisa kekuatannya ia terus maju, menihilkan rasa sakit. Ia ingin membawa seseorang
dalam kematiannya. Fidel menangkap tangan Kardi menggunakan tangan yang dikoyakkan
peluru. Kardi hilang keseimbangan. Tubuhnya maju tak bisa di tahan. Tubuhnya menjadi
lahan. Pisau tertanam, menancap hingga tepian jantung, tepat di bagian tubuh yang sama saat
ia membunuh seseorang lelaki gagah di dekat stasiun Yogyakarta.
Fidel membungkuk. Ia mulai kehabisan tenaga. Taring pitbul itu mulai meretakkan
leher, hampir menembus otak kecilnya. Fidel tersenyum. Seyum itu sedemikian cantik.
Sebuah senyuman yang mewah. Sebuah senyum agung yang berbekas.
Fidel memberikan senyum yang tak akan bisa Riang lihat lagi untuk selamanya.
Senyum itu adalah pertukaran yang sebanding. Sebuah senyum kebahagiaan ketika seseorang
mempertaruhkan hidup untuk sesuatu yang diyakininya.
Ia terkulai. Fidel meninggal. Tubuhnya kandas.
Riang menangis. Ia tak lagi memikirkan kesakitannya sendiri. Riang tergolek lemas.
Cahaya hidupnya di matikan paksa. Ia melihat orang-orang mendekati tubuh Fidel,
memastikan. Urusan Fidel di dunia ini sudah tamat. Kini tubuhnya di seret anjing. Lelaki
320
bertubuh atletis lalu meminta seseorang untuk datang menangani. Anjing pitbul di beri
daging. Rahangnya mengendur. Gigi taringnya lepas dari tengkuk Fidel.
Jasad Fidel dimasukan ke dalam tong. Riang menangis lagi. Ia melihat jasad itu
dihinakan. Ia tak tahan atas perilaku itu. Uratnya mengencang. Riang tak merasa tubuhnya
berguncang-guncang dan tali yang menahan dirinya tiba-tiba terlepas. Riang tidak tahu apa
yang terjadi. Yang ia tahu ia marah. Kemurkaan membuat seluruh kenekatan dan kekuatan
menetap di tubuhnya. Riang merasa jika dirinya seperti di pisahkan dari jasadnya. Ia seakan
menyaksikan sebuah kejadian dalam film, menyaksikan tubuhnya kalap, menyerang orang-
orang yang menggelindingkan tong yang berisi Fidel, sahabat tersayangnya.
Riang pukul mereka.
Ia mencakar!
Ia menendang dengan kekuatan yang memenclengkan tiga orang.
Tong Fidel berhenti menggelinding. Riang menghentikannya. Mendirikannya. Ia tak
mendengar hembus nafas. Ia tak mendengar rintih kesakitan. Riang belum bisa menerima
jika sahabatnya sudah berkawan dengan ajal.
Riang murka dengan derajat kemurkaan yang tak pernah dirasakannya. Ia mengambil
seonggok kayu, mematahkan satu orang yang menyergap badannya. Dua orang datang
memiting Riang. Mereka tak kuat menahan kekuatan magis itu.
Empat orang tak sanggup.
Lima orang dihempaskannya.
Delapan orang, Riang hampir takluk.
Ia dikerubungi. Tangan kakinya di pasung.
Riang terus melawan. Ia masih menggelepar. Digunakannya segala macam cara.
Digigitnya salah satu diantara mereka. Kepingan daging jatuh. Raungan-raungan yang
menjijikan. Mulut Riang di hantam. Mulutnya dimasukan kain. Ia tersumbat. Riang
melemah. Ia tak mampu lagi berbuat apa-apa dan derapun datanglah!
Pukulan dan tendangan bersatu dengan ludan dan makian. Dirinya adalah tempat
sampah. Puas sudah! Tubuh Riang di masukan ke dalam tong. Inilah saat-saat dimana
kepasrahan datang. Tak ada yang bisa menolong Riang.
Tong ditutup…
Cahaya hilang.
Tong..tong..tong..tong..tong..tong.
yang biasa diisi bensin, solar, minyak tanah
saat ini di isi manusia.
321
Tong…tong..tong..tong…
menjadi lorong yanghitam
seperti putaran roda bis …
serasa masuk ke dalam penggilingan.
…berputar…berputar semakin cepat.
suara geledak geleduk…
Suara…suara pukulan yang bising di telinga.
Seperti gemuruh seperti ada ledakan…
Ada drum band.
Semakin cepat betputar…
Pening…pusing…
Riang ingin muntah. Aku ingin muntah.
“Heiiii…buka! Aku mau muntah! Tolong!
Wu..wue…wuek..
WHO…EEEKKKKK!
Tong berhenti berputar. Tong didirikan.
Ada cahaya.
Tutup tong di buka.
Riang melihat ke atas.
Wajah dipenuhi cairan lambungnya sendiri.
Lelaki itu tersenyum sinis…
Ya ia rasa mengenalnya.
Riang berusaha konsentrasi…
…
…
Riang mengenalnya.
Ya…seperetinya dia Kardi.
H a l u s i n a s i
Mata Riang semakin kabur.
Ia dijambak. Diludahi dua kali.
“Kau akan mati!”
Lelaki itu memasukkan beberapa buah benda.
322
Tong ditutup kembali.
Berputa…putar lagi…
Tong-…tong….
Riang mulai merasakan perih…
Ada tusukan…tusukan kecil…
Benda apa yang dimasukkan lelaki itu?
…tubuh Riang seperti ditusuk paku …
Riang mengeram menahan sakit. Ia kencing.
Pipis di celana…
Riang berak di celana!
…tong
…tong
... tong …
Kepala kembali di atas,
kaki di bawa
Leher nyeri tertancap…
Semua badan nyeri tertancap…
Kesakitan memuncak…
Inilah ambang batas ketika Riang tak menyadari segalanya.
Seperti masuk ke alam baka.
Kesakitan perlahan dicerna.
Kesakitan dan pening di lahap.
…di cerna…
Tida..tiba..
Riang masuk ke dalam kedamaian.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………putaran…putaran ini …………………………… …………………. Seolah ia berdiri
di atas bumi melanglang… layang layang. Riang seakan
323
keluar dari tong dan menyaksikan bumi dari luar pengaruh gravitasi. Indahnya. Tong ini
tidak jauh dari bumi yang sedang berotasi. Ada kedamaian. Terus berputar pada porosnya.
….. …………………………….bumi ini adalah tong ……………………………………
…………………………………aku adalah bumi ini……………………………………..
………..…………………………...….ektase……………………………………………..
……………………Apa ektase yang dirasakan Rumi seperti ini …………………………
…………………………………..Riang mengantuk………………………………………..
………….damai…………
Damai..damai….
Allah…………….
……Allah………….Allah…
Allah….Allah…..Allah……....Allah……...Allah……….
Allah……….Allah…….Allah………
Mengapa aku menyebut naman-Nya?
Allah……Allah…….Allah……..kenapa ia melafadzkan kekhasan-Nya?
Allah…..Allah………..Allah……….
Allah………Allah………Alllah………………..
Allah………Allah………………Allah………
Allah………Alllah……………..Allah…….
Damai sekali…
Sejuk…
Tong..tong berputar…
Apakah Fidel merasakan hal yang sama di tong itu?
Riang berharap ya. Ia berharap anugerah yang serupa.
Kuharap ia dapatkan. Keajaiban menihilkan kesakitan….
Ya Tuhan…
Ya Tuhan…
Ayo terus putarkan…
Semakin cepat semakin nikmat….
Semakin dahaga….semakin terasa damai.
Bumiku adalah tong ini…tong ini adalah bumiku….
324
Riang mulai tak merasakan putarannya…
Ia berada di poros bumi…
Allah mematikan hukum alam untuknya
…huah…
Riang mengantuk…lalu senyap… dan tertidur lelap.
RIANG BANGUN, menanti apa yang terjadi. Tapi, di luar tak terdengar apa pun. Ia
menunggu. Terus menunggu. Setelah cukup lama, tong itu ia goyangkan, ke kanan, ke kiri
hingga terjatuh. Ia meneendang tutupnya! Tutup tong terbuka, Riang merangkak dan berdiri.
Dilihatnya keadaan sekeliling.
Tak ada manusia selain dirinya. Ia berada di tengah hutan. Mereka membuang Riang
di jurang. Jauh dari keramaian. Mereka sudah menganggapnya mati.
Riang melongok ke dalam tong sekali lagi. Ia menemukan celana pendek dan puluhan
paku. Ia lantas memperhatikan tubuhnya sendiri. Tak ada bekas paku dan tusukan. Tubuhnya
hanya terasa pegal. Riang kebal. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia mengenakan
celana pendek, kemudian berputar-putar mencari tong lain yang berisi jasad Fidel.
Riang berharap keajaiban tetapi ia tak menemukannya. Ia hanya bisa berharap Tuhan
mematikan hukum alam pada Fidel. Ia berharap luka yang tertancap di tengkuk, luka yang
membuat tubuh Fidel robek dan memar akan terasa seperti yang dirasakannya.
Seandainya Fidel benar mati, ia berdoa semoga tong yang di tempatinya menjadi
lorong kecil yang membebaskan dirinya dari dunia yang profan.
Tak ada kekhawatiran.
Riang seperti terbebas dari angka
Ia menjadi nol lagi.
Hilang semua asa. Lenyap seluruh asa
Ia berjalan… terus berjalan. Jika orang-orang memandangnya kalah, tak mengapa!
Sebab bagi dia kemenangan tidak ditentukan dari hidup dan matinya seseorang, melainkan
tetap beradanya dia di dalam ruang kebenaran…selama-lamanya! Seabadi-abadinya!
Riang memanterakan bahwa dirinya tidak pernah kalah. Bahwa Fidel tak pernah
tunduk untuk mengalah. Ia akan selalu berdiri tegap …
Menantang!
dan mengancam!
-TAMAT-